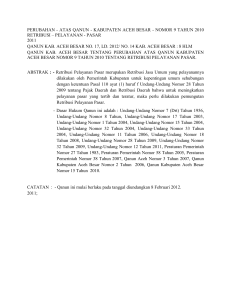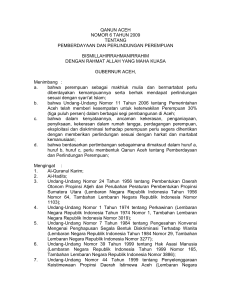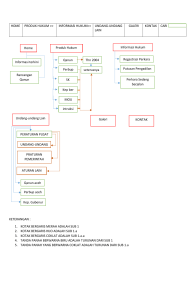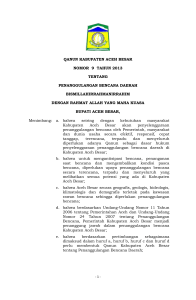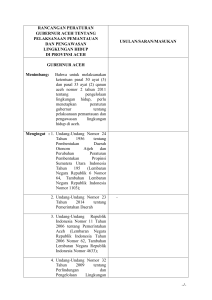Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh
advertisement

Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Controversy of Criminal Qanun Enforcement in Aceh) Oleh Hamdani1 Abstract Sharia Implementation in Aceh starts since 2002 , marked by the birth of the Law no. 44 of 1999 on the Implementation of the Special Province of Aceh Specialties , fortified with the birth of Law No. 11 of 2006 concerning Governance of Aceh, then followed by the birth of tthe official Islamic Shari'a, Wilayatul Hisbah, and Syar'iyyah Court. Government of Aceh along with the legislative (DPRA Aceh) have legislated some criminal law as the rules implementing the law on, inter alia Qanun No. 12 in 2002, Qanun No. 13 of 2003, and Qanun No. 14 of 2003. The last is Qanun of Jinayah on 14 September 2009. There are some obstacles and resistance encounter by the implementing agencies, both internally and externally, as well as the Qanun is not signed by the Governor as the head of Aceh. If it is viewed in a juridical perspective, the Qanun does not oppose to the 1945 Constitution, higher legislation and human rights. . Key words: Controversy, Qanun of Jinayah, Aceh A. PENDAHULUAN Masyarakat Aceh dalam sepanjang sejarah dikenal sangat dekat dan bahkan sangat fanatik terhadap Islam, masyarakat Aceh dalam kehidupannya selalu berbaur dengan ajaran Islam, sehingga sulit untuk dipisahkan antara adat istiadat dengan ajaran Islam dikalangan orang Aceh. Ini dibuktikan dari pernyataan dalam pepatah Aceh, “hukum ngon adat lage zat ngon sifeut” ( hubungan syari‟at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan), sebagai way of life (landasan filosofis) dalam bentuk “adat/adat istiadat”, 1 Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 80 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) yang struktur implementasinya disimpulkan dalam ”Adat bak Poe teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana”.2 Dalam pemahaman masyarakat Aceh, Syari‟at Islam bukan hanya dalam aspek hukum dan peradilan saja, akan tetapi mencakup semua aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Aceh telah mengajukan permohonan dan bahkan menuntut kepada pemerintah pusat agar diberikan izin pemberlakuan Syari‟at Islam. Tuntutan ini akhirnya mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dengan mengesahkan Undang-undang No. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian pada tahun 2001 pemerintah pusat kembali mengesahkan Undang-undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini mengamanatkan pelaksanaan syariat Islam di bumi Aceh secara kaffah. Oleh karena itu keberadaan kedua undang-undang ini juga merupakan momen penting dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hidup dalam masyarakat Aceh secara menyeluruh.3 Dalam hal ini, Aceh diberikan Peradilan Syari‟at Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar‟iyyah, yang kewenangannya telah diatur dengan Qanun, dan pada pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan Syari‟at Islam di Aceh adalah peradilan khusus dalam lingkungan peradilan Agama dan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Aceh sebagai salah satu daerah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki keistimewaan dan otonomi khusus untuk menerapkan dan memberlakukan Syari‟at Islam diwilayah hukumnya. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 44 Tahun 1999, pelaksanaan Syari‟at Islam mulai ditabuh genderangnya di Bumi Serambi Mekkah. Ini ditandai dengan Badruzzaman Ismail, Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh Dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, Tanggal 20 September 2006. hlm. 1 3 Syahrizal Abbas, Kontekstualitas Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Arraniry Press, 2003, hlm. X 2 81 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 adanya 4 (empat) keistimewaaan yang diberlakukan di Aceh yaitu bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan juga peran ulama. Penegakan Syari‟at Islam di Aceh telah dimulai dengan diberlakukannya Qanun Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Khamar (minuman keras), Qanun 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian), dan Qanun 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum). Pelaksanaan penegakan ketiga qanun tersebut ditandai dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah sebagai satuan khusus penegak Syari‟at Islam. Semenjak ketiga qanun di atas diterapkan oleh pemerintah Aceh, dalam perjalanannya ditemukan banyak kelemahan materi hukum yang terdapat dalam ketiga qanun tersebut, salah satunya adalah pelaku jarimah (pelanggar Syariat Islam) tidak bisa ditahan oleh pihak kepolisian sepanjang proses perkara berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2009 pemerintah Aceh bersama DPRA Aceh merumuskan kembali aturan hukum terhadap ketiga qanun jinayah dengan tujuan mengakumulasikan dan menyempurnakan ketentuan Syariat Islam dalam qanun tersebut dalam satu naskah qanun dan juga penerapan aturan formilnya. Pekerjaan penyempurnaan ketiga qanun jinayah tersebut rampung dilaksanakan pada September 2009. Tepatnya pada tanggal 14 September 2009 Qanun Jinayah dan Acara Jinayah disahkan oleh DPRA Aceh yaitu menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai anggota DPRA Aceh. Namun qanun tersebut menjadi pincang karena gubernur selaku kepala pemerintahan Aceh tidak mau menandatanganinya karena merasa dikangkangi dengan alasan paradok dengan undang-undang yang lebih tinggi.4 Setelah pengesahan qanun jinayah tersebut terjadilah kontraversi dikalangan masyarakat Aceh dari berbagai elemen, diantaranya ada yang pro dan kontra, seperti pernyataan ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hasanuddin Yusuf Adan, beliau mengkritik keras sikap gubernur yang tidak mau menandatangani qanun tersebut dengan menyuruh gubernur turun dari tahta.5 Teungku Ibrahim Bardan (Abu Panton), (meninggal 2013), berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan kesejahteraan terlebih dahulu sebelum qanun jinayah tersebut diterapkan.6 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh melakukan berbagai upaya mendesak gubernur segera menandatangani qanun tersebut, sejumlah ulama dayah Serambi Indonesia, 24 Oktober 2009 Serambi Indonesia, 18 September 2009 6 Serambi Indonesia, 17 September 2009 4 5 82 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) di Aceh Utara juga mendesak hal yang sama. Bahrum Rasyid anggota DPRA yang juga andil dalam melahirkan qanun tersebut dengan tegas mengatakan secara otomatis qanun jinayah sah berlaku setelah tiga puluh (30) hari, apakah dengan atau tanpa tanda tangan gubernur.7 Disamping yang pro, juga tidak sedikit kalangan masyarakat yang kontra, seperti yang dilontarkan oleh pegiat HAM dan gender yang mengecam lahirnya qanun tersebut dengan alasan bertentangan dengan hak azasi manusia. Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengkaji sebab musabab terjadinya kotroversi terhadap qanun jinayah dengan melihat dari beberapa aspek penemuan hukum, yuridis normatif dan sosiologis empiris. B. PENGERTIAN QANUN JINAYAH Qanun jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah, kata qanun berasal dari bahasa Arab yaitu qanna, yang bermakna membuat hukum dan kemudian qanun dapat diartikan sebagai hukum, peraturan atau undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, kata (qanun) berasal dari kata (qanna) yang berarti kaidah, undang-undang atau aturan. Adapun jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang. Menurut Ahmad Wardi jinayah secara bahasa adalah: “ اسن لوا يجنه الورء هن شر وها اكتسبهNama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”. Sedangkan pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: سواء وقع،فالجناية اسن لفعل هحرم شرعا “ الفعل على نفس أو هال أو غير ذالكJinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”. Menurut Sayid Sabiq “yang dimaksud jinayah dalam istilah syara‟ adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara‟ untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Menurut Amir Syarifuddin pengertian Jinayah merupakan satu bagian dari pembahasan fiqh. Kalau fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum Allah, dan amaliyah mengatur kehidupan manusia berhubungan dengan Allah dan sesama manusia, maka fiqh jinayah adalah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan sanksi hukuman yang dikenakan itu adalah untuk mendatangkan kemaslahahtan 7 Tabloid Kontras Nomor 509 Tahun XI, 1-7, Oktober 2009 83 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 bagi manusia, baik mewujudkan keuntungan dan manfaat, maupun menghindari kerusakan dan kemudharatan dari manusia. Segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau mahkluk lain dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan tindak kejahatan atau jinayah. Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam pelakunya dengan hukuman tertentu secara khusus disebut jinayah. Menurut Sudarsono istilah fiqh jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang dimana orang yang melakukan wajib mendapat hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa jinayah itu perbuatan dosa besar atau kejahatan (kriminal/pidana) seperti membunuh, melukai seseorang, berzina dan menuduh orang baik berzina. C. PROSES PEMBENTUKAN QANUN Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak berupa peraturan yang tertulis, pada umumnya didasarkan pada dua hal.Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang.Kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum. Ketentuan mengenai prosedur pembentukan undang-undang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan (di Aceh qanun No. 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun). Undang-undang dan qanun ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional dan daerah yang hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selanjutnya dalam angka 10 disebutkan bahwa program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 84 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) Secara yuridis formal dapat diketahui bahwa dari ketentuan diatas merupakan langkah atau proses pembentukan suatu aturan hukum yang berlaku yang dirancang secara sistematis,kata “sistematis” bermakna bahwa dalam membuat suatu aturan telah ada mekanisme dan langkah yang diatur dengan jelas. Dalam UUD1945 hasil amandemen disebutkan tugas pembentukan undangundang adalah DPR, sebagaimana tertuang dalam pasal 20 (1) “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. DPR adalah lembaga legislatif, sebagai pembentuk undang-undang. Presiden sebagai eksekutifjuga dapat mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945, presiden adalah lembaga eksekutif dengan arti mempunyai fungsi yang sama dengan DPR. Namun keterlibatan presiden dalam pembentukan undang-undang berfungsi untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, bukan sebagai pembentuknya. Pasal 20 (2) UUD 1945 yang menyatakan “rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama” presiden dalam proses pembahasan undang-undang hanya untuk mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan presiden terhadap rancangan undang-undang, karena kedua lembaga ini mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda, fungsi presiden dalam hal ini hanya memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan kepadanya, akan tetapi tidak boleh juga ditafsirkan bahwa presiden hanya memberikan persetujuan semata, melainkan mempunyai hak menyempurnakan dan bahkan berhak tidak menyetujuinya. Dalam proses pembentukan qanun di Aceh juga sama halnya dengan pembentukan undang-undang. Pembentukan qanun di Aceh juga merupakan wewenang DPRA sebagai lembaga legislatif dan gubernur sebagai lembaga eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam pembentukan qanun jinayah keterlibatan masyarakat sudah dilakukan melalui public hearing, dengan memberikan kesempatan mengeluarkan pendapat, ditambah lagi keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di dalamnya. Qanun-qanun yang ada dan akan ada di Aceh merupakan peraturanperaturan daerah yang dibuat untuk memenuhi ketentuan UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang tersebut Aceh ditetapkan istimewa dalam empat bidang, yaitu; istimewa dalam bidang 85 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijkan daeran.8 Dalam menjalankan suatu undang-undang harus adapp/perda/qanun. Suatu undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa ada qanun(khusus Aceh) sebagai aturan pelaksananya. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa untuk menjalankan undang-undang harus dibuat qanun-qanun.9 Syahrizal Abbas mengungkapkan dalam membuat sebuah qanun syariat Islam yang bersifat responsif maka dibutuhkan beberapa langkah nyata yaitu: a) Materi qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit al-Quran dan as-Sunnah, namun perlu diselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia. Pemahaman terhadap hakikat keberadaan teks akan menemukan ruh syari‟ah (nilai filosofis); b) Penemuan ruh syari‟ah bukan hanya membutuhkan kajian filsafat hukum Islam, tetapi juga membutuhkan kajian sosiologis dimana pemahaman terhadap kondisi masyarakat ketika teks lahir akan sangat berarti; c) Pendekatan tematis bukan hanya bertumpu pada ayat atau hadis yang berbicara tentang tema yang sama, tetapi perlu juga dilihat pemahaman tema tersebut; d) Semangat sosiologis yang dibangun al-Quran dalam hukumnya perlu mendapat perenungan. Karena banyak praktek dan tradisi telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat; e) Kerangka diatas akan bekerja bila tingkat pendidikan masyarakat dan sosialisasi qanun dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik sehingga keberadaan qanun syariat Islam benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.10 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999, pasal 3 ayat 2. Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999, pasal 11. 10 Syahrizal Abbas dalam buku Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Imlementasi Syariat Islam Di Aceh, editor: Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, diterbitkan oleh Aceh Justice Resource Centre, Banda Aceh, 2009, hlm 64. 8 9 86 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) D. PERSPEKTIF PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF Berbicara mengenai penemuan hukum tentu tidak lepas kepada subjek hukum yang dapat melakukan penemuan hukum,yang disebut rechtsvinding. Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.11 Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa kongkrit. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaanpertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.12 Sebagai subjek yang dapat melakukan penemuan hukum, pada umumnya adalah hakim dengan eksistensinya dapat menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan mengenyampingkan hukum positif yang berlaku. Undang-undang sebagai salah satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, kadangkala belum ada, tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga hakim dituntut untuk menemukan, melengkapinya atau mencari kejelasan akan ketentuan hukumnya, dengan mencari, menggali atau mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehinga putusan hakim akan mereflesikan rasa keadilan dan kebenaran serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara.13 Namun, ada juga pihak lain yang dapat melakukan penemuan hukum , yaitu pihak legislatif selaku lembaga yang berwenang dalam menetapkan hukum. Penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak legislatif yaitu dengan 11Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya, Jakarta, 2001, hlm. 13. 12Ibid 13Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Sinar Grafika, 2010, hlm. 20 87 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 memasukkan ketentuan yang merupakan aspirasi masyarakat dan menampungnya dalam sebuah aturan hukum. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, yaitu : a. Seorang ahli hukum senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja. b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang (wetgever) tertinggal oleh perkembangan didalam masyarakat.14 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap ahli hukum mempunyai peran dan tugas dalam menemukan hukum, sehingga setiap perundang-undangan yang ditetapkan setidaknya merupakan cerminan aspirasi masyarakat, seperti halnya qanun jinayah Aceh, bukan merupakan parasit dalam masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan. E. KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN JINAYAH Kontroversi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terhadap qanun Jinayah dimulai pada saat pengesahan qanun tersebut menjadi hukum positif oleh pihak DPRA pada tanggal 14 September 2009, sebahagian mengatakan bahwa pengesahan tersebut dilakukan sepihak oleh legislatif Aceh. Kontroversi ini mencuat dikarenakan di dalam qanun jinayah memuat hukuman rajam bagi pelaku zina 14 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2001, hlm. 46 88 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) muhsan,15 dan dijilid 100 kali bagi penzina ghairul muhsan,16 yang tercantumpada pasal 24 (1) qanun jinayah, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan „uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan „uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk serta „uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah. Hukum ini dianggap bertentangan dengan HAM, nilai-nilai kemanusiaan,dan bertentangan dengan UUD 1945, demikian pernyataan dilontarkan oleh kalangan yang menolak pemberlakuan qanun ini, ditambah lagi Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di Aceh tidak mau menandatangani qanun tersebut. Ada juga kalangan yang mendukung pemberlakuan hukum rajam dalam Qanun Jinayah, denagn argumen bahwa Qanun Jinayah tidak bertentangan dengan HAM dikarenakan materi hukumnya sudah jelas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 125 yang menyatakan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk memberlakukan hukum pidana Islam (hukum Jinayah). Selain itu hukum Jinayah bagi umat Islam merupakan keharusan yang harus dijalankan karena tuntutan ajaran Islam tidak ada perdebatan pada umat Islam tentang hal ini. Menjalankan Syari‟at Islam merupakan Hak Fundamental dalam kebebasan beragama (freedom of religion), Syariat Islam adalah hasil rekontruksi sosial masyarakat Aceh, sebagaimana diakui dalam konvensi Internasional, sehingga hukum tersebut dianggap tidak bertentangan dengan HAM.17 Secara hukum rancangan 15Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam. (Imam anNawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi,Beirut: Dar al-Fikr, t.t., XI: 180). 16 Penzina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nuur Ayat 2). 17 Dalam deklarasi universal tentang HAM 1948, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki semua hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada perbedaan untuk alasan, seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kekuasaan dan status lainnya. 89 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 qanun tersebut sudah sah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah, hal ini telah dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan pasal 38 (2), juga dalam Qanun No. 3 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, pasal 37 (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Gubernur/ Perlindungan yang tegas mengenai kebebasan beragama, dalam hukum HAM internasional adalah terkait dengan konsep religios intolerant (sikap tidak ada toleransi) yaitu kondisi minoritas tidak boleh menumbuhkan adanya perlakuan diskriminasi. Sejak tahun 1967 rancangan perjanjian internasional telah menegaskan tentang pembatasan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak toleran terhadap agama, termasuk larangan yang bertentangan dengan kebebasan terhadap pemeluk agama. Secara umum dalam pasal 3 Draft Konvensi menyebutkan: a. Bahwa kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk, atau mengubah agamanya merupakan hak asasi. b. Kebebasan untuk mengepresikan perilaku keagamaan atau kepercayaan baik secara pribadi atau bersama-sama, baik secara privat atau umum, merupakan subyek yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Dalam pasal 3 bagian 3, ditegaskan negara-negara wajib untuk melindungi siapapun di bawah yuridiksinya, meliputi; a. Kebebasan untuk beribadah atau mengumpulkan suatu seremonial bersama b. Kebebasan untuk mengerjakan, untuk melakukan disiminasi, dan mempelajari ajaran agama dengan menggunakan bahasa yang suci dengan tradisi menulis, mencetak, mempublikasikan buku, dan sebagainya. c. Kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan keperluannya dengan membangun institusi pendidikan, amal dana bantuan yang diselenggarakan di tempat umum. d. Kebebasan untuk mematuhi peribadatan, makanan dan praktek keagamaan dan untuk memproduksi, menjalankan impor-eksport barang-barang, makanan dan fasilitas yang biasanya dipergunakan untuk pengamalan ajaran agama. e. Kebebasan melakukan kunjungan haji atau perjalanan terkait dengan keyakinan keagamaan, baik di dalam maupun di luar negeri. f. Perlakuan dengan hukum yang setara terhadap tempat-tempat peribadatan, aktivitas dan upacara keagamaan dan tempat-tempat untuk penguburan mayat, sesuai dengan keyakinan agamanya. g. Kebebasan berorganisasi dan memelihara hubungan organisasi secara lokal, nasional dan internasional terkait dengan kegiatan agama, dan melakukan komunikasi dengan penganut agama lain. h. Kebebasan pemaksaan untuk melakukan sumpah menurut ketentuan agamanya. 90 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) Bupati/ Wali Kota dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan qanun disetujui bersama, maka rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas mengatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berbicara tentang Syari‟at Islam dalam kontek UUD 1945 termuat dalam pasal 18 a dan 18 b,18 maka dari sejak awal sudah terdapat permulaan yang baik, seperti terlihat dalam Piagam Jakarta yang mendahului pembukaan UUD 1945. Sekalipun terdapat kontroversi dalam pencoretan terhadap tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta, akan tetapi oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diakui menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Konstitusi. F. IMPLEMENTASI HUKUMAN RAJAM Hukum Islam digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, bar-bar, sadis, dan sebagainya. Ini muncul karena hukum Islam hanya dilihat dari satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia “modern”, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifan hukuman tersebut. Dalam Islam, untuk melaksanakan suatu hukuman seperti rajam harus melalui suatu proses dan etika hukum yang sangat ketat. Pada masa Nabi saja, hukuman rajam yang dijatuhkan relatif sedikit akibat dari sulitnya pembuktian. Lalu bagaimana dengan Aceh seandainya qanun jinayah tersebut mau ditandatangani Gubernur?. Tidaklah mudah untuk memenuhi syarat dan proses pembuktian sehingga sampai kepada hukuman rajam. Allah mensyaratkan adanya empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, Pasal 18 a (2) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18 b (1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 18 91 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (QS. An-Nisa: 15).Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta” (QS. An-Nur: 13). Para saksi tersebut juga tidak bisa main-main dengan kesaksiannya karena mereka juga diancam dengan hukuman yang berat jika memberikan kesaksian palsu: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur: 4). Kesaksian inilah sebagai standar dalam upaya Islam menyaring dan menyeleksi pelaku-pelaku zina dan melindungi orang baik-baik dari tuduhan-tuduhan tersebut. Secara logis, akan sangat sulit mencari empat orang yang benar-benar melihat perbuatan zina kecuali jika yang berzina tersebut memang sengaja “mempertontonkannya”. G. PERAN POLITICAL WILL PEMERINTAH ACEH DALAM MEMBANGUN SYARIAT ISLAM Political will (keinginan politik) dari pemerintah Aceh sangat menentukan dalam menegakkan syariat Islam. Dalam hukum, dikenal dengan jalur struktural-politik yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu jalur top down (dari atas ke bawah) dan jalur bottom up (dari bawah ke atas). Jalur top down cenderung memaksa suatu ketentuan dari aturan hukum sendiri dan jalur bottom up yang biasanya disebut jalur budaya/ kultural yang muncul dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Pasal 238 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun” dan ayat (2) “Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa bentuk political will dapat terjadi melalui jalur bottom up, dimana partisipasi masyarakat juga dapat menentukan baik-buruknya sebuah kebijakan pemerintah. Masyarakat juga dapat menilai sebuah aturan hukum yang sesuai maupun yang bertentangan dengan nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat. 92 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) Demikian halnya dengan pengesahan sepihak dari legislatif Aceh terhadap qanun jinayah tersebut, dimana masyarakat dapat memberikan masukan sebelum sebuah aturan hukum disahkan. Partisipasi masyarakat menjadi tema dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini. Ketiadaan partisipasi masyarakat akan membuat aparatur negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Ketidaksiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dapat mememenuhi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja kelembagaan-kelembagaan perangkat otonomi Daerah. Political will pihak terkait sangat dibutuhkan dalam mendengungkan kembali qanun Jinayah tersebut untuk dibahas ulang. Pembahasan dapat dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat, sehingga aturan hukum tersebut benar-benar mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat, bukan aturan yang dipaksakan. Dengan menjunjung nilai-nilai yang berlaku, pihak legislatif dan Pemerintah Aceh mempunyai peran penting dan bertanggungjawab secara penuh dalam menyukseskan qanun tersebut,karena kewenangan keduanya dalam membuat perundang-undangan tingkat daerah. Peran kedua lembaga tersebut dalam menemukan dan juga menentukan aturan hukum sangatlah besar. Sebuah cita-cita hukum akan tercapai dengan baik apabila tanpa adanya indikasi money politic. Olehitu peran serta seluruh pihak untuk mengadvokasi kembali qanun tersebut agar sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sehingga cita-cita hukum, terhadap pelaksanaan syari‟at Islam secara kaffah terealisasi dengan sebenarbenarnya. H. KESIMPULAN 1. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah hasil rekontruksi sosial masyarakat Aceh yang selanjutnya diatur oleh qanun sebagai aturan pelaksananya. 2. Qanun Jinayah adalah aturan perundang-undangan positif di Aceh yang mengatur segala bentuk tindakan kejahatan (kriminal/pidana) terhadap orang lain. 3. Qanun Jinayah yang telah disahkan oleh DPRA pada 14 September 2009 yang lalu, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena terjadinya kontroversi 93 Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013 ISSN 2302-6219 terhadap salah satu ini pasal tentang hukuman rajam sebagai uqubat bagi pelaku zina. 4. Argumen pihak yang menolak mengatakan qanun Jinayah bertentangan dengan HAM dan undang-undang yang lebih tinggi.Pihak yang menerima mereka berargumen bahwa Qanun Jinayah tidak bertentangan dengan HAM dikarenakan materi hukumnya sudah jelas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 125 yang menyatakan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk memberlakukan hukum pidana Islam (hukum Jinayah),dan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan pasal 38 (2) dan Qanun No. 3 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. 5. Pengesahan Qanun Jinayah Aceh telah melalui proses tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga telah dilakukan uji publik untuk menyerap aspirasi rakyat melalui public hearing. DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Sinar Grafika, 2010. Badruzzaman Ismail, Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh Dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, Tanggal 20 September 2006. Syahrizal Abbas, Kontekstualitas Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2003. Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Serambi Indonesia, 24 Oktober 2009 Serambi Indonesia, 18 September 2009 Serambi Indonesia, 17 September 2009 94 Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh (Hamdani) Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya, Jakarta, 2001. --------------------------- Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2001. Syahrizal Abbas dalam buku Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Imlementasi Syariat Islam Di Aceh, editor: Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, diterbitkan oleh Aceh Justice Resource Centre, Banda Aceh, 2009. Tabloid Kontras Nomor 509 Tahun XI, 1-7, Oktober 2009 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Qanun Aceh No. 3 tahun 2007 95