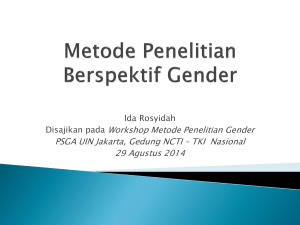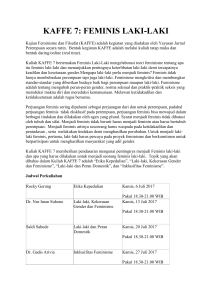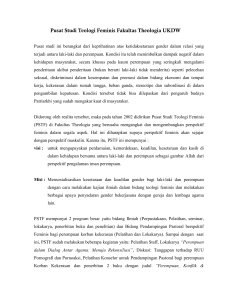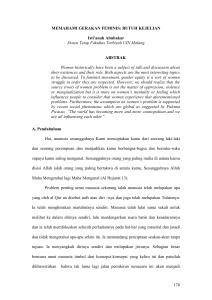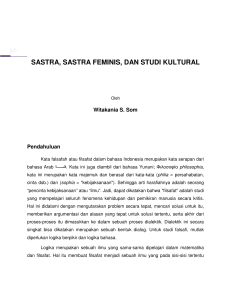BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
advertisement
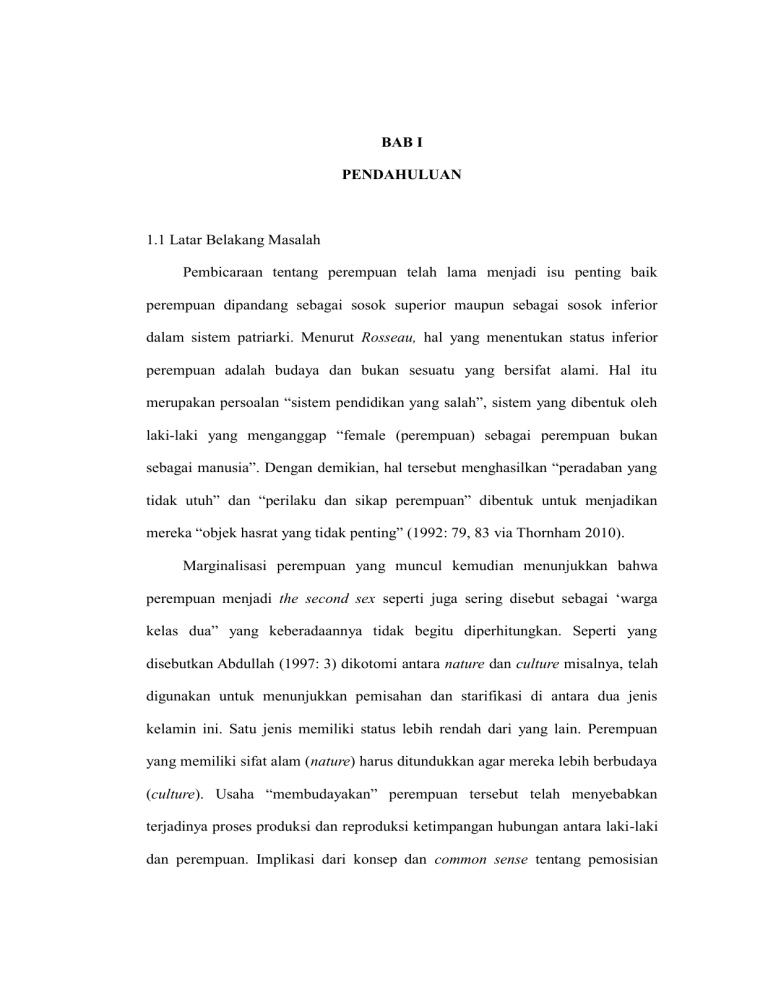
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembicaraan tentang perempuan telah lama menjadi isu penting baik perempuan dipandang sebagai sosok superior maupun sebagai sosok inferior dalam sistem patriarki. Menurut Rosseau, hal yang menentukan status inferior perempuan adalah budaya dan bukan sesuatu yang bersifat alami. Hal itu merupakan persoalan “sistem pendidikan yang salah”, sistem yang dibentuk oleh laki-laki yang menganggap “female (perempuan) sebagai perempuan bukan sebagai manusia”. Dengan demikian, hal tersebut menghasilkan “peradaban yang tidak utuh” dan “perilaku dan sikap perempuan” dibentuk untuk menjadikan mereka “objek hasrat yang tidak penting” (1992: 79, 83 via Thornham 2010). Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex seperti juga sering disebut sebagai „warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Seperti yang disebutkan Abdullah (1997: 3) dikotomi antara nature dan culture misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan starifikasi di antara dua jenis kelamin ini. Satu jenis memiliki status lebih rendah dari yang lain. Perempuan yang memiliki sifat alam (nature) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (culture). Usaha “membudayakan” perempuan tersebut telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari konsep dan common sense tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor domestik dan publik. Perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan. Sama seperti kebanyakan negara di Asia lain, negara Korea yang menganut paham Konfusianisme secara tidak langsung telah membagi status sosial dan peran kedudukan antara kaum lelaki dan perempuan. Konfusianisme adalah suatu ajaran filosofi moral yang masuk ke Korea dari Cina pada zaman Tiga Kerajaan (Widyaningrum, 2000). Dalam ajaran ini dikenal lima dasar hubungan antar manusia yaitu hubungan antara penguasa dengan rakyat, hubungan antara ayah dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara kakak dengan adik, dan hubungan antara teman. Selama berabad-abad ajaran ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Korea baik bidang politik, sosial, maupun budaya. Sebenarnya ajaran konfusianisme adalah ajaran yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, namun terkadang kaum pria salah menginterpretasikan maksud yang sebenarnya dari ajaran ini. Wujud ajaran mengenai kesetiaan dan kesolehan disalah artikan oleh kaum pria dengan menganggap kaum perempuan adalah kaum yang harus mengabdi di rumah kepada kaum pria. Dengan adanya pembagian ranah area kerja inilah yang membuat kaum perempuan terdomestikasi dan tersirat jika kedudukan laki-laki lebih tinggi dalam lingkungan masyarakat. Tatanan patriarki yang telah berakar kuat cenderung memaknai perbedaan jenis kelamin dengan segala implikasinya sebagai suatu bentuk kekurangan pada diri perempuan. Hal ini diperkuat oleh pandangan tentang perbedaan gender, yaitu konsep yang terbentuk dari konstruksi sosial ataupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara itu laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa (Fakih, 2006:8). Konstruksi gender tersebut melahirkan ketidakadilan gender sehingga perempuan tetap dianggap sebagai manusia kelas dua dan harus berada dibawah kendali laki-laki. Ketidakadilan terhadap perempuan selalu hadir dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat terjadi dalam setiap aspek kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dari sejarah kehidupan yang mendiskreditkan perempuan tersebut, timbullah berbagai bentuk perlawanan diberbagai bidang melalui sebuah gerakan yang disebut feminisme. Gerakan ini kemudian mempengaruhi banyak segi kehidupan perempuan. Gerakan feminisme secara umum merupakan suatu reaksi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang patriarki (Mustaqim via Evita 2008: 88). Secara historis, gerakan feminisme di Barat terkait dengan lahirnya renaissance di Italia yang membawa fajar kebangkitan kesadaran baru Eropa. Pada saat itulah muncul para humanis yang menghargai manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu yang bebas menggunakan akal budinya. Feminisme sebagai filsafat adalah gerakan yang berkaitan dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Mortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu perempuan dari kalangan atas sampai kalangan bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hal berpolitik, hak atas milik dan hak pekerjaan. Karena tidak memiliki hak-hak tersebut, kedudukan perempuan tidaklah sama di hadapan hukum. Menurut mereka, ketertinggalan tersebut disebabkan oleh kabanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Pada tahun 1990-an, perbedaan gender di Korea sangat kental terlihat. Fenomena ini merupakan fenomena yang terjadi secara natural sebagai salah proses modernisasi. Namun jika melihat fenomena yang terjadi di Korea Selatan, masa itu situasinya sangat memprihatinkan. Keprihatinan tersebut dapat dilihat dengan adanya demo massa yang sangat dramatis dengan aksi para pendemo perempuan yang mogok kerja. Hal ini tidak lain dilakukan untuk melemahkan kekuatan radikal kaum intelektual yang dipegang oleh kaum laki-laki. Dari peristiwa tersebut, seorang produsen film bernama Kim Min Yeong yang peka akan kejadian tersebut membuat sebuah karya yang akan dikenang sebagai salah satu bagian dari sejarah penyamaan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Film yang menjadi bagian sejarah Korea itu berjudul “Gae kateun Nareui Ohu” atau yang terkenal dengan judul “A Hot Roof” dalam versi Inggrisnya. Film ini dicatat menjadi salah satu film dokumenter karena mengabadikan sejarah mengenai tonggak awal gerakan feminis di Korea. Topik utama film “Gae kateun Nareui Ohu/ A Hot Roof” menceritakan tentang penindasan yang dilakukan oleh seorang suami pada istrinya yang mengobarkan kemarahan kaum perempuan yang akhirnya juga ikut tersadar atas semua perlakuan yang telah dilakukan para laki-laki khususnya suami mereka di masa tersebut. Film ini menggambarkan situasi perempuan di era kekerasan untuk melawan kekuatan kaum laki-laki karena pada saat itu semua aspek penting kehidupan dipegang oleh kaum laki-laki. Bahkan mereka tidak dapat mengadukan ketidakadilan tersebut kepada pihak yang berwenang seperti aparat keamanan negara yang dikepalai oleh seorang laki-laki yang benar-benar tidak mengakui eksistensi kaum perempuan. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, masalah utama yang diangkat dalam studi ini adalah isu-isu tentang perempuan dalam sebuah karya sastra yang berbentuk audio visual (film). Isu-isu tersebut terkait dengan analisis terhadap eksistensi perempuan Korea dalam memperjuangkan persamaan haknya dengan kaum laki-laki. Film memiliki kemampuan mengarahkan perhatian penonton pada masalahmasalah tertentu serta mampu membentuk opini penonton tentang masalah gender. Menurut Mangunhadjana (via Evita 2001), film memiliki daya tarik istimewa dibanding dengan pertunjukkan senilainya. Dengan menonton sebuah film, pemikiran penonton telah dipenuhi oleh gagasan, pendapat atau cita-cita yang disuguhkan dalam film. Sebuah film dapat dikatakan sukses apabila mampu membuat penontonnya ikut larut dalam “kehidupan dunia film” tersebut dan dapat membuat penonton untuk ikut masuk dalam kehidupan yang dikisahkan. Film “Gae Katheun Nareui Ohu atau A Hot Roof” yang mengangkat masalah pelik mengenai perlawanan para pahlawan perempuan Korea untuk menuntut kesetaraan gender diharapkan dapat mengajak penonton membuka pandangan masyarakat dalam menyikapi kesetaraan gender. Permasalahan yang akan diangkat dari film A Hot Roof adalah: Bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalm film yang 1. merupakan cermin realitas sosial pada masa tersebut. 2. Ide-ide feminis yang tergambar dari bagaimana beberapa tokoh perempuan pemeran utama film ini berusaha melakukan perlawanan terhadapnya. 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan mengungkapkan ide-ide feminis yang terkandung dalam film “Gae kateun Nareui Ohu” atau yang dalam judul Inggrisnya “A Hot Roof” yang merupakan cerminan mengenai situasi sosial masyarakat Korea pada tahun 1990-an. Secara spesifik penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan solusi kepada perempuan tentang kesadaran internal untuk menggerakkan eksistensi diri dengan semangat kemandirian. 1.4 Tinjauan Pustaka Pembicaraan mengenai perempuan dalam karya sastra dalam dekade ini sudah banyak dilakukan. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa eksistensi perempuan yang selama ini disudutkan, kini mulai digugat. Gugatan tersebut bisa datang dari kaum perempuan itu sendiri ataupun dari sekelompok kaum laki-laki yang prihatin akan nasib kaum perempuan yang selalu dianggap rendah. Salah satu media yang dinilai representatif untuk menyampaikan permasalahan tersebut adalah karya sastra. Untuk mengungkapkan isi kandungan karya sastra sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas diperlukan cara kerja ilmiah yang bertanggung jawab. Dalam dunia akademik, salah satu cara untuk mengungkapkan kandungan karya satra adalah melalui penelitian ilmiah sesuai dengan prosedur dan teori yang tepat. Dari sejumlah teori yang digunakan untuk membedah karya sastra, salah satu teori yang bisa mengungkapkan fenomena perempuan dalam karya sastra adalah kritik sastra feminis. Dengan menggunakan teori tersebut, diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan perempuan yang tercermin dalam karya sastra. Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, terdapat beberapa penelitian ilmiah yang mengungkapkan eksistensi kaum perempuan Korea dalam sebuah film yaitu penelitian mahasiswa jurusan Bahasa Korea Universitas Gadjah Mada angkatan 2007 yang telah meneliti tentang ide-ide feminis sebagai resistensi terhadap ketidakadilan gender kajian kritik feminis terhadap film yang berjudul Hwang Jin Yi. Evita (2007) menyimpulkan jika tokoh Jin Yi yang berperan sebagai gisaeng telah menunjukkan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadadilan yang berlaku pada dirinya. Dia bereaksi dengan caranya sebagai protes atas tindakan ketidakadilan atas wanita yang berprofesi sebagai gisaeng. Akan tetapi, perlawanan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih terbelenggu dengan adat istiadat setempat. Penelitian ilmiah lain yang mengungkapkan tentang eksistensi kaum perempuan Korea dalam sebuah film yaitu skripsi berjudul ide-ide feminis sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan gender dalam film 미인도 (The Portrait of Beauty) yang ditulis mahasiswa jurusan bahasa Korea yang bernama Edlina Adiaty. Film yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pelukis wanita yang terpaksa menjadi laki-laki itu berkesimpulan akhir pada terwujudnya usaha atas pengungkapan rasa cinta tokoh utama wanita yang bernama Shin Yun Bok kepada pria yang disukainya. Tokoh wanita ini mampu menginspirasi para wanita untuk tidak malu untuk mengungkapkan keinginannya. 1.5 Landasan Teori Untuk mendapatkan hasil analisis yang maksimal berdasarkan permasalahan yang diutamakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan landasan teori yang tepat untuk mengungkapkan maksud penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu, untuk mengungkapkan permasalahan perempuan yang tercermin dalam karya sastra secara komprehensif, penelitian ini menerapkan teori kritik sastra feminis untuk menguraikan ide-ide feminis yang terkandung dalam sebuah film yang diciptakan dari realitas sosial masyarakat Korea pada saat itu. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan kondisi sosial khususnya pada kaum perempuan di Korea pada era tahun 1990-an. Sejak berlangsungnya gerakan feminis di negara Barat, kaum wanita yang melakukan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas juga mulai berkembang, khususnya sekitar tahun 1960 (Ihromi, 1995: 14). Feminisme sebagai suatu gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan kaum suffrage, yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik mengenai kondisi kehidupan maupun tentang status dan perannya. Inti perjuangan kaum suffrage adalah pergolakan kaum sosialis yang menyadari bahwa di dalam masyarakatnya ada suatu golongan manusia yang belum terpikirkan nasibnya. Feminis itu sendiri berasal dari kata ”Femme” (woman), berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial (Ratna, 2004: 184). Tujuan feminis menurut Ratna (2004: 184) adalah keseimbangan interelasi gender. Feminis merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan yang dominan, baik dalam tataran politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial lainnya. Pada dasarnya gerakan feminisme ini muncul karena adanya dorongan ingin menyetarakan hak antara pria dan perempuan yang selama ini seolah-olah perempuan tidak dihargai dalam pengambilan kesempatan dan keputusan dalam hidup. Perempuan merasa terkekang karena superioritas laki-laki dan perempuan hanya dianggap sebagai “bumbu penyedap” dalam hidup laki-laki. Adanya pemikiran tersebut tampaknya sudah membudaya sehingga perempuan harus berjuang keras untuk menunjukkan eksistensi dirinya di mata dunia. Gerakan feminis sudah berkembang pesat pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, yang merupakan suatu gerakan politik di beberapa negara barat tertentu. Sedangkan ciri lain yang bisa menandai tahun 1960 ialah bahwa gerakan politik dan kegiatan akademis yang memilih perempuan sebagai fokus perhatiannya dianggap sebagai tahap pertama dari perkembangan kajian wanita. Sebagai kelanjutan dari anggapan ini, maka yang dianggap sebagai inti pandangan feminisme ialah setiap perempuan juga perlu mempunyai hak untuk dapat memilih apa yang menurut ia baik. Artinya, yang baik bukan yang ditentukan kaum lelaki atau orang lain baginya sebagai perempuan. Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Kritik sastra feminis seperti yang disebutkan dalam Reading as A Woman oleh Millet bukan berarti pengkritik wanita, kritik tentang wanita, atau kritik tentang pengarang wanita melainkan bertugas untuk menganalisis ide-ide pengarang tentang perempuan dalam karya sastra. Reading as A Women menurut Culler yaitu menghindari melihat suatu karya sastra dari sudut pandang pembaca laki-laki tetapi mengidentifikasi dan mengoreksi suatu karya sastra dari sudut pandang wanita. Arti sederhana yang dikandung adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus; kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai wanita berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris atau patrialkal, yang sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra. Perbedaan jenis kelamin pada diri penyair, pembaca, unsur karya dan faktor luar itulah yang mempengaruhi situasi sistem komunikasi sastra. Endraswara mengungkapkan bahwa dalam menganalisis karya sastra dalam kajian feminisme yang difokuskan adalah kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan dan memperhatikan faktor pembaca sastra (.Endraswara 2003: 146 via Evita). Jika pada mulanya penelitian feminis mengenai media meneliti “citra tentang perempuan”, maka sejak pertengahan tahun 1970-an dan seterusnya, banyak feminis yang bergelut dengan film, media dan kajian budaya mulai mengalihkan perhatiannya pada „citra untuk perempuan‟ (Brunsdon 1991, 365). Film perempuan sudah menjadi kategori penting dalam industri perfilman karena target penontonnya perempuan, suatu strategi yang sering dikaitkan dengan sinema Hollywood „klasik‟ tahun 1930-an, 1940-an dan 1950-an. Oleh karena alasan ini, film-film dari periode inilah yang menarik sebagian besar perhatian kritikus feminis. Meskipun ada fakta yang menyebutkan bahwa film perempuan sebagai suatu kategori berkaitan juga dengan berbagai macam genre, tapi masih memungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah ciri-ciri utama yang memberikan koherensi pada kategori film perempuan ini. Misalnya, Maria La Place berpendapat bahwa film perempuan dibedakan oleh tokoh utamanya yang perempuan, sudut pandang perempuan dan narasinya yang sering kali berkutat di sekitar realisme tradisional pengalaman perempuan seperti keluarga, rumah tangga, percintaan, emosi, dan pengalaman yang terjadi sebelum munculnya tindakan atau peristiwa. Salah satu aspek terpenting dari genre ini adalah adanya suatu tempat mencolok yang sesuai dengan hubungan antara perempuannya. (1987, 139). Patricia White berpendapat, film perempuan menghubungkan fokus pada “penggambaran perempuan” dalam kritik sosiologis, yang menjadi keprihatinan sinefeminis, dengan “figur perempuan” (1998, 122). Bagi Rosen, film „merefleksikan perubahan citra perempuan yang terdistorsi: „Cinema Women (perempuan dalam sinema) adalah Popcorn Venus (pemanis), hybrid distorsi budaya yang menyenangkan tetapi tidak substansial‟ (Rosen 1957, 13). Rosen mengatakan bahwa citra feminin yang „salah‟ ini mengisi kepala (kosong) para penonton perempuannya. Haskell juga berpendapat senada, bahwa film tidak hanya merefleksikan „defenisi peran yang diterima masyarakat‟ tetapi juga memaksakan definisi feminitas yang sempit ini (1987): “Film adalah lahan yang kaya akan penggalian stereotipe perempuan….” kalau kita melihat ada stereotipe dalam film, hal ini terjadi karena stereotipe ada dalam masyarakat‟ (Hollows 2000: 30). Meskipun film-film di masa lalu merefleksikan perilaku kemasyarakatan bahkan terkadang memberikan inovasi pada perilaku kemasyarakatan tersebut, tetapi sejak tahun 1950-an film memperlihatkan adanya „keretakan kredibilitas‟ dan menjadi lebih merendahkan perempuan dibandingkan masyarakat sendiri (Hollows 2000: 37). Sama buruknya, sebagai proyeksi nilai-nilai laki-laki (Hollows 2000: 39), film pada tahun 1960-an menanggapi tuntutan perempuan akan kesetaraan dengan serangan balik: sinema menjadi lebih kasar terhadap perempuan dan „pelecehannya terhadap perempuan sangat monolitik (Hollows 2000: 370). Namun Heskell menemukan suatu gambaran yang lebih kontradiksi tentang perempuan dalam film perempuan tahun 1940-an dan mencoba mencari tahu mengapa film-film disepelekan, melalui kaitannya dengan perempuan. Sebagaimana Rosen mengungkapkan adanya perayaan akan kekuatan perempuan dalam beberapa film ini, Haskel juga mengungkapkan bahwa film-film ini tidak hanya menempatkan perempuan „di pusat semesta‟ (1987, 155) tetapi juga memperlihatkan bahwa ranah pribadi dan hubungan pribadi adalah hal penting dan bukan hal sepele. Haskell dan Rosen beranggapan bahwa „pesan‟ suatu film dapat ditransmisikan tanpa masalah kepada penonton yang pasif. Namun, penekanan Haskell dan Rosen saat mengupas hubungan antara teks film diproduksi dan dikonsumsi masih merupakan hal penting. Terlebih, Haskell khususnya, mengungkapkan bahwa daripada feminitas menjadi entitas yang monolitik dan transhistoris, maka dinegosiasikanlah gagasan feminitas yang berbeda-beda dalam film baik di antara maupun di dalam periode historis. Sejak tahun 1971, hubungan antara feminisme dan film sudah dimantapkan dengan peluncuran jurnal film feminis pertama, Women and Film di Amerika, organisasi festival film feminis, dan produksi dokumenter feminis (Thornham 1977, 12-13). Feminis pada periode itu menggandrungi film dokumenter seakan film dokumenter adalah praktik film yang bisa merepresentasikan perempuan dan perkara feminis dengan sangat „akurat‟ dan „jujur‟. Praktek dokumenter ini mendapatkan kritikan yang sama dengan kritik „citra perempuan‟ yang menganggap bahwa makna film feminis transparan dan memiliki „kebenaran‟ yang bisa dikomunikasikan tanpa masalah kepada penontonnya (Kuhn 1982, 149; Citron 1988, 52). Lagi pula posisi ini mengistimewakan sutradara/penulis sebagai orang yang berpengetahuan, oleh sebab itu menghasilkan berbagai pemikiran tentang efek media berdasarkan teori budaya massa (Kaplan 1983, 127). Pemikiran ini menciptakan hierarki yang memosisikan pembuat film feminis sebagai perempuan yang tahu dan dapat mengungkapkan kebenaran kepada para penonton yang tidak begitu tahu. Untuk menganalisis permasalahan perempuan, di Barat telah dikembangkan beberapa perspektif yang masing-masing perspektif mencoba mendeskripsikan keterbelakangan atau opresi yang dialami oleh kaum perempuan. Perspektif feminis tersebut antara lain adalah feminisme liberal, feminisme Marxis, feminisme radikal, feminisme psikoanalisa, feminisme sosialis, dan feminisme eksistensialis (Ihromi 1995: 85). Kelima persfektif yang terakhir merupakan perspektif yang bereaksi terhadap feminisme liberal. Oleh karena itu, Tong mengajak untuk menganalisis feminisme liberal terlebih dahulu sebelum mengenali lebih lanjut kelima perspektif feminis yang terakhir. Feminisme liberal pertama kali dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft (1959-1799) dalam tulisannya A Vindication of the Rights of Women (feminis liberal abad ke-18) dan John Stuart Mill dalam tulisannya The Subjection of Women (feminis liberal abad ke-19), Kemudian Betty Friedan dalam tulisannya The Feminine Mystique dan The Second Stage. Penekanan mereka adalah subordinasi wanita berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi wanita untuk masuk ke lingkungan publik. Masyarakat beranggapan bahwa karena kondisi alamiah yang dimilikinya, wanita kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan pria. Dengan pemikiran tersebut, wanita dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik. Namun hal tersebut dibantah oleh feminisme liberal yang mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal tentang hakikat manusia. Tong berkesimpulan bahwa kaum feminis liberal ini berkeinginan agar manusia, pria dan wanita mengembangkan kepribadian yang androgini (suatu pendekatan konseptual yang tidak mengaitkan derajat hierarki dengan jenis kelaminnya). Feminis Marxis adalah reaksi terhadap pemikiran feminis liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peranan wanita. Paham ini berpendapat jika ketertinggalan yang dialami oleh wanita bukan disebabkan oleh tindakan individu. Bertolak dari konsep Marxis tentang hakikat manusia (human nature) dan teori Marxis tentang masyarakat, ekonomi dan politik, serta teori Engels tentang keluarga dalam The Origin of the Family, Private Poverty and The State, perspektif ini mencoba untuk memahami mengapa perempuan tidak pernah memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum lelaki, dengan menganalisis hubungan antara status pekerjaan perempuan dengan citra dirinya. Oleh karena itu, tidak sedikit feminis Marxis yang mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah reproduksi (misalnya kehamilan, kelahiran dan mengasuh anak) dan sekaligus seksualitas wanita (misalnya pornografi, pelacuran). Jika feminis Marxis memfokuskan perhatiannya pada permasalahan wanita yang berhubungan dengan pekerjaan wanita, Feminis radikal memberikan perhatiannya kepada permasalahan wanita yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas wanita. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki, yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan wanita. Oleh karena itu, sistem patriarki ini tidak hanya harus dirombak, tetapi harus dicabut dari akarnya. Feminis radikal ini sebetulnya bereaksi terhadap mereka yang anti-feminis yang berpendapat bahwa keadaan biologi wanita yang berbeda dari pria adalah kehendak alam yang tidak dapat diubah yang merupakan takdir atau kodrat. Menurut feminis radikal, keteraturan alamiah tidak perlu dipertahankan karena hal tersebut hanya akan menghambat kemajuan wanita saja. Feminisme Psikoanalisis ini bertolak dari teori Freud yang menekankan seksualitas adalah unsur yang krusial dalam pengembangan hubungan gender. Perbedaan ini berakar pada perbedaaan psyche wanita dan pria. Perbedaan psyche wanita dan pria berbeda disebabkan oleh perbedaan biologi antara kedua jenis kelamin. Menurut Freud, anak dalam perkembangannya menjadi manusia dewasa, harus melewati beberapa tahapan perkembangan psikoseksual. Temperamen mereka setelah dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka melalui tahapan perkembangan psikoseksual tersebut. Feminisme Sosialis muncul karena ketidakpuasan terhadap analisis feminis Marxis yang pada intinya berdasarkan pada pemikiran Marxis yang buta gender. Artinya, masalah kelas sosial tidak ada sangkut pautnya dengan masalah gender yang hidup dalam masyarakat. Munculnya perspektif ini juga karena ketidakpuasan terhadap analisis feminis radikal psikoanalisis. Asumsi yang digunakan oleh feminis sosialis adalah hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan wanita. Selain di negara kapitalis, di negara-negara sosialis, para wanitanya juga terjun dalam pasaran tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Namun, dalam kenyataannya mereka masih hidup dalam kungkungan sistem patriarki. Untuk mengatasi keterbatasan perspektif feminis Marxis, feminis radikal dan feminis psikoanalisis, feminis sosialis mengembangkan 2 pendekatan yang berbeda yaitu „dual system theory’ yang dibagi menjadi 2 yaitu suatu teori yang menggabungkan penjelasan tentang patriarki yang non-matrealis dengan penjelasan kapitalisme yang matrealis dan unified-system theory sebagai contoh pembagian kerja berdasarkan gender sebagai konsep tunggal. Teori yang pertama menjelaskan bahwa patriarki dan kapitalisme adalah bentuk-bentuk hubungan sosial khusus, yang apabila keduanya sama-sama berkembang dan berlaku akan menindas wanita lebih buruk lagi. Teori pertama yang menjelaskan kapitalisme sebagai struktur materil yang secara historis berakar dalam „mode of production’ (cara bagaimana produksi dilakukan), yang digabungkan dengan teori yang menjelaskan patriarki sebagai struktur materil yang secara historis berakar dalam mode of production/sexuality. Teori sistem berganda ini dikembangkan oleh Heide Hartmann dalam bukunya The Unhappy Marriage Between Marxism and Feminism. Sebaliknya, Unified-systems theory mencoba menganalisis kapitalisme dan patriarki secara bersama-sama dengan menggunakan satu konsep. Menurut teori ini kapitalisme dan patriarki tidak dapat dipisahkan, seperti halnya pikiran yang tidak dapat dipisahkan dari badan. Mereka yang mengembangkan teori ini adalah Irish Young dalam tulisannya Beyond Unhappy Marriege Nature. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang lazim terjadi. Menurut Diarsi (La Pona dkk., 2002: 9), hal ini dipicu oleh relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran antara hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. Fakih (1997: 17) menyatakan bahwa kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, disebabkan oleh anggapan gender. Fakih menyebutnya sebagai gender-related violence. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan (Fakih 1996: 8). Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender menjadi ketentuan Tuhanseolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaanperbedaan gender yang dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Fakih (1996) menyatakan jika perbedaan gender (gender differences) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (gender role) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tidak digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender, banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan seperti: pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum permpuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa „menganggap penting‟ kaum perempuan. Ketiga, pelabelan negatif (stereotipe) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotipe merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender lain. Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilekatkan kepada mereka. Keempat, kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun intergritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat menyebabkan munculnya bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender seperti pemerkosaan, pemukulan dan serangan fisik dalam ranah domestik, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana, serta pelecehan seksual (Fakih, 1997: 17-20) Espiritu (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:8) mengatakan bahwa secara struktural, kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi penundukan yang berbasis kelas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih inferior dibandingkan dengan laki-laki. Secara kultural, budaya patriarki memberikan legimitasi terhadap keniscayaan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan secara seksual menurut Skaine (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002: 9) disebabkan oleh kecenderungan kaum laki-laki dalam menempatkan diri sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Oleh karena itu kaum laki-laki memberlakukan mekanisme kontrol terhadap perempuan yang oleh Sheffield disebut sebagai sexual terrorism, yakni sistem ideologi yang diberlakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang termanifestasikan melalui kekerasan (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:9). Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai kekerasan fisik, salah satunya adalah Meiyenti (1996: 6-7) yang menjelaskan jenis-jenis kekerasan fisik yang melibatkan penggunaan alat atau anggota tubuh seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang atau senjata. Kelima, karena peran gender perempuan adalah sebagai pengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (burden). Menurut Bhasin, laki-laki mengontrol produktivitas perempuan di dalam dan di luar rumah tangga, dalam kerja bayaran. Di dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua pelayanan untuk anak-anak, suami dan anggota keluarga lainnya, sepanjang hidupnya. Hal ini oleh Sylvia Walby (Bhasin, 1996: 5) disebut sebagai “mode reproduksi patriarkal” karena kerja perempuan diperas oleh suami dan orang lain yang tinggal disana. Menurut Walby, perempuan adalah kelas yang memproduksi, sementara suami adalah kelas yang mengambil alih produksi, kerja berulang-ulang tanpa akhir yang sangat melelahkan, sama sekali tidak dianggap kerja dan ibu rumah tangga dianggap tergantung pada suami. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga mengasuh anak. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu “terisolasi” kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. 1.6 Metode Penelitian Sehubungan dengan judul penelitian yaitu “Bias Gender dalam film A Hot Roof karya Kim Min Yeong ”, maka penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini banyak menggunakan data dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini memiliki metode penelitian sebagai berikut: a. Menentukan objek formal penelitian yaitu ide-ide feminis b. Menentukan objek penelitian berupa film berjudul “A Hot Roof” yang disutradai oleh Lee Min Yeong pada tahun 1995. Objek material sebagai acuan utama untuk memperoleh dan memproses analisis data. c. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan . Studi kepustakaan digunakan untuk mencari informasi yang berguna dan mendukung penelitian. Sumber tertulis yang digunakan sebagai referensi adalah buku, disertasi, thesis, makalah, jurnal, artikel serta skripsi yang berhubungan dengan tema. Metode pengumpulan data tentang proses produksi film, komentar publik seputar film A Hot Roof selain didapat dari sumber pustaka juga didapat dari sumber internet. d. Metode analisis data dilakukan dengan mengolah objek penelitian yaitu film A Hot Roof dari data berupa audio visual menjadi teks serta transkripsi dan transliterasi dialog film A Hot Roof. Data yang telah dipeoleh tersebut kemudian dianalisa berdasarkan kritik sastra feminis dan menemukan ide-ide feminis yang terdapat dalam film tersebut. e. Membuat kesimpulan akhir sebagai laporan dari hasil akhir penelitian yang diharapkan dapat menjawab secara ringkas mengenai isi pembahasan analisis film A Hoot Roof. 1.7 Sistematika Penyajian Sistematika penyajian hasil penelitian iini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari: a. Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian. b. Bab II berupa identifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam film A Hot Roof yang penyajiannya dibagi menjadi dua bagian yaitu tokoh profeminis dan kontrafeminis. c. Bab III berupa manifestasi ketidakadilan gender dalam film A Hot Roof. Keterbatasan pilihan yang dimiliki perempuan berdasar atas status sosialnya dalam masyarakat serta manifestasi ketidakadilan gender yaitu kekerasan, stereotipe dan subordinasi serta penjelasan beberapa adegan yang mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender. d. Bab IV berupa ide-ide feminis sebagai intisari dari film A Hot Roof dalam perannya sebagai rejeksionis terhadap ketidakadilan gender pada masanya. e. Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.