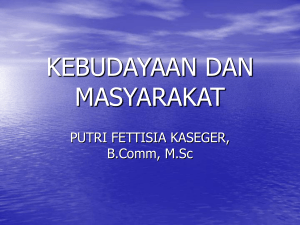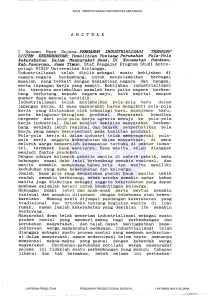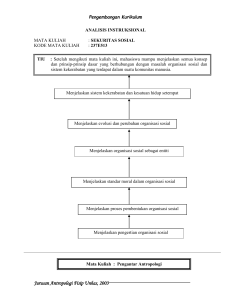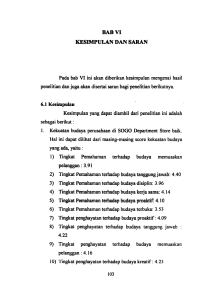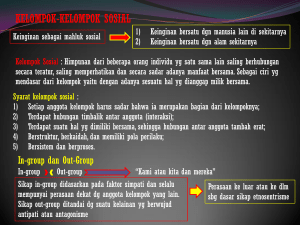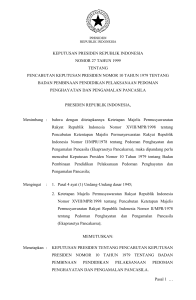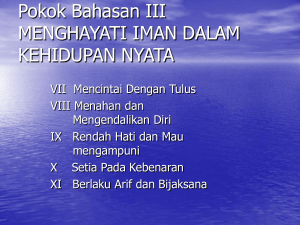Modal Spiritual Kekuatan Tersembunyi di Balik Kemampuan
advertisement

Bab 1 TINJAUAN MODAL SPIRITUAL DALAM PEMBANGUNAN D inamika pembangunan di setiap daerah memiliki kekhasannya tersendiri. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menyajikan sebuah sintesa teori kontekstual untuk situasi pembangunan dalam masyarakat yang komunal, memiliki penghayatan spiritual yang tinggi, dan di wilayah yang memiliki orbitasi rendah terhadap pemerintahan pusat. Hal penting yang ingin ditekankan dalam tulisan ini adalah bahwa modal spiritual sungguh penting dan relevan bagi pembangunan di Indonesia karena masyarakatnya yang memiliki penghayatan spiritual. Banyak teori pembangunan yang berbicara pada level negara dengan berbagai indikasi makro, dan kemajuan pembangunan umumnya dikaitkan dengan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Hofman 2004, Steiner 2006, Werner 2006, Arestis et al. 2007). Namun, tulisan ini justru hendak membicarakan pembangunan dengan berangkat dari sebuah kampung yang terpencil dan terabaikan dalam pembangunan. Alasan utama, kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan berada di level akar rumput, bukan di level negara. Dengan mengacu kepada Lebret, Goulet (2006) mengungkapkan kemajuan pembangunan dilihat dari adanya peningkatan kreativitas masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup lewat segala pengorbanan mereka. Pemenuhan kebutuhan ini tidak lain merupakan usaha untuk mencapai kebebasan sejati yang dapat dinikmati oleh setiap orang 5 (Sen 2000:18). Hal ini diteguhkan pula oleh Yapa (2006) yang membahas pendapat Ariyaratne bahwa pembangunan bukan sekedar diukur dari pertumbuhan material melainkan melibatkan pula perkembangan dimensi psikologis, moral, dan spiritual, sebagaimana dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pembangunan yang melulu berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi bukanlah pembangunan yang sesungguhnya karena tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat untuk menikmati kebebasannya. Kebebasan dalam hal ini bagi Sen (2000:10) dipandang sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk bertindak dan memutuskan, serta suatu peluang yang memungkinkan seseorang memperoleh kebaikan personal dan sosialnya. Di lain pihak, untuk dapat membuahkan pembangunan dibutuhkan modal. Di saat modal dari intervensi negara tidak dapat diharapkan, masyarakat di aras lokal perlu mengusahakan modal itu sendiri, atau memanfaatkan modal yang sudah mereka miliki. Dalam hal inilah modal spiritual hadir untuk menjawab tantangan pembangunan, khususnya di aras lokal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan, ternyata tak dapat digapai dengan meningkatkan kapasitas produksi semata. Muhni (1994:133) menyinggung bahwa Mosjov menyatakan pembangunan semesta adalah pembangunan yang menyeluruh meliputi kesejahteraan moral, spiritual, dan fisik manusia seutuhnya. Betapapun, manusia memegang peranan yang paling utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sekelompok masyarakat yang mempunyai jiwa sebagai insan pembangun, agen-agen perubah, untuk dapat menggapai keberhasilan dalam pembangunan. Dalam sebuah masyarakat yang komunal dan spiritualistis 4, spiritualitas mereka akan mewarnai sikap maupun gaya hidup masyarakat. Pada saat ini, pembangunan di Indonesia jarang memerhatikan modal spiritual. Pada umumnya pembangunan dikaitkan dengan politik dan ekonomi. Bahkan, secara eksplisit Presiden Indonesia periode 2009-2014 menyampaikan bahwa Indonesia perlu memiliki konsensus untuk mewujudkan kemajuan. Untuk itu dibutuhkan enam pilar, pertama adalah menjalankan demokrasi bersama penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas. Pilar kedua adalah peranan pemerintah dalam ekonomi dijalankan tetapi nilai konstruktif dalam kaidah pasar agar kompetitif tidak boleh diabaikan. Ketiga, perusahaan multinasional tidak diutamakan walau ekonomi nasional sudah terintegrasi dengan ekonomi 4 Spiritualistis dalam hal ini merupakan kata sifat dari masyarakat yang berpenghayatan spiritual tinggi. 6 internasional. Keempat, pertumbuhan ekonomi walaupun penting harus diikuti dengan pemerataan dan keadilan sosial sekaligus pemeliharaan lingkungan yang baik. Pilar kelima adalah mendorong pasar domestik, dan pilar yang terakhir adalah pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai (Kompas, 6 September 2010). Tampaklah bahwa untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan, pemerintah merencanakan konsensus yang disandarkan pada pilar-pilar politik dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang tidak memerhatikan kondisi masyarakat dapat menghancurkan kekuatan masyarakat di aras lokal 5 (Summer 1986). Oleh karena itu, diperlukan suatu pola pembangunan berbasis komunitas dengan sistem ”bottom-up” (Ife 2002:25-26). Dalam masyarakat komunal, pembangunan berbasis komunitas masyarakat ini perlu dipikirkan, lebih-lebih di saat kawasan itu berada dalam ancaman terabaikan oleh pembangunan. Tentu saja, keberadaan pembangunan berbasis komunitas ini bukan untuk menafikan peran negara. Secara lebih spesifik, tulisan ini hendak melihat bagaimana peranan modal spiritual dalam pembangunan, salah satu modal yang masih jarang dibahas dalam berbagai tulisan pembangunan (Flora 2009, Johnson 2009). Berhadapan dengan komunitas yang spiritualistis dan hidup dalam kawasan yang terpencil, mempelajari peranan modal spiritual dalam pembangunan kiranya menjadi hal yang urgen. PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN DI ARAS LOKAL Masyarakat di aras lokal mengharapkan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk tingkat lokal, tentu saja pembangunan diharapkan dari peran negara di tingkat lokal, dengan perkataan lain, pemerintah daerah. Harapan ini lebih-lebih semakin meningkat ketika daerah mereka mendapatkan otonominya. Namun, banyak fenomena yang menunjukkan bahwa pembangunan di aras lokal tersebut bisa saja meningkatkan pendapatan daerah namun belum tentu meningkatkan 5 Salah satu contohnya terjadi di Nagari Santiago, Sumatera Barat. Sebelum tahun 1984 jalan menuju kawasan tersebut terpelihara baik oleh swadaya masyarakat. Sejak konsep pemerintahan digantikan oleh pemerintahan desa masa orde baru rakyat tidak terlibat lagi dalam pemeliharaan jalan. Tahun 2001pemerintahan dikembalikan lagi kepada Nagari namun masyarakat sudah enggan bergotong royong. Bulan Juli 2010 jalan dalam keadaan rusak berat, penuh lumpur dan berlubang, sehingga tidak dapat lagi dilalui kendaraan. (Kompas, 25 Juli 2010) 7 kesejahteraan rakyat. Mala (2001) melalui penelitiannya di Nepal menemukan fenomena tersebut. Dikatakannya pemerintah tidak bersifat netral karena memiliki kepentingannya sendiri dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengejar kepentingan tersebut dan dengan demikian, pembangunan menjadi terabaikan. Diuraikan oleh Mala bagaimana segala ”tujuan tak resmi” yang dikejar oleh petahana inilah yang mengemudikan perilaku pemerintah dalam pembangunan. Tak heran jika kemudian timbul ungkapan yang menyatakan negara menjadi aktor utama penghambat pembangunan (Antlöv 2001). Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat berakhir hanya sampai di pertumbuhan ekonomi saja (Martinussen 1995). Kehadiran negara yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat, atau tidak meningkatkan kebebasan bagi masyarakat menurut Sen (2000), justru mengakibatkan peran negara dalam pembangunan kurang terasa (Michie 1981, Antlöv 2000, Mala 2001). Jelaslah di sini berbagai penelitian mendukung bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Sekalipun negara hadir di suatu daerah dan kiprahnya cukup aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, namun bila semua itu tidak efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di aras lokal, seolah negara tidak pernah hadir di sana. Memang, tidak bisa diluncurkan tuduhan yang menggeneralisasi bahwa negara yang peranannya kurang terasa dalam pembangunan adalah negara yang mementingkan kepentingan pribadi para kaum elite pemerintahannya. Demikian pula yang terjadi dengan pemerintahan di aras lokal. Bisa saja para aktor pembangunan memiliki dedikasi yang besar dalam pembangunan namun tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kiprahnya justru membawa ketidaksejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini terjadi jika pemerintah melakukan pembangunan tanpa melihat kondisi masyarakatnya. Mereka seolah membuat keputusan-keputusan dalam kegelapan sehingga akibatnya justru fatal. Goulet (2006) mengamati banyak aktor pembangunan yang bukannya mengambil resiko penuh perhitungan melainkan memaksakan diri mengambil resiko buta. Menurutnya, hal ini terjadi karena para elite tersebut kehilangan prinsip-prinsip penuntun etis, khususnya dalam hal pembangunan. Para pemikir politik masa kini cenderung untuk menjalankan politik tanpa etika atau mengejar keadilan yang samar karena tertutup aura utopia sebab tak mengakar pada dunia nyata. Pola pembangunan ini sebetulnya tergantung dari kebijakan pimpinannya. Beberapa negara memaksakan penarikan sejumlah besar sumber 8 daya namun menyediakan sedikit sekali untuk kebutuhan orang banyak. Cukup beralasan jika negara semacam ini disebut oleh Evans (1989) sebagai Negara Predator. Kaum Elite penguasa sistem yang ada di negara tersebut melakukan perampokan besar-besaran tanpa memerhatikan kesejahteraan masyarakat umum. Jenis negara yang kedua adalah negara yang mampu memfasilitasi kaum swasta untuk berkembang melalui entrepreneurship. Negara seperti ini disebut oleh Evans sebagai Negara Pembangunan. Negara Predator hingga Negara Pembangunan sebetulnya merupakan kontinuum, sehingga banyak negara yang berada di antara keduanya. Yang jelas, kehadiran Negara Predator akan membuat pembangunan absen bagi masyarakatnya. Seberapa besar peranannya dalam pembangunan, tergantung pada posisinya dalam garis kontinuum tersebut. Berdasarkan seluruh uraian di atas, ada dua macam kemungkinan penyebab kurang terasanya peranan negara dalam pembangunan di aras lokal. Kemungkinan pertama adalah karena para elite pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri daripada kesejahteraan masyarakat banyak. Kemungkinan kedua adalah karena pola pemerintahan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kedua kemungkinan ini berada di dalam garis kontinuum yang mendekat ke kategori Negara Predator. Namun, tulisan ini hendak menambahkan sebuah alasan yang lain lagi. Peranan negara tidak terasa signifikan dalam pembangunan di aras lokal karena pemerintah daerahnya masih “terlalu muda” masa kerjanya. Kawasan penelitian berada dalam sebuah kabupaten yang belum lama mendapatkan otonominya, bahkan Bupati pertamanya baru menjalankan masa satu tahun jabatannya. Dengan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, pemerintah daerah harus menentukan prioritas daerah-daerah dan sektor-sektor mana saja yang harus dibangun. 6 Konsekuensinya, akan ada banyak daerah yang tidak menjadi prioritas, berada di bawah ancaman terabaikan oleh pembangunan, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, di saat negara tidak dapat lagi diharapkan untuk melakukan pembangunan, diperlukan sebuah solusi yang lain, yaitu pembangunan berbasis komunitas masyarakat. 6 Kondisi umum pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada lampiran. 9 PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS Pada saat peran negara dalam pembangunan kurang dirasakan dampaknya secara signifikan, perlu dilakukan suatu usaha pembangunan melalui kelembagaan di tingkat komunitas tanpa menafikan peran negara. Walaupun demikian, hal ini juga tidak terlalu mudah. Pada saat pola pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tetap dipaksakan, terjadilah suatu relasi vertikal yang kuat antara negara dan masyarakat pedesaan (Summers 1986). Relasi vertikal ini dapat membuat suatu komunitas masyarakat pedesaan tak berdaya menghadapi dunia yang jauh lebih kuat dan lebih luas dengan adanya urbanisasi, industrialisasi, birokrasi, dan sentralisasi. Suatu perubahan sosial yang terjadi secara makro tersebut seolah telah merampas otonomi masyarakat lokal dalam membuat keputusannya sendiri dan seolah mereka terhisap dalam masyarakat yang lebih luas. Masalahnya adalah masyarakat kecil ini terhisap untuk menjadi semakin tak berdaya karena terdampar dalam dunia global yang melampaui kekuatan dan kemampuan mereka. Di lain pihak, sejarah mencatat pula banyaknya pembangunan yang bersifat top-down atau melalui pendekatan blue-print akhirnya gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Adams 2001). Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun sebuah basis yang kuat di tataran horisontal untuk dapat bertahan hidup. Lebih-lebih, di tengah dunia yang berubah dengan cepat, proses pembangunan perlu menyesuaikan diri baik secara materiil maupun spiritual (Kartodirdjo 1994:4). Pembangunan ini perlu bergerak dalam komunitas kelembagaan masyarakat sehingga menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan rakyat (Uphof 1986, Ife 2002). Istilah pembangunan yang bottom up sebetulnya sudah lama dicetuskan oleh Mahatma Gandhi (Singh 2006). Beliau mengatakan bahwa dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan setiap orang. Setiap desa sesungguhnya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga setiap orang menemukan tempat yang ideal untuk tinggal di desanya. Oleh karena itu, Gandhi tidak menganjurkan politik ekonomi makro. Setiap desa harus berusaha mencukupi dirinya sehingga yang terjadi adalah pembangunan bottom up, bukan top down. Sebuah pembangunan baru dapat berhasil apabila didasarkan pada pengertian politik dan ekonomi lokal, dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat (Adams 2001). Dengan adanya pembangunan yang berbasis masyarakat, pembangunan bukan lagi sesuatu yang jauh dari pusat, tetapi lebih ”mendarat”, bergerak langsung di tengah-tengah orang miskin. 10 Melalui pembangunan yang berbasis masyarakat ini, pembangunan dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dilakukan langsung di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, harapannya pembangunan dapat menjadi milik rakyat yang dapat dinikmati oleh rakyat (public good). Pendekatan pembangunan berbasis komunitas ini cukup panjang lebar disampaikan oleh Ife (2002). Pendekatan tersebut dapat menjadi sebuah teori yang menjanjikan karena kelembagaan masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apa pun. ”Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memedulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhankebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan.” (Soerjono Soekanto 1982) Kalau dicermati, setiap daerah memiliki kelembagaan lokal yang melibatkan para penduduk lokal. Ada nilai-nilai yang disepakati bersama, ada kearifan lokal yang berlangsung turun temurun, semua itu membentuk suatu budaya dan adat istiadat yang khas di tempat tersebut. Setiap perilaku sosial di suatu tempat dipengaruhi oleh ide-ide, pola-pola kebudayaan, dan mitos-mitos yang berkembang di sana. Semua nilai ini membuahkan norma yang dihidupi bersama dan menjadi dasar regulasi dalam kehidupan mereka. Regulasi tersebut mengatur perilaku sosial sekaligus interaksi sosial di antara masyarakat. Dengan adanya norma ini, masyarakat terikat dalam satu komitmen satu sama lain sehingga memunculkan saling percaya di antara mereka dalam sebuah jaringan komunitas masyarakat. Di sebagian tempat, kelembagaan lokal itu terungkap dalam kehidupan bermasyarakat yang terorganisir dengan adanya ketua suku dan para pembantunya. Sementara di beberapa tempat lainnya lebih bersifat egaliter, namun hidup dalam suatu komunitas yang erat seperti klan-klan kecil. Kekerabatan mereka yang berupa jaringan ini dapat menjadi sebuah modal sosial pula. Memang ada banyak kritik dan keberatan terhadap layanan berbasis masyarakat ini. Kritik yang cukup tajam disampaikan oleh John Friedman (Martinussen 1995:292) yang mengatakan bahwa pengembangan masyarakat ini merupakan pendekatan romantik dan khayalan yang dilebih-lebihkan. Ia mengatakan bahwa pendekatan ini berasumsi bebas dari konflik dan komunitas masyarakatnya homogen. Padahal, dalam kenyataannya terjadi banyak konflik kepentingan, ketidaksetaraan dalam banyak hal, diskriminasi perempuan, dan sebagainya. 11 ”Sungguh naif jika percaya bahwa pembangunan alternatif tersebut dapat diciptakan dan dibuat berkelanjutan (sustainable) di tingkat komunitas yang kecil, dan keberadaannya dapat menjadi oposisi yang konsisten terhadap pemerintah negara. Sekalipun pembangunan ini dimulai secara lokal, tidak akan berakhir secara lokal juga. Tanpa bantuan pemerintah negara, kebanyakan masyarakat miskin tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.” (Friedman 1992 dalam Martinussen 1995:292) Bagaimanapun, ide yang disampaikan oleh Ife (2002) cukup menarik, karena ia menawarkan suatu pembangunan yang holistik. Sebuah pendekatan yang kontekstual karena pengembangan masyarakat dilakukan dengan memerhatikan nilai-nilai yang berada di akar rumput, entah itu budaya, spiritual, maupun ideologi yang selama ini dihidupi oleh masyarakat. Walaupun demikian, pendapat Friedman (Martinussen 1995:292) tidak dapat diabaikan begitu saja. Pembangunan berbasis komunitas masyarakat tidak dimaksudkan untuk menafikan peran negara. Situasi yang ideal justru tercipta jika terjadi pembangunan baik dari pihak negara maupun masyarakat, sejauh ada kesinkronan antara keduanya. PENGERTIAN MODAL SPIRITUAL Saat ini, dunia ilmu pengetahuan sudah mulai melihat bahwa penelitian mengenai modal spiritual adalah sesuatu yang urgen. Bahkan, dikatakan modal spiritual merupakan kaki yang hilang dari pembangunan ekonomi dan harus digabungkan dengan kedua kaki lainnya, yaitu modal sosial dan modal personal 7 (Malloch 2003). Pendapat Malloch ini menegaskan bahwa modal spiritual selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Belakangan ini sudah mulai bermunculan berbagai penelitian mengenai modal spiritual walaupun belum terlalu banyak. Meskipun istilah modal spiritual ini sudah mulai digunakan dalam dunia ilmiah, namun tampaknya belum ada kesepakatan mengenai apakah pengertian modal spiritual itu sebenarnya. Cukup banyak yang merumuskan modal spiritual dengan mengaitkan nilai-nilai. Davies & Guest (dalam Flanagan 2007) mengatakan bahwa istilah modal spiritual dimengerti sebagai keterkaitan iman religius dengan penggunaan sumber-sumber budaya. Modal spiritual merupakan kompetensi spiritual yang mengalirkan nilai-nilai seperti pelayanan, mementingkan orang lain, bijaksana, berbudi, dan berbagai nilai yang dibangun secara implisit oleh religi. Sementara Zohar (2004) memandang modal spiritual mengambil satu 7 Modal personal di sini merupakan terjemahan bebas dari human capital. 12 tahap yang lebih tinggi dan lebih luas daripada “modal” lainnya. Modal spiritual menjadi batu karang yang menyangga modal-modal yang lain. Modal spiritual mengandung komoditas perubahan dalam pemaknaan, visi yang menginspirasikan, keluhuran, yang kesemuanya itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Melalui penelitiannya di Amerika Serikat, Zohar (2004) mengungkapkan modal spiritual ini juga ada di dalam sebuah bangsa. Pada saat modal spiritual rendah, masyarakat akan lebih sering sakit dan stress. Selain itu, akan ada banyak depresi, ketergantungan narkoba dan alkohol, bunuh diri, keretakan keluarga, dan banyak orang akan merasa terasing menghadapi egoisme, kriminalitas, dan pengrusakan. Dengan perkataan lain, Zohar (2004) yakin tanpa modal spiritual masyarakat akan kehilangan hatinya. Tak mengherankan, ada yang mengaitkan modal spiritual dengan hati nurani. Secara gamblang, Jauhari (2007) menyatakan modal spiritual adalah makna, tujuan, dan pandangan yang kita miliki bersama mengenai hal yang paling berarti dalam hidup. Modal spiritual bukanlah masalah agama atau suatu sistem kepercayaan, melainkan suatu kecerdasan hati nurani, diawali dengan pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun Beard (2007) dalam tulisannya mengatakan bahwa modal spiritual merupakan istilah yang merujuk kepada keuntungan positif dari pembentukan spiritualitas, psikologi, dan moralitas terhadap seseorang, organisasi, dan komunitas atau sekelompok masyarakat. Dengan demikian, modal spiritual didefinisikan sebagai stok pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan makna, nilai-nilai, dan tujuan fundamental dari individu atau budaya. Hal pendatangan keuntungan yang dikaitkan dengan modal spiritual dibicarakan juga oleh Zohar & Marshall (2004:21). Mereka berargumentasi bahwa modal spiritual mensyaratkan adanya dimensi moral dan sosial terhadap kapitalisme. Oleh karena itu, modal spiritual berbicara tentang mendatangkan keuntungan yang lebih besar dengan menjalankan bisnis melalui konteks yang lebih luas dalam makna dan nilai. Cara ini akan memberikan kesejahteraan tidak saja yang bersifat jasmaniah namun juga batiniah. Berikut ini akan diuraikan berbagai penelitian yang relevan sehingga sedikit demi sedikit dapat diperoleh gambaran mengenai apakah sebenarnya modal spiritual itu. Sesuai dengan namanya yang diawali dengan kata “modal”, peranan utama modal spiritual tidak lain adalah kebangkitan ekonomi. Walaupun berbagai penelitian mengaitkan modal spiritual dengan politik maupun struktur sosial, namun pada akhirnya modal spiritual bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebuah karya tua dan terkenal dari Weber (dalam 2006) telah mengangkat keterkaitan antara etika Protestanisme 13 dengan kapitalisme. Dalam bukunya Weber menjelaskan istilah calling dalam etika Protestan, yaitu suatu panggilan untuk memenuhi kewajiban moral seseorang dalam memenuhi tugas duniawinya. Perilaku religius ini terproyeksikan dalam aktivitas sehari-hari. Calling ini berkaitan dengan kepercayaan kaum Protestan akan takdir yang menentukan orang-orang terpilih saja yang akan memperoleh keselamatan (Weber 2006:71). Efeknya, etika ini mendorong orang untuk bekerja keras, disiplin, dan hemat agar memperoleh kekayaan yang dipercaya oleh mereka sebagai tanda berkat dari Tuhan (Weber 1958 dalam Alatas 2002:111). Bagi manusia yang masih hidup di bumi, state of grace mereka diketahui dari keadaan mereka selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semua orang berlomba untuk menjadi orang-orang terpilih sehingga mereka menjadi dinamis dan progresif. Dengan demikian, prinsip time is money yang dicetuskan oleh Benjamin Franklin mengandung muatan spiritual. Etika Protestan inilah yang akhirnya mendorong perilaku ekonomi individu dengan semangat kapitalisme sehingga melahirkan suatu kebangkitan ekonomi. Kelompok masyarakat kapitalis yang seringkali digolongkan sebagai masyarakat industri modern ini mendobrak ekonomi tradisional kuno yang berada dalam status quo. Dengan demikian, mereka menjadi sumber dinamisme dan kebangkitan ekonomi dari para masyarakat industri. Penelitian Weber ini berkaitan erat dengan masalah spiritual karena sesungguhnya perubahan askese bangsa Amerikalah yang mendukung perilaku ekonomi mereka. Askese ini khususnya yang menyangkut perolehan harta benda duniawi. Ketika masih di Eropa sebelum bermigrasi ke Amerika, umat mengalami keraguan untuk mengejar kekayaan tanpa batas karena penghayatan spiritual mereka yang tidak mendukung hal tersebut. Hal ini diamati oleh Weber dari ajaran-ajaran yang beredar di kalangan umat ketika itu, antara lain: Dia yang mencari perlindungan di bawah harta milik yang diberikan Allah, Allah akan memukulnya bahkan dalam hidup ini. Cara hidup puas diri dengan menikmati kekayaan yang sudah diperoleh hampir selalu merupakan gejala degradasi moral. Jika kita memiliki segalanya yang bisa kita miliki di dunia ini, apakah itu yang kita harapkan? Kepuasan sepenuhnya atas semua keinginan tidak bisa diperoleh di dunia karena kehendak Allah telah menetapkan demikian. (Saint’s Everlasting Rest bab 10 dalam Weber cetakan 2003:406) Demikianlah bahwa Allah memelihara kita dan aktivitas kita; kerja adalah ujung moral serta alami dari kekuatan…. Dengan cara demikianlah Allah bisa dilayani dan dihormati… Kesejahteraan umum atau kebaikan banyak orang harus dijunjung di atas kesejahteraan dan kebaikan diri kita sendiri. (Christian Directory I hal. 375-376 dalam Weber cetakan 2003:406) Pada zaman itu, beberapa sinode di Belanda juga mengutuk dengan keras segala bentuk pencarian impulsif terhadap kekayaan. Diceritakan oleh Weber (dalam 14 2003:405-406) bahwa pada tahun 1574 Sinode Belanda Selatan menyatakan rentenir tidak boleh diterima ke dalam persekutuan meskipun diizinkan oleh hukum. Pada tahun 1958, Sinode Provinsial Deventer memperluas hal ini kepada para pegawai rentenir. Sinode Gorichem tahun 1606 mendeskripsikan persyaratan yang sangat berat dan merendahkan bagi para istri lintah darat, dapat diterima. Setelah hidup di Amerika, perlahan-lahan keraguan untuk mengejar harta duniawi ini terkikis. Time is money yang dicetuskan oleh Benjamin Franklin memiliki pengertian spiritual karena satu jam yang terbuang percuma berarti membuang kesempatan untuk bekerja demi memuliakan Tuhan. Dengan demikian, mencari keuntungan untuk menumpuk kekayaan pribadi menjadi hal yang baik. Bahkan, jika Tuhan menunjukkan jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan jalan yang lainnya, itu merupakan panggilan. Menolak jalan tersebut dengan memilih jalan lain yang keuntungannya lebih sedikit berarti menghilangkan salah satu tujuan panggilan, menolak untuk menjadi pelayan Tuhan, dan menolak pula untuk menerima anugerah Tuhan. Kepercayaan yang tertanam saat itu adalah manusia dapat menjadi kaya bagi Tuhan walau bukan untuk daging dan dosa (Weber dalam 2003:231-238). Hilangnya keraguan untuk mengejar kekayaan yang berkaitan dengan penghayatan spiritual inilah yang akhirnya mengubah perilaku ekonomi bangsa Amerika dan membangkitkan kapitalisme. Sebab jika ada kenyataan bahwa Tuhan, yang kekuasaan-Nya dilihat oleh kaum Puritan dalam setiap kejadian dalam kehidupan, menunjukkan kepada salah satu dari umat pilihan-Nya suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka umat itu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, orang Kristen yang beriman harus menuruti panggilannya dengan memanfaatkan segala keuntungan dari setiap kesempatan yang ada (Baxter dalam Weber cetakan 2003:238). Kebangkitan ekonomi di kalangan masyarakat Jatinom, Jawa Tengah, juga tidak lepas dari penghayatan spiritual masyarakatnya (Abdullah 1994:145). Diungkapkan bahwa masyarakat Jatinom memercayai Allah Yang Esa sehingga para pengusaha di Jatinom merasa mereka harus membangun nilai-nilai budaya Islam melalui bekerja dengan bantuan rahmat Allah. Segala perjuangan dan pengorbanan diikuti oleh ketaatan, ketulusan, dan devosi kepada Allah. Pengajaran spiritual Islam mereka terjemahkan dalam kegiatan ekonomi mereka, yaitu san (lurus), opén (tekun memelihara), dan tlatén (rajin). San dalam arti mereka tidak malu melakukan pekerjaan apapun asalkan halal. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang memulai usahanya dengan rela menjual apapun dan membeli apapun, termasuk barang-barang bekas, hingga 15 akhirnya mempunyai toko sendiri. Opén dalam arti tekun merawat dan mengumpulkan mulai dari yang kecil-kecil hingga terakumulasi. Konsep ini juga merujuk pada sikap ekonomi yang teliti. Adapun tlatén berarti rajin bekerja dan tekun menjalankan usahanya. Pengajaran religius Islam yang menekankan kejujuran dan setia memegang janji ikut mendukung keberhasilan bisnis di Jatinom (Abdullah 1994:145-146). Kebangkitan ekonomi di belahan timur dunia juga ternyata tak dapat dilepaskan dari peranan modal spiritual masyarakatnya. Penelitian Bellah (1992:145) menunjukkan adanya keterkaitan antara Buddhisme Zen dengan etika ekonomi di Jepang. Pada masa Ashikaga (1392-1573), para rahib Zen memainkan peranan yang tidak kecil dalam perekonomian. Sekte Zen ini menghargai kegiatan produktif serta hidup dalam kesederhanaan spartan dan keugaharian. Tidak seperti sekte Buddhis lainnya yang meminta sedekah, para rahib Zen lebih menekankan kerja keras. Kerja dipandang sebagai sesuatu yang suci karena merupakan ungkapan syukur atas rahmat yang telah diterima. Pada masa selanjutnya, Konfusianisme yang mempunyai pengaruh besar di Jepang dapat dipakai untuk mengiluminasi pemahaman hubungan antara ekonomi dan negara (Bellah 1992:146). Dasar pikiran Konfusius adalah kemanunggalan ekonomi dan negara. Ini pula yang menjadi ciri para penguasa Tokugawa8 dalam memberikan perhatiannya terhadap ekonomi rakyat. Inti kebijakan ekonomi Konfusian adalah mendorong produksi dan mengurangi konsumsi, sehingga kekayaan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat tercukupi. Pengurangan konsumsi ini mengambil bentuk lahir dan batin. Konsumsi lahir dibatasi dengan mengurangi pengeluaran sedangkan konsumsi batin dibatasi dengan mengurangi keinginan. Ada dua hal yang menjadi ciri khas nilai-nilai Jepang dalam hal ekonomi. Pertama, dinamisme satu arah untuk mencapai tujuan bersama, dan yang kedua, semangat pengorbanan yang tulus tanpa pamrih demi tercapainya tujuan bersama tersebut. Jika diperhatikan, sikap rajin dan hidup hemat ada di dalam kedua pandangan itu. Pandangan-pandangan ekonomi politik yang lahir dari nilai-nilai masyarakat Jepang ini diterjemahkan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang akhirnya mendongkrak perekonomian Jepang. Salah satunya, pemerintah memberikan banyak fasilitas dan keringanan pajak yang mendorong pembukaan sawah-sawah sehingga di awal pemerintahan Tokugawa luas tanah pertanian berkembang dua kali lipat (Bellah 1992:150). Salah satu wilayah yang terkenal karena mengalami perkembangan ekonomi pesat adalah Yonezawa. Upaya khas yang dilakukan di 8 Tokugawa merupakan sebuah masa pemerintahan di Jepang yang berlangsung dari tahun 1600 hingga 1868. Pemerintahan ini diakhiri oleh Era Meiji (1868-1911). 16 sana pada saat itu adalah mengangkat pengkotbah keliling yang menanamkan nilai luhur dari sifat rajin, jujur, dan hemat dalam upacara-upacara Konfusian kepada masyarakat. Salah satu nilai dalam masyarakat Jepang yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian adalah nilai bakti anak kepada orang tua dan leluhur. Sikap rajin dan kerja keras dipupuk bukan demi profit pribadi melainkan demi profit keluarga. Setiap orang bertekun dalam bisnis demi keharuman nama keluarga dan tidak mempermalukan leluhur. Dengan demikian, integritas pribadi merupakan hal yang patut dipertahankan. Dampak positifnya adalah terciptalah trust sehingga praktik pembayaran dengan cara kredit mulai berlaku dan semakin membangkitkan dunia bisnis. Chen (1976 dalam Alatas 2002:113) juga melakukan penelitian terhadap nilai-nilai Asia. Melalui penelitiannya tersebut, ia melihat nilai-nilai Asia seperti semangat berkelompok, saling menolong, bakti anak terhadap orang tua, dan persahabatan, dapat memainkan peranan dalam memperbaiki hal-hal yang tak menyenangkan akibat efek modernisasi. Bellah menganalisa bahwa Jepang sangat mengutamakan nilai-nilai politis (Bellah 1992:8). Kedudukan sentral dari politik di Jepang terutama terjadi karena adanya nilai kesetiaan kepada atasan. Kesetiaan dipandang sebagai sebuah input dalam sistem integratif atau kelembagaan negara. Adapun outputnya adalah kewenangan koordinasi. Otoritas politik yang memegang wewenang koordinasi berkewajiban melimpahkan on (berkat) kepada rakyat di bawahnya. On ini bisa dalam bentuk kedamaian dari perang, berbagai program penanggulangan kemiskinan, gaji, dan sebagainya. Walaupun demikian, bagi masyarakat Jepang kesetiaan tidak ada kaitannya dengan on, tetapi merupakan kewajiban mutlak. Kesetiaan ini meski merupakan kewajiban mutlak namun tidak mengandung unsur paksaan bagi masyarakat Jepang. Ini terjadi karena identifikasi rakyat yang memandang seluruh bangsa sebagai sebuah keluarga besar. Kaisar adalah yang ilahiah, pangeran, dan ayah dari seluruh keluarga nasional. Sedangkan rakyat adalah pemuja, pelayan, dan anak. Dengan demikian, kesetiaan tidak lain merupakan ketaatan agung seorang anak. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kokutai, yaitu sebuah konsep bernegara yang membaurkan prinsip-prinsip kekeluargaan, politik, dan religius secara tak terpisahkan. Kokutai menjadi sebuah identifikasi dari entitas religius dan politik sekaligus sehingga kegiatan politik menjadi identik dengan kegiatan religius (Bellah 1992:141-142). Dapat dilihat di sini bahwa dinamika politik di Jepang berlatar belakang motivasi religius. 17 Nilai-nilai dalam spiritualitas di Jepang juga memiliki peran yang tidak kecil dalam struktur sosial mereka. Berdasarkan penghayatan spiritualnya, keluarga-keluarga di sana dapat dibedakan antara keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak, serta keluarga satu garis keturunan. Keluarga-keluarga yang berasal dari satu garis keturunan ini berhubungan satu sama lain dalam kerangka rumah induk dan rumah cabang. Dalam lingkup nasional, seluruh keluarga di Jepang adalah satu, dengan keluarga Kaisar sebagai rumah induk dari semua keluarga Jepang yang menjadi keluarga cabang (Bellah 1992:26). Berdasarkan penelitiannya di Jepang, Bellah menjelaskan di dalam sebuah rumah tangga, status kepala keluarga adalah sentral. Namun, di tengah masyarakat, status tersebut merupakan status resmi terendah dalam negara. Keluarga tidaklah otonom di luar negara namun berintegrasi dalam negara, bahkan dalam tingkatan tertentu mengalami campur tangan negara. Di Jepang berkembang sebuah teori kemasyarakatan dengan konsep okupasi. Okupasi ini berkaitan dengan panggilan luhur mereka yang menempatkan setiap orang dalam suatu jabatan atau kedudukan sosial tertentu. Artinya, suatu okupasi merupakan panggilan yang ditentukan dari langit (Bellah 1992:157). Dalam pandangan Konfusian, panggilan ini menjadi suatu kewajiban yang sudah pasti dan tertentu sehingga terbentuklah kelas-kelas dan kelompok fungsional dalam masyarakat. Masalah panggilan ini juga dibahas cukup banyak oleh Weber (1958). Perbedaan mencolok etika Protestan dengan Konfusian adalah masyarakat Protestan bekerja keras agar memperoleh kedudukan sosial yang baik, sebagai tanda mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Sebaliknya, para penganut Konfusian memandang kedudukan sosial yang dimilikinya merupakan tanda panggilan hidupnya. Maka, ia perlu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kedudukan sosialnya tersebut sehingga terciptalah sebuah ekuilibrium yang harmonis dalam sistem sosial masyarakat tersebut. Tampaklah di sini bahwa kekerabatan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang, dan kekerabatan berkaitan erat dengan penghayatan spiritual masyarakatnya. Di Indonesia pun nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat rupanya ikut memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (Geertz 1977, Abdullah 1994). Perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat mulai memasuki kehidupan keluarga, sistem pendidikan, dan berbagai organisasi ekonomi serta politik sehingga memunculkan berbagai perubahan sosial budaya yang cukup besar. Digambarkan oleh Geertz (1977) perubahan itu dapat dilihat dari munculnya proses komersialisasi dalam sektor pertanian, munculnya berbagai 18 perusahaan yang tidak tumbuh lagi dari ikatan kekerabatan, dan munculnya pula penghargaan tinggi terhadap ketrampilan-ketrampilan teknis. Perubahan nilai-nilai inilah yang berada di belakang kuantum variabel-variabel ekonomi. Melalui penelitiannya di Mojokuto, Geertz (1977) menemukan bahwa ternyata golongan entrepreneurs yang muncul di sana berasal dari golongan kaum santri. Pada tingkat ideologis, golongan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai wadah sempurna dari nilai-nilai agama dan moral yang agung di tengah masyarakat luas. Adapun penelitian Geertz di Tabanan menunjukkan golongan entrepreneurs di sana justru berasal dari kalangan bangsawan. Bisa ditebak bahwa hal ini berkaitan juga dengan motivasi spiritual karena setiap klan yang ada di Bali berkaitan dengan pura tempat ibadat mereka. Kenyataan ini mendorong Geertz untuk menyatakan bahwa tak dapat diharapkan satu pola pertumbuhan ekonomi yang uniform di antara berbagai golongan masyarakat Indonesia. Segala kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Dalam hal ini, modal spiritual yang tertuang dalam kelembagaan masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian. Hasil penelitian Geertz di Mojokuto dan Tabanan menunjukkan dengan sangat jelas mengenai hal ini. Doktrin yang dipegang secara radikal oleh para pengusaha di Mojokuto adalah reformasi Islam yang ingin membersihkan agama Islam dari unsur-unsur heterodoks 9 yang masih lumrah terjadi di dalam masyarakat umum. Sementara itu ideologi para pengusaha di Tabanan lebih bersifat liberal dan restorasionis. Bagaimanapun, motivasi yang berada di balik perilaku ekonomi para pengusaha baik di Mojokuto maupun Tabanan adalah nilai-nilai “yang benar” menurut mereka dibandingkan yang lazim ada dalam masyarakat umum. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal spiritual dalam pembangunan ekonomi di Mojokuto dan Tabanan. Demikian pula yang terjadi di India. Ada suku-suku tertentu yang kehilangan akar permukimannya sehingga sepenuhnya hidup untuk melakukan layanan bagi suku lain. Dalam usahanya berasimilasi dengan komunitas Hindu, maka ia mendapatkan predikat sebagai suku paria, suatu kelas sosial rendah yang terjadi karena pengaruh penghayatan spiritual (Andreski 1989:83-84). Namun, karena mereka berhasil beradaptasi dengan penghayatan spiritual setempat, mereka dapat bertahan hidup dan secara relatif mengatasi kemiskinannya yang semula tak punya tempat tinggal sama sekali. Di tengah situasi Srinlanka yang dibelit kemiskinan dan terus memanas karena konflik antara pemerintah dan Tamil (LTTE), Yapa (2006) lewat pembahasannya tentang tulisan Ariyaratne menyatakan yakin bahwa 9 Pengertian heterodoks yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. 19 spiritualitas Buddha merupakan satu-satunya solusi. Untuk mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan, dibutuhkan perubahan pribadi lebih dahulu lewat penghayatan spiritual Buddha yang radikal. Bermula dari kesadaran personal (puroshodaya), kemudian akan melahirkan kebangkitan komunitas atau desa (gramodaya), sehingga dapat pula mengubah situasi negara (deshodaya), dan akhirnya muncullah sebuah kebangkitan dunia yang baru (vishovadaya). Jadi, semua perubahan sosial yang meningkatkan kesejahteraan beradiasi keluar dan kunci pertama dari semua ini adalah agen personal yang menghayati spiritualitasnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak memberikan definisi secara gamblang, namun secara eksplisit Unruh & Sider (2005) menyebut istilah modal spiritual ketika menggambarkan kongregasi dalam Gereja di Amerika Serikat dapat menjadi sumber energi yang besar bagi karya-karya sosial karena memiliki kapasitas yang unik dalam memotivasi dan memobilisasi jaringan konstituennya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Meyer (2001) yang memerhatikan sejarah para presiden Amerika Serikat sejak Washington melihat bahwa religiositas para Presiden berpengaruh langsung terhadap pembangunan di Amerika Serikat. Pada saat dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, George Bush berdoa, Heavenly Father, we bow our heads and thank You for Your love. Accept our thanks for the peace that yields this day and the shared faith that makes its continuance likely. Make us strong to do Your work, willing to heed and to hear Your will, and write on our hearts these words: “Use power to help people.” For we are given power not to advance our own purposes, nor to make a great show in the world, nor a name. There is but one just use of power, and it is to serve people. Help us to remember it, Lord. Amen. (Meyer 2001:128) Hal pertama yang dilakukan Bush ketika menjadi presiden adalah berdoa. Meyer (2001:128-129) menyatakan masyarakat Amerika Serikat percaya bahwa Tuhan telah memilih bangsa Amerika untuk membawa kabar politik yang menggembirakan bagi dunia dengan bersinar menjadi teladan kebebasan, keadilan, dan demokrasi di antara bangsa-bangsa. Untuk itu Tuhan akan membimbing mereka menuju takdir bangsa Amerika tersebut. Para penghuni Gedung Putih silih berganti dan masing-masing menginterpretasikan iman bangsa Amerika melalui religiositasnya masing-masing. Melalui pribadi para Presiden itulah Amerika dipuji dan diagungkan atau dipersalahkan dan diserang. Dalam hal ini, seorang Presiden Amerika menjadi simbol modal spiritual bangsanya. Zohar (2004) yakin seorang Presiden Amerika Serikat dapat menentukan modal spiritual bangsanya. Para bapak pendiri negara Amerika Serikat telah menanamkan nilai-nilai yang menjadi kekayaan rakyat, 20 modal spiritual Amerika. Sayangnya, walau George Bush mengawali masa tugasnya dengan doa dan menarik simpati masyarakatnya, di akhir masa jabatannya justru menuai banyak kecaman. Dinyatakan oleh Zohar (2004) bahwa sikap dan kebijakan politik Bush telah menurunkan modal spiritual bangsa secara serius. Penelitian-penelitian ini hendak menunjukkan bahwa penghayatan spiritualitas seorang pemimpin dapat memengaruhi seluruh komunitasnya. Istilah modal spiritual berasal dari dua kata yang berlawanan, yaitu spiritual dan modal, dipersatukan dalam khazanah pembangunan asosiasi ekonomi dan perkembangan kultural. Dalam zaman kontemporer, Sir John Templeton mendirikan dan mendanai suatu penelitian untuk melihat konsekuensi agama dan spiritualitas terhadap ekonomi dan sosial. Dalam website-nya dikatakan bahwa konsep modal spiritual ini dibangun berdasarkan berbagai penelitian modal sosial yang menunjukkan bahwa agama menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan jaringan sosial dan trust. Hal senada diungkapkan Hardiyanto (2008) yang mengartikan modal spiritual menurut Woodburry, yaitu sebagai konsekuensi ekonomi dan sosial dari agama dan spiritualitas. Selanjutnya, disampaikannya juga bahwa menurut Vaughan modal spiritual merupakan pengalaman subjektif dari yang sakral. Bourdieu (1986, dalam Verter 2003) mengatakan ada tiga bentuk modal spiritual, yaitu dalam bentuknya sebagai pembangun, sebagai objek, dan sebagai kelembagaan. Pada hakekatnya, modal spiritual terjadi melalui proses transubstansiasi. Modal spiritual dalam bentuknya sebagai pembangun terdapat dalam pengetahuan, kemampuan, dan selera yang berkaitan dengan bidang religius. Sebagai kelembagaan, modal spiritual ini terbangun dalam habitus masyarakat serta dalam bagaimana cara mereka memahami dan bertindak yang terstruktur secara sosial. Sebagai suatu objek, modal spiritual mengambil bentuknya dalam rupa material atau komoditas simbolik. Modal spiritual memang seringkali dikaitkan juga dengan simbol-simbol. Tempat persemayaman raja yang diyakini sebagai wakil dewa serta rumah-rumah adat yang menjadi pusat ritual tak jarang menjadi simbol penghayatan spiritual masyarakat setempat. Persepolis 10 yang merupakan istana Raja Persia di masa lampau mengalami kehancuran ketika diserang oleh Aleksander Agung. Doxuan (1995) menyebutnya bahwa modal spiritual masyarakat Persia telah dihancurkan bersama dengan runtuhnya Persepolis. Pada dasarnya, Bourdieu (dalam Weininger [email protected] dan Lareau [email protected]) 10 Saat ini bernama Thakht-e Jamshid dan terletak di Iran (Doxuan 1995). 21 menyatakan bahwa sebuah kompetensi menjadi sebuah kapital atau modal sejauh ia memfasilitasi warisan kultural sebuah masyarakat sehingga menciptakan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang eksklusif. Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, Malloch (2003) memandang modal spiritual lahir dari pengertian bahwa seluruh kekayaan alam ini dipercayakan kepada manusia. Setiap orang dipanggil untuk memelihara dan mengolah dengan baik segala sumber daya alam tanpa memunahkannya. Dengan demikian, modal spiritual berkaitan dengan tanggung jawab akan segala ciptaan di bumi ini. Segala norma yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ini berada di dalam berbagai macam adat istiadat yang mencerminkan pengetahuan lokal dan iman mereka. Adapun (Finke 2003) mendefinisikan modal spiritual sebagai keahlian dan pengalaman khas akan agama, termasuk pengetahuan religius, keakraban dengan ritual agama dan doktrinnya, serta persahabatan dengan saudara seiman. Semua ini akan menolong seseorang untuk menghasilkan komoditas religiusnya yang dipandang bernilai. Sedangkan pendapat lain menyampaikan bahwa modal spiritual merupakan suatu potensi yang kekuatan, pengaruh, pengetahuan, dan disposisinya diciptakan oleh partisipasi tradisi spiritual mereka (Berger and Hefner 2003 dalam Hardiyanto 2008). Semua pengertian mengenai modal spiritual yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa modal spiritual tidak selalu dikaitkan dengan yang transenden. Sesungguhnya, spiritualitas menjalani sebuah proses evolusi pula. Kierkegaard (1843 dalam 1992) menguraikan bahwa proses spiritualitas ini melalui tiga tahapan, yaitu estetik, etik, dan religius. Tahapan estetik merupakan sebuah tahap ketika hidup dikuasai semata oleh naluri-naluri sensual, mood, dan dorongan hati. Pada saat keutamaan moral dianggap sebagai yang terpenting, maka dikatakan seseorang memasuki tahap etik. Puncaknya adalah ketika orang tersebut merasa bersalah jika berada di tahap estetik, merasa kurang sempurna di tahap etik, dan mulai berkembang di dalam iman. Maka inilah yang disebut tahap religius. Bagi Kierkegaard, beriman atau berelasi dengan Tuhan merupakan puncak perealisasian diri sebagai makhluk rohani (Sugiharto 2000:100). Setiap tahapan spiritual ini memiliki nilai-nilai yang dihidupi bersama dalam masyarakat komunal. Oleh karena itu, ada pendapat yang tidak mengaitkan modal spiritual dengan yang transenden sama sekali. Semua pembahasannya bersifat sangat humanis. Hal ini terjadi karena pembahasan modal spiritual tersebut berada di tahapan etik. 22 Dalam berbagai tulisan yang ada, modal spiritual hampir selalu dikaitkan dengan modal sosial (Friedly 2001, Wortham & Wortham 2007, Ramstedt 2008). Baker & Miles-Watson (2010) memandang bahwa paradigma “modal” dalam modal spiritual merupakan sebuah jalan untuk menggambarkan dan mengevaluasi peran serta kontribusi iman terhadap civil society. Pendapatnya ini dibangun setelah melakukan penelitian terhadap modal sosial dan melihat adanya keterkaitan antara modal spiritual dan modal sosial. Dikatakannya, modal spiritual menjadi sumbangan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam publik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa modal spiritual merupakan bagian dari modal sosial, namun ada pula yang justru sebaliknya. Berger & Hefner (2003) menyatakan bahwa modal spiritual merupakan sub spesies dari modal sosial. Alasannya adalah karena modal sosial selalu merujuk kepada kekuasaan, pengaruh, pengetahuan, dan disposisi dari individu yang diperoleh dari keanggotaannya dalam sebuah jaringan sosial. Adapun modal spiritual merujuk kepada kekuasaan, pengaruh, pengetahuan, dan disposisi yang diciptakan oleh partisipasi individu tersebut dalam tradisi religius. Dikatakan oleh Berger & Hefner (2003) bahwa De Tocqueville’s mengamati Gereja di Amerika Serikat pada abad ke-19 merupakan institusi lokal yang menjadi basis penumbuh “habit of the heart” yang kompatibel dengan kehidupan demokrasi. Berbagai penelitian Max Weber di Amerika Serikat dan berbagai negara di Asia juga menjadi dasar dari pernyataan Berger & Hefner ini. Di lain pihak, Weber (dalam 2006) percaya bahwa penghayatan spiritual merupakan determinan terpenting yang memengaruhi rasionalitas dan perilaku seseorang. Hal ini terjadi karena spiritualitas berkaitan dengan kedalaman seseorang; pusat moral kehidupannya dikaitkan dengan yang transenden (McLaughlin 2005). Dengan demikian, hasil penelitian Weber ini mengindikasikan modal spiritual bukan merupakan bagian dari modal sosial melainkan sebuah modal yang mengalirkan modal sosial. Penelitian Putnam (2000) bahkan menunjukkan bahwa lebih dari separuh jaringan sosial di Amerika Serikat merupakan kontribusi dari kehidupan religius masyarakat. Dengan demikian, modal spiritual bukanlah bagian dari modal sosial melainkan sebuah modal lain yang justru dapat melahirkan modal sosial. Beragamnya pengertian modal spiritual sebagaimana dipaparkan di atas mendorong penelitian ini untuk mencari bagaimanakah modal spiritual itu, khususnya dalam konteks Mondo. Dalam tulisan ini modal spiritual akan dipandang sebagai modal yang bukan merupakan bagian dari modal sosial. 23 Modal spiritual juga bukan merupakan bagian kognitif dari modal sosial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para aktor dalam tulisan ini bukan berlandaskan rasionalitas individu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan (Dewey 1997, Voss 1999, Lawang 2005:40), melainkan berdasarkan penghayatan spiritual mereka. Penghayatan spiritual tersebut berkaitan erat dengan hubungan pribadi yang terjadi antara individu dengan yang transenden yang dipercayainya. Oleh karena itu, tulisan ini menempatkan modal spiritual bukan sebagai bagian dari modal sosial melainkan modal yang dapat mengalirkan modal sosial. Dan itulah pula sebabnya, penelitian mengenai modal spiritual menjadi penting. Sampai sini lhooooooooooo MODAL SPIRITUAL DALAM PEMBANGUNAN Pada saat sebuah komunitas masyarakat berada dalam ancaman terabaikan oleh pembangunan, maka dibutuhkanlah sebuah strategi untuk dapat bertahan hidup. Agar dapat mengerti bagaimana sebuah komunitas dapat bertahan dibutuhkan penelitian mengenai apa yang menjadi kekuatan internal mereka. Kekuatan internal ini dapat terungkap dengan mempelajari nilai-nilai yang berada di dalam komunitas maupun yang mengalir keluar (Goulet 2006). Oleh karena itu, dalam mencari kekuatan internal masyarakat yang spiritualistis perlu dipelajari dahulu bagaimana penghayatan spiritual mereka dan nilai-nilai apa yang menonjol di dalamnya. Spiritualitas yang sehat dapat menghantar orang kepada kebebasan sejatinya, suatu tujuan ideal dari pembangunan (Sen 2000, Soedjatmoko 2004). Di sinilah spiritualitas menjadi modal spiritual yang berguna bagi pembangunan. Pada hakekatnya, semua orang memiliki sifat dasar spiritual, yakni perasaan spiritual yang mempersatukan orang-orang, binatang, tanah, dan segala sesuatu ke dalam satu kesatuan. Hal ini tak mengherankan, karena di saat manusia berhadapan dengan alam yang jauh lebih besar dari dirinya, rasa ingin tahunya tentulah akan muncul. Keingintahuannya itu mempertemukannya dengan Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sehingga terjadilah kontemplasi. Dari sinilah manusia mendapatkan rasa religiositasnya. Kemudian, rasa religiositas tersebut berkembang dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian, spiritualitas dan kebudayaan suatu etnis memiliki kaitan yang cukup erat. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ternyata penghayatan spiritual suatu masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan (Ife 24 2002:481). Bahkan, Berger dan Hefner (2003) mengamati adanya dampak langsung antara modal spiritual dengan pasar dan demokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agama, ritual kepercayaan, atau spiritualitas tertentu dapat menjadi sebuah modal spiritual suatu masyarakat. Penghayatan spiritual tersebut memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sempat dilihat oleh Geertz (1995:2) yang mengamati bahwa ibadat kepada leluhur mendukung otoritas hukum generasi yang lebih tua, ritus-ritus inisiasi menjadi sarana untuk penetapan identitas gender atau kedewasaan, pengelompokan ritual mencerminkan oposisi politis, dan mitos-mitos memberikan dasar bagi pranata sosial serta rasionalisasi hak-hak sosial yang istimewa. Shenk (2001:130) mengamati umat Buddha yang bertahan dalam penderitaan memberikan ketabahan yang mengagumkan bagi masyarakat pada umumnya. Di lain pihak, wawasan orang Afrika yang memandang diri sebagai komunitas yang penuh semangat memberikan kesegaran bagi masyarakat sekitar. Sedangkan slametan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan menenangkan rohroh dapat memperkuat solidaritas ketetanggaan (Geertz 1995:77). Semua penghayatan spiritual tersebut memberikan kontribusinya sendiri terhadap pembangunan. Sebagaimana Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, China kini juga terhitung sebagai negara yang maju dari Asia. Dalam pembangunan di China, rupanya semangat Konfusius masih menyala di tengah dunia perpolitikannya. Misi dari Konfusius ini tidak lain adalah mengembangkan filsafat politik yang dapat menjamin politik di negara tersebut dapat berlangsung dengan baik. Hal ini penting karena mereka percaya kehidupan politik yang adil dapat menjamin kesejahteraan kosmos (Shenk 2001:175). Sementara itu, Yewanggoe (2004:133) mencatat Revolusi Petani Tonghak di Korea tak dapat dilepaskan dari pengharapan mesianis pribumi mereka, yang didorong oleh keyakinan shamanistis, suatu aliran yang mewarnai spiritualitas bangsa Korea di masa lampau. Demikianlah dari waktu ke waktu di berbagai tempat, antara penghayatan spiritual dan pembangunan selalu ada kaitan yang erat satu sama lain (Alkire 2006). Itulah sebabnya modal spiritual merupakan hal yang perlu diperhitungkan di tengah masyarakat komunal, karena di dalam struktur sosial mereka tertanam nilai-nilai yang berasal dari penghayatan spiritual mereka. Spiritualitas sesungguhnya merupakan kekuatan yang ada di balik pembangunan (Mohatma Gandhi, dalam Singh 2006). 25 MODAL SPIRITUAL DAN INSTITUSI AGAMA DALAM PEMBANGUNAN Institusi agama berkaitan erat dengan penghayatan spiritual masyarakat. Apabila penghayatan spiritual itu berperan dalam perkembangan pembangunan, maka institusi agama berkaitan erat dengan pembentukan modal spiritual di tengah umatnya. Berdasarkan realita yang ada di berbagai daerah tampak bahwa agama sebagai lembaga kemasyarakatan dapat berperan besar dalam mengembangkan spiritual umatnya dan pada akhirnya mengambil peranan pula dalam pembangunan (Littell 1967, Daeng 1985, Putnam 2000:65-79, Fukuyama 2001, Munzer 2001, Shenk 2001, Brown and Brown 2003, Price 2004, Unruh and Sider 2005:171-239, Ganiel 2009). Paus Benediktus XVI (2009) dalam suratnya kepada duta besar Bulgaria untuk Vatikan, Nikola Ivanov Kaludov, menulis bahwa pembangunan yang otentik membutuhkan dimensi spiritual. 11 Hal ini bisa dimengerti mengingat manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Dengan demikian, pembangunan manusia seutuhnya bukan melulu mengandalkan pembangunan jasmani melainkan sekaligus juga rohani. Hal ini diuraikan cukup panjang lebar oleh Benedictus XVI dalam ensikliknya Caritas in Veritate. “..it is vital for development not to be limited exclusively to economic domination, but that it take account of the integrity of the human person. Human beings must be measured not by what they possess, but by the extension of their being in accordance with the capacities of their nature. This principle finds its ultimate justification in the creative love of God, which fully reveals the Divine Word. In this context, in order for the development of mankind and society to be authentic, it must necessarily have a spiritual dimension". (Caritas in Veritate) Salah satu contoh peran Gereja dalam pembangunan dapat dilihat di Hong Kong. Sebelum tahun 1997, sekolah Katolik merupakan sektor yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Hong Kong (Tan 1997). Dalam hal ini, Gereja memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan pihak pemerintah. Bagaimanapun, sesungguhnya institusi agama dapat berbuat banyak dalam pembentukan penghayatan spiritual umatnya yang akhirnya dapat menggerakkan pembangunan. Agama dan pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejarah politik di berbagai tempat dipenuhi dengan konflik dan kekerasan atas nama pembenaran agama. Sebaliknya, dijumpai dinamika keagamaan penuh dengan konspirasi politik dari orang11 Surat ini dibuatnya pada bulan Oktober 2009 26 orang yang berkoar membela Tuhannya dan agamanya (Mulkhan 2007:4). Begitu dekatnya politik dengan agama karena ternyata menurut Dhakidae (2007:47) yang mengutip ulasannya Carl Schmitt, konsep atau ilmu politik tidak lain merupakan sekularisasi dari konsep-konsep teologis. Dalam pembangunan manusia seutuhnya, umat Buddha memilih untuk tidak aktif mencari dan meraih kekuasaan tetapi memutuskan untuk berpolitik dalam arti tanggung jawab kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat luas (Sutrisno 2007:60). Berbagai kenyataan ini menunjukkan bahwa penghayatan spiritual yang lahir dari institusi agama memiliki peranan yang besar pula dalam dunia politik. Dalam sebuah masyarakat yang kristiani, kehidupan menggereja umat dapat menjadi modal spiritual mereka pula. Verter (2003) mengungkapkan bahwa Iannaccone menyatakan modal spiritual tidak lain merupakan keahlian dan pengalaman dalam keagamaan, termasuk pengetahuannya tentang agama, keakrabannya dengan ritual Gereja dan doktrin-doktrinnya, serta kebersamaan dengan umat dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Institusi-institusi ini merupakan produser sekaligus konservator dari modal spiritual. Menanggapi dunia yang semakin sekuler, Napolitano (1998) melihat adanya sikap baru yang dilakukan oleh Gereja, yaitu terjun langsung ke tengah masyarakat melalui perjuangan mobilisasi sosial yang dapat membawa perubahan struktural dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Konsekuensi dari modal spiritual memang tidak selalu berkaitan langsung dengan ekonomi, walaupun pada akhirnya dapat sampai ke sana pula. Rosenberger (1997) menggambarkan kegiatan Gereja di Amerika Serikat dalam kegiatan karitas seperti pendampingan gadis yang hamil di luar pernikahan, korban AIDS, korban narkoba, dan sebagainya merupakan modal spiritual bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Berger (2001) menunjukkan adanya keterkaitan antara institusi agama dengan demokrasi. Diungkapkan dalam sejarah Amerika Serikat, moralitas kaum puritan sangat kondusif bagi perilaku ekonomi yang dibutuhkan untuk kebangkitan kapitalisme, sebagaimana yang sudah dibahas oleh Weber sebelumnya. Oleh karena itu, kaum puritan tersebut juga kondusif untuk partisipasi demokratik di arena publik. Konsili Vatikan II dalam Gereja Katolik juga ternyata memengaruhi demokrasi di Eropa Selatan, Amerika Latin, Filipina, dan kawasan Katolik di Rusia (Berger 2001:453). Di bawah rezim komunis, resistensi masyarakat di Eropa Timur sangat dipengaruhi oleh penanaman spiritual Gereja kepada umatnya (Coleman 1991). Gereja di Polandia dan Yugoslavia memiliki relasi yang baik dengan 27 Vatikan dan memiliki kekuatan internal yang besar. Masyarakat di kedua negara tersebut memberikan resistensi spiritual yang kuat karena dukungan Gereja yang solid dalam memberikan pembinaan spiritual kepada para seminaris dan juga kepada umat. Bahkan, di tahun 1970 masyarakat dengan dukungan Gereja dapat memberikan kritik terhadap revisi konstitusi nasional, sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh umat di Hongaria dan Cekoslovakia yang kurang memiliki relasi harmonis dengan Vatikan. Sesungguhnya, hingga saat ini spritualitas masih terus relevan dengan dunia politik. Bahkan, Gandhi menekankan bahwa memenuhi kebutuhan akan spiritualitas merupakan langkah pertama yang paling penting bagi para politisi dan pemerintah (Singh 2006). Politik tanpa prinsip dan penghayatan spiritual akan menjadi penyebab dari krisis global dan krisis keharmonisan sosial. Pada saat itu, nilai-nilai tradisional tak mampu lagi menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Jalan yang seperti ini hanyalah akan membawa pembangunan ke jalan yang buntu. Berhubung spiritualitas senantiasa relevan dengan kehidupan realitas setempat, dalam tulisan ini pengertian modal spiritual diambil langsung dari lapangan. Pengertian ini berangkat dari pengertian spiritualitas menurut Keuskupan Ruteng, agar lebih kontekstual dengan kondisi tempat penelitian. Tertulis dalam Garis-Garis Pedoman Kerja Keuskupan Ruteng 2008-2012, spiritualitas dimengerti sebagai kualitas dalam diri manusia yang memengaruhi seluruh pribadi dan kesadaran manusia; sebuah pengalaman keberadaan manusia dalam relasinya dengan Allah yang tentunya juga bertalian dengan dinamika kehidupan manusiawi. Oleh karena itu, modal spiritual merupakan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalaman relasinya dengan realitas tertinggi, yang dapat menstimulasi kreativitas, mendorong perilaku moral, dan memotivasi individu (Hardiyanto 2008). Nilai-nilai yang dibicarakan di sini adalah nilai-nilai spiritualitas yang telah melembaga dalam masyarakat sehingga menjadi nilai-nilai sentral masyarakat setempat. Apakah nilai-nilai itu ada? Sesungguhnya, setiap kelompok masyarakat selalu berusaha untuk mencari nilai-nilai pemaknaan yang menghubungkan mereka dengan dunia (Bell 1976). Seluruh nilai ini tertanam dalam spiritualitas mereka, kebudayaan mereka, dan terungkap pula dalam keseharian mereka. Misalnya, bagi para Kibbutznik, bekerja merupakan panggilan (Bell 1976). Oleh karena itu, ajaran iman kristiani, adat istiadat, tradisi, norma-norma yang dihayati dan dihidupi suatu masyarakat, semua itu dapat dipelajari untuk dapat mengerti modal spiritual dalam sebuah masyarakat 28 yang komunal. Bahkan, mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat pun dapat dipelajari karena setiap mitos menyampaikan pesan tertentu yang akhirnya dapat mengungkapkan nalar mereka (Lévi-Strauss 1980). MODAL SPIRITUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL Bagi jiwa-jiwa yang kontemplatif, kehidupan mereka digerakkan oleh spiritualitas mereka. 12 Dengan demikian, pembangunan dalam masyarakat semacam ini tak dapat melepaskan diri dari mempelajari modal spiritual. Memerhatikan modal spiritual merupakan hal yang penting dalam setiap usaha pembangunan bagi masyarakat komunal yang spiritualistis. Suatu kelompok masyarakat yang spiritualistis akan memandang yang transenden dalam keseharian hidupnya, karena pada hakekatnya manusia senantiasa mencari Allah (Huijbers 1982:10-11). Inilah yang menjadi ciri sekaligus makna dari masyarakat spiritualistis, yaitu mereka yang menyadari kehadiran realitas supernatural dalam realitas sosialnya sehari-hari, yang terutama terungkap dalam upacara kebaktiannya (Janggur 2008:6). Realitas tertinggi itu dilihatnya dalam alam semesta, dalam diri sesamanya, dan dalam berbagai peristiwa di hari-hari hidupnya. Perlahan namun pasti, jiwa-jiwa kontemplatif yang spiritualistis tersebut membiarkan diri tenggelam dalam sesuatu yang melampaui pengertian mereka, yang mengatur alam semesta dan hidup manusia (Indrakusuma 1993). Pada saat itulah mereka menyadari, bahwa setiap insan bukanlah manusia yang lahir untuk menjadi sendirian. Ada udara yang dibutuhkan untuk bernafas, ada alam semesta yang dibutuhkan untuk bernaung, ada manusia lain yang dibutuhkannya untuk berelasi dan bersosialisasi. Yang transenden itu bukan lagi sesuatu yang mereka pelajari melainkan sesuatu yang sungguh-sungguh mereka alami, Ia hadir dalam eksistensi manusia (Huijbers 1982: 248). Kesadaran ini menghantar jiwa nan kontemplatif dalam muara pengertian adanya benang merah yang mempersatukan ia dengan orang lain dan alam semesta. Ia hanyalah titik kecil yang menjadi bagian dari segenap alam semesta. Demikianlah titik-titik kecil itu saling memandang satu sama lain, dengan kesadaran penuh bahwa setiap titik hadir bagi titik lainnya. “Aku menjadi aku karena kamu,” menjadi sebuah kesadaran yang dihidupi oleh mereka (Snijders 2004:27). Kelompok masyarakat yang merupakan kumpulan titik kontemplatif itu pun akhirnya lahir sebagai sebuah masyarakat komunal, 12 Masyarakat tradisional yang selalu mengundang kehadiran arwah para leluhur dalam setiap upacara mereka, merupakan salah satu ciri masyarakat kontemplatif pula yang selalu menyadari kehadiran realitas supernatural dalam keseharian mereka. 29 masyarakat yang terikat oleh suatu komitmen antara satu dengan lainnya; suatu komitmen yang terjadi karena kedekatan mereka dengan yang transenden. Pencarian manusia akan Wajah Allah tidak lain sebetulnya karena Dia yang lebih dahulu telah memanggil manusia kepada Diri-Nya. Allah yang hakekat-Nya adalah sebuah kekudusan yang absolut (Bilaniuk, 1982:46) memanggil manusia kepada kekudusan untuk bersatu dengan-Nya. “Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.” (Im. 20:26) “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." (Mat. 5:48) Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa sepanjang sejarah manusia mencari Wajah yang transenden dan dengan pertolongan-Nya semakin hari semakin masuk dalam kekudusan. Dengan demikian, sejarah penghayatan spiritual umat manusia pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seorang filsuf Karl Jaspers menyebutkan bahwa titik penting perkembangan spiritualitas di dunia terjadi di Zaman Aksial, sekitar tahun 900 – 200 SM (Armstrong 2007:447). Tradisi spiritual besar di dunia lahir di empat titik yang berbeda, yaitu Konfusianisme dan Taoisme di Cina, Hinduisme dan Buddhisme di India, Monoteisme di Israel, dan Rasionalisme Filosofis di Yunani. Sebelum Zaman Aksial, ritual dan pengurbanan hewan merupakan inti agama. Akan tetapi, para bijak Zaman Aksial mengubah hal ini. Walau masih menjunjung tinggi ritual tetapi mereka memberikan pemaknaan etis yang baru dan meletakkan moralitas sebagai dasar kehidupan spiritual. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwa penghayatan spiritual sebuah kelompok masyarakat akan mengejawantah di dalam perilaku sosial mereka. Masyarakat komunal yang terbentuk akibat hubungan mereka dengan realitas yang tertinggi merupakan masyarakat yang spiritualistis. Spiritualitas merekalah yang telah menganyam jalinan hubungan dari hati ke hati, sehingga setiap orang akan melihat sesamanya sebagai “orang sendiri.” Di sinilah spiritualitas memainkan peranannya dalam masyarakat komunal menurut Bourdieu, yaitu mengabadikan relasi yang terjadi di antara sebuah kelompok sosial masyarakat (Verter 2003). Vel (2010) juga mengamati adanya “jarak sosial” di kalangan masyarakat Sumba yang dipengaruhi oleh aturan adat mereka. Ada kelompok kita-kita yang meliputi kerabat-kerabat terdekat dan tetangga-tetangga terdekat, ada kategori bukan orang lain, yang memiliki hubungan tertentu dalam sebuah tatanan yang jelas, dan yang lainnya adalah 30 kategori orang lain yang mencakup ‘orang luar’ bahkan mungkin juga kategori lawan. Aturan adat yang mengatur pengelompokan kategori-kategori ini ternyata memengaruhi jalannya transaksi ekonomi yang terjadi di sana. Kekomunalan yang berkaitan dengan penghayatan spiritual juga ditunjukkan oleh sebuah cabang olahraga yang cukup populer di Jepang, yaitu Sheishin, semacam olahraga dayung yang melibatkan sebuah kelompok dan membutuhkan kesehatian antar anggotanya. Spiritualitas Jepang mengajarkan bahwa pikiran dan tubuh adalah satu, yang dipersatukan oleh spirit atau roh. Oleh karena itu, McDonald & Hallinan (2005) memandang hal ini sebagai modal spiritual karena cabang olahraga yang melibatkan kelompok ini dapat menjadi modal budaya bahkan modal ekonomi. Beberapa kelompok masyarakat menjadi komunal karena kedekatan mereka dengan arwah para leluhur. Ajaran leluhur mewariskan sebuah struktur sosial yang mengikat keturunannya dalam sebuah kekerabatan. Penghayatan spiritual masyarakat yang menghormati leluhur inilah yang membuat mereka menjaga baik-baik setiap wasiat leluhur. Dengan demikian, kekerabatan mereka lahir dari penghayatan spiritual mereka. Sebuah penelitian atas sebuah suku Indian di Lakota menunjukkan hal ini. Bagi Suku Indian di Lakota, batas antara “saya” dan “bukan saya” sangat mudah ditembus dan fleksibel (Voss 1999). Ungkapan “saya” ini dapat menyeberang ke pribadi yang lain sehingga akhirnya kata “saya” dapat mewakili orang lain pula. Hal ini terjadi karena setiap orang memandang sesamanya sebagai warisan dari roh leluhur dan roh-roh segala ciptaan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain dalam sebuah kekerabatan, baik secara biologis, spiritual, maupun secara fisik dalam kehidupan sehari-hari yang komunal. Masyarakat komunal hidup dalam sebuah komunitas sosial. Komunitas yang di dalamnya terjadi interelasi 13 antar anggotanya itu menjadi wadah bagi setiap orang di dalamnya untuk menjalani keseharian mereka. Bagi masyarakat komunal, komunitas menjadi tempat penghayatan kehidupan sehari-hari masyarakat, karena komunitas menjadi pusat religi, literatur, drama, dan seni yang jejaknya terekam dalam hukum, etika, kekerabatan, dan bahkan ekonomi mereka (Turner 2005). Di dalam komunitas tersebut terdapat sebuah local genius, yaitu sejumlah karakteristik kultural yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil pengalaman kehidupan di masa-masa lampaunya (Wales dalam Poespowardojo 1989). Adapun penanaman nilai-nilai spiritual 13 Interelasi ini mengandung pengertian saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain (Encarta Dictionaries, 2009). 31 yang dibicarakan dalam tulisan ini dilakukan dan terjadi dalam kelembagaan masyarakat komunal tradisional. Mereka menerima warisan nilai-nilai leluhur secara turun temurun sekaligus terbuka pula terhadap ajaran iman kristiani. Nilai-nilai ini sesungguhnya merupakan ungkapan aktivitas jiwa. Dijelaskan oleh Aristoteles ketika jiwa berkontemplasi maka ia mendapatkan kebajikankebajikan yang terbaik (Charles et al. 1999). Nilai-nilai kebajikan inilah yang kemudian mendorong tindakan seseorang, yang jika dikaitkan dengan pembangunan menjadi sebuah modal spiritual. MODAL SPIRITUAL DI BALIK KEKERABATAN Berdasarkan penjelasan mengenai peranan modal spiritual dalam pembangunan di atas, tampaklah bahwa pada umumnya modal spiritual memiliki keterkaitan erat dengan kekerabatan masyarakat komunal. Cukup banyak tulisan mengenai kekerabatan, namun jarang yang menghubungkannya dengan modal spiritual (Davidoff 2005, Holtzman 2005, Johnson 2009, Samuels 2010). Padahal, kekerabatan inilah yang kemudian membawa dampak langsung dalam pembangunan. Di balik kekerabatan yang dapat dilihat tersimpan sebuah modal spiritual yang tak terlihat. Bagi masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, antara pembangunan dan kekerabatan memiliki hubungan timbal balik. Bahkan, di beberapa tempat kekerabatan menjadi unsur terpenting yang harus diperhitungkan jika ingin menerapkan politik yang sesuai dengan masyarakat lokal. Pemerintahan Somalia dianggap gagal karena tidak memerhatikan sistem kekerabatan masyarakat secara keseluruhan (Mohamed 2007), sementara campur tangan demokrasi asing justru membuat dunia Arab yang dibentuk oleh kekerabatan menjadi semakin tidak stabil (Maziak dalam Anonymous 2009). Dengan demikian, mempelajari dengan seksama nilai-nilai spiritual yang mewarnai kekerabatan, dapat memberikan tuntunan bagi pembangunan di kalangan masyarakat komunal yang hidup dalam kekerabatan. Kekerabatan dapat memengaruhi pembangunan, sebaliknya, pembangunan juga dapat memengaruhi kekerabatan. Salah satu contoh penelitian di Ethiopia bagian selatan menunjukkan hal ini secara jelas (Ellison 2009). Ketika pemerintah meletakkan kebijakan ekonominya di garis neoliberalisme, secara halus kebudayaan masyarakat pun bergerak melakukan penyesuaian. Di sana ada sebuah ikatan kekerabatan yang disebut dengan Etenta. Kekerabatan ini dibentuk oleh ikatan klan patrilineal yang memiliki hak 32 atas sebidang tanah yang cukup luas. Selain itu, ada pula ikatan kekerabatan lain yang disebut Xauta, terdiri dari para pedagang, penempa, penenun, dan pembuat keramik. Xauta tak memiliki hak atas tanah apa pun, dan karenanya digolongkan sebagai kelompok yang lebih rendah status sosialnya dibandingkan Etenta. Bahkan, mereka yang tergolong dalam kelompok Etenta dilarang untuk berinteraksi akrab dengan mereka yang menjadi anggota kekerabatan Xauta. Namun, ketika panen tak memberikan hasil yang baik, dan terutama ketika pemerintah mulai menaruh perhatian besar terhadap para pedagang dan pengrajin demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, beberapa pria Etenta mulai meninggalkan ladangnya dan bergabung dengan kelompok Xauta. Maka, muncullah sebuah kekerabatan baru, yang bukan terjadi karena hubungan darah, melainkan lebih karena kehidupan yang dijalankan bersama. Hubungan antara kekerabatan dan pembangunan ditunjukkan pula oleh perjalanan panjang masyarakat Mongolia (Jamieson 2006). Ketika para pahlawan Mongol masih sering berkuda membelah padang-padang rumput yang luas, mereka menaklukkan banyak bangsa bahkan berinvasi sampai ke Nusantara. Saat itu mereka hidup dalam kekerabatan yang kuat, yang terjalin dalam ikatan sosial di antara mereka. Namun, saat era industri mulai merambah dunia, Mongol menjadi daerah kecil yang terjepit dua negara raksasa, Rusia dan China. Pada saat itulah Mongol menjadi negara yang miskin, nyaris terisolasi, dan mau tak mau menerima kebijakan komunisme yang disodorkan oleh dua negara raksasa tetangganya. Namun, ternyata komunisme dapat berjalan dengan baik di Mongol karena kekerabatan tradisional Mongol telah lama memraktikkan sosialisme. Kebiasaan yang dijalankan oleh sosialisme berdasarkan kekerabatan tradisional Mongol adalah menyerahkan hartanya sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut tingkatan sosialnya dalam kekerabatan. Namun, ketika Uni Soviet mengalami kejatuhan, komunisme di Mongolia pun perlahan melenyap. Saat itu masyarakat Mongol ditawarkan berbagai produk modernisasi, yang justru membuat mereka tak bisa kembali ke kekerabatan mereka yang semula. Pembangunan negara mengajak masyarakat menuju era industri, yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan kepada Bank Dunia, International Monetary Fund, dan Asian Development Bank untuk menolong masyarakat menghadapi perubahan politik dan ekonomi yang kini berlaku di negeri mereka. Dengan demikian, tampaklah bahwa antara pembangunan dan kekerabatan memiliki keterkaitan satu sama lain. Bagaimana kekerabatan bisa diwarnai oleh sebuah penghayatan spiritual? Berdasarkan penelitiannya atas Suku Semit, Smith menyampaikan bahwa ritual 33 tidak lain merupakan pernyataan berulang-ulang dari sebuah kesatuan yang berfungsi mengonsolidasikan komunitas (Hamilton 2001). Upacara-upacara adat bertujuan untuk menguduskan kelompok sekaligus mempromosikan kekomunalan dan solidaritas dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, muncullah sebuah kekerabatan, perasaan sebagai satu keluarga yang didorong oleh penghayatan spiritual komunitas. Salah satu yang ditekankan oleh Smith adalah bahwa spiritualitas ini merupakan urusan kelompok masyarakat, dan karenanya sekaligus pula merupakan entitas politik. Dalam karya terkenalnya Suicide, Durkheim menemukan bahwa umat Katolik memiliki angka statistik bunuh diri yang rendah (Osborne 2005). Ia percaya ini karena kekomunalan dan anti individualisme dari Katolisisme. Dengan demikian, penghayatan spiritual dapat melahirkan sebuah solidaritas yang akhirnya membentuk kekerabatan. Sebuah penelitian Durkheim atas Suku Aborigin meneguhkan hal ini (Hamilton 2001). Suku tersebut percaya mereka merupakan keturunan dari totem yang sakral, dan karenanya mereka pun sakral. Mereka tidak akan pernah menyebut dirinya bagian dari klan kakaktua putih atau kakaktua hitam tetapi mereka sendirilah kakaktua putih atau kakaktua hitam tersebut. Konsekuensinya, mereka pun sakral sebagaimana totem-totem tersebut. Kesimpulan yang diambil Durkheim saat itu adalah bahwa yang disembah dan yang menyembah tidak lain satu, dengan kata lain, dewa dan masyarakat bukanlah dua hal yang berbeda tetapi satu. Sifat dari dewa adalah superior terhadap umat yang bergantung kepadanya dan umat menjadi sasaran perintah dan kehendaknya. Hal ini sama dengan masyarakat yang membangkitkan perasaan ketergantungan individu terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat tergantung terhadap lingkungan masyarakat yang menaunginya. Oleh karena itu, kekerabatan tidak sekedar mempersatukan anggota-anggota komunitas namun sekaligus mengatur perilaku sosial dan interaksi sosial di kalangan masyarakat komunal tersebut. Semua penjelasan di atas menunjukkan bagaimana penghayatan spiritual dapat mewarnai kekerabatan. Hal yang paling menonjol di kalangan masyarakat komunal umumnya adalah kekerabatan mereka. Namun, jika ditinjau lebih jauh, kekerabatan tersebut sangat diwarnai oleh nilai-nilai yang mereka hayati, yang sudah melembaga dalam masyarakat tersebut. 34 PENGHAYATAN SPIRITUAL DI BALIK MODAL SOSIAL DAN CIVIL SOCIETY Pertanyaan sangat klise yang sering didengung-dengungkan orang adalah mengapa ada negara-negara yang kaya sumberdaya alamnya namun penduduknya miskin, sementara negara-negara lain yang tidak kaya akan sumberdaya alam penduduknya hidup sangat makmur. Seringkali jawaban yang muncul adalah karena faktor manusia. Maka, pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa banyak negara yang masyarakatnya komunal tidak semakmur negara-negara yang masyarakatnya individual? (Keefer and Knack, 2003) Padahal, masyarakat yang komunal itu memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah modal sosial, yaitu trust, norma, dan jaringan (Kumar and Matsusaka, 2004), dan modal sosial merupakan sarana untuk dapat mencapai tujuan bersama (Putnam 1995). Pertanyaan ini mengundang semacam kecurigaan bahwa jaringan modal sosial yang terbentuk di antara berbagai tipe masyarakat tidaklah sama. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Knack and Keefer (1997) menyatakan bahwa nilai trust di negara-negara berkembang cukup rendah. Padahal, kalau kita menerjunkan diri ke lapangan, akan ditemui kenyataan yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di pedesaan negara-negara berkembang banyak yang masih hidup secara komunal dan tradisional. Segala transaksi dan interaksi antar mereka dijalankan menurut adat. Dengan taat mereka menjalankan segala aturan adat, selain didorong kesetiaan kepada tradisi juga karena tak ingin menghadapi sanksi sosial. Oleh karena itu, trust di antara mereka tinggi karena kebanyakan mereka percaya semua orang akan mengikuti aturan adat. Belum lagi cara hidup mereka yang tinggal dalam kekerabatannya masing-masing serta interaksi yang terus menerus, dengan sendirinya membuat trust yang ada di antara mereka cukup tinggi. Kumar and Matsusaka (2004) menengarai kesimpulan Knack and Keefer yang menyatakan trust masyarakat di negara berkembang rendah karena pertanyaan mereka yang salah. Pertanyaan yang diajukan Knack and Keefer kepada responden adalah, “Menurutmu apakah kebanyakan orang dapat dipercaya? Atau, apakah kamu dapat tidak usah terlalu berhati-hati mengadakan persepakatan dengan orang lain?” Kedua pertanyaan ini berkaitan dengan urusan bisnis. Padahal, Kumar dan Matsusaka berpendapat di negara berkembang yang masyarakatnya komunal seharusnya yang ditanyakan adalah seberapa besar trust antar anggota kerabat atau apakah mereka sering 35 berinteraksi satu dengan lainnya sebab cukup banyak transaksi di antara mereka yang tidak berkaitan dengan bisnis. Oleh karena itu, Kumar dan Matsusaka berpendapat bahwa modal sosial ada dua macam, yaitu village capital dan market capital. Village Capital sangat bergantung kepada relasi personal yang tinggal bersama di suatu daerah. Interaksi di antara mereka terjadi berulang-ulang sehingga menjamin terjadinya kontrak di antara mereka. Kumar and Matsusaka percaya bahwa Village Capital ini efisien untuk ekonomi lokal. Sedangkan Market Capital, dikatakan bergantung kepada pihak ketiga seperti auditor, pengadilan, dan institusi formal lainnya. Market Capital ini dibutuhkan demi berjalan efektifnya institusi pasar dan memungkinkan terjadinya perdagangan antar mereka yang tidak saling mengenal. Selain itu, ciri dari Market Capital ini menurut Kumar and Matsusaka adalah spesialisasi yang lebih menonjol dibandingkan Village Capital. Hampir mirip dengan yang dijelaskan Kumar and Matsusaka (2004), Fukuyama (2000) juga menjelaskan akan adanya dua macam jaringan, yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Akan tetapi, Fukuyama menyampaikan bahwa modal sosial akan lahir dari jaringan yang dihidupkan oleh norma-norma informal. Ciri inilah yang membedakan jaringan yang dimaksud Fukuyama berpotensi modal sosial dengan jaringan pasar dan hirarki. Sampai di sini, tampak adanya konfrontasi antara pendapat Fukuyama dengan Kumar and Matsusaka. Fukuyama lebih memercayai jaringan informal untuk mengembangkan modal sosial, yang jika dibandingan dengan konsep Kumar and Matsusaka termasuk kategori village capital. Sebaliknya, Kumar and Matsusaka lebih mengandalkan market capital yang dapat memungkinkan pula terjadinya transaksi antara orang yang tidak saling mengenal. Dalam kalangan masyarakat komunal, ekonomi lokal terbangun terutama atas dasar kekerabatan. Transaksi di sana terjadi antar orang yang sudah saling mengenal. Interaksi ini terjadi berulang-ulang dan melibatkan status mereka dalam relasi kekerabatan. Di sinilah penghayatan spiritual masyarakat memainkan peranannya dalam menentukan bentuk modal sosial karena jaringan yang terbentuk terjalin berdasarkan norma-norma informal. Dengan demikian, modal sosial mereka merupakan village capital yang terbentuk oleh jaringan informal (Kumar and Matsusaka 2004, Fukuyama 2001). Kekerabatan di antara mereka menjadi sebuah kekuatan internal sehingga modal sosial mereka cenderung bersifat bonding yang kuat. Bonding yang dimaksudkan di sini adalah ikatan dalam sebuah kelompok eksklusif yang membedakannya dari 36 kelompok-kelompok lain karena adanya nilai-nilai yang dihidupi bersama, sementara di kelompok lain tidak ada (Woolcock 1998, De Filippis 2001, Lin 2002, Bruegel dan Warren 2003). Walaupun demikian, bukan tidak mungkin pula bonding tersebut bermetamorfosa menjadi bridging, apabila ada keterbukaan masyarakat untuk menjalin relasi dan transaksi dengan dunia di luar kekerabatan mereka. Pada saat itu, mereka dapat menjadi komunitas village capital yang kuat dalam hal bonding namun sekaligus pula menciptakan bridging di saat yang sama ketika bertransaksi dengan orang luar. Yang jelas, jaringan yang terbentuk selalu informal. Adapun bridging yang dimaksud dalam hal ini adalah terbangunnya trust antara dua komunitas yang mereduksi ketidaksamaan yang ada sehingga terfasilitasi sebuah mobilitas sosial di antara keduanya (Woolcock 1998, Bruegel dan Warren 2003). Itulah sebabnya walau mereka berhasil melakukan bridging namun gagal bertransisi ke market capital yang jelas-jelas membutuhkan jaringan formal. Kegagalan ini berarti tidak terjadi linkage social, yaitu jalinan dengan institusi yang memiliki otoritas (Woolcock 1998, Bruegel dan Warren 2003). Modal sosial yang diwarnai oleh penghayatan spiritual ini memampukan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mereka (Putnam, 1995), bukan hanya di bidang ekonomi melainkan juga politik. Putnam (1995) mengatakan bahwa modal sosial berkaitan langsung dengan partisipasi politik karena partisipasi politik berelasi dengan institusi-institusi politik. Sebaliknya, Newton (2001) tak sependapat dengan hal tersebut. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antar individu di dalam asosiasi dan organisasi hanya sedikit sekali yang dilandasi oleh trust. Argumentasinya adalah pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam asosiasi dan organisasi adalah orang-orang yang berkelas tinggi dalam status sosial. Mereka adalah orangorang yang mempunyai rasa percaya diri cukup besar dan bisa dengan mudah memercayai orang lain. Oleh karena itu, trust sudah ada lebih dahulu sebelum mereka menggabungkan diri ke dalam asosiasi, bukan sebaliknya. Lebih lanjut, Newton menunjukkan bahwa mereka yang memiliki trust besar kepada sesamanya belum tentu memiliki trust yang besar pula kepada pemerintah. Beberapa contoh yang dicatat oleh Newton adalah Finlandia yang memiliki trust tinggi antar masyarakatnya, namun sulit untuk menaruh kepercayaan kepada pemerintah pada masa runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tetangga dan partner dagang krusial mereka. Demikian pula Jepang dikenal memiliki level yang tinggi dalam hal modal sosial (Pharr 2000 dalam Newton 2001), namun level kepuasan politik di Jepang umumnya rendah (Newton 2001). Sebaliknya, di Jerman trust sosial meningkat dari tahun 1948 hingga 1993 (Cusack 1997 37 dalam Newton 2001). Hal ini terjadi karena sekitar tahun 1948 negara berada dalam Era Nazi yang penuh ketakutan dan paranoia. Namun, seiring berjalannya waktu, Jerman menjadi negara yang damai, demokratis, dan makmur. Semua kenyataan ini membuat Newton (2001) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara modal sosial dengan stabilitas demokrasi serta civil society. Berdasarkan kasus-kasus di atas, disimpulkan ada dua macam trust, yaitu Trust Sosial dan Trust Politik yang masing-masing independen satu sama lain. Sebaliknya, Fukuyama (2001) menyampaikan bahwa civil society dan demokrasi mempunyai hubungan yang kuat dengan modal sosial. Dikatakannya bahwa kehidupan berasosiasi masyarakat diperlukan untuk membangun suatu demokrasi yang modern. Suatu masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membangkitkan pula suatu fungsi politik yang baik. Dengan perkataan lain, stok yang melimpah dari modal sosial akan menghasilkan civil society yang kuat, yang dibutuhkan oleh demokrasi yang liberal. Civil society inilah yang mengimbangi kekuasaan pemerintah dan melindungi individu-individu dari kekuasaan negara. Oleh karena itu, modal sosial yang rendah dalam suatu negara berkaitan erat dengan pemerintahan lokal yang tidak efisien. Pendapat senada Fukuyama yang mendukung adanya keterkaitan erat antara modal sosial dan demokrasi cukup banyak, antara lain Renshon (2000) yang memandang modal sosial tidak meletakkan fondasi demokrasi kepada trust penduduknya tetapi kepada relasi yang terjadi satu sama lain. Inilah yang membedakannya dengan penelitian yang meletakkan fondasi demokrasi pada trust (Newton 2001, Kumar and Matsusaka 2004), sehingga tidak terjadi hubungan yang kuat antara modal sosial dengan demokrasi serta civil society. Lebih dari itu, pola interaksi sosial yang membentuk modal sosial terdiri dari relasi-relasi antara human capital dan partisipasi politik serta keterlibatan organisasi dalam aktivitas politik (La Due Lake and Huckfeldt 1998). Dengan demikian, modal sosial memberikan kontribusi yang besar dalam bidang politik dengan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses demokrasi. Sehubungan dengan modal sosial dan civil society, Pye (1999) mempunyai tiga konsep. Pertama, ia berpendapat bahwa kehidupan bermasyarakat melibatkan sebagian besar norma-norma umum dari interaksi personal. Kedua, modal sosial menentukan peraihan tujuan bersama bangsa dan komunitas. Ketiga, civil society menjadi dasar yang utama bagi kepentingan pluralistik demokrasi. Pye percaya bahwa modal sosial semakin meningkat karena kondisi sehat dari civil society, yang pada gilirannya akan memberikan dinamika kepada politik 38 demokrasi. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya ada atau tidaknya keterkaitan antara modal sosial dan demokrasi tergantung dari modal sosialnya. Ada yang mengatakan tergantung kepada trust (Newton 2001, Kumar and Matsusaka, 2004) ada juga yang mengatakan tergantung kepada relasi yang terjadi (La Due Lake and Huckfeldt 1998, Pye 1999, Renshon 2000, Fukuyama 2001). Dalam masyarakat yang komunal dan spiritual, trust maupun relasi yang terjadi sangat tergantung kepada penghayatan spiritual yang tertuang dalam kelembagaan adat mereka. Oleh karena itu, bagi kelompok masyarakat yang kehidupan spiritualnya masih sangat kuat, wajarlah jika atmosfer politik mereka dipengaruhi oleh penghayatan spiritual mereka. Sebagai anggota masyarakat dari sebuah negara demokrasi, pemahaman mengenai civil society ini cukup penting. Sebuah otoritas membutuhkan sebuah kekuatan lain yang otonom terhadap hegemoninya agar keseimbangan pemerintahannya terjaga. Tanpa penyeimbang, pemerintahan dapat berjalan kurang sehat karena otorita dapat berkembang tanpa batas dan bersifat diktatoris. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Chandoke (1991), ”Tidak ada teori negara tanpa civil society dan sama pula halnya civil society tidak dapat diteorikan tanpa mereferensi kepada negara.” Untuk keperluan seperti inilah civil society dilahirkan sehingga performa demokrasi suatu negara dapat dipertahankan dengan lebih efektif (Putnam et al. 1995 dalam Pye 1999). Dengan demikian, civil society dapat dimengerti sebagai sebuah kelompok otonom yang dapat memberikan tekanan kepada pemerintah. Sifat otonom civil society ini mengandung pengertian sukarela, swadaya, bebas, dan mandiri, sebagai sebuah upaya mencapai demokrasi (Diamond 1992). Apabila sebuah civil society masih dibayang-bayangi dominasi negara, maka ia tidak fungsional lagi. Berakhirnya masa keemasan feodal telah menumbuhkan berbagai institusi yang dapat menjadi basis kuat pembentukan civil society di zaman republik (Pye 1999). Masa demokrasi ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berbicara dan didengarkan. Dikatakan oleh Hegel bahwa civil society adalah suatu ruang yang berada di antara keluarga dan negara (Stillman 1980). Dengan perkataan lain, civil society juga tidak berkaitan dengan upaya pencapaian kekuasaan negara (Buttigieg 1995). Civil society menjadi sebuah arena tempat masyarakat memasuki hubungannya dengan negara, namun berdiri secara mandiri dalam barisan oposisi (Candhoke 1991). Itulah sebabnya civil society lebih merupakan dinamika interaksi politik dari para aktornya daripada sebuah institusi (Thomas 2001). Dengan demikian, civil society memiliki beberapa ciri tertentu, antara 39 lain, adanya kemampuan dan keberanian untuk melakukan kritik terhadap negara (critical discourse), adanya rasionalitas di dalam meminta pertanggung jawaban negara (rationality), adanya partisipasi politik publik (political participation), adanya kebebasan yang bertanggungjawab (freedom and accountable), adanya keterbukaan (transparancy), adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (human right and non violence), dan adanya sifat yang inklusivitas (inclusivity) (Schulte Nordholt 1999, Suwondo 2004, Suwondo 2005 dalam Suwondo 2009). Dalam suatu masyarakat komunal yang spiritualistis, penghayatan spiritual menjadi pengikat unik antar individu yang membentuk sistem maupun struktur sosial masyarakat. Kekomunalan masyarakat ini dapat dilihat dari karakteristik struktur sosialnya yang unik, definisi yang diberikan mengenai para anggotanya, dan frekuensi serta jenisnya yang tipikal dari relasi sosial mereka (Starr 1954). Setiap level kekomunalan masyarakat yang membentuk struktur sosial ditandai dengan adanya sebuah pusat yang dikelilingi oleh elemen lainnya sebagai satelit. Misalnya, di banyak kelompok masyarakat komunal, rumah adat menjadi pusat kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat itu. Adapun, definisi yang diberikan mengenai anggota biasanya tergantung kepada kesadaran anggota tersebut mengenai siapa atau bagaimana dirinya. Misalnya, masyarakat mendefinisikan dirinya kristiani, atau Orang Manggarai, tergantung apa yang menjadi pusat kehidupan mereka, Gereja atau rumah adat. Adapun relasi sosial di antara mereka akan semakin frekuentatif dalam komunitas yang semakin kecil dan komunal. Dapatlah dimengerti bahwa dalam konteks ini, keberadaan civil society akan dipengaruhi oleh penghayatan spiritual masyarakat tersebut. Kehadiran civil society tak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi karena civil society tidak lain merupakan salah satu ungkapan demokrasi. Seringkali demokrasi digambarkan sebagai kekuasaan di tangan rakyat. Persoalannya adalah rakyat yang dimaksud adalah kelompok warga yang mana? Dahl (1988:35) mengusulkan sebuah Prinsip Kepentingan Yang Terlibat, yaitu rakyat yang dimaksud adalah setiap orang yang dipengaruhi oleh keputusan suatu pemerintahan seharusnya mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut. Dalam hal ini civil society menjadi sekelompok warga yang dipengaruhi oleh keputusan pemerintahan dan berpartisipasi dalam pemerintahan walau bukan di barisan eksekusi melainkan oposisi. Lebih lanjut, Dahl (1988:37-42) mengatakan ada berbagai macam bentuk demokrasi, misalnya demokrasi dasar, perwakilan, referendum, komisi, dan delegasi. Terakhir, berkembang pula prinsip devolusi yang menyerahkan kekuasaan 40 sepenuhnya kepada wilayah subordinasinya (Williams and Mooney 2008, Edward 2009, Encarta dictionaries). Segala bentuk demokrasi yang ada ini tidak memiliki keterkaitan dengan penghayatan spiritual masyarakat. Apabila ada sekelompok masyarakat yang perilaku sosialnya dipengaruhi oleh penghayatan spiritualnya, mungkinkah akan muncul sebuah bentuk demokrasi yang baru? Pada akhirnya tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Di Indonesia pada masa belakangan ini tampak adanya bentuk civil society yang sangat dipengaruhi oleh pertentangan dan konflik sehubungan ikatan primordial dan sentimen keagamaan (Suwondo 2009). Dari sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya ada keterkaitan antara penghayatan spiritual dan civil society. Hal ini terjadi karena bagaimanapun modal sosial yang memengaruhi civil society tak mungkin dilepaskan dari budaya setempat (Coleman 1999, Ife 2002). Budaya lokal inilah yang menjadi titik pusat interaksi sosial yang dapat melibatkan masyarakat hingga lahirnya sebuah civil society. Civil society disusun oleh asumsi-asumsi kultural mengenai keadaan natural manusia, individu, masyarakat, dan sejarah (Thomas 2001). Dengan demikian, tradisi budaya dan identitas kolektif yang menjadi penghayatan spiritual suatu masyarakat menjadi dasar dari modal sosial dan kepemimpinan politik mereka. Itulah sebabnya, pembahasan mengenai pembangunan di aras lokal tak dapat dilepaskan dari budaya lokal yang ada, termasuk di dalamnya penghayatan spiritual yang ada. Penghayatan spiritual dapat juga lahir dari institusi agama. Dengan demikian, institusi agama memiliki keterkaitan pula dengan demokrasi. Beberapa penelitian mengungkapkan bagaimana Gereja dapat memengaruhi situasi demokrasi. Mereka berasumsi bahwa kehadiran Gereja akan membimbing kepada aktivitas politik yang dapat membuahkan dampak signifikan dalam pembangunan lokal (Bebbington 1993, Putnam 2000, Brown and Brown 2003). Di institusi Gereja itulah seseorang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya di bidang-bidang tertentu dan memasuki jaringan komunikasi yang dapat membangun aktivitas politik. Dikatakan oleh Putnam (2000) bahwa komunitas-komunitas iman yang dengannya umat menyembah Tuhan merupakan modal sosial terpenting di Amerika Serikat. Dengan terlibatnya dalam jaringan sosial, tingkat kesadaran seseorang dalam hal informasi dan peluang akan bertambah, termasuk informasi politik. Tentu saja hal ini memberikan efek positif bagi kelompok sosial tersebut. Demikianlah bahwa ternyata di tengah masyarakat yang spiritualistis, ada 41 keterkaitan yang erat antara penghayatan spiritual dengan modal sosial dan civil society. 42