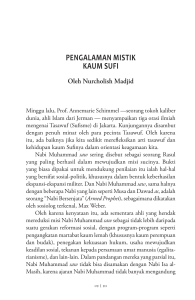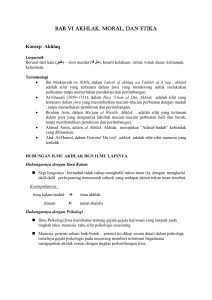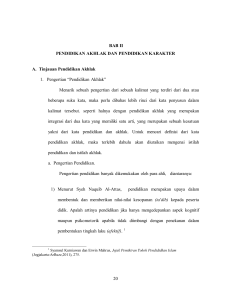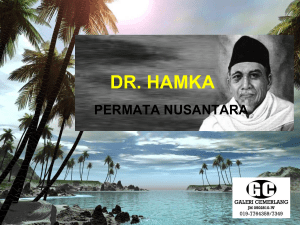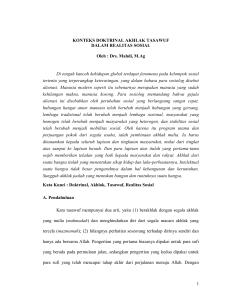Moral Tanistik
advertisement

Tanistik 1. Pengertian Tanistik Tanistik merupakan sebuah akronim dari tasawuf nihilistik. Istilah khusus untuk mistisisme Islam dalam bahasa Arab ialah tasawwuf, orang yang menjalani laku tasawuf disebut sufi.1 Sementara ‘nihilistik’ dirujuk dari pengertian Nihilisme, sebuah model filsafat yang dialamatkan kepada Friedrich Wilhelm Nietzsche. Pada lapisan permukaan, antara Tasawuf dan Nihilisme memang tampak bertolak belakang pasalnya keduanya merupakan dua kajian yang jauh berbeda, bahkan berseberangan. Tasawuf sebagai kajian teistik berbeda dengan Nihilisme yang ateistik, Tasawuf berangkat dari keyakinan kuat terhadap kebenaran al-Qur’an mengenai eksistensi Tuhan. Nihilisme tidak pernah bersentuhan dengan al-Qur’an, akan tetapi menolak kebenaran-kebenaran yang diyakini mutlak. Bahkan Nietzsche sebagai tokoh sentral dalam Nihilisme, terang-terangan mengabarkan kematian Tuhan. Selain itu Tasawuf sangat menghargai adanya kebenaran mutlak (Tuhan), yang oleh Nietzsche dikritiknya sebagai omong kosong. Oleh karena itulah Tasawuf dijunjung tinggi sebagai ilmu ketuhanan (metafisik) alias kehidupan akhirat sementara Nihilisme hanya membicarakan kehidupan duniawi. Namun jika kita melacak lebih jauh ke dalam, kita akan menemukan titik singgung yang mengherankan. Bagaimana mungkin dua kajian yang bertentangan dapat saling bertemu, aneh bukan? Tidak ada sulap dan tak ada sihir dalam kajian ilmiah, itulah prasyarat mutlak. Ada titik kunci yang menjadikan keduanya dapat bertatap-muka, bahkan titik kunci itu telah menjadikan keduanya saling menguatkan. Tasawuf dan Nihilisme, keduanya muncul berdasarkan wacana kritik yang sama, yaitu: kekosongan. Tasawuf mengritik kehidupan dunia dan segala isinya sebagai kehidupan profan, temporal dan tidak bermakna dibandingkan dengan kehidupan akhirat (kekosongan kehidupan dunia). Nihilisme pun mengritik filsafat barat karena dinilai hanyalah kesia-siaan yang tak bermakna alias omong kosong (kekosongan nilai-nilai filsafat modern). Titik kunci lain yang telah mempertemukan keduanya ialah solusi kritik yang sama, keduanya sama-sama menganjak ‘kembali pada diri sendiri’. Sebagai konsekuensi atas wacana kritik yang terlampau pedas, Tasawuf dan Nihilisme mengajak manusia supaya kembali pada diri sendiri sepenuhnya, tanpa berpurapura. Meski setelah itu, keduanya kembali berbeda pendapat demi memenuhi kebutuhan masing-masing. Tasawuf menekankan pengendalian diri untuk mendekat kepada Tuhan, mencapai pencerahan serta menjumpai realitas ketuhanan. Sedangkan Nihilisme menekankan kemandirian bersikap alias kepercayadirian berpikir. Dengan kata lain, Tasawuf dan Nihilisme sama-sama mementingkan eksistensialitas manusia. 1 Menurut Hamka, Tasawuf (mistisisime Islam) merupakan suatu ajaran hidup yang lebih menekankan pentingnya penyucian jiwa. Tasawuf memiliki sejarah panjang dan tersebar dalam aliran yang berbagai rupa. Secara umum tasawuf dibagi menjadi 2 macam; (1) Tasawuf sunni, yakni tasawuf yang didasarkan atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan namanya, tasawuf model ini sangat menjunjung tinggi syari’at Islam. Tasawuf sunni dialamatkan kepada tasawuf Dzunnun alMisri, al-Ghazali dan Abd Qadir al-Jailani. (2) Tasawuf falsafi, yakni model tasawuf yang banyak bersentuhan dengan filsafat Yunani, terutama mistik Phytagoras dan Plotinus. Unsur filsafat yang lebih kental daripada unsur syari’at menjadikan aliran tersebut disebut tasawuf falsafi. Beberapa tokohnya, antara lain: Ibn ‘Arabi, Abu Yazid al-Bustam, al-Hallaj, Suhrawardi, Mulla Shadra dan lainlain. Singkatnya, tasawuf sunni lebih menekankan etika Islam sementara tasawuf falsafi sangat mengedepankan pengalaman mistik (penyatuan diri dengan Tuhan). Nietzsche, meskipun di awal wacana kritiknya berkoar-koar tentang kematian Tuhan, namun Tuhan tidaklah sungguh-sungguh mati di tangannya sebab tidak lama sesudah itu, Nietzsche mengumumkan kelahiran Übermensch sebagai Tuhan yang lebih manusiawi. Dengan ini saya tidak bisa semena-mena turut memahami bahwa Nietzsche seorang ateis, Tuhan yang telah dibunuhnya ialah Tuhan yang arogan, namun tidak dengan Tuhan yang manusiawi. Tuhan yang manusiawi ialah manusia itu sendiri, pasalnya tak ada entitas yang lebih manusiawi selain manusia itu sendiri. Tuhan yang berubah menjadi manusia jelas berbeda dengan manusia yang menjadi Tuhan. “Ya! Nihilisme adalah nama lain untuk tasawuf. Sesuatu yang hampir tak ditemukan apa-apa adalah tasawuf, yang menyelinap dalam nihilisme. Nihilisme hampir menyerupai perang melawan segala yang ada, segala yang mapan. Tasawuf sudah mapan dan harus diperangi. Tasawuf bukan jalan menuju Tuhan, tetapi jalan menuju egosentrisme. Tuhan tak pernah ada kecuali yang telah menyelinap dalam kehendak bidjak seseorang. Orang gila dan orang-orang yang pernah gila, merekalah yang sanggup memahami kehendaknya. Kehendak untuk menguasai sesuatu, menguasai diri sendiri. Semua akan kembali pada kekosongan, tak terkecuali kekosongan itu sendiri. Kekosongan telah menyelinap dalam diriku, ego-ku lebur bersama kehendak dan memunculkan stagnasi ke-inyong-an. Aku yang stagnan, aku yang kosong, aku yang merdeka. Seseorang tak akan pernah tahu apa itu kemerdekaan sampai ia membuangnya jauh-jauh, membuang mimpi-mimpi kemerdekaannya. Nihilisme masuk dalam tubuhku, ia akan mencapai puncak ektase setelah lebur bersama kehendak dan ego-ku. Maka lahirlah apa yang aku sebut “tasawuf nihilistik”. Sesuatu yang telah lama, laammmmaaaaa sekali,” 2 Selanjutnya bagaimanakah tanistik itu? Tanistik sebagai tasawuf nihilistik tentu memiliki mainstream yang berbeda dengan tasawuf pada umumnya, tapi dalam pembahasan ini kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai tanistik sebagai tasawuf nihilistik. Sejauh ini Tanistik, sebagaimana dalam tasawuf alGhazali, sangat kental dengan wacana moral. Moralitas Tanistik merupakan moral yang tidak menggunakan mainstream atas dan bawah –Tanistik menilai sesuatu tidak menggunakan penilaian salah-benar dan/ baik-buruk. Atas-bawah, keduanya bukanlah entitas berbeda yang harus dipertentangkan, keduanya senantiasa berkelitkelindan dan tak dapat dipisahkan. Menilai tindakan dengan tidak menggunakan penilaian salah-benar dan/ baik-buruk –berlaku pula untuk seluruh istilah turunannya3—, itulah yang dimaksud morlitas tanistik. Penilaian tersebut bukan berarti seorang moralis yang enggan menggunakan hak suaranya, bukan juga seorang moralis yang sedang berpura-pura berpikir non-moral. Tanistik tidak sedang melarikan diri dari klaim sokmoralis, hanya saja tidak peduli terhadapnya. Wacana sokmoralitas sulit sekali dihindari ketika manusia masih menjadi manusia, barangkali dengan melupakan sokmoralitas manusia menjadi dirinya sendiri. Tanistik tidak mengajak manusia berputus asa melainkan sebaliknya, mengajarkan kemandirian tingkat tinggi. Manusia mandiri bukanlah manusia yang mudah dipengaruhi oleh isu-isu tak jelas, kekritisan sangatlah penting. Namun kekritisan yang netral sulit sekali diusahakan, kekritisan akan terwujud jika 2Lihat Ngutsman Mukromin. Ah, Sok Moralis!. Belum terbit 3 Turunan moral yang berimplikasi atas-bawah antara lain: baik-buruk, salah-benar, halalharam, sunah-makruh, boleh-terlarang, dan sebagainya. seseorang hanya berpihak pada kekritisan itu sendiri, bukan berpihak pada yang lain. Ketika seseorang hanya berpihak pada kekritisan itu sendiri, saat itulah ia terombang-ambing dalam kekritisan akhirnya tak mampu bersikap. Sementara bersikap ialah menilai, entah dengan penilaian apa. Lalu bagaimana bila menilai menggunakan salah-benar dan baik-buruk ternyata keliru? Untuk menghindari kesalahpahaman digunakanlah istilah keliru dengan asumsi bahwa pengertian “keliru” tidak identik dengan salah ataupun buruk. Orang Jawa menggunakannya dalam konteks yang lebih sederhana yaitu ketika terjadi ketidaksesuaian pandangan, bisa jadi pandangan tersebut tidak berkaitan dengan moral (amoral atau non-moral). Menilai sesuatu dengan tidak menggunakan penilaian salah-benar dan/ baik-buruk, itulah yang dimaksud penilaian non-moral. Saya sepakat bahwa manusia sangat sulit meninggalkan analisis salah-benar dan/ baik-buruk, berlaku pula untuk semua istilah turunannya. Hal itulah yang mengakibatkan manusia disebut sebagai makhluk bermoral, berbeda dengan hewan yang tidak mampu mengeksekusi sesuatu dengan salah-benar ataupun baik-buruk. Namun demikian klaim moral telah mengakibatkan banyak hal yang berujung pada perselisihan. Artinya jiwa manusia sama-sekali tidak berarti kecuali bila bernaung bersama mainstream moral mayoritas yang identik dengan kebenaran, karena suara mayoritas adalah suara Tuhan. Ketika suara mayoritas diartikan sebagai suara Tuhan maka memungkinkan peluang untuk mengartikan suara minoritas sebagai suara setan, sementara setan halal darahnya. Itulah etika yang berdiri di atas logika formal. Etika semacam itu jelas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan semangat Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika). Etika Pancasila sendiri didasarkan atas moral toleransi, setiap perbedaan disambut dengan penghormatan yang sama. Selain toleransi itu, Pancasila sendiri tidaklah mengusung nilai baru yang dapat menolak nilai-nilai yang hendak dihormatinya. Pancasila mengakui nilai-nilai yang bersifat universal, dengan demikian Pancasila dapat menerima segala nilai moral, termasuk nilai moral yang bersifat relatif alias kondisional. Ketika menghadapi perbedaan, nalar tanistik bukan hanya bersifat toleran melainkan juga bersifat open minded, terbuka untuk saran dan kritik dari berbagai pihak. Tanistik sangat lunak terhadap kondisi, mudah menyesuaikan diri hingga terkesan tidak berpendirian padahal itulah pendiriannya. Tanistik memang mementingkan pikiran dan tindakan bidjak, bukan sekedar omong kosong. Penilaian Tanistik berimplikasi rasional-irasional sekaligus, lintas mainstream dan lintas metode, kadang berlakulah anything goes. Dan ketika harus menggunakan etika formal, tanistik tidak berkeberatan. Mata Tanistik menatap tajam kepada suatu keadaan yang disebut bidjak, namun bidjak tidaklah bidjak ketika kondisi menuntut seseorang supaya meninggalkan bidjak. Bila demikian bidjak tidak dapat dimaknai sebagai metode melainkan tujuan. Sekali lagi, sangatlah sulit memahami bidjak dengan pengertian formal. Bila diangkat pada tataran yang lebih tinggi, kita dapat memahami bahwa Tanistik adalah seni hidup (the art of live) yang meliputi seni berpikir dan seni bertindak. Berpikir meliputi semua hal yang berkaitan dengan aktivitas pikiran, demikian pula bertindak yang semua berkaitan dengan gerak sebagian/semua anggota badan. Lalu apakah seni itu? Seni selalu identik dengan keindahan bentuk, keserasian warna, keseimbangan posisi, kebidjkan tindakan, kecerdasan berpikir dan kemandirian (percaya diri) tingkat tinggi. Menariknya, tak ada aturan khusus dalam seni hingga seni pun dapat mengkritisi dirinya sendiri. 2. Melihat Tanpa Menilai Apa susahnya melihat tanpa menilai? Apa susahnya menilai tanpa menggunakan penilaian baik-buruk dan/ salah-benar? Demikianlah pertanyaan sederhana yang begitu sulit dijawab pasalnya secara tidak sadar manusia selalu saja menggunakan penilaiannya. Seorang wanita muda tiba-tiba melintas, berkaos ketat dan celana Levis-nya terlihat kekecilan, mata-mata pria yang melihat pasti mulutnya berkomentar. Siapa yang tertarik akan berkomentar positif sementara sebaliknya, siapa yang merasa jeleh akan berkomentar sebaliknya. Atau bila kata-kata tidak sempat diucapkan pasti penilaiannya terekam dalam memori otaknya. Itulah yang saya maksud dengan penilaian. Demikian mudahnya manusia menilai orang lain dan demikian mudahnya manusia mencibir ataupun menjilat orang lain, semua itu didasari atas sebuah hal: penilaian. Pada dasarnya setiap penilaian hanya memiliki dua implikasi: tinggi (baik, benar, menarik) dan rendah (buruk, salah, jelek) dan anehnya ituah model penilaian yang kerap dimanfaatkan manusia dalam bersosialisasi dengan manusia lain, kepada atasannya menjilat sementara kepada bawahannya menekan. Lalu bagaimana dengan penilaian obyektif? Menurut hemat saya, penilaian objektif hanya ada dalam teori yang sulit terbuktikan. Penilaian para saintis yang akhir-akhir ini sulit pula dipertanggungjawabkan, terlebih setelah temuan menggemparkan atas teori Kuantum dan teori Relativitas dalam fisika modern. Sementara dalam ilmu-ilmu (sains) yang lain kecenderungan yang sama belum nampak jelasnya hingga keyakinan mengenai kebenaran objektif pun masih dipertahankan. Menurut Positivisme Logis bahwa kebenaran objektif disebut pula dengan kebenaran ilmiah, yakni suatu kebenaran yang didasarkan atas penelitian ilmiah (empiris-logis). Pendirian saintifik tersebut akhirnya digunakan pula dalam dunia (ilmu pengetahuan) sosial untuk membaca gejala-gejala sosial. Akhirnya ilmu sosial pun tidaklah berbeda dengan sains, atau disebut pula sains sosial. Anda dapat menjumpai hal tersebut dalam Sosiologi, Anthropologi, Kedokteran maupun Psikologi klasik. Penilaian-penilaian saintifik semacam itu bagaikan sebatang magnet yang memiliki dua kutub: positif dan negatif. Penilaian tersebut diyakini lebih praktis, jelas dan ilmiah; itulah sebelah sisi positifnya namun demikian penilaian tersebut pada dasarnya memperlakukan manusia hanya sebagai objek (benda mati), bukan sebagai makhluk hidup yang bereksistensi. Pastinya eksistensialitas manusia sangatlah bersifat personal (subjektif), antara seorang dengan lainnya sudah tentu berbeda dan luput bila disamakan. Lain halnya dengan pendekatan Fenomenologi yang telah dikembangkan oleh Immanuel Kant, Hegel, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jasper, Albert Camus, Maurice-Merlau Ponty dan kawan-kawan, fenomenologi merupakan jawaban atas kegelisahan mereka terhadap Positivisme. Sebagaimana penuturan Kant bahwa pengetahuan manusia tidak dapat dilepaskan dari fenomena (realitas yang terindera) sementara untuk noumena (realitas yang tak terindera) sebaiknya manusia tutup mulut karena bila tetap memaksakan diri, hanya akan menemukan omong kosong. Hingga pemikir-pemikir sesudahnya sepakat bahwa fenomenologi dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan baru untuk memahami gejala sosial, sedikit lebih realistis daripada positivisme. Sesekali fenomenologi memang diklaim sebagai pendekatan yang unreal, tatkala mendekati agama misalnya, fenomenologi tidak berkepentingan terhadap realitas abstrak maupun realitas konkret secara langsung. Fenomenologi senantiasa menjaga jarak terhadap objekobjek yang terindera, dengan hati-hati fenomenologi tidak mengambil kesimpulannya sebelum relitas tersebut mengungkapkan dirinya. Aneh memang, fenomenologi selalu menempatkan dirinya sebagai proses untuk menjembatani kutub positif dan kutub negatif, suatu proses terus-menerus tanpa hasil akhir. Sangatlah mustahil bagi manusia bila tidak menilai, hingga diam tanpa katakata lebih sulit dilakukan daripada menggosipkan banyak hal. Manusia akan merasakan gatal bila mulutnya terus mengatup sementara isi kepalanya tenang tidak untuk menilai sesuatu. Manusia akan lebih tersiksa dalam kesepian sehingga terus berusaha mencari kawan sebanyak mungkin. Namun bukan berarti kawanan antar manusia tidak menarik hanya saja kawanan yang melestarikan tingkah-tingkah sokmoralis menjadi kawanan kemunafikan. Kawanan alias perkumpulan manusia kerap membangun suatu mainstream tertentu untuk kebutuhan eksistensial atau sekedar untuk mengikat anggota-anggotanya. Namun demikian, tak dapat dipungkiri, hal tersebut memiliki efek moral yang justeru menutup kemungkinan bagi mainstream lain. Kebebasan berpikir setidaknya dapat dimaknai ketika seseorang bebas menentukan pilihan masing-masing, bukan takluk atau mengekor terhadap pikiran orang lain. Dan lucunya, trend mengikuti pendapat orang lain hanya didasarkan atas pertimbangan eksistensial; seseorang rela tunduk di bawah tangan orang lain hanya karena takut dikucilkan dari suatu komunitas. Ketika hal tersebut semakin menggejala dan ditambah adanya persaingan antar komunitas akhirnya konflik moral pun berlangsung. Seseorang, atas nama suatu komunitas, harus merendahkan kelompok lain dengan dalih-dalih moral sebagai mortirnya. Hal ini nampak sangat memalukan karena sangat merugikan bagi pertumbukan toleransi antar sesama. Lebih jelasnya pluralisme hanya menjadi tema-tema seminar yang terus dibicarakan dalam suatu komunitas tertentu dan secara tegas melakukan pelarangan terhadap orang lain yang hendak berpartisipasi dalam seminar tersebut. Sistem semacam itulah yang kerap bermunculan akhirakhir ini. Beberapa hari belakangan di UGM terselenggaralah sarasehan mengenai Pancasila, namun apakah nilai-nilai Pancasila telah diberlakukan dalam seminar tersebut? Saya memaklumi bila sarasehan tersebut memang disikapi sebagai proses untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih matang, namun sampai kapan proses tersebut terus dipelajari? Menunggu-nunggu hari esok, setiap orang selalu menunggu-nunggu hari esok, hanya menunggu-nunggu tanpa berpikir sebaliknya bahwa hari esok tak mungkin berlangsung tanpa keputusan untuk menggumulinya hari ini. Melihat tanpa menilai, ketika memutuskan untuk menyematkan tema ini saya merasakan keraguan untuk menempatkan diri pada sudut pandang semacam apa. Meskipun wacana tersebut hanyalah deskripsi namun saya tidaklah memungkiri bahwa wacana tersebut sedang diarahkan menuju suatu sudut pandang tertentu. Dan ketika dengan sudut pandang tersebut, saya melakukan kajian terhadap kasuskasus tertentu, sama artinya dengan menegaskan bahwa seseorang tidaklah mungkin melihat sesuatu tanpa menilainya. Dalam hal ini saya mengingatkan pembaca mengenai dua hal penilaian. (1) Menilai objek (objek material). Ketika seseorang mengungkapkan kembali tentang sarasehan yang telah diikutinya menggunakan sudut pandangnya sendiri, itulah penilaian, bersifat arbitrer. Klaim tersebut terlontar atas suatu pertimbangan bahwa sesuatu yang telah terjadi, biar bagaimanapun, tidak mungkin terulang kembali. Artinya sehebat apapun koreksi kita terhadapnya, tidak lain hanyalah koreksi yang –nyaris— sia-sia alias tak berguna. Sedikit lebih berguna bila koreksi atau penilaian tersebut dijadikan pedoman untuk event mendatang. (2) Menilai penilaian (objek formal). Selain menilai objek material (objek kajian) kita dapat pula menilai penilaian kita sendiri. Artinya seseorang dapat melakukan kajian kritis (perenungan) terhadap pola pikirnya sendiri, setelah ataupun sebelum dirinya menilai suatu objek tertentu. Inilah satu garis tegas yang membedakan antara merenung dan melamun, perenungan berarti mengkaji secara kritis terhadap keputusan-keputusan diri sendiri sementara lamunan diidentikkan dengan mimpi alias cita-cita. Dengan kata lain perenungan berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan mendatang sedangkan melamun murni tentang masa depan. Meski secara fisik pekerjaan merenung dan melamun sangat sulit dibedakan, tanpa menginterogasi kita tak dapat memutuskan apakah seseorang sedang merenung ataukah melamun. Sehubungan dengan kategorisasi di atas, istilah “melihat tanpa menilai” dapat dipisahkan dalam kategori kedua. “Melihat tanpa menilai” setidaknya dapat mencegah kita dari keputusan arbitrer menilai suatu objek tertentu, terlebih menilai orang lain. Sebelum kita memutuskan melakukan penilaian terhadap seseorang, terlebih dahulu selesai dengan menilai diri sendiri. Inilah kehati-hatian etis yang sedang ditekankan dan menjadi tema sentral dalam bahasan ini. Menilai penilaian diri sendiri akan menghindarkan seseorang dari tuduhan sokmoralis. Secara konseptual kemunafikan dapat dihindari dengan mengakui diri sendiri sebagai munafik, namun solusi etis sama sekali tidaklah demikian. “Melihat tanpa menilai” secara total, itulah solusi etis yang memungkinkan. Etika tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menutup mata dari realitas, tidak juga mengajarkan seseorang untuk diam tanpa berbuat sesuatu. Etika mengajarkan seseorang supaya kritis terhadap pola pikir yang mendasari tindakannya. Etika mengajak kita merenungi sebelum dan sesudah melakukan tindakan tertentu. Sementara terhadap tindakan yang sedang kita lakukan, etika tak berani ikut campur. Etika memberi kesempatan setiap manusia untuk melakukan tindakannya dengan mantap, tanpa terganggu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bukankah manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan moral? Tentu oleh karena kemunculan pertimbangan itu menuntut manusia mempertimbangkan setiap perbuatannya, tepatnya pertimbangan ketika akan melakukan perbuatan tertentu. Kemunculan etika dengan hati-hati dimaksudkan supaya tidak menjadi belenggu bagi manusia namun tidak juga supaya diremehkan. Bukankah manusia terbelenggu oleh nilai-nilai dalam kehidupan? Bagi orang-orang tertentu nilai etik menjadi pertimbangan utama dan tak bisa ditoleransi sementara bagi yang lain malah sengaja mempermainkan nilai-nilai etik, karena terbelenggu oleh nilai yang lain. Namun demikian setiap orang memiliki kecenderungan memberlakukan nilainilai etik meski dengan mainstream yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan, meskipun berbeda, manusia memberlakukan nilai-nilai etik berdasarkan kesepakatan komunitasnya karena bagi yang melanggar harus menelan sanksinya. Nilai etik suatu komunitas itulah yang kemudian disebut sebagai tata tertib, aturan main, unggah-ungguh, sopan-santun dan sebagainya. Sebagian orang memang merasakan belenggu yang dipasang oleh nilai-nilai etik, namun bagi mereka terikat dalam suatu komunitas harus rela menerima belenggu tersebut sebagai “resiko pekerjaan”. Sementara orang-orang yang lebih ekstrem akan tampil sebagai pemberontak moral, sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan pengaruhnya terhadap orang lain. Manusia dengan gejolak muda, mereka itulah makhluk-makhluk yang senantiasa mencari jati diri, mendobrak kemapanan etik tertentu –padahal demi kemapanannya yang lain. Berbeda sekali dengan orang tua yang telah mengalami banyak kehidupan, ia dapat menerima kenyataan dengan lapang dada tanpa menganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain. Sementara itu ia tetap tersenyum dan dengan tenang melanjutkan aktivitasnya sebagai manusia pada umumnya. Secara pribadi saya sepakat bahwa orang-orang tersebut telah mendapat pencerahan etik dan otomatis menjadi tauladan dalam pendidikan etik. Pendidikan etik memang tidak dapat disampaikan melalui teori panjang, kecuali bila didahului oleh keteladanan dari orang-orang yang telah mengalami pencerahan. Artinya kita tak perlu membuangbuang waktu dan tenaga untuk mempelajari moral bila guru kita hanyalah sekelompok manusia sokmoralis. 3. Toleransi dan Keterbukaan Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” yang terdapat dalam lambang negara kita memiliki implikasi logis tertentu: toleransi. Kaki-kakinya berdiri di atas pondasi pluralisme sementara kedua tangannya berpegangan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perbedaan dalam pluralisme hendaknya diartikan sebagai entitas-entitas eksistensial dan memiliki keunikan masing-masing, justeru ketika perbedaanperbedaan disikapi dengan pencampuradukkan tentu semakin menegasikan adanya pluralitas karena pencampuradukkan merupakan upaya penyatuan kembali dalam polanya yang lain. Sementara pluralitas sama-sekali bukanlah penyatuan bentuk melainkan sebaliknya, menghargai perbedaan-perbedaan dalam selaga bentuk. Itulah toleransi, sifat/sikap menghargai perbedaan (WJS. Peorwadarminta, 1984: 1084) dengan tetap mempertahankan eksistensi diri sendiri. Hal ini berbeda sekali dengan mempertahankan eksistensi dengan cara menolak perbedaan yang datang dari orang lain. Pandangan terakhir inilah yang dulu pernah diberlakukan oleh Adolf Hitler hingga sebagai konsekuensinya manusia di luar Ras Aria harus dibumihanguskan karena dinilai tidak memenuhi standard. Pandangan etis semacam itu tidak hanya arbitrer namun juga merugikan orang lain –bukan karena pola pikirnya, melainkan— karena aplikasinya. Aneh bin ajaib, sejarah mencatat ribuan nyawa terpaksa harus menjadi korban hanya karena persoalan sepele: tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, sebagai implikasi atas sikap “melihat tanpa menilai”, satu tingkat di atas toleransi ialah open minded alias keterbukaan. Istilah open minded melulu ada dalam kosa kata Inggris, berarti ‘membuka pikiran’. Istilah tersebut ketika ditranslit dalam Bahasa Indonesia menjadi keterbukaan, meski sebetulnya antara open minded dan keterbukaan memiliki makna yang tidak selaras. Keterbukaan memiliki makna lebih luas dibandingkan open minded, keterbukaan dapat berarti terbuka dalam berbagai hal. Meskipun demikian bukan berarti open minded tak dapat disandingkan dengan keterbukaan, justeru demikian open minded mengalami perubahan makna. Bukankah keputusan manusia, termasuk keterbukaan selalu diawali dari pikirannya? Keterbukaan dinilai selangkah lebih maju karena di samping menghargai juga membuka diri dan menerima kritik-saran dari entitas yang berbeda. Kita bukan hanya bersedia membuka diri terhadap perbedaan melainkan juga menerima kritik dan saran yang datang dari entitas yang berbeda, untuk menyempurnakan eksistensi kita sendiri. Sikap keterbukaan menandakan bahwa seseorang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan memiliki pendirian yang teguh tanpa merasa ketakutan dipengaruhi orang lain. Sikap keterbukaan mensyaratkan seseorang harus rela kehilangan sebagian miliknya dan menerima sesuatu yang baru. Namun demikian, sebagai konsekuensi ekstrem keterbukaan dapat mengancam keutuhan eksistensi seseorang bila tidak dibarengi kecerdasan bersosial. Artinya seseorang tetap harus selektif sebelum ia memutuskan untuk membuka dirinya, padahal seleksi merupakan bagian dari penilaian. Tak dapat dipungkiri bahwa seseorang menilai dengan cara menyeleksi, atau setidaknya seleksi dilakukan untuk menilai sesuatu. Jangan menilai semua hal secara moral, itulah ajakan supaya manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang moralis. Manusia adalah manusia, sementara moral hanyalah sebuah aspek dari realitas hidup, tentu aneh bila satu aspek itulah yang mendominasi kehidupan seseorang. Manusia setidaknya dapat meyakinkan diri bahwa dirinya manusia, eksistensi manusia sebagai manusia bukan sebagai yang lain. Dengan begitu, seseorang akan mengahargai kemantapan hati supaya tidak terombang-ambing gelombang keadaan. Keterbukaan menerima diri apa adanya, itulah keterbukaan yang paling mendasar. Setelah seseorang dapat menerima dirinya sendiri, dengan mudah ia menerima kehadiran pihak lain, dengan apa adanya pula. Keterbukaan dapat menghilangkan sekat-sekat karena basa-basi, kepurapuraan alias saring curiga. Sekat-sekat itulah yang telah menjumudkan hubungan sosial kita selama ini sehingga tidak berkembang. Seolah hubungan yang selama ini kita jalin tidaklah sungguh-sungguh karena tidak dilandasi keterbukaan, tetapi kecurigaan. Atau bila telah berhasil dalam keterbukaan, keterbukaan kita masih berjarak. “Kepada isteri sendiri saja curiga, bagaimana mungkin kehidupan rumah tangga akan nyaman,” itulah analogi yang mendekati. Hubungan sosial kita laksana hubungan suami-isteri yang tak lagi ada jarak di antara keduanya. Hubungan apakah yang dapat kita tangkap antara toleransi, keterbukaan dan “melihat tanpa menilai”? Barangkali –dalam wacana ini— toleransi dan keterbukaan memang tidak dapat hubungan akan tetapi tolerani dan keterbukaan dapat menentukan sikap seseorang ketika “melihat tanpa menilai”. Toleransi, sebagaimana yang telah disinggung di atas, sikap menghargai perbedaan dengan tidak menilainya secara arbitrer, perbedaan tersebut dianggap sebagai eksistensi lain yang menguatkan eksistensi dirinya. Sesama eksistensi yang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa yang satu harus mengganggu yang lain, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Meskipun saling menghargai namun di antaranya keduanya terdapat jarak sebagai demarkasi eksistensi masing-masing. Berbeda sekali dengan keterbukaan yang tidak ada jarak di antara keduanya namun demikian bukan berati pencampuradukan. Pencampuradukan terjadi ketika salah satu atau kedua pihak tidak memiliki pendirian yang jelas mengenai dirinya sehingga eksport-impor pendirian pun tak terelakkan lagi. Dalam keterbukaan masing-masing pihak dimaknai sebagai eksistensi yang memiliki kelebihan dan kekurangan, keduanya saling menguatkan dengan cara take and give atas apa yang mereka miliki dan dibutuhkan oleh yang lain. Dengan kata lain, setelah kita menerima masukan dari pihak lain bukan berarti harus menelannya mentah-mentah tapi mengolahnya kembali supaya sesuai dengan kondisi kita sendiri. Berdasarkan kedua sikap itulah “melihat tanpa menilai” menjadi mungkin dimaknai, bahkan lebih menarik perhatian. Melihat orang lain tanpa menilainya dengan salah-benar dan/ baik-buruk, sama artinya dengan melihat orang lain tanpa menyeleksinya dengan nilai-nilai moral. Lalu bagaimanakah seseorang dapat melaksanakan pendirian tersebut? Toleransi dan open minded, setidaknya itulah jawaban tapi jangan pernah berharap dapat menemukan cara bagaimana bertoleransi dan beropen minded. Toleransi dan open minded bukanlah metode alias cara melainkan tujuan, untuk mencapai tujuaan toleransi dan open minded seseorang berhak mengembangkan caranya masingmasing. Justeru ketika toleransi dan open minded dijadikan sebagai cara baku maka toleransi dan open minded akan kehilangan eksistensinya. 4. Tanistik Sebagai Etika? Etika sebagai sistem pengetahuan, berkembang dari barat lalu menyebar ke seluruh belahan dunia. Sebagaiman informasi dalam bab sebelumnya, etika barat tersebar dalam beberapa aliran, yaitu: etika hedonisme (Aristippon dan Epicuros) etika eudaimonia (Aristoteles), etika deontologi (Immanuel Kant), dan etika nihilisme (Friedrich Nietzsche). Sementara etika yang berkembang di belahan timur terdapat etika Hinddu, etika Tao, etika Islam dan etika Jawa. Masing-masing sistem nilai tersebut memiliki penekanan berbeda yang menjadi ciri khasnya masingmasing. Etika barat berpihak pada rasionalitas sementara etika timur menekankan harmonisasi hidup. Menurut Alasdair Macyntire, berdasar kutipan Amin Abdullah, pada hakikatnya etika modern tidaklah melulu bersangkut-paut tentang baik-buruk (normativitas), etika menyangkut pula bidang kehidupan yang lebih luas, menyangkut analisis-konseptual hubungan dinamis antara manusia sebagai subjek dengan rasio serta dorongan subjektivitasnya (Amin Abdullah, 2004: 293). Analisiskonseptual yang disinggung oleh Macyntire tersebut merujuk pada Immanuel Kant, seorang tokoh besar bidang etika modern. Etika Kant kenal sebagai etika kewajiban karena membatasi etika sebagai kewajiban yang tidak dapat didasari pada pertimbangan subjektif yang bijaksana, etika harus memuat nilai-nilai mutlak (Franz Magnis-Suseno, 2001: 221). Menurut lain pendapat, etika Kant disebut metafisika moral, pasalnya nilai-nilai mutlak tersebut transendental (metafisika). Berdasarkan devinisi di atas, di manakah posisi tanistik sebagai sistem nilai? Singkatnya, dapatkah tanistik disebut sebagai etika? Inilah pertanyaan penting yang hendak kita diskusikan bersama. Ketika tanistik dipahami sebagai penilaian amoral jelaslah bahwa tanistik bukan etika. Namun sebaliknya jika tanistik dipahami sebagai moralitas, masuk dalam kategori etika apakah tanistik itu? Menurut saya pantas dimasukkan dalam kategori etika eudaimonisme, pasalnya ‘bidjak’ telah menjadi tujuan utamanya. Lalu apakah ‘bijak’ sama dengan ‘bidjak’? Pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berdekatan, sehingga tanistik pantas disebut etika eudaimonisme atau etika kebijaksanaan. Menurut Aristoteles, manusia dapat mencapai kebijaksanaan dengan cara mendayagunakan fungsi akalnya dengan baik, pasalnya hanya manusia yang mendayagunakan rasionya dengan benarlah yang berbudi baik. Dengan berbudi baik maka manusia dapat mencapai kebijaksanaan. Itulah rumusan bijak menurut Aristoteles, sayangnya ‘bijak’ sendiri tidaklah bijak bila dirumuskan itulah rumusan dasar tanistik. Sama halnya dengan ‘bebas’ menjadi tidak bebas ketika menemukan definisinya? Menurut Russel, istilah terakhir itu tidaklah berarti karena mengandung antinomi, akan tetapi kita hanya ingin menegaskan bahwa ‘kebebasan’ pun tetap harus dibatasi supaya menjaganya tetap bebas. Demikian pun ‘bidjak’, tetap harus dirumuskan supaya kita mudah mengenalinya sebagai ‘bidjak’. Kalau tidak, apa bedanya istilah ‘bidjak’ dengan ‘kadjib’? Sementara ketika etika didevinisikan mengikuti rumusan Kant, masih dapatkah tanistik disebut etika? Sistem etika yang menempatkan manusia sebagai subjek yang aktif, kreatif dan otonom sangat dikedepankan oleh Kant, dengan tidak mengesampingkan pengalaman religius. Uraian Kant mengenai the antinomy of practical reason menjadi landasan kuat bagi kehidupan agamis, terutama ketika menghadapi keputusasaan (Amin Abdullah, 2004: 293). Secara khusus tanistik tidak memberi penjelasan serinci Kant, tentu sangatlah berlebihan bila tanistik dipaksakan harus mengikuti kaidah Kant. Tanistik mengakui manusia sebagai subjek yang aktif, kreatif dan otonom namun tanistik tidak mengenal antinomi. Tanistik tidak mengenal antinomi karena tanistik sendiri lahir dari antinomi. Ups,.. ini hanyalah lelucon! Mempertahankan perbedaan antara keduanya tentu lebih mengasyikkan daripada menyampuradukkan keduanya, perbedaan itulah yang hendak disikapi oleh tanistik. Tanistik lebih menekankan bertanya daripada merumuskan, berbeda dengan Kant yang sedikit bertanya dan banyak merumuskan. Mengingat kemunculan paham etika yang bermacam-macam, ke manakah tanistik berkiblat? Tanistik mendekatkan dirinya kepada etika timur yang menekankan harmonisasi kehidupan, keputusan tanistik untuk tidak menilai sesuatu secara moral mengimplikasikan bahwa tanistik hendak menghindari konflik yang selama ini terjadi. Sepintas, tanistik memang nampak seperti pengecut yang hendak melarikan diri. Ke manakah tempat pelarian tanistik bila hidup manusia tak pernah keluar dari dunia? Tanistik merumuskan dirinya melalui analisis sejauh manakah manusia memiliki dirinya sendiri. Sepintas manusia selalu mengharapkan dirinya memiliki kemandirian, dengan demikian dapat menjadi subjek. Padahal seseorang yang memiliki ruang privat ialah seseorang yang merasa kesepian dalam kesendirian. Apakah kemandirian identik dengan ruang privat?, keduanya berbeda namun berhubungan. Kemandirian berhubungan dengan privatisasi dan apakah privatisasi eksistensial? Seseorang yang memiliki dirinya menandakan kepemilikan ekistensial sementara eksistensi manusia dilihat secara universal dalam jaring-jaring kehidupan, bukan secara terpisah-pisah. Eksistensi yang ditinjau secara atomik (eksistensi atomis) sama artinya dengan eksistensi yang tidak memiliki pengaruh kehidupan. Eksistensi yang tidak memiliki eksistensi adalah bukan eksistensi, setidaknya eksistensi yang tidak eksistensial. Ketika kemandirian ditandai dengan menutup diri dari kehidupan sosial, pastilah bukan eksistensi. Akan tetapi jika kemandirian dimaknai secara sosial-spiritual, itulah eksistensi yang sedang kita diskusikan. Pada bab sebelumnya kita telah membatasi bahwa pembicaraan etika sejauh berkaitan dengan hubungan sosial, artiya, etika tidak ikut campur dalam urusan privat. Batasan tersebut sayangnya, menemui jalan buntu ketika bersentuhan dengan persoalan pahala-dosa dalam etika Islam, sebagai persoalan pribadi yang tidak sepenuhnya pribadi. Konteks kepribadian setiap muslim selalu berkaitan dengan eksistensi Tuhan, artinya tiada ruang pribadi bagi mereka. Seseorang yang memiliki kepribadiannya secara penuh, pastilah memiliki ruang pribadi yang jauh dari pantauan etika. Sayangnya, ruang privat hanyalah realitas semu. Seseorang tidaklah sungguh-sungguh memiliki ruang privat karena selalu terikat dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan metafisik. Sejauh ini saya menyepakati bahwa Etika merupakan kajian yang memiliki cakupan sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia. Dengan alasan ini pula Etika (dengan “E” besar) bukanlah sebuah cabang Aksiologi yang menjadi cabang umum Ilmu Filsafat. Semua ilmu pengetahuan adalah rumusan-rumusan etika, pasalnya suatu sistem kajian yang tidak berimplikasi terhadap kehidupan manusia secara konkret, hanyalah kajian ilmu yang semu alias tidak bermakna. Makna atau tidaknya sebuah kajian ilmu bukan ditentukan oleh metodologinya melainkan seberapa besarkah berimplikasi terhadap kehidupan manusia. Manusialah yang menggagas ilmu pengetahaun dan manusia pulalah yang akan menikmati hasilnya, demikianlah secara praktis ilmu pengetahuan dirumuskan. Etika menjadi kajian mendasar bukan hanya karena fungsinya melainkan juga letaknya yang paling setrategis, yakni menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Para pemikir semenjak zaman Yunani hingga sekarang telah menempatkan Etika sebagai cabang kajian Aksiologi, hal tersebut dikarenakan mereka hanya melihat etika dari sebuah sisi dengan melupakan sisi yang lainnya. Namun jika mereka bersedia naik sedikit lagi, pastilah dari tangga yang lebih tinggi itu aspek-aspek etika yang lain dapat lebih jelas menampak. Ilmu pengetahuan ibarat manusia dengan anggota tubuhya. Etika adalah jiwa yang menghidupi, bergerak teratur laksana darah yang dipompa jantung melalui nadi-nadi. Metafisika ialah badan, sedangkan sains alam menjadi kaki dan ilmu sosial tangannya. Sementara kepala ilmu pengetahuan ialah epistemologi. Sains alam, ketika terjun ke tengah masyarakat setelah melakukan penelitian ilmiahnya, harus mendapat persetujuan kepala (otak) supaya digerakkan oleh tangan. Begitupun sebaliknya kaki-kaki tak dapat bergerak sebelum kepala menurunkan perintah. Darah yang menggerakan harmoni dari kepala, tangan, badan dan kaki adalah seni (the art of live). Jika seseorang meletakkan metafisika sebagai kepala maka sulitlah ia bergerak selain bergerak dalam diam alias gerak di tempat. Ketika Anda meletakkan sains alam sebagi tangan dan ilmu sosial sebagai kaki, pastilah posisi berdiri Anda sangat labil, berdiri dalam ketidakpastian sama artinya dengan tidak berdiri. Sementara tangan-tangan sains alam bersifat normatif alias kaku. Lebih tepat bila epistemologi menjadi kepala, pasalnya epistemologi dapat memahami semua aspirasi anggota-anggotanya. Meskipun secara fisik otak sebagai pengendali semua anggota tubuh namun bukan otaklah yang menggerakkannya, melainkan jiwa. Jiwa merupakan kesadaran manusia, ketika kesadaran menghilang maka lelaplah tidur seseorang. Bahkan ketika darahnya mengering, maka jadilah mayat. Manusia tidak dapat disebut manusia setelah menjadi mayat. Demikian ilmu pengetahuan, tanpa etika ilmu pengetahuan tidak dapat menjadi ilmu pengetahuan. Setelah ilmu pengetahuan dianalogikan dengan seonggok manusia, maka tanistik sebagai etika telah menempati posisinya. Etika yang menjadi kesadaran ilmu pengetahuan bukanah etika normatif yang hanya mengenal baik-buruk dan/ salahbenar. Sesuai dengan analogi manusia di atas, kajian salah-benar dan/ baik-buruk pastilah menjadi kajian epistemologi. Tentunya kita tak perlu melakukan pembedahan sedemikian sadis terhadap ilmu pengetahuan yang telah mapan, hanya untuk meletakkan tanistik menjadi salah satu bagiannya. Meskipun tanistik tak dapat diakui sebagai bagian ilmu pengetahuan pun tidak menjadikan tanistik kehilangan eksistensi apalagi maknanya. Harmonisasi, itulah nilai-nilai etik yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh banyak ilmuwan. Sebutlah nama Arne Naes, mengusulkan wacana etika ekosentrisme, menginginkan supaya manusia memandang lingkungannya sebagai bagian dari dirinya. Begitupun wacana filsafat organisme yang dimunculkan oleh Alfred North Whitehead, sebuah rumusan filsafat bernada harmonik. Selanjutnya Fritjof Capra dan Michel Talbot, keduanya telah berkerja keras untuk mendamaikan fisika modern dengan mistisisme, hingga melahirkan istilah fisika baru (the new physics). Tanistik hanyalah bagian lain dari wacana-wacana yang sedang berkembang akhir-akhir ini (back to nature) hanya berbeda asumsi. Menurut kacamata tanistik, pokok persoalan yang telah memporakporandakan kehidupan manusia ialah oposisi biner. Selama mainstream manusia masih menggunakan oposisi biner, selama itu pula ijtihad-ijtihad ilmu pengetahuan tidaklah berarti bahkan terkesan mengada-ada. Bagaimana kita dapat menyelesaikan bila akar masalahnya terus dibiarkan berkembang, bahkan kita turut mengembangkannya? Paradoks semacam itulah yang hendak ditengarai oleh tanistik, tanistik melibatkan diri dalam perhelatan ilmu pengetahuan namun dengan caranya yang lain: terlibat dengan tidak melibatkan diri. Tentu berbeda sekali dengan sekedar berpura-pura terlibat. Oposisi biner adalah darah yang terus dipompa oleh jantung etika, mengalir teratur secara merata ke seluruh bagian ilmu pengetahuan. Oposisi biner, yang disimbolkan dengan logika, rasanya sulit sekali dihilangkan dari pikiran manusia. oposisi biner terlanjur telah mengakar kuat, mengokohkan pondasi ilmu pengetahuan. Seandainya oposisi biner dihilangkan, atau sekedar dimodifikasi maka seluruh bangunan ilmu pengetahuan pastilah runtuh, hal tersebut pastilah tidak dikehendaki oleh banyak orang. Jika pondasi ilmu pengetahuan hendak diubah, seperti apakah bentuk barunya? Kalau hanya sekedar anti-oposisi biner pastilah mudah namun sulitlah menentukan basis nilai sekokoh oposisi biner. Kekokohan oposisi biner sebagai basis nilai memang telah teruji hingga kini, karena diasumsikan tak ada nilai lain yang sebanding. Namun itu hanyalah cara pandang para sarjana pemuji status-quo, berbeda sekali dengan cara pandang postmodernisme. Sayangnya postmodernisme hanyalah alat, sekedar bulldozer yang dipakai untuk menghacurkan.