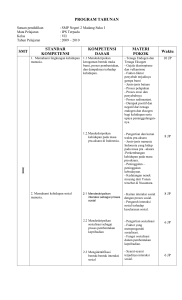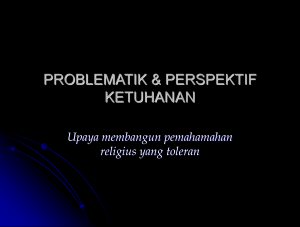View/Open - Repository | UNHAS
advertisement
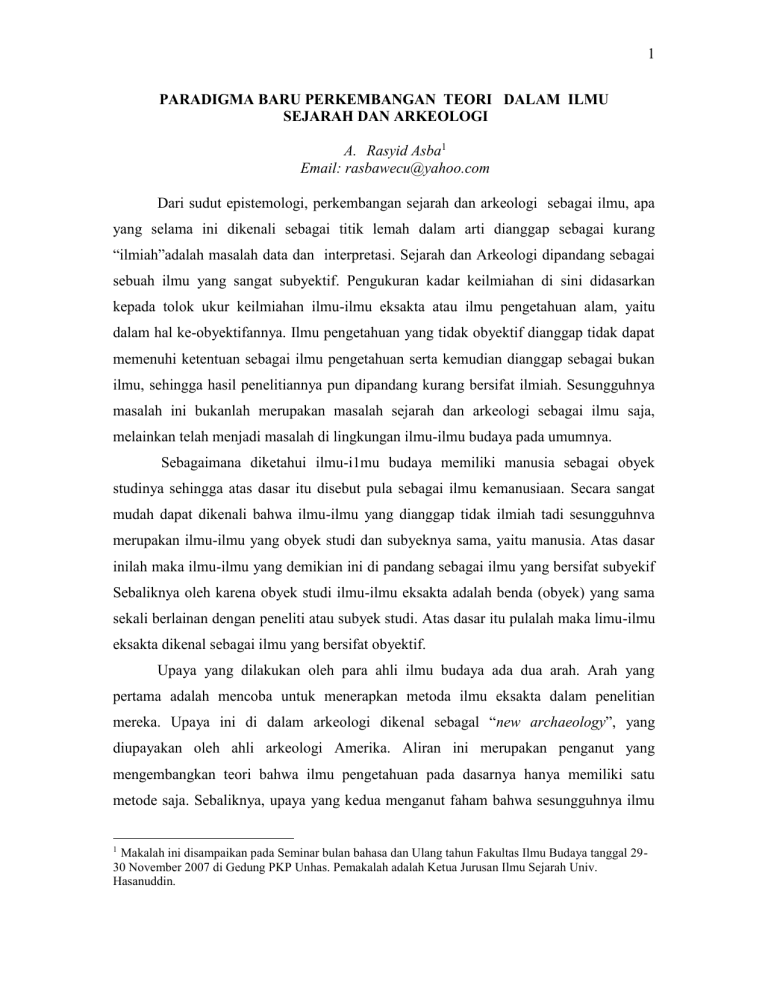
1 PARADIGMA BARU PERKEMBANGAN TEORI DALAM ILMU SEJARAH DAN ARKEOLOGI A. Rasyid Asba1 Email: [email protected] Dari sudut epistemologi, perkembangan sejarah dan arkeologi sebagai ilmu, apa yang selama ini dikenali sebagai titik lemah dalam arti dianggap sebagai kurang “ilmiah”adalah masalah data dan interpretasi. Sejarah dan Arkeologi dipandang sebagai sebuah ilmu yang sangat subyektif. Pengukuran kadar keilmiahan di sini didasarkan kepada tolok ukur keilmiahan ilmu-ilmu eksakta atau ilmu pengetahuan alam, yaitu dalam hal ke-obyektifannya. Ilmu pengetahuan yang tidak obyektif dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagai ilmu pengetahuan serta kemudian dianggap sebagai bukan ilmu, sehingga hasil penelitiannya pun dipandang kurang bersifat ilmiah. Sesungguhnya masalah ini bukanlah merupakan masalah sejarah dan arkeologi sebagai ilmu saja, melainkan telah menjadi masalah di lingkungan ilmu-ilmu budaya pada umumnya. Sebagaimana diketahui ilmu-i1mu budaya memiliki manusia sebagai obyek studinya sehingga atas dasar itu disebut pula sebagai ilmu kemanusiaan. Secara sangat mudah dapat dikenali bahwa ilmu-ilmu yang dianggap tidak ilmiah tadi sesungguhnva merupakan ilmu-ilmu yang obyek studi dan subyeknya sama, yaitu manusia. Atas dasar inilah maka ilmu-ilmu yang demikian ini di pandang sebagai ilmu yang bersifat subyekif Sebaliknya oleh karena obyek studi ilmu-ilmu eksakta adalah benda (obyek) yang sama sekali berlainan dengan peneliti atau subyek studi. Atas dasar itu pulalah maka limu-ilmu eksakta dikenal sebagai ilmu yang bersifat obyektif. Upaya yang dilakukan oleh para ahli ilmu budaya ada dua arah. Arah yang pertama adalah mencoba untuk menerapkan metoda ilmu eksakta dalam penelitian mereka. Upaya ini di dalam arkeologi dikenal sebagal “new archaeology”, yang diupayakan oleh ahli arkeologi Amerika. Aliran ini merupakan penganut yang mengembangkan teori bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya hanya memiliki satu metode saja. Sebaliknya, upaya yang kedua menganut faham bahwa sesungguhnya ilmu 1 Makalah ini disampaikan pada Seminar bulan bahasa dan Ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya tanggal 2930 November 2007 di Gedung PKP Unhas. Pemakalah adalah Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Univ. Hasanuddin. 2 pengetahuan itu terdiri dari dua jenis ilmu, oleh karena keduanya masing-masing mengembangkan “scholarship”nya sendiri. Ilmu kemanusiaan mengembangkan metode “mengerti”sedangkan ilmu eksakta metode “menerangkan”. Suatu penelitian ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari kebenaran dan merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, sama halnya dengan penelitian pada umumnya merupakan suatu proses yang terus menerus yang dilakukan secara kritis dan terorganisasi untuk melakukan analisa, memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan yang kait-mengkait. Peneliti ilmu sosial walaupun berpijak pada metode ilmiah, tetapi beberapa ciri khas yang ada di dalam masing-masing bidang ilmu, menyebabkan si peneliti dituntut memiliki ketrampilan yang khas pula dan harus didukung oleh kerangka teori dan analitik yang berbeda dalam menganalisa interaksi antar fenomena disebabkan kompleksnya fenomena-fenomena yang diteliti. Masalah-masalah sosial yang mudah berubah dan sulit diukur mengakibatkan kurangnya kemampuan melakukan prediksi, tidak se-eksak prediksi dalam ilmu alam. Penggunaan metode kuantitatif yang telah baku dan lazim dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu alam ternyata tidak cukup mampu mengungkapkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam masyarakat karena variabelvariabelnya sulit untuk diukur. Bidang ilmu humaniora yang mencakup bidang hukum, antropologi, sastra, linguistik, filsafat, sejarah, merupakan bidang ilmu yang “kurang cocok” bila dipakai pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu akhir-akhir ini dengan perkembangan teori-teori sosial yang lebih menekankan dan melebihkan unsur makna dalam ”human action” dan “interaction” sebagai determinan utama eksistensi kehidupan bermasyarakat, berkembang teori-teori yang berparadigma baru dengan konsekuensi metodologinya yang hendak lebih mengkaji aksi-aksi individu dengan makna-makna simbolik yang direfleksikannya akan lebih kualitatif daripada kuantitatif. Menurut kaum interaksionis ini, realita kehidupan itu, sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolik sehingga sulit ditangkap lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar melalui beberapa indikator yang cuma tampak di 3 permukaan, melainkan realita sosial hanya mungkin “dipahami serta ditangkap” lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal para subyek pelaku yang berpartisipasi dalam interaksi setempat. Metode kuantitatif yang merupakan metode klasik dan konvensional yang semula efektif terbukti untuk meneliti fenomena alam yang kemudian dipinjam oleh ilmu-ilmu sosial ternyata tidak banyak membantu. mengungkapkan pola-pola dalam tatanan perilaku dan kehidupan manusia serta kurang mampu mengungkapkan nilai, ide, makna dan keyakinan yang “individualized” dan studi-studi sosial yang kian banyak bersifat lintas-kultural. Hal tersebut mengingat pula metode kuantitatif yang “theory testing” untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepkan pada tingkat analisis yang makro sebagai realitas empiris. Bidang ilmu humaniora yang hendak meneliti tatanan perilaku dan kehidupan manusia yang merupakan makna aksi individu dan interaksi-interaksi antara individu, dianjurkan dan untuk banyak dicoba menggunakan metode kualitatif yang paradigma teoretik dan rancangan metodologiknya amat berbeda dengan metode kuantitatif. Mengingat kehidupan manusia saat ini sudah semakin demokratik dan “people centered”, maka metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasuskasus terbatas namun mendalam dan menyeluruh dan juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka yang tak tercampuri oleh pengamat peneliti. Selain dari itu metode kualitatif tidak menganjurkan dikembangkannya perspektif konseptual dari sudut amatan para peneliti. Humaniora adalah bidang ilmu yang memiliki objek manusia sebagai human being dalam masyarakat yang mencakup disiplin-disiplin ilmu antara lain Hukum, Politik, Antropologi, Sosiologi, Perilaku Kesehatan, Linguistik, Sastra, Filologi, Seni, Pendidikan, Sejarah, dan Filsafat. Dengan demikian yang diteliti adalah hal-hal yang lebih menekankan pada aspek budaya manusia sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu cakupan kajian ilmu-ilmu humaniora adalah tentang ekspresi dan aktualisasi yang terwujud dalam perilaku, sikap, orientasi, nilai, norma, tata makna, pandangan hidup, spiritualitas, etika dan estetika. Dengan demikian tema-tema penelitian yang dapat dikembangkan di bidang ini antara lain berkisar tentang perubahan sosial, dampak sosial 4 pembangunan, kontinuitas dan perubahan dalam masyarakat, etos kerja, dan respons masyarakat terhadap berbagai perubahan, dan sebagainya. Apa yang hendak dikemukakan dalam makalah ini adalah bagaimana arkeologi mengembangkan dirinya menjadi salah satu ilmu di antara ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dalam upayanya ini, mau tidak mau yang harus dikembangkan adalah teorinya. Atas dasar ini maka akan diungkapkan beberapa teori yang mendasari pengembangan itu. Teori tersebut akan mencakup dua aspek, yaitu teori yang berkenaan dengan hakekat data arkeologi, dan teori yang berkenaan dengan bagaimana data itu diperlakukan sesuai dengan hakekatnya. Teori yang kedua itu berkenaan dengan teori interpretasi data. Berbicara mengenai masa datang adalah berbicara mengenai arah gejala yang nampak di masa kini yang diperkirakan akan berkelanjutan di masa datang. Ilmu sejarah di masa kini sedang mengalami krisis yang diperkirakan akan berkelanjutan di masa datang. Krisis yang dimaksud adalah pengaruh post-modernisme dalam historiografi termasuk metodologi sejarah. Krisis dalam ilmu sejarah tersebut, yang juga terdapat dalam ilmu-ilmu lainnya itu, nampaknya akan berkelanjutan dalam masa mendatang terutama karena globalisasi yang akan menjadi ciri utama masa datang itu. Doktrin postmodernisme yang menegakan relativitas budaya itu menyebabkan keabsahan ilmu sebagai wacana yang menampilkan kebenaran mengenai kenyataan nampaknya akan makin terancam. Di sini saya akan membahas ciri-ciri pokok dari relativisme budaya yang sedang mengancam ilmu sejarah itu, dan mencoba menampilkan masalah itu dalam historiografi Indonesia masa kini. 1.1 Ilmu Sejarah dan Post Modernisme Istilah postmodernisme pertama kali dimunculkan oleh Jean-Francois Lyotard dan Roland Barthes. Postmodernisme sesungguhnya muncul sebagai reaksi atas "common-sense thinking" dalam kritik sastra. Kritik itu pada awalnya ditujukan pada wacana-wacana moralistik yang menganggap pandangannya sendiri sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dibantah tanpa dikenakan sangsi. Kritik postmodernisme itu kemudian berkembang menjadi kritik terhadap pandangan universalisme yang 5 terkandung dalam suatu sistem budaya tertentu (Barat) dalam kritik sastra. Masalahnya adalah bahwa doktrin ini kemudian juga dianggap berlaku dalam wacana-wacana ilmuilmu alam, ilmu-ilmu teoretis, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu sejarah. Doktrin postmodernisme bersumber pada teori linguistik dari Ferdinand Saussure yang berpendapat, bahwa bahasa hanyalah "signifier" (petunjuk) pada "signified" (yang ditunjuk). Kata, dalam teori tersebut, tidak mengacu pada kebenaran atau realitas, tetapi hanya pada suatu "konsep"." Kata-kata dengan demikian samasekali tidak mengacu pada realitas, dan arti kata-kata baru terungkap dalam hubungan-hubungannya dengan katakata lain dalam bahasa yang bersangkutan. Berkaitan dengan teori itu postmodernisme beranggapan bahwa semua wacana, seperti dikatakan Jean-Francoise Lyotard, hanyalah "language game", dan sebab itu kebenaran atau obyektifitas (realitas) tidak terungkap di dalamnya. Dalam ilmu sejarah itu berarti bahwa historiografi hanyalah permainan katakata, "language game". Para sejarawan yang terpengaruh oleh doktrin tersebut, seperti Hayden White umpamanya, berkeyakinan bahwa dalam historiografi tidak bisa dibedakan antara fiksi dan kenyataan. Bahkan bagi para sejarawan yang tergolong dalam "New Historicisme", tidak ada perbedaan hakiki antara historiografi dan teks biasa; keduanya sama karena hanyalah "language game" tanpa mengandung kebenaran mengenai kenyataan. Masalahnya, seperti dikatakan ahli filsafat ilmu C. Morris adalah. bahwa postmodernisme tidak membedakan antara wacana ilmiah pada satu pihak yang didasarkan pada observasi, inferensi logis atas evidensi faktual yang mendasari eksplanasi, dan pada pihak lain, "bahasa yang digunakan untuk menciptakan dunia fiktif, imajiner atau poetis," dimana persyaratan ilmiah tersebut diatas tidak ada (Morris: 1997: 5,6). Postmodernisme menyanggah kemampuan ilmu pengetahuan mengajukan kebenaran dengan mengatakan, bahwa kebenaran dalam ilmu pengetahuan hanyalah suatu cara untuk melegitimasi kedudukan seorang pakar, dan bahwa kebenaran ilmiah lebih banyak ditentukan oleh ideologi yang dominan pada saat tertentu. Dengan kata lain, postmodernisme tidak mempertimbangkan bahwa setiap cabang ilmu memiliki prosedur untuk menentukan kausalitas yang mengacu pada kebenaran atau realitas; postmodernisme sengaja melupakan bahwa setiap cabang ilmu memiliki apa 6 yang oleh C.Lloyed disebut sebagai "structure of reasoning". 2 Apa yang pada awalnya sesungguhnya muncul hanya sebagai suatu upaya menyempurnakan kritik sastra itu, kini makin gencar dikembangkan oleh berbagai ahli dalam berbagai cabang ilmu. Postmodernisme beranggapan bahwa doktrinnya relevan bagi semua cabang ilmu atau wacana, karena semua cabang ilmu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Maka tidak mengherankan kalau kini muncul berbagai usaha untuk menegakkan kembali keabsahan ilmiah dan menegakkan kembali nilai-nilai tentang kebenaran ilmiah. Gerakan ini terutama muncul karena berkembangnya aliran realisme dalam filsafat ilmu sejak tahun-tahun 1980-an seperti yang terkandung dalam tulisan-tulisan dari Rom Harre, Dudley Shapere, Roy Bhaskar, dan sebagainya. Realisme filosofis juga sekaligus membantah keabsahan historis materialisme dalam ilmu sejarah. Berikut ini akan saya kemukakan dua buah sanggahan mengenai postmoderisme dalam ilmu sejarah, yang pertama khusus menyangkut .pendekatan empiris dalam ilmu sejarah dan yang kedua menyangkut pendekatan strukturis. Yang pertama berasal dari seorang ahli filsafat ilmu, yaitu C. Behan Mc. Cullagh, dan yang kedua berasal dari seorang ahli sejarah ekonomi, yaitu C. Lloyed. Tetapi sebelumnya patut dikemukakan terlebih dahulu bentuk postmodernisme yang merasuk dalam ilmu sejarah. Postmodernisme paling jelas nampak dalam pendekatan empiris dalam ilmu sejarah, pendekatan yang paling umum di kalangan para ahli sejarah. Pendekatan empiris dalam ilmu sejarah itu (baik yang bersifat diskriptif maupun yang menggunakan berbagai teori kausalitas) paling mudah disusupi oleh doktrin postmodemisme karena pada dasarnya modus komunikasi pendekatan ini adalah kisah atau naratif. Pendapat postmodemisme, bahwa semua ilmu tidak terkecuali hanyalah "language game" sangat mudah mempengaruhi pendekatan empiris dalam ilmu sejarah yang mengandalkan natarif. Behan McCullagh, seorang ahli filsafat ilmu, memperlihatkan pengaruh postmodernisme dalam tiga aspek dari ilmu sejarah, yaitu (a) metode sejarah yang digunakan ahli sejarah, (b) pengaruh budaya pada ahli sejarah, dan (c) penggunaan bahasa oleh ahli sejarah3 . 2 3 Chritopher Lloyd. The Structures of History. Blackwell: Cambridge University Press. P. 133-141. 7 Pertama mengenai metode sejarah. Seperti diketahui, ilmu sejarah sesungguhnya tidak mempelajari masa lampau, tetapi ilmu sejarah mempelajari sumber sejarah atau peninggalan dari masa lampau seperti dokumen-dokumen, arsip dan kesaksian lisan. Khususnya mengenai pendekatan empiris dalam ilmu sejarah, penjelasan tentang suatu peristiwa, riwayat hidup atau struktur sosial, bertumpu pada uraian mengenai motivasi atau "intention" dari pelaku sejarah yang diyakini menjadi dasar dari tindakan tokoh sejarah yang bersangkutan. Kalangan post-modernisme berpendapat, bahwa motivasi atau intention yang tercantum dalam dokumen sejarah, tidak mengacu pada kenyataan atau realitas karena pandangan tokoh sejarah dalam sumber sejarah hanyalah gambaran yang berkaitan dengan konsep-konsep budaya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Sumber sejarah hanyalah teks-teks berupa "language game" yang tidak mencerminkan kenyataan. Kenyataan pada dasarnya tidak dapat diungkapkan melalui sumber sejarah, dan menurut postmodernisme tidak perlu. Demikian pun historiografi atau hasil karya sejarah hanyalah teks-teks yang tidak mengandung kebenaran. Dengan kata lain, menurut postmodernisme karya sejarah hanyalah teks yang didasarkan pada teks, atau "language game" yang didasarkan para "language game". Kedua mengenai dampak budaya dalam ilmu sejarah. Postmodernisme berpendapat bahwa setiap ahli sejarah mau tidak mau dipengaruhi oleh konsep-konsep tertentu yang berasal dari sistem budaya masing-masing ahli sejarah. Dengan demikian, menurut doktrin itu, kesimpulan yang diambil ahli sejarah dari sumber sejarah yang digunakannya (inferensi) sudah diwarnai oleh konsep-konsep budaya tertentu. Ini berarti penjelasan mengenai suatu peristiwa, biografi atau struktur sosial bisa berbeda-beda dari sejarawan yang satu dan sejarawan lain, sejalan dengan perbedaan-perbedaan budaya para ahli sejarah itu. Dengan demikian, sekali lagi menurut postmodernisme, historiografi tidak mengandung kebenaran realitas, dan sebab itu historiografi mengandung unsur relativisme budaya. Ketiga mengenai bahasa. Menurut para penganut postmodernis, seperti Roland Barthes (ahli filsafat ilmu) pengaruh teori linguistik dari Saussure jelas menonjol dalam hal ini. Seperti dikemukakan di atas, menurut Suassure, "kata-kata samasekali tidak mengacu pada hal-hal yang terdapat dalam dunia [kenyataan] tetapi hanya mengacu pada 8 konsep-konsep, dan bahwa makna dari kata-kata atau konsep-konsep itu seluruhnya terkandung dalam hubungan-hubungannya dengan kata-kata lain dalam bahasa yang bersangkutan". Kata "coklat", menurut Saussure, "bukanlah suatu konsep yang otonom yang mengacu pada ciri-ciri independen, tetapi merupakan suatu istilah dalam sistem istilah warna yang didefinisikan oleh hubungan-hubungannya dengan istilah-istilah lain yang membatasinya" (McCullan 1998: 37). Karena historiografi juga menggunakan katakata, maka menurut teori tersebut, historiografi juga tidak mengandung kebenaran (realitas), tetapi mengungkapkan suatu peristiwa yang maknanya terkandung dalam hubungan-hubungan antara kata-taka yang bersangkutan dalam suatu sistem bahasa. 1.2 Teori Korelasi Dalam Kebenaran Sejarah C.Behan Mc.Cullagh sebagian besar menerima kritik yang dilontarkan postmodernisme kepada pendekatan empiris-naratif dalam ilmu sejarah . Dalam hal ini ia menyalahkan "correspondence theory of truth" dalam pendekatan sejarah empiris itu, seolah-olah empiris dalam suatu peristiwa, seperti biografi atau struktur sosial, mengacu pada kebenaran yang obyektif (realitas). McCullagh menggantikan teori korespondensi yang dipakai dalam ilmu eksatta diganti dengan teori korelasi ("correlation theory of truth") dalam ilmu sejarah. Teori korespondensi berpendapat bahwa apa yang diungkapkan dalam historiografi empiris itu sama benar dengan kenyataan, sedangkan teori korelasi lebih hati-hati dan mengatakan bahwa apa yang diungkapkan dalam histioriografl empiris itu tidak sama benar dengan kenyataan, tetapi ada kaitannya dengan kenyataan (korelasi). Berdasarkan teori korelasi kebenaran sejarah itu, Mc.Cullan membantah pandangan dalam doktrin postmodernisme, dan mencoba membuktikan melalui penelitian historiografis, bahwa para ahli sejarah, khususnya yang menggunakan pendekatan naratifisme, dapat mengungkapkan kebenaran (realitas) berdasarkan sumber sejarah (dokumen, arsip, kesaksian lisan) karena memiliki cara-cara tertentu (metode sejarah) untuk menilai teks atau dokumen, dan cara-cara tertentu untuk menjelaskannya (diskripsi atau analisis). Bahkan cara yang digunakan ahli sejarah untuk membuat inferensi (inference) atau menarik kesimpulan dari dokumen bisa obyektif, karena pada 9 dasarnya tindakan-tindakan manusia di masa lampau dialami juga oleh manusia masa kini. McCullagh bisa menerima pendapat postmodernisme bahwa para ahli sejarah terikat pada kondisi budaya mereka. Namun hal itu tidak harus menghasilkan relativisme budaya dalam historiografi. Ahli sejarah selalu menjelaskan fakta sejarah melalui generalisasi yang bersifat diskriptif, interpretatif ataupun melalui teori-teori kausalitas tertentu. Generaliasi-generaliasi dan teori-teori itu senantiasa bisa diubah-ubah agar lebih mencerminkan realitas. Dengan demikian metode sejarah dan historiografi bisa juga menjamin bahwa apa yang disampaikan melalui bahasa dalam bentuk naratif itu bukan sekedar "language game" tetapi memiliki kaitan (korelasi) dengan kenyataan. Kemampuan akademik para ahli sejarah itulah yang menjamin bahwa historiografi tidak terjerumus dalam relativisme budaya, dan tetap memiliki kadar realitas yang cukup tinggi. 1.3. Strukturisme Dalam Ilmu Sejarah Sejumlah ahli sejarah lain mencoba mengatasi serangan dari postmodernisme itu dengan upaya menegakkan kembali teori korespondensi dalam ilmu sejarah. Dengan kata lain, mereka berupaya untuk mencari cara-cara yang bisa menjamin realitas sepenuhnya dalam ilmu sejarah, bukan sekedar kaitan atau korelasi saja. Inilah yang oleh sementara ahli disebut sebagai pendekatan "strukturis". Patut dikemukakan di sini bahwa pendekatan strukturis tidak sama dengan pendekatan struktural yang bersumber pada aliran An'nals dari Prancis atau sosiologi Talcott Parson. Kalangan ahli sejarah strukturis samasekali meninggalkan pendekatan empiris dalam ilmu sejarah dan memanfaatkan teori-teori sosiologi tertentu, khususnya konsepkonsep "emergency" dan "agency", untuk mengembangkan suatu pendekatan strukturis. Pendekatan ini mengacu pada cara kerja ("structure of reasoning") dalam ilmu-ilmu alam, tetapi disesuaikan dengan ilmu sejarah dimana data hanya dapat diperoleh dari peninggalan-peninggalan dari masa lampau (sumber sejarah). Dikatakan mirip dengan ilmu-ilmu alam karena pertama-tama realitas yang dicari bukan keseluruhan realitas (yang hanya diketahui oleh Tuhan), tetapi hanya apa yang 10 dinamakan "causal factors" atau "causal mechanism" yang tidak kasat mata (unobservable). Seperti halnya dalam alam, fenomena dapat disaksikan oleh panca indra manusia (observable), tetapi sebab-sebab terjadinya fenomena itu tidak kasat mata (unobeservable). Di dunia ini benda-benda jatuh ke bawah (fenomena, observable), tetapi causal mechanism-nya, yaitu grafitas, tidak kasat mata (unobservable); suara dari radio dapat didengar, atau gambar pada televisi dapat dilihat, tetapi medan magnetik yang menyebabkannya tidak dapat ditangkap oleh pancaindra (unobservable). Demikian pula pendekatan strukturis bertujuan menampilkan realitas dalam bentuk causal factors yang tidak tertangkap oleh pancaindra. Fenomena-fenomena seperti pemberontakan, revolusi, perubahan sosial, dsb. dapat ditangkap melalui pancaindra, karena terkandung dalam sumber sejarah yang dapat dibaca dan dipelajari. Tetapi sebabmusababnya tidak muncul secara empiris dalam sumber sejarah, karena tersembunyi dalam struktur sosial yang unobservable itu. Secara teoritis terdapat interaksi antara manusia (individu atau kelompok) dan struktur sosial dimana mereka' berasal. Maka untuk menampilkan causal factor yang unobservable itu seorang sejarawan yang mendapat datanya dari sumber sejarah harus menggunakannya untuk menganalisa struktur sosial agar dapat menampilkan interaksi antara manusia yang konkrit (observable) dan struktur sosial yang tidak kasat mata itu (unobservable). Pengertian struktur sosial yang unobservable dalam pendekatan ini berasal dari sosiologi realis. Struktur sosial bukanlah kumpulan manusia yang kongkret (agregasi), tetapi suatu unit yang memiliki ciri-ciri umum yang bersifat "emergence" berupa peranperan, aturan-aturan, pola interaksi, dan pemikiran (mentalite). Tetapi berbeda dengan sosiologi pada umumnya, menurut pendekatan strukturis, perubahan sosial tidak disebabkan oleh struktur sosial lainnya (kriminalitas yang meningkat disebabkan pengangguran yang meningkat), tetapi perubahan struktural justru disebabkan tindakantindakan kongkret dan observable dari manusia (individu atau kolektfitas) yang dengan sengaja mengubah peran, aturan, interaksi berdasarkan pemikiran tertentu. Pendekatan strukturis bertujuan menjelaskan perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Pemikiran, pandangan, wawasan manusia kongkret yang menjadi anggota suatu kelompok sosial tertentu, seperti juga dikemukakan dalam pendekatan empiris, 11 terkandung dalam sumber sejarah, yang -dalam pendekatan strukturis disebut sebagai "expressed intentions". Causal factors yang diperoleh melalui analisa teoretis atas sumber sejarah itu dapat diuji kembali kebenarannya pada "expressed intentions" lain. Dengan demikian, seperti halnya dalam ilmu-ilmu alam, teori-teori sejarah memiliki kemampuan prediksi. Sebab-musabab dalam metodologi strukturis itu memiliki ciri-ciri universal yang dapat dirumuskan dalam bentuk wacana. Namun hakekat ilmu sejarah sebagai "ilmu yang mempelajari manusia dalam waktu" (Marc Bloch), menyebabkan para ahli sejarah menyadari betul bahwa unsur perubahan senantiasa menentukan penjelasannya tentang peristiwa-peristiwa. Sebab itu perbedaan-perbedaan waktu dan tempat juga membatasi rumusan causal factors. Inilah perbedaan lainnya antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu alam. Contoh-contoh dari pendekatan strukturis ini bisa kita temukan umpamanya dalam karya-karya dari Max Weber dan Norbert Elias (sosiolog), Mandelbaum dan Le Roy Ladurie (ahli sejarah) Cliffort Geertz (antropolog), dan masih banyak lagi (Lloyed 1993). . Kalau dibandingkan antara kedua pendekatan tersebut di atas (empiris dan strukturis), maka harus dikatakan, bahwa di Indonesia pendekatan empiris lebih menonjol dibandingkan dengan pendekatan strukturis. Hasil historiografi empiris sesungguhnya bisa dibedakan antara karya-karya sejarah yang diskriptlf dan yang anarkis. Di Indonesia diskripsi atau interpretasi terutama digunakan oleh para penulis sejarah yang "amatir" (bukan profesional) dan hasilnya bisa kita saksikan dalam toko-toko buku, baik yang menggunakan peristiwa sebagai unit, atau hidup manusia maupun struktur sosial. Banyak sekali karya-karya jenis ini yang berupa biografi atau otobiografi yang bermunculan dalam tahun-tahun yang lalu. Diantaranya ada yang dapat dikatakan cukup baik, seperti karya A.M. Nasution, baik yang unit diskripsinya adalah suatu peristiwa, atau hidup manusia (otobiografi), maupun struktur sosial (perang kemerdekaan). Kita dapat mengajukan keberatan-keberatan metodologis mengenai karya-karya tersebut di atas. Antara lain mengenai sumber sejarahnya yang tidak selalu jelas atau dikemukakan secara gamblang, atau kesaksian lisan yang tidak menggunakan cara-cara oral history yang baik. Selain itu tentunya kebenaran fakta sering harus diragukan, bahkan tidak lengkapnya uraian mengenai suatu peristiwa atau struktur sosial 12 menyebabkan terjadinya distorsi dan sebab itu tidak memenuhi persyaratan teori kebenaran sejarah. Kalangan akademisi, terutama Prof. Sartono dari UGM dan mereka yang dipromisikannya sebagai doktor, bisa digolongkan sebagai ahli sejarah profesional yang menggunakan analisis dalam penelitiannya, baik untuk menjelaskan suatu peristiwa, kehidupan manusia, ataupun struktur sosial. Para pelopor dalam pendekatan ini (yang oleh Sartono dinamakan pendekatan multi-dimensional) lebih banyak tertarik pada peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai "collective action". Dalam perkembangan lanjut perubahan sosial juga menarik perhatian mereka, salah satu contohnya adalah disertasi mengenai menak Sunda. Tetapi terutama para ahli sejarah ekonomi yang karyakaryanya bermunculan sejak awal 1990-an menaruh perhatian pada perubahan sosial, cq perubahan ekonomi. Pendekatan strukturis belum banyak menarik perhatian kalangan akademisi di Indonesia. Sampai kini baru beberapa disertasi dan monografi yang menjurus kepada metodologi ini, dengan mengikuti jejak-jejak Norbert Elias atau Charles Tilly. Diharapkan dalam masa mendatang lebih banyak ahli sejarah menaruh minat pada pendekatan ini. II . Ilmu Arkeologi dan Perkembangannya Masalah yang dihadapi oleh arkeologi adalah hakekatnya sebagai ilmu yang memiliki obyek yang berkenaan dengan fenomena yang berkembang untuk masa tertentu atau bersifat historis. Seperti halnya dengan ilmu astro fisika, biologi evolusioner, tektonik lempengan dalam geologi, ilmu yang demikian ini tidak dapat diingkari berhadapan dengan obyek studi yang sangat fragmentaris. Hal itu disebabkan oleh karena obyek studinya hanya merupakan peninggalan fisik yang tidak sengaja ditinggalkan. Tambahan pula, peninggalan itu pun hanyalah merupakan peninggalan yang tahan terhadap proses pelapukan alami, sehigga dapat sampai kepada peneliti masa kini. Dengan demikian maka apa yang sampai pada kita sesungguhnya adalah materi tanpa makna. Adapun makna yang dimaksudkan di sini adalah makna penyebab terjadinya atau dalam hal arkeologi makna sebagai yang dimaksudkan oleh pembuat ataupun pemakainya dahulu. 13 Menghadapi keadaan obyek studi yang demikian itu maka tidaklah mengherankan apabila tujuan arkeologi pada pertamanya adalah rekonstruksi. Tujuan arkeologi tidak bisa lain dari rekonstruksi oleh karena di samping jarak waktu, ahli arkeologi juga dipisahkan oleh perbedaan kebudayaan dengan obyek studinya. Peninggalan fisik kebudayaan yang diteliti oleh peneliti sangat berlainan dari kebudavaan ahli arkeologi itu sendiri. Sebagai akibat dari tujuan ilmu ini adalah timbulnya permasalahan epistemologis. Masalah pertama adalah sejauh mana makna tadi dapat direkonstruksikan dari peninggalan kebudayaan fisiknya. Adapun masalah keduanya adalah bagaimana ahli arkeologi dapat melakukan rekonstruksi itu. Dengan lain perkataan, dengan metode apa rekonstruksi itu dapat dilaksanakan. Makalah ini akan berupaya mengemukakan berbagai usaha yang telah dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang bersifat epistemologis tadi. Pendekatan ini dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa ulasan yang dikemukakan merupakan pengungkapan upaya arkeologi untuk memantapkan dirinya sebagai ilmu. Masalah ini dianggap penting terutama agar para ahli arkeologi dapat ikut secara sadar menjaga wibawa keilmuannya dalam melakukan rekonstruksi. Kesadaran yang dimaksudkan adalah menyadari bahwa, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, ditinjau dari hakekat data, ditinjau dari sudut keilmuan serta dengan demikian juga metodenya, arkeologi memiliki berbagai keterbatasan. Dengan demikian maka sebagai akibat dari kesadaran akan keterbatasan metodenya, maka ahli arkeologi kemudian akan dapat mengupayakan cara untuk menanggulanginya. Melalui upaya yang demikian ini maka peninggalan kebudayaan fisik yang terkumpul berkat berbagai penggalian yang telah dilaksanakan dapat direkonstruksikan, sehingga pengetahuan kita tentang kebudayaan masa lalu akan dapat bertambah dengan cepat. Pada gilirannya dari sudut arkeologi itu sendiri, kesadaran ini akan dapat mengembangkan arkeologi sebagai ilmu. 2. .1. Hakekat Data Arkeologi Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, obyek arkeologi adalah peninggalan kebudayaan fisik. Melalui kebudayaan fisik ini ahli arkeologi memperoleh informasi tentang kebudayaan masa lalu. Selanjutnya, berdasarkan atas informasi ini ahli arkeologi melakukan rekonstruksi kebudayaan yang meninggalkan informasi itu. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa rekonstruksi sesuatu kebudayaan yang telah musnah 14 dilaksanakan melalui peninggalan informasinya yang kebetulan sampai kepada kita. Kiranya perlu ditekankan di sini dua hal. Hal pertama adalah bahwa tiap kebudayaan memiliki ciri masing-masing yang berbeda antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Demikian pula halnya, kebudayaan yang telah musnah yang menjadi obyek penelitian arkeologi berbeda dengan kebudayaan ahli arkeologi yang meneliti kebudayaan itu. Hal kedua adalah penggunaan kata kebetulan oleh karena memang informasi tentang kebudayaan yang sampai kepada ahli arkeologi untuk diteliti itu tidak diciptakan sebagai informasi yang dengan sengaja ditinggalkan oleh para pendukungnya. Kita semua mengetahui bahwa peninggalan fisik itu sampai kepada kita dalam bentuk artefak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ahh arkeologi menghadapi artefak dari sebuah kebudayaan yang sama sekali asing dari kebudayaannya sendiri. Kondisi data arkeologi sebagaimana yang diutarakan di atas menimbulkan dua permasalahan, yaitu masalah epistemologis dan masalah metodologis. Masalah epistemologis yang dihadapi oleh ahli arkeologi adalah bahwa di dalam menghadapi informasi tentang kebudayaan yang telah punah dan yang tercipta di masa lalu, tanpa dapat ia hindari, haruslah ia perlakukan melalui pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang kebudayaannya sendiri dari masa kini. Proses berpikir yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai archaeological reasoning. Sebagai akibat dari data yang demikian ini maka archaeological reasoning terhadap data terjadi seperti berikut. Kebudayaan yang telah punah itu dapat dianggap sebagai fakta yang bersifat historis atau fakta yang telah tiada lagi (sebuah historical facts). Pada hakekatnya fakta atau kebudayaan yang telah punah inilah yang oleh ahli arrkeologi itu hendak direkonstruksikan. Namun demikian fakta historis ini meninggalkan records dalam hal ini archaeological records, dalam wujud artefak. Selanjutnya ahli arkeologi, sesuai dengan pengetahuan pengalaman dan kemampuannya, melakukan observasi dan analisis terhadap records ini. Observasi dan analisis itu dilakukannya berdasarkan kebudayaannya sendiri serta bukan berdasarkan kebudayaan yang meninggalkan records tadi. Mengapa hal ini terjadi demikian, oleh karena ahli arkeologi tidak dapat meneliti kebudayaan yang telah menjadi sebuah historical fact. Dengan demikian maka ahli arkeologi hanya dapat mengkajinya melalui archaeological 15 records tadi. Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa hasil observasi dan analisis ahlli arkeologi itu, yang secara teknis dikenal sebagai data sesungguhnya merupakan ciptaan peneliti. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh karena observasi dan analisis terhadap records itu dilaksanakan pada masa kini, berdasarkan kebudayaan peneliti dan ilmu arkeologi mutakhir, walaupun records itu sendiri berasal dari kebudayaan masa lalu. Keadaan inilah yang seringkali terlupakan oleh para peneliti dan yang sejak dekade 80-an diingatkan kembali berkat timbulnya perhatian pada masalah teori dan yang pada gilirannya mengangkat permasalahan yang bersifat epistemologis. Dengan demikian maka data arkeologi itu berupa deskripsi tentang pola-pola yang ditampakkan dari teknik tipologi, klasifikasi dan diperlakukan sebagai contemporary fact4. Akhirnya ahli arkeologi melakukan rekonstruksi melalui data ini. Atau dengan lain perkataan merekonstruksikan historical fact melalui contemporary fact. Aspek lain dari hakekat data arkeologi, masih dalam kaitan dengan rekonstruksi, adalah dari namanya sebagai kebudayaan materi atau fisk Nama ini mengandung dua unsur yaitu materi dan kebudayaan. Unsur materi jelas menunjukkan kaitannya dengan alam, yaitu menyangkut bahan dengan apa artefak itu dibuat. Melalui materi ini arkeologi berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti masalah penentuan waktu, analisis dan sebagainya. Makalah ini tidak akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang demikian ini. Adapun masalah yang akan menjadi perhatian adalah aspek yang kedua yaitu masalah kebudayaan. Sebagaimana diketahui, kebudayaan materi terciptakan sebagai akibat perbuatan manusia. Namun demikian perbuatan ini bukanlah merupakan perbuatan yang asal-asalan tanpa tujuan dan maksud tertentu, melainkan perbuatan yang dilandasi oleh konsep dan makna tertentu. Sebagai akibatnya maka perbuatan itu pun dilaksanakan dalam pola-pola yang baku oleh pendukung suatu kebudayaan. Dengan sendirinya kebudayaan materi yang dihasilkan oleh perbuatan berpola itu pun tercermin dalam wujudnya sebagai kebudayaan materi. Walaupun kebudayaan yang menghasilkannya telah musnah, dan dengan demikian ikut pula hilang konsep-konsep dan makna yang menghasilkannya, namun pola-pola tersebut tetap Lihat Lewis R. Binford, “Data, relativism and archaeological science” dalam Man, New Series, Vol. 22, No. 3, halaman 391 dst. Juga Jeremy Sabloff, Lewis Binford dan Patricia McAnany, “Understanding the archaeological records” dalam Antiquity, Vol. 61 Number 232, halaman 203 dst. 4 16 membayang dalam kebudayaan materi. Kaitan antar artefak dari berbagai tipe apakah yang diketemukan dalam lapisan dan pit, dalam situs maupun wilayah, dalam pekuburan maupun landscapes, tanpa terkecuali masih mempertahankan sisa.-sisa pola perbuatan budaya yang menciptakannya. Kenyataan di atas juga tetap berlaku walaupun kebudayaan materi, atau yang lebih tepat artefak itu, pada waktu sampai kepada ahli arkeologi telah mengalami banyak pengaruh perubahan, baik sebagai akibat alam maupun olah manusia dan bahkan oleh ahli arkeologi sendiri pada waktu melakukan pengggalian atau ekskavasi. Selanjutnya tergantung kepada kemampuan ahli arkeologi sendiri dalam menemukan dan mendeskripsikan pola-pola tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pola-pola tersebut pada waktu penciptaannya dikendalikan oleh konsep-konsep tertentu. Namun demikian perlu diingat bahwa konsep yang abstrak ini tidak dapat dilihat, baik pada waktu kebudayaan itu masih hidup, apalagi pada waktu telah musnah dan menjadi peninggalan kebudayaan materi. Dengan demikian maka, melalui kebudayaan materi, ahli arkeologi hanya dapat menemukan kembali pola-pola tersebut. Selanjutnya rekonstruksi konsep yang mendasari pelaksanaan dan pewujudannya didasarkan atas interpretasi terhadap pola-pola tersebut. Apabila kita boleh meminjarn istilah antropologi, maka penemuan kembali pola-pola itu adalah etik, sedangkan yang dicoba untuk direkonstruksikan itu adalah emik-nya. Mengingat bahwa konsep yang diupayakan untuk direkonstruksi itu bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati melalui peninggalan kebudayaan materi, maka ada sementara ahli arkeologi yang berpendapat bahwa rekonstruksi sebagaimana yang dimaksudkan itu tidaklah mungkin dilaksanakan. Rekonstruksi ahli arkeologi hanyalah mungkin dicapai sampai tingkat etik saja. Atas dasar ini maka dalam makalah ini akan disampaikan pengembangan dan penerapan teori dalam arkeologi yang mencoba mengatasi kemandegan metodologi tadi. Teori itu adalah hermeneutik dan semiotik. 2.2 Hermeneutik 17 Dasar dari pengembangan teori hermeneutik5 ini adalah bahwa kebudayaan materi merupakan bagian dari perwujudan budaya dan makna konseptual. Dengan demikian maka dimungkinkan bagi ahli arkeologi untuk menjangkau pengertian yang lebih jauh dari sekedar tentang penggunaan fisik dan terbatas pada obyek penelitian saja, melainkan sampai kepada makna simbolisnya yang lebih bersifat abstrak. Dalam hal ini upaya untuk menggali makna konseptual dad kebudayaan materi dapat dibandingkan dengan interpretasi terhadap suatu bahasa, karena proses mengerti itu berkaitan dengan penggalian makna dari bahasa yang berwujud fisik atau materi. Sebagaimana halnya bahasa perwujudan makna simbolis ini diatur oleh peraturan-peraturan dan kesepakatan khusus, serta berdasarkan sebuah sistem tertentu. Sistem itulah yang membedakan satu kebudayaan satu dari kebudayaan lainnya. Walaupun sistem itu membedakan kebudayaan yang satu dari yang lain, namun tidak ditentukan oleh masalah-masalah yang bersifat ekonomis, biologis dan fisik. Atas dasar inilah maka perbandingan dengan masalah penerjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain dengan interpretasi dari kebudayaan yang satu dari kebudayaan yang lain dilaksanakan. Ahli arkeologi bekerja dalam kerangka makna yang dimilikinya dan dengan demikian berhadapan dengan kebudayaan yang ditelitinya yang memiliki kerangka makna berbeda bahkan mungkin sama sekali berlainan oleh karena diwujudkan melalui ketentuan dan pengaturan yang berbeda pula. Atas dasar itu maka upaya untuk mengungkapkan makna simbolis itu dapat dibandingkan dengan proses penerjemahan, hanya dalam hal ini penerjemahan itu dilakukan dari kebudayaan yang diteliti ke kebudayaan peneliti. Perlu pula dicatat bahwa ahli arkeologi sesungguhnya memiliki dua kerangka makna, yaitu kerangka makna yang diperoleh dari ilmunya dan kerangka makna yang terwujud dari kebudayaannya. Bagaimana penerjemahan itu dapat dilaksanakan didasari atas tiga pengertian. Pertama perlakuan bahwa kebudayaan materi diciptakan dengan maksud tertentu dalam sebuah kerangka makna konseptual. Walaupun Kebudayaan materi itu diciptakan dan penggunannya diatur dalam satu kerangka makna konseptual tertentu, namun kebudayaan materi yang sama dapat pula diberi makna konseptual lain melalui berbagai cara. Atas dasar ini maka di dalam memperlakukan kebudayaan materi kita harus membedakan 5 Dikembangkan dari Ian Hodder, The Theory and Practice in Archaeology. London, Routledge, 1992. Lihat juga Ian Hodder, Reading the Past. Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 18 antara makna dari fungsi. Adapun yang dimaksudkan dengan fungsi adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh ahli arkeologi seperti “apa maksud pemberian bentuk benda seperti itu?” “Mengapa bangunan tempat tinggal, istana misalnya, dibuat dari bahan yang mudah rusak sedangkan candi dibangun dengan mempergunakan bahan yang tahan lama dari batu kali”. Mudah dimengerti bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak dapat mengungkapkan makna konseptualnya, oleh karena mungkin ada makna-makna konseptual yang tidak diketahui oleh pembuat atau penggunanya. Makna ini, misalnya, menjawab pertanyaan apa konsep yang melatar belakangi wujud sebuah candi. Makna konseptual yang demikian ini pun mungkin tidak dikenali oleh pendiri maupun pengguna candi. Dengan demikian maka terhadap makna ini pun perlu dibedakan makna yang tidak dikenali dan makna yang tidak dimaksudkan. Makna yang tidak dikenali menyangkut makna yang tidak dikenali atau secara samar-samar disadari seperti misalnya kebiasaan menata dan membersihkan kamar tidur atas dasar ketentuan kebudayaan Jawa yang “melarang” orang lain memasuki kamar tidur, misalnya. Makna yang tidak dimaksudkan. Makna yang demikian adalah ketidakpastian dari pihak pencipta atau pengguna suatu obyek bahwa orang lain akan memberikan makna yang sama dengannya terhadap obyek yang sama. Kemungkinan yang demikian ini dapat terjadi oleh karena orang lain dapat menghubungkan obyek tersebut dengan kerangka makna yang lain sehingga memberikan makna yang berbeda. Dalam, kaitannya dengan kebudayaan materi, obvek itu telah terpisah dari pencipta atau penggunanya. Hal ini terlebih-lebih lagi dapat terjadi sebagai akibat dari pemisahan oleh waktu yang lebih lama atau tempat yang lebih jauh, sehingga obyek itu dapat diberi berbagai makn tergantung dari penempatannya dalam berbagai konteks. Sebagai contoh sebuah candi, misalnya, yang maksud pendirian sesungguhnya belum diketahui, namun sekarang diberi makna sebagai makam, bukan makam dan seterusnya. Kedua pengertian bahwa kebudayaan materi harus dipelajari dalam konteks. Hal ini berarti bahwa makna simbolis artefak-artefak tertentukan dalam konteksnya. Dengan demikian maka ahli arkeologi haruslah terlebih dahulu merumuskan konteks itu terlebih dahulu di dala mana obyek penelitiannya memiliki hubungan yang mempengaruhi pemberian maknanya agar ia dapat mengetahui makna pada waktu obyek itu diciptakan. 19 Adapun yang dimaksudkan dengan konteks adalah keseluruhan lingkungan yang relevan. Konteks sebuah obyek arkeologi (apakah itu sebuah situs atau kebudayaan) adalah semua hubungan yang relevan dengan maknanya. Hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan dinamis antara obyek dengan konteksnya. Sebagai akibat dari penempatan obyek ke dalam konteks, maka konteks itu sendiri akan mengalami perubahan. Dengan demikian terdapat hubungan dialektis antara obyek dengan konteks dan teks dengan konteks. Sebagai akibat dari hubungan dialektis ini maka konteks memberi makna kepada obyek dan sekaligus juga mendapatkan makna dari obyek. Ketiga adalah bahwa kebudayaan materi merupakan sesuatu yang aktif dan tidak pasif. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini adalah bahwa kebudayaan materi tidaklah tercipta sebagai produk sampingan perilaku manusia. Hal ini disebabkan oleh karena semua tindakan manusia merupakan tindakan yang kreatif dan interpretatif. Sebagai akibatnya maka makna tidak tampak dengan sendirinya, demikian pula tidak dapat secara pasif dimengerti, melainkan harus secara aktif dibangun pengertiannya. Pada dasarnya cara para ahli arkeologi melakukan interpretasi terhadap makna konseptual adalah melalui konsep yang ada di kepalanya. Apabila seorang ahli menemukan sebuah pola, yang menyerupai sebuah bangunan, maka ia akan memulai analisisnya dengan konsep yang ada di kepalanya. Selanjutnya, konsep bangunan yang masih dapat dikatakan netral ini akan dikembangkan lebih lanjut, karena konsep netral itu dapat diarahkan sebagai bangunan suci, rumah, atau gudang dan seterusnya. Pengembangan ini akan menentukan analisis selanjutnya. Apabila kita dapat menerima kenyataan ini, maka tugas ahli arkeologi adalah bagaimana ia dapat mencapai pengertian yang sedekat mungkin dengan makna konseptual tadi. Untuk ini ia harus tetap berangkat dari konsep bahwa kebudayaan materi selalu harus ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek materi dan aspek kebudayaan. 2.3. Semiotik Teori semiotik6 diterapkan dalam arkeologi, juga didasarkan atas anggapan bahwa sepanjang sejarahnya, manusia menciptakan perkakas bagi keperluan hidupnya tetapi 6 Dikembangkan dari Jean Molino, “Archaeology and Symbol Systems”, dalam Jean Claude Gardin dan Christopher S. Peebles (eds.), Representations in Archaeology. Bloomington, Indiana Polis, Indiana University Press, 1992. 20 juga sistem simbol. Semiotik, kadang-kadang juga disebut semiologi, sesungguhnya merupakan ilmu tentang tanda. Atas dasar itu, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksudkan dengan tanda dalam semiotik. Konsep tentang tanda ini dapat dibagi dalam tiga unsur. Sebuah tanda adalah sesuatu yang memiliki arti tentang sesuatu bagi seseorang, di setiap kesempatan atau tindakan. Dengan demikian tanda ini memiliki arti dalam hubungannya dengan orang atau tanda lain- Setiap obyek atau fenomena hanya dapat diungkapkan melalui tanda lain yang merupakan “interpretan” dari tanda yang pertama. Tanda mewakili obyeknya, mengacu pada obyeknya namun hanya berarti melalui “interpretan”. Fungsi tanda dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu semiologi komunikasi dan semiologi representasi. Fungsi tanda dalam semiologi komunikasi adalah sebagai sarana atau wahana komunikasi. Pada fungsi yang kedua tanda merupakan pengganti dan berfungsi sebagai kognitif. Contoh dari kedua fungsi ini adalah bahasa. Menurut semiologi bahasa dan instrumen, dalam sejarah manusia, berkembang tidak saja sejajar melainkan juga saling berhubungan, karena keduanya merupakan ekspresi dari ungkapan peradaban yang sama. Semua wujud tanda memiliki ciri-ciri modus perwujudannya masing-masing: tanda yang mewujud sebagai materi, sebagai produksi, dan sebagai resepsi. Dalam pengertian ini tanda merupakan produksi, sesuatu yang dengan sengaja diciptakan. Sebagai akibatnya, maka tanda memiliki wujud materi dan menjadi obyek, antara lain ilmu pengetahuan, sehingga dapat dianalisa. Aspek lain dari obyek yang diakibatkan oleh hakekatnya yang demikian itu adalah bahwa walaupun obyek itu dengan sengaja diciptakan, namun arti obyek itu terbuka lebar bagi “interpretan”nya. Kenyataan ini tidak menutup kemungkinan bahwa arti yang diberikan oleh “interpretan” menjadi berbeda, dari apa yang dimaksudkan oleh penciptanya. Bagaimana teori tentang tanda itu, dapat dikembangkan dalam arkeologi. Untuk ini dapat memasukinya melalui pernyataan Leslie A. White, ahli antropologi, yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia merupakan mahluk simbolis dan bukan mahluk rasional, yang menciptakan simbol dan sekaligus juga alat-alat. Simbol menjadi 21 sama mandiri dan sama produktifnya dengan alat-alat. Atas dasar ini dapat dibentuk teori tentang proses-proses simbolik. Sejarah peradaban manusia telah menujukkan, bahwa manusia melalui penciptaan alat-alat secara berhasil telah menaklukkan dunianya. Keadaan yang sama berlaku pula pada simbol. Berbekal simbol-simbol yang diciptakannya, peradaban manusia manata pengalamannya dan kemudian menghadapi dunianya di dalam dan melalui simbol tersebut. Atas dasar ini maka manusia, melalui fungsi simbol sebagai mediasi dan sekaligus juga wahana untuk menjaga jarak antara dirinya dengan dunianya seperti halnya dengan alat-alat, dapat tidak saja membuat proyeksi ke masa lalu melainkan juga ke masa depan. Sebagaimana yang telah berulangkali dikemukakan di muka, penerapan dan pengkaitan semiotik dengan arkeologi secara teoretis adalah juga dimulai dari hakekat data. Ditinjau dari sudut semiotik, data dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari data itu sendiri dan dari ahli arkeologi. Ilmu pengetahuan pada umumnya sesungguhnya tidak mengenal adanya data empiris yang betul-betul murni. Setiap datum senantiasa terkait dengan hipotesa teoretis, oleh karena data itu sebagian merupakan hasil observasi dan sebagian reproduksi sebagaimana yang telah diutarakan. Sementara itu, dari fihak ahli arkeologi yang melakukan observasi juga dipengaruhi oleh kebudayaannya, termasuk di dalamnya ilmunya. Pengaruh yang demikian ini juga dapat diamati pada ilmu pengetahuan kemanusiaan, yang dihadapkan pada masalah yang timbul sebagai akibat dari peranan peneliti sebagai observer dan analis yang menciptakan data kemanusiaan. Arkeologi sebagaimana halnya dengan ilmu kamanusiaan yang bekerja berdasarkan bekas atau jejak yang ditinggalkan oleh pencipta atau penggunanya sebagai obyek penelitiannya. Selanjutnya dalam melaksanakan pengkajian terhadap bukti-bukti kemanusiaan, ia berhadapan dengan data yang homogen dengan persepsinya. Ia mencoba untuk mengerti dan kemudian mereproduksi data yang telah ia olah sesuai dengan pengetahuannya. Dengan demikian maka dalam banyak hal, pada, dasarnya pengertian tentang obyek berkaitan erat dan sangat tergantung pada pengetahuan subyek. Sebagaimana yang telah berulangkali disampaikan, di dalam menghadapi obyek kultural, subyek yang juga kultural secara jelas sangat berperan dalam penciptaan data, serta dalam pemilihan fakta. Masalah yang timbul adalah seberapa besar pengaruh peran tersebut terhadap arkeologi sebagai ilmu. Adapun yang menjadi permasalahan adalah 22 yang bersifat ontologis dan yang bersifat metodologis. Permasalahan pertama berkenaan dengan pertanyaan apakah ada sebuah obyek penelitian arkeologi yang dapat dipisahkan dari subyek kultural yang mempelajarinya. Ditinjau dari permasalahan ontologis ini, maka obyek arkeologi, yang sebagaimana dikatakan di atas terutama berwujud jejak atau bekas, tidaklah mengandung permasalahan yang bersifat epistemologis dalam arti apakah obyek kultural yang tercipta tadi obyektif atau tidak. Dalam ilmu budaya, khususnya dalam perspektif semiologi tentang bentuk-bentuk simbolik, maka kedudukannya menjadi jelas, bahwa jejak dan bekas itu benar-benar ada dalam arti pada kedudukannya yang netral dan sebagai apa adanya. Kedudukan ontologis yang demikian ini memberikan kesempatan bahwa obyek dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan persepsi dan pengetahuan subyek kultural saja. Secara metodologis kesempatan untuk melakukan analisis secara tidak terbatas ini dimungkinkan oleh faktor-faktor yang berkenaan dengan “keberadaan secara berlapis” bekas dan jejak. Adapun yang dimaksudkan dengan lapis di sini adalah lapisan analisis, yaitu jejak sebagai lapisan pertama yang bersifat materi, diperlakukan sebagai obyek bagi berbagai analisis awal yang tergantung pada modelmodel yang dipergunakan. Walaupun demikian, perlu kiranya diingat bahwa jejak pada tingkat material sesungguhnya telah merupakan hasil dari aktivitas dan reproduksi dari subyek kultural. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah bahwa jejak tadi mungkin diketemukan melalui ekskavasi dan direproduksi dalam bentuk deskripsi. Peringatan yang lain adalah bahwa konfigurasi yang diungkapkan sebagai hasil analisis pada jejak lapis materi tidak dengan sendirinya mencerminkan konfigurasi dari kegiatan sosial atau budaya dari mereka yang meninggalkan jejak-jejak itu. Pada gilirannya, konfigurasi tadi juga memberikan kesempatan untuk melakukan dimensi analisis yang baru. Dengan demikian maka kemungkinan penerapan teori semiotik dalam arkeologi adalah kira-kira sebagai berikut. Pertama pada lapis pertama, ahli arkeologi menghadapi data untuk mencoba mengerti dan kemudian merekonstruksikan fenomena. Kedua adalah analisis terhadap lapis netral. Dari records ini ahli arkeologi melakukan identifikasi, klasifikasi, dan mengungkapkan pola atau konfigurasi, untuk kemudian menyajikannya dalam bentuk model simbolis. Terakhir adalah pengungkapan makna terhadap berbagai konfigurasi itu. Jejak-jejak itu dapat diungkapkan maknanya hanya dalam hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang meninggalkan jejak-jejak itu. 23 DAFTAR PUSTAKA Marc Bloch (1989). Pleidooi voor de Geschiedenis of Geschiedenis als Ambacht. Nijmegen: Sun (terjemahan dari bahasa Francis). Leonard Blusse & Femme Gaastra (1998,1. On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in Retrospect. London, Brookfield USA, Singapore: Aldershot. Fernand Braudel (1988) Cilivization and Capitalism, 15th – 18th Century. London: Collins/Fontana Press, 3 jilid (terjemahan dari bahasa Francis). Femand Braudel (1979). Geschiedschrijving. Paarn: Basisboeken Ambo (terjemahan dari bahasa Francis). Peter Burke (1 992). History and Social Theory. London: Polity Press. ; Peter Burke (1990). The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89. Polity Press. E.H. Carr (1990,). What is History. Penguin Books, Rev. ed. (cetakan pertama 1961). R.G. Collingwood (1956). The Idea of History. New York: Oxford University Press. William H. Dray (1989). On History and Philosophers of History. Leiden: E.J. Brill. Norbert Elias (1982). Het Civilisatieprocess. Sodogenetische en Psychogenetische Onderzoekingen. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij het Spectrum (terjemahan dari bahasa Jerman 1937). Haskel Fain (1970). Between Philosophy and History. The Resurrection of Speculative Philosophy of History Within the Analytic Tradition. Princeton University Press. William H. Frederick (1989). Pandangan dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1945). Jakarta: Penerbit Gramedia (terjemahan dari bahasa Inggris). Francis Fukuyama (1992) The End of History and the Last Man. New York: Avon Books. Frank Furedi (1993J. Mythical Past, Elusive Future. History and Society in an Anxious Age. London, Boulder (Colorado): Pluto Press. Hans-George Gadamer (1992). Truth and Method. New York: Crossroad (terjemahan dari bahasa Jerman Wahrheit und Methode, 1960). Clifford Geertz (1983). Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. University of California Press. Clifford Geertz (1980| Negara: The Theater State in Nineteenth Century Ball. Princeton University Press. Felix Gilbert (190). History: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burkhardt. Princeton University Press. James Click (1994). Genius: Richard Feynman and Modern Physics. London: Abacus. Rom Harre (1970). The Principles of Scientific Thinking. London: Macmillan. C.G. Hempel, "The Function of General Laws in History", da/am Journal of Philosophy, no. 39, 1942. 24 C.A. Hooker, "An Evolutionary Naturalist Realist Doctrine of Perception and Secondary Qualities", dalam C.W. Savage (ed.), Minnesota Studies in Philosophy of Science, IX, 1978. Martin Holis (1994). The Philosophy of Social Science. An Introduction. London: Cambridge University Press. Lyn Hunt (ed.J. The New Cultural History. University of California Press. J.J.P. de Jong (1998). De Waaier het Fortuin. De Nederlanders in Azie en de Indonesische Archipel, 1595- 1950. Den Haag: SOU Uitgevers. Gerrit J. Knaap (1996). Shallow Waters, Rising Tides. Shipping and Trade in Java Arround 1775. Leiden: KITLV Press. Gerrit J. Knaap (1987). Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oostindische Compagnie en de Bevolking van Ambon, 1656-1695. Dortrecht - Province: Forris Publications. Thomas Kuhn (1994). Structure of Scientific Revolution. University of Chicago Press. Second Ed. Enlarged. Kuntowidjojo (1992| Metodologi Sejarah. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana. J.C. van Leur (1960). Asian Trade and Society. Esseys in Asian Social and Economic History. Den Haag-Bandung: Voorhoeve. Thomas Lindblad, ed. (1996). Historical Foundation of a National Economy in Indonesia, 1890s- 1990s. Amsterdam: KNAW. Christopher Lloyed (1993). The Structures Christopher Lloyed (1986). Explanation of History. London: Basil Blackwell. in Social History. London: Basil Blackwell. Chris Lorenz (1990). De Constructie van het Veheden. Een Inleiding in de Theorie van de Geschiedenis. Amsterdam: Boom Meppel. M. Mandelbaum (1967). The Problem of Historical Knowledge. New York: Harper Torchbooks (cetakan pertama 1 938). C. Behan McCullagh (1998). The Truth of History. London-New York: Routledge. Luc Nagtegaal (1996;. Riding the Dutch Tiger. The Dutch East India Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1740. Leiden: KITLV Press. Christopher Norris (1997). Against Relativsm. Philosophy of Science, Deconstruction, and Critical Theory. London: Blackwell. Anthony Reid (1993). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Chiang Mai: Silkwormbooks, 2 Jilid. Carl Sagan ( i996). The Demon-Haunted World. Science as a Candle in the Dark. London: Headline Publishing. David Joel Steinberg, ed. (1971). In Search of Southeast Asia. A Modem History. Honolulu: University of Hawaii Press. Sartono Kartodirdjo (1984). Ratu Mil. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 25 Sartono Kartodirdjo (1982). Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: P.T. Penerbit Gramedia. Nico Schulte Nordholt & Leontine Visser, eds. (1997). llmu Sosial di Asia Tenggara. Dan Partikularisme ke Universalisme. Jakarta: :P3ES. Dudley Shapere, "Method in the Philosophy of Science and Epistemology: How to Inquire About Inquiry and Knowledge", dalam N.J. Nersessian (ed.) The Process of Science. Dortrecht: Martinus Nijhoff 1 987. Heather Sutherland (1983). Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan (Terjemahan dari bahasa Inggris). Richard Tarnas (1991). The Passion of the Western Mind. Understanding the Ideas that Have Shaped Our World View. New York: Ballantine Books. Charles Tilly (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company. Charles Tilly (1981). As Sociology Meets History, Studies in Social Discontinuity. Orlando, San Diego, San Fransisco, New York, London: Academic Press Inc. Charles Tilly (1967). The Vendee. Cambridge University Press. Jaap Vogel (1998), "J.C. vartteur, 1908-1942: A Short Life in History", dalam Blusse & Gaastra, op.cit. him. 13-38. Immannuel Walerstein (1991). Unthinking Scocial Science. The Limits of Nineteenth Century Paradigms. London: polity Press. W.H. Walsh (1951). Introduction to Philosophy of History. New York: Hutchinson. David K. Wyatt (1998), "The Eighteenth Century in Southeast Asia", dalam Blusse & Gaastra, him op.cit. 39-55.
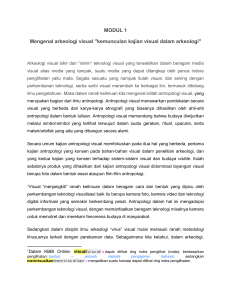
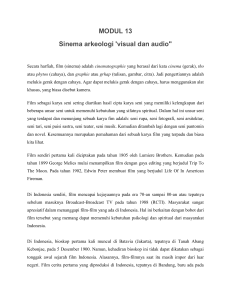
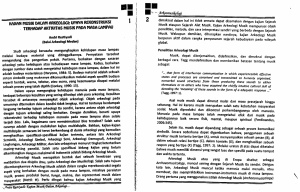


![Modul Pendidikan Agama Khatolik [TM1]](http://s1.studylibid.com/store/data/000101410_1-b4cb9e47485eadc2a3d44a7db8cdca17-300x300.png)