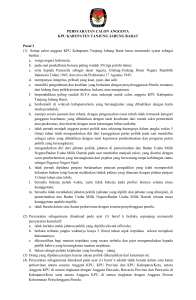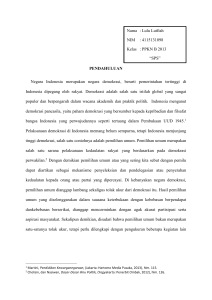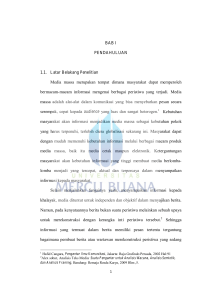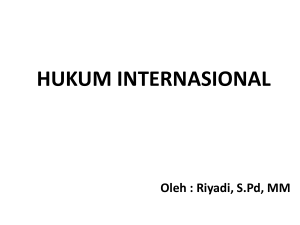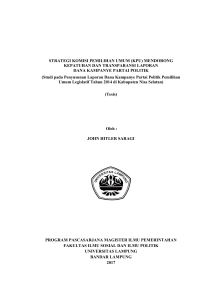progresifitas hukum pemilu mahkamah konstitusi
advertisement

RechtsVinding Online MENJAGA PROGRESIFITAS HUKUM PEMILU* Oleh: Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H.** Hukum tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini tidak saja akibat makin agresifnya lembaga legislasi tetapi juga karena sangat progresifnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melahirkan putusan terkait Pemilu. Putusan-putusan MK tersebut secara garis besar terdiri dari putusan tentang perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dan putusan tentang pengujian undang-undang (PUU). Dari rangkaian putusan yang disistematisasi tersebut terlihat bahwa telah lahir beberapa prinsip hukum baru yang terkait Pemilu sebagai mekanisme penting negara demokrasi konstitusional. Prinsip baru ini lahir dari berbagai terobosan hukum, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil dalam penyelesaian sengketa Pemilu (Janedjri M. Gaffar, 2013). Prinsip baru tersebut menunjukkan bahwa putusan MK terkait Pemilu sangat diwarnai oleh beberapa karakter yang menjadi penyangga utama hukum progresif, yaitu: pertama, hukum adalah untuk manusia dan bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the making) sehingga harus serta peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Karakter ini terlihat dari putusan MK mengembalikan hak pilih sebagai salah satu hak asasi manusia para bekas anggota organisasi terlarang PKI atau yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI. Putusan MK tersebut mengakhiri diskriminasi yang ada sejak masa awal Orde Baru. Sebagai putusan hukum, Putusan MK telah diorientasikan untuk kepentingan pemenuhan hak asasi manusia yang tidak boleh didiskriminasi tanpa ada putusan pengadilan. Begitu juga dengan putusan MK yang menyatakan bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan tidak dapat ditiadakan karena alasan administratif, yaitu tidak terdaftar di DPT. Putusan ini dibuat untuk kepentingan pemenuhan hak memiilih dan hak dipilih yang terancam karena persoalan administratif. Contoh lain yang menunjukkan karakter bahwa hukum adalah untuk manusia adalah putusan MK yang menyatakan bahwa aturan hukum tidak boleh merenggut hak seseorang selamanya karena tindak pidana yang pernah dilakukan orang tersebut. Putusan ini dilandasi oleh argumentasi bahwa larangan seseorang yang pernah dipidana karena tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Karakter ini juga semakin kuat diperlihatkan melalui putusan MK yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, dengan melegalisasi penggunakan sistem noken di Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara. Kedua, karekter hukum progresif yang menolak mempertahankan status quo RechtsVinding Online dalam berhukum. Hal ini terlihat dari putusan MK yang memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk menjadi calon bagi jabatan-jabatan yang dipilih; memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam Pemilukada; mendiskualifikasi calon yang tidak jujur terkait jati dirinya pernah dipidana dalam perkara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan; serta memberikan sanksi diskualifikasi karena pelanggaran yang selain bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, juga dilakukan dengan cara teror dan intimidasi yang melanggar hak rasa aman warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ketiga, karakter hukum progresif yang memberikan perhatian besar pada peranan perilaku manusia dalam hukum. Hal ini terlihat dari putusan MK mengenai hubungan antara KPUD dan DPRD, sehingga untuk penyelenggaraan Pemilukada yang Jurdil, KPUD tidak boleh bertanggungjawab kepada DPRD yang merupakan lembaga politik. Kemudian terlihat juga dari putusan MK yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk mengangkat anggota Panwaslu. Kewenangan tersebut tidak diberikan kepada KPU, karena sangat berpotensi melemahkan tugas Panwaslu itu sendiri. Putusan MK lainnya yang menguatkan karakter ini adalah putusan yang menegaskan bahwa asas jujur dan adil dalam Pemilu hanya dapat terwujud jika penyelenggara Pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga penyelenggara Pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik, sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. (Janedjri M. Gaffar, 2013) Dari karakter progresif ini kemudian lahir prinsip baru dari putusan MK seperti: Prinsip Kebenaran Materiil Mengatasi Kebenaran Formil; Prinsip Keputusan dalam Proses Demokrasi Dapat Dibatalkan Pengadilan; Prinsip Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara; Prinsip Memerhatikan Perkembangan Masyarakat, serta prinsip non diskriminasi. Terdapat optimisme bahwa putusan MK tersebut -beserta prinsip-prinsip hukum yang lahir di dalamnya- merupakan yurispridensi yang harus diikuti dalam kehidupan bernegara. Hal ini karena putusan MK tidak hanya mengikat pihakpihak yang berperkara, tetapi juga mengikat semua orang (erga omnes). Optimisme semacam ini sayangnya masih menghadapi beberapa tantangan pada level implementasi. Sebagai contoh, untuk putusan MK yang melegalisasi penggunakan sistem noken di Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ternyata tidak diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat regulasi teknisnya. KPU masih menganggap bahwa noken papua dalam konsepnya yang asli –yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Duniabelum memenuhi syarat teknis pelaksanaan demokrasi. Putusan MK ini oleh KPU hanya dianggap mengikat para pihak saja dalam perkara tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengaku telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Nomor 1 tahun 2013 tentang Juknis pemungutan suara sistem Noken yang sering dilakukan masyarakat di daerah Pegunungan Papua sebagai suatu kearifan lokal dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurut KPU, noken bisa digunakan jika memenuhi syarat sesuai Juknis KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang teknis penggunaan noken. Ada beberapa syarat sesuai Juknis yakni, saat RechtsVinding Online pemungutan suara noken harus di tancapkan, diikat pada sebatang kau atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Tetapi harus noken harus di tancapkan di area Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang suaranya masuk ke noken harus datang ke TPS, serta tidak bisa diwakilkan guna memenuhi asas langsung. Regulasi teknis yang dibuat KPU ini dapat dianggap sebagai salah contoh tidak ditaatinya putusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final Mahkamah Konstitusi, belum tentu memiliki implikasi riil terhadap implementasi putusannya. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin implementasi putusan final (special enforcement agencies). Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final (Ahmad Syahrizal, 2007: 116). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling penting dalam upaya mengkonkritkan konstitusi di tengah masyarakat. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi perlu pula disertai dengan perangkat “pengaman” yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara agar benar-benar dapat diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihadang oleh “kekuatan” lain dengan alasan yang seolah-olah konstitusional. Kondisi semacam ini perlu diantisipasi oleh MK dan tidak lagi menganggap bahwa putusan MK dengan “aman” berlaku dengan sendirinya (self-executing) tanpa memerlukan upaya paksa. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo kepastian hukum tidak jatuh dari langit (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh sebab itu, kepastian hukum tidak jatuh bersamaan lahirnya undang-undang beserta pasal-pasal dan prosedurnya. Kepastian hukum membutuhkan pengerahan tenaga dan kekuatan. Sehingga, Satjipto Rahardjo yakin bahwa kepastian hukum adalah suatu usaha. Kalau memang demikian halnya maka adalah tidak tepat bila ingin mencapai karakteristik putusan final yang implementatif hanya mengandalkan akseptabilitas normatif diktum Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mendorong pemikiran bahwa tugas peradilan konstitusi tidak sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggungjawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Implementasi adalah fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejewantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara. Richard H. Fallon dalam Implementation the Constitution mengatakan: If we the Court central role as implementing the Constitution, we can better understand why the Justice sometimes must compromise their own view about what would be best in order to achieve coherent, workable constitutional doctrine (Richard H. Fallon, 2001: 37). Dengan demikian, implementasi kaidah-kaidah utama UUD NRI 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, RechtsVinding Online tetapi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya seperti KPU. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD NRI 1945. * Tulisan ini adalah adopsi dari resensi penulis atas buku Janedri M Gaffar (Sekjen Mahkamah Konstitusi) yang dimuat di Majalah Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi No.85 Maret 2014. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah _77_Majalah%20Edisi%20Maret%202014%20.pdf **Penulis adalah Analis Hukum di BPHN Kementerian Hukum dan HAM