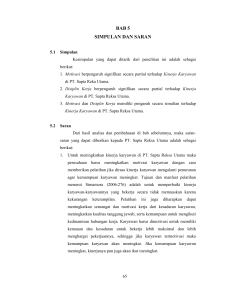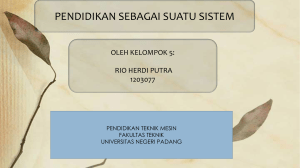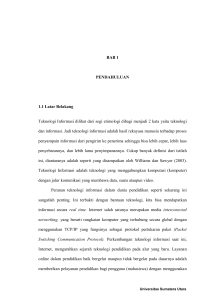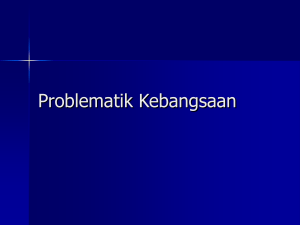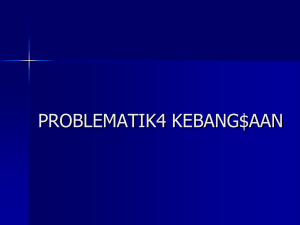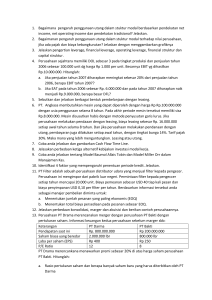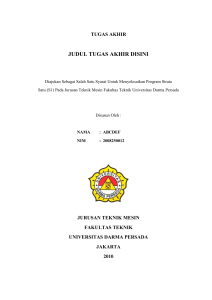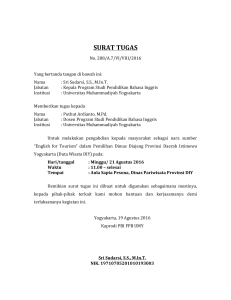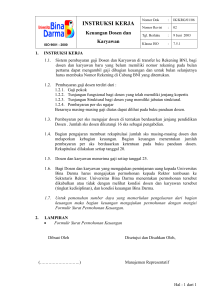1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
advertisement
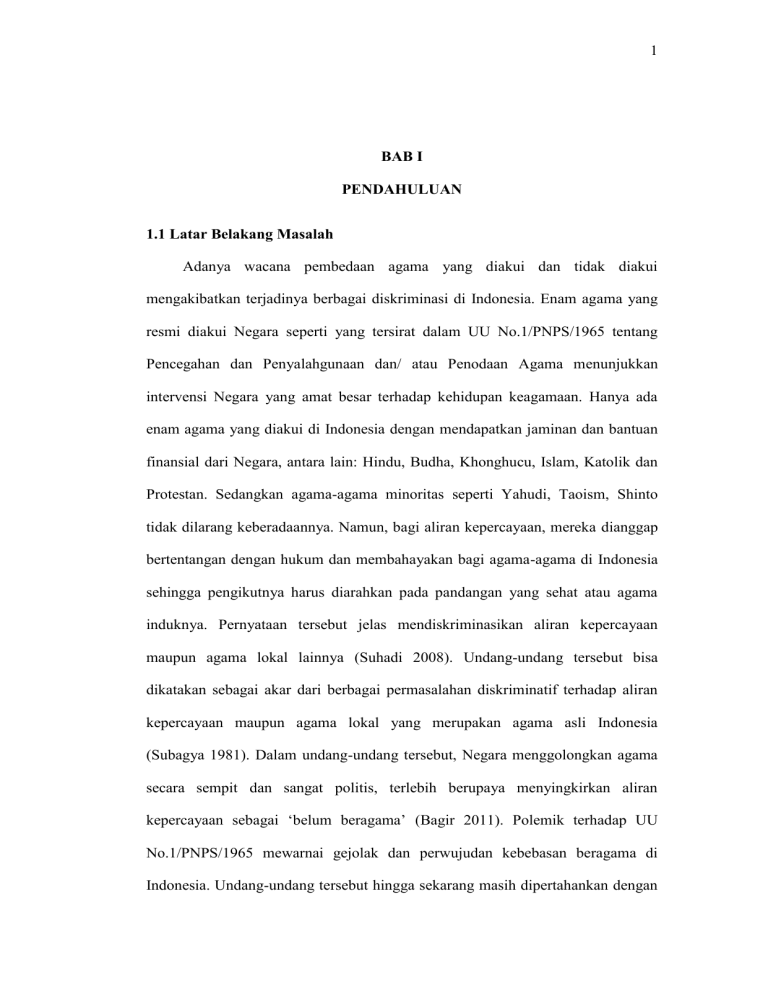
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Adanya wacana pembedaan agama yang diakui dan tidak diakui mengakibatkan terjadinya berbagai diskriminasi di Indonesia. Enam agama yang resmi diakui Negara seperti yang tersirat dalam UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama menunjukkan intervensi Negara yang amat besar terhadap kehidupan keagamaan. Hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia dengan mendapatkan jaminan dan bantuan finansial dari Negara, antara lain: Hindu, Budha, Khonghucu, Islam, Katolik dan Protestan. Sedangkan agama-agama minoritas seperti Yahudi, Taoism, Shinto tidak dilarang keberadaannya. Namun, bagi aliran kepercayaan, mereka dianggap bertentangan dengan hukum dan membahayakan bagi agama-agama di Indonesia sehingga pengikutnya harus diarahkan pada pandangan yang sehat atau agama induknya. Pernyataan tersebut jelas mendiskriminasikan aliran kepercayaan maupun agama lokal lainnya (Suhadi 2008). Undang-undang tersebut bisa dikatakan sebagai akar dari berbagai permasalahan diskriminatif terhadap aliran kepercayaan maupun agama lokal yang merupakan agama asli Indonesia (Subagya 1981). Dalam undang-undang tersebut, Negara menggolongkan agama secara sempit dan sangat politis, terlebih berupaya menyingkirkan aliran kepercayaan sebagai ‘belum beragama’ (Bagir 2011). Polemik terhadap UU No.1/PNPS/1965 mewarnai gejolak dan perwujudan kebebasan beragama di Indonesia. Undang-undang tersebut hingga sekarang masih dipertahankan dengan 2 ditolaknya uji materiil UU No.1/PNPS/1965 pada tahun 2010 (Koban 2011). Uji materiil UU No.1/PNPS/1965 oleh Mahkamah konstitusi berlangsung mulai Desember 2009 hingga April 2010 (Bagir 2011). Melalui TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, disini tertulis bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah termasuk agama. Sejak inilah pemerintah Orde Baru mulai menegaskan dirinya tentang kedudukan aliran kepercayaan di Indonesia. Namun dalam penjelasannya tidak ada definisi yang jelas baik agama maupun kepercayaan yang dimaksud. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan tentang hak kebebasan beragama bagi setiap warga Indonesia, baik agama maupun kepercayaan, namun kenyataanya, dalam praktek maupun kebijakan Negara banyak yang tidak selaras dengan landasan konstitusi tersebut. Konsepsi istilah agama di Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama mensyaratkan adanya wahyu Tuhan, memiliki nabi, kitab suci, dan pengakuan berskala internasional (Saidi et al 2004) (Kholiludin 2009). Terlihat bahwa definisi tersebut sangat politis, sempit dan Abrahamik (Bagir 2011). Jane Monnig Atkinson menambahkan satu syarat lagi yakni bahwa agama akan membawa ke arah yang progresif menuju modernisme (Atkinson 1978). Ditegaskan lagi bahwa definisi tersebut sangat didominasi perspektif agama Kristen dan Islam yang mensyaratkan adanya wahyu tuhan yang tertulis dalam kitab suci, adanya pedoman hukum bagi umatnya, adanya jemaat dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa (Picard dan Madinier 2011). Padahal jika mengacu pada kriteria 3 tersebut, kerokhanian Sapta Darma telah memenuhi semua itu untuk bisa disebut sebagai agama. Kerokhanian Sapta Darma mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan YME, memiliki wewarah tujuh sebagai pedoman, Hardjosapuro sebagai penerima wahyu, pemimpin ajarannya disebut Tuntunan Agung sedangkan penganutnya disebut warga. Namun sebaliknya, fakta yang terjadi mereka tidak mendapat pengakuan untuk itu dan harus puas dengan label aliran kepercayaan (Suhadi 2008). Kenyataan di Indonesia banyak sekali dijumpai agama-agama lokal yang jumlahnya ratusan. Hal ini termasuk bentuk diskriminasi kepada mereka yang tidak memeluk agama besar dunia terlebih agama yang berlabel resmi. Padahal banyak aliran-aliran keagamaan muncul namun karena masih berada dalam payung agama resmi sehingga tidak dipandang sebagaimana aliran kepercayaan (Howell 2005). Harapan besar dari penghayat aliran kepercayaan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Negara dan sejajar dengan agama-agama lainnya. Pengakuan ini dalam politik rekognisi tidak sebatas membiarkan orang lain melakukan kewajibannya, akan tetapi juga menghargai mereka dengan segala perbedaannya (Bagir 2011). Pengakuan sangat diperlukan dalam menghadapi kemajemukan yang ada di kehidupan bermasyarakat seperti di Negara ini. Menurut penuturan salah seorang warga kerokhanian Sapta Darma, dengan tidak diakuinya aliran kepercayaan sebagai agama, sangatlah memungkinkan ancaman bagi mereka diintimidasi, perlakuan kekerasan, diskriminatif, bahkan diklaim 4 sesat.1 Bahkan walaupun mereka diperbolehkan hidup di Indonesia, namun Negara tidak memberi perlindungan yang sama maupun jaminan finansial layaknya enam agama resmi lainnya (Banawiratma, et al 2010). Dalam sejarahnya, pembinaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam wewenang Departemen Agama sebelum dikeluarkannya GBHN tahun 1978. Karena dalam GBHN tersebut disebutkan bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan agama, maka wewenang tersebut dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1982). Paska Reformasi urusan aliran kepercayaan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (KPPO) (Suhadi 2010). Kini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka diberi wadah yang bernama Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Esa yang dibentuk pada tahun 2014. Ada 78 aliran kepercayaan pada tahun 1950 di seluruh Indonesia, lalu meningkat menjadi 300 pada tahun 1964. Karena adanya peristiwa G30S pada tahun 1965 mereka dilarang, dibekukan, dan dibubarkan maka jumlah tersebut berkurang drastis antara tahun 1964 hingga 1971. Pada tahun 1972 terdaftar 644 aliran pada sekretariat Kerjasama Kepercayaan di tingkat pusat maupun cabang (Djoko Dwiyanto dan Saksono 2011). Keberadaan aliran kepercayaan di Negara ini tidak dalam posisi menguntungkan karena begitu banyak hambatan baik berupa kebijakan Negara yang menyudutkan, desakan dari agama resmi maupun 1 Komunikasi personal, 29 Oktober 2014 di sanggar candi Sapta Rengga jl. Taman Siswa Surokarsan Mg.II Yogyakarta. 5 stigmatisasi negatif dari masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, bangkitnya aliran kepercayaan yang merupakan regenerasi agama asli Indonesia merupakan reaksi melawan serangan modernisasi yang berguna sebagai filter yang hendak menyebabkan kemerosotan moral bangsa. Menurut Subagya, penghayat kepercayaan mengembangkan kepribadian asli dalam menghadapi segala pengasingan (Djoko Dwiyanto dan Saksono 2011). Bagi penghayat kepercayaan, mereka yakin bahwa ajaran tersebut akan memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional yang berupa pembentukan budi luhur yang akhir-akhir ini sering terabaikan. Namun sayangnya niat baik tersebut tidak disambut baik oleh beberapa pihak. Terbukti dengan adanya tindak diskriminasi yang sering merugikan mereka. Praktek diskriminasi banyak dijumpai dalam kehidupan beragama di negara ini. Kebijakan Negara pun terkadang bersifat diskriminatif di satu sisi untuk satu pihak, namun netral untuk pihak lain. Misalnya saja kebijakan Negara yang mengharuskan semua warganya untuk memiliki satu agama, hal ini mengundang protes bagi warga yang bukan penganut agama yang diakui Negara. Mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan hak sipilnya, misalnya pengurusan KTP kolom agama dikosongkan yang terkadang menuai protes dari aparat Negara, selain itu dalam hal perkawinan dan pencatatan kelahiran pun demikian. Sejak undang-undang Sistem administrasi Kependudukan (Adminduk) No.23 tahun 2006 disahkan, hal ini cukup memberi peluang bagi penghayat kepercayaan, namun praktek di lapangan belum maksimal. Hal ini disebabkan 6 karena aparat Negara tidak serius menjalankan pelayanan yang adil kepada seluruh warga negara dengan dalih sosialisasi yang kurang. Lembaga keagamaan Negara pun belum berperan maksimal dalam pemenuhan hak warganya. Sekalipun agama Khonghucu sudah diakui resmi oleh Negara, namun hingga saat ini Kementerian Agama belum siap menyediakan Bimas Khonghucu di lembaga tersebut.2 Selama ini pelayanan umat Khonghucu ditangani oleh umat Muslim melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kementerian Agama. Seharusnya ada perwakilan umat Khonghucu yang berada di jajaran Kementerian Agama untuk mengurusi umatnya, bukan dilimpahkan pada umat agama lain.3 Lebih jauh lagi, agama-agama lokal bukanlah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, namun diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan contoh diskriminasi yang dilakukan Negara dan membentuk stigma negatif masyarakat terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu, tindak diskriminatif juga muncul dari masyarakat sekitar atau pihak tertentu. Menurut pengakuan seorang warga kerokhanian Sapta Darma, dalam pendirian sanggar (tempat sujud warga kerokhanian Sapta Darma) seringkali dipersoalkan pihak tertentu. Awalnya masyarakat sekitar menyetujui pendirian sanggar di Kecamatan Sukoreno Kabupaten Jember Jawa Timur, namun karena adanya provokasi seseorang yang tidak suka dengan keberadaan 2 http://infopublik.id/read/67703/presiden-sby-janji-bentuk-ditjen-bimas-khonghucukemenag-ri.html. Diakses pada 27 Mei 2015. 3 http://www.satuharapan.com/read-detail/read/matakin-agama-khonghucu-sama-di-matahukum-indonesia. Diakses pada 27 mei 2015. 7 kerokhanian Sapta Darma, hal ini menimbulkan ketegangan dan pencegahan pendirian sanggar tersebut, padahal semua material sudah disiapkan.4 Dewasa ini, kesempatan untuk berpendapat di ruang publik semakin terbuka lebar. Sayangnya, kesempatan ini digunakan dengan tidak benar oleh pihak tertentu guna menyerang pihak lain. Banyak konflik keagamaan muncul, walaupun kenyataannya sumber konflik seringkali adalah faktor politik, ekonomi maupun sosial. Hal yang sering terjadi hingga saat ini adalah adanya intimidasi yang diterima oleh warga kerokhanian Sapta Darma, seringkali mereka dianggap penganut aliran sesat sehingga mereka tidak berani mengaku atau menunjukkan di depan publik bahwa mereka adalah warga kerokhanian Sapta Darma.5 Di Indramayu Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Kecamatan dengan mudahnya mengeluarkan surat edaran bahwa kerokhanian Sapta Darma termasuk aliran sesat.6 MUI yang merupakan organisasi masyarakat yang menaungi agama Islam seharusnya tidak ikut campur dalam hal tersebut. Persoalan klaim sesat sangat banyak terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan hal ini terjadi di negara ini yang mengaku menghargai kemajemukan. Selain permasalahan yang disebut di atas, masih banyak lagi permasalahan diskriminasi yang dihadapi oleh warga kerokhanian Sapta Darma. 4 Komunikasi personal, 30 Januari 2015 di sanggar candi Sapta Rengga jl. Taman Siswa Surokarsan Mg.II Yogyakarta. 5 Komunikasi personal, 29 Oktober 2014 di sanggar candi Sapta Rengga jl. Taman Siswa Surokarsan Mg.II Yogyakarta. 6 Komunikasi personal, 9 Februari 2015 di sanggar candi Sapta Rengga jl. Taman Siswa Surokarsan Mg.II Yogyakarta. 8 Kerokhanian Sapta Darma7 merupakan salah satu aliran kepercayaan terbesar di Indonesia di samping Susila Budi Darma (SUBUD) (1932), Pangestu (1932) dan Sumarah (1935). Keempatnya telah diakui secara legal di Indonesia dan mempunyai keanggotaan baik nasional maupun level internasional (Utama 2007). Dahulu nama Sapta Darma pernah didahului dengan nama Agama, namun setelah adanhya sidang umum MPR tahun 1978 yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan suatu agama, maka sejak itu diganti dengan nama Kerokhanian Sapta Darma. Kerokhanian adalah sebutan kelompok masyarakat atau individu yang berusaha ingin mempersatukan roh insani dengan roh ilahi tanpa kehilangan kepribadiannya dengan cara semadi atau olah rasa (Ilyas dan Imam 1988). Sedangkan menurut Rachmat Subagya, kerokhanian lebih menekankan aspek mistisisme, artinya bagaimana mencapai kontak langsung anatara roh manusia dengan roh yang mutlak. Cirinya tampak pengaruh teosofi timur dan tashawuf Muslim (Subagya 1981). Pada tahun 1980, kerokhanian Sapta Darma resmi terdaftar sebagai organisasi penghayat dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nomor inventaris I.135/F.3/N.1.1/1980 (Perwira 2011). Aliran yang lahir pada tahun 1952 ini memiliki struktur lembaga yang lengkap mulai tingkat pusat hingga kecamatan, masih merasakan dampak diskriminasi baik yang dilakukan oleh Negara, maupun pihak tertentu di masyarakat. Secara resmi mereka telah mendapatkan pengakuan, namun praktek di lapangan menunjukkan sebaliknya. 7 Lihat Rachmat Subagya, Agama Asli Indonesia, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), 256. 9 1.2 Rumusan Masalah Terkait dengan permasalahan yang kami uraikan di atas, maka penelitian ini akan fokus pada beberapa pertanyaan kami rumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana relasi Negara dan kerokhanian Sapta Darma? b. Bagaimana pengalaman warga kerokhanian Sapta Darma dalam bermasyarakat dan bernegara? c. Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui relasi antara Negara dan kerokhanian Sapta Darma sebagai aliran kepercayaan dan kelompok minoritas di Indonesia. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui pengalaman warga kerokhanian Sapta Darma dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga mengarah pada tujuan ketiga yakni mengetahui solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian religious studies terkait permasalahan yang dialami oleh penghayat kepercayaan. Terlebih penelitian ini diharapkan mampu mendokumentasikan dan memberikan solusi beberapa tindak diskriminatif yang akhir-akhir ini sering nampak mengenai relasi Negara terhadap penghayat kepercayaan maupun sikap warga masyarakat terhadap eksistensi warga kerokhanian Sapta Darma sebagai minoritas. 10 1.4 Kajian Pustaka Kajian mengenai diskriminasi dan aliran kepercayaan sudah banyak dilakukan. Untuk kepentingan teoritis, literatur yang ada, kami bagi menjadi tiga kategori; pertama literatur yang membahas tentang kerokhanian Sapta Darma, kedua adalah literatur yang membahas mengenai perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia, dan yang terakhir adalah literatur yang fokus pada pembahasan diskriminasi. Pada kategori pertama, beberapa peneliti membahas tentang kerokhanian Sapta Darma dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Chandra Utama dalam tesisnya Memayu-hayu Bagya Bawana: Sejarah Gerakan Sapta Darma di Indonesia 1952-2006 menggali lebih dalam tentang dimensi sejarah kerokhanian Sapta Darma mulai dari pewahyuan hingga perkembangan praktek spiritual di kalangan warganya. Tulisan ini fokus pada hubungan kerokhanian Sapta Darma dengan sisi budaya, kemasyarakatan dan negara, selain itu juga membahas sepintas tentang diskriminasi yang dilakukan Negara dan pihak tertentu. Skripsi Willy Budimansyah berjudul Interaksi Sosial di Kalangan Penghayat Kerokhanian Sapta Darma suatu analisis deskriptif tentang tiga pola interaksi sosial warga kerokhanian Sapta Darma yakni di interaksi internal kalangan warga, interaksi sosial dengan pemerintah, dan juga interaksi sosial dengan masyarakat. Berbeda dengan skripsi Indah Setyo Tri Wahyuni yang berjudul Dinamika Umat Islam Penganut Ajaran Sapta Darma di gaten Metroyudan Magelang tahun 1959-1970 fokus pada peristiwa G30S dengan 11 melihat dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Selain itu juga tertulis tentang kebijakan pemerintah dan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam paska peristiwa bersejarah itu. Skripsi Muhammad Yusuf berjudul Agama Islam dalam Kerokhanian Sapta Darma membahas tentang unsur-unsur agama Islam yang ada dalam ajaran Sapta Darma. Sedangkan Sri Munawaroh dalam karyanya Manusia manurut Ajaran Kerokhanian Sapta Darma fokus pada pandangan Sapta Darma terhadap kedudukan manusia khususnya peran perempuan yang menempati status second sex di bawah laki-laki dari segi kebatinan. Dari beberapa penelitian yang membahas kerokhanian Sapta Darma, belum saya temukan penelitian yang fokus pada tindak diskriminatif yang terjadi di kalangan warga kerokhanian Sapta Darma. Pada kategori kedua ada beberapa tokoh yang membahas aliran kepercayaan dan perkembangannya di Indonesia, antara lain Agama Asli Indonesia karya Rachmat Subagya menjelaskan pandangan kepercayaan asli Indonesia tentang konsep ketuhanan, jiwa manusia dan alam dunia serta deskripsi bagaimana cara ibadah dan upacara serta etika dalam kepercayaan asli. Selain itu, penulis memaparkan tentang tantangan agama asli yang tergeser oleh agama-agama impor sehingga membentuk pertahanan berupa aliran kebatinan/ kepercayaan yang eksis hingga saat ini. Dalam bukunya disebutkan bahwa “agama asli sepanjang sejarah berulang kali mengalami krisis eksistensi, puncaknya adalah zaman penjajahan…agama asli menjadi korban penjajahan dan diskriminasi (Subagya 1981)”. Walaupun penulis menyebutkan kata diskriminasi dalam bukunya, namun hal ini tidak dijelaskan secara mendalam. Ini memberi peluang untuk melakukan 12 penelitian lebih lanjut dan fokus pada diskriminasi di kalangan penghayat kepercayaan. Karya yang mirip dengan penulis sebelumnya adalah Bangkitnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME karya Djoko Dwiyanto mengelaborasi kaitan agama asli dengan aliran kepercayaan di Indonesia. Penulis menyebutkan bahwa “bangkitnya penghayat kepercayaan bukan hanya reaksi melawan modernisasi, melainkan juga sebagai usaha aktif untuk mencari identitas kultural yang mewarnai pergulatan orang Jawa dalam menghadapi masa kini”. Ia menambahkan bahwa “kuatnya kebudayaan asli Indonesia/ Jawa memaksa kebudayaan dan agama asing melakukan kompromi budaya (sinkretisme)” (Djoko Dwiyanto dan Saksono 2011). Ia menyatakan bahwa aliran kepercayaan yang tengah berkembang merupakan regenerasi dari agama asli Indoensia. Selain itu, ia juga menjabarkan secara singkat beberapa aliran kepercayaan, namun fokus tulisan ini adalah hanya pada aliran kepercayaan yang ada di DIY. Di akhir tulisan ia melampirkan daftar aliran kepercayaan yang masih aktif dan terdaftar di DIY serta kronik singkat aliran kepercayaan di Indonesia. Mutholib Ilyas dan Ghofur Imam dalam karyanya Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia berisi tentang definisi kepercayaan, kebatinan dan kerokhanian disertai penjelasan tentang beberapa aliran kepercayaan di Indonesia secara garis besar Selain itu mereka juga membahas alur kehidupan kepercayaan di Indonesia dimulai dengan kepercayaan animisme hingga monotheisme. Kronologi turunnya wahyu dan pergantian nama kerokhanian Sapta Darma juga 13 dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Dalam bab terakhir dijelaskan tentang beberapa pandangan penghayat kepercayaan terhadap agama dan juga sebaliknya, Ditinjau dari perspektif penghayat, “agama dianggap tidak bisa membawa ketenangan batin dan ketentraman hidup” (Ilyas dan Imam 1988). Buku tersebut diakhiri dengan menyebutkan daftar organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia. HAMKA dalam bukunya Perkembangan kebatinan di Indonesia membahas kebatinan dilihat dari sudut pandang Islam. Asal mula tumbuhnya gerakan kebatinan, sebab-sebab timbulnya kebatinan semua dikaitkan dengan latar belakang penulis sebagai pemikir Islam, sehingga ada beberapa bagian yang berbeda dengan literatur lain yang kami temukan. Kamil Kartapradja dalam bukunya Aliran kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia menulis tentang kepercayaan masyarakat Indonesia mulai dari animisme, monotheisme, dan sejarah singkat masuknya agama-agama besar. Selain itu, ia membahas beberapa aliran kepercayaan secara garis besar. Ia mendeskripsikan kerokhanian Sapta Darma dengan cara berbeda. Kami menemukan kesan bahwa penulis tidak mendukung adanya aliran kepercayaan berkembang di Indonesia “..banyak gerakan mistik yang menamakan dirinya sebagai agama sehingga minta diakui sebagai agama oleh pemerintah, ini betulbetul merepotkan pemerintah terutama Departemen Agama..”(Kartapradja 1985). Di akhir buku, ia membandingkan perspektif agama dan aliran kepercayaan tentang konsepsi ketuhanan, alam, hubungan Tuhan dengan manusia serta 14 perbuatan luar biasa. Buku ini menjelaskan fokus ajaran kerokhanian Sapta Darma adalah pengobatan karena adanya kepandaian semacam magnetisme yang dinamai atom berjiwa dalam pengobatan mereka. Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia karya El Hafidy diawali dengan deskripsi yang sangat singkat tentang beberapa aliran kebatinan di Indoensia serta pengertian agama, kepercayaan, kebatinan, dan filsafat sebagai kerangka berpikir. Ia menyinggung tentang landasan hukum aliran kepercayaan di Indonesia serta konsepsi agama dan kepercayaan dalam GBHN. Selanjutnya ia menegaskan pendapat yang sangat bias bahwa “..aliran kepercayaan merupakan sesuatu yang dirasakan ‘mengganjal dan meresahkan’ umat beragama, khususnya Islam, jika aliran tersebut dicampuradukkan dengan agama” (El Hafidy 1977). Ia juga menjelaskan beberapa sebab timbulnya aliran baru dalam kepercayaan, mistik dan kebatinan yang sangat memojokkan mereka. Di akhir tulisan ia menambahkan lampiran yang berisi artikel-artikel terkait yang tidak sepakat dengan eksistensi aliran kebatinan di Indonesia. Tashawwuf dan Aliran Kebatinan: Perbandingan antara Aspek-aspek Mistikisme Islam dengan Aspek-aspek Mistikisme Jawa karya Romdon menjelaskan mistikisme dan tashawwuf dengan perspektif Islamnya. Selajutnya ia memberi gambaran umum beberapa aliran kebatinan di Indonesia. Namun buku ini fokus mendeskripsikan tentang konsepsi manusia dalam beberapa aliran kebatinan. Dari hasil tulisannya tersebut terlihat ia membandingkan mistikisme dalam Islam dengan aliran kebatinan. Kami temukan argumen penulis bahwa “ada 15 kemiripan-kemiripan, jika dalam mistikisme Islam Ibn al’ Arabi ada ajaran Nur Muhammad sebagai perantara Tuhan dan makhluknya, sedangkan dalam Pangestu ada Suksma Sejati sebagai aspek Tri Purusa Tuhan” (Romdon 1993). Dalam buku ini, kami temukan deskripsi lengkap kerokhanian Sapta Darma khususnya ajaran Sapta Darma tentang konsepsi manusia. Penulis mengatakan bahwa inti pusat manusia adalah Hyang Maha Suci yang berasal dari Sinar Cahya Tuhan. Karya ini akan membantu untuk menjelaskan kerokhanian Sapta Darma secara lengkap. Rachmat Subagya dalam Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama mengawali bukunya dengan pemaparan masalah-masalah yang ada di dalam kebatinan dihadapkan dengan perkembangan zaman. Rahmat Subagya melemparkan pertanyaan, “apakah perbedaan antara kebatinan dan agama, khususnya agama-agama besar? Apakah kebatinan berhak atas pengakuan dan penegasan resmi setingkat dengan agama-agama resmi, bahkan perlindungan dan bantuan dari negara?” Selain itu, penulis juga menyebutkan sifat-sifat kebatinan secara rinci, hubungan antara kebatinan dan agama, dan ditutup dengan kronik kebatinan. Buku ini tidak memaparkan tentang diskrimisnasi namun tulisan ini akan sangat bermanfaat untuk pijakan mengeksplorasi permasalahan yang ada di sekitar kebatinan dewasa ini. Niels Mulder dalam Ruang Batin Masyarakat Indonesia menyebutkan “..aliran-aliran yang lebih tertata semacam Pangestu dan kerokhanian Sapta Darma situasinya tidak begitu banyak berubah, tetapi secara umum kehidupan aliran kebatinan tidak lagi semarak” (Mulder 2001). Buku ini merupakan hasil 16 penelitian antropologis tentang pergeseran dan perubahan budaya dan nilai-nilai khususnya di Yogyakarta sebagai representasi masyarakat Jawa dan Indonesia. Selain itu, ia juga mendiskusikan tentang Jawanisasi kebudayaan di Indonesia dilihat dari gejala praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang menghegemoni. Buku ini juga penting untuk dijadikan pijakan untuk melihat deskripsi umum kota Yogyakarta beserta persoalan yang terjadi di masa lampau sebagai pusat perkembangan kerokhanian Sapta Darma. Kategori terakhir fokus pada wacana diskriminasi agama yang ada di Indonesia. Suhadi (ed) dalam Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara, Politik Diskriminasi, dan Multikulralisme merupakan antologi tulisan dari berbagai penulis yang fokus pada kajian multikiulturalisme. Berangkat dari tulisan Elga Joan Sarapung, “Negara mendapat legitimasi untuk mengatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan membina umat beragama. Hal yang esensi tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan kewajiban negara terhadap warga negara tetapi secara transparan dilanggar dan tidak dijalankan oleh Negara secara baik dan benar”. Buku ini membahas berbagai bentuk diskriminasi agama dan multikulturalisme di Indonesia. Tesis kami nantinya akan fokus pada diskriminasi yang terjadi di kalangan penghayat kepercayaan khususnya kerokhanian Sapta Darma. Resonansi Dialog Dialog Agama dan Budaya: Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi yang diterbitkan oleh CRCS UGM merupakan kumpulan rekam dialog tentang kebebasan beragama, 17 hak sipil warga, konflik dan perdamaian seta pendidikan multikulturalisme di Indonesia melalui media nasional dan lokal. Melalui narasi Komunikasi yang tertulis dalam buku tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan terkait dengan tindak diskriminatif yang ada dewasa ini. Tesis Hasse J yang berjudul Dsikriminasi terhadap Agama Minoritas: Studi terhadap Eksistensi Komunitas Tolotang di Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, membahas tentang diskriminasi komunitas tersebut. Bentuk diskriminasi datang dari masyarakat terutama kelompok mayoritas dan juga Negara berupa regulasi yang membatasi ruang gerak komunitas Tolotang. Tolotang dikategorikan penulisnya sebagai agama lokal karena eksistensinya yang hanya ada di daerah tersebut. Objek yang kami teliti hampir mirip karena sama-sama sebagai agama minoritas, namun Kerokhanian Sapta Darma yang akan kami teliti dalam tesis ini merupakan aliran kepercayaan yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru karya Anas Saidi dkk mengupas tentang bagaimana istilah agama di Indonesia dikonstruksi dan dipolitisasi oleh penguasa Negara. Selain itu, buku tersebut menjelaskan tentang relasi agama dan Negara serta kebijakan agama ditinjau dari persepktif historis sebagai kerangka pembahasan selanjutnya. Fokus buku tersebut adalah pasa kebijakan agama masa Orde Baru dan Orde Lama dan diakhiri dengan kasus diskriminasi agama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sehingga 18 buku tersebut sangat penting untuk melihat diskriminasi agama secara umum dan diterapkan pada penelitian kami. Tedi Kholiludin dalam bukunya Kuasa Negara atas Agama: Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil membahas tentang diskriminasi hak sipil dan peran negara dalam mengkonstruksi agama resmi di Indonesia. Buku tersebut diawali penjabaran konsep hak sipil secara detail dan kaitannya dengan HAM. Kemudian dalam analisis bukunya, Tedi mengangkat isu jaminan kebebasan beragama dihadapkan dengan kepentingan pemerintah melalui intervensinya terhadap agama. Penulis juga mengkritik pembedaan antara agama dan kepercayaan. Buku serupa diterbitkan oleh eLSA berjudul Jalan Sunyi Pewaris Tradisi yang merupakan hasil penelitian Tedi bersama rekan-rekannya tentang masalah hak sipil penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Pembahasannya tidak jauh berbeda dengan buku pertama yakni pendekatan HAM digunakan untuk menangani masalah layanan publik. Dalam penelitian yang akan dilakukan, kami menemukan adanya kemiripan bahwa hak sipil warga kerokhanian Sapta Darma tidak dipenuhi oleh Negara, namun skop penelitian kami lebih kecil dan fokus pada pengalaman beragama warga dari sebuah aliran kepercayaan. Penelitian-penelitian di atas cukup penting menjadi rujukan atas kajian pengalaman diskriminatif warga kerokhanian Sapta Darma. Penelitian yang kami lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada persoalan 19 diskriminasi baik yang dilakukan oleh Negara maupun pihak tertentu di masyarakat terhadap warga kerokhanian Sapta Darma khususnya di Yogyakarta. 1.5 Kerangka Teori Adapun kata diskriminasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah merujuk pada konsep diskriminasi menurut Liliweri yaitu sikap yang muncul akibat adanya prasangka terhadap seseorang atau komunitas yang kemudian membentuk perilaku yang berupa menyingkirkan, menjauhi, mencemooh baik bersifat fisik maupun sosial dengan kelompok tertentu (Liliweri 2003). Lebih jauh Rose sepakat dengan konsep Liliweri bahwa prasangka merupakan sumber dari tindak diskriminasi. Menurutnya diskriminasi merupakan perlakuan berbeda terhadap seseorang dengan melihat asal kelompok atau kategori lainnya (Rose 1964). Ia mengklasifikasi beberapa bentuk diskriminasi antara lain: menghina dan menyakiti, menolak keberadaan seseorang atau komunitas, dan penyerangan yang berupa kekerasan (Rose 1964). Untuk menganalisis kajian ini diperlukan strategi untuk mencapai keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman, yakni politik rekognisi, politik representasi, dan politik redistribusi sumber daya. Adapun yang dimaksud dengan politik rekognisi adalah pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman yang mana tidak sebatas membiarkan orang lain melakukan kewajibannya, akan tetapi juga menghargai mereka dengan segala perbedaannya dalam hidup bersosialisasi. Prakteknya tidak terbatas dalam konteks hak-hak sipil dan politik, tetapi juga pada hak-hak sosial, ekonomi, identitas dan kultural. Pengakuan tersebut bisa berdampak pada terpenuhinya hak-hak yang tersebut di atas (Bagir 2011). 20 Strategi yang kedua adalah politik representasi, yaitu adanya keterwakilan dari suatu komunitas untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Setidaknya ada 4 model representasi, yakni: pertama, representasi formalistik, prakteknya di Indoneisa seringkali merujuk pada fungsi lembaga formal saja. Kedua, representasi simbolik, meliputi keterwakilan budaya, kepercayaan dan identifikasi. Fokus representasi simbolik adalah pada cara bagaimana seorang wakil dapat diterima sebagai wakil dari kelompok yang diwakilinya. Tingkat keterwakilanya dapat dilihat sebagai tingkat penerimaan dari orang atau kelompok yang diwakilinya. Ketiga adalah representasi deskriptif, yaitu tingkat kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Kemiripan yang dimaksud meliputi kesamaan berdasarkan wilayah, komunitas, kelompok dan gender. Keempat adalah representasi substantif, yaitu menyampaikan pesan komunitas yang diwakili dalam ranah publik dengan berbagai cara yang membawa kemaslahatan. Tingkat keterwakilan dapat diukur dari sejauh mana wakil tersebut dapat memperjuangkan kepentingan yang diwakili (Bagir 2011). Strategi representasi tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun diwakilkan melalui lembaga masyarakat sipil, lembaga politik, tokoh agama dan sebagainya. Strategi terakhir adalah politik redistribusi dimana strategi ini fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Negara sebagai pihak yang bertanggungjawab memainkan sektor ekonomi rakyatnya, apakah berpihak pada golongan tertentu dalam mendistribusikan kebutuhan ekonomi mereka? Apakah muncul permasalahan ekonomi terkait identitas keagamaan? (Bagir 2011). Disamping ketiga konsep pluralisme kewargaan tersebut, kami akan mengelaborasi beberapa 21 upaya advokasi yang telah dilakukan oleh pakar maupun aktivis, yaitu pendekatan berbasis kuasa, pendekatan berbasis hak dan pendekatan berbasis kepentingan (Panggabean 2014) yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang dialami oleh warga kerokhanian Sapta Darma. Selain konsep di atas, kami juga menggunakan konsep scaling up untuk menganalisis permasalahan warga. Scaling up diartikan sebagai proses mengadopsi pengalaman baik yang sudah berjalan digunakan sebagai contoh untuk diterapkan di tempat/ kasus yang berbeda agar mampu menghasilkan dampak yang baik sebagai pemecahan masalah (McDonald et al 2006) (Uvin 1995). Hal ini bermaksud menularkan dampak positif dari satu kasus ke kasus yang lain. Konsep ini dikembangkan pertama kali dari pengalaman pakar yang mampu mereplika mesin kimia lebih dari satu abad yang lalu (McDonald et al 2006). Ada beberapa model scaling up (Uvin 1995) yang sudah berhasil dikembangkan. Pertama, kuantitatif, artinya tujuan proses ini adalah memperbanyak jumlah anggota; kedua, fungsional, artinya menambah fungsi aktivitas tertentu agar hasilnya lebih baik; ketiga, politik, yang artinya memperluas keterlibatan sosial untuk menambah relasi; keempat, organisasi, bermaksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu hal agar mampu bertahan lebih lama seperti peningkatan mutu sebuah lembaga melalui manajemennya. 1.6 Metodologi Penelitian Penelitian ini dilakukan di pusat kerokhanian Sapta Darma sebagai representasi aliran kepercayaan yang ada di Yogyakarta. Kerokhanian Sapta 22 Darma mempunyai struktur lembaga yang lengkap dan terorganisir jika dibandingkan dengan aliran kepercayaan yang lain, sehingga memudahkan untuk diteliti. Selain itu, kerokhanian Sapta Darma termasuk dari lima aliran kepercayaan terbesar di Indonesia dan terdaftar di pemerintah. Adapun sanggar pusatnya beralamat di jalan Taman Siswa Surokarsan mg.II/472 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.8 Karena kami ingin mendalami dan memahami objek secara keseluruhan dengan pendekatan antropologis, sehingga mengharuskan kami untuk bertemu langsung dengan warga kerokhanian Sapta Darma melalui penelitian partisipatif.9 Hal tersebut akan memudahkan dalam mengumpulkan data melalui dokumendokumen yang beredar, pengamatan, maupun Komunikasi dan dokumentasi secara langsung. Wawancara dilakukan secara semi-struktural10 dengan beberapa narasumber melalui metode snowballing atau chain sampling.11 Strategi pemilihan narasumber adalah berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, warga kerokhanian Sapta Darma sejak lama, maupun warga yang 8 Denzin dan Lincoln mendefinisikan ini sebagai seperangkat penafsiran, praktek kebendaan yang mampu membuat objek nampak. Praktek-prakteknya meliputi catatan lapangan, wawancara, percakapan, fotografi, rekaman, dan catatn kecil. Penelitian kualitatif meliputi penafsiran, pendekatan alami terhadap suatu objek. Lihat N.K.Denzin, Y.S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research, 2nd edition, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2000). 9 Penelitian partisipatif adalah metode dimana peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari, ritual, interaksi, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama warga sebagai cara mempelajari hal-hal yang terlihat maupun tidak dalam rutinitas kehidupan dan budaya mereka. Lihat Russel Bernard.H, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, (Oxford: Altamira Press, 2006). 10 Dalam wawancara semi struktural, biasanya ada beberapa daftar pertanyaan untuk membantu melakukan wawancara. Cara ini digunakan ketika waktu kita terbatas dan focus pada objek tertentu. Hal ini juga memudahkan narasumber secara bebas mengekspresikan pendapatnya dan mengikuti alur percakapan. 11 Menanyai narasumber yang telah kita wawancarai tentang narasumber yang lain sesuai kriteriayang kita tentukan. Ini merupakan pendekatan yang tepat untuk objek yang terbatas. Lihat Jane Ritchie, Jane Lewis, eds., Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Reseachers, (New York: Sage Publications, 2003), 94. 23 berpindah keyakinan. Kami mendapatkan 16 narasumber yang terdiri dari 6 pengurus dan 10 orang warga biasa. Kami menghimpun informasi dari para narasumber tersebut dengan menggunakan metode life story12 sehingga memudahkan untuk menggali informasi lebih dalam tentang pengalaman mereka dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dokumen-dokumen internal dan referensi-referensi sekunder yang keduanya saling melengkapi, informasiinformasi lisan dari para warga kerokhanian Sapta Darma dan juga kegiatan sanggaran mereka. Selain itu juga menghimpun dokumen internal yang digunakan adalah buku-buku yang diterbitkan oleh pengurus kerokhanian Sapta Darma. Sumber informasi yang terhimpun, seperti kumpulan data hasil penelusuran media online, dokumentasi, pengamatan maupun wawancara serta penelusuran life story tentang pengalaman warga Kerokhanian Sapta Darma dalam hal diskriminasi ditulis dalam catatan lapangan yang selanjutnya akan diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang mapan. 12 Life story adalah cerita seseorang tentang kehidupannya yang disampaikan secara lengkap dan sejujur mungkin apa saja yang diingatnya dan apa yang ingin diberitahukan orang tersebut pada orang lain, biasanya merupakan hasil dari wawancara terarah oleh orang lain. Lihat lebih lanjut Robert Atkinson, The Life Story Interview (California: Sage Publication, 1998), 8. Ada perbedaan antara life story dan life history. Life story adalah cerita yang disampaikan oleh narasumber atau orang yang mengalami sedangkan life history adalah hasil interpretasi cerita tersebut oleh peneliti. Lihat Annica Ojermark, Presenting Life Histories (CPRC, 2007), 4. Dalam wawancara life story ada 3 tahap yang harus dilakukan: perencanaan wawancara termasuk bagaimana teknik wawancara dan mengetahui apa pentingnya life story, melakukan wawancara, dan terakhir adalah mentranskrip dan menganalisis hasil wawancara. Robert Atkinson, The Life Story Interview, (California: Sage Publication, 1998), 26. 24 1.7 Sistematika Pembahasan Dalam rangka mendapatkan paparan yang sistematis, maka paparan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bagian. Berikut penjelasan masing-masing bagian: Bab I : persoalan-persoalan yang terkait dengan arah dan acuan penulisan tesis, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II : pembahasan tentang kerokhanian Sapta Darma ditinjau dari sejarah, ajaran, kedudukannya dengan aliran kepercayaan yang lain, relasi dengan Negara serta lembaga organisasinya. Bab III : klasifikasi pengalaman beragama warga kerokhanian Sapta Darma yang meliputi tiga bagian besar, yakni: pengalaman diskriminasi, pengalaman negosiasi dan pengalaman sinkretik mereka. Bab IV: berisi analisis masalah yang dialami warga kerokhanian Sapta Darma dalam bermasyarakat dan bernegara serta solusi alternatif yang ditawarkan untuk mengatasinya. Perspektif pluralisme kewargaan digunakan menganalisisnya disertai pendekatan berbasis kuasa, hak dan kepentingan. Bab V : Penutup. dalam