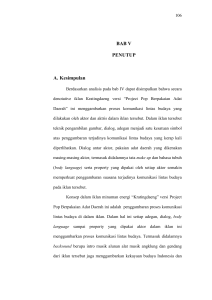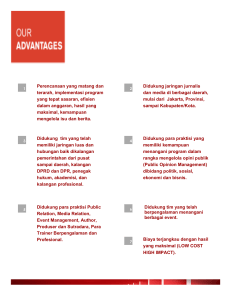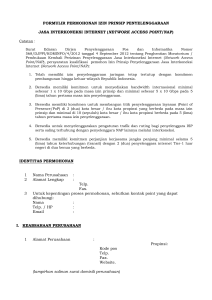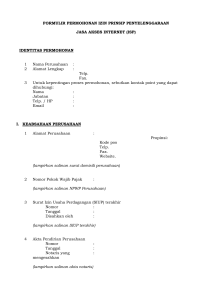Budaya Pop dan Kaum Muda
advertisement

Yang Muda Yang Bertingkah: Konsumsi, Resistensi, dan Kreativitas Kaum Muda dalam Budaya Pop Ikwan Setiawan Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Peneliti di Matatimoer Institute 1. Pengantar: Budaya Pop yang Diperdebatkan Sampai dengan saat ini, budaya populer (selanjutnya disebut “budaya pop), belum bisa dirumuskan dalam sebuah definisi konseptual yang memuaskan. Definisi-definisi yang selama ini berkembang lebih banyak dikaitkan dengan pengertian budaya massa (mass culture) yang merupakan produk utama dari industri budaya (cultural industries) dalam era kapitalisme lanjut (advanced-capitalism) dewasa ini. Musik pop, film, acara televisi, majalah, tabloid, dan koran, selama ini dianggap sebagai wujud dari budaya pop karena paling banyak dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Hal inilah yang menjadi titik pijak para pemikir Mazhab Frankfurt melihat budaya populer sebagai alat untuk pengelabuhan massa (mass deception) dan menggiring mereka sebagai konsumen sejati produk-produk industrial dengan janji-janji perayaan individualisme yang nyatanya serba diatur dalam standard dan komodifikasi homogen (Adorno, 1957; Adorno & Hokheirmer, 1993; Lowenthal, 1957). Kepanikan lain terhadap budaya pop lebih banyak terkait dengan masalah moralitas. Ganz (1974) menjabarkan beberapa kepanikan terhadap popularitas budaya pop dalam beberapa kecenderungan, yakni: (1) budaya pop membahayakan eksistensi budaya tinggi (high culture) karena meminjam dan mengkorupsi struktur dan isi dari budaya dalam bentuk-bentuk yang sepele (trivial) sehingga menghilangkan esensi keadiluhungannya dan (2) budaya pop secara emosional menimbulkan efek negatif kepada para penikmatnya karena lebih banyak mengumbar seks dan kekerasan, serta secara intelektual bersifat destruktif karena menawarkan isi dan tampilan yang eskapis sehingga menjauhkan penikmatnya dari realitas kehidupan. Bisa ditebak, sasaran dari kepanikan ini adalah kaum muda sebagai konsumen mayoritas dari produk industri budaya, karena dipandang sebagai subjek sosial yang masih labil secara mental dan pikiran sehingga sangat mudah terpengaruh oleh tampilan-tampilan surfisial dari budaya pop yang menghanyutkan dan mereduksi kemampuan nalar. Pemahaman di atas memang tidak salah. Namun, simplisitas dan kekakuan paradigma bisa melahirkan sudut pandang sempit dalam memahami budaya pop yang 1 sebenarnya tidak hanya berupa produk ataupun teks estetik, tetapi juga praktik yang melibatkan pemaknaan simbolis, artikulasi-disartikulasi kepentingan ideologis/kuasa, maupun resistensi. Memang benar, budaya pop merupakan produk industrial yang banyak digemari masyarakat, tetapi di balik itu semua, bisa dilihat adanya pertarungan kepentingan, sebagaimana banyak dilontarkan oleh para pemikir cultural studies. Dengan perspektif Gramscian, mereka menjadikan budaya pop sebagai kajian yang menarik dan berusaha melepaskan beban-beban moralitas yang selama ini dikhawatirkan, karena ada persoalan kepentingan kuasa yang dinaturalisasi dan didepolitisasi melalui teks dalam praktik budaya populer yang sudah biasa dikonsumsi oleh rakyat kebanyakan (Bennet, 1986; Storey, 1993; Hall, 1986, 2002). Kajian lain yang masih berada dalam perspektif cultural studies, adalah bagaimana proses konsumsi dan pemaknaan simbolis dalam praktik budaya pop dilakukan oleh konsumen. Mengikuti pemikiran kulturalisme1, Fiske (1995: 325-326) mengajukan satu pemikiran bahwa dalam mengkonsumsi produk industri budaya massa, konsumen mempunyai otoritas sepenuhnya. Budaya pop dalam masyarakat industri benar-benar eksis, meskipun tidak pernah murni dan otentik karena selalu diciptakan dari sumber budaya yang bertentangan dengannya (budaya tinggi, pen.). Budaya pop secara tipikal terikat pada produk dan teknologi budaya massa, tetapi kreativitasnya berada dalam cara-cara menggunakan produk dan teknologi tersebut, bukan dalam proses produksinya...Industri budaya massa industrial bukanlah budaya populer meskipun ia menyediakan sumber kultural bagi lahirnya budaya populer. Budaya pop secara khusus melibatkan seni membuat dari apa yang tersedia/ada. Mengikuti pemahaman tersebut, lahirnya budaya pop sebenarnya berlangsung dalam proses konsumsi yang dilakukan konsumen terhadap produk industri budaya massa. Ketika produk-produk tertentu dianggap sesuai dengan kepentingan konsumen, maka ia akan berubah menjadi budaya pop. Namun, konsumen mempunyai otoritas untuk mempraktikkan “seni membuat dari apa yang tersedia” oleh industri budaya massa. Inilah yang kemudian, menurut Fiske, melahirkan “pertarungan semiotik” (semiotic struggle) dalam budaya pop. Artinya, para penikmat bisa saja memberikan maknamakna simbolis atau ideologis yang berbeda atau bahkan bersikap resisten terhadap produk maupun teks industrial (resistant semiotics). Dengan kata, lain mereka bisa Dalam pemikiran kulturalisme, Williams (1961) menganggap budaya sebagai praktik kehidupan seharihari di mana tidak hanya berupa ekspresi artistik maupun seni rekaman modern, tetapi juga berupa apaapa yang berarti dan berharga bagi rakyat sehingga mensyaratkan adanya komunikasi dan interaksi sosial. Hall (1971) juga menjelaskan bahwa budaya bisa berarti “cara kehidupan sosial dijalani dan diatur, makna dan nilai yang menginformasikan tindakan manusia, yang mewujud di dalam dan memediasi relasi sosial, kehidupan politik, dan lain-lain. Dengan demikian menyiratkan adanya permainan antara penandaan dan interpretasi dari para anggotanya. 1 2 memberikan makna dan memunculkan kenikmatan berdasarkan identitas dan kepentingan sosial masing-masing dalam proses konsumsi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Jansson (2002), dengan memodifikasi dalil encoding-decoding Hall menjelaskan bahwa dalam praktik konsumsi sebuah produk industri budaya—ia menyebutnya budaya citra (image culture) karena dipadukan dengan simulasi dalam mediatisasi— konsumen selalu bergantung pada konteks sosio-kultural dan situasional dan tidak sepenuhnya mau mengikuti keinginan dari produsen. Nyatanya, saat ini memang banyak muncul budaya pop yang semakin digemari oleh masyarakat kebanyakan. Kaum muda adalah salah satu di antara mereka. Mereka yang sedari lahir sudah dikepung oleh kemajuan pesat industri kapitalis sudah biasa menemukan benda-benda di sekelilingnya sebagai produk-produk komodifikasi yang serba standard, homogen, dan massif—dari mainan hingga tayangan kartun di televisi—sebagai karakteristik dari industri budaya yang terus bertransformasi dan berkembang hingga hari ini. Mereka yang sehari-hari bersekolah, kuliah, hingga bekerja menemukan budaya pop sebagai praktik konsumsi yang bisa sedikit membuat rileks dari rutinitas harian. Apakah mereka harus dipersalahkan ketika menjalani kehidupan dalam gemerlap budaya pop? Tentu tidak. Mengapa? Karena mereka adalah subjek-subjek yang menikmati wacana, praktik, dan produk-produk kemajuan sebuah negara yang dengan bangga menyandarkan diri pada kapitalisme di mana lalu-lintas produk industri budaya menjadi menu keseharian bagi bangsa ini. Ketika produkproduk tersebut dimaknai dalam praktik konsumsi budaya pop oleh kaum muda, maka mereka tentu saja tidak harus dipersalahkan. Dengan logika tersebut, kaum muda sebagai pelaku budaya pop tidak harus selamanya dianggap sebagai subjek yang begitu mudah terjebak dalam pengaruh negatif budaya pop, meskipun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kaum muda melakukan praktik konsumsi terhadap produk-produk tersebut? Apakah mereka sebatas terjebak dalam euforia selebrasi konsumsi? Apakah mereka menggunakan budaya pop sebagai bagian dari strategi kultural yang bersifat resisten? Apakah mereka secara semiotik memaknai kembali simbol dan nilai yang ada dalam budaya pop dan selanjutnya meramunya sebagai budaya yang mewadai kepentingan identitas kultural mereka? Dari perkembangan budaya pop dan praktik konsumsi kaum muda, apa signifikansinya terhadap perkembangan budaya Indonesia saat ini? Tulisan ini akan dikembangkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun asumsi yang dijadikan acuan 3 adalah (1) bahwa sangat mungkin dalam menikmati budaya pop, kaum muda mampu melakukan negosiasi-negosiasi kepentingan mereka dengan cara melakukan peramuan (bricolage) dan pemaknaan kembali terhadap budaya massa industrial, demi kepentingan kultural mereka serta resistensi terhadap rejim budaya normatif dan (2) bahwa bisa jadi popularitas budaya pop di kalangan kaum muda bisa memberikan signifikansi—baik yang dianggap positif maupun negatif—terhadap budaya Indonesia saat ini. 2. Kaum Muda dan Budaya Pop: Resistensi dalam Konsumsi Kreatif Pembicaraan tentang kaum muda (young people/youth) dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora sudah lama diperdebatkan, baik dalam hal peran, kenakalan, hingga masalah-masalah psikis terkait dengan perkembangan mental dan pikiran mereka. Parsons, sebagaimana dikutip Barker (2004: 334), memposisikan kaum muda/remaja sebagai kategori sosial yang perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme yang mensyaratkan adanya spesialisasi dalam pekerjaan. Karena tanggung jawab keluarga terhadap anak-anaknya tidak lagi berlangsung seperti jaman pra-kapitalis, maka mengisi masa transisi sebelum menginjak usia dewasa, kaum muda perlu diberikan pelatihan maupun pendidikan yang bisa menjembatani antara masa kanakkanak dan dewasa. Proses ini merupakan fungsi sosialisasi terhadap kaum muda sebelum mereka menginjak ke fase kehidupan kapitalis. Dalam masa transisi inilah, kaum muda lebih banyak diwacanakan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya orang dewasa. Maka, kaum muda bukan lagi semata-mata kategori usia transisional, melainkan sebuah konstruksi dan formasi diskursif yang diwacanakan terus-menerus dalam masyarakat, sesuai dengan konteks kepentingan sosio-kultural yang ada dalam sebuah masyarakat. Sebagai wacana, kaum muda dalam sebuah masyarakat, Indonesia misalnya, memang tidak bisa dikonstruksikan dalam ketunggalan (singularity). Selalu saja bermunculan formasi diskursif yang memposisikan kaum muda dalam ragam wacana, meskipun poin akhirnya tetaplah memberikan acuan kepada masyarakat bagaimana harus memposisikan kaum muda secara stereotip. “Kaum muda penggerak pembangunan”, “kaum muda penerus perjuangan”, “kaum muda pewaris budaya bangsa”, “nasib bangsa ada di tangan kaum muda”, dan masih banyak lagi wacana yang bernada positif. Wacana-wacana tersebut diwujudkan dalam praktik-praktik diskursif pelatihan, pendidikan, dan keorganisasian yang menjadi aparatus yang tepat untuk 4 terus menyebarkan pengetahuan konsensual tentang kaum muda. Dengan wacanawacana itu kaum muda dibayangkan menjadi subjek sosial yang akan menuruti apa-apa yang diharapkan dan diimpikan oleh kelas kuasa dalam masyarakat sehingga ketertiban dan kemajuan bersama bisa diwujudkan. Karena kepentingan konsensual menjadi wacana ideologis hegemonik yang terus disebarkan, maka ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh kelas kuasa adalah menyebarkan wacana terkait dengan “kenakalan remaja”, “kriminalitas remaja”, “kaum muda pengguna narkoba”, “kaum muda dan seks bebas”, “kaum muda pemberontak”, dan wacana-wacana lain yang terkait dengan potensi penyimpangan dan gangguan yang bisa dilakukan oleh dan terjadi pada kaum muda. Inilah yang oleh Grossberg (1992) disebut sebagai “cara pandang ambivalen” terhadap kaum muda. Di satu sisi mereka dijadikan penanda ideologis (ideological sign) yang dibebani oleh citra utopis masa depan, tetapi di sisi lain, mereka ditakuti sebagai ancaman atas norma dan regulasi konsensual dalam masyarakat. Dalam konteks ambivalensi inilah, kaum muda bisa mengalami masalah psikis yang merasa selalu terbebani oleh norma dan harapan yang bersifat sosio-kultural dari orang dewasa atau tua agar mereka menjadi lebih baik dan siap menyongsong kehidupan di masa mendatang, sementara di sisi lain mereka juga ingin merasakan kehidupan di masa kini. Celakanya, kaum muda menemukan realitas bahwa orang dewasa atau generasi tua yang selalu mengarapkan mereka menjadi baik, ternyata tidak banyak memberi memberi contoh-contoh yang sebanding. Korupsi para pejabat publik, perselingkuhan, nepotisme, dan lain-lain menjadi penanda betapa harapan normatif tersebut hanya menjadi retorika lip service yang cenderung berusaha menghegemoni kaum muda dengan wacana-wacana yang ternyata tidak berdasar. Dalam kondisi itulah, kaum muda menemukan budaya pop sebagai ruang, situs, dan praktik yang bisa digunakan untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingan individual yang serba terhimpit oleh kepentingan kuasa dalam masyarakat. Kebaruan dan kedinamisan yang ditawarkan budaya massa industrial menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda yang memang terus berusaha menemukan identitas diri di tengah-tengah segala tuntutan sosio-kultural yang mengepung mereka. Musik, film, pakaian, majalah gaul, handphone, play station, dan lain-lain menjadi produk yang menawarkan beragam kemungkinan untuk memanjakan dan meliarkan hasrat kaum muda yang mendamba kebebasan dalam berekspresi dan berbudaya dalam norma dan ritual mereka sendiri. Dari sinilah muncul praktik budaya pop di kalangan kaum muda 5 di mana mereka berusaha membuat identitas kultural yang berbeda dengan budaya masyarakat. Ketidakmauan untuk mengikuti rejim budaya normative-mainstream yang ada dalam masyarakat inilah yang bisa disebut sebagai resistensi oleh kaum muda dalam praktik budaya pop, meskipun bukan berarti perlawanan secara frontal. Fiske (2002: 241) menjelaskan bahwa: Resistensi merujuk pada penolakan untuk menerima identitas sosial yang ditawarkan ideologi dominan dan kontrol sosial yang menyertainya. Penolakan terhadap ideologi, juga terhadap makna dan kontrol, memang bisa jadi tidak menantang sistem sosial namun melawan inkorporasi serta menjalankan dan memperkuat makna perbedaan sosial yang menjadi pra-syarat bagi tantangan sosial lainnya. Oposisi kenikmatan pop terhadap kontrol sosial berarti bahwa mereka selalu memuat potensi untuk resistensi atau subversi: sebuah fakta bahwa tindakan subversif merupakan persoalan semiotik atau kultural…Sistem sosiopolitik pada akhirnya bergantung pada sistem kultural, atau dengan kata lain, makna oleh masyarakat digunakan untuk membuat relasi sosial dan kenikmatan yang mereka cari bisa jadi menstabilkan atau men-destabilkan sistem sosial tersebut. Makna dan kenikmatan mempunyai efektivitas sosial yang menyebar dan bersifat umum, meskipun tidak harus memberikan efek sosial yang langsung dan demonstratif. Resistensi dalam bentuk penolakan terhadap ideologi dominan yang menyatu dalam budaya masyarakat, menjadikan kaum muda masuk ke dalam hingar-bingar budaya pop yang menjanjikan kenikmatan makna kultural sehingga mereka sejenak tidak harus menghiraukan batasan-batasan normatif di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Apa yang dilakukan kaum muda dengan praktik budaya pop-nya bisa dibaca sebagai bentuk dari fase “liminalitas” (liminality) dalam ritus kehidupan mereka. Turner (1974), meminjam dari van Gennep, secara antropologis menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat sebuah fase di mana mereka mempraktikkan pembebasan dari rejim sosio-kultural normatif di mana ikatan dan batasan sosial diganggu. Fase liminal biasanya terjadi ketika seseorang berada dalam “ruang antara” (in-between space) dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Dalam fase inilah kaum muda berusaha menemukan bentuk dan praktik kultural yang berbeda dengan yang dijalani oleh orang tua atau masyarakatnya sehingga bisa merasakan hilangnya keterikatan dengan rejim sosio-kultural yang ada untuk membangun dunianya sendiri memalui praktik kenikmatan pop. Perayaan dalam mengkonsumsi budaya pop juga bisa dilihat sebagai “praktik karnaval” (carnivalesque) yang memberikan ruang jedah kebebasan bagi kaum muda dari batasan-batasan sosial mereka. Pemikiran tentang carnivalesque berasal dari 6 Mikhail Bakhtin ketika mengkaji novel satiris karya Rabelais melalui perbandingan dengan tradisi karnaval yang pernah hidup di Eropa pada jaman pertengahan di mana orang-orang akan menikmati hari libur dari pekerjaannya serta melakukan “pengejekan” dan “pengonyolan” terhadap kuasa negara dan gereja terbebas dari kuasa rejim gereja melalui pesta minuman keras, makan sepuas-puasnya, dan, bahkan, aktivitas seksual yang terkesan tidak bermoral (Brooker, 2007: 24-25). Dalam pemahaman yang lebih kritis, Webb (2005: 122) berargumen bahwa praktik karnaval bisa dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, selama karnaval terdapat penundaanpenundaan (suspension) terhadap semua pembedaan dan batasan hirarkial, sehingga semua terlihat sama. Kedua, norma dan larangan dalam kehidupan sehari-hari ditunda dalam karnaval sehingga yang muncul adalah atmosfer kebebasan, kejujuran, dan keakraban. Ketiga, karnaval memungkinkan penundaan terhadap pengaturan resmi akan ruang dan waktu sehingga rakyat bisa diorganisir dengan caranya sendiri. Keempat, kebenaran menjadi relatif di dalam karnaval, karena di sini yang dirayakan adalah semangat pembebasan temporer. Kelima, diri individu menjadi begitu cair karena mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari kolektivitas. Budaya pop memang memberikan ruang untuk perayaan fase liminalitas maupun praktik karnaval bagi kaum muda yang menjadi sebuah ruang pembebasan, kenikmatan, dan resistensi terhadap hegemoni rejim budaya dalam masyarakat. Dentuman drum, petikan gitar, dan lengkingan suara penyanyi dalam konser musik nyatanya cukup menarik bagi kaum muda untuk „pergi dan keluar sementara‟ dari kebosanan dan kejenuhan praktik sehari-hari yang berasal dari bermacam tuntutan normatif, baik dari orang tua, guru, maupun pemuka agama. Di bioskop, mall, kafe, maupun diskotik, mereka bisa lepas dari rejim pengawasan orang tua sembari menikmati makan malam, minuman bersoda atau bahkan beralkohol, ngrumpi sebagai penanda identitas dugem. Handayani (2005) dengan riset etnografi di Yogya, menemukan satu realitas bahwa informanya (dua orang mahasiswi di PTS Yogya yang kebetulan nyambi kerja jadi SPG), sudah biasa menikmati gaya hidup dugem dengan motivasi masing-masing. Salah satu informannya, Mi, menjelaskan bahwa ia sejak SMA di Yogya, sudah berani mencoba-coba praktik yang dianggap tidak baik, seperti minum beralkohol—di kafe maupun diskotik—demi untuk mencari pengalaman dan keluar dari tradisi pengawasan yang keras oleh orang tuannya. Meskipun demikian, ia tidak sampai larut dan kecanduan, karena sebelum menjalankan kenakalannya, ia berjanji untuk tidak terjebak dan melupakan tugas belajarnya. Buktinya ia tetap 7 mendapatkan rangking di kelasnya. Rupanya ia sudah punya strategi berupa penanaman keyakinan dalam dirinya agar tidak jauh terlibat sehingga ketika ingin berhenti, ia bisa saja berhenti. Ketika mahasiswa dan menjadi SPG ia juga sering dugem, bukan lagi untuk senang-senang, tetapi untuk mempererat persahabatan dengan sesama SPG sehingga kalau ada job bisa cepat tahu. Dari kasus Mi, bisa dilihat bahwa pemaknaan budaya pop tidak harus selamanya negatif, karena selalu ada konteks dan pertimbangan yang melatarbelakanginya. Hal itu juga menunjukkan bahwa tidak semua yang menikmati budaya pop akan larut dan tidak cenderung berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Di tempat-tempat play station ataupun internet game zone, para siswa SMP/SMA—bahkan anak-anak SD—begitu bergembira memainkan stick atau mouse untuk berperan sebagai „dalang‟ dari permainan kontemporer yang menyerupai wayang tersebut. Keakraban mereka dengan produk-produk budaya tersebut memang, di satu sisi, menandakan adanya perayaan konsumsi, tetapi di sisi lain, melalui praktik di ruang-ruang itulah mereka bisa menegosiasikan kepentingan mereka tanpa harus diganggu oleh bermacam norma. Di ruang itulah, resistensi berlangsung meskipun, setelah kembali ke ruang normatif, mereka harus memasang „muka manis‟ agar terbebas dari sanksi-sanksi sosial yang akan menimpah. Artinya, suatu saat mereka bisa menjadi penurut, tetapi pada saat yang lain mereka benar-benar menjadi subjek resisten. Saat menjadi muda, mereka merayakan dunia pop-nya, karena ketika menginjak dewasa mungkin mereka juga akan kembali ke dalam norma-norma sosiokultural yang akan mengatur kehidupan mereka dalam keberaturan dan ketertiban. Meskipun tidak menutup kemungkinan, mereka tetap akan membawa semangat resistensi yang pernah dirasakan ketika muda, tetapi dalam pemaknaan dan konteks yang berbeda. Anggapan bahwa kaum muda penikmat budaya pop, seperti musik, kafe, mall, maupun diskotik, sebagai semata-mata pemuja konsumerisme yang tidak punya idealisme kritis juga perlu dipertanyakan kembali. Gerakan Kaum muda, semisal mahasiswa, yang biasa nongkrong di kafe atau di mall maupun berselancar di dunia maya, nyatanya bisa menjadi penggerak dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Artinya di balik klub atau komunitas tersebut, kaum muda bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas kreatif yang terkadang bersikap tanggap terhadap kondisi sosial. Mereka bukan lagi kaum muda yang selalu asyik bermotor atau menikmati segelas kopi sembari menari mngikuti alunan musik blue atau jazz, tetapi bisa juga 8 merencakan sebuah gerakan politik untuk mengganggu kemapanan kelas kuasa, meskipun mereka tetap tidak bisa menjadi pahlawan bagi bangsanya (Budiman, 2002). Lalu, bagaimana dengan praktik budaya pop yang dilakukan kaum muda di desa? Apakah praktik budaya yang lahir bisa memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan resistensi dalam kontestasi sosio-kultural? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, perlu kiranya, kita menggeser atau bahkan merubah paradigma dalam memandang masyarakat desa. Masyarakat desa di Indonesia, saat ini tidak sepenuhnya „ndeso‟ dan „katrok‟ seperti yang sering diungkapkan Thukul dalam Empat Mata. Masyarakat desa Indonesia sejak intensifikasi pertanian melalui Revolusi Hijau dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah bertransformasi dalam jagat sosio-kultural yang sangat dipengaruhi budaya modern perkotaan. Kaum muda desa setiap hari bisa menyaksikan gaya hidup dan budaya yang terjadi di perkotaan melalui layar televisi, baik dalam bentuk sinetron maupun film. Kaum muda desa juga biasa menikmati musik-musik industri yang semakin berkembang, baik dari genre rock, melo-pop, hingga dangdut. Genre dangdutlah yang banyak digemari oleh kaum muda desa dan menjadi bagian penting dari budaya pop mereka, meskipun mereka juga sering mendengarkan atau menonton lagu-lagu pop dari Dewa, Padi, Slank, Ungu, Peterpan, dan lain-lain. Bagi kaum muda desa yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau pengangguran sekalipun, praktik budaya pop memang lebih banyak berlangsung di arena pertunjukan musik dangdut atau campursari—dalam konteks masyarakat Jawa. Di ruang-ruang itulah mereka menyemaikan kehidupan subkultur yang sekilas tampak mengumbar hasrat untuk berjoget, mengikuti liukan tubuh penyanyi.2 Keliaran tersebut juga bisa dibaca sebagai pelampiasan dari rutinitas pekerjaan di sawah ataupun permasalahan sehari-hari yang mereka hadapi. Dengan keliaran itu pula, kaum muda berusaha melepaskan diri dari beban norma tradisi yang mengekang mereka dalam kepatuhan: sebuah praktik pembebasan. Pengaruh dari keliaran tersebut adalah terkadang menyebabkan tawuran antarpenonton yang Para penyanyi sering juga mengeluarkan ucapan-ucapan provokatif yang membuat suasana semakin „panas‟. “Gimana, mau goyang lagi?” dan “Apanya yang mau digoyang?” seperti sudah menjadi „dalil‟ wajib yang semakin menggugah hasrat para pemuda untuk bergoyang. Dan para penonoton biasanya menjawab dengan “Terus!” (untuk pertanyaan pertama) dan “Itunya”, “Bokongnya”, “Semuanya” (untuk pertanyaan kedua. Merespons jawaban dari pasukan goyang seperti itu, si penyanyi hanya akan tersenyum genit dan meminta para pemusik untuk memulai lagu berikutnya. Ucapan “mau goyang lagi?”, “apanya yang mau digoyang?”, “itunya”, ataupun “bokongnya” secara denotatif bermakna ajakan untuk terus bergoyang. Secara konotatif bisa jadi bermakna sebuah „ajakan‟ untuk melampaui batasbatas moralitas, karena semuanya kemudian bisa digoyang, mulai dari paha, pantat, perut, maupun wilayah dada. 2 9 biasanya terjadi karena dua penonton saling bersentuhan (nyenggol) dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras, meskipun dalam beberapa kasus tawuran itu memang sengaja diprovokasi oleh aparat keamanan.3 3. Subkultur: Melawan Pop dan Budaya Mainstream Dalam perkembangannya, popularitas budaya pop industrial yang dalam banyak hal serba standard dan seragam, mendorong lahirnya subkultur (subculture). Dalam pemikiran cultural studies, budaya dalam subkultur mengacu pada keseluruhan cara hidup atau peta makna konseptual yang menjadikan wacana dan praktik yang ada dapat dipahami oleh para anggotanya. Wacana dan praktik yang dikembangkan dalam subkultur kaum muda, tentu saja, berbeda dengan budaya mainstream yang ada dalam masyarakat. Beberapa pemikiran tentang subkultur kaum muda, bisa diajukan dengan memodifikasi rangkuman Barker (ibid.hlm.337-339) tentang subkultur secara umum. 1. Atribut yang mendefinisikan subkultur terletak pada bagaimana akses diletakkan pada perbedaan antara kelompok sosio-kultural tertentu dengan budaya masyarakat yang lebih luas. Kaum muda menemukan subkultur sebagai ruang untuk penyimpangan terhadap norma-norma yang ada dalam budaya masyarakat. 2. Subktultur kaum muda memunculkan suatu upaya untuk mengatasi masalahmasalah kolektif yang muncul dari kontradiksi berbagai struktur dan norma sosiokultural dalam masyarakat. Subkultur membangun sebuah identitas kolektif di mana identitas individu bisa diperoleh di luar identitas yang melekat pada kelas, pendidikan, dan pekerjaan. 3. Subkultur kaum muda menyediakan aktivitas hiburan bermakna yang bertentangan dengan sekolah maupun tempat kerja mereka. 4. Subktultur kaum muda memberikan deskripsi wacana dan praktik alternatif dari realitas sosial sehingga bisa menjadi solusi bagi dilema eksistensi mereka. Signifikansi identitas kolektif yang ditawarkan subkultur dalam memandang realitas sosio-kultural masyarakat, tentu memerlukan satu atribut dan praktik yang membedakan mereka dengan apa-apa yang menjadi mainstream. Dalam arena pertunjukan dangdut di beberapa wilayah Jawa Timur, seperti Lamongan, Mojokerto, Lumajang, Jember, dan lain-lain, terdapa istilah “senggol bacok” (menyentuh bacok), yang artinya ketika bersentuhan antarpenonton bisa memicu terjadinya tawuran yang terkadang harus sampai di bawa ke rumah sakit dan berurusan dengan aparat keamanan. Namun, apakah senggolan dan alkohol bisa menyebabkan tawuran. Menurut penuturan Joko Mursyito, pimpinan Orkes Melayu Monalisa di Kulonprogo, Yogyakarta, dalam beberapa kasus aparat keamanan sengaja memancing terjadinya keributan: “Kadang-kadang tawuran itu „tidak murni‟ bersumber dari penonton. Kadang-kadang ada „pihak-pihak tertentu‟ (maksudnya aparat keamanan, pen) yang sengaja masuk ke kerumunan penonton. Biasanya mereka berada di depan panggung. Ketika suasana semakin panas, biasanya beberapa dari mereka mendorong dua kelompok pasukan goyang sehingga saling bersentuhan hingga saling memukul. Hasilnya, ya tawuran itu. Ya, tau sendirilah, setelah itu mesti urusannya ya ke kantor, kemana lagi. Kan dapat duit. Saya sebenarnya juga tidak suka dengan kejadian seperti itu, tapi ya gimana lagi, terkadang saya juga „membutuhkan‟ mereka. Ya sama-sama ngerti lah.” Wawancara, 27 November 2006, ketika penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir salah satu matakuliah di UGM. 3 10 Konsumsi kreatif yang menjadi karakteristik dari praktik dalam subkultur kaum muda memang berasal dari pemaknaan ulang budaya massa industrial yang bersifat massif dan serba seragam. Konsumsi kreatif yang menghasilkan atribut dan praktik kultural tersebut berasal dari proses peramuan kembali (bricolage) yang melibatkan penataan ulang dan rekontekstualisasi barang/objek untuk mengkomunikasikan makna yang lebih baru dan segar (Clarke, 1976: 177). Konsumsi kreatif merupakan bentuk partisipasi aktif dari para anggota sebuah subkultur. Dengan partisipasi aktif itulah komoditas menjadi lebih bermakna untuk kepentingan identitas kolektif sesuai dengan kebutuhan mereka (Douglas & Isherwood, 1979: 75). Subkultur kaum muda, dengan demikian, bukan semata-mata proses konsumsi produk budaya massa industrial. Lebih dari itu, ia merupakan proses konsumsi kreatif yang mempunyai tendensi politis-kultural. Pertama, sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni tradisi besar serta massifikasi dan komodifikasi barang konsumsi. Kedua, sebagai pemaknaan kreatif atas komoditas yang dihasilkan industri demi kepentingan identitas kultural kolektif dan gerakan kaum muda. Ketiga, resistensi terhadap ketidakmapanan sosial sebagai akibat ketidakadilan yang diciptakan kelas kuasa. Dari sinilah pemaknaan „budaya pop‟ dalam konteks subkultur lahir: terciptanya praktik dan ritual yang sudah menciptakan identitas kultural mereka sendiri. Artinya, sebagai respon dari popularitas budaya pop yang dijalani kaum muda kebanyakan, subkultur telah menciptakan budaya popnya yang biasa dijalani oleh para anggotanya sehingga menjadi populer di lingkupnya sendiri. Lahirnya komunitas pecinta musik rock, heavy metal, punk, reggae, underground hingga hi-hop merupakan perwujudan dari hasrat, impian, dan harapan untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam struktur sosial masyarakat kapitalis yang terlalu banyak menguntungkan para pemilik modal dan pejabat-pejabat politik. Tidak mengerankan, ritual pertunjukan musik seringkali menjadi umpatan yang terkadang diselingi dengan praktik kekerasan terhadap diri sendiri sebagai bentuk protes terhadap wacana dan praktik sosio-kultural yang nyatanya tidak bisa membawa kebaikan untuk semua. Di samping itu gerakan politis-kultural yang mereka usung bisa dibaca sebagai perlawanan terhadap standarisasi musik industrial yang lebih berlirik romantis, dan tidak kritis terhadap realitas sosial, serta mengedepankan nada yang teramat melo dan sudah terlanjur menjadi trend budaya pop bagi kaum muda. Kebisingan musik dan kekerasan praktik dalam memainkan musik atau menonton pertunjukan merupakan atribut dan ritual yang menandakan resistensi tersebut. 11 Sementara klub motor maupun klub hobi tertentu—filateli, pembaca buku, ngrumpi di mall, dan lain-lain—memang lebih dekat dengan pemaknaan kreatif dalam budaya pop dalam konteks estetisasi yang bisa membedakan identitas kultural kolektif mereka di tengah-tengah „seragamisasi‟ kehidupan kultural masyarakat kapitalis. Kondisi tersebut memang lebih banyak terjadi di kelas menengah kota. Abdullah (2006: 33-35), menjelaskan, bahwa saat ini dalam kelas menengah kota tengah berlangsung proses konsumsi simbolis dan transformasi estetis yang menunjukkan betapa nilai-nilai simbolis dari produk dan praktik kultural yang menyertainya telah mendapatkan penekanan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai kegunaan dan fungsional (2006: 33-35). Proses konsumsi simbolis paling tidak menandakan (1) terjadinya pembedaan proses konsumsi yang membedakan kelas sosial yang satu dengan yang lain; (2) barang-barang yang dikonsumsi telah menjadi representasi dari kehadiran mereka; dan, (3) konsumsi citra telah menjadi proses konsumsi yang penting di mana citra yang dipancarkan suatu produk dan praktik merupakan alat ekspresi diri bagi kelompok. Sementara proses estetitasi yang terjadi dalam kehidupan kelas menengah kota bisa dilihat sebagai (1) terjadinya proses seni dalam konsumsi barang yang menegaskan nilai-nilai khusus; (2) terjadinya proses individualisasi dalam memaknai sebuah produk. Dalam kehidupan kota, kelompok dengan status sosial tertentu menggunakan pola konsumsi sebagai alat untuk memapankan tingkatan sosial mereka dan sebagai garis pembatas diri mereka dengan kelompok yang lain (Bocock, 1994: 183). Dengan kata lain, realitas konsumsi dalam masyarakat kota menunjukkan bahwa produk budaya massa industri tidak hanya dikonsumsi dalam kepasifan yang seragam, tetapi adanya partikularitas-partikularitas yang kemudian menjadi karakteristik yang membedakan kedirian dan status sosial mereka di tengahtengah masyarakt. Menurut Lury (1996: 45), kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dari pola konsumsi dari producer-led (produsen yang menentukan dan membentuk pola konsumsi) menuju consummer-led (konsumen yang menentukan dan memberikan makna atas apa-apa yang mereka konsumsi). Namun, hal itu bukan berarti mereka kehilangan semangat untuk maju atau tidak mampu menyikapi permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Dalam kasus subkultur kaum muda pengendara motor, bisa dilihat bagaimana motor-motor pabrikan yang diproduksi serba homogen, baik dalam hal kapasitas mesin maupun modelnya, diramu ulang (modifikasi) oleh para anggota klub motor untuk dijadikan 12 ekspresi estetis yang membedakaannya dengan motor lain.4 Di samping itu motor yang berfungsi untuk alat transportasi semata telah menjadi ajang unjuk nyali melalui praktik free style yang mempertontonkan praktik mengendari motor dalam gaya ekstrim. Pada kesempatan lain, anggota sebuah klub motor bisa saja melakukan ritual touring sambil mengadakan bhakti sosial kepada kurban bencana alam atau memberi santunan kepada keluarga miskin. Artinya, keberadaan klub-klub motor ataupun klubklub lain sejenis, tidaklah berusaha menolak keberadaan kapitalisme ataupun ketidakmapanan struktur sosial, tetapi memberikan pemaknaan lain yang lebih estetis terhadap itu semua. Kenyataan betapa kompleksnya budaya pop dan kaum muda, memang tidak bisa didekati hanya dengan sudut pandang resistensi subkultur maupun praktik resistensi dalam konsumsi semata. Thornton (1995) dalam kajiannya tentang klub-klub musik, misalnya, menemukan realitas bahwa praktik budaya pop (dalam konteks subkultur) bukanlah berkaitan dengan resistensi terhadap kelas kuasa, melainkan semata-mata sebagai usaha untuk membuat pembedaan (distinction) antara sebuah kelompok kaum muda dengan kelompok yang lain sebagai modal subkultur (subculture capital). Mereka menerima status di dalam dunia sosio-kulturalnya sendiri melalui kepemilikan terhadap pengetahuan subkultur. Klub kaum muda pecinta jazz di Indonesia, misalnya, akan mengembangkan modal subkultural melalui praktik ritual yang berbeda dengan klub pecinta reggae. Keberbedaan inilah yang menjadi penting ketika kaum muda menemukan dunia mereka serba seragam oleh popularitas budaya pop industrial. Meskipun demikian, tetap ada satu kata kunci yang melekat dalam praktik budaya pop dalam subkultur dengan bermacam variannya, yakni “keinginan untuk berbeda”. 4. Sebuah Jawaban: Budaya Pop sebagai Inspirasi Pembebasan dan Kreativitas Berbasis Komunitas/Budaya Lokal Dari penjabaran bisa dilihat adanya beberapa poin penting terkait dengan praktik konsumsi budaya pop dan kaum muda. Pertama, budaya pop lahir dari proses konsumsi Di samping modifikasi, anggota sebuah klub motor juga dilengkapi dengan seragam berupa pakaian, emblem, atau sticker motor, sebagai atribut yang membedakan dengan klun motor lain. Untuk semakin memperkukuh solidaritas dan identitas kolektif, klub motor melakukan touring dengan waktu berkala, satu minggu atau satu bulan. Dalam touring ini biasanya ada permainan outbond atau kegiatan rekreatif dan sosial lainnya. Klub motor juga memanfaatkan popularitas interbet untuk membuat website yang menjadi sarana komunikasi antaranggota dan sekaligus mempromosikan identitas kelompok mereka di jagat maya. Website-website klub motor, antara lain (1) Scooter, http://scooterownersgroup.org; (2) Depok Tiger Club, http://detic.honda-tiger.or.id; (3) Yahama Jupiter Owners Community, http://www.yjoc.info; (4) Komunitas Honda Tiger Indonesia, http://www.honda-tiger.or.id; (5) Komunitas Yamaha MX Indonesia, http://www.ymci.web.id/; dan lain-lain. 4 13 yang dilakukan oleh kaum muda terhadap budaya massa industrial karena memenuhi hasrat dan keinginan mereka yang dinamis dan ingin terlihat beda dengan generasi tua/dewasa. Kedua, popularitas budaya pop yang serba standard, meskipun bagi banyak kaum muda menjadi penanda dari identitas kultural, ternyata menimbulkan kekurang puasan pada sebagian kaum muda lain sehingga mereka mengembangkan atribut dan ritual dalam subkultur yang sekaligus membedakan mereka dari praktik budaya pop dan budaya mainstream. Keinginan untuk ingin dilihat berbeda, baik dari para penikmat budaya pop, maupun dari pelaku subkultur merupakan resistensi simbolis dari kemapanan yang ada di sekitar mereka. Ketiga, kaum muda dan budaya pop, nyatanya, bukan hanya satu entitas sepele, karena mereka bisa menjelma sebagai kekuatan reformatif di balik semua praktik budaya yang mereka jalani. Namun, pemahaman-pemahaman di atas masih saja memunculkan kekhawatiran terkait dengan nasib budaya lokal bangsa ini karena kaum muda semakin tenggelam dalam budaya yang mengagungkan gaya hidup (life style) yang cenderung memuja Barat. Memang kaum muda berhasil melakukan konsumsi kreatif demi perayaan identitas mereka, tetapi, kalau disimak lagi, apa-apa yang mereka konsumsi—dari pakaian, musik, film, hingga majalah—merupakan turunan dari model atau bentuk yang berkembang sebelumnya di dunia Barat. Laki-laki dan perempuan muda di mall banyak mengenakan model pakaian terbaru yang berasal atau dijiplak dari model yang biasa dikenakan kaum selebritis Amerika—yang kemudian juga dijiplak oleh para selebritis Indonesia. Wacana dan praktik Barat, nyatanya, memang sangat hegemonik di Indonesia sehingga pilihan untuk menjadi subjek yang terbaratkan, bukan lagi sebuah paksaan, tetapi kesadaran yang menjadi semacam tuntutan apabila ingin dikatakan gaul. Inilah kenyataan kalau kita membicarakan budaya pop dan kaum muda dalam konteks keindonesiaan. Meskipun demikian, kekhawatiran berlebihan terhadap persoalan itu tidak perlu terus dipelihara karena hanya menghabiskan energi. Kenyataanya, kehadiran yang Barat, bukan hanya masalah yang dihadapi Indonesia. Negara-negara bekas jajahan, juga mengalami hal serupa di mana budaya Barat menjelma sebagai paktik diskursif yang terus menghantui eksistensi budaya lokal yang hendak dikembangkan sebagai antitesa, apalagi dengan proses globalisasi informasi dan komunikasi media dewasa ini. Budaya Barat, tentu saja tidak semua jelek, karena di dalamnya juga terdapat pemikiran atau praktik yang mengarah kepada kemajuan. Seperti dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada periode 30-an, bahwa untuk menjadi maju, bangsa 14 Indonesia harus mau mengambil pemikiran dari negara-negara maju, seperti Amerika dan Eropa (1998: 2-11). Namun, seperti dikemukakan Armin Pane, sebagaimana dikutip Faruk (1999: 6), hal itu bukan berarti harus meninggalkan kasanah budaya lokal, tetapi mengambil yang baik dari Barat sembari terus mengembangkan yang lokal—yang tentunya masih hidup dan berkembang. Yang berbahaya sebenarnya adalah ketika kaum muda sekedar larut dalam gaya hidup Barat tanpa bisa mengambil pikiran-pikiran maju ala Barat dan mengolahnya menjadi produk yang menandakan keindonesiaan. Bagi masyarakat poskolonial seperti Indonesia, mengikuti pemikiran Bhaba (1994), sebenarnya selalu tersedia “ruang ketiga” (third space) atau “ruang antara” di mana praktik mimikri (mimicry) selalu terjadi dan mewujud dalam produk dan praktik budaya hibrid yang menegosiasikan kepentingan subjek poskolonial terhadap kuasa diskursif superioritas Barat dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh narasi besar pembaratan. Menurut Hesmondhalgh (2007: 235), sebagian besar musik pop lokal saat ini memang lebih banyak diwarnai dengan hibriditas sebagai hasil dari reinterpretasi terhadap gaya dan teknik bermusik, tetapi berbasis pada kepentingan kaum muda lokal, baik untuk mengekspresikan persoalan hidup atau mengkritisi ketimpangan sosial. Musik yang diusung Dewa, Slank, Padi, Gigi, Peterpan, Nidji, dan lain-lain, semua memang mengambil gaya dan teknik dari cara bermusik Barat, bahkan major label yang memproduksi dan mendistribusikannya tidak jarang merupakan perusahaan transnasional yang beroperasi di Indonesia. Begitupula dengan film-film pop Indonesia. Namun, apabila diperhatikan mereka tetap mengusung tema-tema berbasis lokal Indonesia sehingga menjadi begitu populer di kalangan kaum muda sebagai ekspresi identitas kultural. Pertunjukan mereka selalu dipenuhi oleh kaum muda yang begitu histeris dengan penampilan band-band idolanya, meskipun terkadang harus menelan kurban setelah terjadinya keributan atau desak-desakan antarpenonton akibat kurangnya kapasitas stadion atau gedung. Yang harus dikritisi adalah ternyata tidak semua budaya pop dalam musik, misalnya, mampu menjadi kekuatan penggerak yang memunculkan kreativitas bagi kaum muda untuk bergerak dalam ikut berpartisipasi dalam permasalahan konkrit yang dihadapi masyarakat. Mereka hanya berhenti pada proses perayaan konsumsi kreatif hiburan dan gaya hidup yang beraroma neotribalisme,5 sebagai penegas identitas kultural mereka yang melampaui kelas sosial. Shildrick (2004), mengutip pendapat Bennet, Maffesoli, dan Holland, menjelaskan bahwa budaya kaum muda saat ini tidak lagi terjebak pada subkultur yang merayakan identitas dalam kepentingan kelas5 15 Meskipun demikian, ada juga band, seperti Slank, yang memberikan contoh dalam memperhatikan kehidupan orang kecil dengan melakukan touring sosial dan terlibat dalam aktivitas mereka. Persoalan apakah tindakan yang dilakukan diikuti oleh para penggemarnya, Slankers, bukanlah kapasitas tulisan ini untuk menjelaskannya. Memang, saat ini banyak kaum muda yang larut dalam budaya pop dan mereka bertingkah seperti orang Barat tanpa menghiraukan budaya lokalnya lagi. Tetapi, masih banyak pula kaum muda yang peduli dengan budaya atau komunitas lokalnya dan berusaha menggunakan budaya pop untuk dijadikan inspirasi bagi perjuanganperjuangan kemanusiaan maupun kultural. Mereka bisa saja berada dalam ruang ketiga dengan meniru sebagian budaya pop yang berasal dari Barat dan meramunya dengan kasanah budaya lokal demi kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan Barat. Memang sekilas tampak mereka sudah terhegemoni Barat, tetapi sebenarnya mereka sedang bernegosiasi untuk kepentingan yang lebih luas dan dalam praktiknya mampu menciptakan budaya pop berbasis lokal. Bahruddin, pengelolah Sekolah Alternatif Qarriyah Thayyibah (QT) di Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah adalah salah satu contohnya.6 Dia tidak menolak budaya pop dalam kehidupan kaum muda, tetapi menggunakannya untuk memberdayakan kreativitas mereka. Melalui sekolah berbasis internet dan komunitas lokal, ia dan para siswa yang sekaligus menjadi kawannya, tidak pernah alergi dengan friendster, e-mail, ataupun situs-situs unlimited di internet, meski mereka tinggal di desa. Para siswa juga sudah biasa menonton film, sinetron, maupun mendengarkan musik. Semua bentuk budaya pop yang ada dalam kehidupan mereka, diolah kembali menjadi piranti untuk pembelajaran yang bisa memberikan pencerahan. Para siswa dibiarkan merdeka dengan pilihannya sendiri. Bagi mereka yang gemar menulis fiksi dipersilahkan menulis novel atau puisi. Bagi mereka yang suka melihat film, dipersilahkan membuat film. Konsep pendidikan dengan media budaya pop tersebut, ternyata berhasil membangkitkan gelora ekspresif-kreatif dari para siswa sehingga di usia SMP atau SMA mereka sudah pandai menulis artikel, puisi, novel, ataupun kelas sosial. Budaya kaum muda saat ini lebih banyak ditandai dengan konsumsi gaya estetik dan penggunaan musik pop yang sesuai dengan kepentingan individual yang lebih cair dan transisional dan tidak lagi didasarkan kepada kepentingan kelas seperti yang dilakukan oleh pemikir cultural studies dalam kajian subkultur. Artinya, semua kaum muda, tanpa memandang kelas sosial mereka, bisa terlibat dalam perayaan gaya hidup maupun musik yang lebih ditentukan oleh pilihan-pilihan pembeda (community of choice) sebagai penanda lahirnya “persona posmodern” atau “identifikasi berlipat ganda” dari budaya kaum muda saat ini sehingga tidak bisa hanya dipandang dalam konteks subkultur yang begitu ketat. 6 Informasi tentang QT diperoleh penulis dari wawancara dengan Bahruddin dan beberapa siswanya, pada 19 April 2008 di Kalibening Salatiga. 16 menciptakan lagu sekaligus aransemen musiknya. Kalau semula budaya pop sekedar menjadi pembeda antara dunia kaum muda dan kaum tua, bagi para siswa di QT telah menjadi kawan untuk menimbulkan inspirasi kreatif sehingga mampu meciptakan budaya pop yang sesuai dengan kesukaan dan kebutuhan mereka sendiri yang sekaligus membebaskan mereka dari kekangan sistem dan kurikulum pendidikan formal di Indonesia. Capaian-capaian yang diperoleh dan dinikmati oleh para siswa QT, bisa diasumsikan oleh Habermas dengan ruang publik borjuisnya. Habermas (2007) memaparkan ruang publik klasik sebagai tempat untuk memperdebatkan berita atau karya sastra sebagai bentuk budaya pop yang dihasilkan industri budaya massa. Ruang publik telah menjadi praktik budaya pop yang berhasil memposisikan individu-invidivu di kedai kopi maupun salon dalam perdebatan kreatif tentang isu-isu politik, hukum, maupun ekonomi tanpa menghiraukan status kelas, meskipun dalam perkembangannya ruang publik tersebut perlahan menghilang karena industri telah mengkomodifikasi perdebatan-perdebatan tersebut sebagai opini dari para pakar tertentu. Di QT yang terjadi adalah bagaimana budaya pop dijadikan sarana untuk memperdebatkan dan membebaskan ide dari kekangan-kekangan normatif sembari mengkritisi persoalan sosial maupun keseharian sehingga melahirkan ruang publik emansipatoris yang mampu mendorong lahirnya produk-produk baru budaya pop untuk kepentingan pembebasan kreatif para siswa. Di Banyuwangi Jawa Timur, dalam konteks yang berbeda, budaya pop yang merupakan hasil dari hibridasi dengan budaya pop bernuansa Barat, juga berkembang luas, bahkan sudah menjadi penggerak industri rekaman lokal. Kaum muda berkumpul membentuk satu grup musik yang memadukan genre musik pop Barat, seperti blues dan rock, dengan genre musik Using yang mendayu-dayu, tetapi dinamis (Setiawan, 2007a). Meskipun pada awalnya dianggap sebagai penyimpangan, nyatanya, genre musik baru yang diberi nama patrol opera Banyuwangi ini mampu menjadi budaya pop yang tidak hanya menarik perhatian kaum muda, tetapi juga kaum tua, baik di Banyuwangi maupun kabupaten di sekitarnya (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso), bahkan sampai di Malang dan Surabaya. Bahkan salah satu album yang beredar dalam satu tahun (2002) berhasil mencapai angka 150 ribu copy CD yang terjual. Aransemen blues dan rock dengan alat modern seperti gitar, bass, drum, keyboard, diramu sedemikian rupa dengan aransemen musik Using yang diwarnai dengan kendang, seruling, dan kempul. Hibridasi aransemen dan jenis musik tersebut 17 dilengkapi dengan lirik berbahasa Using dengan tema lagu beragam, dari masalah cinta (mayoritas) sampai persoalan sosial rakyat kecil. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Jember Jawa Timur, di mana beberapa kelompok jaranan/jathilan, menggunakan produk budaya pop dalam konteks yang lebih parsial. Beberapa kaum muda yang terlibat di dalam kelompok, menawarkan kepada para anggota yang lebih tua (secara usia) untuk memasukkan unsur musik pop, seperti dangdut, untuk dijadikan pelengkap—atau lebih tepatnya tempelan—dalam pertunjukan jaranan (Setiawan, 2005). Penyanyi dangdut dipersilakan menyanyi pada atraksi tarian jaranan dan sesudah pertunjukan tarian selesai. Para penonton dipersilahkan memberikan saweran. Hal itu dilakukan agar rakyat desa—terutama kaum muda—yang sudah terbiasa dengan musik dangdut, mau menonton kembali atraksi pertunjukan jaranan dengan tarian-tarian dan atraksi trance-nya sehingga kesenian ini tetap bisa digemari oleh komunitas pendukungnya dan “tidak terasing di desanya sendiri”. Hal serupa juga dilakukan beberapa dalang muda di Jember. Pembukaan pertunjukan wayang diawali dengan musik dangdut atau campursari yang bisa menarik kedatangan para penonton yang berasal dari kaum muda agar mau menonton wayang. Terbukti, banyak di antara mereka yang menikmati pagelaran wayang, meskipun ada juga yang pergi dan kembali lagi ketika sesi cinguk limbuk diisi kembali dengan musik dangdut (Setiawan, 2007b). Apakah ini bisa dikatakan sebagai hegemoni budaya pop industrial? Tunggu dulu. Budaya pop industrial hanya dijadikan alat untuk menegosiasikan budaya lokal, dan titik tekannya tentu saja tetap pada usaha untuk pemberdayaan yang terus berlanjut. 5. Jangan Main-main dengan Budaya Pop dan Kaum Muda: Simpulan Paparan di atas, paling tidak, mengimplikasikan bahwa untuk mengkaji persoalan kaum muda dan budaya pop di Indonesia, bermacam sudut pandang bisa digunakan. Selalu ada konteks partikular maupun konteks yang lebih luas dalam mempersoalkan kaum muda dan konsumsi budaya pop. Penyederhanaan konteks dalam paradigma moralitas atau kapitalisme, tentu saja akan menjadikan kajian terjebak dalam dalil-dalil deterministik yang tidak bisa membongkar persoalan yang sebenarnya, meskipun itu tidak sepenuhnya salah. Yang pasti, jangan selalu memposisikan kaum muda sebagai „makhluk-makhluk dungu‟ yang hanya terjebak dan tidak bisa keluar lagi dari gaya hidup dan praktik budaya pop karena mereka sebenarnya merupakan individu-individu 18 yang mempunyai beragam kepentingan dan pertimbangan dalam menjalakan kebudayaannya sendiri. Budaya hari ini adalah budaya pop itu sendiri, dan kaum mudalah yang banyak menjadi penggerak dan pelakunya demi capaian dan kepentingan kultural yang mereka impikan. Maka, kajian-kajian dalam konteks yang lebih partikular—baik melalui kajian teks maupun etnografi—menjadi begitu penting untuk dilakukan karena kemampuan memetakan praktik, bentuk, dan perayaan budaya pop di kalangan kaum muda, bisa membuka kesadaran kritis terus menerus akan persoalan budaya yang sebenarnya dihadapi bangsa ini. Bukan sekedar usaha untuk memperdebatkan dan mempertahankan budaya nasional yang teralu utopis, karena realitas budaya pop sudah semakin menggejala. Kalau memang kaum muda selalu diposisikan sebagai penerus perjuangan bangsa, maka kontribusi kajian budaya pop menjadi signifikan karena akan bisa diketahui bagaimana sebenarnya mereka membayangkan budaya dan perjalanan bangsa ini ke depan menurut cita-cita dan pemikiran ideal mereka sendiri. Di sinilah dibutuhkan kesiapan strategi, sudut pandang, dan cara analisis dari kalangan akademisi-kritis untuk membongkar apa yang ada di balik teks dan praktik budaya pop, bukan sekedar dalil-dalil yang berusaha menghakimi mereka dalam konteks degradasi dan dekadensi moral. Kekayaan paradigma akan menjadi faktor penentu yang mampu mengarahkan kajian budaya pop dan kaum muda dalam lingkup yang spesifik sembari terus memberikan kritik sehingga kesadaran berbudaya tidak lagi diposisikan sebagai “harus ini” dan “harus itu” tetapi pada “bagaimana mereka menjalani?”, “bagaimana mereka menginterpretasi?”, “bagaimana mereka bernegosiasi dalam kreativitas?”, “apakah mungkin terjadi hegemoni melalui teks budaya pop”, dan “apakah mungkin mereka terhegemoni, melawan, atau menyiasati?” Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan memunculkan kritik terus menerus yang diharapkan akan semakin menumbuhkan kedewasaan dalam melihat budaya pop dan kaum muda serta kemungkinankemungkinan strategi agensi untuk semakin memberdayakan kaum muda dan juga budaya pop yang mereka jalani. Dengan demikian, kaum muda dan budaya pop tidak lagi harus diletakkan di wilayah margin, tetapi dimasukkan ke dalam bagian sah dari kebudayaan yang ada di bangsa ini: kebudayaan yang terus menjadi, bukannya sudah jadi. Budaya pop memang sudah menjadi realitas yang tidak bisa ditolak lagi. Ke depan, kaum muda akan terus “bertingkah” dalam beragam kondisi, bentuk, dan 19 praktik yang bisa saja membuat para akademisi budaya merasa ngeri atau tersenyum manis. Ketika para akademisi tidak menyiapkan diri untuk menjawab realitas tersebut, maka, bisa jadi mereka akan menjadi penonton yang hanya bisa mengumpat, menangis, atau bahagia, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di samping kesiapan kajian, keterlibatan aktif-partisipatoris untuk masuk ke dalam praktik budaya pop dan ruang publik kaum muda, menjadi kepentingan yang sudah semestinya selalu diusahakan oleh para akademisi sehingga tidak sekedar berdiri di menara gading, tetapi terlibat sebagai intelektual organik yang secara sadar berusaha memberikan kontribusi yang mencerahkan, bukan sekedar menghakimi. Yang muda memang akan selalu bertingkah, tetapi sangat ironis kalau yang lebih mengerti atau yang lebih tua hanya bisa kepradah (kebingunan dan terkaget-kaget). Semoga kita tidak menjadi bagian dari mereka yang kepradah. Daftar Bacaan Abdullah, Irwan.2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Antariksa, “Bioskop dan Kemajuan Indonesia Awal Abad XX”, dalam Budi Susanto (ed).2005. Penghibur (an): Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino bekerjasama dengan Penerbit Kanisius. Adorno,Theodor W. “Television and the Pattern of Mass Culture”, dalam Bernard Rosenberg and David Manning White (ed).1957. Mass Culture. Illionis: The Free Press. Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer.1993. “The culture industry: enlightment as mass deception”, dalam Simon During (ed).1957. The Cultural Studies Reader. New York: Routledge. Alisjahbana, Sutan Takdir, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, dalam Achdiat K. Miharja (ed).1998. Polemik Kebudayaan (Cetakan ke-3). Jakarta: Balai Pustaka. Barker, Chris.2004. Cultural Studie, Teori dan Praktik (terj. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Bennet, Tony, “Introduction: the turn to Gramsci” and “The Politics of „the popular‟ and popular culture”, dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds).1986. Popular Culture and Social Relations. Philadelpia: Open University Press. Bhabha, Homi K.1994. The Location of Culture. London: Routledge. Bocock, Robert.1994. “The Emergence of the Consumer Society”, dalam The Polity Reader in Cultural Theory. Cambridge: Polity Press. Brooker, Peter.2007. A Glossary of Cultural Theory (Second Edition). London: Arnold. Budiman, Hikmat. 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 20 Clarke, J., “Style”, dalam Stuart Hall & T. Jefferson (eds).1976. Resistence through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. London: Hutchinson. Douglas, Mary & Isherwood, Mary.1979. The World of Goods, Toward an Anthropology of Consumption. New York: Routledge. Faruk, “Mimikri dalam Sastra Indonesia”, dalam Jurnal Kalam, Edisi 14, 1999. Fiske, John, “Popular Culture” dalam Lentricchia & Thomas McLaughin (et.al).1995. Critical Terms for Literary Study. Chicago: University of Chicago. __________.2002. Television Culture. London: Routledge. Gans, Herbert J.1974. Popular Culture and High Culture, An Analysis and Evaluation of Taste. New York: Basic Books Inc. Grossberg, L.1992. We Gotta Out This Place: Popular Conservation and Postmodern Culture. London: Routledge. Habermas, Jürgen.2007. Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis (terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Haesmondhalgh, David.2007. The Cultural Industries, 2nd Edition. London: Sage Publication. Hall, Stuart, “Popular culture and the state” dan David Cardiff&Paddy Scannell.1986. “Good luck war workers! Class, politics, and entertainment in wartime broadcasting” dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds).1986. Popular Culture and Social Relations. Philadelpia: Open University Press. __________.1971. “Introduction”, in Working Paper in Cultural Studies, Spring. Birmingham: CCCS Birmingham University. ___________, “Notes on Deconstructing The Popular”, dalam Stephen Duncombe (ed).2002. Resistance Culture. London: Verso. Handayani, Christina S., “Para Saksi Identitas Dugem”, dalam Budi Susanto (ed).2005. Penghibur (an): Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino bekerjasama dengan Penerbit Kanisius. Jansson, Andre, “The Mediatization of Consumption: Towards an analytical framework of image culture”, dalam Journal of Consumer Culture, Vol. 2, No. 1, 2002. London: Sage Publications. Lowenthal, Leo, “Historical Perspective of Popular Culture, dalam Bernard Rosenberg and David Manning White (eds). Mass Culture. Illionis: The Free Press. Lury, Celia.1996. “Material Culture and Consumer Culture” dalam Consumer Culture. Cambridge: Polity Press. McDonald, Dwight.1956. “A Theory of Mass Culture” dalam Bernard Rosenberg and David Manning White (eds).1957. Mass Culture. Illionis: The Free Press. Saputro, Kurniawan Adi, “Melihat Ingatan Buatan: Menonton Penonton Film Indonesia 1900-1964”, dalam Budi Susanto (ed).2005. Penghibur (an): Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino bekerjasama dengan Penerbit Kanisius. 21 Setiawan, Ikwan.2005. “Menjaga Ritual Menyiasati Pasar: Strategi Survival Kelompok Jaranan di Jember. Laporan penelitian (belum dipublikasikan) Dana Internal Grant. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. ______________, “Transformasi Masa Lalu dalam Nyanyian Masa Kini: Hibridasi dan Negosiasi Lokalitas dalam Musik Populer Using”, dalam Jurnal Kultur, Vol. 1, No. 2, September 2007a. Jember: Pusat Penelitian Budaya Jawa dan Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember. ______________.2007b. “Menyemaikan Multikulturalisme: Peran Strategis Seni Pertunjukan Etnis dalam Mengembangkan Masyarakat Multikultural di Jember”. Laporan penelitian (belum dipublikasikan) Dana DIKTI. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. Shildrick, Tracy, “Youth culture, subculture, and the important of neighbourhood”, dalam Jurnal Young, Vol. 14, No. 1, 2006. London: Sage Publications. Storey, John.1993. An Introductory Guide to Culture.Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. Cultural Theory and Popular Thornton, Sarah.1995. Club Cultures: Music, Media, and Subcultural Capital. London: Polity Press. Turner, Victor.1974. Dramas, Field and Metaphors. Itacha: Cornell University Press. Webb, Darren, “Bakhtin at the Seaside: Utopia, Modernity, and Carnivalesque”, dalam Journal of Theory, Culture, and Society, Vol. 22, No. 3, 2002. London: Sage Publications. Williams, Raymond.1961. The Long Revolution. London: Chatto and Windus. 22