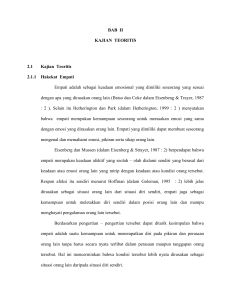Pokok-Pokok Proposal Tesis
advertisement
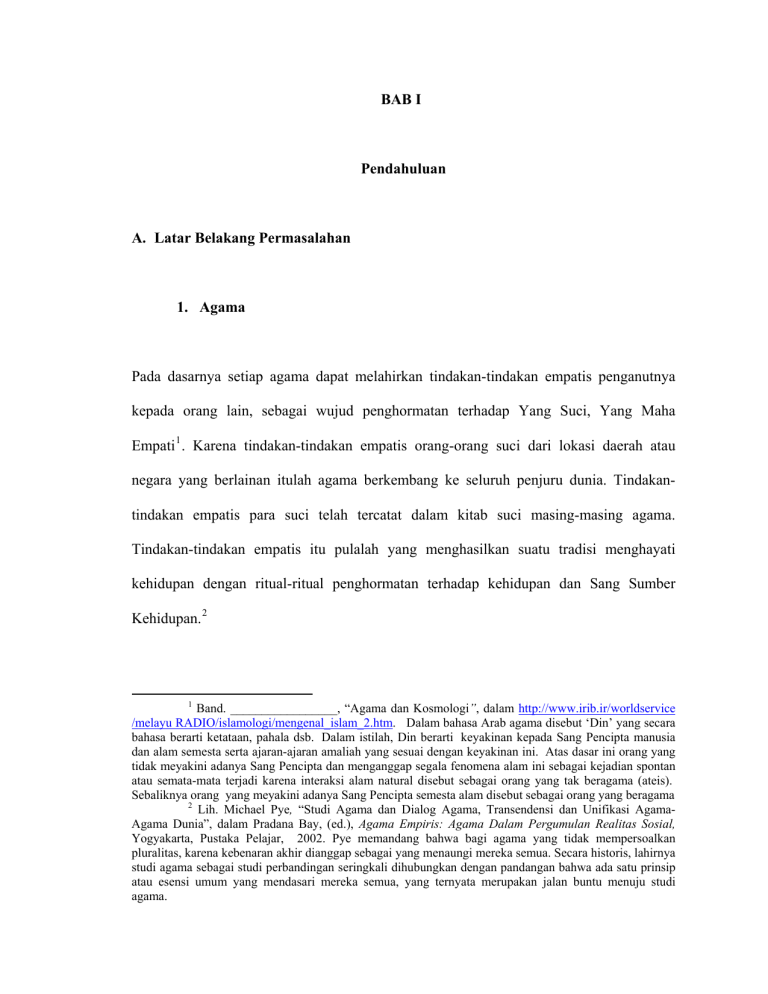
BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Permasalahan 1. Agama Pada dasarnya setiap agama dapat melahirkan tindakan-tindakan empatis penganutnya kepada orang lain, sebagai wujud penghormatan terhadap Yang Suci, Yang Maha Empati 1 . Karena tindakan-tindakan empatis orang-orang suci dari lokasi daerah atau negara yang berlainan itulah agama berkembang ke seluruh penjuru dunia. Tindakantindakan empatis para suci telah tercatat dalam kitab suci masing-masing agama. Tindakan-tindakan empatis itu pulalah yang menghasilkan suatu tradisi menghayati kehidupan dengan ritual-ritual penghormatan terhadap kehidupan dan Sang Sumber Kehidupan. 2 1 Band. _________________, “Agama dan Kosmologi”, dalam http://www.irib.ir/worldservice /melayu RADIO/islamologi/mengenal_islam_2.htm. Dalam bahasa Arab agama disebut ‘Din’ yang secara bahasa berarti ketataan, pahala dsb. Dalam istilah, Din berarti keyakinan kepada Sang Pencipta manusia dan alam semesta serta ajaran-ajaran amaliah yang sesuai dengan keyakinan ini. Atas dasar ini orang yang tidak meyakini adanya Sang Pencipta dan menganggap segala fenomena alam ini sebagai kejadian spontan atau semata-mata terjadi karena interaksi alam natural disebut sebagai orang yang tak beragama (ateis). Sebaliknya orang yang meyakini adanya Sang Pencipta semesta alam disebut sebagai orang yang beragama 2 Lih. Michael Pye, “Studi Agama dan Dialog Agama, Transendensi dan Unifikasi AgamaAgama Dunia”, dalam Pradana Bay, (ed.), Agama Empiris: Agama Dalam Pergumulan Realitas Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002. Pye memandang bahwa bagi agama yang tidak mempersoalkan pluralitas, karena kebenaran akhir dianggap sebagai yang menaungi mereka semua. Secara historis, lahirnya studi agama sebagai studi perbandingan seringkali dihubungkan dengan pandangan bahwa ada satu prinsip atau esensi umum yang mendasari mereka semua, yang ternyata merupakan jalan buntu menuju studi agama. 2 Namun pada kenyataannya tindakan-tindakan empatis tersebut sering tidak mendapat ruang yang memadai untuk dikembangkan menjadi suatu pola kehidupan sejati antar manusia, sehingga terjadilah semacam anomali atau yang berlawanan dengan harapan kita, yakni munculnya tindakan-tindakan kekerasan yang di-“haram”-kan oleh agama 3 . Anomali tersebut sebagai akibat dari tidak tersedianya ruang untuk mengembangkan tindakan-tindakan empatis yang menjadi inti dari kehidupan beragama. Sebagian orang akan setuju bila dikatakan bahwa pada dasarnya agama itu baik, yang tidak baik adalah orangnya. Penulis menyetujui pernyataan itu, karena pernyataan itu menegaskan kembali bahwa agama itu harus benar baik dari sisi teologis maupun sisi hubungan antar manusia. Dalam sejarah tersebarnya ajaran kebenaran menjadi suatu institusi agama, suatu agama dapat dikatakan benar secara teologis serta masih dapat diyakini kebenarannya ketika diikuti tindakan-tindakan empatis kemanusiaan 4 . 3 Band. Dr. Abdul Munir Mulkhan, “Etika Kebangsaan Dalam Pluralitas Sosial Dan Keagamaan”, dalam http://www.cides.or.id/ Publikasi/ Publikasi.asp, Center for Information and Development Studies, 2002. Menurutnya, dalam membicarakan masalah etika kebangsaan diperlukan dialog terbuka antara lembaga-lembaga yang mengatasnamakan masyarakat (ormas), sehingga “DPR jalanan” yang merupakan gejala perpolitikan masa depan tidak akan berkembang dalam arti memperbanyak korban. Pasca “era perang dingin” dan disintegrasi negara besar seperti Uni Sovyet serta munculnya berbagai ramalan konflik baru kebangsaan global. Masalah konflik baru banyak dikaitkan dengan problem keagamaan dan etnisitas seperti tesis Huntington (1995) yang kini sedang dirasakan bangsa Indonesia, sesudah krisis ekonomi yang meluas merambah ke dunia politik. Namun, patut dipersoalkan apakah etnisitas dan keagamaan sebagai faktor pemicu konflik dan kerusuhan yang dominant. Bukankah konflik keagamaan dan etnisitas bisa menjadi lebih hebat dan baru “kemudian” muncul sesudah faktor pencetus utama yakni sosial, ekonomi dan politik tidak teratasi. Uniformisasi nilai, budaya dan keberagamaan adalah bentuk kekerasan yang lebih dahsyat di permukaan bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk dari kehalusan budi dan pemihakan pada tatanilai kebaikan dan kebenaran. Lebih dahsyat lagi ketika upaya penyeragaman itu memakai legitimasi keagamaan dan religiositas di mana ke-unik-an personal dan kolektif dianggap melanggar norma keagamaan sehingga mudah dituduh sebagai bentuk kesesatan keagamaan yang diancam api neraka dan kemarahan Tuhan. Elite politik dan keagamaan secara bersama memproduksi diri sebagai tuhan-tuhan kecil yang lebih berkuasa dari Tuhan dan setiap saat memasukkan seseorang ke dalam neraka atau surga menurut versinya sendiri. 4 Band. Komaruddin Hidayat, “Dari Inklusivisme ke Pluralisme”, dalam Harian Kompas, Selasa, 8 April 1997. Menurutnya, sebuah doktrin agama selalu tumbuh dalam lingkup historis yang bersifat partikular, sedangkan kuasa dan kasih Tuhan mengatasi ruang historis. Ini berarti klaim kebenaran agama 3 Tersebarnya ajaran Yesus Kristus yang kemudian melembaga menjadi agama Kristen, yang menjadi sumber ajaran kebenaran bahwa kasih kepada Allah segera diikuti kasih kepada sesama manusia. Demikian juga tersebarnya ajaran Nabi Muhammad saw. yang melembaga menjadi agama Islam, yang menjadi sumber ajaran ketaatan kepada Allah, diikuti dengan contoh kehidupan Nabi yang mendamaikan suku-suku. Pola yang demikian ini, sebagaimana ajaran kebenaran yang diikuti tindakan yang empatik kemanusiaan ini selalu bersama dengan keberhasilan pemberitaan kabar sukacita atau dakwah. Seseorang dikatakan sebagai orang beragama pertama-tama bukan karena apa yang dipercayanya, tetapi oleh karena apa yang dilakukannya. Apabila perilaku dan tindakan seseorang itu baik maka dapat dikatakan ia adalah orang beragama 5 . Tetapi sebaliknya, jika tindakannya tidak baik, maka akan sulit untuk dikatakan bahwa ia adalah orang beragama. (religious truth claim) yang bersifat eksklusif tidak bisa menyisihkan (to exclude) dan menegasikan kehendak dan karya Tuhan untuk membukakan pintu keselamatan bagi hambaNya dalam rentang waktu historis selama hal itu dikehendakiNya. Dengan demikian kita perlu membedakan antara tradisi agama (religious tradition) disatu sisi dan sikap keberagamaan primordial (primordial religiousity) pada sisi yang lain, serta kemungkinan-kemungkinan baru karya Tuhan sebagai manifestasi kepedulianNya kepada hamba-hambaNya. 5 Band. Taufik Abdullah & M. Rusli Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, hal.1. Mattulada menyatakan beragama sebagai kepercayaan tetap akan menyatakan dirinya secara sosio-kultural. Oleh karena itu penelitian agama adalah mendasarkan diri pada fenomena perilaku orang yang beragama. 4 Oleh karena kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dunia kehidupan obyektif, maka kehidupan beragama dapat dipelajari secara obyektif6 . Sekalipun kehidupan beragama yang obyektif bukan hanya karena adanya indikasi bahwa agama hanya berhubungan dengan tindakan baik dan tidak baik 7 . Kehidupan orang beragama adalah kehidupan yang menyangkut keyakinan individu terhadap Tuhan, namun selain itu di dalam individu yang percaya tersebut terdapat perasaan-perasaan, motivasi-motivasi yang membentuk kepribadiannya. Jadi, membicarakan keberagamaan pada dasarnya membicarakan individu yang beragama yang berarti membicarakan perasaan-perasaan, motivasi-motivasi individu yang dapat membentuk suatu tindakan empatis. 2. Pendekatan Empatis Di Indonesia, pluralitas adalah suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak 8 . Penolakan terhadap realitas plural berarti suatu pengingkaran terhadap realitas Indonesia itu sendiri. 6 Band. Komaruddin Hidayat, “Dari Inklusivisme ke Pluralisme”, dalam Kompas, Selasa, 8 April 1997. Sesungguhnya semua doktrin agama selalu berkembang dalam perjalanan historisnya sehingga apa yang disebut teologi, misalnya, adalah juga bersifat antropologis. 7 Band. Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J., Percikan Filsafat, Jakarta, PT. Pembangunan, 1978, hal.22. Durkheim berpandangan bahwa baik buruknya sesuatu ditentukan oleh masyarakat. Artinya, yang menjadi asal dan dasar dari kewajiban adalah masyarakat. Menurutnya, manusia adalah individu atau perorangan, sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat, oleh karenanya ditentukan oleh masyarakat. Selanjutnya ia berpandangan bahwa kesusilaan sebetulnya hanyalah ikatan dari masyarakat. Menurut konsepnya ini, individu atau perseorangan tidak merupakan tujuan dari tindakan yang disebut baik. Yang harus menjadi tujuan agar perbuatan menjadi baik adalah masyarakat. Contoh, misalnya korupsi dan pelacuran tidak akan dianggap baik atau buruk, kalau tidak ditentukan oleh masyarakat. Drijarkara tidak setuju dengan etikanya Durkheim ini, karena memberlakukan depersonisasi kemanusiaan. Mengingkari hakekat manusia sebagai pribadi. Dampak yang lain dari teori Durkheim, dapat membenarkan kolonialisme, dengan mengatakan baiklah kita merampas kemerdekaaan negara tetangga kita. 8 lih. Muhadjir Darwin, “Pluralisme”, dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu, 3 Agustus 2005. Ketika penulisan ini tengah berjalan akhir Juli 2005, MUI mengeluarkan 11 fatwa , yang salah satunya mengharamkan pluralisme. Namun kemudian segera muncul berbagai reaksi terhadap fatwa tersebut dan meminta agar MUI meninjau kembali fatwa tersebut, yang justru dapat menghambat arah dialog antar agama yang tengah mulai dibangun. Muhadjir melihat, bahwa dari 11 fatwa terdapat tiga fatwa dari sisi hubungan antar agama termasuk kontroversial, yakni pertama terkait dengan haramnya kelompok Islam 5 Sebagai contoh, kasus fatwa yang mengharamkan pluralisme dan menolak realitas justru banyak menuai protes dari masyarakat luas dan sebenarnya tidak mempunyai dasar pijakan empirik maupun teoritis yang kuat. Dalam konteks pluralitas agama-agama di Indonesia yang demikian itu, posisi pendekatan empati menjadi demikian penting untuk dapat saling berdialog dan membuka ruang kesadaran individu. Kita sudah sangat sering mendengar kata “toleransi” yang demikian khas Indonesia, tetapi sebenarnya toleransi justru dapat menemukan maknanya sendiri ketika pendekatan empati dipraktekkan. Karena hampir sulit dipastikan bahwa tanpa Ahmadiyah, kedua, pluralisme, sekularisme dan liberalisme haram; ketiga, doa bersama lintas agama serentak juga diharamkan. Ia mempertanyakan keberadaan fatwa MUI sebagai respon permintaan atas keresahan masyarakat mengapa tidak memberikan solusi, malah terkesan memperburuk masalah? Sementara konflik sosial horisontal atas nama suku dan agama tengah menggerogoti integrasi bangsa, malah usaha membuat sekat identitas primordial semakin kuat. Ia mengritik fatwa MUI sebagai bukan sumbangan apapun untuk memperbaiki masyarakat yang berada dalam kerusakan tatanan sosial. Ia mengusulkan agar fatwa ulama yang dibuat mendorong kehidupan sosial yang damai, santun dan saling menghormati dan mengharamkan tindak kekerasan atau teror. Perlu ada fatwa bahwa amar ma’ruf nahi mungkar, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara “mungkar”. Sebagai sosok yang tulus Islam, penulis ingin Islam melihat kebesaran pemimpin Islam, yakni Nabi Muhammad, dan juga tokoh Nasional Islam seperti Moh. Roem yang berbesar hati dengan pandangannya yang pluralis. Oleh karena pluralisme berintikan pengakuan dan penghormatan antar individu yang berbeda identitas termasuk agama, maka Indonesia adalah negara pluralis. Ideologi Pancasila berarti ideologi pluralis. UUD juga konstitusi pluralis, dapat menjadi Rohnya Agama. Karena fatwa MUI bertentangan dengan dasar dan konstitusi negara, maka sebaiknya ditinjau kembali. Ia cemas ketika banyak fatwa dihasilkan tetapi tidak dilakukan, justru akan menggerogoti kewibawaan Islam sendiri. Namun dapat juga Muhadjir melupakan fakta bahwa ideologi pluralitas selama ini ternyata hanya menghasilkan koruptor-koruptor, yang membuat sebagaian besar umat Islam menjadi korban ketidakadilan dari sistem pluralitas. Atau memang selama ini ternyata bangsa ini tidak sadar pluralitas? Band. catatan Pdt. Djaka Soetapa terhadap Seminar Agama-Agama PGI setiap tahun menyatakan bahwa, dalam beberapa kali Seminar Agama-agama, Pancasila dipahami sebagai penjamin demokrasi dan kesetaraan setiap anak bangsa. Agama-agama tidak memiliki sisi keberatan dalam hal ini, justru mendukungnya. Melalui Pancasila ada penjamin negara dan bangsa dalam kesejajaran. Ini pulalah yang nampaknya begitu diagungkan sehingga tanpa sadar ada agenda lain yang terlupa. Agama-agama menjadi tidak lagi kritis terhadap konsep-konsep yang dikembangkan selanjutnya. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan jaminan kekuasan bagi cita-cita negara, maka agama sebagai lembaga kemudian dianggap berada di bawah perlindungan Pancasila. Disinilah letak kelemahan agama-agama. Dengan demikian mereka tidak lagi independen, yang dapat secara bebas memberikan pertimbangan, penilaian, masukan berdasarkan penghayatan masing-masing. 6 tindakan empatis bentuk toleransi dapat ditentukan 9 . Konflik konflik antar suku dan antar agama yang terjadi di Indonesia selama ini dapat menjadi indikator yang nyata, bahwa belum ada titik tolak kesadaran empatis yang dapat menjadi indikator model hidup yang toleran. Sehingga kita dapat melihat suatu ironi kehidupan beragama yang kita jumpai, fenomena yang berkembang sekarang ini banyak yang memperlihatkan agama justru memperlihatkan “wajah” perlawanan terhadap proses toleransi yang baru belajar berjalan? 10 . Oleh karena pendekatan empatis mengasumsikan masih adanya ruang untuk dapat belajar hidup dalam dunia yang semakin multikultur, maka menjadi demikian penting bagi penulis untuk dapat memahami primordialitas kita sekaligus memahami kehadiran orang lain yang berbeda. 11 Primordialitas seorang individu dapat mengingatkan batas kemampuan kita menangkap dan memahami dunia di luar kita, sebaliknya individu yang lain dapat memperkenalkan kita dengan bagaimana batas kemampuannya dapat memberi kita pemahaman yang baru. 9 Lih. Michael Pye, “Studi Agama dan Dialog Agama: Transendensi dan Unifikasi AgamaAgama Dunia”, dalam Pradana Bay, (ed.), Agama Empiris: Agama Dalam Pergumulan Realitas Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal 4. Ia mengatakan bahwa, pentingnya studi agama adalah untuk mengawal perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena beberapa agama menyebabkan lebih banyak kekacauan dan penderitaan sosial daripada agama lain. Wartawan dan komentator sosial dapat mendiskusikan dengan tepat apabila memiliki informasi yang jelas dapat dipertanggungjawabkan tentang beragam agama yang tengah didiskusikan. 10 Lih. Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jakarta, BPK, 2004, hal. 497. 11 Lih. Pdt. Supriatno, “Disintegrasi Bangsa dalam Sikap dan Pandangan Umat Beragama”, dalam http://www.gkp.or.id/index.asp?id=3030. Dengan mengutip Franz Magnis-Suseno yang mengatakan konflik dapat dipecahkan dengan dua cara: perang atau melalui kesepakatan bersama Supriyatno menyimpulkan bahwa fenomena kehidupan bangsa yang diwarnai adanya keinginan sekelompok elemen bangsa yang berambisi memisahkan diri, pasti dapat dikategorikan tengah berkonflik. Dilihat dari sudut sebagai seorang yang beragama Kristen, saya berharap lembaga agama harus mengupayakan lahirnya damai yang berkeadilan. Dengan langkah pastoral lembaga agama menangkap pergumulan riil dari pihak yang ingin memisahkan diri, dan didasari perasaan empati mengartikulasikan perasaan diperlakuan tidak sesuai haknya, agar para pengambil kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya meresponnya dengan sikap respek. Di pihak lain, kewajiban mereka untuk menjaga keutuhan kehidupan bangsa. Jadi, di sini lembaga agama seyogyanya bisa berperan mengajak pihak yang berkonflik bisa mencari dan menemukan 7 B. Hubungan Islam Kristen di Indonesia Studi Agama-Agama dalam konteks Indonesia menempatkan hubungan antar agama sebagai bagian dari usaha yang besar untuk membangun kesadaran hidup bersama antar agama 12 . Studi agama-agama memang mempunyai ruang yang tidak terbatas, yang tidak mungkin dapat diselesaikan selama agama ini masih ada, maka ruang lingkup penelitian ini akan bertitik tolak juga dari kondisi hubungan Kristen dan Islam di Indonesia yang masih selalu dipengaruhi oleh keadaan politik hubungan antara sebagian kelompok muslim dan negara yang masih belum dapat didamaikan. Studi ini secara lebih khusus lagi ingin mencari suatu pendekatan yang metodologis dalam membangun hubungan antar agama. Metodologi pendekatan empatis dalam hubungan agama-agama, mempunyai asumsi bahwa setiap relasi berarti di dalamnya terdapat komunikasi. Dengan asumsi tersebut maka metode empati yang dimaksud bertujuan membangun pola hubungan dan komunikasi antara agama Islam dan agama Kristen. Selain itu, studi penelitian ini dilatarbelakangi juga oleh aktivitas penulis yang di satu sisi menjadi pendeta Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Pringsewu Lampung, di sisi yang lain juga melakukan aktivitas dialog agama-agama di Kabupaten Tanggamus. titik temu untuk menyepakati menjaga keutuhan bangsa. Dan pihak yang berkonflik saling mengindahkan kepentingan masing-masing. 12 Band. Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jakarta, BPK, 2004, hal. 497. Jan menunjukkan bahwa kegiatan Seminar Agama-Agama telah diselenggarakan Yayasan Wakaf Paramadina sejak tahun 1980-an dan telah berlangsung sekitar 200 kali. Jan juga menunjuk tulisan Djaka Soetapa, “Hubungan Agama-agama di Indonesia dan Peranan PGI di Dalamnya”, sebagai 8 Kedua aktivitas tersebut mendorong studi agama-agama ini untuk dapat semakin memperlengkapi lebih banyak orang agar dapat terlibat dalam dialog antar agama 13 . Satu pertanyaan sederhana namun menjadi sangat penting bagi penulis dari seorang anggota jemaat Gereja adalah bagaimana dialog antar agama dapat dilakukan secara baik? Pertanyaan tersebut paling tidak dapat menjawab pertanyaan penulis yang terpendam sekian lama, yakni mengapa tidak banyak anggota jemaat yang ikut ambil bagian dalam dialog antar umat beragama? Jadi dapat dikatakan kurang berkembangnya dialog antar umat beragama bukan karena masyarakat tidak mau berdialog, tetapi karena terdapat persoalan metodologis yang sederhana namun penting dalam melakukan dialog 14 . C. Obyek Empati: Pemikiran Kartosoewirjo Untuk melengkapi obyektivitas pendekatan empatis dalam studi agama-agama ini, penulis meneliti sejarah Kartosoewirjo. Mengapa harus Kartosoewirjo? Terdapat beberapa alasan, yakni: ikhtisar isi penyelenggaraan Seminar Agama-Agama setiap tahun oleh PGI sejak tahun 1981 hingga tahun 1999. menunjukkan usaha-usaha untuk membangun sebuah kesadaran. 13 Band. Lih. Michael Pye, “Studi Agama dan Dialog Agama: Transendensi dan Unifikasi Agama-Agama Dunia”, dalam Pradana Bay, (ed.), Agama Empiris:Agama Dalam Pergumulan Realitas Sosial, yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal 6. Menurut Pye, pokok yang bisa menjadi presuposisi agama adalah presepsi tentang pluralitas agama. Sekalipun demikian pluralitas bukan persoalan problematik tetapi persoalan ilmiah. “Bagaimana dua agama (dalam konteks dialog Budhisme dan Kristianitas) bisa “samasama benar?” Pada bagian ini, Pye juga menunjuk pada karya Peter Berger, The Pluralistic Situation and The Coming Dialogue Between The World Religions” (1981,31-41), sebuah Kajian Budhis-Kristen. 14 Band. Amin Abdullah, “Dialog Antar-agama”, dalam Kompas, Sabtu, 4 Mei, 2002. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/04/ Menurutnya, "Teologi harus diformat ulang," katanya dalam sebuah seminar terbatas di Yogyakarta, 20 April 2002. Masyarakat sudah berubah sedemikian drastis, sehingga pembaruan teologi adalah keharusan. Bertolak dari sana, kajian ilmu Kalam atau teologi Islam menjadi pokok, ilmu yang masuk rumpun Ushuluddin (dasar-dasar dan sumber agama). Ilmu ini sampai batas-batas tertentu "mendominasi" arah, corak, maupun muatan materi dan metodologi kajian keislaman yang lain. Begitu kokohnya kedudukan ilmu Kalam, sampai-sampai terlupakan sisi metodologi dan sistematika keilmuan. 9 Pertama, pendekatan empatis sebagai cara memahami “yang lain” memerlukan obyek fenomenologis, dalam hal ini fakta historis. Sejarah Kartosoewirjo yang terkenal dengan konsep Darul Islam (Negara Islam) merupakan fakta sejarah yang layak dipertimbangkan secara empatis. Kedua, Kartosoewirjo sebagai sosok beragama Islam yang mengembangkan empati keagamaannya dapat melahirkan konsep-konsep integral antara agama dan negara. Ketiga, terdapat dua model penulisan sejarah Kartosoewirjo, yakni versi orde baru dan orde reformasi. Artinya, versi sejarah yang dibuat pada jaman orde baru menempatkan Kartosoewirjo sebagai pemberontak 15 . Versi orde reformasi yang lebih terbuka dan ditulis oleh pemikir Islam sendiri, yakni Al Chaidar, menempatkan Kartosoewirjo sebagai bapak proklamator Negara Islam Indonesia 16 . Keempat, belum ada terdapat sebuah studi mengenai gerakan keagamaan yang menjadi gerakan politik Islam, khususnya dari agama Kristen. Kalaupun ada sangat bersifat umum, dalam arti hanya disentuh kulitnya saja. Ia pernah menyatakan juga dalam pidato pengukuhan guru besarnya, bahwa diperlukan satu rekonstruksi metodologi studi agama dalam masyarakat multikultural dan multireligius. Dalam studi ilmu Kalam dimanfaatkan filsafat sebagai metodologi, dan bukan sebagai buah pikir atau isme-isme. 15 Prof. Dr. H. Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (jilid 3: O – Z), Jakarta, Djambatan, 2002, hal. 579 16 Lih. Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, Jakarta, Darul Falah, 1999 10 Dari keempat alasan tersebut, penulis hendak menempatkan diri sebagai pribadi yang mendekati sejarah Kartosoewirjo dengan metode empati. Penulis di sini akan lebih banyak memerankan diri sebagai pelaku dengan metode empati. Sebagai pribadi yang mempunyai latar belakang pembentuk individu yang sama sekali berbeda dengan latar belakang baik dari sisi waktu, konteks dan agama. Posisi penulis yang beragama Kristen melakukan pendekatan terhadap fenomena perjuangan Darul Islam Kartosoewirjo merupakan tantangan tersendiri. Namun dilandasi dengan keyakinan bahwa pendekatan empatis dapat membantu penulis memahami latar belakang sebuah perjuangan yang didasari keyakinan agama, maka studi ini menjadi demikian penting. Pentingnya studi ini bagi pengembangan metodologi studi agamaagama di Indonesia, pertama, dikarenakan penulis harus berusaha melepaskan stereotipe negatif tentang agama Islam. Ini berarti suatu langkah pasca dogmatis harus diambil, untuk memasuki studi mengenai agama lain. Kedua, Kartosoewirjo dalam karya sejarah nasional Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan termasuk bagi sebagian besar umat Islam. Dalam kebanyakan buku sejarah, Kartosoewirjo yang dicitrakan sebagai pemberontak dapat dipakai untuk membangun stereotipe negatif terhadap Islam. Stereotipe negatif tentang Islam dapat menghambat upaya membuka suatu ruang kesadaran empatis untuk membangun kembali suatu pola dialog yang sehat dan terbuka. Melalui studi empatis ini, penulis tidak berpretensi untuk membela posisi Kartosoewirjo, melainkan penulis bermaksud menggali keberagamaan Kartosoewirjo yang dapat melahirkan konsep bernegara. Selain itu penulis mencari kemungkinan penyebab dan 11 pendorong agama dapat menuju kepada sebuah negara serta adakah motif-motif yang mendorong pemikiran keagamaan (Islam) menjadi cerdas untuk mengembangkan dirinya menjadi kekuatan sebuah negara, yakni Darul Islam. 1. Permasalahan Munawir Sadzali 17 dalam dunia Islam terdapat tiga pandangan mengenai hubungan Agama dan Negara. Pandangan pertama ini menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh termasuk kehidupan bernegara atau sistem politik. 18 Pandangan kedua berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad tidak pernah diutus untuk mendirikan dan mengepalai negara. Dengan asumsi ini Islam tidak punya urusan dengan soal pemerintahan atau politik atau Islam mempunyai tugas berdakwah sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Pandangan ketiga sebagai hasil sintesa dari kedua pandangan di atas bahwa secara normatif, Islam (al-Quran dan as-Sunnah) tidak memberikan ketentuan bagaimana negara dibentuk, tetapi menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas atau sebaliknya. Yang penting dalam Islam adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju baldah tayyibah wa rabb ghafur 19 . 17 H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1990, hal. 1-2 18 Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol.4, No.2, Surakarta, UMS, 2002, hal. 204. Pandangan ini diwakili oleh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha, Abul A’la alMaududi. Pandangan kedua diwakili oleh Ali Abdur Raziq dan Thaba Husain. 19 Lih. Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, Jakarta, Tiara Wacana, 2001, h.12 Negara sejahtera dan diridhoi Tuhan’. Band. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya, Jakarta, Toha, 1989, as-Saba (34) ayat 15: … (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha pengampun). 12 Yang menjadi persoalan mengenai agama dan negara bagi penulis bukan yang pandangan yang kedua atau pandangan yang ketiga, tetapi pandangan yang pertama. Oleh karena itu yang menjadi masalah penting bagi penulis adalah mengapa dan bagaimana pemikiran Islam (tertentu) memperjuangkan Negara Islam di Indonesia. Penelitian secara empiris akan ditujukan kepada pemikiran Kartosoewirjo. 2. Hipotesis Teori empatis dapat membantu memecahkan persoalan sejarah keagamaan yang menempatkan seorang individu dalam stereotipe negatif. Asumsi di belakang hipotesis ini suatu peristiwa sejarah dapat mempengaruhi suatu ajaran agama tertentu untuk menjadi diskontinyu terhadap nilai yang dipegangnya semula. 3. Metodologi Penulisan Tesis Teori yang digunakan sebagai metode di sini adalah teori empati menurut Pemikiran Edit Stein. Tentu saja dalam menggunakan teori empati ini penulis juga perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan kritis, karena kasus psikologis yang dihadapi Edit Stein juga berbeda baik ruang dan waktu maupun metode penjelasannya. Teori empatis merupakan teori yang berlatar belakang teori fenomenologi untuk menganalisis pemikiran mengenai fenomena keberagamaan subyek lain dari diri peneliti 13 sendiri. Pemilihan kepada teori ini dikarenakan obyek penelitiannya sudah jelas pemikiran seorang tokoh dengan bahan-bahan yang cukup memadai, sehingga pendekatan dengan teori empatis ini akan dapat menemukan esensi pemikiran Kartosoewirjo dari dirinya sendiri, bukan sekedar dari rekonstruksi historis. Selanjutnya, pendekatan empatis akan membantu penulis untuk memahami lebih jauh metodologi dan juga untuk menjawab tantangan historis yang telah menempatkan Kartosoewirjo dalam stereotipe negatif. Teori empatis juga bukan sekedar teori psikologi yang dapat digunakan dalam mengamati proses fenomena perilaku beragama, pendekatan empatis ini akan dapat menjawab tawaran-tawaran para teolog agama mengkomunikasikan antara yang eksklusifis dengan yang inklusifis 20 . Bahwa teori empatis menempatkan peran individual yang saling 20 _____________, “Kemitraan Lintas Agama Perlu Inklusif Total”, dalam Kedaulatan Rakyat, Rabu, 29 Juni 2005. Din Syamsuddin mewakili Indonesia dalam Konferensi Kerjasama Agama untuk Perdamaian di Markas PBB New York. Konferensi tersebut dilaksanakan dengan latar belakang, Deklarasi Milenium PBB yang menintik beratkan pentingnya membagi nilai dan prinsip seperti persamaan hak dalam kebebasan, solidaritas dan toleransi sebagai hal penting dalam hubungan Internasional abad 21. Din menyatakan, bahwa dialog, kerjasama dan kemitraan lintas agama perlu bersifat inklusif total, jangan ada kelompok yang ditinggal. Oleh karena itu menurutnya, perlu ada common platform dari perdamaian seperti apa yang disebut toleransi, kesepakatan, saling menghargai dan kerja sama dalam bentuk konkrit. Namun yang dapat menjadi tantangan komunikasi tersebut diantaranya faham supersessionisme, yakni suatu faham dan keyakinan doktrinal-teologis bahwa agama yang datang belakangan berfungsi mengabrogasi atau menggeser agama sebelumnya. Lih. Komaruddin Hidayat, “Dari Inklusivisme ke Pluralisme”, dalam Kompas, Selasa, 8 April 1997. Eksklusifisme teologis umat Kristiani terhadap agama Yahudi yang bersimbiose dengan eksklusifisme faham Arianisme di Jerman pada akhirnya telah memicu timbulnya konflik antar mereka dan puncaknya adalah keterlibatan sentimen teologis umat Kristiani Jerman sehingga sebagian dari mereka ikut mendukung holocoust dalam Perang Dunia ke-2 yang menelan korban ribuan umat Yahudi. Tentu saja Nazi bisa mengajukan alasan lain, misalnya dominasi politik-ekonomi oleh bangsa Yahudi, namun sulit dielakkan bahwa semangat supersessionisme ikut terlibat di dalamnya (Arthur E. Zannoni, Jews & Christians Speak of Jesus, 1994). Dan ketika Muhammad pada gilirannya mendakwahkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang mengoreksi, menyempurnakan dan mengakhiri semua risalah Illahi yang pernah muncul sebelumnya, maka Islam sekaligus memperoleh dua tantangan, dari Yahudi dan Kristen. Lagi-lagi semangat supersessionisme yang eksklusifistik telah memperpanjang konflik berdarah antar umat beragama yang memuncak pada Perang Salib. 14 mempengaruhi dengan individu yang lain, maka kesadaran murni individual akan kehadiran yang lain dapat mengantarkan bangsa ini pada kesadaran komunal yang murni. Apakah yang dimaksud dengan kemurnian dalam pola hubungan antar agama? Apakah bila agama mendasarkan diri pada wahyunya (kitab sucinya) masing-masing, atau ketika menyadari diri individunya perlu bersikap secara empatis terhadap konteks kehidupan bersama dengan yang lain? Lingkup studi agama-agama memang demikian luas, namun melalui pendekatan empatis ini penulis akan dapat menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas. Dalam mencari jawaban terhadap persoalan tersebut, penulis membatasi diri pada kasus pemikiran Kartosoewirjo, beberapa persoalan berkaitan dengan tempat empati dalam dialog diharapkan dapat memberi sumbangan dalam menjawab persoalan hubungan antar agama. D. Penjelasan Judul Tesis Judul Tesis ini adalah Pendekatan Empatik dalam Studi Agama-Agama terhadap Pemikiran Kartosoewirjo mengenai Agama dan Negara. Pendekatan empatis dengan latar belakang fenomenologis akan meneliti esensi beragama yang menciptakan sistem beragama dalam diri Kartosoewirjo. Studi agama-agama lebih menekankan titik berangkat penelitian dari sudut pandang agama-agama dibandingkan empatis yang sering 15 diasosiasikan dengan psikologis semata. Pemikiran Kartosoewirjo sebagai obyek penelitian empatis untuk membedakan dengan pemikiran yang dibentuk oleh sejarah 21 . E. Sistimatika Penulisan Bab I. Pendahuluan Pada bab pertama, penulis menyampaikan latarbelakang permasalahan di sekitar penulisan tesis, sekaligus maksud tujuan dan metodologi pemecahan permasalahan mengenai sistem pemikiran keagamaan sampai kepada ekspresi pemikiran dalam tanggungjawab politik umat beragama. Bab II. Pendekatan Empatis Pada bagian ini penulis bermaksud menjelaskan bagaimana pendekatan empatis dapat dipakai dalam membahas fenomena pemikiran keagamaan dikembangkan dalam format politik kenegaraan. 21 Pendekatan empatis ini menurut penulis sudah saatnya Penulisan-penulisan mengenai Kartosoewirjo yang telah dilakukan sebagai berikut: pertama, Nieuwenhuijze (1958) yang hingga akhir tahun 1949, bekerja sebagai penasehat Gubernur Jenderal Belanda untuk urusan Islam di Jakarta. Dia menulis sebuah artikel tentang gerakan Darul Islam dimana dia mengemukanan sebagai alasan pembentukan gerakan itu adalah masalah-masalah ekonomi dan ideologi. Kedua, Jackson (1971) menulis disertasi anthropologi sosial untuk membuktikan hipotesanya tentang akar pengaruh kebudayaan Indonesia “bapakisme” (kesetiaan tanpa kritik) terhadap dukungan rakyat terhadap pemimpin yang mereka akui. Ketiga, Cees van Dijk (1983) menulis tentang Darul Islam di Jawa Barat tetapi juga tentang yang ada di Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. Penulisan lain mengenai Kartosoewirjo dalam bentuk buku dilakukan juga telah dibuat oleh Pinardi (1960), Amak Sjarifuddin (1962), selebihnya sebagai artikel-artikel ditulis oleh Hiroko Horikoshi (1975), Soebardi (1983), Federspiel (1985) telah menyebutkan bahwa gerakan Darul Islam sebagai kesatuan Militer Masjumi pada awal perang kemerdekaan. 16 dipertimbangkan untuk mencari makna toleransi, kesepakatan, saling menghargai dan kerjasama dalam bentuk konkrit 22 . Pendekatan empatis ini merupakan alat teknis untuk dapat melihat dan menghasilkan penjelasan bekerjanya suatu sistem politik keagamaan dalam pemikiran seorang Kartosoewirjo yang menghubungkan konsep agama menjadi sebuah konsep negara dengan seluruh perlengkapan peraturannya. Oleh karena itu, mengingat agama sebagai sebuah kesatuan sistem kepercayaan individu kepada yang ilahi, maka kesatuan sistem pemahaman individu tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan empatis. Teori empatis yang akan digunakan yang sebagian besar merujuk pada teori empatis Edith Stein 23 , namun demikian penulis tidak melupakan teori fenomenologis sebagai dasar dari teori empatis ini. Tiga langkah pendekatan empatis yang dihasilkan dari penelitian adalah merasakan, menyadari dan mengkonfirmasikan persepsi. Bab III. Kartosoewirjo dalam Pandangan Seorang Muslim Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana seorang sejarawan muslim, yakni Al Chaidar menempatkan Kartosoewirjo sebagai tokoh proklamator Negara Islam Indonesia. Pada bagian ini pula, Kartosoewirjo di mata seorang pejuang Neo Darul Islam 22 Lih. _____________, Kemitraan Lintas Agama Perlu Inklusif Total, dalam Kedaulatan Rakyat, Rabu, 29 Juni 2005. 23 Edith Stein, On The Problem of Empaty, (transl.), Netherlands, The Hague, 1964. Sampai sekarang penulis tidak menemukan topik khusus yang baru tentang empati. Kalaupun ada merupakan tulisan-tulisan praktis mengenai empati bukan sebagai sistem psikologis, tetapi empati yang dipraktekkan, misalnya, C.A.J. Ten Boom, Empati, Yogyakarta, PPY, 1990. Dalam karya tersebut tidak disebutkan juga sumber teorinya, dan masih merupakan bagian yang dibahas oleh Edith Stein. 17 merupakan seorang tokoh yang perlu diteladani dalam hal ke-Islaman dan kesederhanaannya serta sebagai pemulih harapan bagi terbentuknya kekhalifahan Islam dunia pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Prinsip-prinsip ideologis “ad-din wa dawlah” perjuangan Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo dalam sejarah total yang masih menggema sampai sekarang akan tetap menjadi alternatif yang dapat menghidupkan perasaan dan perjuangan umat Islam jika Pancasila gagal menjalankan fungsi perlindungan bagi semua rakyat di negara Indonesia. Melalui bab III ini langkah pertama dari tiga langkah pendekatan empatis sudah dimulai dengan sejarah yang dapat menghidupkan perasaan keagamaan yakni untuk menyadari bahwa keprihatinan Kartosoewirjo sebagai keprihatinan teologis dalam sejarah antikolonialisme Islam. Pada bab ini proses epoch dalam teori fenomenologis telah dimulai dengan meletakkan bagian secara tersendiri dalam rangka menemukan inti pemikiran Kartosoewirjo. Bab IV. Sejarah Kartosoewirjo dari Sudut Pandang Kekuasaan Dari sudut pandang kekuasaan dengan dan atas nama Pancasila, berbagai penulisan sejarah telah menempatkan Kartosoewirjo sebagai pemberontak dengan gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesianya. Hal ini menunjukkan bahwa melalui rekonstruksi sejarah yang terkesan obyektif melalui kronologi peristiwa sejarah linear telah menempatkan Kartosoewirjo sebagai obyek penderita atau tokoh antagonis yang menjengkelkan, yang tidak pernah bisa membela dirinya sendiri.. 18 Holk Harold Dengel adalah salah seorang yang menulis sejarah linear dengan data-data yang menurutnya lengkap, karena berasal dari sumber-sumber primer yang dilengkapi dokumen pemeriksaan Kartosoewirjo dari dokumen-dokumen TNI. Dengel berusaha menetralisir sudut pandangnya dalam rangka merekonstruksi sejarah Kartosoewirjo, namun demikian masih nampak peran “kekuasaan” sangat mempengaruhinya. Rekonstruksi fakta dan kronologi peristiwa-peristiwa sejarah menarik dari Dengel akhirnya dapat membantu penulis menyadari posisi Kartosoewirjo dalam konteks kronologis pada waktu itu. Kesadaran ini merupakan langkah kedua dari pendekatan empatis dengan memahami betapa kompleksnya peristiwa di sekitar pemikiran Kartosoewirjo, oleh karena itu pada bab ini penulis dapat mulai menyusun suatu persepsi pemikiran mengenai konteks yang menekan Kartosoewirjo. Bab V. Pemikiran Kartosoewirjo “Ad-Din wa Dawlah” Pemikiran Kartosoewirjo dalam bab ini berbeda dengan dan bukan sekedar kata sejarawan mengenai Kartosoewirjo, tetapi sebagai langkah ketiga, pada bagian ini penulis mengkonfirmasikan persepsi-persepsi yang diperoleh dari perasaan dan pemikiran dengan mempertimbangkan konteks yang telah dideskripsikan oleh sejarah. Melalui dokumen-dokumen yang dibuat oleh Kartosoewirjo serta dikumpulkan Al Chaidar penulis dapat mengkonfirmasikan secara obyektif salah satu sisi pemikiran Kartosoewirjo mengenai agama dan negara. Pada bagian ini pula konsep “hijrah” Kartosoewirjo 19 menjadi dasar mengenai “ad-din wa dawlah” atau kesatuan antara Agama dan Negara yang dilandasi ajaran agama Islam tidak hanya dapat dipahami, tetapi hidup sebagai roh perjuangan anti penderitaan rakyat dan berperang melawan penindas rakyat. Bab VI: Kesimpulan Pendekatan empatis sebagai usaha subyek untuk dapat mengenali individu “yang lain”, khususnya yang mendapat stigma negatif sejarah atau semacam “kesesatan” agama mengasumsikan adanya keterputusan subyek dalam mengenali obyeknya. Pendekatan empatis sejak semula mengasumsikan manusia sebagai arus proses pengalaman menjadi di mulai dari merasakan, menyadari dan mengkonfirmasikan persepsinya secara terus menerus dalam sebuah “ruang”. “Ruang” setiap subyek itu memiliki keterbatasan dalam mengalami, mengenali, menyadari dan mempersepsi obyek. Obyek Kartosoewirjo dan obyek sejarah baik sejarah total maupun sejarah konvensional linear adalah proses menemukan kebenaran, baik melalui ideologi politik maupun melalui ajaran agama. Ajaran agama pada umumnya berkaitan dengan kepercayaan individu yang mengatur perilaku individu agar dapat hidup secara benar. Ideologi politik pada umumnya berkaitan dengan proses mengatur negara dengan semua latar belakang dan sistem pemerintahannya. Oleh karena persoalan agama dan negara sebenarnya mengenai masalah “ruang” privat dan “ruang” public, maka pendekatan empatis ini hendak memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk dapat saling berdialog, membentuk hegemoni 20 wacana kebenaran ketimbang menutup ruang-ruang dialog dan mendominasi kekuasaan dengan membungkam yang lain atau mengkambinghitamkan yang lain. Studi Agama-Agama sebagai titik tolak penelitian ini berupaya memahami pemikiran Kartosoewirjo yang mewakili cara berpikir keagamaan yang kemudian secara ideologis berbenturan dengan ideologi Pancasila. Namun yang patut disayangkan dalam sejarah internal bangsa pasca kolonialisme, yaitu ketika pola perbenturannya sudah bukan lagi membicarakan ide negara melalui proses demokratis, tetapi ketika proses menjadi itu harus diakhiri dengan kekerasan yaitu dengan perang. Belum selesai dengan penumpasan dan perang, pembunuhan karakter Kartosoewirjo juga secara sempurna dilakukan dengan penyusunan sejarah yang bersifat stigmatitatif. Dengan demikian pendekatan empatis terhadap fenomena Kartosoewirjo dengan pandangannya tentang “ad-din wa daulah” dapat menunjukkan suatu nilai penting dalam era post kolonial seperti pada masa sekarang ini. Karena di bawah dominasi ideologi Pancasila fenomena kekerasan terhadap rakyat bukan barang “haram”, sebaliknya dalam potensi hegemonik ideologi alternatif seperti Islam, penghormatan terhadap keberbedaan, baik beda pendapat, beda budaya dan beda agama merupakan suatu kewajiban. 24 24 Lih. Jaka Soetapa, “Hubungan Agama-Agama dan Peran PGI di Dalamnya”, dalam 50 Tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta, PGI, 2000, hal. 200. Dalam beberapa kali Seminar Agama-agama, Pancasila dipahami sebagai penjamin demokrasi dan kesetaraan setiap anak bangsa. Agama-agama tidak memiliki sisi keberatan dalam hal ini, justru mendukungnya. Melalui Pancasila ada penjamin negara dan bangsa dalam kesejajaran. Ini pulalah yang nampaknya begitu diagungkan sehingga tanpa sadar ada agenda lain yang terlupa. Agama-agama menjadi tidak lagi kritis terhadap konsep-konsep yang dikembangkan selanjutnya. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan jaminan kekuasan bagi cita-cita negara, maka agama sebagai lembaga kemudian dianggap berada di bawah perlindungan Pancasila. Disinilah letak kelemahan agama-agama. Dengan demikian mereka tidak lagi independen, yang dapat secara bebas memberikan pertimbangan, penilaian, masukan berdasarkan penghayatan masing-masing. Disatu sisi gereja merasa mendapatkan perlindungan karena jaminan kebebasan di bawah 21 Oleh karena itulah pendekatan empatis ditawarkan agar dapat menjadi pendekatan alternatif untuk sampai kepada pemahaman bagi perlunya proses melihat obyek secara bersama-sama. Melalui pendekatan empatis ini sesuatu yang relatif menjadi obyek bagi suatu proses dialog. Demikian juga bagi tercapainya suatu proses dialog agama-agama perlu suatu kesadaran mendasar, bahwa agama adalah persoalan yang sangat individual, oleh karenanya pendekatan empatis adalah untuk menempatkan individu dari titik tolaj individu. Melalui pendekatan empatis ini, khususnya bagi yang telah mendapat stigma negatif dari “ideologi dominan yang berkuasa” dapat menjelaskan dari dirinya sendiri yang disaksikan sejarah bahwa di dalamnya terdapat suatu nilai yang berharga, yang tidak pernah dilihat pada sejarah masa lalu. i H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1990 i Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol.4, No.2, Surakarta, UMS, 2002
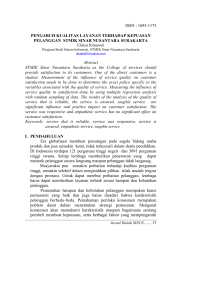
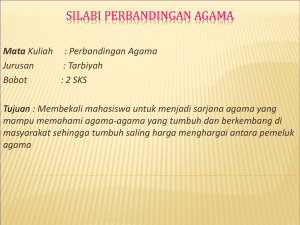
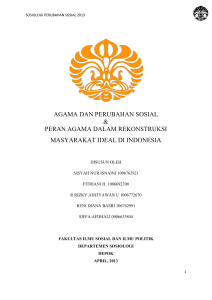
![INTERKSI DAN KOMUNIKASI [Compatibility Mode]](http://s1.studylibid.com/store/data/000708973_1-0cca17b7d1fe970f8fb4f11293ddb4ef-300x300.png)
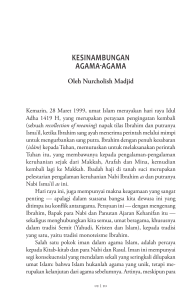
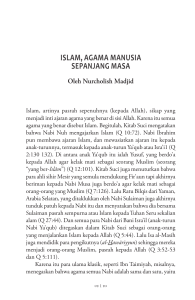


![Modul Pancasila [TM9]. - Universitas Mercu Buana](http://s1.studylibid.com/store/data/000491905_1-01c9b072436801cd796d72b5d21cfbc2-300x300.png)