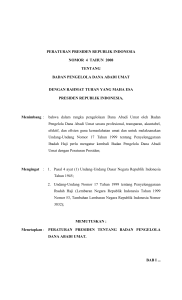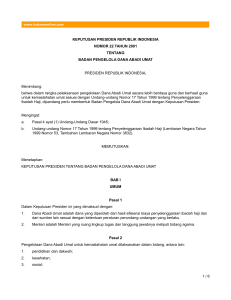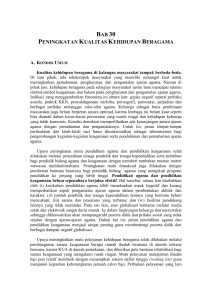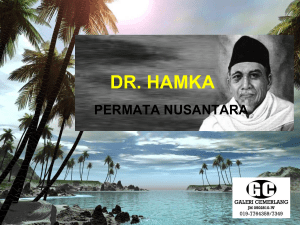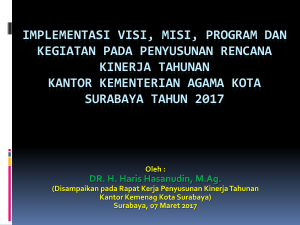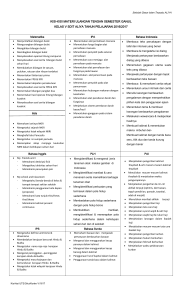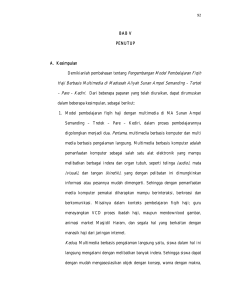haji sebagai ibadah korban - Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara
advertisement

HAJI SEBAGAI IBADAH KORBAN Oleh : Yamin Latief Tjokra, S.HI, M.Pd. (Wakil Ketua PW. GP Ansor Prov. Maluku Utara) (Staf Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara) Sejak ibadah haji dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim (Abraham) sekitar 3600 tahun lalu, jumlah penziarah ke Baitullah di Mekah dari tahun ke tahunnya terus bertambah. Penambahan ini terus meningkat pada masa umat Nabi Muhamad, seiring dengan semakin menyebar dan meluasnya dakwah dan kekuasaan Islam. Sebagaimana kita ketahui tradisi ritual haji ini tetap dipelihara dan dilanjutkan pada masa kenabian Muhammad. Pada saat ini, dimana hampir tidak ada satu wilayahpun di ”kolong langit” ini yang tidak tersentuh dakwah Islam, maka jumlah jemaah yang hadir ke tanah suci tersebut tiap tahunnya telah mencapai jutaan orang. Dan khusus dengan jemaah haji asal Indonesia, maka ia merupakan jemaah yang terbesar dibandingkan jemaah-jemaah dari negara Islam lainnya. Haji di negeri ini merupakan ibadah yang memiliki tempat khusus di hati dan pandangan masyarakatnya, baik secara personal maupun sosial. Secara personal banyak sekali masyarakat Indonesia yang merindukan untuk dapat hadir di rumah Allah tersebut agar dapat beribadah secara khusyuk dan mendapat ”ganjaran” yang besar. Terbayang di lubuk hati mereka, betapa mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat aura yang dipancarkan oleh kota suci tersebut pada bulan haji. Mereka seakan-akan dapat berhadapan langsung dengan Sang Maha Hadir untuk menyampaikan keinginan mereka dan sekaligus memohon ampunan kepada-Nya. Kerinduan ini tentunya bukan hanya milik mereka yang berkelebihan secara ekonomi, tetapi juga mereka yang kesehariannya hidup dalam kesederhanaan. Sering kita dengar orang-orang yang keserahiannya hidup dalam kesederhanaan, tetapi mampu berangkat haji dengan cara berjerih-payah menyisihkan sebagian hartanya selama bertahun-tahun. Dari sisi sosial, ada penghargaan yang lebih, yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang telah berhaji. Hal ini dapat dilihat dari gelar Haji yang diberikan kepada mereka. Dalam interaksi sosial, masyarakat juga akan lebih menghargai dan menghormati para Haji ini. Bagi masyarakat, seorang haji adalah pribadi yang telah memiliki kadar keislaman dan keimanan yang lebih tinggi; pengetahuan agama yang luas; dan kemempuan ekonomi yang lebih. Wajar, jika kemudian para Haji ini memiliki status sosial yang tinggi di lingkungan masyarakatnya. Mereka biasanya dikategorikan sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat. Lebih lanjut, haji juga akan memberikan dampak kepada kehidupan ekonomi dan politik seseorang. Dalam kehidupan ekonomi, seorang haji akan lebih mudah melakukan interaksi bisnis dengan masyarakat, karena dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan dermawan. Sedangkan dalam kehidupan politik, tidak jarang haji digunakan oleh pejabat atau elit politik sebagai simbol untuk dapat memperoleh dukungan politis, terutama menjelang momen-momen tertentu, seperti menjelang pilkada dan pemilu. Hal ini dimungkinkan karena haji merupakan simbol yang dapat membangkitkan afinitas sosial dan religi sebagian kelompok masyarakat. Sebenarnya, penghormatan masyarakat yang tinggi terhadap para Haji ini bukan tanpa alasan. Mereka berharap bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada para Haji tersebut akan memberi dampak pada 1 kehidupan sosial mereka. Mereka berharap, para Haji setelah pulang dari Mekah bukan hanya memiliki kesalehan personal tetapi juga kesalehan sosial. Ironi Ibadah Haji Namun ironisnya, sebagaimana disinyalir oleh Djohan Effendi (2004) dalam bukunya Menemukan Makna Hidup, masih banyak kasus di banyak tempat, ada orang yang berkali-kali pergi haji, namun tetangganya yang sakit dan tak punya biaya saja ia tutup mata. Pun juga dalam kehidupan sehari-hari masih kita lihat seorang pejabat publik yang diberi amanat untuk memberdayakan, menyahterakan dan melindungi rakyatnya, setelah melakukan haji, ternyata tetap saja melakukan tindakan yang membodohi, menyengsarakan dan menjalimi rakyat. Ia masih saja tetap melakukan korupsi, mark up proyek, penggusuran dan berselingkuh dengan pemilik modal demi kepentingan pribadi. Yang lebih tragis lagi terkadang mereka ini berangkat haji dengan menggunakan ”uang rakyat” dengan dalih sebagai pemimpin atau pemandu jemaah. Lantas apa maknanya berhaji, terlebih bagi mereka yang telah berkali-kali, kalau hajinya tidak memiliki implikasi sosial. Sejatinya ritual haji harus berdampak kepada kehidupan sosial seseorang, karena hampir semua praktik ibadah tersebut mengandung penekanan untuk menjaga kemaslahatan dan kemanusiaan. Sebut saja praktek Ihram, yaitu niat melakukan haji di Miqat Makany dengan menanggalkan pakaian keseharian dan mengenakan pakaian yang serba putih tanpa berjahit. Ini merupakan simbol dari pengakuan Islam terhadap kesederajatan (egalitarian) umat manusia. Di sini para jemaah diajarkan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah, tidak ada perbedaan manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali takwanya. Sebagaimana kita ketahui pakaian pada realitasnya berfungsi sebagai pembeda antara seseorang dan sekelompok lainnya, yang dapat mengantar pada perbedaan status sosial, ekonomi atau profesi. Pada saat haji, masing-masing identitas pribadi dan kelompok yang telah menjadikan manusia terkotak-kotak berdasarkan letak geografis, etnis, warna kulit, status sosial dan lain-lainnya, dilebur dan diganti dengan identitas baru yang bersifat universal, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang pada saatnya akan kembali kepada-Nya dengan meninggalkan segala yang dimilikinya. Kemudian praktek Thawaf, sebuah gerakan mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali, menggambarkan ketundukan jagad dan seisinya kepada hukum Allah (sunnatullah), baik berkenaan dengan hukum alam maupun kemasyrakatan. Selain itu, thawaf juga mencerminkan larut dan berbaurnya umat manusia dalam upaya mencapai satu tujuan yang sama, yakni berada dalam lingkungan-Nya. Sa’i, berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah merupakan simbol dari usaha anak manusia yang tidak kenal putus asa dari rahmat Allah. Wukuf di ’Arafah, yaitu berhenti atau berdiam diri sampai terbenamnya matahari di ’Arafah, sebuah padang luas dan gersang. Disini, di tempat dimana Adam dan Hawa dipertemukan kembali di Jabal Rahmah (bukit ’Arafah) merupakan simbol kasih sayang dan usaha manusia menemukan jati dirinya yang sejati. Dan yang terakhir Jumrah, melempar kerikil di Mina, merupakan simbol dari kebencian manusia terhadap Syaitan dan usaha memeranginya, yang selama ini selalu mengajak dan melakukan tipu daya terhadap manusia agar ia terjerembab jatuh dalam kehinaan dan kejaliman. Haji dan Korban Hal lain lagi yang perlu diperhatikan lagi adalah, bahwa ibadah haji yang bersumber dari tradisi keagamaan Nabi Ibrahim, sangat terkait dengan ibadah korban. Karenanya Hari Raya Haji (’Idul ’Adlha) dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Korban (’Idul Qurban). 2 Dalam ritual korban yang menjadi esensi bukanlah materi korban itu, melainkan sikap takwa dari pelakunya. Allah Yang Maha Kaya dan Maha Terpuji sama sekali tidak membutuhkan korban dalam artian sesajen atau sakramen. Yang Ia pandang adalah keikhlasan dan kerelaan seseorang dalam upayanya mendekatkan diri (taqarrub) kepada-Nya. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj/22 ayat 37 yang berbunyi :”Tidaklah bakal sampai kepada Allah daging korban itu, dan tidak pula darahnya! Tetapi yang bakal sampai kepada-Nya ialah takwa dari kamu”. Ketakwaan sebagai indikator diterimanya korban tidak hanya terkait dengan aspek personal tetapi juga sosial. Aspek personal terkait dengan keimanan kepada Allah dalam kegaiban. Meskipun kita tidak dapat melihat secara kasat mata, namun kita selalu menyadari kehadirannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Sedangkan aspek sosial terkait dengan tingkah laku yang baik dan terpuji (akhlaqul karimah) seseorang. Aspek sosial ini merupakan implikasi dari kesadaran atau keimanan kepada Allah, zat Yang Maha Hadir. Seseorang yang sadar akan hal tersebut akan selalu berhati-hati dan mempertimbangkan segala tingkah lakunya. Ia sadar tak sekejappun ia akan lepas dari pengawasan Allah. Selain itu, iapun meyakini bahwa setiap perilakunya akan memperoleh konsekwensi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, setiap korban dalam artian usaha mendekatkan diri kepada Allah akan senatiasa terhambat atau bahkan mungkin menjauhkan seseorang dari-Nya tanpa dilandasi keimanan dan diiringi dengan perbuatan baik kepada sesama manusia. Dalam ayat lain Allah menegaskan :”Bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami, tetapi hanyalah orang yang beriman dan berbuat kebaikan; mereka itulah yang mendapat pahala berlipat ganda atas segala yang mereka kerjakan ...” (Q.S. 34 : 37). Dalam kaitannya dengan ibadah haji, maka tanpa dilandasi dua hal tersebut di atas, ia akan menjadi ibadah yang sia-sia, yang tidak mendapat apa-apa orang yang berhaji kecuali kelelahan dan berkurangnya kekayaan. Dan keinginannya untuk berjumpa dengan Allah di kediamannya, Baitullah di Mekah akan ditolak. ”Barangsiapa ingin berjumpa dengan Tuhannya hendaklah ia berbuat baik dan janganlah dalam berbakti kepada Tuhannya itu ia mempersekutukan-Nya dengan seseorang siapapun juga (Q.S. 18 : 110), demikian penjelasan Allah. Dengan demikian jelaslah, bahwa ibadah haji bukan hanya menuntut pelakunya untuk berkorban demi kepentingan personal yang bersifat spiritual, yaitu membelanjakan sebagian harta kekayaannya untuk berangkat haji ke Mekah dan secara bersungguh-sungguh menunaikan segala rukunnya disana agar memperoleh kedekatan dan merasakan kebersamaan kehadiratnya (communion with God). Tetapi yang juga penting dan utama adalah berkorban untuk mengekang hawa nafsu individualnya sendiri, demi mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbuat baik terhadap sesama, terutama membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteksnya yang lebih luas dan mendalam, kiranya menarik memperhatikan usulan Djohan Effendi kepada mereka yang pernah berangat haji, agar bersedia berkorban diri untuk tidak pergi haji berkalikali, sehingga uang ongkos naik haji dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Bagi beliau, berulang-ulang pergi haji tidak akan memiliki makna yang signifikan bagi pelakunya, jika hajinya tersebut tidak berimplikasi dalam kehidupan sosial. Bahkan beliau mengingatkan mereka yang telah berulang-ulang pergi haji, tetapi makna dan kualitas haji tidak bersambungan dengan kualitas hidup keseharian sebagai sebuah pertanda hajinya belum diterima Allah. Wallahu a’lam. 3 ***** Penulis adalah alumni Pondok Peasantren An-Najah Bekasi Cabang dari Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Tahun 2005 menyelesaikan S1 jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah di STAIN Ternate, dan pada tahun 2006 penulis diangkat menjadi PNS. Pada tahun 2009 penulis mendapatkan Beasiswa dan melanjutkan Studi S2 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP). Sewaktu kuliah S1 pernah aktif di Organisasi PMII dan sekarang sebagai Wakil Ketua PW. GP Ansor Provinsi Maluku Utara. 4