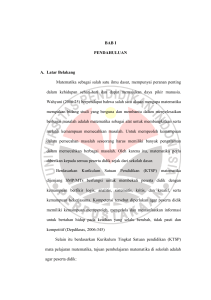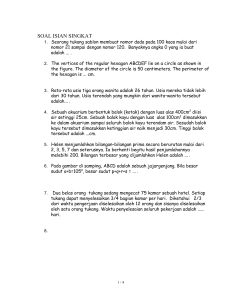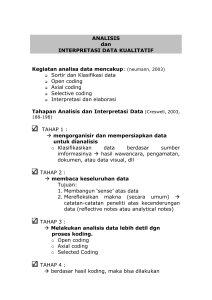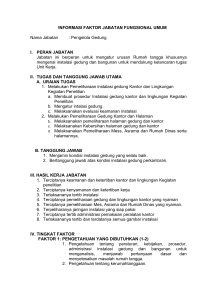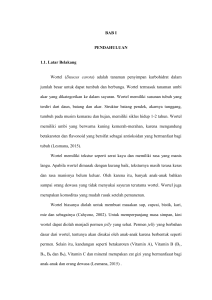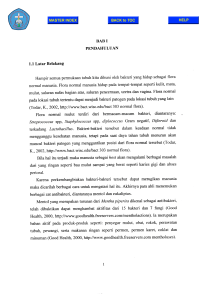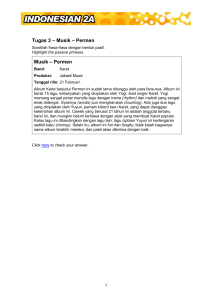politik identitas anak-anak dalam iklan anak-anak
advertisement

POLITIK IDENTITAS ANAK -ANAK DALAM IKLAN ANAK-ANAK Titik Puji Rahayu Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unair, Surabaya Abstract This article tells that glamour of advertisement as media for the socialization and internalization of social values at children has become imaginary institution of education of modern children, even has followed reschedule and dictate the time for studying, playing, and sleeping. Keywords: glamour of advertisement, imaginary institution M elalui sebuah pernyataan “you are the screen and the television is watching you”, (Ibrahim,1997:247), Baudrillard menggambarkan sebuah fenomena di mana televisi saat ini menjadi bagian penting dari rutinitas kehidupan manusia. Televisi dengan arogansinya telah menjadwal ritual dan rutinitas kehidupan manusia melalui jadwal berbagai program acara yang disajikan. Baudrillard sekaligus menyampaikan sebuah personifikasi, bahwa televisilah yang sedang menonton berbagai polah tingkah manusia sebagai “anak kebudayaan massa”. Manusia berlomba-lomba menjadi “manusia yang seharusnya” dengan tolakukur image media massa. Dengan dibungkus kosmetik dan style manusia berusaha menyampaikan sesuatu tentang dirinya, Siapa saya?, Saya berbeda!, Tergabung dalam kelompok mana saya?, dan lain sebagainya. Jika realitas simbolik yang ditampilkan televisi telah diterima individu sebagai realitas sosial, dan ketika realitas sosial bercermin pada realitas yang ditampilkan televisi, maka televisi itulah dunia dan manusia hidup di dalamnya. Maka tidaklah mengherankan kal au Esslin menyebut abad ke -20 sebagai Abad Televisi di mana sebagai agen budaya, televisi dengan fungsi informasinya menyebarluaskan berbagai informasi dan pengetahuan di tingkat lokal maupun global, sehingga dapat menjadi sarana memperlancar proses transf ormasi budaya (cultural agent). Di sisi lain ketika televisi telah menjadi dunia bagi pemirsanya di mana menonton televisi menjadi suatu suatu rutinitas bahkan keharusan dan ketika televisi digunakan sebagai representasi nilai eksklusif, modern, urbanis, d an kosmopolitan, maka televisi itu sendiri telah menjadi suatu bentuk budaya ( cultural form) (Ibrahim,1997:348-349). Selanjutnya, ketika iklan merambah media televisi, maka pesan -pesan yang disampaikan media televisi semakin bersifat informatif, persuasif bahkan transformatif, pesan dikemas dalam bentuk audio visual sedemikian rupa dalam rangka menjaring konsumen demi kepentingan pasar. Melalui medium televisi pesan -pesan iklan menjadi semakin hidup, bergairah, dan memenuhi sasaran secara lebih efektif bila dibandingkan dengan iklan melalui medium lainnya. Hal ini dapat diterima, mengingat televisi memiliki kemampuan audio sekaligus kemampuan visual yang tidak dimiliki medium lain, sehingga dapat lebih mudah menggambarkan image-image dengan lebih konkret yan g selanjutnya meninggalkan kesan di dalam pikiran pemirsanya. Ditambahkan oleh D. Smythe (1981), ketika individu menghadapi kotak ajaib bernama TV, individu sesungguhnya tidak hanya berhadapan dengan informasi an sich, tetapi juga sedang berhadapan dengan kebudayaan yang dipaketkan atau kebudayaan kemasan (Ibrahim,1997:350). Di dalam budaya kemasan, citra menjadi lebih penting dari makna. Untuk membangun citra, produk barang yang diiklankan atau komoditas itu perlu dikemas dan diperindah dengan begitu memukau. Tidak lain untuk memenuhi prasyarat komoditas tontonan yang akan dipajangkan di etalase kebudayaan pop. Iklan sebagai salah satu bentuk tayangan televisi, juga merupakan tempat pencitraan, khususnya bagi produk yang diwakilinya. Selanjutnya, peneliti akan menfokuskan penelitian ini pada iklan anak -anak (iklan yang ditujukan pada target audience anak-anak) yang ditayangkan di televisi. Sebagaimana telah dijabarkan dalam paragraf -paragraf sebelumnya, iklan di televisi, termasuk iklan anak -anak di televisi, merupakan produk dari dunia kapitalis yang dipenuhi dengan pencitraan -pencitraan dan penggambaran tentang dunia atau realitas. Bahkan iklan merupakan medium untuk sosialisasi dan internalisasi nilai -nilai sosial pada anak-anak. Televisi telah menjadi l embaga pendidikan imajiner anak -anak zaman modern, bahkan telah ikut menjadwal -ulang dan mendiktekan waktu belajar, bermain, dan tidur anak. Pencitraan Iklan Anak-anak, tidak berbeda dengan orang dewasa mendapat terpaan iklan yang yang cukup besar, seiring dengan frekuensi mereka menonton televisi. Apalagi ketika televisi -televisi komersial secara khusus membuat suatu bentuk program acara yang ditujukan bagi anak -anak, maka para pengiklan pun otomatis memanfaatkan momen tersebut untuk membidik mereka seb agai target audience dari iklan produknya. Hasil penelitian MRI ( Marketing Research Indonesia ) yang dilakukan pada Mei s/d Juni 2001 terhadap ibu dan anak berusia 7 -14 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak diterpa media televisi semenjak bayi (25%). Begitu us ia menginjak lebih dari satu tahun, hampir semua anak terbiasa menonton televisi (92%). Selanjutnya ketika memasuki usia TK (4-6 tahun) hingga SMP (12-14 tahun), semua (100%) sudah menjadi penonton setia televisi (http://www.suarapembaharuan.com/News/2001/ 10/21/Editor/ed02.html, diakses Rabu, 3 April 2002). Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa sejak kecil anak -anak telah terbiasa menghabiskan banyak waktu untuk bergaul dengan televisi, dan waktu menonton semakin panjang dengan bertambahnya usia. Jam menonton televisi anak-anak berbeda antara hari Minggu dengan hari -hari biasa. Pada hari Senin hingga Sabtu, bayi hingga umur satu tahun, menurut para ibunya, menonton televisi rata-rata ½ jam, pada usia balita (1 -4 tahun) menghabiskan waktu 2 jam, dan diata s usia ini menghabiskan waktu 2½ jam s/d 3 jam per hari. Sedangkan pada hari minggu, terjadi lonjakan waktu menonton televisi, para ibu memperkirakan bayi mereka menonton televisi sekitar 1 jam pada hari itu, balita menonton sekitar 3 jam, sedangkan anak -anak yang lebih besar menghabiskan 4 jam s/d 5½ jam per hari untuk menonton televisi (http://www.suarapembaharuan.com/News/2001/10/21/Editor/ed02.html, diakses Rabu, 3 April 2002). Angka-angka yang tesaji menunjukkan bahwa anak -anak Indonesia tergolong heavy viewer, yaitu memliki kebiasaan menonton televisi di atas 3 jam dalam sehari. Hal ini didukung survey YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) yang dilakukan pada April 2002, bahwa anak-anak menonton televisi 30 s/d 35 jam perminggu (Http://www.kompas .com/kompascetak/0207/16/dikbud/anak20.htm, diakses Selasa, 22 Oktober 2002). Kondisi semacam ini menjadikan anak -anak sebagai sasaran empuk bagi para pengiklan. Anak-anak sebagai konsumen jelas berpotensi vital bagi dunia bisnis dan industri. Para pema sar produk anak-anak dengan cerdik mengeksploitasi rasa bersalah kaum dewasa, terutama ibu sebagai penggelitik gairah beli terhadap produk anak -anak yang ditawarkan. Para orang tua memang bukan konsumen, namun pembeli bahkan pelanggan produk anak -anak yang potensial. Di samping itu, harus disadari kembali bahwa anak -anak sebagai target audience dari iklan anakanak sedang berhadapan tidak hanya dengan produk yang diiklankan, melainkan juga kebudayaan yang dipaketkan atau kebudayaan kemasan dan bahwa televis i menawarkan ideologinya sendiri yang khas. Dengan tayangan -tayangannya yang batas-batasnya begitu cair, televisi mencampur adukkan berbagai realitas pengalaman individu yang berlainan sehingga individu sendiri sulit mengidentifikasikan pengalamannya yang sebenarnya. Demikian juga dalam iklan anak anak di televisi, berbagai nilai sosial dan ide -ide dikonstruksi dalam kemasan pesan yang begitu menarik, sehingga anak -anak akan terhanyut dalam realitas vitual dan mengganggapnya sebagai kebenaran. Sedangkan seb agai mana kita ketahui, anak anak adalah makhluk yang masih begitu mudah untuk diwarnai. Penelitian ini lebih jauh berusaha mengungkapkan bagaimanakah definisi atau penggambaran anak-anak menurut iklan anak -anak di televisi. Berusaha mengungkapkan bagaimanakah periklanan Indonesia mendefinisikan dan mengkonstruksi anak -anak ideal melalui realitas virtual yang dibangunnya. Siapakah anak -anak? Bagaimanakah anak-anak? Dan bahkan Apakah yang dimaksud dengan anak -anak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarn ya merupakan upaya untuk mempertanyakan identitas, yaitu identitas anak -anak. Bagaimanakah identitas anak-anak berdasarkan iklan anak -anak di televisi? Bagaimanakah anak -anak yang seharusnya menurut iklan anak -anak di televisi? Uraian diatas merupakan sebu ah pengantar untuk memahami politik identitas. Politik Identitas Sebagai Konstruksi Sosial Menurut Young, politik identitas identitas berkaitan secara erat dengan gagasan atau ide tentang terjadinya penindasan terhadap kelompok -kelompok sosial berkaitan dengan identitas mereka (baik berdasarkan ras, etnis, gender, seksualitas, kelas, dll). Artinya, identitas seseorang sebagai seorang wanita atau sebagai seorang penduduk asli Amerika misalnya, membuatnya rentan terhadap imperialisme kultural (termasuk te rjadinya stereotipe atau penyalahgunaan identitas kelompok), kekerasan, eksploitasi, serta marjinalisasi atau ketidakberdayaaan, (http://plato.stanford.edu/entries/identity -politics, diakses Sabtu, 25 Januari, 2003). Gerakan gerakan yang dipandang sebagai politik identitas, memandang telah terjadi penindasan dan berusaha merekomendasikan dilakukannya klaim ulang, deskripsi ulang, atau transformasi ulang terhadap catatan-catatan keanggotaan kelompok yang sebelumnya distigmatisasikan. Stuart Hall menjelaskan identity politics sebagai the politics of location (Hall, 1996:1) artinya politik menempatkan individu-individu pada lokasi-lokasi (realitas sosial) tertentu yang telah dengan sengaja dikonstruksi. Politik identitas selalu berhubungan dengan the definition of self/subject dalam konstruksi tersebut. Dengan kata lain, politik identitas merupakan pemahaman bahwa identitas-identitas individu didasarkan pada tempat atau posisi dimana individu tersebut diletakkan (place-based identity). Sedangkan menurut Madan Sarup, politik identitas atau identity politics merupakan “As politics is about the production of identities —politic produces the subject of its action.” (Sarup, 1996:48). Artinya politik identitas merupakan politik tentang produksi identitas -identitas, penciptaan-penciptaan subyek beserta tindakan dan nilai yang dipandang baik dan seharusnya dijalani subyek tersebut sebagai sebuah kehidupan yang tidak bisa dipertanyakan. Dalam perspektif social construction of reality, politik identitas dipandang sebagai k onstruksi sosial, usaha penciptaan identitas yang dilakukan secara sadar dan melaui berbagai cara, bukan dipandang sebagai sesuatu yang secara alami dianugerahkan oleh Tuhan maupun sesuatu yang sifatnya anatomis. Sebagaimana dikemukakan Madan Sarup “all identities, whether based on class, ethnicity, religion or nation, are social constructions...Though identity may be constructed in many different ways, it is always constructed in the symbolic, that is to say, in language.” (Sarup, 1996: 48). Jika pandangan Stuart Hall ini dikaitkan dengan pandangan Madan Sarup, maka politik identitas dapat dipahami sebagai produksi identitas -identitas melalui penciptaan tempat -tempat atau posisi-posisi subyek dalam lingkungan sosial beserta tindakan -tindakan yang seharusnya dilakukan subyek sesuai dengan tempat dan posisinya tersebut. Memasuki millenium of television, sebagai salah satu indikator modernitas (Bungin, 2001: 25), maka permasalahan identitas menjadi lebih problematik, lebih mudah mengalami perubahan. Sebagaimana dikemukakan Kellner bahwa dalam masyarakat modern, identitas lebih bersifat personal, artinya individu memiliki kesempatan dan peran dalam menentukan identitas yang diinginkan dan sesuai untuknya. Identitas lebih berkaitan dengan style, untuk memproduksi suatu image bagaimana individu ingin menampilkan dirinya. Memilih dan membentu — dan selanjutnya membentuk ulang — identitas merupakan sebuah kemungkinan dalam masyarakat modern. Identitas tidak lagi secara mutlak ditetapkan masyarakat atas diri ind ividu, sehingga identitas merupakan refleksi dari diri individu, bukan lagi mutlak refleksi institusi sosial dimana individu berada. Tetapi masih, identitas dalam masyarakat modern juga bersifat sosial, dalam hal ini dikenal istilah mutual recognition, dimana identitas seseorang tergantung pada pengakuan pihak lain yang selanjutnya dikombinasikan dengan self-validation dari individu bersangkutan. Individu harus berusaha memperoleh pengakuan untuk menerima pengesahan sosial atas identitas yang dipilihnya, sehingga merupakan identitas yang diakui (Kellner, 1999:232). Dalam pandangan postmodern, budaya manusia saat ini menunjukkan bahwa identitas individu lebih cenderung dimediasi melalui image-image atau citra-citra yang ditampilkan individu tersebut, baik melalui fashion, kosmetik, gaya bicara maupun style (Kellner, 1999:231). Sehingga media massa, termasuk tayangan iklan di dalamnya yang mengandalkan teknologi pencitraan, memiliki peran yang besar dalam proses konstruksi identitas individu. Maka dengan demikian tayangan iklan selain mengkonstruksi identitas melalui citra -citra, juga sekaligus memberikan mutual recognition atas identitas tersebut. Sehingga iklan merupakan salah satu bentuk tayangan televisi yang menjadi sumber atau rujukan bagi individu untuk melakukan kategorisasi, identifikasi dan pembandingan sosial ( Social Identity Theory) dalam proses konstruksi identitas. Konstruksi identitas melalui image-image atau citra-citra, khususnya dalam iklan anak-anak di televisi merupakan politik identitas, yai tu produksi identitas-identitas anak. Penciptaan anak-anak ideal beserta tindakan dan nilai yang dipandang baik dan seharusnya dijalani oleh anak-anak tersebut, melalui citra-citra yang ditampilkan dalam realitas virtual iklan anak-anak di televisi. Konstruksi sosial atas identitas, menurut Seyla Benhabib merupakan proses pertarungan politik, sosial dan budaya untuk saling bersaing menghegemoni diantara kelompok -kelompok sosial, masing-masing berusaha mendominasi atau membebankan definisi -definisi identitas tertentu terhadap kelompok sosial lain, (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES yearbook/94_docs/BENHABIB.HTM, diakses Sabtu, 1 Juni 2002). Maka tayangan iklan anak anak di televisi pun merupakan arena sosial, di dalamnya terjadi proses pertarungan politik, sos ial dan budaya dimana suatu kelompok sosial tertentu berusaha menghegemoni dan membebankan definisi-definisi tertentu atas identitas anak -anak. Dikaitkan dengan politik identitas anak, Social Construction of Reality memberikan suatu pola berfikir bahwa kon struksi identitas anak dalam iklan anak-anak di televisi pada akhirnya diterima oleh target audience (dalam hal ini anak-anak) sebagai sebuah realitas yang taken for granted. Penggambaran identitas-identitas anak diterima sebagai pengetahuan sehari -hari yang pada akhirnya dipandang dan dipercaya sebagai sebuah realitas sosial dan menjadi stock of knowledge bagi individu, khususnya anak -anak. Individu dalam masyarakat membangun sebuah realitas media melalui iklan anak -anak di televisi (eksternalisasi) yang selanjutnya diterima dan diyakini oleh target audience (anak-anak) sebagai kebenaran, sebagai realitas yang taken for granted (obyektifasi). Karena diyakini sebagai kebenaran, realitas (yang sesungguhnya) buatan tersebut pada akhirnya memiliki kekuatan yang memaksa terhadap individu atau kelompok (anak -anak) yang mendiami realitas tersebut untuk bersikap dan bertindak sesuai dengannya tipifikasi -tipifikasi yang dicontohkan dalam realitas media. Media Massa dan Konstruksi Identitas Saat ini, kebebasan yang besar dalam mengakses media telah memberikan pengaruh besar dalam proses konstruksi identitas individu, terutama bagi kalangan remaja dan anak -anak. Sebagaimana dikemukakan Grodin dan Lindlof sebagai berikut: “With a simple flip of the television chann el or radio station, or turn of the newspaper or magazine page, we have at our disposal an enormous array of possible identity models.” (http://www.aber.ac.uk/media/students/klh9802.html, diakses 24 Sept 2001). Identitas, saat ini dimediasi melalui images yang ditampilkan media. Sehingga tidak mungkin lagi identitas individu dikonstruksi hanya oleh komunitas kecil ( peer group) atau hanya dipengaruhi oleh keluarga saja. Proses terjadinya pengaruh media terhadap konstruksi identitas dijelaskan oleh Brown sebagai berikut, bahwa individu secara aktif dan keatif mencontoh simbol simbol budaya, dongeng, dan ritual yang tersedia di media selama mereka membangun identitas diri mereka. Media memegang peranan penting dalam proses ini, karena dipandang sebagai sumber pilihan budaya yang tidak menyusahkan. (http://www.aber.ac.uk/media/students/klh9802.html, diakses 24 Sept 2001). Identitas bukanlah sesuatu yang stagnan, identitas dikonstruksi sepanjang waktu dan dapat secara konstan diperbaharui atau dirubah secara to tal. Jadi, pengaruh media populer dalam konstruksi identitas tidak berlangsung dalam kurun waktu sesaat saja, melainkan terus -menerus, sepanjang individu tersebut berinteraksi dalam lingkungan sosialnya dan sepanjang terdapat terpaan media pada individu. Dalam konstruksi identitas, tidak dapat dilupakan adanya faktor tekanan dari masyarakat atau kelompok sosial tehadap orang muda dan anak -anak ketika mereka dalam proses konstruksi identitas. Bentuk tekanan ini menurut Hamley dapat berupa sejumlah harapan -harapan tertentu oleh masyarakat tentang bagamana individu harus atau seharusnya hidup (http://www.aber.ac.uk/media/students/klh9802.html, diakses 24 Sept 2001). Dengan kata lain masyarakat memberikan batasan -batasan tentang identitas yang harus dipelihara dan identitas yang tidak dapat diterima. Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan bahwa identitas yang diharapkan oleh masyrakat sesungguhnya berbeda atau bahkan berlawanan dengan identitas yang dianggap cocok oleh individu bagi dirinya. Dalam memahami poses pembentukan identitas, Henry Tajfel dan John Turner mengemukakan Teori Identitas Sosial ( Social Identity Theory) bahwa proses pembentukan identitas dalam diri individu melalui tiga thapan, yaitu: kategorisasi, identifikasi, pembandingan sosial (htt p://www.psy.anu.edu.au/social/socident.htm, diakses 24 Sept 2001). Yang pertama kategorisasi ( categorization), individu menganali dan mengelompokkan identitas -identitas berdasarkan kategori sosial seperti etnis, ras, religi, pekerjaan, status sosial, dll. Kategori-kategori ini selanjutnya akan memberikan suatu pengertian tentang siapa dan bagaimana individu pemilik identitas. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi ( identification). Pada tahap ini individu mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok -kelompok tertentu dimana ia terafiliasi. Dalam identifikasi terkandung dua makna dalam diri individu, pertama, bahwa sebagian dari diri individu dibangun berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok. Dalam hal ini terdapat pemikiran kami vs mereka. Kedua, bahwa pada saat tertentu individu berfikir bahwa dirinya sebagai aku, dan memandang orang lain sebagai dia. Jadi pada saat tertentu individu memandang dirinya sebagai anggota suatu kelompok, yang disebut sebagai social identity, dan pada saat yang lain memandang dirinya sebagai individu yang unik, yang disebut sebagai personal identity. Tahap ketiga dari proses pembentukan identitas adalah pembandingan sosial ( social comparison), yaitu tindakan individu yang membuat perbandingan antara dirinya dengan orang lain dalam rangka mengevaluasi dirinya. Anggota suatu kelompok membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain untuk menguatkan persepsinya bahwa kelompoknya adalah positif, dan implikasinya, memperoleh konsep diri bahwa dia sebagai anggota kelompok juga po sitif. Hegemoni Realitas dalam Iklan Realitas yang ditampilkan dalam iklan, bukanlah sebuah sebuah cermin realitas sosial yang jujur. Tapi iklan adalah sebuah cermin yang cenderung mendistorsi realitas, atau Marchand menyebutnya sebagai a hall of distorting mirrors. Iklan cenderung membangun realitas yang cemerlang, melebih-lebihkan, dan melakukan seleksi tanda -tanda atau images, sehingga tidak merefleksikan realitas akan tetapi mengatakan sesuatu tentang realitas. Iklan merangkum dilema dilema sosial atau aspek-aspek realitas sosial dan mempresentasikannya secara tidak jujur. Iklan menjadi cermin yang mendistorsi realitas yang dipresentasikannya dan sekaligus menampilkan images dalam visinya (Noviani, 2002:53 -55). Tidak ada iklan yang ingin menangkap keh idupan seperti apa adanya, akan tetapi selalu ada maksud untuk memotret ideal -ideal sosial dan menampilkannya sebagai sesuau yang normatif. Iklan tidak berbohong akan tetapi juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Dunia abstrak yang dipresentasikan iklan me rupakan sebuah usaha yang disengaja untuk mengkonstruksi asosiasi -asosiasi antara suatu produk dengan imajinasi individu, dengan kelompok demografik maupun psikografik tertentu, atau dengan dengan kebutuhan dan kesempatan tertentu. Sedikit berbeda, menurut Schudson, iklan tidak merepresentasikan realitas, tidak pula membangun sebuah dunia yang betul -betul fiktif. Iklan berada dalam ruang realitasnya sendiri, yang disebutnya sebagai capitalism realism. Periklanan dalam masyarakat kapitalis tidak menggambarkan realitas dengan apa adanya, akan tetapi realitas yang seharusnya ( what the life should be) dengan berusaha menyamai atau melebihi nilai kehidupan (Noviani, 2002:56). Iklan berusaha menampilkan sebuah representasi realitas konkret yang secara historis b enar dalam perkembangan kapitalisnya. Iklan pun melakukan simplifikasi -simplifikasi dan tipifikasitipifikasi sebagai upaya untuk mencapai efektifitas penyampaian pesan. Iklan juga selalu mengemukakan kemajuan atau progress, memfokuskan pada hal -hal yang baru, dan kalaupun menghadirkan tanda maupun image budaya, itu hanya dalam rangka membantu khalayak mengasimilasi kreasi baru dari iklan. Dalam iklan selalu ada optimisme dengan cara mengidentfikasi solusi dari setiap permasalahan dengan produk -produk tertentu mapun dengan gaya hidup. Pemahaman capitalism realism Schudson hampir sama dengan apa yang dikemukakan Erving Goffman mengenai commercial realism. Commercial realism adalah sebuah transformasi standar yang diterapkan dalam periklanan, yaitu semacam pe nggambaran tentang publik yang digunakan oleh iklan. Commercial realism membedakan cara orang mempresentasikan dirinya dalam kehidupan aktual dengan dua cara, yaitu: 1. Jika dalam kehidupan nyata aktivitas manusia bersifat sangat ritual, didasarkan pada idealisasi-idealisasi sosial, maka dalam iklan, aktivitas tersebut bersifat lebih ritual lagi. Iklan justru menyangatkan atau melebihkan apa yang terjadi di dunia nyata; 2. Dalam kehidupan nyata individu tidak cukup bisa memperbaiki kehidupan mereka untuk mendapatkan idealisasi sosial yang betul -betul ritual sifanya. Akan tetapi dalam commercial realism perbaikan kehidupan dapat dilakukan dengan sangat cermat sehingga idealisasi sosial dapat digambarkan dengan selengkap mungkin (Noviani, 2002:56 -57). Demikianlah realitas iklan, seperti dijelaskan Schudson dan Goffman, merupakan capitalism realism atau commercial realism. Menyajikan realitas-realitas yang merupakan penyangatan dari realitas sosial yang nyata, menyajikan simplifikasi, idealisasi sosial, dan tipifikasi yang diterima individu sebagai kebenaran, realitas yang taken for granted. Iklan, sebagai bagian dari masyarakat kapitalis, memang powerfull dan sulit dielakkan. Menyediakan gambaran tentang realitas, sekaligus mendefinisikan kebutuhan dan keingin an individu. Iklan mendefinisikan makna gaya hidup, makna selera dan cita rasa yang baik, bukan sebagai sebuah kemungkinan atau saran, melainkan sebagai tujuan yang hendak dicapai dan tidak bisa untuk dipertanyakan. Menurut Williamson, iklan selain memili ki fungsi untuk menjual produk pada individu, juga memiliki fungsi yang lain, yaitu menciptakan struktur makna. Dalam menjalankan fungsinya untuk menjual produk, iklan harus memperhitungkan bukan hanya kualitas dan karakter yang melekat pada produk, tetapi juga memperhitungkan cara -cara yang dapat dilakukan untuk membuat benda tersebut mean something to us. Dengan kata lain, periklanan harus mampu menerjemahkan pernyataan dari things statements menjadi human statements (Judith, 1985:12). Sebagai contohnya, iklan berlian, berlian melalui iklan dipasarkan dengan menghubungkannya dengan cinta abadi. Dalam hal ini telah diciptakan simbolisasi, di mana berlian tidak lagi diartikan berdasarkan istilah aslinya sebagai sejenis bebatuan, akan tetapi dilekati istilah manusiawi yaitu cinta dan kesetiaan, maka berlian menjadi sebuah tanda. Ketika hubungan antara benda dengan tanda terbentuk, individu akan memandang berlian (signifier) sebagai sebuah tanda yang menunjuk cinta dan kesetiaan (signified), benda yang mewakili perasaan. Iklan melalui pesannya mempertukarkan nilai -nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada produk. Iklan memberikan makna sosial tertentu terhadap sebuah produk. Jadi periklanan menjual sesuatu yang lain disamping barang -barang konsumsi, iklan menyediakan struktur atau kelas tertentu bagi individu dimana mereka dan produk dapat dipertukarkan. Iklan menjual pada kita ourselves (diri kita). Dan individu membutuhkan diri tersebut. Iklan membuat individu merasa sebagai in-group atau out-group dari suatu kelompok sosial melalui barang-barang konsumsi yang mampu mereka beli, dan hal ini mengaburkan posisi dan kelas sosial sesungguhnya dari individu. Sistem kepercayaan dan gagasan semacam inilah yang merupakan ideologi. Dalam ideologi, terdapat makna -makna tertentu yang dibuat penting oleh suatu kondisi masyarakat sekaligus terdapat usaha -usaha untuk mengekalkan kondisi tersebut. Individu merasa perlu untuk terafiliasi ke dalam suatu kelas atau kelompok tertentu, memiliki tempat sosial tertentu Di sini, ideolog i menggambarkan produksi makna dan ide, bagaimana kelompok-kelompok digambarkan dan diposisikan. Ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan yang diterima individu dari kelompok atau kelas sosial tertentu, bukan sesuatu yang ada dalam diri individu. Merupak an seperangkat kategori yang sengaja dibuat dan kesadaran palsu yang bekerja dengan membuat hubungan -hubungan sosial tampak nyata, wajar, dan alamiah, dan tanpa sadar diterima sebagai kebenaran. Selanjutnya, Antonio Gramsci membangun teori tentang hegemon i yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap idelogi kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai dan tanpa kekerasan. Gramsci berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan ( force) dan hegemoni. Jika kekuatan ( force) menggunakan daya paksa membuat pihak lain mengikuti dan mematuhi cara -cara produksi atau nilai-nilai tertentu, maka hegemoni meliputi perluasan dan pe lestarian kepatuhan aktif (secara sukarela) dari kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik. Proses ini terjadi dan berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan ketika individu menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Jadi hegemoni bekerja melalui dua saluran, yaitu ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja (Eriyanto, 2001: 103-104). Hegemoni bekerja melaui konsensus ketimba ng upaya penindasan. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Dalam hal ini media dapat menjadi sarana di mana suatu kelompok me ngukuhkan posisinya dan memarginalkan kelompok lain melalui wacana yang dibangun. Proses marginalisasi wacana tersebut berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dihayati bersama sehingga menjadi konsensus. Wacana diterima secara taken for granted (tidak perlu dipertanyakan), sebagai suatu common sense maka saat itulah hegemoni telah terjadi. Analisis Iklan Permen Milkita Iklan Permen Milkita dipilih karena menampilkan anak -anak dalam setting sosial keluarga. Dengan melakukan analisis teks iklan Permen Mi lkita peneliti berusaha mengungkapkan konstruksi identitas anak dalam setting keluarga, dimana menurut William J. Goode masyarakat merupakan struktur yang terdiri dari keluarga -keluarga. Kedudukan utama setiap keluarga menurutnya adalah sebagai penghubung individu dengan struktur masyarakat yang lebih besar, hal ini membawa konsekuensi bahwa eksistensi lembaga -lembaga sosial lainnya sangat tergantung pada keluarga. Keluarga menyumbangkan hal -hal berikut pada masyarakat; kelahiran, pemelihaaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, dan kontrol sosial. (Goode, 1991: 2-9) Dengan didasarkan pada kerangka analisis teks yang dikemukakan Norman Fairclough, maka teks berupa iklan Permen Milkita Colek dianalisis untuk mengungkapkan tiga hal sebaga i berikut: representasi anak-anak dalam iklan, relasi antara anak -anak dengan individu lain dalam iklan dan identitas. Dalam melakukan analisis teks, peneliti menggunakan perspektif Social Construction of Reality, memandang realitas media sebagai sebuah ko nstruksi. Realitas media, yang pada awalnya merupakan realitas sosial yang terdistorsi (Noviani, 2002:56 -57), pada tahap selanjutnya diterima individu sebagai pengetahuan sehari -hari yang secara taken for granted dipandang sebagai realitas sosial tanpa ind ividu memandang apakah realitas tersebut valid atau tidak. 1. Relasi yang Timpang antara Anak dan Orangtua: Sub-ordinasi Anak dalam Aspek Ekonomi Anak Ayah : Pah...permennya ! : Iya-iya Sebagaimana dikemukakan Jaya Suprana, bagi produk tertentu orangtua bukan merupakan konsumen, namun seringkali merupakan pelanggan produk anak -anak yang sangat potensial (Mulyana dan Ibrahim, 1997:185). Iklananak -anak selain membidik anak -anak juga membidik orangtua sebagai target audience. Sebagaimana dikemukakan Leny Marlina (advertising agency Permen Milkita), secara demografis target audience iklan Permen Milkita adalah individu usia 3 th s/d 12 th (user) dan 25 th s/d 40 th ( influenver-ibu muda). Menurutnya dengan mengangkat kualitas atau kelebihan produk Perm en Milkita, kreatif iklan berusaha meyakinkan orangtua bahwa stereotipe permen tidak baik untuk kesehatan adalah tidak benar. Mengutip pernyataan Leny Marlina: “…image permen buat orangtua terutama ibu bahwa permen bisa merusak gigi, batuk, dll, masih cukup diterima (dipercaya). Untuk itu dari tim kreatif mengangkat kelebihan dari produk Permen Milkita dengan penyelesaian masalah antara pro -kontra bapak dan ibu tentang permen, dan Milkita adalah jawaban dari mengapa orangtua memperbolehkan anak makan perme n.” (Marlina, 2003: Interview). Anak-anak merupakan kelompok non -produktif, yaitu tidak menguasai sumber -sumber ekonomi atau tidak memiliki penghasilan secara mandiri. Dengan demikian anak -anak dalam pandangan kapitalisme merupakan pihak yang lemah secar a ekonomi, sehingga diperlukan sebuah strategi untuk dapat mempertahakan anak -nak sebagai konsumen potensial produk -produk di pasaran. Berkaitan dengan realitas sosial maupun realitas iklan bahwa anak -anak lemah secara ekonomi, salah seorang dari kreatif i klan Permen Milkita, Leny Marlina mengemukakan bahwa walaupun harga produk permen Milkita relatif bisa dijangkau oleh anak -anak SD yang sudah bisa jajan di kantin sekolah, namun untuk menyiasati ketergantungan anak pada orangtua dalam memperoleh produk jajanan, pihaknya berusaha tidak hanya membangkitkan keinginan mengkonsumsi dalam diri anak -anak, tetapi juga berusaha mempengaruhi orangtua, dalam hal ini khususnya pihak ibu, untuk mendukung konsumsi produk Permen Milkita oleh anak -anak (Marlina, 2003: Interview). Dominasi orangtua dalam aspek ekonomi ini dapat dijelaskan melalui pandangan yang dikemukakan Marx, bahwa kelas dominan merupakan kelas yang menguasai alat -alat produksi material, sehingga memiliki kontrol terhadap alat -alat tersebut, dan sebagai konsekuensinya kelompok yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi material ditaklukkan (Berger, 1993:50). Dengan menguasai sumber perekonomian keluarga, orangtua memiliki kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap sumber perekonomian tersebut, bahka n kontrol terhadap individu yang tidak memiliki akses pada sumber perekonomian keluarga, yaitu anak -anak. Anakanak berbeda dengan orangtua, karena anak -anak lemah secara ekonomi. Realitas iklan menampilkan anak-anak sebagai pihak yang tidak menguasai sumb er ekonomi dan berada di bawah kontrol orangtua. Sedangkan orangtua menguasai sumber ekonomi dan memiliki kontrol atas anak-anak. Penggambaran relasi yang demikian antara anak dan orangtua menunjukkan adanya kelas atau hirarki dalam keluarga berdasarkan fa ktor kepemilikan sumber-sumber ekonomi. Dalam strata atau kelas tersebut, tokoh anak digambarkan sebagai pihak yang sub ordinat dari aspek ekonomi 2. Anak-anak Konsumtif Dalam adegan iklan Permen Milkita digambarkan terjadinya pertengkran antara kedua orangtua akibat perilaku konsumtif anak, dimana tokoh ibu tidak setuju dan menilai sembarangan atas tindakan tokoh ayah membelikan produk jajanan yang dipesan tokoh anak. Selanjutnya digambarkan tokoh anak terdorong untuk melerai pertengkaran kedua orangtuanya dengan menyampaikan alasan-alasan yang merupakan pembenaran atas perilaku konsumtifnya. Anak : 2 lolly Milkita sama dengan segelas susu berkalsium tinggi. Ibu : Iya ! Anak : Ini permen susu mahal ! Anak : Milki cuma minta permen susu. Lolly milk...susu asli Milkita. Ayah : Hmm...!! Pembenaran pertama disampaikan tokoh anak laki -laki melalui representational code “Milki cuma minta permen susu...”. Melalui pembenaran ini tokoh anak diposisikan sebagai seorang anak yang sebenarnya tidak menu ntut berlebihan, cuma minta permen susu. Anak direpresentasikan tidak nakal, tidak bersalah, karena ia cuma minta permen susu. Karenanya tidak semestinya kedua orangtuanya bertengkar karena yang diminta tokoh anak adalah cuma permen susu. Pembenaran yang kedua disampaikan melalui representational code “Ini permen susu mahal, disertai visualisasi simbol Rp 500, yang bermakna bahwa Permen Milkita adalah permen susu mahal sehingga boleh dikonsumsi. Tidak seharusnya kedua orangtua bertengkar karena tokoh anak laki-laki digambarkan tidak sembarangan mengkonsumsi produk jajanan, tapi produk yang mahal. Melalui representational code ini, realitas iklan menyajikan harga sebagai tolak ukur baru dari mutu dan kualitas produk Sebagaimana dikemukakan Leny Marlina, di masukkannnya kata mahal dalam realitas iklan Permen Milkita merupakan permintaan klien (produsen Permen Milkita). Dengan alasan produk Permen Milkita benar-benar terbuat dari susu asli sehingga harganya pun harus disesuaikan. Dalam hal ini harga memang dit ujukan untuk merepresentasikan kualitas Permen Milkita yang terjaga (Marlina, 2003: Interview). Pembenaran ketiga disampaikan melalui representational code dua lolly Milkita sama dengan segelas susu berkalsium tinggi. Represenatitonal code yang ketiga ini merupakan pembenaran dari sudut pandang kesehatan, bahwa Permen Milkita memang boleh dikonsumsi karena memiliki kandungan gizi tertentu. Representational code ini didukung oleh icon 2 lolly Permen Milkita dan icon segelas susu berkalsium tingggi, yang meng konstruksi makna bahwa 2 lolly milkita sama dengan atau setara dengan segelas susu berkalsium tinggi. Berkaitan dengan adegan penyampaian pembenaran anak atas perilaku konsumtifnya, Leny Marlina mengemukakan bahwa lifestyle dari keluarga yang merupakan target market sekaligus target audience dari iklan ini adalah keluarga modern, sehat cerdas, dan ceria. Asumsinya dalam keluarga semacam itu konsep demokrasi dapat berjalan, sehingga dengan kecerdasannya seorang anak mampu meyakinkan orangtua mengenai kuali tas produk jajanan atau permen yang ia sukai (Marlina, 2003: Interview). Jadi dalam realitas iklan Permen Milkita, sebenarnya tokoh anak laki laki sedang meyakinkan orangtuanya tentang kualitas produk jajanan yang disukainya. Dengan kata lain membenarkan perilaku konsumtifnya. Dalam hal ini konstruksi realitas iklan Permen Milkita memuat kepentingan untuk membudayakan perilaku konsumtif, dengan membangun citra mahal dan sehat dari sebuah produk, yang merupakan alasan dibenarkannnya perilaku konsumtif. Realitas iklan juga merepresentasikan sebuah ritual baru, yaitu suatu cara hidup sehat yang instan, bahwa ritual minum susu dapat digantikan dengan mengkonsumsi Permen Milkita. Dalam pandangan praktisi periklanan, perilaku konsumtif anak merupakan hal yang waj ar, bukan sebuah kenakalan. Sebagaimana dikemukakan Leny Marlina: “Kenakalan pada seorang anak adalah hal yang sangat wajar jika kenakalan tersebut masih dalam bentuk kenakalan dunia anak -anak, dan pada dasarnya semua anak suka jajan, terutama mencoba jajanan yang baru atau iklan makanan yang ada di TV. Dan perilaku konsumtif bukanlah bentuk kenakalan.” (Marlina, 2003: Interview) Cara pandang ini dapat dimengerti mengingat budaya konsumtif merupakan salah satu syarat bertahannya ideologi kapitalis. Bagai mana sebuah industri bertahan sangat tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Melalui realitas iklan Permen Milkita, ideologi kapitalis berusaha mengekalkan dominasinya melalui konstruksi realitas bahwa perilaku konsumtif pada anak -anak adalah wajar. Ketika sebuah nilai telah diterima secara taken for granted, sebagai sebuah kewajaran, maka telah terjadi hegemoni. 3. Anak Laki-laki Nakal: Stereotipe Gender dalam Keluarga Sesuai dengan critical discourse analysis, peneliti mencoba mempertanyakan kembal i (melakukan dekonstruksi) atas realitas dalam iklan Permen Milkita, mengapa tokoh anak laki -laki ditempatkan pada posisi trouble maker? Mengapa bukan tokoh anak perempuan yang diposisikan demikian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan konstruksi relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki -laki. Dalam pandangan peneliti hal ini berkaitan dengan konteks masyarakat patriarki. Sebagaimana masyarakat dimana peneliti tinggal, terdapat sebuah nilai yang taken for granted bahwa kenakalan adalah wajar bagi anak laki-laki. Sebagai misal, jika ada seorang ibu mengeluhkan kenakalan anak laki -lakinya maka seringkali tanggapan yang muncul adalah bahwa kenakalan itu wajar karena memang dia anak laki-laki. Pandangan masyarakat aka n berbeda jika pelaku kenakalan adalah perempuan. Dalam masyarakat patriarki terdapat nilai -nilai sosial bahwa anak perempuan yang baik adalah yang penurut dan pendiam. Anak perempuan yang banyak tingkah atau terlalu aktif dinilai tidak pantas, bahkan lebih dari itu dapat dikenai sanksi sosial melalui keluarga. Nilai -nilai ini diterima dalam masyarakat, bukan hanya oleh kelompok laki -laki bahkan diterima pula oleh kelompok perempuan, yang dalam pandangan kritis diposisikan sebagai korban atau mengalami peni ndasan. Berkaitan dengan kenakalan dan stereotipe gender, Leny Marlina ( advertising agency Permen Milkita) mengemukakan bahwa : “…karena menurut hasil survey yang kami lakukan, anak perempuan lebih bisa diarahkan dan cenderung penurut sedangkan anak l aki-laki untuk umur seperti yang ada pada iklan masih dalam masa-masa aktif, seorang anak laki -laki lebih cenderung susah diarahkan.” (Marlina, 2003: Interview) Jadi sebagai tim kreatif iklan, Leny Marlina pun sepakat bahwa dirinya, dengan mendasarkan pada hasil survey, menganggap bahwa anak perempuan cenderung penurut dan anak laki-laki memiliki kecenderungan aktif dan susah diarahkan. Dalam analisis peneliti, data hasil survey tersebut justru menguatkan asumsi peneliti bahwa dalam masyarakat dimana ikla n diproduksi dan diinterpretasi terdapat penerimaan stereotipe gender berkaitan dengan kenakalan anak. Data survey berbeda dengan sebuah hasil penelitian psikologis. Data survey tidak menunjuk pada perilaku atau karakter anak berkaitan dengan jenis kelamin , melainkan menunjuk pada stereotipe-stereotipe yang ada dalam masyarakat mengenai jenis kelamin dan karakter anak -anak. Cara pandang patriarki tampaknya mendominasi pola pikir dan pola sikap masyarakat dimana survey tersebut telah dilakukan. Tim kreatif iklan, dalam hal ini diwakili oleh Leny Marlina pun nampaknya menerima stereotipe gender sebagai sebuah kewajaran, seolah -olah kenakalan merupakan sebuah siklus biologis yang pasti dilalui anak -anak laki-laki seusia tokoh Milki. Padahal stereotipe semacam ini secara mendasar merupakan konstruksi sosial yang selanjutnya secara evolusional dapat mempengaruhi kondisi biologis masing -masing jenis kelamin. Sebagaimana dikemukakan Mansour Fakih: “Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang ters osialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing -masing kelamin.” (Fakih, 2001: 9 -10) Misalnya, karena konstruksi sosial gender bahwa laki -laki harus kuat, maka kaum laki -laki semenjak kecil telah tersosialisasi dan termot ivasi untuk menjadi kuat dan berbadan tegap. Dengan demikian, sebuah stereotipe gender yang sebenarnya merupakan konstruksi sosial pada akhirnya mempengaruhi realitas sosial, mempengaruhi biologis masing -masing jenis kelamin. Representasi legitimasi atas stereotipe gender bahwa anak laki -laki dipandang wajar sebagai trouble maker, diperkuat dengan tidak ditampilkannya sanksi sosial kepada tokoh anak laki-laki atas masalah atau konflik yang ditimbulkannya. Adegan dalam iklan Pemen Milkita hanya menggambarkan secara eksplisit bahwa tokoh anak laki -lakilah yang menyebabkan timbulnya masalah atau konflik dalam keluarga. Sedangkan adegan selanjutnya sama sekali tidak menampilkan adanya sanksi sosial dari anggota keluarga (ayah, ibu, kakak perempuan) terhadap tokoh anak laki-laki sebagai trouble maker. Bahkan yang ditampilkan dalam adegan -adegan selanjutnya adalah pembenaran -pembenaran oleh tokoh anak laki -laki atas perilaku konsumtifnya yang menyebabkan konflik dalam keluarga. 4. Anak Perempuan Pasif dan Penuru t : Stereotipe Gender dalam Keluarga Anak Perempuan : Kamu sih...! Adegan ini menampilkan dialog antara tokoh anak perempuan (anonim) dengan tokoh anak laki-laki (Milki). Tokoh anak perempuan menyalahkan tokoh Milki atas pertengkaran yang terjad i diantara kedua orang tua mereka, yang ditunjukkan melalui representational codes yang dikemukakan tokoh anak perempuan, “kamu sih... !”. Tokoh anak -anak ditampilkan dengan latar belakang kedua orang tuanya yang sedang bertengkar. Representational codes “Kamu sih... !”, merupakan signifier yang merepresentasikan posisi tokoh anak laki -laki sebagai penyebab pertengkaran orangtua. Dengan kata lain, melalui representational codes yang dikemukakan tokoh anak perempuan, Anak laki -laki diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Makna suatu konsep menurut Saussure, dibangun melalui hubungan yang paling mendasar, yaitu oposisi. Dengan kata lain, karakteristik dari suatu konsep adalah “ being what anothers are not”, sehingga tidak ada sesuatu yang memiliki makna di dal am dirinya sendiri, melainkan makna dibangun melalui hubungan konsep dalam suatu sistem, yakni hubungan oposisi (Berger, 1993:180). Dengan demikian ketika muncul representasi pihak yang bersalah maka sekaligus muncul representasi pihak yang tak bersalah. Lalu siapakah representasi dari pihak yang bersalah dan siapa pula representasi dari pihak yang tak bersalah dalam adegan tersebut? Hal ini dapat dianalisis melalui relasi antara tokoh anak laki-laki dan tokoh anak perempuan. Dalam realitas iklan Permen Mi lkita anak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bersalah, sedamgkan anak perempuan diposisikan sebagai pihak yang tidak bersalah. Posisi sebagai pihak yang bersalah merepresentasikan perilaku aktif, menciptakan sebuah masalah sehingga menjadi pihak yan g bersalah. Sedangkan posisi sebagai pihak yang tak bersalah merepresentasikan perilaku pasif. Dengan demikian dikonstruksi relasi dimana anak laki-laki digambarkan aktif sedangkan anak perempuan digambarkan pasif. Konstruksi relasi anak laki-laki aktif dan anak perempuan pasif merupakan pengekalan stereotipe gender. Berkaitan dengan hal ini, Leny Marlina, tim kreatif iklan Permen Milkita mengemukakan bahwa: “…menurut hasil survey yang kami lakukan, anak perempuan lebih bisa diarahkan dan cenderung penurut sedangkan anak laki-laki untuk umur seperti yang ada pada iklan masih dalam masa -masa aktif seorang anak laki-laki, lebih cenderung susah diarahkan.” (Marlina, 2003: Interview) Data survei tersebut semakin menguatkan asumsi peneliti bahwa dalam masyark at dimana iklan diproduksi dan diinterpretasi terdapat penerimaan stereotipe gender berkaitan dengan pensifatan bahwa anak perempuan cenderung pasif.. Data survey berbeda dengan sebuah hasil penelitian psikologis. Data survey tersebut tidak menunjuk pada p erilaku atau karakter tertentu dari anak-anak berkaitan dengan jenis kelamin mereka, melainkan menunjuk pada stereotipe stereotipe yang ada dalam masyarakat mengenai jenis kelamin dan karakter anak -anak. Selanjutnya, dalam adegan tersebut juga ditampilkan penyerahan tanggung jawab atau pelepasan tanggung jawab oleh tokoh anak perempuan kepada tokoh anak laki -laki. Dengan menyalahkan tokoh anak laki-laki sebagai penyebab, tokoh anak perempuan melepaskan diri dari masalah, membebankan sebuah sanksi bagi yang bersalah untuk menyelesaikan masalah. Terlepas dari siapakah pihak yang bersalah, tokoh anak perempuan tidak digambarkan berinisiatif melerai pertengkaran kedua orangtuanya. Berbeda dengan tokoh anak laki -laki yang digambarkan secara aktif melakukan usaha untuk melerai kedua orangtuanya sekaligus menyampaikan pembenaran atas perilakunya yang menimbulkan masalah dalam keluarga. Selain dalam adegan tersebut, secara keseluruhan realitas iklan Permen Milkita memang tidak menampilkan adanya penggambaran inisiat if atau peran yang dominan dari tokoh anak perempuan. Bahkan tokoh anak perempuan ditampilkan tidak lebih hanya sebagai substitusi atau pelengkap dalam sebuah keluarga, bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang berhak dan mampu menentukan. 5. Anak-anak “Mahal” : Anak-anak, Permen dan Identitas Kelas Sosial Anak-anak : Ini permen susu mahal ! Dengan ditampilkannnya representasi produk Permen Milkita sebagai permen “mahal” anak-anak sebagai konsumen Permen Milkita pun menyandang label “mahal”. Artinya, realitas iklan Permen Milkita merepresentasikan anak -anak dengan kelas sosial menengah atas, yang diwakilkan melalui konsep “mahal”. Dari adegan ini dikonstruksi sebuah perbedaan ( difference) dan eksklusi (exclusion). Bahwa Permen Milkita berbeda dengan produk permen lain, karena Permen Milkita “mahal”. Permen Milkita dikonstruksi bukan hanya sekedar sebuah produk, melainkan sebagai sebuah label atau penanda dari identitas kelas sosial tertentu. Sebuah kelas sosial yang mahal, kelas sosial menegah atas. Di sisi lain, dikonstruksi sebuah realitas media dimana anak-anak sebagai konsumen Permen Milkita pun berbeda dari anak -anak yang mengkonsumsi produk permen merek lain. Konsumen Permen Milkita memiliki sebuah identitas kelas sosial yang berbeda, yai tu kelas sosial yang “mahal” atau kelas sosial menegah atas. Kelompok kelas sosial ini selanjutnya mengeksklusi atau mengecualikan diri dari individu atau kelompok lain, membuat batas antara kelompok kelas sosial yang “mahal” dengan individu atau kelompok dengan kelas sosial yang dipandang “murahan” atau tidak mahal. Sebagaimana dikemukakan Williamson, iklan selain memiliki fungsi untuk meningkatkan penjualan produk, juga berfungsi untuk menciptakan struktur makna. Iklan menterjemahkan pernyataan dari things statements menjadi human statements, membuat sebuah produk industri “mean something to us” (Williamson,1985:12). Dalam iklan Permen Milkita ini, iklan menjual sesuatu yang lain di samping sekedar produk permen. Iklan menjual pada kita ourselve, menyediakan struktur tertentu di mana diri individu dan suatu produk dapat dipertukarkan. Iklan membuat individu merasa sebagai in-group atau out-group dari suatu kelompok sosial tertentu melalui kepemilikan atau penggunaan barang -barang konsumsi. Selanjutnya, dikemukakan Leny Marlina bahwa penggunaan konsep “mahal” merupakan permintaan dari klien mereka (produsen Permen Milkita). “kata-kata mahal dimasukkan adalah permintaan dari klien, dengan alasan bahwa permen yang dijual benar-benar terbuat dari susu asli s ehingga harga pun harus disesuaikan dari apa yang diberikan oleh klien, dengan kualitas yang terjaga. Sementara mayoritas kompetitor dari ekstrak kimia (buka susu) sehingga dijual lebih murah.” (Marlina, 2003: Interview) Jadi jelaslah bahwa dari sisi pro dusen pun terdapat ide atau gagasan yang mengaitkan antara konsep “mahal” dengan kualitas Permen Milkita. Permen Milkita mahal memang karena dibuat dari bahan berkualitas, yaitu susu asli bukan ekstrak kimia. Bahwa harga sebuah produk industri ditentukan oleh kualitas produksi, sekaligus harga pula yang selanjutnya menjadi indikator dari kualitas produk. Konsep “mahal” dijadikan senjata untuk membidik target audience karena konsep tersebut mampu membawa image kelas sosial menengah atas dan image produk yang berkualitas. Dengan melekatkan konsep “mahal” pada suatu produk melalui iklan, maka produk memiliki eksklusivitas dan kualitas tersendiri. Dengan demikian melalui iklan Permen Milkita, ideologi kapitalis mencitrakan kelas sosial dan kualitas. Esensi sebuah produk industri menjadi kabur. Permen bukan lagi sekedar jajanan, lebih dari itu sebagai penanda kelas sosial. Harga bukan lagi sekedar sejumlah uang, melainkan indikator dari eksklusivitas dan kualitas sebuah produk industri. Daftar Pustaka Berger, Arthur Asa, Media Analysis Techniques (London: Sage Publication, 1993). Bungin, Burhan, Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik (Yogyakarta: Jendela, 2001). Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar A nalisis Teks Media (Yogyakarta: LkiS, Yogyakarta, 2001). Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Goode, William J., Sosiologi Keluarga (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, dalam Stuart Hall dan Paul Du Gay, (eds), Question of Cultural Identity, 1996, Penerbit: Sage Publication, London. Mulyana, Deddy & Ibrahim, Idi Subandy, 1997). Bercinta dengan Televisi (Bandung: Rosdakarya, Kellner, Douglas, Media Culture, Cultural Studies, Identity and Politics between The Modern and The Postmodern (London & New York: Routledge, 1998). Kitley, Philip, Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, Lembagaa Studi Pers dan Pembangunan dan PT M edia Lintas Inti Nusantara, 2001). Noviani, Ratna, Jalan Tengah Memahami Iklan, Antara Realitas, Representasi dan Simulasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Sarup, Madan. Identity, Culture and The Postmodern World (Athens: The University of Georgia Press, 1996). Siregar, Ashadi. Menyingkap Media Penyiaran, Membaca Televisi Melihat Radio , (Yogyakarta: LP3Y, 2001). Sumantono. Terperangkap (BanFABETA, 2002) dalam Iklan; Meneropong Imbas Pesan Televisi, 2002, Williamson, Judith. Decoding Advertisements, Ide ology and Meaning in Advertising, 1985, Penerbit: Marion Boyars Publishers Inc., New York. INTERNET : Benhabib, Seyla. From Identity Politics to Social Feminism: A Plea for The Nineties , Sabtu, 1 Juni 2002, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES -yearbook/94_docs/BENHABIB.HTM Hamley, Katherine. Media Use in Identity http://www.aber.ac.uk/media/students/klh9802.html Construction , 24 Sept 2001, Herrmann, Stefan. Do we learn to ‘read’ television like a kind of ‘language’ , Jum”at, 29 Maret 2002, Http://www.aber.ac.uk/media/students/sfh9901.html Kompas-Online. Anak Yang Ketagihan “Nonton” TV , Selasa, http://www.kompas.com/kompas -cetak/0207/16/dikbud/anak20.htm 22 Oktober 2002, Ibrahim, Idi Subandy dan Chaerowaty, Dede L . Dunia Anak di Tengah Limbah Budaya Massa , Selasa, 22 Oktober 2002, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/ 0702/23/0802.htm Stanford Encyclopedia of Philosophy , Identity http://plato.stanford.edu/entries/identity -politics Politics, Sabtu, Suara Pembaruan Daily, Anak-anak dan Televisi, http://www.suarapembaruan.com/News/2001/10/21/Editor/ed02.html 25 3 Social Identity, 24 Sept 2001, http://www.psy.anu.edu.au/social/socident.htm Januari, 2003, April 2002,