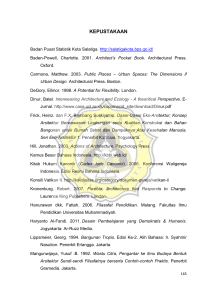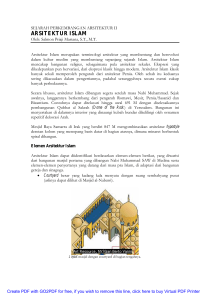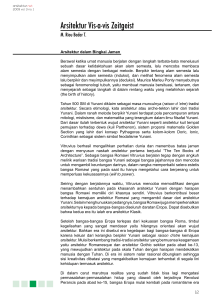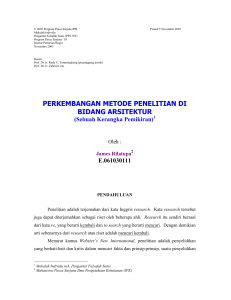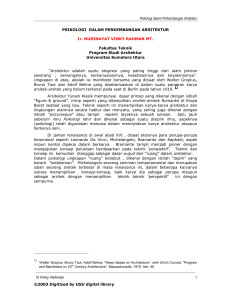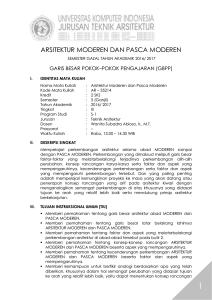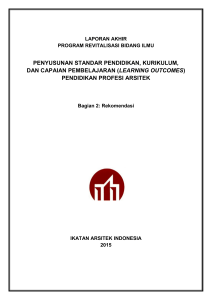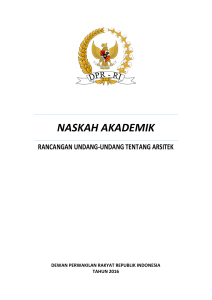ketukangan - arsitekturindonesia.org
advertisement

k e tu k a nga n kesadaran material bawah sadar arsitektural Ketukangan Kesadaran Material, Bawah Sadar Arsitektural KETUKANGAN: KESADARAN MATERIAL, BAWAH SADAR ARSITEKTURAL Modernitas datang di Indonesia dengan wajah penjajah. Sejak itu, sejarah bicara dalam suara sumbang, dengan kaca cembung. Meminjam metafor Pramoedya Ananta Toer, bangsa yang terjajah hidup bagaikan sebuah preparat yang diletakkan dalam “rumah kaca”. Tetapi, perbandingan dengan preparat tidak tepat. Dalam “rumah kaca” itu kita berada dalam dua posisi sekaligus: sebagai yang dipandang dan yang memandang. Dalam memandang ke luar maupun ke dalam, mau tak mau kita membanding-bandingkan diri, laku yang disebut Bennedict Anderson (yang mengutip tokoh nasionalisme Filipina, Jose Rizal,) sebagai "the spectre of comparisons." Dalam Polemik Kebudayaan di tahun 1930-an, dari "rumah kaca" itu, dari "spectre of comparison" itu, ada persoalan "menolak Barat" atau "mengikuti Barat". Sementara itu, yang terjadi hari demi hari adalah praxis yang tidak sepenuhnya mengikuti gagasan mengenai identitas dan tak bisa dibatasi oleh proyek-proyek pengukuhan identitas. Dalam hal ini, arsitektur merupakan contoh yang baik. Usaha memproduksi dan mencipta telah, selalu, dan akan terkait dengan dengan tenaga, ketrampilan, informasi dan bahan yang ada. Dalam kondisi itu, praxis menunjukkan tidak semua hal mengikuti kehendak, menolak, atau mengadopsi modernitas. Ide dan rencana yang dirumuskan dengan sadar pada akhirnya dibentuk oleh proses yang tak bisa diperhitungkan, bahkan sebelumnya tak disadari. Terkait dengan hal itu, kami mau menggaris-bawahi bahwa dalam pengalaman kerja arsitektur Indonesia ada yang bisa kita sebut "the architectural unconscious." Yaitu: "ketukangan". Mengikuti Richard Sennett dalam The Craftsman, “ketukangan”, ditandai oleh komitmen untuk mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. "Ketukangan", bahkan juga "seni" (fine arts) dan juga arsitektur, merupakan hibriditas antara berbagai jenis kerja – tetapi tetap dengan dasar "kesadaran material". Kesadaran material, atau "material conciousness" adalah kesadaran bekerja “melalui” dan “dengan” perkakas yang ada pada kita. Artinya kepekaan kepada tenaga manusia, bahan, lingkungan alam, dan semua yang kongkrit, berubah, dan majemuk. Dalam perjalanan sejarah arsitektur Indonesia yang tak bisa menghidar dari gulungan modernitas, “ketukangan” merupakan jalan alternatif ke arah memanusiakan kembali kerja yang menjadi terasing karena kapitalisme. Kita tahu, dalam kapitalisme, kerja bukanlah kesenangan, melainkan komoditi. Di sinilah ketukangan merupakan jawaban ekonomis, estetis, bahkan etis terhadap materialitas. KETUKANGAN: KESADARAN MATERIAL, BAWAH SADAR ARSITEKTURAL Fundamentals. Absorbing modernity: 1914 – 2014. Tema Venice Architecture Biennale tahun 2014 memaksa kita untuk melihat seratus tahun sejarah arsitektur “kita” dalam “persinggungan”nya dengan modernitas. Pada pengantarnya, Rem Koolhaas meminta tiap peserta pameran untuk menunjukkan, dengan caranya masingmasing, proses terkikisnya “karakter nasional” karena diadopsinya sifat universal sebuah bahasa modern yang melahirkan sebuah repertoar tunggal dari kancah tipologi yang beraneka-ragam. Kita langsung dihadapkan pada beberapa pertanyaan sekaligus. Siapakah “kita” dalam sejarah (arsitektur)? Bagaimana bentuk “persinggungan” dengan modernitas yang terjadi? Dan sebelum bisa menjawab apakah benar modernitas mengikis “karakter (arsitektur) nasional” kita, bukankah harus dijawab lebih dahulu pertanyaan tentang apakah “kita” memiliki “karakter (arsitektur) nasional”? Dan di dasar semua pertanyaan itu, kita harus mencari apa yang “fundamental” dalam perjalanan seratus tahun arsitektur di Indonesia yang berurusan dengan modernitas. Ini sebuah pekerjaan yang tak mudah. * Modernitas datang di Indonesia dengan wajah penjajah. Sejak itu, sejarah bicara dalam suara sumbang, dengan kaca cembung. Meminjam metafor Pramoedya Ananta Toer, bangsa yang terjajah hidup bagaikan sebuah preparat yang diletakkan dalam “rumah kaca”. Tetapi sebenarnya memakai perbandingan dengan preparat tidak tepat. Dalam “rumah kaca” itu kita berada dalam dua posisi sekaligus: sebagai yang dipandang dan yang memandang. Sebagai yang dipandang oleh tatapan kolonial, kita diletakkan seakan-akan dalam kurun waktu yang lain. Meminjam istilah Jonathan Fabian, (dalam Time and the Other) di sini tatapan kolonial melakukan "denial of coevalness", menampik kenyataan bahwa yang dijajah hidup sebaya atau dalam kurun waktu yang sama dengan yang menjajah. Yang terjajah diletakkan sebagai Yang-Lain yang masih hidup di dunia yang lampau: bukan "modern", yang hampir sinonim dengan "baru", melainkan "tradisional," yang maknanya hampir sama dengan "lama", bahkan "terkebelakang". Dalam tatapannya, pemerintah penjajahan juga mereduksi semua anggota masyarakat kolonial ke dalam satuan-satuan yang bisa dikategorikan, dibungkus dan dipisahkan oleh indeks atau label yang ditentukan oleh yang berwenang. Indeks atau label itu seakan-akan merupakan esensi mereka. Tetapi di dalam "rumah kaca", seperti disebut di atas, posisi kita tidak hanya pasif. Kita juga memandang, baik memandang ke luar maupun ke dalam. Dengan kata lain, ada ambiguitas dalam melihat. Karakter kaca yang opasitasnya bisa berubah dari transparansi ke refleksi, tergantung dari intensitas cahaya di kedua sisinya, memungkinkan the ambiguity of seeing itu. Dalam memandang ke luar maupun ke dalam, mau tak mau kita membanding-bandingkan diri. Kita terpukau oleh apa yang disebut Bennedict Anderson (yang mengutip tokoh nasionalisme Filipina, Jose Rizal,) sebagai "the spectre of comparisons." Ketika memandang Indonesia, mau tak mau kita berpikir tentang dunia Barat, dan begitu pula sebaliknya. Anderson (dalam The Spectre of Comparisons) mengambarkannya sebagai "kesadaran ganda yang baru dan resah," a new, restless double-consciousness. Kesadaran kebangsaan (nationhood) bermula dari situ. Tetapi tidak hanya itu. Dalam pukauan "spectre of comparison" itu, juga tumbuh pandangan baru tentang dunia, nilai-nilai, selera, gaya hidup, pola konsumsi. Semua didorong oleh dua kehendak: (1) kehendak mengukuhkan "beda" atau "keunikan diri" (dengan sebutan, misalnya, "karakter nasional") atau sebaliknya (2) kehendak mengadopsi yang "modern", yang "baru", dan meninggalkan yang "lama". Dalam bahasa yang umum dikenal di Indonesia, seperti kita dapatkan dalam Polemik Kebudayaan di tahun 1930-an, dari "rumah kaca" itu, dari "spectre of comparison" itu, ada persoalan "menolak Barat" atau "mengikuti Barat". Kedua kehendak itu sebenarnya sama: keduanya melihat bahwa keduanya bertolak dari pengukuhan identitas. Dengan kata lain: "yang Barat" dan yang "nasional" atau "Timur" diperlakukan sebagai identitas yang sudah transparan dan final. Sementara itu, dalam perjalanan waktu, yang terjadi hari demi hari dari dan di dalam "rumah kaca" adalah praxis yang tidak sepenuhnya mengikuti gagasan mengenai identitas dan tak bisa dibatasi oleh proyek-proyek pengukuhan identitas. Dalam hal ini, arsitektur merupakan contoh yang baik. Di antara harapan dan kecemasan yang jadi ciri penghuni "rumah kaca" – kita bisa menyebutnya sebagai "post-colonial anxiety" – usaha memproduksi dan mencipta telah, selalu, dan akan terkait dengan dengan tenaga, ketrampilan, informasi dan bahan yang ada. Di Indonesia, itu berarti semua hal yang terdapat dalam modus produksi pra-industrial dan industrial (bahkan kemudian juga pasca-industrial) berbareng di satu kurun waktu: adanya tenaga kerja yang surplus, tradisi kerja tangan yang kuat, waktu kerja yang lebih longgar, masih kuatnya kerja kolektif, banyaknya bahan-bahan yang masih langsung diambil dari alam, kuatnya peran perkakas (tools) – tetapi juga diterapkannya manajemen modern, masuknya kapitalisme, dan kemudian, di abad ke-21, teknologi digital. Dalam kondisi itu, praxis justru menunjukkan tidak semua hal mengikuti kehendak, menolak, atau mengadopsi modernitas. Ide dan rencana yang dirumuskan dengan sadar pada akhirnya dibentuk oleh proses yang tak bisa diperhitungkan, bahkan sebelumnya tak disadari. Terkait dengan hal itu, kami mau menggaris-bawahi bahwa dalam pengalaman kerja arsitektur Indonesia ada yang bisa kita sebut "the architectural unconscious." Yaitu: "ketukangan". Analog dengan yang pernah dikatakan Nirwan Dewanto dalam pengantarnya untuk pameran S. Teddy D., bahwa gambar adalah bawah-sadar lukisan, "ketukangan" merupakan bawahsadar arsitektur. Dalam sejarahnya, "ketukangan" – yang merupakan proses kerja para tukang (artisan) – tidak jarang berkembang menjadi "kekriyaan" (craftmanship). Kerja yang dilakukan dengan tubuh dan tangan – yang berbeda dengan kerja mendesain – berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih. Jika kita mengikuti ulasan Richard Sennett dalam The Craftsman, "kekriyaan" atau dalam cakupan yang lebih luas “ketukangan”, ditandai oleh komitmen untuk mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. Artinya "ketukangan" tidak terbatas pada ketrampilan kerja tangan. Meskipun demikian, sependapat dengan Sennett, kita tetap melihat bahwa "ketukangan", bahkan juga "seni" (fine arts) dan juga arsitektur, merupakan campuran (hibriditas) antara berbagai jenis kerja – tetapi tetap dengan dasar "kesadaran material". Kesadaran material, atau "material conciousness" dalam istilah Sennett, adalah kesadaran bekerja “melalui” dan “dengan” perkakas yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang craftsman untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan kepada apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya kepekaan kepada tenaga manusia, bahan, lingkungan alam, dan semua yang konkrit, berubah, dan majemuk. Dalam perjalanan sejarah arsitektur Indonesia yang tak bisa menghindar dari gulungan modernitas, “ketukangan” merupakan jalan alternatif ke arah memanusiakan kembali kerja yang menjadi terasing karena kapitalisme. Kita tahu, dalam kapitalisme, kerja bukanlah kesenangan, melainkan komoditi. Di sinilah ketukangan merupakan jawaban ekonomis, estetis, bahkan etis terhadap materialitas. * Instalasi yang kami desain adalah representasi dari “rumah kaca”, sebuah kritik terhadap konstruksi identitas. Pada bidang-bidang dindingnya akan diproyeksikan bagaimana “ketukangan”, sebuah praxis yang dalam setiap kondisi adalah tanggapan yang kreatif, kadang subversif, terhadap modernitas. Kami mencoba menyajikan kondisi tersebut dalam periodisasi kesejarahan, seperti tema biennale yang berikut, meskipun dalam hal “ketukangan” waktu bersifat relatif, tidak deterministik. * PERIODISASI KESEJARAHAN Arsitek Belanda, Tukang Hindia: 1914-1942 Awal abad ke-20 merupakan periode yang dinamis. Di Eropa berkembang gerakan Arts & Crafts yang merupakan reaksi artistik terhadap desakan industrialisasi yang pesat. Gerakan ini menyarankan keterlibatan penuh para desainer dan artisan terhadap berbagai bentuk karya rancang dan seni. Arsitektur didorong untuk menjadi sebuah gesamtkuntswerk – karya seni total - yang merangkai kegiatan merancang dan perwujudannya dalam satu keutuhan, dari skala gedung hingga perabotan. Gerakan ini masuk ke nusantara bersama dengan arsitek-arsitek Belanda yang berkarya di Hindia Belanda. Mereka – diantaranya P.A.J. Moojen, E. Cuypers, F. Ghijsels, T. Karsten, W.C. Schoemaker – yang datang belakangan ini mengkritik rancangan-rancangan yang langsung diadopsi dari model-model di Eropa dan mempromosikan model-model baru yang dihasilkan dari “sintesa”. Arsitek Henri Maclaine-Pont mempunyai tempat istimewa. Bukan hanya karena wujud karyanya yang menonjol, namun juga karena ia mewakili praktik kritis zamannya. Motivasinya awalnya pragmatis, ia kekurangan tenaga tukang lokal yang trampil yang bisa mewujudkan proyek-proyeknya. Namun karena ia aktif menulis dan meneliti situssitus arkeologi, Maclaine-Pont menemukan bahwa teknik ketukangan lokal pernah mencapai kejayaannya pada masa lampau sehingga ia berkesimpulan bahwa ketukangan lokal pantas “maju” dengan tidak berhenti pada teknik-teknik tradisional dan bahan-bahan lokal, namun juga menguasai ilmu keteknikan modern Eropa dan menghasilkan bentuk-bentuk baru yang “modern” sekaligus “lokal”. Paparan kami menyoroti wujud arsitektur Maclaine-Pont – Aula Barat ITB dan Gereja Puh Sarang – yang merupakan interpretasi bentukan bangunan adat yang dihasilkan lewat eksperimentasi struktur dan konstruksi modern. Ruang-ruang pada kedua bangunan ini adalah hasil dari gagasan arsitektonika yang dapat dipandang sebagai sebuah upaya untuk “membina” dan “menaikkan” kemampuan tukang. Peran dan posisi arsitek yang digagas oleh Maclaine-Pont digambarkan sebagai agen perubahan yang sadar dan percaya diri – sebagai “pembina” yang bekerja di belakang tabir rasionalitas. Bentuk dan ruang arsitekturnya merupakan upaya melampaui apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan dipasang sebagai sebuah tolok akhir yang harus dicapai dalam proses pembangunannya. Monumen-monumen Kecil bagi Bangsa: 1945-1966 Memasuki pertengahan abad ke-20, sejarah jadi saksi bahwa arsitektur berperan sebagai etalase bagi tatanan politik dunia. Negara-bangsa baru bermunculan dan menghendaki berbagai atribut arsitektural untuk melengkapi identitas budaya dan sosial mereka di tengah tatanan dunia modern yang baru. Dalam arsitektur modernis, Sukarno menemukan sebuah solusi model untuk “nation building” dan untuk mengatasi keragaman Indonesia yang “menggelisahkan”. Di masa ini, Indonesia dibayangi disintegrasi wilayah dan secara sosial budaya dihadapkan pada tantangan akan kesatuan bangsa. Sukarno merasa karakter arsitektur modernis yang bersih, terbuka, dinamis, dan netral, dapat berperan sebagai simbol identitas kebangsaan yang baru, lepas dari beban kultural masa lalu dan bayang-bayang kolonialisme. Sukarno membangun berbagai “monumen” dalam bentuk tugu, patung, gedunggedung pemerintahan, infrastruktur jalan, dan stadion. Peran sentral Friedrich Silaban dalam karya-karya monumental era ini (Masjid Istiqlal, Bank Indonesia, dan lain-lain) bisa dilihat dalam perspektif yang berbeda ketika ditinjau dari karyanya yang paling intim: rumahnya sendiri. Berada di pinggir wacana proyek-proyek monumental, rumah Silaban menunjukkan perhatian besar pada tektonika dan ketukangan. Silaban merancang rumahnya hingga ke tiap sudut, diselesaikan dengan pengolahan detail yang prima. Dibangun dengan material yang “modern” pada masanya (1959-1960) – baja, beton bertulang, tegel teraso, serta paduan batu-batu lokal – rumah ini adalah hasil abstraksi dari renungan mengenai hunian dan lokalitas. Posisi arsitek dalam sosok Silaban adalah sebagai seorang yang intelek dan rasional, yang terlibat dalam setiap jengkal karya terbangunnya. Arsitek memprakira beban konstruksi, menentukan tulang beton, mengatur hubungan antar elemen, dan semuanya dilakukan dengan perhitungan lewat teori-teori, rumus-rumus, serta asumsi-asumsi. Tidak dengan coba-coba. Fenomena menarik terjadi pada praxis “tepian”. Kebutuhan akan hunian rakyat pada masa awal kemerdekaan hingga dekade 1970 kebanyakan dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat, lewat tukang-tukang atau aneemer profesional. Mereka adalah para ahli gambar dan bangunan yang memulai karirnya lewat pendidikan menengah pada masa kolonial. Mereka dididik untuk bekerja sebagai asisten arsitek, namun setelah tidak lagi ada arsitek Belanda yang berpraktek di Indonesia, mereka akhirnya maju sebagai arsitek. Banyak bangunan institusional dan rumah tinggal era ini yang menampilkan bentuk dan konstruksi yang unik dan “nakal”; proporsi bangunan yang “aneh”, tiang dan dinding yang miring, lempengan beton tipis yang lebar tanpa penopang, atap-atap unik yang terpancung, dinding-dinding yang kaya akan ornamen dan material, pelat beton lipat, dan lain sebagainya. Arsitektur ini dijuluki “jengki”, mengadopsi sebutan yang sama untuk berbagai hal “baru” yang diasosiasikan dengan “yankee” atau “Amerika”. Termasuk di dalamnya gaya rambut, sepeda, hingga celana. Pada arsitektur ini, ketukangan tampil ke depan dan muncul tanpa beban kultural yang besar. Berbagai bentuk, artikulasi, dan konstruksinya justru seolah lahir dari proses coba-coba ketimbang rencana teliti pada gambar. Melampaui Batas Peran dan Identitas: 1966-1998 Pada dekade 1970, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat terbukanya ekonomi global. Namun Indonesia juga berada dalam pemerintahan yang represif terhadap kebebasan berekspresi. Arus modal, barang, jasa dan manusia memberdayakan masyarakat menengah-atas perkotaan, namun pada saat bersamaan menghasilkan kantongkantong masyarakat yang miskin dan tidak terjangkau pembangunan ekonomi. Bali berkembang kembali menjadi tujuan wisata internasional dan dipromosikan sebagai wisata kultural yang lengkap. Pembangunan hotel-hotel di Bali membangkitkan kembali wacana arsitektur tradisional dan craft dalam “merayakan” identitas ke-Bali-an dalam mendukung industri pariwisatanya. Pengusaha dan seniman mancanegara ikut mempengaruhi perkembangan estetika dan arsitektur hotel pada dekade 1980. Wija Waworuntu, misalnya, merombak sebuah hunian di kawasan Sanur menjadi salah satu hotel butik pertama di Bali, dan mengundang arsitek Srilanka Geoffrey Bawa untuk merancang komplek resort Batujimbar. Hotelier Adrian Zecha memulai jaringan hotel butik elitnya – Amanresorts – di Bali: menawarkan pengalaman “otentik” tinggal di rumah-rumah tradisional Bali dengan pelayanan yang mewah. Efek dari kondisi ini meluas. Kerajinan mengambil posisi sentral dalam arsitektur, bahkan mendominasi tampilan arsitektur rumah tinggal di kota-kota besar. Sentra-sentra kerajinan kayu, batu candi, dan marmer menyediakan berbagai kreasi yang mendukung pasar ini. Seiring dengan “mengeras”-nya identitas Bali, negara juga berperan dalam membentuk kotakkotak identitas baku berdasarkan daerah administrasi provinsi. Sebuah cultural theme-park Taman Mini Indonesia Indah digagas oleh Tien Soeharto untuk mempromosikan hal tersebut. Keragaman kultural Indonesia direduksi menjadi 27 entitas propinsi, disandingkan dengan 27 rumah adat dan 27 pasang pakaian adat. Bangunan-bangunan pemerintahan dan publik juga “dihimbau” untuk merepresentasikan kedaerahannya dengan cara yang serupa. Namun tetap ada praktik-praktik kritis yang berusaha menggugat “stabilitas” tersebut, baik secara estetis maupun etis. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, imam Katolik sekaligus arsitek, berusaha berpihak pada yang termarjinalkan. Di Kali Code, Yogyakarta, Y.B. Mangunwijaya melakukan penataan permukiman di bantaran sungai yang telah lama dianggap pemerintah sebagai sarang masalah sosial yang perlu diberantas. Mangunwijaya melakukan pendampingan sosial dan melakukan perbaikan fasilitas lingkungan. Arsitektur perkampungan tersebut dibentuk oleh upaya konstruksi swadaya dengan bimbingan dari sang arsitek. Pada Peziarahan Sendangsono dan Wisma Kuwera, Mangunwijaya mempekerjakan dan membina tukang-tukang untuk berkreasi dan mengekspresikan kemampuan masing-masing dengan material yang mudah diperoleh. Mangunwijaya memberikan ruang gerak bagi ekspresi ketukangan, sekaligus merintis peran arsitek sebagai penggerak pengembangan ketrampilan dan pelatihan konstruksi bagi para tukang. Arsitek jadi “pemimpin” dengan gagasan dan strategi politik tertentu, sementara arsitektur (bentuk, ruang, material, dan konstruksi) “hanya” sebagai media. Sementara itu, Yuswadi Saliya (bersama Kiki Dharmawan dalam Atelier 6) melakukan pendekatan modernis tapi tetap peka dengan konteks lingkungan dan tantangan iklim pada proyek Hilton Executive Club. Proyek yang berangkat dari modul ‘segitiga’ yang digubah melalui permainan skala dan proporsi menjadi 2 bentukan massa dan ruang seperti atap Tajug besar. Proyek ini juga mulai menggunakan teknologi beton secara maksimal. Koridorkoridor yang dinaungi oleh kantilever pergola beton adalah ekspresi kecanggihan teknologi dan ketukangan pada masanya. Ragam Peran dan Peluang: 1998-2014 Indonesia, juga dunia, kini jauh lebih terbuka dan cair. Proses yang lebih cair dan dinamik terjadi pada masyarakat menengah atas perkotaan yang menjadi pasar terluas bagi praktik arsitektur kontemporer di Indonesia. Bagi kebanyakan arsitek Indonesia, merancang rumah tinggal pribadi masih merupakan “makanan pokok”. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, muncul praktik-praktik yang berpengaruh dan memberikan dampak yang cukup luas dalam industri arsitektur pada segmen ini. Arsitek senior Tan Tjiang Ay merupakan tokoh yang telah menentukan patokan kualitas yang tinggi. Karya-karyanya selalu sederhana, namun cermat, teliti, dan sangat disiplin dalam memperlakukan bentuk, ruang, dan elemen-elemen arsitektural. Karya-karyanya memberi perlindungan terhadap hujan, matahari, dan ketidaknyamanan lain dengan cara yang tidak berlebihan. Proporsi ruang-ruang dan elemen-elemennya ditimbang dengan cermat. Materialmaterial yang berbeda ditampilkan tidak lebur dan tetap hadir sebagai instalasi – mencerminkan kerja sistematik dari para tukangnya. Meskipun “sederhana”, arsitektur Tan Tjiang Ay mensyaratkan keterlibatan sekumpulan ahli mumpuni, mulai dari kontraktor, tukang batu, tukang dinding, tukang aci, tukang kayu, tukang cor beton, tukang besi, tukang pasang keramik, tukang furniture. Tan Tjiang Ay telah memberikan tolok ukur baru pada kualitas ketukangan. Pada konteks layanan jasa yang sama, ada beberapa upaya untuk mengekplorasi material dan merangkainya dengan cara unik sehingga dapat diwujudkan dengan baik meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kualitas ruang yang hadir ditentukan oleh ekspresi bahanbahan dan tektonika yang digunakan. Contohnya Le Bo Ye (Andra Matin) dan Rumah Baja Wisnu (Ahmad Djuhara). Pada beberapa kesempatan lain – di mana anggaran tidak seketat pada kasus sebelumnya – kebebasan diberikan pada tukang dengan arahan arsitek untuk mengolah material lokal, termasuk bahan/elemen bangunan bekas, sehingga tampil unik dan memberikan ciri khas bagi proyek-proyek tersebut dan turut menentukan kualitas ruang yang baru, diantaranya: Potato Head, Bali dan Rumah Agus Suwage (Andra Matin) dan Rumah Setiabudi (Adi Purnomo). Dekade pertama di milenium baru juga merupakan dekade penuh gejolak dan bencana. Beberapa daerah di Indonesia mengalami runtutan bencana yang dampaknya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Gempa dan tsunami di Aceh (2004), gempa di Padang, Sumatera Barat (2009), gempa di Yogyakarta (2009), letusan Merapi (2010), serta berbagai bencana alam dan lingkungan lainnya. Hal ini menyadarkan kembali masyarakat Indonesia bahwa kita membutuhkan ketahanan sosial yang baik untuk dapat menghadapi bencana yang senantiasa dapat hadir. Sebuah pendekatan yang menarik ditampilkan lewat proses pembangunan kembali dusun Ngibikan, Bantul, Yogyakarta yang melibatkan mandor Maryoto, dengan bantuan arsitek Eko Prawoto. Pada kasus ini peran arsitek berada berdampingan dengan masyarakat pengguna dan pelakunya. Eko Prawoto menawarkan sebuah sistem kuda-kuda limasan sederhana tahan gempa, yang mudah dikerjakan. Kuda-kuda ini diperuntukkan sebagai struktur utama bagi rumah-rumah permanen baru sebagai pengganti rumah-rumah yang rusak. Setelah bersama-sama mendata kerusakan dan kerugian, masyarakat Ngibikan juga bersama-sama menghitung jumlah material yang bisa digunakan kembali maupun yang harus didatangkan, serta tenaga kerja yang mereka miliki. Bermodalkan sistem yang disepakati mereka mulai membangun kembali rumahnya tanpa dukungan sama sekali dari pihak luar. Kisah sukses ini menyadarkan banyak pihak bahwa ketahanan sosial masyarakat terhadap bencana sebenarnya bisa dibangun tanpa biaya yang mahal dan tanpa banyak campur tangan dari pihak luar. Pada kasus ini, arsitek dan arsitektur justru memberikan banyak kontribusi ketika memberikan ruang dan takaran yang tepat pada sebuah proses sosial masyarakat. Ketika area-area terpencil juga turut berkembang, ada kekhawatiran bahwa akan banyak kearifan, pengetahuan, serta ketrampilan lokal yang akan memudar. Sebuah upaya yang sangat unik telah dilakukan sekelompok arsitek dalam program Rumah Asuh. Rumah Asuh berperan bukan sebagai perancang dan perencana, namun justru berperan sebagai perekam dan penghubung donatur dengan masyarakat adat serta instansi dan tokoh-tokoh lokal terkait untuk menyatukan upaya dalam membangun kembali rumah-rumah adat. Kesulitan dana, kelangkaan material, ketiadaan tenaga ahli diupayakan oleh advokasi Rumah Asuh sehingga tradisi membangun dan ketukangan lokal dapat dilanjutkan. Upaya untuk merespon isu-isu lingkungan dilakukan dengan mengeksplorasi konstruksi dan melalui manajemen lingkungan hidup. Paulus Mintarga, arsitek yang juga kontraktor, mengembangkan dua propertinya untuk dijadikan workshop dan showroom kreatif Rempah Rumah Karya dan penginapan Rumah Turi di Solo. Upaya lain juga dilakukan dengan menggunakan kembali material (seperti bambu) yang sudah ada namun dengan cara dan kesadaran akan keberlanjutan (dengan menghitung dan membandingkan embodied energy, biaya persiapan, konstruksi serta biaya-biaya lingkungan). Demonstrasi yang menarik telah dilakukan pada OBI Eco Campus Jatiluhur (Andry Widyowijatnoko), Green School (PT Bambu), Gereja Bambu (E. Pradipto), Rumah di Tanah Teduh (Adi Purnomo). RENCANA ANGGARAN BIAYA VENICE ARCHITECTURE BIENNALE A. ANGGARAN BIAYA RUMAH KACA No Keterangan B. ANGGARAN BIAYA PROYEKTOR Jumlah Harga per Unit Total Harga I Pekerjaan Baja 1 Panggung IWF 200 / Koridor No Keterangan 1 Projector 500,00 m2 975.000 487.500.000 Jenis Panasonic 2 Projector Mount Balok Baja Tepi Kolom 3 Dataton Watchpax ++ Besi Balok Anak/Siku 4 Accessories Cabling, Power, Switcher, etc 170,00 m2 600.000 102.000.000 3 Mur Baut/Skrup 1,00 ls 30.000.000 30.000.000 4 Zinkromat + Cat Hitam Naja 1,00 ls 30.000.000 30.000.000 II Pekerjaan Kaca Kaca Area Prologue (I Glass) - Smart 1 Glass 43,00 m2 25.000.000 1.075.000.000 2 Kaca 3x2,4 m tebal 19 mm 30,00 unit 36.000.000 1.080.000.000 Kaca 2x2,4 m tebal 19 mm 10,00 unit 25.000.000 250.000.000 264,00 m2 4.000.000 1.056.000.000 3 Stiker Auropluss Canon REALiS WUX400ST 4000 lumens Panasonic PT-RW430UK 500,00 m2 300.000 1,00 ls 30.000.000 30.000.000 3 Cat Baja Lantai / Floor Paint 170,00 m2 800.000 136.000.000 150.000.000 1,00 ls 60.000.000 60.000.000 1,00 ls 20.000.000 20.000.000 1 Manpower 30 hari (15 orang) 1,00 ls 150.000.000 150.000.000 2 Uninstall Manpower 10 hari (12 orang) 1,00 ls 60.000.000 IV Pekerjaan Instalasi di Site Pekerjaan Instalasi Baja Pekerjaan Instalasi Kaca 60.000.000 Rp4.716.500.000 http://www.projectorcentral.com/CanonREALiS_WUX400ST.htm http://www.projectorcentral.com/Panaso nic-PT-RW430UK.htm Panasonic Short Throw lens Panasonic PT-DZ770UK* Panasonic Short Throw lens 1 Plastik + Plywood 3 mm di cat hitam Aksesoris Perkuatan Kaca , Ketel - Mur 2 Baut / Pelat dsb TOTAL 500 22.500 48 2.300 110.400 1 20.000 USD 4000 lumens III Pekerjaan Lain-lain 4 Biaya y Peralatan g p dan Alat Bantug 5 Kontainer 5.500 45 247.500 20.000 USD 400.400 Pilihan Proyektor 7000 lumens Total Harga 45 TOTAL Pelat Stiffener 2 Pelat Baja Tebal 3 mm Jumlah Harga per Unit http://www.projectorcentral.com/Panaso nic-PT-RW430UK.htm *model tahun 2012 ketersediaan mungkin terbatas 6.900 5.500 2.000 http://www.projectorcentral.com/Panaso nic-PT-DZ770UK.htm 17.100 2.000 JADWAL KERJA KURATOR VENICE ARCHITECTURE BIENNALE RINCIAN SUSUNAN KERJA Rekrutmen asisten peneliti,asisten grafis, tim video fotografi Riset materi Revisi/ proses kelengkapan rancangan instalasi Revisi/ proses kelengkapan RAB Proses administrasi kontrak kerja & berbagai pemesanan materi Revisi/ proses kelengkapan rancangan instalasi Persiapan produksi video Penyusunan program-program kegiatan tambahan Persiapan produksi video Penyusunan brosur, leaflet, dan buku program Dokumentasi video (Jakarta) Rencana instalasi final Dokumentasi video (Bandung) Dokumentasi video (Yogyakarta) Editing video Pendekatan dengan pihak panitia untuk penyelarasan teknis Editing akhir video Pembentukan tim advance dan koordinasi dengan pihak panitia Biennale/ event organizer Penyelarasan akhir brosur, leaflet, dan buku program Penyelarasan akhir teknis lapangan Tim advance melakukan koordinasi dengan pihak panitia Biennale/ event organizer untuk persiapan Proses pembangunan instalasi Proses pencetakkan brosur, leaflet, dan buku program Proses pemasangan perangkat elektronik Penyelarasan akhir video Penyelenggaraan Biennale Pembongkaran instalasi Pengiriman barang-barang ke Indonesia Penerimaan barang-barang di Indonesia 2013 September Oktober November 2014 Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli-November Desember