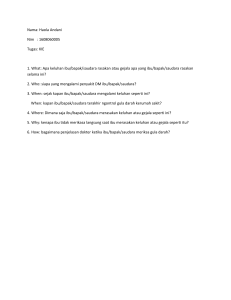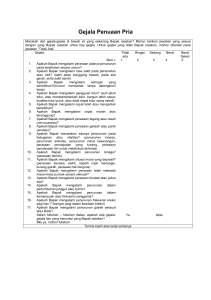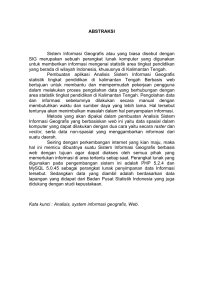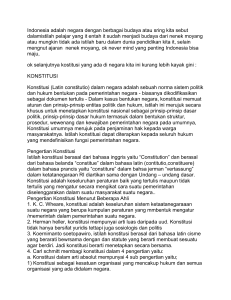SOSIOLOGI - FISIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET Diskusi Publik
advertisement

SOSIOLOGI - FISIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET Diskusi Publik, Solo : The Spirit of Java ? Kentingan, 21 Desember 2010 KOTA (SOLO), IDENTITAS, DAN MULTIKULTURALISME Halim HD : [email protected] Page - 1 KOTA DAN PROSES KEBERAGAMAN: Pada dasarnya, dalam rentang sejarah sosial perkotaan di manapun juga, khususnya di wilayah geografi nusantara, sebuah kota tidak memiliki identitas tunggal. Kota sebagai ruang sosial, ekonomi, senibudaya, politik merupakan suatu ruang di mana siapa saja bisa bertemu dan mempertemukan tatanan nilai yang dibawanya. Dan di dalam sebuah kota pula kita mendapat dan menemukan berbagai sistem nilai sosial, ekonomi, senibudaya, politik yang satu dengan lainnya saling merumuskan kembali: menyusun suatu tatanan baru yang sesuai dengan kebutuhan warga yang tinggal dan menghidupi ruang kehidupan tata kota. Dengan kata lain, sebuah kota juga memiliki kemungkinan dan bahkan secara nyata menjadi melting pot: masing- masing tatanan nilai yang diusung oleh warga dengan latar latar sosialnya secara kompromis dan dialogis melakukan pelumatan. Dan dengan proses itu pula maka tatanan baru, sejenis tradisi baru ter/dibentuk secara bersama-sama. Dalam proses pembentukan tatanan baru, tradisi baru itu, maka konsekuensi logisnya adalah suatu bentukan yang memiliki keberagaman nilai dan perspektif. Dan yang terpenting lagi, sesungguhnyalah suatu ‘tradisi’ dalam ruang sosial di manapun juga senantiasa terbuka; dan atau dipaksa terbuka oleh berbagai intreraksi dan pengaruh yang datang dari wilayah kebudayaan lainnya. Kondisi ini, tentu saja merupakan suatu tuntutan kebutuhan dari warganya yang menyadari benar bahwa suatu jaman memang membutuhkan hal-hal yang baru. Maka konsekuensi logis lainnya yang bisa kita rasakan dan membutuhkan perhatian, yakni masalah konservasi dan eksperimentasi: menjaga, memelihara, nguri-uri tradisi dan berbagai khasanah kebudayaan yang merupakan tugas warga dan pengelola kota, yang juga disertasi oleh proses eksperimentasi ke arah pencarian nilai serta tatanan baru. Dalam kaitan dengan eksperimentasi ini, sebagaimana karakter tata ruang perkotaan kita bisa menganggapnya sebagai suatu ruang laboratorium kehidupan warga dalam berbagai seginya. Dalam konteks inilah maka salah satu karakter lain dari tata ruang perkotaan bersifat mengalir, dan di sana pulalah warganya dengan kapasitasnya sebagai ‘perantau-nilai’ melakukan penanaman dan pencarian melalui pertemuan dan dialog kebudayaan. Lihatlah dan rasakan tatanan nilai dunia boga (kulineri), bakso, bakmi, nasi goreng, snack, minuman dengan berbagai jenis dan rasa; dan saksikan dengan teliti tata Page - 2 busana yang digunakan oleh masing-masing warga; amati dengan jeli tata pergaulan antar warga, etiket dan etika relasi sosial yang setiap harinya diterapkan oleh warga. Singkat kata, semua yang kita rasakan, kita gunakan dan kita saksikan sesungguhnya suatu bentukan (konstruksi) sosial dan sejarah. Dan sebagai bentukan sosial dan sejarah, sistem nilai itu bukanlah sesuatu yang ‘netral’. Artinya, ketika warga kota membentuk tatanan dalam proses yang panjang melalui saling pemahaman dan di antara dialog serta diskusi dan friksi yang terjadi dalam proses ‘tawar menawar’, di situ kita menyaksikan suatu bentukan kebutuhan. Dan jika kita bicara tentang bentukan atau konstruksi kebutuhan, berarti kita bicara tentang bukan hanya kemau-an atau ke- ingin-an (want), tapi yang terpenting niat (need) untuk memahami jaman yang karakternya membutuhkan penafsiran dan pelacakan secara berkesinambungan. Singkat kata, dengan kata lain, sesungguhnyalah bahwa sejarah sosial perkotaan juga dibentuk oleh kebutuhan warga. Dari perspektif inilah perlu kita tegaskan, bahwa sejarah bukan hanya milik elite, juga bukan hanya dibentuk dan dimiliki oleh mereka yang berada di puncak struktur piramidal. Melalui pemahaman tata ruang kota yang menjadi wilayah di mana berbagai tatanan nilai yang dibawa oleh setiap warga dan bertemu, berdialog di dalam tata ruang publik perkotaan, di situ pula sesungguhnya seluruh tatanan nilai kebudayaan dalam berbagai seginya, meminjam konsep Koentjaraningrat – bahasa, tehnologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, organisasi, sistem politik dan kesenian - dibentuk secara bersama-sama. Saksikan dan dengarkan jenis musik keroncong yang sangat beragam, seperti juga sistem karawitan, atau jenis seni pertunjukan lainya seperti wayang orang, ketoprak, sandiwara atau teater, sebagaimana juga tatanan sistem politik yang dari suatu jaman ke jaman diubah dan disesuaikan menurut kebutuhan warga kota. Contoh paling konkrit adalah proses demokratisasi sebagai proses yang secara terus-menerus membutuhkan pengembangan infra struktur sosial dan berbagai perangkat hukum lainnya, agar kondisi demokratis benar-benar dirasakan oleh warga. Dari beberapa contoh kecil yang kita saksikan pada setiap harinya, maka ada sesuatu yang penting yang perlu kita renungkan secara mendalam, agar kita tidak terperosok ke dalam sikap dan perspektif chauvinism yang menciptakan sejenis ethnonasionalism lokal yang bisa memberangus khasanah atau cara pandang lainnya. Page - 3 Renungan yang senantiasa perlu dan mesti kita terapkan, uji dan selalu kita lacak ke dalam pengalaman, memori sosial serta pelacakan ke dalam rentang sejarah perkotaan kita, yakni – kembali ingin saya tegaskan – bahwa sebuah kota tak memiliki identitas tunggal. Konsekuensi logis dari perspektif ini, juga ingin mengajak ke dalam permenungan lainnya, bahwa tak ada yang asli, original, dalam seluruh tatanan sistem nilai serta wujud kebudayaan dan kehidupan yang kita alami dan rasakan. Singkat kata, kita mestilah mengikis sikap dan cara berpikir hegemonic yang sentralistik, centering, yang senantiasa mengagung-agungkan ke-asli-an dan ke-tunggal-an sistem nilai. Perangkap sistem hegemonic yang sentralistik itu kerap membentuk cara pandang warga ke dalam sikap chauvinistic yang menganggap suku atau kebudayaannya yang paling ‘adiluhung’, yang bisa dan dapat meremehkan sikap dan cara pandang warga lainnya. Selama ini kita ter/dibelenggu dan dikungkung oleh cara perspektif hegemonic yang ingin menyeragamkan cara pandang dan sikap hidup melalui praktek-praktek hegemonic yang mengikis proses demokratisasi di dalam kehidupan sosial-politik warga melalui penyeragaman. DE-TRADISIONALISASI: Dalam konteks masakini pula, kita sering mendengar tentang penekanan kepada suatu ‘identitas’ dari suatu wilayah, suku atau etnis, yang nampaknya hal ini berkaitan proses global culture, kebudayaan global, yang datang dari belahan negeri-negeri industri, yang dengannya seiring pula mendesakan suatu sistem politik ekonomi yang bersifat liberal, yang kita kenal dengan neo-liberalism. Dengan kata lain, sesungguhnya sistem, bentuk dan proses global culture memiliki kemiripan – dengan tambahan kecanggihan dalam berbagai seginya – dengan imperium kebudayaan yang oleh kalangan nasionalis disebut ‘neo imperialism’ yang beriringan dengan ‘neo-capitalism’. Dalam suatu cengkeraman imperium kebudayaan yang didasarkan kepada sistem tehnologi industri yang canggih dan dibekingi politik ekonomi neo-liberal, maka yang kita saksikan adalah berbagai bentuk proses ekonomisasi seluruh nilai-nilai. Secara praktis, seluruh sistem nilai kebudayaan menjadi komoditas. Dunia pariwisata, tourism, pada prakteknya adalah salah satu industri kebudayaan yang secara konkrit menjadikan nilainilai tradisi, kebudayaan ke dalam perspektif komodifikasi: semuanya diperjualbelikan. Page - 4 Dalam kondisi dan posisi seperti itulah kita menyaksikan berbagai jenis khasanah dan sistem nilai tradisi digerus oleh global culture. De-tradisionalisasi terjadi diberbagai segi kehidupan masyarakat. Seluruh tatanan sistem nilai yang ada bukan hanya mengalami keguncangan. Tapi lebih dari itu, mengalami perubahan secara mendasar. Marilah kita ambil contoh, apa yang kita anggap sebagai konsep laku dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Jawa seperti alon-alon waton kelakon, kini bubar, dan banyak orang Jawa yang tak lagi bisa sabar, hidup kepontal-pontal dan cenderung beringas. Jalan raya, adalah contoh yang paling konkrit, dan ditambah lagi oleh begitu banyak konflik horisontal bukan hanya karena kesenjangan sosial ekonomi yang kian melebar, tapi juga kapasitas silaturahim, dan dialog kian menipis dan bahkan sirna. Dalam konteks ini nampaknya politik identitas yang didengung-dengungkan berkaitan dengan kondisi, posisi dan fungsi kehidupan masyarakat beserta tradisinya yang kian tergerus oleh proses kebudayaan global, dan berusaha untuk mempertahankan diri. Namun kita perlu kiranya bertanya dan bahkan melakukan gugatan secara mendasar: dapat dan bisakah proses menahan laju derasnya de-tradisionalisasi, membendung global culture, hanya melalui suatu politik identitas, yang bahkan jika kita telusuri secara teliti dan jeli nampak terasa cenderung sloganistik, dan bahkan justeru dengan politik identitas itu pula kita ter/di-perangkap ke dalam sikap chauvinism yang memunculkan ethnonationalism yang bersifat kanibal? Saya ingin kembali menegaskan, bahwa kondisi kehidupan di dalam masyarakat kita sejak ideologi dan politik pembangunan diterapkan di negeri ini, dan tak pernah adanya praktek-praktek keadilan sosial di dalam berbagai segi kehidupan, seperti sosbudpolek, di situ pula sesungguhnya keguncangan akar nilai-nilai tradisi kita mengalami pengeroposan. Sebab, seperti kita ketahui, tepa salira, urip sing samadya misalnya sebagai contoh – dan banyak lagi contoh lainnya – dan semua ungkapan yang filosofis yang memiliki kandungan nilai etika dan moral yang menjadi tuntunan dan pegangan warga mengalami keguncangan dan bahkan bubar oleh kesewenang-wenangan sistem pembangunan yang tak peduli kepada inner space, suara paling dalam, ruang batin warga. Obyektifikasi warga dalam proses pembangunan pula yang membuat seluruh tatanan nilai dan sistem yang secara praktis semula jadi pegangan, meluntur dan warga – yang sesungguhnya subyek – menjadi obyek, dan dijejalkan oleh berbagai instruksi. Page - 5 Proses dan kondisi yang jauh dari rasa ke-adil-an inilah yang membuat warga kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, termasuk di antaranya kehilangan orientasi kepada elite yang dalam perspektif tradisi menjadi panutan beserta sistem nilainya. Dalam konteks yang lebih luas, kita bisa melacak kepada persoalan dari masalah ketidak adilan sosial yang kian jauh dari harapan, pada sisi lainnya, dalam kaitan dengan ideologi dan politik pembangunan itu, nampak secara kasat mata bahwa pengelola negeri ini tak memiliki sama sekali bukan hanya political will dalam kehidupan senibudaya, tapi juga tiadanya cultural will yang secara nyata bisa dijadikan sebagai pegangan dalam praktek-praktek kehidupan. Kasus penghancuran ruang publik, dan pembabatan pepohonan yang berusia bukan hanya puluhan tapi seratusan tahun serta dijadikannya ruang-ruang publik (public space) sebagai komoditas, misalnya dalam periode Walikota Hartomo dan beberapa Walkot berikutnya menjadi bukti dari praktek politik ekonomi yang jauh dari kebutuhan warga. Dan bahkan warga diasingkan dari berbagai keputusan penting yang menyangkut hajat hidup mereka. Dengan kata lain, dari memori sosial itu, kita merasakan benar bahwa tiadanya political & cultural will adalah juga berarti ketiadaan komitmen dan moral courageous pemerintah pusat dan pengelola kota : tiadanya keberpihakan kepada warga sebagai produsen, pengusung-pengemban tatanan nilai di dalam kehidupan perkotaan. Dan pada praktek sosial ekonomilah yang kita rasakan betapa ketiadaan keberpihakan pengelola kota kepada warga kebanyakan. Sebuah kota yang ‘berhasil’ dan ‘dianggap maju’ adalah kota yang memiliki banyak mall. Praktek politik yang keblinger seperti inilah yang kita rasakan selama beberapa dekade terakhir. Sesungguhnya, jika kita bicara tentang kondisi rapuh yang penuh dengan ketegangan dan kecurigaan, paranoia sosial, dan lalu ingatan kita melongok kepada isu dan pola historis yang disebut dalam bentuk ‘sumbu pendek’ dalam konteks kota Solo, suatu gejolak dan kerusuhan sosial yang akan selalu ter/di-ulang, maka kita bisa menyatakan bahwa elite pemerintah dan pengelola kotalah yang sesungguhnya yang menciptakannya. KONFEDERASI JARINGAN SOSIAL: Kota Solo yang secara streotipe dianggap sebagai ‘pusat tradisi’, yang dalam perjalanan sejarah sosialnya telah membuktikan sebagai bagian dari khasanah kebudayaan dan berbagai segi tatanan nilainya yang telah memperkaya kehidupan Page - 6 kebudayaan di nusantara. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa Solo sebagai sebuah laboratorium senibudaya, dan di situ pula kita menyaksikan terdapatnya berbagai institusi atau lembaga pendidikan tradisi dan modern secara formal dan informal, seperti SMKI, ISI, dan berbagai jurusan kesenian di UNS serta sanggar-sanggar yang telah ikut memberikan kontribusi di dalam pembentukan ‘identitas’ kota Solo. Dari pengalaman dan pengamatan sehari-hari yang kita temukan, kita juga menyaksikan munculnya kerapuhan yang di dalam kehidupan kemasyarakatan di mana kondisi kehidupan tatanan tradisi mengalami keguncangan, atau lebih tepatnya krisis seperti yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Krisis nilai dan tatanan dialami bukan hanya oleh mereka yang kini kita anggap kaum remaja dan kaum muda, misalnya dalam tatanan etika sosial. Tapi juga oleh kalangan kaum tua. Tudingan kepada kaum remaja-muda yang dianggap mengalami krisis nilai itu, sesungguhnya suatu sikap pengkambinghitaman. Sebab, jika kita telusuri secara teliti, krisis ini bermula dari sistem pendidikan dan relasi sosial di dalam kehidupan kekeluargaan akibat kian derasnya sumber informasi tehnologi canggih yang merasuk ke dalam ruang-ruang personal dan sosial. Singkat kata, terdapat kesenjangan nilai-nilai antara kaum tua dan kaum remajamuda, dan sementara itu kian menyusutnya ruang-ruang publik akibat komodifikasi, yang menyusutkan ruang dialog, dan ditambah oleh sistem relasi yang bersifat patronase, yang pada praktek konkritnya sudah kehilangan trust, dan hanya bermain pada wilayah interest politik praktis yang bersifat transaksional. Dalam konteks itulah perlu bagi kita menelusuri kembali sejarah kehidupan sosial pembentukan kota Solo yang pada dasarnya dibingkai dan diisi oleh jaringan sosial yang datang dari wilayah perkampungan dan pedesaan. Secara hipotetis, saya merasa yakin bahwa nilai-nilai keberagaman, pluralitas yang ada di dalam kehidupan kota Solo dibentuk oleh warga dan nlai-nilai yang dianggap ‘adiluhung’ sesungguhnya berangkat dari kebutuhan warga di dalam memahami dan mengembangkan orientasi jamannya: perumusan cita-cita dan harapan beserta praktek-praktek relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang, yang di dasarkan kepada kesadaran masa lampaunya. Hipotesa ini ingin mengajak kepada siapa saja bahwa pembentukan sejarah beserta sistem nilainya mestilah datang dari sumber dan akar kehidupannya: desa dan Page - 7 kampung. Dan dengan perspektif itu pula, maka penguatan serta partisipasi warga di dalam proses pemeliharaan, pengembangan serta pemahaman pencarian nilai-nilai untuk masa yang akan datang harus menjadi sumber utama. Melalui partisipasi jaringan sosial desa-kampung itulah pemahaman dan pengembangan keberagaman sebuah kota akan bisa dijaga dan dilanjutkan perkembangannya pada masa yang akan datang. Maka salah satu konsekuensi logis secara politis, cultural dan sosial ekonomi bagi pengelola kota Solo adalah bagaimana merenovasi, menumbuhkan dan mengembangkan ruang-ruang publik pedesaan dan perkampungan. Akar keberagaman serta pewarisan tatanan nilai di dalam kehidupan kebudayaan dan tradisi kita pada dasarnya bersumber dari ruang keluarga dan ruang publik di pedesaan dan perkampungan. Ruang-ruang publik, seperti latar amba di kampung dan desa menjadi ruang sosial di mana warga satu dengan lainnya saling mengenal dan saling berbagi serta berinteraksi melalui latar belakang sejarah keluarga serta sejarah sosial masing-masing. Dan melalui ruang public itu pulalah dialog kebudayaan antar warga dibentuk dan dikembangkan. Pada tingkat prakteke yang paling konkrit, misalnya dalam seni pertunjukan serta berbagai jenis dan bentuk ritual kampung dan desa bermula dari ruang publik dan jalinan jaringan sosial antar keluarga. Maka jika pengelola kota Solo ingin mempertahankan, mengembangkan ‘identitas’ kota yang sejak beberapa dekade ini mengalami krisis, dibutuhkan political & cultural will yang benar-benar berangkat dari inner space wilayah pedesaan dan perkampungan. Jika tidak, kota Solo akan selalu terperangkap ke dalam pola historis ‘sumbu pendek’ bentukan militer dan mereka yang selalu memancing di air keruh kesenjangan sosial ekonomi melalui isu rasis. Dan pada sisi lainnya kota akan menjadi seragam mirip dengan kota-kota lainnya dan menjadi tong sampah global culture, jika pengelola kota Solo tidak menyadari sejarah sosial pedesaan dan perkampungan yang memiliki ciri khas dan karakter perdikan: kapasitas ke-unik-an, ke-otentik-an yang datang dari kebutuhan warga dalam menjawab tantangan jaman. -o0oHalim HD. – Penulis & Networker Kebudayaan. Page - 8