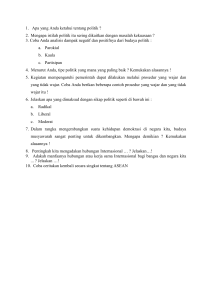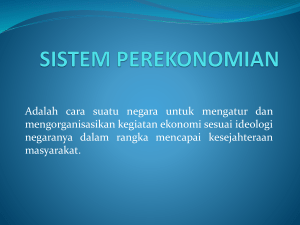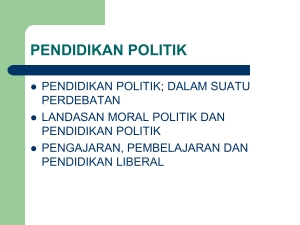Pram, Sastra Kiri dan Pembebasan
advertisement

MODERASI ISLAM DAN PEMBELAJARAN KERUKUNAN Firdaus Muhammad1 Abstract: The Indonesian pluralism multicultural is a strategy which is used, read and appreciated to the differences and variety. The substantive of multicultural education is not free value. The suggestion (book of Allah) is to function as real power from the multicultural Islam education. In other wards, commitment strengthen Islam moderation, awared or no, is faced to reality which appear extremism fundamentalism which is productive now. This accure because of be rotten (hollow) economic and political system which is not sure or certain. This are aspecs which need to be collective awareness of muslim’s moderation after Cak Nur and Gus Dur. The end, the multicultural is not free from the value of God and is to be proof of servant to Allah who is great of educater. Key Words: Islamic Moderation, Multicultural, Education Pendahuluan Dalam peta keberagamaan di Indonesia, diwarnai menggeliatnya arus radikalisme dan liberalisme, acapkali menumbuhkan kegamangan beragama. Sehingga, upaya mengetengahkan pandangan muslim secara moderat menjadi niscaya, saat menguatnya arus pemikiran Islam radikal dan liberal yang terus bergulat dalam altar diskursus berkepanjangan itu. Di tengah pergulatan kutub pemikiran tersebut, diniscayakan kehadiran pemikiran yang moderat dalam bingkai perspektif moderasi Islam, terutama dalam merentang ihwal perdamaian dan toleransi di tengah menguatnya tindakan intoleransi. Menebarkan moderasi Islam dalam konteks keindonesiaan, kian relevan di tengah konstruksi sosial masyarakat yang acap intoleransi, tepatnya sebagai ancaman serius atas toleransi yang telah dipancangkan dalam konstruk keberagamaan di tengah pluralisme dan multikulturalisme masyarakat. Sikap moderasi menjadi penting bagi seorang muslim, sebagai kaum mayoritas sejatinya dapat memberi keteladanan bagi kaum minoritas dalam menata bangunan toleransi. Visi moderasi tidak terlepas dari obsesi meneguhkan komitmen terhadap kemaslahatan umat seiring proses demokrasi 1 Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. E-mail: [email protected]. yang kian membaik. Komitmen meneguhkan moderasi Islam, disadari atau tidak, kini diperhadapkan pada realitas menguatnya arus eksteremisme kaum fundamentalis yang kian subur, akibat keroposnya sistem perekonomian dan politik yang tak menentu. Aspek inilah yang perlu menjadi kesadaran kolektif muslim moderat pasca Cak Nur dan Gus Dur. Toleransi Antarumat Beragama 1. Moderasi Islam Dalam perspektif moderasi muslim moderat, sejumput persoalan di atas ihwal realitas keberagamaan yang terkait toleransi, terorisme dan asa terhadap perdamaian itu dipandang menjadi agenda yang mengharuskan adanya resonansi kearifan intelektual muslim moderat. Sedikitnya, tiga persoalan umat yang meniscayakan perspektif moderasi muslim moderat sebagai implementasi komitmennya dalam menebarkan pandangan yang memberi solusi. Pertama, membangun benteng toleransi. Toleransi kembali diteguhkan sebagai membendung tindakan intoleransi, guna menyemai nilai-nilai pluralisme. Spirit pandangan ini berpijak pada kontestasi bahwa toleransi dan intoleransi sebagai fakta sejarah, yang kini tetap menjadi wajah keberagamaan. Karenanya, menjadi keniscayaan meneguhkan konstruksi sosial dalam merawat toleransi, meminimalisir intoleransi dalam konteks menjaga kemaslahatan keumatan dan kebangsaan sekaligus. Demikian pentingnya toleransi diusung sebagai kuasa nilai, dalam perspektif moderasi Islam membidik relasi toleransi dan demokrasi sangat erat, sebab demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo-toleransi, toleransi yang rentan menimbulkan konflik-konflik komunal. Karenanya, toleransi dan demokrasi harus berkait kelindan dalam tatanan masyarakat. Tetapi, toleransi bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit sebagai barang jadi, tetapi ia mewujud dalam kearifan kekuasaan yang memiliki determinasi dalam merawat toleransi. Jika tidak, justru akan memunculkan persoalan akut lainnya seperti gejala terorisme yang intoleransi itu, lahir sebagai implikasi ketidak-arifan kekuasaan dalam merawat toleransi, sehingga mewujud intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Sungguh, bersikap intoleran jauh lebih mudah dibanding toleran, sehingga butuh perhatian kolektif menjadikan problem sosial yang niscaya selekas mungkin diselesaikan, baik oleh pemerintah-negara maupun ormas sekaliber NU dan Muhammadiyah. Kedua, seorang muslim moderat, mendedahkan terorisme yang menjadi ancaman kemanusiaan dengan segenap balutan ideologis dan jaringannya. Berlatar pada kemiskinan ekonomi, ketimpangan keadilan sosial dan kedangkalan pemahaman keagamaan, menjadi penyubur tumbuhnya geneologi ideologis dan penguatan jaringan terorisme yang berbasis di tanah air. Selain itu, sensitivitas agama dengan melihat ketidakberdayaan Palestina, Irak dan Afganistan telah melahirkan solidaritas dan militansi agama untuk melakukan pembelaan, tetapi dilakukan dengan tindak kekerasan atas nama agama. Mengunduh terorisme yang belakangan menjadi isu sensasional di tanah air bahkan dunia, terutama setelah jaringan mereka berhasil “diamputasi” pihak keamanan. Selaras pandangan Amartya Sen, ia berhasil mengidentifikasi keterkaitan terorisme dengan identitas soliter, sehingga pembaca menemukan titik problem terorisme, dimana identitas merupakan salah satu dimensi paling rentan melahirkan terorisme. Identitas acap ditafsirkan “mereka” sebagai takdir, bukan sesuatu yang bersifat dinamis dan kontekstual, karenanya masyarakat sejatinya dibebaskan dari mewabahnya virus identitas soliter yang menyuburkan aksi teroris. Dibalik peliknya soal ancaman global terorisme, masih tersisa harapan dengan menanamkan optimismenya akan lahirnya oase perdamaian yang menjadi antitesa terorisme. Oase perdamaian menjadi asa realistis dengan membebaskan manusia dari kubangan kemiskinan dan ketidak-adilan sosial serta kebodohan. Berpijak pada prinsip itu, pembangunan manusia yang sejahtera dan berkeadaban niscaya mewujud menjadi realitas, sekiranya perdamaian tercapai. Kedua sudut pandang tersebut mencerminkan moderasi pandangan dan pemahaman keagamaan muslim moderat sebagai penyuara moderatisme Islam secara sejati. Pandangan muslim moderat senantiasa dirindukan sebagai penyelamat umat dan bangsa, di tengah fragmementasi kaum fundamental dan liberal. Disinilah, relevansi perspektif moderasi muslim moderat yang “dikhotbahkan” sejumlah muslim moderat yang mencerminkan kesungguhannya dalam menyemai Islam keindonesiaan yang manusiawi dan moderat, sesuai dengan kultur Islam di Indonesia. Dalam melihat isu aktual dengan berbagai dinamikanya, serta tawaran solutif dari muslim moderat yang memosisikan diri sebagai muslim moderat. Terlepas dari itu, pandangan muslim moderat selalu vis a vis dengan kutub pemikiran “Islam kanan” dan “Islam kiri”. Oleh karena itu, untuk meneropong Islam dalam perspektif moderasi terhadap pelbagai isu yang dihadapi umat Islam menyisakan asa perdamaian atas resonansi muslim moderat dalam merajut karakteritik Islam Indonesia yang moderat. 2. Dialog AntarIman Dalam tulisannya bertajuk Urgensi Dialog Antariman, (Media Indonesia/22/92008) Zuhairi Misrawi meniscayakan dialog antariman yang dibangun di atas prinsip keinginan untuk mencari titik temu. Karenanya, dibutuhkan kearifan dari para pemuka agama untuk tidak memunculkan kembali sentimen di masa lalu, terutama sentiman yang bernuansa negatif. Selanjutnya, tulisan intelektual muda NU ini menjadi menarik dan relevan dalam konteks menyikapi kasus pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh Vatikan melalui pidato Paus Benedictus XVI di Universitas Rogensburg, Jerman, 12 September lalu. Meskipun geger tafsir jihad Paus atas Islam itu mendapat reaksi keras, tetapi umat Islam masih mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan aksi anarkis. Di tengah meradangnya kebencian umat Islam atas pidato provokatif Paus Benediktus XVI, justru Vatikan menunjukkan sikap damai. Selain permintaan maaf Paus sendiri, juga yang paling urgen adalah seruan petinggi Vatikan itu untuk berdialog. Hal itu dikemukakan dalam pertemuan Paus dengan diplomat negara-negara Muslim di kediamannya di Castel Gandolfo, Roma, Senin 25/9 lalu (Media Indonesia 26/9/2008). Secara yakin Paus menegaskan bahwa dialog antara Islam dan Kristen sangat penting untuk memelihara perdamaian dan stabilitas dunia yang terancam oleh ketegangan agama. Sungguh mendiskusikan soal merebaknya kekerasan yang meruntuhkan solidaritas dan melahirkan luka baru, adalah sesuatu yang tidak nyaman. Sebab begitu banyak kerusakan sosial di tengah lirihnya suara kaum moralis, sebutlah elit agama. Justru virus konflik diembuskan elit agama sendiri selain oleh propaganda negara. Maka relevan untuk belajar dari Vatikan diembuskan benihbenih konflik melalui pidato Paus yang menafsirkan Jihad dalam Islam secara keliru. Hal ini memiliki potensi virus konflik yang dapat merobek dan melerai simpul-simpul kerukunan relasi antarumat beragama yang dibangun dalam dialog secara intensif lintas agama. Hal ini terjadi di tengah upaya melampaui dialog agama, justru menjadi suatu kemunduran drastis. Fenomena kekerasan atas nama agama, kepentingasn kelompok, ideologi bahkan atas nama agama masih juga terus berulang. Kekerasan yang dioperasikan oleh komunitas kaum beragama nyata melukai misi kemanusiaan yang menjadi ajaran suci setiap agama. Bahkan ironisnya, agama justru dijadikan tameng untuk memperkeruh suasana konflik. Padahal, semua agama hadir untuk membawa kedamaian, atau paling tidak, menjadi alternatif dari sistem untuk mewujudkan stabilitas dalam konteks kerukunan beragama. Semua agama pada prinsipnya mewartakan ajarannya yang agung masing melalui masjid, gereja, sinogog, pure, vihara, kelenyteng dan tempat persembahyangan lainnya. Upaya ini membumikan ajaran langit bagi kpeentingan kehidupan manusia. Ajaran yang suci dan mulia itu sejatinya dijadikan spirit untuk membantu orang-orang yang menghayati dan berkomitmen bagi perdamaian tanpa terjebak pada sekat-sekat agama dan ideologi lainnya. Agama yang dalam dirinya terkandung kebenaran mutlak harus berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang memiliki hak yang sama untuk eksis dan berinteraksi demi kedamaian di bumi. 3. Menelisik Akar Konflik Akar konflik dan kekekreasan atas nama agama dipicu karena perbedaan teologis dan non-teologis semisal ekonomi dan politik. Kepentingan-kepentingan tersebut sering terakumulasi sekaligus bermetamorfosa dalam bentuk konflik dan kekerasan. Ketidaksiapan umat beragama untuk hidup dalam masyarakat plural kadang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik tertentu untuk membakar fanantisme unmat dari tujuan jangka pendek. Hal ini menjadi virus konflik kadang sulir dibendung ditenh berkecamuknya konspirasi politik yang memperalat isu sensitivitas atas nama agama. Maka yang tumbuh adalah menbalnya rasa fanatisme agama dan lahirnya primordialisme sempit. Sejarah social masyarakat agama hampitr tidak pernah lepas dari konflik, baik karena sentiment agama itu senditi atau factor di luar agama. Agama hanya bias menjadi pencipta perdamaian di tegah dunia ini bila umat beragama sadar bahwa perdamaian bukan didapat dengan membenci atau memusuhi umat lain. Perdamaian hanya bias dihasiulkan melalui kemampuan menghatgai dan menghormati sesamamnya serta melalui komitmennya untuk membela siapaun yang tertindas dan tidak diperlakukan tidak adil. Mamang sulit untuk malahirkan karakter beragama yang pfanatik tetapi tidak ekstrim kecuali melalui proses intelektualitas untuk memahami kedewasaan beragama. Agama merupakan realitas sosial yan hidup dan termanifestasikan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, gama yang memiliki konsepsi terhadap realitas absolut terhadapan dengan realitas social yang selau berubah-ubah. Salah satu factor pemicu lahirnya kekerasan atsa nama agama, tidak terkecuali kerusuhan yang dimobilisir atas senrtimen teologis dipicu pemahaman keagamaan yang sempit. Pemahaman yang literal dan parsial lebih mendorong kaum beragama untuk mengedepankan emosionalnya disbanding rasionalitas mereka. Terperangkapnya kaum beragama yang demikian hanya dapat diselamatjkan melalui upaya melakukan kontekstualisasi ajaran agamanya dalam wawasan yang tidak menyempit. Selain faktor pemahaman, kekerasan atas nnama agama juga dipicu adanya kesenajangan politik dan ekonomi serta tumbuhnya sikap saling curiga terhadap the other. 4. Merawat Dialog Lintas Agama Berangakat dari fenomena ini, maka upaya dialog tetap menjadi tawaran alternative, baik yang bersifat local, nasional, regional hingga internasional. Meskipun beragam dialog yang demikian dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan. Justru itu, perlu dievakuasi hal-hal yang mempersulit mencari titik temu di latar perbedaan teologis tersebut. Urgensi dialog lintas agama terwujud bila didasari kesadaran masing-masing elit agama untuk mencari kar persoalan secara substansial untuk menekan menegnatalnya konflik lintas agama. Selama ini masih ditengarai dialog-dialog hanya bersifat seremonial bahkan kadang bernunas politis tanpa menyentuh kara persoalan. Sejatinya, bukan dialog antara elit semata sebab merea telah memiliki tingkat kedewasaan bergama yang tinggi sehingga terdapat kesepahaman, tetapi yang terpenting bagaiamana mengola masaa masing-masing untuk tidak anarkis. Kesadaran terhadap realitas pluralitas berragama duyakini dapat meredam, paling tidak, memminimalisir konflik dan kekerasan atas nama agama. Dengan begitu, ada ruang yang tercipta bagi masing-masinmg pihak untuk terbuka, jujur dan saling memahami serta saling mneghargai. Untuk itu, elit agama memiliki tanggung jawab untuk merawat kerukunan beragama yang selama ini telah dibangun melalui dialog-dialog. Jika mereka mampu memainkan perannya secara signigikan dan optimal dengan mengeliminir potensi konflik dengan memeberi pemahaman agama yang konstekstual, terbuka. Syahdan, para elit agama dan politik perlu memilki kearifan dalam menyelesiakan setiap persoalan yang mengaitkan agama dengan menelisi akar maslah untuk merwat kerukunan beragama yang cedera dan terluka karena kepentingan actor politik tertentu dan keterbatasan pemahaman terjadap akjaran agama sebagain penagut agama. Mereka memiliki sentiman dan fanatisme agama yang mengental sehingga perilakunya menjadi ekstrem. Inilah problematika kaum beragama dalam membangun dialog dan relasi sosial secara global. Maka alternatif solutif adalah membangun dialog kearah rekonsiliasi antariman sebagai pintu masuk kedamaian dalam bingkai pluralitas agama. Kesiapan masing-masing kaum beragama untuk berdialog berarati tumbuh kedewasaan dan kesadaran beragama yang tinggi, sebab tidak lagi terjebak pada adagium "menyamakan semua agama", melainkan tumbuh semangat untuk menghargai, yakni mengakui adanya perbedaan dan mencari tuitik temu melalui dialog menuju sikp keberagaam yang dewasa. Sebab konflik anataragama bukan karena ajaran atau norma-norma agama, melainkan karena sikap keberagaaamn yang kurang dewasa. Dapatkan luka kerukunan bergama ini disembuhkan, tergantung pada sikap kedewasaan masing-masing kaum beragama. Wajah Fasisme Dan Diabolisme Dalam (Ber) Agama Sekadar jika merunut wajah beragama yang kini memasuki era kebebasan, menarik dicermati, terutama secra psikologis banyak orang merasa termarginalkan sehingga merasa butuh dengan pengukuhan dan pengakuan identitasnya, tidak kerkecuali dalam ranah sosial keagamaan sekalipun. Kondisi ini kelak menyisakan persoalan pelik, sekelompok orang yang krisis identitas "berhasil" mengukuhkan diri dan mendapat pengakuan akan eksistensinya kemudian menafikan kehadiran kelompok lain. Maka berseliwerannya polarisasi agama yang stigmatis, saling menyesatkan dan merasa paling benar sehingga kegaduhan wacana agama tidak terelakkan lagi. Terang saja jika menelisik lanskap pemikiran Islam Indonesia kontemporer, setidaknya ada dua kutub atau "mashab" pemikiran yang menjadi maenstream secara realistis saling berbenturan, baik dalam altar wacana maupun gerakan, yakni mashab Islam liberal dan radikal. Dalam konteks inilah perlu objektivikasi dalam "membaca" dua kutub pemikiran tapi (mungkin) satu kitab, interpretasi atas teks saja yang berbeda. Sepertihalnya ketika mendedah pemikiran Islam liberal dari dunia maya hingga buku dan diskusi, maka isu, pemikiran dan wacana dari sayap radikal juga perlu disikapi secara arif. Sebab kedua kutub tersebut masing-masing mengisi "ruang kosong" meski kadang "rebutan lahan". Lalu bagaimana jika diantara mereka saling menilai (baca:menuding, menuduh dan memvonis) satu sama lain dengan merujuk "mashab" masing-masing. Setidaknya itulah yang dengan mudah kita pergoki dalam ekspresi dan pengukuhan identitas keberagamaan belakang. Media yang sering dijadikan ruang bebas mendedahkan ekspresi itu, isalnya, melalui buku. Salah buku yang cukup provokatif dan subyektif dalam membaca the others (Islam liberal) diantaranya karya Adian Husaini, seorang intelektual bersayap kanan-fundamental, berjudul Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual. Didalamnya terkuak sebuah pembacaan "the others" (Islam radikal-fundamental) terhadap "the Others" (Islam liberal) yang lain. Subjektivitas menjadi keniscayaan untuk meneguhkan keyakinan sang penulis. Secara garis besar pemikiran yang tertuang didalamnya yakni, mengungkap fenomena Islam liberal pasca fatwa MUI akhir Juli 2005 lalu. Term -yang kemudian menjadi stigma- diabolisme adalah sebuah pemikiran, watak dan perilaku iblis terhadap intelektual Islam liberal menjadi provokasi seperti secara gamblang tersingkap dalam pandangan Syamsuddin Arif (2005), seorang peraih doktor ISTAC-Malaysia - kini sedang mengambil doctor keduanya di Frankfurt Jerman - mencoba mengelaborasi ciri-ciri intelektual bermental iblis (diabolis), diantaranya, selalu membangkang, bermuka dua atau menggunakan standar ganda. Selain itu, mental diabolis lainnya ialah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran, mereka tahu yang benar dan yang salah namun ia sengaja memutarbalikkan data dan fakta (h.104). Karakter diabolis dan talbis itulah yang disematkannya kepada intelektual liberal. Untuk menyebut beberapa diantaranya, sebut Ulil Abshar Abdalla yang kini sekolah di Barat, Amerika. Tokoh muda inilah yang menjadi bidikan buku ini yang membela pluralisme agama dan penyeru liberalisme Islam paling giat. Tokoh tua yang tak terlewatkan, Dawam Rahardjo, misalnya. Meretas bagian-bagian buku ini menceminkan keseriusan penulisnya dalam membongkar propaganda Islam liberal. Penulis mengawali kajiannya dengan mengambil titik pijak pada penentangan sayap liberal atas 11 fatwa MUI, akhir Juli 2005. Khusus fatwa atas pelarangan Ahmadiyah, liberalisme, pluralisme dan sekularisme, menuai kritik, hujatan dan kecaman. Bahkan Ulil sang lokomotif kaum liberal muda NU ini menyatakan fatwa itu konyol dan tolol. Sementara Adian mencoba membongkar diabolisme Islam liberal dengan suatu simpulan atas pokok-pokok ajaran (sesat) Islam liberal yang selama diproyeksikan meliputi; menghancurkan aqidah Islam dengan menyebarkan faham pluralisme, meruntuhkan bangunan syariat Islam melalui kontekstualisasi ijtihad dengan tawaran metodologi hermeneutik, mengugat wahyu, ulama serta membongkar konsep-konsep dasar Islam dalam jubah liberalisme dan relativisme beragama. Maka setelah MUI mengeluarkan fatwa keharaman Ahmadiyah, liberalisme, sekularisme dan pluralisme menjadi palu godam atau alat pemukul yang menakutkan bagi Islam liberal di Indonesia dalam merealisasikan proyek liberalisme Islamnya. Namun Adian juga mengakui dengan penuh kekhawatiran atas penyebaran virus Islam liberal yang sudah meluas ke berbagai sendi-sendi kehidupan umat, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi maupun bidang studi Islam. Kelompok fundamentalis yang selalu berseberangan pemikiran dengan kelompok liberalis cenderung mengurai pluralisme agama dan islam liberal yang oleh penulisnya diasumsikan sebagai tren baru dalam mengacak-acak ajaran Islam. Sejurus itu, bagian kedua masih mendaras soal pluralisme agama kaitannya sikap dan perilaku islam liberal atas penginkarannya atas otentisitas al-Qur'an. Obsesi salah satu kontributor pemikiran Islam liberal, Taufik Adnan Amal yang juga dosen tafsir di UIN Alauddin Makassar itu, meniscayakan hadirnya al-Qur'an dalam edisi kritis. Di sisi lain, fenomena menggeliatnya "virus" liberalisme di tubuh Muhammadiyah. Meskipun sekelompok anak muda NU seperti Ulil Abshar Abdalla, Sumanto alQurtuby dan Zuhairi Misrawi merupakan "janin" Islam liberal di "rahim" NU, tetapi NU tidaklah terlalu dipersoalkan buku ini, seiring (mungkin) dalam Muktamarnya ke 31 di Solo, 2004 lalu, NU menolak faham liberalisme secara telak.akan halnya, geliat liberalisme di Muhammadiyah, bagi dimata penganjur mashab fundamentalis menaruh kecurigaan akan meruntuhkan bangunan Islam ditandai tampilnya tokoh Muhmmadiyah sekaliber Tarmizi Taher melalui tulisannya; " Memetik Nilai-Nilai Pluralisme dari KH. Ahmad Dahlan". Syahdan, hal itu menjadi aneh sebab Muhammadiyah dianggap mendukung pluralisme yang selama ini menjadi hantu yang menakutkan bagi kelompok fundamental-radikal. Selain Tarmizi, Sukidi Mulyadi seorang tokoh muda Muhammadiyah, juga tidak lepas dari intaian Adian, secara gamlang dan gampang memekikkan pluralisme sebagai sunnatullah. Moeslim Abdurrahman juga mendapat kecaman setelah mendukung buku "sesat" Sumanto alQurtuby, Lubang Hitam Agama. Bagi penggagas Islam transformative ini, buku Sumanto perlu dibaca oleh siapapun yang ingin ber-taqarrub untuk mencari kebenaran. Sementara buku tersebut dianggap melecehkan alquran, Nabi Muhammad dan para sahabat nabi. Sepertihalnya kaum liberal NU gagal menyusupkan liberalisme di ormas terbesar di Indonesia itu, kaum liberal Muhammadiyah seperti Dawam Rahardjo, Abdul Munir Mulkhan dan amin Abdullah, juga terbilang gagal melakukan hal yang sama. Tampilnya Din Syamsuddin yang juga tokoh MUI masih dinilai oleh kaum liberal belum jelas sikapnya bahkan dalam banyak kesempatan justru mengkritik Islam liberal, meski tergolong intelektual modernis tetapi sangat hati-hati. Wajah lain pemikiran kaum fundamentalis berupaya mengusung tema dalam pandangan stigmatis seperti menelusuri jejak sekularisasi, syariat Islam, Islam dan sekularisme, pluralisme yang diklaim kebenaran yang berbahaya dan kritik mereka terhadap upaya reinterpretasi dan liberalisasi penafsiran oleh komunitas islam liberal yang giat menggugat alquran. Pemikiran ini memunculkan diri sebagai wacana pembanding dan pembendung Islam liberal yang makin menggejala. Melihat berbagai persoalan yang dibahas buku ini tampak harus lebih arif, sebab pada beberapa bagian perlu kearifan untuk tidak terprovokasi sepertihalnya dalam membaca dan membedah pemikiran aktivis Islam liberal. Dalam hal ini tersibak aura gugatan bahkan cenderung ke arah dekonstruktifrekonstruktif atas biabolisme Islam liberal oleh sekelompok penganjut dan penganut mashab fundamental. Bagaimanapun apresiasi kita (mendukung atau sebaliknya) terhadap pemikiran yang demikian, sejatinya dapat kita jadikan ruang menenggak perbedaan dengan kearifan beragama kita, meski hanya sebatas wacana yang selalu mengawan-awan untuk diperdebatkan, untuk tidak mengatakan dibenturkan. Sementara itu, momentum jatuhnya rezim Orde Baru telah dimanfaatkan secara amat baik oleh kelompok Islam radikal untuk bangkit. Bangkitnya gerakan Islam radikal seiring dengan dibukanya kran demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, baik dalam wilayah politik praktis maupun dalam tataran sosial keagamaan, sehingga kondisi tersebut memunculkan reaksi logis dari tatanan politik monolitik yang ditandai dengan ledakan partisipasi politik yang lebih luas. Eforia reformasi dengan kebebasan berekspresi tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompokkelompok politisi yang dinikmati pula oleh mempunyai agenda politik tertentu saja, akan tetapi kelompok-kelompok agama yang secara transparan menggunakan simbol-simbol agama dalam menyuarakan aspirasinya. Kelompok agama yang dulu tidak mendapat tempat untuk mengangkat ide-ide Islam sebagai dasar negara, kini dengan mengatas-namakan demokrasi mereka bebas memperjuangkannya. Demikian juga dengan kelompok-kelompok agama yang tidak memiliki agenda politik secara langsung, dengan tidak merasa dicurigai sebagai ancaman negara lantang mengkritik ketimpangan-ketimpangan moral masyarakat. Ada dua tipe gerakan yang mengemuka dalam memperjuangkan ide-ide Islam formalis ini. Pertama gerakan mereka yang memperjuangkannya melalui jalur partai politik dan lobi-lobi politik formal, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan kemudian berubah PKS [Partai Keadilan Sejahtera]), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PUI (partai Umat Islam),Partai Masyumi Baru, PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi) PPP (Partai Persatuan Pembangunan ) dan sebagainya. Kedua mereka yang lebih memilih gerakan sosial terlebih dahulu untuk mensosialisasikan ide kulturalnya dan sedikit menampilkan simbol-simbol kekuasaan. Pola ini dapat dilihat dari aktivitas Ormas Islam seperti FPI (Front Pembela Islam), FKSW (Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah) yang kemudian populer dengan sebutan Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, HAMMAS, dan Majlis Mujahidin, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam)2 dan sebagainya. Namun secara umum dua tipe ini memiliki kesamaan ciri sebagaimana dikemukakan oleh Horace M.Kallen. Pertama mereka tampil mendakwahkan pentingnya penerapan ajaran Islam secara menyeluruh (Kaafah) di tengah zaman modern, baik dalam bidang sosial maupun politik bahkan urusan domestik pribadi. Kedua, mereka mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy). Ketiga mereka sangat memusuhi Barat dengan segala bentuk peradabannya seperti sekulerisasi dan modernisasi, keempat perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia. 3 Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang menarik di kalangan pengamat sosial baik dari luar maupun dalam negeri. Mereka sering menyebut gejala ini sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme. Suatu istilah baku dalam Ilmu Sosiologi (Sosiologi Agama), yang mempunyai pengertian suatu gerakan penolakan terhadap isu-isu modernitas yang didasarkan atas keyakinan agama yang difahaminya secara mutlak dan harfiyah. Istilah ini sering diidentikkan dengan gerakan kaum reaksioner Kristen di Amerika Serikat ( 1870) yang merasa terancam oleh ajaran teologi liberal, sehingga menganggap perlu untuk kembali ke asas fundamen. Mereka berpangkal pada asas tak-mungkin-salah dari al-Kitab, termasuk bentuk huruf asli dari al-Kitab dan tidak mau tau pandangan teologi baru dan penafsiran yang mencoba menyentuh bentuk kepercayaan tradisional mereka. Untuk menunjuk gerakan Islam di Indonesia selain istilah fundamentalisme muncul juga istilah lain diantaranya Islam radikal, Islam ekstrim, Islam militan, Islam skriptualis, Islam anti Liberal, Islam Garis Keras dan sebagainya. R. William Liddle jauh-jauh hari telah meramalkan kemunculan kebangkitan Islam ini dengan menyebut kelompok Islam skriptualistik dalam artikelnya berjudul “Skriptualisme Media 2 KISDI merupakan lembaga yang berafiliasi dengan DDII. Lihat Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia , Jakarta : ISAI, 2001, hal. 197 3 Bachtiar Effendy dan Hendro Prasetyo, (peny), Radikalisme Agama, Jakarta , PPIM-IAIN, 1993 hal. xvii-xviii. Dakwah : Suatu bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru”. Dalam ramalannya Islam Skriptulistik akan kebangkitannya disaat iklim menemukan metamorfose politik Indonesia berubah yang diwarnai dengan 4 keterbukaan dan kebebasan. Dan ramalan ini ternyata memang benar-benar menjadi dan menjadi bukti sebagai bagian dari kebangkitan Islam secara makro. Menurut John L. Esposito Kebangkitan Islam dan demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia orang-orang beramairamai menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini.5 Sebenarnya penggunaan istilah radikal atau fundamentalis masih sangat problematik bila disandingkan pada aktivitas gerakan Islam, sebab penggunaan istilah ini masih sangat bias dan kebarat-baratan. Di sebagian kalangan muslim menolak karena istilah radikal atau fundamentalisme dikesankan sebagai istilah pejoratif yang terbelakang dan terkesan teroris. Namun penggunaan istilah dalam kajian penelitian ini tidak bersifat eksklusif sebagaimana difahami di dunia Barat. Istilah ini digunakan semata-mata hanya kebutuhan akademis yang memerlukan ketegasan variabel. Istilah lain yang serupa sengaja tidak digunakan karena untuk mempermudah analisis saja. Dalam kajian sosiologi pun istilah ini telah menjadi term yang mapan. Bernard Lewis, seorang ahli sejarah Islam, juga berpendapat bahwa penggunaan istilah ini sudah mapan dan dapat diterima, terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Alasannya ciri radikalisme, fundamentalisme yang agresif dan konservatif dalam gerakannya seringkali ditemukan juga di kelompok agama-agama lain. 6 Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam, (1994) menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat sebagai Islam Fundamentalis, ia menunjuk contoh seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama’ati Islami dan Islamic Salvation Front (FIS).7 Demikian juga John L. Esposito menyebutkan bahwa 4 R. William Liddle “Skriptualisme Media Dakwah : Suatu bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru” dalam Mark R. Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Memetakan paradigma Mutakhir Islam Indonesia, cet. 1,Bandung ,Mizan, 1999. hal. 304 5 John L.Esposito dan John O.Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek, Bandung , Mizam, 1999, hal. 11 6 Dawam Raharjo ”Fundamentalisme” dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed), Rekontruksi dan renungan Religius Islam, Paramadina, Jakarta, 1996, cet. 1, hal. 87. 7 Tarmizi Taher, Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam sejarah Islam” dalam Bachtiar Effendy dan Hendro Prasetyo, (peny), Radiaklisme Agama, Jakarta , PPIM-IAIN, 1993 hal. 6 fundamentalisme dicirikan pada sifat “kembali kepada kepercayaan fundamental agama”8 Jadi pengertian fundamentalis dapat saja diartikan sebagai sekelompok penganut agama Islam yang memiliki sikap dan pandangan yang berpegang teguh pada halhal yang dasar dan pokok dalam Islam sesuai dengan interpretasi mereka sendiri, kemudian mereka menolak upaya kompromi, adaptasi dan interpretasi kritis atas teksteks dasar dan sumber-sumber kepercayaannya.9 Menurut Wiliam Liddle bangkitnya gerakan ini paling tidak dipicu tiga faktor penting : Pertama, ajaran-ajaran mereka lebih mudah difahami oleh kebanyakan masyarakat muslim Indonesia. Kedua, kemungkinan aliansi politik antara kaum skriptualis dengan kelompok-kelompok sosial lain yang sedang tumbuh dan ketiga, nafsu besar para politisi ambisisus untuk membangun basis massa.10 Dalam kajian gerakan pemikiran Islam gerakan radikal dan fundamentalisme ini paling tidak dapat dicirikan dengan empat kategori. Pertama oppositionalisme, yakni mereka giat melalukan upaya perlawanan terhadap segala bentuk pemikiran dan pemahaman yang dinilainya mengancam dan bertentangan dengan al-Qur’an. Kedua menolak hermeneutikasi. Menolak bentuk pemahaman rasional yang didasarkan ta’wil semata. Standar pemahaman yang benar adalah pemahaman harfiyah yang tidak keluar dari batasan logika bahasa. Ketiga Menolak pluralisme dan relatifisme. Mereka cenderung memandang masyarakat secara “hitam putih” yakni masyarakat yang meyakini dan mengamalkan Islam yang sempurna (kaafah) dan masyarakat jahiliyah yang tidak meyakini dan mengamalkannya. Keempat Menolak perkembangan historis sosiologis. Bahwa realitas masyarakat harus menyesuaikan nilai ajaran Islam, bukan sebaliknya ajaran Islam menyesuaikan kondisi zaman. 11 Menelisik ihwal geneologis aksi teror tersibak fakta bahwa gerakan radikal ini dilatari kebencian yang akut atas hegemoni kekuasaan-negara yang tidak mengakui 8 Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam, London : I.B Tauris & CO Ltd, 1994, hal. 2-4 9 Jhon O Voll “ Fundamentalis” dan The Oxford Ensyclopedia of Modern Islamic World, Oxford University, 1995,hal. 84 10 R. William Liddle “Skriptualisme Media Dakwah : Suatu bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru” dalam Mark R. Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Memetakan paradigma Mutakhir Islam Indonesia, cet. 1,Bandung ,Mizan, 1999. hal. 304 11 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 109 identitas (kelompok) mereka yang kemudian mewujud sebagai kelompok militan. Jika demikian adanya, maka persoalan teroris tidak terlepas dari persoalan kebijakan dan kearifan sebuah kekuasaan. Artinya, persoalannya bukanlah persoalan agama melainkan persoalan politik pengakuan dan perlakuan belaka. Sementara agama hanya dijadikan jubah pembenar dan spirit. Hegemoni Amerika, misalnya, dalam memperlakukan negara-negara muslim seperti Afghanistan dan Irak menjadi "janin baru" yang lahir dari "rahim" radikalisasi sebagai bentuk perlawan oposisional atas kebijakan "politik imprealis" negara adidaya tersebut. Dalam kaitannya dengan menggejalanya isu dan aksi terorisme belakangan, muncul pertanyaan yang sulit terjawab, kecuali dengan apologi-apologi an sich, adakah korelasi fungsional antara doktrin agama dan aksi terorisme? Bisakah gerakan keagamaan yang diduga dalang terorisme sebagai representasi Islam, baik dalam ranah ajaran maupun pengikutnya? Stigmatisasi Islam sebagai agama teroris makin dahsyat, Islam sebagai agama yang selalu tertuduh teroris. Ini terkait erat dengan maraknya gerakan Islam Politik yang menunjukkan pandangan dan gerakan fundamentalistikpolitis. Ironisnya bangunan (politisasi) opini Barat atas Islam teroris justru diamini sejumput kalangan. Misalnya, bangunan opini via video oleh pemerintah justru melahirkan penguatan dan pembenaran opini tersebut. Mengerasnya sikap Islam garis keras dipengaruhi hegemoni Barat atas dunia Islam sebagai amunisi potensi-pontensi bagi terbentuknya pemahaman keagamaan yang menjurus pada terorisme disebabkan pandangan tekstual terhadap kitab suci dalam melakukan perlawanan secara radikal. Maka dalam aras kesadaran beragama, sejatinya wacana Islam dan Terorisme (al-Irhab wa al-Islam) didedahkan bahwa terorisme dalam (tradisi) Islam terbentuk melalui pandangan keagamaan yang mengancam dan menakutkan (al-tahdid wa al-takhwif) dikalangan kaum fundamentalistik-radikalistik kemudian membenarkan aksi kekerasan, teroris untuk melawan “musuh Tuhan”. Barat dalam hal ini ditahbiskan sebagai salah satu simbol musuh Tuhan yang menebar propaganda dan kebencian dengan kesewenang-wenangannya kepada dunia Islam tadi. Arus stigmatisasi Islam-teroris kian menderas dan menjadi suatu ancaman yang membahayakan bagi eksistensi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Artinya akan lahir stigma bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi sarang teroris. Implikasinya, stigma teroris ini menjadi stigma agama (Islam). Munculnya stigma Islam sebagai teroris harus dibendung untuk menjaga kesucian Islam yang cinta perdamaian dan menjunjung tinggi kemanusiaan universal. Tindakan sekelompok kecil umat Islam dari garis keras (radikal) yang selama ini menjadi ancaman di mana-mana, sesungguhnya sesuatu yang paradoks dengan nilainilai ajaran Islam itu sendiri. Adanya mis-interpretasi pada makna jihad juga menjadi kendala untuk menjinakkan radikalisme agama yang memperburuk citra Islam belakangan ini, di tanah air khususnya. Hal inilah yang menjadi problematika di dunia Islam. Sikap anti AS yang ditunjukkan Islam Radikal-Fundamentalis di Timur Tengah melalui ghirah agama yang tinggi, kemudian mereka melakukan tindak kekerasan tapi hanya sia-sia dan konyol (secara politis, bukan agama). Di Indonesia, misalnya, sekelompok umat Islam melakukan aksi anti AS, kenyataannya mereka tidak berhadapan dengan AS melainkan mendapatkan perlakuan kasar dari aparat dan akibat aksinya merusak tatanan perekonomian dan merugikan kemaslahatan kemanusiaan. Bukankah ini kekonyolan dan kesia-siaan belaka di mana aparatpemerintah berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Selain itu, faktor lain dari fenomena radikalisme agama ini mengindikasikan tindakan mereka juga tidak terlepas dari kekecewaannya terhadap pemerintah serta menguatnya keinginan untuk mendirikan negara Islam. Jadi sikap anarki selama ini yang dimunculkan Islam garis keras secara sinergis merupakan akumulasi kekecewaanya terhadap ketidakadilan Barat terhadap umat Islam, kemudian kekecewaan terhadap pemerintah yang korup serta obsesi mereka untuk menegakkan negara Islam. Nyatanya, tujuan mereka semakin jauh dari kenyataan, yang terjadi justru mereka semakin dimarginalkan dalam politik nasional sebagai pihak yang selalu dikambing-hitamkan setiap ada tindak kekerasan atas nama agama, selain itu juga menuai kecaman dari umat Islam sendiri yang tidak membenarkan tindakan mereka yang dianggap justru semakin memperburuk citra Islam. Kasus penyerbuan aktivis Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang dikenal Insiden Monas, kian memperpanjang daftar kekerasan atas nama agama oleh kelompok radikalis. Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi saat anak bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni, nyata mencederai nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai simbol perekat keragaman atau kemajemukan dan kebangsaan. Insiden monas sejatinya menjadi titik balik untuk merawat dan menata sikap beragama secara arif dalam bingkai kebangsaan. Fenomena FPI yang lahir dari rahim reformasi menjadikan wajah kehidupan beragama yang bringas. Perilakunya bertentangan ajaran Islam yang cinta kedamaian. FPI merupakan organisasi Islam yang akhirnya cukup diperhitungkan pasca Orde Baru. Gerakannya bersifat anarkis, aksi-aksinya radikal dan menimbulkan ketakutan bagi sebagian besar masyarakat. Obsesi kelompok ini adalah memberlakukan syariat Islam dalam bingkai tafsir monolitik atas teks suci al-Qur'an dan penolakannya secara hitam putih terhadap segala hal yang berasal dari Barat. Pada konteks ini, kelompok agama yang dulu tidak mendapat tempat untuk mengangkat ide-ide Islam sebagai dasar negara, kini dengan mengatas-namakan demokrasi mereka bebas memperjuangkannya. Demikian juga dengan kelompok agama yang tidak memiliki agenda politik secara langsung, dengan tidak merasa dicurigai sebagai ancaman negara lantang mengkritik ketimpanganketimpangan moral masyarakat. Menelisik ihwal geneologis gerakan radikal ini dilatari kebencian yang akut atas hegemoni kekuasaan-negara yang tidak mengakui identitas (kelompok) mereka yang kemudian mewujud sebagai kelompok militan. Jika demikian adanya, maka persoalan aksi radikal tidak terlepas dari persoalan kebijakan dan kearifan sebuah kekuasaan. Tepatnya, radikalisme atas nama agama adalah bentuk perlawanan terhadap negara. Misalnya, kasus penanganan Ahmadiyah melalui SKB oleh pemerintah, justru berpotensi menjadi bom waktu konflik horizontal. Artinya, persoalannya bukanlah semata persoalan agama melainkan persoalan politik pengakuan dan perlakuan belaka. Tetapi jika itu dilakukan maka kelompok garis keras mendapat angin segar untuk melakukan "sweeping akidah" terhadap ajaran lain yang distigma sesat, dengan dalih berbeda dengan keyakinannya. Jika dilihat dalam bingkai kebangsaan, tindakan anarkis kaum radikalis yang mengatasnamakan agama, apapun nama laskar mereka, menjadi penanda ketidakarifannya terhadap nilai-nilai pluralitas dan kebangsaan. Keberagamaan mereka cenderung emosional dengan mendoktrin bahwa dirinya sebagai pihak paling benar dengan menegasikan komunitas lain, bahkan disertai tindak kekerasan. Klimaksnya, mereka mengatasnamakan agama untuk pembenaran tindakannya, yang justru merusak citra Islam. Dalam menyikapi fenomena ini, setidaknya solusi yang dapat ditawarkan untuk “menjinakkkan radikalisme agama” di tanah air yakni, dalam menyikapi berbagai propaganda dan ketidakadilan Barat terhadap dunia Islam, seharusnya tidak direspon secara berlebihan seperti melakukan tindak teroris dan bentuk kekerasan lainnya karena toh hanya merugikan umat Islam. Alternatifnya, justru kita harus menunjukkan kearifan agama yang diperankan dalam perilaku keagamaan kita sebagai cerminan martabat dan harga diri sebagai bangsa yang luhur dan utuh, tidak mudah diintervensi pihak manapun. Sementara itu perlawanan dalam bentuk radikalisme agama justru merupakan tindakan bunuh diri adalah haram dan terkutuk. Dalam lanskap sikap beragama yang arif, membendung stigma teror menjadi stigma agama, kini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh anak bangsa, khususnya umat Islam. Dalam aras ini, Islam dan keindonesiaan (nasionalisme) menjadi relevan ditunjukkan secara arif bahwa, Islam di Indonesia senantiasa mengembangkan amar ma’ruf nahi mungkar dalam koridor kedamaian. Indonesia merupakan dar da’wah bukan dar harb. Artinya gerakan dakwah yang dilakukan berorientasi pada perwujudan kedamaian melalui pertautan nilai-nilai Islam yang substantif dan universal. Hal ini untuk membendung keterjebakan umat Islam terhadap berbagai propaganda politisasi dan pemutarbalikan fakta melalui media asing (Barat) yang mendominankan yang bias dan membiaskan yang dominan. Maka akibatnya wajah Islam secara kultural di Indonesia yang ramah, damai menjadi bias dan lahir dominasi Islam radikal dalam pemberitaan media asing yang manipulatif hingga berujung pada stigma teroris. Untuk itu, dalam membendung stigma teror menjadi stigma agama. Sejatinya umat Islam mempertahankan citra Islam yang damai sebagaimana selama ini ditunjukkan. Upaya umat Islam kultur Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam ikatan solidaritas yang tinggi sesama umat Islam yang kemudian dipadukan dengan ukhuwah wathaniyah (nasionalisme) dan ukhuwah bashariyah (humanisme universal) menjadi keniscayaan yang harus dipertahankan. Atas pijakan ini, Islam Indonesia dapat mensinergikan antara nilai-nilai Islam, nasionalisme dan kemanusiaan universal sebagai substansi Islam itu sendiri. Secara substantif Islam tidak membenarkan tindak kekerasan, anarkis, apalagi di tindakan teroris yang mengatasnamakan agama (Islam). Islam menjunjung tinggi kemanusiaan, sebab bila seseorang menyelamatkan satu jiwa, ia seolah-olah menyelamatkan seluruh umat manusia (Alquran; 5:32), sebaliknya jika seseorang menghilangkan nyawa orang lain (termasuk menciptakan rasa tidak aman) maka ia seolah-olah menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan. Atas dasar ini, Islam senantiasa menunjukkan kepribadiannya dengan menjalankan syariat Islam dan akhlaq Islam dengan sesungguhnya dengan nuansa penuh kearifan dan kedamaian. Dalam tataran ini, Islam kultural (keindonesiaan) menjadi solusi dengan berpijak pada lokalitas Islam melalui upaya pribumisasi Islam sebagai perwujudan Islam keindonesiaan, bukan Islam yang diadopsi dari negara yang ekstrimitas Timur Tengah. Sejatinya, umat Islam di Indonesia harus membendung stigma Islam sebagai agama teroris dan menghilangkan citra sebagai sarang teroris dengan menjalankan ajaran Islam secara substantif sesuai kondisi lokalitas-kultural Islam Indonesia yang damai sebagaimana dalam sejarahnya, Islam masuk dan berkembang di Indonesia secara damai, tidak dengan tindak kekerasan (redikalisme agama) melainkan dengan prilaku damai yang senantiasa mencerminkan ruh Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. DAFTAR PUSTAKA Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Postmodernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996) Baidhawy, Zakiyuddin, Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan, (Jakarta: 2005). Al-Baqi, Muhammad Fuad, Mu'jam Al-Mufahras li Ahfaz Al-Qur'an Al-Karim, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1981). Effendy, Bachtiar dan Hendro Prasetyo, (peny), Radikalisme Agama, Jakarta, PPIMIAIN, 1993 Esposito, John L. dan John O.Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek, Bandung , Mizam, 1999 Fatooni, Lovay, Jihad In The Qur'an: The Truth From The Source, (Kualalumpur, Noordeen, 2002) Firestone, Reuven, Jihad: The Origin of Holy War In Islam, (Oxford University Press, 1999). Ghafur, Waryono Abdul, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks, (Yogyakarta: eLSAQ, 2005) Hefner, Robert W. Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia , Jakarta : ISAI, 2001 Jamhari, Jajang Jahroni, Gerakan Salafy Radikal di Indoensia, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) Liddle, R. William “Skriptualisme Media Dakwah: Suatu bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru” dalam Mark R. Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Memetakan paradigma Mutakhir Islam Indonesia, cet. 1,Bandung ,Mizan, 1999. Raharjo, Dawam ”Fundamentalisme” dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed), Rekontruksi dan renungan Religius Islam, Paramadina, Jakarta, 1996 Rahardjo, Dawam, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 2002). Roy, Oliver, The Failure of Political Islam, London: I.B Tauris & CO Ltd, 1994 Taher, Tarmizi, Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam sejarah Islam” dalam Bachtiar Effendy dan Hendro Prasetyo, (peny), Radiaklisme Agama, Jakarta , PPIM-IAIN, 1993. Voll, Jhon O “ Fundamentalis” dan The Oxford Ensyclopedia of Modern Islamic World, Oxford University , 1995 Zada, Khamami, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam di Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2002).