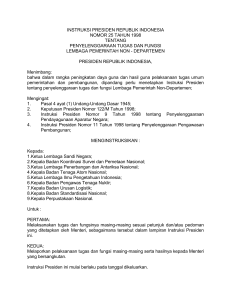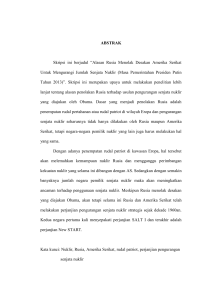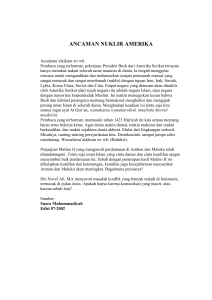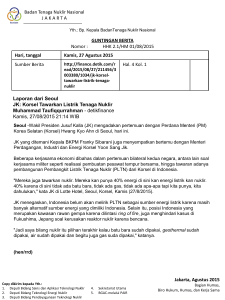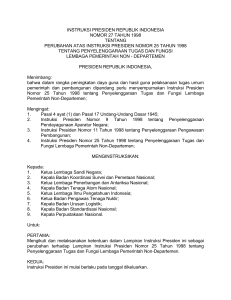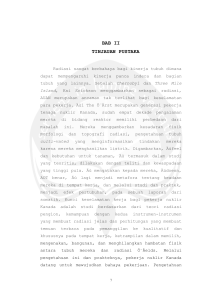Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global
advertisement

Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global: Teorisasi dan Implementasi I Gede Wahyu Wicaksana7 Abstract Expansion and proliferation of nuclear weapons have become an international issue since World War II, with their serious implications to peace and security. International efforts to restrict and eliminate nuclear weapons undergo ups and downs. The Non-Proliferation Treaty, however, is widely considered to have worked out well in decreasing the prospects for further nuclearization. This article looks in detail at what the norm is effective in achieving the goal of global denuclearization. It presents theoretical and case-based analysis to show determining factors ofstates’ decisions to abandon nuclear weapon programs. Perspectif of strategic realism, liberal institutionalism and constructivism are canvassed to search for policy explanation. Keywords: denuclearization, NPT, nuclear weapons. Pendahuluan Seruan bagi pelucutan senjata nuklir telah terdengar sejak era nuklir dimulai pada Perang Dunia ke-2. Kehancuran kota-kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang akibat bom atom dengan segera mendorong masyarakat internasional untuk mengupayakan penciptaan sebuah mekanisme global demi mencegah perluasan senjata nuklir, dimana produksi energi atom dibatasi hanya untuk tujuan damai (Alagappa, 2008:1). Resolusi pertama yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Januari 1946 memuat ajakan untuk membentuk Komisi Energi Atom Internasional yang akan mengembangkan proposal bagi eliminasi senjata nuklir dan berbagai komponen persenjataannasional lain yang dapat diadaptasi menjadi senjata pemusnah masal (Hagold, 2009:24). Selama Perang Dingin, usaha masyarakat internasional untuk pelucutan senjata nuklir mengalami pasang surut yang terutama disebabkan oleh ketidaksepakatan antara dua negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Kedua negara mengajukan inisiatif pelucutan senjata nuklir dari perspektif masing-masing. Baruch Plan didesain oleh Washington untuk menciptakan rezim Penulis adalah dosen Politik dan Keamanan Internasional pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 165 nuklir internasional dengan kewenangan regulasi, inspeksi dan sanksi kepada negara yang melanggar. Proposal ini ditolak oleh Soviet dengan alasan akan dapat memunculkan hegemoni nuklir yang berbahaya bagi keamanan dunia. Moskow ingin tetap mempertahankan Dewan Keamanan PBB serta hak veto sebagai instrumen kontrol dan manajemen konflik senjata internasional (Johnson, 2009: 45; 7). Pada awal tahun 1961, Washington dan Moskow setuju untuk mengadakan putaran negosiasi pelucutan senjata nuklir yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Kesepakatan ini dekenal sebagai “the McCloy-Zorin Plan”. Traktat nonproliferasi nuklir yang melegitimasi tujuan abolisi senjata nuklir yang sudah dibuat sejak Perang Pasifik kemudian diadopsi pada 1968 (Alagappa, 2008: 17). Sekalipun demikian, baik AS yang memimpin blok barat maupun Uni Soviet sebagai pemimpin blok timur terus membangun fasilitas nuklir dengan kapasitas persenjataan yang semakin mutakhir sehingga perlombaan senjata antara mereka menjadi semakin sengit. Perang Dingin yang terjadi pada 1978-1985 merupakan puncak ketegangan nuklir antara kedua blok. Hanya setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan bersepakat untuk mengintensifkan diplomasi dan negosiasi eliminasi senjata nuklir, angin segar perdamaian nuklir berhembus kembali. Walaupun kebijakan AS dan Uni Soviet tidak berubah secara radikal, tiga perundingan sepanjang tahun 1986 hingga 1990 antara Moskow dan Washington cukup berhasil menurunkan tensi rivalitas nuklir kedua pihak (Weber, 1990: 55-65). Sejak Perang Dingin usai, urgensi politik untuk merevitalisasi rezim pelucutan senjata nuklir global kembali menguat.Ini berjalan seiring dengan transformasi fundamental dalam hal peran pollitik dan militer senjata nuklir bagi kebijakan luar negeri negara besar –khususnya Amerika Serikat– untuk merespon perubahan orde internasional (Nye, 1992: 1293-1296). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi signifikansi advokasi untuk pemusnahan senjata nuklir. Pertama, penyebaran senjata nuklir yang relatif kurang terkontrol sebagai implikasi pelemahan tata kelola yang dimonopoli AS dan Rusia sebagai pengganti Uni Soviet. Kedua, kemunculan negara-negara nuklir di luar orde non-proliferasi yang semakin menunjukkan ketidakefektifan strategi deterrence (Cortright dan Vayrynen, 2009: 15). Kedua faktor ini menjadikan tantangan keamanan dan 166 stabilitas yang diakibatkan oleh penyebaran kapabilitas dan penguasaan teknologi senjata nuklir dewasa ini lebih kompleks. Tulisan ini ditujukan untuk mengetengahkan tinjauan yang berkonsentrasi pada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Pertama, dengan semakin meningkatnya atensi masyarakat internasional terhadap konsekuensi keamanan dari perlombaan senjata nuklir, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi determinan efektifitas rezim pelucutan senjata nuklir global? Kedua, dalam situasi bagaimanakah ambisi suatu negara untuk menguasai dan mengembangkan senjata nuklir bisa dicegah atau paling tidak dikendalikanoleh institusi internasional? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis akan berfokus pada teorisasi yang dimaksudkan untuk menyelidiki kondisi obyektif di balik keputusan negara tertentu untuk melakukan proses denuklirisasi. Spektrum teori yang dibahas di sini mencakup elemen-elemen perdebatan perspektif mulai dari realisme strategis, liberal institusionalisme hingga konstruktivisme atauteori normatif. Studi kasus disajikan untuk memverifikasi teori yang dirujuk sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Determinan Denuklirisasi Studi yang dilakukan antara lain oleh Tagma (2010), Utgoff (2000) dan Zagare (1996) menyimpulkan ada beragam faktor yang mendorong permerintah suatu negara memutuskan untuk menghentikan program senjata pemusnah masal yang sudah dimiliki ataupun diwarisi. Terdapat tiga faktor determinan pokok yang muncul dalam ketiga studi tentang denuklirisasi yang mengindikasikan gagasan realisme strategis. Pertama, faktor yang sangat mendasar, yaitu peningkatan situasi keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada pengurangan relevansi senjata nuklir. Denuklirisasi dianggap paling potensial terjadi dalam kondisi internasional yang stabil. Kedua, faktor yang berkenaan dengan pergeseran kebijakan domestik, semisal orientasi yang lebih kuat pada demokrasi, good governance, dan liberalisasi pasar dalam integrasi internasional. Ketiga, faktor eksternal, khususnya yang berupa insentif dari negara lain, seperti Amerika Serikat yang membuat daya tarik nuklir menjadi berkurang. Insentif biasanya dalam bentuk bantuan ekonomi dan komitmen keamanan bersama. Ketiga faktor 167 ini bekerja saling menunjang dalam menentukan keputusan suatu negara untuk melakukan denuklirisasi. Bowen dll (2012) dan Wilson (2005) mengadakan studi kuantitatif yang bercorak liberal institusionalis terhadap 37 negara sejak tahun 1945untuk menguji korelasi antara faktor-faktor domestik dan internasional dalam kebijakan denuklirisasi. Mereka memetakan empat variabel tambahan yang mempengaruhi keputusan suatu negara untuk melanjutkan atau sebaliknya menghentikan program senjata nuklir, yaitu karakteristik rezim, imperatif teknologi,jaminan keamanan aliansi, dan peran norma denuklirisasi internasional. Hasilnya, sama dengan studistudi sebelumnya, aspek isu keamanan nasional merupakan faktor penentu yang dominan mempengaruhi pilihan kebijakan nuklir suatu pemerintah. Tipe rezim dan norma internasional diyakini sebagai faktor pengontrol yang signifikan. Argumen mereka bertentangan dengan asumsi realis yang menekankan pada jaminan keamanan aliansi sebagai faktor yang krusial. Selain itu, para liberal institusionalis –misalkan Evan dan Hays (2006)– menemukan tidak ada bukti bahwa kemampuan ekonomi dan teknologi berhubungan secara langsung dengan keputusan untuk membangun persenjataan nuklir. Mario Carranza (2006) mengklaim bahwa tidak ada korelasi langsung antara jaminan keamanan aliansi militer dan kebijakan non-proliferasi nuklir. Banyak akademisi dan praktisi nuklir percaya jika jaminan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam “payung keamanan regional” maupun ‘strategi global deterrence’ efektif mencegah negara sekutu untuk memproduksi bom nuklir (Bertsch dll, 1997; Fitzpatrick 2008). Fakta memperlihatkan bahwa negara seperti Pakistan dan Israel sama sekali tidak peduli pada komitmen aliansi keamanan yang dibimbing oleh AS. Mereka justru lebih yakin pada kebijakan internal untuk memperkuat instalasi nuklir dalam negeri (Asada, 2011:9). Negaranegara di luar sistem aliansi keamanan Washington di Asia Timur dan Timur Tengah bahkan tidak berusaha untuk menjadi kekuatan nuklir (Asada, 2011: 11). Anomali yang diungkapkan dalam studi Asada merupakan kritik tajam terhadap realisme strategis yang sangat meyakini keandalan keamanan kolektif sebagai preventive measure proliferasi nuklir. 168 Perlu dicatat bahwa kerangka analisis liberal institusionalis tidak sama sekali menafikan adanya koneksi antara jaminan keamanan aliansi dan kebijakan denuklirisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Boulden dll (2009: Bab 2 dan Bab 3), negara-negara seperti Jepang dan Jerman yang menjadi sekutu dekat AS tidak mengembangkan senjata nuklir. Menurut Boulden dll (2009: 71-75) terdapat dua hal yang menjadi faktor penyebab situasi ini. Pertama, nilai strategis anggota aliansi bagi AS di satu sisi yang mempengaruhi besar kecilnya insentif keamanan yang diberikan oleh Washington, dan di sisi yang lain derajat dependensi anggota aliansi yang berkaitan dengan pilihan-pilihan kebijakan strategis alternatif di luar formula keamanan bersama dalam aliansi. Kedua, strategi deterrence yang tidak relevan, bukan arti penting aliansi secara politik maupun militer yang lebih luas. Jepang dan Jerman, menurut Boulden dll (2009: 82), tidak memutuskan untuk menjadi negara bersenjata nuklir karena Washington telah menjamin keamanan mereka dalam bidang politik dan militer secara penuh. Sehingga, dari penjelasan ini, kesimpulan yang bisa ditarik ialah jaminan aliansi memainkan peran dalam konteks yang lebih spesifik terhadap pilihan kebijakan non-proliferasi nuklir. Spektrum perspektif ketiga, yakni konstruktivisme atauteori normatif, seperti diulas oleh Bergner (2012), Karp (2012), Lettow (2010), Marks (2009) dan Olav (2010), menghubungkan fenomena non-proliferasi dengan upaya mencegah diversifikasi senjata pemusnah masal seperti senjata kimia dan biologi melalui mekanisme kelembagaan dan sosialisasi internasional. Realis dan liberalis memang berhasil mengobservasi faktor-faktor kunci penyebab kepatuhan atau ketidakpatuhan negara pada agenda denuklirisasi. Kedua pendekatan utama ini menjelaskan interplay faktor domestik dan faktor eksternal yang bekerja dalam proses pembuatan keputusan. Namun, mereka tidak menyediakan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan mengapa setelah Perang Dingin terjadi penurunan drastis dalam produksi senjata pemusnah masal negara-negara nuklir utama seperti Rusia dan Amerika Serikat, padahal sebelumnya terjadi peningkatan produksi besar-besaran sepanjang tahun 1980-an. Fenomena yang berkebalikan ditemui di negara-negara nuklir seperti India, Pakistan, dan Korea Utara yang setelah Perang Dingin berakhir justrusemakin menguatkan kapabilitas militer mereka (Potter, 2010: 80). Konstruktivis seperti Gregory Schulte (2010) dan 169 Jacqueline Reich (2011) berargumen bahwa faktor yang mendorong kemunculan paradoks tersebut ialah efektifitas sosialisasi dan akomodasi yang mendorong “changes in the international institutional and normative environment encourage reductions in military capabilities and discourage the acquisition of new weapon system”. Dengan menuruti argumen ini, berarti norma dan sosialisasi internasional hanya bisa diterapkan dengan baik untuk negara-negara nuklir utama, sedangkan negara-negara nuklir seperti India, Pakistan, dan Korea Utara bebas untuk tidak taat. Pemaknaan ini muncul –sebagai contoh dikemukakan oleh realis seperti Simpson dan Howlett (1994) serta Steinberg (1994)–karena aspek normatif konstruktivisme sulit dijelaskan secara faktual. Kritik lain diarahkan pada asumsi liberal institusionalis yang mengaitkan demokrasi dengan kebijakan non-proliferasi. Liberalis berpandangan bahwa terdapat korelasi positif antara perubahan jenis rezim dan pilihan kebijakan nuklir yang diambil. Rezim yang beralih dari otoritarianisme menuju demokrasi dan mengadopsi ekonomi pasar akan condong pada kebijakan non-proliferasi, sementara bila rezim yang memerintah tidak demokratis, kebijakan yang ia buat ialah mengembangkan senjata pemusnah masal. Argumen ini berdasar pada teori perdamaian demokratis ala Kantian dalam studi hubungan internasional (Boulden dll, 2009: Bab 4). Kritik dibuktikan oleh survei yang kontras, khususnya di negara-negara demokrasi Dunia Ketiga, dimana tidak ditemukan relevansi positif antara tipologi rezim dengan luaran kebijakan nuklir, apalagi antara pilihan ekonomi pasar dengan preferensi non-proliferasi.China, India, Israel, dan Pakistan adalah empat sampel dalam kritik yang memfalsifikasi argumen perdamaian demokratis pemikir liberalis. Di luar negara Dunia Ketiga, demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mempertahankan program nuklir mereka untuk waktu yang lama (Sur, 2010: Bab 5). George Perkovich (2011) menganalisis kegagalan demokrasi sebagai resep efektif denuklirisasi dengan menyebutkan kehadiran variabel nasionalisme dan patriotisme dalam demokrasi yang cenderung mengarahkan kebijakan nasional pada urgensi kepemilikan senjata nuklir demi kepentingan nasional. 170 Norma Non-proliferasi Global Norma non-proliferasi nuklir global telah berhasil mengurangi tendensi perluasan dan pengembangan senjata pemusnah masal dengan cara persuasif untuk mengajak negara-negara nuklir menghentikan program senjata nuklir mereka. Non-Proliferation Treaty (NPT) mulai diberlakukan pada tahun 1970. Sebelum itu, sekitar 40% negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan teknologi untuk memproduksi senjata nuklir memilih kebijakan pengembangan nuklir dalam rangka pertahanan nasional.Setelah NPT diterapkan, terjadi penurunan jumlah aktor nuklir internasional secara signifikan, walaupun muncul beberapa pemain baru (Thakur, 2006: 104). Negara-negara yang bersedia menghentikan program senjata nuklir mengaku bahwa motivasi mereka ialah kepatuhan pada norma internasional yang sah. Sementara itu, negara yang belum sepenuhnya mengikuti NPT dan negara nuklir yang baru muncul mengemukakan alasan yang bervariasi. Studi konstruktivis seperti dilakukan oleh Jane Boulden dll (2009: 207) dan Nick Wilson dll(2005: 274-282) menyebut demokrasi sebagai faktor adaptif kebijakan nasional terhadap norma internasional. Negara yang mempraktikan sistem politik demokrasi dan ekonomi pasar terbuka dinilai lebih mudah menerima pengaruh transformatif rezim non-proliferasi nuklir global dibandingkan dengan negara dengan sistem politik dan ekonomi tertutup. Karena jumlah negara demokrasi terus bertambah, maka akseptabilitas norma nonproliferasi nuklir yang didukung oleh masyarakat internasional pun semakin tinggi. Survei yang dilansir oleh Wilson dll (2005: 275) memperlihatkan efektifitas NPT untuk membujuk negara-negara bekas Uni Soviet agar meninggalkan program senjata nuklir.Selain itu, NPT berhasil mencegah Argentina dan Brazil untuk mengembangkan senjata nuklir.Bagi negara-negara yang baru demokratis, terdapat satu alasan yang sangat mendasar di balik keputusan mengakhiri percobaan pengayaan senjata pemusnah masal, yakni keinginan untuk mendapatkan kemudahan diplomatik –dengan legitimasi internasional yang lebih kuat– sehingga bisa memperoleh keuntungan seperti insentif perdagangan dan finansial. Jadi, adaptasi demokrasi terhadap efek normapelucutan nuklir global berbanding lurus dengan motivasi memperoleh 171 legitimasi, yang pada gilirannya akan dapat membantu usaha perbaikan hubungan politik, keamanan dan ekonomi perdagangan sebuah negara dengan masyarakat internasional. Dalam kasus keputusan denuklirisasi oleh negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Ukraina, Belarusia dan Kazakhstan, peluru kendali berkepala nuklir yang berada di wilayah mereka dikembalikan kepada Rusia dengan alasan mereka ingin menjadi negara yang berdaulat penuh dan menjadi bagian utuh dari sistem internasional (Wilson dll, 2005: 276). Selain itu terdapat alasan-alasan yang bersifat lebih pragmatis. Keahlian untuk pemeliharaan senjata nuklir bekas Uni Soviet hanya dimiliki oleh teknisi dari angkatan bersenjata Rusia, sehingga mereka akan tergantung pada bantuan teknis Rusia, suatu hal yang tentu saja akan berimplikasi secara ekonomi dan politik. Eksistensi senjata nuklir mengingatkan masyarakat di ketiga negara tentang imperialisme Uni Soviet.Atas dasar ini, maka sebagai bagian dari usaha rekonsiliasi nasional senjata nuklir bekas Uni Soviet lebih baik dipulangkan. Pertimbangan keamanan regional dan global juga menjadi alasan. Pemerintah Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan menganggap bahwa mereka bisa berkontribusi dalam mencegah perluasan senjata nuklir, dalam hal ini potensi jatuhnya teknologi rudal balistik dengan hulu ledak nuklir ke tangan teroris, apabila senjata yang diwarisi dari Uni Soviet tidak dikembalikan ke pemilik yang sah, yaitu Rusia (Taubes, 1995: 1096-1097). Para konstruktivis percaya bahwa negara-negara nuklir harus didekati dengan cara persuasif untuk melakukan pelucutan senjata. Pengalaman sejarah program denuklirisasi internasional dalam wadah NPT mengajarkan bila masyarakat internasional hendak mencegah suatu rezim mengembangkan senjata nuklir, maka metode terbaik ialah menghindari koersi. Bentuk-bentuk tekanan kekerasan hanya akan berakhir dalam ketegangan dan kontroversi berlarut-larut (Blair, 2011: 173). Para pemimpin politik harus diberi pemahaman mengenai senjata nuklir sebagai instrumen yang kontraproduktif dalam diplomasi internasional, terutama karena program nuklirisasi militer tidak dilegitimasi oleh masyarakat internasional. Denuklirisasi secara negatif melalui sanksi ekonomi dan tekanan politik secara fisik hanya berhasil dalam satu kasus, yakni di Irakpasca Perang Teluk ke-2. Hal itu pun lebih banyak dipengaruhi oleh keberhasilan 172 pasukan multinasional melucuti persenjataan tentara nasional pengawal Saddam Hussein (Pilat, 1992: 1224). Dalam kasus-kasus lain, pendekatan yang mengandalkan pada penggunaan ancaman kekerasan secara eksesif biasanya tidak efektif. Oleh karena itu, di samping faktor norma non-proliferasi nuklir dan metode persuasi, faktor kalkulasi domestik memainkan peran penting di balik kebijakan denuklirisasi. Aktor-aktor pengusung agenda denuklirisasi global perlu meyakinkan elite pembuat kebijakan di tingkat lokal/nasional mengenai biayayang harus dikeluarkan jika mereka ingin menjadi negara nuklir (Boulden dll, 2009: 119). Sekalipun demikian, para konstruktivis tidak mengecilkan arti penting sanksi internasional untuk menyukseskan program denuklirisasi di suatu negara. Lindsay dan Takeyh (2010: 33) mengungkapkan bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara yang dituduh oleh pihak Barat memiliki senjata nuklir seperti Iran berdampak kepada semakin mahal biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah Iran untuk program nuklir, sekaligus memperlambat kemajuan program nuklir sipil mereka. Sanksi juga berfungsi untuk menambah tingkat efektifitas insentif yang dijanjikan. Dalam konteks ini, sanksi dan insentif merupakan taktik yang dapat dipadukan secara positif. Komitmen pemberian insentif setelah sanksi dicabut menjadi bagian tawar-menawar diplomatik yang terbukti berhasil memperlancar proses mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Seni berdiplomasi menggabungkan kemampuan membujuk dan mengancam demi melakukan pendekatan persuasif dan memberi imbalan kepada negara yang bersedia mengadakan perubahan kebijakan menuju denuklirisasi. Studi empiris mengkonfirmasi efektifitas kombinasi pendekatan diplomatis yang disertai dengan instrumen sanksi. Seperti diungkapkan oleh Bamaby (1993: 44), insentif tidak datang begitu saja dari negara penekan. Insentif adalah bagian dari formula proposal yang juga mencakup ancaman sanksi, dengan target untuk mempengaruhi kalkulasi kebijakan nuklir negara yang sedang didekati. Oleh karena itu, dalam satu paket usulan terdapat dua jenis tawaran, yakni yang berupa iming-iming bantuan, biasanya dalam bentuk finansial, dan ancaman berupa sanksi (bisa politik, ekonomi dan militer) agar negara nuklir mengurungkan niat mengembangkan senjata pemusnah masal.Para analis 173 kebijakan denuklirisasi, misalnya Serge Sur (2010: 77-88), berpendapat bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara metode pendekatan nirkekerasan dengan perubahan sikap negara nuklir. Bukti empiris mengindikasikan bahwa persuasi lebih efektif daripada sanksi. Kombinasi antara sanksi dan insentif lebih ampuh daripada insentif semata. Perlu dicatat bahwa dalam praktik sulit untuk membedakan dengan tegas antara insentif dan sanksi.Komitmen untuk mencabut sanksi ekonomi bisa menjadi wujud insentif, sedangkan keengganan untuk memberikan kemudahan akses ekonomi dan diplomasi dapat berarti sanksi. Dalam beberapa kasus –seperti isu Nuklir Korea Utara– paket insentif untuk program denuklirisasi ekuivalen dengan “diplomasi dollar.” Imbalan keuangan dan komersial diberikan ketika negara target bersedia mengubah perilaku kebijakan nuklirnya. Amerika Serikat telah menjadi negara utama yang memakai bantuan ekonomi sebagai pengganti program nuklir suatu negara (Tilleli dan Snyder, 2010). Jepang, Jerman, dan Rusia juga menggunakan pendekatan serupa, sekalipun terbatas pada asistensi teknis dan insentif finansial tertentu. Biasanya, ketiga negara ini memilih jenis insentif dengan sangat hati-hati, dengan faktor keamanan nasional masing-masing menjadi pertimbangan yang paling penting. Mereka membantu promosi agenda non-proliferasi nuklir hanya jika urusan keamanan prinsipilterganggu (Hughes 2007). Dalam kasus senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki dan sedang diperkuat oleh Iran, Jerman mengambil inisiatif penuh menggiatkan diplomasi, sementara Jepang dan Rusia aktif mendekati Washington agar bersedia berunding. Konsiderasi mereka berhubungan erat dengan potensi ancaman regional dan global dari krisis nuklir Timur Tengah (Hymans, 2010: 165). Fokus memajukan aktifitas non-proliferasi nuklir juga mencakup upaya penangkalan, yang meliputi pengawasan lalu lintas material uranium, kontrol terhadap ekspor bahan baku nuklir, serta pengendalian teknologi senjata yang kini dipunyai oleh semua negara yang bergabung dalam Nuclear Suppliers Group(NSG). Ward Wilson (2007: 168), seorang pakar keamanan regional Asia Timur dan Pasifik, mengatakan bahwa upaya penangkalan saja tidak cukup, apalagi bila tidak dilengkapi dengan mekanisme sanksi dan insentif. Bagi Wilson (2007: 170), negara yang mencoba membuat bom nuklir sedang mengalami 174 kondisi, atau paling tidak memiliki persepsiakan keamanan nasional yang sangat terancam dalam bentuk agresi eksternal. Dalam kondisi demikian, intervensi asing demi non-proliferasi harus dilakukan dalam bentuk diplomasi yang mampu meyakinkan negara nuklir bahwa kebijakan nuklir akan berdampak lebih merugikan, sekaligus mengajak untuk kerja sama keamanan. Isolasi dan sanksi hanya akan memperkeruh situasi, dan pada titik ekstrim membuat negara nuklir hanya mengetahui satu pilihan, yakni menciptakan bom nuklir. Untuk kasus nuklir Korea Utara, menurut Wilson (2007: 177) dan didukung pula oleh Tilleli dan Snyder (2010: 99-100), solusi terbaik adalah strategi diplomasi give-and-takeyang mencakup reassurance dan kerja samayang saling menguntungkan. Sanksi, koersi, dan pengucilan akan berakibat kontra produktif terhadap upaya pelucutan senjata nuklir. Demokratisasi dan Denuklirisasi Pengaruh faktor domestik dalam penentuan kebijakan suatu negara untuk melakukan pelucutan senjata nuklir diilustrasikan oleh kasus Argentina dan Brazil. Pemerintahan sipil yang menggantikan rezim militer di Argentina sejak 1983 dan Brazil sejak 1985 berketetapan untuk mengakhiri proyek senjata pemusnah masal berkepala nuklir yang diwariskan oleh rezim militer sebelumnya. Mereka beralasan senjata nuklir berbahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Era demokratisasi membawa perubahan fundamental pada arah politik luar negeri Argentina dan Brazil yang menjadi lebih kooperatif. Di bawah rezim militer, Argentina dan Brazil memang telah memulai proses trust-building, namun baru ketika pemerintahan sipil berkuasa proses tersebut diakselerasi melalui pembuatan keputusan yang lebih demokratis (Ricupera, 1992: 20). Kebijakan Washington memberlakukan pembatasan perdagangan material nuklir di benua Amerika, dalam konteks tertentu, memainkan peran penting untuk menghambat pembangunan instalasi nuklir Argentina dan Brazil, khususnya di bawah rezim militer. Paling tidak, Amerika Serikat berhasil mengalangi kesepakatan kerja sama antara Argentina dan Brazil dengan mitra nuklir mereka di Eropa dan NATO, seperti Jerman dan Perancis. Washington memblokade akses Argentina dan Brazil untuk memperoleh teknologi tingkat tinggi sebagai penunjang reaktor 175 nuklir mereka. Akses kedua negara untuk mendapat bantuan ekonomi dan keuangan lembaga-lembaga donor internasional juga dipersempit. Amerika Serikat berhasil mencegah Argentina dan Brazil menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kapabilitas nuklir (Albright, 1989). Para realis seperti Mitchell Reiss dan Robert Litwak (1994: 35) berargumen bahwa kasus kontrol ekspor nuklir yang diterapkan Washington terhadap Argentina dan Brazil membuktikan keefektifan mekanisme penangkalan fisik yang bertujuan untuk mengurangi laju konstruksi fasilitas nuklir negara yang berambisi memiliki proyek pengembangan nuklir. Secara sistematis, menurut Verdier (2008: 442), hambatan luar yang berasal dari kekuatan regional maupun global efektif guna menurunkan kompetensi nuklir suatu negara. Strategi restriksi nuklir secara spesifik berhasil memperlambat perkembangan program nuklir pada tahap awal. Baik Brazil maupun Argentina tidak dikenaisanksi sama sekali, pendekatan persuasi melalui janji insentif pun belum dicoba oleh Washington. Karena energi yang harus dikerahkan guna mengakses teknologi dan material nuklir eksternal semakin besar, biaya semakin banyak, dengan prediksi hasil yang belum bisa dipastikan, maka elite politik domestik memutuskan untuk meninggalkan program pengembangan senjata nuklir (The Economist,14 Maret 1992: 47). Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa keputusan menjalankan denuklirisasi lebih dilatarbelakangi oleh konsiderasi matematis domestik daripada respon positif terhadap tekanan asing. Pemimpin sipil di Argentina dan Brazil bisa menyamakan visi untuk memperbaiki hubungan bilateral. Mereka membangun momentum agar kerja sama antara kedua negara bertetangga kembali normal. Penyesuaian terhadap norma non-proliferasi dipandang penting demi meraih legitimasi yang berkaitan erat dengan akses diplomasi politik dan finansial dari masyarakat internasional. Mobilisasi sumber daya dari luar, bukannya kejayaan nasional di bidang militer,merupakan kepentingan nasional yang utama. Mantan Menteri Sains dan Teknologi Argentina Jose Goldemberg (dalam Marx, 1992: 10) menuturkan kisah di balik sukses kedua negara mengakhiri isolasi akibat proyek nuklir mereka. Kisah itu berawal dari keinginan kuat pemerintah Argentina untuk meyakinkan Brazil bahwa musuh utama mereka adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang 176 tidak perlu dihadapi dengan bom nuklir. Gagasan Argentina diterima oleh Presiden Brazil Fernando Collor de Mello. Kedua pihak lantas setuju melakukan pengurangan senjatanuklir dalam beberapa tahap, yang secara formal dirampungkan pada tahun 1991.Treaty of Tlatelolco mengesahkan pembentukan Brazilian-Argentine Accounting and Controls for Nuclear Materials yang bertugas sebagai lembaga inspeksi gabungan untuk menegakkan kepatuhan masing-masing pada agenda non-proliferasi bilateral (Schwab, 1989: 1400). Pengalaman Argentina dan Brazil menunjukkan bahwa resolusi atau setidaknya ameliorasi perbedaan politik dan kepentingan yang mendasar perlu dilakukan sebelum kerja sama denuklirisasi bisa berjalan. Para pengamat program non-proliferasi nuklir internasional seperti Michael Mazarr (1995) serta James Wirtz dan Peter Lavoy (2012) menggarisbawahi bahwa kasus Argentina dan Brazil memberi preseden untuk lingkup yang lebih luas, yakni sengketa nuklir di belahan lain dunia, termasuk antara India dan Pakistan, Israel dan negara-negara Teluk, serta Korea Utara hanya akan dapat diselesaikan melalui negosiasi apabila telah didahului dengan manajemen dan resolusi persoalan-persoalan fundamental yang menyangkut tujuan nasional setiap pihak yang terlibat. Dengan kata lain, resolusi konflik nuklir adalah implikasi positif dari resolusi konflik yang lebih menyeluruh. Perubahan Lingkungan Keamanan dan Denuklirisasi Berbeda dengan kasus Argentina dan Brazil yang memutuskan untuk meninggalkan program senjatanuklir setelah era pemerintahan sipil demokratis mulai berkuasa, denuklirisasi militer di Afrika Selatan didorong oleh perubahan persepsi elite mengenai lingkungan keamanan eksternal dan pengaruh pergeseran kecenderungan politik dalam negeri menuju demokrasi. Faktor eksternal lebih berperan dalam kasus Afrika Selatan.Sejak 1990, terjadi perombakan konstelasi politik regional menyusul memudarnya pengaruh Uni Soviet terhadap kekuatankekuatan komunis di Afrika bagian selatan yang semula menjadi ancaman eksternal utama bagi Afrika Selatan (Cock dll, 1998). Para akademisi politik nuklir global bersepakat bahwa kasus denuklirisasi di Afrika Selatan didorong oleh faktor ketiadaan justifikasi yang kuat untuk membangun persenjataan nuklir 177 setelah Perang Dingin usai (Olu, 2002). Isolasi internasional akibat praktik apartheid berimplikasi negatif terhadap keinginan elite Afrikaner untuk memiliki senjata penghancur masal. Isolasi internasional meningkatkan sentimen parokial dalam pandangan dunia para pemimpin kulit putih Afrika Selatan, yang kemudian merasa perlu untuk memiliki bom nuklir demi melindungi diri (Van Wyk, 2010: 57). Persepsi elite Afrika Selatan berubah drastis ketika Tembok Berlin runtuh, yang diikuti dengan kejatuhan rezim komunis di Afrika. Momentum yang sangat signifikan terjadi tahun 1989 saat Afrika Selatan, Angola, dan Kuba menyepakati perjanjian trilateral. Salah satu poin terpenting perjanjian yang merupakan kepentingan strategis Afrika Selatan ialah penarikan pasukan Kuba dari Angola dan kemerdekaan Namibia. Halini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kekuatan kawasan dari semula pro melawan kontra komunis, menjadi tinggal yang antikomunis. Presiden Afrika Selatan F. W. De Klerk mengakui bahwa keputusan pemerintahnya untuk menghentikan produksi senjata berhulu ledak atom didorong oleh situasi keamanan yang baru berupa lingkungan tanpa ancaman komunisme. Dengan demikian, Afrika Selatan tidak perlu lagi mengembangkan senjata nuklir untuk menghadapi Kuba (dalam Goodson, 2012: 210). Terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa de Klerk termotivasi oleh semangat rasial yang terus melekat dalam kepribadian dan politik luar negeri apartheid, di mana rezim kulit putih Afrika Selatan tidak mau mewariskan kekuatan nuklir kepada Partai Kongres Nasional yang dipimpin Nelson Mandela (Van Wyk, 2010: 62). Perubahan signifikan dalam politik administrasi juga berpengaruh dalam memuluskan jalan bagi denuklirisasi. Memasuki era rekonsiliasi nasional yang ditandai dengan pembebasan Mandela, negosiasi antara pemimpin kulit putih di bawah de Klerk dan Partai Kongres pun membicarakan soal pelucutan enam instalasi senjata nuklir Afrika Selatan. Mandela memutuskan untuk berkonsultasi dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta masuk ke dalam NPT pada tahun 1991 (Van Wyk, 2010: 70).Faksi di dalam pemerintah apartheid sendiri tidak solid mendukung nuklirisasi. Golongan teknokrat dan bisnis yang dominan sejak awal 1980-an telah resisten terhadap program senjata nuklir, 178 dengan alasan program nuklir Afrika Selatan memperburuk hubungan dengan Washington dan Eropa. Usaha Afrika Selatan untuk menjadi bagian komunitas negara-negara Barat pun dipersulit akibat sentimen negatif terhadap persenjataan nuklirnya (Goodson, 2012: 212). Walaupun Afrika Selatan telah membina kerja sama nuklir dengan Israel, dampak pengembangan senjata nuklir lebih merugikan bagi kepentingan nasional Afrika Selatan secara keseluruhan. Senjata nuklir menimbulkan stigma bahwa rezim apartheid agresif, disamping label diskriminatif dan rasis yang selalu inheren dengan rezim tersebut. Persepsi yang buruk dari masyarakat internasional membuat Afrika Selatan mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi nuklir dan penunjangnya yang bersifat sipil dan damai. Kerja sama dengan negara mitra seperti Israel tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modernisasi teknologi nuklir Afrika Selatan (Goodson, 2012: 213). Di sini, faktor legitimasi internasional yang dibawa oleh norma global seperti NPT dan the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) memegang peran penting dalam kasus denuklirisasi. Presiden De Klerk (dalam de Villiers dll, 1993: 100) memberikan pengakuan pribadi soal tekanan Barat terhadap Pretoria yang ingin menjadi kekuatan nuklir Afrika. Pada akhir dekade 1970-an, persiapan telah dilakukan untuk uji coba bom nuklir Afrika Selatan di Gurun Kalahari. Namun, rencana itu bocor karena tertangkap satelit Soviet. Datanglah tekanan bertubi-tubi dari Amerika Serikat dan masyarakat Eropa agar Afrika Selatan menyudahi program senjata nuklirnya. De Klerk pun membela kebijakan nuklir negaranya atas dasar kehendak untuk memperkuat masyarakat Afrika di panggung politik internasional. Tetapi, tindakan tersebut menyebabkan Pretoria dianggap sebagai negara agresif di kawasan dan dalam lingkungan global (dalam de Villiers dll, 1993: 101). Seorang pengamat politik Afrika Donald Goodson (2012: 230) mengatakan bahwa Afrika Selatan yang akhirnya menghentikan program pengayaan senjata nuklir bisa mengkritik negara-negara lain yang tidak mengambil kebijakan sejenis. Afrika Selatan memiliki legitimasi moral yang ditegaskan dalam NPT maupun CTBT. 179 Kesimpulan Penjelasan diatas mengindikasikan tiga hal utama untuk dicatat mengenai agenda global untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir. Pertama, dalam konteks akademik berbagai pendekatan teoritis yang menjelaskan faktor-faktor pendorong pemerintah suatu negara untuk mengembangkan ataupun meninggalkan program persenjataan nuklir sebenarnya bisa dipadukan secara eklektis demi memperoleh perspektif berfikir yang komprehensif. Semua faktor, baik yang mencakup situasi dalam negeri maupun lingkungan internasional, memainkan peran yang penting. Elemen strategis dan normatif seperti legitimasi menjadi determinan kebijakan denuklirisasi yang efektif. Metode yang dianjurkan pun bervariasi, mulai dari persuasi, sanksi hingga koersi, tergantung perhitunganuntung-rugi yang dibuat oleh pihak luar dalam rangka menyukseskan agenda denuklirisasi negara nuklir tertentu. Di sini, masing-masing sudut pandang teori dan praksis mempunyai kelebihan. Komponen-komponen kelebihan tersebut dapat digabungkan secara sinergis demi tujuan perubahan kebijakan negara nuklir menjadi non-nuklir. Kedua, arti penting denuklirisasi bagi perwujudan masyarakat internasional yang tertib dan aman sudah diakui sejak masa awal Perang Dingin. Dinamika kekuatan rezim non-proliferasi nuklir global paralel dengan perubahan tata dunia yang dikonstruksi oleh negara nuklir besar/utama (major nuclear powers), negara nuklir menengah (middle-range nuclear powers), dan negara yang aktif mengusahakan diri menjadi kekuatan nuklir/negara nuklir baru (new nuclear powers). Berbagai kebijakan denuklirisasi di Dunia Ketiga mengilustrasikan peran kekuatan nuklir besar yang lebih berpengaruh, khususnya dalam mendiktekan resolusi bagi kebijakan nuklir negara nuklir baru. Keefektifan rezim NPT dan CTBT di Dunia Ketiga berkorelasi dengan kemampuan negara nuklir utama untuk memainkan instrumen-instrumen pendekatan, persuasi dan sanksi kepada negara nuklir baru. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa politik nuklir internasional bersifat hierarkis, sentralistik dan asimetris. Dalam kondisi demikian, pertanyaan yang relevan bukanlah bagaimana menciptakan institusi global yang adil demi mencegah proliferasi senjata nuklir, tetapi apakah dengan segala mekanisme yang ada masyarakat internasional akandapat mengontrol 180 perilaku negara nuklir yang melanggar kesepakatan bersama. Ketiga, dalam tataran praktis isu nuklir menggabungkan empat elemen kebijakan luar negeri, yakni kepentingan nasional, persepsi pembuat keputusan, moralitas dan legitimasi internasional, serta diplomasi. Norma internasional seperti NPT dan CTBT didesain untuk menjalankan fungsi yang unik sebagai pencipta ketertiban di tengah anarki. Perjanjian antarnegara merupakan alat kontrol tindakan politik luar negeri yang tidak berorientasi pada nilai seperti kerelaan maupun kebajikan. Ketertiban diupayakan dengan cara-cara yang rasional dan untuk situasi spesifik bersifat pragmatis. Terdapat evaluasi untung rugi yang menjadi landasan kepatuhan negara nuklir pada agenda denuklirisasi global. Dapat disimpulkan bahwa substansi ketertiban melalui proses diplomasi NPT maupun CTBT berada di level yang lebih tinggi dari pada individualisme realpolitik dan politik moral utopis. DAFTAR PUSTAKA Buku Alagappa, Muthiah. 2008. The long shadow: nuclear weapons and security in 21st century Asia. Stanford: Stanford University Press. Bamaby, Frank. 1993. How nuclear weapons spread: nuclear weapons proliferation in the 1990s. London: Routledge. Bergner, Jonathan D. 2012. “Going nuclear: does the non-proliferation treaty matter?”Comparative Strategy.31(1): 84-102. Boulden, Jane dll. 2009. United Nations and nuclear orders. Tokyo: United Nations University. Cock, Jacklyn dll. 1998. From defence to development: redirecting military resources in South Africa. Ottawa:International Development Research Centre. Hagold, Mathew. 2011. International law in a multipolar world. Hoboken: Taylor & Francis. Johnson, Rebecca. 2009. Unfinished business: the negotiation of the CTBT and the end of nuclear testing. New York & Geneva: United Nations. Lettow, Paul. 2010. Strengthening the nuclear non-proliferation regime. New York: Council on Foreign Relations. Olav, Njelstad. 2010. Nuclear non-proliferation and international order: challenges to non-proliferation treaty. Hoboken: Taylor & Francis. 181 Olu, Adeniji. 2002. The treaty of Pelindaba on the African nuclear weapon free zone. Geneva: UNIDIR. Reiss, Mitchell dan Robert Litwak. 1994. Nuclear proliferation after the Cold War. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press. Thakur, Ramesh C.,dll. 2006. Arms control after Iraq: normative and operational challenge. Tokyo: United Nations University Press. Tilleli, John M. dan Scott Snyder. 2010. U.S. policy toward the Korean Peninsula. New York: Council on Foreign Relations. Utgoff, Victor A. 2000. The coming crisis nuclear proliferation: U.S. interests and world order. Cambridge: MIT Press. Wirtz, James dan Peter Lavoy. 2012. Over the horizon proliferation threats. Pallo Alto: Stanford University Press. ..... 010. International law, power, security and justice. Oxford: Hart Publishing. Jurnal Albright, David. 1989. “Bomb potential for South America.”Bulletin of the Atomic Scientists.45(4): 16-20. Asada, Masahiko. 2011. “The treaty of the non-proliferation of nuclear weapons and the universalization of additional protocol.”Journal of Conflict and Security Law.19(1): 3-34. Bertsch, Garyk dll. 1997. “Trade, export control and non-proliferation in the Asia Pacific region.”The Pacific Review.10(3): 407-425. Blair, Bruce. 2011. “Can disarmament work? debating the benefits of nuclear weapons.”Foreign Affairs.90(4): 173. Bowen, Wyn C., dll. 2012. “Multilateral cooperation and the prevention of nuclear terrorism.”International Affairs.88(2): 349-368. Carranza, Mario E. 2006. “Can the NPT survive? theory and practice of the U.S. nuclear non-proliferation policy after September 11.”Contemporary Security Policy.27(3): 489-525. Cortright, David dan Raimo Vayrynen. 2009. “Chapter one: why disarmement? why now?”The Adelphi Papers.49(410): 13-32. De Villiers, J. W. dll. 1993, “Why South Africa gave up the bomb.”Foreign Affairs.72(5): 98-109. Evan, William M. dan Bretb Hays. 2006. “Dual use technology in the context of nonproliferation regime.”History and Technology.21(4): 105-113. Fitzpatrick, Mark. 2008. “Non-proliferation and counter proliferation: what is the difference?”Defense & Security Analysis.24(1): 73-79. Goodson, Donald I. 2012. “Catalytic deterrence: apartheid South Africa’s nuclear weapon strategy.”Politikon.10(1): 309-330. Hughes, Llewelyn. 2007. “Why Japan will not go nuclear (yet): international and domestic constraints to nuclearization of Japan.”International Security.31(4): 6796. 182 Hymans, Jacquese C. 2010. “When does state become a nuclear weapon state? an exercise in measurement validation.”The Nonproliferation Review.17(1): 161-180. Karp, Regina. 2012. “Nuclear disarmament: should America lead?”Political Science Quarterly.127(1): 47-71. Lindsay, James M dan Ray Takeyh. 2010. “After Iran gets the bomb: containment and its complications.”Foreign Affairs.89(2): 33. Marks, Joel. 2009. “Nuclear prudence or nuclear psychosis?: structural realism and proliferation of nuclear weapons.”Global Change, Peace and Security.21(3): 325340. Marx, Gary. 1992. “Latin American nuclear proliferation dims as nations stress trade.”Journal of Commerce and Commercial.392(27720): 10. Mazarr, Michael. 1995. “Going just a little nuclear: non-proliferation lessons from North Korea.”International Security.20(2): 92-122. Nye Jr., Joseph S. 1992.“New approaches policy.”Science.256(5061): 1293-1297. to nuclear non-proliferation Pilat, Joseph F. 1992. “Iraq and the future of non-proliferation: the roles of inspections and treaties.”Science.255(5049): 1224-1229. Potter, William C. 2010. “The NPT; the sources of nuclear restraint.”Daedalus.139(1): 68-81. Reich, Jacqueline C. 2011. “Achieving the vision of NPT: can we get there step by step?”The Nonproliferation Review.18(2): 369-384. Ricupero, Rubens. 1992. “No bombs for Brazil.”The Christian Science.84(64): 20. Schulte, Gregory. 2010. “Stopping proliferation before it starts: how to prevent nuclear wave.”Foreign affairs.89(4): 85. Schwab, Carol M. 1989. “Treaty for the prohibition of nuclear weapons in Latin America.”International Legal Materials.28(6): 1400-1423. Simpson, John dan Darryl Howlett. 1994. “The NPT renewal conference: stumbling toward 1995.”International Security.19(1): 41-71. Steinberg, Gerald. 1994. “Non-proliferation: time for regional approaches?”ORBIS.38(3): 409-424. Sur, Serge. 2005. “Non-proliferation and the NPT review.”The International Spectator.40(3): 7-18. Tagma, Mustafa. 2010. “Realism at the limits: post-cold war realism and nuclear rollback.”Contemporary Security Policy.31(1): 165-188. Taubes, Gary. 1995. “The defence initiative of the 1990s.”Science.267(5201): 1096-1099. “The Latin safety network: growth of democratic governments and nuclear nonproliferation in Latin America.”The Economist, 14 March 1992. 322(7750): 47. Van Wyk, Martha. 2010. “Sunset ver atomic apartheid: United States-South African nuclear weapon relations, 1981-1993.”Cold War History.10(1): 51-79. Verdier, Daniel. 2008. “Multilateralism, bilateralism, and exclusion in the nuclear proliferation regime.”International Organization.62(3): 439-476. Weber, Steve. 1990. “Realism, Organization.44(1): 55-82. detente, and nuclear weapons.”International 183 Wilson, Nick dll. 2005. “Lessons from the unsuccessful 2005 nuclear non-proliferation treaty.”Medicine, Conflict and Survival.21(4): 274-282. Wilson, Ward. 2007. “The winning weapon: rethinking nuclear weapon in light of Hiroshima.”International Security.31(4): 162-179. Zagare, Franks. 1996. “Classical deterrence theory: a critical assessment.”International Interactions.21(4): 365-387. 184