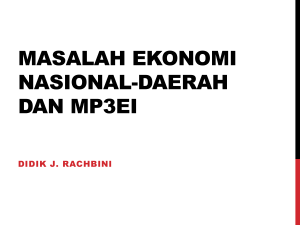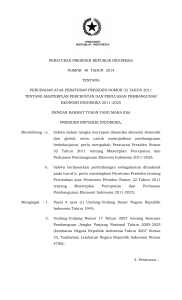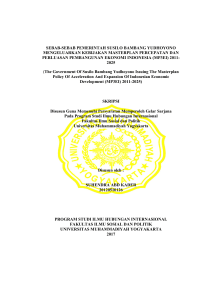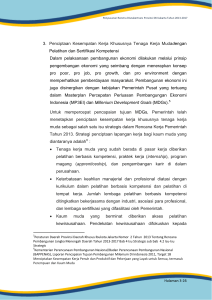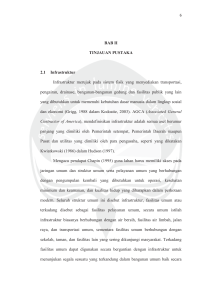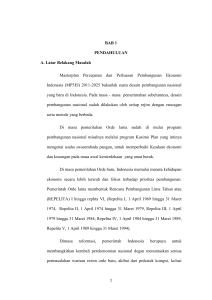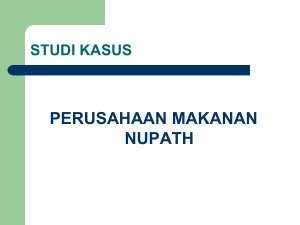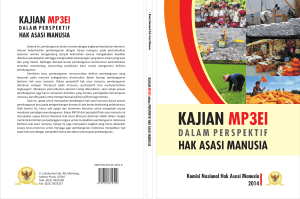pointers - Referensi HAM
advertisement

POINTERS Beberapa Catatan tentang Pembangunan di Indonesia Disusun oleh: Asep Mulyana, SIP, MA Peneliti pada Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Disampaikan pada Seminar “MP3EI: Harapan atau Utopia?” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 30 Juli 2013 1 Beberapa Catatan tentang Pembangunan di Indonesia Oleh Asep Mulyana, SIP, MA Peneliti Komnas HAM A. Pengantar 1. Indonesia telah melakukan transisi menuju demokrasi sejak 1998. Ada banyak perubahan besar terjadi. Tiga perubahan yang layak dicatat dan berpengaruh pada politik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, yaitu: (a) adopsi norma dan standar HAM yang diakui secara internasional ke dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya; (b) bandul pendekatan pembangunan yang bergeser dari teknokratisme-terpusat menuju model pembangunan partisipatif kemudian kembali ke semula; (c) desentralisasi yang menyebarkan sumber daya politik dari pusat ke daerah. 2. Segera setelah Soeharto jatuh pada 1998, rejim pasca-Soeharto mengesahkan amandemen UUD 1945 yang mengadopsi sejumlah norma HAM ke dalam konstitusi. Pada saat yang nyaris bersamaan, pemerintah juga mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dengan demikian, HAM memiliki skema perlindungan yang sangat memadai karena ia telah menjadi hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh para pemegang kekuasaan negara. 3. Namun demikian, penyusunan norma dan kelembagaan HAM tersebut tidak serta-merta menghilangkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bahkan pada rejim politik SBY jilid II, kasus-kasus konflik dan kekerasan ibarat “bom waktu” yang meledak di berbagai lini. Konflik dan kekerasan akibat perebutan sumber daya (baca: lahan) antara negara, perusahaan, dan warga, misalnya, meruyak di beberapa tempat. Kasus-kasus itu bermuara pada minimnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga, baik hakhak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Selama ini, analisis-analisis tentang politik HAM terjebak pada pendekatan legalistik yang membayangkan bahwa penegakan HAM akan mudah dilakukan ketika regulasi, kelembagaan, dan norma HAM diperkuat. Namun fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM terus terjadi meski penguatan regulasi, kelembagaan, dan norma HAM telah dilakukan. 5. Sesungguhnya proses penegakan HAM tidak berdiri di ruang hampa. Mata rantai pelanggaran HAM tidak akan terputus jika paradigma pembangunan yang sangat propasar dan promodal masih menjadi primadona. Dalam konteks ini, analisisanalisis HAM belum mampu menjelaskan relasi antara paradigma pembangunan dengan tingkat pelanggaran HAM. Penghampiran HAM selama ini cenderung terlalu legalistik. Penghampiran ini tidak melihat pola pembangunan nasional yang terlalu propasar dan promodal justru menjadi pemicu lahirnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia (Rosser, 2013). 6. Pelanggaran HAM terjadi ketika dalam proses pembangunan warga mengalami eksklusi dari sumber-sumber daya ekonomi dan sosial. Situasi ini bertambah rumit ketika desentralisasi yang sejatinya bertendensi untuk menghapus 2 sentralisasi kekuasaan, justru hanya mengalihkan sentralisasi tersebut dari pusat ke daerah. 7. Desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah memberikan jaminan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial secara mandiri. Dalam ruang politik dimana relasi patronase dan pencarian rente masih menjadi watak politik yang dan warga masih belum menjadi kekuatan politik yang menonjol, maka sumber-sumber daya ekonomi dan sosial masih dikuasai oleh oligarki politik yang terbangun di daerah. Warga tetap mengalami eksklusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. B. Pergeseran Paradigma Pembangunan 7. Skema penataan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh paradigma ekonomi mainstream dan hegemonik yang mendasari pembangunan di negara-negara bangsa di dunia. Sulit untuk membantah bahwa paradigma ekonomi neoliberal yang diinjeksi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, utamanya Bank Dunia dan IMF, telah menjadi landas pijak tata kelola ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia selama puluhan tahun. 8. Namun neoliberalisme—paradigma ekonomi hegemonik yang telah menjadi landasan berpikir dan praktik dalam tata kelola ekonomi dan sosial negaranegara bangsa di dunia—sebetulnya tidak berwajah tunggal. Neoliberalisme telah mengalami tiga kali pergeseran secara paradigmatik. Saad-Filho (2010) mencatat tiga kelompok pandangan utama dalam neoliberalisme, yaitu: (a) Neoliberal pra-Konsensus Washington; (b) Neoliberal Konsensus Washington; (c) Neoliberal Paska-Konsensus Washington (PKW). 9. Neoliberal Pra-Konsensus Washington ditandai oleh dominasi gagasan modernisasi dan teori pembangunan. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan oleh buruknya modal (mesin, infrastruktur, dan uang). Menurut gagasan ini, masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Dunia Ketiga dapat diatasi jika negara-negara di Dunia Ketiga melakukan transisi melalui modernisasi ke tipe ideal kapitalisme maju dengan lima tahapan yang dipopulerkan oleh Rostow (1960). Pembangunan dan industrialisasi sebagai salah satu tahap modernisasi dijalankan dengan melembagakan kebijakan ekonomi di bawah koordinasi negara atas proyekproyek investasi berskala besar—termasuk kepemilikan publik atas sektorsektor kunci—untuk membangun infrastruktur ekonomi yang penting bagi industrialisasi yang dipimpin oleh sektor swasta. Pendekatan “big push” ini diasumsikan akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat yang merangsang penciptaan kesempatan kerja, stabilitas makroekonomi, dan keseimbangan pembayaran berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mampu menghapus kemiskinan melalui “trickle down effect”. (Saad-Filho 2000). Pandangan ini banyak menuai kritik setelah didapati kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesetaraan dalam ekonomi global dan gagal menghapus kemiskinan dan ketimpangan domestik. Paradigma ini justru melahirkan rejim-rejim pembangunan yang otoriter secara politik. 3 10. Paradigma pembangunan yang teknokratik-terpusat ini dilembagakan dalam proses pembangunan pada era Soeharto hingga 1980-an (Mas’oed 1989). Ketika menerapkan paradigma ini, rejim politik mampu melahirkan kelas kapitalis domestik (Robison 1986). Namun kelas ini tidak mandiri karena ia tidak muncul secara organis dari borjuasi kecil islam tradisional. Negara yang kuat memiliki otonomi relatif terhadap kepentingan modal. Pada era ini pula politik pendisiplinan warga yang ketat melalui berbagai instrumen politik diterapkan untuk memuluskan jalan pembangunan. Pelanggaran HAM pun marak di berbagai tempat. 11. Neoliberal Konsensus Washington (KW) melekat pada ideologi neoliberal universal dengan komitmen absolut pada pasar bebas dan membayangkan bahwa negara merupakan sumber korupsi dan inefisiensi. Pendekatan ini percaya bahwa pasar—dan bukan negara—yang seharusnya berperan dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan industri, penciptaan kesempatan kerja, dan penyetaraan kompetisi internasional. Pendekatan ini memprioritaskan pengetatan anggaran, privatisasi, penghapusan intervensi negara dalam harga, fleksibilitas pasar buruh dan perdagangan, keuangan, dan liberalisasi modal. Pnghampiran ini juga memberikan tekanan pada deregulasi dan privatisasi untuk membatasi pencari rente, korupsi, dan menekan kebijakan distribusi. Pandangan ini mengundang kritik ketika kemiskinan makin meruyak akibat proses penyesuaian struktural dan stabilisasi serta politik domestik tidak ramah terhadap politik demokratik (Saad-Filho 2000). Pembangunan di Indonesia pascaderegulasi awal 1980-an hingga awal krisis 1997 sangat dekat dengan paradigma ini. 12. Neoliberal Pasca-Konsensus Washington dikembangkan dari teori ekonomi institusional baru yang dipopulerkan oleh Stiglitz—seorang pejabat teras Bank Dunia. Pendekatan ini melibatkan dimensi sosial dalam skema pembangunan, karena percaya bahwa inklusi ekonomi warga ke dalam pasar untuk mencapai kesejahteraan. Pendekatan ini juga mengusung kebijakan berdimensi sosial, utamanya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, dalam tata kelola pemerintahan (Carroll 2000, Jayasuriya 2006). Pembangunan di Indonesia pascareformasi, utamanya pada rejim SBY jilid I, sangat dekat dengan penghampiran ini. Hal ini, misalnya, tampak pada adanya program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mendorong partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Pro-poor pro-growth pro-job menjadi jargon yang terkenal. Meski demikian, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan isu hubungan kekuasaan di dalam pasar serta membangun sebuah pendekatan manajerial-teknokratik ke dalam politik yang berdampak pada depolitisasi konflik dan perjuangan kelas dalam pembangunan (Carroll 2007). Dalam ruang politik yang masih kental dengan patronase politik, paradigma ini menjadikan politik menjadi antipolitik. Partisipasi tidak bersifat genuine, dan lebih tampak sebagai mobilisasi. Pendekatan ini lebih fokus pada peningkatan kapabilitas ekonomi warga, sehingga warga dapat berpartisipasi dalam ruang ekonomi pasar. Pendekatan ini mengabaikan urgensi kapasitas politik warga dalam pembangunan. Dengan demikian, Kewargaan yang dibangun bukan kewargaan sosial, melainkan kewargaan pasar. 4 C. MP3EI: Bandul yang Kembali 13. Pada 20 Mei 2011, Presiden SBY merilis Peraturan Presiden (Perpres) No.32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 (MP3EI). Perpres ini dilampiri oleh buku setebal 210 halaman, berisi strategi, tata cara, dan protokol pelaksanaan kegiatan pembangunan. Secara umum, MP3EI bertujuan agar pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. 14. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa MP3EI bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pemerataan pembangunan regional, ketahanan pangan, pembangunan sektor maritim secara terpadu, pengembangan infrastruktur untuk membanguna konektivitas antarwilayah, indutri berbasis SDA, dan peningkatan IPM. 15. Dalam slogannya, disebutkan bahwa MP3EI merupakan terobosan dan “not business as usual”. MP3EI juga mengawal konektivitas dan bottlenecking untuk percepatan investasi. Dalam perspektif MP3EI, Indonesia dibagi ke dalam enam koridor ekonomi. Adapun enam koridor itu, yaitu: a. Koridor Sumatera: sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; b. Koridor Jawa: pendorong industri dan jasa nasional; c. Koridor Kalimantan: pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; d. Koridor Sulawesi: pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional; e. Koridor Bali dan Nusa Tenggara: pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional; f. Koridor Papua dan Maluku: pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan. 16. MP3EI menggunakan pendekatan Geografi Ekonomi Baru (Krugman 1991) yang membentuk ulang geografi ekonomi baru dalam rangka memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang, dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi-konsumsi. Reorganisasi dan penataan geografi yang tepat diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi dan transaksi serta meningkatkan pertumbuhan. Pendekatan ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan pembangunan geografi yang tak merata (uneven geographical development)—yang dihasilkan oleh neoliberalisme untuk masuk kembali ke dalam reproduksi kapitalisme. Dengan demikian, kerangka MP3EI merupakan cara untuk meneguhkan kembali kekuasaan kelas yang dominan (Sayogyo Institute 2013). 17. MP3EI seperti mengembalikan bandul pembangunan ke tempat ketika rejim Orde Baru berkuasa dimana pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menjadi kata kunci. Dalam konteks ini, bukan pula sebuah kebetulan jika pemerintah mendesakkan regulasi yang bertujuan pada pendisiplinan warga. UU Pengadaan Tanah, UU Ormas, dan RUU Keamanan Nasional—untuk menyebut beberapa— memiliki spirit untuk membangun ketertiban umum dan disiplin warga. 18. MP3EI mengembalikan “bulan madu” negara dan pasar. Sejak keterbukaan politik terjadi pasca-1998, kaum kapitalis domestik, baik di level nasional maupun lokal, mulai menggeliat. Kompetisi politik yang terbuka, utamanya di 5 19. 20. 21. 22. 23. tingkat lokal, telah memungkinkan kaum kapitalis lokal dapat menjangkau dan memasuki ranah politik (Aspinal 2013). Di tengah kapasitas politik warga yang lemah di satu sisi, dan kendali modal yang kuat di sisi lain, perencanaan kebijakan pembangunan sangat rawan dikendalikan oleh oligarki modal-kuasa. Lagi-lagi, warga akan mengalami eksklusi dari proses politik, ekonomi, dan sosial. Proyek-proyek MP3EI yang bernilai sangat besar (triliyunan) bisa menjadi ruang bagi pencarian rente para birokrat di daerah. Sebuah riset menunjukkan bahwa menjelang Pemilukada, penerbitan ijin usaha di sektor perkebunan dan pertambangan meningkat tajam. Pembiayaan Pemilukada diduga menjadi latar belakang fenomena ini. Dampak dari pencarian rente dalam penerbitan ijin dirasakan oleh warga yang kehilangan hak-hak dasarnya. Belum lagi akibatakibat lain dari proyek-proyek pembangunan yang minus kontrol publik, antara lain, pencemaran, deforestasi, dan kemiskinan yang makin akut. Dalam beberapa hal, MP3EI mirip dengan pola pembangunan yang dibangun pada era kolonial dimana pembangunan infrastruktur digenjot untuk memuluskan aliran sumber daya alam mentah dan akumulasi modal primitif. Proyek-proyek MP3EI yang lebih banyak menggenjot pembangunan infrastruktur sangat rawan dengan proses eksklusi terhadap warga dari tempattempat yang menjadi sumber penghidupannya. Tanpa skema penyelesaian konflik agraria yang komprehensif, maka proyek-proyek MP3EI hanya akan melestarikan proses pembangunan yang merampas hak-hak dan kebebasan dasar warga, utamanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di atas semua itu, pendekatan pembangunan di dalam skema MP3EI yang kurang memperhatikan partisipasi warga, lebih top-down, dan berwatak teknokratik, cenderung mengekslusi warga dari proses pembangunan nasional, yang semua itu bermuara pada pelanggaran HAM yang makin massif dan sistemik. D. Pembangunan Berbasis HAM: Sebuah Alternatif 24. Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan adanya revisi total atas paradigma pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada kepentingan pasar dan modal sebagaimana diusung MP3EI. 25. Sebagai sebuah alternatif, sebuah pendekatan pembangunan berbasis hak (rights-based approach to development) menjadi penting untuk dikemukakan agar pembangunan mencapai tujuan kesejahteraan. Pendekatan ini mengandaikan pembangunan dan HAM menjadi dua konsep yang tak terpisahkan dalam sebuah proses perubahan sosial (Uvin 2004: 122). Pendekatan ini merupakan suatu kerangka kerja yang terintegrasi dan multidisiplin untuk pembentukan, artikulasi, dan implementasi kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan. 26. Tiga hal yang harus ada di dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, yaitu bahwa pembangunan harus: a. berbasis pada prinsip-prinsip HAM; b. menghormati isi normatif HAM; c. sejalan dengan sifat dan level kewajiban HAM yang dipikul oleh negara. 6 27. Adapun prinsip-prinsip HAM yang mendasari pendekatan pembangunan berbasis HAM, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi rakyat, kapasitas legislatif, independensi lembaga peradilan, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip nondiskriminasi, perhatian pada kelompok rentan, pemberdayaan, universalitas, interdependensi, saling terhubung satu sama lain, dan tidak bisa dibagi-bagi. Prinsip-prinsip HAM ini mensyaratkan beberapa hal, yaitu jaminan akses untuk proses pembangunan, kelembagaan, dan informasi, memasukkan mekanisme ganti-rugi dan akuntabilitas, serta mengintegrasikan mekanisme pengamanan atas ancaman HAM dan memperkuat keseimbangan kekuasaan (Diokno 2004). BIBLIOGRAFI Aspinal, Edward. 2013. “Kemenangan Modal? Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia”. Prisma Volume 32 No. 1. Carroll, T. 2007. The Politics of The World Bank’s Socio-Institutional Neoliberalism. Perth: Murdoch University Diokno, Maria Socorro I. 2004. Human Rights Centered Development. Quezon City: The University of the Philippines Press Freeman, Michael. 2002. Human Righs. Cambridge: Polity Press Jayasuriya, K. 2006. Statecraft, Welfare, and the Politics of Inclusion. New York: Palgrave Macmillan. Critical Asian Studies 36 (4). Roberts, K. 1995. “Neoliberalisme and the Transformation of Populism in Latin America: the Peruvian case”. World Politics 48 (1): 82—116 Robison, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen and Unwin Rosser, Andrew. 2013. “Memahami Pelanggaran HAM di Indonesia”. Prisma Vol. 32 No. 1 Rostow, WW. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. Saad-Filho. 2010. “Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth” DESA Working Paper No. 100. ST/ESA/2010/DWP/100 Stiglitz. J. 2004. “The Post Washington Consensus Consensus”. Initiative for Policy Dialogue. Columbia University. Uvin, Peter. 2004. Human Rights and Development. Bloomfoeld: Kumarian Press Weyland, K. 1996. “Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities”. Studies in Comparative International Development 32 (3): 3—31. Weyland, K. 2003. “Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: how much affinity?” Third World Quarterly. Vol 24 No 6 pp 1095–1115. Yustika, Ahmad Erani. 2013. “Analisis Sosial Ekonomi MP3EI”. Presentasi tidak diterbitkan, disampaikan pada Diskusi Berseri MP3EI di Komnas HAM, Jakarta, 24 April 2013. 7 Tentang Asep Mulyana Asep Mulyana adalah peneliti yang meminati isu-isu HAM, demokrasi, dan pembangunan. Ia pernah mengikuti pendidikan HAM tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Equitas di Montreal, Kanada (2008). Pada 2011 Asep menyelesaikan sekolah pascasarjana ilmu politik dengan konsentrasi HAM dan Demokrasi di Universitas Gadjah Mada (Indonesia) dan Universitetet i Oslo (Norwegia). Sejak 2006 hingga kini, Asep bekerja sebagai peneliti di Komnas HAM. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: [email protected]. 8