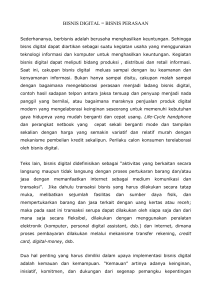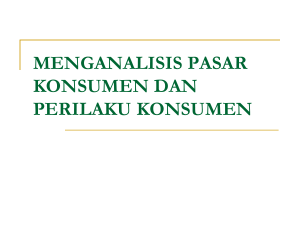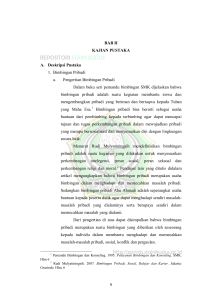Pergulatan Identitas dan Ghibah Infotainment
advertisement

KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan p-ISSN: 1979-598X e-ISSN: 2548-1770 Vol. 32 No. 2, Desember 2016 Pergulatan Identitas dan Ghibah Infotainment: Analisis Resepsi atas Aktivitas Bermedia Salafi di Yogyakarta Identity and Infontainment Grave: Analysis of the Reception of Salafi Activities in Yogyakarta Robby Habiba Abror Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakartka Jl. Marsda Adisucipto No. 1 Depok Sleman Yogyakarta Email: [email protected] Submitted: Nov 27, 2016; Reviewed: Des 8, 2016; Accepted, Des 10, 2016 Abstrak: Komunitas Salafi sebagai ritus praksis Islamisme sering diidentikkan dengan stigma terorisme, fundamentalisme, radikalisme, konservatisme, dan skripturalisme. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka menjalani hidup ini dengan mengikuti praktik kehidupan Salafus Salih yaitu tetap merujuk dan berpegang teguh pada manhaj Salaf. Dalam praktiknya, komunitas Salafi ini menyikapi berbagai tantangan modernitas dalam keserbagaraman perspektif. Hal ini disebabkan komitmen mereka terhadap dogmatisme agama yang ketat dan mengikat. Realitas tersebut menjadikan komunitas Salafi menjadi gerakan subkultur Islam yang menarik untuk diteliti. Pada praktiknya, dalam konteks resepsi mereka terhadap ghibah infotainment, terjadi kontestasi makna dan negosiasi terhadap dogma-dogma agama serta para mufti. Untuk itu, penelitian ini mengoperasikan konsep subkultur Hebdige, resepsi Stuart Hall, aktivisme Islamis Wiktorowicz, negosiasi Ting-Toomey, dan kontestasi Vancil. Fokus pada enam pondok pesantren Salafi di Yogyakarta (Pesantren Ihyaus Sunnah, Pesantren al-Anshar, Pesantren bin Baz, Pesantren Taruna al-Quran, Pesantren Hamalatul Quran, dan Pesantren Khoiro Ummah) serta jama’ah Masjid MPR. Praktik subkultur Salafi menunjukkan adanya tegangan di antara dogma agama dan modernitas. Komunitas Salafi melakukan afirmasi gaya hidup dalam keteguhan kredo serta negosiasi makna dan identitas mereka dalam kontestasi vis-a-vis dogmatisme agama dan mufti serta komunitas Islam mainstream. Dengan bercadar, wanita Salafi telah melakukan bunuh diri sosial. Komunitas Salafi mengonsumsi teknologi dan meresepsi fenomena Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 141 ghibah infotainment, tidak anti-modernitas, menampilkan sikap estetis-religius sebagai penanda perlawanan simbolik-eksistensial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas Salafi tidak selamanya ajeg dalam gerakan Islamisme yang monoton, tetapi mereka mempresentasikan bentuk eksistensi sebagai Salafi postmodern dengan pilihan dan kebebasan hidup serta genre dakwah barunya, selanjutnya mereka memposisikan diri dalam trend baru gaya Salafi dalam modernitas. Kata-kata kunci: Salafi, ghibah infotainment, negosiasi, kontestasi, dan Islamisme. Abstract: The Salafis, an Islamic praxis sect, are commonly presumed to be associated with terrorism, fundamentalism, radicalism, conservatism, and literalism. Although its followers originate from diverse backgrounds however they all share the common feature of adhering to the Salafus Salih, implying the commitment to refer to the Salaf manhaj in guiding their way of life. Nevertheless the challenges of modernity inevitably push Salafists to embrace a diversity of understanding with relation to their beliefs. This is because on the one hand, they are strongly loyal to their religious dogma and on the other, modernity purportedly constrains the application of religious dogma in the everyday lives of the Salafists. Such realities make the Salafists an Islamic subculture movement which becomes an interesting object of research. Interestingly in the context of the Salafists’ reception towards infotainment ghibah (gossip television programs), contested meanings and negotiations towards religious dogma as well as mufti rulings are evident. Therefore, the current study utilized Hebdige’s concept of subculture, Hall’s concept of reception, Wiktorowicz’s concept of Islamic activism, Ting-Toomey’s concept of negotiation and Vancil’s concept of contestation. A qualitative approach was selected, using the phenomenological-cultural studies paradigm. Six Salafist Islamic boarding schools in Yogyakarta (Ihyaus Sunnah, al-Anshar, bin Baz, Taruna al-Quran, Hamalatul Quran, and Khoiro Ummah) and also Salafist community in Masjid MPR were analyzed. The study collected data by interviewing 16 informants, in addition to conducting direct observation and documentation as a way to clarify and confirm the primary data. The data was then analyzed using an interpretativecritical method using Miles, Hubermas, and Creswell’s 3 phase technique of data reduction, presentation, and conclusion or verification. Based on a review of the theoretical literature as well as data from the field, the research found that the Salafists’ experienced tension between the requirements of strict adherence of dogma and the embracement of modernity. With veiled (purdah), Salafist woman has committed social suicide. The Salafist community affirms their life style by strictly following their creeds as well as negotiating the Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 142 meaning of their identity in contestation vis-à-vis religious dogmatism and mufti rulings as well as the mainstream Islamic community. The study found that the Salafist community are consumers of technology and gossip television programs, are not anti modernity, and they display a religious aesthetic attitude as a symbol of symbolicexistential resistance. This study also found that Salafists are not always rigid with regard to the Islamic movement. Nevertheless, they represent the postmodern Salafists of which choice and liberty color the new preaching (dakwah) genre, and thus subsequently position themselves as the new Salafist trend in modernity. Key words: Salafi, infotainment gossip, negotiation, contestation, and Islamism. A. Pendahuluan Berkaitan dengan dogma dan modernitas, komunitas Salafi sebagai salah satu gerakan Islamis yang seringkali dicap radikal, fundamentalis, dan konservatif, justru mempunyai gaya subkulturnya sendiri dalam melakukan interpretasi terhadap dogma agama yang mengikat maupun tantangantantangan modernitas. Mengacu pada pendapat Habermas1 yang membenarkan fundamentalisme agama yang selalu resisten terhadap modernitas dalam batas tertentu dapat dipahami, dan pendapat Barton 2 yang memisahkan radikalisme Islam dengan konservatisme agama dapat memperkaya dan membantu analisis terhadap gerakan Salafisme yang kenyataannya memang mempunyai kecenderungan lari dari modernitas dan membangun kehidupan serba dogmatis dengan selalu berusaha menghadirkan masa Salafus Salih dalam kehidupan mereka sehari-hari. Komunitas Salafi menjadi salah satu gerakan Islamis yang paling konsisten dalam berpegang teguh pada manhaj Salaf dan menjalani seluruh kehidupan mereka berdasarkan syari’at Islam. Tetapi apakah komunitas Salafi menampik atau menerima politik? Untuk konteks Indonesia sampai penelitian ini selesai dilakukan, mereka tetap bersikap apolitis dengan sikap pesimisme terhadap politik di tanah air. Tetapi dalam sejarah, sebenarnya Salafi juga pernah berpolitik praktis. Menurut Kahar, bahwa asumsi lama, Salafi itu kaum ultra-konservatif Islam, apolitis, dan hanya memusatkan Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 143 perhatian kepada urusan-urusan ritualistik Islam, sedangkan analisisnya mengatakan bahwa doktrin politik Salafisme menunjukkan, tak hanya idealisasi politik yang dominan dalam ide mereka, tetapi juga kemungkinan pragmatisme politik.3 Jika diamati sepintas sikap fatalis Salafi dalam urusan politik ini dapat dianggap sebagai sikap apolitis. Tetapi tidak bagi Salafi, karena tidak terlibat aktif dalam kancah politik bukanlah sikap apolitis, tetapi bagi Salafi, politik yang relevan di masa kini adalah meninggalkan politik. Mereka juga mengklaim hal itu sebagai sikap yang akurat dalam menimbang keadaan. Dengan posisi Salafi yang demikian, Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan terlalu terganggu oleh Salafi politik karena mereka sebenarnya tidak serta merta anti-Amerika, tetapi musuh Amerika dan Barat yang sesungguhnya adalah Salafi-jihadi. Kahar juga mendefinisikan Salafi sebagai paham yang berusaha mempurifikasi pandangan dan gaya hidup masyarakat Muslim dengan ajaran-ajaran yang lebih dogmatis dan puritan berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya kurun adalah era Islam awal (generasi masa lampau/Salaf).4 Dengan dogma seperti itu dan dengan pemahaman yang kurang mendalam tentang spirit Muslim awal, sebagian kalangan Muslim modern mencoba berpikir dan bertindak berdasarkan pemahaman mereka tentang Muslim era awal. Sebagian mencoba mempraktikkan cara makan, berpenampilan, berpikir, dan bertindak seperti Muslim generasi awal sehingga tidak jarang perilaku mereka tampak aneh di mata dunia modern. Menurutnya, merujuk pada ulasan seorang pemikir Saudi, Salman al-Audah dalam karyanya al-Ighraq fi al-Juz’iyyat (Terperosok ke Persoalan-persoalan Sepele), keanehan itu karena mereka telalu tenggelam dalam aspek-aspek yang parsial dan artifisial dari etos kaum Muslim awal. Gejala negatif ini kini tak jarang dijumpai pada sebagian Muslim dari Eropa sampai Amerika, dari Nigeria sampai Indonesia. Bagaimanapun, komunitas Salafi harus menghadapi kenyataan dan berbagai tantangan modernitas. Kepatuhan terhadap dogma agama yang Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 144 ketat akan berhadapan dengan hasil-hasil dari modernitas dan menantang komunitas Salafi untuk menafsirkan ulang dogma agama dan pemahaman mereka tentang realitas teknologi. Televisi jarang ditemui di rumah-rumah Salafi, karena keberadaannya yang dianggap membawa maksiat daripada manfaat. Tetapi tentang isi berita televisi bahkan tayangan-tayangan gosip infotainment, sebagian dari mereka ternyata tidak ketinggalan berita. Dari berbagai program hiburan yang marak di berbagai stasiun televisi, program infotainment terlihat paling sukses meraih animo khalayak dan memiliki daya tahan yang sangat kuat, terbukti program ini marak di berbagai stasiun televisi, dari tahun ke tahun. Selama Januari 2013 sampai dengan Januari 2014, penelitian ini mencatat bahwa dengan menyuguhkan 27 jenis acara dari 9 televisi swasta nasional dengan jam tayang mencapai 6570 menit (109,5 jam)5 selama seminggu, tayangan infotainment sebenarnya menjadi “penghibur dominan” yang mampu memanfaatkan setiap waktu luang dan sibuk dari khalayaknya. Belum lagi jika harus berbicara tentang tema-tema yang beragam yang diangkat pada setiap tayangan infotainment. Infotainment, dengan demikian, bebas memasuki kehidupan khalayaknya secara masif dengan keberhasilan kapitalisme media dalam mengkomodifikasi gosip-gosip para selebriti. Program infotainment marak disodorkan berbagai stasiun televisi nasional dengan jumlah jam tayang yang sangat signifikan. Sembilan stasiun televisi swasta setidaknya menayangkan infotainment dalam durasi sekitar 30 menit (yaitu MNCTV sebagai stasiun televisi yang paling rendah durasi tayangnya) sampai dengan 150 menit/2,5 jam (yaitu Global TV dengan durasi tayang paling tinggi) per hari dengan variasi waktu tayang pagi, siang, sore dan malam hari. Dalam infotainment disuguhkan beberapa jenis tayangan gosip, seperti: Seleb @ Seleb dan Seputar Obrolan Selebritis di ANTV, Hot Spot, Obsesi, Seleb on Cam dan Fokus Selebriti di GlobalTV, Kiss Pagi dan Hot Kiss Sore di Indosiar, New Star dan Sensi di KompasTV, Go Spot, Intens, Silet dan Kabar-kabari di RCTI, dan lain sebagainya.6 Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 145 Afirmasi identitas diri Salafi terejawantah dalam praktik kehidupan keagamaan mereka yang selaras dengan al-Quran dan sunnah Nabi saw, sehingga tembok tebal hukum agama atau syariat Islam menjadi sebentuk sabuk pengaman iman. Memiliki televisi saja dilarang apalagi menontonnya. Hampir seluruh pengikut Salafi di Yogyakarta tidak mempunyai ‘kotak ajaib’ itu di rumah-rumah mereka. Bagaimana mereka tahu tentang tayangan dan konten infotainment dan berghibah tentangnya sementara hukum ghibah itu sendiri jelas haram. Di sinilah sisi menariknya, bahwa praktik-praktik keagamaan yang normatif itu tidak sepenuhnya selaras dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pengikutnya, sehingga menonton televisi, bahkan menggunakan hasil-hasil dari modernitas seperti hand phone dan media elektronik lainnya sulit dihindari, sesuatu yang tak tabu lagi, sehingga tindakan ghibah infotainment yang semula dilarang atau wajib untuk dijauhi, pada kenyataannya, menjadi bagian yang tidak terpisah dalam aktivitas komunikasi mereka. Fenomena Salafi tersebut sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang terdapat pada Kristen Protestan di mana aliran Mennonite merepresentasikan diri mereka sebagai aliran yang membatasi diri dan menegosiasikan diri mereka dengan modernitas. Kaum Mennonite konservatif dan apolitis, tetap patuh menjalankan ajaran Yesus. Mereka tidak mau hormat pada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.7 Komunitas Salafi di satu sisi dapat dideskripsikan sebagai umat Islam yang meyakini dan menerapkan dalam kehidupan mereka praktik-praktik keagamaan yang harus selaras dengan ajaran-ajaran al-Quran dan mengikuti Sunnah Nabi saw. Kebanyakan dari komunitas Salafi menjaga jarak dengan modernitas dan hasil-hasilnya, seperti menolak menonton televisi apalagi mengonsumsi berbagai tayangan infotainment serta dengan tegas mengharamkan ghibah. Tetapi di sisi lain, praktik-praktik keagamaan yang normatif tersebut tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan konsisten oleh para pengikutnya, sehingga menonton televisi, bahkan menggunakan hasilKontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 146 hasil dari modernitas seperti hand phone, smartphone, dan media elektronik lainnya tidak lagi ditabukan, sehingga tindakan ghibah atau bergosip tentang konten infotainment—terutama tentang ustadz/ustadzah selebriti atau para selebriti yang mayoritas beragama Islam yang sering diberitakan tentang proses kawin-cerai, perselingkuhan, dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) mereka, misalnya—yang semula dilarang atau wajib untuk dijauhi pada kenyataannya menjadi bagian yang tidak terpisah dalam aktivitas komunikasi mereka sehari-hari. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Melalui instrumen apa, kapan, di mana dan bersama siapa komunitas Salafi meresepsi tayangan infotainment? Bagaimana komunitas Salafi memahami ghibah infotainment dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana bentuk resistensi dan negosiasi Salafi dalam meresepsi fenomena ghibah infotainment baik terhadap komunitas mereka sendiri atau di luar komunitas mereka serta terhadap dogma manhaj Salaf yang ketat dan fatwa para mufti ataupun sikap mereka terhadap modernitas? B. Kerangka Teoretis dan Metodologis Pada bagian ini akan dibahas dua permasalahan, yaitu landasan teori dan metode penelitian. Yang pertama berupa konsep teoretis yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi objek penelitian dengan berbagai permasalahannya yang muncul dalam proses pembahasan, sedangkan yang kedua berupa cara dan pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan data penelitian melalui konsep di atas. B.1. Landasan Teori Dalam upaya memahami obyek kajian, peneliti menggunakan sejumlah konsep teoretis yang dianggap relevan dalam proses pembahasan. Komunitas Salafi merupakan subkultur Islam yang menyimpan banyak misteri dan kerapkali bertentangan dengan pandangan umum. Dalam Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 147 pandangan Dick Hebdige, kata “subkultur” itu sarat misteri, karena mengesankan kerahasiaan dan dunia bawah. Makna subkultur sebenarnya ditentukan oleh berbagai definisi yang saling bertentangan tentang gaya, karena di balik gaya sebenarnya tersirat sinyal penolakan, melawan yang alami, memotong proses pewajaran, menyerang mayoritas diam, menyanggah prinsip kesatuan dan keterpaduan, serta menentang mitos konsensus.8 Makna subkultur dengan demikian sebenarnya lebih jelas daripada makna kultur yang selama berabad-abad pemakaiannya selalu tampak tidak ajeg. Pada gilirannya, keberadaan subkultur ini dapat menarik anggota baru dan menciptakan kepanikan moral.9 Hebdige juga menafsirkan subkultur sebagai bentuk resistensi di mana kontradiksi yang dialami maupun penolakan terhadap ideologi yang berkuasa secara tak langsung dipresentasikan lewat gaya.10 Merujuk pada konsep Hebdige, maka komunitas Salafi dapat dikatakan sebagai kelompok subkultur dengan beberapa penekanan gaya dan identitas yang mereka tampilkan. Mengenakan pakaian serba gelap atau cenderung menghindari warna yang mencolok, kemudian memelihara jenggot dan celana congklang di atas mata kaki bagi kaum pria, serta cadar dan jilbab besar bagi kaum wanita, sebenarnya cukup menunjukkan bagaimana gaya subkultur itu dipelihara sedemikian ketat dan konsisten. Pemeliharaan gaya yang demikian itu sebenarnya menyiratkan sinyal perlawanan dan pewajaran terhadap komunitas Muslim kebanyakan. Komunitas Salafi tetap terjaga dalam keadaan yang sarat misteri disebabkan konsistensi mereka yang berhasil membungkus makna gaya dan identitas mereka di tengah konsensus tentang kehidupan yang serba alami dan pergaulan sosial yang semestinya. Dengan demikian, representasi gaya dan identitas subkultur Salafi sebagaimana yang selama ini mereka tampilkan telah menjadi derau dan sekaligus bentuk resistensi bagi mayoritas Muslim di luar kelompok mereka. Lagipula, subkultur Salafi tidak diragukan lagi menunjukkan keberhasilan mereka dalam merekrut dan memperbanyak Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 148 anggota mereka, sehingga realitas tersebut melahirkan kepanikan moral bagi mayoritas Muslim di luar kelompok mereka. Sebagai Islam subkultur, komunitas Salafi jelas mempunyai kepentingan dalam gerakannya, yaitu memperluas dakwah manhaj Salafi di tengah-tengah mayoritas Muslim lainnya serta tentu saja memperjelas ideologi mereka dengan menunjukkan dan mengikuti praktik-praktik keagamaan yang diajarkan oleh para Salafus Salih. Yang menarik adalah bahwa komunitas Salafi yang sebenarnya berasal dan berlatar belakang dari mayoritas Islam kebanyakan, kemudian menunjukkan sikap oposisi terhadap budaya dominan yang terdapat di sekitar mereka dan pada kenyataannya tidak sedikit dari para pengikutnya yang benar-benar berbeda dan telah membedakan diri mereka dengan para pendahulu mereka dari basis organisasi yang lama ataupun dengan orang tua mereka sendiri. Gaya subkultur Salafi tidak berhenti di situ, mereka juga dapat memanfaatkan komoditas berupa barang atau pun kain untuk kepentingan mereka—kain yang memiliki makna yang umum dan dijual bebas di pasaran telah didekap dalam “perakitan”, dipola menjadi jilbab besar, cadar, atau celana congklang sedemikian rupa demi mewujudkan tujuan dan maknanya, seperti tampak di etalase Toko Ihya’ dan beberapa toko Salafi lainnya. Stuart Hall11 mengidentifikasi posisi-posisi hipotesis yang darinya dekoding atas diskursus televisi oleh khalayak dapat dikonstruksi: (1) kode hegemonik-dominan dimana khalayak mengambil makna yang terkonotasikan dari siaran program televisi dan mendekode pesannya dari sudut pandang kode rujukan yang telah dienkodekan; (2) kode yang dinegosiasikan mengandung campuran unsur-unsur yang bersifat adaptif dan oposisional; serta (3) kode oposisional merupakan posisi dimana khalayak memahami secara sempurna perubahan harfiah maupun perubahan konotatif yang diberikan oleh diskursus tetapi kecuali mendekode dengan cara yang bertentangan secara keseluruhan.12 Proses berikutnya yaitu menemukan jawaban hasil interpretasi khalayak, dengan menggunakan teori Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 149 resepsinya Hall sebagai sebuah usaha untuk menentukan posisi resepsi khalayak. Khalayak dari komunitas Salafi dikategorikan sebagai khalayak aktif yang menginterpretasi ghibah infotainment. Mereka memaknai pesan tersebut dari pengalaman mereka menggunakan internet atau televisi dari teman-teman di lingkungannya. Berbagai sudut pandang dapat terbentuk dari hasil interpretasi khalayak, di antaranya dari tilikan yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, rerasan budaya dan hegemoni masyarakat. Sedangkan konsepsi tentang kontestasi mengacu pada pandangan David L. Vancil yang mengartikan kontestasi sebagai bentuk pertentangan antara berbagai pihak sehingga menimbulkan clash of argument, di mana di dalamnya terdapat pertukaran yang saling bersaing tentang nilai, fakta dan kebijakan atas masalah tertentu yang memotivasi berbagai tindakan tertentu pula.13 Dalam pemahaman yang bersifat tunggal dapat melahirkan penafsiran serupa atau semakna, sebaliknya dalam keserbaragaman makna yang meliputi pemahaman yang berbeda-beda atas suatu dogma agama misalnya, niscaya dapat melahirkan perspektif yang berbeda-beda pula. Komitmen komunitas Salafi untuk berpegang teguh pada dogma agama berdasarkan manhaj Salaf dipahami sebagai pemahaman yang seragam, tetapi maknanya dapat menjadi serba ragam bilamana terjadi kontestasi antara persepsi individu dan penafsirannya di satu sisi dengan dogmatisme agama dan para mufti sebagai pemegang otoritas di lain sisi. Realitas keserbaragaman tersebut melahirkan kontestasi makna dan multitafsir dalam komunitas Salafi itu sendiri. Selain itu, Stella Ting-Toomey mengemukakan negosiasi identitas sebagai a mutual communication activity. Individu-individu berusaha untuk membangkitkan identitas yang mereka inginkan dalam interaksi, mereka juga berusaha untuk menantang atau mendukung identitas yang lain.14 Konsep yang dikemukakan oleh Ting-Toomey tersebut dapat digunakan untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang terjadi di kalangan Salafi yang meliputi komunikasi simbolik, kestabilan identitas Salafi dalam situasi Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 150 budaya Jawa dan keindonesiaan yang kerap bertabrakan dengan eksistensi dan dogma Salafi, serta gaya subkultur Salafi dalam mengomunikasikan pandangan dogmatis mereka yang ketat dalam komunikasi antarbudaya Islam yang majemuk. Sebagai bagian dari representasi pergerakan kelompok Islamis, Salafi sering dituduh radikal dan memobilisasi massa untuk kepentingan mereka, termasuk juga dalam kaitannya dengan perebutan budaya. Wiktorowicz mengemukakan bahwa aktivisme Islamis merupakan respon terhadap imperalisme budaya Barat dan kapitalisme yang mekar di dunia Islam dan menjadi counter culture terhadap dominasi Barat.15 B.2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berparadigma kajian budaya (cultural studies) serta berfokus pada studi kasus. Kajian kualitatif kerapkali disebut sebagai penelitian multimetode yang bersifat interpretif dan kritis. Dengan pendekatan fenomenologi akan membantu proses penelitian khususnya dalam mengungkapkan realitas yang murni, karena fenomenologi bergerak dari individu dan kelompok kecil untuk memahami realitas sosial yang sesungguhnya. Hasil penelitian fenomenologi pada umumnya lebih dikenal natural atau alamiah. Suatu realitas tampak alami, sebab realitas tersebut tidak mendapat intervensi keinginan peneliti. Pada sisi lain, realitas muncul secara reflektif, makna mencerminkan keadaan yang sesungguhnya; dan realitas menjadi otentik, sebab data diperoleh peneliti dari sumber pertama dan pelaku yang mengalaminya.16 Fenomenologi mencoba mencari pemahaman tentang bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Disebut intersubjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Makna Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 151 yang dikonstruksi tersebut dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas seseorang, dan juga memperhatikan peran orang lain di dalamnya.17 Kajian ini dilakukan pada enam pondok pesantren Salafi yang ada di Yogyakarta, yaitu Pesantren Ihyaus Sunnah, Pesantren al-Anshar, Pesantren bin Baz, Pesantren Taruna al-Quran, Pesantren Hamalatul Quran, dan Pesantren Khoiro Ummah, serta jama’ah Salafi di Masjid MPR (Masjid Pogung Raya). Untuk mengumpulkan data utama dari keenam lokasi tersebut digunakan tiga cara, yaitu wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Berkenaan dengan teknik yang pertama, peneliti mewawancarai 16 informan. Kedua, peneliti langsung mengamati secara seksama situasi dan kondisi yang terjadi dan berlangsung di keenam lokasi tersebut. Dan terakhir, peneliti juga menggunakan informasi dari dokumentasi dalam berbagai bentuk, yaitu majalah, buku dan internet yang berkaitan dengan komunitas Salafi yang diteliti. Data yang kemudian dianalisis, secara interpretif-kritis, melalui teknik analisis Miles dan Hubermas18 dan juga Creswell19 yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. C. Hasil Penelitian Sejalan dengan penelitian ini, pemaknaan khalayak (decoding) atas ghibah infotainment dibagi atas dominant hegemonic reading, negotiated reading, dan opposition reading. Penempatan posisi khalayak ke dalam tiga tipe itu dilakukan dari hasil interpretasi dengan latar belakang ghibah infotainment dan pengalaman mempunyai mengonsumsi interpretasi yang program beda-beda tersebut. dalam Masing-masing memaknai ghibah infotainment. Tipe resepsi masing-masing informan di atas terbagi berdasarkan interpretasi mereka pada ghibah infotainment. Informan dari 16 orang Salafi, 5 orang Salafi tidak menjadi konsumer/tidak mengonsumsi tayangan gosip infotainment secara langsung, dan 11 orang Salafi Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 152 mengonsumsi program tersebut baik melalui televisi, internet maupun smartphone dengan aplikasi android. Penampang 1. Peta Identitas Islamis Komunitas Salafi di Yogyakarta Dari masing-masing informan tersebut masing-masing mempunyai interpretasi yang kemudian menunjukkan hasil penelitian ini, mereka terbagi atas beberepa resepsi: Pertama, dominant hegemonic reading: informan sejalan dengan ghibah infotainment dan menyetujui konten dari tayangan tersebut. Informan yang berada dalam tipe ini diketahui terdapat 5 orang salafi, kelima orang salafi tersebut semuanya setuju dengan ghibah infotainment. Kelima informan menyetujuinya karena dinilai dapat dijadikan sebagai sarana tabligh, bahan materi dakwah, representasi dakwah Islam, dan rekreasi untuk keseimbangan hidup. Kedua, negotiated reading: informan dalam tipe ini menginterpretasikan ghibah infotainment sebagai acara yang dibolehkan untuk ditonton asalkan program tersebut memberikan pesan moral dan mengandung nilai-nilai pendidikan bagi khalayak, dan diharamkan untuk dikonsumsi jika berisi pesan yang merusak Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 153 akhlak melanggar syariat Islam. Terdapat 8 orang informan yang berada dalam tipe ini, 6 orang Salafi merupakan konsumen infotainment melalui televisi, internet, dan smartphone, sedangkan 2 informan lainnya mendapatkan berita-berita selebriti dari koran, tabloid Salafi dan temantemannya. Dan ketiga, opposition reading: informan dalam tipe ini mengetahui para selebriti dalam ghibah infotainment, tetapi tidak menyetujui konten yang disampaikan program infotainment. Terdapat 3 informan yang berada dalam posisi ini, ketiganya tidak mengonsumsi tayangan infotainment secara langsung, tetapi mendapatkan berita gosip selebriti melalui internet, tabloid Salafi, smartphone dan teman. Menurut mereka, bahwa ghibah infotainment itu mutlak haram karena mubadzir, membuang-buang waktu untuk beribadah, merusak akhlak dan menghancurkan keluarga atau rumah tangga orang. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh langsung di lapangan, dan wawancara dengan Ustadz Mustafa dan beberapa informan Salafi lainnya, peneliti mengkategorikan komunitas Salafi yang ada di Yogyakarta ke dalam tiga varian atau kelompok, yaitu: (1) kelompok mutasyaddid, kelompok salafi yang ekstrem; (2) mutawassith, kelompok salafi yang tengah-tengah; dan (3) mutasahhil, kelompok salafi yang mudah. Kategorisasi ini tidak bersifat mengikat atau kaku, sebab setiap pengikut Salafi dapat bergerak dan condong kepada imam yang sesuai dengan pemikirannya. Sehingga setiap Salafi yang masuk dalam kategori atau varian tertentu dapat bergeser kepada kategori atau varian yang lain dengan bebas. Kendatipun dalam praktiknya, setiap tindakan melangkah atau hijrah kepada kelompok lain akan membuat setiap Salafi menjadi “orang baru” atau mengalami “awamisasi”, kecuali jika seorang Salafi itu telah memiliki nama atau dikenal di kalangan jamaah Salafi yang lain. Sedangkan mengenai parameter atas masing-masing varian tersebut dapat dilihat penampang berikut ini. Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 154 Pendapat komunitas Salafi tentang ghibah infotainment berdasarkan tiga kelompok sangat beragam. Pertama, kelompok mutasyaddid mutlak mengharamkan ghibah infotainment. Mereka beranggapan bahwa menonton televisi bahkan program infotainment hanyalah membuang-buang waktu saja, mubadzir, sehingga hukumnya haram. Di samping itu, televisi beserta program dan kontennya sangat merusak akhlak dan ujung-ujungnya dapat menghancurkan kebahagiaan rumah tangga karena dampak yang ditimbulkannya. Kedua, kelompok mutawassith berpendapat bahwa ghibah infotainment itu di satu sisi dihukumi seabgai haram jika benar-benar melanggar syariat Islam, dan di sisi lain, boleh asalkan mengandung nilainilai pendidikan yang dapat membimbing umat Islam ke jalan yang benar. Ketiga, kelompok mutasahhil berpendirian agak bebas dan longgar. Mereka berpendapat bahwa ghibah infotainment itu boleh dengan alasan bahwa hal itu dapat dinilai sebagai rekreasi untuk keseimbangan hidup, sebagai sarana tabligh yang merupakan sifat Nabi saw yang keempat, dan juga merupakan representasi dakwah dalam Islam. Komunitas Salafi yang masuk dalam kelompok mutasyaddid selaras dalam apa yang disebut sebagai Islamisme, sebagai gerakan yang khas dengan militansi dan keteguhan subkultural Salafi terhadap kitab suci dan para pemegang otoritas yakni ulama Salafi, terbatasi dan ‘teralienasi’ oleh garis demarkasi doktriner yang sangat membatasi kebebasan mereka, sehingga praktik tahdzir menjadi tak terbantahkan. Di samping itu, terjadi kontestasi makna dalam kehidupan mereka dimana ketegangan subjektivitas/kedirian dengan kuasa doktriner ulama Salafi mendesak ke pola kehidupan ambivalen, mengejawantahkan doktrin dalam praktik keseharian, atau menafsir ulang doktrin keagamaan di tengah tantangan modernitas (kemajuan jaman). Mereka juga terlihat melakukan perlawanan simbolik subkultural terhadap budaya dominan baik dari komunitas Islam mainstream ataupun dari penduduk lokal dengan budaya yang lebih Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 155 heterogen. Komunitas Salafi dengan demikian menerapkan teknologi diri di tengah karnaval ekstasi komunikasi (ghibah infotainment). Komunitas Salafi juga melakukan negosiasi identitas bahwa mereka tetap teguh bersalafi (jenggot, celana congklang di atas mata kaki, perempuan bercadar atau mengenakan jilbab besar), tidak anti-modernitas, tetapi juga bukan machinized human. Pada praktiknya, mereka mengonsumsi teknologi juga (Rodja’ TV, blackberry messenger (BBM), line, kakaotalk, wechat, whatsapp, internet, facebook, twitter, majalah, percetakan, penerbitan, bisnis pengobatan alternatif, bekam, dll). Mereka melakukan afirmasi gaya hidup Salafi yang khas sebagai subkultur di hadapan Islam mainstream. Fashion dan kredo subkultural Salafi menegosiasi identitas diri dalam realitas pergaulan sosial. Tampak pula politik afinitas subkultural Salafi, di samping juga transfigurasi diri spiritual komunitas Salafi yang dilakukan terus-menerus sebagai bagian dari dakwah atau pantulan eksistensi subyektivitas/kedirian mereka. Selain itu, peneliti menemukan bahwa praktik subkultur Salafi menunjukkan adanya tegangan di antara dogma agama dan modernitas. Komunitas Salafi melakukan afirmasi gaya hidup dalam keteguhan kredo serta negosiasi makna dan identitas mereka dalam kontestasi vis-a-vis dogmatisme agama dan mufti serta komunitas Islam mainstream atau budaya dominan masyarakat Islam. Komunitas Salafi mengonsumsi teknologi dan meresepsi fenomena ghibah infotainment, tidak anti-modernitas, menampilkan sikap estetis-religius sebagai penanda perlawanan simbolikeksistensial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas Salafi tidak selamanya ajeg dalam gerakan Islamisme, tetapi mereka mempresentasikan bentuk eksistensi sebagai Salafi postmodern—ada sebentuk pergeseran makna dari sekadar bermanhaj Salaf ke representasi urban Salafi/wahabi— dengan pilihan dan kebebasan hidup dalam pendisiplinan model panoptikon Foucauldian serta genre dakwah barunya, selanjutnya mereka memposisikan diri dalam trend baru gaya Salafi dalam modernitas. Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 156 Selanjutnya, peneliti mengkritisi ideologi purdah yang terejawantah dalam komunitas Salafi. Bahwa dengan mengenakan cadar yang menutupi hampir seluruh wajah perempuan Salafi itu sebenarnya merepresentasikan inferioritas wanita Salafi dan pengucilan mereka dari kehidupan sosial. Meskkipun lelaki Salafi mengatakan bahwa itu demi keselamatan dan kehormatan wanita Salafi. Justru peneliti melihat bahwa wanita Salafi seperti dalam posisi disisihkan dan selalu berada di rumah empat dinding itu, sedangkan di luar rumah itu semua urusan lelaki Salafi sampai sejauh mata memandang. Kebebasan wanita Salafi betul-betul terpangkas habis, seolaholah hanya menyisakan kewajiban diri sebagai pelayan suami saja dan pelayan bagi anak-anak mereka. Memang bagi kaum wanita Salafi modern khususnya bagi mereka yang kaya dan bermodal, tindakan keluar dari zenana ke wilayah mardana bisa saja mereka lakukan dengan mengendarai dan menyetir mobil. Ironisnya, mereka seringkali dengan gigih mengobarkan seruan mematuhi manhaj Salaf, meskipun tidak dapat menutupi rasa ingin bersosialisasi secara lebih bebas sebagaimana ibu-ibu muslimah pada umumnya. Fenomena ini dapat dijumpai di sekolah-sekolah Salafi yang telah memodernisasi diri. Sebaliknya, bagi wanita-wanita Salafi dari kelas menengah ke bawah tentusaja kebebasan itu semakin sulit terwujud, hal ini sama dengan ibu-ibu salafi yang berada di pesantren-pesantren, eksistensi mereka benar-benar terbatasi. Fenomena purdah dapat melegitimasi penyisihan dan penyingkiran wanita salafi dari gelanggang sosial, ekonomi dan politik secara sistematis. Emansipasi wanita dalam sistem purdah yang terstruktur dalam komunitas Salafi sangat sulit diwujudkan. Fenomena ini dapat disebut sebagai bunuh diri sosial yakni interpretasi atas pengelabuan sistemik atas kodrat wanita yang mestinya mensyukuri dirinya sebagai makhluk Tuhan yang berdaya guna dengan tindakan praksis dan dapat berperan penting dan lebih dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi secara lebih terbuka. Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 157 D. Penutup Komunitas Salafi merepresentasikan diri mereka sebagai subkultur Islam yang menyelenggarakan proses modernisasi diri dalam upaya peneguhan moral di bawah manhaj Salaf serta merta melakukan proses purifikasi ideologis terhadap berbagai macam bid’ah dan tantangan modernitas. Sebagai gerakan subkultur, komunitas Salafi terlibat dalam wacana kontestasi makna dengan para pemegang otoritas fatwa (mufti) yang selama ini menjadi sumber otoritatif untuk menafsirkan al-Quran dan Hadits dalam menyikapi berbagai permasalahan umat. Sehingga benturan perspektif tak dapat dihindarkan, tindakan tahdzir antar sesama kelompok Salafi memperenggang dan memutus jembatan komunikasi di antara mereka. Kesatuan dan kebersamaan atas nama dakwah Salafiyah yang awalnya solid akhirnya terpecah belah dan masing-masing telah mendirikan sebuah komunitas tersendiri serta tetap mengembangkan dakwah mereka dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Militansi dakwah Salafi dan kecenderungan mereka untuk mudah bersitegang dengan sesamanya atau apalagi dengan mayoritas Islam mainstream telah menyebabkan stigmatisasi terhadap mereka menjadi tak terelakkan, cap teroris, ultrakonservatif, fundamentalis, revivalis, skripturalis, dan Islamis, pada kenyataannya terus terpelihara. Problematika historis inilah yang menyulut munculnya ghirah (gairah) kebebasan individu Salafi untuk memaknai ulang eksistensi mereka baik di hadapan dogma agama yang ketat ataupun dalam menyikapi tantangan-tantangan modernitas. Penelitian ini mengklasifikasi model-model resistensi dan negosiasi komunitas Salafi khususnya dalam meresepsi fenomena ghibah infotainment. Tiga kelompok Salafi—mutasyaddid, mutawassith, dan mutasahhil—merepresentasikan eksistensi mereka dalam estetika-religius yang beragam. Ada yang cenderung memutlakkan pengharaman dan pelarangan terhadap praktik ghibah infotainment, ada yang menarik penafsiran dua arah baik mematuhi fatwa ataupun Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 158 mereformulasikan tafsir baru yang lebih dapat menjawab kebutuhan, dan ada pula yang mengembalikan semua tanggung jawab moral itu kepada pribadi masing-masing. Fenomena ustadz/ustadzah selebriti yang banyak menghiasi layar kaca, kajian-kajian kerohanian Islam, dan bahkan iklan-iklan di televisi, membuat gusar komunitas Salafi ini. Akhlak ustadz-ustadzah seleb tersebut tentusaja yang menjadi bidikan tajam, dimulai dari penceramah agama yang alay, arogan, yang melakukan kawin-cerai dan poligami, sampai dengan seorang pesulap dan mentalis yang tiba-tiba menjadi ustadz. Fenomena ghibah infotainment berlangsung dalam komunikasi verbal di kalangan Salafi dengan dalih menjadikannya pelajaran yang tak patut dicontoh yang dipakai dalam materi-materi dakwah mereka, atau melalui komunikasi non-verbal yang membahas problematika tersebut dalam website Salafi dan di beberapa situs yang mereka miliki. Komunitas Salafi tidak tunggal. Mereka merepresentasikan diri mereka dalam berbagai model afirmasi gaya hidup agar dapat tetap menjadi pribadi yang religius dalam keserbaragaman. Gaya subkultur Salafi sebenarnya merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap dogmatisme Islam dan peneguhan eksistensial mereka terhadap represi doktriner para mufti, sehingga dengan demikian mereka tetap dapat berada dalam koridor dakwah salafiyah secara patuh sembari mengkonsumsi teknologi sebagai hasil dari modernitas. Komunitas Salafi menggunakan teknologi diri mereka dalam mengoperasikan kebebasan dan pilihan-pilihan individu untuk mencapai kepentingan dan kebahagian mereka masing-masing. Meskipun hidup dalam komunitas Salafi, mereka tidak kehilangan kehendak otonom untuk merayakan kebebasan individu dengan alat-alat teknologi yang membawa mereka dapat menjelajah dunia maya dan melewati pagar-pagar pembatas doktriner yang ketat. Mereka tidak melakukan pelanggaran etika, melainkan berani memposisikan identitas diri mereka secara proporsional dan Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 159 mengkontekstualisasikan konsepsi ideal manhaj Salaf dan spirit Salafus Salih dalam kehidupan modern. Tampilan gaya subkultur Salafi yang eksis dalam estetika-religius mengkonstruk komitmen yang kukuh terhadap dogmatisme agama, sedangkan gaya hidup mereka yang mencitrakan inklusivitas dalam memaknai modernitas menyulut api kebebasan dan pilihan setiap individu Salafi. Konsumsi terhadap teknologi informasi dan gosip infotainment memperlihatkan posisi kekebasan Salafi dan membangun kategorisasi baru yang dalam wacana keislaman mutakhir dapat disebut sebagai postIslamisme. Salafi posmodern bergerak dari militansi aktivisme Islamis menjadi representasi dari kelompok post-Islamisme yang menandai identitas dan status sosial mereka dengan tanda-tanda konsumerisme. Beberapa kritik dapat diutarakan terhadap komunitas Salafi. Pertama, kritik atas komunitas Salafi dapat diterapkan pada realitas problematik dalam subyektivitas diri Salafi yang kerapkali enggan melakukan interelasi dan interkoneksitas ilmu agama—dalam apa yang sering mereka istilahkan sebagai ’ilmiyyah—dengan kelompok Salafi yang lain serta bersikap monoton dan kembali eksklusif bahkan dalam batas tertentu dapat bersikap agresif dan reaktif melihat kelompok Salafi yang berbeda. Kecenderungan merasa diri paling benar dan menghapus ingatan pada setiap lawan membuat setiap kelompok Salafi seolah-olah dapat menikmati kehidupan dalam komunitas mereka yang terbatas tanpa kelompok Salafi yang lain, sementara kelompok Salafi yang lain terus melakukan ekspansi ideologis di pasar budaya untuk memperbanyak pengikut dan mendorong munculnya kepanikan moral dari komunitas Islam mayoritas. Kedua, kritik terhadap gaya resepsi komunitas Salafi yang masih terkesan malu-malu untuk mengakui keberadaan dan fungsi media dalam kehidupan mereka. Jawaban yang berputar-putar dan sikap cenderung mengelak untuk mengakui tidak perlu dipertahankan. Buat apa menolak memiliki televisi dengan dalih merusak akhlak sedangkan dengan ‘Syeikh Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 160 Google’ mereka dapat menjelajah lebih luas dan mengakses lebih bebas apasaja data, siaran infotainment dan berita yang disajikan oleh televisi. Keberadaan internet dan alat-alat komunikasi seperti smartphone dapat memudahkan setiap individu untuk berselancar dalam media maya atau cyberspace. Jika benar demikian, bahwa kebutuhan atas informasi dan tujuan dakwah salafiyah memang mengharuskan untuk menggunakan media televisi atau pun internet, mestinya komunitas Salafi meminta fatwa yang lebih kontekstual kepada para mufti atau ulama Salaf untuk memodernisasi fatwa-fatwa mereka demi mengakomodasi realitas dan kebutuhan komunitas Salafi terhadap modernitas. jika benar ini dapat dilakukan, maka komunitas Salafi akan lebih terbuka dan maju, meskipun tetap dengan gaya penampilan mereka yang konsisten. Dan ketiga, kritik atas ekslusivitas budaya dan religiusitas Salafi yang mudah menaruh curiga dan dalam batas tertentu tidak jarang melakukan tahdzir bahkan takfir (pengkafiran) terhadap sesama muslim yang tidak sehaluan dengan kelompok Salafi tertentu. Kesan menakutkan terhadap komunitas Salafi tetap akan ada, selama mereka tidak membuka diri dan menumbukan rasa toleransi dan inklusivitas dalam bermasyarakat dan berbudaya. Komunitas Muslim mayoritas tentu saja akan terus menjaga jarak dan selamanya akan mempropagandakan penolakan atas kehadiran komunitas Salafi di manapun mereka berada. Terakhir, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka kajian ini mustahil untuk dapat memotret seluruh komunitas Salafi yang lebih kompleks. Atas dasar keterbatasan ini, peneliti merekomendasikan tiga saran. Pertama, kajian tentang komunitas Salafi sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini peneliti akui masih jauh dari sempurna. Kajian-kajian serupa yang mengangkat tentang tema komunitas Salafi dapat dinilai kurang komprehensif jika hanya meneliti satu aspek saja dari subkultur Salafi ini. Tetap dibutuhkan kajian dan penelitian yang lebih luas mengenai komunitas Salafi yang setiap pemikiran dan tindakan mereka Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 161 mengundang misteri dan rasa penasaran orang-orang awam. Belum lagi stigma yang dilekatkan pada komunitas dengan tampilan khasnya ini yang sering juga diidentikkan dengan terorisme yang belakangan marak menebar teror di Indonesia. Jauh dari apa yang dituduhkan A.M. Hendropriyono dalam riset disertasinya, justru memahami komunitas Salafi dengan perspektif cultural studies dapat dipaparkan tentang Salafi yang mengembangkan ajaran cinta damai, anti kekerasan, dan membuka komunikasi terbuka terhadap siapapun yang mau berdialog di majlis ilmu untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis di negeri ini. Kedua, dengan mengembangkan riset yang lebih dalam dan luas tentang subkultur Salafi yang ada di Indonesia, dapat diharapkan terciptanya dialog yang lebih membebaskan dan jauh dari sikap saling mencurigai antar kelompok Islam sehingga bangsa ini dapat terhindar sedini mungkin dari akar-akar konflik yang kerapkali mudah tersulut. Pemerintah dapat memfasilitasi untuk mengajak segenap komponen bangsa ini untuk melihat eksistensi komunitas Salafi sebagai bagian integral dan kaya dari kemajemukan anak bangsa ini. Meskipun berbeda ideologi dari Islam mainstream, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), subkultur Salafi dapat menempatkan diri mereka lebih baik dan santun, tanpa mengusik apalagi mengganggu kelompok Islam mayoritas yang merasa hadir lebih awal dalam pengembangan dakwah Islamiyah di Indonesia. Demi bangsa yang menganut filosofi Bhinneka Tunggal Ika, maka narasi-narasi kecil sebagaimana ditampilkan dengan keberadaan kelompok-kelompok Salafi tersebut perlu dirayakan, disapa, dan dirangkul atas nama toleransi dan kebebasan menjalankan ajaran keagamaan. Ketiga, kajian tentang bisnis dan keterlibatan komunitas Salafi dalam dakwah di dunia maya serta barangkali juga keterlibatan aktor-aktor Salafi dalam politik representasi dapat menjadi kajian lebih lanjut yang kaya dan menantang. Tetapi paling tidak penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi cultural studies untuk melihat Salafi dari perspektif lain yang lebih Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 162 membebaskan dan menggugah minat kajian-kajian budaya dan media tentang Salafi berikutnya. Catatan: 1Giovanna Boradori, Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida, terj. Alfons Taryadi. Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 105-106. 2Greg Barton, Jemaah Islamiyah: Radical Islamism in Indonesia. Singapore: NUS Publishing, 2004, hlm. 29 3Novriantoni Kahar, Salafi Politik dan Politik Salafisme. Makalah Seminar Internasional di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 24 November 2012. 4Novriantoni Kahar. Salafisasi Dunia Muslim dalam http://satuharapan.com/readdetail/read/salafisasi-dunia-muslim/ diakses pada 17 Agustus 2013. 5Data diolah peneliti dari 9 televisi swasta nasional. 6Ibid. 7http://crcs.ugm.ac.id/wednesday-forum-news/328/Gerakan-Kristen-Mennonitedi-Indonesia.html diakses pada 15 Januari 2014. 8Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style. London dan New York: Routledge, 1999, hlm. 15-38. 9Istilah “kepanikan moral” didefinisikan oleh Hartley (2010: 145) sebagai suatu deskripsi atas kecemasan publik tentang penyimpangan kesadaran atau perlakuan dalam budaya itu sendiri yang diajarkan untuk menantang norma, nilai dan kepentingan umum masyarakat yang berlaku 10 Dick Hebdige, hlm. 263 11Stuart Hall, “Encoding/Decoding” dalam Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe dan Paul willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 1972-1979. London dan New York: Routledge in association with the Center for Contemporary Cultural Studies University of Birmingham, 2005, hlm. 125-127. 12Pertti Alasuutari, Rethinking the Media Audience: The New Agenda. London, Thousand Oaks dan New Delhi: Sage Publications, 1999, hlm. 4. 13David L. Vancil, Rhetoric and Argumentation, Boston: Allyn and Bacon, 1993, hlm. 70-82. 14Stella Ting-Toomey, Communicating Across Cultures. New York dan London: The Guilford Press, 1999, hlm. 39-40. 15Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press, 2004, hlm. 5-7. 16Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods. USA: Sage Publications Inc., 1994. 17Engkus Kuswarno, Metodologi Penelitian Komunikasi “Fenomenologi”: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 2. 18Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermas, Analisa Data Kualitatif. Terj. Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19 19John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publications Inc., 1998, hlm. 110 Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 163 DAFTAR PUSTAKA Alasuutari, Pertti. 1999. Rethinking the Media Audience: The New Agenda. London, Thousand Oaks dan New Delhi: Sage Publications. Barton, Greg. 2004. Jemaah Islamiyah: Radical Islamism in Indonesia. Singapore: NUS Publishing. Boradori, Giovanna. 2005. Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida, terj. Alfons Taryadi. Jakarta: Kompas. Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publications Inc. Hall, Stuart. 2005. “Encoding/Decoding” dalam Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe dan Paul willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 1972-1979. London dan New York: Routledge in association with the Center for Contemporary Cultural Studies University of Birmingham. Hebdige, Dick. 1999. Subculture: The Meaning of Style. London dan New York: Routledge, 1999, hlm. 15-38. Kahar, Novriantoni. “Salafi Politik dan Politik Salafisme.” Makalah Seminar Internasional di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 24 November 2012. ______ . “Salafisasi Dunia Muslim” dalam http://satuharapan.com/readdetail/read/salafisasi-dunia-muslim/ diakses pada 17 Agustus 2013. Kuswarno, Engkus. 2009. Metodologi Penelitian Komunikasi “Fenomenologi”: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran. Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubermas. 1992. Analisa Data Kualitatif. Terj. Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press. Moustakas, Clark. 1994. Phenomenological Research Methods. USA: Sage Publications Inc. Ting-Toomey, Stella. 1999. Communicating Across Cultures. New York dan London: The Guilford Press, 1999. Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 164 Vancil, David L. 1993. Rhetoric and Argumentation, Boston: Allyn and Bacon. Wiktorowicz, Quintan (ed.). 2004. Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press. Kontekstualita, Vol. 32, No. 2, 2016 165