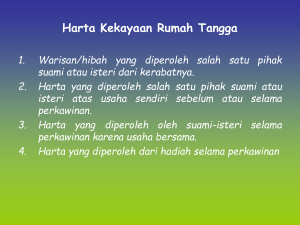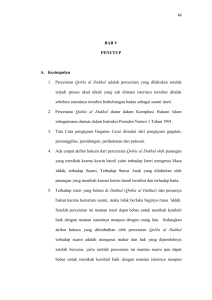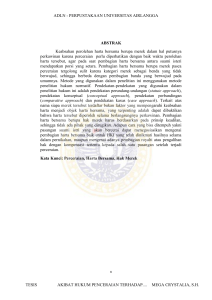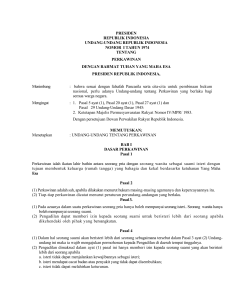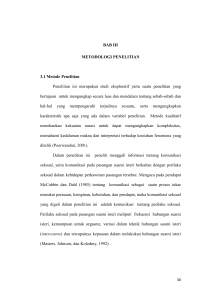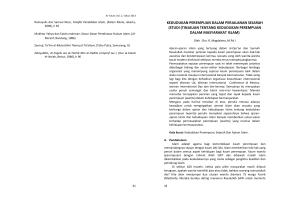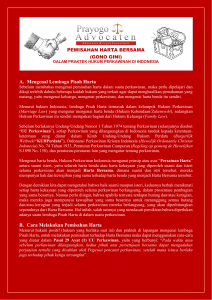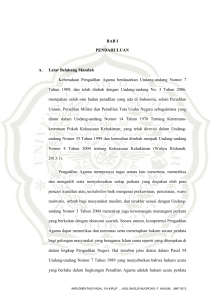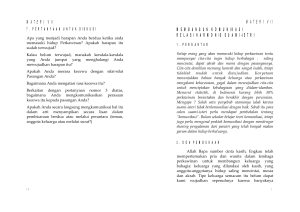studi perbandingan hukum harta kekayaan perkawinan dalam
advertisement

STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh: Suratman NIM : E0000204 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008 PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Disusun oleh: SURATMAN NIM : E0000204 Disetujui untuk Dipertahankan Pembimbing I Endang Mintorowati, S.H., M.H. NIP. 130814527 Pembimbing II Andri Astuti, S.H. NIP. 131285214 PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Disusun oleh: SURATMAN NIM : E0000204 Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada: Hari : Rabu Tanggal : 14 Mei 2008 TIM PENGUJI 1. Endang Mintorowati, S.H., : ................................................. M.H. NIP. 130814527 2. Andri Astuti, S.H. : ................................................. NIP. 131285214 3. Djuwityastuti, S.H. : ................................................. NIP. 130814527 Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum UNS Moh. Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 131570154 MOTTO DAN PERSEMBAHAN “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Q.S. al-Fatihah: 1-7) Kupersembahkan skripsi ini untuk seseorang yang kucintai: Indah Nugrahaningsih KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada manusia dan ala mini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyullah Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau. Rasa syukur teramat dalam penulis persembahkan kepada Allah sehingga penulisan hukum yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini membahas tentang ketentuan harta perkawinan, ketentuan harta perkawinan jika ada perjanjian perkawinan, dan akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan yang ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Hal tersebut ditulis karena adanya kasus-kasus harta kekayaan perkawinan yang muncul di masyarakat dan masih minimnya pemahaman masyarakat, khususnya calon suami istri terhadap perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap persoalan tersebut. Penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penulisan hukum ini sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Syamsul Hadi, Sp.Kj. selaku rektor Universitas Sebelas Maret. 2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Ibu Endang Mintorowati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi bagi penulis. 4. Ibu Andri Astuti, S.H. selaku pembimbing pembimbing skripsi bagi penulis. 5. Ibu Djuwityastuti, S.H. selaku penguji skripsi. akademik dan 6. Ust. Ahmad Yani al-Hafizh yang telah mengajarkan Al-Qur’an kepada penulis dan makna nyantri. 7. Ust. Sholihan MC yang telah mengajarkan berbagai “pemikiran yang lain” dan semangat berfikir. 8. Ayahanda Ahmad Ngalimi dan Ibunda Riyati yang telah merawat dan mendidikku dengan tulus dalam kesederhanaan, serta adik-adikku: Sugeng, Warti, dan E’un yang kucintai walau jarak memisahkan kita sejak kecil. 9. Bapak Suwarjono dan Ibu Siti Aminah yang telah menjadikanku “anaknya” penuh keikhlasan. 10. Bapak Djumbadi dan Ibu Sri Enny Purwaningsih yang telah menerimaku sebagai belahan jiwa putri sulungnya, serta adik-adikku: Nopa dan Ningnong yang memberikan semangat. 11. Indah Nugrahaningsih, wanita yang telah menerimaku apa adanya, menjadikan nafas hidupku berdenyut kembali, dan melukiskan warna hidup sejati. 12. Santri Pesantren Mahasiswa Ar-Royyan, khususnya angkatan pertama hingga generasi Maret 2008 yang mengajarkan makna persaudaraan dan hidup bersama: Mas Lukman, Mas Furqon, Mas Agus Virdy, Rudi, Farisy, Dhani ‘Dokter’, Ahmad ‘Bambang’, Indra ‘Indleks’, Hartoko, Masjudi, Auriga, Didin, Nanang, Agus Dani, Ro’uf, Abob, Dodik, dan semuanya. 13. Ust. Bimo, Lc. dan Mas Edy ‘Abyan’ yang memberikan banyak dukungan dan teman di masa-masa penuh cobaan. 14. Ir. Bambang Maryatno dan keluarga yang telah banyak direpotkan semasa perjuangan di Arimatea. 15. Bunda Dewi dan Pak Nadianto yang juga selalu menyemangatiku saat di Arimatea. 16. Teman-teman seperjuangan di KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Solo, FMRD (Front Mahasiswa Religius Demokratik) yang getol menggoyang Gus Dur dan Megawati, JN UKMI UNS tempat meneduhkan hati, DEMA (Dewan Mahasiswa) FH UNS dan DEMA UNS, Partai Gerbang UNS, serta para kenshi di Dojo Shorinji Kempo UNS yang mengajarkan ‘kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezhaliman dan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan’. 17. Para ustadz dan santri di Ma’had Al-Bina’, Pesantren Nurul Wahid Kutoarjo, PUSQBA Tsaqifa, Pusat Kajian Kitab Gundul Al-Furqon, dan Ma’had Abu Bakar Ash-Shiddiq. 18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan di masa datang. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat. Amin. Penulis, Mei 2008 Penulis DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………....... HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………….. HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………. HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………... KATA PENGANTAR …………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………. DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………… ABSTRAK ………………………………………………………………. i ii iii iv v viii x xi xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ……………………………………… B. Rumusan Masalah ……………………………………………. C. Tujuan Penelitian …………………………………………….. D. Manfaat Penelitian …………………………………………… E. Metode Penelitian ……………………………………………. F. Sistematika Skripsi …………………………………………… BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1 6 7 7 8 13 A. Kerangka Teori ……………………………………………….. 1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum …………. 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ………………………………………………………. 3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam …………………. 4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ……………………… 5. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan …………. B. Kerangka Pemikiran …………………………………………. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 dan Hukum Islam …………………………………………… 48 1. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ……………………………………………………. 2. Ketentaun Harta Kekayaan Perkawinan Bersadarkan Hukum Islam ………………………………………………….. 48 B. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1Tahun 1974 dan Hukum 54 Islam ………………………………………………………………. 1. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 2. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada 62 Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam ……….. C. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika 62 Ada Perjanjian Perkawinan Berdasrkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam …………………………………………………. 68 1. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan 71 Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ……………………………………………………. 2. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam …………………………………………………………… BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ………………………………………………………. B. Saran ……………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan rumah tangga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. (A. Azhar Basyir, 1990: 1) Satu hal yang harus diakui bahwa dalam setiap kehidupan keluarga, sudah tentu akan muncul sejumlah persoalan. Persoalan tersebut sangat beragam, baik yang menyangkut finansial, kasih sayang, maupun sosial. ( Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, 2006: 64) Setelah melangsungkan ijab kabul, seorang suami istri melangkah ke kahidupan baru mengarungi bahtera kehidupan nyata. Keduanya akan berhadapan dengan realita kehidupan yang mungkin selama sebelum menikah tidak pernah dihadapi. Mereka akan berhadapan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, ayah atau ibu bagi anak-anaknya, dan sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, mereka akan dihadapkan pada persoalan keluarga dan masyarakat luas. Salah satu akibat perkawinan adalah terhadap masalah harta. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, dan Pasal 65. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai harta perkawinan selama tidak ada perjanjian lain mengenainya. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan tindakan hukum atas harta perkawinan. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika terjadi perceraian. Sedangkan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika poligami. Dengan demikian, bisa dimungkinkan pengaturan lain harta perkawinan jika ada perjanjian lain mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai perjanjian perkawinan yang bisa memperjanjikan masalah harta perkawinan yang berbeda dengan ketentuan harta perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perkawinan di atas. Pada banyak kasus, bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan disampaikan, namun juga berkembang menjadi masalah keluarga antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Dengan adanya keterkaitan emosi yang begitu tinggi di antara pasangan yang akan menikah, bisa menghalangi objektivitas untuk mengantisipasi potensi masalah finansial dalam sebuah perkawinan, termasuk risiko perceraian. Anggapan bahwa jika kita saling mencintai maka kita tidak akan memiliki masalah keuangan, sebenarnya kurang tepat. Faktanya, masalah keuangan tetap saja muncul tidak peduli betapa pasangan berdua saling mencintai. Betapa besarnya masalah keuangan yang akan muncul ketika pasangan suami istri tidak lagi saling mencintai dan memutuskan bercerai. (Mike Rini, http://www.danareksa.com, diakses tanggal 26 September 2007). Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian pernikahan yang dibuat pasangan sebelum mereka menikah, meskipun sejumlah pasangan di Indonesia sudah melakukan hal tersebut. Selain hal itu tidak biasa dilakukan masyarakat Timur, juga menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga pernikahan. Seakanakan pernikahan hanya merupakan sebuah “company” layaknya kerjasama dalam bisnis, sehingga harus diantisipasi kerugian atau risiko yang akan terjadi jika suatu saat terjadi perceraian. Tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia sempat heboh ketika artis Desy Ratnasari membuat perjanjian pernikahan sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan Ir. Pramugara beberapa tahun lalu. Pro kontra pun dilancarkan masyarakat terhadap tindakan Desy tersebut. Drs. Saepuddin, penasihat BP4 Kandepag Kota Bandung, mengatakan bahwa bila dicermati, pada dasarnya pernikahan itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin atas dasar iman. Maka, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, perjanjian ini akan melahirkan perjanjian-perjanjian baik tertulis maupun tidak. Menurutnya, Pasal 29 UU Perkawinan secara tegas menyebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan pasal tersebut, maka dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian pemisahan harta suami dan istri sebagai harta bawaan. Karena, ketika menikah akan timbul konsekuensi waris, yang sumbernya dari harta bawaan, mahar (bagi istri) atau hadiah dan hibah lainnya, serta harta gono gini. Pasal tersebut bisa menjadi landasan membuat perjanjian selain akad nikah yang disahkan menurut undang-undang dan dicatat dalam akta perkawinan. Dalam akta perkawinan ditegaskan bahwa apakah ada perjanjian lain selain akad nikah. Bila secara hitam di atas putih telah dibuat perjanjian perkawinan, maka akan ditulis pada akta perkawinan bahwa ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. (http://www.pikiranrakyat.com, diakses tanggal 3 Oktober 2007). Diah Nurwitasarim Dipl. Ing., Ketua Lembaga Dakwah dan Pemberdayaan Potensi Muslimah (LDP2M) Permata Bandung menyatakan bahwa fenomena perjanjian perkawinan bisa berkembang pesat di masyarakat perkotaan, di mana budaya praktis atau instan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Sehingga, bila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam pernikahan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan, dibuatlah perjanjian-perjanjian untuk mengatur sistem hidupnya. Bila sudah demikian, kebergantungan manusia pada sistem hukum, selain yang telah ditetapkan Allah melalui Al-Qur’an dan as-Sunnah, akan melemah. Ditinjau lebih jauh, adanya perjanjian pemisahan harta suami dan istri merupakan sikap yang dibentuk dari hasil pemikiran untuk menimbang secara matang saat memasuki jenjang pernikahan. Secara sederhana hal tersebut bisa dilihat dari rentetan kecenderungan tersebut, di mana ada indikator yang signifikan yaitu kecenderungan menunda menikah. Ini menandakan pola pikir dalam merencanakan pernikahan lebih matang lagi, dengan berupaya mengantisipasi segala sesuatunya yang bisa timbul akibat pernikahan. Fenomena lain yang bisa mendorong adanya perjanjian tersebut angka partisipasi kerja perempuan yang juga semakin meningkat, didorong oleh perbaikan taraf hidup dan pendidikan yang lebih baik pula. Selain itu, sudah menjadi suatu kewajaran seiring dengan tantangan hidup di perkotaan yang sangat kompetitif dan dinamis, suami menghendaki istri bekerja dengan pertimbangan untuk sama-sama membangun rumah tangga, saling membantu dalam perekonomian. Atau, karena istri sudah memiliki karier sebelumnya. Semua kecenderungan yang sudah menjadi pola hidup masyarakat perkotaan kemudian terbawa ketika memasuki jenjang pernikahan. Karena hal inilah perjanjian pemisahan harta suami dan istri menjadi sesuatu yang biasa terjadi dan berkembang di masyarakat. Sepintas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta muncul dimaksudkan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa dialami dalam berumahtangga. Bila sudah demikian, dapat ditebak bahwa ada mosi ketidakpercayaan terhadap insitusi pernikahan, sehingga risiko-risiko yang bisa ditimbulkan, misalnya saja perceraian, sudah diperhitungkan sejak awal. Selanjutnya, apakah perjanjian pemisahan harta ini diperbolehkan dalam Islam? Dikatakan boleh atau tidak boleh, bisa menjadi sesuatu yang kontradiksi. Tidak bisa dikatakan tidak boleh, namun juga bukan berarti boleh. Karena akan berbenturan dengan tujuan pernikahan. Yang harus dipahami, Islam merupakan sistem hidup yang telah mengatur segala sesuatunya demi kebaikan umat manusia, di dalamnya sudah diatur tentang perjanjian-perjanjian, khususnya dalam berumahtangga. Sudah menjadi fitrah dan keinginan semua orang dalam berkeluarga bisa membangun ketentraman dan kenyamanan lahir batin sebagai keluarga yang sakinah, mawahdah warahmah. Dalam Islam sudah jelas bahwa harta istri sangat dihormati. Harta bawaan istri tidak menjadi kewajiban untuk dijadikan sumber menafkahi keluarga. Sementara bagi suami, kewajiban menafkahi menjadi mutlak, hartanya akan dinikmati istri dan anak. Namun, bila harta yang dibawa dan harta yang dihasilkan istri digunakan untuk kepentingan anak dan suami itu merupakan merupakan ladang amal baginya. Hartanya sebagai shadaqah. Hal tersebut yang harus dipahami sehingga tidak lagi terjebak materialistik. Visi berkeluarga ini yang harus dikedepankan, sehingga istri tidak menjadi tampil dominan dalam keluarga karena menguasai harta yang lebih banyak atau lebih besar. Tujuan keluarga muslim tidak hanya kebahagiaan dunia, namun juga membangun kebahagiaan di akhirat. Jadi, bisa saja ada perjanjian pembagian tanggung jawab dari penghasilan suami atau istri untuk dialokasikan pada satu pos tertentu. Misalnya saja suami hanya membiayai kebutuhan material yang besar dan berat, sementara istri lebih mengurus kebutuhan anak. Dalam pasal 34 UU N0. 1 Tahu 1974 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Walaupun sudah ditegaskan dalam pasal tersebut bukan berarti istri tidak menolong suami. Pada kasus tertentu bisa saja suami tiba-tiba berhenti atau diberhentikan dari pekerjaanya, dan istri bisa menopang ekonomi keluarga. Di sinilah perlu saling pengertian dan mendukung agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis. (http://www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 3 Oktober 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang hukum perjanjian perkawinan, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”. B. Rumusan Masalah Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian, termasuk penelitian hukum. Agar subyek permasalahan yang ada nanti dibahas lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka sangat penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan penulis adalah: 1. Bagaimanakah ketentuan harta kekayaan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam? 2. Bagaimana ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam? C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. b. Untuk mengetahui perkawinan jika ketentuan ada harta perjanjian kekayaan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum perdata Indonesia dan hukum Islam dalam hal perjanjian perkawinan. b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Karena, nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata serta hukum Islam pada khususnya. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perjanjian perkawinan menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. 3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitin sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam hal perjanjian perkawinan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam hal perjanjian perkawinan bagi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mempunyai kepedulian dapat pihak-pihak dan membantu terkait ketertarikan yang terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. E. Metode Penelitian Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Jenis Penelitian Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitin hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang utamanya meneliti data primer). Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto,1986 : 10). 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk meneliti hakikat dan makna suatu hal, kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian. 4. Jenis Data Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Adapun ciri-ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2003 : 24) yaitu: a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made); b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu; c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. 5. Sumber Data Sumber data merupakan tempat di mana data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga, yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: 1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. 2) Peraturan Dasar (a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945; (b) Ketetapan-ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Peraturan perundang-undangan: (a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf; (b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf; (c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf; (d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf; (e) Peraturan-peraturan daerah. 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5) Yurisprudensi. 6) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya KUH Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht). b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasi karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 52). 6. Instrumen Pengumpulan Data Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, literatur, dan yang mendukung. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. 7. Tempat Penelitian Tempat penelitian ini penelitian untuk adalah berbagai di memperoleh data perpustakaan, dalam yaitu di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, Perpustakaan Pesantren Mahasiswa Ar-Royyan Solo, perpustakaan pribadi peneliti, dan media internet. 8. Analisis Data Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Adapun pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada. Berukut ini saran dari Bogdan dan Taylor (1975 : 82-84), yang telah diterjemahkan oleh Moleong (1990 : 103-104) seperti di bawah ini, yaitu: a. Membaca dengan teliti catatan yang ada Seluruh data dibaca dan ditelaah secara mendalam. Seluruh bagiannya merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dicari. b. Memberi kode Setelah membaca seluruhnya dan memperoleh kesan tertentu, peneliti kemudian memberi kode pada data yang ada. Setelah diberi kode, data kemudian dipelajari dan ditelaah lagi serta disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema. c. Menyusun menurut tipologi Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa. d. Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan setting penelitian. Selama dan sesudah mengumpulkan data, kepustakaan terkait dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional. Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah merumuskan hipotesa-hipotesa atau pernyataanpernyataan (Burhan Ashshofa, 1996 : 66-68). F. Sistematika Skripsi Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab perbandingan ini hukum, diuraikan yaitu tentang membandingkan sistem-sistem hukum untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, tinjauan hukum Islam, tinjauan perkawinan, tinjauan perjanjian perkawinan, kerangka pemikiran. BAB III : PEMBAHASAN dan uraian mengenai Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas tentang ketentuan harta perkawinan, ketentuan harta perkawinan jika ada perjanjian perkawinan, akibat hukum harta perkawinan jika ada perjanjian perkawinan yang masing-masing ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan permasalahan yang ada. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN saran-saran mengenai BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum a. Pengertian Perbandingan Hukum Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum antara lain Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsvergelijking (istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman). Di dalam Black’s Dictionary dikemukakan bahwa Comparative Jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law). (Barda Nawawi Arief, 2003 : 3). Sedangkan apabila diamati istilah asingnya, comparative law maka dapat diartikan bahwa, titik berat adalah comparative, pada dalam perbandingannya hal ini kalimat atau comparative memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingakan). Istilah perbandingan hukum dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti sedalamnya dari pengertian istilah perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum (Romli Atmasasmita, 2000 : 7). Berkaitan dengan pengertian perbandingan hukum, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian perbandingan hukum diantaranya sebagai berikut (Romli Atmasasmita, 2000 : 7-10): 1) Rudolf B. Schlesinger, perbandingan penyelidikan mengatakan hukum dengan bahwa merupakan tujuan untuk metoda memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapai unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. 2) Winterton, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah membandingakan suatu metoda sistem-sistem yang hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. 3) Gutterdige, menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu. 4) Lemaire, mengemukakan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan ) mempunyai lingkup: ( isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. 5) Ole Lando, mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup: “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecendrungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. 6) Hessel Yutema, mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai berikut: Comparative law is simply another name for legal science and an integral part of the more comprehensive universe of social science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook: it contemplates that while the technique nay vary, the problems of justice are basically the same in time and space throughout the world. Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang universal; sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia. 7) Orucu, mengemukakan bahwa comparative law is a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal instutions and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these system with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc. Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan- hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum, dan lain-lain. Adapun Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau, membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1983 : 60). R. Soeroso, perbandingan hukum S.H. menyimpulkan adalah suatu bahwa cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret (R. Soeroso, 1999 : 8). Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa ada dua kelompok definisi perbandingan hukum yaitu kelompok pertama, definisi yang menganggap perbandingan hukum sebagai metoda dan kelompok kedua yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum (science) (Romli Atmasasmita, 2000 : 12). Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, penulis akan mengkaji perbandingan hukum sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L menyebutkan bahwa dalam Penelitian hukum normatif atau kepustakaan itu mencakup: a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; b) Penelitian terhadap sistematika hukum; c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; d) Perbandingan hukum; e) Sejarah hukum. 2) Manfaat Perbandingan Hukum Manfaat atau kegunaan perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan beberapa ahli antara lain sebagai berikut (Ade Maman Suherman, 2004 : 17-19): a) Menurut Sudarto Kegunaan yang bersifat umum: (1) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah; (2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri; (3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Yang bersifat khusus berkaitan dengan asas nasional aktif yang membawa konsekuensi Pasal 5 Ayat 1 KUHP. Pendapat di atas khususnya mengenai yang bersifat khusus memfokuskan hukum pidana. b) Rene David dan Brierly pada masalah (1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis; (2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri; (3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu, memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional. c) Tahir Tungadi (1) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional; (2) Berguna untuk konvensi harmonisasi internasional hukum, dengan antara peraturan perundangan nasional; (3) Untuk pembaharuan memperdalam hukum pengetahuan yakni dapat tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional; (4) Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional). Hal ini penting dalam menentukan the general principles of law yang merupakan sumber yang penting dari hukum public internasional; (5) Sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus; (6) Diperlukan dalam penasihat-penasihat program hukum pendidikan pada bagi lembaga perdagangan internasional dan kedutaan- kedutaan, misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional. d) Menurut Ade Maman Suherman Perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoeh suatu pemahaman yang comprehensive tentang semua sistem hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat: (1) Manfaat internal, dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional; (2) Manfaat eksternal, baik individu, organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam dengan melakukan negara lain hubungan yang hukum berlainan sistem hukumnya; (3) Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional. Sedangkan Soerjono Soekanto (1986 : 263) mengemukakan bahwa kegunaan dari penerapan perbandingan hukum antara lain memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. Hasil-hasil bermanfaat perbandingan bagi hukum penerapan akan hukum sangat di suatu masyarakat majemuk seperti Indonesia, terutama untuk mengetahui bidang-bidang mana yang dapat diunifikasikan dan bidang manakah yang harus diatur dengan hukum antartata hukum. Adapun tujuan mempelajari perbandingan hukum menurut Prof. R. Subekti yaitu kita tidak sematamata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebabsebab adanya perbedaan-perbedan tesebut. Untuk itu, kita perlu mengetahui latar belakang dari peraturanperaturan hukum yang kita jumpai. 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 a. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut UU N0. 1 Tahun 1974 1) Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan dan wanita untuk hidup bersama, atau dengan kata lain disebut “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata dan mengikat pihak yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat tapi harus ada. Karena, tanpa ikatan batin, maka ikatan lahir akan rapuh. (K. Wantjik Saleh, 1980 : 14-15). 2) Tujuan Perkawinan Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan perkawinan di atas berarti: perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri saling membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga akan bahagia jika kebutuhan pokok jasmani dan rohaninya terpenuhi. (Salim H.S., 2003 : 62). 3) Syarat-syarat Perkawinan Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan dua syarat perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun kedua syarat tersebut dapat dijelaskan di bawah ini (Salim H.S., 2003 : 62-63). Syarat-syarat intern perkawinan adalah: a) Persetujuan kedua belah pihak; b) Izin dari kedua orang mencapai umur 21 tahun; tua apabila belum c) Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati; d) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin; e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddah-nya 90 hari, dan jika karena kematian 130 hari. Syarat-syarat ekstern perkawinan adalah: a) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk; b) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat: (1) Nama, pekerjaan, umur, tempat agama/kepercayaan, kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Selain itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu; (2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. Jika syarat-syarat di atas, baik syarat intern maupun syarat ekstern terpenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan. 4) Sahnya Perkawinan Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi hal-hal berikut ini, yaitu (Salim H.S., 2003 : 64-65) : a) Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974); b) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing bertujuan untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah: a) Untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lain; b) Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kemudian hari jika timbul sengketa antara anak kandung dan anak tiri; c) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi Pegawai Negeri Sipil. 5) Akta Perkawinan Akta perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 11 dan 12 PP No. 9 Tahun 1975. (Djaja S. Meliala, 2003 : 56). Akta perkawinan adalah bukti suatu perkawinan. Akta perkawinan itu dianggap sah, kecuali kalau dapat dibuktikan adanya kepalsuan. Sebagai alat bukti, maka akta perkawinan memiliki tiga sifat, yaitu: a) Sebagai satu-satunya alat bukti yang memiliki arti mutlak; b) Sebagai alat bukti penuh, artinya, di samping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain; c) Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu. 6) Akibat Perkawinan Perkawinan membawa akibat bagi pihak yang melangsungkannya dan pihak lain yang berkaitan. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan membawa tiga akibat, yaitu: a) Adanya hubungan suami istri; b) Hubungan orang tua dengan anak; c) Masalah harta kekayaan. Akibat perkawinan dalam masalah harta kekayaan adalah adanya ketentuan hukum dalam masalah harta perkawinan. Mengenai harta kekayaan perkawinan akan dibahas dalam subbab tersendiri. b) Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37. Dalam ketentuan tersebut dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)) (Salim H.S., 2003 : 75). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1) dan (2)). Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya (Hilman Hadikusuma, 1990 : 122123). 3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam a. Ruang Lingkup Hukum Islam Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fiqih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bidang ibadah (mahdhah) dan bidang muamalah (ghairu mahdhah). Ibadah (mahdhah) adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seseorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi dimana ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadat. Yang mungkin berubah adalah penggunaan alatalat modern dalam pelaksanaannya. Adapun muamalat (ghairu mahdhah) dalam pengertian yang luas yakni ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu (Mohammad Daud Ali, 1999 : 48-49). Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum ini. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, munakahat, wirasah, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau ukubat, al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), siyar, dan mukhasamat (H.M. Rasjidi, dalam Muhammad Daud Ali, 1999 : 50). Apabila hukum Islam disistematikan seperti hukum Eropa yaitu hukum perdata dan hukum publik, maka hukum Islam dapat kita sistematikan berupa hukum perdata Islam dan hukum publik Islam. Hukum perdata Islam terdiri dari: 1) Munakahat, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. 2) Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. 3) Muamalat, dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Sedangkan hukum publik Islam terdiri dari: 1) Jinayat, yang memuat perbuatan-perbuatan aturan-aturan yang menenai diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari hadd = batas). Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. 2) Al-ahkam as-sulthaniyah, membicarakan soal-soal yang berhubungan pemerintahan, baik dengan pemerintah kepala negara, pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. 3) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. 4) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara (Mohammad Daud Ali,1999 : 51). b) Tujuan dan Sumber Hukum Islam Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akherat, dengan jalan mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan Abu Ishaq as-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut “maqashid al-khamsah” (M. Farkhan M, 2006 : 56). Adapun sumber hukum Islam yaitu: 1) Al-Qur’an Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. 2) As-Sunnah (Al-Hadits) As-Sunnah (Al-Hadits) adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang AlQur’an. 3) Akal Pikiran (Ra’yu) Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam Al-Qur’an dan al-Hadits. Adapun jalan atau cara yang digunakan di antaranya, yaitu: (1) Ijmak, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. (2) Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadits) karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). (3) Istidal, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. (4) Mashalih al-mursalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik dalam AlQur’an maupun kitab-kitab hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. (5) Istihsan, yaitu cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. (6) Istishab, yaitu menetapkan hukum sesuatu hal menurut sebelumnya, keadaan sampai yang terjadi ada dalil yang ‘urf yang tidak mengubahnya. (7) Adat istiadat atau bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan masyarakat tetap terus berlaku yang bagi bersangkutan. (Muhammad Daud Ali, 1999 : 100-111). c.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam 1) Pengertian Perkawinan Menurut syari’at (hukum) Islam, hakikat perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, yaitu akad antara calon laki (suami) istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. Sedangkan yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya (Mahmud Yunus, 1977 : 1). 2) Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari’at (Ny. Soemiyati, 1986 : 12). Dengan kata lain, tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah agar turut (tunduk kepada) perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Yunus, 1977 : 1). 3) Rukun dan Syarat Perkawinan Rukun dipenuhi perkawinan dalam perkawinan adalah sesuatu pelaksanaan adalah sesuatu yang perkawinan. yang harus harus Syarat dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan. Rukun perkawinan ada lima, yaitu: a) Calon suami, dengan syarat: Islam, tidak dipaksa, bukan mahramnya, tidak sedang haji atau umrah. b) Calon istri, dengan syarat: Islam, bukan mahramnya, tidak sedang haji atau umrah, tidak sedang dalam masa iddah, tidak bersuami, mendapat izin wali. c) Wali, dengan syarat: Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik. d) Dua orang saksi, dengan syarat: Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad perkawinan. e) Ijab kabul, dengan syarat: dengan mengatakan nikah atau zawaj (kawin), ada kecocokan antara ijab dan kabul, berturut-turut (tidak dilakukan di lain waktu), tidak ada syarat yang memberatkan dalam pernikahan itu (Khuslan Haludi dan Abdurrahim Sa’id, 2004 : 135-136). 4) Sahnya Perkawinan Dalam hukum Islam, nikah dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun perkawinan, yaitu (Abu Bakr Jabir alJazairi, 2006 : 575-577): a) Adanya wali nikah; b) Adanya dua orang saksi; c) Adanya akad nikah; d) Adanya mahar. 5) Akta Perkawinan Dalam hukum Islam tidak secara tegas sebuah perkawinan harus dicatat dalam sebuah akta perkawinan, tetapi jika akta perkawinan itu memberikan maslahat (kebaikan) bagi para pihak, maka hukum Islam juga tidak melarang perkawinan dicatat dalam akta perkawinan. Hal yang demikian itu termasuk hal yang mubah (boleh dilakukan). 6) Akibat Perkawinan Perkawinan menurut hukum Islam membawa tiga akibat, yaitu: a) Adanya hubungan suami istri; b) Hubungan orang tua dengan anak; c) Masalah harta kekayaan. d. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan. Yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta berlangsung. maskawin Dalam (mahar) Al-Qur’an ketika terdapat perkawinan ayat yang menyatakan: “... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ....” (Q.S. an-Nisa’: 32) Ayat tersebut bersifat umum, tidak ditujukan terhadap suami atau istri. Dengan demikian, tidak ditujukan kepada suami istri saja, melainkan kepada semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya seharihari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami. Masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada, dan harta bawaan istri itu kemudian bertambah dengan maskawin yang diterimanya dari suaminya (Hilman Hadikusuma, 1990 : 126-127). 4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Perdata Masalah perjanjian masuk dalam lingkup hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata, dan tidak terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perjanjian perkawinan masih tetap memiliki hubungan dengan KUH Perdata terhadap masalah-masalah yang di UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang merupakan salah satu bentuk perjanjian, pada prinsipnya mengikuti ketentuan KUH Perdata selama tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, masalah tinjauan mengenai “perjanjian” didasarkan pada KUH Perdata. Yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1976 : 1) Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2001 : 339). Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan. Suatu perjanjian batal demi hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi, dan suatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dsapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu, suatu perjanjian hendaknya dibuat dengan itikad baik dari pihak yang berjanji (Pasal 1338 KUH Perdata). Dalam KUH Perdata terkandung asas-asas perjanjian, yaitu: 1) Asas kebebasan berkontrak; 2) Asas konsensualisme; 3) Asas kekuatan mengikat; 4) Asas persamaan hukum; 5) Asas kepastian hukum; 6) Asas kebiasaan; 7) Asas itikad baik; 8) Asas kepercayaan. b. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Islam Dalam hukum Islam, perjanjian termasuk dalam lapangan muamalah yang diperbolehkan. Ayat Al-Qur’an menyatakan: "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al Isrâ' : 34) Dalam kitab Fiqhu as-Sunnah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disyaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib dihormati dan dipenuhi, hal-hal berikut ini, yaitu : 1) Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya. Sabda Rasulullah saw. : "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat." Yang dimaksud dengan 'kitab Allah' dalam pengertian di atas adalah hukum Allah, yaitu syariat (hukum) Islam. 2) Harus sama-sama ridha (rela, ikhlas) dan ada pilihan (tidak dalam paksaan) karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan dan tidak ada penghargaan terhadap akad (perjanjian) yang tidak memenuhi keabsahannya. 3) Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi kesalahpahaman yang pada bisa menimbulkan waktu penerapannya (pelaksanaannya) (Sayyid Sabiq, 1978 : 196). Dalam hukum Islam sebuah janji harus dipenuhi dengan baik. Penghormatan teerhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan mengenai perjanjian: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S. Al Mâ'idah : 1) "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al Isrâ' : 34) 5. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan a. Tinjuan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 1) Pengertian Perjanjian Perkawinan Ada beberapa istilah untuk perjanjian perkawinan yang digunakan, antara lain “perjanjian kawin”, “perjanjian pranikah” atau dalam Burgelijk Wetboek disebut “huwelijksvoorwaarden”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “prenuptial agreement”. Pengertian perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1074 adalah perjanjian bersama secara tertulis antara calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan di mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., perjanjian perkawinan adalah “perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum dilangsungkan atau untuk pada saat mengatur perkawinan akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka”. (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 128). Sedangkan Salim H.S., S.H., M.S. mengartikan perjanjian perkawinan sebagai “perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. (Salim H.S., 2003 : 72). 2) Pengaturan Perjanjian Perkawinan Perjanjian perkawinan diatur dalam KUH Perdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 139 s.d. Pasal 154, sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 29, dan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 diatur dalam Pasal 45 s.d. 51. 3) Alasan dan Maksud Perjanjian Perkawinan Perjanjian perkawinan dibuat untuk memperjanjikan hal-hal yang ingin diperjanjikan oleh pasangan calon suami istri setelah perkawinan berlangsung. Secara umum, suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan sebagai berikut (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 129) : a) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain; b) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar; c) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut; d) Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing sendiri-sendiri. akan bertanggunggugat Maksud pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama (Pasal 119 KUH Perdata). Dengan demikian para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Alasan diserahkan dan maksud kepada perjanjian para pihak, perkawinan asalkan tidak melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum dan beberapa hal yang ditentukan dalam KUH Perdata (Pasal 139 KUH Perdata), tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). 4) Waktu dan Berlakunya Isi Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (1)). Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak (suami istri) ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat (3) dan (4)). Isi perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu suami istri yang bersangkutan, juga berlaku bagi pihak ketiga yang bersangkutan pula (Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). 5) Isi dan Sahnya Perjanjian Perkawinan Berdasarkan pengertian perjanjian perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa isi perjanjian perkawinan adalah memperjanjikan masalah harta kekayaan suami istri yang bersangkutan. Namun demikian, jika melihat pasal-pasal yang mengatur perjanjian perkawinan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka isi perjanjian tidak hanya mengatur masalah harta kekayaan, tapi boleh juga mengatur hal lain selain harta kekayaan. Isi perjanjian perkawinan mengenai hal lain selain harta kekayaan tidak dibatasi dan sangat luas. Hal tersebut tetap sah asalkan tidak melanggar tertib umum, batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Mengenai isi perjanjian perkawinan, UU Perkawinan tidak membahas, yang ada bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian, mengenai isi perjanjian perkawinan diserahkan kepada pejabatpejabat umum yang memiliki wewenang untuk memberikan penafsirannya. (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 130-131). Dalam peraturan pelaksanaan UU Perkawinan sendiri, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, sepanjang mengenai mengatur lebih pembatasan apakah Sehingga apa mengenai dengan perjanjian lanjut saja harta perkawinan tentang yang demikian, pembatasan- dapat benda tidak diperjanjikan, atau sepanjang yang lain. mengenai perjanjian perkawinan luas sekali perumusannya yang dapat ditafsirkan banyak berbagai hal. (Soedaryo Soimin, 2002 : 20). Tidak ditentukan perjanjian itu mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa yang dimaksud “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak”. (K. Wantjik Saleh, 1980 : 32). Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 131) : a) Tidak membuat janji-janji (bedingen) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; b) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hakhak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama; c) Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan; d) Tidak dibuat janji-janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva; e) Tidak dibuat janji-janji bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing. 6) Prosedur dan Bentuk Perjanjian Perkawinan Prosedur perjanjian perkawinan adalah dibuat oleh kedua belah pihak calon suami istri dengan kesepakatan bersama secara tertulis yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). b. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam hukum Islam, walaupun tidak dinyatakan secara tegas sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan hadis Nabi perjanjian Muhammad, perkawinan namun dalam berdasarkan penerapan perjanjian sebagai syarat perkawinan terdapat beberapa pendapat mengenai hal itu di kalangan ulama mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sayyid Sabiq dalam kitabnya, Fiqhu as-Sunnah, mengemukakan penjelasan mengenai ijab kabul yang disertai dengan syarat beserta siapa yang berpendapat seperti itu. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa apabila dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi hukum perkawinan, atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh perempuannya, atau mengandung syarat yang dilarang oleh agama, maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri yang secara ringkas disebutkan di bawah ini, yaitu: 1) Syarat yang wajib dipenuhi. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu yang termasuk dalam rangkaian dan tujuan perkawinan serta tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti: menggauli dengan baik; memberikan nafkah/belanja, pakaian, dan tempat tinggal yang pantas; tidak mengurangi sedikit pun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya sama dengan istriistrinya yang lain (jika ta‘addud atau poligami); tidak boleh keluar rumah suaminya kecuali jika diizinkan; tidak mencemarkan suaminya; tidak berpuasa sunnah kecuali jika diizinkan suaminya; tidak menerima tamu orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izin suami; dan tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izin suami; dan lain sebagainya. 2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi. Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi akad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan, seperti: tidak memberi nafkah/belanja; tidak mau bersetubuh atau memisahkan diri dari kawin tanpa mahar; istrinya; istrinya yang harus memberikan nafkah atau memberi sesuatu hadiah kepada suaminya; dalam sepekan hanya tinggal bersama semalam atau hanya mau tinggal dengan istrinya di siang hari, tidak di malam harinya. Syarat-syarat di atas semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum perkawinan dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami istri sebelum ijab kabul. Oleh karena itu, tidak sah, sebagaimana kalau seorang Syafi'i yang mengurangi hak-hak barang Syuf'ahnya sebelum dijual. Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syaratsyaratnya tadi berada di luar ijab kabul, yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, akadnya tidak batal, sebagaimana kalau disyaratkan mahar yang haram waktu ijab kabul. Sebab, pernikahan seperti ini tetap sah, sekalipun tidak disebut apa yang nanti harus menjadi mas kawinnya. Jadi, ijab kabul dengan adanya syarat yang batal itu tetap sah. 3) Syarat-syarat yang hanya untuk perempuannya. Di antara syarat-syarat yang guna dan faedahnya untuk perempuannya saja, seperti: suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar dari rumah atau kampung halamannya; tidak mau pergi bersamanya; atau tidak mau dimadu; dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, segolongan ulama berpendapat bahwa nikahnya tetap sah dan syarat-syarat tersebut tidak berlaku, dan suaminya tidak harus memenuhinya. Pendapat kedua, segolongan ulama lain berpendapat bahwa wajib memenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya, dan jika tidak dipenuhi, maka istrinya berhak minta fasakh. Pendapat pertama merupakan paham Abu Hanifah, Syafi'i, dan sebagian besar ulama. Alasan mereka berpendapat demikian adalah sebagai berikut : Rasulullah saw. pernah bersabda : "Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali jika syarat tersebut menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal." Mereka mengatakan bahwa syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di atas, yaitu: bermadu (ta‘addud atau poligami), melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang kesemuanya ini dihalalkan oleh agama. Sabda Rasulullah saw. : "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat." Mereka mengatakan bahwa syarat di atas tidak ada dalam kitab Allah, karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama. Mereka juga mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut di atas tidak mengandung kemaslahatan dalam perkawinan dan tidak pula masuk dalam rangkaiannya. Adapun pendapat kedua adalah paham Umar bin Khattab, Sa‘ad bin Abi Waqash, Mu‘awiyah, ‘Amru bin ‘Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza‘i, Ishaq, dan golongan Hambali. Alasan mereka berpendapat demikian adalah sebagai berikut : Firman Allah ta'ala : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S. Al Mâ'idah : 1) Sabda Rasulullah saw. : "Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka." Hadis Bukhari, Muslim, dan lain-lain yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah saw. bersabda : "Perjanjian yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin (persetubuhan) bagi kamu." Maksud dari hadis di atas adalah bahwa perjanjian yang paling patut untuk ditunaikan ialah perjanjian dalam perkawinan, kerena masalahnya paling sungguh- sungguh dan paling berat. Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan janji tetap tinggal di rumahnya. Kemudian, suaminya bermaksud mengajaknya pindah. Lalu, mereka (keluarganya) mengadukan kepada Umar bin Khattab. Maka, Umar bin Khattab memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya. Di sini, hak suami atas istri batal karena ada perjanjian. Selain itu, karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada maksud, perempuan yang menghalangi mengandung asalkan perkawinan. manfaat maksudnya Maka, sah tadi dan tidak hukumnya, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi. Ibnu Qudamah menguatkan pendapat (kedua) ini dan melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata: “Adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat (Nabi saw.) setahu kami tidak ada yang berlainan di zaman mereka itu, bahkan sudah menjadi ijmak.” Rasulullah saw. pun bersabda : "Setiap syarat yang tidak ada di dalam agama Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat." Maksudnya, syarat yang tidak ada dalam hukum Allah dan agama-Nya. Padahal, masalah ini (perjanjian dalam perkawinan) hukumnya boleh sebagaimana telah kami terangkan alasan-alasan yang membolehkannya, dan alasanalasan yang menyalahi pendapat yang mengatakannya boleh. Karena itu, orang yang menolak pendapat tersebut haruslah memberikan dalil-dalilnya. Jika mereka berkata bahwa perjanjian seperti di atas itu berarti mengharamkan yang halal, maka kami jawab : bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta fasakh bilamana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Dan, jika mereka berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka kami jawab : hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuannya, karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi satu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi maslahat di dalam akadnya. Pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bagi orang yang berakal sehat, apabila mengadakan perjanjian, yang perjanjian itu mengandung kebaikan bagi tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia akan mau mundur atau mengkhianatinya. Seperti batas waktu pinjam-meminjam barang, membayar harga barang-barang tertentu yang terjadi di beberapa tempat, menjelaskan keadaan barang-barang yang dijualbelikan, dan keterampilan tertentu yang disyaratkan kepada salah seorang dari suami istri. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau bahkan lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali. 4) Syarat-syarat yang dilarang agama. Ada syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan kepada suaminya agar mentalak madunya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, atau membeli barang yang akan dibeli saudaranya, dan perempuan yang minta madunya ditalak agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian saudaranya, padahal rezekinya itu sudah ada dalam ketetapan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim) Dalam lafazh lain, riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Nabi melarang perempuan mensyaratkan madunya ditalak. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda : "Tidak halal bagi perempuan yang dikawin dengan meminta lainnya agar ditalak." (H.R. Ahmad) Larangan hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang, oleh karena perempuan itu mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya, menggugurkan hak memadu dan hak madunya. Maka, syaratnya tidak sah sebagaimana kalau dia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual belinya. Apa bedanya antara perempuan yang mensyaratkan agar suaminya tidak kawin dengan perempuan lain, dengan mentalak madunya, di mana yang pertama dibolehkan, sedangkan yang kedua dibatalkan? Jawaban Ibnu Qayyim tentang masalah tersebut menyatakan bahwa perbedaan antara kedua hal di atas, karena meminta agar madunya diceraikannya berarti merugikan perempuan lain, menyakitkan hatinya, merusak rumah tangganya, memberikan kesempatan kepada musuh-musuh untuk menghinanya, karena dia ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain. Karena itulah, agama membedakan hukum kedua hal tersebut, dan mengqiaskan yang pertama kepada yang kedua dalam perkara ini hukumnya batal. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah tidak diperbolehkannya melakukan perjanjian sebagai syarat perkawinan yang syarat-syarat tersebut dilarang agama. B. Kerangka Pemikiran Perbandingan hukum atau dalam istilah asingnya disebut comparative law dapat diartikan bahwa titik berat bahasannya adalah pada perbandingannya atau comparative, dalam hal ini kalimat comparative dibandingkan). Istilah memberikan sifat perbandingan kepada hukum hukum dengan (yang demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti sedalamnya dari pengertian istilah perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum (Romli Atmasasmita, 2000 : 7). Dalam berbagai pendapat para tokoh hukum, diskusi mengenai perbandingan hukum ini membentuk polarisasi pengertian. Di satu sisi para tokoh hukum berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode, sedangkan di sisi lain para tokoh hukum yang tidak sependapat menggolongkan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan. Pada intinya, kedua pandangan mengenai perbandingan hukum ini sebenarnya mengerucut pada tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu pembaharuan hukum (Indianto Suhardi, 2005 : 42). Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis antara calon suami istri sebelum atau pada waktu pernikahan dilangsungkan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka maupun masalah lain selain harta benda. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian perkawinan adalah peraturan hukum yang dijadikan pedoman dalam perjanjian perkawinan tersebut, karena perjanjian perkawinan akan menimbulkan konsekuensi hukum (akibat hukum) seperti hak dan kewajiban, baik bagi suami dan istri maupun konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan perbandingan hukum untuk membandingkan UU No. 1 Tahun 1974 dengan sistem hukum Islam dalam melihat bentuk-bentuk hubungan hukum dalam perjanjian perkawinan. Sehingga, dari judul penelitian yang diangkat penulis, yaitu “STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”, kerangka pemikirannya dapat disusun sebagai berikut: Harta Kekayaan Perkawinan · · · Ketentuan harta kekayaan perkawinan Ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan jika ada Hukum Islam Al-Qur’an UU No. 1 Tahun 1974 as-Sunnah Persamaan dan Perbedaan Pembaharuan hukum, Unifikasi hukum, Harmonisasi Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 1. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Masalah harta benda atau harta kekayaan merupakan masalah pokok dalam pekawinan yang dapat menimbulkan pelbagai perselisihan dalam perkawinan, sehingga akan menghilangkan kerukunan hidup berumah tangga. Menginngat pentingnya masalah tersebut, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan masalah harta kekayaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 (K. Wantjik Saleh, 1976 : 35) Adapun ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, harta kekayaan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Rachmadi Usman, 2006 : 369): a. Harta milik bersama (harta bersama), yaitu harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang di antara keduanya. b. Harta milik sendiri, yang terbagi dalam dua jenis, yaitu: 1) Harta bawaan, yaitu harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian di bawa ke dalam perkawinan. 2) Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang intinya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978 : 28). Jika dilihat dalam Penjelasan atas UU No. 1 tahun 1974 juga tidak menjelaskan mengenai masalah ini, sehingga dengan demikian tidak menjadi persoalan siapa yang bekerja menghasilkan harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, apabila harta itu atas hasil kerja suami, istri tetap memiliki hak atas harta tersebut. Begitu sebaliknya, apabila harta itu atas hasil kerja istri, suami juga memiliki hak atas harta tersebut, karena harta bersama tidak mempersoalkan atas hasil kerja siapa. Jika ditinjau dari kenyataan hidup sekarang, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah kurang adil karena dalam pasal tersebut tidak ada kejelasan mengenai “hasil kerja siapa”, apakah harta yang menjadi harta bersama itu hasil kerja suami atau hasil kerja istri. Jika suami yang bekerja dan istri tidak bekerja, kemudian si istri mendapatkan penghidupan yang layak adalah sebuah keharusan karena suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi jika istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, sedangkan harta hasil kerja istri menjadi harta bersama adalah tidak adil karena seharusnya suami yang menjadi pokok dalam mencari penghidupan keluarga. Kenyataan ini semakin terasa ketika sekarang ini banyak istri yang bekerja sementara suami mereka tidak bekerja, atau istri lebih banyak menghasilkan harta daripada suaminya. Jika dilihat dari rasa keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga apabila yang bekerja mencari harta adalah istri, maka Pasal 35 ayat (1) juga tidak adil, apalagi jika nantinya terjadi perceraian, karena harta bersama akan dibagi dua. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita disebutkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dalam hubungan keluarga atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya akan menjamin hak yang sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda baik secara cumacuma maupun dengan penggantian uang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, maka seorang istri mempunyai persamaam dengan suami dalam memiliki (hak milik) suatu harta benda, memperoleh harta benda, mengurus administrasi harta benda, melakukan pengelolaan, dan menikmati harta benda dari hasil kerja atau usahanya. Selain itu, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami untuk memindahtangankan harta bendanya baik dengan cuma-cuma atau dengan penggantian uang. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984 menempatkan istri pada posisi yang adil terhadap hak-hak yang dimiliki suami dalam masalah harta benda dalam perkawinan, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan kejelasan mengenai hal-hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984. Adapun dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dinyatakan bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, harta benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak. Suami maupun istri pun hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. Berarti pula persetujuan kedua belah pihak dari suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak suami atau istrinya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam (Rachmadi Usman, 2006 : 370). Riduan Syahrani, S.H. (1978 : 32) juga berpendapat bahwa syarat persetujuan kedua belah pihak handaknya dipahami sedemikian rupa dengan luwes, di mana tidak dalam segala hal mengenai penggunaan harta bersama itu diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak secara formal atau secara tegas. Dalam beberapa hal tertentu, persetujuan kedua belah pihak harus dianggap ada, sebagai persetujuan yang diamdiam. Contoh dalam hal ini adalah penggunaan harta bersama untuk keperluan hidup sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesan kaku suami istri dalam pergaulan hidup bersama di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, sehingga akan terlihat sangat kaku apabila seorang istri harus selalu minta persetujuan suaminya setiap hari hanya untuk mengunakan uang membeli bumbu masak. Persoalannya adalah dalam hal apa dan apakah penggunaan harta bersama itu diharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak? Sebaliknya juga, dalam hal apa dan penggunaaan harta bersama yang bagaimana yang dianggap telah ada persetujuan kedua belah pihak sebagai persetujuan diam-diam? Persoalan ini hendaknya dilihat secara kasuistis, yakni dengan melihat pada keadaan sosial ekonomi, tata hidup dan kehidupan suami istri, serta kehidupan masyarakat di mana suami istri itu tinggal. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dan melihat Penjelasan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan “cukup jelas”, maka harta bersama dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk keperluan apa saja dan berapa pun jumlahnya asalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) dan penjelasannya tidak menyebutkan untuk hal apa saja dan berapa jumlah harta bersama yang bisa digunakan oleh suami maupun istri. Dengan demikian ada kebebasan bagi suami atau istri untuk menggunakan harta bersama. Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama dengan persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam keadaan seorang beristri lebih dari satu orang (poligami), menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 974, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Masing-masing istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa harta benda milik bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri-sendiri (Rachmadi Usman, 2006 : 370). 2. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dalam hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai hukum harta perkawinan. Menurut Hazairin, di dalam Al-Qur’an tidak mengandung ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan, juga sunnah (hadis) Rasulullah Muhammad. Sunnah Rasulullah hanya menyebut soal syirkah. Oleh karena itu, untuk mengaturnya menjadi hak otonom setiap masyarakat Islam dengan cara (kesepakatan) syura bainahum, yaitu bermusyawarah di antara mereka. (Hazairin dalam Rachmadi Usman, 2006 : 371). Pendapat Hazairin ini juga senada dengan Anwar Harjono yang menulis mengenai harta bersama, yakni harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan, tidak diatur dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang bersangkutan untuk mengaturnya. Selain itu ada lagi H. Abdoeraoef, S.H. yang menuliskan dalam disertasinya dengan menyatakan bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada peraturan-peraturan mengenai harta perkawinan. Pendapat Hazairin dan yang senada dengannya dikritik dan tidak disepakati oleh Prof. Dr. T. Jafizham, S.H. dengan menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak sejalan dengan tafsiran Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, di mana dalam pasal tersebut terdapat ketentuan hukum agama dalam masalah harta benda perkawinan (T. Jafizham, 2006 : 117). Dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceeraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dengan demikian, ada hukum agama Islam yang mengatur masalah harta perkawinan. Prof. Dr. T. Jafizhman, S.H. menyatakan bahwa suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur masalah harta benda perkawinan, karena semua persoalan diatur oleh hukum Islam, ditentukan pula hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal dan tidak dibahas. Tentang tidak diaturnya dalam AlQur’an secara eksplisit, jelas, dan rinci, bukan berarti tidak diatur oleh hukum Islam. benar bahwa Al-Qur’an adalah sumber hukum utama dan pertama, tetapi masih ada sumber hukum Islam yang lain, yaitu hadis Nabi Muhammad dan lainnya. hadis Nabi Muhammad berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan juga bisa berfungsi membuat hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an (T. Jafizhman, 2006 : 118). Walaupun mungkin tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan rinci dalam Al-Qur’an, tetapi ada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditarik darinya dari hadis Nabi Muhammad. Prof. Dr. T. Jafizhman, S.H. mengemukakan bahwa dasar hukum harta benda perkawinan berdasar dari hukum syarikat yang diatur dalam hadis Nabi Muhammad seperti berikut (T. Jafizhman, 2006118): Dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw., Allah ta’ala telah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Maka, apabila salah seorang berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (H.R. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim) Dari Saib al-Mahzumi, bahwasanya ia adalah sekutu Nabi Muhammad saw. sebelum menjadi Rasul. Dia datang pada hari terbukanya kota Makkah. Maka Nabi berkata: “Selamat datang saudaraku dan sekutuku.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) Ada dua pendapat yang berkembang mengenai harta bersama dalam perspektif hukum Islam. Pendapat pertama, menyatakan bahwa dalam percampuran harta kekayaan hukum antara Islam tidak suami istri dikenal karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Begitu pula harta kekayaan milik suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Argumentasi pendapat pertama ini didasarkan pada dua ayat Al-Qur’an, yaitu Q.S. an-Nisa’: 32 yang menyatakan bahwa bagi laki-laki dan wanita masing-masing ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Q.S. al-Baqarah: 228 yang menyatakan bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf (baik). “... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ....” (Q.S. anNisa’: 32) “... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf ....” (Q.S. al-Baqarah: 228) Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai Q.S. al-Baqarah: 228 menyatakan bahwa para istri mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masingmasing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik (Ibnu Katsir, 2004 : 449). Karena istri mendapat perlindungan, baik tentang nafkah lahir, nafkah batin, moral dan material maupun tempat tinggal, biaya pemeliharaan maupun pendidikan anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami. Oleh karena itu, tidak ada harta bersama antara suami istri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, maka itulah yang menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi milik suami, kecuali bila terjadi syirkah (M. Idris Ramulyo dalam Rachmadi usman, 2006 : 371). Dengan demikian, pada dasarnya dalam perspektif hukum Islam, masing-masing suami istri memiliki kewenangan penuh terhadap harta milik pribadinya. Suami tidak berwenang mencampuri harta milik pribadi istri meskipun di antara mereka telah terjadi perkawinan, karena harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan milik penuh istri. Demikian juga jika suami hendak menggunakan harta milik istri, maka ia harus meminta persetujuan dari istrinya. Namun demikian, kebersamaan dapat diwujudkan melalui syirkah. Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami istri itu terpisah. Dengan demikian, masing-masing memiliki hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu pihak lain. Dr. Lutfi, seorang ahli hadis dari Universitas Yordania dan Universitas Kebangsaan Malaysia menyatakan bahwa dalam perkawinan ada dua hak, yaitu hak milik dan hak guna. Dr. Lutfi juga menyatakan dari sudut fikih ditentukan bahwa harta yang dibawa suami adalah milik suami. Begitu pula harta yang dibawa istri adalah harta milik istri, sedangkan harta yang didapat di dalam perkawinan adalah milik dari pihak yang mencari atau mendapatkannya, sehingga dengan demikian harta yang didapat suami adalah milik suami, sementara harta yang didapat istri adalah milik istri. Konsekuensi dari ketentuan tersebut berarti rumah dan barangbarang di dalam rumah tangga itu adalah milik yang membeli atau mendapatkannya. Meskipun demikian, di dalam rumah tangga terdapat pula hak guna yang memungkinkan anggota rumah tangga menggunakan barang-barang di dalam rumah itu bersama-sama, misalnya menggunakan peralatan rumah tangga serta barang lain seperti kursi dan meja. (http://www. sarikata.com, diakses tanggal 7 April 2008). Jika dilihat dari kenyataan sekarang, pendapat yang pertama ini lebih adil, mengingat masing-masing memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri-sendiri. Dengan demikian tidak terjadi suatu ketimpangan dalam hal perolehan harta perkawinan dan hak memilikinya. Jika istri bekerja, maka hasil kerjanya menjadi miliknya. Jika suami bekerja, maka hasil kerjanya menjadi miliknya, di samping ia punya kewajiban menghidupi keluarganya sebagai kepala keluarga. Prof. Dr. Mahmud Yunus menjelaskan pula bahwa maskawin yang diberikan suami kepada istrinya menjadi hak milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Terhadap maskawin ini istri berhak membelanjakannya, menghibahkannya, mensedekahkannya, dan lainnya dengan tiada perlu meminta izin kepada wali atau suaminya. Prof. Dr. Mahmud Yunus juga menjelaskan bahwa harta benda istri lainnya selain maskawin tetap menjadi hak milik istri dan tidak ada hak suami untuk menghalanginya, kecuali jika istri itu safih (pemboros, tidak pandai berbelanja), maka istri boleh dihajar (dilarang) ber-tasarruf (boros) dengan harta bendanya. Pendeknya, kekuasaan istri terhadap harta bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena perkawinan. Tentang ini telah sepakat para ulama. Selain itu, suami tidak boleh suami tidak boleh membelanjakan harta benda istri untuk belanja keperluan rumah tangga kecuali dengan izin istri. Harta benda istri yang digunakan untuk belanja rumah tangga menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya kecuali jika dibebaskan oleh istrinya. Hal ini karena nafkah rumah tangga menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika istri berbelanja lebih dari cukup dengan harta bendanya sendiri dan dengan kemauannya sendiri, maka istri tidak berhak meminta ganti kepada suaminya. Tentang hal ini pun ulama telah sepakat. Harta yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang merupakan hasil kerja mereka masing-masing dan bukan sebagai hasil usaha bersama. Yang termasuk harta ini misalnya adalah menerima warisan, hibah, hadiah, dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh Sajuti Thalib, ditinjau dari segi asal-usulnya, harta kekayaan suami istri dapat dikelompokkan ke dalam: a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah. b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan melalui hadian, hibah, dan wasiat atau warisan. c. Harta yang berasal dari usaha salah seorang suami istri yang diperoleh selama mereka berada dalam hubungan perkawinan. d. Harta yang diperoleh atas usaha bersama selama mereka berada dalam hubungan perkawinan. Selain itu, dalam hukum Islam masih dikenal lagi harta peninggalan dan harta kewarisan. Harta peninggalan adalah harta milik pribadi suami istri yang ditinggalkan, karena yang bersangkutan meninggal dunia atau menyatakan gaib. Adapun harta kewarisan adalah harta peninggalan seorang pewaris yang telah dikurangi dengan biaya-biaya pemakaman, membayar hutang (jika ada), dan melaksanakan wasiat pewaris sendiri yang bersangkutan dengan harta peninggalannya (M. Hidjazi Kartawidjaya dalam Rachmadi Usman, 2006 : 369-370). Adapun menurut Soemiyati, S.H. (Soemiyati, 1986 : 99) harta kekayaan perkawinan jika ditinjau dari asalnya digolongkan menjadi tiga, yaitu: a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya. Harta ini disebut harta bawaan. b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama selam berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing. c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta ini disebut harta pencaharian. Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah status harta pencaharian. Apakah harta pencaharian itu dapat dianggap sebagai harta bersama dari suami istri? Ataukah istri hanya berhak atas harta yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya, misalnya: nafkah, barang-barang perhiasan, atau lainnya yang telah jelas diberikan kepadanya? Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama. Dengan demikian, masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia di mana hasil oemikiran tersebut harus sesuai dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam. Menentukan status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai staus harta tersebut jika di kemudian hari terjadi perceraian, walaupun perceraian sangat tidak diinginkan, atau jika terjadi kematian salah satu pihak suami atau istri. Dalam hal terjadi kematian salah satu pihak, jika status hartanya jelas, maka akan mudah ditentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan dalam hal terjadi perceraian, jika status hartanya jelas, maka dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan harta mana yang menjadi hak suami. Dengan kejelasan status harta tersebut dapat menghindarkan persengketaan ahli waris maupun antara suami istri yang bercerai. Dalam hukum perkawinan Islam, istri memiliki hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu, pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Selain itu, dimungkinkan juga ada pemberianpemberian tertentu dari suami kepada istri, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lainnya yang pada umumnya langsung dipakai oleh pihak istri. Ketentuan yang demikian ini berlaku jika yang berusaha atau bekerja mencari nafkah hanya suami saja, sedangkan istri tidak ikut serta bekerja sama sekali. Namun demikian, jika keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu. Jika usaha keduanya sama-sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang. Jika suami lebih banyak usahanya dibandingkan istrinya, maka hak suami lebih besar daripada hak istri. Demikian pula sebaliknya, jika istri lebih banyak usahanya dibandingkan suaminya, maka hak istri atas harta bersama juga lebih besar daripada hak suaminya. Prof. Dr. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa tambahan harta benda karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi hak milik bersama antara suami istri. Jika istri turut berusaha mencari rezeki bersama suaminya, padahal yang demikian itu bukan kewajiban istri, maka istri berhak mendapat keuntungan dari usaha tersebut menurut besar kecilnya usaha suami istri itu. Apabila suami istri bekerja sama beratnya dan sama banyaknya, maka keuntungannya 50% untuk masingmasing. Tetapi, apabila usaha istri hanya sekedar membantu suaminya, maka ia berhak mendapat untung menurut besar kecil bantuannya itu. Jika besar bantuannya, maka besar pula untungnya, begitu sebaliknya menurut neraca keadilan. Mengenai hal ini tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Dengan demikian, jika perkawinan itu putus karena suatu sebab, maka harta benda tersebut dibagi menurut keseimbangan besar kecilnya usaha suami istri itu (Mahmud Yunus, 1977 : 109). Pendapat kedua, menyatakan bahwa mulai saat akad nikah dilangsungkan, maka demi hukum sejak saat itu telah terjadi percampuran atau persatuan harta kekayaan, sehingga tidak perlu lagi diperjanjikan sebagaimana pendapat yang pertama. Sajuti Thailib dan Hazairin mengakui hal ini bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau suami saja yang bekerja, sedangkan istrinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak. Tidak perlu didiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab kabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri tersebut (Rachmadi Usman, 2006 : 373). B. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 1. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat Bab V Pasal 29 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Adapun bunyi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah: Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan , setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal di atas memiliki banyak kemungkinan mengenai isi perjanjiannya. K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa tidak ditentukan perjanjian itu mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa yang dimaksud “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak” (K. Wantjik Saleh, 1980 : 32). Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 memang memberikan ruang lebih lebar mengenai isi perjanjian. Artinya, isi perjanjian perkawinan yang akan dilakukan oleh calon suami istri sangat luas wilayahnya, bisa menyangkut masalah harta maupun selainnya. Hal ini sependapat juga dengan Prof. H. Hilma Hadikusuma, S.H. yang menyatakan bahwa isi perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 “lebih terbuka” tidak saja yang menyangkut perjanjian kebandaan tetapi juga yang lain. Sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan mengenal apa yang dinamakan “perjanjian perkawinan”. Ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari sari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Banyak yang sependapat dengan pernyataan R. Subekti di atas. Masyarakat umum juga beranggapan bahwa perjanjian perkawinan lebih banyak mengatur masalah harta perkawinan, karena masalah yang paling rawan dan rumit dalam perkawinan sehingga memerlukan perjanjian adalah masalah harta, walaupun masalah yang lain selain harta juga cukup rumit jika ada masalah. Jika kita melihat beberapa pendapat di website hukum mengenai isi perjanjian, kebanyakan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undangundang. Materi yang diatur dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami istri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pada umumnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian (http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 3 Oktober 2007). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pendapat para pakar, pada umumnya mereka menganggap bahwa isi perjanjian perkawinan adalah mengatur harta perkawinan. Bagaimana selanjutnya ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan? Ketentuan harta perkawinan menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan, maka dengan sendirinya terjadi kebersamaan harta yang terbatas (penyatuan harta terbatas) antara suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “terbatas” adalah terbatas pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah atau warisan. Dengan demikian, yang menjadi harta bersama hanya harta yang diperoleh selama perkawinan. Sebaliknya, jika calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan menghendaki kebersamaan harta yang menyeluruh, maka mereka harus mengadakan perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut. Yang demikian itu dapat disimpulkan dari kata-kata pada akhir Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “... sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Adapun yang dimaksud dengan “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” adalah “perjanjian perkawinan” (R. Soetojo Prawiromahidjojo, 1986 : 68). Berdasarkan menghendaki penjelasan di atas, jika calon suami istri kebersamaan harta (penyatuan harta) yang menyeluruh meliputi harta harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri, maka mereka dapat melakukan perjanjian perkawinan yang isinya mengatur hal tersebut. Kebersamaan harta yang menyeluruh ini merupakan “penyimpangan” dari ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang sebenarnya dalam pasal tersebut menentukan kebersamaan harta terbatas. Akan tetapi, karena dalam Pasal 35 ayat (2) memungkinkan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur kebersamaan harta yang menyeluruh, maka perjanjian perkawinan mengatur hal lain yang menyimpang dari ketentuan awal Undang-undang, dan hal ini sah. Selanjutnya, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 UU No. 1 Tahun1974 di atas mengatur harta perkawinan yang tidak ada perjanjian perkawinan di dalamnya, sehingg ketentuan mengenai harta bersama dan harta bawaan suami istri tetap sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Menurut R. Soetojo Prawiromahidjojo (R. Soetojo Prawiromahidjojo, 1986 : 68) dari uraian mengenai Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dibuat yang isinya: a. Kebersamaan harta (penyatuan harta) yang menyeluruh/bulat. b. Peniadaan setiap kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan yang isinya mengenai kebersamaan harta yang menyeluruah atau penyatuan harta bulat dibuat sebagai penyatuan harta bersama dan harta bawaan calon suami istri sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan jika calon suami istri ingin harta mereka benar-benar terpisah, baik terpisahnya harta bersama (tidak ada harta bersama) maupun harta bawaan, maka mereka dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang lain juga. Pendapat R. Soetojo Prawiromahidjojo mengenai perjanjian perkawinan yang isinya peniadaan setiap kebersamaan harta selaras dengan nilai-nilai persamaan antara suami istri dalam perkawinan. Dengan adanya peniadaan kebersamaan harta tersebut berarti masing-masing memiliki hak yang sama berkaitan dengan harta yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan. Suami memiliki hak terhadap harta yang diperolehnya tanpa meninggalkan kewajibannya menafkahi keluarga. Istri pun memiliki hak terhadap harta yang diperolehnya tanpa ada intervensi dari suami. Jika antara calon suami istri mengadakan perjanjian perkawinan yang menentukan “tidak ada kebersamaan harta yang menyeluruh” atau “tidak ada penyatuan harta bulat”, maka masing-masing memiliki dan berhak hanya atas hartanya masing-masing. Walaupun demikian, hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga tetap harus dilaksanakan dengan baik. Artinya, walaupun suami memiliki harta sendiri dan istri memiliki harta sendiri, tapi si suami tetap harus memberikan nafkahnya sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anakanaknya dengan baik. Perjanjian perkawinan yang demikian selaras dengan rasa keadilan dan nilai-nilai persamaan antara suami istri dalam perkawinan, khususnya masalah harta selama perkawinan yang mereka hasilkan masing-masing. Adapun untuk kebersamaan harta terbatas menurut ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tidak perlu dibuat perjanjian perkawinan yang isinya mengatur hal tersebut karena tanpa perjanjian perkawinan pun sudah dengan sendirinya terjadi kebersamaan harta yang terbatas (penyatuan harta terbatas). Kebersamaan harta terbatas di sini adalah terbatas pada kebersamaan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan bukan harta bawaan masing-masing suami istri. Hal penting dalam perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan adalah adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian bisa terlaksana dengan baik dan perkawinan berlangsung dengan tenteram. 2. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Pada dasarnya ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam adalah terpisah antara harta suami dan istri dengan tidak ada harta bersama. Selain ketentuan umum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dimungkinkan juga antara suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau istri atas usaha bersama suami istri atau usaha sendiri-sendiri selama dalam hubungan perkawinan. Perjanjian harta perkawinan yang demikian ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum mengenai harta kekayaan perkawinan. Percampuran harta suami istri inilah yang disebut dengan syirkah. Selain itu, dimungkinkan juga antara suami istri mengadakan syirkah sebagai sebuah bentuk perjanjian perkawinan untuk harta yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing. Mengenai harta suami istri yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing, harta tersebut tetap menjadi milik sendiri-sendiri, namun dapat juga dicampurkan menjadi harta milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu (Soemiyati, 1986 : 99-101). Yang dimaksud oleh Sumiyati sebagai “cara-cara tertentu” di sini adalah syirkah. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd (Ibnu Rusyd, 2002 : 143), syirkah secara bahasa artinya percampuran. Syirkah adalah percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tidak dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum fikih, istilah syirkah itu adalah hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (Ismuha dalam Rachmadi Usman, 2006 : 371). Sebagaimana dikatakan oleh Sajuti Thalib, dalam pemikiran mazhab Syafi’ dan Hanafi, syirkah itu ada tiga jenisnya (Mohammad Daud Ali dalam Rachmadi Usman, 2006 : 372), yaitu: a. Syirkah ‘inan (milik), yakni syirkah terhadap suatu kekayaan tanpa sengaja dibuat perjanjian khusus untuk itu. b. Syirkah mufawadah, yakni syirkah yang sengaja dibentuk dengan memasukkan harta kekayaan tertentu ke dalam syirkah itu. c. Syirkah abdan, yakni syirkah yang sengaja dibentuk dengan pemberian jasa. Melihat pada bentuk-bentuk syirkah di atas, adapun mengenai terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri (harta syirkah) dapat dilakukan sebagai berikut: a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyatanyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha pencaharian. mereka sendiri-sendiri ataupun harta b. Syirkah dapat ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau keduaduanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut. c. Di samping dengan dua cara di atas, percampuran harta kekayaan suami istri (syirkah) dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri tersebut. Cara ketiga ini hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan atas usaha yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memanga telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup dalam hal ini tidak hanya masalah nafkah saja dengan usaha keluar rumah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun mungkin dalam kenyataannya yang bekerja adalah suami, tetapi jika istri tidak dapat melaksanakan urusan rumah tangganya dengan baik, maka usaha suami pun tidak akan maju. Oleh karena itulah, dalam hal pengumpulan harta kekayaan rumah tangga banyak tergantung pada manajemen dan pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri (Sajuti Thalib dalam Soemiyati, 2006 : 101 dan Rachmadi Usman, 2006 : 372). Berdasarkan terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri (harta syirkah) di atas, maka cara pertama, yaitu mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri-sendiri ataupun harta pencaharian dapat dilakukan dengan atau sebagai perjanjian perkawinan. C. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 1. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Perjanjian perkawinan berlaku selama perkawinan berlangsung dan selama para pihak tidak menentukan untuk merubahnya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu jika perkawinan putus, maka perjanjian perkawinan pun putus dengan membawa akibat hukum pada harta yang diperjanjikan. Putusnya perkawinan yang juga secara otomatis memutus perjanjian perkawinan adalah kematian salah satu pihak dan perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat hukum harta kekayaan perkawinan yang ada perjanjian perkawinan mengenai harta tersebut. Jika ada perjanjian kawin mengenai harta perkawinan dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut berfungsi sebagi undangundang bagi pihak suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap harta yang diperjanjikan adalah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan memperjanjikan harta bersama, maka harta tersebut menjadi milik bersama di mana penggunaannya juga harus dengan persetujuan bersama. Jika perjanjian perkawinan memperjanjikan harta terpisah, maka harta tersebut menjadi milik masing-masing dan yang berhak menggunakannya juga masing-masing pihak. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akibat hukumnya juga sebagaimana yang diperjanjikan. Jika perjanjian perkawinan memperjanjikan harta bersama, maka harta tersebut di atur sesuai Undang-undang, yaitu mengikuti ketentuan hukum agamanya masing-masing. Hal ini karena dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kata-kata “hukumnya masing-masing” dalam pasal tersebut adalah hukum yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan dan kemudian mengadakan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, dalam penelitian ini fokusnya adalah hukum Islam, yang berarti dilakukan oleh orang Islam, maka “hukumnya masing-masing” di sini adalah hukum Islam. Walaupun pasal tersebut menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, tapi karena masalah putusnya perkawinan yang berakibat pada perjanjian perkawinan tidak ada pasal yang menyatakannya secara jelas tentang kematian salah satu pihak, maka akibat hukum terhadap harta yang ada perjanjiannya juga kembali pada hukum Islam. 2. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Bila terjadi perceraian, masing-masing suami/istri berhak atas harta masing-masing sesuai konsep harta milik dalam perkawinan. Istri berhak mendapat nafkah iddah dan suami wajib memberikan nafkah itu, dan harta yang didapat selama perkawinan dibagi sesuai konsep kepemilikan harta, dibagi dua jika disyaratkan sebelum akad, atau milik istri jika disyaratkan sebelum akad. Apabila harta perkawinan adalah harta syirkah, kemudian terjadi perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri yang turut berusaha dalam syirkah. Dalam yurisprudensi di Indonesia dapat dilihat keadaan ini pada Keputusan Landraad Serang tertanggal 29 Agustus 1929, yang didasarkan pada pendapat Raad van Justitie Jakarta tanggal 28 Desember 1928, menetapkan bahwa tidak ada milik bersama antara suami istri, meskipun barang-barang diperoleh karena pekerjaan dan kewajiban bersama kecuali jika hal itu dengan jelas disetujui pada waktu perkawinan. Selain itu, dapat juga dilihat dalam Ketetapan/Fatwa Syarikah tentang harta bersama antara suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Februari 1978 Nomor 21/C/1978, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan: “Apabila terjadi syirkah (syirkah harta bersama) pada suatu masa tertentu, maka harta tersebut dibagi dua, karena terjadi perceraian atau meninggal dunia salah satu pihak. Demikian juga dengan Fatwa Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 28 April 1975 Nomor 54/C/1975 (M. Idris Ramulyo dalam Rachmadi Usman, 2006 : 372-373). BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan harta kekayaan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jika ditinjau dengan kenyataan hidup sekarang dinilai tidjelas dan kurang adil, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan harta tersebut apakah hasil kerja suami atau istri. Ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri karena perkawinan. Pendapat pertama ini yang kuat. Pendapat kedua, menyatakan bahwa mulai saat akad nikah dilangsungkan, maka demi hukum sejak saat itu telah terjadi percampuran atau persatuan harta kekayaan, sehingga tidak perlu lagi diperjanjikan sebagaimana pendapat yang pertama. 2. Ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29, yaitu mengatur tentang perjanjian perkawinan. Calon suami istri bisa melakukan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan sebagai penyimpangan dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang, baik mengenai baik kebersamaan harta yang menyeluruh maupun pemisahan harta perkawinan atas harta bersama (tidak ada kebersamaan harta menyeluruh). Dalam hukum Islam antara suami istri dapat mengadakan syirkah sebagai sebuah bentuk perjanjian perkawinan untuk harta yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing. 3. Akibat hukum terhadap harta kakayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat hukum harta kekayaan perkawinan yang ada perjanjian perkawinan mengenai harta tersebut. Jika perjanjian perkawinan memperjanjikan harta bersama, maka harta tersebut di atur sesuai undang-undang, yaitu mengikuti ketentuan hukum hukum Islam. Dalam hukum Islam, jika terjadi perceraian atau talak, harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri yang turut berusaha dalam syirkah. B. Saran 1. Pemerintah segera merevisi UU No. 1 Tahun 1974, khususunya pasal mengenai harta bersama perkawinan ketika terjadi perceraian, di mana pembagian menjadi dua tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan harta tersebut terutama jika istri yang bekerja. Hal ini tidak adil jika dilihat sekarang banyak istri yang bekerja lebih daripada suaminya. Hendaknya undang-undang memberikan hak yang adil dan tidak bias gender. 2. Pemerintah, khususnya lembaga perkawinan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan untuk menjaga hak-hak suami istri secara adil dan berimbang. 3. Pemerintah, khususnya lembaga perkawinan memberikan perhatian kepada kasus-kasus harta perkawinan secara adil agar tercipta keselarasan dalam keluarga di masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni. Abu Bakr Jabir al-Jazairi. 2006. Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim. Jakarta: Darul Falah. Achmad Ichsan, S.H. 1986. Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: SuatuTinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Ade Maman Suherman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo. A. Azhar Basyir. 1990. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Barda Nawawi Arief. 2003. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Burhan Ashshofa. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Djaja S. Meliala. 2006. Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: CV. Nuansa Aulia. Ibnu Katsir. 2004. Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. Ibnu Rusyd. 2002. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Jakarta: Pustaka Amani. Indianto Suhardi. 2005. Studi Perbandingan Hukum Kartu Kredit Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Surakarta : Skripsi. K. Wantjik Saleh. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Khuslan Haludhi dan Abdurrohim Sa’id. 2004. Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam. Surakarta: Tiga Serangkai. Mahmud Yunus. 1977. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). M. Farkhan M., Moh. Muchtarom, dkk. 2006. Pendidikan Agama Islam. Surakarta: UNS Press. Moch. Chidir Ali, dkk. 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Mandar Maju. Mohammad Daud Ali.1999. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Muhammad Kamil Hasan al-Mahami. 2006. Al-Mausû'ah Al-Qur'âniyyah (Ensiklopedi Al-Qur'an). Jakarta: PT Kharisma Ilmu. Rachmadi Usman. 2006. Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. R. Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata. 1999. Jakarta. Sinar Grafika. R. Soetojo Prawiromahidjojo. 1986. Pluralisme dalam Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia. Suarabaya: Airlangga University Press. R. Subekti. 2000. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju. Salim H.S. 2003. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. Soedharyo Soimin. 2002. Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Soedjono Dirdjosisworo. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 2003: PT.Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Subekti. 1970. Pokok-pokok dari Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pembimbing Masa. Subekti. 1976. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka. T. Jafizham. 2006. Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Mestika. http://www.danareksa.com, diakses tanggal 26 September 2007. http://www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 3 Oktober 2007. http://www.hukumonlne.com, diakses tanggal 3 Oktober 2007. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LAMPIRAN Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10 Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11 (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN Pasal l3 Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14 (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 15 Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 16 (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 18 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Pasal 19 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 21 (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. BAB IV BATALNYA PERKAWINAN Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undangundang ini. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 40 (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. BAB IX KEDUDUKAN ANAK Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. la berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. BAB XI PERWALIAN Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 52 Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini. Pasal 53 (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak Pasal 55 (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia Pasal 56 (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal 57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58 Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 59 (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undangundang Perkawinan ini. Pasal 60 (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syaratsyarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masingmasing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61 (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. Pasal 62 Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63 (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya. (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Pasal 65 (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuanketentuan berikut: a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PENJELASAN UMUM: 1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. 2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut : a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper- cayaannya itu dari yang bersangkutan. 4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwaperistiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 2 Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Pasal 3 1. Undang-undang ini menganut asas monogami. 2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 1. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas. 6. Cukup jelas. Pasal 7 1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. 3. Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 1. Cukup jelas. 2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. 3. Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019