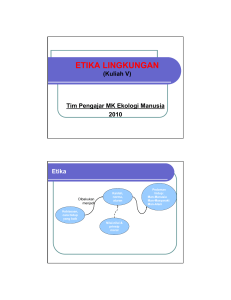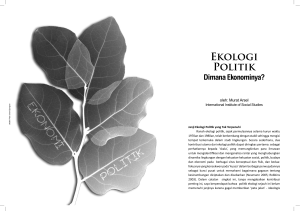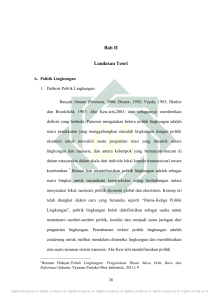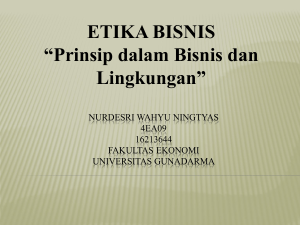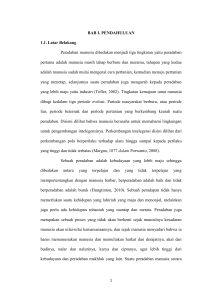agama dan etika lingkungan hidup
advertisement

AGAMA DAN ETIKA LINGKUNGAN HIDUP Subair* Abstraks: Not only deforested induced human greed, polluted rivers and the sea was so intense. religions would be in favor of the interests of the environment. Lately, even among some religious adherents a motivator of violence. In addition, many examples show that religion (Bible verses, religious institution, or religious leaders) can also use even ¬ manipulated to support the interests of the economic interest that is not environmentally friendly. The ability of religion to get in on the bottom layer of society and it has great potential to be able to contribute to the improvement of this nature. So, How can religion play a role? A Hindu scholar, Vasudha Narayanan, name three elements that religion can be a source of problem solving: Text, Temple, Teacher holy books, holy places (places of worship), and teachers (religious leaders). All religions have this component. Scriptural religions is a source of life philosophy and ethics in fav or of the welfare of the universe and its contents, and hence can be a powerful inspiration of nature preservation. Second, community-based religious shrines and religious institutions, are an effective means of social mobilization. Similarly, in the period in which the less-recognized public authority, religious leaders-clerics, monks, priests, and so on-can be central to the formulation of problem-solving efforts as well as the mobilization of community resources. Keywords: Religion, Environmental Ethics, Realism, Environmental Crises Pendahuluan Cukup lama agama dipandang sebagai sumber moral yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Weber, misalnya membuktikan bahwa etika Protestan merupakan landasan kapitalisme dan materialisme yang cenderung materialistik dan hedonistik sangat berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Sementara masalah lingkungan hampir tidak mendapatkan tempat dalam agama selain Protestan,1 termasuk Islam. Sehingga sungguh suatu ironi manusia Indonesia yang dikenal beragama justru dikenal pula sebagai perusak lingkungan kelas wahid. Tidak hanya hutan yang gundul akibat ulah serakah manusia, sungai dan laut pun tercemari sedemikian hebat. Menurut Charles Kimball, meskipun sangat potensial, tetapi agama bisa pula menjadi bencana. Jelas, bukan suatu keniscayaan bahwa agama-agama akan berpihak pada kepentingan lingkungan. Belakangan ini agama justru di kalangan sebagian pemeluknya menjadi motivator tindakan kekerasan. Banyak pula contoh menunjukkan bahwa agama (ayat-ayat kitab suci, lembaga keagamaan, atau pemuka agama) dapat juga di(salah)gunakan bahkan dimanipulasi untuk mendukung kepentingankepentingan ekonomis yang tak ramah lingkungan. 2 Tetapi justru karena semua itulah, bagi kaum beragama, penting untuk membuktikan bahwa agama masih bisa memenuhi misi sucinya menyelamatkan manusia, menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemampuan agama masuk pada lapisan masyarakat yang paling bawah dan kemampuannya mengorganisir diri sampai ke tingkat bawah adalah potensi besar yang dimilikinya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan alam ini. Mengingat agama adalah aspek yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, adalah penting untuk mencoba menelusuri keterkaitan Dosen Sosiologi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Ambon. Kandidat Doctor pada Jurusan antara * Sosiologi Pedesaan SPs Institut Pertanian Bogor. Email; [email protected]. Lihat Max Weber. The Protestan Ethics and the Spirit of Capitalism, London: Hyman.1990, h. 215 lihat Zainal Abidin Bagir, Bagir, Zainal Abidin. “Merawat Bumi, Merevitalisasi Agama”, dalam Buletin Lingkungan Hidup, Yog- 1 2 yakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, Desember 2006, h. 78 32 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 agama dan masalah ekologi yang membutuhkan perhatian besar saat ini. Di samping itu, berangkat dari mengakarnya pengaruh agama dalam seluruh lapisan masyarakat juga membuat agama memiliki peluang besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keterkaitan antara cita-cita ideal religius dengan berpijak pada cita-cita ideal kehidupan alam. Bagaimana agama dapat berperan? Seorang sarjana Hindu, Vasudha Narayanan, menyebutkan tiga unsur agama yang dapat menjadi sumber pemecahan masalah: Text, Temple, Teacher -kitab suci, tempat suci (tempat ibadah), dan guru (pemuka agama).3 Semua agama memiliki komponen ini. Kitab suci agama-agama merupakan sumber filsafat hidup dan etika yang berpihak pada kesejahteraan alam semesta beserta isinya, dan karenanya dapat menjadi inspirasi kuat pemeliharaan alam. Kedua, komunitas agama yang berpusat di tempat suci maupun lembaga-lembaga keagamaan, adalah sarana mobilisasi sosial yang efektif. Demikian pula, di masa di mana makin sedikit otoritas yang diakui masyarakat, pemuka agama -kyai, bhikku, pendeta, dan sebagainya- bisa menjadi pusat perumusan upaya-upaya pemecahan masalah sekaligus mobilisasi sumberdaya masyarakat. Krisis Lingkungan: Lubang Hitam Peradaban Modern Dunia kita hari ini disergap oleh sebuah krisis global dalam arti yang sesungguhnya karena menyangkut hajat hidup seluruh penghuni bumi tanpa kecuali, yang lintas batas negara, etnis, ideologi, budaya, dan agama. Krisis itu adalah krisis lingkungan (environmental crisis), yang dalam pembahasan lebih ilmiah filosofis disebut juga krisis ekologis (ecological crisis). Setiap individu di seluruh pelosok bumi memiliki kepentingan yang sama untuk menghirup udara bersih, air jernih yang tak tercemar, dan lingkungan yang sehat sebagai prasyarat dasar merengkuh kehidupan berkualitas sehingga berkesempatan mengaktualisasikan potensi-potensi kemanusiaannya. Terkait dengan kompleksitas krisis lingkungan itu, semakin banyak sarjana dari pelbagai disiplin ilmu yang mulai menyadari bahwa kritisnya kualitas lingkungan hidup hari ini merupakan kondisi yang tak terelakkan dari peradaban modern yang berporos pada pandangan dunia (worldview) sekulerisme, antroposentrisme, materialisme (ilmiah dan atau budaya), utilitarianisme, dan kapitalisme. Gregory Baum (1972) menulis bahwa kebanyakan kita dikendalikan oleh epistemologi yang salah. Telah jelas sekarang bahwa banyak bahaya katastropik yang telah tumbuh akibat kekeliruan-kekeliruan epistemologi Barat (Occidental errors ofepistemology). Gejala-gejala ini mulai dari penggunaan berlebihan insektisida sampai polusi, malapetaka atomik, dan kemungkinan mencairnya puncak es kutub Antartika. Di atas segalanya, hasrat fantastik kita terhadap individualisme telah menciptakan kemungkinan bahaya kelaparan dunia pada masa mendatang. Baum mengkritik tajam epistemologi Barat modern yang telah mengkondisikan manusia terasing dari alam, dari sesamanya, dan bahkan, dari dirinya sendiri. Ia menuding epistemologi Barat sebagai kekeliruan fundamental (fundamental error) yang berujung pada penderitaan subjek manusia itu sendiri. Berdasarkan pengalamannya yang luas dan intensif dalam bidang kajian biologi, antropologi budaya, psikiatri, dan ekologi, Bateson bermuara kepada kesadaran bahwa carut-marutnya problem dan krisis global dunia modern ini sangat terkait dengan cara pandang, sistem nilai dan gaya hidup yang dianut dan dipraktekkan oleh manusia modern pada umumnya. Berlawanan secara diametral dengan sekulerisme modern yang telah membunuh rasa simpati dan cinta kepada kosmos, Bateson menyatakan kekagumannya terhadap pola-pola, keteraturan, atau tatanan yang terjadi pada pelbagai fenomena alam raya. Begitu pula, kontras dengan paham evolusi Darwin yang mekanistik tanpa tujuan, Bateson menjelaskan bahwa seleksi alamiah tidak dapat menjadi satu-satunya determinan arah perubahan evolusioner dan bahwa asal variasi spesies tidak dapat menjadi suatu persoalan acak. Terdapat regularitas dan “lawfulness” dalam proses evolusioner itu. Bateson mengutarakan rasa syukurnya kepada keyakinan mistik terhadap kesatuan yang meliputi segenap fenomena dunia. Ibid. H. 117. 3 Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 33 Kembali kontradiktif dengan paradigma modernisme yang antroposentristik, Bateson pun memandang bahwa sistem hidup tidak bersifat linier, melainkan merupakan sistem yang kompleks. Menurutnya, prinsip “bigger is better” tidak berlaku pada sistem kehidupan. Konsumsi makanan dan vitamin yang lebih banyak tidak selalu lebih baik dari yang sedikit. Yang banyak bin menjadi racun. Sebaliknya, prinsip “small is beautiful”, yang kerap lebih sesuai dengan sistem biologis dan sosial, menunjukkan bagaimana alam bekerja bahwa “segala yang berlebihan adalah buruk; proporsionalitas adalah baik”. Etika Lingkungan Mengapa terhadap lingkungan diperlukan etika? Apa gunanya? Dan apa relevansinya? Bagaimanapun pertanyaan ini harus dipahami dengan benar. Karena lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Manusia dapat mengarahkan teknologi ke arah mana saja, baik atau buruk, benar atau salah. Di sinilah letak peran etika, yang dapat mengarahkan perilaku manusia, baik atau buruk, benar atau salah. Perhatian terhadap lingkungan hidup semakin besar, dan seringkali diwujudkan dalam organisasiorganisasi masyarakat. Di mana perhatian utama mereka lebih kepada pentingnya etika ekologi baru. Secara teoritis, terdapat tiga model teori etika lingkungan, yaitu yang dikenal sebagai Shallow Environmental Ethics, Intermediate Environmental Ethics, dan Deep Environmental Ethics. Ketiga teori ini juga dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme (Keraf 2002). Etika lingkungan yang bercorak antroposentrisme merupakan sebuah kesalahan cara pandang Barat, yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern, di mana perhatian utamanya menganggap bahwa etika hanya berlaku bagi komunitas manusia. Maksudnya, dalam etika lingkungan, manusialah yang dijadikan satu-satunya pusat pertimbangan, dan yang dianggap relevan dalam pertimbangan moral, yang dilihat dalam istilah Frankena -sebagai satu-satunya moral patient (Frankena 1979). Akibatnya, secara teleologis, diupayakan agar dihasilkan akibat baik sebanyak mungkin bagi spesies manusia dan dihindari akibat buruk sebanyak mungkin bagi spesies itu. Etika antroposentrisme ini dalam pandangan Arne Naess dikategorikan sebagai Shallow Ecology (kepedulian lingkungan yang dangkal). Cara pandang antroposentrisme, kini dikritik secara tajam oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Etika ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan “memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan”4 Ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada biosentrisme, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Salah satu bentuk etika ekosentrisme ini adalah etika lingkungan yang sekarang ini dikenal sebagai Deep Ecology. Sebagai istilah, Deep Ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 4 1999). 34 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 seluruh komunitas ekologis. Etika ini dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Etika ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme. Dengan demikian, Deep Ecology lebih tepat disebut sebagai sebuah gerakan diantara orang-orang yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan samasama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Jika gerakan Ekologi Dangkal hanya mempunyai satu prinsip dan tujuan, maka gerakan Ekologi Dalam memiliki tujuh prinsip. Prinsip gerakan Ekologi Dangkal adalah “menentang polusi dan pengurasan sumber daya” dengan tujuan sentral: kesehatan dan kesejahteraan rakyat di negara-negara tnaju. Sedangkan tujuh prinsip gerakan Ekologi Dalam adalah: (1) Relasi intrinsik antar spesiesspesies dalam jaringan biosfer; (2) Egalitarianisme biosferis; (3) Keanekaragaman dan simbiosis; (4) Sikap anti-kelas; (5) Penentangan terhadap polusi dan pengurasan sumber daya; (6) Kompleksitas, bukan komplikasi; dan (7) Otonomi lokal dan desentralisasi.” Akar gerakan Deep Ecology telah ditemukan pada teori ekosentrisme pada umumnya dan kritik sosial dari Henry David Thoureau, John Muir, DH Lawrence, Robinson Jeffers, dan Aldo Huxley. Pengaruh Taoisme, Fransiskus Asisi, Zen Budhisme, dan Barukh Spinoza juga sangat kuat dalam teori-teori dan gerakan Deep Ecology (Session 1995). Apa yang membedakan antara Ekologi Dalam dengan Eekologi Dangkal? Sedikitnya ada tiga. Pertama, dari segi kerangka dasarnya. Kedua, dari segi model hubungan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Ketiga, dari aspek tujuan jangka panjangnya. Dalam perbedaan yang pertama, Ekologi Dangkal banyak dibentuk oleh pemikiran-pemikiran modern yang positivistik dan antroposentrik, yang berimplikasi pada penguasaan manusia atas alam. Sedangkan Ekologi Dalam, karena basisnya filsafat dan agama, maka kesatuan ekologis menjadi pandangan yang paling utama dengan menempatkan hak asasi manusia dan alam. Manusia diakui hak asasinya atas alam, karena potensi dan kedudukannya sebagai pengelola alam – sebagai khalifah fi al-ardl dalam doktrin spiritualisme Islam. Alam pun diakui hak asasinya, karena berlakunya hukum keseimbangan dalam alam semesta. Pandangan dasar tersebut mempunyai pengaruh terhadap hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jika Ekologi Dangkal lebih memusatkan pada manusia (antroposentrik), sehingga memunculkan hubungan yang sepihak, yang dapat dilihat pada eksploitasi yang sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Maka, dalam Ekologi dalam, model hubungan yang diciptakan adalah keseimbangan. Dalam konteks keseimbangan ini, eksploitasi terhadap alam tetap dilakukan, namun harus berdasar pada prinsip keseimbangan ekologi. Jika Eekologi Dangkal lebih berorientasi pada produksi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, maka Ekologi Dalam lebih diorientasikan pada terpeliharanya moralitas manusia yang tetap menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks kontemporer, etika antroposentris oleh Duarte (2001) disebut sebagai visi “Managing the Planet”, yang berupaya memproteksi alam agar terus berkemampuan mereproduksi masyarakat industrial modern via pembangunan ekonomi. Pandangan ini berkembang menjadi kesadaran moral berlabelkan “Instrumental Globality” yang belakangan berkembang menjadi gerakan “Ecological Modernization”, dimana gerakan ini berkeyakinan bahwa dengan dukungan perangkat institusi, maka masyarakat industrial modern mampu menghadapi krisis ekologi. Dengan memelihara dan mengembangkan lingkungan alam sekitarnya, alam dan lingkungan itu sendiri pun dapat berada dan berkembang an sich. Artinya, alam itu terus ada dan berkembang, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan semesta. Inilah yang mendesak manusia berpikir tentang perlunya sebuah etika baru yang berlandasan kuat dalam kosmos. Etika yang mengharuskan manusia berpikir dengan bertolak dari alam, bukan dari dirinya sendiri, yakni sebuah etika yang disebut etika ekosentris. Menurut Duarte (2001), etika ini pada konteks selanjutnya berkembang menjadi kesadaran Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 35 moral yang dilabel sebagai “Ecocentric Globality” sesuai dengan pandangan filosofis dari Naess tentang Deep-Ecology. Visi gerakan ini adalah “Saving the Planet” yaitu mencoba mempertahankan bumi tanpa kompromi dari aktivitas degradatif yang berlanjut. Dalam diskursus lingkungan selanjutnya, etika antroposentris dan ekosentris saling berlomba untuk menguasai paradigma pengelolaan sumberdaya dan pembangunan masyarakat manusia. Paradigma ini adalah dua paradigma dalam oposisi biner. Dalam peradaban yang sangat berorientasi pada kebutuhan ekonomi saat ini, tampaknya paradigma antroposentris memenangkan perlombaan itu. Ia lebih realistis daripada paradigma ekosentris yang cenderung “kontra peradaban” dengan seruan moralnya “Saving the Planet”. Memang benar bahwa etika ini telah mengesahkan sikap eksploitasi terhadap alam selama ini, yang secara langsung atau tidak melahirkan watak kapitalismematerialisme– tetapi bukan berarti bahwa ia tidak dapat dirombak dan dibalik menjadi sebuah etika lingkungan yang bisa mengayomi dan melayani seluruh makhluk hidup, dengan tidak merombak filsofi dasarnya bahwa manusia adalah tujuan dari segalanya. Meskipun dalam iklim peradaban dunia yang berdasar pada liberalisme/neoliberalisme kapitalistik paradigma ini mungkin dapat dituduh sebagai biang filosofis degradasi ekosistem bumi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya manusialah yang menguasai bumi dan baginya bumi ini diciptakan. Hanya beberapa ‘kesalahan-kesalahan’ yang merupakan bawaan dari kapitalisme memang harus diperbaharui. Managing the Planet harus dilakukan perumusan pola-pola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi selain kepada kesejahteraan umat manusia juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan alam. Hubungan emansipatif, cinta dan saling menghormati di antara manusia pun harus diperpanjang sampai ke alam lingkungan secara keseluruhan. Sehingga, keharmonisan dan kedamaian di alam semesta dapat tercipta di bumi ini. Satu dasawarsa kemudian muncul gerakan Ekologi Sosial (Social Ecology), yang dirintis oleh Murray Bookchin. Penggagas Ekologi Sosial berpandangan bahwa eksploitasi manusia terhadap alam bukanlah produk dari kerangka pikir antroposentris, melainkan manifestasi dari dorongandorongan yang bertanggung jawab terhadap praktek penindasan manusia oleh manusia. Ekologi Sosial memandang penindasan manusia, yang secara luas dipahami sebagai pengekangan kebebasan individu dan perkembangan diri, sebagai sebuah problem struktural dalam sistem sosial yang didasarkan atas relasi kuasa dan dominasi. Oleh karena itu, aktivis Ekologi Sosial berpandangan bahwa kunci membangun relasi yang lestari dengan alam adalah perwujudan desentralisasi lingkungan politik dengan kehadiran komunitas-komunitas semi-otonom yang mengkonstruksi cara-cara hidup yang merefleksikan keragaman nilai-nilai keotentikan manusia dan keragaman konteks bioregional. Pemikiran Ekologi Sosial dibangun atas dasar filsafat dialektika Hegelian, teori evolusi sosial Peter Kropotkin, dan teori sosial Lewis Mumford. Ekologi Sosial menganggap gagasan-gagasan ekosentrisme Ekologi Dalam seperti holistik, interkoneksi, interrelasi, dan interkoneksi sebagai hal-hal yang irasional, antihumanis, dan dogmatis yang hanya bersandarkan pada sentimen, intuisi subjektif serta kepercayaan supranatural dan mistik yang anti-intelektual. Bookchin nampaknya juga tidak berkenan terhadap usulan pergeseran paradigma yang diusung Ekologi Dalam, yang cenderung menuju pemikiran Timur, karena dianggapnya tidak sesuai dengan era kemajuan zaman modern. Oleh karena itu, ia lebih melihat faktor-faktor sosial sebagai penyebab krisis ekologis global seperti ketidakadilan, kapitalisme, atau dominasi kelas sosial. Pada saat yang sama, aliran ekologi ini juga mengenyampingkan Ekologi Dangkal sebagai cara penyelesaian masalah lingkungan. Alih-alih menerapkan apa yang disebutnya sebagai “nalar konvensional” (instrumental, analitik, manipulatif) yang merupakan cara berpikir Ekologi Dangkal, Bookchin menawarkan cara berpikir yang menggunakan “nalar dialektis” dalam sistem pemikiran naturalisme dialektis, dengan mengacu kepada pemikiran dialektika Hegel. 36 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 Meskipun demikian, George Sessions menyebutkan bahwa penolakan Bookchin terhadap ekosentrisme dapat dipahami mengingat ia sebetulnya masih menggunakan cara pandang antroposentrisme dan gagasan tentang “alam kedua” yang dicipta oleh manusia melalui sains dan teknologi. Bookchin pun, kata Sessions, memandang sains ekologi tidak relevan dengan kemanusiaan dan masyarakat. Jadi, penggunaan term ekologi bagi pemikiran Bookchin hendaklah dipandang sebagai bentuk pendekatan apa yang disebut Arne Naess sebagai Ekologi Dangkal. Masih terdapat dua aliran ekologis lainnya, yaitu Ekologi Sosialis (Socialist Ecology) dan Ekofeminisme, yang bisa kita kelompokkan sebagai bentuk lain dari Ekologi Sosial. Jika Ekologi Sosialis menuding sistem kapitalisme yang meniscayakan eksploitasi ekonomis terhadap manusia dan sumber daya alam sebagai penyebab utama krisis lingkungan, maka Ekofeminisme menuding budaya patriarkal Barat yang mengeksplotasi wanita dan alam sebagai akar penyebab kerusakan lingkungan. Ekofeminisme merupakan sintesa dari gerakan femininitas yang tidak memberikan efek peningkatan status perempuan, malah ada kecenderungan perempuan justru mengikuti tindak tanduk lakilaki secara tak sadar. Ini yang disebut fenomena male clon. Watak rasionalisme dan tiadanya kaitan spritualitas antara gerakan feminisme dan ekologi menjadi kritik utama gerakan ekofeminisme terhadap gerakan feminisme yang ada. Asumsi dasarnya adalah bagaimana perempuan dengan kualitas femininnya dapat merubah dunia melalui perannya sebagai ibu, pengasuh, pemelihara dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Istilah ekofeminisme pertama kali digunakan oleh Francoise D’Eaubonne, namun Maria Mies dan Vandhana Shiva (1993) yang berhasil melakukan rekonstruksi pandangan ini. Mereka mengawinkan antara prinsip ekologi dan feminisme dalam melawan ketidakadilan perempuan. Paradigma yang dipakai yang menjadi dasar perjuangan ekofeminisme adalah pandangan dan ideologi yang ramah sesama manusia dan lingkungan. Teori-teori feminisme moderen berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme adalah teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Interdependence, yaitu: When in the course human events, it become necessary to create a new bond among people of the earth, connecting each to the other, undertaking equal responsibilities under the lows of nature, a decent respect for the welfare of humankind and all life on earth requires us to declare our interdependence…that humankind has not woven the web of life; we are but one thread within it. Whatever we do the web, we do to ourselves. (Spring, 1990). Deklarasi ini menegaskan bahwa manusia memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen kehidupan bumi. Ia harus berinteraksi satu dengan lain untuk suatu perubahan yang hakiki yakni peningkatan kesejahteraan ummat manusia. Karena itu, gerakan feminisme yang cenderung ingin memisahkan dirinya dengan prinsip maskulinitas mendapatkan kritikan. Maskulinitas dipandang sebagai entitas yang hidup untuk berinteraksi di atas bumi ini. Dalam paradigma ini, bumi dan alam berada dalam prinsip feminin. Merajalelanya prinsip maskulinitas yang anti-nature, berakibat tidak saja meningkatkan ketidakadilan bagi kaum miskin dan perempuan, namun berakibat juga pada penghancuran alam dan lingkungan. Dalam perjalanannya, maskulinitas berhasil mendominasi dan hegemonik. Sebaliknya, gagasan ekofeminisme berakar pada kepedulian kaum perempuan atas proses penghancuran ekologi yang bersandar pada budaya partiarkhi dan kapitalisme. Dalam peristiwa pengrusakan alam, laki-lakilah yang sebenarnya paling banyak berperan dan kaum perempuan yang paling merasakan dampak negatifnya. Terjadi ketidakadilan ekologi yang dibangun oleh sisitim kapitalistik dengan jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Memahami peristiwa alam dalam bingkai ekofeminisme berarti memperlakukan alam dalam hubungan Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 37 spritualitas, perlu dijaga, dilestarikan, dimuliakan sebagaimana sifat-sifat yang melekat dalam prinsip feminin. Dengan demikian, pengrusakan, penjarahan, dan bentuk eksploitatif lainnya akan direduksi dengan kegiatan-kegiatan ekplorasi yang menguntungkan keberlangsungan kehidupan bumi. Agama dan Lingkungan: Menuju Spiritualitas Agama Sejalan dengan tumbuhnya kesadaran sejumlah sarjana terkemuka akan pentingnya manusia modern untuk kembali ke alam, “berpikir sebagaimana alam berpikir”, para sarjana yang peduli terhadap isu-isu lingkungan juga tiba pada kesadaran bahwa manusia modern perlu kembali merengkuh spiritualitas dan menghormati peran agama dalam kehidupan sosial. Kini makin banyak sarjana pemerhati lingkungan yang menyadari potensi besar agama untuk ikut berperan aktif dalam proyek global yang amat urgen dan penting ini, proyek penyelamatan rumah Bumi kita. Martin Palmer (1998) menulis bahwa selama lebih dari 30 tahun lembaga-lembaga besar dunia, para saintis dan pemerintahan, dan sejumlah besar NGO telah mengkompilasi dan menganalisis secara rinci tentang proses perusakan planet yang tengah kita lakukan Tetapi, krisis lingkungan masih bersama kita. Kenyataannya adalah pengetahuan kita tentang krisis ini belum memadai. Pada dasarnya, krisis lingkungan adalah sebuah krisis pemikiran. Kita adalah apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan dibentuk oleh budaya, keyakinan dan kepercayaan kita. Jika para pemerhati/aktivis lingkungan (environmentalist) memerlukan sebuah kerangka kerja bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan tersebut berdaya guna, maka adakah yang lebih baik dari kembalinya kita kepada upaya kerja sama dengan kelompok-kelompok internasional dan jaringan-jaringan masyarakat yang terbesar di dunia? Mengapa kita tidak menoleh kepada peran agama-agama besar dunia? Selaras dengan kesadaran Martin Palmer di muka, David E. Cooper dan Joy A. Palmer (Spirit of The Environment, 1998) mengkompilasi tulisan belasan sarjana internasional -dari pelbagai bidang seperti filsafat, agama, sains, pendidikan, sastra, antropologi- yang kesemuanya sepakat bahwa wawasan spiritual terhadap alam menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam upaya kita memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan planet Bumi. Sementara itu, di kutub yang kritis, Lynn White. Jr. dalam papernya yang menghebohkan The Historical Roots of Our Ecological Crisis, seraya menuding antroposentrisme Yudeo-Kristiani sebagai akar penyebab krisis lingkungan, menyarankan untuk merengkuh panteisme atau tradisi agama-agama Timur dalam membangun kosmologi yang berwawasan spiritual. Gary Gardner (2002), mendesak para environmentalist (pemerhati dan aktivis lingkungan) untuk menjalin kerja sama dengan kaum agamawan, yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ia berharap agar manusia modern tidak lagi meminggirkan peran agama dalam kehidupan global dan memulai visi dan sikap baru dengan menggandeng kaum agamawan dalam menyelamatkan rumah ekologis kita, Bumi yang tercinta. Lebih dari itu, Gardner memandang bahwa keterlibatan agama merupakan sebuah keharusan ilmiah karena agama memiliki, setidaknya, lima aset yang sangat berguna dalam upaya memelihara bumi dan membangun dunia yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis (a socially just and environmentally sustainable world). Kelima aset penting agama itu adalah: (1) kapasitas membentuk kosmologi (pandangan dunia) yang sejalan dengan visi ekologis; (2) otoritas moral; (3) basis pengikut yang besar; (4) sumberdaya materi yang signifikan; dan (5) kapasitas membangun komunitas. Menurut Gardner, sebuah tantangan besar bagi peradaban kita sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan kembali hati dan akal masyarakat kita, membangun spiritualitas sebagai mitra dialog dengan sains. Untuk menjawab tantangan ini, tradisi agama-agama dunia perlu mengintensifkan keterlibatan merelca dalam isu-isu lingkungan dan pembangunan. Pada sisi yang lain, organisasi-organisasi lingkungan dan pembangunan perlu membuka dirt terhadap dimensi-dimensi 38 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 spiritual program kelestarian alam, sebagaimana Sierra Club telah melakukannya. Terakhir, Gardner juga menyerukan diakhirinya kecurigaan dan kesalahpahaman yang telah berlangsung lama antara dua kelompok tersebut: kaum agamawan dan aktivis lingkungan. Jauh sebelum Gardner, tepatnya 40 tahun lalu, ketika istilah ‘ekologi’ belum sepopuler sekarang, Seyyed Hossein Nasr telah mengingatkan kaum sarjana dan manusia modern umumnya tentang perlunya menghadirkan kembali dimensi spiritualitas ke dalam kehidupan global jika kita memang sungguh-sungguh berkomitmen mencintai rumah Bumi dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan Nasr, krisis ekologis dan pelbagai jenis kerusakan Bumi yang telah berlangsung sejak dua abad lalu berakar pada krisis spiritual dan eksistensial manusia modern pada umumnya. Melalui pelbagai karyanya, khususnya Man and Nature (1976) dan Religion and The Order of Nature (1996), Nasr membedah sebab-sebab utama dan mendasar munculnya krisis lingkungan pada peradaban modern seraya menekankan pentingnya perumusan kembali hubungan Manusia, Alam, dan Tuhan yang harmonis berdasarkan wawasan spiritualitas dan kearifan perenial. Nasr secara tajam dan bernas mengkritik pemikiran dan sains modern yang disebutnya telah kehilangan sama sekali visi spiritual dalam mernandang kosmos raya. Menurut Nasr, pandangan dunia sains modern yang berkarakter kuantitatif, sekular, materialistik, dan profan benar-benar telah mengikis makna-makna simbolik dan pesan-pesan spiritual yang terkandung dalam alam raya. Menurut Nasr, dalam pandangan modernisme, kosmos telah mati dan ia hanyalah kumpulan onggokan benda mati, materi yang tidak bernyawa, tak berperasaan, tak bernilai apa-apa, kecuali semata-mata nilai kegunaan ekonomis. Alam telah diperlakukan seperti layaknya ‘pelacur’, yang dieksploitasi tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya. Krisis lingkungan bisa dikatakan disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat Tuhan sebagai “Lingkungan” yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modem untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologis berdiri sendiri, terpisah dari Lingkungan Ilahiah yang tanpa berkah pembebasanNya lingkungan menjadi sekarat dan mati. Oleh karena itu, bagi Nasr, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan apa yang ia sebut resakralisasi alam semesta (resacralizadon of nature) sebagai pengganti proyek mekanisasi gambaran dunia (mechanization of the world picture) yang dicanangkan sejak Renaisans dan Revolusi Ilmiah tiga abad lalu. Untuk itu, usul Nasr, kita perlu membangun kosmologi baru yang berbasis kepada tradisi spiritualitas agama yang sarat makna dan kaya kearifan. Agama pun, pada gilirannya, bisa menjadi sumber visi, inspirasi dan motivasi bagi pemerhati lingkungan untuk mengkonstruksi etika lingkungan sebagaimana juga program-program konservasi alam. Dalam pandangan Nasr, membangun etika lingkungan tanpa wawasan spiritual terhadap kosmos adalah tidak mungkin sekaligus tidak berdayaguna. Dalam konteks diskursus ekologi, kebangkitan spiritualisme ini membawa implikasi pada pergeseran paradigma ekologi, yaitu suatu pandangan yang mencari dasar-dasar pijakan spiritual untuk mengangkat ekologi lebih dari sekadar ilmu dan beroperasi lebih dari sekedar dalam konteks politik. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Ekologi Dalam (deep ecology) sebagai lawan dari paradigma Ekologi Dangkal (shallow ecology). Ekologi Dalam ini mempunyai pijakan pada filsafat dan agama. Dari sinilah kemudian paradigma spiritual ecology dibangun. Spiritual ecology pada dasarnya ingin memberikan wacana baru, bahwa krisis ekologis lebih banyak berhubungan dengan manusia dalam memandang realitas alam ini. Jika kita tidak ingin tertimpa bencana alam untuk kali kesekian, maka saatnya bagi kita untuk membangun sekaligus membumikan spiritualitas ekologi di negeri ini. Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 39 Islam dan Krisis Lingkungan: Respons Realisme Islam Bagaimana Islam memandang krisis lingkungan ini? Apakah ia sejalan dengan pemikiran Ekologi Dangkal atau Ekologi Dalam ataukah Ekologi Sosial? Apakah pemikiran Islam lebih sesuai dengan Ekologi Dalam yang menekankan perubahan cara pandang, nilai budaya dan sikap hidup dalam menyelamatkan Bumi ataukah dengan Ekologi Sosial yang memfokuskan kepada perubahan struktur sosial? Ataukah Islam memiliki karakternya sendiri yang membedakannya dari aliranaliran ekologis itu? Jika demikian halnya, lalu bagaimana kita menjelaskan dan memposisikannya? Mengacu kepada pemikiran Allamah Tabataba’i (guru Seyyed Hossein Nasr) dan Murtadha Muthahhari (murid Tabataba’i), Islam merupakan sebuah pandangan dunia yang realis, dalam pengertian bahwa kebenaran adalah sesuatu yang riil (nyata) dan yang nyata adalah tolok ukur kebenaran; bahwa segala yang ada mengambil peran dan memiliki posisi dalam lautan realitas yang tunggal. Realisme Islam mengakui semua jenis keberadaan pada keragaman tingkat-tingkat eksistensi, yang mencakup alam fisik, alam mineral, alam biologis, alam psikologis, alam imajinatif, alam intelektual, dan alam spiritual; mengafirmasi keberadaan manusia dan pengada-pengada non-manusia; mengakui kebermaknaan intrinsik semua maujud di alam raya dengan memosisikan manusia—yang sesuai dengan potensinya sebagai khalifah Tuhan yang merupakan sebuah amanat, tanggung jawab kosmos. Realisme Islam memandang alam raya dengan penuh simpati, cinta, dan tanggung jawab karena alam adalah sumber belajar dan kearifan, sarat makna simbolik, dan kaya pesan spiritual. Kecuali sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) kehadiran Tuhan dan manifestasi nama-nama Indah Tuhan (Asma ul-Husna), kosmos dalam pandangan realisme Islam juga merupakan alam primordial bagi kemunculan manusia, sang makhluk cerdas. Realisme Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk pilihan Tuhan yang kompleks, potensial, multidimensi (makhluk fisik sekaligus ruhani; makhluk kultur sekaligus makhluk struktur; makhluk moral sekaligus makhluk pencari legalitas), dan dinamis (manusia tidak seragam). Menurut Muthahhari, manusia bukanlah makhluk yang ditakdirkan sebelumnya (predestined). Manusia bukanlah makhluk yang ditakdirkan atau ditentukan, melainkan makhluk yang menentukan dan mentakdirkan apa yang dikehendaki dirinya sendiri. Manusia itu sendirilah yang menentukan untuk “menjadi apa” dan “menjadi bagaimana”. Meskipun demikian, pada saat yang sama realisme Islam juga meyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut Muthahhari, bermasyarakat merupakan sesuatu yang fitrah dan bersemayam pada jati diri manusia. Oleh karena itu, bermasyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara berada manusia itu sendiri. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes yang menganggap manusia terpaksa bermasyarakat guna melayani naluri self-preservation semata-mata; juga berbeda dengan sosialisme Karl Marx yang memandang kemasyarakatan manusia sebagai takdir-deterministik yang menentukan manusia berdasarkan kelas semata-mata; berbeda pula dengan individualisme Emile Durkheim atau Max Weber yang memandang bahwa eksistensi kemasyarakatan manusia hanya sebagai pilihan rasio-instrumental guna keuntungan bersama (masyarakat dianggap kumpulan individu-individu yang tercerai berai satu sama lain; yang eksis, hanyalah individu manusia, sedang masyarakatnya hanyalah bentukan epifenomenal). Dalam masalah pengetahuan, realisme Islam berpijak pada cara-pandang realis-eksistensial yang sangat kaya dan dinamis dengan makna-makna keilmuan serta mengakui pengalaman empiris, imajinasi, akal, dan intuisi sebagai sumber dan sarana pengetahuan. Makna ’mengetahui’ sesuatu dalam epistemologi Islam bukan saja memiliki dan menguasai objek tertentu dalam pikiran, namun juga berarti ‘mengada’. Bagi filsuf seperti Mulla Shadra, Murtadha Muthahhari, Hairi Yazdi, tindakan mengetahui itu merupakan sebuah proses mengada, modus eksistensi (al-‘ilmu nahwun minal wujud). Epistemologi Islam juga menyelesaikan problem dualisme dalam struktur pengetahuan (subjek-objek) yang tak pernah terpecahkan dalam epistemologi Barat, menjembatani rasionalisme dan empirisme, 40 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 dan mengintegrasikan kecakapan nalar diskursif dan intelek intuitif, sesuatu yang selalu dianggap berseberangan dalam sistem epistemologi Barat atau bahkan filsafat Timur. Implikasi ilmiah dan sosial dari epistemologi Islam seperti itu adalah tumbuhnya etos keilmuan yang tinggi dalam semua jenis ilmu pengetahuan secara seimbang dan proporsional, mulai matematika, logika, sains, sejarah, sastra, filsafat hingga tasawuf. Menurut Thabathaba’i, AlQur’an mendorong manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu kealaman, matematika, filsafat, sastra, dan semua ilmu pengetahuan yang dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Al-Qur’an menyeru kita untuk mempelajari ilmu-ilmu ini sebagai jalan untuk mengetahui Al-Haq dan Realitas, dan sebagai cermin untuk mengetahui alam, di samping juga adanya manfaat praktis dari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut C.A. Qadir, terdapat 750 ayat -sekitar seperdelapan isi Kitab Suci Al-Qur’an- yang mendorong kaum beriman untuk menelaah alam, merenungkan, dan menyelidikinya. Berbeda dengan tiga aliran utama ekologi kontemporer yang cenderung berat sebelah, timpang, dan terfokus pada satu dimensi, Ekologi Islam bisa merangkul segenap dimensi yang ditekankan oleh masing-masing olch Ekologi Dangkal, Ekologi Dalam, dan Ekologi Sosial. Pemikiran Ekologi Islam sesuai dengan spiritualitas kosmos yang ditawarkan Ekologi Dalam, tapi pada saat yang sama juga apresiatif terhadap aktivitas sains dan riset ilmiah yang ditekankan oleh Ekologi Dangkal. Begitu pula, Ekologi Islam mendukung kuat argumen Ekologi Dalam bahwa kita harus mengubah cara pandang dan sikap hidup manusia untuk melestarikan lingkungan, tetapi pada saat yang sama Ekologi Islam juga menaruh perhatian pada isu-isu sosial dan struktur masyarakat -yang disuarakan oleh Ekologi Sosial-dalam menangani krisis dan isu lingkungan. Sebaliknya, ketika Ekologi Islam sangat menaruh perhatian terhadap aktivitas riset ilmiah dan penegakan keadilan sosial, pada saat yang sama juga berkemampuan menawarkan dimensi spiritualitas terhadap isu-isu lingkungan. Itulah karakteristik pertama Ekologi Islam, yaitu berkemampuan menawarkan dan mengakomodasi dimensi-dimensi lingkungan secara terpadu tanpa saling meniadakan seperti yang terjadi pada mazhab-mazhab ekologi lainnya. Karakter ini muncul karena watak Ekologi Islam yang mengacu kepada proposisi realisme, yaitu “mengafirmasi segala yang nyata”, yaitu mengapresiasi semua hal yang memiliki dampak dan pengaruh terhadap peristiwa alam dan sosial, baik secara kultural maupun struktural, langsung atau tak langsung, individual atau sosial, profan atau sakral, teknikal maupun spiritual. Inilah asas pertama realisme Islam, yaitu asas integrasi. Lalu, asas kedua realisme Islam, yang menjadi pondasi Ekologi Islam yang tengah kita bicarakan, adalah asas proporsionalitas. Dengan asas proporsionalitas yang berbunyi “segala sesuatu diletakkan pada tempatnya yang sesuai dengan tingkat eksistensinya”, maka Ekologi Islam bisa memberi jalan tengah antara kaum konservatisme pendukung lingkungan alamiah dengan kaum pembela kemajuan peradaban manusia. Di satu sisi, Ekologi Islam mendukung program pelestarian biodiversity (keragaman spesies) yang tidak menghambat keselamatan umat manusia, dan di lain sisi Ekologi Islam memiliki sistem moral dan ekonomi yang mencegah eksploitasi alam atas nama kemajuan peradaban manusia. Bagaimanapun juga, Ekologi Islam memandang bahwa manusia adalah tujuan evolusi kosmos sehingga menempati hirarki keberadaan yang lebih tinggi dari spesies-spesies lainnya. Namun, ini sama sekali bukanlah antroposentrisme model Ekologi Dangkal, karena diletakkan dalam horison pandangan spiritualitas kosmos dan konsep khalifah Tuhan yang harus bertanggung jawab (memiliki dimensi spiritual dan moral). Ekologi Islam berpotensi memasukkan pandangan spiritualitas kosmos pada kurikulum studistudi keislam dan studi lingkungan secara filosofis dan sufistik seraya secara simultan juga berkemampuan membangun kesadaran ilmiah dan wawasan saintifik melalui lembaga-lembaga pengajaran yang didukung oleh institusi-institusi sosial politik, termasuk finansial (Baitul Maal). Realisme Islam, sebagaimana yang terbukti dalam sejarah emasnya, bisa melahirkan saintis yang Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 41 peka spiritualitas (seperti Pangeran Dokter Ibn Sina yang filsuf-sufistik), dan mencetak sufi yang cinta riset keilmuan (seperti sufi Jabir Ibn Hayyan yang mendirikan laboratorium kimia pertama dalam sejarah). Pada dimensi lain, Ekologi Islam juga sangat apresiatif terhadap program riset ilmiah, pengembangan sains dan teknologi serta aktivitas-aktivitas keilmuan lainnya, yang juga sangat berguna dalam membantu program pemeliharaan ling-kungan yang sehat. Dengan demikian, Ekologi Islam menawarkan jalan tengah antara spiritualitas kosmos dengan sosialitas kosmos; mengintegrasikan pandangan saintifik dengan visi kearifan lokal. Demikian pula halnya, Ekologi Islam bisa mengintegraskan dimensi sosial ekonomi dan politik—yang diusung oleh Ekologi Sosial- dengan dimensi moral—seperti yang diusung oleh Ekologi Dalam, tanpa harus meremehkan salah satu dimensi tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Ekologi Sosial dan Ekologi Dalam. Bagi Ekologi Islam, sesuai dengan pandangannya tentang manusia sebagai makhuk multidimensi, pelbagai metode dan pendekatan mesti ditempuh untuk program-program konservasi lingkungan dan penyelamatan Bumi sejauh metode-metode dan pendekatan-pendekatan itu bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan secara etis dan sosial. Ekologi Dalam berpandangan bahwa hubungan yang harmonis antarspesies (interspesies) di muka bumi adalah kunci penyelesaian krisis lingkungan. Sedang-kan Ekologi Sosial menganggap bahwa membangun hubungan yang setara dan serasi antar manusia (intraspesies) sebagai faktor utama keberhasilan proyek penyelamatan Bumi. Nah, dalam perspektif ini, Ekologi Islam bisa mengakomodasi kedua sudut pandang itu dengan menempatkan mereka sebagai modus-modus relasi eksistensial yang terinterkoneksi secara gradual. Maksudnya, Ekologi Islam memandang bahwa problem interspesies (relasi manusia dan makhluk non-manusia) dan problem intraspesies (relasi antar manusia) merupakan dua keadaan yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan implikasi dari pandangan dunia yang tidak utuh. Perbedaan seperti itu terkait dengan cara pandang dalam melihat problem dan krisis ekologis yang tengah kita hadapi. Bagi Ekologi Dangkal, krisis ekologis lebih dilihat sebagai problem teknis; Ekologi Dalam lebih melihatnya sebagai problem visi dan nilai; Ekologi Sosial memandangnya sebagai bagian dari problem sosial; dan Ekologi Islam memandang krisis ekologis sebagai bagian dari problem eksistensial manusia (berdimensi teknisetis-sosial-spiritual). Pada gilirannya, perbedaan cara pandang memahami krisis ekologis ini terkait dengan aliran filsafat dan pandangan dunia yang dianut oleh masing-masing mazhab; Ekologi Dangkal memeluk antroposentrisme, Ekologi Dalam menganut ekosentrisme, Ekologi Sosial menganut naturalisme dialektis, dan Ekologi Islam menganut realisme. 42 Tasamuh, Volume 4 Nomor 1, Juni 2012 : 31-43 DAFTAR PUSTAKA Bagir, Zainal Abidin, 2006. “Merawat Bumi, Merevitalisasi Agama”, dalam Buletin Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, Desember 2006. Baum, Gregory, 1999. Agama dalam Bayang – Bayang Relativisme, Tiara Wacana, Yogyakarta. Bryant, R.L. and Bailey, S. 1997. Third World Political Ecology. London: Routledge. Bryant, Raymond L., 1998. “Power, Knowledge and Political Ecology in the Third World: A Review”, Progress in Physical Geography Vol 22 (1), 1998. Capra, Fritjof, 1999. Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Chiras, Daniel D. 1991. Environmental Science: Action for a Suitainable future. New York: The Benyamin Cummings Publishing Company, Inc. Dharmawan, Arya Hadi, 2007. Otoritas Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Menatap Otonomi Desa dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan dan Ekologi Politik, Makalah disampaikan pada “Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030” diselenggarakan oleh PKSPL, PSP3IPB dan P4W LPPM IPB, dilaksanakan di Kampus Manajemen Bisnis IPB Gunung Gede, Bogor 9-10 Mei 2007. Duarte, Fernanda de Paiva, 2001. ‘Save the Earth’ or ‘Manage the Earth’? The Politics of Environmental Globality in High Modernity, Current Sociology, January 2001, Vol. 49(1), SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi. Dwivedi, Ranjit, 2001. Enviromental Movements in the Global South, Issues of Livelihood and Beyond dalam International Sociology Vol 16 (1), 2001. Escobar, A. 1998. “Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movement”, Journal of Political Ecology, Vol. 5, 1998. Foltz Richard C. 2007. “Krisis Lingkungan di Dunia Muslim” dalam Mangunjaya, Fachruddin M. (et.al.). Menanam sebelum Kiamat. Jakarta: YOI. Forsyth, T. 1996. Science, Myth, and Knowledge: Testing Himalayan environmental Degradation in Thailand dalam Geoforum 27, 1996. Fukuyama, F. 2004. State-Building:Governance and World Order in the 21st Century. Ithaca. New York: Cornell university Press. Heriyanto, Husain. 2007. “Respons Realisme Islam Terhadap Krisis Lingkungan” dalam Mangunjaya, Fachruddin M. (et. al.). Menanam sebelum Kiamat. Jakarta: YOI. Koten, Thomas Sumber, “Dari Etika Egosentris, Homosentris, ke Ekosentris” diunduh dari http:// wap.korantempo.com tanggal 22 Oktober 2008. Mangunjaya, Fachruddin M. (et.al.). 2007. Menanam sebelum Kiamat. Jakarta: YOI. Nainggolan, R. 2007. Teladan dari Toro: Harmonis bersama Alam. http://www.kompas.com. Nygren, A. 1999. Local Knowledge in the Environment-Development Discourse. Critique of Anthropology, Vol. 19/3, 1999. Shiva,Vandana, dkk. 1993. Keragaman Hayati: PerspektifSosial dan Ekologi, Jakarta: Konphalindo. Subair, Agama dan Etika Lingkungan Hidup 43 Soemarwoto, Otto. 1985. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Susilo, Y. Eko Budi, 2003. Memahami Sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan, Jakarta: Averroes Press. Weber, Max. 1990. The Protestan Ethics and the Spirit of Capitalism, London: Hyman.