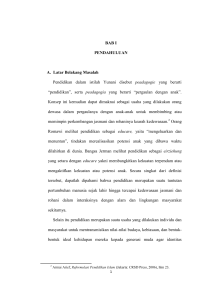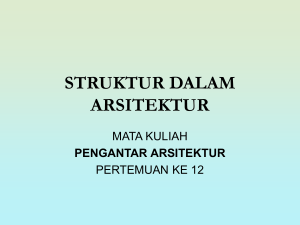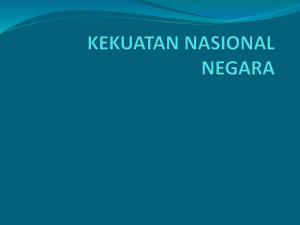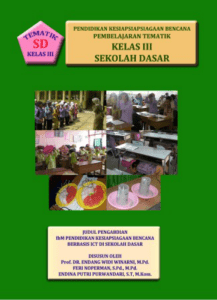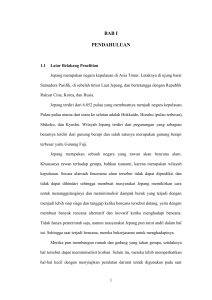pelaksanaan latihan menghadapi bencana sebagai struktur dalam
advertisement

PELAKSANAAN LATIHAN MENGHADAPI BENCANA SEBAGAI STRUKTUR DALAM PEMBENTUKAN HABITUS DAN PRAKTIK KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT JEPANG TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI Firman Budianto Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia E-mail: [email protected] Abstrak Skripsi ini menganalisis hubungan antara pelaksanaan latihan menghadapi bencana dengan pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori integrasi struktur dan agen yang dikemukakan Bourdieu mengenai konsep habitus dan praktik. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang dilihat sebagai struktur dalam pembentukan habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Dengan demikian, kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi merupakan habitus dan praktik yang mengintegrasikan struktur dan agen dalam pelaksanaan manajemen bencana di Jepang. Kata Kunci : Bourdieu; habitus; kesiapsiagaan; latihan menghadapi bencana; manajemen bencana; praktik; struktur Implementation of Disaster Drills and Exercises as Structure in the Making of Japanese Disaster Preparedness Habitus and Practice Abstract The focus of this work is to analize the relationship between implementation of disaster drills and exercises and the making of Japanese disaster preparedness. This work was compiled using Bourdieu’s theory of habitus and practice. This work was a qualitative research. This work found that implementation of disaster drills and exercises is seen as structure in the making of Japanese disaster preparedness habitus and practice. Therefore, Japanese disaster preparedness is habitus and practice that integrate agent and structure in the implementation of disaster management in Japan. Keywords : Bourdieu; disaster drills and exercises; disaster management; habitus; practice; preparedness; structure. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 1. Pendahuluan Dalam menyelenggarakan kehidupan di dunia, manusia tidak pernah terlepas dari resiko terdampak bencana. Setidaknya terdapat 500 kejadian bencana yang menimbulkan lebih dari satu juta korban jiwa1 dengan total kerugian lebih dari USD 40 milyar setiap tahunnya (IFRC, 2012). Menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007, bencana2 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi bencana tersebut mengelompokkan bencana ke dalam “bencana alam” dan “bencana nonalam”. Di antara kedua jenis bencana tersebut, bencana yang manusia tidak bisa melakukan kontrol dan tidak memiliki kuasa terhadapnya adalah bencana alam. Di antara berbagai jenis bencana alam, ada bencana yang memiliki sifat ‘tidak dapat diprediksikan kedatangannya’, misalnya kejadian gempa bumi, yang sering kali diikuti oleh kejadian tsunami3. Salah satu gempa bumi terbesar yang pernah terjadi di dunia adalah Gempa Bumi Besar Jepang Timur atau 東日本大震災 (Higashi Nihon Daishinsai) yang terjadi pada 11 Maret 2011. Gempa ini merupakan gempa bumi tektonik yang terjadi di Samudra Pasifik, tepatnya di sebelah timur laut Jepang dengan kekuatan gempa M9,0. Gempa ini tercatat sebagai gempa bumi terbesar kedua di dunia dari segi magnitude-nya dan juga merupakan gempa bumi terbesar yang melanda Jepang sejak masa pengukuran dan pencatatan gempa bumi modern dimulai tahun 1900. Bencana ini bahkan dinyatakan sebagai megadisasters, yaitu bencana terburuk yang pernah terjadi di dunia (World Bank, 2012), dan melibatkan tiga bencana dalam sekali waktu : gempa bumi dengan skala M9,0; gelombang tsunami yang mencapai ketinggian sepuluh meter; serta krisis reaktor nuklir Fukushima. Bencana Gempa Bumi Besar Jepang Timur ini melanda daerah Tohoku, khususnya Prefektur Iwate, Miyagi, dan Fukushima, serta mengakibatkan jatuhnya korban meninggal sebanyak 15.861 jiwa (MLIT, 2012 dalam Statistic Bureau of Japan, 2013). 1 Data berdasarkan rerata jumlah bencana yang terjadi sepanjang tahun 2001-2011 beserta jumlah rerata korban jiwanya. 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 3 Tsunami (津波) adalah istilah yang telah diterima secara internasional untuk mengacu pada gelombang raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 Tabel 1. Gempa Bumi Terbesar dari Segi Jumlah Korban Jiwa Tanggal Lokasi 28 Juli 1976 16 Des 1920 26 Des 2004 12 Jan 2010 1 Sep 1923 12 Mei 2008 9 Okt 2005 28 Des 1908 Hebei, China Ningxia, China Aceh, Indonesia Port-au-Prince, Haiti Kanto, Jepang Sichuan, China Kashmir, Pakistan Messina, Italia 11 Mar 2011 Tohoku, Jepang Nama Gempa Gempa Bumi Tangshan Gempa Bumi Haiyuan Gempa Bumi Sumatra Gempa Bumi Haiti Gempa Bumi Besar Kanto Gempa Bumi Sichuan Gempa Bumi Kashmir Gempa Bumi Messina Gempa Bumi Besar Jepang Timur Korban Jiwa Kekuatan (M) 242.800 235.502 227.898 222.500 105.000 87.587 86.000 82.000 7,8 8,5 9,1 7,3 7,9 8,1 7,7 7,1 15.861 9,0 Sumber : Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism of Japan (2012) dalam Statistic Bureau of Japan (2013), (telah diolah kembali). Pada saat terjadi bencana Gempa Bumi Besar Jepang Timur, dilaporkan bahwa seluruh siswa-siswi SD dan SMP yang saat itu berada di sekolah masing-masing, berhasil menyelamatkan diri mereka, dan bahkan siswa SMP Kamaishi Timur turut membantu siswasiswi sekolah dasar di sekitarnya untuk mengevakuasi diri ke tempat yang aman (Nishikawa, 2011: 42). Dari total 2.924 orang siswa SD dan SMP di Kota Kamaishi, hanya lima orang yang menjadi korban, dan dari kelima orang tersebut, empat orang di antaranya adalah mereka yang tidak masuk sekolah atau mereka yang meninggalkan sekolah lebih dulu, dan satu orang lainnya diketahui hilang tersapu tsunami setelah pulang berkumpul bersama keluarganya (The Asahi Shinbun, 2011). Informasi baik ini kemudian tersebar ke seluruh Jepang dan disebut sebagai “The Miracle of Kamaishi” (Nishikawa, 2011: 42, dan The Asahi Shinbun, 2011). Para siswa tersebut menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut bisa mereka ambil berkat pengetahuan yang mereka peroleh dari pendidikan kebencanaan melalui latihan menghadapi bencana yang mereka ikuti di sekolahnya (Nishikawa, 2011: 42). Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara pelaksanaan latihan menghadapi bencana dengan pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Penulis merumuskan proposisi penelitian sebagai berikut, “terdapat hubungan antara pelaksanaan latihan menghadapi bencana dengan pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi”. Variabel yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel (bivariat), yaitu : (1) pelaksanaan Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 latihan menghadapi bencana di Jepang, dan (2) kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi, dengan analisis hubungan korelasi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah masyarakat Jepang dengan scope negara Jepang. 2. Tinjauan Teoritis Penulis menggunakan teori integrasi struktur dan agen yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1977, 1990) dengan menggunakan pendekatannya mengenai konsep praktik dan habitus sebagai landasan teoritis penelitian ini. Praktik, dalam pemikiran Bourdieu, dilihat sebagai hasil dari integrasi struktur mental dengan struktur sosial, dalam konteks hubungan antara struktur dan agen. Bourdieu (1990: 14) menjelaskan konsep integrasi struktur dan agen sebagai berikut : “The analysis of objective structure -those of different fields- is inseparable from the analysis of genesis, within biological individuals, of the mental structures which are to some extent the product of incorporation of social structures; inseparable, too, from the analysis of the genesis of these social structure themselves: the social space, and the groups of occupy it, are the product of historical struggles (in which agents participate in accordance with their position in the social space and with the mental structures through which they apprehend this space).” Bourdieu (1990: 14) Melalui definisi tersebut, Bourdieu berupaya mengintegrasikan dimensi dualitas struktur dan agen. Di sini, Bourdieu menekankan pemikirannya mengenai hubungan antara struktur sosial objektif dengan struktur mental individual, yang dalam konteks hubungan struktur dan agen akan menghasilkan praktik. Struktur mental tersebut lahir dari produk internalisasi struktur dunia sosial ke dalam diri agen, yang akhirnya akan membentuk suatu system of dispositions yang akan menentukan bagaimana praktik diproduksi dan distrukturasi (Bourdieu, 1970: 72), atau yang dalam konteks pemikiran Bourdieu disebut sebagai habitus. Praktik, dalam pandangan Bourdieu berperan dalam mengintegrasikan struktur dan agen dengan medium habitus. Habitus juga berfungsi sebagai basis generatif dari kesatuan objektif praktik sosial yang terstruktur, di samping juga merupakan hasil dari praktik yang diciptakan oleh kehidupan sosial (Ritzer dan Goodman, 2011). Hubungan antara struktur sosial, habitus, dan praktik dapat dijelaskan sebagai berikut, “struktur sosial akan memproduksi habitus, yang pada gilirannya akan menghasilkan praktik, yang akhirnya juga akan memproduksi kembali (reproduce) struktur sosial (Rapport, 2000: 2).” Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 Berangkat dari pandangan Bourdieu mengenai habitus (1977; 1990), Kleden (2005) mencoba merangkum tujuh dimensi mengenai habitus [(Kleden, 2005: 361-375; dan Binawan, 2007: 28-29) dalam Adib (2012: 97)]. Pertama, habitus sebagai produk sejarah berarti habitus merupakan seperangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulangulang. Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan produk historis sehingga sesuai dengan pola dan skema yang ditimbulkan oleh sejarah (1990: 54), sehingga pada akhirnya habitus akan menciptakan tindakan individu dan kolektif [Bourdieu (1990: 91) dan Wacquant (2005)]. Kedua, habitus lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu ia menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial dimana dia diproduksi. Bourdieu (1977: 72) menyebut habitus sebagai “struktur yang distruktur (structured structure)”, yaitu bahwa habitus merupakan struktur yang distruktur oleh dunia sosial. Ketiga, habitus mempunyai dispositions yang terstruktur, yang berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan membentuk persepsi, representasi, serta tindakan agen. Bourdieu (1977: 72) menyebut habitus sebagai “struktur yang menstruktur (structuring structure)”, yaitu bahwa habitus merupakan struktur yang menstruktur dunia sosial. Keempat, habitus bersifat transposable, yakni bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain Bourdieu (1970: 72), walaupun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Kelima, habitus bersifat pre-conscious atau berada di luar pertimbangan rasional sehingga habitus bukan merupakan hasil dari refleksi rasio semata. Habitus lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tidak pula dikehendaki dengan sengaja, tetapi di lain sisi, habitus juga bukan merupakan suatu gerakan mekanistis yang terjadi tanpa latar belakang sejarah sama sekali (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Keenam, habitus bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Habitus bukan hanya merupakan a state of mind, tetapi juga a state of body dan bahkan menjadi the site of incorporated history (Adib, 2012). 3. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengumpulkan data- data primer, serta studi dokumen untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder. Metode pertama adalah metode wawancara mendalam (in-depth interview). Metode ini dipilih karena metode ini lebih cocok digunakan untuk menggali informasi mengenai perasaan, pendapat, pemikiran, serta pemilihan tindakan agen dalam konteks analisis habitus dan juga mengenai Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 analisis kesiapsiagaan agen terhadap bencana gempa bumi. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan terhadap empat orang Jepang yang ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan daerah tempat tinggal di Jepang. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak mengutamakan generalisasi tetapi lebih kepada analisis makna, maka metode wawancara juga lebih cocok untuk menggali makna tersebut. Metode kedua adalah metode studi dokumen yang digunakan untuk memeroleh data primer lain maupun data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dari laporan resmi pemerintah Jepang (hakusho), buku, jurnal ilmiah, surat kabar, maupun situs-situs internet milik Pemerintah Jepang. Alasan dipilihnya metode studi dokumen adalah karena metode inilah yang paling memungkinkan bagi penulis untuk mengumpulkan data-data yang terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Metode studi dokumen, menurut Bailey (1994: 294-295), memungkinkan peneliti untuk meneliti fenomena dimana peneliti tidak memiliki akses kepadanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data yang ada, sehingga penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi temuan penelitian. Penelitian dilakukan secara sistematis dan faktual, serta menganalisis relevansi antara data tersebut dengan kerangka teori yang digunakan, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data dan kerangka permasalahan penelitian di awal. 4. Hasil dan Pembahasan Analisis integrasi struktur dan agen dalam konteks pelaksanaan manajemen bencana di Jepang yang terwujud dalam habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi dapat dimulai dengan analisis karakteristik struktur, habitus, dan praktik yang terdapat di dalam kesiapsiagaan tersebut. Secara teoritis, praktik berperan dalam mengintegrasikan struktur dan agen dengan medium habitus, namun di sisi lain, sebagai stuktur mental, habitus hanya diwujudkan di dunia sosial melalui praktik tersebut. Untuk memahami konsep tersebut, penulis paparkan data mengenai kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks respons terhadap bencana gempa bumi. I : Misalnya, jika saat ini terjadi gempa bumi, apa yang seharusnya dilakukan? Mmm, bangunan ini delapan lantai ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di lantai delapan? Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 R: I : R: I : R: Misalnya orang yang ada di lantai delapan ya... Selama gedung berguncang karena gempa bumi, karena bahaya tertimpa perabotan atau pecahan kaca, lindungi diri dengan bersembunyi di bawah meja. Itu yang pertama? Ya, hal pertama yang harus dilakukan dibandingkan segera mengevakuasi diri adalah bersembunyi di bawah meja untuk melindungi diri agar tidak terluka, itu yang pertama. Setelah itu, setelah guncangan gempa berhenti, evakuasi diri. Pada saat mengevakuasi diri, jangan menggunakan elevator, gunakan tangga atau tangga darurat untuk pergi ke luar. Tindakan-tindakan tersebut, apakah juga dipelajari saat latihan menghadapi bencana? Ya, dipelajari. Itulah (tindakan-tindakan) yang pertama kali dipelajari. [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 26 Nov 2013] “Karena (kami) sudah mengikuti latihan menghadapi bencana sejak kecil, maka lahirlah pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan secara alami, sesuai saat mengikuti latihan yang berulang kali, sehingga ketika bencana itu terjadi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan tersebut, kami sudah terbiasa (mi ni tsuiteiru),…, kami akan dapat bertindak secara alami.” [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 26 Nov 2013] Data tersebut menunjukkan kesiapsiagaan Ibu Takai dalam konteks respons terhadap kejadian gempa bumi, serta keikutsertaan dia dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut lahir sebagai hasil keikutsertaan dia dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana, sehingga dalam konteks ini, kesiapsiagaan tersebut dilihat sebagai habitus agen yang distruktur melalui pelaksanaan latihan menghadapi bencana. Dalam pandangan Bourdieu (1977: 72), habitus merupakan struktur yang distruktur oleh dunia sosial (structured structure). Habitus menurut Bourdieu dilihat dalam diri agen sebagai individual. Dengan demikian, dalam penelitian ini pelaksanaan latihan menghadapi bencana dilihat sebagai struktur yang menstruktur habitus kesiapsiagaan dalam diri agen yang kemudian terwujud dalam praktik kesiapsiagaan dalam konteks respons terhadap bencana gempa bumi. Untuk lebih memahami pelaksanaan latihan menghadapi bencana sebagai struktur dalam pembentukan habitus kesiapsiagaan, berikut ini penulis paparkan beberapa data terkait pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang. Dalam konteks habitus sebagai product of history, habitus merupakan seperangkat struktur mental yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang-ulang (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Dengan demikian, habitus kesiapsiagaan tersebut distruktur melalui pelaksanaan latihan menghadapi bencana yang dilakukan berulang-ulang dalam konteks Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 perjalanan historis agen sehingga habitus tersebut merupakan product of history. Berikut ini penulis paparkan data mengenai frekuensi keikutsertaan agen dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang dan konten yang mereka lakukan saat mengikuti latihan. “Pada dasarnya di Jepang, ada latihan menghadapi bencana, di SD, SMP, dan SMA. Setahun dua kali, di bulan April dan September.” [Wawancara dengan Sdr. Kuno (22), 09 Nov 2013] “Ya, baik di sekolah maupun di perkantoran juga melakukan pelatihan. [Wawancara dengan Bp. Yokoyama (49), 12 Nov 2013] “Latihan dimulai sejak SD, SMP, SMA, ..., perguruan tinggi, mm.. saya tidak belajar di perguruan tinggi, jadi saya tidak tahu, kemudian di perusahaan juga ada, jadi di Jepang semua orang pernah mengalaminya (latihan).” [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 26 Nov 2013] Di Jepang, pelaksanaan manajemen bencana secara nasional diselenggarakan berdasarkan Disaster Countermeasures Basic Act 1961. UU ini mewajibkan pelaksanaan latihan menghadapi bencana secara nasional sebagai implementasi dari perencanaan pencegahan bencana (DCBA, 1961: Art.46, Para.2). Pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang diatur dalam lima pasal dalam Disaster Countermeasures Basic Act 1961. Sesuai dengan yang tertulis dalam Disaster Countermeasures Basic Act 1961, pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang diselenggarakan secara nasional, baik di tingkat prefektur maupun di tingkat lokal. Terhitung sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1961 hingga saat ini (tahun 2013), latihan telah diadakan di Jepang selama 52 tahun. Latihan diadakan selama dua kali di lingkungan pendidikan dasar-menengah, dan setahun sekali di lingkungan pekerjaan. Dengan begitu, Penulis berasumsi bahwa seluruh masyarakat Jepang yang berusia di bawah 58 tahun saat penelitian ini dilakukan, seluruhnya mempunyai pengalaman ikut serta dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana. Setidaknya mereka telah mengikuti latihan selama 12 tahun atau sebanyak 24 kali latihan (setahun dua kali) selama mereka duduk di bangku SD-SMA. “Seingat saya, di sekolah kami tidak melakukan latihan seperti bagaimana cara menggunakan alat pemadam api. Tetapi kontennya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, adalah berlatih mengevakuasi diri dengan cepat, dengan mengikikuti jalur evakuasi yan telah ditentukan sebelumnya.” [Wawancara dengan Sdr. Kuno (22), 09 Nov 2013] Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 I : R: Itu berarti di dalam latihan menghadapi bencana, tidak hanya latihan mengevakuasi diri saja, ya? Ya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengevakuasi diri pun ada, seperti misalnya sebelum mengevakuasi diri “harus bersembunyi di bawah meja selama guncangan gempa terjadi”, atau juga “memutus aliran gas”. Pengetahuan yang seperti itu, telah (kami) dengar sejak masa kecil. [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 12 Nov 2013] Dilihat dari jenis latihan yang dilakukan, sebagian besar aktivitas latihan yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah latihan evakuasi, maksudnya adalah latihan bagaimana mengevakuasi diri keluar dari gedung sekolah atau universitas dengan cepat saat terjadi bencana, dengan melewati jalur evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, diajarkan pula halhal yang harus dilakukan saat terjadinya bencana. Misalnya latihan bersembunyi di bawah meja saat gempa bumi terjadi. Selanjutnya, para siswa, guru, bahkan juru masak sekolah, akan melakukan simulasi evakuasi diri ketika terjadi gempa bumi. Setelah mereka semua keluar dari gedung, mereka akan berkumpul di tempat lapang dan diberikan pengarahan dan pengetahuan kebencanaan oleh guru atau penanggungjawab pendidikan kebencanaan di sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan agen dalam latihan menghadapi bencana dapat dilihat sebagai perjalanan historis agen yang berperan dalam proses pembentukan habitus. Selanjutnya, masih dalam pandangan Bourdieu dalam konteks habitus sebagai product of history, habitus tersebut nantinya akan mengarahkan tindakan-tindakan agen (1990: 91), dan tindakan tersebut sesuai dengan skema yang dihasilkan oleh sejarah (1990: 54). Karakteristik ini yang Bourdieu (1977: 72) sebut bahwa habitus merupakan structuring structure. Pada dasarnya habitus mengandung dispositions yang terstruktur, yang berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan membentuk persepsi, representasi, serta tindakan agen (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012. Bourdieu (1977: 72) menyebut habitus sebagai “struktur yang menstruktur (structuring structure)”, yaitu struktur yang menstruktur dunia sosial. Habitus kesiapsiagaan yang lahir dari keikutsertaan masyarakat Jepang dalam latihan menghadapi bencana akan mempengaruhi dan mengarahkan praktik kesiapsiagaan mereka dalam konteks respons terhadap bencana gempa bumi. Kemampuan habitus untuk menstruktur tindakan agen ini yang menyebabkan habitus disebut sebagai struktur yang menstruktur. Inilah kekuatan teori Bourdieu mengenai integrasi struktur dan agen yang terletak pada konsep habitus (Aldridge, Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 1998 dalam Ritzer dan Goodman, 2003: 522) yang Bourdieu sebut sebagai structuring structure. Sebagai structuring structure, habitus mampu mengarahkan agen dalam pemilihan tindakan mereka dalam konteks praktik kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. Berikut ini penulis paparkan data pertama mengenai praktik kesiapsiagaan agen dalam konteks persiapan yang dilakukan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi menurut Sdr. Kuno. I : R: Mengapa orang-orang melakukannya? Dengan menyiapkan tas darurat yang di dalamnya memuat bahan makanan untuk bertahan beberapa hari, hal itu membuat kita setidaknya sedikit merasa tenang. Saya pikir itu juga alasan utama orang-orang melakukannya. [Wawancara dengan Sdr. Kuno (22,) 12 Nov 2013] Data di atas menunjukkan bahwa praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang dengan menyediakan tas darurat lebih didasari pada kesadaran pribadi akan resiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga praktik tersebut juga dilihat sebagai habitus. Dalam proses perwujudan habitus dalam dunia sosial, terutama dalam karakteristiknya sebagai structuring structure yang mampu mengarahkan agen dalam pemilihan tindakan mereka dalam konteks praktik kesiapsiagaan, habitus mempunyai beberapa karakteristik. Secara teoritis, habitus bersifat teratur dan berpola, namun bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Habitus bukan hanya merupakan a state of mind, tetapi juga a state of body dan bahkan menjadi the site of incorporated history (Adib, 2012). Pada proses pembentukannya, habitus tersebut dilihat sebagai produk internalisasi struktur dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana ke dalam diri agen yang akan menentukan bagaimana tindakan mereka diproduksi. Dalam konteks perwujudan habitus dalam praktik kesiapsiagaan dalam konteks persiapan menghadapi bencana gempa bumi, misalnya praktik penyediaan tas darurat. Praktik tersebut tidak lagi sepenuhnya diproduksi sebagai bentuk ketertundukan masyarakat Jepang terhadap peraturan tertentu, namun diproduksi sebagai perwujudan habitus kesiapsiagaan yang ada dalam diri mereka masingmasing. Inilah sifat habitus yang disebut Kleden (2005, dalam Adib, 2012) dapat mengarahkan praktik agen namun bukan sebagai ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu. Praktik kesiapsiagaan kedua dalam konteks persiapan adalah keikutsertaan masyarakat Jepang dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana secara sukarela. Berikut ini penulis Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 paparkan data mengenai keikutsertaan masyarakat Jepang dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat menurut Ibu Takai. “Namun, latihan yang diadakan oleh lingkungan, bukan merupakan kewajiban. Orang yang berminat, silakan ikut serta, bukan merupakan sebuah kewajiban.” [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 26 Nov 2013] Data di atas menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat Jepang dalam pelaksanaan latihan di lingkungan masyarakat tidak lagi sepenuhnya merupakan ketertundukan mereka terhadap peraturan tertentu, melainkan merupakan praktik yang diproduksi oleh habitus dalam diri mereka. Habitus kesiapsiagaan yang mereka peroleh sebagai produk internalisasi struktur dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana, kemudian terwujud dalam keikutsertaan mereka secara sukarela dalam pelaksanaan latihan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh data kecenderungan peningkatan perkembangan jishubou di Jepang yang menunjukkan peningkatan, yang pada tahun 1988 hanya sebesar 31,7% menjadi 61,3% pada tahun 2003 (Bajek, et., al., 2007). Selain menstruktur praktik kesiapsiagaan agen dalam konteks persiapan, habitus juga menstruktur praktik dalam konteks respons. Berikut ini Penulis paparkan data mengenai praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks respons ketika bencana gempa bumi terjadi. R: Ketika terjadi gempa yang guncangannya besar, pertama-tama lindungi keselamatan badan, seperti misalnya bersembunyi di kolong meja... agar badan tidak terluka oleh karena kejatuhan perabotan seperti televisi, lemari es, atau kipas angin, selama guncangan gempa agar bersembunyi di kolong meja. Setelah guncangan gempa berhenti, kemudian mematikan aliran gas, lalu menyelamatkan hewan peliharaan, misalnya anjing atau kucing, kemudian keluar rumah. [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 09 Nov 2013] I: R: Apa perbedaan tindakan yang Anda ambil ketika terjadi gempa bumi besar dan gempa bumi kecil? Ketika gempa bumi kecil, tidak ada hal yang dikhawatirkan secara khusus. Misalnya, walaupun ketika terjadi gempa bumi pintu rumah jadi tidak bisa dibuka, tidak ada kekhawatiran saluran gas terkoyak. Di Jepang saluran gas berasal dari bawah tanah, bukan dengan tabung gas seperti di Indonesia, ketika gempa bumi besar, ada ketakutan pipa saluran gas tersebut akan pecah/terkoyak, gasnya bocor, kemudian listrik memercikkan api, dan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, sebelum gas tersebut sampai di rumah, ada pengetahuan untuk segera memutus aliran gas tersebut saat gempa besar. [Wawancara dengan Ibu Takai (41), 29 Nov 2013] Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 R: Mm, untuk mengevakuasi diri. … Pertama-tama, bersembunyi di tempat yang aman dan agar tidak keluar sampai guncangan mereda. Lalu, ketika guncangan sudah berhenti dan situasinya sudah tampak kembali normal, berkemas, memasukkan hanya barang-barang penting yang bisa dijinjing ke dalam tas, kemudian pergi ke luar. [Wawancara dengan Bp. Yokoyama (49), 12 Nov 2013] I: R: Ketika terjadi gempa bumi besar, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? Selain yang tadi itu, (kita) perlu juga untuk memastikan hal-hal seperti apakah daerah sekitar kita dalam keadaan berbahaya, atau apakah kondisi tempat kita aman. Terutama, wilayah-wilayah yang berada di dekat pantai atau sungai, karena kemungkinan datangnya tsunami cukup besar, saya pikir harus segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau pergi menjauh dari bibir pantai. Selain itu, jika memungkinkan, untuk mengecek keselamatan keluarga dan kenalan yang juga berada di daerah terdampak bencana. [Wawancara dengan Bp. Yokoyama (41), 11 Nov 2013] Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Jepang pada umumnya akan merespons dengan cara yang sama ketika bencana gempa bumi terjadi, yaitu segera bersembunyi di tempat yang aman dari resiko tertimpa perabotan atau pecahan kaca sambil menunggu guncangan gempa bumi selesai, lalu segera mengevakuasi diri ke luar bangunan. Namun, dalam konteks habitus kesiapsiagaan dalam diri agen yang, sesuai pandangan Bourdieu, dilihat sebagai individual, habitus tersebut dapat terwujud dalam praktik yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Dari data di atas, diketahui bahwa ada beberapa praktik yang berbeda antara Ibu Takai dengan Bp. Yokoyama. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun habitus merupakan struktur mental yang menstruktur tindakan agen, habitus tersebut dapat terwujud dalam praktik yang berbeda untuk tiap-tiap agen. Seperti yang telah dipaparkan pada analisis pada paragraf sebelumnya, dalam proses perwujudan habitus dalam praktik di dunia sosial terutama dalam konteks respons, habitus memiliki dua karakteristik, yaitu pre-concious dan transposable. Karakteristik pertama, yaitu habitus bersifat pre-conscious (Bourdieu, 1977) atau berada di luar pertimbangan rasional. Habitus bukan merupakan hasil dari refleksi rasio semata, habitus lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tidak pula dikehendaki dengan sengaja, tetapi di lain sisi, habitus juga bukan merupakan suatu gerakan mekanistis yang terjadi tanpa latar belakang sejarah sama sekali (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Dalam konteks habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang yang terwujud dalam praktik sebagai respons terhadap gempa bumi, habitus tersebut terwujud dalam praktik agen untuk bersikap tenang, kemudian segera bersembunyi di bawah meja untuk melindungi dirinya dari tertimpa perabotan atau pecahan kaca Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 sambil menunggu guncangan gempa bumi selesai. Masyarakat Jepang telah memahami bahaya yang ditimbulkan jika mereka panik ketika terjadi gempa bumi, sehingga mereka segera bertindak untuk mengamankan diri mereka terlebih dahulu. Setelah guncangan gempa berhenti, baru mereka mengevakuasi diri ke luar bangunan. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, masyarakat Jepang berada dalam posisi antara sadar dan tidak sadar. Oleh karena itu, habitus kesiapsiagaan dalam konteks praktik sebagai respons tersebut bersifat pre-concious atau prasadar. Namun, sekali lagi Penulis menekankan bahwa habitus tersebut bukan sebagai gerakan mekanistis saja, namun juga dipengaruhi oleh analisis bagaimana habitus tersebut distruktur dalam konteksnya sebagai product of history masyarakat Jepang, yang dalam konteks penelitian ini, sejak masa kecil telah mengikuti latihan menghadapi bencana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Karakteristik kedua, yaitu habitus bersifat transposable, yakni bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain walaupun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu (Kleden, 2005 dalam Adib, 2012). Habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang lahir sebagai struktur mental sebagai produk dari keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang. Sebagai struktur mental, habitus terinternalisasi ke dalam pikiran agen dan dapat dialihkan ke kondisi sosial yang lain. Seperti yang ditunjukkan pada data sebelumnya, dalam konteks saat terjadinya bencana gempa bumi, masyarakat Jepang akan meresponsnya dengan cara yang sama jika terjadi gempa bumi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa habitus kesiapsiagaan dalam konteks respons terhadap bencana gempa bumi tersebut tetap terwujud walaupun mereka berada dalam kondisi sosial yang lain. Keberadaan mereka di tempat yang berbeda kondisi sosialnya dengan Jepang tidak serta merta menyebabkan habitus dalam diri mereka tidak dapat terwujud. Data berikutnya yang menunjukkan karakteristik habitus yang bersifat transposable adalah data mengenai habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks persiapan terhadap bencana gempa bumi. “Sekarang di Indonesia pun, saya menyiapkan senter dan semacamnya.” [Wawancara dengan Kusano (22), 27-Nov-2013] “Karena ketika (kita) sedang tidur, kemudian terjadi gempa bumi, ada kemungkinan besar almarinya jatuh, menimpa kita, dan kemudian tewas, maka dari itu di sekeliling tempat tidur saya saat ini, saya tidak menempatkan barang-barang yang besar.” [Wawancara dengan Bp. Yokoyama (49), 27 Nov 2013] Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 Data di atas menunjukkan bahwa habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks persiapan tetap terwujud meskipun mereka sedang berada di Indonesia. Habitus kesiapsiagaan dalam konteks persiapan dan respons terhadap bencana gempa bumi tersebut juga dapat diwujudkan di tempat yang kondisi sosialnya berbeda dengan di Jepang atau bersifat transposable. Dengan demikian, dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Bourdieu mengenai habitus dan praktik, pelaksanaan latihan menghadapi bencana dilihat sebagai struktur dalam pembentukan habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Sedangkan agen atau keagenan dalam penelitian ini, sesuai dengan pandangan Bourdieu mengenai habitus, dilihat sebagai individual yang pendapat serta pemikirannya berperan dalam pemilihan tindakan mereka di dunia nyata. Sebagai struktur, pelaksanaan latihan menghadapi bencana menstruktur habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang, yang kemudian terwujud dalam dunia sosial sebagai praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks persiapan dan respons terhadap bencana gempa bumi. Karakteristik dan sifat habitus kesiapsiagaan dalam proses pembentukannya hingga proses perwujudannya dalam dunia sosial sebagai praktik kesiapsiagaan, antara lain : (1) habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang merupakan produk hasil keikutsertaan masyarakat Jepang dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana yang dilakukan berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang (product of history); (2) habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang merupakan struktur mental yang distruktur atau dibentuk oleh latihan menghadapi bencana sebagai struktur yang menstruktur habitus tersebut (structured structure); (3) habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang memengaruhi dan mengarahkan tindakan mereka, baik individu maupun kolektif, dalam praktik kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi (structuring structure) dalam konteks persiapan dan respons terhadap bencana gempa bumi, termasuk mengarahkan tindakan mereka untuk ikut serta dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana; (4) habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang yang terwujud dalam dunia sosial sebagai praktik kesiapsiagaan bukan sepenuhnya merupakan hasil refleksi rasio. Habitus tersebut lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari namun tidak pula dikehendaki dengan sengaja, sehingga bisa dimengerti bahwa agen berada dalam Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 posisi antara sadar dan tidak sadar ketika mewujudkan habitus tersebut dalam dunia sosial (pre-conscious) sebagai praktik kesiapsiagaan; (5) habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang dapat dialihkan ke kondisi sosial yang lain. Habitus tersebut juga dapat diwujudkan (transposable) sebagai praktik kesiapsiagaan di Indonesia, tempat yang kondisi sosialnya berbeda dengan Jepang, tempat dimana habitus kesiapsiagaan tersebut distruktur pertama kalinya; Karakteristik dan sifat habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang di atas menunjukkan bahwa habitus kesiapsiagaan dan praktik kesiapsiagaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang yang distruktur melalui pelaksanaan latihan menghadapi bencana hanya terwujud dalam dunia sosial melalui praktik kesiapsiagaan, di sisi lain, praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang tersebut distruktur oleh habitus kesiapsiagaan dalam diri mereka. Pelaksanaan latihan menghadapi bencana yang dalam penelitian ini dilihat sebagai struktur dalam pembentukan habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi, dapat juga dilihat sebagai struktur dalam pembentukan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan latihan menghadapi bencana dalam penelitian ini dilihat sebagai struktur dalam pembentukan habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi, dan si sisi lain, kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi tersebut dilihat sebagai habitus dan praktik yang mengintegrasikan struktur dan agen dalam pelaksanaan manajemen bencana di Jepang. 5. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa kesiapsiagaan masyarakat Jepang dalam konteks persiapan dan respons terhadap bencana gempa bumi, telah menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging dan mengakar sedemikian rupa sebagai akibat dari keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan latihan menghadapi bencana di Jepang yang dilakukan secara periodik, berulangulang, dan berkelanjutan sejak masa kecil mereka. Dilihat dari pandangan Bourdieu mengenai habitus dan praktik, hal ini dapat dilihat sebagai integrasi struktur dan agen dalam konteks pelaksanaan manajemen bencana di Jepang yang terwujud dalam habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 Temuan penelitian ini berimplikasi terhadap teori Bourdieu, bahwa hubungan antara struktur, habitus, dan praktik adalah benar dapat diamati dalam kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi dalam konteks pelaksanaan manajemen bencana di Jepang. Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung keabsahan teori Bourdieu mengenai habitus dan praktik. 6. Studi Selanjutnya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi temuan penelitian, melainkan lebih kepada kedalaman analisis setiap data penelitian. Dalam penelitian ini, pelaksanaan latihan menghadapi bencana dilihat sebagai struktur dalam pembentukan habitus dan praktik kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi. Namun, Penulis tidak mengklaim bahwa pelaksanaan latihan menghadapi bencana merupakan satu-satunya faktor dalam pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana, khususnya bencana gempa bumi. Pelaksanaan latihan menghadapi bencana ini bisa jadi merupakan satu dari sekian banyak faktor dalam pembentukan kesiapsiagaan tersebut. Penulis berharap adanya penelitian lanjutan yang menganalisis pembentukan kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana gempa bumi dari perspektif teoritis lain. Selain itu, dari sisi metodologis, Penulis menyarankan agar pengumpulan data juga dilakukan melalui metode observasi langsung untuk melihat gejala-gejala yang tidak bisa dijangkau melalui wawancara mendalam atau studi kepustakaan. Daftar Referensi Act No. 223 Disaster Countermeasures Basic Act. 15 November 1961. Japan. Adib, Mohammad. 2012. “Struktur dan Agen dalam Pandangan Pierre Bourdieu”. Jurnal BioKultur Vol.I, No.2 : 91-110. Bailey, Kenneth D. 1994. Methods of Social Research, Fourth Edition. New York : The Free Press. Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of Theory of Practice. Cambridge : Cambridge University Press. ---------------. 1990. The Logic of Practice. Cambridge : Polity Press. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 Cabinet Office, Japan. 2011. Nihon no Saigai Taisaku. Tokyo : Director General for Disaster Management. (Dokumen diunduh pada 18 Agustus 2013 pada pukul 15.47 dari laman http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipanf_e.pdf ) ---------------. 2013. Heisei 25 Nen Do Sougou Bousai Kunren Taikou. (Laporan resmi Pemerintah Jepang). (Dokumen diunduh pada 30 September 2013 pada pukul 22.57 dari laman http://www.bousai.go.jp/oukyu/pdf/h25taiko.pdf ) Carter, W. Nick. 1991. Disaster Management. Mandaluyong City : Asian Development Bank. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2012. World Disasters Report 2012 : Focus on Forced Migration and Displacement. Geneva : IFRC. (Dokumen diunduh pada 19 Agustus 2013 pada pukul 12.30 dari laman http://www.ifrcmedia.org/assets/pages/wdr2012/resources/1216800-WDR-2012-ENFULL.pdf ) Kodoatie, Robert J, dan Sjarief, Roestam. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Jakarta : Yarsif Watampone. Navarro, Zander. 2006. “In Search of a Cultural Interpretation of Power: The Contibution of Pierre Bourdieu.” IDS Bulletin, Vol. 37, No. 6 : 11-22. Nishikawa, Satoru. 2011. “Japan’s Preparedness and the Great Earthquake and Tsunami.” Pp. 1847. Lesson From the Disaster : Risk Management and the Compound Crisis presented by the Great East Japan Earthquake. Yoichi Funabashi dan Heizo Takenaka, editor. Tokyo : The Japan Times. Perry, Ronald W. 2005. What is a Disaster? New Answer to Old Questions. USA : Xlibris Corporation. Rapport, Nigel dan Overing, Joanna. 2000. Social And Cultural Anthropology : The Key Concept. New York : Routledge. Ritzer, Geoge dan Goodman, Douglas J. 2011. Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam. Terj. Cetakan 7. Jakarta: Kencana. Statistic Bureau of Japan. 2013. Japan Statistical Yearbook 2013. Tokyo : MIC. (Dokumen diunduh pada 18 Agustus 2013, pukul 19:11 dari laman http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/c01cont.pdf ) Sutton, Jeannette dan Tierney, Kathleen. 2006. Disaster Preparedness : Concept, Guidance, and Reasearch. Boulder : University of Colorado. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013 The Asahi Shinbun. 2011. “Tsunami Drills Paid Off for Hundreds of Children.”, (Diakses pada 7 Desember 2013, pukul 18.54 dari laman http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ201103233378 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Jakarta. Wacquant, Loïc. 2011. “Habitus as Topic and Tool : Reflections on Becoming a Prizefighter.” Qualitative Research in Psychology.Vol. 8: 81-92. Winchester, Daniel. 2008. “Embodying the Faith: Religious Practice and the Making of a Muslim Moral Habitus”. Social Force Vol. 86, No. 4 : 1754-1780. Pelaksanaan latihan..., Firman Budianto, FIB UI, 2013