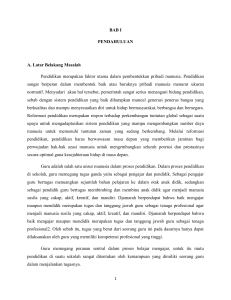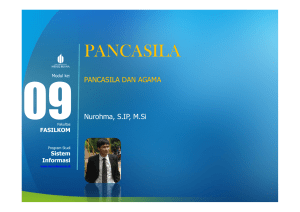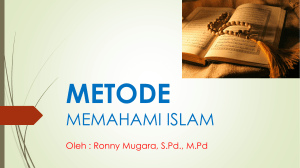PDF (Bab 1)
advertisement

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembahasan tentang politik Islam tidak pernah kering dari kajian‐kajian yang dilakukan oleh para akademisi baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Beratus pemikir dan beribu jilid buku berkaitan dengan politik Islam menghiasi sejumlah perpustakaan di dunia. Beragam bentuk karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, tesis atau disertasi yang membahas politik Islam telah memberikan kontribusi pengayaan pemikiran politik Islan. Perbedaan pemahaman pun tak terelakkan lagi baik antara kalangan muslim sendiri atau bahkan antara kalangan Barat sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kajian politik Islam merupakan kajian yang cukup rumit akan tetapi tetap menarik dan menantang untuk dikaji. Kajian tentang hubungan Islam dan politik adalah suatu kajian yang tidak aka nada habis‐habisnya sebagaimana diumpamakan oleh Nurcholis Madjid laksana menimba air Zamzam di tanah suci. Kenapa? Pertama, disebabkan kekayaan sumber bahasan, sebagai buah limabelas abad sejarah akumulasi pengalaman Dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Kedua, kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Pembahasan yang menyeluruh akan menuntut tidak saja kemampuan yang juga menyeluruh, tapi juga kesadaran untuk tidak membiarkan diri terjerembab ke 2 dalam reduksionisme dan kecenderungan penyederhanaan persoalan. Ketiga, pembahasan tentang agama dan politik dalam Islam ini agaknya akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang mau‐tak‐mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum Muslim sendiri.1 Masih menurut pendapat Nurcholis Majdid pula bahwa usaha memahami masalah politik dalam Islam memang bukan perkara sederhana. Hal itu karena ada dua alasan. Pertama, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari empat belas abad. Jadi akan merupakan suatu kenaifan jika kita menganggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stationer dan berhenti. Kesulitannya ialah, sedikit sekali kalangan kaum Muslim yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran, tentang sejarah itu. Kedua, selain beraneka ragamnya bahan‐bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti kekuatan‐kekuatan dinamik di belakangnya, juga terdapat perbendaharaan teoritis yang kaya raya tentang politik yang hambpir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa atau gejala sejarah yang penting.2 Kesulitan dalam memahami masalah politik dalam Islam, berimplikasi pada belum adanya kesepakatan pendapat mengenai konsep negara Islam. Musdah Mulia, dalam karya disertasinya tentang pemikiran politik Islam Husain 1Nurcholish Madjid, Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip‐Prinsip Hukum dan Keadilan dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I Nomor I, Juli Desember 1998 (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 48. 2 Nurcholish Madjid, “Kata Sambutan” dalam Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI‐Press, 1993), h. vi‐vii 3 Haekal yang mengutip pendapat John L. Esposito dalam Islam dan Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), menyebutkan beberapa faktor ketidaksepakatan itu: 1) negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dipandang ideal ternyata tidak memberikan suatu model terperinci, 2) pelaksanaan khilafah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas hanya memberikan suatu kerangka mengenai lembaga‐lembaga politik dan perpajakan, 3) pembahasan mengenai rumusan ideal (hukum Islam dan teori politik) hanya menghasilkan rumusan idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang utopian, dan 4) hubungan agama dan negara dari masa ke masa menjadi subyek bagi keragaman interpretasi.3 Munawir Sadzali menyebutkan tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan kenegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata‐ mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Karena itu, Islam tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem negara Barat. Sistem politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh empat al‐Khulafa al‐Rasyidin. Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran 3 Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 2‐3 4 ini Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul‐rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem negara. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.4 Berdasarkan ketiga aliran tersebut, Sukron Kamil, dalam tulisannya di Jurnal Universitas Paramadina, melakukan tipologisasi pemikiran politik Islam: tradisional, sekuler, dan moderat. Tipologi tradisional, memandang bahwa Islam adalah agama dan negara. Hubungan Islam dan negara betul‐betul organic dimana negara berdasarkan syariat Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif. Yang termasuk tipologi ini adalah Rasyi Ridla, Sayyid Qutub, Al‐ Maududi, dan di Indonesia Muhammad Natsir. Tipologi Sekuler, memandang bahwa Islam adalah agama murni bukan negara. Tipologi ini terbelenggu dan sangat terpesona oleh pemikiran nation state Barat Modern. Pemikir yang termasuk tipologi ini adalah Ali Abd al‐Raziq, A. Luthfi Sayyid, dan di Indonesia Soekarno. Tipologi Moderat, memandang bahwa meskipun Islam tidak 4 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 1‐2 5 menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip‐prinsip moral atau etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Yang termasuk tipologi ini adalah Muhammad Husein Haikal (1888‐ 1956), Muhammad Abduh (1862‐1905), Fazlurrahman, Mohamed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholish Madjid.5 Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang dikenal dengan Buya Syafii Maarif, adalah seorang cendekiawan muslim yang concern dalam bidang politik Islam. Ia berlatar belakang pendidikan formal Muallimin Jogjakarta yang kemudian melanjutkan kesarjanaannya dalam bidang sejarah. Karya disertasinya yang diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul “Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante”, adalah sebuah refleksi dari pemikirannya tentang politik Islam meskipun tidak secara utuh. Penelitian ini akan mengerucutkan pemikiran politik Islam Syafii Maarif secara utuh yang masih berserakan di berbagai makalah dan buku‐bukunya. Sebagai pembuka wacana pemikirannya tentang politik Islam, pak Syafii membagi Islam kedalam dua pandangan, yaitu Islam sejarah dan Islam cita‐cita. Islam sejarah ialah Islam sebagaimana dipahami dan diterjemahkan ke dalam konteks sejarah oleh umat Islam Indonesia dalam jawaban mereka terhadap tantangan sosio‐politik dan cultural yang dihadapkan kepada mereka sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sedangkan Islam cita‐cita ialah Islam sebagaimana 5 Sukron Kamil, Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: h. 63‐76 6 yang dikandung dan dilukiskan oleh al‐Qur’an dan al‐Sunnah, tetapi yang belum tentu senantiasa terefleksi dalam realitas sosio‐historis umat sepanjang abad. Islam cita‐cita ini menggambarkan suatu totalitas pandangan hidup muslim, sekalipun belum dirumuskan secara sistematis oleh yuris dalam sejarah Islam.6 Paling tidak ada tiga pokok pemikiran politik Islam Syafii Maarif: Pertama dalam Islam cita‐cita, negara tidak lain dari sebuah alat yang perlu bagi agama. Dengan kata lain, ia menolak tesis yang menyatakan bahwa Islam itu din dan daulah. Tentang penolakan terhadap tesis ini ia menulis: Tapi kuatkah tesis yang mengatakan bahwa Islam itu din dan daulah? Dari al‐Qur’an dan Sunnah, begitu pula dari Piagam Madinah, kita tidak menemukan landasan yang kuat untuk mengikuti pendapat itu…. Yang kita gagal memehaminya ialah daulah ditempatkan sejajar dengan din yang berasal dari wahyu. Bukankah tesis ini dapat bermakna bahwa kita secara tidak sadar telah menyamakan alat dengan risalah?7 Kedua, bentuk negara adalah hasil kreasi manusia, karena itu ia dapat saja berubah sesuai perkembangan zaman. Prinsip utama bagi suatu negara untuk dapat dikatakan bercorak Islam ialah jika keadilan, persamaan, dan kemerdekaan, benar‐benar terwujud dan terasa di dalamnya, serta mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat. Tentang hal ini ia menulis: Al‐Quran nampaknya tidak tertarik pada teori khas tentang negara yang harus diikuti oleh umat Islam. Perhatian utama al‐Quran ialah agar masyarakat ditegakkan atas keadilan dan moralitas. Maka atas dasar nilai‐ nilai etik al‐Quran‐lah bangunan politik Islam wajib ditegakkan. Tapi karena al‐Quran tidak menegaskan bentuk khas suatu negara, maka 6 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 4 7 Ahmad Syafii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993), h. 205 7 model dan struktur ketatanegaraan Islam bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah. Ia senantiasa terikat dengan perubahan, modifikasi, dan perbaikan menurut kebutuhan waktu dan ummat.8 Ketiga, karena konsep syura merupakan gagasan politik utama dalam al‐ Quran, maka sistem politik demokrasi nampaknya lebih dekat kepada cita‐cita politik Qur’ani, sekalipun ia tidak semestinya identik dengan praktek demokrasi Barat.9 Dari pemaparan tentang pemikiran politik Islam Syafii Maarif tersebut, ia dapat dimasukkan kedalam tipologi moderat yang menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Dalam setiap karya tulisnya tentang politik Islam, baik berupa makalah maupun buku, selalu mengutip pendapat‐pendapat Fazlurrahman. Ini menandakan bahwa pemikiran politik Islam Syafii Maarif dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran Fazlurrahman. Sebagaimana diakuinya bahwa Fazlurrahman adalah pembimbingnya yang utama dalam penyusunan disertasi doktoralnya sekaligus mentornya dalam pemikiran Islam. Buya Ahmad Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang selalu mengedepankan hati nuraninya dalam tulisan‐tulisannya. Ia seorang tokoh yang memiliki integritas yang tinggi dalam memegang sebuah prinsip. 8 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 18 9 Said Tuhuleley, Pencarian Tiada Henti: Spiral dan Sikap Syafii Maarif, dalam Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif: 70Tahun Ahmad Syafii Maarif, (Jakarta: Maarif Institute, 2005), h. 96‐98 8 Kiprahnya dalam bidang dakwah dan kemasyarakatan telah membawanya ke posisi puncak di persyarikatan Muhammadiyah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah antara tahun 1998‐2005. Ada yang menarik dari sisi pribadinya, dimana ketika orang mendapatkan posisi puncak dalam sebuah organisasi biasanya tergoda untuk terjun dalam politik praktis yang memberikan harapan kekuasaan, ia tidak menggunakan “peluang”tersebut untuk memasuki dunia politik praktis, justru lebih memilih berkiprah di Muhammadiyah dan memainkan peran Muhammadiyah sebagai civil society. Lebih dari itu, ia ,dalam pemaparan tulisan‐tulisannya, kaya akan ungkapan metaforanya. Salah satu kelebihan Buya Syafii Maarif adalah memiliki sikap empati yang tinggi kepada stiap orang meskipun terhadap orang yang berbeda pendapat. Kritiknya terhadap partai Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dalam perdebatan di sidang Majelis Konstituante, disampaikan dengan sikap empati yang cukup tinggi. Akan tetapi, dalam konteks pemikiran kenegaraan, ia tidak memberikan sikap empatinya terhadap al‐Maududi. Misalnya, dalam karya disertasinya tersebut ia mengkritik tentang konsep “Kedaulatan Tuhan” yang diyakini secara kuat oleh al‐Maududi, dengan menulis: Bila teori di atas kita hadapkan kepada konsep “Kedaulatan Tuhan” yang dipercaya sebagai inti dari sistem politik Islam dan yang dibela dan dinyatakan oleh sebagian penulis muslim kontemporer, seperti Abul ‘Ala al‐Maududi, kita menemukan sesuatu yang aneh. Pendapat macam ini telah “banyak menimbulkan kebingungan….”10 10 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 51 9 Padahal,al‐Maududi adalah pemikir muslim yang sangat berpengaruh pada masanya di seluruh dunia terutama di dunia muslim. Tulisan‐tulisannya tentang pemikiran Islam sangat bernash dan selalu mengembalikan kepada al‐ Quran dan al‐Sunnah sebagai pedoman dasar dalam mengungkapkan pemikiran‐ pemikirannya. Termasuk dalam pemikiran politik Islam, seperti dalam bukunya Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam dan Khilafah dan Kerajaan yang kedua bukunya diterbitkan oleh Mizan, bandung, selalu menyandarkan kepada syariat Islam. Sementara dari hasil kajian penulis terhadap pemikiran politik Islam Buya Syafii Maarif nampaknya kering dari konsep syar’i. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang kemudian ditinjau dari perspektif ulama al‐ salaf al‐shalih. Sebagai seorang muslim sudah semestinya mengkaji kembali dan menimbang‐nimbang perbedaan pemahaman dari para akademisi yang memang berkompeten untuk kemudian menentukan sebuah keyakinan akan kebenaran yang dipilihnya. Sudah barang tentu tidaklah mudah untuk memutuskannya. Perlu kajian yang komprehensif dan bernash berdasarkan kaidah‐kaidah ilmiah yang benar. Karena berkaitan dengan pemikiran Islam, tentunya kita memandang dengan kaca mata Islam yang berlandaskan al‐Qur’an dan al‐Sunnah sebagaimana yang dipahami para ulama salaf, bukan dengan kaca mata orang Barat yang tidak meyakini Islam sebagai kebenaran yang hakiki. 10 B. Perumusan Masalah Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pemikiran Ahmad Syafii Maarif tetang hubungan Islam dan negara? 2. Bagaimanakah tinjauan al‐salaf al‐shaleh terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan‐ pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan masalah. Lebih rinci, peneltian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara. 2. Menganalisis dan mengkritisi pemikiran Ahmad Syafii Maarif tetang hubungan Islam dan negara dalam timbangan al‐salaf al‐shaleh. b. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan khasanah pemikiran politik Islam di Indonesia. 2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi keperluan dakwah. Khususnya dalam menyebarkan Islamic Worldview dalam semua konsep kehidupan termasuk negara Islam. Menyadari akan maraknya 11 pemikiran‐pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralism yang dikumandangkan bukan hanya oleh pemikir non muslim, bahkan oleh pemikir muslim sendiri, penulis tergerak untuk, paling tidak, memberikan sedikit kontribusi untuk menangkal pemikiran‐pemikiran tersebut dengan menggunakan sudut pandang Islamic Worldview D. Tinjauan Pustaka Dari hasil penelusuran penulis terhadap hasil penelitian tentang pemikiran Ahmad Syafii Maarif didapatkan beberapa karya dalam bentuk skripsi. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian tentang pemikiran Ahmad Syafii Maarif. Dewi Khusna dalam skripsi Negara dan Kekuasaan dalam Pemerintah: Studi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif (2000) menguraikan konsep negara, kedudukan negara dan kekuasaan rakyat dalam pemerintah. Nur Khasanah dalam skripsi Relasi Islam dan Demokrasi Pancasila di Indonesia Menurut Ahmad Syafii Maarif (2003), mendekripsikan pandangan Syafii Maarif yang melihat prospek demokrasi Pancasila di mata kaum Muslim masa depan. Imam Muklis dalam skripsi Dialektika ke‐Islaman dan ke‐Indonesiaan dalam Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif (2008), menyimpulkan pemikiran Ahmad Syafii Maarif bahwa hubungan Islam dan ke‐Indonesiaan bersifat simbiosis mutualistik. Negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat bertindak sesuai dengan tata nilai, etika, dan moral dalam kehidupan 12 berbangsa dan bernegara. Sebaliknya agama pun memerlukan negara untuk dapat berkembang. Ahmad Asroni dalam skripsi yang berjudul Pandangan Ahmad Syafii Maarif tentang Diskursus Negara Islam dan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia (2009). Dalam tulisannya, Ahmad Asroni menyatakan bahwa Syafii Maarif termasuk tokoh muslim yang berkeberatan apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara dan formalisasi syariat Islam. Berkaitan dengan relasi antara Islam dan negara, secara normatif, Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum muslimin. Ia menolak gagasan negara Islam karena menurutnya tidak memiliki basis religio‐ intelektual yang kukuh. Adapun secara historis, terminology negara Islam tidak terdapat dalam literature klasik. Ia juga menolak tesis yang mengatakan bahwa Islam merupakan din dan daulah. Dalam persoalan formalisasi syariat islam di Indonesia, Syafii Maarif tidak menolak asalkan dengan cara konstitusional dan demokratis. Namun demikian, ia tetap mengkritik kalangan yang menginginkan pendirian negara Islam dan formalisasi syariat islam di Indonesia Dari hasil penelusuran penelitian yang mengkaji pemikiran Ahmad Syafii Maarif, khususnya tentang politik Islam, belum didapatkan pemikiran yang utuh dan bahkan belum ada penelitian yang bersifat studi kritis. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mengkritisi pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara dalam bingkai Islamic Worldview. Tentunya tanpa 13 mengurangi rasa hormat kepada Ahmad Syafii Maarif yang dalam beberapa penulis sangat mengaguminya . E. Landasan Teori Sebelum memaparkan landasan teori relasi Islam dan negara, akan dipaparkan teori ilmu politik secara umum sebagaimana yang digunakan oleh ilmu politik modern. Berikut ini dipaparkan tentang dasar‐dasar teori ilmu politik. Miriam Budiardjo mengutip pendapat Andrew Heywood, bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan‐peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.11 Adapun tentang teori politik, menurutnya adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara‐cara mencapai tujuan itu, kemungkinan‐kemungkinan dan kebutuhan‐kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban‐kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep‐konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga‐lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.12 11 Miriam Budiardjo, Dasar‐Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 16 12 Ibid, h. 43 14 Mengenai konsep negara, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.13 Adapun unsur‐unsur negara adalah sebagai berikut: 1. Wilayah, kekuasaan negara meliputi tanah, laut di sekelilingnya sampai batas 12 mil, dan angkasa di atasnya. 2. Penduduk, yang menyatukan masyarakat dalam suatu negara adalah nasionalisme yang merupakan perasaan subyektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita‐cita aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau nation. Ernest Renan, filosof prancis mengatakan, “Pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. 3. Pemerintah, organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan‐keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. 4. Kedaulatan, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang‐undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.14 13 14 Ibid, h. 17 Ibid, h. 51‐54 15 Louay. M. Shafi menyatakan bahwa kata daulah sudah digunakan dalam al‐Quran dan hanya ada pada satu tempat yaitu pada QS. 59:7 yang berhubungan dengan pendistribusian harta fa’I agar tidak beredar pada golongan orang kaya saja. Namun penggunaan kata daulah yang berkonotasi politis baru dimulai sejak abad ke enam dan tujuh Masehi. Lu’ai M. Shafi menulis: In the Sixt and seventh centuries of the Muslim era, the term daulah began to acquire a political connotation. Muslim scholars at this time, mainly historians, began to employ the word in reference to the various Muslim dynasties wich emerged when the institution of khilafah lost its executive power, while reduced to a nominal affice symbolizing Muslim units, while the real political and military power fell into the hands of strong clane and families.15 Fred M. Donner mendefenisikan negara sebagai institusi yang harus memiliki persyaratan sebagai berikut sebagaimana ditulisnya dalam sebuah jurnal: the "state" is defined as a set of political institutions resting on a conception of legal authority; the institutions considered relevant are (a) a governing group, (b) army and police, (c) a judiciary, (d) a tax administration, and possibly (e) institutions to implement state policies other than taxation, adjudication, and maintenance of control by the elite.16 Ahmad Ali Nurdin, dalam jurnal internasional, membuat kategori negara‐ negara Islam yang berkaitan dengan aplikasi hubungan Islam dan negara dalam tiga kategori. Ia menulis: First, there are countries which still regard syaria as thefundamental law and apply it more or less in its entirety. Saudi Arabia is acase in point. 15 Louay M. Safi, The Islamic State: A Conceptual Frame Work, The American Journal of Islamic Social Sciences, 1991, Vol. 8, No. 2, h. 222 16 Fred M. Donner, The Formation of The Islamic State, Journal of The American Oriental Society, Vol. 106, No. 2, (April‐June, 1986), h. 283 16 Second, there countries where syaria law has been abandoned completely and substituted by a secular one. Turkey fits into this category. Third, there are countries which try to reach a compromise between the two domains of law, by adopting secular law preserving syaria at the same time. These include such countries as Egypt, Tunisia, Iraq Indonesia, and Malaysia.17 Mengenai keterkaitan antara Islam dengan persoalan kenegaraan, para ulama salaf telah menyepakati akan pentingnya kepemimpinan umat yang diformulasikan dalam institusi imamah. Bahkan para ulama salaf telah mewajibkan penegakan imamah sebagai fardlu kifayah. Para ulama Ahlu Sunnah dan Murji’ah secara umum, Mu’tazilah kecuali segelintir dari mereka, dan Khawarij kecuali kelompok al‐Najdaat berpendapat wajibnya menegakkan imamah. Pendapat Syi’ah secara umum pun termasuk mewajibkan, meskipun mereka memiliki pemahaman berbeda dalam makna wajibnya.18 Menurut pendapat Ahlus Sunnah, dasar atau dalil diwajibkannya penegakkan imamah adalah ijma shahabat, menurut Dhiauddin Rais, bahkan bisa jadi adalah dalil satu‐satunya dan dalil‐dalil yang lain hanya dianggap mengikutinya. Dalil ijma ini dibuktikan oleh peristiwa setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dimana para shahabat mengadakan pertemuan di Saqifah milik Bani Sa’idah untuk memilih pemimpin umat Islam yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam pertemuan itu dihadiri oeh para pembesar Anshar dan Muhajirin. Persoalan pemilihan pemimpi ini didahulukan 17 Ahmad Ali Nurdin, Islam and State: A Study of The Liberal Islamic Network in Indonesia, 1999‐2004, New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 7, No. 2, (December 2005), h. 28 18 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 91 17 dari urusan yang paling penting bagi mereka, diantaranya persiapan pemakaman Rasulullah SAW. Perbedaan yang terjadi dalam pertemuan itu bukanlah tentang wajib atau tidaknya penegakan imamah, akan tetapi perbedaan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin. Akhirnya semua shahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar r.a sebagai pemimpin.19 Keterkaitan Islam dengan kenegaraan juga diungkapkan oleh banyak ulama terutama yang concern terhadap permasalahan politik Islam sebagaimana yang dikutip Dhiauddin Rais. Diantaranya al‐ Mawardi dalam bukunya al‐Ahkam al‐Sulthaniyah memberikan alasan diwajibkannya keimamahan dalam Islam, ia mengatakan: “… Seandainya bukan karena para wali (pemimpin), niscaya mereka menjadi kacau tidak terurus serta menjadi biadab dan liar…”. Imam al‐Ghazali berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban‐kewajiban agama baik yang bersifat individu maupun sosial dapat terlaksana jika ditegakkannya institusi keimamahan dalam suatu pemerintahan. Karena itu dia mengatakan, “Agama dan kekuasaan adalah dua anak kembar… Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaga… Sistem aturan agama tidak akan tercapai selain dengan menggunakan sistem aturan dunia, dan sistem aturan dunia tidak akan dicapai kecuali dengan adanya seorang imam yang dipatuhi”.20 Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, turut memperkuat teori tentang keterkaitan Islam dengan kenegaraan. Ia memaparkan teori‐teori politiknya dalam bukunya al‐Muqaddmimah, ia menulis, “Kemudian bahwa melantik imam 19 20 Ibid, h. 94 Ibid, h. 97‐99 18 adalah wajib yang kewajibannya diketahui dari agama dengan ijma para shahabat dan tabi’in karena para shahabat Rasulullah SAW, ketika beliau wafat, segera membai’at Abu Bakar r.a. dan menyerahkan kepadanya untuk mengatur urusan mereka. Demikian pula dalam setiap era setelah itu. Manusia atau umat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kacau dalam suatu masa dari berbagai masa. Maka dinyatakanlah hal itu sebagai ijma yang menunjukkan wajibnya melantik imam.”21 Teori keterkaitan Islam dan kenegaraan ternyata juga disepakati oleh beberapa orientalis terkenal. Diantaranya, Dhiauddin Rais menukil beberapa pernyataan orientalis, adalah V. Fitzgerald berkata, “Islam bukanlah semata agama namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada decade‐ dekade terakhir ada beberapa kalangan dari kaum umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.” C.A. Nalinno menulis, “ Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara. Dan batas‐batas territorial negara yang dia bangun it uterus terjaga sepanjang hayatnya.” Bahkan H.A.R. Gibb dengan tegas mengatkan, “Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang 21 244 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Kairo: Daar al‐Fajr Li al‐Turats, 2004), h. 19 independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang‐undangan, dan institusi.”22 Untuk memahami politik Islam diperlukan pemahaman konsep‐konsep dasar yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu al‐Quran, al‐Sunnah, dan ijma para shahabat. Konsep‐konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep tentang Ummah, Syura, dan Imamah atau Khilafah. Konsep‐konsep ini tidak terdapat dalam konsep politik modern Barat. Ummah, menurut pengarang Lisan al‐Arab,dalam pengertian bahasa artinya adalah sekelompok dan kaum di kalangan manusia. Raghib al‐Ashfahani dalam al‐mufradat fi gharib al‐Quran secara lebih jelas mendefinisikan ummat adalah setiap jama’ah yang disatukan oleh sesuatu hal; satu agama, satu zaman, atau satu tempat. Baik factor pemersatu itu dipaksakan ataupun berdasarkan atas pilihan.23 Secara lebih terperinci, Sa’id Hawwa, menjelaskan unsur‐unsur pemersatu ummah dalam hal ini adalah umat Islam. 1) Kesatuan aqidah, dimana umat Islam mempunyai suatu sistem yang menghimpun setiap orang yang mengucapkan la ilaha illa Allah secara ikhlash. Sehingga barang siapa tidak mengucapkannya, maka tidak termasuk bagian umat ini. 2) Kesatuan ibadah, ibadah yang diwajibkan Allah kepada umat Islam semua adalah satu. Setiap muslim diwajibkan shalat lima waktu sehari semalam, shaum di bulan ramadlan setiap 22 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 5‐6 Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, Menuju Jama’atul Muslimin: Telaah Sistem jama’ah dalam Gerakan Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 1991), h. 43‐44 23 20 tahun, zakat apabila telah cukup nishab, dan kewajiban‐kewajiban Islam yang lain. 3) Kesatuan adat dan prilaku, setiap umat Islam mempunyai keteladanan yang baik pada diri Rasulullah SAW. 4) Kesatuan sejarah, seorang muslim tidak terikat oleh tanah air atau warna kulit tertentu, dan hanya sejarah Islamlah yang menjadi ikatan dan kebanggaannya. 5) Kesatuan bahasa, merupakan suatu yang alami jika bahasa Arab menjadi salah satu factor pemersatu umat Islam, karena undang‐undang Islam adalah al‐Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. 6) Kesatuan jalan, sesungguhnya jalan kaum muslimin adalah satu, yaitu jalan para Nabi dan Rasul. Karena itu, seorang muslim dituntut agar teguh dan konsisten di jalannya. 7) Kesatuan undang‐undang, sumber undang‐undang umat Islam adalah al‐Quran dan al‐Sunnah. Kaum muslimin dilarang mengambil rujukan, untuk menata dan mengatur gerakan mereka di atas bumi ini, kecuali dari apa yang diturunkan Allah dan dibawa Rasul‐Nya. 8) Kesatuan pimpinan, umat Islam sepakat bahwa pemimpinnya yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian para khalifah‐nya yang terpimpin. Masing‐masing dari mereka menjadi pemimpin pada zamannya.24 Makna syura menurut bahasa adalah meminta‐keluar, seperti dalam ungkapan syara’ al‐‘asala yasyuruhu syauran, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.25 Secara istilah, musyawarah dapat berarti meminta pendapat dari para ahli tentang suatu masalah. Menurut pengarang al‐Munjid menyimpulkan 24 Sa’id Hawwa, Al‐Islam, (Jakarta: Al‐I’tisham Cahaya Umat, Terj., 2002 M)m, 2/112‐117 Ibnu Manzhur, Lisan al‐‘Arab, (Beirut: Daar Shadir, 1388 H), 6/103 25 21 bahwa Majelis Syura ialah majlis yang dibentuk untuk membahas urusan‐urusan negara.26 Jadi, konsep syura merupakan unsur yang sangat penting dalam hubungannya Islam dan kenegaraan. Sebagaimana Sayyid Quthb, ketika menafsirkan ayat “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”, mengatakan, “Ini adalah nash yang tegas yang tidak boleh diragukan lagi oleh umat Islam, bahwa syura adalah dasar asasi bagi tegaknya sistem pemerintahan Islam. Islam tidak boleh tegak kecuali di atass prinsip ini.”27 John L. Esposito menyatakan bahwa umat Islam menerima demokrasi dalam kehidupan politiknya karena hampir sama dengan konsep syura yang terdapat dalam al‐Quran. Ia menulis: Muslim interpretation of democracy build on the well established Qur’anic concept of shura (consultation), but place varying emphases on the extend to wich “the people” are able to exercise this duty. One school of thought argues that Islam is inherently democratic not only because of the ptonciple of consultation, but also because of the concept of ijtihad and ijma’ (consensus).28 Istilah imam, khalifah atau amir al‐mu’minin ditujukan kepada satu pengertian, yaitu kepemimpinan tertinggi umat Islam, tetapi masing‐masing dari istilah tersebut mempunyai latar belakang historis dan politis tersendiri. Al‐ Mawardi mendefinisikan imam dengan mengatakan, “Imamah dibentuk untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”29 Adapun penyebutan khalifah berawal dari pemilihan Abu Bakar r.a pada 26 Al‐MunjidFi al‐Lughah Wa al‐A’lam, (Beirut: Daar al‐Masyriq, 1986 M) h. 407 Sayyid Quthb, Fi Zhilal al‐Quran, (Bairut: Daar al‐Syuruq, 1992), 4/117 28 John L. Esposito and James P. Piscatori, Democratization and Islam, The Middle East Journal, Vol. 45, No. 3, (Summer, 1991). 29 Al‐Mawardi, Al‐Ahkam Al‐Sulthaniyah, (Beirut: Daar al‐Kutub al‐‘Ilmiyah), h. 5 27 22 peristiwa saqifah untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dan memelihara kemaslahatan mereka.30 Adapun gelar amir al‐Mu’minin diberikan pertama kali kepada khlaifah yang kedua, Umar ibn al‐Khaththab.31 F. Metode Penelitian Penelitian yang baik dan benar adalah penelitian yang berdasarkan landasan ilmiah dengan mengacu kepada metodologi peneltian yang benar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan metode penelitian sebagai berikut: a. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku‐buku yang terkait dengan focus kajian sebagai sumber data (library research).32 Data‐data yang dikumpulkan adalah berupa jurnal‐jurnal ilmiah, buku‐buku, dan karya tulis baik berupa skripsi ataupun tesis yang berkaitan dengan tema penelitian. b. Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis‐ filosofis. Pendekatan historis adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan‐ keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati‐hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah 30 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 78 Ibid, h. 82 32 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), h. 9 31 23 serta iterpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan‐kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Ahmad Syafii Maarif, sehingga dapat dipelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis. c. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dikelompokan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku‐buku asli karya Ahmad Syafii Maarif tentang politik Islam. Diantaranya adalah: 1. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1996). 2. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959‐1965), (Jakarta: GIP, 1996). 3. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993). Adapun datan sekunder adalah semua sumber data yang mendukung dalam pembahasan penelitian tentang negara Islam baik tentang pemikiran 24 Ahmad Syafii Maarif maupun tentang pemikiran tokoh muslim yang lainnya. Diantara sumber data sekunder yang dibunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Buku Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif: 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, (Jakarta: Maarif Institute, 2005, editor Abd Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay), adalah merupakan kumpulan tulisan tentang pemikiran politik Islam Ahmad Syafii Maarif. 2. Jurnal Ahmad Asroni Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia, (Millah Vol. X, No 2, Februari 2011) 3. Buku Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), buku ini merupakan hasil karya disertasi Musdah Mulia yang diterbitkan oleh penerbit Paramadina. 4. Buku M. Dhiauddin Rasi, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 5. Buku Al‐Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung:Penerbit Mizan, 1995) 6. Buku Al‐Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993) 7. Buku Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993) 25 d. Analisis Data Penelitian ini bersifat deskriptif‐analitis. Deskripsi, berarti menggambarkan secara tepat sifat‐sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analisis, adalah jalan yang diteliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah‐milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya.33 Metode deskriptif‐analitik dengan demikian adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama‐sama maka diharapkan objek dapat diberi makna secara maksimal.34 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data.35 Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 33 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), h. 47‐49 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336 35 Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h. 112 34 26 Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoraganisasikan sehingga data terpilah‐ pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil simpulan. Setelah dilakukan analisis dengan metode di atas, kemudian data dianalisis kembali dengan menggunakan perspektif ulama al‐salaf al‐shalih, yakni melakukan deskriptis analitis berdasarkan metodologi yang digunakan oleh para ulama al‐salaf al‐shalih. Pada tahap ini, peminjaman metode yang dibangun oleh perkembangan ilmu pengetahuan perlu dilakukan secara kriris‐selektif, dengan menjadikan Islam sebagai basic of knowledge. G. Sistematika Penulisan Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistem penulisan sebagai berikut: Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasana teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan penutup. Bab kedua, memaparkan biografi Ahmad Syafii Maarif yang terdiri dari; biografi Ahmad Syafii Maarif, Latar Belakang intelektual Ahmad Syafii Maarif, 27 metodologi dan corak pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Karya‐karya Ahmad Syafii Maarif. Bab ketiga, mendeskripsikan pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara yang terdiri dari; landasan teori politik Islam, konsep negara Islam, konsep Piagam Madinah, konsep syura sebagai prinsip dasar politik Islam, dan cita‐cita negara Islam dalam konteks ke‐Indonesiaan. Bab keempat, membahas analisis pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang relasi Islam dan negara perspektif ulama al‐salaf al‐shalih yang terdiri dari; konsep pemahaman ulama al‐salaf al‐shalih,dasar‐dasar teori politik Islam, relasi Islam dan negara menurut ulama al‐salaf al‐shalih, tinjauan pemahaman ulama al‐salaf al‐shalih terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif. Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran‐saran.