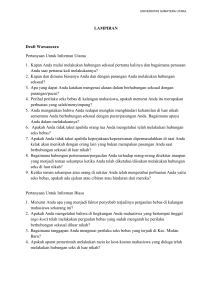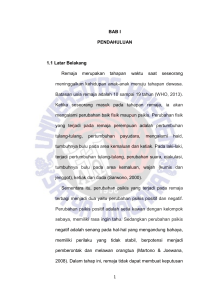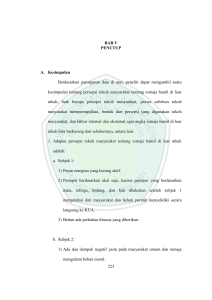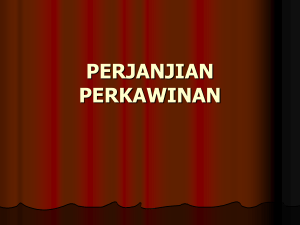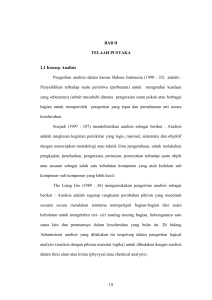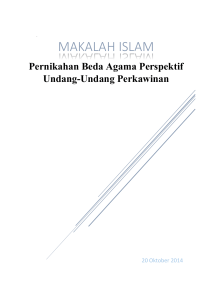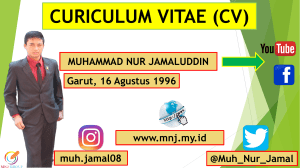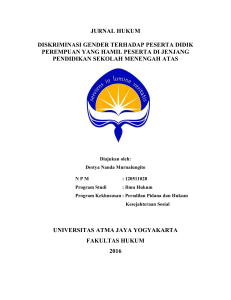Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status
advertisement

Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan Oleh: Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. I. Pendahuluan. Dalam pandangan Islam perkawinan (nikah) merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Agar perkawinan itu mempunyai nilai ibadah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi semua unsur yang menjadi ukuran keabsahan perkawinan tersebut, menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pencipta Syari’at itu sendiri (Allah SWT dan Rasul-Nya) seperti rukun, syarat dan tidak adanya larangan di antara mereka yang melaksanakan perkawinan. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan seseorang adalah perkawinan yang dinyatakan sah menumt ketentuan agama yang dipeluknya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). II. Keabsahan Perkawinan. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah kalau perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan serta larangan-larangan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum Islam (Fiqh Munakahat) sebagaimana tertuang dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (sebagai himpunan hukum Islam hasil kesepakatan ulama Indonesia) sebagai berikut : 1. Rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 14 s.d pasal 29. 2. Larangan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 39 s.d Pasal 44. III. Pencatatan Perkawinan. Negara Indonesia wilayah Negara hukum. Perkawinan yang dilaksanakan di negara Indonesia harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, tidak hanya harus sah menurut hukum (agama) Islam, namun juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan hukum di Indonesia yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, adalah adanya pencatatan perkawinan tersebut. Dasar hukum pencatatan perkawinan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2)). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nornor 1 Tahun 1974 (Pasal 2 s.d Pasal 9). 4. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 5, 6 dan 7). Disampaikan dalam acara “Penelitian dan Pengkajian Aspek Hukum Itsbat Nikah” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 14-16 Mei 2012, bertempat di Hotel Le Dian Serang, Banten. Guru Besar Fakultas Syari’ah, IAIN “SMHB”, Fakultas Hukum UNTIRTA dan Fakultas Hukum UNMA Banten. 1 Jadi perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, maka perkawinan itu belum memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia, karena perkawinan tersebut tidak mempunyai dokumen hukum otentik sebagai bukti adanya perbuatan (perkawinan) hukum tersebut. Mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan pencatatan perkawinan, disebutkan dalam Ketentuan Pidana Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan sebagai berikut : (1). Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggitingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). (2). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. Dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan sebagai berikut: Pasal 3 : (1). Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (2). Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsutigkan. (3). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 10 (1). Perkawinan dilangsungkan setelah han kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2). Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3). Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. IV. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah Sepanjang yang dapat kita baca dalam perundang-undangan, pengertian Itsbat Nikah adalah : 1. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penjelasan pasal 49 ayat (2) angka nomor 22 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 huruf a nomor 22). 2. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b. hilangnya akta nikah. c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. e. adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lihat Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 3. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang (Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010, angka 6) huruf a) hal. 147). Dasar hukum Itsbat Nikah: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (5) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasa Pasal 49 ayat (2) angka 22) jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a angka 22. 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (2), (3), (4). Kalau kita urut dan dasar hukum di atas, maka istilah “Itsbat Nikah”, baru muncul dalam Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak muncul istilah Itsbat Nikah tersebut. Dalam penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atau penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, istilah yang muncul adalah. “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain “. V. Analisis Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah Munculnya ketentuan lisbat Nikah tidak bisa dipisahkan dan ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Landasan hukum Itsbat Nikah, kalau kita analisis bisa dibedakan menjadi: 1. Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22, yang kemudian dipertegas dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. 3 2. Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya dan pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Munculnya ketentuan Itsbat Nikah juga berkaitan dengan masalah status pencatatan perkawinan. Ada dua pandangan mengenai masalah status pencatatan perkawinan tersebut: (1). Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, tidak merupakan persyaratan sahnya suatu perkawinan, jadi pencatatan perkawinan hanya proses untuk mendapatkan suatu bukti, bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang. (2). Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan. Menurut pendapat pertama sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan agama yang dipeluk oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan berada di luar unsur keabsahan perkawinan tersebut. Saat mulal sahnya suatu perkawinan adalah sesaat setelah terjadinya ijab qobul antara wali nikah dengan calon pengantin pria. Argumentasi yang mengatakan bahwa pencatatan merupakan bagian dan sahnya perkawinan, terutama dengan alasan kepastian hukum tentang bukti adanya perkawinan tersebut. Dalam pandangan mi ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh alasan pandangan ini dihubungkan dengan manfaat kemaslahatan yang didapat dengan pencatatan tersebut, dengan mengacu kepada maslahat mursalah atau untuk menghindari akibat yang merugikan / tidak diinginkan (sad al‘dzari’ah). Ada juga pandangan yang meletakkan pencatatan perkawinan sebagai ganti kehadiran saksi, sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad nikah. Berkaitan dengan status pencatatan nikah, menurut informasi masalah mi sejak awal sudah dibicarakan. Ada informasi bahwa menurut Wasit Aulawi (seorang pejabat Direktorat Peradilan Agama yang banyak terlibat dengan penyusunan UndangUndang 1974), kalau dilihat sejarah proses pembentukan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, konsep awalnya menjadikan pencatatan sebagai syarat sah. Tetapi karena tidak disetujui fraksi Partai Persatuan, akhirnya hanya menjadi syarat administrasi. Wacana dua pandangan di atas sudah sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Pandangan-pandangan mereka dengan argumentasi masing-masing, sulit untuk dipertemukan. Selanjutnya untuk menentukan mana yang terbaik dan dua pandangan tersebut, tinggal terserah kepada kita bangsa Indonesia, apakah kita mau memasukan Diunduh dari Web Internet: http://pendidikan-hukum.blogspot/2010/11/pencatatan-perkawinan-dalampandangan.html#1/11/pencatatan-perkawinan-dalam-pandangan.html 4 pencatatan perkawinan sebagai bagian dan sahnya suatu perkawinan, atau pencatatan perkawinan tersebut hanya bersifat administratif dengan tetap mempertahankan kemungkinan munculnya Itsbat Nikah. Menurut penulis, saat ini harus ada kejelasan dan keberanian pemerintah yang harus didukung oleh para ulama, cendekiawan muslim tentang status pencatatan perkawinan kaitan dengan Itsbat Nikah tersebut, yaitu dengan mengubah pasalpasal dalam undangundang tentang perkawinan. Pertama, kalau kita ingin pencatatan perkawinan merupakan bagian dan syarat sahnya perkawinan, maka hal itu hams dimunculkan dalam undang-undang, yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan gabungan dan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 tersebut. Sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan “. Apabila alternatif ini yang dipillh, maka perlu dipikirkan lebih lanjut tentang sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, memerlukan pemikiran yang cukup lama dan mendalam serta konfrehensif. Sebagaimana kita maklumi pada saat ini, sanksi mengenai pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, apabila kita akan mempertahankan pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif, tidak merupakan bagian dan syarat sahnya perkawinan, maka dalam Undang-Undang perlu ada klausul yang menyatakan tentang kemungkinan adanya Itsbat Nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi ketentuan Itsbat Nikah harus diatur dalam Undang-Undang, bukan dalam Instruksi Presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata / istilah Itsbat Nikah dan landasan hukum Its bat Nikahbagi perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan bukan kepada undang-undang, tapi didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Ttahun 1991. Terhadap Kompilasi Hukum Islam ini ada yang memandang hanya sebagai fiqh Indonesia yang sifatnya tidak mengikat. Di sisi lain menurut informasi praktek produk Pengadilan Agama mengenai Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah cukup banyak, yang berarti masih banyak perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setelah herlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum mengikuti ketentuan pencatatan perkawinan. Bila alternatif ini yang dipilih, penulis setuju dengan ungkapan dalam Buku Panduan Teknis administrasi Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa: “untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan Itsbat Nikah”. Untuk menentukan pilihan dan dua alternatif di atas, perlu ada rencana besar dan pemerintah dan para ulama serta cendekiawan muslim untuk menuntaskan masalah status pencatatan perkawinan dan Itsbat Nikah tersebut. Selanjutnya menarik untuk dikaji sejauhmana kekuatan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan Itsbat Nikah bagi 5 perkawinan yang tidak dicatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kalau dihubungkan dengin ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 49 (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 huruf a angka 22 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara explicit tidak membuka ruang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sebenarnya menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak rnungkin ada Itsbat Nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat dan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Mengenai hubungan kedudukan Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan Undang-Undang (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dapat kita lihat dalam Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pernerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-unctangan sesuai dengan hierarki tersebut di atas. Dengan melihat urutan perundang-undangan di atas, lnstruksi Presiden sebagai produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Presiden berada di bawah Undang-Undang, termasuk urutan kelima setelah Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, UndangUndang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. VI. Kepastian Hukum Itsbat Nikah. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka menurut agàma tersebut, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan menurut perundang-undagan di Indonesia (Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974). Bila perkawinan tersebut tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah “Itsbat Nikah”. Bila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui Itsbat Nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan). Karena itu maka : 1. dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti perkawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. 6 Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami istri dalam Itsbat Nikah tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2. dengan keluarnya Itsbat Nikah, anak yang lahir dalam perkawinan (anak yang lahir dalam batas minimal kandungan setelah akad nikah) atau anak yang lahir akibat perkawinan (anak yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus) yang sah atau telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dan suarni istri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan Itsbat Nikah tersebut. Hubungan anak-anak tersebut dengan orang tuanya (suami istri yang telah dinyatakan sah dengan Itsbat Nikah) memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 45 s.d Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Anak-anak yang lahir sebelum / kurang dan batas minimal kandungan atau anakanak yang lahir setelah / lebih dan batas maksimal kandungan merupakan anak-anak yang tidak sah (anak luar kawin). Mereka hanya mempunyai hubungan perdata / hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab / hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran mereka. 3. dengan keluarnya Itsbat Nikah, harta yang berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah tersebut, baik harta bawaan Mengenai batas minimal kandungan (Aqollu Muddatilhamli) dan batas maksimal kandungan (Aktsaru Muddatilhamli) secara tegas belum disebutkan dalam perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 102 KHI hanya mengatur jangka waktu bagi suami kalau akan mengajukan gugatan bila Ia akan mengingkari seorang anak yang lahir dan istrinya. Menurut Jumhur Ulama batas minimal kandungan adalah 6 bulan, yaitu dengan menggabungkan pemahaman arti Q.S al Luqman 31: 14 dan Q.S al Ahqaf 46 : 15. Sedang mengenai batas maksimal kandungan mereka tidak sepakat ada yapg mengatakan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Hukum Waris Mesir Nomor 77 Tahun 1943 disebutkan bahwa batas minimal kandungan adalah 270 hari sedang batas maksimal kandungan adalah 365 hari. Selanjutnya berdasarkan Pasal 251 BW, disebutkan bahwa batas minimal kandungan adalah 180 hari dari tanggal perkawinan dan berdasarkan Pasal 255 BW maksimal kandungan adalah 300 hari setelah putusnya perkawinan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal pengucapan 17 Februari 2012 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagal ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan perlu pengkajian yang mendalam. Terhadap Putusan MK tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2011 Isi Fatwa tersebut antara lain menyebutkan sebagai berikut : (1). Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, (2). Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan kelurga ibunya, (3). Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, (4). Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl’), (5). Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta‘zir lelaki penzina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah, (6). Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. 7 suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama) mereka, bila perkawinan mereka putus merupakan harta yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sejak perkawinan tersebut disahkan sesuai dengan Itsbat Nikah ybs. Pengaturan harta bawaan suami istri (termasuk harta warisan dan hadiah yang didapat oleh masing-masing suami atau istri) dan harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 s.d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 s.d 51 serta Pasal 85 s.d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tetap menjadi milik dan dikuasai oleh mereka masing-masing. Sedangkan harta perkawinan merupakan milik mereka berdua. Apabila perkawinan mereka putus masing-masing suami istri berhak mendapat seperdua dan harta perkawinan (harta bersama) tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjajian perkawinan. Kepastian hukum sebagaimana digambarkan di atas, adalah kepastian hukum bagi status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan sejak tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan Istbat Nikah, baik terhadap perkawinan yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. VII. Penutup. Dalam rangka kepastian hukum Itsbat Nikah terhadap status perkawinan dan hal yang berhubungan dengan perkawinan seperti status anak dan status harta perkawinan, perlu segera diambil keputusan oleh kita mengenai status pencatatan perkawinan yang ada hubungannya dengan Itsbat Nikah. Apakah kita akan mengakhiri Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bagian dan sahnya suatu perkawinan, atau kita akan tetap memberlakukan Itsbat Nikah terhadap perkawinan baik yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974, dengan memasukkan ketentuan Itsbat Nikah tersebut dalam Undang-Undang, tidak hanya dalam Instruksi Presiden. Pada saat ini peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dirasa sudah banyak yang harus disempumakan. Selain masalah pencatatan perkawinan dan Itsbat Nikah masih ada masalah lain umpama masalah status anak luar kawin yang diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga isi Kompilasi Hukum Islam, banyak yang harus disempurnakan baik dalam Hukum Perkawinan maupun dalam Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Wallahu ‘alam bishshawab. Serang, 14 Mei 2012 Penyaji, Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. 8