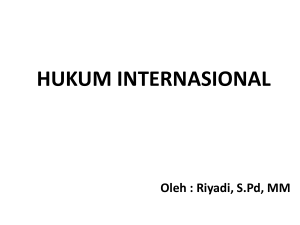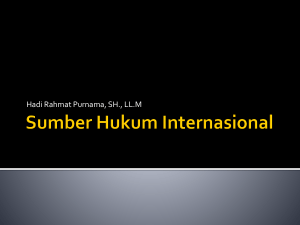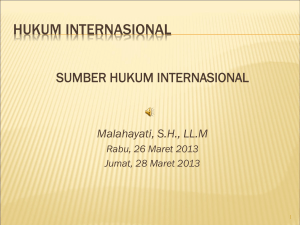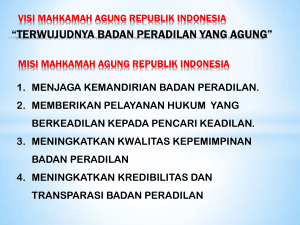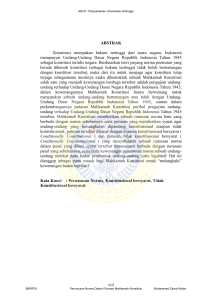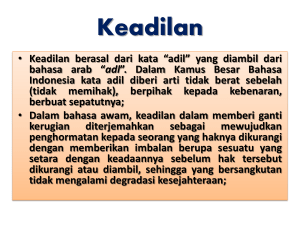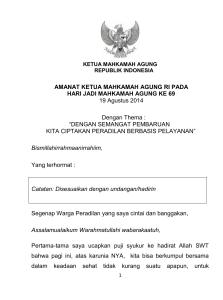Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014
advertisement

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan memuat naskah/artikel yang bersumber dari hasil penelitian/penelaahan tentang Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan. Jurnal Hukum dan Peradilan terbit tiga kali dalam setahun (Maret, Juli, November) Penasehat : Penasehat Penanggung Jawab Ketua Dewan Editor Editor : : : : Editor Tamu : Mitra Bestari : Kepala Sekretariat Anggota : : Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH. MH. Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. H. Suwardi, SH. MH. Ny. Siti Nurdjanah, SH. MH. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. Dr. Ismail Rumadan, MH Moch. Iqbal, SH., MH. Rita Herlina, SH. LLM. Johanes Brata Wijaya, SH. Budi Suhariyanto, SH., MH. 1. Zezen Zainal Muttaqin, SHI., LLM 2. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA 1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS 2. Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag 3. Prof. Dr. Sri Hajati, SH., MS 4. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., M.Hum 5. Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum 6. Prof. Dr. Widodo Eka Tjahyana, SH., M.Hum 7. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF., SH., LLM 8. Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH., PhD 9. Imam Prihandono, SH., LLM., PhD 10. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH 11. Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH H. Moch. Amirullah Sholeh, SH., MM 1. Suhenda, SH 2. Bintang Alvita, Ss 3. Tri Mulyani, A.Md 4. Maryam Sugiarti, S.Sos 5. Dinar Wardani, SHI 6. Dini Widaningsih 7. Imam Buchori Alamat Redaksi : Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jln. Jend. A. Yani (By Pass) Kav. 58 Lt.10 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 13011 Email: [email protected] [email protected] Isi Jurnal dapat dikutip dengan menyebut nama sumbernya (Citation is permitted with acknowledgement of the source) Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Volume 4 Nomor 1 Maret 2015 Daftar Isi Pengantar Redaksi Daftar Isi Daftar Abstrak Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK ……………. 1 - 16 Moh. Mahfud MD Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ……………………………………………………………. 17 - 30 Saldi Isra Freedom & Impartial of Judiciary : Antara “Peradilan Bebas” & “Pers Yang Bebas” ……………………………………………… 31 - 50 Indriyanto Seno Adji Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks UndangUndang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan …………………………………………………………………………… 51 - 64 Philipus M. Hadjon Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung Melalui Undang-Undang Jabatan Hakim …………… 65 - 82 Siti Nurjannah Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum ……………. Ridwan Mansyur Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak 83 - 100 Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi 2003 …………………………………………………… Lilik Mulyadi 101 - 132 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik ………………………………………………………. 133 - 152 Agus Budi Susilo Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan …………………………………………………………………………………. 153 - 170 Budi Suhariyanto Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Undang-Undang terhadap Nomor 16 Orang Miskin Sesuai Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ………………………………………………………………………. Isnandar Syahputra Nasution Biodata Penulis Pedoman Penulisan Jurnal Hukum dan Peradilan 171 - 188 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 PENGANTAR REDAKSI Bisminllahirrahmannirrahim Puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik, amin. Salah satu program prioritas Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, yakni penerbitan jurnal Hukum dan Peradilan diharapkan menjadi upaya positif Puslitbang MA-RI sebagai Supporting Unit Mahkamah Agung RI secara kelembagaan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Kehadiran Jurnal Hukum dan Peradilan sebagai media bagi insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum diharapkan dapat menjadi wadah mengaktuasikan ide pemikiran melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum dan peradilan secara ilmiah, yang nantinya dapat menjadi pencerah ditengah upaya besar bangsa untuk menata pembangunan hukum dan peradilan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan seluruh Unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI yang terus memberi dukungan untuk terbitnya jurnal ini, Juga terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI dan Kepala Puslitbang Kumdil MA-RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penerbitan jurnal ini. Begitupun kepada para penulis yang telah berkontribusi mengirimkan artikelnya dan para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktu untuknya mereview artikel para penulis, Semoga amal kebaikannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jakarta, Maret 2015. Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Moh. Mahfud MD TITIK SINGGUNG WEWENANG ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 1-16 Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Agung (MA) baik dalam filosofi universalnya maupun dalam sejarah dan perdebatan partikularnya. Menjadi wajar jika dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa titik singgung kewenangan yang harus diselesaikan bukan saja secara akademis tetapi secara yuridis. Jika kewenangan-kewenangan MK itu dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan MA maka tampak ada persilangan kewewenangan antara kedua lembaga tersebut. MK mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun MA juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundang-undangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Kata kunci: Titik Singgung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Moh. Mahfud MD AUTHORITY CONNECTIVITY CONSTITUTIONAL COURT OF SUPREME COURT AND Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 1-16 The existence of the Constitutional Court (MK) in Indonesia is linked to the Supreme Court (MA) both in the universal philosophy and in history and the particular debate. Being natural in practice found several points of authority tangency which must be resolved not only academically but in juridiction. If powers of the Constitutional Court was elaborated and then linked with the authority of the Supreme Court the authority then it appears there is a cross between the two institutions. The Constitutional Court judge rules conflict which is abstract at once judges conflicts (disputes) between the person or institution that is concrete. There is also the Supreme Court also adjudicates conflicts (disputes) between people or institution that is concrete as well adjudicates conflicts between rules which are abstract. Here appears the cross testing authority in legislation between the Constitutional Court and the Supreme Court because they both have the authority to conduct testing, but to different degrees. Keywords: Connective Point, Supreme Court, Constitutional Court Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Saldi Isra TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 1 hlm. 17-30 Percampuran kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, muncullah persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan misalnya, meski Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan, namun dengan berbedanya jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang diuji, maka penafsiran peraturan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dua lembaga tersebut mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab, validitas norma adalah bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, apapun putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan tersebut bersifat erga omnes, termasuk bagi hakim agung di Mahkamah Agung dan hakim-hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kata kunci : Wewenang, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Saldi Isra AUTHORITY CONNECTIVITY OF SUPREME COURT (MA) AND CONSTITUTIONAL COURT (MK) Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 17-30 The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court have the same right to test the legislation, but with different types and hierarchy of legislation being tested, then the interpretation of the rules of the legislation for which they were these institutions must be subject to a hierarchical system of laws and regulations that apply. Therefore, the validity of the norm is derived from the legislation is higher. Moreover, any decision of the judicial review of the UUD, this decision is erga omnes, including for judges of the Supreme Court and judges of the court under the Supreme Court. Keywords : Authority, Constitutional Court, Supreme Court Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Indriyanto Seno Adji FREEDOM AND IMPARTIAL OF JUDICIARY “PERADILAN BEBAS DAN PERS YANG BEBAS” : ANTARA Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 31-50 Kemerdekaan Pers yang dianut oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan aksentuasi dari sistem Libertarian Press yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Previlege Right Absolut dari Pers memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan –moral hazard- atas dasar Interest of justice atau national security atau for prevention of disorder or crime yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria Sub Judice Rule ataupun Disobeying a Court Order dari pranata Contempt of Court. Suatu pemberitaan yang merupakan wujud kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” serta telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers Libertarian) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara ethik norma maupun hukumnya. Kata kunci : Peradilan, Pers, Bebas Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Indriyanto Seno Adji FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY : BETWEEN “FREEDOM OF JUDICIARY” AND “FREEDOM OF THE PRESS” Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 31-50 Press of independence adopted by Law No. 40 of 1999 on the Press is an accentuation of the Libertarian Press system which requires the existence of a absolute total "freedom of pers" by putting all the legal consequences on the substance of its news through judicial institutions, without calls for criminalization forms of the press with all the reason and limitedly direction purpose. Absolute Privilege Right of the Press have signs that provide a limitation on -moral hazard- based on Interest of justice or national security or for the prevention of disorder or crime that can be issued by the judiciary as a form of Sub Judice Rule criteria or Disobeying a Court Order from Contempt of Court institutions. a proclamation which is a form of freedom of expression with the news that "prejudicial", even the news substance pose a "misleading conclusion and opinion" as well as has provided an opinion and conclusions that are misleading or incorrect and negative impact on the course of judicial proceedings and other parties broadly (as recognition of the Press Libertarian System) may be faced with a sense of responsibility of the press itself, either ethic norms and laws. Keywords : Judicial, Pers, Freedom Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Philipus M. Hadjon PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANGUNDANG NO.30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 51-64 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1.1 adalah tata lakasana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Jika dibandingkan dengan Algemene wet Bestuursrecht (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas. AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (bestuursrecht) sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi, namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU AP merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar. Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi. Kata kunci : Peradilan, Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Philipus M. Hadjon ADMINISTRATIVE COURT ACCORDING TO LAW NO. 30 YEAR 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 51-64 Act No. 30 Year 2014 on Government Administration (UU AP) instead of administrative law. The concept of public administration (AP) in Article 1.1 is governance in the decision and/or action by the official agency and / or government. When compared with the Dutch Algemene wet Bestuursrecht (AWB), it seems obvious differences. AWB moved from the concept of administrative law (bestuursrecht) while the AP is the starting point of government administration. That in AP there are aspects of administrative law, but the concept of administrative law is confusing. On the basis, the common explanations of AP stating AP Act is a substantive law of the State Administrative Court system becomes a big question mark. AP Act provisions concerning Administrative Court is not based on a clear conceptual approach. On the basis, AP Act concerning Administrative Court is very difficult to apply in judicial practice as well as vague concepts is also contrary to the concepts of administrative law. Keywords : Judicial, Administrative Court, Act No. 30 Year 2014 on Government Administration Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Siti Nurjannah MEWUJUDKAN VISI MAHKAMAH AGUNG TENTANG BADAN PERADILAN YANG AGUNG MELALUI UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 65-82 Status jabatan Hakim telah ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS. Pembiaran atas status ganda tersebut, senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial maupun terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Jika independensi mulai tereduksi maka implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Kata kunci : Visi Mahkamah Agung, Undang-Undang, Jabatan hakim Siti Nurjannah REALIZE THE VISION OF THE SUPREME COURT THROUGH THE AGENCY LAW JUDGE POSITION Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 65-82 Judges official status has been affirmed as a state official, but in fact on some aspect on it is still bound by the Civil Service system. Therefore judge positions are often said to be dual status as state officials and civil servants. Nullifying the dual status is, in fact has caused serious problems in terms of both managerial and related to the potential reduction of judicial independence. If the independence start to reduce, the implications of the problems of the post of Judge is hampering efforts to realize the vision of the Supreme Court which is to realize the Supreme Courts. Keywords : Supreme Court Vision, Acts, and Official state of Judges Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Ridwan Mansyur KETEBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 83-100 Sebagai lembaga publik dibidang peradilan, Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dalam konteks transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kata kunci : Keterbukaan Informasi, Peradilan, Integritas dan Kepastian Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Ridwan Mansyur INFORMATION TRANSPARENCY IN THE COURT IN ORDER TO IMPLEMENT INTEGRITY IMPLEMENTATION AND LEGAL CERTAINTY Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 83-100 As a public institution in the field of justice, the Supreme Court is required to commit to apply the disclosure of information. Nowadays, transparency of information disclosure in the context of justice for the Supreme Court is not only the public needs but also the needs of all residents of the judiciary. With the judicial transparency, will slowly happen to strengthen accountability and professionalism and integrity of the judiciary residents. Commitment to provide disclosure of both the process and the end result is a concrete manifestation of public services as access to justice (access to justice) given by the Court at the lowest levels up to the Supreme Court. Quality of excellent public services through the transparency of the judicial information disclosure is the estuary of execution Reform of Bureaucracy. Keywords : Information Transparency, Judicial, Integrity and Legal Certainty Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Lilik Mulyadi ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA ANTI KORUPSI 2003 Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 101-132 Artikel ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003. Terdapat 2 pertanyaan mendasar yang menjadi obyek penelitian, pertama: sejauh mana pergeseran beban pembuktian telah dilaksanakan di pengadilan pidana tentang kasus korupsi, dan kedua, untuk sejauh mana kebijakan legislasi berlaku untuk pergeseran beban pembuktian dalam kaitannya dengan UNCAC 2003. Artikel ini menggunakan penelitian normatif berupa regulasi, konseptual, kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian tersebut menekankan interpretasi dan konstruksi hukum untuk memperoleh beberapa norma hukum, konsepsi, daftar peraturan dan implementasinya dalam kasus nyata. Peraturan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui, keberadaan, konsistensi dan harmonisasi mengenai pergeseran beban pembuktian atas tindak pidana korupsi dalam tubuh Undang-Undang. Pendekatan kasus menggunakan perbandingan hukum mengenai beban pembalikan pembuktian atas korupsi offencer antara Indonesia dan negara-negara lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian tidak pernah diterapkan untuk kasus korupsi di Indonesia. Pengalaman mereka tidak sama dengan pengalaman melawan korupsi di Hong Kong dan India, yang menerapkan beban pembalikan pembuktian dengan menggunakan beberapa pendekatan yang disebut probabilitas seimbang prinsip dalam kaitannya dengan properti atau aset yang berasal dari terdakwa. Kebijakan regulasi korupsi Indonesia, khususnya pasal 12B, 37, 37A, 38B ternyata itu tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pungutan langsung warisan pergeseran beban formulasi bukti sehubungan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Jadi, diperlukan (kebutuhan) dari modifikasi biaya pergeseran beban pembuktian formulasi yang preventif, represif dan restoratif. Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Hukum Pidana Indonesia Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Lilik Mulyadi THE REVERE BURDEN OF PROOF AGAINST CORRUPTION LAW IN INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM RELATED WITH THE 2003 UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 101-132 This article describes some problems of the result of research regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in the Indonesian system of criminal law with regards UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. There are two basic questions which become the research objections, firstly: to what extent the shifting of burden of proof has been implemented in the criminal court regarding corruption cases, and secondly, to what extent does the legislation policy apply for the shifting of burden of proof in relation with UNCAC 2003. The article uses normative research which regulation, conceptual, case and comparative approach. Such research emphasizes interpretation and legal construction to obtain some legal norms, conception, regulation list and its implementation in concreto cases. Regulation and conceptual approach to used how to know, existention, consistency and harmonization regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in legislation body. The cases approach uses comparative law regarding the reversal burden of proof upon corruption offencer between Indonesia and the other countries. This research shows that the shifting of burden of proof has never yet applied for in the corruption cases Indonesia. Those experiences is not similar with the experiences of against corruption Hong Kong and India, which implement the reversal burden of proof by using some approach so-called balanced probability of principles in the relation to the property or asset of defendant comes from. The Indonesian corruption regulation policy, especialy article 12B, 37, 37A, 38B apparently it’s not cleaq and disharmony to norm of sudden charge of fortune the shifting of burden of proof formulation in connection with United Nations Convention Against Corruption 2003 (KAK 2003). So, necessary (needs) of modification sudden charge of fortune shifting of burden of proof formulation which preventive, represive and restorative characteristic. Keywords : Shifting the Burden of Proof, Corruption Offences, Criminal Justice System Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Agus Budi Susilo MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 133-152 Dalam rangka melakukan tindakan hukum, pejabat publik sering melakukan tindakan di luar ketentuan hukum tertulis. Keadaan ini sebagai suatu konsekuensi logis, bahwa Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya seringkali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman, perubahan nilai, dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan kemajuan yang dicapainya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan “diskresi” sebagai sarana pengembangannya. Ironisnya, tidak jarang penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, justru mengorbankan hak-hak masyarakat baik secara individu pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Untuk mengantisipasinya, perlu ada konsep lain yang mengendalikan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, dan konsep tersebut adalah good governance, yang sering diartikan tata pemerintahan yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip utama dari tata pemerintahan yang baik itu sendiri, diharapkan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dapat diterapkan sesuai rel hukum (rechtmatigheid van regering). Kata kunci : Diskresi, Keputusan Pejabat Publik, Tata Pemerintahan yang Baik Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Agus Budi Susilo THE MEANING AND CRITERIA OF DISCRETION OF PUBLIC POLICY AND/OR ACT OF PUBLIC OFFICIALS IN GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 133-152 In order to do the legal action, public officials often execute out of written law, this condition is a logic consequence, that the acts and others written laws are left behind in anticipating the development of the era, the change of values, and increasing need of human life along with the progress that they have achieved in science and technology. Therefore, to make legality principle on operational stage can be done as good as it could, so the development instrument of the discretion is needed, ironically, not the rare things, the use of discretion sometimes misuse by public officials, pretending bases on public need and legal certainty in fact they abandon civil rights, either individually, in group or even civil corporate body. To anticipate it all, another draft is required to control the discretion of public policy and/or act of public officials, and that draft is good governance, which usually assume as good governance system. By understanding main principle from good governance itself, it’s hoped that the discretion of public policy and/or act of public officials can be applied together with code of conduct in law (rechtmatigheid van regering). Keywords : Discretion, Public Officials, Good Governance Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Budi Suhariyanto PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENANGANI PROBLEMA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 153-170 Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/ Pelanggar dibawah umur). Kata kunci : Diversi, Pelanggaran Lalu lintas, Pengadilan Budi Suhariyanto DIVERSION APPLICATION TO HANDLE PROBLEM INFRINGEMENT CASE SETTLEMENT TRAFFIC IN COURT Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 153-170 Basically cases of traffic violations is a matter of simple so categorized quick examination. However, when the volume of his case matters reach thousands of cases and should be heard in court within a day, in fact has given rise to problems. In addressing these problems, improvement of handling and settling disputes traffic violation in court is an absolute must do. But apart from that alternative settlement traffic violation outside the court, namely through the implementation of diversion should be used as an alternative way to reduce the caseload and problems in court. Functionally, the application of diversion used as part of the education and guidance systems and community protection systems (especially against children/Offenders under age). Keywords : Diversion, Traffic Violations, the Court Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Kata Kunci bersumber dari artikel lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Isnandar Syahputra Nasution PERAN PENGADILAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN SESUAI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 hlm. 171-188 Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ketiga hal tersebut adalah layanan pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan serta penyedian Posbakum Pengadilan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Posbakum ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Posbakum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. Kata kunci : Pengadilan, Bantuan Hukum, Orang Miskin Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Isnandar Syahputra Nasution URGENCY OF COURT ENROLLMENT IN GIVING A LEGAL AID SERVICE ON POOR PEOPLE BASED ON LAW NO. 16 YEAR 2011 ON LEGAL AID Journal of Law and Justice, Vol. 4 No. 1 page 171-188 Implementation of Legal Aid Post (Posbakum) by the District Court includes three (3) the scope of legal services in accordance with the provisions contained in the Perma No. 1 Year 2014. Those 3 scopes are services of fee waiver, and the holding of the trial outside the court building and providing Posbakum Court. In connection with the implementation of this Posbakum actually State Court only provides room facilities to Posbakum for three Legal Aid Provider or accredited lawyers organization. As for the legal aid fund handling each case will be filed by the Court through the Lokal Office of Kemenkumham. However, this does not mean that the facilitator function can be ignored, considering this Posbakum takes place in the Court, it is noteworthy that there is a special mandate from the State Officials to the Court in order to succeed the free legal services for the poor. Therefore, it can also be expected that the presence of the Posbakum in the Court can erode the negative and scary stigma on the Court for the general public. Keywords : Court, Legal Aid, the Poor TITIK SINGGUNG WEWENANG ANTARA MA DAN MK 1 (Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court) Moh. Mahfud MD Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2008-2013 Email : [email protected] Abstrak Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Agung (MA) baik dalam filosofi universalnya maupun dalam sejarah dan perdebatan partikularnya. Menjadi wajar jika dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa titik singgung kewenangan yang harus diselesaikan bukan saja secara akademis tetapi secara yuridis. Jika kewenangan-kewenangan MK itu dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan MA maka tampak ada persilangan kewewenangan antara kedua lembaga tersebut. MK mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun MA juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundangundangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Kata kunci: Titik Singgung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Abstract The existence of the Constitutional Court (MK) in Indonesia is linked to the Supreme Court (MA) both in the universal philosophy and in history and the particular debate. Being natural in practice found several points of authority tangency which must be resolved not only academically but in juridiction. If powers of the Constitutional Court was elaborated and then linked with the authority of the Supreme Court the authority then it appears there is a cross between the two institutions. The Constitutional Court judge rules conflict which is abstract at once judges conflicts (disputes) between the person or institution that is concrete. There is also the Supreme Court 1 Makalah untuk Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta. 1 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 also adjudicates conflicts (disputes) between people or institution that is concrete as well adjudicates conflicts between rules which are abstract. Here appears the cross testing authority in legislation between the Constitutional Court and the Supreme Court because they both have the authority to conduct testing, but to different degrees. Keywords: Connective Point, Supreme Court, Constitutional Court A. Mahkamah Konstitusi di Indonesia Ketika pada tahun 1945 melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) para pejuang kemerdekaan dan pendiri negara menyiapkan Rancangan Undang-Undang Dasar salah seorang anggotanya M. Yamin mengusulkan pemberian wewenang kepada lembaga yudikatif untuk menguji Undang-undang terhadap UUD. Tetapi usul Yamin tersebut tidak disetujui oleh anggota-anggota yang lain, seperti Soepomo, dengan alasan Indonesia tidak sama dengan negara Barat yang liberal, Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, dan pada saat itu Indonesia belum mempunyai ahli-ahli. Meski pada akhirnya BPUPKI menolak usul Yamin tetapi dari fakta historis terlihat bahwa pemikiran tentang adanya lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang judial review sudah ada sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Praktik peradilan ketataengaraan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun yang dibangun sebagai sistem tersendiri seperti di Austria tampaknya sudah menjadi referensi para ahli hukum yang ikut menjadi anggpota BPUPKI maupun pemikir-pemikir sesudahnya. Setelah Indonesia merdeka tuntutan pemberian wewenang judicial review kepada MA tidaklah surut. Daniel S. Lev mencatat bahwa pada tahun 1955 muncul ketidakpuasan para hakim karena gajinya kecil dan Parlemen menolak usul menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata tentang kenaikan gaji para hakim itu. Para hakim kemudian melakukan pemogokan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 1956 dengan menolak untuk melakukan pemeriksaan atas seluruh perkara. Kemudian, mengambil momentum terbentuknya Konstituante (berdasar hasil Pemilu 1955) para hakim ini menyampaikan keluhannya kepada Konstituante yang kala itu akan segera bekerja untuk menyiapkan konstitusi atau UUD yang baru. Mahkamah Agung yang tidak mendukung tindakan pemogokan ternyata mendukung penyampaian masalah oleh para hakim itu kepada Konstituante. Kepada Konstituante, dengan diwakili oleh beberapa hakim, para hakim itu mengajukan usul-usul yang perlu dimasukkan ke dalam Konstitusi terkait kekuasaan kehakiman. Di antara usul yang sangat penting adalah usul agar MA diberi kewenangan konstitusional untuk meninjau kembali semua Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Usul itu didukung oleh 2 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD Ketua MA Wirjono Prodjodikoro yang dalam forum pertemuan dengan Konstituante ikut menegaskan, “...dalam hemat kami, sangat diharapkan bahwa kondisi saat ini di Indonesia diubah sedemikian rupa, sehingga Mahkamah Agung (bukan pengadilan-pengadilan lain), mempunyai kekuasaan untuk menetapkan sebuah Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi”. 2 Semula usul para hakim ini diterima dengan beberapa penyempurnaan oleh Konstituante tetapi, seperti kita tahu, Konstituante sendiri tidak dapat merampungkan tugasnya membentuk Konstitusi baru karena dibubarkan melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama gagasan melembagakan judicial review atau pengujian UU oleh lembaga judicial muncul lagi ke permukaan. Pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto dihadapkan pada tuntutan-tuntutan penertiban hukum dan peraturan Perundang-undangan melalui pelembagaan judicial review. Tuntutan ini bisa masuk melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pada tahun 1968 Panitia Ad Hoc di MPRS menetapkan usul pemberlakuan pengujian UU terhadap UUD tetapi usul tersebut ditolak oleh Pemerintah. Namun karena gagasan pengujian UU itu terus bergelora maka pada tahun 1970 Pemerintah mengadopsi pengujian peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundangperundangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang; artinya judicial review bisa dilakukan untuk Peraturan Pemerintah ke bawah terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. UU tetap tidak bisa diuji sebab, secara politis, pemerintah khawatir kalau peluang itu dibuka akan banyak UU yang diuji ke MA sehingga bisa mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan. Ketentuan tersebut semula dimuat di dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk kemudian diperkuat di dalam Tap MPR No.IV/MPR/1973 dan Tap MPR No. III/MPR/1978. Pengaturannya mencakup tiga hal pokok: Pertama, Mahkamah Agung dapat menguji peraturan perundang-perundangan di bawah UU; Kedua, Pengujian itu dilakukan pada pemeriksaan di tingkat kasasi dan; Ketiga, peraturan Perundang-undangan yang terkena pengabulan pengujian dicabut sendiri oleh instansi yang mengeluarkannya, tidak langsung bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan yang demikian mengandung kerancuan yuridis sehingga tidak pernah bisa dilaksanakan sampai jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Kerancuan itu, antara lain, terletak pada ketentuan 2 Lihat dalam Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, hl. 46-49. 3 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 adanya pemeriksaan judicial review pada tingkat kasasi. Ketentuan tersebut menutup pintu bagi dilakukannya judicial review karena istilah kasasi merupakan istilah teknis-prosedural yang bersifat mendasar yakni pemeriksaan oleh Mahkamah Agung setelah ada putusan dari pengadilan di bawahnya. Dengan keharusan pemeriksaan melalui kasasi maka orang yang akan mengajukan gugatan ke MA tidak bisa karena istilah kasasi mengharuskan adanya putusan lebih dulu dari pengadilan di bawahnya; tetapi kalau akan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri lebih dulu tentu Pengadilan Negeri akan menolak karena menurut UU maupun menurut Tap MPR pemeriksaan judicial review itu menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung. Jadi pintu masuknya tidak ada. Distorsi lain adalah ketentuan bahwa peraturan Perundang-undangan yang terkena pengabulan pengujian hanya bisa dicabut sendiri oleh instansi yang mengeluarkannya. Soalnya, bagaimana jika instansi yang bersangkutan tidak mau mencabut peraturan Perundang-undangan yang pengujiannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Menghadapi problem yuridis yang seperti itu pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1993 yang membuka pintu pengajuan pengujian langsung ke Mahkamah Agung, tanpa harus melalui Pengadilan negeri meskipun peraturan dasarnya menyebut prosedur kasasi. Pengajuan judicial review menurut PERMA tersebut bisa dengan gugatan (melalui pengadilan di tingkat bawah) dan bisa dengan permohonan (langsung ke Mahkamah Agung). Tetapi pintu yang dibuka oleh Mahkamah Agung ini tidak pernah efektif, terbukti sampai jatuhnya pemerintahan Soeharto tahun 1998 belum pernah ada peraturan perundangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena judicial review. Barulah setelah jatuhnya rezim Orde Baru, tepatnya setelah kita masuk ke era reformasi pada tahun 1998, perjuangan memberlakukan judicial review terhadap UU dan peraturan-peraturan di bawahnya mendapat sambutan dan tempat yang layak. Pada saat itu sudah mulai muncul gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD. Langkah pertama dalam menampung gagasan tersebut adalah dikeluarkannya Tap MPR No. III/MPR/2000 yang salah satu isi pentingnya adalah pemberian wewenang kepada MPR untuk menguji UU terhadap UUD. Namun langkah itu kemudian diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD 1945 tahap ketiga, tahun 2001, dengan menempatkan pengaturannya di dalam Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen tersebut. Mahkamah Konstitusi ini diberi wewenang melakukan pengujian judisial tentang konstitusionalitas UU terhadap UUD disertai wewenang-wewenang lain sebagaimana diatur didalam Pasal 7B dan Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen. Diantara 4 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD latar belakang pemikiran tentang pembentukan dan pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: 1. Pada zaman Orde Baru banyak UU yang dinilai bertentangan dengan UUD atau melanggar hak-hak konstitusional warga negara tetapi tidak bisa dibatalkan melalui pengujian oleh pengadilan. UU hanya bisa diubah atau diperbaiki oleh legislatif melalui legislative review. 2. Pada masa lalu Presiden bisa dijatuhkan dari jabatannya hanya dengan keputusan politik, bukan berdasar putusan hukum, sehingga yang berlaku adalah dalil yang kuat dan menang bisa menjatuhkan atau bertahan. Timbul gagasan agar pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya harus melalui putusan pengadilan lebih dulu. 3. Pada masa lalu belum tersedia mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya, padahal potensi untuk terjadinya konflik dalam pelaksanaan tugas cukup besar. Pada masa lalu kekompakan antar lembaga negara hanya bertopang pada kewibawaan Presiden Soeharto. 4. Pada masa lalu pembubaran partai politik oleh pemerintah tidak pernah melalui putusan pengadilan. Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia hanya dengan Penetapan Presiden No.4/PNPS/1960 sedangkan Presiden Soeharto memaksa dilakukannya fusi parpol-parpol untuk kemudian dimasukkan di dalam UU No. 3 Tahun 1975. Ada ide, partai politik hanya bisa dibubarkan melalui putusan Pengadilan atau karena membubarkan diri karena keputusan internal. 5. Pada masa lalu pemilu dilaksanakan dengan penuh kecurangan tetapi tidak ada peradilan yang efektif untuk mengadili agar pemilu bisa terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Idenya, untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil harus ada lembaga pengadilan yang bisa mengadili pemilu dengan efektif. Hal-hal itulah yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia melalui amandemen ketiga UUD 1945. Semula ada pemikiran alternatif agar kekuasaan kehakiman di Indonesia tetap berada di satu poros yaitu Mahkamah Agung sehingga masalah-masalah tersebut dijadikan kewenangan Mahkamah Agung. Tetapi pada saat itu lebih kuat pemikiran tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai poros baru kekuasaan kehakiman, apalagi Mahkamah Agung sendiri mengisyaratkan kurang setuju jika hal-hal tersebut dijadikan kewenangan Mahkamah Agung. Mengingat tugasnya yang begitu berat dan tumpukan perkara yang begitu besar maka saat itu Mahkamah Agung lebih setuju dibentuk Mahkamah Konstitusi dan dirinya hanya bersedia melanjutkan untuk 5 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 melakukan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di berbagai negara pun pemberian kewenangan pengujian UU tidak seragam, ada yang digabung dengan kewenangan MK dan ada yang diberikan kepada lembaga yang berdiri sendiri. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Konstinental kewenangan pengujian UU dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi di Autria, Jerman, Turki dan beberapa negara di kawasan Anglo Saxon kewenangan pengujian dilakukan oleh MK yang dibentuk sebagai lembaga yudikatif tersendiri. Di Inggris lembaga yudikatif tidak diberi wewenang menguji UU dengan alasan di negara tersebut berlaku supremasi parlemen sehingga tidak boleh ada lembaga yang bisa menguji produk hukum yang dibuat oleh Parlemen. Menjadi jelas bahwa di Indonesia keberadaan Mahkamah Konstitusi mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Agung baik dalam filosofi universalnya maupun dalam sejarah dan perdebatan partikularnya. Oleh sebab itu menjadi wajar jika dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa titik singgung kewenangan yang harus diselesaikan bukan saja secara akademis tetapi secara yuridis. B. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Banyak yang diperdebatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang fungsi dan berbagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi hasil perdebatan tersebut dikerucutkan pada kesepakatan yang kemudian dituangkan di dalam Passal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 yang membedakan tugas MK ke dalam kewenangan dan kewajiban. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 MK mempunyai empat kewenangan sedangkan menurut Pasal 7B Ayat (1) MK mempunyai satu kewajiban. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan empat kewenangan MK adalah: (1) menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD; (2) mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) membubarkan partai politik; (4) mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK diatur di dalam Pasal 24C Ayat (2) dan Pasal 7B Ayat (1) yakni memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 24C Ayat (2)] dan/atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B Ayat (1)]. Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD, baik pengujian materiil maupun pengujian formal, yang diajukan ke MK biasanya disebut judicial review, sedangkan permintaan putusan atas pendapat DPR yang diajukan ke MK bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum tertentu atau tak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden/Wapres dalam praktik 6 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD sehari-hari disebut sebagai impeachment (pendakwaan) yang bisa dijadikan alasan untuk pemakzulan. Berikut ini hal-hal yang dapat didiskusikan terkait dengan titik singgung kewenangan antara MA dan MK. Sejauh menyangkut kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD ada beberapa hal yang perlu diberi catatan dalam konteks titik singgung wewenang antara MA dan MK yaitu soal kewenangan pengujian yang bersifat silang, kekuatan mengikat vonis MK, keluhan konstitusional (constitutional complaint), dan pertanyaan konstitusional (constitutional question). C. Kewenangan Linear dan Silang Seperti diketahui pada saat MK akan dibentuk telah terjadi perdebatan tajam terkait dengan dasar filosofis maupun yuridis Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengkristal dengan pengaturan dalam Pasal 24C UUD 1945. Jika kewenangan-kewenangan MK itu dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan MA maka tampak ada persilangan kewewenangan antara kedua lembaga tersebut. MK mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun MA juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. Kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD adalah kewenangan mengadili konflik peraturan sedangkan kewenangan lainnya adalah kewenangan-kewenangan dalam mengadili konflik antar orang dan atau lembaga. Pada sisi lain kewenangan MA dalam menguji peraturan Perundangundangan di bawah UU terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi adalah kewenangan mengadili konflik peraturan sedangkan kewenangan lainnya adalah mengadili konflik antar orang dan atau antar lembaga. Seperti diketahui berdasar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 pada saat berlangsung perdebatan di MPR tentang wewenang pengujian UU oleh lembaga yudikatif pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD dilakukan oleh MK sedangkan pengujian legalitas3 peraturan Perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan oleh MA. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundang-undangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda. 3 Saya berpendapat bahwa pengujian UU terhadap UUD adalah menguji konstitusionalitas sedangkan pengujian peraturan Perundangan-undangan di bawah UU terhadap peraturan yang lebih tinggi merupakan pengujian legalitas. 7 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 Secara akademis, mungkin perlu dipikirkan agar pengujian semua peraturan Perundang-undangan mulai dari UU sampai pada hierarki terbawah disatukan di bawah MK secara linear, tidak lagi bersilangan. Hal ini penting agar ada jaminan konsistensi penuangan pemikiran konstitusional ke dalam semua tingkat peraturan Perundang-undangan dari satu lembaga penafsir konstitusi. Ada pun sebagian dari kewenangankewenangan MK yang menyangkut konflik antar orang dan atau lembaga bisa dipindahkan ke MA. Kewenangan MK yang bisa dialihkan ke MA, misalnya, kewenangan membubarkan partai politik, kewenangan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. D. Kekuatan Vonis MK terhadap MA Seperti dikemukakan di atas, putusan MK dalam pengujian UU adalah sama kuat daya ikatnya dengan UU. Bahkan Hans Kelsen mengatakan bahwa Parlemen (dan lembaga legislatif) sama-sama membuat UU atau menjadi legislator yang membuat hukum yang setingkat dengan UU. Bedanya, Parlemen atau lembaga legislatif merupakan positive legislator sedangkan MK merupakan negative legislator. Oleh sebab itu dalam membuat putusan-putusan atas perkara yang ditanganinya MA juga terikat dan harus berpedoman pada putusan-putusan MK dalam perkara pengujian Undang-Undang. Dalam memutus perkara tentu saja MA harus berpedoman pada ketentuan UU dan putusan-putusan MK tentang judicial review. Selain itu di dalam UU tentang MK diatur bahwa apabila ada pengujian suatu UU maka MK harus memberitahukan kepada MA agar bisa mengetahui bahwa sedang ada yang mempersoalkan suatu UU. Bahkan ditentukan juga bahwa MK harus menunda pemeriksaan permohonan judicial review tentang satu peraturan Perundang-undangan di bawah UU apabila batu uji untuk permintaan judicial review ke MA itu adalah UU yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal, misalnya, ada Peraturan Pemerintah yang diuji karena bertentangan dengan UU X padahal UU X itu sedang diuji di MK maka MA harus menunda pemeriksaan permohonan judicial review itu untuk menunggu vonis MK tentang UU itu. Maka menjadi lebih penting untuk diperhatikan bahwa semua vonis pengujian atas UU yang telah dikeluarkan MK berlaku sebagai UU yang juga harus dipedomani oleh MA, MK sendiri, dan lembaga-lembaga negara lainnya serta masyarakat pada umumnya.4 4 Sekedar catatan MA pernah memutus tenaga kesehatan dengan pasal UU yang telah dibatalkan oleh MK, tanpa sedikit pun menyinggung vonis MK. MA juga pernah menjatuhkan putusan menghukum pencabutan hak politik kepada koruptor tanpa sedikit 8 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD E. Keluhan Konstitutional (Constitutional Complaint) Di dunia akademis pada pada awal tahun 2010 muncul gagasan agar MK diberi kewenangan mengadili perkara keluhan konstitutional atau constitutional complaint seperti yang berlaku di beberapa negara, misalnya di Jerman. Constitutional complaint adalah pernyataan seseorang atau sekelompok orang yang menolak perlakuan pemerintah yang telah melakukan pelanggaran hak konstitusional tetapi tidak tersedia baginya upaya hukum yang wajar. Dapat juga dikatakan bahwa constitutional complaint adalah pengaduan konstitusional oleh seseorang yang nyata-nyata dirugikan secara hukum tetapi tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh karena vonis pengadilan sudah selesai dan final sampai tingkat MA tetapi tak bisa dilaksanakan atau nyata-nyata mengandung kesalahan dalam pembuatannya. Dalam hal ini bisa dicontohkan ada vonis pengadilan yang sudah final dan memerintahkan aparat pemerintah tertentu untuk menyerahkan tanah yang ternyata bukan haknya kepada seseorang yang berhak secara hukum. Tetapi hal itu tidak dapat dieksekusi karena tanahnya sudah berpindah tangan beberapa kali, atau, tanahnya sudah tidak dikenali lagi batas-batasnya karena diatutup oleh bangunan besar yang mencakup banyak pemilik dan para pemilik tersebut sesudah berganti-ganti. Dalam keadaan sangat sulit seperti itu, di negara-negara yang MK-nya mempunyai kewenangan mengadili constitutional complaint, MK bisa memeriksa pengaduan itu dan membuat putusan atau perintah yang dapat menjadi jalan keluar untuk memenuhi hak konstitusional pengadu. Kasus seperti ini saat ini sangat banyak di Indonesia. Banyak vonis pengadilan yang tidak bisa dieksekusi baik karena kerumitan keadaan obyek vonis maupun karena kesengajaan aparat pemerintah untuk menolak melaksanakan vonis pengadilan. Penyebab lain yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan constitutional complaint adalah adanya vonis yang final tetapi setelah itu ternyata ada kesalahan dalam pembuatan vonis yang final itu. Ketika salah seorang hakim MK diadili dan dihukum karena korupsi muncullah tudingan-tudingan bahwa banyak vonis di MK yang dibuat secara salah atau dibuat karena penyuapan. Tetapi tidak ada jalan hukum untuk mengatasi masalah tersebut karena kita tidak mengenal constitutional complaint. pun menyinggung bahwa MK sudah membuat putusan tentang pencabutan hak politik yang berlaku selama 5 tahun sejak narapidana keluar dari penjara dan setelah itu dibolehkan menggunakan hak politik (dipilih) dalam jabatan-jabatan yang dipilih dan bukan dalam jabatan-jataban yang diangkat (political appointee). Saya menduga majelis hakim MA yang memutus kasus-kasus ini tidak mendapat informasi bahwa sudah ada vonis MK yang terkait dengan itu. 9 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 Contoh lain yang terkait dengan ini adalah permohonan pengujian oleh Polycarpus Budihari tentang konstitusionalitas Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, ”... Pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali”. Berdasar ketentuan tersebut pada pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh kejaksaan Polycapus Budihari dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman majelis hakim kasasi. Menurut Polycarpus pemeriksaan dan putusan PK itu bertentangan dengan Pasal 263 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa “PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya”. Oleh karena dirinya dihukum atas pemohonan PK yang diajukan oleh jaksa maka Polycarpus berdalil bahwa MA telah salah menerapkan KUHAP dan dia mengajukan pengujian pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tersebut ke MK. Tentu saja MK menolak permohonan Polycarpus sebab bunyi pasal yang dimintakan pengujian itu sudah jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalaulah vonis MA itu dianggap salah maka yang salah bukanlah isi UU yang diuji melainkan salah dalam penerapannya. Jika benar salah dalam penerapan maka hal itu pun bukan menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya, sebab MK hanya menguji isi UU dan bukan mengadili penerapan UU. Problemnya, Polycarpus merasa diputus dengan hukum acara yang salah, padahal putusan itu sangat merugikan dan sudah final. Di Indonesia kasus-kasus seperti ini belum bisa diselesaiakan secara hukum di pengadilan karena pengadilan kita tidak atau belum mengenal pengaduan konstitusional atau constitutional complaint. Oleh sebab itu perlu juga dipikirkan pemberian kewenangan mengadili constitutional complaint ini di dalam hukum peradilan kita sebab dalam faktanya banyak putusan pengadilan baik dari lingkungan MA maupun di lingkungan MK yang sudah final tetapi bermasalah dan tidak ada upaya hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikannya. F. Pertanyaan Konstitusional (Constitutional Question) Selain constitutional complaint dalam cakupan kompetensi MK yang terkait dengan kompetensi pengadilan umum di lingkungan Mahkamah Agung ada juga gagasan tentang constitutional question. Secara umum constitutional question sebenarnya merujuk pada semua persoalan konstitusi yang penyelesaiannya menjadi cakupan atau masuk dalam wilayah kewenangan MK untuk menyelesaikan atau memberikan jawabannya. Tetapi secara spesifik constitutional question adalah upaya seorang hakim untuk mencari kepastian kosntitusionalitas UU kepada MK atas perkara 10 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD yang sedang diadilinya berhubung sang hakim ragu apakah UU yang akan menjadi dasar putusan perkara tersebut konstitusional atau tidak. Misalnya seorang hakim sedang menangani kasus kejahatan melalui media sosial dengan menggunakan pasal tertentu dari UU Informasi Teknologi dan Elektronik namun sang hakim ragu apakah pasal UU tersebut konstitusional atau tidak. Dalam keadaan ragu seperti itu maka sang hakim mengajukan pertanyaan kepada MK dan selama MK belum menjawab pertanyaan tersebut maka sang hakim menunda pemeriksaan perkara yang ditanganinya. Itulah yang disebut constitutional question. Dalam banyak kasus di Indonesia sering kali terdengar adanya penilaian terhadap UU yang dipergunakan di pengadilan-pengadilan di lingkungan MA bahwa UU yang dijadikan dasar untuk memutus adalah UU yang memuat substansi yang inkonstitusional atau sekurang-kurangnya konstitusionalitasnya masih dipersoalkan. Penggunaan pasal-pasal KUH Pidana misalnya sering kali dituding sebagai penggunaan UU zaman kolonial yang bertentangan dengan konstitusi. Contoh lain, misalnya, penerapan status keagamaan seseorang dalam bidang perkawinan yang banyak dianggap inkonstitusional. Akan menjadi lebih baiklah penguatan kehidupan konstitusional kita manakala peluang memastikan konstitusionalitas suatu UU melalui pengajuan constitutional question oleh hakim kepada MK dapat dimasukkan di dalam cakupan kewenangan MK. Pembukaan peluang hukum untuk mekanisme constitutional question dapat melengkapi mekanisme judicial review sebab pada dasarnya constitutional question itu merupakan bagian dari judicial review. Constitutional question sebenarnya merupakan judicial review tetapi dasar dan caranya bersifat lebih halus. Jika judicial review diajukan oleh warga negara atau sekelompok orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya suatu UU maka constitutional question diajukan oleh hakim pengadilan di luar MK yang merasa ragu atas konstitusionalitas UU yang akan dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara yang sedang ditanganinya sehingg perlu beranya lebih dulu kepada MK. G. Impeachment (Pendakwaan) terhadap Presiden/Wapres Salah satu hal penting yang juga terkait dengan titik singgung antara kewenangan MA dan kewenangan MK adalah kewenangan MK untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sehingga dapat diberhentikan (dimakzulkan) dalam masa jabatannya. Pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum atau tidak memenuhinya syarat lagi Presiden dan/atau 11 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 Wakil Presiden yang oleh DPR diajukan ke MK untuk diputus biasanya disebut impeachment atau pendakwaan sebagai langkah untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih dalam jabatannya. Seperti diketahui DPR dapat mengajukan impeachment atau meminta putusan MK atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan tindakan tercela; kemudian ditambah satu hal lagi yang tidak spesifik merupakan pelanggaran hukum yakni “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” seperti yang diatur di dalam Pasal 7B Ayat (2) UUD 1945. Persoalannya, jenis-jenis pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pendakwaan (impeachment) itu adalah pelanggaran hukum pidana yang secara umum menjadi kompetensi peradilan pidana dengan segala hukum acara dan tahap-tahap yang panjang mulai dari Pengadilan Negeri sampai pada kasasi, bahkan Peninjauan Kembali, di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah putusan MK tentang impeachment karena pelanggaran hukum pidana itu bisa langsung dilakukan oleh MK ataukah harus melalui peradilan pidana dulu di lingkungan MA? Ada dua persoalan terkait dengan ini. Pertama, kalau harus diadili dulu melalui peradilan pidana waktunya akan sangat lama pada hal tujuan akhir dari pendakwaan yakni pemberhentian dalam masa jabatan dibatasi oleh waktu. Bagi MK sendiri kalau harus menunggu peradilan pidana lebih dulu menjadi tidak logis karena dalam memutus pendapat DPR tentang pendakwaan itu MK pun dibatasi oleh waktu, tidak lebih dari 60 hari. Kedua, jika pelanggaran pidana itu tidak diputuskan oleh peradilan pidana lebih dulu maka timbul persoalan, karena pada umumnya tidaklah tepat jika pembuatan pidana tidak diadili oleh peradilan pidana. Sementara ini MK sendiri berpendapat bahwa pelanggaranpelanggaran hukum yang dijadikan dasar impeachment bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak perlu diadili lebih dulu oleh peradilan pidana melainkan langsung diadili oleh MK sebagai kasus khusus pidana ketatanegaraan. Hal ini dituangkan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Secara lebih jelas ada minimal tiga alasan, mengapa MK mengatur bahwa pemeriksaan pendakwaan atau impeachment terhadap Presiden/ Wakil Presiden dapat langsung dilakukan oleh MK dan tidak harus didahului oleh pengadilan pidana di lingkungan MA. Pertama, kewenangan 12 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD MK tersebut merupakan kewenangan absolut yang diberikan langsung oleh konstitusi dalam perkara hukum tata negara. Kedua, pelanggaranpelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana dalam kaitan ketatanegaraan yang penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang pendek sehingga menjadi tidak mungkin kalau harus melalui peradilan pidana yang memakan waktu panjang lebih dulu. Ketiga, kalau harus melalui peradilan pidana lebih dulu akan menjadi sangat rancu sebab akan timbul masalah, apakah MK bisa memutus secara berbeda dengan putusan peradilan pidana. Kalau putusan peradilan pidana sudah final dan tak bisa diputus lain oleh MK, lalu untuk apa MK diminta lagi memutus impeachment itu. Alasanalasan itulah yang mendasari pendirian MK dalam menetapkan bahwa pemeriksaan dan putusan MK atas pendakwaan atau impeachment yang diajukan oleh DPR tidak perlu menunggu atau didahului oleh peradilan pidana. Meskipun begitu, masalah titik singgung kewenangan antara MA dan MK dalam masalah ini masih perlu terus didiskusikan sampai ada pengaturan lebih tepat dan proporsional. H. Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilukada Persoalan kewenangan MK untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) juga mempunyai titik singgung dengan kewenangan MA sebab di dalam kenyataannya ada dua macam pengaturan pemilu. Ada pemilu yang diatur di dalam UUD 1945 yakni di dalam Pasal 22E Ayat (2) dan ada pemilu yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 (yang kemudian diubah dengan UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah. Pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 hanya mencakup “pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD” sedangkan pemilu yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 (dan UU No. 12 Tahun 2008) adalah pemilihan umum kepala daerah. Menurut putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur di dalam UU No.32 Tahun 2004 adalah termasuk rezim pemilu seperti yang dimaksud Pasal 22E UUD 1945 karena ia juga bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia dan diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Dalam perjalanan sejarahnya kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil pemilihan umum pernah mengalami perkembangan cakupan kompetensi. Semula, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu hanya mencakup Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Tetapi sejak tahun 2008 berdasar ketentuan Pasal 296C UU No.12 Tahun 2008 tentang 13 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kompetensi MK diperluas sampai mencakup kompetensi mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Tetapi berdasarkan Putusan MK No.97/PUU-XI/2014 tanggal 19 Mei 2014 ketentuan Pasal 296C UU No. 12 Tahun 2008 yang memberi kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah tersebut dinyatakan inkonstitusional dan MK menolak untuk melaksanakan wewenang mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2008 itu. MK hanya mau mengadili sengketa hasil pemilu untuk pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Meskipun demikian tak dapat diartikan bahwa MK telah mengubah pendiriannya bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu. Pemilihan kepala daerah secara langsung tetaplah pemilu sebagai dimaksud dalam konstitusi hanya saja tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud UUD 1945 sehingga pengadilannya pun tidak harus menjadi kompetensi MK. Oleh sebab itu tidaklah salah dan tetap konstitusional adanya apabila kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah dijadikan kewenangan MA. Melalui putusan No.97/PUU-XI/2004 itu MK tidak mengubah pendiriannya bahwa pemilu kepala daerah masuk dalam rezim pemilu. Melalui putusan tersebut MK hanya menyatakan pendirian bahwa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kompetensi MK untuk mengadilinya adalah pemilu untuk institusi-institusi yang disebut di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 sedangkan pemilu kepala daerah atau pemilu untuk jabatan lain (kalau ada) bukanlah menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya. Pendirian MK tentang pembedaan pengadilan perselisihan hasil pemilu untuk pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dan untuk pemilu kepala daerah ini sama sekali tidak bertentangan dengan gagasan perlunya penyatuan kewenangan pengujian peraturan Perundangundangan secara linear di bawah MK sebab filosofi dan obyeknya memang berbeda. Tidak seperti perselisihan hasil pemilu, pengujian peraturan Perundang-undangan oleh lembaga yudikatif itu memerlukan konsistensi penurunan ide dan prinsip konstitusi ke dalam semua peraturan Perundangundangan sampai pada hierarki yang terendah sehingga lebih terjamin jika diletakkan secara linear di bawah satu lembaga yudikatif. Daftar Pustaka Abdul Mukti Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press Jakarta, Citra Media, Yogyakarta, 2006. 14 Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK, Moh. Machfud MD Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995. CF Strong, Modern Political Constitution, The English Language Book Society, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1966. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1973. Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengjian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. KC Wheare, the Modern Constitutions, Oxford University Press. London, 1951. M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Prapantja, Jakarta, 1959. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1997 dan Rajagrafindo Persada, Jakarta, cet. VI, 2014. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES Jakarta (2006) dan PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES Jakarta, 2007 dan PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Moh. Mahfud MD dan kawan-kawan, Constitutional Question, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusionanal, Universitas Brawajiaya Press, Malang, 2010. Rita Triana Budiarti, Kontroversi Mahfud MD, di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerbit Konstitusi Pers (Konpres), Jakarta, 2013. Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif, Penjelajahan Satu Gagasan” dalam Majalah Newsletter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No. 59/2004. 15 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 1-16 16 TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1 (Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court) Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Email : [email protected] Abstrak Percampuran kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, muncullah persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan misalnya, meski Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan, namun dengan berbedanya jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang diuji, maka penafsiran peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dua lembaga tersebut mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab, validitas norma adalah bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, apapun putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan tersebut bersifat erga omnes, termasuk bagi hakim agung di Mahkamah Agung dan hakim-hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kata kunci : Wewenang, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Abstract The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court have the same right to test the legislation, but with different types and hierarchy of legislation being tested, then the interpretation of the rules of the legislation for which they were these institutions must be subject to a hierarchical system of laws and Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014. 1 17 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 regulations that apply. Therefore, the validity of the norm is derived from the legislation is higher. Moreover, any decision of the judicial review of the UUD, this decision is erga omnes, including for judges of the Supreme Court and judges of the court under the Supreme Court. Keywords : Authority, Constitutional Court, Supreme Court Pendahuluan Pascaperubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung (Supreme Court) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri2 yang secara umum diberi nama Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua mahkamah secara bersamaan. Diselenggarakannya satu cabang kekuasaan oleh dua institusi yang berbeda setidaknya akan menimbulkan dua dampak. Di satu sisi, kekuasaan tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif, di mana antara dua institusi pelaku kekuasaan sama-sama dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengalami persinggungan kewenangan yang dapat menimbulkan persoalan. Di lain sisi, pelaksanaan satu kekuasaan oleh dua atau beberapa institusi potensial terjadinya tumpang tindih kewenangan, atau setidak-tidaknya akan muncul pesinggungan kewenangan yang dapat berujung pada tidak efektifnya pelaksanaan kekuasaan dimaksud. Idealnya, pembagian kewenangan dalam rangka melakukan satu kekuasaan kepada dua institusi berbeda mesti diikuti dengan pemberian batas demarkasi kewenangan yang jelas. Dimana, kewenangan institusi yang satu dibedakan secara pasti dengan kewenangan lembaga yang lainnya. Sehubungan dengan itu, pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif secara konseptual dapat dibelah menjadi dua bagian, yaitu mahkamah sistem hukum (court of law) dan mahkamah keadilan (court of justice). Di mana, dengan pembelahan seperti itu diyakini akan 2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 201 18 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra mampu menghindari terjadinya benturan antar kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan pembelahan semacam itu, institusi pelaku kekuasaan kehakiman diidealkan akan fokus pada bidang kewenananganya masing-masing. Secara bersamaan, benturan dalam pelaksanaan kewenangan tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dihindari sedemikian rupa. Hanya saja, membaca desain yang ada, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan seperti itu pada saat munculnya ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, UUD 1945 tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah. Padahal, dari sudut pandang teoretik, kehadiran Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai mahkamah sistem hukum (court of law).3 Sedangkan Mahkamah Agung tetap dengan kedudukannya sebagai mahkamah keadilan (court of justice).4 Hanya saja, dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, MK tidak hanya bertindak sebagai court of law, melainkan juga court of justice, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara di lain pihak, Mahkamah Agung juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab, MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law terhadap peraturan Perundang-undangan meski dibatasi untuk peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang. Di mana berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Jika hendak menempatkan MA dan MK sebagai dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dengan persinggungan kewenangan yang sangat tipis, tentunya kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan sepenuhnya mesti diberikan kepada MK, sedangkan penyelesaian sengketa seperti sengketa hasil pemilihan umum sebagai bagian dari kerja court of justice sepenuhnya juga diserahkan kepada MA. Dengan pembagian kewenangan demikian tentunya persinggungan kewenangan yang potensial memunculkan masalah dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi. Pada kenyataannya, “percampuran” kewenangan antara MK dan MA telah menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, muncullah 3 Yuliandri, Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pascaamandemen UUD 1945, dalam Mohammad Fajrul Falaakh (Penyunting), Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 62 4 Ibid. 19 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Atas dasar itu pula muncul berbagai pertanyaan terkait persinggungan kewenangan dan jalan penyelesaiannya, terutama kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan (judicial review). Pertanyaan dimaksud adalah: Pertama, apakah ratio legis ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi? Kedua, dalam hal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyangkut tentang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa suatu Undang-Undang tidak sah karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah putusan tersebut secara juridis mengikat terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya? Ketiga, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan dalam suatu Undang-Undang, maka penafsiran manakah yang secara juridis harus dipedomani oleh pencari keadilan? Semua pertanyaan di atas akan dijawab menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian peraturan Perundang-undangan terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan MA dan MK dalam Judicial Review Sebagaimana disinggung sebelumnya, MA dan MK mempunyai kewenangan yang berbeda, namun kewenangan tersebut saling bersinggungan. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UndangUndang. Sementara itu, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MK berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, 20 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sesuai ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, MA berwenang untuk menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sementara berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar. Merujuk ketentuan tersebut, penggunaan wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan (judicial review) menjadi salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK. Hal itu sangat mungkin terjadi pada ketika seseorang mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang pada Mahkamah Agung. Dimana, pada saat bersamaan, Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian di Mahkamah Agung juga diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman yang pernah terjadi misalnya, pada Tahun 2009, Zainal Maarif dan kawan-kawan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 kepada Mahkamah Agung melalui Perkara Nomor 15 P/HUM/2009. Dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 22 huruf c dan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Ketentuan tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.5 Pada tanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terhadap perkara uji materil (judicial review) tersebut, di mana, MA menyatakan permohon dimaksud beralasan hukum dan dikabulkan.6 Sebab, Pasal 22 huruf c dan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dinilai bertentangan dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Akibat putusan tersebut, Partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 15.P/HUM/2009 terkait Pengujian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemiihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, hlm. 9 6 Ibid., hlm. 18 21 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 tidak akan dihitung sebagai suara sisa dan tidak akan mendapatkan perolehan kursi. Akibat putusan pengujian Peraturan KPU tersebut, sejumlah partai politik dan caleg7 mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 205 dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab, kedua ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut dianggap multitafsir, terutama dalam kaitannya untuk mengimplementasikan sistem proporsional yang dianut Undang-Undang Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.8 Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 dan Pasal 212 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)9 sepanjang dimaknai bahwa suara partai partai politik yang tidak memenuhi angka BPP tetap dihitung sebagai suara sisa dan diikutkan dalam pembagian perolehan kursi DPR dan DPRD. Pengalaman di atas menunjukkan bahwa hubungan kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan Perundang-undangan sangat rapat. Di mana, pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal itu merupakan konsekuensi dari sistem hierarkis peraturan Perundang-undangan Indonesia. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi sesuai konsep stufentheorie yang dibangun oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky. Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan, baik yang dimiliki MA maupun MK adalah dalam rangka mempertahankan dan menegakkan prinsip norma yang hierarkis tersebut.10 Dalam konsep hierarkis dimaksud, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundangundangan terdiri atas : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7 Partai Politik dan caleg dimaksud adalah : Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Ahmad Yani, Zainut Tauhid Sa’adi, Romahurmuziy, Machmud Yunus dan Muhammad Arwani Thomafi, semuanya caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, hlm. 1-2 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, hlm. 99 9 Ibid., hlm. 110 10 Maruarar Siahaan, Implementasi Putusan MK dalam Judicial Review, makalah, 21 Oktober 2014 22 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum dari tujuh jenis peraturan Perundang-undangan di atas adalah sesuai dengan hierarkinya masing-masing.11 Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat dipahami bahwa kekuatan hukum sebuah Undang-Undang adalah kesesuaiannya atau ketidakbertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Demikian juga dengan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, kekuatan hukum berlakunya tergantung pada kesesuaiannya dengan Undang-Undang. Sepanjang peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (yang puncaknya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi), maka peraturan tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebaliknya, apabila bertentangan, maka dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal itu juga dikuatkan dengan apa yang pernah dikemukan Alexander Hamilton, bahwa: a constitution is, in fact, and must be regarded by the judges as, a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain meaning as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body. If there should happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has seperior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or in other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the people to the intentions of their agents.12 Dalam kerangka hubungan hierakis antara peraturan Perundangundangan yang satu dengan yang lain inilah hubungan MA dan MK dibangun. Di mana, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 11 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12 James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, dalam The Federalist Papers, Mentor Book, The New American Library, 1961, hlm. 467 23 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 Dalam konteks ini, MK memiliki wewenang konstitusional untuk menafsirkan UUD 1945 dalam rangka menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang dalam rangka menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam hal ini, proses pengujian yang dilakukan MA akan sangat bergantung pada bagaimana panafsiran MK terhadap Undang-Undang Dasar dalam menguji Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dengan hubungan kewenangan yang seperti itu, ruang perbedaan pandangan antara MA dan MK terbuka lebar. Sebab, sangat mungkin terjadi kondisi di mana hakim agung dalam melakukan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak sejalan dengan penafsiran konstitusi oleh MK dalam menguji UndangUndang yang dijadikan MA sebagai batu uji. Secara normatif, persoalan tersebut sebetulnya terjawab dengan keberadaan Pasal 55 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 yang menyatakan, pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila UndangUndang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan ketentuan tersebut, hasil pengujian peraturan Perundangundangan oleh MA akan sangat bergantung pada hasil pengujian peraturan perundangundangan yang lebih tinggi oleh MK. Selain itu, sesuai ketentuan tersebut, kemungkinan terjadinya permasalahan antara putusan MA dengan putusan MK dalam pengujian peraturan Perundang-undangan dapat diatasi dengan merujuk pada pembagian kewenangan judicial review yang dimiliki dua mahkamah tersebut. Lingkup Keberlakuan Putusan Pengujian UU Oleh MK Dengan persinggungan kewenangan pengujian peraturan perundangundangan antara MA dan MK sebagaimana telah diulas sebelumnya, berikut akan diuraikan tentang daya berlaku dan daya jangkau putusan pengujian Undang-Undang yang dilakukan MK. Secara lebih khusus, apakah putusan MK tersebut secara yuridis juga mengikat terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut berhubungan erat dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sesuai ketentuan 24 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra tersebut, putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah final. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Dengan demikian, apabila MK melalui putusan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang menyatakan : materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejak saat itu, putusan tersebut bersifat final. Sehingga norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan. Pertanyaan selanjutnya, apakah putusan bersifat final tersebut hanya mengikat pembentuk Undang-Undang atau mengikat semua pihak, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung? Terkait siapa saja addresat putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Thomas Gawron dan Ralf Ragowski pernah mengemukan, in our view, it is important... to distinguish between effect of the court according to addresees and to look for specific arena of implementation... five main addressees, respectively arenas of implementation, can be distinguished : legislative arena, the judicial arena, the administrative arena, the arena involving associations and political parties, and the private arena involving establishments and citizens.13 Mengikuti pendapat Thomas Gawron di atas, addresat putusan pengujian peraturan Perundang-undangan adalah semua pihak (umum), di mana lembaga peradilan termasuk salah satunya. Sejalan dengan itu, Marurar Siahaan juga penah mengemukakan, putusan pengujian UndangUndang oleh hakim konstitusi sebagai negative legislator mengikat secara umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara. Akibatnya, semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan.14 Dengan demikian, sifat erga omnes putusan MK mengikat semua orang, termasuk pejabat dan otoritas 13 Thomas Gawron dan Ralf Ragowski, Constitutional Courts in Comparation, The US Supreme Courts and The German Federal Constitutional Court, Berghahn Books, New York Oxford, 2002, hlm. 242, dalam Maruarar Siahaan, Implementasi, hlm. 7 14 Maruarar Siahaan, Op.cit., hlm. 8 25 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 publik atau lembaga negara, oleh karenanya putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya.15 Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, Undang-Undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya.16 Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada Undang-Undang tertentu. Dalam konteks itu, jika Undang-Undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya. Daya keberlakuan putusan MK untuk umum seperti dijelaskan di atas juga dapat dikonfirmasi dengan daya jangkau keberlakuan sebuah Undang-Undang. Di mana, akibat hukum dari pengundangan satu undangundang berlaku sama dalam hal Undang-Undang atau bagian UndangUndang tersebut dibatalkan. Dalam arti, daya berlaku Undang-Undang berbanding lurus dengan daya jangkau ketidakberlakuannya. Dalam konteks itu, sebagai sebuah produk legislasi, Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum.17 Sebuah Undang-Undang berlaku untuk siapapun, baik warga negara maupun penyelenggara negara. Setiap Undang-Undang mesti dipatuhi oleh semua orang dan semua lembaga negara. Keberlakukan Undang-Undang tidak dipilah-pilah melainkan berlaku untuk semua. Dengan demikian, setiap peraturan Perundang-undangan dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang 18 atau semua pihak. Seiring dengan sifat keberlakuan Undang-Undang, maka pada saat Undang-Undang atau bagian dari Undang-Undang tersebut dibatalkan melalui proses pengujian Undang-Undang, maka ketidakberlakukan norma tersebut juga berlaku umum. Ketidakberlakuan Undang-Undang bukan hanya bagi Pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang, juga bukan hanya bagi pembentuk Undang-Undang semata, melainkan berlaku 15 Ibid., hlm. 15 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 195 17 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 18 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta hlm. 158 16 26 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra untuk semua pihak. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghilangkan keberlakuan sebuah norma di dalam Undang-Undang. Beda Penafsiran Terhadap Undang-Undang, Mana yang Diikuti? Sebagaimana disinggung di atas, disebabkan sama-sama memiliki kewenangan dalam menguji peraturan Perundang-undangan dan hanya berbeda dalam hal jenis peraturan yang diuji, perbedaan penafsiran antara MA dan MK akan sangat mungkin terjadi. Bila memang betul-betul terjadi, penafsiran manakah yang secara juridis harus dipedomani oleh pencari keadilan? Pertanyaan tersebut pada dasarnya dapat dijawab dengan sistem hierarki peraturan Perundang-undangan yang dianut dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana, MK diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sementara MA diberi kewenangan untuk menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undangundang. Perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini sangat mungkin terjadi ketika hendak menafsirkan Undang-Undang. Sebab, bagi MK undangundang merupakan objek yang diuji terhadap UUD 1945, sedangkan bagi MA Undang-Undang adalah batu uji untuk menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Apabila perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut benar-benar terjadi, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi. Dalam hal ini, sumber validitas penafsiran MK adalah konstitusi. Sementara sumber valitasi penafsiran MA adalah UndangUndang itu sendiri. MA sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan MK. Oleh karena itu, MA pun mesti tunduk pada penafsiran yang dilakukan MK terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian Undang-Undang tertentu. Secara konseptual, MK merupakan lembaga yang diberikan otoritas oleh konstitusi bertindak sebagai organ yang menjalankan pengawasan terhadap Undang-Undang, di mana lembaga ini dapat saja menghapus sepenuhnya Undang-Undang yang tidak konstitusional.19 Dalam kapasitas seperti itu, Bishop Hoadly sebagaimana dikutip Kelsen pernah mengatakan: 19 Hans Kelsen, Op,cit., hlm. 195 27 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 Whoever hath an absolute authority to interpret any written or spoken laws, it is he who is truly the law-giver to all intents and puposes, and not the person who first wrote or spoken them: a fortiori, whoever hath an absolute authority not only to interpret the Law, but to say what the Law is, is truly the Law-giver. (barangsiapa mempunyai wewenang absolut untuk menafsirkan hukum tertulis atau tidak tertulis, maka dialah orang yang sesungguhnya pemberi makna hukum kepada semua maksud dan tujuan hukum tersebut, dan bukan orang yang pertama kali menuliskannya atau mengucapkannya; lebih tegas lagi barangsiapa mempunyai wewenang absolut bukan hanya untuk menafsirkan hukum, tetapi juga untuk mendefenisikan hukum, maka dialah sesungguhnya pemberi makna hukum)20 Apabila pendapat tersebut disandingkan dengan norma Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan otoritas yang memiliki kewenangan konstitusional untuk bertindak sebagai penafsir konstitusi. Dalam konteks itu, MK merupakan lembaga yang sesungguhnya berwenang memberi makna terhadap UndangUndang sebagai hukum. Posisi MK sebagai penafsir konstitusi sekaligus sebagai lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, --di mana penafsiran MK-lah yang mesti dipedomani ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang)-, juga dikuatkan dengan keberadaan beberapa norma yang terdapat dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 53 Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Pasal 55 Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. 20 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, 1949, hlm. 153-154 28 Titik Singgung Wewenang MA dengan MK, Saldi Isra Pemberitahuan kepada MA tentang adanya permohonan pengujian Undang-Undang serta adanya kewajiban MA untuk menghentikan proses pengujian terhadap peraturan Perundang-undangan di bawah undangundang ketika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang diuji oleh MK menyiratkan dua hal pokok, yaitu: pertama, kewenangan pengujian peraturan Perundangundangan di bawah undangundang oleh MA tunduk pada sistem hierarki peraturan Perundang-undangan. Di mana, apabila Undang-Undang sebagai peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sedang diuji di MK, maka pengujian peraturan Perundang-undangan di bawahnya mesti dihentikan. Kedua, penafsiran Undang-Undang dalam rangka menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dilakukan MA mesti mengikuti penafsiran Undang-Undang sebagai peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dilakukan oleh MK. Penutup Sebagai catatan penutup, meski MA dan MK sama-sama memiliki wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan, namun dengan berbedanya jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang diuji, maka penafsiran peraturan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dua lembaga tersebut mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab, validitas norma adalah bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, apapun putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan tersebut bersifat erga omnes, termasuk bagi hakim agung di Mahkamah Agung dan hakimhakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 29 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30 30 FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY : ANTARA “ PERADILAN BEBAS” & “PERS YANG BEBAS” 1 (Freedom and Impartial of Judiciary : Between “Freedom of Judiciary” and “Freedom of The Press”) Indriyanto Seno Adji Guru Besar Hukum Pidana Pengajar Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum Email : Abstrak Kemerdekaan Pers yang dianut oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan aksentuasi dari sistem Libertarian Press yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Previlege Right Absolut dari Pers memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan –moral hazard- atas dasar Interest of justice atau national security atau for prevention of disorder or crime yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria Sub Judice Rule ataupun Disobeying a Court Order dari pranata Contempt of Court. suatu pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” serta telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers Libertarian) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara ethik norma maupun hukumnya. Kata kunci : Peradilan, Pers, Bebas Abstract Press of independence adopted by Law No. 40 of 1999 on the Press is an accentuation of the Libertarian Press system which requires the existence of 1 Seminar diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. dengan tema “Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial”, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, jam 09.00 - Selesai di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan No. 72, Jakarta 10120 . 31 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 a absolute total "freedom of pers" by putting all the legal consequences on the substance of its news through judicial institutions, without calls for criminalization forms of the press with all the reason and limitedly direction purpose. Absolute Privilege Right of the Press have signs that provide a limitation on -moral hazard- based on Interest of justice or national security or for the prevention of disorder or crime that can be issued by the judiciary as a form of Sub Judice Rule criteria or Disobeying a Court Order from Contempt of Court institutions. a proclamation which is a form of freedom of expression with the news that "prejudicial", even the news substance pose a "misleading conclusion and opinion" as well as has provided an opinion and conclusions that are misleading or incorrect and negative impact on the course of judicial proceedings and other parties broadly (as recognition of the Press Libertarian System) may be faced with a sense of responsibility of the press itself, either ethic norms and laws. Keywords : Judicial, Pers, Freedom Pendahuluan Kehendak suatu kebebasan pers (“A Freedom of the Press”) telah menjadi sesuatu kenyataan sejak memasuki Era Reformasi. Bila Era Orde Lama terkesan adanya suatu Power Approach (pendekatan kekuasaan) berupa tindakan prevensi yang membatasi kebebasan pers itu sendiri. Kilas balik Era Orde Baru, dengan UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers, melalui “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab” (“Free and Responsible Press”) sebagai karakter social responsibility, press seharusnya lebih menekankan pada Legal Approach (Pendekatan Hukum). 2 polar yaitu, yaitu polar pertama, pers bebas yang harus dimaknai sebagai larangan dilakukan tindakan prevensi, sedangkan pers yang bertanggung jawab sebagai polar kedua, untuk menyelesaikan berkaitan dengan pemberitaan pers melalui mekanisme hukum. Implementasi Pers Bebas dan Bertanggungjawab ini nyatanya berlainan dengan makna dan konsepnya, karena implementasinya merubah orientasi menjadi “pers bertanggung jawab” lebih ditempatkan sebagai polar pertama dan “bertanggungjawab” dilakukan dengan tindakan prevensi terhadap pers, sehingga polar “bebas” sama sekali tidak tampak dalam kehidupan ketatanegaraan dan pers di era orde baru, akibatnya makna dari pendekatan hukum menyerupai dengan pendekatan kekuasaan, yang membenarkan tindakan prevensi berupa sensor maupun breidel terhadap substansi pers . Kekuatan konsep libertarian ini muncul sejak Era Reformasi dengan disahkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, khususnya Pasal 2, istilah yang digunakan bukanlah “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab”, tetapi “Kemerdekaan Pers” (“Freedom of The Press”) sebagai 32 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji aksentuasi dari sistem libertarian yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Pada sistem Libertarian di era reformasi ini, tidak dikehendaki adanya tindakan prevensi dalam bentuk apapun, artinya polar kebebasan sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas – kebebasan total absolut - yang hanya tunduk pada Behavior Code atau Kode Etik Internal komunitas pers, yang dianggap berlainan dengan penyelesaian jalur hukum. Karakter antara sistem pers social responsibility dengan sistem pers libertarian memiliki kesamaan identitas, yaitu tunduk pada Syarat Limitatif (artinya, tidak diperkenankan membetuk atau menciptakan ketentuan-ketentuan yang justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri) dan Syarat Demokratis (artinya tidak diperkenakan melakukan pemidanaan terhadap pernyataan-pernyatan yang bersifat prive, seperti diatur dan yang masih berlaku pada Pasal 132 bis KUHP yang undemokratis sifatnya). Suasana eforia demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menempatkan era a Freedom of the Press ini memiliki keterkaitan dengan kehendak paralelitas adanya suatu a Freedom and Impartial Judiciary (Peradilan yang Bebas dan Tidak Berpihak). A Freedom of The Press menjadi salah satu karakter dari Social Power di Negara yang menganut Sistem Demokrasi dalam ketatanegarannya, selalin adanya Civil Society, begitu pula dengan bermunculan Supporting State Organ, yang lebih berfungsi sebagai kekuatan paralel yang dapat mengawasi kinerja Lembaga Negara Utama (Main State Organ) . Bagi Kekuasaan Peradilan, konsepsi ide yang berkembang secara universal mengenai perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak –suatu “freedom and impartial judiciary”– yang tentunya kehendak peradilan ini bebas dari segala sikap dan tindak maupun bentuk multiintervensi merupakan ide yang universal sifatnya. Kehendak progresif terhadap suatu freedom and impartial judiciary merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi Negara dan Masyarakat, baik yang mengenal sistem Hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, yang menyadari keberpijakan pada prinsip “Rule of Law”. 3 ciri khusus Negara Hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip “Rule of Law” (dalam pengertian yang lebih luas daripada Dicey), yaitu : 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang-bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan, 2) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, 3) peradilan yang bebas, tidak bersifat 33 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.2 Dengan demikian, tegas Oemar Seno Adji, ciri-ciri tersebut menunjukan bahwa ada persamaan prinsip yang diterapkan di semua negara-negara termasuk Amerika Serikat dibawah “Rule of Law”, terutama yang digariskan oleh International Commission of Jurisrt tersebut . Identitas persamaan fungsi dalam hal kebebasan fungsional, kebebasan dalam tugas peradilan dan teknis judisial, karenanya tidak memungkinkan pengaruh ekstra judisial terhadap peradilan merupakan persyaratan fundamental, karenanya adalah Mahkamah Agung sebagai top judicial institution menghendaki adanya suatu penghindaran peran ekstra judicial terhadap kekuasaannya yang secara historis justru menempatkan area ekstra judisial terhadap kebebasan peradilan yang mandiri. Pendekatan sejarah terhadap fungsi dan kewenangan peradilan, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak tanggung jawab peradilan, dilakukan segala cara, bentuk dan formulasi sehingga menempatkan makna kebebasan peradilan pada titik semu yang minimal, bahkan pola intervensi kekuasaan ekstra yudisial menghasilkan pola variatif pendekatannya, termasuk dengan secara tidak langsung memanfaatkan pola “pembentukan opini”, melalui “public opinion” sebagai “misleading opinion” melalui peran media, khususnya eksistensi kebebasan pers yang sangat luas di era reformasi ini. Disatu sisi, Kebebasan Pers dan Kebebasan Peradilan merupakan kekuasaan yang memiliki paralel yang seharusnya bermakna impartial, terpisah dan tidak dapat dimasuki oleh kepentingan manapun, baik kepentingan individu, kelompok, kekuatan politik maupun kekuasaan negara. Namun demikian disisi lain, Kebebasan Pers tanpa batas seringkali justru menimbulkan inparalelitas dengan berjalannya Kebebasan Peradilan manakala adanya penyimpangan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial dengan melakukan pemberitaan yang “misleading opinion”, baik yang mengarah bagi pembentukan opini maupun penyimpangan opini, yang secara tidak langsung berdampak aksentuasi pada kesan adanya intervensi quasi pada kehidupan Kebebasan Peradilan. Beberapa variasi dan metode terhadap intervensi yang tegas dan jelas maupun quasi sifatnya, telah berlangsung sejak era kemerdekaan bangsa dan negara ini, sampai pasca kemerdekaan maupun era reformasi ini sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan berikut ini. 2 Ibid, halaman 167. 34 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji A. Kebebasan Pers : Kearah “Misleading Opinion” & Peradilan Bebas Yang Quasi Dalam tataran sistem tata negara yang mengakui eksistensi demokrasi, suatu kebebasan berpendapat merupakan suatu syarat yang tak dapat dihindari lagi. Namun demikian, pendekatan demokratis terhadap kebebasan berpendapat tersebut tetap tidak diartikan sebagai pendekatan yang absolut. Apapun formulasi kebebasan yang bermakna absolut justru akan membahayakan kebebasan itu sendiri, karena itu kebebasan itu seringkali memberikan makna-makna pembatasan, meskipun pembatasan itu tidak dalam konteks meniadakan, tetapi sekedar memberikan makna kebebasan secara adequat, yaitu mencari keseimbangan antara kebebasan dengan perlindungan terhadap individu, masyarakat (termasuk keluarga) dan Negara, suatu “balances of freedom and protection”. Kebebasan yang adequat ini mengingatkan kita semua pada makna kebebasan pers di negara-negara Eropa Barat. Antara kebebasan pers dengan kebebasan berpendapat memiliki persamaan makna, yaitu suatu kebebasan yang berimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Convention on the Freedom of Information tahun 1985 di Roma yang adequat dengan perkembangan asas kebebasan berpendapat, tetap memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers, yaitu apabila pemberitaan pers yang secara substansial memuat: 3 a. National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum, seperti Bab I, II, V dari Buku II KUHP); b. Expression to war or to national, racial or religious hatred (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama); c. Incitement to violence and crime (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan, seperti Pasal 160, Pasal 161 KUHP); d. Attacks on founders of religion (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik “blasphemy”, seperti Pasal 156a KUHP); e. Public health and moral (kesehatan dan moral, seperti Pasal 281, Pasal 282 KUHP); f. Rights, honour and reputation of others (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat “delik penghinaan”, seperti pasal-pasal 154, 155, 156, 157, 207, 208, 310, 315 KUHP, walaupun sudah ada yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai “haatzaai artikelen”); 3 Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit : Erlangga. 1991, halaman 35. 35 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 g. Fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari “contempt of court”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP). Nampak tegas bahwa kebebasan pers dengan Sistem Libertarian-pun tidak menghendaki adanya suatu kebebasan pers yang sangat absolut, yang justru akan menimbulkan suatu tirani kekuasaan yang berkelebihan dan akan menghancurkan makna kebebasan tersebut. Memang tidaklah mudah menterjemahkan antara pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada pihak lain secara luas. Pemberitaan-pemberitaan yang substansial sebagai kekuatan atas kebebasan pers yang absolut mengandung suatu “misleading opinion” sebenarnya sebagai pengakuan kehidupan dari Sistem Pers Libertarian. Dipahami bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran Libertarian dengan Negative Freedom-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu Right to Lie (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “Trustworthy Source” (sumber terpercaya), Right to Vilify (Hak untuk mencemarkan nama baik), Right to Distort (Hak untuk Mengacaukan) maupun Right to Invade Privacy (Hak memasuki kehidupan pribadi). Di Inggris, seperti halnya di Indonesia, pers sangat memperoleh perlindungsan hukum dalam membuat suatu berita. Pers mempunyai “privilege right” untuk tidak menyebutkan sumber berita. Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya. Hak istimewa ini bersifat absolut, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaan, dan yang terpenting harus bersifat “fair and accurate”. Apabila berkaitan dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu: jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan. Andaikata aturan ini dilanggar, maka ia akan menghadapi masalah, bahkan akan ditelusuri “trustworthy source” yang memberikan informasi tersebut. Kasus klasik adalah “Admiralty Spy Case” mengenai pemberitaan yang menyesatkan dari 2 wartawan (Mulholland dan Foster) yang diberitakan melibatkan pejabat teras Angkatan Laut Inggris, yaitu Admiral Willian Vassal. Kedua wartawan menolak memberikan nama “sumber terpercaya” dan Pengadilan dengan tetap menghargai “privilege 36 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji right” wartawan, berpendapat bahwa Hakim adalah “the Person Entrusted” yang bertindak atas kepentingan masyarakat dan dengan alasan “Interest of Justice” maka wartawan seharusnya wajib menyebutkan sumber informasinya. Dengan penolakan tersebut, wartawan dikenakan hukuman penjara 6 bulan (Mulholland) dan 3 bulan (Foster) atas dasar pelanggaran “disobeying a court order” (tidak mematuhi perintah pengadilan) melalui keputusan dari Judge of Court Appeal oleh Lord Justice Denning, seorang Hakim Tinggi kharismatik dan dihormati di Inggris dengan mendasari Section 10 Contempt of Court Act 1981, yang menyatakan bahwa : “No Court has power to order a person to disclose, nor is any person guilty of contempt for refusing to disclose the source of any information contained a publication for which he is responsible, unless the court is satisfied that disclosure is necessary in the interest of justice or national security or for prevention of disorder or crime”. 4 Dapatlah dicermati bahwa Inggris dengan sistem Kebebasan Pers yang absolut masih memberikan rambu-rambu limitasi terhadap kebebasan melalui antara lain, lembaga Contempt of Court. Limitasi atas suatu kebebasan pers (absolut) didalam kebebasan pers yang seharusnya dianut oleh Negara Hukum dikemukakan oleh Oemar Seno Adji dinilai oleh seorang pakar Hukum Tata Negara Satya Arinanto sebagai karakteristikkarakteristik terbaik yang pernah dikemukakan oleh seorang ahli hukum pers hingga saat ini, yang dapat menggambarkan secara keseluruhan kondisi-kondisi ideal pelaksanaan konsep kebebasan pers yang seharusnya dianut oleh suatu Negara Hukum, yaitu: Kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari expression tadi, seperti dikemukakan oleh negara-negara sosialis, Ia tidak mengandung lembaga sensor preventif, Kebebasan ini bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya, Ia merupakan suatu kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu, dengan syarat limitatif dan demokratis, seperti diakui oleh Hukum Nasional, Hukum Internasional dan Ilmu Hukum, Kemerdekaan Pers ini dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban-kewajiban yang untuk pers sendiri disalurkan melalui “beroep ethiek” mereka, 4 Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji. Peradilan Bebas & Contempt of Court. Cetakan Kesatu. Jakarta. Penerbit: Diadit Media. 2007, Halaman 208-211. 37 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 Ia merupakan kemerdekaan yang disesuaikan dengan tugas pers yang sebagai kritik adalah negatif dalam karakternya, melainkan pula ia positif sifatnya, apabila ia menyampaikan “wettige initiatieven” dari Pemerintah, Aspek positif diatas tidak mengandung dan tidak membenarkan suatu konklusi bahwa posisinya adalah “subordinated” kepada penguasa politik, Adalah suatu kenyataan bahwa aspek positif ini jarang ditentukan oleh kaum Libertarian sebagai suatu unsur essentieel dalam persoalan masscommunication, Pernyataan bahwa pers itu tidak “subordinated” penguasa politik berarti bahwa konsep Authoritarian adalah tidak acceptable bagi pers Indoensia, Konsentrasi perusahan-perusahan pers, bentukan dari “chain” yang bisa merupakan ekspresi dari kapitalisme yang “ongebreideid” merupakan suatu hambatan yang “daadwerkelijk”, “feitelijk” dan ekonomis terhadap pelaksanaan ide kemerdekaan pers. Pemilihan suatu bentuk perusahaan, entah dalam bentuk co-partnership atau co-operative entah dalam bentuk lain, yang tidak memungkinkan timbulnya konsentrasi dari perusahaan pers dalam satu atau beberapa tangan saja adalah perlu, Kebebasan Pers dalam lingkungan batas limitatif dan demokratis, dengan menolak tindakan preventif adalah lazim dalam Negara Demokrasi dan karena itu tidak bertentangan dengan ide pers merdeka, Konsentrasi perusahaan-perusahaan yang membahayakan “performance” dari pers yang eksesif, kebebasan pers yang dirasakan berkelebih-lebihan dan seolah-olah memberikan hak kepada pers untuk misalnya membohong (the right to lie), mengotorkan nama orang (the right to vilify), the right to invade privacy, the right to distort dan lainlain, dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri. 5 Persyaratan doktrin dan konvensi internasional mengenai kebebasan informasi yang berkaitan dengan kebebasan pers ini merupakan rujukan dan basis yang menekankan bahwa suatu a freedom of the press dalam alam Libertarian itu, bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya, namun demikian tidaklah diperkenakan pelanggaran atas syarat limitatif dan demokratis dalam kehidupan pers tersebut . 5 Oemar Seno Adji. Pers: Aspek-Aspek Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1977. Halaman 96-97. 38 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji B. Intervensi Peradilan Bebas : Pengaruh Kekuasaan Negara – Pola Usia Pendekatan sejarah terhadap kebebasan peradilan menjadi wacana yang memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial, dan karenanya indikasi yang demikian merupakan karakterisasi dari negaranegara yang mengakui konsepsi “Rule of Law”, baik negara dengan sistem liberal, neo liberal maupun sosialis. Beberapa konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi-pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui adanya prinsip due process of law dan suatu acuan junjung tinggi prinsip “Rule of Law” tersebut. Suatu kehendak a freedom and impartial yudiciary harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim, sebagaimana ditegaskan Bagir Manan bahwa selain kondisi internal, martabat Hakim ditentukan juga oleh tatanan lingkungan yang menawarkan berbagai godaan yang dapat menurunkan martabatnya, yang karenanya tidak layak baginya menjadi hakim. 6 Beberapa sarana dan prasarana ekstra yudisial memberikan area peluang lembaga-lembaga non-yudisial untuk mempengaruhi idea konsepsi peradilan bebas, antara lain interelasi antara kewenangan Hak Asasi Manusia dengan segala implikasi terhadap polemik pola, cara ataupun bentuk intervensi terhadap peradilan bebas dan tidak memihak sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini . (1) Pola “Hak Uji Materil MA Terhadap UU” & Pola “Usia” Persoalan klasik tentang Judicial Review atau Materiele Toetsingsrecht (Hak Uji Materil atau "HUM") Mahkamah Agung (MA) terhadap Perundang-undangan mencuat kepermukaan lagi. Menengok kebelakang, saat Purwoto Gandasubrata (alm. mantan Ketua MA) menghendaki agar MA diberikan hak tersebut agar Hakim dapat mengambil keputusan yang lebih jernih dan melalui suatu kasus yang diperkarakan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum. Tidak tertinggal pula T. Mulya Lubis menginginkan agar Mahkamah Agung harus proaktif melakukan hal tersebut, sebaliknya Albert Hasibuan dan Oetojo Oesman (mantan Menteri Kehakiman) tidak menghendaki adanya HUM terhadap Perundang-undangan karena wewenang itu lebih sesuai diberikan kepada MPR (saat itu, dan sekarang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi) dengan cara lebih mengaktifkan Badan Pekerja MPR untuk menguji UU. 6 Bagir Manan. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian). Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung. 2005, halaman 51. 39 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 Saat itu, Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 (Kekuasaan Kehakiman) maupun Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 (Mahkamah Agung) memang mengatur pembatasan kewenangan HUM Mahkamah Agung hanya terhadap peraturan yang tingkatannya dibawah UU saja. Persoalannya sekarang adalah bagaimana implementasi HUM Mahkamah Agung terhadap UU yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya selama ini? Memang, penempatan secara kodifikasi tersebut membatasi HUM Mahkamah Agung hanya terhadap peraturan yang tingkatannya dibawah UU, namun tidak sedikit dalam implementasi praktik Mahkamah Agung telah melakukan HUM dengan mengadakan penyingkiran terhadap ketentuan UU yang tingkatannya adalah "wet" atau UU dalam arti formil. Pada era Soebekti (mantan Ketua MA) pernah melakukan judicial review terhadap UU yang dipandang sebagai pasal-pasal yang secara urgensif tidak sesuai dengan dinamisasi masyarakat dan melanggar asas keadilan, misalnya dalam lingkup hukum perdata melalui Pasal 284 ayat 3 (pengakuan anak), Pasal 108 (perbuatan perdata seorang istri) ataupun Pasal 1460 KUHPerdata (resiko jual beli) yang selanjutnya dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Pada bidang hukum pidana (formil), peran Adi Andojo Soetjipto (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung) melakukan HUM terhadap UU. No. 8 Tahun 1981 (Hukum Acara Pidana) yang muncul saat kasus tindak pidana korupsi R. Natalegawa (Bank Bumi Daya). Saat itu Adi Andojo Soetjipto membenarkan upaya Jaksa / Penuntut Umum mempergunakan upaya kasasi meskipun berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat kasasi, karena dipandang pasal ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sejak saat itu Pasal 244 KUHAP hampir dikatakan "mati" dalam praktiknya. Dari pengamatan tersebut, ternyata Mahkamah Agung telah sejak dahulu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan pengujian materil terhadap peraturan yang mempunyai tingkatan sama dengan UU (dalam arti formil), meskipun aturan menegaskan Mahkamah Agung tidak mempunyai HUM terhadap UU. Sarana yang dipergunakan Mahkamah Agung untuk melakukan HUM tersebut diatas adalah dengan wewenang dan fungsi justisial (putusan) dan legislatifnya (SEMA) dan kesemua pengujian itu dilakukan terhadap UU yang secara materil sudah tidak sesuai dengan dinamisasi masyarakat, begitu pula dengan hak uji materil terhadap UU, khususnya dalam penanganan kasus, khususnya UU (Pidana) yang isinya ternyata tidak demokratis dan melanggar hak mengeluarkan pendapat, meskipun terdapat akibatnya, berupa adanya bentuk quasi intervensi tersamar dari kekuasaan. 40 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji Dari pendekatan historis, Mahkamah Agung pernah melakukan pencabutan terhadap beberapa pasal yang masuk dalam kelompok "Haatzaai Artikelen" Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, yaitu Pasal 153 bis, Pasal 153 ter dan pasal 161 bis KUHPidana karena dipandang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mahkamah Agung, atas inisiatif Adi Andojo Soetjipto pun, pernah melakukan pengujian secara materil terhadap Pasal 160 KUHPidana (menghasut melakukan tindak pidana) dalam kasus Muchtar Pakpahan karena dipandang sebagai pasal kolonial dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat masa kini, meskipun pengujian itu akhirnya dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali dari Soerjono (saat itu Ketua Mahkamah Agung). Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan Mahakamh Agung dalam memberikan penafsiran, sekaligus pengujian atas UU (dalam arti formil) melalui penanganan kasus yang ada di hadapan Mahkamah Agung, akhirnya memiliki dampak pada lembaga kekuasaan kehakiman, yang tentunya sebagai bentuk cerminan dari Quasi Intervensi dari lembaga ekstra judisial, khususnya terhadap kasus-kasus yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik. Memang harus diakui, dalam praktik komparatif negara-negara berkembang yang mengakui adanya HUM Mahkamah Agung terhadap UU akan selalu menimbulkan "friksi politis". Contohnya, sewaktu Ketua Mahkamah Agung (saat itu) Oemar Seno Adji, memungkinkan melakukan HUM melalui metode “interpretasi” terhadap Perundang-undangan agar dapat sesuai dengan perkembangan dinamis dari masyarakat, meskipun polemik “interpretasi” saat itu, kebijakan Ketua Mahkamah Agung dipandang sebagai pola pengujian materil terhadap Undang-Undang. Dalam perkara MALARI, Pasal 270 KUHAP (Jaksa sebagai eksekutor putusan pidana yang berkekuatan tetap) secara substansial menjadi “noneksekutabel”, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan ekseksui berdasarkan Pasal 270 KUHAP karena dikeluarkannya “beleid” Ketua Mahkamah Agung agar para Terpidana perkara MALARI (Hariman Siregar cs) tidak perlu melaksanakan pidana, karena wajib menyelesaikan sisa studi, meski non-eksekutabel pasal 270 KUHAP hanya bersifat case by case basis, tetapi beleid Ketua Mahkamah Agung ini menimbulkan friksi diantara 2 kepentingan politis kekuasaan, eksekutif dan yudikatif. Friksi inilah yang menimbulkan “pola usia” sehingga terjadi pensiun dini karena dianggap “beleid” ini tidak mengabdi pada kekuasaan yang memiliki kepentingan politik tersendiri atas perkara MALARI tersebut. Pola usia yang kemudian memaknai pembatasan usia 65 tahun bagi Hakim Agung inilah sebagai hasil pengabdian usang dari “beleid” non-eksekutabel Ketua Mahkamah Agung atas perkara MALARI . 41 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 Ide progresif pembaruan peradilan harus didukung, namun tetap dihindari sentralitas patrimonial kekuasaan yang justru melanggar independensi lembaga Mahkamah Agung. The dangerous potential of judge’s recruitment is intervention of external institution. Ahsin Thohari mengutip pendapat F. Andrew Hassen bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu Negara, karena secara tehnis sistem perekrutan dan promosi Hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik didalamnya. Rekruitmen Hakim (Agung), termasuk pula promosi, eksaminasi, dan permasalahan usia memang memberikan arah peluang intervensi kekuasaan lembaga ekstra yudisial. Menilik sisi komparasi hukum, polemik atas pola rekruitmen maupun pola usia Hakim (Agung) merupakan lahan intervensi eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Era Marcos di Philipina, manakala Presiden Marcos menerbitkan Internal Security Act/ISA (sejenis UU Subversi), judicial review atas ISA ditolak Supreme Court. Atas “pengabdian” Mahkamah Agung ini, Pemerintah menerbitkan Martial Law (semacam PERPU) yang berisi perpanjangan usia Hakim Agung. Atas Martial Law ini, para pemutus ini memperoleh reward perpanjangan usia sebagai Hakim Agung. Sebaliknya di India ketika era Indira Gandhi menerbitkan UU Nasionalisasi Bank-Bank Asing. Judicial Review dikabulkan Supreme Court untuk menyatakan tidak sah UU tersebut. Atas sikap oposisinya yang tidak mengabdi kekuasaan, Pemerintah menerbitkan Martial Law yang berakibat Supreme Court memperoleh “punishment” berupa pensiun dini para pemutus sebagai Hakim Agung yang seharusnya memasuki usia pensiun masih 3 tahun kedepan . (2) Pola “Rekruitmen” Melalui Interelasi Lembaga Negara Independensi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu wacana yang imperatif sifatnya. Lord Elwyn-Jones (mantan Labour Lord Chancellor) mengkritisi intervensi prosesual dan substansial terhadap independency of judiciary dengan menyatakan bahwa in Nazi Europe and the Fascist countries before the War, the authoritarian regime’s first victims were the independence of the judiciary and the independence of the legal profession. Bahkan Lord Justice Dening, seorang Hakim Court of Appeal Inggeris yang kharismatis, menegaskan bahwa melewati 30 tahun integritas para Hakim have become increasingly cautious about what they have seen as assaults on their privileges and positions. The assaults were on the institution of the judiciary . Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi peradilan itu begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemas 42 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji dalam bentuk tahapan-tahapan prosesual pra-ajudikasi yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, kesemua ini memberikan arah seolah adanya suatu justifikasi yang berlindung di balik prinsip legalitas, bahkan kemasan ini dilakukan kemudian melalui regulasi dengan metode pola rekruitmen Mengutip ulang dari Ahsin Thohari mengutip pendapat F. Andrew Hassen bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu Negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi Hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik didalamnya. Rekruitmen Hakim (Agung), termasuk pula promosi, eksaminasi, dan permasalahan usia memang memberikan arah peluang intervensi kekuasaan lembaga ekstra yudisial. Hubungan antara Lembaga Negara sungguh pernah mengalami polemik yang substansial yang tidak dikehendaki terulang dihari kedepan nantinya. Betapa tidak, sebagai suatu ingatan yang lalu saja bahwa ide progresif Komisi Yudisial dengan alasan reformasi yudikatif menimbulkan pro-kontra, lebih-lebih manakala PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dijadikan sandaran arah legalitas. Ide melakukan reevaluasi melalui seleksi ulang para Hakim Agung Aktif merupakan bentuk ketidakpercayaan Komisi Yudisial terhadap institusi peradilan tertinggi di Indonesia, ada semacam resistensi Komisi Yudisial seolah sebagai representasi publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini. Disatu sisi, pengamat membenarkan ide Komisi Yudisial ini sebagai salah satu bentuk mosi tidak percaya kepada Mahkamah Agung sekaligus “pembersihan” terhadap Mahkamah Agung sebagai simbol institusi keadilan, tetapi pendapat lain menegaskan bahwa ide Komisi Yudisial justru menempatkan norma legislasi yang kontradiktif dan membentuk demoralisasi institusi peradilan tersebut. Tidak dipungkiri lagi, ide progresif Komisi Yudisial ini merupakan kepanjangan dari proses kasus suap lembaga Mahkamah Agung dalam perkara Probosutejo. Ketidak hadiran Ketua Mahkamah Agung atas panggilan Komisi Yudisial telah memicu “ketegangan” hubungan antara lembaga negara ini. Walaupun akhirnya tidak terwujud, ide Seleksi Ulang Hakim Agung Aktif dari Komisi Yudisial mendapat respon Presiden dengan “janji” memberi sandaran legalitas Perpu untuk merealisasikan ide tersebut. Salah satu pertimbangan tidak terealisasi Rancangan PERPU ini adalah kesan pola rekruitmen Hakim Agung Aktif sebagai bahagian intervesi quasi terhadap Lembaga Judisial Tertinggi di Indonesia . Harus selalu menjadi suatu ingatan, sebagaimana pernah dikatakan secara kritis oleh Denny Indrayana saat itu bahwa ide revolusioner adalah 43 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 yang berpotensi menimbulkan tabrakan lebih mematikan bagi prinsip independence of judiciary ke depan. Tidak mustahil, dimasa datang hadir rezim otoriter yang menjadikan rujukan atau preseden Perpu seleksi ulang hakim agung demikian untuk merombak susunan hakim agung yang tidak mengabdi pada kekuasaannya. 7 Bayangkan saja, andai putusan MA dianggap tidak mengabdi pada kekuasaan, saat itu pula dilakukan pemberhentian Hakim Agung dengan berlindung secara legalitas di balik Perpu melalui pola seleksi ulang. PERPU dapat dimanfaatkan oleh Kekuasaan politik, juga menjadi sarana kewenangan yang polemik oleh lembaga pemegang PERPU tersebut itu. C. Lembaga Contempt of Court sebagai Pranata ‘Safeguard’ Kebebasan Peradilan & Trial by the Press Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa salah satu rambu-rambu dari Kebebasan Pers adalah persoalan mengenai a fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari pranata “contempt of court”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP dan lain-lain), suatu pranata dari kebutuhan adanya “safeguard” bagi berlangsungnya a freedom and impartial judiciary yang sangat universal sifatnya. Berbagai komparasi praktik dan konsep pers bebas, Sistem Libertarian-pun tidak menghendaki adanya suatu kebebasan pers yang sangat absolut, yang justru akan menimbulkan suatu tirani kekuasaan yang berkelebihan dan akan menghancurkan makna kebebasan tersebut. Memang tidaklah mudah menterjemahkan antara pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada pihak lain secara luas. Pemberitaan-pemberitaan yang substansial sebagai kekuatan atas kebebasan pers yang absolut mengandung suatu “misleading opinion” sebenarnya sebagai pengakuan kehidupan dari Sistem Pers Libertarian. Dipahami bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran Libertarian dengan Negative Freedom-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu Right to Lie (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “Trustworthy Source” (sumber terpercaya), Right to Vilify (Hak untuk mencemarkan nama baik), Right to Distort (Hak untuk Mengacaukan) maupun Right to Invade Privacy (Hak memasuki kehidupan pribadi). 7 Denny Indrayana. Urgensi “Reshuffle” Hakim Agung. Kompas, 27 Januari 2006. 44 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji Di Inggris, seperti halnya di Indonesia, pers sangat memperoleh perlindungsan hukum dalam membuat suatu berita. Pers mempunyai “privilege right” untuk tidak menyebutkan sumber berita. Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya. Hak istimewa ini bersifat absolut, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaam, dan yang terpenting harus bersifat “fair and accurate”. Apabila berkaitan dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu: pertama, jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, kedua, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan. Kebutuhan akan tertibnya penyelenggaraan peradilan sesuai konsep due process of law di Indonesia, telah memberikan pengakuan legislatif terhadap eksistensi lembaga Contempt of Court sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu UU yang mengatur peniindakan terhadap perbuatan, tingkat laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”. Bahkan Rancangan KUHP telah menempatkan pranata Contempt of Court pada Bab VI (Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan) yang tercantum pada Pasal 326 sampai dengan Pasal 340 KUHP yang mencakup pendekatan doktrin terhadap makna Contempt of Court yang meliputi, antara lain perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pengadilan . Kriteria konstitutif ini sesuai doktrin yang mencakup perbuatanperbuatan merendahkan martabat peradilan, yaitu: Sub judice rule, suatu usaha untuk mempengartuhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan, Disobeying a court order, tidak mematuhi perintah peradilan, Obstructing justice, membikin gangguan/obstruksi peradilan, Scandalizing pengadilan, melanggar sopan santun di pengadilan Misbehaving in court, tidak berkelakukan baik dalam pengadilan Lembaga atau pranata ini akan memberikan jaminan penyelenggaraan peradilan yang baik dan sesuai aturan Undang-Undang, 45 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 dengan tetap memperhatikan doktrin, regulasi konstitutif maupun konvensi internasional tentang safeguard of free and impartial judiciary. Dalam keterkaitan antara perbuatan dalam lingkup Sub Judice Rule dengan Trial By the Press berkaitan dengan “misleading opinion”, surat kabar Daily Mirror (Inggris) yang memberikan komentar yang mengarah pada prejudice dari fair trial dengan memberi judul “Vampire Arrested”. Surat kabar ini dihukum denda 10 Ribu Pound dan editor dihukum pidana penjara 3 bulan. Hakim Lord Goddard dalam keputusannya menyatakan“: Let the Directors beware. If this sort of thing should happen again, they may find that the arm of the Law is strong enough to reach them too!”. 8 Semua ini menjelaskan bahwa pembentukan “misleading opinion” melalui peran media sebagai kekuatan sosial dari Freedom of the Press, tidaklah selalu bersifat total absolut, ia memiliki rambu-rambu hukum sebagai pengawasan kekuatan tangan keadilan! Kesimpulan yang dapat diberikan secara garis besar mengenai Peran Media, Opini Publik dan keterkaitannya dengan A Freedom & Impartial of Judiciary dirangkumkan sebagai berikut : 1. Kilas balik Era Orde Baru, dengan UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers, melalui “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab” (“Free and Responsible Press”) sebagai karakter sistem Social Responsibility Press seharusnya lebih menekankan pada Legal Approach (Pendekatan Hukum). 2 polar yaitu, yaitu polar pertama, pers bebas yang harus dimaknai sebagai larangan dilakukan tindakan prevensi, sedangkan pers yang bertanggung jawab sebagai polar kedua, untuk menyelesaikan berkaitan dengan pemberitaan pers melalui mekanisme hukum. Implementasi Pers Bebas dan Bertanggungjawab ini nyatanya berlainan dengan makna dan konsepnya yang justru mengarah pada Sistem Authoritarian yang mengenal breidel dan sensor. 2. Sejak Era Reformasi dengan disahkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, khususnya Pasal 2, istilah yang digunakan bukanlah “Pers Bebas dan Bertangguing Jawab”, tetapi “Kemerdekaan Pers” (“Freedom of The Press”) sebagai aksentuasi dari Sistem Libertarian Press yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Pada sistem Libertarian di era reformasi ini, tidak dikehendaki adanya tindakan prevensi dalam bentuk apapun, 8 Lord Denning. The Due Process of Law. First Reprint. London: Billing & Sons Limited. 1980. Page 17. 46 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji artinya polar kebebasan sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas– kebebasan total absolut - yang hanya tunduk pada Behavior Code atau Kode Etik Internal komunitas pers, yang dianggap berlainan dengan penyelesaian jalur hukum, yaitu tunduk pada Syarat Limitatif (artinya, tidak diperkenankan membetuk atau menciptakan ketentuan-ketentuan yang justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri) dan Syarat Demokratis (artinya tidak diperkenakan melakukan pemidanaan terhadap pernyataan-pernyatan yang bersifat prive, seperti diatur dan yang masih berlaku pada Pasal 132 bis KUHP yang undemokratis sifatnya). 3. Konvensi Internasional dan doktrin mengenal rambu-rambu terhadap kemerdekaan pers dan berpendapat, yang akhirnya diserahkan kembali kepada pers dalam menegakkan peran self-cencorship secara institusional pers, yaitu antara lain, tidak menyimpangi dari (a). National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum, seperti Bab I, II, V dari Buku II KUHP); (b). Expression to war or to national, racial or religious hatred (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama); (c). Incitement to violence and crime (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan, seperti Pasal 160, Pasal 161 KUHP); (d). Attacks on founders of religion (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik “blasphemy”, seperti Pasal 156a KUHP); (e). Public health and moral (kesehatan dan moral, seperti Pasal 281, Pasal 282 KUHP); (f). Rights, honour and reputation of others (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat “delik penghinaan”, seperti pasalpasal 154, 155, 156, 157, 207, 208, 310, 315 KUHP, walaupun sudah ada yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai “haatzaai artikelen”); (g). Fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari “contempt of court”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP). Rambu-rambu seperti ini memberikan aktuensi bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran Libertarian dengan Negative Freedom-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu Right to Lie (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “Trustworthy Source” (sumber terpercaya) sebagai Previlege Right, adanya pula Right to Vilify (Hak untuk mencemarkan nama baik), Right to Distort (Hak untuk Mengacaukan) maupun Right to Invade Privacy (Hak memasuki kehidupan pribadi). 4. Walaupun Pers mempunyai “privilege right” yang absolut untuk tidak menyebutkan sumber berita, Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya 47 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaan, serta ramburambu lainnya, dan yang terpenting harus bersifat “fair and accurate”. Apabila berkaitan Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu : pertama, jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, kedua, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan, karenanya suatu pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers Libertarian) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara etik norma maupun hukumnya. 5. Previlege Right Absolut dari Pers adalah memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan -suatu moral hazard- atas dasar Interest of justice atau national security atau for prevention of disorder or crime yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria Sub Judice Rule ataupun Disobeying a Court Order dari pranata Contempt of Court. 6. Pada Negara Demokrasi yang universal dan proses demokratisasi transisi seperti Indonesia yang mengenal adanya suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi, keberadaan pranata Contempt of Court adalah sesuatu kebutuhan mendesak -an urgent need- yang sebenarnya telah ada sejak UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun terwujud melalui Rancangan KUHP Nasional, suatu “safeguard” terhadap a Freedom & Impartial Judiciary!. Daftar Pustaka Bagir Manan. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian). Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung. 2005. Denny Indrayana. Urgensi “Reshuffle” Hakim Agung. Kompas, 27 Januari 2006 . 48 Freedom & Impartial of Judiciary, Indriyanto Seno Adji Lord Denning. The Due Process of Law. First Reprint. London: Billing & Sons Limited. 1980 Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit: Erlangga. 1991 ------------------------. Pers: Aspek-Aspek Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1977 Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji. Peradilan Bebas & Contempt of Court. Cetakan Kesatu. Jakarta. Penerbit: Diadit Media. 2007 49 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 31-50 50 PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Administrative Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government Administration Law) Philipus M. Hadjon Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Trisakti Jakarta Email : [email protected] Abstrak Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1.1 adalah tata lakasana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Jika dibandingkan dengan Algemene wet Bestuursrecht (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas. AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (bestuursrecht) sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi, namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU AP merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar. Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi. Kata kunci : Peradilan, Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Abstract Act No. 30 Year 2014 on Government Administration (UU AP) instead of administrative law. The concept of public administration (AP) in Article 1.1 is governance in the decision and / or action by the official agency and / or government. When compared with the Dutch Algemene wet Bestuursrecht (AWB), it seems obvious differences. AWB moved from the concept of administrative law (bestuursrecht) while the AP is the starting point of government administration. That in AP there are aspects of administrative 51 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 law, but the concept of administrative law is confusing. On the basis, the common explanations of AP stating AP Act is a substantive law of the State Administrative Court system becomes a big question mark. AP Act provisions concerning Administrative Court is not based on a clear conceptual approach. On the basis, AP Act concerning Administrative Court is very difficult to apply in judicial practice as well as vague concepts is also contrary to the concepts of administrative law. Keywords: Judicial, Administrative Court, Act No. 30 Year 2014 on Government Administration I. Pendahuluan Judul tulisan ini menggunakan istilah dalam konteks, bukan berdasarkan. Istilah itu digunakan karena UU ini bukan tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun mengkaitkan ketentuan UU ini dengan PTUN. Ketentuan terkait PTUN antara lain: 1. Penjelasan Umum menyangkut hukum materil dari sistem PTUN 2. Ketentuan Peralihan a. Pasal 87: menyangkut kompetensi absolute PTUN (ktun) b. Pasal 85: menyangkut gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan umum 3. Pasal 10 tentang AUPB 4. Pasal 17: penyalahgunaan wewenang 5. Pasal 21: putusan tentang unsur penyalahgunaan wewenang II. Penjelasan Umum Menyangkut Hukum Materil dari Sistem PTUN Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka UU ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasa Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UU ini merupakan hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini bukan UU tentang Hukum Administrasi. Konsep Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1.1 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kalau dibandingkan dengan Algemene wet Bestuursrecht (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas karena AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (bestuursrecht). 52 Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon Untuk itu dipaparkan perbandingan isi AWB dengan isi AP. AWB Algemene wet Bestuursrecht I. Inleidende Bepalingen (Ketentuan Pendahuluan) II. Verkeer tussen burger en bertuursorganen (hubungan antara rakyat dan pemerintah) III. Algemene bepalingen over besluiten (Ketentuan Umum tentang Keputusan) IV. Bijzondere bepalingen over besluiten (Ketentuan Khusus tentang Keputusan) V. Handhaving (penegakan hukum) VI. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep (Ketentuan umum tentang keberatan dan banding) VII. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep (Ketentuan khusus tentang keberatan dan banding administrasi) VIII. Bijzondere bepalingen over beroep bij de rechtbank (Ketentuan khusus tentang gugatan ke pengadilan) IX. Bepalingen over bestuurrorganen (Ketentuan tentang organ pemerintah) X. Slot bepalingen (Ketentuan Penutup) UU AP UU Administrasi Pemerintahan I. Ketentuan Umum II. Maksud dan Tujuan III. Ruang Lingkup dan Asas IV. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan V. Kewenangan Pemerintahan VI. Diskresi VII. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan VIII. Prosedur Adminitrasi Pemerintahan IX. Keputusan Administratif X. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan XI. Sanksi Administrasi XII. Ketentuan Peralihan XIII. Ketentuan Penutup Paparan perbandingan tersebut jelas menggambarkan perbedaan titik tolak AWB adalah hukum administrasi sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU ini (UU AP) merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar. III. Ketentuan Peralihan 1. Pasal 87 menyangkut Kompetensi Abdolut PTUN Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 53 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 b. c. d. e. f. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Permasalahan: - Apa fungsi Ketentuan Peralihan? - Di samping itu butir a s.d. f Pasal 87 sangat aneh. Untuk itu dipaparkan analisis butir a s.d. f. Butir a Ketentuan ini memperluas konsep keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1.9 UU PTUN. Menjadi tanda Tanya besar bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual. Apakah hal tersebut bukan merupakan Contradictio in termino? (bandingkan: yang dimaksud kambing juga mencakup kucing). Menjadi pertanyaan: apakah dengan ketentuan tersebut kompetensi absolut PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1.10 diperluas? Kalau ya, harusnya yang dirubah adalah ketentuan Pasal 1.10. Apakah tepat memperluas kompetensi absolut PTUN hanya dengan ketentuan peralihan UU yang bukan UU PTUN? Apakah asas contrarius actus tidak berlaku? Apakah lex generalis in casu UU AP dapat merubah lex specialis (UU PTUN) dengan dalih UU AP lex posterior? Apakah lex posterior generalis dapat merubah lex prior specialis? Butir b Apakah dengan memperluas jangkauan eksekutif, legislatif, yudikatif (yudisial?) otomatis penetapan tertulis tidak lagi hanya merupakan tindakan hukum tata usaha Negara? Pendekatan konseptual hendaknya tetap menjadi penentu. Konsep tindakan hukum tata usaha negara sudah tepat karena menunjukan ranah hukum administrasi. Butir c 54 Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon Apa makna ketentuan ini? AUPB merupakan salah satu parameter legalitas. Jadi frasa peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 1.9 UU PTUN sudah tepat dan mubasir ditambah AUPB. Butir d Apa makna bersifat final dalam arti luas? Apa makna bersifat final dalam arti sempit? Penjelasan Pasal 87 Butir d: Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Penjelasan tersebut disamping tidak jelas juga membingungkan kalau dilakukan pendekatan konseptual menyangkut konsep final. Apa maksud penjelasan yang menyatakan: mencakup keputusan yang diambil alih Atasan yang berwenang? Dalam rangka delegasi atau mandat atau pengawasan? Butir e Apa makna berpotensi menimbulkan akibat hukum? Apakah rumusan melahirkan akibat hukum tidak tepat? Bagaimana kaitan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN? Butir f Apa yang dimaksud keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat? 2. Pasal 85: menyangkut gugatan yang sudah diajukan ke Pengadilan Umum Sangat tidak logis substansi Pasal 85 mendahului Pasal 87 yang berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN in casu tindakan faktual. Ini salah satu contoh sistematis yang tidak logis dari UU AP. IV. Pasal 10 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum; 55 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk menganalisis ketentuan Pasal 10 tersebut diuraikan tentang konsep AUPB dan AUPB dalam hukum kita (sebelum UU No. 30 Tahun 2014). a. Pengaruh Belanda Kita mengenal AUPB karena pengaruh Belanda. Dalam perkembangan hukum Belanda dikenal de algemene beginselsen van behoorlijk bestuur (abvbb). Ciri-ciri abvbb adalah: - Ongeschreven (tidak tertulis) Pertanyaan: Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 ongeschreven? - Rechtsbeginsen (asas hukum) berkaitan dengan rechtmatigheidsnormen sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan onrechtmatig. Pertanyaan: Apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 th. 2014 merupakan rechtsbeginselen seperti: kemanfaatan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. - Algemene beginselsen memuat karakter azas (beginsel) dan sifatnya umum. Dalam ayat 5 sub d Arob en 8 sub d Arob dikatakan asas-asas itu merupakan in het algemeen rechtsbewustzijn levend moet zijn (kesadaran hukum umum yang hidup). (vide: F.H. van Der Burg, G.J.M. Cartigny, Rechtsbesherming tegen de overheid, PP 100 – 134) b. AUPB dalam Hukum Kita (sebelum UU No. 30 th. 2014) Dalam hukum kita aupb baru dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 9 thn. 2004. Dalam penjelasan pasal tersebut dirinci 6 asas yang dikutip dari Pasal 3 UU No.28 tahun 56 Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 tersebut memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara. Jadi bukan aupb. Hal itu dikutip juga dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II (edisi 2007) halaman 62. Dari buku Pedoman tersebut yang bisa menjadi acuan adalah butir 10. Penerapan AUPB dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam putusan-putusan MA (halaman 63). AUPB meliputi: a. Asas persamaan b. Asas kepercayaan c. Asas kepastian hukum d. Asas kecermatan/ketelitian e. Asas pemberian alasan/motivasi f. Larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) g. Larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur) Note: butir h bukan aupb karena bukan asas hukum Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan. Untuk pemahaman asas-asas tersebut dipaparkan uraian singkat menyangkut asas-asas tersebut. Asas Persamaan - Perlakuan sama dalam kondisi sama - Larangan diskriminasi Asas Kepercayaan - Asas ini terkait dengan asas kepastian hukum - Juga dikaitkan dengan harapan yang wajar Asas Kepastian Hukum - Asas ini berkaitan dengan asas kepercayaan dan harapan yang wajar. Asas Kecermatan/Ketelitian (karakter formal dan prosedural) - Asas kecermatan formal - Persiapan yang baik Asas Pemberian Alasan (Motivasi) - Dasar fakta - Akibat hukum yang lahir harus didasarkan atas fakta nyata. 57 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 Larangan Penyalahgunaan Wewenang (detournement de pouvoir) - Larangan menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan atau mengalihkan wewenang untuk tujuan lain. Larangan Bertindak Sewenang-wenang (willekeur; onredelijkheid) - Tidak rasional - Parameter : rasionalitas (bandingkan F.H. van der Burg supra) Berdasarkan konsep aupb yang telah dipaparkan pertanyaan yang muncul: a. Apakah aupb tertulis? Pasal 10 a quo: AUPB tertulis? b. Apakah kemanfaatan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik merupakan asas hukum? Kepentingan umum adalah asas tambahan Kuntjoro terhadap 11 asas yang dipaparkan Crince Le Roi di Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 1978. Kalau bukan asas hukum, pelanggaran terhadap asas tersebut bukan merupakan tindakan onrechtmatig. Apakah larangan sewenang-wenang tidak termasuk AUPB? Apakah larangan sewenang-wenang merupakan species dari larangan penyalahgunaan wewenang (Pasal 17 ayat (2) butir c)? V. Pasal 17 : Penyalahgunaan Wewenang (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Larangan melampaui Wewenang b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang UU a quo tidak menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang (Penjelasan Pasal 17: cukup jelas), tepi anehnya ayat (2) menentukan 3 jenis penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu pertama-tama diuraikan tentang penyalahgunaan wewenang dan analis atas ketentuan Pasal 17 ayat (2) dikaitkan ketentuan Pasal 18. a. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep détournement de pouvoir. Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR 58 Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon BESTUUR dirumuskan sebagai: het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel [p.163] (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialitas). Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk mempertajam konsep penyalahgunaan wewenang dikutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam putusan MA nomor: 572 K/Pid/2003 (kasus Ir. Akbar Tandjung). Pertimbangan MA terhadap pertimbangan Judex Facti : Sehubungan dengan pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub b UU no. 3 tahun 1971, sehingga putusan Majelis Hakim menjadi keliru dan menyesatkan. (Amir Syamsudin, pp. 187188). Pertimbangan MA terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi: Bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan….dst” pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tinggi Jakarta telah mencampuradukkan pengertian perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” dengan pengertian “Perbuatan Sewenang-wenang”. (Amir Syamsudin, p. 200). 59 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 Pertimbangan MA Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti, bahwa unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” itu disimpulkan terbukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa I yang tidak melakukan atau mengusahakan suatu mekanisme koordinasi kerja yang tidak terpadu dengan baik, sehingga perbuatan materiil Terdakwa I menurut hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang Negara padahal Terdakwa I memiliki wewenang untuk itu. Menurut pendapat Mahkamah Agung, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa I memang mempunyai kesengajaan (opzet) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan bahwa memang Terdakwa I menghendaki dan mengetahui (met willens en wetens) bahwa perbuatan itu dilarang, tapi tetap dilakukannya. (Bandingkan pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta 2003, halaman 152 dst). (Amir Syamsudin, p. 296) Tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang adalah: - Met opzet (dengan sengaja) - Mengalihkan tujuan wewenang - Ada interest pribadi yang negatif Apakah konsep penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Pasal 17 adalah seperti paparan di atas? Nampaknya tidak jelas konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17. Lebih tidak jelas dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) menyangkut tiga species larangan penyalahgunaan wewenang. Lebih menyesatkan lagi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18. b. 60 Pasal 18 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundangundangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Analisis terhadap ketentuan Pasal 18 Pasal 18 ayat (1) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir a dan b bukan menyalahgunakan wewenang tapi tidak berwenang (onbevoegd). Pasal 18 ayat (1) butir c bukan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan peraturan Perundangundangan bukan melanggar aupb. Larangan penyalahgunaan wewenang termasuk kategori aupb. Pasal 18 ayat (2) Konsep mencampuradukan kewenangan adalah terjemahan yang keliru dari konsep misuse of competence. Dalam buku Prof. Kuntjoro Purnopranoto berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Aministrasi Negara” (1978) diuraikan 13 aupb. Asas-asas tersebut berasal dari kuliah Prof. R. Crince Le Roi di Fakultas Hukum UNAIR tentang 11 asas sedangkan dua asas adalah tambahan dari Prof. Kuntjoro. Dalam kuliah Prof. R. Crince Le Roi, asas ke-6 adalah: principle of non misuse of competence. Asas itu dalam bukunya Prof. Kuntjoro diterjemahkan asas jangan 61 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 mencampuradukan kewenangan. Terjemahan tersebut agaknya kurang tepat karena misuse berarti menyalahgunakan bukan mencampuradukan. Atas dasar itu apakah ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir b mencampuradukan wewenang adalah terjemahan dari misuse of competence? Atas dasar itu ketentuan Pasal 18 ayat (2) sangat tidak rasional karena pendekatan konseptual yang tidak jelas. Pasal 18 ayat (3) Konsep sewenang-wenang dalam hukum Belanda semula dikenal dengan istilah willekeur dan dewasa ini populer dengan istilah onredelijkheid. Dalam hukum kita dikenal dengan istilah sewenang-wenang. Parameter sewenangwenang adalah rasionalitas. Atas dasar itu ketentuan Pasal 18 ayat (3) membingungkan dan merusak konsep hukum administrasi tentang larangan sewenang-wenang. VI. Pasal 21: Putusan tentang unsur Penyalahgunaan Wewenang (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksdu pada ayat (5) bersifat final dan mengikat. Berkaitan ketentuan ayat (3), pertanyaan yang muncul: a. Dalam konteks apa seorang Pejabat mengajukan permohonan a quo? b. Apakah putusan pengadilan terkait ketentuan ayat (3) bersifat mengikat dalam hal ada gugatan TUN terhadap Pejabat 62 Peradilan TUN dalam Konteks UU No.30 Thn 2014, Philipus Hadjon tersebut juga terkait dakwaan tindak pidana terhadap Pejabat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)? VII.Penutup Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi seperti nampak dalam paparan supra. Daftar Pustaka J.Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utara, 2003 Kuntjoro Purnopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Aministrasi Negara, Jakarta, Pradnja Paramita, 1978. Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Jakarta, Mahkamah Agung, 2007. 63 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64 64 MEWUJUDKAN VISI MA TENTANG BADAN PERADILAN YANG AGUNG MELALUI UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM (Realize The Vision of The Supreme Court Through The Agency Law Judge Position) Siti Nurjannah Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kab. Bogor Email : [email protected] Abstrak Status jabatan Hakim telah ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS. Pembiaran atas status ganda tersebut, senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial maupun terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Jika independensi mulai tereduksi maka implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Kata kunci : Visi Mahkamah Agung, Undang-Undang, Jabatan hakim Abstract Judges official status has been affirmed as a state official, but in fact on some aspect on it is still bound by the Civil Service system. Therefore judge positions are often said to be dual status as state officials and civil servants. Nullifying the dual status is, in fact has caused serious problems in terms of both managerial and related to the potential reduction of judicial independence. If the independence start to reduce, the implications of the problems of the post of Judge is hampering efforts to realize the vision of the Supreme Court which is to realize the Supreme Courts. Keywords : Supreme Court Vision, Acts, and Official state of Judges A. Pendahuluan Beberapa waktu lalu tersiar kabar yang menggembirakan bahwa RUU jabatan Hakim telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi kalangan Hakim khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya. Melalui RUU 65 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 tersebut diharapkan profesi Hakim semakin mendapatkan kedudukan yang jelas dan sesuai dengan hakikat martabatnya. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, kedudukan Hakim sebagai sebuah jabatan dinilai masih bias dan belum tertegaskan secara integral. Bilamana Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi telah jelas penetapannya sebagai pejabat negara dengan segala implementasinya. Tidak demikian dengan Hakim karier yang bertugas di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, kedudukan dan perlakuan terhadapnya baik dari segi normatif maupun implementatif masih belum sepenuhnya ditempatkan layaknya pejabat negara. Pada satu sisi ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks ini secara simultan Hakim memiliki status sebagai PNS. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS. Jabatan Hakim ini diibaratkan satu kakinya berada di wilayah eksekutif sedangkan satu kaki yang lain berada di wilayah judikatif. Atas penetapan status jabatan yang demikian, senyatanya negara telah bersikap inkonsisten dalam penerapan pemisahan atau pembagian kekuasaan secara konstitusionalism. Selain itu secara fungsional, status dan kedudukan antara sebagai pejabat negara dengan sebagai pegawai negeri sipil memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaannya antara lain terletak pada sistem dan pola rekrutmen, pengangkatan, gaji dan tunjangan, hak dan kewajiban, pembinaan, promosi dan mutasi, maupun protokolernya. Pembiaran atas status ganda yang tersandangkan dalam jabatan Hakim ini senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial pada umumnya, maupun secara khusus terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Selanjutnya jika independensi mulai tereduksi maka secara qonditio sine quanon, implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Oleh karenanya tiada mungkin badan peradilan yang agung dapat terwujud jika independensi kekuasaan kehakiman terlemahkan eksistensinya baik secara personal (Hakim) maupun institusional (fungsi manajerial jabatan Hakim). B. Masalah Inkonsistensi Manajemen Jabatan Hakim Momentum reformasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan, diantaranya perubahan yang terkait dengan masalah peradilan. Apabila pada masa sebelumnya, berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan 66 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan lembaga peradilan berada di bawah dua atap, yaitu di bawah Pemerintah dan di bawah Mahkamah Agung. Secara finansial dan administratif berada di bawah Pemerintah dalam hal ini Departemen terkait, sedangkan secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung. Dualisme pembinaan pengadilan beserta aparaturnya tersebut dinilai sebagai pelemahan terhadap pelaksanaan prinsip independensi judisial. Karena menyangkut adminsitratif dan finansial menempatkan lembaga pengadilan beserta aparaturnya berada di bawah kekuasaan eksekutif. Tonggak reformasi telah menancapkan ide dan gagasan besar terkait dengan upaya untuk mengkhiri adanya dualisme pembinaan hakim dan pengadilan oleh lembaga peradilan dan pemerintah dan berupaya untuk mewujudkan prinsip independensi judisial melalui perubahan undang undang kekuasaan kehakiman yang mengarah terbentuknya sistem satu atap kekuasaan kehakiman (one roof system of judicial power). Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya undang undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dijalankan proses transisi peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan, yang semula sebagian diantaranya berada di tangan Pemerintah dalam hal ini Menteri atau Kementerian yang terkait, menjadi beralih sepenuhnya ke tangan Mahkamah Agung. Peristiwa transisi kewenangan tersebut dikenal sebagai peralihan pembinaan dari pembinaan dua atap menjadi satu atap, atau dikenal sebagai “penyatuan atap” pembinaan hakim dan pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung (one roof system of judicial power). Apabila sebelumnya pembinaan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri terkait, namun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengalami perubahan, dimana pembinaan hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sejak saat itu Menteri tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan. 1 Adapun khusus untuk pembinaan terhadap hakim dan Pengadilan Militer hingga saat ini masih bersifat dua atap, yaitu 1 Hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 67 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan secara adminsitratif dan personil masih berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. 2 Perubahan peraturan serta peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim menjadi di bawah satu atap Mahkamah Agung ternyata dalam kenyataannya tidak terlalu banyak membawa perubahan yang berarti, boleh dikatakan hanya sekedar hilangnya kewenangan Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap hakim. Hal tersebut disebabkan oleh karena sistem kepegawaian hakim masih tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang memperlakukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status dan kedudukan hakim pada satu pihak telah dinyatakan sebagai pejabat negara namun pada pihak yang lain menyangkut masalah kenaikan jabatan dan kepangkatan hakim masih tetap disamakan dengan PNS. Penyatuan atap pembinaan Hakim dan badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung ternyata masih juga menyisakan berbagai permasalahan lain yang tidak kalah seriusnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim. Permasalahan tersebut antara lain: Pertama, masalah definisi atau jenis jabatan yang disandang Hakim. Konsep dan pengertian tentang apa sejatinya yang dimaksud sebagai “pejabat negara” yang hal tersebut masih menjadi bahan perdebatan tersendiri. Definisi pejabat negara masih belum sepenuhnya jelas, baik dari segi normatif maupun dari segi implementatif. Meskipun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai pejabat negara. Definisi jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini, merubah definisi jabatan Hakim sebelumnya yaitu sebagai pejabat negara tertentu (UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Dalam beberapa Undang-Undang lainnya Hakim definisikan secara berbeda misalnya disebut sebagai penyelenggara negara (Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) hingga pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Atas konsekuensi dari perbedaan definisi jabatan Hakim ini selanjutnya berpengaruh terhadap penentuan pola rekrutmen, sistem kepangkatan, sistem penilaian kinerja, fasilitasi hak jabatan (yang terdiri dari gaji, tunjangan, jaminan kesejahteraan, keamanan, protokoler 2 Hal tersebut mungkin disebabkan karena menyangkut policy dan political will dari jajaran pimpinan militer bahwa proses penyatuan atap masih memerlukan kajian secara lebih mendalam, mengingat adanya sifat yang khas dan strategis keberadaan peradilan militer maupun status dan kedudukan hakim militer. 68 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah dan lain-lain), promosi dan mutasi serta kepensiunan yang notabene sebagian mengikuti pejabat negara sementara di bagian lain diterapkan sistem layaknya PNS. Atas problema tersebut maka definisi jabatan Hakim ini perlu diintegralkan dan dibakukan sehingga terwujud satu pola ideal yang sama dan sinergis serta konsisten baik secara normatif maupun implementatif. Kedua, masalah rekrutmen Hakim. Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa rekutmen hakim dari pegawai negeri sipil telah dihapuskan. Ketentuan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi juridis yang cukup problematik dan dilematis sifatnya. Suwardi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Judisial mengemukan beberapa permasalahan menyangkut hal pola dan proses rekrutmen Hakim diantaranya: 3 1. Apakah statusnya apabila seseorang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam rekrutmen Hakim? 2. Bagaimana melakukan uji kompetensi dan psikotest selama mengikuti pelatihan sebelum yang bersangkutan secara resmi diangkat menjadi Hakim? 3. Apakah selama mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para calon hakim yang bersangkutan sudah berhak untuk menerima gaji atau tunjangan? 4. Apabila dinyatakan telah berhak menerima gaji dan tunjangan maka pertanyaannya adalah yang bersangkutan dalam kapsitasnya sebagai apa (pegawai negeri ataukah sebagai apa)? 5. Sebab yang bersangkutan bukan sebagai pegawai negeri, juga bukan sebagai pejabat negara karena yang bersangkutan belum mendapatkan pengangkatan sebagai hakim? 6. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah lulus dari kegiatan pendidikan dan pelatihan calon hakim dan kemudian diangkat secara resmi sebagai hakim sehingga pada saat itu juga menduduki jabatan sebagai pejabat negara, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan sistem penggajian dan tunjangannya? Karena dalam kenyataannya gaji dan tunjangannya masih mengacu pada sistem penggajian sesuai dengan ketentuan tentang pegawai negeri sipil. 3 Suwardi, Rekrutmen dan Pembinaan Hakim : Tantangan, Kendala dan Konsepnya, 9 September 2014 69 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 Selain beberapa masalah rekrutmen dari perspektif calon Hakim diatas, masalah kelembagaan yang mengatur kewenangan pengadaan atau seleksi calon Hakim juga belum terkonstruksi secara normatif dan implementatif. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun, menurut Taufiqurrohman Syahuri sampai saat ini peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang seleksi Hakim tersebut belum dibentuk. Idealnya peraturan bersama ini mengatur secara rinci metode seleksi hakim dan formula sistem yang tepat untuk seleksi hakim. Penyusunan peraturan bersama ini sebaiknya disusun dengan segera, sebab kekosongan peraturan tersebut mengakibatkan tertundanya proses rekrutmen/seleksi hakim yang pada akhirnya kebutuhan lowongan hakim tidak dapat dipenuhi. Selain itu, apabila ketentuan tentang seleksi ini tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin proses pengangkatan hakim akan cacat secara formil (karena tidak sesuai dengan ketentuan UU). 4 Ketiga, masalah sistem kepangkatan Hakim. mengingat di dalamnya juga menyangkut sistem dan jenjang kepangkatan hakim sebagaimana layaknya PNS. Apakah setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, jenjang kepangkatan Hakim masih harus tetap mengikuti pola sebagaimana PNS yang dimulai dari golongan kepangkatan III-A, III-B, III-C, III-D, IVA, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E? Ataukah perlu untuk merumuskan model penggolongan kepangkatan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi Hakim berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersendiri yang akan dibuat di kemudian hari. Selama peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang model penggolongan dan kepangkatan tersendiri bagi hakim sebagaimana dimaksud belum berlaku, maka hal tersebut sama halnya dengan melakukan pembiaran yang akan secara terus menerus melestarikan permasalahan-permasalahan ketidakjelasan sistem dan pola kepangkatan, penggolongan serta pembinaan hakim. Padahal di satu pihak sudah ditegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara, namun mengapa di pihak lain masih tetap menggunakan sistem dan pola kepangkatan pegawai negeri sipil. 4 Taufiqurrohman Syahuri, 2014, Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014. 70 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah Keempat, masalah sistem penilaian kinerja Hakim. Saat ini meskipun telah tertegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam sistem penilaian kinerja Hakim masih mengikuti PNS. Jika sebelumnya Hakim dinilai kinerjanya dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), setelah diberlakukan UU ASN berubah menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua sistem penilaian kinerja bagi PNS tersebut senyatanya kurang relevan secara substantif jika diterapkan kepada Hakim yang notabene pejabat negara. Selain itu secara prosedural dimana Atasan Hakim memegang kuasa penilaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya jika terdapat konflik kepentingan diantara mereka. Irfan Fachruddin berpendapat bahwa pada saat ini DP3 belum dapat dijadikan pegangan dalam mempertimbangkan seorang Hakim menjadi unsur pimpinan. Ada baiknya mempertimbangkan untuk mengikuti langkah sistem evaluasi kinerja jabatan fungsional yang telah ada, yaitu mengadakan instrumen khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Hakim dan disesuaikan dengan karakteristik tugas yudisial kekuasaan kehakiman. Antara lain: (1). Independensi dan Akuntabilitas; (2). Konsistensi putusan dengan hukum (legal uniformity); (3). Penemuan dan konstruksi hukum; (4). Manajemen persidangan dan ketepatan penerapan asas-asas hukum acara; (5). Ketepatan memenuhi jadwal penyelesaian perkara; (6). Sikap Hakim terhadap para pihak; dan (7). Ketaatan Hakim terhadap ketentuan etik Hakim.5 Oleh karenanya perlu diformulasikan metode dan mekanisme penilaian kinerja Hakim sebagai pejabat negara ini agar menjadi jelas sistem pembinaannya yang khusus dan tepat guna serta menjamin independensi Hakim. Kelima, masalah kepensiunan. Meskipun Hakim telah dikategorikan sebagai pejabat negara, namun kepensiunannya tidak selayaknya seorang pejabat negara, tetapi masih menggunakan sistem kepensiunan PNS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil”. Berdasarkan ketentuan tersebut seolah masih menyuguhkan sebuah kenyataan normatif dan implementatif bahwa jabatan organik Hakim sebagiannya masih PNS, karenanyalah status calon Hakim 5 Irfan Fachruddin, Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, Hlm.84. Lihat juga dalam Budi Suhariyanto, Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013. 71 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 sebelum pengangkatannya dan setelah purna baktinya adalah PNS. Dalam konteks ini kepensiunan Hakim menjadi kontra produktif dan inkonsisten dengan status pejabat negaranya. Berdasarkan beberapa masalah jabatan Hakim tersebut yang seakan berada dalam dua status yang sama-sama belum tepat, antara Pejabat Negara dan PNS ataukah sejatinya statusnya adalah PNS yang ditempeli dengan beberapa predikat yaitu pejabat negara, penyelenggara negara, dan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.6 Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini status dan kedudukan hakim berada di area abu-abu (grey area) beserta segala kompleksitas dan akibat hukumnya. Karena itulah perlu dilakukan upaya untuk redefinisi dan rekonstruksi jabatan Hakim. C. Urgensi Redefinisi dan Rekonstruksi Jabatan Hakim Momentum penerbitan UU ASN telah memberikan angin segar bagi kalangan Hakim khususnya dan lingkungan peradilan pada umumnya. Kedudukan jabatan Hakim sebagai “pejabat negara” tertegaskan secara eksplisit dalam UU ASN (Pasal 121 dan Pasal 122 huruf “e”). 7 Namun selain didefinisikan pejabat negara, dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku lainnya jabatan Hakim didefinisikan secara berbeda UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengkategorikan Hakim sebagai penyelenggara negara (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2). Sedangkan UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan jabatan Hakim sebagai “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman” (Pasal 19). Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab masalah inkonsistensi manajemen jabatn Hakim di atas, harus diakui bahwa sampai saat ini 6 Ansyahrul, Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm.7 7 Pasal 121 UU ASN mengatur bahwa : “Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara” sedangkan Pasal 122 huruf “e” mengatur bahwa : “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali hakim ad hoc” (garis bawah penulis). Dalam rumusan ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan perkecualiannya, hal tersebut terkait dengan status dan kedudukan hakim ad hoc yang dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian sebagai pejabat negara. Hingga pada saat ini, masih belum terlalu jelas apa sejatinya yang menjadi ratio legis adanya ketentuan perkecualian tersebut. Karena di dalam rumusan ketentuan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit tidak ditemukan ratio legis adanya perkecualian hakim ad hoc dari status dan kedudukan sebagai pejabat negara. Penelusuran terhadap naskah akademik (academic draft) UU ASN kiranya perlu dilakukan, dalam rangka untuk menemukan apa latar belakang pemikiran adanya perkecualian 72 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah definisi “nyata” terhadap jabatan Hakim yang pejabat negara ini masih bias. Berkaitan dengan hal ini Ansyahrul menyatakan : 8 Yang menjadi permasalahan adalah dalam kenyataannya Pejabat Negara lainnya itu (kecuali Hakim) adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para Hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batas waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain-lain (bukan sampai usia pensiun seperti Hakim). Semua Pejabat Negara pada kenyataannya harus memiliki latar belakang, apakah: PNS, TNI, Polri, atau Swasta. Bila para Hakim memilih Pejabat Negara dan melepaskan PNS berarti dianggap berlatarbelakang swasta. Dan kenyataannya lagi bahwa karena para Hakim diberi predikat Pejabat Negara secara kolektif (kolosal) dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan Pejabat Negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan, sehingga perlu diatur tersendiri pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang aturan pelaksanaannya hingga sekarang belum ada. Selain itu para Hakim yang memasuki masa pensiun, hanya diperlakukan sebagai PNS, bukan sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara. Selanjutnya apabila para Hakim dilepaskan dari PNS, bagaimana aparat peradilan lainnya yang non Hakim, tentu masih berstatus PNS, berarti lembaga peradilan kembali di bawah dua atap, karena administrasi kepegawaiannya mendua (sebagian masih berada di bawah kekuasaan eksekutif). Lebih lanjut Ansyahrul 9 menjelaskan bahwa permasalahn mendasar lainnya adalah belum tersosialisasinya prinsip peradilan di bawah satu atap secara mendalam dan luas di kalangan masyarakat, komunitas hukum, pihak eksekutif, di pihak legislatif sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dan membangkitkan political will dari pihak eksekutif dan legislatif untuk memikirkan secara serius mengenai status para Hakim dalam sistem dan struktur ketatanegaraan kita. Apalagi dari internal para Hakim belum ada gambaran, konsep, dan rumusan yang jelas mengenai apa yang diinginkan, dan bagaimana status/kedudukan para Hakim yang seharusnya. Pendapat yang bersifat reflektif tentang masalah definisi jabatan Hakim dari Ansyahrul ini penting untuk diperhatikan secara serius. Setidaknya dapat terevaluasi bahwa keberadaan definisi yang kurang integral tersebut merupakan cerminan dari ketiadaan perhatian dan pengkajian yang serius dari internal maupun eksternal peradilan yang terkait 8 Ansyahrul, Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm. 7-8 9 Ibid 73 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 dalam memperjuangkan dan menempatkan Hakim dalam sistem dan struktur organ kenegaraan. Berdasarkan konteks tersebut maka pemikiran tentang pentingnya redefinisi jabatan Hakim yang integral dan konsisten secara konseptual dan normatif sangat penting keberadaannya. Upaya redefinisi jabatan Hakim ini tentu tidak mudah. Sebagai konsekuensi dari adanya pengaturan status dan kedudukan hakim yaitu pejabat negara, maka ke depannya akan memerlukan pengaturan tersendiri yang menyangkut tentang pola rekrutmen, sistem kepangkatan, penilaian kinerja, promosi dan mutasi (serta demosi) yang tidak lagi mengacu persis sebagaimana sistem dan pola pembinaan karir pegawai negeri sipil pada umumnya. Selanjutnya dari redefinisi jabatan Hakim tersebut juga akan berdampak pada rekonstruksi manajemen jabatan Hakim melalui sebuah proses inpassing. Proses inpassing dari kedudukan Hakim saat ini menjadi seorang pejabat Negara ini menurut Jaja Ahmad Jayus juga perlu diatur, penyesuaian ini sangat dibutuhkan terkait keberadaan hakim yang telah ada saat ini. Hakim adalah jabatan mulia, menempatkan hakim sebagai pejabat negara merupakan marwah dimana hakim seharusnya berada. Status Hakim sebagai pejabat negara tidak bisa diartikan hanya berujung pada Hak keuangan dan fasilitas semata, tetapi juga kualifikasi serta perlakuan yang outstanding untuk menjadikan profesi Hakim benar-benar layak disebut sebagai pejabat negara. Salah satu contohnya dalam hal evaluasi kinerja, dimana posisi Hakim sebagai pejabat negara juga membawa konsekuensi serius pada hasil penilaian kinerjanya. Pada umumnya masa jabatan pejabat negara datur secara periodik lima tahunan, maka seharusnya perlakuan yang sama juga dituntut terhadap para hakim dimana performanya dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara periodik. Hasil penilaian kinerja tersebut juga harus berujung pada tindak lanjut yang signifikan, sehingga hakim yang kapasitasnya kurang maka perlu untuk dikembangkan dan jika hasil penilaian memutuskan untuk tidak dipertahankan maka bisa diajukan pemberhentian. Dengan menjadikan hakim seorang pejabat negara melalui aturan manajemen yang jelas diharapkan mampu menjaga independensi hakim dan proses peningkatan kapasitas hakim dalam hal keilmuan terus berkembang, melalui proses manajemen yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan hakim mampu menjawab tantangan penegakkan hukum di Indonesia.10 10 Jaja Ahmad Jayus, Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm.1-2. 74 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status hakim sebagai pejabat negara. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilanpengadilan yang ada. Tidak harus ditetapkan sama persis dengan sistem dan pola kepangkatan pada pegawai negeri sipil, namun sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding, belum lagi bagaimana menentukan gradasi diantara para hakim yang masing masing memiliki masa kerja dan pengalaman yang berbeda beda antara satu dengan yang lain. Karena itu perlu kiranya dipikirkan ke depan perumusan peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai pejabat negara sehingga daripadanya dapat menjamin pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judisial. RUU jabatan Hakim menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen jabatan Hakim yang integral dan komprehensif hingga independensi kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra judisial. D. Urgensi RUU Jabatan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Indonesia Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya serta dihubungkan dengan penyelenggaraan negara hukum ini memiliki arti 75 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 sangat dalam. Di satu sisi diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka sehingga berhubungan dengan ajaran pembagian kekuasaan dan di sisi lain dimaknai sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum. Terhadap hal ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa: 11 Sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (machtenscheiding) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (machtenverrdeiling), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “condition sine qua non” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keniscayaan bagi sebuah negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi adalah sebuah independensi peradilan yang integral atas segala aspek institusional, manajerial, maupun personal (Hakim). Oleh karenanya independensi tersebut harus diartikan secara komprehensif dan tidak parsial, sebagaimana Ahmad Kamil 12 membagi pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidak-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim. Berkaitan dengan independensi personal ini, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari 11 Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7. 12 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.221 76 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain.13 Berdasarkan pendapat Moh. Koesnoe tersebut, maka segala perlakuan dan kebijakan terhadap Hakim yang berpotensi mereduksi independensinya harus ditiadakan atau diminimalisir, termasuk yang terkait dengan status jabatan serta sistem manajemen karirnya. Harus diakui bahwa perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan Hakim sebagai pejabat negara ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan konstruksi jabatan Hakim di masa lalu yang notabene Hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini telah senafas dengan konsepsi pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen Hakim sebagai PNS masih belum lepas secara mutlak. Menurut Jaja Ahmad Jayus, status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan overlapping peraturan yang terkait dengan manajeman Hakim. Upaya untuk mengatur proses manajemen Hakim secara menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang. 16 E. Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung Melalui UU Jabatan Hakim Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:15 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 13 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Imperium, 2013, h. 147 16 Jaja Ahmad Jayus, Op Cit, Hlm. 1. 15 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010, Hlm. 14 77 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu. Adapun usaha-usaha ideal dalam mewujudkan visi tersebut kemudian diturunkan dalam misi badan peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu : (1). Menjaga kemandirian badan peradilan; (2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan (4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.16 Sehubungan dengan point-point penting dari usaha ideal visi dan misi Badan Peradilan yang Agung diatas terdapat korelasi penting dengan pembahasan jabatan Hakim terutama yang berhubungan dengan kemandirian badan peradilan. Disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 17 Kemandirian peradilan yang merupakan usaha utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek institusional (menempatkan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sederajat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif) saja tetapi juga termasuk secara personal yaitu individu Hakim. Karena Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam 16 17 78 Ibid Ibid, Hlm. 11 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya Hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan Hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. 18 Termasuk diantara kemandirian secara personal Hakim adalah kedudukan profesi atau jabatannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya “campur tangan dari pihak lain”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun di satu pihak telah ditegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara, namun ternyata di pihak lain secara simultan masih memiliki status sebagai PNS. Dalam konteks sistem manajemen PNS dari Hakim ini, potensi atas campur tangan dari pihak lain (Pemerintah) pada kemandirian peradilan secara langsung tidak langsung pasti tak terelakkan. Selain itu kebijakan yang terkait gaji, tunjangan, fasilitasi sarana prasarana, perumahan, protokoler, perlindungan, keamanan, dan lain-lain masih berada dalam wilayah kewenangan Pemerintah (eksekutif) sehingga realisasi dan implementasinya tidak sepenuhnya mandiri pada Mahkamah Agung. Tidak salah kiranya kemudian terdapat kekhawatiran bahwa secara simultan permasalahan konsistensi pemberian hak dan kedudukan serta fasilitasi terhadap jabatan Hakim ini berkorelasi dan mempengaruhi independensi peradilan. Apalagi jika dihubungkan dengan realitas kekerasan dan ancaman yang dihadapi para Hakim dalam melaksanakan tugasnya telah menandakan bahwa jaminan keamanan serta perlindungan terhadap mereka masih minim. Demikian pula jika dihubungkan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim sebagai akibat minimnya kesejahteraanya sehingga tergoda untuk tidak profesional dan independen dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, semakin membuat urgen rekonstruksi jabatan Hakim untuk dilakukan secara komprehensif dan integral. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi jabatan Hakim dalam Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi landasan ideal bagi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan yang Agung. F. Penutup Kemandirian peradilan yang merupakan usaha utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek institusional (menempatkan lembaga pelaksana kekuasaan 18 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 39 79 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 kehakiman sederajat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif) saja tetapi juga termasuk secara personal yaitu individu Hakim. Termasuk diantara kemandirian secara personal Hakim adalah kedudukan profesi atau jabatannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya “campur tangan dari pihak lain”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun di satu pihak telah ditegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara, namun ternyata di pihak lain secara simultan masih memiliki status sebagai PNS. Dalam konteks sistem manajemen PNS dari Hakim ini, potensi atas campur tangan dari pihak lain (Pemerintah) pada kemandirian peradilan secara langsung tidak langsung pasti tak terelakkan. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi jabatan Hakim dalam Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi landasan ideal bagi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan yang Agung. Daftar Pustaka Buku Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012 Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010 Budi Suhariyanto, Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013 Irfan Fachruddin, Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Imperium, 2013 Makalah Ansyahrul, Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi 80 Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung, Siti Nurjannah untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014. Jaja Ahmad Jayus, Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 Suwardi, Rekruitmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep, Jakarta, Makalah, 9 September 2014 Taufiqurrohman Syahuri, Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014 81 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 65-82 82 KETERBUKAAN INFORMASI DI PERADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty) Ridwan Mansyur Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat Email : [email protected] Abstrak Sebagai lembaga publik dibidang peradilan, Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dalam konteks transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kata kunci : Keterbukaan Informasi, Peradilan, Integritas dan Kepastian Hukum Abstract As a public institution in the field of justice, the Supreme Court is required to commit to apply the disclosure of information. Nowadays, transparency of information disclosure in the context of justice for the Supreme Court is not only the public needs but also the needs of all residents of the judiciary. With the judicial transparency, will slowly happen to strengthen accountability and professionalism and integrity of the judiciary residents. Commitment to provide disclosure of both the process and the end result is a concrete manifestation of public services as access to justice (access to justice) given by the Court at the lowest levels up to the Supreme Court. 83 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 Quality of excellent public services through the transparency of the judicial information disclosure is the estuary of execution Reform of Bureaucracy. Keywords : Information transparency, Judicial, Integrity and Legal Certainty A. Pendahuluan Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi dan data kelola lembaga pelayanan publik untuk direformasi dalam dinamika tuntutan masyarakat. Sebagai lembaga publik dibidang peradilan Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010 - 2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia. 84 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Arah yang ingin dicapai pengelolaan informasi yang berkualitas pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan kinerja Pengadilan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.1 Menilai tingkat integritas layanan publik merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik. Penilaian yang dilakukan juga dapat menggambarkan sifat-sifat korupsi di layanan publik tersebut. Hasil integritas mencerminkan apakah unit layanan pada lembaga/instansi pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Lembaga peradilan pada dasarnya mempunyai kekhususan dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga peradilan harus mandiri. Untuk menyeimbangkan kemandirian itulah keterbukaan informasi menjadi penting sebagai pertanggungjawaban terhadap publik. Hal ini yang mendasari mengapa keterbukaan informasi dalam institusi peradilan menjadi penting. Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai 1 Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahakamah Agung RI, 2010 85 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 dengan jajaran paling bawah demi terwjudnya penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas peradilan. Tujuan besar dari Teknologi Informasi adalah untuk meningkatkan manajemen internal dan akuntabilitas pengadilan.Hal ini telah disepakati sebagai satu pokok arahan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Jadi, kepemimpinan yang efektif atas semua aspek Teknologi Informasi sama pentingnya terhadap organisasi dan manajemen pengadilan modern dengan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan administrasi umum Tulisan ini mencoba untuk mencoba dan menganalisa bagaimana menyelenggarakan dan menyusun regulasi dan kebijakan serta kegiatan terhadap Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum dikaikan dengan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dalam perspektif integritas. B. Pembahasan Pada masa transisi dan pra pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan setiap Badan Publik wajib mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan stardar yang dapat menjamin ketersediaan informasi bagi layanan publik. Manajemen Teknologi Informasi merupakan permasalahan yang diidentifikasi oleh Mahkamah Agung sebagai kunci untuk mencapai visi pembaruan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010-2035. Tanpa mengesampingkan upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan manajemen informasi dan untuk memberikan askes publik terhadap informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan, masih terdapat banyak keluhan mengenai pelayanan Teknologi Informasi yang ada dan permintaan akan perluasan pelayanan. Mahkamah Agung juga menyadari perlunya suatu kerangka kebijakan dan protokol Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memfasilitasi praktek-praktek manajemen informasi modern tidak hanya di dalam Mahkamah Agung, tetapi juga di semua pengadilan di bawahnya. Hasilnya adalah sistem manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi yang hampir sama dengan akses informasi dan pelayanan pemrosesan informasi berbasis Teknologi Informasi, yang tersedia bagi pengguna melalui praktek-praktek bisnis modern yang dilaksanakan oleh organisasi sektor swasta terkemuka seperti perbankan dan retail. 86 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur Peran teknologi informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi mencakup kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengolah, menata, menyimpan sampai menyiapkan data dan informasi bagi layanan publik dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintah dan badan publik lainnya. Data dan Informasi disediakan oleh setiap satuan kerja di Badan Publik, dengan ketentuan: a. Badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi yang sudah ada. b. Pejabat Pengelola melekat pada fungsi unit kerja yang sudah ada. c. Informasi harus mengalir secara otomatis (automatically) d. Informasi harus sama dari tingkat pusat hingga daerah. B.1. Peraturan Pedukung Keterbukaan dan Pelayanan Informasi di Pengadilan B.1.1. UU Keterbukaan Informasi (UU No. 14 Tahun 2008) Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008. Keterbukaan informasi merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna mewujudkan kepemerintaahan yang baik (Good Governance) Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu 2. B.1.2. UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) Undang-Undang Pelayanan Publik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 3 2 3 http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik 87 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 B.1.3. SK KMA Keterbukaan Informasi di Pegadilan (SK KMA 1144/KMA/SK/I/2011) Dalam konteks keterbukaan informasi di Pengadilan, pilar kekuasaan ini telah lebih dulu memiliki peraturan internal yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Empat tahun kemudian pasca dikeluarkannya UU Kerterbukaan Informasi, Surat Keputusan KMA itu direvisi dengan Surat Keputusan KMA Nomor1144/KMA/SK/I/2011 dengan menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan. Ada 3 kategoriinformasi yang dikenal dalam SK 1-144/2011: 1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; 3. Informasi yang dikecualikan. B.1.4. SK KMA Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik. B.2. Pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk Reformasi Birokrasi Seorang pemimpin di Pengadilan harus mampu memberikan pemahaman bahwa reformasi tidak akan mengenakkan bagi sebagian orang, dan cenderung akan menimbulkan resistensi, sehingga harus siap melakukan melakukan manajemen perubahan. Para pemimpin juga harus memiliki karakteristik yang harus ditanamkan dan diperjuangkan. Seorang pemimpin harus visioner dan berpikir melebihi kemampuan orang (thinking ahead), berpikir terus menerus (thinking again) dan berpikir lintas batas (out of the box, out of the book). Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukanlah perkara mudah. Pimpinan harus menjadi contoh untuk mereformasi dan melakukan perubahan. Pimpinan perlu mengelola derajat perubahan yang seharusnya 88 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur terjadi di unit kerjanya. Pemimpin tidak hanya menjadi agen perubahan, tetapi pemimpin harus menjadi manajer perubahan itu sendiri.4 B.3. Standar Pelayanan Peradilan Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan pengadilan juga kan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara. Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masingmasing pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi kini dijadikan sebuah solusi praktis. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Tak terkecuali di pengadilan, hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Pelayanan seperi ini ini juga telah diterapkan di Mahkamah Agung Singapura dengan sangat representatif sebagai peradilan modern dengan E-Managementdan E-Litigation yang kesemuanya berbasis IT. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. 4 Holidin, Defny, Reformasi Birokrasi dalam Praktik, Jakarta, 2013, hal-iv 89 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 B.4. Fungsi dan Manfaat Informasi Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 1 mengartikan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Data-data yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasikan menjadi bahan awal untuk berbagai macam riset. Data jumlah perkara sebagai contoh, dapat dijadikan bahan untuk mengetahui sejauh mana case load sebuah pengadilan, beban perkara hakim, waktu yang harus dihabiskan untuk penangan perkara dan insentif bagi SDM. Informasi yang dikelola Mahkamah Agung maupun Pengadilan merupakan harta karun yang belum tergali. Kajian dan Pengelolaan atas informasi seperti : putusan, data statistik perkara, data jumlah dan penyebaran Hakim dan Pegawai atau data administrasi perkara, dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat 5 : a. Penentuan dan Perubahan Peraturan dan Kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja, dll) b. Mendorong Pembangunan Hukum dan Konsistensi Putusan c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim d. Evaluasi dan Monitoring Kinerja dan Integritas Hakim serta Pegawai e. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat atas Keadilan f. Meminimalisasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Kesalahpahaman g. Meningkatkan kepercayaan Publik. B.5. Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Peradilan Indonesia Adapun Pejabat Pokok yang harus ada di Mahkamah Agung maupun pada empat lingkungan Peradilan di bawahnya bagi terselenggaranya Keterbukaan Informasi Pengadilan ini sesuai SK KMA Nomor :1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan adalah sebagai berikut : PENGELOLA Atasan Pejabat Pengelola 5 PENGADILAN TINGKAT PERTAMA / BANDING Pengadilan Pengadilan Umum / TUN Agama / Militer Pimpinan Pengadilan Pimpinan Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perkara : Panitera MA Non Perkara : Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung:USAID-C4J, 2011, Hal 17-18 90 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur Informasi & Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Petugas Informasi Penanggung Jawab Informasi Sekretaris MA Panitera/Sekretaris Panitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV Perkara : Panitera/ Kepala Kepaniteraan Non Perkara : Sekretaris/ Ka TU Dalam Panitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV PPID MA : Kepala Biro Hukum & Humas, Badan Urusan Administrasi MARI PPID Satker : Setiap Dirjen/ Kepala Badan MA/BUA : Kasubag data & Pelayanan Informasi Ditjen : Kasubag Dokumentasi & Informasi Balitbangdiklat : Kasubag TU Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV Tabel Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan B.6. Media Pengumuman Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan B.6.1. Website Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan tidak harus mendatangi langsung karena dapat mengakses website resmi. Dengan website ini program transparansi informasi badan peradilan dapat diakses pencari Informasi, dimana Pencari Informasi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan dalam aplikasi perkara perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (justiciabelen). Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah membangun Sistem Informasi Perkara yang mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara, seperti : 1. Info Perkara Mahkamah Agung. 2. Direktori Perkara Mahkamah Agung. 91 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 3. CTS (Case Tracking System)/SIPP (Sistem Informasi Penelusuran alur Perkara) pada Peradilan Umum. 4. SIAD (Sistem Informasi Administrasi Perkara) - PTA/PA pada Peradilan Agama. 5. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara. 6. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – MIL pada Peradilan Militer. Penyediaaan layanan aplikasi perkara bertujuan agar : 1. Terciptanya tertib administrasi perkara di Pengadilan 2. Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal Pengadilan dan pihak lain yang membutuhkan informasi perkara 3. Informasi dapat di akses dengan baik oleh pencari keadilan serta masyarakat (keterbukaan informasi Pengadilan) 4. Tersedianya perangkat pendukung yang memberikan kemudahan administrasi dalam : Monitoring dan evaluasi perkara dengan adanya pengingat (reminder) setiap tahapan proses perkara Cari temu (search & found) data perkara Pelaporan otomatis untuk memperoleh gambaran kinerja pengelolaan perkara di pengadilan Analisis bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkara B.6.2. Meja Informasi Sarana yang wajib tersedia sebagai sumber informasi adalah Meja Informasi. Adanya meja informasi ini memudahkan para pencari informasi mendapatkan informasi yang diinginkan. Meja Informasi adalah suatu meja informasi sebagai pusatlayanan informasi publik terpadu dan pengaduan yang berada disatuan kerja, baik di Mahkamah Agung, pengadilan banding maupunpengadilan tingkat pertama. Diharapkan meja informasi ini menjadi pintu gerbang pengadilan bagi para pencari informasi yang kemudian nantinya akan diarahkan oleh petugas informasi kebagian bagian informasi yang mereka butuhkan. Mahkamah Agung maupun seluruh satuan kerja Pengadilan di Indonesia telah dilengkapi meja informasi yang telah memiliki standar penyelenggaraan sebuah meja informasi. 92 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur B.6.3. Papan Pengumuman Papan pengumuman adalah salah satu media komunikasi yang biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam lingkup tertentu. Media ini adalah salah satu media yang paling murah, paling diacuhkan dan paling efektif. Apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, maka papan pengumuman akan banyak menarik perhatian orang-orang yang berada dilingkup sekitar dimana papan itu berada. B.6.4. Humas (Hubungan Masyarakat) Eksistensi Humas pada institusi peradilan adalah sebuah keniscayaan. Humas sebagai perantara informasi badan peradilan dengan Publik. Peran Humas adalah untuk menjaga independensi, integritas dan kejujuran sangat dipegang teguh sehingga mereka tidak akan berada atau membiarkan berada dalam situasi apapun yang akan mengganggu independensi, integritas dan kejujurannya, termasuk mempengaruhi atau dipengaruhi media. Citra tersebut tak lepas dari peran humas.Sebagai pintu gerbang informasi, humas dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi. B.7. Tujuan jaminan hak masyarakat untuk mengakses Informasi Peradilan6 B.7.1. Perwujudan dari Hak Asasi Manusia Hak untuk mengakses informasi, termasuk informasi pengadilan, adalah salah satu hak yang dijamin dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 19) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UUD 1945. B.7.2. Bentuk Akuntabilitas Hakim dan Pengadilan Independensi Hakim dan Pengadilan bukanlah tanpa batas.Ia dibatasi oleh berbagai prinsip, termasuk prinsip keterbukaan sebagai sarana mendorong akuntabilitas. “Openness ensures that when judges sit at trial, [they also] stand on trial” (Aharon Barak). B.7.3. Sarana pendidikan Publik serta Pengembangan Hukum Keterbukaan informasi, khususnya putusan, dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan hukum.Tentunya jika keterbukaan ini dimanfaatkan oleh stakeholders Pengadilan untuk mengkritisi dan mendiskusikan putusan pengadilan. 6 Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung:USAID-C4J, 2011, Hal 5 93 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 B.7.4. Peningkatan Kepercayaan Publik Secara tidak langsung keterbukaan pengadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pelaksanaan keadilan (administration of justice). B.8. Sarana dan Prasarana Layanan publik perlu didukung sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan standar pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kebutuhan ini meliputi fasilitas penyimpanan dan penyediaan data dan informasi, sarana berupa peralatan penyimpanan, perangkat komputer dan printer, serta perangkat lunak seperti skema klasifikasi data dan informasi, kode klasifikasi, indeks, serta sistem database yang didesign dengan software aplikasi yang sesuai kebutuhan. Fasilitas ini sebaiknya memenuhi standar minimal yang mampu memberikan kemudahan operasional pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik. Untuk memenuhi standar minimal setidaknya perlu tersedia rungan penyimpanan data dan informasi, ruang pengolahan data dan informasi serta ruang kerja pimpinan dan staf unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi. B.9. Keamanan Kedepan, aspek keamanan juga menjadi titik fokus Mahkamah Agung. Arsitektur gedung pengadilan sangat berperan dalam menjaga keamanan pengadilan. Untuk menjamin independensi, hakim tidak akan pernah berjumpa dengan para pihak karena memiliki jalan khusus. Terdakwa juga tidak akan berpapasan di ruang terbuka dengan korban atau saksi karena mereka memiliki jalan masuk dan keluar yang khusus. Pengamanan ruang tahanan dijaga dengan perbandingan dua petugas keamanan dan satu terdakwa. Untuk perkara-perkara yang sangat khusus keamanan ruang sidang dan para pihak diatur secara khusus. B.10. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi Hukum menjamin hak Pemohon Informasi untuk menempuh upaya hukum bila tidak puas atas pelayanan informasi oleh Petugas Informasi atau PPID Pengadilan: 94 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur Jika Tidak Puas dengan Layanan Petugas/PPID ??? Gambar Alur Mekanisme dan Sengketa Informasi Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan, sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, Pemohon harus menempuh Keberatan dahulu. Sebelum menggugat ke PN/PTUN, harus melalui Komisi Informasi dahulu.Alasan Pengajuan Keberatan antara lain : a. Permohonan informasi ditolak : b. Tidak diumumkannya informasi yang wajib diumumkan c. Permohonan informasi tidak ditanggapi d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan e. Permintaan informasi tidak dipenuhi f. Pemohom dimintai biaya yang tidak wajar B.11. Sanksi Pidana, Administratif dan Gugatan Peradata B.11.1. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pasal 51 UU No. 14/2008 ... sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum. Pasal 52 UU No. 14/2008 ... sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau yang harus diberikan atas permintaan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 53 UU No. 14/2008 ... sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Sanksi Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000,00 Kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000,00 Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal 95 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 Tindak Pidana Publik yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pasal 54 UU No. 14/2008 .... sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan. Sanksi Rp 10.000.000,00 Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 ATAU Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (tergantung informasi rahasia apa yang dibuka) Pasal 55 UU No. 14/2008 ... sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain. Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00. B.11.2. Administratif Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 (SK 1-144) Menurut dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan tertentu dalam UU tersebut (misalnya tidak mengumumkan informasi seperti profl penyelenggara, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan) diancam sanksi penurunan gaji (Pasal 54 [5]). B.11.3. Gugatan Perdata Implisit dimungkinkan pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum jika badan publik tidak menjalankan kewajibannya sesuai UU dan mengakibatkan kerugian bagi seseorang. C. Kesimpulan Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan insturmentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk 96 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ada beberapa hasil kemajuan pembaharuan yang telah diperoleh Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya melalui pemanfaat teknologi informasi, antara lain : 1. Perekaman Proses Persidangan Perkara Tipikor dan Perkara Menarik Perhatian Publik Lainnya 2. Standarisasi template putusan dan pemberlakuan E-document 3. Modernisasi Manajemen Perkara pada melalui Implementasi Aplikasi Perkara di Pengadilan 4. Badan diklat MA menggunaan sistem E-Learning dalam sistem pembelajaran. 5. Sistem penggandaan dan pembacaan berkas secara elektronik yang merupakan implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali 6. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset, MA mendapat penghargaan Laporan Keuangan denga Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 7. Proses E-Manajemen seperti Lelang Online (LPSE), RKAKL Online, SIMPEG dan lain-lain. Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwjudnya good governance. Dalam menjaga konsistensi penerapan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Atasan PPID, PPID, Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi berdedikasi untuk menjadi organ pelaksana pelayanan pengadilan merupakan salah satu faktor sangat penting. Mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam melayani permohonan informasi. Perlu diadakan sosialisai kepada masyarakat akan adanya Keterbukaan Informasi Badan Publik teruatam Keterbukaan Informasi pada badan peradilan yang pada akhirnya sudah tidak pada 97 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 tempatnya lagi sekarang menyalahkan peradilan karena tidak membuka akses informasi kepada masyarakt. Justru kenyataannya berbalik, adalah menjadi tanggung jawaban komuitas hukum untuk memanfaatkan serta merespon keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh badan peradilan. Tolok ukur sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Faktor kepuasaan masyarakat tersebut akan jatuh pada lembaga pelayanan publik yang baik dan koperatif. Terbukti pada tahun 2014, Mahkamah Agung mendapatkan Penghargaan tertinggi untuk survey integritas sektor publik tahun 2013 dari KPK. Sudah jadi kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan warganya lewat pelayanan publik.Kualitas pelaksanaannya yang dilakukan oleh perangkat negara adalah penanda kinerja sebuah lembaga publik. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor yang menjamin kesejahteraan rakyat. Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan harus diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Daftar Pustaka _________, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008 _________, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008 _________, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelayanani Publik, UU No. 25 Tahun 2009 _________, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, No. 1-144/KMA/SK/I/2011 _________, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, No. 026/KMA/SK/II/2012 _________, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, No. 1 Tahun 2010 Holidin, Defny, Reformasi Birokrasi dalam Praktik, Jakarta, 2013 Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung: USAID-C4J, 2011 98 Keterbukaan Informasi di Peradilan, Ridwan Mansyur Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahakamah Agung RI, 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_ Publik http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik 99 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 83-100 100 ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 20031 (The Revere Burden of Proof Against Corruption Law in Indonesian Criminal Law System Related With The 2003 United Nations Convention Against Corruption) Lilik Mulyadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl. Laksamana RE. Martadinata No.4, Ancol Selatan, Jakarta Utara Email : [email protected] Abstrak Artikel ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003. Terdapat 2 pertanyaan mendasar yang menjadi obyek penelitian, pertama: sejauh mana pergeseran beban pembuktian telah dilaksanakan di pengadilan pidana tentang kasus korupsi, dan kedua, untuk sejauh mana kebijakan legislasi berlaku untuk pergeseran beban pembuktian dalam kaitannya dengan UNCAC 2003. Artikel ini menggunakan penelitian normatif berupa regulasi, konseptual, kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian tersebut menekankan interpretasi dan konstruksi hukum untuk memperoleh beberapa norma hukum, konsepsi, daftar peraturan dan implementasinya dalam kasus nyata. Peraturan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui, keberadaan, konsistensi dan harmonisasi mengenai pergeseran beban pembuktian atas tindak pidana korupsi dalam tubuh Undang-Undang. Pendekatan kasus menggunakan perbandingan hukum mengenai beban pembalikan pembuktian atas korupsi offencer antara Indonesia dan negaranegara lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian tidak pernah diterapkan untuk kasus korupsi di Indonesia. Pengalaman mereka tidak sama dengan pengalaman melawan korupsi di Hong Kong dan India, wihich menerapkan beban pembalikan pembuktian dengan 1 Artikel ini merupakan ringkasan disertasi penulis yang telah dipertahankan pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 19 September 2007 dengan predikat cumlaude 101 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 menggunakan beberapa pendekatan yang disebut probabilitas seimbang prinsip dalam kaitannya dengan properti atau aset yang berasal dari terdakwa. Kebijakan regulasi korupsi Indonesia, khususnya pasal 12B, 37, 37A, 38B ternyata itu tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pungutan langsung warisan pergeseran beban formulasi bukti sehubungan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Jadi, diperlukan (kebutuhan) dari modifikasi biaya pergeseran beban pembuktian formulasi yang preventif, represif dan restoratif. Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Hukum Pidana Indonesia Abstract This article describes some problems of the result of research regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in the Indonesian system of criminal law with regards UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. There are two basic questions which become the research objections, firstly: to what extent the shifting of burden of proof has been implemented in the criminal court regarding corruption cases, and secondly, to what extent does the legislation policy apply for the shifting of burden of proof in relation with UNCAC 2003. The article uses normative research which regulation, conceptual, case and comparative approach. Such research emphasizes interpretation and legal construction to obtain some legal norms, conception, regulation list and its implementation in concreto cases. Regulation and conceptual approach to used how to know, existention, consistency and harmonization regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in legislation body. The cases approach uses comparative law regarding the reversal burden of proof upon corruption offencer between Indonesia and the other countries. This research shows that the shifting of burden of proof has never yet applied for in the corruption cases Indonesia. Those experiences is not similar with the experiences of against corruption Hong Kong and India, wihich implement the reversal burden of proof by using some approach socalled balanced probability of principles in the relation to the property or asset of defendant comes from. The Indonesian corruption regulation policy, especialy article 12B, 37, 37A, 38B apparently it’s not cleaq and disharmony to norm of sudden charge of fortune the shifting of burden of proof formulation in connection with United Nations Convention Against Corruption 2003(KAK 2003). So, necessary (needs) of modification sudden charge of fortune shifting of burden of proof formulation which preventive, represive and restorative characteristic. 102 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Keywords : Shifting the Burden of Proof, Corruption Offences, Criminal Justice System A. Pendahuluan Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya maka dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Lebih lanjut, menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bijzondere belangen). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukum pidana formal (“Formeel Strafrecht” / “Strafprocesrecht”).2 Dikaji dari perspektif sejarahnya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi3 menyebutkan bahwa hukum pidana yang bersifat hukum publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui suatu perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat. Konsekuensi logis dimensi perkembangan hukum pidana sebagaimana konteks di atas, ada sifat privat dari hukum pidana. Seiring berjalannya waktu dan masyarakat hukum yang relatif lebih maju maka hukum pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik seperti dikenal sekarang ini. Secara gradual, hukum pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang 2 Lebih detail dapat dilihat: L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 171, Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas PasalPasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 5, J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 2-3, A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 4-5, H. Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006, hlm. 37, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 73-75, Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1970, dalam: Yurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1970, hlm. 143-146 dan Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3 3 E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996, hlm. 38 103 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak. Selanjutnya, ketentuan hukum pidana sesuai konteks di atas dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus (bijzonder lijkfeiten) 4. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003)5 mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disingkat KAK 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan subtansi gabungan dua sistem hukum yaitu “Civil Law” dan “Common Law”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Romli Atmasasmita menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment) dimana ketentuan Pasal 20 (United Nations 4 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandsche Strafrecht, NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwollo, 1959, Hlm. 32-33, H.J.A. Nolte, Het Strafrecht en de Alzonderlijke Welten, Nijmegen: Utrecht-Dekker & von de vegt, 1949, hlm. 97, Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 61 dan E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.Cit, hlm. 22. 5 Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 dan Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1., dan vide pula: Romli Atmasasmita, Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di Sektor Swasta Dalam Lingkup Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 7, serta: Romli Atmasasmita, Indonesia Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 5 dan: Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 3 104 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Convention Against Coruuption (UNCAC) 2003 menentukan, bahwa: ...each State Party shall consider adopting... to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income” 6. Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Goverment” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa : 1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official): a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“can destroy the potential effectiveeness of all types of govermental programmes”) b. Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”). c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“victimize individuals and groups”). 2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.7 Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.8 Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (law making policy dan law enforcement policy), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat Administrative Penal 6 Romli Atmasasmita, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 9-10 dan vide pula: Romli Atmasasmita, Desain Pemberantasan Korupsi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 2 7 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69 dan vide pula: Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 148 8 Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan ..., Op.Cit, hlm. 1 105 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 Law.9 Melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) maka telah ada peraturan Perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (ius constitutum) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.10 Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sebagaimana dikemukakan. Romli Atmasasmita, bahwa: “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crimes). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia 11. 9 Dalam konteks Hukum Pidana maka istilah Administrative Penal Law adalah semua produk legislasi berupa Perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Tidak semua Administrative Penal Law merupakan tindak pidana korupsi, dan untuk menentukannya sebagai tindak pidana korupsi harus mengacu kepada ketentuan Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan ”Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidan korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal tersebut di atas memegang teguh asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generali karena melalui penafsiran secara a contrario Pasal 14 menentukan, selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam undangundang lain merupakan tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan. (Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 45 dan vide: Indriyanto Seno Adjie, ”Kendala Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang”, Paper, Jakarta, 2007, hlm.5 serta: Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 40) 10 Hukum Positif (ius constitutum) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 11 Tahun 2005, Inppres Nomor 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya. 11 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25 dan vide pula: Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111 106 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia (SHPI) meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian. Secara teoritik asasnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam UndangUndang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undangundang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Pada UU tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. Pertama, pembalikan beban pembuktian12 dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian 12 Ada beberapa terminologi untuk menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia) yaitu Shifting of burden of proof atau Reversal burden of proof (Inggris), Omkering van de bewijslast (Belanda), dan Onus of Proof (Latin) 107 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (in strijd met zijn plicht) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok. Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan “bribery” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “Prevention of Corruption Act 1916” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (Presumption of corruption in certain cases) yang redaksional berbunyi sebagai berikut: “where in any proceeding against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1906, or the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, it is proved that any money, gift, or other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from His Majesty or any Goverment Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such 108 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi inducement or reward as in mentioned in such Act unless the contrary is proved” 13. Di Malaysia atas dasar Pasal 42 Akta Pencegahan Rasuah 1997 (“Anti Corruption Act 1997 (Act 575)”) yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 1998 menentukan: “Where in any proceeding against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be acepted, obtained, or attempted to be abtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved” 14. Berikutnya di Singapura, atas dasar “Prevention of Corruption Act (Chapter 241)” ditegaskan pula sebagai berikut: “Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Goverment or any department there of or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Goverment or any department there of or any public body, that grafitication shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as a inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved” 15. Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian 16 dikenal juga dalam rumpun hukum Eropa 13 Muladi, Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof), Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001, hlm. 122. 14 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 53 15 Muladi, Sistem Pembuktian ....., Op. Cit., hlm. 123 dan vide pula: M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Penerbit Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm. 31 16 Dalam ketentuan UU 20/2001 maka dikenal pembalikan beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut/mutlak seperti ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 38 B yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata, dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b dan Pasal 38 C UU 20/2001 dan terdakwa maupun Penuntut Umum secara berimbang membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 37 dan 37A. 109 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 Kontinental seperti Indonesia. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Dimensi ini diakui Oliver Stolpe bahwa: “One of the most difficult issues facing prosecutors in large-scale corruption cases is meeting the basic burden of proof when prosecuting offenders and seeking to recover proceeds”. 17 Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian (shifting of burden proof) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi, walaupun pembalikan beban pembuktian dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi delik penyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam praktik hal ini telah diterapkan Pengadilan Tinggi Hongkong (Court of Appeal of Hong Kong) berdasarkan ketentuan Pasal 11 17 Oliver Stolpe, Meeting the burden of proof in corruption-related legal proceedings, unpublished, hlm. 1 110 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi ayat (1) Hong Kong Bill of Rights Ordinance 1991 18. Apabila dikaji secara selayang pandang dimensi filosofis mengapa kebijakan legislasi menterapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi disebabkan ada kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (offender) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya, diperlukan ada aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian sehingga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga tetap memperlakukan sistem pembuktian beyond reasonable doubt. Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan problematika. Pertama, ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembalikan beban pembuktian. Kedua, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Krusial dapat dikatakan, walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada 18 Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 antara Attorney-General of Hong Kong v Hui Kin Hong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 (Section 10 of the Prevention of Bribery Ordinance of Hong Kong) meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa Hui Kin Hong tidak melakukan korupsi. PT Hong Kong berpendapat sebelum terdakwa dipanggil membuktikan asal usul kekayaan yang jauh melebihi penghasilannya maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu secara “beyond reasonable doubt”, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Apabila penuntut umum dapat membuktikan seluruhnya, maka kewajiban terdakwa menjelaskan bagaimana dapat hidup mampu dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya untuk mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan tersebut. Apabila pembuktian tersebut telah dilakukan maka PT Hong Kong harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standart hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya. PT Hong Kong berpendapat proses acara itu tidak bertentangan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong (Articel 11Hong Kong Bill of Rights Ordinance Nomor 59 Tahun 1991) karena terdakwa sudah diberikan haknya untuk menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta kekayaannya dan juga penuntut umum sudah diwajibkan untuk membuktikan hal-hal tersebut, sistem pembuktian seperti ini, disebut sistem “balance probabilities”. 111 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 dirinya. Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk Undang-Undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Ketiga, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Keempat, pasca berlakunya KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (civil procedure) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi. Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12B UU UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37A in casu hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, dari apa yang telah diuraikan konteks di atas ternyata dimensi pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menurut ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ditemukan ketidakharmonisan normanya terlebih lagi dihubungkan dengan KAK 2003. Pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Anglo Saxon atau Case Law pada Negara Malaysia, Singapura, Inggris dan lain sebagainya mengenal pembalikan beban pembuktian diterapkan terbatas terhadap perkara-perkara tertentu (“certain cases”) yang berkaitan dengan 112 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi tindak pidana korupsi, khususnya pemberian (“gratification”) dalam konteks penyuapan (“bribery”). Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi jikalau dihubungkan dengan KAK 2003 dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya pasca berlakunya KAK 2003. Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya terutama menyangkut asal usul kekayaan pelaku dengan implikasi adanya KAK 2003 yang sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia. B. Metode Pendekatan Tulisan ini mempergunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif. Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, terutama terhadap bahan yang ada hubungannya dengan obyek penulisan ini. C. Tinjauan Pustaka Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga. Secara konseptual maka teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (rechts zekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights). Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. 113 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 Substansi elementer dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (equality) juga pembatasan (restriction). Batas-batas kekuasaan ini juga berubahubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Keduaduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Roescoe Pound19 menyebutkan ada dua kebutuhan pentingnya pemikiran secara filosofis tentang negara hukum. Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum. Kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban guna mewujudkan keamanan mendorong manusia mencari aturan yang mengatur manusia terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa maupun individu sehingga dapat mendirikan suatu masyarakat yang mantap. Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum dan membuat kompromi-kompromi baru secara terus menerus dalam masyarakat karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan adanya penyesuaianpenyesuaian agar tercapai suatu hukum yang sempurna. Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma 20. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (wholes), memiliki beberapa elemen (elements), semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian membentuk struktur (structure) 21. Lawrence M. Friedman, menyebutkan sistem hukum dalam arti luas dengan tiga elemen yaitu struktural (structure), substansi (substance) dan budaya hukum (legal culture) 22. Ketiga elemen tersebut saling mempunyai korelasi erat. Lawrence M. Friedman lebih lanjut mendeskripsikan ketiga elemen sistem hukum tersebut diumpamakan sebuah mesin dimana budaya hukum sebagai bahan bakar yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut. Konsekuensi aspek ini maka budaya hukum begitu urgen sifatnya. Oleh karena itu, tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti seekor ikan mati yang terkapar di dalam keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di lautan.23 19 Roescoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven, 1959, hlm. 107 20 Hans Kelsen, Loc. Cit. 21 Charles Sampford, Loc. Cit. 22 Lawrence Friedman, Loc. Cit. 23 Lawrence Friedman, American Law..., Op. Cit., hlm. 7 menyebutkan dengan terminologi, “without legal culture, the legal system is inert – a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”. 114 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial 24. Sistem Hukum Pidana asasnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic), adanya asas-asas hukum (legal principles), adanya norma atau peraturan Perundang-undangan (legal rules) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (legal society). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat 25. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum maka asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum 26. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan ”jantungnya” peraturan hukum 27. Paul Scholten memformulasikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.28 Lebih lanjut, menurut J.J.H. Bruggink, maka asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya sehingga asas-asas hukum itu berada baik di dalam sistem hukum maupun di belakangnya.29 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, menyebutkan asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin tengah yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer) 30. Roeslan Saleh, selanjutnya menegaskan, bahwa : ”...tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstitutif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat 24 Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems (London, Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4-5, dikutif dari: Barda Nawawi Arief, Loc. Cit. 25 Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22 26 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Penerbit Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hlm. 5 27 Satjipto Rahardjo, Ilmu ...., Op. Cit., hlm. 45 28 J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang..., Op. Cit., hlm. 119-1 2 0 29 J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi..., Ibid, hlm. 122 30 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9 115 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non-hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum” 31. Pendapat Marc Ancel dan A. Mulder memberikan pengertian sistem hukum pidana meliputi 2 (dua) aspek krusial yaitu mengenai sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Secara singkat maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Oleh karena itu, maka sistem pemidanaan merupakan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan lingkup sistem hukum pidana. Sistem Hukum Pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansial. Analisis dari sudut fungsional dimaksudkan berfungsinya sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundangan-undangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Barda Nawawi Arief 32 secara lengkap membagi sistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal, dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Oleh karena itu, maka ketiga subsistem tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan satu subsistem saja. Kemudian dari sudut substantif diartikan sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan Perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). 33 Sistem Hukum Pidana selain mempunyai dimensi sistem pemidanaan bersifat fungsional dan substansial maka menurut asumsi dan batasan dari Marc Ancel serta A. Mulder berorientasi juga dengan pembaharuan hukum pidana. Barda Nawawi Arief melihat upaya pembaharuan hukum pidana (“penal reform”) pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “law enforcement policy”, “criminal policy”, dan “social policy.”34 Aspek ini dapat diartikan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum (legal substance), bagian kebijakan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai 31 Roeslan Saleh, Ibid. Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 262 33 Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 263 34 Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 3 32 116 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi social defence dan social welfare dan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“value oriented approach”).35 Mudzakkir36 menyebutkan pembaharuan hukum pidana terjadi melalui beberapa kemungkinan. Pertama, pembaharuan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (bottom up). Kedua, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen di bawahnya (top down). Ketiga, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai atau elemen masyarakat hukum tidak secara otomatis membawa pergeseran hukum tetapi hukum yang berlaku diberi perspektif baru sesuai nilai baru atau keadaan baru tersebut. D. Praktik Pembuktian Perkara Tindak di Hong Kong dan India Praktik pembuktian kasus korupsi dengan pembalikan beban pembuktian di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Akan tetapi, praktik pembuktian perkara tindak pidana korupsi di beberapa negara telah dilaksanakan seperti di Hong Kong dan India. Pada kasus di Hong Kong Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara The Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong dan The Attorney General of Hong Kong v Lee Kwong Kut 37 Konklusi dasar kasus di atas memberikan deskripsi memadai bahwa Pengadilan Tinggi Hong Kong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa Hui Kin Hong tidak melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Hong Kong berpendapat bahwa sebelum terdakwa dipanggil untuk membuktikan tentang asal usul kekayaannya yang jauh melebihi penghasilannya maka jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu secara “beyond reasonable doubt”, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Apabila penuntut umum dapat membuktikan seluruhnya, maka kewajiban terdakwa untuk menjelaskan bagaimana yang 35 Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 3-4 Mudzakkir, Op. Cit., hlm. 159 37 Hong Kong Legal Information Institute melalui http://www.hklii.org/cgihklii.org /disp.pl/hk/jud/en/hkca/1997/CACC000722%5f1995.html?queryz%7e+hui+kin+hong didownload pada tanggal 15 Januari 2007 36 117 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 bersangkutan dapat hidup mampu dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya atau bagaimana terdakwa Hui Kin Hong mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan atau harta kekayaan tersebut. Pengadilan Tinggi Hong Kong kemudian harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standrat hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya. Secara gradual asumsi dasar polarisasi demikian maka Pengadilan Tinggi Hong Kong berpendapat bahwa, dengan proses acara seperti itu tidak ada pertentangan dengan konstitusi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong karena yang bersangkutan sudah diberikan haknya untuk menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta kekayaan terdakwa dan juga jaksa penuntut umum sudah diwajibkan untuk membuktikan hal-hal tersebut.38 Pembalikan beban pembuktian yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 terhadap terdakwa Hui Kin Hong maka untuk itu terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum membuktikan terhadap diri terdakwa tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Pada dasarnya, teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya. Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan pada hakikatnya tetap mempertahankan prinsip pembuktian “beyond reasonable doubt” yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan terdakwa. Sistem pembuktian yang bersifat “berimbang” atau “balance probabilities” tersebut pada pokoknya menempatkan HAM pelaku tindak pidana korupsi pada level yang paling tinggi karena apabila tidak ditempatkan seperti itu akan rentan terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara, instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian dengan demikian pada level yang paling bawah secara bersamaan maka pelaku tindak pidana korupsi membuktikan beban pembuktian terbalik terhadap asal usul mengenai harta kekayaannya yang diduga berasal dari delik korupsi. Dalam praktiknya maka sistem “balance probabilities” bukan saja diterapkan pada kasus korupsi akan tetapi juga diterapkan terhadap kasus narkotika, hasil pemilihan umum, HAM, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk kasus narkotika pada kasus Salabiaku v France 13 EHRR 379, Hoang v France 16 EHRR 53, hasil pemilihan umum pada kasus R v DPP ex parte Kebilane (2000) 2 AC 326, Brown v Scott (2001) 2 WLR 817, kasus HAM pada Drozd and Janousek v France (1992) 14 EHRR 745, dan lain sebagainya. 38 118 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Bertrand de Speville dengan titik tolak dari Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong sebagaimana konteks di atas secara eksplisit menyatakan pembalikan beban pembuktian secara “balanced probabilities” antara Jaksa dan terdakwa yaitu Jaksa membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta bendanya tersebut tidak bertentangan dengan HAM.39 Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe 40 menyebutkan ada korelasi erat antara asas praduga tidak bersalah dengan aspek pembalikan beban pembuktian dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi. Apabila dijabarkan, korelasi dimensi tersebut disatu sisi untuk mendapatkan keseimbangan hak antara kebutuhan masyarakat melindungi diri dari praktik korupsi dan disisi lain implisit mensiratkan adanya kebutuhan atas rasa aman dari tuduhan yang tidak adil, gangguan secara tidak adil ke dalam hak milik seseorang atau kesalahan atas penghukuman. Kemudian terhadap praktik di India berdasarkan Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255).41 Putusan Mahkamah Agung India (Supreme Court of India) dalam putusannya melalui register perkara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) kemudian menyatakan bahwa terdakwa A. Vaidnyanatha Iyer dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan beban pembuktian dari terdakwa dan penuntut umum telah terbukti bahwa apa yang diterima terdakwa berupa uang sejumlah Rs. 800 tersebut merupakan perbuatan korupsi dan bukan merupakan pinjaman. Dikaji dari perpektif hukum pembuktian maka perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung India antara State of Madras selaku pemohon kasasi dengan A. Vaidnyanatha Iyer termohon kasasi dibawah register perkara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) menyatakan beban pembuktian adalah 39 Bertrand de Speville, Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms, The Papers, 8th International Anti-Corruption Conference, hlm. 4-6 melalui http://ww1.transparency.org/iacc/ 8th_iacc/papers/despeville.html di down load pada tanggal 23 Desember 2006 40 Nihal Jayawikrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe, Legal Provisions to Facilitate, Op.Cit, hlm. 23 dan Bertrand de Speville, Reversing the Onus, Op.Cit., hlm. 7-8 41 World Legal Information Institute melalui http://72.14.235.104/search? q=cache: eNJF 5hI4VcJ:scc.lexum.umontreal.ca/en/1988/1988rcs2903/ 1988rcs2903. pdf+ judgment+ balanced+of+probabilities+bribery&hl=id&gl=id&ct= clnk&cd=14& client= firefox-a didownload pada tanggal 5 Februari 2007 119 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 pada Penuntut Umum sebelum ditemukan fakta hukum yang mengharuskan terdakwa membuktikan sebaliknya dengan pembalikan beban pembuktian. Pada kasus a quo maka fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah Agung India ternyata uang sejumlah Rs. 800 ada pada terdakwa sehingga di samping Penuntut Umum maka terdakwa juga harus membuktikan bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh terdakwa dari korban bukan sebagai pemberian yang dikualifikasikan melanggar hukum dalam hukum pidana akan tetapi merupakan pinjaman yang bersifat hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) maka walaupun ketentuan pasal tersebut menentukan asas umum bahwa dugaan tindak pidana kepada terdakwa Penuntut Umum yang membuktikan akan tetapi dalam kasus korupsi asas tersebut dapat disimpangi dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang yaitu baik terdakwa maupun Penuntut Umum untuk saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa. Pada dasarnya, kasus a quo identik dengan kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503), Ikramuddin v The State of India (1958 Kar. 21), Ghulam Muhammad v The State of India (1980 P.Cr. L.J. 1039) dan Putusan Badshah Hussain v The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299).42 Pada kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503) kaidah dasarnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa begitu uang yang ditandai telah ditemukan pada diri terdakwa maka kewajiban untuk menerangkan bagaimana terdakwa menerimanya serta bagaimana uang tersebut dapat berpindah tangan pembuktian ada pada diri terdakwa. Jadi pengadilan tidak dapat menerima adanya pembuktian dari terdakwa bahwa uang tersebut didapatkan terdakwa dengan tidak meminta dari yang bersangkutan dan pemberian tersebut adalah pemberian hadiah yang tidak melawan hukum. Begitu juga dasar pertimbangan dalam kasus ini identik dengan dasar pertimbangan pada putusan Badshah Hussain v The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299) yang menyatakan bahwa, “begitu uang yang telah ditandai tersebut dikembalikan dan dipindahtangankan kepada terdakwa maka beban pembuktian ada pada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947). Apabila dijabarkan lebih detail maka perspektif pembuktian kasus hukum India ini maka identik dengan hukum pembuktian dari Negara Pakistan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Pakistan antara 42 World Legal Information Institute melalui http://72.14.235.104/search?q= cache: eNJF5hI4VcJ:scc.lexum.umontreal.ca/en/1988/1988rcs2903/1988rcs2903. pdf+ judgment+ balanced+of+probabilities+bribery&hl=id&gl=id&ct=c lnk&cd= 14 & client= firefox-a didownload pada tanggal 7 Februari 2007 120 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Khan Asfandyar Wali v Federation of Pakistan, Abdul Razak Rathore v The State PLD 1992 Karachi 39, Al-Jehad Trust v Federation of Pakistan 1996 S.C. 324 43. Dikaji dari hukum pembuktian pada umumnya dan pembalikan beban pembuktian pada khususnya maka praktik pembuktian kasus korupsi di beberapa Negara terdapat praktik yang berlainan. Di Indonesia maka sistem pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diterapkan adalah bersifat negatif atau berdasarkan asas “beyond reasonable doubt” yang berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP.44 Tegasnya, praktik perkara korupsi di Indonesia pada tataran aplikatifnya tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian padahal perangkat hukum memberikan hak kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk menterapkan Akan tetapi praktik perkara tindak pidana korupsi di beberapa Negara berlainan dengan Negara Indonesia. Pada Negara Hong Kong dan India maka pembalikan beban pembuktian diterapkan dengan “balance probabilities” dimana baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama membuktikan. Eksplisit Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sedangkan Terdakwa membuktikan asal usul kepemilikan harta bendanya. Pada Negara Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General of Hong Kong v Lee Kwang Kut) merupakan kajian subtansial dimensi di atas. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 antara Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong maka pembuktian bersifat balance probabilities 45 tersebut diimplementasikan dengan bentuk 43 Judicial Indepedence Pakistan melalui http://72.14.235.104/search?q= cache: mOZ1WFmq SAYJ: merln.ndu.edu/archive/icg/judicialindependenceinpakistan.pdf+ Khan+Asfandyar+ Wali+v.+Federation+of+Pakistan,+PLD.+2001+Supreme+Court+607,+883884.+223&hl=id &gl=id&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a didownload pada tanggal 2 Januari 2007 44 Redaksional ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Hampir identik dengan pasal tersebut di atas maka ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” 45 Pada hakikatnya dengan pelbagai bentuk dan manifestasinya maka pembuktian “balance probabilities” juga dikenal dalam praktik perkara perdata (civil prosedure). Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUH Perdata maka ditentukan, “barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hal orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.” Dalam praktik dimana adanya dua akta autentik maka beban pembuktian diterapkan secara “balance probabilities” yang dilakukan 121 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 Jaksa Penuntut Umum diberikan beban pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan status terdakwa Hui Kin Hong (Senior Estate Surveyor of the Bulildings and Lands Department of the Hong Kong Goverment) adalah sebagai pembantu kerajaan dan membuktikan total biaya hidup yang dilakukan olehnya selama masa dakwaan, kemudian Penuntut Umum harus membuktikan keseluruhan jumlah kekayaan selama periode tersebut sehingga diperkirakan kekayaan yang dinikmati selama ini di luar kewajaran dari kekayaan resminya. Setelah itu kemudian baru terdakwa Hui Kin Hong diberikan beban pembuktian harus membuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 (Section 10 of the Prevention of Bribery Ordinance of Hong Kong) yang berbunyi “setiap orang yang menjadi atau telah menjadi pembantu ratu menyelenggarakan taraf hidup yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari penugasan resminya selama ini,” dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Ordonansi Pencegahan Penyuapan Bab 201 tentang, “mengontrol sumber daya keuangan yang sebanding dengan penugasan resminya selama ini, kecuali tidak dapat memberi penjelasan memuaskan kepada pengadilan tentang taraf hidup atau sumber daya keuangan yang berada di bawah kontrolnya, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana”, merupakan kewajiban terdakwa memberikan penjelasan untuk membuktikannya. Konsekuensi logis pembuktian demikian maka dasar pertimbangan (ratio decidenci) Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 menyatakan pembalikan beban pembuktian demikian tidak bertentangan dengan ketentuan asas praduga tidak bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong (Articel 11 Hong Kong Bill of Rights Ordinance Nomor 59 Tahun 1991) yang berbunyi, “setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya menurut hukum”. Begitu pula aspek dan dimensi pembalikan beban pembuktian ini selaras dan identik dengan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 90 Tahun 1992 tanggal 18 Juni 1992 antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut). Praktik perkara tindak pidana korupsi di Negara India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Selain itu, di luar Indonesia, salah satu misalnya pada Republik Vanuatu dimana Mahkamah Agung Republik Vanuatu dalam Putusan Naukaut V Naunun (1999) VUSC 2; Election Petition No 031 of 1998 (27 Januari 1999) antara Shem Naukut (Penggugat) melawan Harris Laris Naunun dkk (Para Tergugat) dimana Mahkamah Agung menetapkan beban pembuktian secara “balance probabilities” dimana baik Penggugat maupun Para Tergugat diwajibkan membuktikan bahwa hasil pemilu Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 1998 untuk daerah pemilihan Tanna dilakukan dengan kecurangan karena adanya suap. 122 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) juga menterapkan asas pembalikan beban pembuktian. Pada Putusan Mahkamah Agung India dibawah register perkara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) beban pembuktian diimplementasikan pada kasus a quo ditemukan fakta hukum uang sejumlah Rs 800 ada pada terdakwa sehingga beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang tersebut sedangkan terdakwa diwajibkan untuk membuktikan uang itu diperoleh terdakwa bukan sebagai pemberian (gratification) yang dikualifikasikan melanggar hukum pidana akan tetapi merupakan pinjaman yang bersifat hukum perdata. Pada dasarnya, dikaji dari perspektif hukum pembuktian maka pembuktian bersifat berimbang atau “balance probabilities” juga diikuti dalam Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) serta juga diterapkan dalam praktik peradilan kasus korupsi di Negara Pakistan sebagaimana dalam kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503), Ikramuddin v The State of India (1958 Kar. 21), Ghulam Muhammad v The State of India (1980 P.Cr. L.J. 1039) dan Putusan Badshah Hussain v The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299). E. Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dikaji dari aspek kebijakan legislasi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia terhadap pembalikan beban pembuktian sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan Perundang-undangan korupsi disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (extra ordinary measures). Selanjutnya kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”. Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka tersangka tidak 123 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya. Kebijakan legislasi dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal: a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum. (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim. (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 124 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Politik hukum46 Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan otentik ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa: Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistim pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk) Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 masih terdapat kelemahannya dan selanjutnya telah dilakukan perbaikan-perbaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Perbaikan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian terhadap responden tentang pengetahuan mengenai pengaturan kasus korupsi dengan pembalikan beban pembuktian dalam 46 Pengertian politik hukum dapat dikaji dari perspektif etimologis maupun dari perspektif terminologis. Dari perspektif terminologis menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. (Padmo Wahjono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Majalah Forum Keadilan, Nomor 29, April 1991, hlm. 65). Teuku Mohammad Radhie menyebutkan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. (Teuku Mohommad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 4). Soedarto menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. (Soedarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, Majalah Hukum dan Keadilan, Nomor 5 Tahun VII, JanuariFebruari 1979, hlm. 15-17) dan Satjipto Rahardjo mendifinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ..., Op. Cit., hlm. 352). 125 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 pasal-pasal berikut menunjukan hasil seperti tersebut pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Pengetahuan Responden Mengenai Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi n= 30 responden Pertanyaan Apakah Sdr/i mengetahui pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001? A/% B/% C/% Tahu Tidak Tahu Tidak menjawab 30/100% 0/0% - Sumber: Jawaban Responden Analisis: Seluruh responden mengetahui adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut pendapat penulis, maka pengaturan pembalikan beban pembuktian secara baik telah diketahui oleh para teoretisi maupun para praktisi dalam praktik peradilan. Ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terhadap delik suap. Selain ketentuan tersebut maka pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan Pasal 35 47 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Politik hukum kebijakan legislasi mengenai pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, bahwa: “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”. Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada Pasal 35 menentukan: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” 47 126 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok. Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 mengundang poblematis atau bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana. Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk UU ketika membahas tentang UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mana ditegaskan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan asas pembalikan beban pembuktian. Begitu pula halnya terhadap ketentuan Pasal 37, 37A dan 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menentukan delik korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 menganut pembalikan beban pembuktian. Dari dimensi ini, maka politik hukum tentang kebijakan legislasi relatif nampak adanya ketidakjelasan perumusan pengaturan norma pembalikan beban pembuktian sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan UU tersebut. F. Kesimpulan Implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara pidana korupsi di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Praktik pembalikan beban pembuktian di Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut) dan India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India 127 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 (AIR 1963 SC 255) dilakukan terhadap asal usul kepemilikan harta pelaku dengan mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principles) sehingga implementasinya tetap menjunjung tinggi HAM dan ketentuan hukum acara pidana. Teori balanced probability principles menempatkan hak asasi pelaku tindak pidana korupsi dalam kedudukan (level) paling tinggi mempergunakan teori probabilitas berimbang yang sangat tinggi (highest balanced probability principles) dengan sistem pembuktian menurut UU secara negatif atau beyond reasonable doubt. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi diterapkan asas pembalikan beban pembuktian melalui teori probabilitas berimbang yang diturunkan (lowest balanced probability principles) sehingga kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena harta kekayaan orang ditempatkan pada level paling rendah ketika pelaku tersebut dalam kedudukan belum kaya. Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (materiele feit) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperatif membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem accusatoir yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Pasca berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) diperlukan suatu modifikasi perumusan norma pembalikan beban pembuktian yang bersifat preventif, represif dan restoratif. 128 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Daftar Pustaka Abidin, Andi Zainal., Hukum Pidana I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan”, Jakarta, 2006, ”Kendala Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang”, Paper, Jakarta, 2007 Ancel, Marc, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965 Apeldoorn, L.J. van., Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2005 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007 Atmasasmita, Romli, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1982, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002 Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979 Friedman, Lawrence M. dan Steward Macaulay (ed), Law and the Behavioral Sciences, The boobs Merrill Company, Indianapolis, 1969, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984 Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Hamzah, Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Hong Kong Legal Information Institute melalui http://www.hklii.org/ cgihklii.org/disp.pl/hk/jud/en/ hkca/1997/ CACC 000722%5f1995. html?queryz%7e+hui+kin+hong didownload pada tanggal 15 Januari 2007 Howard, Collin An Analysis of Sentencing Authority, in Reshaping the Criminal Law, P.R. Glazebrook (ed), Stevens & Sons, London, 1978 In The Supreme Court of The Republic of Vanuatu, Election Petition No. 31 of 1998 melalui Vanuatu : Taranban http://www.paclii.org/vu/ cases/ VUSC/2004/15.html di download pada tanggal 7 Februari 2007 129 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 Yurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1970 Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Russell and Russell, New York, 1973 Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof), Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001 Nolte, A., Het Strafrecht en de Alzonderlijke Welten, Utrecht-Dekker & Von de vegt, Nijmegen, 1949 Pompe, W.P.J., Handboek van het Nederlandsche Strafrecht, NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwollo, 1959 Poernomo, Bambang, Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982 Pound, Roescoe, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven, 1959 Radhie, Teuku Mohammad, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II, Desember 1973 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Remmelink, Jan, Hukum pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 Rukmini, Mien, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006 Saleh, Roeslan, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Penerbit Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996 Sampford, Charles, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell Inc, New York, 1989 Speville, Bertrand de, Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms, The Papers, 8th International Anti- 130 Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tipikor, Lilik Mulyadi Corruption Conference, hlm. 4-6 melalui http://ww1.transparency.org/iacc/ 8th_iacc/papers/despeville.html di download pada tanggal 23 Desember 2006 Stolpe, Oliver, Meeting the burden of proof in corruption-related legal proceedings, unpublished 131 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132 132 MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (The Meaning and Criteria of Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in Good Governance Implementation) Agus Budi Susilo Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat Email : [email protected] Abstrak Dalam rangka melakukan tindakan hukum, pejabat publik sering melakukan tindakan di luar ketentuan hukum tertulis. Keadaan ini sebagai suatu konsekuensi logis, bahwa Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya seringkali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman, perubahan nilai, dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan kemajuan yang dicapainya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan “diskresi” sebagai sarana pengembangannya. Ironisnya, tidak jarang penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, justru mengorbankan hak-hak masyarakat baik secara individu pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Untuk mengantisipasinya, perlu ada konsep lain yang mengendalikan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, dan konsep tersebut adalah good governance, yang sering diartikan tata pemerintahan yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip utama dari tata pemerintahan yang baik itu sendiri, diharapkan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dapat diterapkan sesuai rel hukum (rechtmatigheid van regering). Kata kunci : Diskresi, Keputusan Pejabat Publik, Tata Pemerintahan yang Baik Abstract In order to do the legal action, public officials often execute out of written law, this condition is a logic consequence, that the acts and others written laws are left behind in anticipating the development of the era, the change of values, and increasing need of human life along with the progress that they have achieved in science and technology. Therefore, to make legality 133 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 principle on operational stage can be done as good as it could, so the development instrument of the discretion is needed, ironically, not the rare things, the use of discretion sometimes misuse by public officials, pretending bases on public need and legal certainty in fact they abandon civil rights, either individually, in group or even civil corporate body. To anticipate it all, another draft is required to control the discretion of public policy and/or act of public officials, and that draft is good governance, which usually assume as good governance system. By understanding main principle from good governance itself, it’s hoped that the discretion of public policy and/or act of public officials can be applied together with code of conduct in law (rechtmatigheid van regering). Keywords : Discretion, Public Officials, Good Governance A. Pendahuluan Sebagai pemangku utama otoritas penyelenggaraan kepentingan umum (public service) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pejabat publik mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan yang luas ini diperoleh dari peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Akan tetapi, pada tataran praktek, pejabat publik sering melakukan tindakan diluar ketentuan hukum tertulis. Keadaan ini sebagai suatu konsekuensi, bahwa Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya seringkali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman, perubahan nilai, dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan kemajuan yang dicapainya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsep hukum administrasi negara, tindakan diluar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan, yaitu agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien. Konsep tersebut dikenal dengan “diskresi”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan diskresi sangat diperlukan dalam rangka melengkapi atas segala kekurangan dan kelemahan prinsip legalitas. Diskresi memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.1 Utamanya dalam mengisi kekosongan ketentuan tertulis, serta melenturkan ketentuan yang kaku (rigid) dan sudah usang (out of date). Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekininan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat (public). Realitasnya terkadang berbanding terbalik, yaitu penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan 1 Beatson, dkk, Administrative Law: Text and Materials, Oxford University Press, UK, 2011, hlm. 113-114. 134 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo kepastian hukum, justru telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi tersebut, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang “klise” dan “paradoks”. Pandangan tersebut ada benarnya, apabila ditelaah kembali terhadap kasus-kasus hukum yang pernah ada dan sedang terjadi saat ini, yang dilakukan pejabat publik dalam memahami makna diskresi, misalnya diskresi yang menimbulkan ekses negatif adalah “kasus bulog”, “kasus texmaco”, “kasus pembangunan bandar udara samarinda kutai kartanegara”, “kasus bank century”, “kasus hambalang” dll. Banyaknya kasus kaitannya dengan “diskresi” tersebut, menurut penulis diawali dengan adanya “celah” bagi pejabat publik dalam menafsirkan peraturan Perundang-undangan sesuai kehendaknya atau kepentingan dirinya maupun kelompok tertentu. Kasus-kasus hukum yang sering muncul terkait diskresi pejabat publik dapat terjadi dalam jenis atau bentuk apapun, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian maupun keuangan negara (seperti : pengadaan barang dan dana hibah/bansos). Di tingkat pemerintah pusat, beberapa peraturan memungkinkan adanya “diskresi” yang dilakukan oleh menteri selaku bawahan presiden, misalnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai perangkat pemerintah, kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang dilakukan oleh kementerian adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya, mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya dan melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya, mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, mengelola 135 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya. Ketentuan di lingkungan kementerian negara tersebut, memberi peluang kepada para menteri untuk melakukan diskresi, karena banyaknya norma yang memberi wewenang kepada menteri untuk melakukan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya masing-masing dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kemudian, di dalam pemerintahan daerah juga masih mengalami banyak kendala dalam mengimplementasikan diskresi, seperti apa yang tercantum dalam aturan dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang kemudian sebagian normanya dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012. Secara spesifik, dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) pada pokoknya menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dan dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya norma ini, pemerintah daerah mempunyai diskresi untuk melakukan tindakan berupa pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos). Pada kenyataannya penggunaaan dana untuk hibah dan bansos ini, sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Modus penyimpangan “diskresi” yang dilakukan pejabat publik terhadap penyaluran hibah dan bantuan sosial di beberapa daerah dengan dalih ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, diantaranya : dana yang diberikan tidak seutuhnya sesuai pagu yang di tetapkan, melakukan mark-up, adanya kolusi dan nepotisme dengan lembaga penerima dana hibah, diberikannya dana hibah secara fiktif, dsb. Menariknya, diskresi keputusan dan/atau tindakan mengenai pemberian hibah dan bansos meskipun mempunyai tujuan yang positif, akan tetapi rentan untuk disalah gunakan, terlebih menjelang adanya kegiatan yang bersifat politis, misalnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karenanya, untuk menghindari penyalahgunaan tindakan yang bersifat diskresi keputusan dan/atau tindakan terhadap pemberian dana hibah dan bansos, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memoratorium dana-dana tersebut dalam menghadapi Pemilihan Umum 2014, sampai dengan pelaksanaan “pesta demokrasi” tersebut selesai.2 2 Kompas, Terbit Hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014, hlm. 1 136 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo Penyelesaian kasus-kasus yang berkenaan dengan “diskresi” sering dijumpai adanya titik singgung dari segi pemaknaannya dari lapangan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara pengkajiannya banyak dalam ruang lingkup “konsep” dan pada saat ini sudah dituangkan dalam beberapa pasal UU Administrasi Pemerintahan sebagai rencana Undang-Undang materiil hukum administrasi negara di Indonesia. Berbeda dengan lapangan hukum pidana, yang secara normatif tercantum jelas dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk membatasi penulisan di sini, penulis hanya mengkaji mengenai bagaimanakan makna dan kriteria diskresi terkait keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dari aspek hukum administrasi negara, terutama dalam perspektif tata pemerintahan yang baik (good governance)? Dalam mengkaji tema tersebut, penulis menguraikannya dengan bentuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan norma dalam Perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan konsep atau teori-teori hukum menyangkut tema yang dikaji yakni diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik. Kemudian menganalisisnya, dan lebih khusus lagi akan dieksplor mengenai makna dan kriteria diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Analisanya, penulis tetap berpedoman pada hukum positif dan doktrindoktrin dalam ilmu hukum (yuridis-normatif). B. Pembahasan 1. Konsep Kewenangan Pejabat Publik Sebagai Dasar Melakukan Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Konsepsi pejabat publik, dari segi istilah ada dua pengertian, yaitu “pejabat” dijumbuhkan dengan orang sebagai pemangku atau yang mempunyai jabatan, dan “publik” yang diartikan sebagai masyarakat (umum). Peristilahan “pejabat publik” ini sering dikaitkan dan disepadankan dengan istilah asing, antara lain “government”, “administration”, “bestuur”, “overheid”, dan sebagainya. Di beberapa negara yang menggunakan bahasa inggris “government” dari segi istilah diartikan pemerintah yang melakukan pelayanan publik, sedangkan “administration” (dalam konteks sebagai administrasi negara) adalah merupakan keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Adapun istilah hukum secara klasik yang sering digunakan di Indonesia, sering “meminjam” istilah dari bahasa belanda, seperti “bestuur” dan “overheid”. Arti “bestuur” dari segi bahasa diartikan sebagai 137 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 pemerintah sebagai pelaksanan Undang-Undang, sedangkan “overheid” mempunyai arti pemerintah sebagai lembaga, akan tetapi secara teoritis pengertian “bestuur” adalah disepadankan dengan kekuasaan atau kewenangan eksekutif (executive power), berbeda dengan “overheid” yang mempunyai arti lebih luas, yaitu pemerintah yang memiliki fungsi eksekutif, inspektif, legislatif, dan yudikatif. Istilah-istilah tersebut diatas, hanya sering digunakan dalam beberapa literatur. Berbeda dengan istilah dalam norma tertulis yang saat ini berlaku, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan, pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Lebih lanjut, dalam ketentuan yang sama yaitu Pasal 1 angka 3, pengertian “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Beranjak dari pengertian tersebut, pejabat publik sama artinya dengan regering.3 Untuk mencapai tujuan negara, pejabat publik bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam melakukan tindakantindakan hukum, khususnya dalam bentuk suatu keputusan-keputusan yang bersifat administratif sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.4 Kewenangan atau wewenang pejabat publik dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan merupakan dasar berpijak atau sebagai kekuasan yang diberikan berdasarkan hukum (legal authority). Kewenangan mengandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dengan kata lain, perbuatan (melakukan atau tidak melakukan) bukan untuk dirinya sendiri melainkan ditujukan dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan mengatur. Arti penting dari adanya Kewenangan adalah adanya persyaratan yang akan diberikan kepada pejabat 3 Dalam khasanah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dalam artinya yang luas, pemerintah disebut regering. Lihat Amrah Muslimin, Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm.83, dan Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 66 4 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 28 138 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo publik untuk diberikan Kewenangan, karena segala bentuk tindakan hukumnya menyangkut pihak masyarakat luas (publik).5 Di Belanda istilah “kewenangan” dikenal dengan “bevoegheid”, dan istilah ini di Indonesia sering diterjemahkan dengan “kewenangan” atau “wewenang”.6 Padahal kalau ditelusuri lebih lanjut terdapat perbedaan yang mendasar antara “kewenangan” dan “wewenang”, karena arti “kewenangan” kaitannya dengan hukum administrasi negara sepemahaman penulis adalah awal mula otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan “wewenang” merupakan bagian dari “kewenangan” tersebut. Meskipun terdapat ketidak samaan arti antara keduanya, dalam tulisan ini penulis tetap menjadikan keduanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut F.A.M. Stroink pembahasan “bevoegheid” ini merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (hukum publik). Dalam hukum tata negara “bevoegheid” dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (teehtement) atau yang berkaitan dengan kekuasaan, sedangkan dalam hukum administrasi negara membahas wewenang pemerintahan (bestuurbevoegheid).7 Menurut Henc van Maarseveen, dalam konsep hukum publik kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Sedangkan komponen dasar hukum, bahwa kewenangan atau wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standard kewenangan atau wewenang, yaitu standar umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standard khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu). Setelah penulis uraikan tentang makna kewenangan atau wewenang, selanjutnya perlu ditelusuri bagaimana kewenangan itu diperoleh oleh pejabat publik. Dalam khasanah hukum administrasi negara terdapat tiga macam cara untuk memperolah kewenangan pemerintahan (bestuurbevoegheid), yaitu : atribusi (merupakan pemberian wewenang 5 Baqir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 59 dan 60 6 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda – Indonesia, Penerbit PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 78. Dalam bahasa Inggris disebut “competence” yang berarti being competent; ability or legal authority lihat A.P. Cowie (chief editor), Op.Cit, hlm. 235. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut “pouvoir” atau “puissance” bahasa Jerman “gezag” lihat SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admnistratif di Indonesia, Penerbit Libety, Yogyakarta, 1997, hlm. 153. 7 Pendapat Henc van Maarseveen disitir oleh Philipus M.Hadjon dalam tulisannya di Gema Peratun Tahun VI No.12 Agustus 2000, MARI Lingkungan Peratun, hlm. 103. 139 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan Perundangundangan), delegasi (terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh pejabat publik yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada pejabat publik lainnya), dan mandat (tidak terjadi pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari pejabat publik yang satu kepada yang lain, yang ada hanya hubungan internal). Dari ketiga kewenangan pejabat publik tersebut, menurut sifatnya dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu : 1. Kewenangan yang bersifat pilihan (facultative) Kewenangan semacam ini berdasarkan norma yang pada peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut digunakan. 2. Kewenangan yang bersifat Terikat (gebonden) Norma yang ada dalam peraturan dasarnya sudah menentukan tetang isi dari keputusan yang harus diambil. 3. Kewenangan yang bersifat (diskresioner) Wewenang yang diberikan oleh peraturan dasar tidak bersifat terikat, yaitu ketika pejabat publik menentukan isi dari suatu tindakannya bebas dilakukan berdasarkan interpretasinya.8 Terhadap kewenangan yang bersifat diskresioner tersebut, tidak bersifat terikat sama sekali. Di sini peraturan dasarnya memberikan suatu ruang lingkup kebebasan kepada pejabat publik yang bersangkutan. Di satu pihak, batas (marge) kebebasan seperti itu sedikit banyak merupakan hal yang tidak dapat diperhitungkan, karenanya merupakan hal yang sedikit banyak tidak pasti. Tetapi di pihak lain, kebebasan demikian itu memberikan kemungkinan untuk diadakan penyesuaian dengan kekhususan dari hal atau keadaan senyatanya yang hendak diurus kepentingannya. Pejabat publik tersebut memang harus mengadakan tindakan ke arah individualisasi dan konkretisasi. Kemungkinan untuk mengindividualisir dan mengkonkretisir itu tidak hanya dalam bentuk kewenangan untuk menolak atau mengabulkan saja apa yang dimohon masyarakat, tetapi juga memberikan kemungkinan bagi pejabat publik yang bersangkutan untuk melekatkan syarat-syarat pada penetapan tertulis (izin) yang ia keluarkan. Jenis-jenis perbuatan atau tindakan pejabat publik yang bersifat diskresi dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, termasuk luas cakupannya meliputi bidang perizinan, kepegawaian, pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. 8 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 99 sampai dengan 101 140 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo 2. Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Berkenaan dengan masalah yang akan penulis kaji yaitu yang berkaitan dengan makna diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, maka makna disini sama halnya dengan mencoba menelusuri arti dan maksud dari diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik itu sendiri dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep yang ada dalam hukum administrasi negara. Pertama; konsep yang dipengaruhi dari beberapa pemikiran yang berlaku di beberapa negara, yakni : a) Negara Inggris, dasar pemikiran adanya diskresi (discretionary powers) adalah jenis tindakan Raja atau Ratu (the Crown or the Queen) yang legal dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan dari Parlemen (lembaga legislatif). Bahkan dalam sejarahnya, pejabat publik sebagai abdi Raja atau Ratu berdasarkan ketentuan yang ada, dapat melakukan diskresi untuk melanggar hukum umum dan menyerahkan seorang asing pada pemerintahnya sendiri untuk diadili, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi tahun 1870.9) Menurut AV. Dicey: “The discretionary authority of the Crown originates generally, not in Act of Parliament, but in the prerogative………. The prerogative appears to be both historically and as a matter of actual fact nothing else than the residue of discretionary or arbitrary authority, which at any given time is legally left in the hands of the Crown”. Dengan demikian, discretionary powers di Inggris pada umumnya berasal dari hak prerogatif Raja atau Ratu, bukan dari Undang-Undang, sebagaimana di negara lain. Bahkan secara historis, hak-hak prerogatif faktanya hanyalah residu (sisa) dari kewenangan diskresi (discretionary powers), yang kurun waktu tertentu secara legal tetap ada di tangan Raja atau Ratu. Argumentasi yang dibangun, Raja atau Ratu pada dasarnya (sebagaimana namanya) adalah merupakan seorang penguasa, atau istilah dalam hukum adalah bagian yang paling kuat dari suatu kekuasaan yang berdaulat (the most powerful part of the soverign power). b) Negara Belanda, sebagai negara dipengaruhi sistem kerajaan, melekatkan istilah diskresi dengan jabatan atau organ pemerintahan (inherent aan het bestuur). Menurut J.B.J.M. ten Berge, diskresi eksis karena adanya tiga 9 AV. Dicey, Introduction to the study of The Law Of The Constitution, Macmillan & Co LTD, London, 1959, hlm. 422 dan 423 141 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 macam kebebasan, yaitu interpretatievrijheid, beoordelingsvrijheid, dan beleidsvrijheid.10 Pengaturan mengenai adanya diskresi tertera dalam AwB (Algemene wet Bestuursrecht) atau General Administrative Law Act, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia “Undang-Undang Umum Hukum Administrasi Negara”. Undang-Undang ini mengatur proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat publik, baik yang bersifat terikat (gebonden) maupun bebas (vrijheid). Selain mengatur batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pejabat publik ketika mengeluarkan atau mengambil keputusan, ketentuan tersebut juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kemungkinan terkena dampak diambilnya keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat publik. J.B.J.M. ten Berge dan beberapa ahli hukum Belanda lainnya mengartikan wewenang diskresi (discretionary bevoegdheden) sebagai berikut: “Discretionaire bevoegdheden, publiekrechtelijke bevoegdheden, waarbij voor het bestuursorgaan beleidsvrijheid m.b.t. het gebruik daarvan. Het staat hier ter beoordeling van het bestuursorgaan in hoeverre men een bepaalde maatregel toepast of een beschikking verleent. Bij vrije beschikkingen is deze beoordelingsvrijheid aanwezig, zoals b.v. hij het verleneen van subsidie. Deze beleidsvrijheid is echter niet onbegrensd, maar wordt ingeperkt door de inhoud van de wettelijke bepaling waarop de bevoegdheid berust en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, alsmede door eventueel ter zake gelgende beleidsregels of privaatrechtelijke overeeenkomen” (artinya : wewenang diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Di sini terletak pemberian wewenang pertimbangan bagi organ pemeritnah sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan tertentu atau pengambilan keputusan. Dalam keputusan bebas terdapat kebebasan mempertimbangkan ini, misalnya keputusan pemberian subsidi. Meskipun demikian, kebebasan mengambil kebijakan ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh isi ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar wewenang diskresi tersebut dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga tidak boleh menyimpang dari peraturan kebijakan yang berlaku atau perjanjian perdata).11 Alur pikir adanya diskresi di negara Belanda, oleh H.D Sout, dianggap sebagai sebuah konsekuensi fungsi pemerintahan yang sangat luas dalam 10 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 236 11 Ibid., hlm. 127 142 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo negara hukum modern yang ada dibeberapa negara eropa (termasuk Belanda). c) Negara Jerman, terdapat berbagai bentuk keputusan dan/atau tindakan administratif, ada yang bersifat tertulis atau pun tidak tertulis, diantara bentuk-bentuk keputusan dan/atau tindakan tersebut ada yang disebut dengan ”Eremessen” atau diskresi. Menurut ketentuan Pasal 40 UndangUndang Prosedur Administrasi Pemerintahan (Verwaltungsverfahrensgesetz) pada pokoknya menyatakan setiap lembaga negara / publik memiliki kewenangan berbuat “Ermessen”, jika menggunakan kewenangan tersebut haruslah sesuai dengan kegunaan kewenangan itu dan batas-batas hukum yang berlaku bagi adanya “Ermessen”. Berdasarkan ketentuan yang mendefinisikan “Ermessen” tersebut, terlihat bahwa secara konseptual berbeda dengan istilah yang sering digunakan banyak pakar hukum baik di Indonesia maupun negara lain, yaitu menyama-artikan dengan istilah “Freies Ermessen”. Perbedaan tersebut terlihat seakan-akan istilah “Freies Ermessen”, bebas “Freies” melakukan tindakan “Ermessen”, padahal dalam “Ermessen” terikat dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Jerman. Persyaratan adanya tindakan diskresi dalam bentuk, isi, dan prosedur yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan administratif, ditetapkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga terkadang aturan internal di lembaga pejabat publik berada (Verwaltungsvorschrif/ Petunjuk Teknis). Diskresi tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk apapun, dapat dikeluarkan secara lisan tulisan atau bentuk lainnya (misalnya: keputusan tertulis). Tindakan administratif lisan harus dipertegas dengan tulisan yang mengandung tanda tangan atau nama pejabat publik (selaku pemilik otoritas) atau pihak yang berwenang untuk memberikan/menetapkan tindakan tersebut. Pengecualian terhadap aturan ini dibuat untuk sarana otomatis. Dari uraian ketiga negara tersebut, apabila dibuat dalam bentuk bagan, maka menurut penulis sebagai berikut : Negara 1. Inggris 2. Belanda 3. Jerman Sumber Hukum Konstitusi AsalMuasal Kedaulatan Kerajaan Karakter (yang dominan) Politik (Hak Prerogatif) Peraturan Perundangundangan Peraturan Perundangundangan Kedaulatan Kerajaan Hukum (Kewenangan) Kekuasaan Negara Hukum (Kewenangan) Produk Kebijakan dan/atau Tindakan Keputusan dan/atau Tindakan Keputusan dan/atau Tindakan 143 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 Kedua; pengertian “diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik” menurut beberapa ahli hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu : a) Prajudi Atmosudirjo yang mengartikan diskresi sebagai kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dari para pejabat publik yang berwenang dan berwajib menurut pendapatnya sendiri. Pendapat ini melihat adanya hubungan antara diskresi dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan diskresi pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan Perundangundangan.12 b) Kemudian Sjachran Basah menyatakan bahwa dalam hal pejabat publik memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan (diskresi), sikap-tindaknya yang demikian harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Pertanggung jawaban dimaksud, adanya batas-batas ketaatan akan asas atau ketaat-asasan, yaitu batas-atas dan batas-bawah. 13 c) Pengertian yang lebih konkrit lagi adalah yang disampaikan oleh Fatimah Achyar, menurutnya diskresi diartikan sebagai salah satu rumusan kekuasaan pemerintahan negara, yaitu memberikan ruang gerak kebebasan (memberikan freies ermessen) kepada pejabat publik yang diberi kekuasaan untuk menentukan sendiri, bagaimana mengartikan (menangkap maksud dan tujuan) dari kekuasaan dengan maksud menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan, dan menentukan sendiri apakah ia akan melaksanakan kekuasaannya itu, serta pejabat publik tersebut dapat menentukan sendiri kapan ia akan berbuat demikian dan bagaimana caranya menggunakan kekuasaan itu. 14 d) Diskresi oleh E. Utrecht diartikan sebagai pemindahtanganan (kewenangan) badan legislatif kepada badan pemerintahan (eksekutif) sebagai konsekuensi adanya konsep welfare state (negara kesejahteraan).15 e) Muchsan menjabarkan diskresi, sebagai kewenangan yang bersifat bebas yang diberikan kepada pejabat publik, karena peraturan Perundang12 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 82 dan 103 13 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm 3, 4 , dan 5., dan Sjachran Basah, Beberapa Permasalahan Pokok Sebelum Realisasi Efektif Pengadilan Administrasi, dalam : Bunga Rampai HTN dan HAN, FH UII, Yogyakarta, hlm. 98 dan 99 14 Fatimah Achyar, Selintas Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Diterbitkan Mahkamah Agung RI, 1989, Jakarta, hlm. 111 15 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 31 144 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo undangan yang menjadi dasar kewenangan memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertindak. Maksudnya, pejabat publik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan (menangkap maksud dan tujuan) dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya.16 f) Sedangkan Indroharto berpendapat bahwa diskresi sebenarnya merupakan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik, maka yang kurang baik, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Dalam implementasinya, diskresi mempunyai dua pola, yaitu : 1. Kebebasan untuk menilai secara obyektif, yaitu apabila norma dalam Undang-undangnya bersifat samar-samar akan tetapi sesungguhnya dimaksudkan sebagai norma hukum yang obyektif, karena rumusan eksplisitnya sulit untuk diberikan, misalnya : rumusan “bertingkah laku sebagai abdi negara yang baik”. 2. Kebebasan menilai secara subyektif, artinya adanya kebebasan melakukan suatu kebijakan sendiri, karena Undang-Undang memberikan wewenang kepada pejabat publik untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu peristiwa konkrit.17 Ketiga; pengertian “diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik” dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU-AP), yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, mengartikan bahwa diskresi sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan Perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Ketentuan ini, sedikit lebih luas pengertiannya dari Naskah Akademik UU-AP tersebut, yang menyatakan bahwa diskresi merupakan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang bebas karena belum diaturnya suatu hal tertentu dalam peraturan Perundang-undangan yang ada. Dari kedua pendekatan ini, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa diskresi pejabat publik mengandung makna adanya kebebasan menafsirkan suatu teks (norma) peraturan Perundang-undangan oleh pejabat publik sesuai kewenangan yang ada padanya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan mematuhi 16 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 13 17 Indroharto, Op. Cit., hlm. 98 dan 99 145 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 rambu-rambu berupa taat asas dan ketentuan hukum yang berlaku, karena tetap ada pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Penafsiran di sini pun, dengan syarat teks (norma) peraturan Perundangundangan sebagai dasar pijakan pejabat publik tersebut memberikan pilihan atau ada “ruang kosong” yang memungkinkan diambil kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan kewenangannya, yang apabila tidak diambil kebijaksanaan akan menimbulkan stagnasi pemerintahan. Sedangkan, yang menjadi kriteria diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik ada beberapa point, yaitu : (1) Diskresi merupakan pengecualian dari adanya asas legalitas, yang mengharuskan pejabat publik dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk mentaati teks-teks dalam norma yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan. (2) Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. (3) Penilaian pejabat publik terhadap situasi/kondisi tertentu atau keadaan mendesak atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, dapat bersifat subyektif dan obyektif, akan tetapi yang dibenarkan oleh hukum adalah penilaian yang bersifat obyektif. (4) Adanya stagnasi pemerintahan. (5) Memberikan kepastian hukum. (6) Terdapat unsur kebijaksanaan atau kebijakan yang diberikan kepada pejabat publik dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan, baik yang bersifat suatu perintah (imperatif) untuk menafsirkan suatu teks tertulis maupun adanya konfik norma (antinomi teks) atau ketidak jelasan (vague van normen) atau kekosongan suatu teks dalam ketentuan tertulis (leemten van normen), dan terhadap kebijaksanaan atau kebijakan ini tidak dapat diuji oleh hukum (adanya prinsip pengujian hukum sebatas rechtmatigheid bukan doelmatigheid). (7) Meskipun ada ruang “kebebasan penafsiran” dalam melakukan diskresi keputusan dan/atau tindakan, pejabat publik harus memperhatikan tujuan diskresi. (8) Taat asas, yaitu batas-atas dan batas bawah (hierarkis peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik). (9) Diskresi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat publik, harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, baik kepada atasan atau institusi pejabat publik tersebut, maupun kepada masyarakat. (10) Bentuk pertanggungjawaban diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik adalah dengan adanya pengujian secara hukum dalam 146 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo suatu proses peradilan secara administratif (dalam hal ini peradilan tata usaha negara). Dari makna tersebut, terlihat adanya penyerahan wewenang lembaga legislatif atau pembuat Undang-Undang kepada pejabat publik. Sikap pembuat Undang-Undang yang menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat publik menurut Struycken dan van Wijk disebut “terugtred wetgever” (sikap mundur dari pembuat Undang-Undang). Dengan demikian, pejabat publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan memperoleh wewenang diskresioner yang sangat luas, khususnya dalam mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan hukum. Selain adanya penyerahan atau pelimpahan wewenang, adakalanya rumusan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak pejabat publik bersifat samar-samar atau istilah Muchsan merupakan blanco volmacht, seperti dalam suatu norma atau pasal peraturan tersebut ada kata atau kalimat sebagai berikut : - “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota” (Pasal Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). - “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan.......” (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). - “Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan” (Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). - “........penetapan kebijakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). - “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat........” (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007). - “Apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya”, dan “Apabila pembayaran kompensasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran kompensasi dimasukkan dan 147 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya” (Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa contoh diatas hanyalah sebagian kecil adanya diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, masih banyak lagi peraturan Perundang-undangan yang memberikan celah bagi pejabat publik untuk melakukan atau tidaknya suatu keputusan dan/atau tindakan. Banyaknya kata atau kalimat “apabila dipandang perlu”, “dapat”, “dikonsultasikan”, “atas usul”, “seijin” atau “dengan ijin”, “kecuali”, “persetujuan”, dan sebagainya, dalam suatu norma merupakan bentuk adanya diskresi yang dilakukan oleh pejabat publik. Akan tetapi, terkadang diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik bermakna ganda (dapat positif sekaligus negatif). Untuk menghindari tindakan diskresi keputusan dan/atau tindakan yang disalahgunakan pejabat publik, diperlukan sarana yang membatasi diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Maksud sarana di sini adalah tolok-ukur atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dalam mempertimbangkan atau menentukan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut UU-AP, tolok-ukur diskresi keputusan dan/atau tindakan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut : a) Memberikan kemungkinan adanya dua bentuk keputusan, yaitu bersifat cetak tertulis dan/atau elektronis (dapat diakses melalui media elektronik). b) Harus tetap memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu: asas legalitas (peraturan Perundang-undangan), asas perlindungan terhadap HAM, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). c) Bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. d) Dilakukan sesuai dengan kewenangannya (tidak melampaui wewenang). e) Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatannya. f) Harus berdasarkan alasan-alasan yang obyektif dan dilakukan dengan itikad baik. g) Tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak mencampuradukkan wewenang. h) Menghindari konflik kepentingan. 148 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo i) Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, maka pejabat pemerintahan wajib memperoleh persetujuan dari atasan. j) Penggunaan diskresi yang menimbulkan keresahan di masyarakat keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadinya bencana alam maka pejabat pemerintahan wajib memberikan pelaporan kepada atasan, dengan menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan. k) Memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak ke tiga ikut terlibat dalam prosedur penerbitan keputusan, terutama dalam memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen dan fakta yang terkait sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi individu warga masyarakat. l) Wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. m) Sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan. n) Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan (khususnya mematuhi putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap), pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat. Selain itu, dalam Naskah Akademik UU-AP, ada beberapa batasan atau rambu-rambu bagi penilaian diskresi itu melanggar hukum atau tidak ini didasari atas dua hal : pertama, deskresi mengandung penyalahgunakan wewenang (terjadi penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan atau penggunaan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang itu diberikan); dan kedua, diskresi mengandung arbitrenis (diskresi dinilai melanggar prinsip proposionalitas). Sedangkan secara konseptual dan normatif sarana sebagai tolok-ukur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tercermin dalam asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut : 149 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 Diskresi Keputusan Pejabat Publik harus memenuhi AAUPB menurut UndangUndang No. 9Tahun 2004 / Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, yaitu: 1. Adanya Kepastian Hukum Diskresi Keputusan Pejabat Publik tidak boleh bertentangan dengan AAUPB menurut Pasal 10 RUU-AP, yaitu : Diskresi Keputusan Pejabat Publik tidak boleh bertentangan dengan AAUPB, yang menurut Crince Le Roy dan Koentjoro Purbopranoto, yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Melaksanakan Tertib Penyelenggaraan Negara 2. Kecermatan 1. Kepastian Hukum dan Meniadakan AkibatAkibat Suatu Keputusan Yang Batal 2. Bertindak Cermat 3. Memperhatikan Kepentingan Umum 3. Kepentingan Umum 3. Penyelenggaraan Kepentingan Umum 4. Adanya Keterbukaan 4. Keterbukaan 4. Menanggapi Penghargaan Yang Wajar 5. Keseimbangan, Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Permainan Yang Layak, Keadilan Atau Kewajaran, Perlindungan Atas Pandangan Hidup Pribadi, dan Kebijaksanaan 6. Tidak Boleh Mencampuradukkan Kewenangan 5. Dilakukan Proporsional Secara 5. Ketidakberpihakan 6. Bertindak Professional 6. Tidak Menyalahgunakan Wewenang 7. Adanya Akuntabilitas 7. Kemanfaatan 7. Motivasi Untuk Setiap Keputusan Pejabat Administrasi Beranjak dari tolok-ukur inilah diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik bersandar. Dalam perspektif dogmatika hukum, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pejabat publik dalam melakukan diskresi keputusan dan/atau tindakan harus mematuhi kriteria-kriteria tersebut (baik apa yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, konsep AAUPB, maupun Pasal 10 RUU-AP). Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut : 150 Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik, Agus Budi Susilo Proses (Implementasi) Masukan (Input) Hasil (Output) Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Kewenangan Prosedur Substansi AAUPB atau Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Tata Pemerintahan Yang Baik Publik C. Kesimpulan Pemaknaan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, merupakan pengecualian dari adanya asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). Akan tetapi, tetap berpedoman pada kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundangundangan, meskipun kewenangan dalam peraturan tersebut bersifat multitafsir, atau dalam kondisi tertentu maupun keadaan mendesak pejabat publik diwajibkan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, dan dapat juga dikarenakan adanya stagnasi pemerintahan, dengan mengacu pada terwujudnya kepastian hukum dan dilakukan demi kepentingan umum. Sedangkan kriteria diskresi keputusan dan/atau tindakan pada umumnya ditandai dengan lahirnya hukum baru atau keadaan baru, membentuk atau membubarkan suatu lembaga atau badan hukum, berbentuk perintah, dapat bersifat menguntungkan (positif) atau merugikan (negatif) bagi pihak terkait (stakeholder), dan perbuatan yang dilakukannya merupakan salah satu tugas dan kewajibannya (sesuai kewenangannya). Agar diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pejabat publik dalam melakukannya harus demi kepentingan umum, sehingga perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan menyangkut segala kepentingan pihak terkait. Kemudian adanya kewajiban bagi pejabat publik agar taat asas, yaitu batasatas dan batas bawah (hierarkis peraturan Perundang-undangan), dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, meliputi : kepastian hukum, kemanfaatan, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas atau keseimbangan, profesionalitas, akuntabilitas atau ketidakberpihakan, kecermatan, tidak melampaui / tidak menyalahgunakan / tidak mencapuradukkan kewenangan, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan dan/atau tindakan yang batal, menanggapi penghargaan yang wajar, dan motivasi. 151 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152 Daftar Pustaka A. Buku Literatur : A.V. Dicey, Introduction to the study of The Law Of The Constitution, Macmillan & Co LTD, London, 1959 Amrah Muslimin, Asas & Pengertian Pokok tentang Administrasi & Hukum Administrasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1985 Baqir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004 Beatson, dkk, Administrative Law : Text and Materials, Oxford University Press, UK, 2011 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994 Fatimah Achyar, Selintas tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Diterbitkan Mahkamah Agung RI, 1989, Jakarta Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000 Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992 Paulus Effendie Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admnistratif di Indonesia, Penerbit Libety, Yogyakarta, 1997 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992 Sjachran Basah, Beberapa Permasalahan Pokok Sebelum Realisasi Efektif Pengadilan Administrasi, dalam : Bunga Rampai HTN dan HAN, FH UII, Yogyakarta B. Jurnal Hukum, Kamus, dan Surat Kabar: Gema Peratun Tahun VI No.12 Agustus 2000, MARI Lingkungan Peratun S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda – Indonesia, Penerbit PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996 Kompas, Terbit Hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014. 152 PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENANGANI PROBLEMA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN (Diversion Application to Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic in Court) Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat Email : [email protected] Abstrak Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur). Kata kunci : Diversi, Pelanggaran Lalu lintas, Pengadilan Abstract Basically cases of traffic violations is a matter of simple so categorized quick examination. However, when the volume of his case matters reach thousands of cases and should be heard in court within a day, in fact has given rise to problems. In addressing these problems, improvement of handling and settling disputes traffic violation in court is an absolute must do. But apart from that alternative settlement traffic violation outside the court, namely through the implementation of diversion should be used as an alternative way to reduce the caseload and problems in court. Functionally, the application of diversion used as part of the education and guidance systems and community protection systems (especially against children / Offenders under age). Keywords : Diversion, Traffic Violations, the Court 153 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 A. Pendahuluan Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang cukup sederhana. Baik dari segi penangkapan oleh Kepolisian, pembuktian di persidangan Pengadilan maupun eksekusi oleh Kejaksaan tidaklah rumit. Oleh karenanya acara pemeriksaannya cepat. Meskipun demikian penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini bukan tidak terdapat kendala atau masalah. Khususnya di Pengadilan Negeri (Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya) yang harus menangani perkara pelanggaran lalu lintas dengan volume jumlah perkara mencapai ribuan (bahkan terkadang bisa tembus sepuluh ribu), berbagai masalah dan kendala pun tidak dapat terelakkan. Masalah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan ini dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Masalah internal misalnya terkait dengan minimnya aparatur peradilan yang harus diberdayakan mengelola perkara pelanggaran lalu lintas untuk melayani ribuan para pelanggar yang datang bersidang di Pengadilan dalam waktu bersamaan. Di Pengadilan tertentu terkadang juga terpaksa melibatkan Pegawai Tidak Tetap (Honorer) dan Siswa/Mahasiswa yang magang untuk membantu baik dari aspek administrasi maupun mengatur ketertiban dan keamanan di Persidangan. Selain itu sarana prasarana pendukung di dalam maupun di luar persidangan terkadang menjadi rusak karena begitu banyaknya Pelanggar yang menggunakannya. Selain itu masalah eksternal seperti keberadaan Calo yang sebelum maupun saat hari persidangan berkerumun dan menyebar di sekitar Pengadilan membuat persepsi kurang baik bagi citra Pengadilan. Berdasarkan problema-problema tersebut diatas, senyatanya perkara pelanggaran lalu lintas yang notabene adalah sederhana ini telah menjadi beban bagi Pengadilan. Bahkan terkadang berpotensi menjadi batu sandungan aparatur peradilan melakukan pelanggaran disiplin. Misalnya terkait dengan kurang cermatnya pemberkasan maupun titipan uang denda yang tidak segera di diserahkan dan dieksekusi oleh Kejaksaan. Padahal secara subtantif sesungguhnya perkara ini adalah cukup sumir bilamana dibandingkan dengan perkara lain yang ditangani oleh Pengadilan. Oleh karenanya kemudian memunculkan gagasan untuk mengeluarkan perkara pelanggaran lalu lintas ini dari Pengadilan, minimal para Pelanggar tidak berduyun-duyun datang ke persidangan. Dengan demikian sistem fiterisasi perkara oleh aparat Kepolisian sangat diharapkan. Misalnya saja dengan optimalisasi penggunaan uang titipan (slip biru) dan penerapan diversi bagi kasus-kasus dan Pelaku pelanggaran lalu lintas tertentu. Pada asasnya penerapan diversi secara proporsional terhadap pelanggaran lalu lintas ini sejalan dengan konsepsi visi politik hukum 154 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto peradilan Indonesia yang notabene telah mengarah pada penyelesaian perkara yang efektif dan efisien serta berdasar atas restoratif justice. Penerapan diversi dalam penyelesain perkara pelanggaran lalu lintas ini dapat menjadi alternatif solusi mengatasi problema penyelesaian dan penumpukan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan. Namun terkadang persepsi negatif muncul dari penerapan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian karena seringkali diasosiasikan sebagai sebuah “pungli”. Berdasarkan latar belakang yang demikian maka menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian. B. Eksistensi Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara normatif, UU LLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian.1 Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.2 Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara. 3 Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan 1 Sebagaimana perbandingan pengaturan wewenang penyidikan dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262 dan Pasal 263 UU LLAJ 2 Pasal 267 UU LLAJ 3 Pasal 268 UU LLAJ 155 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 bersifat final dan mengikat.4 Adapun terkait dengan persidangan, ketentuan dalam UU LLAJ hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar. Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan5 maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.6 Dari uraian sebelumnya yang merujuk pada ketentuan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas belum terlihat pengaturan teknis terhadap penyelenggaran sidang tilang oleh pengadilan. Dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum ada empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran,7 pelaksanaan sidang,8 pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.9 4 M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Cetakan ke 12 : 2010, hlm.423 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu: penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1)); dan pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); serta persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)). Dari ketentuan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur sidang untuk perkara pelanggaran lalu lintas. 6 Terdapat lima butir pengaturan dalam surat kesepakatan tersebut dalam bagian mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan tersebut tidak mengatur detil mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Surat kesepakatan tersebut merujuk pada pasal 214 yang mengatur mengenai pemeriksaan cepat. 7 Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan berkas / surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang. Selanjutnya Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara. Kemudian Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar. 156 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto C. Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Secara kuantitatif, perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan sangat mendominasi jumlah perkara yang harus diperiksa, diselesaikan dan diputuskan oleh Hakim. Pada tahun 2013 tercatat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar. Total jumlah perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada 2013 berjumlah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40% merupakan perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Perkara pidana biasa pada 2013, sebesar 119.876 atau 3,60%. Sisanya merupakan perkara pidana singkat sebesar 231 perkara atau 0,01%.10 Bahkan dalam setiap minggu pada pengadilan di kota besar dapat menerima 2000 (dua ribu) sampai dengan 4000 (empat ribu) perkara.11 Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa dari sisi jumlah, perkara tilang merupakan perkara terbesar yang ditangani seluruh Pengadilan Negeri. Sehingga, pada perkara tilanglah interaksi antara Pengadilan dan masyarakat pencari keadilan paling banyak terjadi. Bisa dibayangkan jika setiap tahun sekitar 3 juta orang yang harus menempuh sidang tilang dan berinteraksi dengan pengadilan menemui pengalaman buruk di Pengadilan, maka terdapat potensi 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Dan harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas. 12 Namun sayangnya, dari berbagai pemberitaan media massa yang ada selama ini, tidak sedikit keluhan dan persepsi negatif terhadap pengadilan yang muncul dari sidang perkara tilang. Dari sebuah artikel koran, pernah diberitakan bahwa seorang petugas Pengadilan Negeri bersikap tidak sopan kepada pengurus surat tilang karena kelelahan mengurus sidang tilang seharian penuh. Kondisi itu diperburuk dengan menjamurnya calo kasus8 Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara. 9 Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar. 10 Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dan PSHK, Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil dan PSHK, 2014, Hlm. 4 11 Sebagaimana disampaikan oleh Yahya Syam Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pada seminar penelitian “Alternatif Pengelolaan Perkara Lalu Lintas di Pengadilan”. Acara yang merupakan rangkaian kegiatan Penelitian tentang Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang di Pengadilan ini diselenggarakan di Jakarta, 17 Juni 2014 12 Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dan PSHK, Op Cit, Hlm. 5 157 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 kasus tilang. Ketua MA Hatta Ali pernah mengakui bahwa calo semakin banyak berkeliaran di pengadilan, terutama ketika sidang tilang digelar. Menurut Ketua MA, meski calo tilang bukan oknum yang berasal dari pengadilan, namun ulah mereka menyebabkan Pengadilan mendapat kesan buruk dari masyarakat selama ini. Calo, menurut Hatta Ali, marak tumbuh di perkara tilang karena pada acara cepat hakim dapat menjatuhkan vonis tanpa mensyaratkan kehadiran pelanggar. Pengadilan selama ini tidak mampu menertibkan keberadaan dan ulah calo, meski secara terbatas upaya penertiban pernah ditempuh beberapa pengadilan.13 Penelitian Baseline Survey PSHK yang dilakukan pada tahun 2013 menunjukan rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan sidang tilang. Dari keseluruhan responden nasional, hanya 23 % responden yang menyatakan puas terhadap persidangan tilang. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan aspek-aspek layanan lainnya, yang mencapai kepuasan responden berada pada kisaran angka 50 %. 14 Survei integritas pelayanan publik yang diselenggarakan KPK pada 2012 juga menyatakan bahwa sidang tilang di seluruh PN di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palu dikelola di bawah standar. Temuan ini diperkuat oleh Ketua MA 2009-2012, Harifin A. Tumpa, yang mengeluhkan volume kerja dari perkara tilang yang sangat besar sebagai penyebabnya, yang pada akhirnya membuat banyak pengadilan kewalahan. Sumberdaya pengadilan banyak tersedot oleh perkara tilang, padahal perkaranya sendiri bersifat sederhana atau sumir.15 Beban kerja pengadilan yang terlalu besar di perkara tilang yang sumir akan menjadi disinsentif bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan lainnya untuk berfokus meningkatkan kualitas kerjanya (lewat putusan yang konsisten dan argumentatif) saat menangani perkara-perkara yang substansial, yang lebih luas dampaknya bagi masyarakat. Perkara tilang selama ini menjadikan konsentrasi dan sumberdaya pengadilan terlalu banyak tersedot oleh urusan yang sederhana. Di samping itu persepsi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai layanan pengadilan terbukti banyak dikontribusikan oleh penyelenggaraan perkara tilang. Persepsi negatif tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan mampu menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, imparsial, dan profesional. Jika rasa tidak percaya tersebut berkembang, 13 Ibid, Hlm. 5-6 Tim Survey Kepuasan Pengadilan 2013, Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) & Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas), 2013, hlm.89 - 94 15 Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dan PSHK, Op Cit, Hlm. 6-7 14 158 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto masyarakat menjadi enggan mengakses layanan pengadilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang dihadapinya.16 D. Alternatif Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Berdasarkan realitas masalah yang dihadapi oleh pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut, kemudian muncul beberapa opsi solusi sempat diusulkan oleh berbagai pihak. Opsi-opsi solusi tersebut berkisar pada: pertama, keinginan untuk mempertahankan beban kerja perkara tilang di pengadilan, namun dengan perbaikan-perbaikan tertentu dalam penyelenggaraannya, atau kedua, mengeluarkan atau mengurangi perkara tilang dari beban kerja pengadilan, khususnya bagi perkara di mana pelanggar mengakui kesalahannya (uncontested cases). Pada opsi pertama, ide-ide perbaikan pernah dilontarkan. Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tilang, ada yang mengusulkan agar polisi tidak perlu melibatkan jaksa sebagai penuntut karena dalam acara cepat, penyidik bisa mengajukan perkara ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Untuk memperbaiki kualitas layanan pengadilan di perkara tilang, sebagian pihak mengusulkan agar pengadilan menyelenggarakan sidang setiap hari, tanpa perlu dipusatkan di hari tertentu agar tidak bertumpuk. Ada juga yang mengusulkan agar sidang tilang diselenggarakan di malam hari (konsep night court) sebagaimana pernah diutarakan mantan Ketua MA Harifin Tumpa. Atau usul lain mengangkat hakim khusus untuk menangani perkara tilang yang sangat besar jumlahnya. Terkait usaha meminimalisir praktek calo di pengadilan, terdapat usulan untuk me-rolling staf yang ditugasi mengurus sidang tilang guna memutus mata rantai antara pegawai pengadilan dengan calo, mewajibkan pelanggar lalu lintas untuk secara langsung mengikuti sidang diruang sidang, atau mensyaratkan adanya surat kuasa bagi mereka yang mewakili pelanggar lalu lintas di persidangan.17 Sementara di opsi kedua, Ketua MA Hatta Ali pernah menyatakan harapannya agar sidang tilang diperlakukan sama seperti sidang akta kelahiran, yang pada akhirnya tidak perlu sampai ke Pengadilan. Usulan Ketua MA Hatta Ali tersebut disambut positif oleh sekelompok hakim yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI). Mereka mengusulkan agar pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, segera duduk bersama untuk mengambil langkah konkrit. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyetujui jika perkara tilang yang sumir tidak perlu sampai ke 16 17 Ibid, Hlm. 9 Ibid, Hlm. 7-8 159 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 Pengadilan. Bahkan Ketua MK saat itu, mengatakan bahwa sidang tilang adalah sesuatu yang mubazir, karena sumberdaya pengadilan idealnya diarahkan pada perkara-perkara hukum yang substansial.18 Untuk menjajaki berbagai kemungkinan menentukan opsi yang terbaik untuk dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum dan kebijakan yang terkait penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas maka sangat penting dilakukan penelitian dan pengkajian. Pada tahun 20132014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), didukung AIPJ melakukan penelitian tentang “Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan” yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Adapun lokasi penelitian meliputi PN Jakarta Timur, PN Medan, PN Surabaya, PN Palu, PN Ternate, dan PN Binjai. Diantara hasil kesimpulan penelitian adalah penerapan kebijakan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan tidak melalui pengadilan masih memerlukan beberapa syarat. Secara legalistik, KUHAP dan UU LLAJ mengatur kewenangan pengadilan dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Wacana mengeluarkan perkara pelanggaran lalu lintas perlu mengubah dua Undang-Undang tersebut yang membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Selain itu masih kuatnya paradigma tentang urgensi pelibatan pengadilan sebagai bentuk due process of law yang menjadikan Hakim sebagai tempat mengadu/minta keringanan dan pelanggar dapat menjelaskan alasan pelanggaran lalu lintas serta Hakim berperan memberikan pertimbangan terhadap unsur keadilan. Contoh: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan keringanan hukuman atas dasar pelanggaran lalu lintas, seperti masuk jalur Transjakarta, karena kondisi infrastruktur jalanan yang disediakan pemerintah buruk. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang dibagi dalam jangka menengah dan pendek. Rekomendasi jangka menengah meliputi : 19 1. Mengeluarkan perkara uncontested dari pengadilan melalui perubahan peraturan Perundang-undangan. 2. Perlu perbaikan pola hubungan dan koordinasi pelaksanaan peran masing-masing dalam perkara tilang antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan 18 19 Ibid, Hlm. 8 Ibid, Hlm. 216 160 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto 3. Mengkaji ulang pengaturan dalam UU LLAJ yang menetapkan uang titipan harus senilai maksimum ancaman denda karena menjadi disinsentif masyarakat untuk langsung membayar denda. 4. Perubahan ketentuan untuk membedakan perlakuan antara slip biru (pelanggar yang mengaku) dengan slip merah (pelanggar yang keberatan, baik yang hadir maupun verstek) Adapun rekomendasi jangka pendek yang disusun berdasarkan penelitian lapangan yang diadakan meliputi : 20 a. Perbaikan SKB Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu tertanggal 19 Juni 1993 (SKB 19 Juni 1993) b. Identifikasi praktik-praktik baik yang sudah diterapkan di berbagai pengadilan dan menjadikan model untuk jadi standar nasional. c. Mengembangkan buku standar pelayanan pengadilan untuk pengelolaan perkara tilang. d. Memperbaiki layanan dengan mengoptimalkan peran SDM di pengadilan disesuaikan dengan beban perkara tilang. e. Memperbaiki fasilitas pengadilan terutama penyediaan loket khusus dengan kaca, pengaturan lokasi layanan yang berdekatan dan media informasi pengadilan yang berkaitan dengan pelayanan perkara tilang. f. Mengurangi ruang gerak calo dengan layanan dan fasilitas yang optimal antara lain melalui larangan penawaran jasa pengurusan tilang (sebagai kuasa atau perantara) di lingkungan pengadilan dan kemungkinan pencantuman kuasa dalam buku register atau daftar tilang yang dipublikasikan pengadilan. g. Koordinasi pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara tilang, dengan melakukan: 1) Pembuatan laporan rekapitulasi perkara tilang tiap hari sidang (seperti praktik di PN Jakarta Timur). 2) Pembuatan laporan penyetoran penerimaan negara dari perkara tilang. 3) Kesepakatan penyampaian daftar perkara tilang dari Kepolisian ke Pengadilan dalam format soft copy. 4) Peningkatan kapasitas SDM dalam layanan perkara tilang sebagai optimalisasi peran pengadilan bagi penegakan hukum, ketaatan hukum masyarakat, dan budaya berlalu lintas yang baik. 20 Ibid, Hlm. 216-217 161 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 E. Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Berdasarkan hasil penelitian “Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan di atas, direkomendasikan (salah satunya) mengeluarkan perkara uncontested (khususnya pelanggaran lalu lintas) dari pengadilan melalui perubahan peraturan Perundang-undangan. Pengeluaran pelanggaran lalu lintas dari pengadilan ini dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu: Pertama, pelanggaran lalu lintas seyogyanya tidak masuk ke pengadilan karena dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hatta Ali bahwa harapannya agar sidang tilang diperlakukan sama seperti sidang akta kelahiran, yang pada akhirnya tidak perlu sampai ke Pengadilan. Di Singapura dan New Zealand, semua pelanggaran lalu lintas sudah bukan pelanggaran pidana, tapi administrasi. Kalau melanggar, jelas harus membayar. Di Korea juga sudah digunakan dananya untuk meningkatkan fasilitas transportasi dan pelayanan umum.21 Kedua, pengadilan tetap dapat menerima pemeriksaan dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas hanya untuk perkara yang Pelaku tidak menerima dan menentang ketika ditilang. Sementara untuk yang menerima dan tidak membantah atau menentang (uncontested) tidak perlu melalui sidang pengadilan. Dalam konteks ini bukan berupa sistem “uang titipan” sebagaimana dianut dalam UU LLAJ yang notabene masih memerlukan perbaikan secara subtantif maupun implementatif. Diantara perbaikan substasi yaitu terkait jumlah nominal denda maksimum dalam “uang titipan” yang harus dititipkan seringkali membuat masyarakat khususnya Pelanggar (mayoritas menengah ke bawah) lebih memilih hadir di persidangan. Ditetapkannya membayar denda maksimum adalah untuk mengantisipasi putusan Hakim yang lebih tinggi daripada “uang titipan”. Kondisi keuangan atau perekonomian menjadi salah satu alasan Pelanggar tidak memungkinkan untuk membayar secara langsung melalui tranfer lewat Bank pada saat itu dengan nominal denda maksimum yang cukup tinggi. Apalagi dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki disparitas yang signifikan dengan denda maksimum yang dibayarkan melalui mekasime uang titipan. Terlebih lagi secara prosedur mekanisme “uang titipan” bagi sebagian masyarakat dinilai tidak sederhana, 21 Sebagaimana disampaikan oleh Kombes Indrajit Koordinator Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian pada seminar penelitian “Alternatif Pengelolaan Perkara Lalu Lintas di Pengadilan”. Acara yang merupakan rangkaian kegiatan Penelitian tentang Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang di Pengadilan ini diselenggarakan di Jakarta, 17 Juni 2014. 162 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto karena harus datang lagi ke Bank untuk mengambil selisih nominal uang dari putusan pengadilan. Di sisi lain dalam optik implementatif, mekanisme “uang titipan” seringkali dijadikan sebagai pengancaman untuk membuat takut atau jera Pelanggar. Misalnya dalam pelanggaran jalur bus way di Jakarta. Secara faktual semakin membuat masyarakat atau Pelanggar enggan memilih mekanisme “uang titipan”. Padahal pengaturan dan penerapan “uang titipan” tersebut diharapkan agar tidak semua pelanggaran lalu lintas masuk ke pengadilan. Dalam konteks ini penerapan mekanisme “uang titipan” ini menjadi kontraproduktif dari tujuan untuk melakukan percepatan dan kemudahan serta keringanan biaya. Sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Berdasarkan fakta yang demikian maka perubahan ketentuan untuk membedakan perlakuan antara slip biru (pelanggar yang mengaku) dengan slip merah (pelanggar yang keberatan, baik yang hadir maupun verstek) sangat penting. Oleh karenanya pengkajian ulang pengaturan dalam UU LLAJ yang menetapkan uang titipan harus senilai maksimum ancaman denda karena menjadi disinsentif masyarakat untuk langsung membayar denda. Selain itu pengkajian ulang tersebut juga terkait dengan penguatan hak bagi Pelanggar untuk menentukan pilihan terbaik dan akomodatif dalam menjalani mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Di pihak lain penegak hukum (Kepolisian) juga perlu diberikan wewenang untuk membantu penentuan pilihan tersebut kepada Pelanggar. Dalam konteks demikian perlu dipertimbangkan penerapan diversi yang proporsional, tepat dan akuntabel dalam penyelesaian dan penanganan pelanggaran lalu lintas. Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, Pelaku, Korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Secara normatif, diversi diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian diversi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dalam UU SPPA juga diatur mengenai proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau 163 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversi menurut Marlina merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.22 Adapun tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi‟.23 Eva Acjani Zulfa menjelaskan, Aronson memaknai diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan Undang-Undang, penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari penegak hukum. Diskresi dalam istilah Heffernan dan Stroup merupakan hard choices in law enforcement (meskipun dalam tulisannya titik berat pilihan penggunaan diskresi ada pada Polisi sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana). Dinyatakan sebagai pilihan yang berat karena apa yang ditentukan dalam aturan tertulis dibandingkan dengan situasi yang nyata dalam realitanya bisa jadi sangat berbeda. Adanya perbedaan antara konsep ideal yang ditentukan secara formal dalam aturan Perundang-undangan dengan situasi yang berbeda dalam realitasnya, menyebabkan petugas harus mengambil kebijakan menurut pertimbangannya sendiri sebagai respon atas situasi tersebut. Oleh karenanya kewenangan diskresi sebagai alat untuk melakukan diversi dalam prosess peradilan pidana dapat dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Polisi dan petugas pemasyarakatan.24 Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui penerapan diversi adalah cukup relevan dan urgen baik ditinjau dari perspektif filosofis, teoritis, dan soiologis. Ditinjau dari perspektif filosofis, melalui penerapan diversi lebih terjamin aktualisasi restoratif justice.25 22 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, Hlm. 1 23 Ibid, Hlm.2 24 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Lubuk Agung, 2011, Hlm.159 25 Menurut Andi Hamzah, Andi Hamzah menerjemahkan dengan peradilan restoratif sama dengan criminal justice diterjemahkan dengan peradilan pidana (Andi Hamzah, Restoratif 164 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto Sebagaimana diketahui bahwa beberapa dekade terakhir ini terdapat pergeseran dari retributif justice menuju restoratif justice.26 Hal ini ditandai dengan berbagai produk peraturan Perundang-undangan maupun pembentukan hukum oleh pengadilan yang mengandung orientasi dan paradigma restoratif justice. Misalnya UU SPPA, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lain. Pergeseran tersebut dapat dimaknai sebagai peroses refilosofi hukum nasional, dikatakan refilosofi karena pada asasnya bangsa Indonesia telah menganutnya sejak lama namun karena penjajahan kolonial maka lambat laun nilai-nilai hukum yang berorientasi restoratif justice tersebut tergerus. Oleh karena itu tidak salah kiranya jika paradigma restoratif justice juga diaktulisasikan dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui penerapan diversi. Pelibatan para pihak yaitu Pelanggar dan penegak hukum pada saat pra ajudikasi dalam sebuah media musyawarah mufakat yang demokratis (sila keempat Pancasila) dan bervisi pelayanan hukum yang prima akan dapat memberikan sentuhan rasa peradilan yang manusiawi (keadilan yang beradab/manusiawi) bukan penegakan hukum yang mekanistik. Pelanggar diberikan penguatan hak untuk menentukan pilihan hukum menyelesaikan perkara pelanggarannya di luar atau melalui pengadilan dengan kebebasan untuk mengukur kebersalahan dan penyerahan serta pengakuan atas pelanggaran yang dilakukannya. Jika mengaku dan terima serta tidak membantah saat dilakukan tindakan oleh Polisi maka diselesaikan dengan pembayaran denda Justice dan Hukum Pidana Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, Hlm.5). Sementara itu Bagir Manan lebih cenderung mengartikan Restorative justice sebagai sebuah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. (Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir( Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hlm. 4) 26 Terdapat 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (retributif justice) dan keadilan restoratif (restoratif justice). Lihat dalam Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana FHUI, 2001, Hlm.25 dan lihat juga dalam Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 43. Restoratif justice merupakan suatu model pendekatan baru (meskipun merupakan nilai tradisional) dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, Korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. (Eva Achjani Zulva, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI, 2009) 165 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 lewat Bank yang nilai nominalnya terjangkau atau diterapkan denda minimal tanpa melalui pengadilan. Dengan demikian penanganan dan penyelesaian pelanggran lalu lintas menjadi responsif karena memberikan hak pada Pelanggar untuk memilih secara ekonomis (dapat insentif denda minimum) dan tidak birokratis (tanpa proses lebih lanjut ke pengadilan yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga lebih) dan ujungnya menyebabkan pengadilan tidak terlalu dibebankan oleh perkara yang ringan/cukup sumir dan SDM dapat berfokus pada penyelesaian perkara yang lebih subtantif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat, terhadap Pelanggar diberikan pemahaman oleh penegak hukum tentang posisi tindakan dan kesalahan serta pilihan hukum yang dapat diambilnya. Kemudian dalam kondisi tertentu Polisi dimungkinkan melakukan kebijaksanaan untuk tidak memproses perkara tersebut jika dinilai edukasi dan pembinaan masih memungkinkan digunakan bilamana terdapat alasan tertentu yang akuntabel dan tanpa adanya sifat koruptif. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum pidana yaitu ultimum remedium yang menegaskan bahwa hukum pidana adalah sarana paling akhir jika sarana lain sudah tidak berhasil. Dalam teori kebijakan hukum pidana (criminal policy), penggunaan sarana non penal semaksimal mungkin digunakan sebelum sarana penal diambil atau bisa juga digunakan secara terpadu (integralitas). Bassiouni menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk: 27 1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai; 2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang akan diperoleh delam hubungannya dengan tujuan yang dicari; 3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan 4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. Menurut Eva Achjani Zulfa, terdapat pandangan bahwa fungsi ultimum remedium dari hukum pidana nyata sejak awal proses perumusannya di dalam lembaga legislatif. Terlebih lagi ada anggapan 27 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm.30 166 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto bahwa Undang-Undang tanpa sanksi pidana ibarat macan ompong. Karenanya fungsi hukum pidana diterjemahkan tidak dalam level kebijakan tetapi lebih pada kemampuan bagaimana penegak hukum mampu menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyaringan terhadap permasalahan-permasalahan apa yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dan mana yang tidak. Kewenangan yang seperti ini seringkali dikenal sebagai discresionary power.28 Dalam konteks penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dapat merupa sebagai diversi. Ditinjau dari optik sosiologi hukum, pengalaman penerapan hukum pidana selama ini telah menjelaskan kepada kita bahwa perkara pidana yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan dengan menggunakan sarana hukum pidana, secara yuridis formal telah selesai akan tetapi secara sosial masih meninggalkan persoalan-persoalan dan sebaliknya ada perkara yang secara sosial telah selesai akan tetapi untuk menegakkan hukum pidana maka harus diproses berdasarkan hukum pidana.29 Seharusnya pemahaman dan penerapan hukum yang demikian sudah mulai dire-evaluasi dan direorientasikan untuk tidak mempersulit suatu proses penegakan keadilan dengan alasan mekanime hukum yang mekanistik. Persoalan pelanggaran lalu lintas yang pelanggarnya sudah mengaku dan tidak membantah serta mau membayar denda masih harus mengurusi sisa atau selisih denda. Padahal jika bervisi efisiensi dan sederhana dalam memprosesnya, maka pengaturan penentuan denda yang tepat, proporsional dan mudah dijangkau serta meringkaskan perkara pada pembayaran denda di tahap pra ajudikasi hingga tidak perlu datang lagi ke Kejaksaan atau Bank untuk mengambil selisih denda akan memberikan sebuah kepraktisan hukum dan peradilan sebagaimana asa peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Bukankah negara semakin diuntungkan dengan adanya diversi bagi perkara yang sumir dan mengoptimalkan penyelesaian perkara di pengadilan pada perkara-perkara yang lebih subtantif dan produktif misalanya korupsi, illegal logging, money laundering, illegal mining, dan lain-lain yang berpotensi mengembalikan kerugian negara. Selain itu tidak akan rugi jika pendapatan negara melalui denda pelanggaran lalu lintas didapatkan dengan mekanisme yang lebih efsien, sederhana dan sangat cepat tanpa birokrasi dan pentahapan proses penyelesaian yang kurang sederhana dan tidak cepat serta biayanya cukup mahal sebagaimana yang berlaku sekarang, bukan? 28 Eva Achjani Zulfa, Op Cit, Hlm.15-16 Lalu Parman, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah yang dipresentasikan pada seminar penelitian tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diadakan oleh Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung di Mataram pada tanggal 12 Mei 2011 , Hlm.2-3 29 167 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 F. Penutup Volume perkara pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada Pengadilan Negeri tertentu yang sampai mencapai ribuan perkara dan disidangkan dalam waktu sehari senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversi patut dijadikan salah satu cara mengurangi beban perkara di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/ Pelanggar dibawah umur). Terhadap Pelanggar diberikan pemahaman oleh penegak hukum tentang posisi tindakan dan kesalahan serta pilihan hukum yang dapat diambilnya. Kemudian dalam kondisi tertentu Polisi dimungkinkan melakukan kebijaksanaan untuk tidak memproses perkara tersebut jika dinilai edukasi dan pembinaan masih memungkinkan digunakan bilamana terdapat alasan tertentu yang akuntabel dan tanpa adanya sifat koruptif. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum pidana yaitu ultimum remedium yang menegaskan bahwa hukum pidana adalah sarana paling akhir jika sarana lain sudah tidak berhasil. Daftar Pustaka Andi Hamzah, Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008 Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir( Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008 Eva Achjani Zulva, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI, 2009 -------------------------, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Lubuk Agung, 2011 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010 168 Diversi untuk Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Budi Suhariyanto Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana FH-UI, 2001 M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Cetakan ke 12 : 2010 Lalu Parman, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah yang dipresentasikan pada seminar penelitian tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diadakan oleh Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung di Mataram pada tanggal 12 Mei 2011 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dan PSHK, Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil dan PSHK, 2014 Tim Survey Kepuasan Pengadilan 2013, Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) & Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas), 2013. 169 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 170 URGENSI PERAN PENGADILAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Urgency of Court Enrollment in Giving a Legal Aid Service on Poor People Based on Law No.16 Year 2011 on Legal Aid) Isnandar Syahputra Nasution Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Jl. Tambun Bungai No.55, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah Email : [email protected] Abstrak Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah layanan pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan serta penyedian Posbakum Pengadilan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Posbakum ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Posbakum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. Kata kunci : Pengadilan, Bantuan Hukum, Orang Miskin Abstract Implementation of Legal Aid Post (Posbakum) by the District Court includes three (3) the scope of legal services in accordance with the provisions contained in the Perma No. 1 Year 2014. Those 3 scopes are services of fee waiver, and the holding of the trial outside the court building and providing Posbakum Court. In connection with the implementation of this Posbakum actually State Court only provides room facilities to Posbakum for three Legal Aid Provider or accredited lawyers organization. 171 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 As for the legal aid fund handling each case will be filed by the Court through the Lokal Office of Kemenkumham. However, this does not mean that the facilitator function can be ignored, considering this Posbakum takes place in the Court, it is noteworthy that there is a special mandate from the State Officials to the Court in order to succeed the free legal services for the poor. Therefore, it can also be expected that the presence of the Posbakum in the Court can erode the negative and scary stigma on the Court for the general public. Keywords : Court, Legal Aid, the Poor A. Pendahuluan Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (law enforcement) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan Hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan Hakim Pengadilan Negeri. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti seluasluasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (law information management) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta 1 Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945. 172 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution (iii) fungsi yudikatif atau judisial.2 Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparatur tingkat pusat, aparatur tingkat provinsi, dan aparatur tingkat kabupaten/kota. Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah,3 tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law), kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (law making), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (law enforcing). Bahkan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem civil law, yaitu berlakunya teori fiktie yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Orang kaya di Jakarta harus diperlakukan sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah terpencil di Mentawai (Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan, ataupun suku terpencil di pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Nusantara. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif 2 Montesquieu, The Spirit of the laws, Translated by Thomas Nugent, (London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67. 3 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hal. 115 dan 123-124. 173 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguhsungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badanbadan peradilan.4 Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (information technology); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.5 4 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994. 5 Jimly Assidiqie, “UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan”. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998. 174 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.6 Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri. Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri 6 Jimly Assiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 175 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial. Pemberitaan mengenai hak-hak rakyat miskin yang terabaikan saat berhadapan dengan proses hukum, akhir-akhir ini menjadi tema besar yang ramai dibicarakan. Hak-hak rakyat miskin yang dinodai, bukan merupakan barang baru di lingkungan pengacara publik. Sudah terlalu banyak pencari keadilan yang datang ke berbagai lembaga bantuan hukum, yang mengandalkan pendampingan prodeo, mengalami hal tersebut. Sayangnya, instrumen hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi rakyat, khususnya rakyat miskin, masih terbatas. KUHAP hanya mengenal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kurang dari itu harus menggantungkan diri pada nasib atau perekonomian sendiri. Contoh kasus, seorang Pemulung seperti Saleh yang “memiliki” ganja, karena dipaksa, sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan KUHAP. Ganja yang termasuk narkotika golongan I memiliki ancaman hukuman 4 tahun sampai 12 tahun penjara. Lagipula pemberian bantuan hukum dilakukan di tingkat pemeriksaan mana, juga tidak jelas pengaturannya. Niat pemerintah mengatur pemberian bantuan hukum melalui peraturan pemerintah (PP) maupun aturan setingkat Instruksi Menteri juga belum menyentuh permasalahan tersebut. Aturan-aturan tersebut hanya memberi acuan pemberian bantuan hukum dan belum mengakomodasi hak rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, PP tersebut yang merupakan amanat UU Advokat tidak tepat untuk mengatur LBH/penggiat bantuan hukum, yang karakter dan fungsinya berbeda dengan advokat dalam hal pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hakikatnya, pemberian bantuan hukum bukan semata-mata merupakan tanggung jawab LBH, para advokat, maupun partai politik yang memiliki semacam divisi bantuan hukum. Dikatakan dalam konstitusi, bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (pasal 34 UUD 1945). Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara. Kondisi yang kontras dengan persidangan korupsi maupun kasus-kasus lainnya yang melibatkan para pejabat tinggi ataupun orang-orang yang berduit banyak, yang justru 176 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution memperlihatkan bahwa hak untuk didampingi pengacara kelas atas merupakan akomodasi primer. Sedangkan bagi rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum saja sudah cukup sulit. Hal ini membuat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sepertinya menjadi sesuatu yang terlalu muluk. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Bantuan Hukum Litigasi meliputi : 1. Kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2. Kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 3. Kasus Tata Usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi: 1. Penyuluhan hukum; 2. Konsultasi hukum; 3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4. Penelitian hukum; 5. Mediasi; 6. Negosiasi; 7. Pemberdayaan masyarakat; 8. Pendampingan di luar pengadilan; dan / atau 9. Drafting dokumen hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni: 1. Keadilan; 177 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 2. 3. 4. 5. 6. Persamaan kedudukan di dalam hukum; Keterbukaan; Efisiensi; Efektivitas; dan Akuntabilitas Ada 310 Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi/akreditasi untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yang terdiri dari 10 OBH terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi C. Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilakasanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? 2. Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin? C. Pembahasan 1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum yang Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; 178 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: 1. Berbadan hukum; 2. Terakreditasi; 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4. Memiliki pengurus; dan 5. Memiliki program Bantuan Hukum. b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat: 1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. 2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan: 1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. 2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud diatas Pemberi Bantuan 179 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. 180 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution c. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP 42/ 2013. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam: 1. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 3. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP 42/2013 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP No. 42/2013. Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan 181 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PP 42/2013. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri. 182 d. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) PP. 42/2013 . Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit: 1. Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 2. Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PP No. 42/2013, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri. Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya. Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. e. Pengawasan Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum. Pengawasan oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian. Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) PP 42/2013 mempunyai tugas : 1. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; 2. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah; 3. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; 4. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/ atau masyarakat; 5. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan 6. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia pengawas daerah terdiri atas wakil dari unsur: 1. Kantor Wilayah Kementerian; dan 2. Biro hukum pemerintah daerah provinsi. Panitia pengawas daerah mempunyai tugas: 1. Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; 2. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan 3. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian. Panitia pengawas daerah dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak 183 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang. Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti. Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat: 1. Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum; 2. Menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau 3. Tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima 2. 7 Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum Salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya baik dibidang hukum perdata maupun pidana (pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).7 Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Dalam kaitannya dengan tugas pokok Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan, Mahkamah Agung Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005 184 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (CumaCuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014 ini, maka SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma No. 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Mahkamah Agung sendiri telah menyerahkan Perma No. 1 Tahun 2014 ini kepada Menkumham untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara dan sudah sah berlaku. Kemudian Mahkamah Agung akan mensosialisasikan ke setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan. Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti secara teknis melalui masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah 1. Layanan Pembebasan Biaya 185 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 Perkara, 2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan 3. Penyedian Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan. Untuk layangan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu Pemohon mengsisi formulir permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya (Bab III Pasal 7 Point 2 Perma No.1 Tahun 2014) ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui meja 1 bersamaan dengan surat gugatan/permohonan. Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran dan melanjutkan proses dengan menyampaikan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera / Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan. Apabila permohonan dikabulkan maka Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara akan tetapi jika permohonan ditolak maka pemohon harus membayar biaya perkara seperti biasa. Untuk memudahkan pelaksanaan Perma ini setiap Dirjen harus mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Perma No.1 Tahun 2014 dalam bentuk surat edaran Dirjen. SEMA No.1 Tahun 2014 ini merupakan perubahan SEMA No.14 Tahun 2010 yang juga mengharuskan setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha negara/pajak/pidana/pidana khusus/pidana militer, harus menyertakan dokumen eletronik. Dokumen elektronik yang dimaksud misalnya untuk permohonan kasasi meliputi: relasi pemberitahuan putusan banding, akta permohonan kasasi, tanda terima memori kasasi, memori kasasi, putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding. Penyertaan dokumen elektronik dilakukan melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. D. Penutup 1. Kesimpulan a. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: 186 Peran Pengadilan dalam Bantuan Hukum Orang Miskin, Isnandar S. Nasution b. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: 1. Berbadan hukum; 2. Terakreditasi; 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4. Memiliki pengurus; dan 5. Memiliki program Bantuan Hukum. Tata cara pemberian bantuan dapat dilakukan dengan : 1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. 2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah 1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan 3. Penyedian Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos 187 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188 Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum. 2. Saran Perlu adanya mekanisme keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan agar tidak ada lagi rasa takut dan stigma negatif tentang pengadilan. Daftar Pustaka Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994. ----------, “UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan”. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998. --------, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. --------, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, New York; Russell & Russell, 1961. Montesquieu, The Spirit of the laws, Translated by Thomas Nugent, London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914. 188 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 BIOGRAFI PENULIS Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., lahir di Sampang, Madura, tanggal 13 Mei 1957, lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof. Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013), Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Andalas (UNAND) dengan predikat Summa Cumlaude tahun 1994, Master of Public Administration di Universitas Malaya Kuala Lumpur tahun 2001, dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2009 dengan predikat Cumlaude. Tahun 2011-2016 Ketua Program Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNAND. Mengikuti kursus “Law and Governance in Developing Countries” di Van Vollenhoven Institute Faculty of Law Leiden University, SeptemberDesember 2003 dan Chevening Fellowship dalam kursus “What Democracy Means” di University of Birmingham, Inggris, Januari-April 2006. Tahun 2003-2007 peneliti The Indonesian-Netherlands Studies of Decentralization of the Indonesia “Rechsstaat” (Negara Hukum, Rule of Law) and Its Impact on Agrarian (INDIRA) kerja sama beberapa universitas di Indonesia dengan Van Vollenhoven University of Leiden, Belanda. Sepanjang SeptemberOktober 2009 peserta “Rule of Law Forum” di Dallas-Texas, Washington dan New York AS. Visiting Scholar di Gakushuin University-Tokyo, Oktober 2011. Aktif Menulis di beberapa media cetak nasional dan sampai saat ini sekitas 600 (enam ratus) tulisan telah dipublikasikan di Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, The Jakarta Post, Koran Seputar Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Majalah Tempo, Majalah Gatra, dll. Tidak hanya itu, sejauh ini telah menghasilkan belasan buku dan 50-an tulisan berbagai jurnal ilmiah dan ratusan makalah yang disampaikan dalam seminar nasional maupun internasional. Sepanjang 2004-2014 menerima beberapa penghargaan, di antaranya: (1) Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), 2004; (2) Award of Achievement for People Who Make a Difference dari Gleitsman Foundation, USA, 2004; (3) UNAND Award atas prestasi bidang penelitian dan karya ilmiah, 2007; (4) Tokoh Muda Inspiratif versi Kompas, 2009; (5) dan Megawati Soekarno Putri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi, 2012. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada: Universitas Indonesia, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Badiklat Kejaksaan Agung R.I., Kelas Khusus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum FHUI, Badiklat Mahkamah Agung R.I. Bagi Pelatihan Hakim Tipikor dll, Penasehat Ahli Hukum (Pidana) Kapolri, Tim Pakar Hukum (Pidana) Menteri Hukum dan HAM RI, mantan Konsultan Ahli Hukum (Pidana) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum & HAM, mantan Ahli Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Tim Perumus Perubahan KUHP/KUHAP, Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Suap, Pembuktian Terbalik, Perampasan Aset, KUHP, KUHAP dll, serta Advokat Senior pada “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan”. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., lahir di Larantuka, Flores tahun 1945. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unair pada 1973. Setelah mengikuti Sandwich Program di Leiden 1984, memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum tahun 1985 di Universitas Airlangga. Hingga 2010 mengabdi pada Universitas Airlangga, sebagai tenaga pengajar. Bidang keahlian utama Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, minat yang dikembangkan Teori Hukum dan Argumentasi Hukum. Sering tampil sebagai saksi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri dalam perkara yang menyentuh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Juga tampil sebagai ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi perkara permohonan pengujian konstitusionalitas UU. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Siti Nurjannah, S.H. M.H., lahir di Sleman, 01 November 1956. Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Jabatan Administrasi : Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. : Lahat - Palembang : 11 November 1959 : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Mahkamah Agung RI Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Utara Kav. 9-13 Blok F 202 Alamat Rumah : Nirwana Estate Blok L No. 1 Cibinong Pengalaman Pekerjaan : 1. Hakim Tinggi Jakarta/Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI 2011Sekarang 2. Ketua Pengadilan Negeri Palembang 2010-2011. 3. Ketua Pengadilan Negeri Batam 2008-2010. 4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam 2007. 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta 2006. 6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2002. 7. Hakim Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2002. 8. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong 1998. 9. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur 1995. 10. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim 1989. 11. Calon Hakim Pengadilan Negeri Bekasi 1986. Tambahan : 1. Dosen Program Pasca Sarjana pada Universitas Sriwijaya Palembang (2010 - Sekarang) 2. Dosen Program Pasca Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Palembang (2010 - Sekarang) 3. Dosen Program Pasca Sarjana pada Universitas Jayabaya Jakarta (2012 - Sekarang) Pendidikan : 1. Doktor, Universitas Pajajaran Bandung 2009 2. S2 Hukum, Jakarta 1998 3. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 1984 Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. adalah Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Prima Indonesia (Medan), Dosen, Penguji dan Pembimbing Disertasi (Co Promotor) Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta) dan Penguji Tamu Program S3 Universitas Brawijaya (Malang), Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Semarang), Universitas Veteran (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Pusdiklat MA RI. Menyelesaikan Program S1 (1985) dan S2 (2002) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan Program S3 (2007) dalam waktu 2 (dua) tahun pada Program Doktor Universitas Padjadjaran dengan predikat cumlaude (IPK 3,97). Ketika Mahasiswa aktif sebagai Ketua Senat, Ketua BPM, Redaktur Pers Kampus, Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Mahasiswa Teladan I Fakultas Hukum dan Teladan I Universitas Udayana (1985). Sebagai Hakim Peradilan Umum mempunyai spesifikasi sebagai Hakim Umum, Hakim Niaga, Hakim TIPIKOR, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Hakim Lingkungan serta pernah melakukan studi banding tentang Sistem Peradilan Pidana, Terorisme dan Hak Kekayaan Intelektual ke Bangkok, Jerman, Perancis dan Spanyol serta mendapat Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI. Kemudian pernah bertugas di Pengadilan Negeri Serui/Papua (1991), Pengadilan Negeri Kandangan (1995), Pengadilan Negeri Bangli (1999), Pengadilan Negeri Denpasar (2000), Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI dan TIPIKOR Jakarta Pusat (2004), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen (2007), Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen (2009), Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara (2011), dan sejak bulan Agustus 2013-sekarang sebagai Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara. Disamping menulis Buku Ilmu Hukum juga mempublikasikan tulisan ilmiah tentang hukum pada Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Terakreditasi), Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Terakreditasi), Majalah Mahkamah Agung, Majalah Varia Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan (Puslitbang Mahkamah Agung), serta sebagai Mitra Bestari pada Jurnal Yudisial Komisi Yudisial dan Jurnal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Buku yang telah ditulisnya dan diterbitkan oleh Penerbit PT Alumni, PT Citra Aditya Bakti, PT Djambatan, CV Mandar Maju, Bayu Media Publising dan Puslitbang Mahkamah Agung RI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buku. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., adalah Hakim Yustisial di Mahkamah Agung, pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Yogyakarta Tahun 1999, Magister Hukum (S-2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2004, dan sejak tahun 2010 sampai saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti Muda bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penalitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected] atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H., lahir di Natal, Sumatera Utara, 4 Desember 1981. S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 PEDOMAN PENULISAN JURNAL Jurnal Hukum dan Peradilan adalah media yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, terbit setahun 3 (tiga) kali (Maret, Juli dan November). Jurnal Hukum dan Peradilan menerima sumbangan naskah di bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan: 1. Naskah dikirim dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti hasil penelitian lapangan, analisis/tinjauan putusan lembaga peradilan, kajian teori, studi kepustakaan serta gagasan kritis konseptual yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptis. 2. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana dan mudah difahami dan tidak mengandung makna ganda. 3. Naskah harus orisinil dibuktikan dengan pernyataan akan keorisinilan naskah tersebut oleh penulis. 4. Naskah dapat dalam bahasa Indonesia sepanjang 10-20 halaman. Naskah diketik diatas kertas A4 menggunakan huruf Time New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Naskah harus disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara 100-150 kata. 5. Sistematika penulisan hasil penelitian harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Abstrak (berhasa Indonesia dan bahasa Inggris), Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Hasil penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, daftar Pustaka. 6. Sistematika penulisan analisis putusan, kajian teori, wacana hukum harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Abstrak (berhasa Indonesia dan bahasa Inggris), Pendahuluan, Pembahasan (dibuat sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), Kesimpulan, Daftar Pustaka. 7. Penulisan daftar pustaka secara alfabetis mengikuti Turabian Style dengan tata cara penulisan sebagai berikut: Buku. Weiss, Daniel A. Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence, Seattle: University of Washington Press, 1962. Makalah. Knight, Robin. “Poland’s Feud in the Family.”, New York, 10 September 1990, 52-53, 56. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Artikel Jurnal. Sommer, Robert. “The Personality of Vegetables: Bonatical Metaphors for Human Characteristics.” Journal of Personality 56, no. 4 (December 1988): 665-683. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan. Tillich, Paul. “Being and Love” In Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen, 661-72. New York: Harper & Bros., 1952. Internet Rost, Nicolas, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl. “A Global risk assessment model for civil wars.” Social Science research 38, no. 4 (December 2009): 921-933. http//www.sciencedirect.com/science/ article/ B6WX84 WMM7CY1/2/aa8571448b4774e8831a (accessed October 15, 2009) 8. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi paling mutakhir. 9. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnotes) mengikuti turabian Style dengan tata cara penulisan sebagai berikut: Buku. Daniel A. Weiss, Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence (Seattle: University of Washington Press, 1962), 62. Makalah. Robin Knight, “Poland’s Feud in the Family.”,U.S. New and Work Report, 10 September 1990, 52. Artikel Jurnal. Robert Sommer, “The Personality of Vegetables: Bonatical Metaphors for Human Characteristics.” Journal of Personality 56, no. 4 (December 1988): 670. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan Paul Tillich, “Being and Love,” in Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen (New York): Harper & Bros., 1952), 663. Internet Nicolas Rost, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl, “A global risk assessment model for civil wars,” Social Science Research 38, no.4 (December 2009): 922, http://www.sciencedirect.com/science/ B6WX84WMM7CY1/2/aa85435453ae88c432a 10. Naskah kiriman dalam bentuk softcopy atau hardcopy yang dilampiri dengan biodata singkat (CV) penulis, copy NPWP penulis, alamat email, No. telp/hp, naskah dapat dikirim via email ke e-mail redaksi jurnal atau puslitbang kumdil Mahkamah Agung RI 11. Naskah dikirim atau diserahkan secara langsung, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penerbitan kepada: Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274 Redaksi Jurnal Mahkamah Agung Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat 13011 email: [email protected] atau puslitbangkumdil @yahoo.co.id 12. Naskah yang tidak memenuhi format ketentuan diatas tidak akan diseleksi. Dewan editor berhak menyeleksi dan mengedit naskah yang masuk tanpa merubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Redaksi Jurnal Mahkamah Agung. artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan kepada penulis. Jurnal Hukum dan Peradilan Menyampaikan terima kasih Kepada para Mitra Bestari (referee) dan semua pihak Yang telah membantu penerbitan jurnal ini Volume 4 Nomor 1 Maret 2015 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 ISSN : 2303-3274