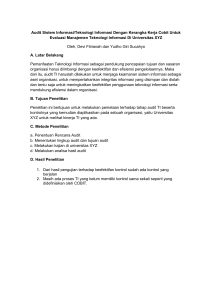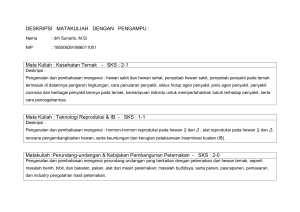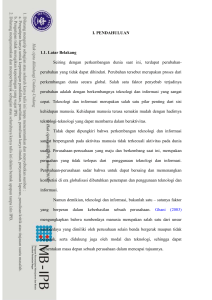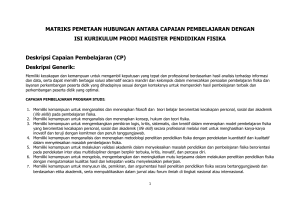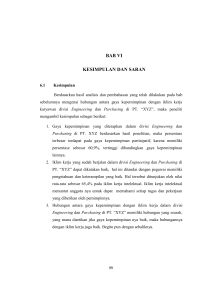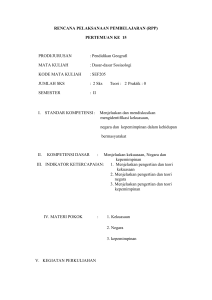Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu
advertisement

Kalbiscentia,Volume 3 No. 2, Agustus 2016 ISSN 2356 - 4393 Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu Implementasi Manajemen Pengetahuan di Lembaga Pendidikan Tinggi Julia Loisa Sistem Informasi, Universitas Bunda Mulia Jakarta Jalan Lodan Raya No. 2 Jakarta 14430 Email: [email protected] Abstract: This research aims to overcome the obstacles that are often faced by a higher education institution. One of the obstacle is when the employees who are also the owner of the intellectual capital move into another department or to another agency by applying the concept of knowledge management that related to the curriculum construction. Furthermore, the research approach used are library research / literature study about knowledge management, conducting observation and interview with program managers. The result shown that a study program can produce an integrated and systematic curriculum at every stage of the preparation of the curriculum. All stages of the curriculum should be documented as a set of plans and arrangements regarding learning outcomes of graduates, study materials, processes, and assessments used to guide the implementation of study program.. Keywords: knowledge management, intellectual capital, curriculum design, knowledge management life cycle Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengatasi kendala yang kerap dialami lembaga pendidikan tinggi jika pemilik intelektual dan para pelakunya mengemban tugas lain pada lembaga yang sama maupun berbeda dengan menggunakan konsep manajemen pengetahuan dalam kaitannya dengan penyusuan kurikulum. Pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka mengenai manajemen pengetahuan, observasi dan interview dengan pengelola program studi perihal penyusunan kurikulum. Hasil penelitian ini adalah program studi menghasilkan kurikulum yang terintegrasi dan sistematis pada setiap tahap penyusunan kurikulum. Semua tahapan penyusunan kurikulum harus didokumentasikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi . Kata kunci: manajemen pengetahuan, modal intelektual, penyusunan kurikulum, siklus manajemen pengetahuan I. PENDAHULUAN Perubahan lingkungan global menjadi salah satu faktor perubahan pada lingkungan bisnis dan organisasi. Menurut Thomas Friedman pada bukunya The World is Flat, secara umum peradaban manusia terbagi pada 3 (tiga) era: (1) Globalisasi 1.0 (1492 – 1800); ditandai dengan penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus; (2) Globalisasi 2.0 (1800 – 2000); ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt dan menjadi cikal bakal era industri; dan (3) Globalisasi 3.0 (2000- sekarang); ditandai dengan penggunaan teknologi informasi semakin merata, di mana pengetahuan mudah diperoleh dan mudah pula menjadi kadaluarsa, sehingga disebut dengan era pengetahuan. [1]. Pada era pengetahuan, perkembangan teknologi semakin canggih mampu 72 mengambil alih pekerjaan administrasi dan fisik, seperti kemampuan pengolahan data dan kemampuan produksi yang saat ini telah digantikan oleh mesin. Manusia menjadi sangat tergantung pada alat komunikasi dan komputer dalam berbagai aspek kehidupannya. Perubahan kedua hal tersebut mengakibatkan manusia harus mengubah peran dan kompetensinya dalam pekerjaan menjadi seorang karyawan berpengetahuan, sedangkan manusia yang tidak siap dengan perubahan akan menjadi korban dan ketinggalan zaman. Seorang karyawan berpengetahuanlah yang bisa mengembangkan ide, inovasi, melakukan perubahan pada organisasi, sehingga organisasi yang tanggap biasanya melakukan investasi dan memelihara karyawan karena dianggap asset yang berharga. Asset yang berharga itu disebut dengan modal intelektual Julia Loisa, Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu Implementasi Manajemen... sebagai produk dari pembelajaran individu, berbagi pengetahuan, pembelajaran di dalam komunitas, dan serangkaian aktivitas lainnya yang mampu melahirkan ide-ide sangat cerdas. Tantangan pertama adalah bagaimana organisasi mampu menciptakan suasana dan budaya keorganisasian yang dapat menfasilitasi atau memotivasi proses transformasi pengetahuan dalam organisasi, sehingga melahirkan pengetahuan tacit dan eksplisit. Tantangan kedua, setelah ide dan inovasi tersebut berkembang dengan subur adalah bagaimana organisasi mampu menangkap ide tersebut menjadi sebuah pengetahuan eksplisit dalam organisasi. Untuk menjawab tantangan kedua biasanya organisasi menerapkan sistem internal dengan bantuan sistem informasi. Tantangan yang sama terjadi juga pada lingkungan akademik di sebuah lembaga pendidikan tinggi, di mana produk sebuah pendidikan tinggi adalah kurikulum, sistem pengajaran, dan proses pembelajaran yang sangat tergantung pada pengetahuan intelektual para pelakunya. Kendala yang kerap dialami lembaga pendidikan tinggi adalah kala pemilik intelektual dan para pelakunya mengemban tugas lain pada lembaga yang sama maupun berbeda. Akibatnya, pewarisnya hanya mampu menebak maksud dari pendahulunya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan membahas implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan lembaga pendidikan tinggi dalam hal penyusunan kurikulum di Universitas XYZ di Jakarta Utara. A. Siklus Manajemen Pengetahuan Siklus manajemen pengetahuan terdiri dari penangkapan, penciptaan, kodifikasi, berbagi, menilai, aplikasi, dan penggunaan kembali pengetahuan (capture, creation, codification, sharing, accessing, application, and reuse). Salah satu pendekatan yang menggambarkan siklus manajemen pengetahuan ini adalah menurut Bukowitz and Williams yang menjelaskan bagaimana organisasi menghasilkan, mempertahankan, dan menyebarkan secara stratejik kumpulan pengetahuan yang mampu menciptakan nilai bagi organisasi. [2] Gambar. 1 The Bukowitz and Williams KM Cycle, Dalkir, Kimiz, (2005), Tahap Pertama, get adalah mencari informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan, dan menemukan inovasi. Pada tahapan ini termasuk mengetahui sumber pengetahuan dan cara mengakses pengetahuan tersebut baik pengetahuan eksplisit atau pengetahuan tacit. Artinya, seorang pengguna pengetahuan tidak hanya terhubung pada pengetahuannya saja, tetapi juga pada sumber pengetahuannya. Tahap kedua, use adalah bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan inovasi organisasi. Pada tahap ini, yang lebih tepat adalah penggunaan pengetahuan itu dari pada terlalu fokus pada menghasilkan suatu inovasi baru. Tahap ketiga, learn adalah proses pembelajaran dari pengalaman sebagai sarana menciptakan keunggulan bersaing. Organisasi belajar dari pengalaman yang gagal maupun sukses. Pada tahap pembelajaran ini adalah transisi setelah organisasi mencari dan mengaplikasikan pengetahuan (get and use) dengan menciptakan suatu hal baru dari pengetahuan tersebut, jika tidak pengetahuan tersebut hanya sebagai bagian dari “gudang” pengetahuan. Tahap keempat, constribute adalah tahapan seseorang menuliskan apa yang telah mereka pelajari pada knowledge base (pangkalan pengetahuan) organisasi. Pada tahap ini pengetahuan seseorang menjadi tersedia secara eksplisit dalam organisasi. Namun, bukan hanya sekedar mempublikasikan apa yang diketahui oleh seseorang, tetapi termasuk kontribusi pengetahuan mengenai pengalaman sukses dan gagal, sehingga seseorang tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Manajemen memori organisasi yang baik harus terdiri dari mempertahankan atribusi, membutuhkan otorisasi publikasi pengetahuan, menyediakan mekanisme umpan balik, dan menelusuri penggunaan kembali pengetahuan. Salah satu penghargaan terhadap kontribusi adalah memberikan pengakuan atas popularitasnya, misalnya berdasarkan jumlah kutipan yang mengacu pada tulisan tersebut. Tahap kelima, assess adalah tahapan evaluasi modal intelektual dan mengharuskan organisasi mendefinisikan pengetahuan yang kritis dan memetakan modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan masa depan. Organisasi perlu mengembangkan ukuran yang memperhitungkan peningkatan pangkalan pengetahuan dan manfaat berinvestasi modal intelektual. Teori organisasi perlu dilibatkan agar dapat menangkap dampak pengetahuan terhadap kinerja organisasi, termasuk 73 Kalbiscentia,Volume 3 No. 2, Agustus 2016 mengidentifikasi modal dengan bentuk yang lain seperti modal insani (kompetensi), modal pelanggan (relasi dengan pelanggan), modal keorganisasian (pangkalan pengetahuan, proses bisnis, infrastuktur teknologi, nilai, norma, dan budaya organisasi). Penilaian ini perlu menempatkan bagaimana kelenturan organisasi yang mempu mengubah pengetahuannya menjadi produk dan jasa yang bernilai bagi pelanggan. Serangkaian kerangka, proses, dan ukuran yang mengevaluasi basis pengetahuan harus dimasukkan semuanya ke dalam proses manajemen secara keseluruhan. Tahap keenam, build / sustain adalah memastikan modal intelektual masa depan organisasi mampu membuat organisasi tetap layak dan mampu berkompetisi . sumber daya harus dialokasikan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan pengetahuan , dan mereka harus disalurkan sedemikian rupa untuk menciptakan pengetahuan baru dan memperkuat pengetahuan yang ada. Tahap terakhir adalah divest. Organisasi tidak seharusnya mempertahankan asetnya baik intelektual maupun fisik jika aset tersebut sudah tidak lagi memberikan nilai. Organisasi perlu menguji modal intelektualnya apakah sumber daya yang digunakan untuk memelihara pengetahuan tersebut lebih bernilai jika digunakan untuk kepentingan lainnya. Hal ini melibatkan pemahaman mengapa , kapan, di mana , dan bagaimana secara resmi melepaskan bagian dari pangkalan pengetahuan. Analisis biaya dalam mempertahankan pengetahuan harus dimasukkan ke dalam praktek standar manajemen. Tahap pertama hingga keempat terjadi secara alamiah karena mereka dipicu oleh peluang atau tuntutan pasar, dan mereka biasanya menghasilkan pengetahuan yang digunakan sehari-hari untuk menanggapi tuntutan tersebut. Tahap kelima hingga terakhir lebih bersifat stratejik yang dipicu oleh perubahan lingkungan makro. Tahapan ini fokus pada proses yang menghubungkan modal intelektual dengan kebutuhan stratejik organisasi. B. The Choo KM Model Aktivitas utama pada siklus pengetahuan KM (The Bukowitz and Williams KM Cycle ) memerlukan kerangka kerja konseptual untuk beroperasi , jika tidak aktivitas-aktivitas tidak akan terkoordinasi dengan baik dan tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan KM. Bahwa The Choo SenseMaking KM Model menekankan pada bagaimana elemen informasi terseleksi dan menjadi bagian dari tindakan organisasi. Tindakan organisasi merupakan 74 hasil dari penyerapan informasi dari lingkungan eksternal ke dalam setiap siklus Choo’s Knowledge Management Model (Sense Making, Knowledge Creation, dan Decision Making). [2] Gambar.2 Choo’s (1998) Knowledge Management Model, Dalkir, Kimiz, (2005), C. Proses Penyusunan Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. [3] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (p5) jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi, maka kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada gambar berikut ini [4]. Gambar 3. Paradigma kurikulum sebagai sebuah program, Kemenristek DIKTI (2016), Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai sebuat proses yang diawali dari proses perancangan, diimplementasikan dalam proses pembelajaran, dan menghasilkan lulusan dengan capaian yang diharapkan. Penyusunan Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal (peraturan pemerintah, kebutuhan industri, benchmarking perguruan tinggi lain) dan internal (tracer study, fasilitas, visi misi institusi), termasuk Julia Loisa, Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu Implementasi Manajemen... analisis perkembangan keilmuan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang diakui oleh masyarakat. Penyusunan kurikulum terbagi dalah 3 (tiga) tahap besar yaitu: (1) Penentuan Profil Lulusan yang kemudian menghasilkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan; (2) Pemilihan Bahan Kajian, membuat Matriks (Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian), yang kemudian menghasilkan konsep mata kuliah dan besarnya satuan kredit semester (sks); dan (3) Penyusunan Struktur Kurikulum & Rancangan Pembelajaran menghasilkan dokumen kurikulum yang berisi seluruh tahapan penyusunan kurikulum Tahapan penyusunan kurikulum tersebut terlihat pada gambar berikut ini [4]: selanjutnya. Ketiga, Selection Phase adalah tahapan di mana individu berusaha untuk menafsirkan alasan untuk perubahan dengan membuat pilihan. Keempat, Retention Phase adalah organisasi dilengkapi dengan informasi yang telah terseleksi pada tahapan sensemaking. Pada tahap sense-making menghasilkan informasi terseleksi dari lingkungan eksternal yaitu peraturan pemerintah, kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, masukan dari para alumni, masukan dari para pengguna lulusan, dan perkembangan keilmuan dan teknologi. Tahap Knowledge Creating adalah tahap transformasi pengetahuan antar pribadi melalui diskusi atau kegiatan lainnya. Program studi bersama dengan tim melakukan sesi diskusi, rapat untuk menentukan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, pemilihan bahan kajian, matriks pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian sehingga menghasilkan daftar mata kuliah dan penentuan satuan kredit semester (sks) tiap mata kuliah. Tahapan ini menghasilkan berbagai alternatif pengetahuan baru dan alternatif solusi dengan segala pertimbangan resikonya. Gambar 4. Tahapan perancangan kurikulum, Kemenristek DIKTI (2016), D. The Choo Sense-Making KM Model dan Proses Penyusunan Kurikulum Tahap The sense-making adalah upaya memahami informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Tingkat prioritas dan kepentingan diidentifikasikan dan digunakan untuk menyaring informasi. Setiap orang membangun interpretasinya dengan membandingkan kondisi saat ini dan pengalaman masa lampau. Pada tahap sense making ini terdiri dari empat proses mulai dari perubahan kondisi ensternal hingga menentukan pilihan informasi mana yang harus ada dalam organisasi. Pertama, Ecological Change adalah perubahan pada lingkungan luar yang berdampak terhadap organisasi. Dalam hal penyusunan kurikulum kondisi eksternal yang sangat berdampak pada organisasi adalah perubahan peraturan pemerintah. Kedua, Enactment Phase di mana individu membangun, mengatur kembali, dan memusnahkan elemenelemen konten yang bertujuan memperjelas isi dan isu yang akan digunakan untuk proses seleksi Gambar 5. Matriks pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian, Kemenristek DIKTI (2016), Tahap Decision Making digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi berbagai alternatif yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, yaitu mengambil keputusan dan menghasilkan dokumen kurikulum baru. Pada tahapan ini distribusi mata kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester telah ditentukan. Ketiga tahap model Choo ini masih dibatasi pada tahap rancangan kurikulum, karena jika mempertimbangkan Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program (gambar 3), maka pembelajaran merupakan satu proses lain. Kurikulum sebagai proses terdiri dari proses perancangan dan diikuti oleh proses pembelajaran. 75 Kalbiscentia,Volume 3 No. 2, Agustus 2016 E. Evaluasi Proses Pembelajaran dan Lulusan Sebelum pembahasan mengenai proses evaluasi, perlu batasan jelas antara data, informasi, dan knowledge. Pada berbagai literature, secara umum data adalah fakta mentah yang menjadi informasi ketika data dihubungkan dengan sebuah konteks dan dikombinasikan sehingga menjadi struktur bermakna, yang kemudian menjadi knowledge bila informasi bermakna tersebut dikombinasikan dengan pengalaman dan berbagai pertimbangan. Hirarkri data-informasi-knowledge dilihat secara terbalik oleh Tuomi bahwa pengetahuan ada ketika diartikulasi, diungkapkan, dan distrukturisasi sehingga menjadi informasi, dan kemudian ditentukan standar interpretasi informasi tersebut sehingga menjadi data. Oleh sebab itu, menurut Tuomi data mentah itu tidak ada, karena dipengaruhi oleh knowledge atau pemikiran tersebut pada proses identifikasi dan pengumpulan data. [5]. Gambar 5. Hirarki data informasi Knowledge, Jing Tian Yoshiteru Nakamori Andrzej P. Wierzbicki, (2009) Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). [3]. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Sebagai pengelola program studi wajib melakukan 2 (dua) evaluasi yaitu: (1) Evaluasi proses pembelajaran (kesuaian proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran mata kuliah); dan (2) Evaluasi lulusan (kesesuaian kualifikasi lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan). Evaluasi proses pembelajaran dan lulusan menjadi bagian penting Knowledge Management Life Cycle sebagai dasar melalukan perbaikan. Knowledge yang diharapkan menginterpretasikan informasi yang diperlukan dan data mentah apa saja yang perlu dicari. 76 F. Siklus Manajemen Pengetahuan dan Penyusunan Kurikulum Penyusunan kurikulum hanya menjadi bagian dari siklus manajemen pengetahuan. Jika dikaitkan dengan siklus manajemen pengetahuan menurut Bukowitz dan Williams, maka siklus manajemen pengetahuan penyusunan kurikulum adalah: 1. Get. Mengikuti seminar mengenai Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI). Mengikuti acara sosialisasi SN-Dikti. Mencari sumber eksplisit dan tacit knowledge. 2. Use. Penyusunan kurikulum tahap 1 hingga tahap 3 sesuai Gambar 4. Rangkuman Proses Penyusunan Kurikulum 3. Learn. Mempelajari kekurangan kurikulum yang telah dioperasionalkan dan membuat revisi mata kuliah maupun kurikulum untuk meminimalkan kekurangan. 4.Constribute. Seseorang menuliskan apa yang telah mereka pelajari pada knowledge base (penyimpanan pengetahuan) organisasi termasuk konstribusi pengetahuan mengenai pengalaman sukses dan gagal sehingga seseorang tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Dampak dari konstribusi tersebut adalah memperkaya content memori organisasi. Tentunya, untuk dapat menfasilitasi ini organisasi perlu memiliki medianya, misalnya content management system, e-learning, news letter, dan lain sebagainya. 5.Assess. Organisasi menentukan arahan strategi ke depan dan mengidentifikasi modal capital yang diperlukan seperti kapital insani(kompetensi), modal pelanggan (relasi dengan pelanggan), modal keorganisasian (pangkalan pengetahuan, proses bisnis, infrastuktur teknologi, nilai, norma, dan budaya organisasi). Berarti, Organisasi mendefinisikan pengetahuan yang kritis dan memetakan modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan masa depan yang berdampak pada peningkatan konten pada pangkalan pengetahuan yang bertujuan agar organisasi mampu mengubah pengetahuannya menjadi produk dan jasa yang bernilai bagi pelanggan. Lembaga perguruan tinggi menentukan visi dan misi, kemudian menentukan strategi pencapaiannya terutama yang berkaitan dengan pangkalan pengetahuan. 6. Build/Sustain. Organisasi mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan modal intelektual masa depan agar dapat disalurkan kembali untuk Julia Loisa, Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu Implementasi Manajemen... menciptakan pengetahuan baru dan memperkuat pengetahuan yang ada. 7.Divest. Organisasi menentukan asset intellectual mana yang masih perlu dipertahankan dan dipelihara, sedangkan aset intelektual yang sudah tidak diperlukan agar dilokalisasikan. 3. Pasca Penyusunan Kurikulum Pada tahap ini terdiri dari: (a) Pengkodean mata kuliah; (b) Penyusuan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (c) Evaluasi proses pembelajaran; dan (d) Evaluasi lulusan. II. METODE PENELITIAN Jadwal penyusunan kurikulum yang dilakukan pada Universitas XYZ seperti pada Gambar 6: Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan tulisan ini adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan manajemen pengetahuan dan Pengembangan Kurikulum berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mengikuti seminar, mempelajari Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, wawancara, dan pengamatan dengan pengelola program studi di Universitas XYZ. A. Tahapan Penyusunan Kurikulum Berikut ini adalah tahapan penyusunan kurikulum yang diterjemahkan berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (2016) dan disesuaikan dengan budaya universitas[4]: 1 . Pra Penyusunan Kurikulum Pada tahap pra penyusunan kurikulum, pihak universitas menentukan ataupun menyesuaikan dengan rencana strategi (renstra) universitas untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan dan mempelajari arahan dari pemerintah, yang menghasilkan kebijakan universitas dalam hal penyusunan kurikulum: (a) Fokus kurikulum yang ingin dicapai (diturunkan dari visi misi universitas); (b) Mata kuliah wajib negara, mata kuliah wajib universitas dan satuan kredit semester; (c) Kebijakan operasional terkait standar pengajaran 2. Penyusunan Kurikulum Pada tahap penyusunan kurikulum dilakukan oleh setiap program studi. Pada Universitas XYZ terdapat 11(sebelas) program studi. Tapahan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh setiap program studi adalah: (a) Analisis Internal & Eksternal: (1) SWOT & Benchmark: (2) Perkembangan keilmuwan dan masukan dari asosiasi (3) Tracer Study, masukan lulusan, dan masukan pengguna lulusan; (b) Penentuan Profil Lulusan dan deskripsi kemampuannya; (c) Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (d) Penentuan Bahan Kajian (e) Matriks CPL dan Bahan Kajian menghasilkan mata kuliah dan sks; dan (f) Struktur Kurikulum & Dokumen Kurikulum B. Jadwal Penyusunan Kurikulum Gambar 6. Jadwal penyusunan kurikulum pada Universitas XYZ Selanjutnya, tahap pasca penyusunan kurikulum yang terdiri dari evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi lulusan masih merupakan proyek lanjutan yang belum diidentifikasikan waktunya III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Seminar dan Pengarahan Umum Tahap ini termasuk pada tahapan pra penyusunan kurikulum. Universitas XYZ melakukan pertemuan yang membahas mengenai: (1) Peraturan pemerintah yang mendasari penyusunan kurikulum; (2) Ketentuan Universitas dalam hal: (a) Mata wajib negara, mata kuliah wajib universitas dan sks-nya; (b) Batasan minimum dan maksimum total sks program studi berdasarkan jenjang pendidikan; (c Surat Keputusan Rektor tim penyusunan kurikulum B. Penyusunan Kurikulum oleh Program Studi 1. Analisis Internal dan Eksternal Berikut ini adalah sebahagian dari analisis internal dan eksternal pada 11 (sebelas) program studi di Universitas XYZ adalah: l Program studi satu Terkait dengan saran yang diberikan oleh pengguna lulusan dan alumni, menyatakan bahwa kemampuan bidang akuntansi keuangan telah cukup memadai. Namun masih perlu ditingkatkan dalam hal penguasaan praktik Audit dan praktik Perpajakan (terutama kemampuan dalam pengisisian e-Fin dan e-Faktur) l Program studi dua Kekuatan: Penguasaan lulusan terhadap teknologi informasi cukup memadai: Kelamahan: 77 Kalbiscentia,Volume 3 No. 2, Agustus 2016 Jabatan Akademik Dosen masih banyak tenaga pengajar; Peluang: Banyak tawaran kerjasama; Ancaman: Luasnya ilmu manajemen l Program studi tiga Berdasarkan masukan dari alumni dan pengguna lulusan, didapat data bahwa bidang ilmu yang banyak digunakan di tempat kerja adalah Business English Program studi empat Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini bergeser dari bidang ilmu kajian sastra dan budaya ke arah kajian penerapan bahasa, kajian interdisipliner, dan kajian multidisipliner seperti kajian penerapan bahasa dalam bidang pengajaran, bidang media massa, bidang bisnis, serta kaitannya dengan bidang ilmu lain seperti ilmu komunikasi, ilmu manajeman, dan lain-lain. l Program studi lima Era digital tersebut merambah ke bidang kehumasan. Dalam berbagai institusi, baik dalam bentuk korporasi, pemerintahan ataupun nirlaba mulai menyadari pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana peningkatkan citra institusi, penanganan krisis lintas sektoral, menunjang kegiatan pemasaran yang terintegrasi, dan wadah kreativitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini mutlak dilakukan mengingat persaingan industri di kancah global memberi ruang yang terbatas dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas Public Relations maupun Marketing Communication menggunakan media sosial menjadi strategi yang jitu sebagai solusi. l Program studi enam Fenomena perubahan dalam keluarga dan masyarakat menimbulkan kerentanan psikologis pada individu, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bekerja dan berinteraksi dalam masyarakat, membuat ilmu Psikologi semakin dibutuhkan untuk menangani klien dan memberikan intervensi psikologis. Berbagai kesempatan-kesempatan dari perubahan di masyarakat membuat psikologi menjadi ilmu yang relevan dan dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu kesehatan, pendidikan anak dan remaja, dan manajemen organisasi. l Program studi tujuh Seiring pertumbuhan di sektor industri pariwisata, di wilayah jabodetabek saja sudah terdapat (10) sepuluh lembaga pendidikan setingkat Universitas, Sekolah Tinggi atau Akademi yang menyelenggarakan program studi di bidang pariwisata l Program studi delapan Perkembangan strategi pemerekan (baik perusahaan maupun perorangan) yang semakin kompetitif sehingga keberadaan desain komunikasi visual menjadi salah satu kunci akan kemajuan usaha. Program studi Sembilan Dalam arah perkembangan yang menuju usaha pengurangan pemakaian bahan alam dan usaha lain untuk menjaga lingkungan hidup, keilmuan teknik industri juga dituntut untuk mampu menguasai konsep-konsep produksi ramah lingkungan seperti green manufacturing, green supply chain dan lain sebagainya. l Program studi sepuluh Sebagaimana didefinisikan oleh Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS), dan Association of Information Technology Professionals(AITP), Sistem Informasi sebagai disiplin ilmu akademik mencakup dua area utama yaitu (1) area yang berkaitan dengan upaya pengembangan sistem dan (2) area yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan teknologi informasi. l Program studi sebelas Berdasarkan masukan pengguna alumi bahwa perlu ditingkatkan kemampuan softskill pada mahasiswa. (sumber pengguna Alumni Accenture, 2014) l 2. Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan Panduan Penyusunan Kurikulum wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam berikut ini. [4] l 78 Gambar7. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi, Kemenristek DIKTI (2016) Julia Loisa, Penyusunan Kurikulum Sebagai Salah Satu Implementasi Manajemen... 3. Penentuan Bahan Kajian Bahan kajian adalah komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan. Berikut ini adalah sebagian dari bahan kajian pada 11 (sebelas) program studi di Universitas XYZ adalah: Tabel 1. Penentuan bahan kajian Program Studi Program Studi Satu Program Studi Dua Program Studi Tiga Program Studi Empat Program Studi Lima Program Studi Enam Program Studi Tujuh Bahan Kajian Akuntansi Keuangan; Auditing; Perpajakan; Akuntansi Manajemen Bisnis; Keuangan; SDM; Stratejik; Ritel; Pemasaran Teaching; Translation; Linguistics; Culture; Introduction to Literature; Skills Keterampilan Berbahasa; Linguistik; Budaya; Pengajaran bahasa; Bahasa Tionghoa dalam Bisnis; Penerjemahan Broadcast Production; Broadcast Journalism; Public Relations; Marketing; Communication F&B service; Food Production; Pastry Production; Liquor and Wine; Room Front Office; Housekeeping; Tour; Event Eksplorasi Visual; Kajian Desain; Visual Informasi; Visual Identitas; Visual Persuasi; Pengolahan Kreativitas; Graphic Design; 2D Animation; 3D Animation; Cinematography Program Studi Sembilan Teknik-Teknik Optimasi; Pemodelan Sistem; Teknik Produksi& Manufaktur; Perancangan Teknik Industri Program Studi Sebelas Gambar 8 menunjukkan matriks yang menghubungkan CPL dengan bahan kajian, yang membentuk cikal bakal mata kuliah (R1, R2, dst). Perspektif Psikologi; Biopsikologi; Teori Kepribadian; Perkembangan Manusia; Kesehatan Mental; Psikologi Organisasi; Metode Penelitian; Konseling; Prinsip Pembelajaran; Perubahan Perilaku Program Studi Delapan Program Studi Sepuluh Gambar 8. Matriks capaian pembelajaran dan bahan kajian pada Universitas XYZ Algoritma & Pemrograman; Bisnis & Manajemen; Pengolahan Data; Sistem Enterprise; Rekayasa Perangkat Lunak Ilmu matematika; Algorithm dan pemrograman; Sistem Cerdas; Rekayasa Perangkat Lunak; Komputer Arsitektur; Jaringan Komputer; Kecakapan Hidup 4. Matriks CPL dan Bahan Kajian menghasilkan mata kuliah dan sks Penetapan mata kuliah dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks, yaitu menghubungkan Capaian Pembelajaran Lulusan (horizontal) dengan bidang keilmuwan program studi (vertikal). Gambar 9. Metode penentuan satuan kredit semester pada Universitas XYZ Gambar 9 menunjukkan metode penentuan sks: (1) Isilah materi yang diperlukan untuk bahan kajian/mata kuliah tertentu; (2) Tentukan bobot yang diperlukan untuk materi tersebut; (3) Jumlahkan semua bobot untuk satu bahan kajian/mata kuliah (total bobot bk); (4) Jumlahkan semua bobot untuk seluruh mata kuliah pada program studi tersebut (total bobot prodi); (5) Hitunglah sks: (total bobot bk / total bobot prodi) x total sks prodi; (6) Lakukan pembulatan ke atas atau ke bawah untuk menentukan sks; (7) Jika sks yang diperoleh terlalu besar, maka bahan kajian bisa dipecah lagi menjadi mata kuliah. Setelah melalui tahap di atas, maka hasilnya adalah daftar mata kuliah dengan bobot sks nya. 5. Struktur Kurikulum & Dokumen Kurikulum Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 79 Kalbiscentia,Volume 3 No. 2, Agustus 2016 secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem parallel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik (Panduan penyusunan kurikulum, p18) [4]. Pada tahap akhir ini, program studi menentukan distribusi mata kuliah sesuai pendekatannya. Setelah itu, untuk menghasilkan dokumentasi kurikulum yang ideal sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, semua tahap di atas (tahap 1-6) dirangkaikan menjadi sebuah dokumen sah. C. Pasca Penyusunan Kurikulum Mengacu kembali pada Gambar 3. Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program, pasca penyusunan kurikulum adalah tahapan yang perlu dilakukan untuk menerjemahkan rancangan kurikulum pada proses pembelajaran dan hasilnya (luaran), sehingga kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) Pengkodean mata kuliah; (2) Penyusuan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (3) Evaluasi proses pembelajaran; dan (4 Evaluasi lulusan. Tahap pasca penyusunan kurikulum merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan capture knowledge yang diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan. IV. SIMPULAN 1.Jika Human Resource Management (HRM) adalah tentang mengelola orang secara efektif dan jika sumber daya manusia yang paling berharga adalah pengetahuan, maka HRM dan KM sangat erat kaitannya. Bahkan, HRM dan KM berbagi kegiatan umum dan tujuan yang sama ketika menciptakan unit kerja, tim, kerjasama lintas fungsional, serta proses komunikasi dan jaringan dalam organisasi. 2. Berarti, berbicara mengenai manajemen pengetahuan sangat perlu mengetahui arah pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi, lebih jauh lagi perlu mengetahui kebijakan/arahan stratejik organisasi. 3. Oleh sebab itu, Implementasi knowledge management sangat membutuhkan dukungan dari 80 pimpinan organisasi terutama dalam dua aspek: Membangun/mengubah budaya organisasi dan Penggunaan dukungan teknologi informasi dalam implementasi manajemen pengetahuan. 3. Kurikulum merupakan modal intelektual bagi sebuah perguruan tinggi karena merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4.Jika manajemen pengetahuan dikaitkan dengan Gambar 3. Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program, maka selain penyusunan kurikulum, lembaga pendidikan tinggi perlu membedakan manajemen pengetahuan untuk level proses pembelajaran. 5.Kelebihan penyusunan kurikulum yang dilakukan pada Universitas XYZ adalah integrasi setiap tahap mulai dari pra penyusunan, proses penyusunan, dan pasca penyusunan sehingga mampu menurunkan Visi dan Misi Universitas XYZ ke dalam rancangan kurikulumnya. 6. Kelemahan penyusunan kurikulum yang dilakukan pada Universitas XYZ adalah setiap tahap yang dilakukan membutuhkan pemikiran yang sistematis dan detil, sehingga waktu dan sumber daya manusia yang dirasakan sangat terbatas. V. DAFTAR RUJUKAN [1] K. Rainer, B. Prince, & H. W. R. Reizer. Management Information System: Moving Business Forward, United States: John Wiley & Sons, Inc, 2015, 39. [2] K. Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice, United States: John Wiley & Sons, Inc. 2005, 32 [3] Peraturan Menteri Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . 2015, 5 [4] Kementerian Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Dirjen Pembelajaran, “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi”, 2016 . 5 [5] J. Tian, Y. Nakamori & A. P. Wierzbicki ”Knowledge management and knowledge creation in academia: a study based on surveys in a Japanese research university”, Journal of Knowledge Management, 2009. Vol. 13 Iss 2 . 2009, pp. 76 – 92 [6] I. Svetlik, E. Stavrou-Costea, “Connecting human resources management and knowledge management”, International Journal of Manpower, Vol. 28 Iss 3/4 pp. 2007, 197 – 206