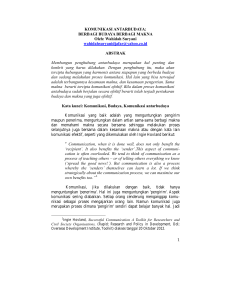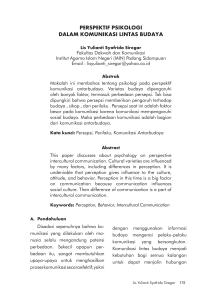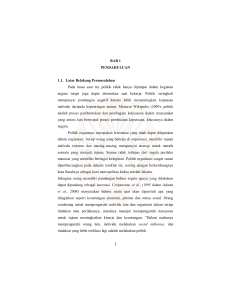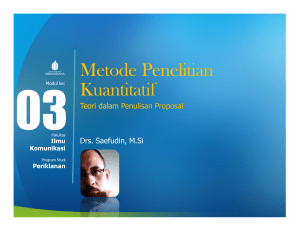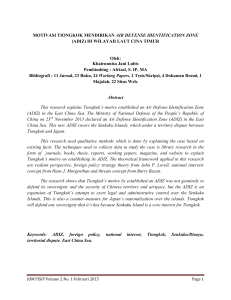2.2. Intercultural Sensitivity
advertisement

1 2 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Budaya Guna menghasilkan pemahaman yang lebih baik selama mengulas intercultural sensitivity, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya serta relevansinya terhadap konsep lintas budaya/intercultural. Tylor (dalam Soares, Farhangmehr, mendefinisikan budaya sebagai kesatuan & Shoham, 2007) yang rumit yang berisi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, kebiasaan dan kemampuan serta kebiasaan lainnya yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat. Sementara Schaefer (2008) mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan ide, nilai, pengetahuan, perilaku dan kebiasaan yang diwariskan secara sosial oleh sekelompok orang. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan umum bahwa budaya adalah suatu fenomena kolektif yang membedakan orang dari satu kelompok atau kategori, dengan orang yang berasal dari kelompok atau kategori lainnya. Budaya adalah suatu konsep yang sangat luas dan berpengaruh terhadap banyak dimensi perilaku manusia. Hal ini menyebabkan penelitianpenelitian seringkali mengalami kesulitan dalam mendefinisikan atau mengoperasionalisasikan batasan budaya. Untuk mengatasi hal ini, Roth (dalam Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007) merangkum beberapa tipologi yang valid untuk digunakan dalam mengoperasionalisasikan budaya. Salah satunya adalah dengan menggunakan afiliasi regional, yaitu menggunakan batas antar negara atau dalam negara untuk membedakan budaya satu dan lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep lintas budaya/intercultural dapat merujuk pada lingkup yang lebih besar yaitu pembedaan budaya berdasarkan negara (contoh: Indonesia, Malaysia, Australia) atau pada lingkup yang lebih kecil yaitu pembedaan antara segmen-segmen budaya lokal dalam satu negara. 2.2. Intercultural Sensitivity Kajian terhadap konsep yang menyerupai intercultural sensitivity tidak hanya dapat dilakukan dengan perspektif ilmu psikologi, melainkan juga dari perspektif disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, komunikasi, hubungan internasional dan sosiologi. Karena itulah dalam penelitianpenelitian ilmiah, lazim ditemukan beragam pengertian dan cara pengkategorian berbeda yang disematkan pada intercultural sensitivity. Secara umum tokoh-tokoh dapat dibagi berdasarkan cara mereka mengkategorikan konsep intercultural sensitivity. Tipe pertama adalah tokoh yang mengkategorikan intercultural sensitivity sebagai salah satu dimensi yang menyusun suatu konsep yang lebih besar. Tokoh yang pandangannya termasuk ke dalam kategori ini antara lain Chen dan Starosta (Kashima, 2006) yang menyatakan bahwa intercultural sensitivity merupakan dimensi afektif dari variabel intercultural communication competence. Juga Cui dan Van den Berg (Panggabean, 2004) yang menyatakan bahwa cultural empathy adalah salah effectiveness. satu dimensi yang menyusun Tipe kedua adalah tokoh variabel intercultural yang menganggap bahwa intercultural sensitivity merupakan suatu variabel tunggal yang sifatnya mandiri dan bukan salah satu dari banyak dimensi yang menyusun sebuah konsep. Tokoh yang pandangannya termasuk ke dalam tipe ini antara lain Bhawuk dan Brislin (1992) serta Bennett (1998, 2004). 2.2.1. Definisi Intercultural Sensitivity Dalam penelitian ini, definisi intercultural sensitivity yang digunakan berasal dari Hammer, Bennett dan Wiseman (2003). Ketiga tokoh ini mendefinisikan intercultural sensitivity secara konseptual sebagai “ability to 3 4 discriminate and experience relevant cultural differences”, atau kemampuan seseorang untuk membedakan serta mengalami adanya perbedaan budaya. Definisi ini berasal dari teori Developmental Model of Intercultural sensitivity (DMIS) yang dikembangkan oleh Bennett (1998, 2004). Teori psikologi yang mendasari perkembangan DMIS adalah teori personal construct George Kelly (Bennett, 2004). Teori personal construct menjelaskan bahwa pengalaman seseorang adalah fungsi dari kategori mental yang digunakannya untuk menafsirkan suatu kejadian. Artinya, apabila secara kognitif seseorang tidak memiliki kategori mental yang tepat untuk menafsirkan suatu kejadian, maka ia dapat dikatakan tidak mengalami kejadian tersebut. Dengan kata lain, eksistensi sebuah fenomena bergantung pada kemampuan seseorang untuk membedakan fenomena tersebut dengan fenomena-fenomena serupa lainnya (Feist & Feist, 2009). Prinsip kegunaan kategori mental dalam teori personal construct Kelly diaplikasikan oleh Bennett untuk menjelaskan konsep intercultural sensitivity dalam ruang lingkup interaksi lintas budaya. Menurut Bennett (2004), persepsi yang berbeda terhadap tiap budaya hanya dapat dihasilkan apabila seseorang memiliki kategori mental yang tepat untuk mengkategorikan masing-masing budaya tersebut. Semakin kompleks kategori mental yang dimiliki seseorang, maka semakin mampu juga orang tersebut untuk membedakan dan merasakan perbedaan budaya. Dengan kata lain, kualitas intercultural sensitivity seseorang ditentukan oleh seberapa kompleks kategori mental miliknya yang berkenaan dengan pengkategorisasian berbagai budaya lain (Bennett, 1998, 2004; Bennett & Bennett, 2001). 2.2.2. Tahap Perkembangan Intercultural Sensitivity Intercultural sensitivity adalah suatu orientasi terhadap perbedaan budaya, yang dapat berkembang melalui proses pembelajaran. Menurut teori Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) yang dikemukakan oleh Bennett (2004), perkembangan orientasi intercultural sensitivity seseorang akan berlangsung dengan mengikuti enam rangkaian tahapan yang sifatnya kontinu dan gradual. Enam tahap perkembangan intercultural 5 sensitivity mulai dari tahap terendah hingga tertinggi dapat dilihat dalam gambar 2.1. DMIS telah digunakan dalam berbagai penelitian sebagai dasar untuk mengukur sejauh mana tahap perkembangan intercultural sensitivity seseorang (Hammer dkk, 2003; Holm, Nokelainen & Tirri, 2009; Patterson, 2006; Romano, Cummings, Coraggio & Kromrey, 2007). Sumber : www.intercultural.org Gambar 2.1. Tahap Perkembangan Intercultural Sensitivity Menurut Bennett (2004), pada hakikatnya perkembangan orientasi intercultural sensitivity setiap orang akan dimulai dari tahap pertama, yaitu Denial. Tahap Denial ditandai dengan penolakan dan pengabaian seseorang terhadap perbedaan budaya, serta adanya anggapan bahwa budaya yang melekat di diri sendiri merupakan satu-satunya budaya yang benar di dunia. Namun kondisi ini tidak bersifat menetap. Sifat intercultural sensitivity yang dapat berkembang membuat semua orang memiliki potensi untuk naik ke tahap-tahap selanjutnya hingga mencapai tahap akhir yaitu Adaptation atau Integration. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahap perkembangan intercultural sensitivity menurut teori DMIS yang dikemukakan oleh Bennett (2004). 6 1. Tahap Denial Dalam bukunya, Bennett (2004:63-64) menjelaskan bahwa Denial adalah: “The state in which one’s own culture is experienced as the only real one-that is, the patterns of beliefs, behaviors, and values that constitute a culture are experienced as unquestionably real or true. Other cultures are either not noticed at all, or they are construed in rather vague ways. People with a Denial worldview generally are disinterested in cultural difference even when it is brought to their attention, although they may act aggresively to avoid or eliminate a difference if it impinges on them. Another way a Denial worldview shows up is as an inability(and disinterest) in differentiating national cultures” Berdasarkan pemaparan Bennett (2004), tahap Denial adalah tahap dimana terdapat anggapan bahwa budaya yang melekat pada diri seseorang merupakan satu-satunya budaya di dunia dengan pola kepercayaan, perilaku dan nilai-nilai yang nyata adanya. Budaya yang berbeda tidak diakui eksistensinya, atau ditafsirkan dengan cara yang samar-samar. Contohnya, mengkategorikan semua orang dari budaya lain sebagai “orang asing”. Secara umum, orang-orang yang berada pada tahap Denial tidak tertarik pada fakta bahwa terdapat perbedaan budaya karena mereka tidak mengakui eksistensi budaya lain. Karakteristik lain dari tahap Denial adalah ketidakmampuan dan ketidaktertarikan seseorang untuk membedakan budaya nasional berbagai negara. Contohnya adalah orang Amerika Serikat yang tidak mampu dan tidak tertarik untuk membedakan mana orang yang berasal dari Jepang dan China. Hal ini terjadi karena budaya yang berbeda dari diri seseorang, ditafsirkan semata-mata sebagai “orang asing” atau “budaya asing”. 7 Dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004), peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Denial: Keyakinan bahwa pola kepercayaan dan nilai budayanya merupakan satu-satunya pola kepercayaan yang benar dan nyata di dunia Keyakinan bahwa pola perilaku budayanya merupakan satu-satunya pola perilaku yang benar dan nyata di dunia Tidak tertarik pada fakta bahwa terdapat perbedaan budaya Tidak mampu dan tidak tertarik untuk membedakan budaya nasional berbagai negara 2. Tahap Defense Menurut penjelasan Bennett (2004:65), tahap kedua dalam perkembangan intercultural sensitivity yaitu Defense merupakan: “The state in which one’s own culture (or an adopted culture) is experienced as the only viable one- the most “evolved” form of civilization, or at least the only good way to live. People at Defense have become more adept at discriminating difference, but the Defense worlview structure is not sufficiently complex to generate an equally “human” experience of the other. People at Defense are more openly threatened by cultural differences than are people in a state of Denial. The world is organized into “us and them”, where one’s own culture is superior and other cultures are inferior.This Defense experience is accompanied by positive stereotyping of one’s own culture and negative stereotyping of other culture.” Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada tahap Defense, ada anggapan bahwa budaya yang melekat pada diri seseorang merupakan satu-satunya budaya yang paling maju dan paling baik di dunia. Anggapan ini mengindikasikan bahwa pada tahap Defense seseorang sudah mengakui bahwa keragaman budaya adalah sesuatu yang nyata dan ada di dunia, namun dianggap sebagai sesuatu yang negatif. 8 Karena pada tahap Defense seseorang telah mengakui adanya perbedaan budaya, mereka juga secara terbuka menunjukkan adanya perasaan terancam yang disebabkan oleh keberadaan budaya lain. Bagi orang-orang di tahap Defense, dunia dapat dibagi menjadi “kami” dan “mereka”. “Kami” ditujukan bagi orang-orang yang berasal dari budaya yang sama dengan dirinya, yang dianggap superior dan diidentikkan dengan stereotype positif. Sementara “mereka” ditujukan bagi semua orang yang berasal dari budaya lain, yang dianggap inferior dan diidentikkan dengan stereotype negatif. Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004) peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Defense: Keyakinan yang dipertahankan bahwa budaya miliknya merupakan budaya yang paling maju di seluruh dunia Adanya perasaan terancam karena keberadaan budaya lain Anggapan bahwa budaya miliknya lebih superior daripada budaya lain Mengasosiasikan budaya lain dengan stereotype yang bersifat negatif 3. Tahap Minimization Dalam bukunya, Bennett (2004:66) menyatakan bahwa Minimization adalah tahap dimana: “In Minimization, the threat associated with cultural differences experienced in Defense is neutralized by subsuming the differences into familiar categories. For instance, cultural differences may be subordinated to the overwhelming similarity of people biological nature (physical universalism). The experience of similarity of natural physical processes may then be generalized to other assumedly natural phenomena such as needs and motivations. The experience of similarity might also be experienced in the assumed cross-cultural applicability of certain 9 religious, economic or philosophical concepts (transcedent universalism). People at Minimization expect similarities, and they may become inistent about correcting others’ behavior to match their expectations.” Berbeda dengan Defense, orang yang berada pada tahap Minimization tidak lagi merasa terancam pada kenyataan adanya perbedaan budaya. Hal ini terjadi karena mereka menggunakan kategorikategori yang lebih familiar untuk menjelaskan tentang kesamaan antara budaya satu dan lainnya. Mereka memiliki keyakinan tentang adanya physical universalism dan transcendent universalism yang berlaku bagi semua orang dari semua budaya. Physical universalism adalah adanya kesamaan dari segi jasmaniah yang berlaku secara universal. Sementara transcendent universalism adalah adanya kesamaan konsep abstrak (agama, ekonomi,filosofi) yang berlaku secara universal. Pada tahap Minimization, seseorang mengharapkan terciptanya kesamaan antar budaya satu dan lainnya. Harapan inilah yang kerapkali membuat orang yang berada di tahap Minimization berusaha untuk mengubah perilaku orang dari budaya lain agar sesuai dengan ekspektasi yang mereka miliki. Berdasarkan pemaparan Bennett (2004), dapat disimpulkan beberapa indikator dari tahap Minimization: Minimisasi perbedaan budaya karena meyakini adanya kesamaan jasmaniah semua manusia (physical universalism). Minimisasi perbedaan budaya karena meyakini adanya konsep abstrak yang berlaku secara universal (transcedent universalism). Berusaha untuk mengubah perilaku orang lain agar sesuai dengan ekspektasi dari budayanya 4. Tahap Acceptance 10 Tahap keempat dalam kontinum perkembangan intercultural sensitivity adalah Acceptance. Bennett (2004:68-69) menjelaskan: “Acceptance of cultural difference is the state in which one’s own culture is experienced as just one of a number of equally complex worldviews. People with this worldview are able to experience others as different from themselves, but equally human. They are adept at identifying how cultural differences in general operate in a wide range of human interactions” Pada tahap Acceptance, budaya yang melekat pada diri seseorang dianggap sebagai satu dari berbagai kemungkinan pandangan terhadap dunia (yang berasal dari berbagai budaya lain) yang sama kompleksnya. Mereka menerima dan mengapresiasi unsur-unsur dari budaya lain. Orang-orang yang berada pada tahap ini menerima kenyataan bahwa orang yang berasal dari budaya lain memiliki nilai dan pola perilaku yang berbeda namun tetap sederajat dengan mereka sebagai manusia. Mereka juga mahir dalam mengidentifikasi bagaimana implikasi yang ditimbulkan perbedaan budaya dalam berbagai interaksi manusia. Perlu diingat bahwa pada tahap Acceptance, penerimaan seseorang terhadap perbedaan budaya tidak selalu berarti persetujuan. Bennett (2004:69) mengatakan bahwa, “Acceptance does not mean agreement”. Seseorang pada tahap Acceptance bisa saja menerima, namun tidak setuju terhadap aspek-aspek tertentu dari budaya lain. Penilaian-penilaian yang dilakukan seseorang pada tahap ini menjadi tidak bersifat ethnocentric karena tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan dari budaya lain. Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004), peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Acceptance: Menganggap bahwa budayanya merupakan satu dari berbagai kemungkinan pandangan terhadap dunia yang sama kompleksnya Menganggap orang dari budaya lain sebagai berbeda namun setara dengan mereka sebagai manusia 11 Mampu mengidentifikasi bagaimana perbedaan budaya beroperasi dalam berbagai interaksi manusia 5. Tahap Adaptation Tahap kelima yang disebut juga sebagai Adaptation to cultural difference dijelaskan Bennett (2004:70) sebagai: “The state in which the experience of another culture yields perception and behavior appropriate to that culture. One’s worldview is expanded to include relevant constructs from other cultural worldviews. People at Adaptation can engage in empathy-the ability to take perspective or shift frame of referenve vis-a-vis other culture. They are able to express their alternative cultural experience in a culturally appropriate feelings and behaviors.”. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap Adaptation, persepsi yang dibuat serta perilaku yang dimunculkan seseorang sudah sesuai dengan konteks budaya lain. Cara pandangnya terhadap dunia juga menjadi lebih luas karena telah mencangkup cara pandang yang berasal dari budaya lain. Karakteristik lain dari tahap Adaptation adalah kemampuan empati. Seseorang pada tahap ini akan mampu melihat suatu hal dengan menggunakan perspektif budaya lain. Kemampuan empati terhadap budaya lain ini tidak hanya menghasilkan perubahan secara kognitif (yaitu kemampuan “perspective taking”) namun juga perubahan dari segi afektif dan perilaku. Mereka mampu memberikan respon berupa perasaan atau perilaku yang sesuai dengan konteks tiap budaya yang berbeda. Yang terjadi dalam tahap Adaptation berbeda dengan apa yang disebut sebagai asimilasi budaya. Dalam asimilasi, seseorang harus melepaskan identitas budaya aslinya untuk kemudian mengadaptasi nilainilai budaya baru ke dalam kehidupannya. Sementara dalam tahap 12 Adaptation, seseorang tidak menggantikan nilai-nilai dan cara hidup dari budaya aslinya dengan budaya lain, melainkan ia memperluas sistem nilai dan kepercayaannya dengan menambahkan aspek-aspek dari budaya lain. Perluasan sistem nilai dan kepercayaan pada tahap Adaptation membuat seseorang dapat membangun hubungan yang efektif dalam berbagai konteks budaya berbeda. Sehingga dengan mengacu pada pemaparan Bennett (2004) peneliti menyimpulkan beberapa indikator dari tahap Adaptation: Mampu mempersepsikan sesuatu sesuai dengan konteks budaya lain Mampu berperilaku sesuai dengan konteks budaya lain Mampu berempati, yaitu melihat suatu hal dari perspektif budaya lain (“perspective taking”) 6. Tahap Integration Tahap terakhir dalam perkembangan intercultural sensitivity yaitu Integration, dijelaskan Bennett (2004:72) sebagai: “The state in which one’s experience of self is expanded to include the movement in and out of different cultural worldviews. People are dealing with issues related to their own “cultural marginality”; they construe their identities at the margins of two or more cultures and central to none.” Integration adalah tahap dimana pengalaman seseorang atas dirinya sendiri diperluas sehingga mencangkup pergerakan keluar dan masuk dari budaya yang berbeda-beda. Bennett (2004) menjelaskan bahwa, “Movement to the last stage does not represent a significant improvement in intercultural competence. Rather, it describe a fundamental shift in one’s definition of cultural sensitivity”. Artinya, perpindahan seseorang dari Adaptation ke Integration tidak merepresentasikan adanya peningkatan yang signifikan pada kualitas intercultural sensitivity orang tersebut. 13 Alasan adanya tahap Integration dalam teori DMIS dijelaskan Bennett (2004) karena “It is descriptive of a growing number of people, including many members of non-dominant cultures, long-term expatriates, and “global nomads”. Tahap Integration dimasukkan ke dalam teori DMIS karena merepresentasikan banyaknya fenomena serupa yang terjadi di dunia, dimana seseorang merasa memiliki identitas budaya yang bersifat “global”. Karena tidak ada perbedaan fundamental antara Acceptance dan Integration maka dalam berbagai pengukuran intercultural sensitivity berdasarkan teori DMIS, Integration tidak dimasukkan ke dalam skala pengukuran (Hammer dkk, 2003; Holm, 2009). Guna merangkum tahap perkembangan intercultural sensitivity yang telah dideskripsikan di atas, Bennett (1998, 2004) menyatakan bahwa pada tahap-tahap yang lebih rendah seperti Denial, Defense/Reversal dan Minimization, persepsi serta penilaian seseorang terhadap budaya lain masih bersifat ethnocentric, yaitu dilakukan dengan berorientasi pada budaya yang melekat di dirinya sendiri. Sementara persepsi dan penilaian pada tahaptahap yang lebih tinggi, seperti Acceptance, Adaptation dan Integration, secara umum sudah bersifat ethnorelative, dimana seseorang merasa nyaman dengan standar dari berbagai budaya sehingga ia mampu menyesuaikan penilaian dan perilakunya agar sesuai dengan konteks budaya lain (Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003). Bennett (1998, 2004) juga menekankan bahwa DMIS tidak hanya sekedar deskripsi dari kognisi, afek atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan perbedaan budaya. DMIS adalah suatu kerangka teori yang menjelaskan bahwa perubahan cara pandang seseorang terhadap perbedaan budaya yang bergerak dari tahap ethnocentric ke tahap ethnorelative, akan menghasilkan perkembangan orientasi intercultural sensitivity. Perubahan pada aspek kognisi, afek dan perilaku di tiap tahap DMIS adalah hasil manifestasi dari perkembangan orientasi intercultural sensitivity yang dialami orang tersebut. 14 2.2.3. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Intercultural Sensitivity Pada hakikatnya semua manusia di dunia awalnya lahir dan disosialisasikan menjadi orang-orang ethnocentric yang mengutamakan praktik-praktik budayanya sendiri di atas budaya lainnya (Triandis dalam Bhawuk, Sakuda, Munusamy, 2008). Dalam bukunya, Bennett (2004) menjelaskan bahwa pandangan yang bersifat ethnocentric merupakan kondisi “default” atau bawaan pada semua manusia yang ada di dunia. Artinya, apabila ditinjau dari tahapan perkembangan intercultural sensitivity Bennett (2004), semua manusia pada dasarnya memiliki karakteristik yang ada pada tahap-tahap awal seperti Denial, Defense dan Minimization. Namun sejalan dengan proses pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan seseorang, orientasi intercultural sensitivity dapat berubah dan berkembang ke tahaptahap akhir yang bersifat ethnorelative, yaitu Acceptance, Adaptation dan Integration. Karena intercultural sensitivity merupakan sesuatu yang tidak bersifat statis melainkan dinamis dan dapat dikembangkan, maka berbagai penelitian berusaha melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang diprediksi berpengaruh atau sekurang-kurangnya berhubungan dengan perkembangan intercultural sensitivity. Berikut adalah beberapa faktor yang ditemukan berpengaruh atau berhubungan dengan intercultural sensitivity: 1. Studi di luar negeri Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah kaitan antara studi di luar negeri terhadap intercultural sensitivity. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai arah hubungan antara studi di luar negeri dan peningkatan intercultural sensitivity. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang ditimbulkan studi di luar negeri terhadap kualitas intercultural sensitivity seorang mahasiswa. Penelitian komparatif yang dilakukan Williams (2005) menunjukkan bahwa mahasiswa yang melanjutkan studi di luar negeri memiliki intercultural sensitivity yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang melanjutkan studi di dalam 15 negeri. Penelitian lain yang bersifat longitudinal dilakukan oleh Anderson dkk (2006) dimana ditemukan bahwa program studi ke luar negeri, meskipun hanya selama 1 bulan, sudah menunjukkan memiliki dampak positif terhadap peningkatan intercultural sensitivity mahasiswa. Penelitian lainnya oleh Straffon (2003) menunjukkan bahwa semakin lama waktu studi di luar negeri yang dihabiskan mahasiswa, maka semakin tinggi juga levelnya dalam tahapan DMIS. Ketiga hasil penelitian di atas mendukung pernyataan Bennett (2004) bahwa menempuh studi di luar negeri yang membuat mahasiswa terlibat dalam kontak terus menerus dengan budaya asing, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada intercultural sensitivity mahasiswa tersebut. Hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian lain yang dilakukan oleh McMurray (2007). Hasil penelitian McMurray menunjukkan bahwa mahasiswa yang pernah ikut dalam program studi ke luar negeri tidak memiliki intercultural sensitivity yang secara signifikan lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti program serupa. Menurut McMurray (2007), hal ini dapat terjadi apabila pengalaman studi ke luar negeri mahasiswa terjadi bertahun-tahun sebelum pengukuran intercultural sensitivity dilakukan. Rentang waktu yang lama antara pengalaman studi ke luar negeri dan pengukuran intercultural sensitivity membuat hasil penelitian tidak dapat menemukan perbedaan yang signifikan antara intercultural sensitivity mahasiswa yang pernah menjalani studi di luar negeri dan yang belum pernah. 2. Pendidikan tentang keragaman budaya Penelitian yang dilakukan oleh Margarethe, Hannes dan Wiesinger (2012) serta Bradshaw dan Biggs (2007) menunjukkan bahwa mahasiswa yang menempuh program studi dengan pendidikan tentang keragaman budaya sebagai salah satu mata kuliahnya, memiliki intercultural sensitivity yang lebih tinggi daripada daripada mahasiswa yang tidak 16 mendapatkan pendidikan serupa dari universitas tempatnya menjalani studi. Pendidikan tentang keragaman budaya yang dimaksud dalam penelitian Margarethe dkk adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang mengapa perbedaan budaya dapat terjadi (why question) dan bagaimana cara menyikapi perbedaan budaya tersebut (how question). 3. Pengalaman pergi ke luar negeri Penelitian oleh Baños (2006) menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara intercultural sensitivity siswa yang pernah tinggal di luar negeri dan siswa yang tidak pernah. Intercultural sensitivity secara signifikan lebih tinggi pada mereka yang memiliki pengalaman menetap di luar negeri dalam jangka waktu apapun. Penelitian lain dari McMurray (2007) juga menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki pengalaman wisata ke luar negeri akan memiliki intercultural sensitivity yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki pengalaman serupa. Kedua hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pengalaman wisata ke luar negeri dan tingkat intercultural sensitivity seseorang. 4. Jenis kelamin Ada tidaknya hubungan antara jenis kelamin dan tingkat intercultural sensitivity seseorang bervariasi dari beberapa hasil penelitian. Penelitian Margarethe dkk (2012) menemukan bahwa wanita dan pria tidak memiliki perbedaan intercultural sensitivity yang signifikan secara statistik. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh McMurray (2007) serta Holm dkk (2009), dimana dalam dua penelitian terpisah yang mereka lakukan, ditemukan bahwa rata-rata tingkat intercultural sensitivity wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Kedua penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan ini dapat terjadi karena wanita secara alamiah memiliki kemampuan empati yang lebih baik 17 daripada pria. Kemampuan empati membuat wanita dapat beradaptasi dalam lingkungan lintas budaya dengan lebih baik daripada pria. 2.3. Mahasiswa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (kbbi.web.id), mahasiswa diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Rentang usia mahasiswa di Indonesia umumnya 18-22 tahun, sehingga secara perkembangan dapat dikategorikan masuk ke masa transisi dari remaja ke dewasa awal (Papalia, Feldman, & Martorell, 2013). Meskipun usia kronologis tidak selalu dapat dijadikan acuan untuk mengkategorikan tahap perkembangan seseorang, namun beberapa penelitian mendukung bahwa mahasiswa usia 18-25 tahun ada pada periode transisi dari tahap remaja ke dewasa awal, atau disebut sebagai emerging adulthood (Arnett & Scheer dalam Santrock, 2008). 18 2.4. Kerangka Berpikir Penelitian ASEAN Economic Community 2015 Pergerakan bebas tenaga kerja asing ke dalam Indonesia Kebutuhan agar mahasiswa membekali diri dengan intercultural sensitivity, kompetensi yang memfasilitasi peningkatan kinerja seseorang dalam lingkungan kerja lintas budaya berbagai negara Pemetaan intercultural sensitivity pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Bina Nusantara dan universitas swasta lain di Jakarta dengan menggunakan teori DMIS Bennett (2004) Sumber : Olahan peneliti Gambar 2.2.Kerangka Berpikir Penelitian Gambar 2.2. menunjukkan kerangka berpikir peneliti yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini. Ide penelitian ini awalnya muncul sebagai reaksi terhadap adanya program ASEAN Economic Community (AEC) yang akan diberlakukan sejak 2015 di kawasan Asia Tenggara. AEC bertujuan untuk mengubah Asia Tenggara menjadi kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya (ASEAN Secretariat, 2008). Guna merealisasikan hal tersebut, AEC membuat kebijakan-kebijakan yang secara umum disebut sebagai free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, dan free 19 flow of skilled labor. Artinya, akan ada aliran bebas barang, jasa, investasi, aliran modal dan tenaga kerja terampil antar negara-negara anggota ASEAN. Salah satu kebijakan AEC, yaitu free flow of skilled labor, diprediksikan banyak pihak termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Wamenkeu Anny Ratnawati (Izzudin, 2013; Maesaroh, 2013) akan membuat perusahan-perusahaan di Indonesia kedatangan banyak tenaga kerja asing. Hal ini akan mengakibatkan perubahan komposisi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga muncul kebutuhan agar masyarakat Indonesia membekali diri dengan kompetensi yang memfasilitasi kesuksesan kinerja dalam tim lintas budaya asing. Kompetensi yang ditemukan berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang yang bekerja dalam lingkungan kerja lintas budaya adalah intercultural sensitivity. Definisi konseptual dari intercultural sensitivity menurut Hammer, Bennett dan Wiseman (2003) adalah kemampuan seseorang untuk membedakan serta mengalami adanya perbedaan budaya. Definisi ini merupakan bagian dari teori perkembangan intercultural sensitivity milik Bennett (1998, 2004) yang dinamakan sebagai Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS). Teori DMIS hingga sekarang digunakan dalam banyak penelitian sebagai dasar pengoperasionalisasian intercultural sensitivity. Pengukuran intercultural sensitivity cukup banyak dilakukan dalam berbagai penelitian di luar Indonesia. Namun sebaliknya, hingga sekarang minim penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kompetensi lintas budaya masyarakat Indonesia terhadap budaya asing (Panggabean, 2004). Padahal tidak sedikit timbul kesalahpahaman dan konflik dalam tataran kehidupan bermasyarakat akibat perbedaan keyakinan atau nilai-nilai yang dianut antara budaya Indonesia dan budaya asing. Inilah mengapa muncul kebutuhan untuk mengukur intercultural sensitivity masyarakat Indonesia terhadap budaya asing, sebagai bentuk persiapan untuk menyambut berlakunya AEC 2015. Kebutuhan untuk mengembangkan intercultural sensitivity khususnya berlaku bagi mahasiswa jenjang S1 yang akan masuk ke dunia 20 kerja dalam waktu dekat. Kebutuhan ini didukung temuan dari penelitian Shaftel, Shaftel dan Ahluwalia (2007) yang menemukan bahwa mahasiswa program S1 yang memiliki intercultural competence akan lebih sukses di dunia kerja bahkan lebih dihargai dan diminati oleh perusahaan-perusahaan daripada mahasiswa yang tidak mengembangkan intercultural competence. Fenomena yang telah dipaparkan di atas memunculkan kebutuhan agar peneliti melakukan kajian tentang gambaran intercultural sensitivity pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Bina Nusantara dan universitas swasta lain di Jakarta.