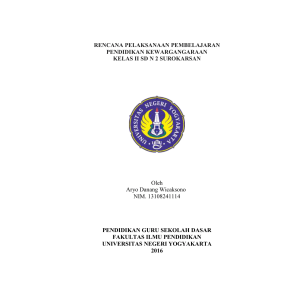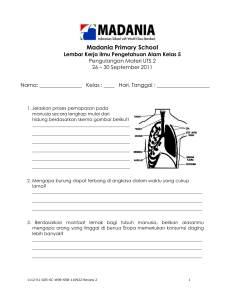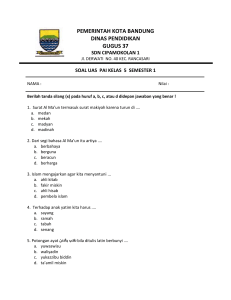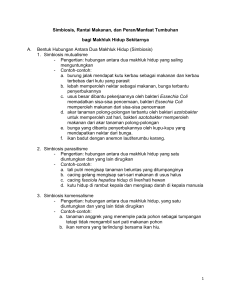Dinamika dan Konfigurasi Kepentingan di Balik
advertisement

BAB II Tinjuan Teoritis 2. 1 Pemaknaan Burung di Masyarakat Pemaknaan terhadap burung mencakup beberapa dimensi yang beragam, antara lain dimensi ekonomi, dimensi ekologis, dimensi sosio-kultural, dan dimensi estetika. Secara ekonomi, burung dimaknai sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan seperti halnya barang-barang produksi. Nilai ekonomi burung dalam konteks ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, nilai ekonomi burung untuk kepentingan perdagangan bagi komunitas penggemar burung. Hobi memelihara burung menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Temuan Jepson dan Ladle menunjukkan bahwa satu dari lima rumahtangga di lima kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Surabaya, Semarang, Bandung dan Jakarta memilih memelihara burung sebagai satwa peliharaan. Kuantitas pemeliharaan burung sebagai satwa peliharaan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa satwa peliharaan lainnya seperti ikan, anjing, kucing dan kuda (Jepson and Ladle, 2005). Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin maraknya kegiatankegiatan yang memiliki daya tarik bagi para komunitas penggemar burung dan semakin tingginya harga jual burung di pasaran. Beberapa jenis burung yang banyak diperdagangkan untuk kepentingan hobi antara lain murray batu, anis merah, anis kembang, cucak rawa, cucak hijau, cendet dan kenari. Murrai Batu misalnya merupakan jenis burung yang paling banyak digemari oleh komunitas penggemar burung meskipun keberadaannya di alam semakin terancam1. Kedua, nilai ekonomi burung dari pemanfaatan burung untuk kepentingan bahan makanan. Pemanfaatan burung untuk kepentingan dijual dagingnya sebagai bahan makanan paling mudah ditemukan di masyarakat. Jenis burung yang biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan ini adalah burung dara (merpati), beberapa jenis burung laut (pelikan), selain jenis dari unggas (Mackinnon, 1984; 1 Bagian ini didapatkan dari keterangan salah seorang aktivis NGO’s yang konsern pada pelestarian burung di Indonesia (Birdlife Indonesia atau sekarang menjadi Burung Indonesia) pada salah satu media massa yaitu Harian Kompas, Minggu, Tanggal 19 Februari 2006. www.kompas.com. Diakses pada Tanggal 3 November 2007 Alikondra, 1993). Burung yang dimanfaatkan untuk bahan makanan bisa didapatkan dari kegiatan peternakan burung atau melalui kegiatan penangkapan di alam. Kegiatan penangkapan langsung di alam merupakan hal yang paling banyak ditemukan dalam rangka pemanfaatan daging burung untuk kepentingan bahan makanan. Burung juga memiliki peran secara ekologis. Pada masyarakat tertentu peran ekologis burung berada pada posisi yang penting. Di Indonesia, peranan burung secara ekologis dapat dilihat pada pemanfaatan burung sebagai “musuh alami” dari beberapa jenis hama tertentu di sawah. Burung elang misalnya adalah predator alami terhadap jenis hama tikus dan ular di sawah. Beberapa jenis burung lainnya yang memiliki peran ekologis sebagai “musuh alami” di sawah adalah Cangak, Mandar, Sri Gunting, Bentet dan Sikatan. Burung-burung tersebut berperan sebagai musuh alami bagi serangga. Di beberapa Negara maju, keberadaan burung dimanfaatkan sebagai biomonitoring terhadap perubahan lingkungan. Burung dalam konteks ini dilihat keberadaanya untuk mengetahui apakah lingkungan tersebut mengalami perubahan kualitas atau tidak. Di Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan Inggris misalnya burung dimanfaatkan untuk bio-monitoring terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Jika burung tertentu menghilang dari habitat alaminya yang biasa dipergunakan untuk kehidupan seharinya-harinya, maka dapat disimpulkan terjadi perubahan pada lingkungan tersebut, yang biasanya adalah pencemaran lingkungan (Furness and Greenwood, 1993). Sementara itu, secara sosio-kultural pemaknaan terhadap burung dapat ditelaah dari keberadaan burung sebagai bagian dari entitas kultural masyarakat. Di Indonesia, bagi sebagian etnis burung memiliki keterkaitan dengan entitas kultural. Pada komunitas Dayak Laut misalnya, burung memiliki dimensi magis dalam tradisi kultural mereka. Beberapa jenis burung tertentu dianggap sebagai bagian dari simbol ritual religius mereka. Mereka memaknai beberapa jenis burung yaitu Raja Udang, Trogon, Jay dan Pelatuk sebagai representasi dari para menantu dewa-dewa yang mereka sembah. Keberadaan bebera jenis burung tersebut sangat dijaga dan dilestarikan oleh komunitas tersebut. Di sisi lain, komunitas Dayak Laut juga meyakini bahwa jenis burung yang disebutkan sebelumnya memberikan simbol-simbol tertentu bagi kepentingan kehidupan mereka. Salah satunya adalah komunitas Dayak Laut mempercayai bahwa kegiatan pembukaan hutan tidak dapat dilakukan jika mendengar suara burung tertentu. Hal ini dilakukan karena suara burung tersebut memberikan pertanda bagi keselamatan mereka (Welty, 1979). Demikian juga yang berkembang pada sebagian masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa yang memiliki tradisi kultural keraton yang masih kuat, burung dijadikan sebagai simbol status sosial, simbol ketenangan dan keindahan serta simbol kesempurnaan dalam hidup. Bagi masyarakat Jawa hidup menjadi sempurna jika seseorang telah memiliki harta (simbol kekayaan), tahta (simbol kekuasaan), wanita (simbol pasangan hidup), turangga (simbol dari kendaraan atau tunggangan) dan kukila (simbol dari satwa peliharaan)2. Burung dalam konteks ini adalah bagian dari simbolisasi kukila. Dengan memiliki satwa peliharaan maka kesempurnaan hidup seseorang menjadi lengkap setelah memiliki empat hal lain yang disebutkan sebelumnya. Pemaknaan terhadap kesempurnaan hidup ini lebih banyak dilekatkan dengan kalangan priyayi atau bangsawan keraton karena memang aspek-aspek yang menjadi prasyarat kesempuranaan hidup lebih mungkin dicapai oleh kalangan masyarakat dari kelas priyayi atau bangsawan. Sedangkan bagi kaum masyarakat kebanyakan, mereka lebih banyak disibukkan dengan urusan pemenuhan harta sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menyempurnakan aspek-aspek lainnya dalam mencapai kesempuranaan. Namun demikian, dalam perkembangannya dimensi sosio-kultural dari burung berkembang tidak hanya berkaitan dengan filosofi kesempurnaan hidup pada masyarakat Jawa. Saat ini perkembangan pemeliharaan burung melibatkan hampir sebagian lapisan masyarakat, baik dari kalangan kelas atas, menengah, dan bawah, termasuk juga kalangan non priyayi atau bangsawan. Pemaknaan terhadap dimensi sosio-kultural burung pun berkembang tidak pada konteks sebagai simbolisasi status sosial akan tetapi lebih pada hobi untuk mendapatkan kepuasan 2 Kukila merupakan simbolisasi dari satwa peliharaan, namun demikian dalam banyak hal pemaknaan terhadap kukila dilekatkan dengan burung sebagai satwa peliharaan. Jenis burung yang banyak dimaknai sebagai simbol kesempurnaan hidup adalah perkutut yang memang popular dikalangan masyarakat Jawa (Muchtar dan Nurwatha, 2001). psikologis dengan mendengarkan dan menikmati keindahan suara, warna dan gerak gerik burung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Jepson dan Ladle, yang menemukan bahwa kegemaran memelihara burung saat ini dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat di kota, mulai dari tingkat pendidikan rendah hingga tingkat pendidikan tinggi. Hobi memelihara burung menjadi pilihan paling digemari dibandingkan dengan memelihara jenis satwa lainnya (Jepson and Ladle, 2005). Dimensi lain berkaitan dengan peran burung adalah dimensi estetika, yaitu menjadikan burung sebagai simbol dari kreativitas karya seni tertentu. Di kalangan seniman Bali, nilai estetika dari burung cukup besar dalam menginspirasi para seniman dalam menghasilkan karya. Burung menjadi salah satu inspirasi untuk menggambarkan tentang keindahan. Terdapat sejumlah komunitas seniman di Bali yang selalu menjadikan burung sebagai sumber inspirasi pada setiap hasil karya seni lukisnya. Pemaknaan seperti ini tidak hanya memberikan dampak psikologis berupa kepuasan bagi para seniman tersebut, akan tetapi juga menjadi media komunikasi non-verbal untuk menjaga dan melestarikan keberadaan burung (Surata, 1993). 2. 2 Masyarakat Jawa: Genealogi Sistem Kultural Masyarakat Jawa Genealogi sistem kultural masyarakat Jawa berkembang sejak masa zaman pra sejarah hingga konteks kekinian. Namun demikian, kajian mengenai sistem kultural masyarakat Jawa mulai marak dilakukan sejak berkembangnya sistem kerajaan di Jawa. Sistem kerajaan yang berkembang awal di Jawa adalah kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruh sistem nilai Hindhu dan Budha. Pada masa ini Jawa dapat dikelompokkan menjadi dua tipologi kerajaan, yaitu kerajaan yang berkembang di daerah pesisir dan menjadi pusat kegiatan ekonomi perdagangan dan kerajaan di pedalaman. Kedua kerajaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam sistem kulturalnya. Kerajaan yang berkembang di daerah pesisir pada umumnya adalah daerah perdagangan dengan basis jalur transportasi laut. Kerajaan pesisir biasanya memiliki pelabuhan laut yang dimanfaatkan untuk jalur transportasi perdagangan. Di kerajaan pesisir pada umumnya tidak memiliki daerah pedesaan yang luas dan penduduk petani yang jumlahnya besar. Salah satu contoh kerajaan yang termasuk dalam tipologi kerajaan di daerah pesisir adalah kerajaan Sriwijaya (Koentjaraningrat, 1994). Sementara itu, untuk kerajaan yang berkembang di daerah pedalaman terdapat di daerah yang relatif subur. Kerajaan ini biasanya didasarkan atas sektor pertanian, dengan penduduk petani yang jumlahnya relatif besar. Mereka hidup di desa-desa sekita kerajaan dengan menjadikan sektor pertanian sebagai sistem pola nafkah utama dalam rumahtangga. Kerajaan di pedalaman memiliki tradisi membangun simbol-simbol religi untuk penghormatan kepada dewa-dewa dalam bentuk candi yang letaknya biasanya agak berjauhan dengan area kerajaan. Candicandi tersebut dipergunakan sebagai tempat peribadatan atau sebagai tempat persemayaman dari para raja setelah meninggal. Perawatan candi dibebankan kepada masyarakat yang terdapat di sekitar candi, sebagai kompensasinya masyarakat di desa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak seperti desa lainnya. Desa-desa yang berada di sekitar candi dan dibebaskan dari pajak ini dinamakan sebagai desa mardeka atau merdekan (Koentjaraningrat, 1994). Pada masa perkembangan kerajaan Hidhu-Budha di Jawa, raja memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam masyarakat, tidak hanya dalam aspek kekuasaan politik akan tetapi juga dalam aspek sosio-kultural dan mistis. Pada masa ini raja diasosiasikan sebagai representasi dari dewa-dewa, sehingga membuat kedudukannya menjadi sangat absolut di segala aspek kehidupan. Titah (pembicaraan atau perintah raja) dipahami layaknya perintah dari dewa-dewa. Raja menjadi tokoh yang menjadi pusat dari alam semesta, di mana di dalamnya dibebani oleh tugas-tugas keagamaan yang berat. Raja selalu dianggap memiliki kesaktian yang berasal dari dewa-dewa, di mana kesaktian tersebut disebarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya karena hubungan perkawinan, kekerabatan atau karena tugas kerajaan. Sementara itu, posisi rakyat adalah sebagai abdi dhalem (orang yang tunduk dan patuh pada perintah raja) dari raja. Rakyat mempunyai kewajiban memberikan upeti kepada raja sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan terhadap raja. Kepatuhan yang terbentuk pada rakyat dipahami sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada raja, tidak sebagai kewajiban yang membebani (Koentjaraningrat, 1994; Soemardjan, 1986). Pada masa kerajaan Hidhu-Budha sistem kultural yang berkembang pasa masyarakat Jawa lebih banyak yang bersifat mistis, yaitu adanya kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Kepercayaan terhadap adanya kesakten (kesaktian), pengagungan dan penghormatan terhadap tempat-tampat tertentu yang dianggap keramat menjadi ciri khas sistem kultural yang berkembang pada masyarakat Jawa (Koentjaraningrat, 1994; Kuntowijoyo, 1987 dan 2006 ; Astiyanto, 2006) Perkembangan selanjutnya pada masyarakat Jawa adalah masuknya nilainilai Islam yang kemudian menjadi awal perkembangan kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam berkembang setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan HindhuBudha yang berkembang lebih awal di tanah Jawa. Seperti halnya perkembangan kerajaan Hindhu-Budha, kerajaan Islam berkembang juga di daerah pesisir dan pedalaman. Kerajaan Islam di pesisir pada umumnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang berbasiskan pada pelabuhan. Sementara itu, kerajaan Islam di pedalaman masih mempertahankan struktur mata pencaharian yang menggantungkan diri pada sektor pertanian (Koentjaraningrat, 1994&1974). Sistem kultural yang berkembang pada masa kerajaan Islam, dalam beberapa hal menggeser nilai-nilai yang melembaga pada masa kerajaan HindhuBudha. Posisi sakral raja menjadi pusat dari alam semesta tidak lagi dipertahankan. Hal ini memberikan dampak terhadap konteks absolutisme yang berkembang pada raja-raja zaman Hindhu-Budha. Raja hanya menjadi penguasa politik kekuasaan, tidak lagi menjadi simbol dari religiuisme yang disembah dan diagungkan-agungkan oleh masyarakat kebanyakan (abdi dhalem). Meskipun demikian, ternyata masih terdapat nilai-nilai Hindhu-Budha yang bertahan pada masa Islam, yaitu nilai-nilai Islam yang dipengaruhi nilai-nilai kejawen, yaitu sistem nilai yang meyakini adanya kekuatan-kekuatan supranatural (mistis) di alam (Koentjaraningrat, 1994&1974; Suseno, 2001). Kolonialisme masuk ke Indonesia, termasuk juga di Jawa dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan struktur sosial dan sistem kultural masyarakat Jawa. Kolonialisme masuk dengan membawa nilai-nilai yang cenderung bersifat kapitalistik. Hal ini ditandai dengan masuknya sistem perdagangan kolonial yang bersifat eksploitatif, tanaman komersial serta sistem perkebunan sebagai representasi dari investasi modal (lihat Soemardjan, 1986; Burger, 1983). Menurut Booke masuknya nilai-nilai komersial pada masyarakat Jawa memberikan dampak terhadap terbentuknya dualisme ekonomi di Jawa, dan Indonesia secara umum. Ekonomi kapitalistik ala barat tidak dapat berintegrasi dengan sistem ekonomi tradisional ala Jawa. Sebagai akibatnya di masyarakat berkembang dua sistem ekonomi sekaligus, yaitu sistem kapitalistik kolonial dan sistem tradisional masyarakat pribumi (Sajogyo, 1982). Sudut pandang lain mengenai dampak dari masuknya sistem kapitalistik dalam sistem tradisional masyarakat Jawa dikemukakan oleh Geertz yang menyatakan bahwa masuknya perkebunan tebu di Jawa melahirkan bentuk adaptasi kelembagaan masyarakat Jawa, tepatnya masyarakat yang bergantung pada padi-sawah, dalam bentuk gejala perumitan kelembagaan atau dikenal dengan istilah ”agricultural involution” (Geertz, 1976). Dalam pandangan lainnya Geertz mengemukakan bahwa sistem kultural masyarakat Jawa dapat dibedakan ke dalam dua tipologi komunitas, yaitu sistem kultural yang dimiliki oleh para santri dan sistem kultural para ”abangan”. Santri dalam konteks ini dilekatkan pada komunitas yang memiliki pengaruh nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Dalam pandangan sistem nilai dikalangan santri hal-hal yang bersifat mistis dan supranatural seperti berkembang pada masyarakat Jawa masa kerajaan Hindhu-Budha sudah mulai ditinggalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Sementara itu, tradisi kaum ”abangan” justru sebaliknya, mereka tetap mempertahankan hal-hal yang bersifat mistis dan supranatural meskipun mereka sudah menyatakan diri sebagai orang Islam. Keislaman yang mereka ikrarkan pada dasarnya merupakan bentuk akulturasi dengan sistem nilai Jawa tradisional warisan nenek moyang mereka (Kuntowijoyo, 1987; Koentjaraningrat, 1994)). Masuknya kolonialisme, dalam perkembangannya berdampak pada pola hubungan feodalistik yang merupakan warisan kerajaan-kerajaan Jawa. Runtuhnya sistem feodalisme sangat terlihat pada pola hubungan agraria di Jawa. Pada masa ini sistem upeti dan privilege bagi kaum bangsawan Jawa digantikan dengan sistem pajak tanah, tanam paksa dan sistem investari modal asing. Ketiga sistem tersebut diinstroduksikan dalam waktu berbeda-beda. Sebagai implikasinya adalah berkembang nilai-nilai komersial di Jawa, tidak hanya pada pola hubungan produksi akan tetapi pada aspek-aspek lain kehidupan (Soemardjan, 1986; Burger; 1983; Husken; 1998; Husken dan White, 1989). Nilai komersial pada sistem kultural masyarakat Jawa semakin berkembang seiring dengan masuknya paradigma developmentalisme yang dijadikan sebagai pendekatan dalam pembangunan di Indonesia. Kebijakankebijakan pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu, menitikberatkan pada masuknya introduksi teknologi dan moda produksi modern yang cenderung bersifat kapitalistik. Sebagai akibatnya nilai-nilai ekonomi uang semakin terlihat berkembang pada sistem kultural masyarakat Jawa (Husken, 1998; Temple, 1994). Konteks di atas menunjukkan geneologi sistem kultural masyarakat Jawa dikaitkan dengan masuknya kekuatan-kekuatan politik kekuasaan yang ada di Jawa, di mana kekuatan politik kekuasaan tersebut memberikan pergeseran terhadap sistem kultural tradisional masyarakat Jawa. Sudut pandang yang berbeda dalam menelaah tentang sistem kultural masyarakat Jawa dapat dilihat dari konstruksi teoritis Kluckhon dalam melihat orientasi nilai budaya yang berkembang pada masyarakat Jawa. Sistem kultural masyarakat Jawa dapat dilihat dari tiga aspek penting yaitu sistem kultural yang berkaitan dengan hakekat hidup, hakekat hubungan dengan sesama manusia dan hakekat hubungan dengan alam (Koentjaraningrat, 1994; Gauthama, et.al, 2003). Hakekat hidup bagi masyarakat Jawa dimaknai sebagai ”nasib” yang harus diterima dan dijalankan apapun kondisinya. Hidup merupakan ketentuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, di mana manusia tidak memiliki kekuatan untuk merubahnya. Manusia hanya diberikan kemampuan untuk menerimanya dalam menjalankan. Nilai-nilai seperti merupakan representasi dari istilah ”nrimo ing pandum” yang sering dilekatkan pada masyarakat Jawa, yaitu sebuah pemaknaan yang memiliki pengertian senantiasa menerima keadaan yang telah diberikan oleh tuhannya (Koentjaraningrat, 1994; Gauthama, et.al, 2003). Hakekat hubungan dengan sesama manusia pada masyarakat Jawa menekankan adanya keselarasan, kedamaian dan kebersamaan yang kuat. Hal ini direpresentasikan oleh sikap hormat dan ”tepa slira” atau tenggang rasa satu dengan lainnya (Suseno, 2001). Pemahaman dasar mengenai kebersamaan, keselarasan dan prinsip saling menghormati dan menghargai pada masyarakat Jawa terbentuk atas konstruksi pemaknaan bahwa kehidupan di dunia ini dijalankan secara bersama-sama, di mana antara satu orang dengan yang lainnya akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan di dunia ini tidak akan dapat berjalan normal tanpa adanya kerjasama antar satu orang dengan yang lainnya. Untuk itu, maka sistem kultural masyarakat Jawa dalam konteks hubungan dengan sesama manusia meghindari terjadinya konflik dalam kehidupan. Konflik merupakan sesuatu hal yang harus dihindari dalam hidup bermasyarakat dan berhubungan satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan agar hidup dapat berjalan dengan normal, saling bisa mengisi, membantu dan menghormati satu dengan lainnya. Konstruksi sosial mengenai hekakat hubungan sesama manusia pada masyarakat Jawa yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dapat dilihat pada nilai-nilai guyub rukun dan gotong-royong (Koentjaraningrat, 1994; Gauthama, et .al, 2003). Hakekat hubungan dengan alam, bagi masyarakat Jawa alam merupakan anugerah dari tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa hakekat hubungan dengan alam menempatkan manusia untuk senantiasa selaras dengan alam. Pandangan yang bersifat eksploitatif terhadap alam seperti yang berkembang pada nilai-nilai kapitalistik tidak sesuai dengan pandangan masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan bagi masyarakat Jawa keberadaan alam sangat penting dalam kehidupan, di mana jika terjadi kerusakan pada alam pada akhirnya mereka meyakini bahwa hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kehidupan manusia (Koentjaraningrat, 1994; Gauthama, et.al, 2003). Sistem orientasi nilai yang dijelaskan di atas merupakan konseptualisasi normatif mengenai masyarakat Jawa kebanyakan dalam memandang kehidupan dalam berbagai dimensi. Meskipun bukan merupakan representasi universal dari masyarakat Jawa, namun demikian konseptualisasi mengenai orientasi nilai masyarakat Jawa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat di atas masih relevan untuk menelaah konteks kekinian masyarakat Jawa. Arus perubahan sosial yang cukup signifikan terjadi di Jawa karena berbagai macam konfigurasi sosial, baik kepentingan politik, ekonomi dan juga kultural, masyarakat Jawa secara normatif masih mempertahankan sejumlah nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Inti kebudayaan masyarakat Jawa sebagai sebuah sistem kultural masih bertahan dan unik mencirikan ke-Jawa-annya. 2. 3 Teori Sosiologi Interpretatif: Peran Aktif Aktor Teori sosiologi interpretatif berkembang sebagai kritik teori terhadap teori sosiologi strukturalisme. Teori sosiologi interpretatif mengkritik pandangan strukturalisme mengenai peran aktor. Dalam pandangan strukturalisme aktor dimaknai pasif memainkan perannya dalam struktur sosial, di mana tindakan sosial aktor dikendalikan atau sangat ditentukan oleh struktur sosial yang berada di atasnya. Aktor tidak memiliki peran melalui keberadaan dirinya dalam menentukan tindakan sosial yang dilakukan. Aktor hanya menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan dari struktur sosialnya. Pandangan teori sosiologi interpretatif memaknai sebaliknya mengenai peran aktor. Aktor merupakan pelaku aktif dalam memainkan perannya dalam struktur sosial dan melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial aktor dilakukan secara sadar melibatkan proses berpikir di tingkat aktor, hingga membentuk struktur sosial. Dalam konteks ini keberadaan tindakan sosial aktor tidak dimakni sebagai sesuatu hal yang telah ditentukan oleh struktur sosial, di mana aktor hanya tinggal menjalankannya saja (Poloma, 2004; Slaterry,2003; Ritzer dan Goodman, 2004; Calhoun, et.al, 2002 dan Turner, 1998). Teori sosiologi interpretatif lahir dari tradisi pemikiran yang menggabungkan antara sosiologi dengan psikologi, yang kemudian dikenal dengan disiplin psiko-sosial. Kajian sosiologi interpretatif menekankan pada analisis tingkat mikro level atau sampai pada meso level. Konsepsi teori sosiologi interpretatif tidak masuk pada ranah makro sosiologi (makro struktur), yang berkembang lebih awal dalam disiplin ilmu sosiologi dan merupakan kajian dari sosiologi strukturalisme. Konsepsi teoritis dari sosiologi interpretatif menekankan pada konstruksi sosial yang terbentuk pada struktur sosial sebagai hasil dari proses interaksi sosial antar aktor, di mana di dalamnya berlangsung pertukaran makna dan simbol-simbol . Perkembangan teori sosiologi interpretatif melahirkan sejumlah konsepsi teori yang saling menguatkan satu sama lain. Di antara konsepsi teori yang dikategorikan sebagai teori sosiologi interpretatif adalah dramaturgi dari Ervin Goffman, etnometodologi dari Harold Garfinkel, dan interaksionisme simbolis dari Herbert Blummer. Ketiga konsepsi teori sosiologi interpretatif tersebut samasama menfokuskan kajiannya pada peran aktif aktor dalam konstruksi sosial di masyarakat melalui proses interaksi sosial dan interpretasi terhadap makna dan simbol (Poloma, 2004). Pandangan Goffman mengenai dramaturgi pada dasarnya menjelaskan bahwa aktor dalam struktur sosial memainkan peran-peran tertentu. Pemaknaan terhadap suatu peran akan menjadi ada ketika dikaitkan dengan peran aktor-aktor lainnya. Dalam proses memainkan perannya dalam struktur sosial, aktor tidak hanya mengikuti ketentuan yang telah ada, akan tetapi juga melalui proses berpikir dan menginterpretasikan peran aktor lainnya sehingga secara keseluruhan hubungan peran antar aktor tersebut membentuk struktur sosial. Dalam konteks ini, hal yang dipertukarkan untuk saling diinterpretasikan di tingkat aktor bisa berupa simbol-simbol atau bahasa sebagai simbol yang paling konkrit. Dramaturgi dari Goffman mengasosiasikan peran-peran aktor dalam sebuah struktur sosial seperti pertunjukkan drama, di mana setiap aktor memainkan peran masingmasing dan peran itu akan bermakna ketika dikaitkan dengan peran-peran lainnya. Menurut Goffman paran aktor dalam kehidupan keseharian melakukan tindakan sosial dapat dibedakan ke dalam tipologi. Pertama, adalah tindakan aktor ketika berada di ”depan panggung” (front region), di mana dalam posisi seperti ini aktor dituntut untuk memerankan hal yang bersifat normatif (ideal) sesuai dengan peran yang dia dapatkan dalam struktur sosial tertentu. Aktor menutupi dirinya dari tindakan-tindakan sosial yang tidak sesuai dengan tuntutan perannya. Kedua, adalah belakang panggung” (back stage), di mana aktor dapat memerankan dirinya tidak selalu sesuai dengan konteks ideal yang seharusnya dilakukan. Keberaaan aktor baik di depan panggung maupun di belakang panggung tidak hanya dalam konteks memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam struktur sosial, akan tetapi terdapat proses berpikir dan menginterpretasikan diri atas perannya di dalam struktur sosial (Poloma, 2004; Calhoun, et.al, 2002; Ritzer dan Goodman, 2004). Etnometodologi dari Garfinkel dikategorikan sebagai studi empiris mengenai bagaimana orang menangkap pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Secara empiris konsepsi teori ini mempelajari tentang konstruksi realitas yang dibuat seseorang di saat interaksi sehari-hari berlangsung (Poloma, 2004). Etnomotologi menolak pandangan bahwa realitas sosial yang ada dalam masyarakat merupakan sesuatu yang berada ”di luar”, yakni berupa ketentuan yang telah tetap dan bersifat universal di mana aktor dalam realitas sosial tersebut hanya menerima saja. Bagi kaum yang menjadi pendukung aliran etnometodologi, realitas sosial bersifat inheren dalam masyarakat, di mana di dalamnya terdapat proses interpretasi atas makna-makna yang dipertukarkan dalam interaksi sosial sehingga kemudian terbentuk konstruksi sosial mengenai nilai dan struktur sosial. Realitas sosial dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat subyektif, tidak obyektif seperti konsepsi teori dari kaum strukturalisme (Poloma, 2004; Slaterry,2003; Ritzer dan Goodman, 2004; dan Turner, 1998). Etnometodologi menekankan pada kajian simbol yang berbentuk bahasa untuk memahami konstruksi pemaknaan mengenai realitas sosial yang dibangun oleh hubungan antar aktor. Meskipun demikian, etnometodologi tidak sama dengan hermeunetik yang hanya menfokuskan konstruksi sosial pada kajian bahasa (lihat Ricoeur,2006) . Dalam etnometodologi bahasa hanya merupakan salah satu bentuk simbol yang diinterpretasikan, akan tetapi terdapat simbol-simbol lain selain bahasa. Interaksionisme simbolis tidak memiliki perbedaan yang begitu mendasar dengan konsepsi teori sosiologi interpretatif yang dikemukakan sebelumnya. Pandangan Interaksionisme Simbolis menekankan pada interpretasi makna yang dilakukan oleh aktor dalam interaksi sosial. Pandangan ini juga memposisikan diri sebagai kritik teori terhadap pandangan strukturalisme. Konsepsi teori interaksionisme simbolis memiliki asumsi dasar bahwa interaksi antar aktor menghasilkan sebuah konstruksi sosial melalui pertukaran makna dan simbol. Blummer (1969) sebagai salah satu tokoh penting yang melahirkan pandangan interaksionisme simbolis menyatakan bahwa konsepsi teori ini bertumpu pada tiga premis yaitu: 1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada ”sesuatu” itu pada mereka 2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain 3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi berlangsung Pandangan teori interaksionisme simbolis menolak adanya realitas obyektif, di mana terhadap realitas dipahami sebagai sesuatu yang sudah inheren dan bersifat universal pada sistem sosial apapun. Menurut teori interaksionisme simbolis, makna pada realitas sosial, baik itu benda maupun tindakan sosial manusia, tidak bersifat inheren tergantung pada konstruksi pemaknaan yang dibangun dalam proses interaksi sosial antar aktor, di mana setting sosial (dimensi ruang dan waktu) memberikan pengaruh terhadap terbentuknya konstruksi pemaknaan yang dihasilkan (Poloma, 2004). Konstruksi pemaknaan melibatkan aktor dalam proses memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasi makna dalam hubungannya dengan situasi di mana dia ditempatkan dan arah tindakannya. Konstruksi makna dari proses interpretasi merupakan hal yang terus diorgansisasikan oleh aktor untuk kepentingan pengarah bagi tindakan sosialnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini Blummer menjelaskan bahwa manusia adalah aktor yang sadar dan refleksif yang menyatukan obyekobyek yang diketahuinya melalui proses self indication, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan menentukan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut (Poloma, 2004). Pandangan mengenai aktor yang bersifat kreatif juga dikemukakan dalam penjelasan teori strukturasi agen-struktur yang dikemukakan oleh Giddens. Dalam pandangan Giddens aktor memiliki kesadaran kreatif dalam melakukan tindakan sosial. Perbedaan Giddens dengan beberapa tokoh sosiologi interpretatif adalah penjelasan mengenai struktur sosial, di mana dalam teori agen dan strukturnya Giddens juga memberikan penjelasan mengenai keberadaan struktur dalam memberikan pengaruh terhadap tindakan aktor. Menurut Giddens, aktor (peran aktor atau agency) memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan struktur sosial yang diistilahkan dengan dualitas. Konsep dualitas ini pada dasanya menekankan adanya hubungan antara konteks mikro-makro yang selama ini menjadi perdebatan teoritis antara interaksionisme dan strukturalisme. Giddens membangun konsepsi teori yang menjembatani perdebatan antara kedua pendekatan tersebut. Aktor bertindak berdasarkan kesadaran yang dimiliki (aktif) namun demikian di lain pihak kesadaran tersebut ”dibatasi” oleh keberadaan struktur sosial yang mengarahkan tindakan aktor. Struktur sosial berposisi sebagai kekuatan inheren yang membangun kesadaran aktor dalam melakukan tindakan sosial (Ritzer dan Goodman, 2004; Turner, 1998). Teori sosiologi interpretatif secara eksplisit tidak menyediakan penjelasan yang memadai untuk menjelaskan konsep perubahan. Kekuatan penyebab perubahan dan arah perubahan sosial dalam masyarakat tidak mendapatkan perhatian dalam kerangka teori ini. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh lagi sebenarnya teori sosiologi interpretatif dapat dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena perubahan sosial. Hal ini dapat ditelaah dari pemahaman teori ini yang menyatakan bahwa pada dasarnya konstruksi sosial merupakan sebuah proses yang terus-menerus disempurnakan dalam interaksi sosial (Poloma, 2004). Artinya, konstruksi sosial merupakan sesuatu hal yang bersifat dinamis dalam konteks terjadi penyempurnaan-penyempurnaan (di dalamnya terdapat proses perubahan atau pergeseran) terhadap hal tersebut. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan adanya pemahaman teori dalam sosiologi interpretatif yang menyatakan bahwa konstruksi sosial bersifat kontekstual dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam setting ruang dan waktu tertentu konstruksi sosial yang terbentuk akan berbeda satu sama lain (unik atau tidak universal). Jika pemahaman ini ditarik dalam kerangka adanya perkembangan waktu, maka konstruksi sosial dalam teori ini dipahami sebagai sesuatu yang bersifat dinamis (berubah atau bergeser). 2. 4 Kerangka Teoritis Burung memiliki dimensi makna yang sangat beragam tergantung pada setting sosial dan konteks munculnya pemaknaan. Pemaknaan terhadap burung meliputi dimensi ekonomi, sosio-kultural, ekologi dan estetika (keindahan). Dimensi pemaknaan burung secara ekonomi dapat dilihat dari pemanfaatan burung sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan para penggemar burung dan bahan makanan. Saat ini tingkat kegemaran memelihara burung menunjukkan pergeseran yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil kajian Jepson dan Ladle di lima kota besar di Indonesia (empat diantaranya terdapat di Jawa) yang menunjukkan bahwa burung merupakan satwa peliharaan yang paling digemari dibandingkan dengan jenis satwa peliharaan lainnya, seperti kucing, ikan, anjing, dan kuda (Jepson and Ladle, 2005). Hal ini memberikan dampak terhadap semakin meningkatnya perdagangan burung di Indonesia, baik yang dilakukan di pasar-pasar burung maupun di luar pasar burung. Jenis burung yang saat ini marak diperdagangkan antara lain jenis burung kakak tua dan beberapa jenis berkicau seperti cucak rawa, anis merah, dan murrai batu. Potensi keuntungan ekonomi yang cukup besar dari perdagangan burung menjadi salah satu faktor penting yang menjadi penarik semakin maraknya perdagangan burung di Indonesia. Pemanfaatan burung secara ekonomi dapat dilihat juga dari pemanfaatan burung untuk kepentingan bahan makanan. Pemaknaan burung sebagai bahan makanan lebih dahulu terbentuk dibandingkan dengan pemanfaatan burung sebagai ”komoditas” perdagangan. Di Indonesia terdapat jenis burung tertentu yang dagingnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang diperjualbelikan, seperti misalnya, burung merpati atau beberapa jenis burung laut (pelikan) (Mackinnon, 1984). Burung dalam dimensi sosio-kultural dimaknai sebagai bagian dari entitas kultural komunitas tertentu. Komunitas Dayak Laut misalnya memaknai beberapa jenis burung tertentu sebagai simbol dari mistis dan religiusitas, di mana burung ditempatkan sebagai representasi dari dewa-dewa yang mereka sembah (Welty, 1979). Sementara itu, bagi kalangan masyarakat Jawa, jenis burung tertentu menjadi simbol dari status sosial dan kesempurnaan dalam hidup. Memelihara burung menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, di mana burung merupakan representasi dari kukila dalam filosofi kesempurnaan hidup masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa, khususnya yang memiliki tradisi kultural tradisional yang masih kuat, memiliki filosofi tentang kesempurnaan hidup, yaitu meliputi harta (kekayaan), tahta (kekuasaan), wanita (pasangan/istri), (kendaraan/tunggangan) serta kukila (Muchtar dan Nurwatha, 2001). turangga Sedangkan secara ekologis, pemaknaan terhadap burung dapat dilihat dari pemanfaatan burung sebagai bio-monitoring terhadap perubahan lingkungan. Di beberapa negara maju pemanfaatan burung sebagai bio-monitoring sudah banyak dilakukan, seperti untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran lingkungan dan pencemaran pestisida (Furness and Greenwood, 1993). Di Indonesia, secara tradisional peran burung sebagai bio-monitoring dapat dilihat pada pemanfaatan burung sebagai ”musuh alami” dari beberapa jenis serangga di kegiatan pertanian. Hal ini menjadi local knowledge yang dimanfaatkan oleh petani, di mana burungburung tertentu dibiarkan mendatangi areal pertaninya untuk memakan hama serangga (Mackinnon, 1984). Dari dimensi estetika burung dimanfaatkan oleh kalangan seniman sebagai obyek karya seni (lukisan) mereka (Surata, 1993). Dalam konteks sosio-kultural pemaknaan burung yang berkembang pada masyarakat Jawa menempatkan burung sebagai bagian dari entitas kultural masyarakat Jawa. Secara historis, memelihara burung di kalangan priyayi (bangsawan) menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan sebagai simbol status sosial mereka. Jenis burung yang populer adalah jenis burung perkutut, yang menjadi simbol dari ketenangan dan kewibawaan. Akan tetapi kecenderungan yang berkembang dalam konteks kekinian, pemaknaan burung di kalangan masyarakat Jawa lagi hanya sebatas pada pemaknaan sosio-kultural yang bersifat tradisional. Dimensi sosio-kultural burung dalam konteks kekinian membentuk konstruksi pemaknaan yang menempatkan burung sebagai hobi untuk pengisi waktu luang saat beristirahat. Burung menjadi simbol dari ketenangan dan keindahan dengan mendengarkan keindahan suara burung. Fenomena ini tidak hanya melibatkan masyarakat Jawa dari kalangan kelas atas (bangsawan/priyayi) seperti masa lalu, akan tetapi melibatkan masyarakat Jawa dari berbagai lapisan3. Di samping itu, pada kalangan masyarakat Jawa saat ini juga mulai berkembang konstruksi pemaknaan burung secara ekonomi, di mana burung dijadikan sebagai komoditas perdagangan yang menguntungkan. Semakin meningkatnya tingkat kegemaran memelihara burung pada masyarakat Jawa menjadi salah satu faktor 3 Meskipun bersifat multi-strata, yaitu melibatkan hamper sebagian besar dari lapisan masyarakat Jawa, akan tetapi secara faktual sebagian besar masyarakat Jawa yang terlibat dalam kegemaran hobi memelihara burung masih didominasi oleh msyarakat lapisan atas dan menengah (Jepson and Ladle, 2005) penting yang menjadikan maraknya perdagangan burung. Burung saat ini menjadi dimaknai sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan potensi keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan. Hal ini menunjukkan terbentuknya kecenderungan komersialisasi terhadap burung. Nilai-nilai komersial pada masyarakat Jawa sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Masuknya kolonialisme yang memperkenalkan (secara paksa) nilai-nilai kapitalitik melalui moda produksi kapitalistik membentuk nilai-nilai komersial pada hubunganhubungan sosial di pedesaaan (Husken, 1998; Soemardjan, 1986 dan Sajogyo, 1982 dan Penny, 1982&1990). Nilai-nilai komersial tidak hanya berkembang pada pola hubungan sosial, akan tetapi pada tindakan-tindakan sosial tertentu seperti kerja.4 Pergeseran konstruksi pemaknaan pada komunitas penggemar burung di Jawa dalam konteks ini dipahami sebagai adanya pergeseran terhadap konstruksi pemaknaan burung di tingkat komunitas penggemar burung. Berkembangnya nilai-nilai komersial terhadap burung merupakan hasil dari interpretasi makna dalam proses interaksi sosial antar komunitas penggemar burung yang dalam perkembangannya tidak hanya menjadikan burung sebagai bagian dari kehidupan untuk mengisi waktu luang, akan tetapi memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Semakin maraknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunitas penggemar burung menjadi salah satu bentuk daya tarik yang menempatkan burung tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol keindahan dengan mendengarkan suara, warna dan gerak-geriknya. Akan tetapi burung menjadi komoditas yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, baik sebagai penghasilan alternatif atau utama. Dalam perkembangannya, pemaknaan lain yang berkembang terhadap burung di masyarakat, tepatnya komunitas penggemar burung adalah pemaknaan konservasi terhadap burung. Dalam konteks ini burung menjadi salah satu perhatian satwa yang harus mulai diupayakan pelestariannya seiring dengan semakin terancamnya beberapa jenis burung tertentu karena kegiatan perburuan 4 Sebelum masuknya nilai-nilai komersial dari kolonialisme barat, pemaknaan terhadap kerja bersifat sosio-kultural, di mana kerja dilakukan secara bersama-sama antar sesama warga (dikenal dengan istilah gotong royong) yang kemudian bergeser menjadi sistem upah. (Husken, 1998; Soemardjan, 1986) dan perdagangan burung. Secara tradisional, sebenarnya dimensi pemaknaan konservasi terhadap burung sudah terbentuk yaitu ketika dikaitkan dengan tradisitradisi kultural komunitas tertentu. Burung dilestarikan dan dijaga keberadaannya karena menjadi bagian dari entitas kultural komunitas tersebut (lihat Welty, 1979; Muchtar dan Nurwatha, 2001). Konstruksi pemaknaan di tingkat komunitas penggemar burung dipahami sebagai sesuatu hal yang bersifat dinamis. Semakin berkembangnya komunitas penggemar burung, di mana di dalamnya juga berkembang sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan burung merupakan faktor mendasar yang membentuk kedinamisan pemaknaan dalam komunitas penggemar burung. Komunitas penggemar burung sebagai aktor menjadi representasi dari berbagai bentuk kepentingan pada komunitas penggemar burung. Dalam praksis sosial tindakan sosial aktor merupakan representasi dari kepentingan yang terdapat pada komunitas penggemar burung. Tindakan sosial aktor dalam konteks dapat dipahami sebagai proses kreatif aktor (kesadaran aktor) dalam menginterpretasikan sejumlah kondisi secara terus menerus, namun juga dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran aktor struktur sosial yang menjadi bagian dari sistem sosialnya. Atau dengan kata lain, tindakan sosial aktor pada komunitas penggemar burung dapat dipahami sebagai dualitas antara kesadaran aktor dan tekanan struktur. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Giddens dalam teorinya mengenai struktur dan agensi, di mana antara aktor sebagai agen dengan struktur sosial tidak ditelaah secara terpisah satu sama lain dalam kerangka yang berlawanan (Ritzer dan Goodman, 2004; Turner, 1998)