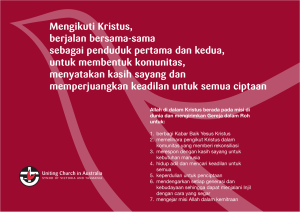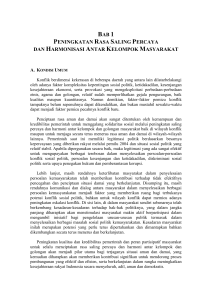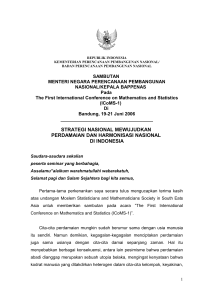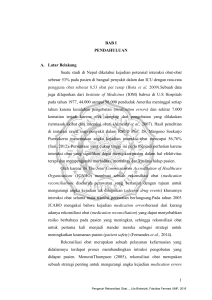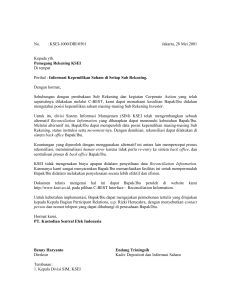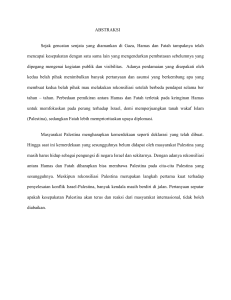1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
advertisement

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rekonsiliasi adalah sebuah tema yang banyak menghiasi wacana publik belakangan ini. Hal itu tidak terlepas dari merebaknya berbagai kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat, yang selain menimbulkan berbagai efek negatip seperti dendam, kebencian, trauma, dll., juga karena cara penyelesaiannya seringkali dipersoalkan. Konflik tampaknya merupakan fenomena universal kehidupan manusia baik dalam ranah sosial maupun budaya. Penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan manusia dapat beraneka, di antaranya: konflik karena perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, ideologi, keyakinan, budaya, dan karakter masyarakat. Karena itu dapat diduga bahwa konflik telah ada setua umur manusia di bumi. Konflik yang disebabkan oleh berbagai perbedaan tersebut terejawantah atau teraktualisasi dalam berbagai bentuk tindakan – entah fisik maupun non-fisik – yang cenderung destruktif. Karena itu dalam konteks kehidupan masyarakat yang heterogen, potensi konflik itu relatif lebih besar dibanding masyarakat yang berciri homogen, misalnya dari segi etnisitas. Para pakar berteori bahwa konflik tidak selalu memiliki efek negatip atau destruktif dalam kehidupan manusia. Konflik dapat membawa dampak positif dan konstruktif, di antaranya: mendorong terjadinya perubahan sosial; memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan; dapat mempererat persatuan dan 2 solidaritas kelompok; serta membangun dan memelihara identitas kelompok.1 Kendati demikian, dalam kehidupan sehari-hari perhatian terhadap dimensi konstruktif tersebut jarang digubris. Pada umumnya orang melihat konflik sebagai hal yang negatif dan destruktif. Karena itulah dalam setiap kelompok masyarakat dan budaya, orang memiliki dan mengembangkan pengetahuan, cara atau mekanismenya masing-masing dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Mekanisme tersebut dapat berupa praktek-praktek budaya atau kearifan lokal (local wisdom) yang dapat membantu menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan yang terganggu karena konflik. Jadi konflik mengandung bahaya tetapi juga kesempatan (opportunity). Indonesia adalah negara dengan latar belakang masyarakat berciri majemuk. Belakangan ini kita menyaksikan terjadi konflik di berbagai tempat dalam masyarakat. Terjadinya aneka konflik tersebut tidak terlepas dari realitas kemajemukan masyarakat baik dari segi suku, agama, ras (SARA), dan juga budaya. Tidak mengherankan bahwa terjadinya aneka konflik dan kekerasan di berbagai tempat, dipicu adanya sentimen berbau SARA. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia adalah negara yang rentan terhadap konflik yang bersifat latent. Selain itu terjadinya krisis multi dimensional seperti krisis ekonomi, politik, dan persoalan ketidakadilan ikut memicu terjadinya konflik dan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam pergaulan antar komunitas maupun individu, juga terjadi aneka konflik sebagai realitas yang bisa dialami oleh siapa saja, termasuk para pembaca tulisan ini. Konflik dalam berbagai bentuk dapat terjadi di mana saja, misalnya konflik dalam rumah tangga, di tempat kerja, termasuk di dalam gereja 1 Lewis Coser, The Functions of Social Conflict (New York: The Free Press, 1956), pp. 33-38. Lihat juga: Dean G. Pruit & Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 / Terj), hlm. 1315. 3 atau jemaat. Konflik-konflik yang demikian ada yang dengan mudah dapat diselesaikan tapi tidak sedikit yang sulit bahkan tidak terselesaikan. Konflik dan kekerasan merupakan realitas multi dimensi yang saling kait-mengait satu dengan yang lainnya, dan membutuhkan kearifan tertentu untuk menyelesaikannya. Francis Fukuyama berpendapat bahwa dunia kita sekarang ini sedang mengalami suatu goncangan atau kekacauan besar (a great disruption).2 Hal itu dicirikan oleh tingkat kejahatan dan kekacauan sosial yang meningkat, menurunnya fungsi keluarga dan kekerabatan sebagai sumber kohesi sosial, menurunnya tingkat kepercayaan, meningkatnya individualisme, serta melemahnya ikatan-ikatan sosial dan nilai-nilai yang diyakini bersama dalam masyarakat. Dengan kian terkikisnya tingkat kepercayaan di antara berbagai elemen dalam masyarakat, akibatnya terbentuk stigma dalam masyarakat yang oleh Fukuyama disebut low trust society.3 Konflik dan kekerasan, bagaimanapun telah memakan banyak korban, bukan hanya harta benda tetapi juga nyawa manusia yang tak bersalah. Perang dan konflik bukan hanya menghancurkan bangunan fisik tetapi juga menunjukkan runtuhnya bangunan sosial dan rapuhnya kekayaan spiritual yang menyangga kehidupan. Ia juga menghancurkan hasil kebudayaan dan peradaban manusia yang telah dibangun sekian lama. Pertikaian bernuansa SARA yang pernah terjadi di Indoensia seperti di Maluku, 2 Lih. Francis Fukuyama, The Great Disruption – Hakekat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial (Yogyakarta: Penerbit CV. Qalam, 2002 / Terj. Ruslani), hlm 6-12, 68, 87. 3 Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, menurut Fukuyama ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yakni: kebajikan sosial (social virtues) dan modal sosial (social capital). Yang dimaksud dengan modal sosial adalah nilai-nilai seperti kejujuran, saling menolong, keterandalan, kesediaan bekerjasama, dan rasa bertanggungjawab terhadap orang lain. Sedangkan modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya hubungan di antara mereka. Atau dengan kata lain, kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan physical capital (tanah, bangunan, mesin) dan human capital (pengetahuan dan keterampilan yang kita simpan di kepala kita). Lih. Francis Fukuyama, TRUST – Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002/ Terj. Ruslani), hlm 33-45, 65; Fukuyama, The Great Disruption, hlm. 19-22. 4 Poso, dan Kalimantan Barat, telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar, di samping gelombang pengungsian penduduk untuk mencari tempat yang lebih aman.4 Hal amat penting yang sering diabaikan adalah situasi pasca-konflik. Ia meninggalkan trauma yang dalam, stress, dendam yang membara, semangat permusuhan, saling curiga, maupun luka yang dalam dan rasa sakit hati di antara mereka yang bertikai. Perasaan sakit hati maupun kebencian yang tak terdamaikan akan menjadi semacam jerami kering yang mudah membara disulut api. Atau ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hal itu akhirnya membentuk mentalitas masyarakat yang haus akan konflik dan kekerasan. Tidak jarang orang menjustifikasi kekerasan sebagai sebuah seni atau cara dalam penyelesaian konflik. Konflik dan kekerasan yang dimotivasi keinginan balas dendam dan kebencian pada gilirannya akan menciptakan suatu lingkaran balas dendam (cycles of revenge).5 Hal ini dapat dianalogikan dengan kritik Yesus terhadap hukum pembalasan (retaliation) dalam khotbah di Bukit, yakni: “mata ganti mata dan gigi ganti gigi” (Mat 5:38). Yesus sebaliknya mengajarkan untuk membalas dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Konflik dan kekerasan ibarat anak kembar yang selalu mewarnai sejarah peradaban manusia hingga saat ini. Dalam kondisi seperti itu orang mempertanyakan bagaimana peranan nilai-nilai budaya maupun agama seperti toleransi, harmoni, solidaritas, saling menghargai, mengasihi, dll., yang seolah telah terkikis oleh perkembangan-perkembangan yang 4 Mengenai fenomena ini lihat antara lain tulisan Bernard Raho, “Konflik di Indonesia, Problem dan Pemecahannya ditinjau dari perspektif Sosiologis” dalam: Guido Tisera (ed.), Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian. Maumere: LPBAJ, 2002, hlm 121-132; Tuhana Taufiq A, Konflik Maluku (Yogyakarta: Global Media, 2000), hlm 39-92. 5 Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness – Facing History after Genocide and Mass Violence (Boston: Beacon Press, 1998), p. 10. 5 diakibatkan oleh modernisasi dan globalisasi. Adanya berbagai konflik dan krisis membuat kehidupan masyarakat ibarat dalam kondisi sakit yang butuh tindakan pemulihan (healing). Dari perspektif iman Kristen, apa yang sangat urgent yang kita butuhkan saat ini adalah suatu rekonsiliasi (sosial, kultural, maupun spiritual). Ini adalah upaya terobosan untuk memutuskan mata rantai konflik, kekerasan, dan balas dendam secara elegan, kredibel, dan bermartabat. Karena betapa pentingnya rekonsiliasi dalam konteks kehidupan dewasa ini, Robert J. Schreiter berpendapat bahwa rekonsiliasi adalah model misi gereja yang amat penting dalam milenium ini.6 Rekonsiliasi amat dibutuhkan untuk merajut kembali benang kebersamaan yang telah terkoyak, untuk menjalin kembali hubungan kemanusiaan sebagai sesama anak bangsa dan sebagai sesama makluk ciptaan Tuhan. Rekonsiliasi membantu menghilangkan dendam dan menyembuhkan luka-luka batin, sehingga tercipta relasi sosial yang sehat, harmonis, dan penuh damai. Dengan beberapa pertimbangan di atas, penulis berpendapat bahwa rekonsiliasi adalah hal yang amat urgent sekaligus menantang dalam konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat saat ini, karena itu penulis tertarik untuk membahasnya di sini. B. POTRET PERMASALAHAN DAN FOKUS PENELITIAN 1. Seputar Paradigma dan Pendekatan Rekonsiliasi. Mencermati berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia, telah banyak usaha dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh badan non-pemerintah lainnya untuk mengupayakan rekonsiliasi. Sekalipun demikian konflik dan kekerasan masih saja terus terjadi. Hal ini membersitkan pertanyaan, mengapa usaha-usaha seperti itu 6 Robert J. Schreiter, “Reconciliation as a Model of Mission” dalam: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft – Nouvelle Revue de Science missionarie (no. 52-1996), pp. 243-350. 6 gagal atau tidak memadai? Salah satu kelemahan yang terjadi adalah pendekatan yang terlalu berorientasi yuridis-formal dan dari atas (top down approach). Rekonsiliasi dan nilai-nilainya seringkali dipaksakan dari atas dalam hal ini penguasa, dan kurang mengakomodasi dan mendorong inisiatif masyarakat. Pendekatan penyelesaian masalah lewat lembaga-lembaga formal seperti lembaga pengadilan dengan memakai hukum positif terlampau bertumpu pada penanganan masalah an sich, ketimbang perbaikan relasi.7 Pendekatan formal terhadap konflik dan rekonsiliasi lebih bercorak rasional (rational aprroach), dengan mengandalkan logika hukum dan aturan-aturan formal lainnya. Penerapan prinsip keadilan dalam menyelesaikan perkara entah konflik maupun kekerasan – sekalipun perlu dan penting – lebih bersifat menghakimi dan menghukum (punitif) ketimbang merehabilitasi para korban, atau merestorasi relasi-relasi manusiawi di antara mereka. Dengan demikian rekonsiliasi terabaikan dan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik tetap berantakan. Hubungan mereka adalah antara yang menang (the winner) dan yang kalah (the loser), antara yang kuat (the powerful) dan yang lemah (the powerless). Atau sebagai sesama lawan yang berusaha saling menjegal dan menghabisi dalam sebuah panggung sandiwara pengadilan. Yang menjadi keprihatinan utama dari pendekatan formal semacam itu adalah hilangnya wajah humanitas, berupa apresiasi terhadap keluhuran martabat manusia. Masalah mendasar lainnya adalah bahwa upaya rekonsiliasi di antara berbagai elemen maupun individu dalam masyarakat seringkali tidak berakar pada kultur masyarakat. Dalam hal ini mekanisme penyelesaian masalah dengan 7 Paulus S. Widjaja, “Pengantar” dalam: John Paul Lederach, Transformasi Konflik (Terj. Daniel K. Listijabudi). (Yogyakarta: PSPP UKDW, 2005), hlm 6-7. Lihat juga: Miroslav Volf, “Forgiveness, Reconciliation & Justice” dalam: Raymond G. Helmick & Roney L. Petersen (eds), Forgiveness and Reconciliation (Philadelphia & London: Templeton Foundation Press, 2001), pp. 40-41. 7 memanfaatkan instrumen kearifan budaya lokal dan nilai-nilai inheren dalam masyarakat yang bersangkutan.8 Hal ini semakin diperparah lagi dengan telah terpinggirkannya fungsi-fungsi lembaga adat atau perangkat pemangku budaya lokal dalam penanganan konflik. Jadi persoalan pokoknya di sini terletak pada paradigma yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, yakni cenderung satu arah dengan penekanan pada dimensi rasional-objektif dan mengabaikan aspek kultural dan sisi humanitas manusia. Penulis berkeyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat, setiap suku dan budayanya memiliki keragaman kultur pendamaian yang khas dan inheren, serta kearifan atau pengetahuan lokal (local knowledge) yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.9 Studi ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengkaji dan menawarkan semacam paradigma alternatif dalam penyelesaian konflik dan rekonsiliasi yang berakar atau bersumber pada pendekatan kultural. 2. Rekonsiliasi dan Pendekatan Kultural. Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu propinsi di kawasan Indonesia bagian Timur. Daerah ini didiami oleh banyak suku dengan keragaman budaya, bahasa, dan juga agama atau keyakinan. Suatu studi yang pernah dilakukan menemukan bahwa dalam wilayah ini terdapat 15 kelompok etnik besar atau 75 8 Para pemerhati dan penggiat upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi seperti Lederach dan Augsberger telah menandaskan betapa pentingnya proses-proses rekonsiliasi yang terikat atau berakar pada budaya. Lih. John Paul Lederach, Preparing for Peace: Conflict Transformasi Across Culture (Syracuse: Syaracuse University Press, 1995), pp. 3-10; David W. Augsberger, Conflict Mediation Across Cultures (Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1992), khususnya pp. 259-287. 9 Beberapa contoh atau uraian mengenai praktek pendamaian dalam beberapa suku di Indonesia dapat dibaca dalam: Andreas A. Yewangoe, Pendamaian – Suatu studi tentang pemulihan relasi antara Allah, manusia dan alam semesta (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983). Lihat juga uraian tentang kearifan lokal dalam: Clifford Geertz, Local Knowledge – Further Essays in Interpretive Anthropology (Third Edition). (USA: Basic Books, 2000). 8 kesatuan etnik atau 500 suku, masing-masing dengan budayanya yang khas dan masih terpelihara hingga saat ini.10 Sesuai latar belakang di atas, daerah ini rentan terhadap konflik yang disebabkan oleh berbagai hal, baik konflik terbuka maupun terpendam. Di antaranya konflik yang disebabkan masalah tanah adat, urusan-urusan adat seperti perkawinan, konflik dalam rumah tangga, ketegangan yang dipicu masalah politik dan keagamaan, termasuk konflik antar suku yang disebabkan sentimen primordialisme dan perbedaan-perbedaan nilai, tradisi dan karakter masyarakat. Dalam konteks seperti ini menurut F.D. Wellem, gereja baik Katolik maupun Protestan di NTT berkarya di wilayah yang rawan konflik. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensi konfliknya sangat tinggi sehingga sewaktu-waktu jikalau ada pemicu maka potensi konflik itu akan teraktualisasi.11 Sebagaimana suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku di NTT seperti: Sabu, Timor, Rote, Alor, Sumba, dll., memiliki keragaman pendekatan kultural dalam penyelesaian konflik.12 Pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik berakar pada nilai-nilai, praktek-praktek budaya, ritual maupun kepercayaan agama suku yang dalam taraf tertentu masih terpelihara dan diwariskan turun-temurun. Salah satu dari komunitas masyarakat yang ada di NTT adalah suku Sabu dan budayanya. Orang Sabu adalah komunitas etnis dengan lingkungan kebudayaan dan basis komunitasnya mendiami dua pulau di NTT, yaitu pulau Sabu dan Raijua. 10 Alo Liliweri, “Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik di Kupang” dalam: Alo Liliweri dan Gregor Neonbasu (penyunting), Perspektif Pembangunan, Dinamika dan Tantangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur (Kupang: Yayasan Insan Pembaru, 1994), hlm. 1. 11 Fred D. Wellem, “Peranan Gereja dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik di NTT” dalam: Guido Tisera (ed), Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian, hlm. 112. 12 Di kalangan suku Atoni di Timor NTT misalnya, pendekatan budaya untuk pendamaian dilakukan lewat ritual adat yang disebut “Halan Nekaf” (Halan = Damai; Nekaf = hati). Halan Nekaf artinya mendamaikan hati antara mereka yang berkonflik atau yang hatinya sakit. Ritual ini antara lain ditandai dengan makan sirih pinang bersama disertai hidangan makanan yang ditanggung bersama. 9 Pendekatan kultural berkaitan dengan rekonsiliasi di kalangan masyarakat suku Sabu terkait erat dengan narasi-narasi, nilai-nilai, dan worldviews13 yang bersumber dari budaya maupun agama suku Sabu. Adapun nilai-nilai budaya Sabu yang punya kaitan makna dengan rekonsiliasi di antaranya nilai atau prinsip hidup harmonis dan seimbang. Prinsip seperti ini bersumber dari pandangan bahwa sesuai hukum ilahi semua yang ada di dunia ini tercipta mengikuti hukum harmoni dan keseimbangan.14 Semua yang ada dalam alam semesta saling berhubungan dan bergantung dalam suatu tatanan yang seimbang. Dalam rangka menjaga harmoni dan keseimbangan relasi antara sesama manusia maka nilai kekerabatan dan solidaritas sosial perlu dipelihara dan dijunjung tinggi. Berdasarkan keyakinan tersebut, konflik dipandang sebagai hal yang mengganggu dan menciderai keseimbangan dan harmoni. Selanjutnya gangguan terhadap harmoni dan keseimbangan akan mendatangkan bencana atau malapetaka. Karena itu rekonsiliasi mutlak diperlukan untuk menjaga harmoni, keseimbangan, dan relasi sosial. Dalam rangka rekonsiliasi antara sesama dalam masyarakat suku Sabu terdapat tindakan simbolik yang amat khas dan punya peranan penting dalam menjaga dan merawat hubungan-hubungan sosial, yakni budaya Hengèd’u.15 Budaya hengèd’u adalah suatu praktek ciuman khas suku Sabu dengan saling menempelkan 13 Yang dimaksud dengan world-view dalam perspektif budaya adalah pandangan hidup atau cara pandang manusia terhadap Allah, dunia, manusia dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya . Di sini world-view menjadi asumsi dasar, konsep, premis, dan nilai-nilai dalam mana masyarakat sebagai entitas sosial dan kultural terikat dan taat kepadanya. 14 Robert Riwu Kaho, Orang Sabu dan Budayanya (Yogyakarta: Jogja Global Media, 2005), hlm 79-86. 15 Praktek Hengèd’u menjadi praktek budaya yang unik dan khas di kalangan etnis Sabu. Mengapa? Karena bagi kebanyakan orang, berciuman lebih dikaitkan dengan romantisme yang belakangan ini oleh kelompok tertentu malah dipandang sebagai pornoaksi. Namun bagi orang Sabu, ciuman punya multi makna, antara lain simbol kekerabatan dan persaudaraan yang rukun. Oleh karena itulah setiap berjumpa, khususnya dalam acara-acara kekeluargaan seperti perkawinan, kedukaan, dll., orang Sabu akan secara spontan berciuman (di depan umum). Sebab itulah di kalangan suku-suku di NTT, praktek ciuman semacam ini populer disebut “Ciuman Sabu”. 10 ujung hidung antara dua orang, dengan makna atau tujuan tertentu. Praktek ciuman yang demikian memiliki beberapa makna simbolik. Selain memiliki makna romantisme atau kasih sayang, juga simbol relasi kekerabatan dan persaudaraan yang harmonis.16 Karena itu dalam pergaulan sehari-hari, berciuman di tempat umum bagi orang Sabu entah di antara sesama jenis maupun beda jenis kelamin menjadi hal yang familiar. Jadi ia bukan suatu pornoaksi. Dalam konteks resolusi konflik, hengèd’u menandai rekonsiliasi atau pemulihan relasi. Yakni sebagai tanda kasih, penghargaan, penyesalan, ketulusan dan kerendahan hati, simpati dan bela rasa, permohonan maaf (ami huba) dan pemberian maaf (pehuba hala), antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini ciuman biasanya disertai adegan saling berangkulan, yakni dengan memeluk atau melingkarkan tangan di leher seseorang. Dengan cara demikian maka rekonsiliasi atau relasi yang harmonis (peha’u ade - penuhi penge) dirajut kembali.17 Tindakan simbolik semacam ini dalam perspektif budaya Sabu biasanya sudah cukup untuk menyingkapkan hasrat hati dan kata-kata yang tak terujar atau tak mampu diucapkan seseorang sehubungan dengan hasrat untuk berdamai. Selain hal di atas, agama dan budaya suku Sabu juga mengenal ritual simbolik berkaitan dengan rekonsiliasi yang disebut Penèta (memaniskan). Hal itu dilakukan manakala terjadi konflik yang berdampak pada terganggu atau rusaknya hubungan-hubuangan sosial dalam komunitas suku. Konflik dipandang bukan saja sebagai persoalan ketidakberesan yang mengganggu hubungan antara manusia, tetapi 16 Radja Rona, Wawancara, Kupang, 23 Agustus 2006. Kadangkala dalam penyelesaian suatu persoalan atau konflik, walaupun proses pembicaraan belum selesai namun bila ada pihak yang sadar dan merasa telah melakukan kesalahan maka ia akan dengan spontan bangun dan mencium pihak yang lain sebagai tanda pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Dengan cara demikian maka masalah dianggap telah selesai dan hubungan yang terganggu di antara mereka pada saat yang sama juga dipulihkan. 17 11 juga berakibat terganggunya hubungan dengan yang ilahi. Karena itu hubungan yang harmonis perlu dipulihkan. Pendamaian melalui praktek ritual-simbolik yang disebut penèta juga mencakup tindakan kultural berupa berciuman, dan persembahan korban kepada yang ilahi.18 Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa kultur pendamaian dalam masyarakat suku Sabu bersumber dari world-view tertentu yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan sosial, merawat dan memperbaiki relasi sosial (social healing) yang menunjang keberadaannya sebagai sebuah masyarakat komunal. Dalam pemahaman ini, upaya rekonsiliasi menekankan peranan manusia dalam hal ini pelaku kejahatan sebagai pengambil inisiatif untuk rekonsiliasi. Inisiatif yang demikian dilakukan dalam bentuk pengakuan kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Dalam pemahaman kultural tentang rekonsiliasi, hal mengakui kesalahan (tada hala), dan meminta maaf (ami pehuba hala) adalah hal yang amat prinsipil dan integral dalam setiap upaya rekonsiliasi kultural. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan kultural terhadap konflik dan rekonsiliasi lebih bercorak relasional dan simbolik atau ritual.19 Fokus dari penelitian ini adalah sebuah upaya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai, ideals, dan world-views tentang rekonsiliasi yang berakar pada kultur masyarakat lokal. Pendekatan semacam ini dalam rangka studi 18 Binatang yang biasanya digunakan adalah babi, domba atau ayam. Dalam bahasa adat, ritual untuk mempersembahkan babi sebagai korban untuk yang illahi disebut èki wawi natuu Deo artinya: mengikat atau mempersembahkan babi untuk Tuhan. 19 Lihat ulasan mengenai pendekatan ritual sehubungan dengan rekonsiliasi dalam tulisan Lisa Schirch, “Ritual Reconciliation: Transforming Identity/Reframing Conflict” dalam:Mohammed Abu-Numer (ed), Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice (Oxford: Lexington Books, 2001), pp. 145160. 12 teologi dapat dilihat sebagai sebuah upaya berteologi secara kontekstual, dengan menghargai perspektif budaya masyarakat, khususnya masyarakat suku Sabu di NTT. 3. Rekonsiliasi: Problema Teologis. Rekonsiliasi sebagai sebuah konsep teologis yang berakar pada kekristenan, dipahami sebagai suatu spiritualitas maupun strategi.20 Rekonsiliasi sebagai sebuah spiritualitas pada dasarnya dipahami sebagai karya Allah atau inisiatif Allah. Rekonsiliasi dan pengampunan dalam teologi Kristen diyakini bersumber dari Allah yang terjadi lewat hidup, pelayanan, dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Akan tetapi rekonsiliasi sebagai suatu gagasan teologis bukanlah hal yang berdiri sendiri. Ia berkait-paut dengan gagasan teologis lainnya seperti pertobatan, pengampunan, kebenaran, keadilan, dll. Secara teologis maupun sosial dan kultural, menjadikan rekonsiliasi sebagai instrumen penyelesaian konflik bukannya tanpa perdebatan. Perdebatan tersebut antara lain menghasilkan suatu paradoks pemahaman seputar rekonsiliasi, yakni apakah rekonsiliasi adalah prasyarat untuk pengampunan dan pertobatan ataukah sebaliknya? Dan apakah rekonsiliasi mengabaikan penegakkan kebenaran dan keadilan? Masalah ini juga menghasilkan semacam dikotomi sehubungan dengan peran Allah dan manusia dalam rekonsiliasi, terutama berkaitan dengan pertanyaan tentang dari manakah suatu tuntutan rekonsiliasi mesti berawal? Dan siapakah yang menjadi subjek yang tepat dalam sebuah rekonsiliasi sosial? 20 Robert J. Schreiter, The Minsitry of Reconciliation: Spirituality & Strategy (Maryknoll, New York: Orbis Books, 2003), pp. 3-22; 105-130. 13 Pertanyaan di atas mencerminkan apa yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Adanya ketegangan atau perbedaan persepsi berkaitan dengan rekonsiliasi bisa mendatangkan kebingungan bahkan pertentangan, yang pada akhirnya menghambat usaha-usaha dan pelayanan rekonsiliasi itu sendiri. Pada hemat penulis, pelayanan rekonsiliasi (yang berhasil) harus memperhatikan konteks maupun latar belakang religius, kultural maupun sosial yang ada. Setidaknya, pendekatan kultural yang menjadi fokus studi ini perlu diberi tempat yang proporsional. Inilah yang menjadi pokok kegundahan dan mendorong minat penulis untuk mengkaji permasalahan ini. Sehubungan dengan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan refleksi teologis terhadap rekonsiliasi dengan menggunakan narasi Alkitab yang relevan.21 Dalam rangka mengkaji permasalahan yang ada dibutuhkan cara berefleksi tertentu terhadapnya. Menurut Archie C.C. Lie, pendekatan yang relevan adalah metode hermeneutik lintas tekstual (cross-textual hermeneutics).22 Dalam perspektif ini perlu dilakukan kajian yang mendalam baik terhadap narasi-narasi budaya dan keyakinankeyakinan dasar agama suku, demikian juga halnya dengan narasi Alkitab tentang rekonsiliasi, kemudian mendialogkan atau mencari saling hubung antara keduanya sehingga diperoleh pemahaman rekonsiliasi yang kontekstual dan transformatif.23 21 Ada banyak rujukan dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama (PL) dan terutama Perjanjian Baru (PB) tentang rekonsiliasi, baik eksplisit maupun implisit, entah dalam bentuk ajaran, metafora atau perumpamaan, maupun tindakan simbolis lainnya seperti mencium dan merangkul. 22 Archie C.C. Lie, “Cross-Textual Interpretation and its Implication for Biblical Studies” dalam: Asnath Natar, dkk (penyunting), Teologi Operatif – Berteologi dalam Konteks Kehidupan yang Pluralistik di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm 8-9. 23 Dalam sebuah karangannya Robert J. Schreiter memahami upaya berteologi semacam ini sebagai Teologi Lokal, yakni sebuah interaksi dinamis (juga dialektis) antara Injil, gereja, dan budaya. Ia hendak menunjukkan kepekaan terhadap konteks dalam mana sebuah upaya berteologi dilakukan. Lihat bukunya, Rancang Bangun Teologi Lokal (Terj. Stephen Suleeman). (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), hlm 38. 14 C. JUDUL DAN PENJELASANNYA Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas maka tesis ini akan digagas dan dikaji di bawah judul: REKONSILIASI KULTURAL - Suatu Studi Terhadap Budaya Hengèd’u Suku Sabu. Berkaitan dengan judul tersebut, beberapa hal penting perlu dielaborasi sebagai berikut: 1. Rekonsiliasi Rekonsiliasi adalah sebuah terminologi yang punya padanan makna dengan kata “pendamaian” dalam bahasa Indonesia. Ungkapan tersebut aslinya berasal dari bahasa Latin, reconciliare (kata kerja), dan reconciliatio (kata benda), yang berarti: re-estabilishing mendudukkan (membangun kembali), kembali), restoration reinstatement (memugar, (menerima memulihkan), atau renewel (membaharui). Dalam bahasa Latin, penggunaan istilah ini amat luas dan bersifat umum. Ia dipakai dalam dunia sekuler maupun religius.24 Rekonsiliasi pada hekekatnya berbicara soal relasi atau hubungan, yakni menyangkut pemulihan atau pembaharuan hubungan yang terganggu, rusak atau terputus.25 Dalam pemahaman yang lain, rekonsiliasi adalah upaya membangun persahabatan dan perdamaian dengan menyingkirkan kebencian dan permusuhan sehingga terciptanya keutuhan (oneness).26 Jadi dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah upaya untuk merajut, merujuk, dan merukunkan kembali para pihak yang 24 Lihat juga: Th. Verhoeven, Kamus Latin – Indonesia (Flores: Nusa Indah, 1969), hlm. 1029. David Noel Freedman (ed.), Eermands Dictionary of the Bible (Michigan, Grand Rapids/UK, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000), p. 112. 26 Keith Crim (Gen. editor), The Interpreter’s Dictionary of the Bible (Suplementary Volume). (Nashville: Abingdon Press, 1984), p. 728. 25 15 berkonflik entah personal maupun komunal (sosial) sehingga relasi baru penuh damai dijalin kembali. 2. Kultural Kata kultural adalah kata sifat dari kata benda kultur atau kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, nilai-nilai moral, hukum, adat kebiasaan, dan hal-hal lainnya berupa kemampuan dan perilaku yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.27 Dari sudut yang lain, Koentjaraningrat memberi sebuah definisi sederhana yang menekankan pada tindakan manusia, bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.28 Polapola perilaku (behavioral patterns) itu dibentuk oleh nilai-nilai, ide-ide dan normanorma sebagai suatu sistem pemaknaan sosial. Jadi kebudayaan tidak hanya berupa kesenian dan adat-istiadat, tetapi termasuk nilai dan pandangan hidup (worldview). Dihubungkan dengan tema rekonsiliasi sebagai fokus dari kajian ini maka rekonsiliasi yang hendak dibahas di sini adalah yang berakar pada nilai-nilai, pandangan hidup, dan norma-norma budaya sebagai suatu sistem pemaknaan sosial yang sudah berakar dan inheren dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang menjadi fokus perhatian penulis adalah dimensi rekonsiliatif dari pendekatan atau praktek kultural dalam penanganan konflik. Atas dasar itulah judul tesis ini diberi nama: rekonsiliasi kultural.29 Dengan istilah ‘kultural’ juga hendak memberi batasan 27 Lih. Louis J. Luzbetak, The Church and Cultures – New Perspectives in Missiological Anthropology (Maryknoll: Orbis Book, 2000), p. 134. 28 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 5. 29 Johan Galtung menggunakan istilah “perdamaian kultural” sebagai hal yang menunjuk pada aspek-aspek suatu kultur yang menjustifikasi dan melegitimasi perdamaian. Jika dalam suatu kultur ditemukan banyak 16 bahwa wacana rekonsiliasi yang dibahas di sini adalah dalam konteks atau bingkai budaya. 3. Perihal studi atau tinjauan Dalam rangka studi ini penulis memakai refleksi teologis-etis yang didasarkan pada narasi Lukas 15: 11-32. Studi terhadap narasi ini sendiri merupakan upaya untuk memahami pesan dan nilai-nilai teologis-etis yang terkandung di dalamnya, dengan memakai metode tafsir kritis naratif. Sekalipun kata rekonsiliasi tidak disinggung di sini, penulis berasumsi bahwa perumpamaan ini memperlihatkan adanya nuansa tertentu sehubungan rekonsiliasi kultural seperti mencium dan merangkul (bdk. Kej. 33:4; 45:15; 2Sam.14:33), di samping karakteristik lainnya dari perumpamaan ini berkaitan dengan rekonsiliasi.30 Dengan melakukan hermeneutik lintas narasi diharapkan akan dijumpai saling hubung atau titik temu maupun titik pisah antara narasi Alkitab dan narasi budaya tentang rekonsiliasi. Seperti dikatakan oleh E.G. Singgih bahwa dalam rangka menghayati kebenaran Injil dalam budaya, mau tidak mau, upaya semacam ini melibatkan unsur konfirmasi dan konfrontasi di dalamnya, dalam mana yang menjadi patokan adalah berita keselamatan dan penebusan Kristus.31 Akan tetapi karena berita keselamatan dan penebusan mengandung elemen pembaharuan (renewal) yang berakar pada kebenaran Injil yang transenden maka terbuka peluang dan beragam aspek sejenis ini maka ia dapat disebut “kultur perdamaian”. Lih. Johan Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban (Terj. Asnawi dan Safruddin). (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 430. 30 Lihat antara lain: R. Alan Culpepper, The Gospel of Luke dalam: Leander E. Keck (eds), The New Interpreter’s Bible, Volume IX. (Nashville: Abingdon Press, 1995), pp. 300-304. Bnd. Miroslav Volf, Exclusion & Embrace, pp. 156-165. 31 Emanuel Gerrit Singgih, Berteologi dalam Konteks (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 28. 17 bagi kebenaran Injil untuk mentransendensi pemahaman budaya tentang rekonsiliasi.32 Karena itu studi ini akan mengarah kepada pendekatan yang bersifat transformatif. D. RUMUSAN MASALAH. Dengan memperhatikan deskripsi permasalahan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Sabu tentang rekonsiliasi, khususnya yang berakar pada narasi-narasi budaya dan worldview yang ada, sebagaimana nampak dalam budaya hengèd’u, dan mengapa hal seperti itu penting bagi rekonsiliasi? 2. Bagaimana memahami nilai-nilai teologis-etis dari perumpamaan Yesus dalam Lukas 15:11-32 sehubungan dengan rekonsiliasi, dan mengapa hal itu penting bagi rekonsiliasi? 3. Bagaimanakah hubungan pemahaman budaya tentang rekonsiliasi dengan narasi Injil dan pandangan teologis Kristen tentang rekonsiliasi, dan sejauhmanakah hal itu dapat memberi sumbangan dalam rangka upaya-upaya rekonsiliasi? 32 Lih. Charales H. Ktaft, Christianity in Culture: A Study ini Dynamic Biblical Theologizing in CrossCultural Perspective (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1981), pp. 113-115; 345-366. 18 E. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI. 1. Tujuan Penelitian. Dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: a. Menggali pemahaman dan worldview masyarakat suku Sabu tentang rekonsiliasi yang berakar pada narasi-narasi budaya dan religinya sebagaimana terejawantah lewat budaya hengèd’u dan tindakan ritualsimbolik lainnya. b. Memahami pesan atau narasi Injil tentang rekonsiliasi khususnya dalam konteks narasi perumpamaan Yesus dalam Lukas 15:11-32, dan mengapa atau sejauhmana hal itu penting bagi rekonsiliasi? c. Mencari hubungan pemahaman budaya dengan narasi Injil dan pandangan teologis Kristen tentang rekonsiliasi, dan mengupayakan pemahaman baru yang dapat dijadikan semacam paradigma alternatif dalam rangka upayaupaya rekonsiliasi. 2. Signifikansi. Studi tentang rekonsiliasi kultural dalam rangka studi ilmu teologi diharapkan tidak saja memberi kontribusi secara akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis. Karena itu kegunaan dari penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Memberi masukan dan memperkaya diskursus teologis bagi studi tentang rekonsiliasi di Indonesia dalam konteks keragaman budaya yang ada, kuhususnya bagi pengembangan teologi sosial yang kontekstual. 19 b. Memberi penyadaran dan dorongan bagi komunitas masyarakat khususnya suku Sabu untuk mencintai, menghargai, dan memelihara warisan nilai-nilai budaya luhur dan berharga yang mereka miliki. c. Memberi masukan dan membantu gereja dalam menjalankan misi dan pelayanan rekonsiliasi, entah dalam konteks GMIT maupun di tempat lainnya. d. Membekali penulis sehubungan dengan keterlibatan dalam tugas-tugas akademik, dan dalam pelayanan untuk rekonsiliasi di tengah jemaat dan masyarakat. F. METODE RISET DAN PENULISAN Penelitian merupakan usaha memahami fakta secara rasional empiris yang ditempuh melalui prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti.33 Dalam rangka menggarap penelitian ini, adapun rancangan dan prosedur penelitian dilakukan sebagai berikut: 1. Sifat dan jenis penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kebudayaan (baca: etnografi) yang disasarkan untuk mendapatkan pemahaman di balik fenomena atau kenyataan budaya yang diamati atau diindera secara langsung. Karena itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research). Dari sudut pandang penelitian kualitatif, proses memahami fakta sasaran penelitian selalu akan melibatkan apa yang disebut interpretatif perspective dan human experience.34 Upaya 33 34 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 1. Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan, hlm. 2-3. 20 untuk mendapatkan pemahaman yang demikian disebut juga dengan verstehen (pemaknaan), yakni memproduksi makna sebagaimana dihayati oleh seseorang atau sekelompok masyarakat.35 Dalam studi ini adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah kultur rekonsiliasi dalam masyarakat suku Sabu. Sesuai dengan sifat dari penelitian ini maka kajian terhadap masalah ini akan menggunakan pendekatan induktif-analitis, yakni telaahan yang bertitik tolak dari pandangan, perasaan, sikap dan perilaku masyarakat yang menjadi subjek penelitian. 2. Metode pengumpulan dan analisa data. Pengumpulan data penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara kreatif dengan menggunakan panduan pertanyaan yang menjadi pegangan penulis dalam penelitian. Karena sifat penelitian ini untuk menggali (probing) pemahaman dan pengalaman para nara sumber atas masalah atau pokok tertentu, maka pengumpulan data ditempuh dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview).36 Nara sumber akan dipilih secara purposive, yakni dengan memilih secara cermat para responden atas dasar kepentingan dan pertimbangan peneliti. Mereka terdiri dari: para pemangku adat, pemuka agama, pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat biasa. Nara sumber lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan perkembangan riset di lokasi penelitian. 35 Lih. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (Selected Essays). (New York: Basic Books Publishers, 1973), pp. 13-14. 36 Lih. Andreas Subagyo, Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif - Termasuk Riset Teologi dan Keagamaan (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), hlm. 228-232. 21 3. Lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di pulau Sabu. Penelitian dipusatkan di kelurahan Limaggu, Kecamatan Sabu Timur – Kabupaten Kupang, sebagai unit penelitian. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan: Pertama, Sabu Timur adalah salah satu dari lima wilayah kerajaan yang pernah ada di Sabu yang memiliki pranata sosial dan budayanya sendiri. Kedua, masih terdapatnya komunitas dan praktek adat yang secara kelembagaan dipimpin oleh para pemangku adat yang disebut dewan mone ama atau kètu rai. Ketiga, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di wilayah ini sehubungan dengan pokok kajian yang diangkat penulis. Keempat, pertimbangan praktis, penulis dilahirkan dan dibesarkan di Sabu Timur, karena itu memudahkan penulis dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan budaya setempat dalam rangka penelitian. G. KERANGKA PEMBAHASAN Penggarapan tesis ini dilakukan dengan menggunakan kerangka pembahasan sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisikan informasi umum sehubungan dengan desain penelitian yang mencakup: Latar Belakang Penelitian, Permasalahan dan Fokus Penelitian, Judul dan Penjelasan Judul, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Metode Riset dan Penulisan, Metode Pengumpulan dan Analisa Data, serta Tempat dan Waktu Penelitian. Bagian pendahuluan ini diakhiri dengan keterangan tentang Kerangka Penulisan. Bab II. Narasi tentang Rekonsiliasi dalam Kebudayaan suku Sabu. Bagian ini dimulai dengan Gambaran Umum lokasi penelitian, Dinamika Sosial Budaya, dan 22 Sistem Kepercayaan (Religi). Selanjutnya pemaparan tentang Rekonsiliasi Kultural. Setelah itu dilanjutkan dengan Analisa dan Tinjauan, kemudian diakhiri dengan sebuah Rangkuman. Bab III. Narasi Alkitab (Injil) tentang Rekonsiliasi. Bagian ini merupakan upaya pemahaman terhadap narasi Lukas 15:11-32. Kajian teks ini diawali dengan pengantar memahami Injil Lukas sebagai narasi, Tafsir naratif terhadap Lukas 15:1132, kemudian disusul dengan upaya untuk merumuskan makna dan pesan teologisetis di balik narasi yang ada. Lalu diakhiri dengan suatu rangkuman. Bab IV. Rekonsiliasi Kultural: Sebuah Perspektif Teologis Etis. Bagian ini berisikan dialog dan tanggapan iman Kristen mengenai rekonsiliasi kultural. Sifat tanggapan atau refleksi ini diarahkan untuk kepentingan upaya berteologi yang menghargai perspektif pemahaman budaya lokal sehubungan dengan rekonsiliasi. Bab V. Bab ini merupakan bagian Penutup dari studi ini. Bagian ini berisikan dua hal: Pertama, Kesimpulan atas hasil kajian dari tesis ini. Kedua, diakhiri dengan suatu Rekomendasi.