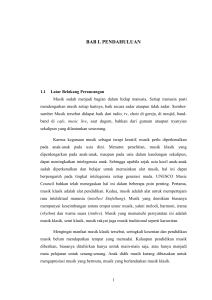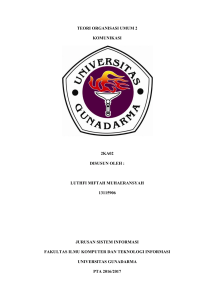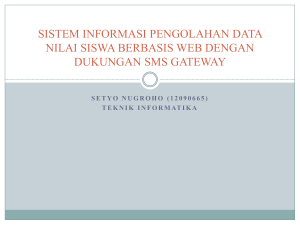short music service
advertisement

SHORT MUSIC SERVICE Prophetic Freedom Project adalah project yang membantu setiap orang untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk buku, film atu karya lain yang dapat diapresiasi publik. Project ini menghimpun sejumlah relawan yang terdiri dari penulis, desainer, seniman, editor dan tenaga profesional lainnya. Mereka siap berkolaborasi dengan Anda untuk mewujudkan gagasan dalam bentuk karya nyata. SHORT MUSIC SERVICE Refleksi Ekstramusikal Dunia Musik Indonesia Erie Setiawan SHORT MUSIC SERVICE Copyright (c) 2008 Erie Setiawan Penyunting Fahd Djibran Penata Letak Huda Albanna Perancang Sampul Fahd Djibran Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved Cetakan Pertama, Februari 2008 Diterbitkan oleh Prophetic Freedom Jln. Cilengkrang 2 No. 467 Bandung telp. +62 813 2265 6523 http://www.propheticfreedom.co.nr E-mail: [email protected] _____________________________________________________________ Setiawan, Erie Short Music Service / Erie Setiawan, — cet. 1 — Bandung: Prophetic Freedom, 2008 244 hlm; 21 cm ISBN 978-979-16818-9-6 I. Judul II. Setiawan, Erie _____________________________________________________________ Aku persembahkan untuk kedua orang tuaku, Yohanes Soewardi dan Fransisca Siti Handayati. Semoga berbahagia. DAFTAR ISI BUKU Pengatar Penerbit – xi Pengantar Sabrang Mowo Damar Panuluh – xiii Prolog: Sebuah Perjalanan Musikal – xv Ucapan Terima Kasih – xix Bab I Kepu(si)ngan Musik – 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SMS: Short Music Service – 3 Kepu(si)ngan Musik – 5 Andaikan Musik Manusia – 7 Dicari Penyanyi Fals – 9 Surat Untuk Piano – 13 Tom & Jerry – 17 Pesan buat Musik – 21 Cuma Musik, Kadang Itu Cukup – 23 Beethoven, Aku Mencintaimu – 25 Musik Barat, Dibawa Ke Barat? – 31 Musisi dan Ketegangan – 35 SMS: Short Music Service viii 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Fatamorgana Musika – 37 Ayo Ngamen! – 41 Cucak Rowo – 45 Adakah Musik Aneh? – 47 Kon(on)temporer – 49 Musik dan Kuda – 53 Akan Sepi Tanpa Mereka – 55 Gejala Baru: Semacam Kepungan Audio – 59 Rekor Musik: Perayaan Kuantitas atau Kualitas? – 61 21. A Tribute to Indonesia: Musik “Tragedi Aceh” – 63 Bab II Sekali Klik Dengar Musik – 65 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kritik Musik – 67 Selalu Terbuka Terhadap Kritik – 73 Soundscape Gaya Tony – 77 Persoalan (Ilmu) Musik – 83 Jagad Perbukuan Musik di Indonesia – 89 Jurusan Musik SMK N 8 Solo: Sejarahmu Kini dan Esok – 95 Jazz dan Selera Wong Solo – 101 Wadah Pecinta Jazz di Solo – 107 “Mendengarkan” Orska – 111 Piknik Musikal bersama Amari – 123 Surat Cintaku Buat Kiai Kanjeng – 133 Renungan 62 Tahun Musik Indonesia – 139 Menonton (Konser) Musik ? – 145 Kepadamu Seniman Jalanan – 151 Borobudur Live in Concert: Antara Potensi dan Politisi? – 155 Demonya Si Tukang Bonang – 165 Dari Sarasehan 'Jalin Bapilin': Hari Gini Ngomongin SMS: Short Music Service 18. 19. 20. 21. 22. ix Tradisi? – 171 Aneh, Musik Serius Jadi Guyonan! – 177 Rieko Suzuki : “Tak Cukup Memahami Notasi” – 181 Sekali Klik Dengar Musik – 187 Karya Baru Musik Keroncong – 193 Disco-nya Kaum Spiritualis – 197 Bab III Retrospeksi – 201 Retrospeksi – 203 Komentar Pembaca Pertama – 243 Tentang Penulis – 245 Pengantar Penerbit: Membaca Musik T elinga kita mungkin tak terlalu peka ketika mendengar seorang artis menyanyi dengan suara sumbang, terlalu tinggi, atau “keluar jalur”. Dan kita acuh saja. Seolah tak terjadi apa-apa, kita pun tetap memuji mereka sebab—seolaholah—mampu memukau penonton sampai jerit terakhir yang begitu histeris. Tapi tidak bagi Erie, telinganya selalu resah. Keresahan-keresahan itu lantas berubah gerutu, kemudian menjelma “kritik”, yang (pada gilirannya) ia tuliskan dengan khidmat menjadi sekumpulan esai yang kini berada di tangan Anda. Bagi kita (awam), alunan nada yang indah mungkin hanya lewat begitu saja di telinga. Membekaskan sedikit impresi pada memori. Lalu sudah. Tapi tidak bagi Erie. Baginya musik adalah keagungan yang, layaknya firman Tuhan, harus dijunjung tinggi. Baginya, mendengarkan keindahan itu, adalah kenikmatan yang tak sudah-sudah. Inilah yang akan Anda jumpai dari buku kumpulan esei pertamanya: refleksi, kritik, apresiasi, dan segala hal yang SMS: Short Music Service xii mungkin dituliskan seorang “pecinta musik” tentang musik—dunia yang baginya seperti segalanya. Maka akan Anda jumpai kekaguman, kekesalan, kemarahan, kegelian, keterpesonaan, penyesalan, dan pengharapan yang terasa begitu akrab dalam tulisan-tulisan refleksinya tentang dunia musik yang ia dengar, baca, hayati, dan jalani. Buku ini, sebagai sebuah refleksi ekstramusikal, adalah sebuah kerja intelektual musikolog masa depan yang patut diacungi jempol. Saya mungkin tak mengerti banyak soal musik, tapi Erie memberitahu saya banyak hal lewat buku ini. Mungkin banyak musikolog atau kritikus musik kelas wahid yang mengungguli kemampuan analisisnya soal musik, tapi sayang sekali tak banyak dari mereka yang menulis. Dalam tulisan-tulisan Erie saya bisa membaca keseriusan, kekhidmatan, dan intensitas menulis yang mengagumkan. Inilah yang tak habis-habis saya pujikan darinya. Pramoedya Ananta Toer mungkin akan sangat menyayangi Erie ketika melihat keseriusannya dalam upaya “merekam” gagasan-gagasan musikalnya dalam tulisan, seraya berkata, “Kau, Nak, paling sedikit kau harus bisa berteriak. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu takan padam ditelan angina, akan abadi, ampai jauh, jauh di kemudian hari… Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Akhirnya, tidak banyak buku yang secara khusus ditulis sebagai sebuah kritik sekaligus apresiasi pada jutaan nada yang setiap hari berseliweran di keseharian kita. Karena itulah, buku ini amat penting untuk dibaca. Selamat Membaca, tentu saja. Fahd Djibran Direktur Prophetic Freedom Project Catatan Pengantar Sabrang Mowo Damar Panuluh S epertinya tulisan ini adalah kumpulan pemikiran si penulis. Tulisan yang mencakup banyak hal yang terdistilasi di otak sang penulis. Si pecinta musik, yang belajar di sekolah musik dan sepertinya bernafas dengan “ritme ¾”, apapun itu maksudnya. Ketika musik menimbulkan reaksi kepada sebuah kesadaran, tulisan-tulisan di buku ini menimbulkan kesadaran pada sebuah reaksi. Mungkin kita akan sependapat (atau tidak), akan tertawa, akan meragukan, atau malah memaklumi kata-kata sang penulis sebagai sebuah bentuk kefrustasian yang (hebatnya) diakhiri dengan sebuah kesimpulan pemikiran. Dan, dengan reaksi itu, kita dipaksa untuk mengambil (tersadar) posisi dan sudut pandang yang jelas pada sebuah topik yang tidak setahun sekali muncul di otak kita. Musik, ternyata tidak sesederhana leyeh-leyeh memejamkan mata dan menikmati. Dari sudut pandang seorang pelajar musik, sebentuk alunan membuai harus melewati banyak gerbang pemikiran SMS: Short Music Service xiv dan kontemplasi. Dari sudut pandang seorang scholar musik, sebentuk alunan adalah representasi social standing seseorang di tengah society-nya. Dari sudut pandang seorang pemikir musik, sebentuk alunan adalah batu bata dalam pertumbuhan sebuah peradaban. Dari sudut pandang seorang pelaku musik, sebentuk alunan bisa jadi palette warna untuk menggambar hidupnya. Dari sudut pandang seorang penulis buku ini, kita diajak menaiki roller coaster ide, pemikiran, kontemplasi, dari sebuah kepala yang memakai kacamata bernada. Buku ini adalah “komposisi musik” yang indah dan menarik, walau tanpa nada. Ketika membaca buku ini, kita berkesempatan untuk (sesekali) tidak hanya menikmati musik, tapi mencoba memahaminya. Jakarta, 15 Januari 2008 Prolog: Sepenggal Perjalanan Musikal T atkala SMP, ketika bermain musik (band) pertama kali, tepatnya 1997, saya merasa ada yang aneh, “ada alam lain” yang tiba-tiba mengubah hidup. Sebelumnya, cita-cita saya adalah Rohaniwan, menjadi Pastur. Hampir setiap hari saya hidup menggereja, mengabdi pada Tuhan. Ketika awal mengenal musik, saya mulai bermain lagu-lagu agak cadas semacam Bush, Radio Head, Green Day, Nirvana, dan lainnya. Lama kelamaan, musik membuat saya semakin terlena, asyik dan tergiur. Lalu, gereja saya “tinggalkan” begitu saja, namun Tuhan tetap saya jaga baik-baik. Saya mengurungkan niat menjadi Pastur, saya memilih menjadi pemusik saja. Niat saya yang semakin tak terbendung menggiring saya menekuni pendidikan musik. Tahun 1999, SMKI Solo (sekarang SMK N 8 Surakarta), Jurusan Musik Diatonis, menjadi pilihan yang menurut saya paling tepat. Karena, untuk merantau ke Yogyakarta (Sekolah Menengah Musik), orang tua tak punya biaya. Mulailah babak baru kehidupan SMS: Short Music Service xvi (pendidikan) musik saya. Beberapa band saya bentuk semasa SMA. Ada yang khusus bermain lagu-lagu Mr. Big, Slank atau God Bless, sembari mempelajari teori musik, membaca notasi dan mendengar. Semua saya nikmati. Pekerjaan saya berkelana, main musik kesana kemari. Berguru kemana pun. Ikut lomba. Juara. Sempat terbesit keinginan selintas menjadi artis. Setelah berbagai pentas saya jajaki, akhirnya saya menemu bosan juga. Pekerjaan saya berkelana itu ternyata malah berhadapan kepada kondisi yang semakin serius saja. Saya urung jadi artis (pop). Lalu seorang guru memotivasi saya untuk belajar musik klasik (gitar), dan menyarankan agar belajar ke perguruan tinggi musik. Saya pun menyanggupinya. Kota yang paling dekat dengan Solo, yang ada perguruan tinggi musiknya, tentulah Yogyakarta. Tahun 2002 saya mendaftar ke Jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan langsung diterima. Lagi-lagi, babak baru dimulai kembali. Saya dihadapkan ke arena yang padat. Arena yang berisi banyak kepala. Arena yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kegiatan main band saya tinggalkan begitu saja, seperti ketika saya “meninggalkan” gereja. Namun, meskipun main band saya tinggalkan, “roh dan jiwa” nge-band saya tetap tertinggal di Solo. Saya berpikir, suatu ketika, saya akan kembali mengambil “roh dan jiwa” itu lagi. Di Yogyakarta, mulailah saya belajar musik klasik. Setiap hari latihan 8 jam. Ikut konser. Ketika itu, saya sangat mencintai gitar klasik dan pernah berkeinginan menjadi gitaris klasik terkenal seperti John Williams, Julian Bream, Andres Segovia, dan lainnya. Waktu terus berjalan. Ternyata saya (malah) tidak menemukan kepuasan apa-apa terhadap gitar klasik. Gitar yang saya punyai ketika itu cuma seharga seratus ribu. Hasil pesanan dari seorang pengrajin gitar di Baki Sukoharjo. Jelas SMS: Short Music Service xvii tidak mungkin sebagai modal menjadi gitaris profesional. Tidak punya modal apa-apa. Saya urung lagi. Mengurungkan niat menjadi gitaris klasik. Kembali lagi saya merasa bosan, dan bahkan merasa benci, pada gitar klasik. Saya pindah haluan. Kegemaran saya adalah menonton bermacam jenis pertunjukan kesenian dan membaca buku apa saja. Setiap hari, daripada latihan gitar, saya lebih memilih ke perpustakaan, membaca sampai siang. Rekreasi keliling dunia lewat buku. Kadang-kadang kuliah saya tinggalkan, sengaja tidak masuk. Tibalah saya di babak yang semakin baru. Ratusan buku yang saya baca menyeret saya ke dunia yang lebih terasing lagi dari bunyi-bunyian, meskipun saya tetap mendengarkan musik dan “nyanyi-nyanyi” setiap hari. Saban hari, yang berkumpul mengadakan “arisan” di otak saya hanyalah ribuan teks dan rumusan-rumusan ilmu. Buku, terutama filsafat, membawa saya ke alam pemikiran yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Mulailah saya jadi pembaca. Biar lebih lengkap, saya menulis. Saya berangkat sendiri, hujan-hujan, naik sepeda, mendatangi seminar, diskusi, sarasehan, yang saya harapkan semakin memacu pertumbuhan pemikiran saya sepulang mengikutinya. Dari situlah semangat tumbuh, berbagai tokoh saya kenal, yang musik maupun yang bukan. Saya dihadapkan pada rimba yang lebih luas lagi bernama kesenian dan kebudayaan. Saya semakin bingung. Jika saya flash back, ini tentu berbeda dengan kegiatan-kegiatan saya sebelumnya. Tetapi biarlah, saya masih menikmatinya. Akhirnya saya pun membaca banyak buku dengan keras. Output-nya saya pakai buat menulis, mengajar, membuat komposisi musik, ceramah, dan memberi prasaran kepada murid-murid di SMK N 8 Surakarta dan teman-teman pemusik. SMS: Short Music Service xviii Sampailah saya saat ini pada dunia yang jauh dengan sebelumnya. Saya juga tidak sadar, (kenapa) perjalanan saya sampai di dunia pemikiran (musik). Dunia yang benar-benar memeras otak. Membuat kerut di wajah bertambah setiap harinya. Muka semakin menua, dan lainnya. Tetapi lagi-lagi, dalam “ketidaksadaran” itu saya tetap menikmatinya sebagai sebuah pencarian yang belum selesai. Saya juga tidak tahu, apakah ini jalan yang akan saya tekuni di masa depan. Atau jangan-jangan saya bosan dan banting stir lagi? Saya tidak mengerti dan tidak berhak menjawab pertanyaan ini. Buku yang ada di tangan Anda ini adalah bunga rampai, kumpulan tulisan (musik) yang terkumpul dan sudah diseleksi dari tahun 2003-2008. Sebuah kegelisahan yang berkepanjangan. Ada artikel surat kabar, makalah ilmiah, makalah ceramah, diskusi, esai, dan, sebagai bonus, saya tulis juga catatan belajar (curhat) saya pada kampus tercinta; yang tak henti-henti menuntun saya untuk percaya diri. Menjadi pemusik atau apa saja bukan menjadi persoalan buat saya. Saya hanya ingin menjadi salah satu bagian dari ratusan ribu pecinta musik di Tanah Air. Dan inilah salah satu sumbangsih saya untuk kehidupan musik. Demikianlah pengantar singkat. Harapan saya setelah Anda membaca buku ini adalah kritik. Buku ini masih sangat jauh dari sempurna. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin dan terima kasih. Selamat Membaca. Prancak Glondong, 18 Januari 2008 Ucapan Terima Kasih B uku ini tidak bisa hadir di hadapan pembaca sekalian tanpa bantuan banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati, secara khusus, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, para perantau dari Probolinggo, Bandung, dan Tegal. Mereka adalah M. Nizar, Fahd Djibran dan Huda Albanna (Prohetic Freedom). Ketiga orang cerdas itulah yang membuka “pintu gerbang” sehingga buku ini bisa terbit. Mereka pulalah yang banyak memberi dukungan, motivasi, pelajaran dan kesempatan mengenal dunia (buku) lebih luas lagi. Sungguh, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Kepada Dr. Djohan Salim, M. Si., yang bersedia meluangkan waktu membaca dan membersihkan “virus” di naskah saya, juga atas saran, komentar, pelajaran, dan nasihat psikologis yang begitu berarti bagi saya. Tidak hanya demi buku ini, namun demi pergulatan pemikiran dan intelektual saya. Mas Agus Bing, sosok motivator yang tak henti-hentinya SMS: Short Music Service xx memberi saya dukungan, dorongan dan kritik yang sangat membangun. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk membaca naskah dan memberi komentar untuk buku ini. Mas Sabrang, terima kasih juga buat komentarnya yang teramat puitis. Semoga buku ini bisa menjadi media dialog (wacana) antara kita berdua yang berbeda “rel”. Cornelius Prapaska, secara khusus saya berterima kasih untuk bantuannya. Kepada sahabat, guru dan seteru intelektual saya Gatot D. Sulistiyanto, atas ilmu, saran, komentar, kritik, dan kerendahan hati dalam setiap pergumulan berbagi cerita dan wacana. Seluruh civitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Para dosen Jurusan Musik dan kepada siapa saja yang pernah membimbing proses belajar saya. Mereka adalah inspirasi terbesar yang menjadi stimulus perubahan paradigma berpikir saya tentang musik. Sahabat-sahabat di Forum Studi Musik Turanggalila dan Jurasik Today. Tanpa mereka otak saya layu dan tidak subur. Sahabat-sahabat terdekat saya, yang menemani saya saban hari, yang selalu membaca dan memberi evaluasi tak henti buat diri saya dan naskah-naskah saya; Heryandi, Jamlikun, Muslim. Terima kasih banyak. “Yo'i Coy...” Kepada rekan-rekan yang selalu saya repoti, yang menemani saya menulis, yang motornya selalu saya pinjam untuk bolak-balik mengurus naskah ke Gamping; Apri, Saman, Dewi Simbolon, Nona, Putri. Kepada para maha-guru Suka Hardjana, Amir Pasaribu, R.A.J. Soedjasmin, R.M. Suhastjarja, F.X. Sutopo, J.A. Dungga, L. Manik, Binsar Sitompul, Sumaryo L.E., Remy Sylado, Slamet Abdul Sjukur, Karl. Edmund Prier SJ, Prof. Dieter Mack, Prof. Dr. Victor Ganap, Prof. Dr. Rahayu Supanggah, Dr. Suhardjo Parto, Triyono Bramantyo, Ph.D, Dr. Sunarto, Franki Raden, Sutanto SMS: Short Music Service xxi Mendut, Ponoe Banoe, Royke B. Koapaha, I Wayan Sadra; lewat tulisan-tulisan maupun ceramahnya saya mengenal ribuan hal tentang musik, mulai dari sejarah, filsafat, teori, wacana, kritik sampai berbagai polemik. Ternyata musik tak seindah menikmati pemandangan alam. Tak seindah yang orang awam kira. Musik juga bisa berontak, mengamuk, murka, marah, seperti gempa dan badai. Para tokoh-tokoh itulah yang membuat saya merenung tiada habisnya, selalu restart dan re-start lagi, berpikir ulang dan refleksi. Kepada Emha Ainun Nadjib, atas tulisan dan ceramah yang belakangan memberi inspirasi luar biasa. Kepada dua sahabat, Drs. Robertus Suryadi dan Dany Wijayanto, atas dukungan, motivasi, kritik, dan guyonanguyonan yang “gila”. Juga kepada teman-teman band saya: Soro' Band dan Blue Skin, terima kasih untuk dimensi bunyibunyiannya. Teramat khusus, kepada kedua orang tua saya (Yohanes Soewardi dan Fransisca Siti Handayati). Beliau mengajarkan selama bertahun-tahun tentang ilmu kesabaran, cinta kasih, kekuatan, yang membuat saya selalu berkaca, belajar dan introspeksi. Kedua orang tua selalu hadir, menjelma menjadi motivasi yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kedua kakakku tercinta, Aris Sumantri dan Hengky Hernawan, atas kerelaannya memberikan rejeki dan dukungan buat saya untuk menerbitkan buku ini. Sebagai puncak rasa syukur, kepada yang memberiku nafas dan akal budi. Tuhan Yesus Kristus maha-segala di atas segalanya. Buku ini saya dedikasikan kepada semua orang yang mencintai musik, di mana saja mereka berpijak; di “aliran” mana saja mereka bermusik. Bab I Kepu(si)ngan Musik SMS: Short Music Service K ehidupan musik yang baru kemarin terjadi, atau sudah ribuan tahun silam, terus membayangi peradaban ini. Musik menemui dinamikanya sendiri yang unik. Ratusan, bahkan ribuan tokoh berperan dengan berpikir dan berkarya demi kecintaan pada musik—yang merupakan wahyu tak ternilai dari yang tak pernah terjamah. Jika musik disebut kehidupan, berarti ada nyawa dan pemikiran yang terus berlangsung. Para tokoh dan pemikir musik memberikan kontribusi melalui pelayanannya masingmasing. Ada yang sangat lelah berpikir sampai tua. Ada yang hanya berkarya sekali, lalu mati. Ada yang mati muda seperti Cornel Simanjuntak. Ada pula tokoh yang sampai sesudah kematiannya pun tetap membawa kemenangan abadi dan berkah tak ternilai bagi dunia musik; sebut saja Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ia disebut Bapak Musik Dunia karena karya-karya musiknya yang luar biasa. Kita lewatkan saja yang telah lalu. Saat ini, semua menyadari segalanya telah berubah. Perubahan-perubahan SMS: Short Music Service 4 itu terjadi karena ulah manusia juga, bukan kesalahan musiknya. Bertahun-tahun, berabad-abad, manusia selalu semakin pintar dalam segala hal, mampu berinovasi, mencipta teknologi, memanipulasi dan memanfaatkan musik untuk berbagai kepentingan. Ada kepentingan positif, ada kepentingan negatif. Kepentingan positif adalah memanfaatkan musik tanpa tendensi apa-apa selain menghargainya sebagai proses kebudayaan. Yang negatif adalah yang menguntungkan satu pihak, namun menyengsarakan banyak pihak. Semua manusia berhak menikmati musik, juga berpikir tentang musik. Karena sesungguhnya, musik tidak dimiliki siapa pun. Manusia hanya akan terus-menerus menjadi “pemakai musik” yang mencurahkan energinya sesuka hati demi pemuasan-pemuasan batiniah dan klimaks lahiriah yang tak kunjung usai. Manusia hanya menjalankan musik dan (sejatinya) tidak pernah menciptakan musik. Manusia hanya hidup singkat, seperti SMS. Jika semua manusia mampu berpikir tentang musik, walau singkat-singkat, hal ini akan membawa pengaruh bagi kehidupan dan pertumbuhan musik. Jika semua manusia tidak pernah mau berpikir tentang musik, walau singkatsingkat, hal ini hanya akan menjadi kumpulan kotoran dan bangkai yang meracuni peradaban. Biar adil, setiap manusia tidak perlu berpikir banyakbanyak tentang musik, cukup singkat saja seperti SMS. Pemikiran-pemikiran singkat yang terkumpul dari ribuan manusia itu akan menjadi bunga rampai yang akan menjamin masa depan musik menjadi lebih baik dan bernilai, bukan membawanya ke kondisi yang lebih carut marut dan berantakan. Yogya, 15 Januari 2008 Kepu(si)ngan Musik I ni soal ruang dengar yang terhubung dengan masalah etnisitas, tak pernah terjangkau: terasa aneh dan sangat aneh. Ini dan itu, ada jangkauan kosmis, yang menandakan bahwa musik juga bisa menyoal alam, bisa bersumber darinya, berjajar satu baris dengannya, koheren. Bahkan menjadi seperti jelmaan, wujud serupa yang tak pernah tampak aslinya. Ini memungkinkan kita mendeteksi betapa uniknya musik, tak pernah selesai dirumuskan dan disampaikan melalui teori kata-kata. Sepertinya, musik hanya menarik untuk didengarkan, dirasakan, atau dihayati saja, karena barangkali itulah dimensi sesungguhnya. Misteri. Kekuatan intuisi atau penerjemahan batin kita mewariskan atas adanya apresiasi, juga kreativitas yang membahana. Bukankah mustahil kita menganggap musik itu sama sekali tidak berarti apa-apa kecuali sekadar ilusi-ilusi yang tak pernah selesai dibicarakan. Mendengar musik untuk kesekian kalinya bagi telinga. SMS: Short Music Service 6 Ratusan. Ribuan. Mendengar banyak musik, apalagi bermain banyak musik, menangkap berbagai maksud. Ada banyak selera yang masuk ke kuping, ke imaji, ke hati, sampai ke masalah lain, jiwa misalnya. Pandangan kita terarah pada sesuatu yang tak pernah selesai dibicarakan. Lagi-lagi tak pernah selesai. Itulah musik, terus terang saya dibuat pusing olehnya. Benar-benar dibuat pusing. Ini salah saya kenapa saya memilih mencintai musik, bukan yang lain. Andaikan Musik Manusia S ebenarnya tidak ada masalah, di dunia ini orang mau pilih musik apa, main musik apa, maupun jatuh cinta pada musiknya siapa. Toh, seperti kejatuhan hujan yang turunnya membawa akibat macam-macam: bisa berkah bisa bencana. Hadirnya musik tanpa kita tahu sejarahnya pun—cukuplah menjadi menu yang kita nikmati setiap saat: pagi siang sore malam. Kita menikmati musik tanpa tendensi apa-apa, sama seperti menghirup udara, bernafas—kadang-kadang kita juga tidak menyadari kita ini sedang hidup bersama jutaan manusia di dunia yang saling mencemooh satu sama lain. Andaikan musik manusia, ia tidak akan menginginkan dinikmati (hanya) oleh status sosial tertentu. Musik akan marah jika cuma dinikmati segelintir orang saja, yang katanya ekslusif, elit, borjuis, dan lain sebagainya. Musik bisa jadi akan menjadi murka dan marah karena dikotak-kotakkan—tidak dibaurkan pada siapa saja. Padahal, manusia—sebagai inti berbaurnya roh, jiwa, dan akal budi—merasa merindukan musik sebagai buah-buah segar yang jatuh dari langit. SMS: Short Music Service 8 Hadirnya membawa lapar jadi kenyang, membawa ketenangan hati, keteduhan pikiran, kenyamanan, sampai pada urusan psikologis yang terlampau jauh dan kadang tidak masuk akal. Andaikan musik manusia, ia pasti menginginkan demokrasi, kebebasan berpendapat. Makanya muncul kolaborasi, musik Barat kawin dengan musik Timur misalnya. Tidak masalah banyak terjadi kegagalan dialog. Banyak ahli menyangka, misalkan saja, diatonis dan pentatonis itu secara hukum tuning amatlah berseberangan. Namun pada kenyataannya, Manthous pun menggabungkan ini dan laris manis. Cak Diqin bagai Dewa di tengah masyarakat primitifprimordial penggila campur sari. Musik satu dan yang lain cuma ingin berdialog. Perbedaan yang dimiliki ya sama seperti perbedaan manusia negara A dan negara B. Untuk bisa enjoy berdialog ya butuh pembiasaan, cara, dan adaptasi tertentu, tho? Ini pun, bukan urusan selera yang berbeda—namun secara kodrati—musik itu milik siapa saja dan berhak pula dinikmati siapa saja. Makanya, saya memilih dengar musik apa saja. Harapannya, ada sesuatu yang unik di kuping. Bercampur. Menggelitik. Mengoyak-ngoyak. Saya tidak pernah punya hasrat membeda-bedakan musik. Nanti seperti ada kecemburuan individu di dalam hati. Toh, secara hakiki, bendawi, spiritual, budaya, musik bukan milik kita. Buat apa diperebutkan? Bukankah itu sama seperti kita memperebutkan alam semesta? Solo, 11 Desember 2007 Dicari: Penyanyi Fals “Hak setiap orang untuk menyanyi meski suaranya pas-pasan atau fals sekalipun. Dan lewat kompetisi menyanyi, mulai yang serius macam Indonesian Idol hingga hiburan seperti Selebriti Jam, kesukaan orang menyanyi itu diakomodasi. Mau jadi penyanyi sungguhan atau iseng, silakan.” (Kompas, 6/01/08). P aragraf di atas saya kutip persis sama dari koran yang barusan saya baca. Isinya memang “demokratis” —intinya—siapapun boleh nyanyi. Sumbang tak jadi soal. Bahkan, sebelum kontes hiburan “ngawur-ngawuran”, semisal Supermama (Indosiar) muncul, suara sumbang, fals, parau, sengau, tidak pas—di Indonesia ini sudah laku sejak dulu. Lihat saja setiap hari berapa ribu pengamen memanggungi konstelasi jagad raya ini. Tidakkah sebagian besar di antara mereka bernanyi fals? Namun hasil “kerja keras” mereka tetap menuai rejeki. Itu artinya, suara tetap laku meski dihargai seratus perak dengan menodong tombak. SMS: Short Music Service 10 Memang nasib para pengamen (jalanan) tak seberuntung Iwan Fals dan Doel Sumbang—yang dari namanya saja sudah sangat komersial dan menjual. Mereka berdua memakai nama tipuan untuk “menipu”. Pada kenyataannya suara Iwan Fals itu tidak fals; dan Doel Sumbang juga tidak sumbang. Yang harus diingat, bahwa yang meramaikan panggung permusikan (di) Indonesia ini sebetulnya semua pengamen. Dari genjrang-genjreng di bis kota, kafe, hotel, restoran, panggung, sampai di tingkat artis kawakan sekaliber Ahmad Dhani pun, mereka semua pengamen. Penjaja suara. Penampung recehan, entah sekeping atau yang berlipat ganda seratus kali. Maka dari itu, Indonesia ini—bahkan di Negara belahan dunia mana pun— boleh saja disebut Negara Pengamen. Lalu apakah fals sudah tidak lagi menjadi soal? Pertanyaannya kemudian, adakah undang-undang yang mengatur lalu-lintas musik di Negara ini? Apakah dengan bernyanyi fals orang bisa terjerat hukum? Adakah Negara menjamin sakralitas musik dengan tidak membiarkannya diamini begitu saja oleh siapa saja, sampai di tingkat disepelekan menjadi, katakanlah, fals tidak masalah? Apakah musik sudah menjadi mainan yang bisa dengan sembarangan ditiup seperti gelembung sabun? Ya, Tuhan, baru kali ini aku melihat dan mendengar kacaunya sikap orang akan seni dan kebudayaan. Kacaunya orang yang tidak menjaga buah-buah perenungan dan nilai perjuangan para perumus dan pemikir musik. Hilangnya sakralitas musik—yang berubah menjadi 100% hiburannya para rakyat yang disopiri pedagang (mafia) di media. Oh, betapa tidak kuasanya aku menyimak sakitnya peradaban ini. Betapa sedih dan sakit. Di setiap lini, bangsa ini membutuhkan semangat demokrasi, yang kurang lebih bermaksud memperjuangkan kebebasan berpendapat, mencari ilmu, nafkah, dan kebebasan apa saja yang mengangkat derajat, harkat, dan SMS: Short Music Service 11 martabat bangsa—membawa kemajuan. Demokrasi itu sungguhlah suatu angin segar yang melepaskan bangsa ini dari penat masa lalu. Menjadi plong menghirup udara segar sebebas-bebasnya. Meski Negara ini kuat dengan segala aturan hukumnya (walaupun kesulitan menjalankan), namun bangsa ini adalah bangsa yang sudah merdeka secara komunikasi, meskipun belum secara lahir batin. Begitu pula dalam lini menyanyi. Apakah musik itu membutuhkan demokrasi semacam itu? Apakah kebebasan lantas dibikin menjadi pembebasan atas segala hal? Ekses yang ditimbulkan adalah: bernyanyi sumbang pun menjadi hak. “Tidak masalah, bung!”. Tunggu dulu. Bahwa sangat beruntung, para pedagang dan mafia industri musik di balik acara hiburan instan yang asal itu tak pernah tahu siapa Zoltan Kodaly. Anda yang membaca tulisan ini juga belum tentu tahu siapa tokoh musik asal Hongaria itu? Bahwa sekali lagi, sangatlah beruntung orang yang tidak mengenal Zoltan Kodaly. Saya pun menjadi orang yang tidak beruntung karena saya mengenalnya, meski cuma lewat buku. Zoltan Kodaly (1882-1967), salah seorang tokoh musik yang jadi kiblat di dunia pendidikan musik, dalam fatwanya yang amat terkenal mengatakan, “dasar dari pendidikan musik adalah bernyanyi”. Ia juga sekiranya menyarankan, berlatihlah bernyanyi dengan baik, hindari fals. Ahhh... Kuping saya ini apa masuk dalam kategori kuping sensitif? Yah, bisa jadi. Taruhlah misalnya begini, jika saya dengar orang (artis) bernyanyi fals—apalagi yang di tivi-tivi komersial itu—kuping saya langsung panas. Saya mbatin, yang kayak begitu-itu kok ya laku, tha? Masih mending jika saya naik bis keliling kota dengar pengamen jalanan nyanyi fals. Masih mending dan langsung saya beri uang receh. Karena pengamen jalanan itu tak pernah punya motif apa-apa dan jujur dalam bekerja. Lha kalau artis-artis itu sukanya kan SMS: Short Music Service 12 menipu. Di rekaman bagus, tapi suara aslinya sebenarnya jelek. Kalau nyanyi live ternyata juga fals. Berbohong, kan? Yang mau latihan nyanyi dengan baik dan benar, solehah, taat, teratur, ikut normanya, paling-paling cuma 10% saja. Sisanya adalah orang-orang yang tidak suka perjuangan. Tidak suka berdarah-darah. Sering berpihak pada hasil saja. Para artis, selebritis atau orang biasa (produser) yang bergejolak di acara nyanyi-nyanyi instan apa saja itu bermotif dan bermodus, dan bilang dengan amat meyakinkan bahwa mereka itu memajukan dan meramaikan kehidupan musik Indonesia. Buat saya tak ada bukti apa-apa. Wong yang namanya kemajuan itu kan dicapai dengan kerja keras, sungguh-sungguh, tidak hiburan apalagi main-main. Lha wong nyanyi saja sumbang, parau, keplintir, tidak akurat, bindeng, sengau, tidak pas saja kok mau ikut memajukan bangsa.Walah-walah, aneh-aneh saja sampeyan itu! Akhir kata saya cukup punya satu pertanyaan buat Anda semua, para pelaku instan: bukankah menjual suara fals di tivi itu sama saja seperti menjual nasi yang belum tanak? Kalau perut Anda tidak sakit berarti Anda hebat, maka sebaiknya saya memilih berguru kepada Anda saja, bukan kepada Zoltan Kodaly. Yogya, 6 Januari 2008 Surat Untuk Piano K epadamulah, piano, aku bertumpu. Aku belajar mendengarkan (Solfes) pertama kali atas bantuanmu— mumpung kamu ada dan lahir di dunia. Di dalam Solfes, yang senjata ajarnya piano, aku kenal progresi akor, pitch, melodi, tangting-tangting ritme, dan lainnya. Terutama saat guru mata pelajaran Solfes di SMA ku—Mursid Hananto, S.Sn— mengenalkan aku akan pelajaran yang sangat menyenangkan itu. Piano, kamu kupercaya sebagai yang maha-nada, tabungan registermu banyak sekali, wawasanmu luas, dan kepadamulah aku bisa mengenal “nada-nada ikutan” (overtone series)—yang kata dosen Ilmu Harmoniku, Y. Edhi Susilo, S.Mus, M.Hum, “inilah gambaran alam semesta.” Meskipun aku tak paham maksudnya. Kepadamulah, piano, aku pasrah saja. Namun kamu bukan bencana alam dan bukan sang Khalik. Aku pasrah karena kamu instrumen maha-segala. Aku mengenalmu dari ratusan gambar komponis, yang selalu berfoto bersama piano. Franz Liszt misalnya, adalah “dewa” yang menekunimu hingga SMS: Short Music Service 14 Tarentella yang gagah tercipta. Atau Claude Debussy dengan Clair de lunenya yang amat indah dan manis. Kamu, wahai piano, membantu para komponis untuk “uji coba” nada, harmoni, melodi—sebelum mereka bikin komposisi. Kepada piano para komponis berpasrah, selanjutnya ia meracik dan menekuni karya-karyanya. Piano, kamu membuatku pasrah, kamu alat musik yang multi-guna, punya banyak manfaat. Aku tak kuasa menghunuskan kritik padamu. Pokoknya aku pasrah. Kamu mau bagaimana aku tetap ngikut dan manut. Kepada piano: aransemen, orkestrasi, transkripsi, para kreator musik perlu bantuanmu. Ada surat permohonan bantuan dilayangkan kepada yang terhormat: piano. Dibubuhkan tanda tangan dengan asli pakai tinta gelap. Pianonya merk apa saja tak masalah. Yang penting 7 oktaf, tidak fals. Untuk tahu luasnya ragam bentuk register, rendah sampai tinggi, tengah ataupun yang bergemuruh di pojokpojok, bisa ditemukan di piano—tidak yang lain. Aransemen, orkestrasi, transkripsi, akan selalu lebih mudah karena piano menolong, menyelamatkan, membantu. Tak masalah, jika ada piano, semua beres, minimal pekerjaan menjadi lebih mudah. Sampai pada suatu ketika, entah kenapa, aku mendadak protes pada piano, tiba-tiba jengkel. Saking jengkelnya aku lalu menulis surat untuknya. Kepada Ytc. Piano “Piano, kenapa aku tak pernah melihatmu dimainkan oleh dosen-dosenku yang mengajar piano? Dimainkan dalam suatu resital tunggal? Kenapa kamu tidak berontak? Kenapa kamu diam saja? Piano...tolong jawab pertanyaanku! Kenapa kamu memilih sembunyi dan lari dari tangan-tangan mereka, para dosen-dosen piano itu? Kenapa kamu diam saja ketika kamu tidak ditekan, tidak dipijit, tidak diinjak, tidak dibelai, tidak SMS: Short Music Service dipeluk, tidak diraba, tidak dipilin. Kenapa kamu memilih diam saja? Apakah para dosen-dosen yang memilih kamu sebagai kekasihnya sudah lupa daratan? Dan membiarkanmu terdiam begitu saja, tidak mengajakmu jalan-jalan, pergi, disaksikan banyak orang? Ditepuki banyak orang? Piano!! Kenapa aku harus protes padamu, kenapa kamu tidak marah ketika para dosen piano tidak menyentuhmu lagi? Setidaknya dalam lima tahun terakhir, tak satupun kulihat resital, yang disitu ada kamu dan dosen mayor piano sedang membelaimu! Piano, apakah kamu sudah tidak cinta lagi kepada yang memilihmu jadi istri, jadi suami? Ataukah, yang memilihmu sudah tidak mencintaimu lagi? Piano... Jawablah!! Kalau tidak lebih baik aku mati...” 15 Tom & Jerry A da seorang teman, sebut saja namanya Ahmad, bertanya pada saya, “Musik apa yang kamu pelajari di kampus?” Saya menjawab, “Musik klasik.” (Toh, pada kenyataannya saya tidak begitu serius mempelajarinya, perjalanan saya lebih banyak melenceng dan tertarik ke ilmu lain). Ahmad melanjutkan lagi, “Musik klasik itu yang seperti apa?” Meladeni orang awam yang tak tahu musik klasik seperti Ahmad, saya musti ekstra hati-hati dan tidak boleh menjawab secara formal—karena pasti—Ahmad tak akan mengerti. Lalu saya bilang begini, “Klasik itu ya bukan yang kayak di tivi-tivi itu. Bukan Peter Pan atau Krisdayanti. Klasik itu musik yang sudah sangat kuno, sebelum tivi dilahirkan. Biasanya difungsikan orang awam untuk menghantar tidur. Jika kamu nonton film kartun semacam Tom & Jerry, nah, di situlah biasanya ada latar belakang musik klasiknya.” Maklum, ngomong dengan tukang potong rambut Madura yang polos seperti Ahmad ini harus dengan penjelasan yang SMS: Short Music Service 18 bisa menjelaskan. “O....Ya, ya. Aku tahu”, jawab Ahmad dengan yakin. Lalu ditambahkannya lagi pertanyaan, “Berarti kamu bisa dong bikin musik buat iringan film kartun?” Ahhh, dasar Ahmad! Jawaban saya yang panjang tadi seperti jadi bumerang. Saya menjawab terus terang saja, “Tidak bisa.” Ahmad menimpali, “Lha, terus buat apa kamu kuliah musik?” Ahhh, sekali lagi, dasar orang Madura satu ini! Tapi saya tidak menyerah untuk menjawab pertanyaannya yang makin seru. “Ya buat cari duit kalau sudah lulus.” Ahmad mengangguk tapi mukanya dikecuti rona penasaran. “Berarti kamu jadi artis saja, duitnya bakalan banyak!” Haha. Saya ketawa sendiri. “Bukan, bukan, saya tak mau jadi artis. Saya mau jadi orang biasa saja, kok.” Ahmad sedikit ketawa, dilanjutkannya lagi obrolan. “Lha, terus, kalau kamu belajar musik klasik dan tidak bisa bikin musik klasik seperti musik Tom & Jerry itu, terus kamu bikin musik apa?” Pertanyaannya ringan tapi menggigit. Saya jawab lagi, “Ya saya bikin musik yang bukan klasik.” “Loh...”, Ahmad kaget. “Katanya tadi kamu belajar musik klasik, kok malah bikin musik yang nggak klasik? Gimana tho kamu ini?” Saya jawab lagi, “Musik klasik itu kan musik kuno, seperti yang saya bilang tadi Mad. Lha zaman sekarang kan bukan kuno lagi. Jadi nggak ada musik klasik, yang ada pop, keroncong, disco, dangdut, jazz, hip-hop, rock, metal, punk, grunge, death-metal, cong-dut, dan lainnya!” Melihat jenis-jenis kelamin musik yang saya sebutkan itu, Ahmad malah semakin bingung. Saya berdosa padanya tidak SMS: Short Music Service 19 bisa menjelaskan dengan baik. Dan terakhir dia bilang pada saya, sebelum ada pelanggan yang hendak potong rambut di kiosnya, “Wah, kamu ini aneh rie, sekolahnya musik klasik tapi nggak bisa bikin musik klasik, malah menyebutkan musik-musik yang lain. Sebenarnya kamu mau jadi apa sih?” Saya cuma menjawab seperti ini, “Hahaha... saya juga bingung, nggak tahu mau jadi apa. Jadi Tom atau Jerry sajalah, biar dibikinin musik.” Ahmad masuk kios, merapikan tempat duduk “salon”nya, mempersilakan pelanggannya duduk, menyelimutkan kain hitam di tubuh pelanggan. “Mau potong model apa, pak?”, tanya Ahmad pada pelanggan. “Seperti Tom & Jerry, ya...” “Haa...???” Ahmad memandang saya heran. Pesan Buat Musik T idak ada pesan kebajikan yang paling mujarab selain pesan yang terlahir melalui musik. Karena beberapa asumsi: pertama, musik bukan hadir verbal seperti kotbah yang disampaikan Ustadz atau Pastur yang tidak lebih dari pemahaman teks dan logika. Kedua, musik mewakili dua dimensi sekaligus, teks (syair) berbicara verbal, sementara bunyi, sebagai aspek stimulan berfungsi merangsang perasaan, mendekatkan keindahan. Ada mood yang terbangun melalui alur progresi akor maupun gerakan melodi yang tanpa disadari membawa alur sendiri dalam batin, terlepas dari persoalan logika. Media musik menuntun untuk menghargai keindahan yang tidak bisa terwakili apapun. Musik tidak boleh terikat oleh ruang (sosial). Oleh sebab itu musik bisa diakses kapan pun dimana pun. Karena sifatnya yang anytime anywhere pesanpesan musik yang ingin kita dengar akan lebih bisa diulangulang semau kita dan kapan saja. Orang bisa menilai apa saja atas musik. Kadang-kadang SMS: Short Music Service 22 penilaian masyarakat amatlah berseberangan dengan pendapat para ilmuwan atau pakar. Untuk menilai pesan musik barangkali amatlah terlampau abstrak—katakanlah ketika ia hadir tanpa teks—tidak ada goal pemahaman yang valid, selain musik cuma sebagai stimulus yang mengoyakoyak saraf. Musik instrumental pun kadang-kadang membuat bingung. Seperti apa maksudnya? Biasanya, yang paling unggul implementasinya—dalam hal ini—adalah musik bersyair religius, yang jelas-jelas menawarkan pesan kebajikan. Bimbo misalnya, yang sangat kuat karena syair-syair gubahan sastrawan terkemuka Taufiq Ismail. Yang dalam kenyataannya, musik bisa berbicara secara luar dalam. Melodi dan harmoni mewakili stimulus terhadap ruang imajiner, perasaan, bayangan, dll. Sementara syair mewakili dimensi perjalanan hidup manusia yang sesungguhnya. Kalau dalam lagu-lagu pop, yang kebanyakan kini bertema cinta, sesungguhnya kurang ada muatan yang begitu berarti. Tingkat subyektifitas manusia, yang mendorong pemisahanpemisahan berdasarkan selera musik, membuat tema cinta (remaja), kurang begitu bisa tampil mewakili kondisi kehidupan sejati yang dicita-citakan manusia. Selain biasanya, tebaran tema cinta remaja sangatlah bersifat semu, mudah lewat dan mudah lalu. Kecuali memang syair yang dihadirkan begitu kuat menusuk dalam ingatan. Demikianlah, sekadar uraian singkat yang bisa disampaikan. Cuma Musik, Kadang Itu Cukup T idak semua orang gemar musik. Tidak semua orang mengerti dan memahami musik. Tidak semua orang bisa menikmati musik dengan baik. Semua perlu cita-cita khusus untuk mengerti hakikat musik—yang bisa jadi—satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Hakikat musik adalah menghayati pendengaran, perasaan, dan pikiran. Tiga hal tersebut adalah mutlak dan selalu dibutuhkan ketika orang berhadapan dengan musik, terutama ketika mendengar. Jika kita sebagai musisi, ketiga hal di atas lebih penting selain aktifitas motorik (skill/ketrampilan fisik) yang tidak terlalu menjadi hal utama. Musik sudah ada sejak sebelum masehi. Banyak hal telah diperbuat oleh filsuf-filsuf semacam Plato, Phytagoras dan Aristoteles untuk membuktikan kekuatan atau manfaat musik bagi kehidupan manusia. Selain itu, musik juga dipergunakan sebagai sarana memuja dewa. Saat ini hampir semua musik SMS: Short Music Service 24 mengandung unsur komersial. Kalau tidak bisa menguntungkan secara finansial, orang tidak mau bermain musik: mungkin jawaban dari fenomena ini adalah profesionalisme dalam musik. Namun, musik sebetulnya bukan produk komersial, musik adalah suatu kesenian, yang setiap detik memiliki perubahan dinamis seiring tingkat kreativitas kreator. Sementara, kreativitas musik di dunia media (pasar) telah dicekal, tidak boleh bebas: harus ini harus itu. Sejak banyak stasiun tivi muncul, radio bertebaran di mana-mana, siaran musik pop (yang semuanya komersiil), yang di radio juga semakin banyak itu, mencetak masyarakat konsumen. Sehingga, taste atau selera masyarakat pun terbentuk karena unsur media yang membooming tersebut, selain CD atau kaset yang dijual bebas: dengan harga murah. Kini, penikmat musik adalah semua kalangan. Pemain musik pun berasal dari semua kalangan. Anak-anak kecil hingga manula. Semua main musik, entah hobi, iseng, atau profesi. Tujuan yang diinginkan oleh masing-masing orang tentu berbeda. Saat banyak orang merasa harus mendengarkan musik pada saat-saat tertentu saja, inilah yang dinamakan hobi. Jika orang sekadar bernyanyi-nyanyi tanpa punya tujuan tertentu, inilah iseng. Jika orang yang merasa selalu membutuhkan musik dalam kesehariannya, pagi siang malam, sampai kembali pagi lagi, inilah yang dinamakan profesi: musik pun digunakan sebagai sandang pangan. Mendengar musik adalah juga kebutuhan yang urgen. Bagaimanapun juga, orang butuh musik. Itu sudah cukup. Yogyakarta, 2007 Beethoven, Aku Mencintaimu J ika dengar nama Beethoven, apa yang Anda bayangkan? Komponis temperamen, emosional, rambut acak, kegagahan, melankolik, cinta, symphony, klasik-romantik, tuli, gila, jomblo sepanjang hidup, komponis berbakat, virtuos-piano, atau malah seekor anjing dengan tuts hitamputih? Terserah. Kali ini Anda saya bebaskan untuk menafsir Beethoven dengan 1001 cara. Tetapi, jika suatu ketika Anda mendapati Beethoven sedang belanja burung di Ngasem Yogyakarta, apa yang Anda lakukan? Tertegun, kaget, melotot, nggak nyangka, heran, minta tanda tangan, biasa saja, so what gitu loh? Pianonya jadi kroto (telur/semut). Kertas partitur jadi uang recehan. Rambut acaknya sudah disisir rapi. Atau misalkan begini saja, secara tiba-tiba dari jauh tampak Beethoven turun dari becak, lalu menggandeng ibu muda asli Nitiprayan, nama baptisnya Maria Fransisca. Mungkinkah peristiwa ini terjadi? Bukankah ini cuma rekayasa sejarah? Ataukah Anda akan SMS: Short Music Service 26 mempercayai begitu saja kebingungan-kebingungan cerita saya? Atau justru, setelah lima tahunan lebih Anda belajar musik klasik, Anda malah tidak tahu siapa Beethoven sesungguhnya. Komponis yang suka bikin bulu kuduk merinding itu atau bikin dada kita bergetar tatkala dengar Shympony-nya. Sungguh pun, ia komponis luar biasa sepanjang sejarah—yang namanya tak bakal hilang walau digosok dengan 1001 penghapus. Amir Pasaribu saja menulis demikian, “...ia (Beethoven) berhasil menciptakan bangun yang indah murni serta kekal abadi dalam mencurahkan getaran jiwanya baik malam ataupun siang.” Lebih lanjut ditulisnya lagi, “Beethoven memberontak, berevolusi melawan yang telah usang, berevolusi terhadap diri dan nasibnya. Ciptaan-ciptaannya dilahirkannya dalam kepedihan, tetapi yang timbul itu kekal remaja untuk selamalamanya. Walaupun ia telah tiada, namun jiwa musiknya hidup terus!”. Sebelum ke Ngasem, Beethoven menginap di Hotel Melati, kawasan Prawirotaman, yang bangunannya begitu sederhana. Ia membuat janji dengan Maria Fransisca di Jokteng Wetan jam 5 pagi. Beethoven menunggang becak. Menenteng tas kulit yang dibawanya dari Bonn, ada satu buah PIN bertuliskan “My Music, My Life”. Kenapa Beethoven mencoba menunggang becak? Karena di Bonn tak pernah diciptakan becak. Beethoven pun kaget tatkala harus menaikinya. Ia berpikir seratus kali. Bertanya pada sopir, “Bagaimana cara naiknya, pak?” Dijawab oleh sopir, “Ya tinggal naik saja, kok bingung?” Jawaban yang ketus. Jidat Beethoven naik. Sopir tampaknya tak tahu bahwa tamunya itu datang dari jauh. Komponis kawak yang mendadak hidup SMS: Short Music Service 27 lagi di zaman sekarang. Bangkit dari kubur setelah tidur sejak tahun 1827. Sepanjang perjalanan, yang dinikmatinya hanya rindang pepohonan, sambil tetap dudal dudul tuts HP—memantau Maria Fransisca sudah menunggu atau belum. Masih subuh. Jam 4. Hari Sabtu, 8 Desember 2007. Sementara, saat kisah ini berlangsung, karya agungnya, Shympony No.1 sedang dipikirkan oleh banyak teman-teman “Orkestra 2007”. Nanti malam mereka membawakan karya itu dalam sebuah konser di Sewon. Beethoven pun tak diberitahu kalau karyanya akan dimainkan, di SMS-pun nggak, ditelfon apalagi. Padahal seharusnya Beethoven dapat royalti dari karya besar ini—yang nilainya tentu tak sedikit. Beethoven sudah sampai di Jokteng. Tengak-tengok mencari Maria Fransisca. Belum juga ketemu. Beethoven ambil HP di sakunya, ditelfonlah Maria Fransisca. Mail-box. Geram. Marah. Kesal. HP Maria cuma satu, jadi tidak ada alternatif lain selain menunggu. Beethoven duduk di pojok, dekat Burjo. Lihat jam, sudah jam 5 lewat 5. Maria Fransisca telat 5 menit. Kuncinya sabar dulu. Secara mendadak hujan deras. Beethoven kelabakan mencari tempat teduh. Tetap tak ada. Bingung. Sampai kebingungan. Beethoven menyerah. Jam 6 sudah. Kembali ke hotel dengan rasa kecewa. Diobrak-abriknya tempat tidur yang tadinya rapi. Kacanya dipecah. Gelas dilempar. Pakaianpakaian dirobek. Geram. Kesal. Amarah. Benci. Dendam. Luka. Bukan Beethoven kalau tidak pandai melampiaskan emosi. Bukan pula seniman jika kalah dengan masalah cinta tak bisa berbuat apa-apa. Beethoven telah dikhianati Maria SMS: Short Music Service 28 Fransisca. Ia dibohongi dengan gombal. Buat Beethoven ini tak jadi soal yang sampai bikin patah semangat. Ia melampiaskan kesal dengan bikin komposisi. Dipikirkannya cara-cara untuk merubah emosi menjadi karya seni yang bernilai bagi sejarah. Beethoven adalah wujud pengembaraan totalitas yang sejati. Jika dunia Islam punya Sunan Kalijaga, jagad musik punya Beethoven, bukan Bach atau Mozart. Beethoven akan “disetubuhi” sebagai roh. Satu, karena semangat juangnya yang tinggi. Dua, gejolak dan keteguhan yang tinggi. Tiga, pantang menyerah. Empat, punya daya pikat yang menggabungkan romantisme dan absurditas. Lima, karakter ketokohannya yang tak pernah tergantikan. Maria Fransisca mendadak hilang dari genggaman kalbunya, berubah menjadi karya-karya. Berangsur menjadi aliran-aliran melodius yang menyibakkan nurani. Mengobrakabrik kalbu menjadi harmoni. Bahkan sampai menuntun tingkah laku dengan menyemai sejuta keindahan abstrak yang tak tampak—namun hadir sebagai kekuatan rohani. Mirip seperti kita merasakan desir angin di pinggir pantai, yang tanpa jelas kemana arah angin. Angin tetap menusuk sampai ke dasar jantung paling dasar. Legalah hati Beethoven. Sambil merokok di depan hotel, Beethoven memandangi burung Jalak Uren yang barusan dibelinya. Ia nyingsoti (bersiul) dengan penuh semangat. Dengan penuh kegembiraan. Menjelang sore, hujan deras, angin sangat kencang, sakit liver Beethoven tiba-tiba kambuh. Beethoven terjatuh, ia lalu mati untuk kedua kali di hotel Melati. Kematiannya sendiri. Tanpa siapa-siapa. Hanya disaksikan sejarah yang tersisa. SMS: Short Music Service 29 Namun kematiannya mengagumkan. Dilayat 10.000 umat manusia. “Beethoven, jika aku boleh mengatakan, sejujurnya aku mencintaimu, kenapa kau tinggalkan aku?”, demikianlah bisik Maria Fransisca di telinganya yang sudah tak lagi berfungsi. Walaupun demikian, Beethoven adalah fenomen sejarah yang tak habis-habisnya mengiang di telinga banyak orang. Ditulis di ratusan buku. Dirayakan dalam semangat keberagaman fantasi dan imaji liar yang menggenangi alam fikiran. Beethoven tetap menjadi tokoh abadi sepanjang zaman, karena semangat hidup yang tak pernah pupus. Ludwig van Beethoven, ijinkan aku mencintaimu juga. Ijinkan! Musik Barat Dibawa ke Barat? O rang Timur (Indonesia) bingung kalau sudah mulai belajar main musik Barat! Mau di mana mereka cari jam terbang supaya terus “laku”, eksis, dihargai di sana-sini, diapresiasi di sana-sini?! Indonesia—yang notabene negara timur, adalah salah satu contoh negara yang kebingungan itu. Lain jika menegok ke Jepang, pengelolaan SDM (musik) yang bisa dibilang sudah sangat profesional. Mulai dari managerial, administrasi, link, maupun pendanaan untuk berbagai konser musik. Musik Barat memang amit-amit, begitu luas—tapi lebih ramai kekayaan kita. Tapi untuk menunjuk ciri utamanya, pantaslah kita menyebut musik klasik (yang lahir di Eropa Barat) sebagai center of culture. Hal itu bisa diakui, sebab, memang musik itulah yang mendominasi berbagai sub-kultur di wilayah Eropa selama barabad-abad. Tak heran jika klasik di sana bagaikan pula gamelan disini. Prancis, Jerman, dan Italia adalah contoh negara-negara maju di bidang musik Barat. SMS: Short Music Service 32 Indonesia dengan kota-kotanya (Solo, Yogyakarta, Bali) adalah contoh wilayah maju di bidang gamelan. Lalu selanjutnya, dari manakah kita harus me-meta-kan pikiran untuk menjawab pertanyaan, seperti apa eksistensi musisi klasik kita di Barat? [karena di Indonesia rasanya mereka semakin kebingungan karena tidak mendapat dukungan moril, apalagi materiil dari banyak pihak terutama pemerintah]. Melihat pesimisme yang seperti desakan itu, apa kita menyerah? Kita boleh sedikit menyebut dua contoh saja. Nama seperti Ananda Sukarlan (Piano), Iwan Tanzil (Gitar), mereka sekarang justru hidup di Eropa [Ananda: Spanyol; Iwan Tanzil: Jerman]. Mereka punya jam terbang luar biasa di sana. Ketrampilan mereka bisa disejajarkan dengan musisi Eropa (biasanya Eropa Timur yang gudangnya pemain)—yang notabene secara kultur, sebenarnya orang Eropa lebih unggul (lahir batin). Hal ini, semakin menyudutkan perhatian kita untuk, pertama, benarkah potensi yang ada di “tubuh dan negara” kita bisa unggul (diunggulkan)? Kedua, apakah eksistensi dan ukuranukuran profesionalisme musisi klasik Indonesia harus diukur dari jam terbang mereka di Barat? Mengapa mereka tidak memilih eksis di negaranya sendiri? Ketiga, langkah apa yang harus diperbuat untuk tidak semakin ambigu terhadap budaya Barat dan berusaha mengadopsi budaya Barat itu secara transparan dan terbuka? (asal tidak merugikan). Hal itu wajar sebagai kegelisahan para musisi Indonesia yang masih punya niat “panjang umur” di bidangnya. Jika para musisi justru terbelenggu: Wah, ini Barat! Wah, Barat itu susah! Wah, ini minim dukungan! dsb., semestinya pikiran “pintas” seperti itu harus segera dimusnahkan. Jelas sekali bahwa posisi kita dengan negara tetangga yang lain (Singapura misalnya, apalagi Jepang!) sudah kian jauh SMS: Short Music Service 33 tertinggal. Hal itu membuat kita semakin tergerak untuk mengangkat jari kita dan lantas menggigitnya! Dilihat dari SDM-nya sebenarnya kita punya ribuan kemampuan. Selanjutnya, Apakah tidak ada upaya untuk memikirkan hal ini lebih serius? Menggantinya dengan rasa percaya diri? Apapun yang diasup adalah pelajaran sampai mati. Jakarta, 4 Februari 2005 Musisi dan Ketegangan M usik bukan persoalan ketegangan. Dalam bermain musik justru orang ingin berusaha melepas ketegangan. Melepas segala yang menjadi beban hidup. Namun, musik bukan semata-mata menjadi hiburan yang murah harganya dan bukan menjadi sekadar tontonan yang melulu menjadi pemuas dan penghibur. Musik, sengaja diperbuat untuk mendulang apresiasi atas pemaknaan sedalam mungkin akan bunyi, bukan atas pemusik saja. Paradoks akan hal ini dapat kita lihat dalam musik pop. Artis dipuja-puja dengan histeria layaknya memuja dewa, sementara musik menjadi sesuatu yang murah sekali harganya. Akhir-akhir ini, banyak anak-anak kecil menyukai musik. SD, SMP, banyak yang pergi ke studio untuk (iseng) nge-band main musik sepulang sekolah. Gaya mereka berusaha meniru artis-artis terkenal semacam Ungu, Letto, Samsons, dll. Meski skill yang mereka punyai masih dalam tahap amat amatir, SMS: Short Music Service 36 namun spirit mereka untuk mengenal musik cukup mendapat sambutan yang positif, daripada lari ke hal yang berbahaya semacam narkoba, seks bebas, dll. Sekali lagi, musik bukan persoalan ketegangan. Ketidakabadian musik dalam ruang dan waktu membuat permainan musisi di panggung satu ke yang lain tak pernah sama. Menyesuaikan tempat, waktu, keadaan, situasi, dan referensi antar pemain. Entah, hal seperti ini diamini atau tidak, namun itulah yang terjadi. Pada saat berlatih di rumah atau studio semua berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, di panggung, kita menemukan sesuatu yang amat berbeda dari sebelumnya. Musisi justru tegang dan sulit berkonsentrasi, sehingga membuat apa yang dimainkan salah semua. Luput semua. Bubrah. Suatu pentas malah menemui kegagalan yang fatal. Apalagi jika banyak improvisasi di sana. Banyak 'kretivitas dadakan' yang hadir di pentas. Semua problem itu memang dapat diatasi, namun tidak bisa begitu saja teratasi. Karena, musik adalah suatu proses terus-menerus yang tidak bisa dengan mudah dipelajari. Bahkan, hasil tidak boleh terlalu dibicarakan. Kini, bila seorang musisi menemui ketegangan, grogi, keringatan dalam berpentas, apa obatnya? Obatnya ya obat pusing. Ya apa? Solo, 17 Maret 2007 Fatamorgana Musika Catatan: 10 tahun sudah saya kenal musik, setiap hari hidup bersama musik. Selama 10 tahun itu pula saya kenal orang berbagai tipe. Tentang banyak kawan itu, aku punya cerita yang lebih ramai dari pasar malam. Yang satu punya jiwa seni yang kuat: kreatif dan tidak stagnan, Yang satu punya jiwa seni yang tidak kuat: tidak kreatif dan stagnan Yang satu lemah namun punya semangat: tidak peduli kritik, Yang satu bagai filsuf: apa pun lahap sampai ke akar, Yang satu penghibur sejati: lagu apa pun yang di-request selalu bisa, Yang satu seni untuk uang: tidak berpikir otak kanan-kiri, apalagi idealisme, Yang satu seperti superman: sering terbang ke luar negeri sambil bawa seruling, Yang satu mirip nasi rames: apa pun masuk, semakin campur SMS: Short Music Service 38 semakin asyik Yang satu disiplin di satu rel: punya satu tujuan, tak pernah terpengaruh Yang satu tidak pandai: (namun) sekali genjreng dan nyontong satu juta Yang satu cuma gaya doang: main musiknya biasa, malah nggak bisa Yang satu pemikir sejati: malah kurang bisa main musik dengan baik Yang satu pembohong sejati: live show kok rekaman, purapura nyanyi: lip sing Yang satu tak tahu ilmu: namun segudang musik dia tahu Yang satu perfeksionis: salah senada cocokin di undangundang Yang satu cuma iseng: aslinya dokter gigi, bagusnya kalau nyanyi Killing Me Softly Yang satu penyakitan: main tanpa bayaran nggak mau Yang satu cakep: main musik bagus, dandan bagus, ini boy's band Yang satu sudah tua: tetap pingin perang ama yang muda, padahal jaman udah lain Yang satu pintarnya minta ampun: ratusan ilmu musik bisa apal Yang satu maniak alat: semua ingin dipelajari tanpa perhitungan anatomi Yang satu all around: pop, jazz, rock, keroncong, klasik, rock and roll, ora masalah... Yang satu dandan rapi: mainnya musik klasik doang Yang satu rambutnya pirang: cuma nyanyi di kafe, tidak berani di lapangan bola Yang satu udah terlanjur kaya: tidak bisa bercerita tentang SMS: Short Music Service 39 duka jadi seniman Yang satu miskin total: justru IQnya lebih tinggi dari yang udah terlanjur kaya Yang satu bisa 'main' yang lain: habis nyanyi diboking Yang satu agresif: sekali berteriak semua bergetar Yang satu sekolahan: main tanpa partitur ibarat sayur tanpa garam Yang satu tidak sekolahan: suka “menghina” yang sekolahan Yang satu punya musikalitas luar biasa: nada c seberapa dia tahu Yang satu obsesinya harus masuk TV: seperti Nidji Yang satu tak punya obsesi: penting cukup duit anak istri Yang satu suka cinta: bikin lagu harus ada kata cintanya Yang satu pemabuk: bisa improvisasi blues kalau pas lagi mabuk saja Yang satu pendekar segalanya: salah bicara sehuruf saja bisa binasa Yang satu rela berkorban demi nusa bangsa: hanya pas bencana saja nyumbangnya Yang satu jago rekaman: di panggung nguyuh di tempat Yang satu pendiam: tidak berpikir gempa akan mengguncang Yang satu punya obsesi: sebatas di mulut saja Yang satu aneh: melototin komputer sehari semalam demi bunyi aneh Yang satu cantik: udah sexy, pinter nyanyi, bisa kencan tapi satu juta semalam Yang satu sok artis: padahal ia manusia biasa Yang satu cuma suka nongkrong: kumpul teman-teman musik biar tambah musikal Makin ramai makin asyik! Ayo Ngamen! F enomena pengamen bisa menjadi sesuatu yang mengasyikkan sekaligus menakutkan. Mereka tetap selalu ada dalam transportasi umum. Bahkan kehadirannya nyaris seperti kereta api—sambung menyambung jadi satu—tanpa henti, meski di dalam bus yang sama. Paling tidak, jika Anda melakukan perjalanan jauh dengan bus umum, siapkanlah beberapa uang recehan untuk mengasihani pengamen. Tetapi bila Anda jago berkelahi, silakan saja tidak membawa uang receh, toh kemungkinan yang terjadi jika pengamen tidak diberi uang akan memeras penumpangnya, tak segan mereka memukul penumpang. Siap-siap saja untuk hal ini. Namun, pengamen bukan sepenuhnya fenomena kehidupan yang buruk. Mereka sama seperti pegawai negeri, buruh, menteri, atau pedagang asongan—yang sama-sama mencari makan untuk hidup dengan cara masing-masing. Anggapan mayoritas orang yang memberi cap kepada SMS: Short Music Service 42 pengamen adalah sesuatu yang meresahkan memang telah menjadi image yang sulit dihapus. Namun harus disadari, bahwa lagu-lagu yang dibawakan pengamen pasti pernah menghibur hati kita. Oleh sebab itu mereka juga berjasa bagi kita. Uang seratus rupiah yang kita sisihkan untuk mereka adalah balas budi yang bermanfaat bagi mereka. Pengamen senyum, kita pun senyum. Tetap saja, suatu profesi ada perkecualiannya dalam hal resiko. Pengamen yang baik adalah pengamen yang sadar penuh akan pekerjaannya; menyadari penuh bahwa mereka bekerja. Ikhlas. Jika tidak diberi uang ya tetap tersenyum, itu berarti rezeki belum berpihak. Perkecualian yang membuat kita resah adalah seringkali pengamen bekerja sambil mabuk, menenggak minuman keras, mereka lepas kendali dan kemudian menyerang penumpang dengan semena-mena, padahal itu bukan hak mereka. Pengamen yang setengah baik setengah buruk contohnya begini: mereka selalu sopan dalam menjalankan pekerjaannya, tidak pernah marah bila uang belum menghampirinya, dan selalu berusaha bernyanyi dengan bagus. Namun, uang hasil jerih payahnya selalu mereka pergunakan untuk urusan haram seperti judi dan mabuk! Nah, bagaimana kita menilai sikap pengamen seperti ini? Tentu itu tergantung persepsi kita masing-masing. Ngapain pusingpusing mikirin mereka? Ayo kita ngamen saja! Biar tahu bagaimana rasanya ngamen, supaya tidak mengkotbahi pengamen terus. Solo, 8 Agustus 2005 SMS: Short Music Service 43 Catatan: Tahun 2000, saat kelas 2 SMA, saya pernah iseng sekali dua kali jadi pengamen perempatan jalan. Jam 7 sampai jam 9 malam saya “beraksi”, mengumpulkan uang sekitar 5000 rupiah. Sampai akhirnya saya berhenti karena dimarahi orang tua. Ini sepenggal kisah saja. Cucak Rowo O rang menyebutnya organ tunggal, masih juga dinikmati sebagi hiburan paling fresh di pelosok-pelosok Nusantara ini. Musik memang membuat suasana menjadi segar, itu kalau penyanyinya membawa suasana segar pula. Lagu yang dinyanyikan juga harus segar-segar. Kalau nggak, buyarlah semua planing penghiburan paling murah dan nyaman itu! Jangan menjadi penyesalan yang berlarut-larut jika hiburan di acara hajatan sudah jarang 'menempatkan' lagi unsur seniseni tradisi. Karena pada kodratinya, yang tradisi memang bukan sekadar hiburan—yang tradisi [konon] harus diapresiasi. Maka, cucak rowo lebih 'beruntung' daripada Sinom Parijatha. Inul lebih diminati daripada Nartosabdo. Itu sudah menjadi pilihan di zaman instan ini. Alhasil, itulah yang dinamakan keputusan tanpa pertimbangan. Tiada yang merugikan dari keputusan itu. Tidak mungkin kita lantas kontra sepenuhnya terhadap hal tersebut. Sepantasnya, untuk kasus seperti itu, masalah idealisme harus segera SMS: Short Music Service 46 disingkirkan. (eit, bukan berarti harus dibuang!]. Karena permasalahan idealisme masih sangat penting untuk mengukur ketajaman berpikir sebagai kontribusi bagi geliat (penghiburan) yang (mudah-mudahan) bisa konstruktif. Di segala lini zaman, hiburan adalah kewajiban yang harus dipandang sebagai naluri manusia yang wajar—di setiap peradaban yang masih mau belajar. Hiburan menjadi sinkronisasi atas kesibukan dunia yang sering memunculkan ketegangan atau aktivitas yang seram-seram. Pada saat hiburan hadir dan tawa muncul, perasaan menjadi tenang dan terhibur, hilang sudah semua beban yang melekat di 'tubuh' setiap orang. Walaupun, setelah usai menikmati hiburan, problem yang memuakkan bagai tumpukan sampah itu datang lagi tiada henti. Stres, bisa diatasi dengan menghibur diri, termasuk mendengar musik, atau rekreasi ke mana pun disuka. Kembali pada soal organ tunggal (yang mestinya keyboard tunggal atau solo keyboard), pilihan itu memang (sepantasnya) dibiarkan saja, tapi tetap harus dicermati setiap detail duduk persoalannya. Hiburan organ tunggal, adalah hak asasi yang bebas dipilih setiap insan. Jika ingin dikuak, masalah sebenarnya hanya ada pada: jangan sampai keyboardis, organis, dan penyanyi, bermusik seenaknya—dengan tendensi asal laku dan orang senang! Itu lama-lama bisa bahaya, orang nggak mikir kualitas musik lagi. Ditinggal pergi keyboard bunyi sendiri. Ya ampun ya ampun. Jakarta, 5 Februari 2005 Adakah Musik Aneh? S ebetulnya, kalau mau jujur, tidak ada keanehan dalam musik kontemporer. Pembuatan komposisi dilakukan dengan sadar, serius, dan ada (banyak) komponis yang membuat komposisi berdasarkan teori-teori komposisi, melakukan pembacaan ide secara sadar, sampai melakukan perenungan. Para komponis mengambil konsep yang beragam. Ketika tampil di panggung, menjadi kelihatan “aneh”, tetapi sebetulnya tidak. Ada dua contoh ketidaknormalan dalam karya dua komponis. I Wayan Sadra mengikutser takan sapi di atas panggung. Dalam komposisinya, Sadra bereksplorasi dengan sapi. Akhirnya, sapi itu “ber-telur” di panggung. Shin Nakagawa mencoba berdialog dengan sapi dan kambing di sebuah kandang di Gunung Kidul Yogyakarta. Hewan dan manusia, dalam urusan komposisi tidak ada bedanya, bahkan mereka harus membaur tanpa sekat. Setidaknya itulah pernyataan Shin Nakagawa yang pernah saya dengar. Karena masalah “belum tersosialisasikan” dengan luas SMS: Short Music Service 48 dengan sekaligus pemahamannya, persoalan musik “aneh” abad ke-20/21 ini agaknya memang menjadi “pil pahit” bagi penonton. Penonton seperti dipaksa untuk “muntah” akibat menelan “pil pahit” komposisi yang “nganeh-anehi” itu. Pusing kepala hanya karena menyaksikan “ketidakmengertian” maksud komposisi. Saya jadi ragu lagi, bahwa konsep estetika dalam ruang lingkupnya, yang selalu bicara tentang indah dan tidak indahnya seni di saat sekarang ini rasanya sudah bergeser. Namun, saya jadi bertanya-tanya nih, apakah semua musik harus indah? Ataukah yang terpenting hanyalah kreasi-kreasi dari kreator dan keproduktifan berkarya dengan gagasangagasan yang selalu baru—bahkan harus terkesan “mengagetkan dan aneh”?! Sebetulnya—sekali lagi—kalau mau jujur, tidak ada keanehan dalam musik kontemporer. Justru, gagasangagasan baru yang dimunculkan komponis kontemporer dari penjuru dunia adalah bukti representasi sebagai upaya—salah satunya mendekonstruksi budaya. Tergantung, komponis itu ngawur atau punya dasar dalam berkarya! Karena, tidak semua komponis itu bisa menjalankan titah dan amanahnya dengan baik. Komponis harus terus menerus melakukan self-training, begitulah petuah bijak dari Sang Maha-Guru Suka Hardjana. Beginilah sekadar uneg-uneg. Yogyakarta, 7 Oktober 2005 Kon(on)temporer S enin, 13 Desember 2004, saat berlangsung Festival Musik Kontemporer #2 SIMPATETIKUM di Gedung Teater Besar STSI Solo, saya ingat betul, kenalan saya Mas Yasudah, komponis kontemporer, menyebar sinopsis karyanya. Ia menulis begini: Ketika Renaisans berlangsung, kurang lebih 1350 di Eropa, musik yang tercipta waktu itu, itulah Kontemporernya. Begitupun pada zaman Barok, Rokoko, Klasik, Romantik, Impresionik, Ekspresionik atau apa punlah nama-nama zaman yang pernah singgah di benak kita. Di Asia, Afrika, dll, entah apa namanya. Belum lagi, dari modus-modus zaman Baheulak, Gregorian, sampai yang Pelog dan Slendroan, dari susunan dia-tonis, whole-tonis, kromatis, mikro-tonis, ocer-tonis hingga non-intonatif atau ngarang sendiri: apa yang belum dimainkan musiknya? SMS: Short Music Service 50 Daripara Dadais, Avant-gardis tahun 1930-an Abad lalu, hingga munculnya musik Kongkrit, Elektronik, dan sekitarnya, sampai detik ini apa yang benar-benar baru? Ditambah lagi, polemik panjang dan multi-kotomi antara Kontemporer vs Klasik vs Etnis vs Tradisional vs Religius vs Industri Komersial vs dll vs dst, mengandung berbagai kepentingan serta segala dampaknya. (Yasudah, dengan karya KONONTEMPORER) Saya yang waktu itu masih “sangat kecil” sungguh tak tahu menahu apa maksud tulisan itu. Apalagi terhadap karya Mas Yas yang dimainkan rekan saya di kelompok Sarang Damelan itu. Saya hanya suka jalan-jalan lihat (dengar) musik, wong rumah saya waktu itu dekat sekali dengan STSI Solo (sekarang ISI Solo). Tinggal jalan kaki, sampai. Terus terang, saya tetap nggak ngerti. Sinopsis itu tak baca berulang-ulang, saya hanya menangkap satu maksud, betapa luasnya musik itu. Lalu sampailah saya pada kebencian-kebencian pada pikiran saya sendiri, yang tak kunjung memahami maksudmaksud karya-karya aneh yang muncul di zaman saya ini. Jika saya mengamini teori Sussane K. Langer, pakar filsafat dan estetika, saya tidak perlu repot memahami dan mengerti maksud karya-karya baru. Karena Sussane berpesan, bahwa “simbol seni adalah satu dan utuh, karena itu ia tidak menyampaikan “makna” (meaning) untuk “dimengerti”, melainkan “pesan” (import) untuk “diresapkan”. Terhadap “makna” orang hanya dapat mengerti atau tidak mengerti, tetapi terhadap “pesan” dari seni orang dapat tersentuh secara lemah dan secara intensif. Di sini terdapat elastisitas SMS: Short Music Service 51 yang luas terhadap peresapan “pesan” seni itu.” Pendapat Sussane K. Langer itu pun juga baru saya baca belum lama ini di sebuah buku filsafat. Jadi waktu itu, tahun 2004 saya benarbenar tak ngerti. Saat ini malah saya semakin tak ngerti, karena semakin banyak komponis melakukan kebingungan atas karyakaryanya sendiri. Bisa jadi, komponis yang karyanya anehaneh, malah tak tahu dan tak bisa meresapi karyanya sendiri. Sebelum berusaha diresapi orang lain, apakah tidak lebih baik komponis meresapi (merenungi) karyanya sendiri? Ataukah saya harus patuh teori Eduard Hanslick (kritikus musik) yang bilang bahwa, “karya musik itu tetap indah meskipun tidak bisa menyampaikan apapun yang merangsang perasaan pendengar.” Musik dan Kuda Rusia memang jagonya sirkus! T etapi, untuk hal berkuda, orang Jawa ternyata jauh lebih mumpuni! Lho, mengapa perbandingannya Jawa dan Rusia? Nggak ada hubungannya. Musik, awalnya adalah untuk komunikasi. Merembet kemudian, untuk berbagai prosesi ritual dan agama. Lalu, untuk pengiring tari-tarian, drama, teater atau opera. Lantas, dengan munculnya media elektronik (radio dan televisi), musik telah berubah total menjadi hiburan! Musik dan kuda lalu mau diapain? Kuda itu tiba-tiba berdiri tegak 90 derajat seiring suara rolling snare drum yang makin lama makin keras. Pawang kuda—dengan menggunakan tongkat panjang—terus menggerakkan laju kuda untuk ber-atraksi sesuai kehendak pawang. Tentu, kuda sudah dilatih. Kuda berputar-putar di halaman tanah berbentuk bundar yang tidak begitu luas tapi SMS: Short Music Service 54 memadai untuk joget bung-bung. Apa hubungannya? Itu adalah nukilan atraksi sirkus yang kebetulan tertangkap dengan mata ketika saya “pergi” ke Rusia lewat televisi punya sendiri yang tidak begitu canggih, sebab, tanpa remoute. Di zaman ini, musik membantu sendi kehidupan apapun. Konon, musik adalah (seni) paling laris di dunia! Laris, dalam arti banyak diminati, mungkin juga laku dijual (?). Mengapa demikian? Ada banyak jawaban berbeda pada setiap kepala. Musik sirkus harus dimainkan secara live. Kalau tidak, mana mungkin menarik? Wong sirkus itu sarat dengan hal spontan, ketidakterdugaan, dan yang serba dadakan. Mata pemusik sirkus harus jeli membaca suasana dan gerak-gerik pemain sirkus, termasuk kuda yang tiba-tiba nimbrung. Bagai pengiring musik untuk teater, pengiring (musik) sirkus itu sama saja. Bedanya, jika di teater ada alur, di sirkus tidak; di teater ada peran (watak dan tokoh), di sirkus tidak; di teater tidak melulu menegangkan, tetapi—pertunjukan sirkus professional—selalu membuat jantung bergetar! Ya, Tuhan... Musik dan kuda, dibilang hal baru boleh, dibilang nggak baru juga suka-suka! Untuk urusan beginian, tidak ada hal yang “merangsang” untuk didiskusikan. Untuk sekedar lepas lelah dan “bullshit-bullshit-an” barangkali sah-sah saja. Suara rolling snare drum yang 'merengek-rengek' itu tetap 'menghiasi' kuda supaya merespon dengan gerakan yang sinkron dan menarik. Siapa yang untung? Ya toko musik, karena snare drumnya laku keras…! Jakarta, 4 Februari 2005 Akan Sepi Tanpa Mereka Komponis Melewati hari-hari tanpa orang-orang ini bakalan sepi. Mereka adalah ahlinya musikyang berpikir teliti dan detail. Yang disiplin masalah harmoni, melodi, ritme, tensi, frekuensi, sampai tak bisa sembarangan meletakkan nada. Mereka orang-orang jeli yang melintasi rel sejarah. Kepada merekalah kreativitas musik itu paling bertumpu. Kehidupan musik menjadi punya gairah dan tidak statis. Mereka melakukan dengan penuh keikhlasan, dedikasi, sampai menjajaki musikmusik paling baru yang berkembang. Ijinkanlah saya menyebut 3 orang sahabat saya ini, yang melintasi rel sejarah penciptaan komposisi. Mereka masih muda-muda. Yang pertama kali harus saya catat adalah bujang Bandung Tony Maryana: sahabat karib—orang aneh yang pinternya minta ampun. Saya sangat menghormatinya. Pernah suatu ketika saya punya acara. Saya minta dia mengisi acara itu. Saya tak perlu mengundangnya secara formal, pakai SMS: Short Music Service 56 undangan, rekomendasi, dll. Saya datang ke kosnya di samping kuburan, saya menodong poster—yang disitu sudah ada nama dia, padahal dia belum tahu apa-apa. Tanpa pikir panjang dia pun menyepakati tawaran saya dengan berjoget. Kami pun berjoget berdua, “hajar saja, coy...”, katanya sambil tertawa lebar. Yang kedua kali adalah Gatot D. Sulistiyanto—orang Bagongan, Magelang. Si jenius yang berpikir banyak hal. Orang ini pinternya juga minta ampun. Dedikasinya terhadap dunia musik sudah sepantasnya ditulis di buku ini agar terkenang sepanjang masa. Orang seperti Gatot semestinya “dirawat” dengan baik. Jika dia hilang dalam sejarah, kaki kreativitas—pemikiran, dan sejarah musik bakalan pincang. Yang ketiga, Gozaldi Nur Muhammad, asli Padang. Suka menghilang lama, ternyata berkarya, tiba-tiba bikin Opera. Kuliahnya banyak yang tertinggal karena kesibukan berkarya. Di tahun 2006 saya sudah mencatatnya, mengakuinya sebagai sosok muda kreatif—yang saya harapkan mewakili dunia penciptaan dengan inovasi-inovasi yang tidak kacangan. Ini harus berlanjut. Jika ketiga orang itu hilang, saya tak bisa bilang apa-apa kecuali merasa sungguh kehilangan. Musikolog Tanpa sosok Musikolog, wawasan tidak terbuka, tidak ada “parade nama”, tidak ada analisis, tidak ada penulisan, tidak ada penelitian, tidak ada kritik, tidak ada polemik, tidak ada gairah, tidak ada pemikiran, tidak ada benih-benih yang membongkar cakrawala musik hingga nun jauh di sana. Ijinkanlah juga saya menyebut nama sahabat yang mencintai musikologi secara lahir batin. SMS: Short Music Service 57 Adalah Heryandi. Jejaka Medan. Teman satu kos. Tahu banyak hal soal musik, dari sejarah sampai situasi terakhir. Menulis. Kaya wawasan. Hapal ratusan nama dan rumahnya para komponis. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan baginya agar suatu ketika sejarah mencatatnya sebagai memorandum yang tak pernah terbeli siapa pun—kecuali kepada sejarah itu sendiri. Heryandi adalah salah satu mahasiswa musikologi yang cerdas, yang tersisa, yang cukup pantas ditulis karena dia berpikir, berpikir dan berpikir terus-menerus. Performer Tanpa mereka tidak bakal ada panggung, cahaya lampu, energi, pesona, standing ovation, album musik. Kehadirannya menghibur, sekaligus representasi atas segala kebekuan yang tak tersalurkan—kecuali lewat keberanian mental di panggung, pentas, stage, dan berbagai kesempatan tatap muka menyaksikan keindahan-keindahan. Komponis dan performer adalah seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisah. Barangkali (sementara) orang-orang inilah: Setyawan Jayantoro, Ika Sri Wahyuningsih, Nino Ario Wijaya. Mereka (menurut pengetahuan saya) punya latihan rutin harian, pentas-pentasnya direncanakan, punya rencana dan tujuan-tujuan tertentu yang diusahakan. Semoga panggung menghidupinya kelak. Reputasi rekaman membuatnya membuka link ke mana saja. Membuat suatu gerakan kultural yang menghidupi kesenian. Musik membuatnya kaya raya. Syukur-syukur bisa ke luar negeri, habis itu kembali lagi ke sini, membangun musik (di) Indonesia saja biar tidak pamali. Pedagog Tanpa mereka, moral tidak dibicarakan. Apalagi sampai SMS: Short Music Service 58 etika, rumusan, metode, atau apa pun yang menggiring kita ke wacana pendidikan musik. Maslikhatun Nisa. Datang turun gunung dari Gunung Kidul hanya untuk berpikir bagaimana memperbaiki pendidikan musik yang sudah sedemikian hancur. Niat hatinya yang tulus ikhlas membawanya menjadi penekun dunia pendidikan musik untuk anak autis. Thomas Yulian, orang Bekasi. Bukan guru bukan pendidik, tapi jika Anda bertanya kepadanya seputar masalah-masalah musik pendidikan, tak tanggung-tanggung dia menjawabnya. Penyiar radio di Eltira FM Yogyakarta untuk siaran musik klasik dan jazz ini punya banyak wawasan, terampil berbahasa. Oleh sebab itu harus dijaga dan diperhatikan. Semoga sejarah mencatat nama-nama mereka. Mencatatnya, dan jangan dilupakan begitu saja. Bisa pamali. Kuwalat. Nyunggi langit bumi kapok kowe... Penutup Untuk sebuah dedikasi, yang dibutuhkan adalah keikhlasan berkarya tanpa tendensi dan motif apa-apa, selain memperjuangkan musik itu sendiri. Semua bertugas memberi kontribusi. Apa pun dedikasi haruslah menjadi semacam panggilan hidup, demikian pendapat Christianto Hadi Jaya, seorang komponis. Gejala Baru: Semacam Kepungan Audio K ecenderungan ini belumlah lama, setidaknya baru 2-3 tahun terakhir—di mana, banyak teman-teman saya yang merasa jenuh dengan beban studi formal, berpikir musik klasik misalnya, memilih otak-atik audio, belajar tentang seluk beluk dunia rekaman, dan berbagai aplikasi yang dimungkinkan dari komputer (musik). Banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. Selain para performer dalam merekam ketrampilannya sangat tergantung pada sound engineer ini, usaha “pengalihan beban” ini adalah respon perkembangan teknologi yang sedang berlangsung. Utamanya, ini memungkinkan keseimbangan “medan kerja musik”—yang selalu tak henti-hentinya bekerja di wilayah manual dan digital. Jadi, dalam musik, ada dimensi manual dan digital. Musik manual dihasilkan oleh olah tangan manusia, sementara yang digital dihasilkan oleh teknologi (misalnya komputer) dengan berbagai pirantinya. Manual dan digital bukan paradoks yang bertentangan. Keduanya saling SMS: Short Music Service 60 mengisi dan melengkapi satu sama lain. Di zaman sekarang, komputer jelas tidak bisa lepas dari kehidupan manusia modern, yang bekerja menggunakan alat canggih ini. Untuk kerja kesekretariatan harian, mendeteksi cuaca, aplikasi hand-phone, pengolahan data, “penciptaan” audio, sungguh terbantukan dengan komputer. Tulisan ini tidak bicara komputer. Namun, tulisan ini ingin sejenak meninjau bahwa kesibukan-kesibukan manusia di bidang komputer ini pun memacu berbagai dampak. Jika banyak teman-teman tertarik ke hal ini, dan malah justru banyak yang meninggalkan unsur manual—misalnya berusaha menjadi pemain musik yang tangguh—akan menyebabkan kehidupan musik mengalami dekadensi, alias tidak maju. Jika para musisi sepenuhnya menggunakan energi manusia dalam berpikir dan bertindak, komputer hanyalah media yang paling suka diperintah. Jika banyak orang lari ke masalah audio, ada prediksi bahwa pemain menjadi sepi, musikolog sepi, pedagog juga sepi, komponis berada di titik aman karena banyak orang masih menggunakan komputer sebagai media untuk membikin musik. Makanya perlu sedikit hati-hati. Kebiasaan zaman sekarang adalah kebiasaan instan, yang cepat dipelajari dan cepat menghasilkan. Inilah tantangannya. Apakah kita berpihak pada proses atau hasil, seimbang atau berat sebelah? Manual dan digital akan menjadi sama derajatnya jika sama-sama dilalui dengan proses yang matang, bukan instan, dipikirkan secara seimbang bukan asal-asalan. Rekor Musik: Perayaan Kuantitas atau Kualitas? M anusia punya batas energi tertentu seperti bateray. Tenaganya tidak bisa diforsir maupun dipaksakan hingga melebihi kekuatan standar. Misalkan begini, orang yang sehari-harinya hanya bersepeda sejauh 10 km, tiba-tiba disuruh menempuh 100 km tanpa boleh berhenti. Ini tentu menyedihkan dan menyakitkan, orang itu bisa mati di jalan. Sama halnya dengan musik. Jika tiap harinya orang cuma mampu bermusik 3-5 jam, tiba-tiba disuruh 24 jam tanpa berhenti, pasti tewas seketika. Manusia bukan robot yang tak pernah mengeluh. Manusia bisa sakit jika dia disakiti. Rekor MURI ketika itu mencatat seorang drumer yang main sekian puluh jam, namanya saya lupa. Belum lama ini, di Karanganyar, ada pemecahan rekor main musik campur sari sepanjang 33 jam 33 menit 33 detik. Mereka-mereka itu sesungguhnya mau apa? Ternyata ada beberapa alasan. Musik itu, jika kita berkunjung ke kebun binatang, ibarat bermacam satwanya. Para satwa itu dijaga betul-betul. SMS: Short Music Service 62 Menghuni rumah khusus yang sengaja dibuat agar satwa tidak lari, hilang dan mati begitu saja ditembak orang. Perayaan pemecahan rekor MURI campur sari, yang disupport oleh Bupat Karanganyar Hj. Rina Iriani, S.Pd, M.Hum, adalah salah satu penjagaan atas musik campur sari. Yang dengan adanya ini, seolah seperti media perawatan bagi musik. Bupati bilang bahwa dengan adanya pemecahan ini, musik campur sari semakin diresapi masyarakat sebagai bagian dari seni-budaya yang tak bisa dilepaskan oleh (khususnya) masyarakat Surakarta. Maka dari itu, usaha pemecahan rekor ini bukan sematamata menunjukkan kualitas ketahanan stamina pemain saja, namun juga upaya yang diyakini sebagai pelestarian ini. Wong dalam event itu juga tampil banyak grup, tak hanya satu. Konon, bahwa dalam banyak kesempatan pemecahan rekor yang terselenggara di Indonesia ini pada umumnya tidak bertarung secara nyali atau kualitas. Namun selalu diukur dari kuntitas: panjangnya, lamanya, jumlahnya, dsb. Namun jarang sekali yang sungguh-sungguh dengan ketulusan, panggilan, berusaha menempatkan suatu potensi tanpa motif dan modus menjadi yang utama atau ber-rekor, melainkan semua didasarkan atas perhatian budaya tanpa embel-embel apaapa. Dengan tidak berpikir meraih rekor yang seolah-olah hanya perjuangan kuantitas itu, sesungguhnya inilah yang lebih mulia dan berkenan. Karena yang rekor itu amatlah sesaat, temporer, dan pada saat itu saja. Atau barangkali inilah tabiat orang Indonesia, suka yang cepat, fantastis, glamour, spektakuler, besar, tapi menafikan isi, esensi, dan kualitas. A Tribute to Indonesia: Musik Tragedi Aceh S angat beruntung Indonesia masih memiliki Twillite Orchestra yang masih saja terus bertahan untuk eksis, terutama saat ini, dalam mewacanakan kemanusiaan lewat musiksebagai anugerah Tuhan yang begitu mengena sanubari, meskipun ada 'embel-embel' industrial yang kadang-kadang saya nggak ngerti maksudnya. Acara konser itu dilangsungkan di Studio Metro TV, 4 Februari 2005 dengan menghadirkan Twillite Orchestra, Sherina, Edo Kondologit, Memes, dan beberapa penyanyi lainnya. Dihadiri pula oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh, para pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Tragedi Aceh yang memilukan telah berlalu lebih dari sebulan yang lalu. Namun, dengung acara-acara kemanusiaan di berbagai sudut negeri ini masih tetap saja menggema. Mereka menyuarakan doa, berbelasungkawa, dan membantu dalam bentuk materi. Peristiwa Aceh adalah pelajaran sangat bermakna bagi peradaban bangsa ini. SMS: Short Music Service 64 Musik, adalah upaya yang jauh lebih efektif untuk urusan refleksi kemanusiaan daripada sekedar tutur kata ataupun doa. Karena musik tidak pernah berdiri hanya semata oleh faktor verbal. Musik membuka ruang otonomi bunyi dan harmoni yang langsung bisa “menaklukkan” perasaan. Selain taburan lirik-lirik lagu kemanusiaan yang menyentuh, di sisi laindengan bantuan musikkedua unsur itu akan semakin efisien untuk menjelajahi alam kesadaran kita sampai sedalam mungkin. Musik dapat menghibur disaat manusia s e d a n g m e n g a l a m i ke te r d e s a k a n m e n t a l y a n g mengarakibatkan stres, karena musik menstimulasi sarafsaraf di otak dan mengendorkannya dari ketegangan. Lagu “Indonesia Menangis” yang dibawakan Sherina di awal acara itu memukau para hadirin yang khusu' mendengarkan. Selanjutnya, Edo Kondologit menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang diarransir Addie MS juga dengan sangat memukau. Harapan yang timbul tentunya, agar acara yang disiarkan langsung itu bisa sampai ke Aceh untuk menghibur saudara-saudara kita yang mengalami harubirunya musibah. Walaupun hiburan ini sangat belum sepenanggung derita batin dan fisik yang menimpa saudara kita. Singgih Sanjaya, diakui masih menjadi Arranger kreatif yang dimiliki Indonesia saat ini. Lagu tradisional Aceh “Bungong Jeumpa” mampu diolah olehnya dengan orkestrasi yang begitu menarik. Selamat kepada musik persembahan buat Aceh. Kejujuran nurani tanpa motif akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Jakarta, 4 Februari 2005 Bab II Sekali Klik Dengar Musik Kritik Musik D alam masyarakat kesenian, status seniman atau kritikus seni selalu bersifat achieved status, yaitu suatu kedudukan yang membutuhkan kemampuan atau bakatbakat khusus (special qualities). Dalam banyak hal, kritik sering lebih banyak keliru (meleset) dari benar. Mengapa? Karena dalam banyak hal, kritik cenderung sering tertinggal satu langkah dari karya seni. Kritik Seni Secara teoritis, menurut C.J. Ducasse, dalam bukunya Art : The Critics and You, ada tiga aktivitas manusia dalam kehidupan seni. Pertama: aktivitas kreasi seni, kedua, aktivitas penghayatan atau kontemplasi estetik dan yang ketiga, aktivitas kritik seni. Semula kritik seni dibangun dari konsep filsafat-metafisis. SMS: Short Music Service 68 Dari sini timbul jenis-jenis kritik yang bersifat dogmatis, tetapi belakangan tampaknya pendekatan empiris lebih diterima dan dipraktekkan secara luas. Pendekatan yang terakhir memandang karya seni sebagai basis pengajuan hipotesis dalam menafsirkan nilai seni. Konsep yang menempatkan pentingnya unsur pembuktian dalam proses pengkajian nilai seni. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa kritik (secara harafiah) berarti menghakimi, namun kritik belum tentu menghakimi. Kritik hadir sebagai bahasa kedua selain bahasa ekspresi seni (karya seni) yang tentunya menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu, Suka Hardjana memberi pendapat bahwa kritik cenderung tertinggal satu langkah dengan karya seni. Kritik Musik Musik, di luar konteks pengkajian atas berbagai latar belakang yang melingkupinya, seringkali hanya merupakan persepsi manusia terhadap bunyi (sound) yang bersifat auditif-afektif. Ketika musik hadir sebagai wacana yang harus dimengerti (mutlak) secara ilmu pengetahuan, sesungguhnya ini kurang pada tempatnya—berat sebelah. Namun, kritik bukan berbicara atas kondisi faktual yang merekayasakan penikmatan inderawi. Kritik justru menjadi atmosfir yang berusaha melengkapi berbagai dimensi yang terpendam untuk dikuak menjadi sebuah wacana yang koheren. Mudji Sutrisno menulis artikel menarik, 'Dalam budaya mutakhir dimana produksi komoditas bersanding dengan produksi simbolik makna dan penggairahan provokatif lewat iklan yang merangsang basic instinct untuk mengkonsumsi terus-menerus dan menuruti selera yang diciptakan oleh SMS: Short Music Service 69 penguasa pasar, pemahaman dan penulisan kritik seni mesti bisa melihat sisi the sacred dalam komoditas konsumtif sekaligus yang simbolik dari citraan-citraan dunia hiburan agar erosi nilai pembendaan diketahui kapan mulainya. Mampukah kritik seni keluar dari makian dan menuding kapitalisme sebagai biang tandingan mencoba menanggapi secara cerdas, kultural, dan alternatif yang memaksa penguasa pasar menghargai sumber berkesenian sebagai perayaan hidup dalam festival?' (Kompas Minggu, 24/4/05). Kemudian, upaya apa untuk menjembatani persoalan kritik? Suka Hardjana selalu menyarankan, bahwa disamping kritik, jembatan tengah agar tidak terjadi kesenjangan antara publik dan karya seni adalah dengan apresiasi. Dalam kondisi keterasingan karya seni dengan publiknya, kritik tidak mungkin beroperasi secara ideal. Oleh karena itu, pesanpesan apresiasi dibutuhkan untuk menjembatani jarak kesenjangan antara kritik, seni dan publiknya. Tujuan kritik seni adalah evaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke arah yang lebih kreatif dan inovatif. Bagi masyarakat, kritik berfungsi memperluas wawasan. Bagi seniman, kritik tampil sebagai 'cambuk' kreativitas. Benarkah demikian? Bagaimana seandainya WS. Rendra mengatakan dengan tegas bahwa ia sangat benci dengan kritikus? Pada tahun 1894, Bernard Shaw menulis sebuah artikel menarik berjudul How To Become a Music Critic, yang lantas dipublikasikan kembali di New York melalui New Music Review pada tahun 1912. There are three main qualifications for a music critic, besides the general qualification of good sense and knowledge of the world. SMS: Short Music Service 70 Salah satu kecakapan kritikus musik bagi Bernard Shaw adalah bahwa kritikus memiliki pengetahuan tentang dunia. Jika Jakob Sumardjo memberi pemaparan bahwa kritikus seni bersifat achieved status, kiranya hal itu memang benar. Di Indonesia, siapa yang berani dengan lantang menyebut dirinya kritikus musik? Hal ini kiranya akan menjadi persoalan serius. Wacana Kritik Musik Generasi silam, Amir Pasaribu misalnya, memulai 'koarkoar' dengan bahasa kritiknya yang pedas dengan menerbitkan buku Analisis Musik Indonesia (1986). Suka Hardjana menerbitkan dua buah buku (Esai dan Kritik Musik, 2003; Musik Antara Kritik dan Apresiasi, 2004) yang isinya berupa tulisan-tulisan tajam yang menguliti berbagai aspek musik. Dr. FX. Soehardjo Parto (alm.) dulunya sangat sering menulis di harian Kompas untuk mewacanakan pengetahuan tentang bagaimana sebetulnya musik yang tepat dan layak dikonsumsi (Musik Seni Barat dan Sumber Daya Manusia, 1995). Begitu pula Prof. Dieter Mack, yang punya kontribusi penting bagi gairah kritik musik di Indonesia. Pada tahun 2002, Sutanto Mendut menerbitkan buku Kosmologi Gendhing Gendheng yang cukup cermat mencatat pengalamannya dan menyampaikan wacana musik diselingi bahasa kritik yang ringan namun tajam. Hingga kini, Sutanto masih aktif mengkritisi fenomena musik. Selain nama-nama di atas, tentu muncul nama lain seperti Franki Raden, Remy Silado, Slamet Abdul Syukur, Yohanes Bintang Prakarsa, yang turut 'menegangkan' suasana kehidupan musik dengan gayanya masing-masing yang khas. Buku-buku, maupun berbagai publikasi tulisan yang berisi SMS: Short Music Service 71 kritik musik adalah semacam penggairahan provokatif sebagai wujud kecintaan manusia akan musik. Pada prinsipnya, kritik musik menjadi suatu gejolak yang memiliki nilai khas, karena ia menerangkan, menjelaskan, dan menginginkan kesempurnaan asumsi atas kehidupan kesenian yang berlangsung. Mengkonsumsi atau menelurkan kritik bukanlah momok yang dijauhi masyarakatnya. Kritik akan memicu gairah dan membuktikan bahwa kehidupan menjadi dinamis. Sederet aktivitas kritik musik di Indonesia pernah terjadi secara mengejutkan, namun kini, agaknya sudah jarang lagi muncul atmosfir kritik musik. Bahkan, kritik musik telah lama mengalami 'tidur panjang'. Di beberapa media, ulasan musik hanyalah membicarakan seputar pementasan musik yang hanya bersifat review oleh wartawan, ataupun pengamat musik yang masih setengah hati untuk menyebut dirinya sebagai kritikus musik. Jika mau jujur, dunia kritik seni rupa lebih maju dibandingkan dengan kritik musik. Dalam dunia seni rupa Indonesia, ada beberapa orang yang berani mencantumkan 'label'nya sebagai kritikus seni rupa. Sudarmadji, Sanento Yuliman, Jim Supangkat, Kuss Indarto, adalah sederet namanama kritikus seni rupa yang berpengaruh. Hal ini adalah keberanian yang musti dihargai. Persoalan profesi (kritikus) seringkali menjadi persoalan penting, yaitu ketika sepak terjang seseorang, dalam ketegasan-ketegasan penobatannya, ikut ambil bagian dalam kehidupan seni. Kritikus musik di Indonesia masih (melulu) dianggap/terkesan terlalu ekslusif, seolah keberadaannya sangatlah tiada penting. Padahal tidaklah demikian. Nama-nama Eropa (Jerman) seperti Robert Schumann dan SMS: Short Music Service 72 Richard Wagner pernah sama-sama disebut sebagai seniman yang sekaligus kritikus. Pada zamannya di abad ke-19, mereka adalah orang-orang yang aktif dalam panggung pementasan, namun juga terlibat dalam kegiatan jurnal musik dan wacana perdebatan lainnya. Richard Wagner menentang keras musik Brahms dengan tudingan-tudingan yang tidak mengenakkan jika didengar, sama ketika Adorno dengan pandangannya yang terkesan subyektif a là Marxis, menuding musik Stravinsky sebagai musik 'plagiat' masa lalu yang sama sekali tidak kreatif. 'Prosedur musik Neo-Klasik sangatlah otoriter karena komponis bisa seenaknya memotong musik tertentu yang terkait dengan sejarahnya (misalnya musik Klasik dalam zamannya sendiri) dan kemudian menyusunnya kembali sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sehingga, musik yang dihasilkan Stravinsky tidak mempunyai obyektivitas'. Sebetulnya, apakah fungsi kritik selalu bersifat justifikasi, menuding, menghukum, mencela, atau memberi 'kebencian' yang tajam terhadap seniman atau karya seni? Tidakkah posisi kritik sebenarnya justru menjembatani (sebagai pengetahuan) antara karya seni dan publik; juga seniman dan publik. Haruskah kritik melulu mencela? Suatu kritikan yang baik bukanlah tindakan menudingnuding hidung orang dan menggarisbawahi titik-titik lemah karya seni orang yang bersangkutan. Sebaliknya, tulisan kritis mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal menarik yang terdapat dalam karya seni yang sedang disoroti. Dengan demikian, kritik musik tentulah menjadi mediator yang keberadaannya musti disikapi dan diikuti seiring, seimbang, dan sejalan dengan kehidupan kekaryaan musik beserta dinamika kehidupannya. Sealu Terbuka Terhadap Kritik Komponis bukan menjadi Raja bagi musiknya. (Otto Sidharta) P emusik, komponis, atau 'pengrajin' musik pada umumnya harus terbuka terhadap kritik. Di situlah ada kehidupan, dinamika. Para pekerja seni sehebat apa pun, jika tidak dapat menerima kritik, ia tidak akan berlaku dalam rel sejarah dan akan menjadi asing. Bahwa kritik itu bukan cemooh, bukan suatu penghinaan, atau berusaha mengecewakan yang dikritik. Sejatinya, kritik wujud perhatian. Gemati, orang Jawa bilang. Jika karena kritik manusia menjadi benci, lemah, tidak lagi termotivasi, berarti ia tidak menganggap manusia lain yang melingkupinya ada dalam sejarah. Berhentilah berkarya saja, dan hiduplah sendiri dalam keterasingan dengan cukup ditemani lampu 5 watt. Belakangan, selama 2 3 tahun terakhir saya mencoba memasuki ruang-ruang diskusi. Dari obrolan skala SMS: Short Music Service 74 tongkrongan, kampusan, tidak formal sampai ke tingkat seminar. Pembicaraan kadang lari kemana-mana. Ada yang tetap bertahan dan fokus. Ada yang membingungkan dan cenderung berputar-putar seperti itu saja, monoton. Ada yang tak tentu arah, tak punya tujuan. Pada berbagai persoalan menarik seputar kehidupan, saya jadi terjerumus ke aneka pengetahuan, tak cuma musik. Pada titik tertentu saya harus berjuang keras melatih pola pikir kritis terhadap fenomena musik yang melingkupi lingkungan yang saya hadapi, yang biasanya sangat bersifat fenomenologis. Hal ini lantas memotivasi untuk berpikir lebih jauh mengenai kritik. Hingga pada saatnya saya (cukup) menemukan esensi dari hal itu. Bahwa kritik itu cuma asesoris, belum tentu menjadi penting namun keberadaannya dibutuhkan. Kadang-kadang dualisme. Sering tidak digubris, namun ternyata abadi. Menyakitkan tapi memotivasi. Agus Noor dalam Matinya Toekang Kritik (2006) bilang, “dikritik memang sakit, lebih sakit lagi jika kritik tidak didengar”. Ini menunjukkan bahwa orang harus terbuka terhadap kritik, tanpa alasan apapun. Tanpa tedeng aling-aling. Dari ratusan pementasan musik yang saya tonton di berbagai kesempatan, tidak semuanya memberi kenikmatan pada nurani saya. Ada yang janggal, itu pasti. Jika berkesempatan bertemu dengan pemusik yang saya tonton, kiranya saya tak segan berbicara sejenak dengan mereka. Menyampaikan sesuatu, entah dianggap kritik atau masukan. Ada beberapa teman pemusik yang selalu meminta kritik seusai pementasan. Saya menyampaikan sesuatu sebatas yang saya ketahui saja. Dan ternyata ini adalah sarana komunikasi. Ketika penonton (publik) dan seniman itu berdialog. Bukan saling menjatuhkan, tetapi sama-sama SMS: Short Music Service 75 memperjuangkan kesenian. Dalam musik, tabiat pola pikir kritis yang keras seperti yang dipunyai sosok yang saya kagumi semacam Halim HD, Suka Hardjana, Sutanto Mendut, Agus Bing, adalah bagian indikator adanya dinamika kehidupan seni. Tanpa mereka seolah dunia musik menjadi kering tak ada gairah. Kata-kata yang mereka lontarkan kadang-kadang sarkastis, menyiksa batin, namun sungguh, kata Agus Bing, tidak ada maksud apa-apa di balik itu, selain mencoba memunculkan tegangan demi perjuangan mencari hakikat seni yang ideal. Karena wujud perhatian dan cinta, sama-sama peduli untuk membawa ke kehidupan lebih baik. Keberadaan mereka membuat decak kagum yang cukup menggugah saat otak saya sedang tumpul. Demikianlah, jika beberapa pelaku kritik musik yang saya contohkan di atas dianggap selalu mewakili lintas diskusi untuk penggairahan provokatif, maka sebaiknya pikiran mereka dipelajari dan disaring untuk melakukan pemahaman-pemahaman lebih dalam lagi. Sekalipun, banyak sekali orang yang masih bisa ditemui sebagi gudangnya bahasa kritik. Sejauh saya menyimak berita koran, membaca ratusan buku dan ulasan musik, para kritikus musik sepertinya malu menyebut diri mereka sebagai kritikus. Hanya satu orang yang berani mencantumkan label Kritikus Musik, dia adalah Yohanes Bintang Prakarsa, saat menulis Amir Pasaribu, Riwayatmu Kini (Kompas, 2003). Pertanyaan saya, apakah memang dunia kritik musik tidak menjejakkan kakinya di tanah seni yang pasti? Apakah profesi ini memang tidak begitu menjadi prioritas, karena semua lahan sudah ada di tangan seniman (komponis) ? Mungkin demikian adanya. Akan sangat berbeda ketika kita mencoba membandingkannya SMS: Short Music Service 76 dengan dunia seni rupa, atau sastra misalnya, yang bertebaran kritikus dimana-mana. Namun bukan itu yang menjadi persoalan. Kritik, siapa pun dan apa pun isinya, berhak dihadirkan oleh siapa saja yang empunya bakalan mengkritik. Jika karya seni itu bakwan, kritik itu cabe rawitnya. Oleh sebab itu, siapa pun manusia berhak melakukan kritik, tidak usah terlalu resah berpikir tentang identitas yang menempel di tubuhnya. Jika siapa pun bersikap simpati akan kesenian, orang akan melemparkan penilaian, serangan, kritik, hujatan, komentar, yang mengarah ke tujuan konstruktif. Jika banyak orang memilih diam dan tidak bisa bergerak melihat berbagai kondisi yang kurang pas, maka inilah yang akan membawa ke tingkat destruktif. Jadi, siapa pun berhak mengkritik, dan siapa pun harus terbuka terhadap kritik. Soundscape Gaya Tony T ampil dalam Pekan Komponis ke-11, Tony Maryana bereksplorasi dengan bermacam perangkat noninstrumen musik. Berbicara tentang “Putaran I dan II” karya Tony Maryana sebetulnya hanya tinggal meneruskan saja apa yang pernah dikehendaki John Cage ketika menciptakan First/Second/Third Construction in Metal antara tahun 1939 1941. Jika John Cage, yang ketika itu (60-an tahun yang lalu!) telah berhasil memanfaatkan hampir sebagian besar idiom metal pada karya perkusinya, Tony telah mencoba bereksplorasi dengan tanah, air, aluminium, kaca, kelereng, sampai amplas, untuk sekedar menghasilkan konstruksi bunyi baru yang diinginkannya, meski sesungguhnya, ini jelas bukan sejarah yang baru. Pemikiran Tony untuk mengeksplorasi segala kemungkinan auditif perkusif yang bisa 'dimungkinkan' dari apa yang 'mungkin' menjadi sesuatu yang menarik. Tidak SMS: Short Music Service 78 heran jika karyanya yang dipentaskan oleh KESPER (Kelompok Studi Perkusi) ISI Yogyakarta: Bayu, Cesar, Wasis, Bagas, pada Pekan Komponis 11 yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta, 9 Desember 2005 di STSI Surakarta cukup memberikan daya pikat kepada banyak penikmat. Penuh Ketakterdugaan Musik, dalam wilayah penikmatan akan bunyi, tentu bukan persoalan baru. Wilayah auditif yang sengaja/bisa dihasilkan oleh idiom apapun yang (kadang-kadang) tidak masuk akal justru menjadi re-presentasi simbolis untuk menghasilkan sound yang unik. Seperti itulah yang saat ini banyak dicari komponis experimental music. Karya Tony, pemuda asal Bandung ini, mengolah keunikan timbre, tekstur, kompleksitas pengolahan tema, rhythm and duration, aktualisai ide dalam mewujudkan komposisinya. Meski tampak sangat 'jor-joran' dan boros dalam memanfaatkan segala kemungkinan bunyi perkusif, biarkan itu terjadi pada sosok yang selalu ber-eksplorasi dengan kreativitas ini. Demikian penting dan dihormatinya alat musik sebagai medium penyampaian bahasa ekspresi diri sehingga boleh dikatakan bahwa instrumen adalah sebuah privilege yang sangat pribadi bagi pemainnya (Suka Hardjana: 2003). Ternyata, justru inilah yang menarik perhatian dan akan menjadi sebuah permasalahan estetika musik yang penting untuk dicermati. Komposisi ini tidak lahir sebagai karya yang melodius atau harmonis. Juga, bukan diciptakan untuk memperindah suasana atau berimajinasi dengan keteraturan kalimat musik yang bisa diprediksi sebelumnya. Menyaksikan karya Tony berarti harus bersiap untuk ketegangan dan ketakterdugaan SMS: Short Music Service 79 yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Selalu mengagetkan penonton, kadang memunculkan kesan lucu yang spontan dan menimbulkan tawa pelan dari kursi penonton. Misalnya ketika pemain meniup air lewat selang yang menimbulkan bunyi: “blekhutuk-blekhutuk...”, atau oleh bunyi lempengan metal yang setelah dipukul lalu dimasukkan dalam air hingga menimbulkan timbre menarik yang tak pernah terduga sebelumnya. Marshall McLaughan pernah mengatakan, “alat menentukan cara”. Sementara, David H. Cope dalam bukunya New Direction in Music (1984) pernah mengatakan bahwa untuk mencipta karya baru (musik perkusi), dalam usaha pencapaian estetika (performance) dibutuhkan kejelian terhadap mallet: jenis mallet yang digunakan, cara memperlakukannya, penempatan yang tepat pada instrumen, dan memerlukan notasi yang sangat berbeda dan baru. Tony, yang menimba ilmu di Jurusan Musik, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini memang jarang menciptakan karyakarya komposisi melodius atau 'yang indah-indah'. Komposisinya tidak mengajak orang bernyanyi. Hampir sebagian besar dasar kreativitasnya ada pada suasana ritmikal, yang perkusif, yang dipukul. Tony juga menggunakan noise dan sound-scape pada karya ini, meski bukan 'soundscape lepas' suatu istilah yang diberikan Tony untuk mengidentifikasi gaya kompositorisnya, yang artinya tidak menggambarkan representasi riil kehidupan manusia. Bukan Kebaruan James R. Brandon pernah meneliti relief yang ada di Angkor (abad ke-13) dan menemukan sejumlah pahatan alat perkusi yang bermacam-macam. Karya Tony mencoba membaca SMS: Short Music Service 80 kembali sejarah musik perkusi ratusan tahun silam dan merepresentasikannya lewat isu-isu kekinian yang terkait dengan wilayah filsafat atau teori musik Barat abad ke-20, serta mengolah berbagai kemungkinan musikalitas dengan gaya-gayanya yang lugas, sederhana saja, walaupun kompleks. Sesungguhnya, di sini tidak ada lagi kebaruan, barangkali hanya sekadar perlakuan yang berbeda pada sejumlah instrumen, itupun hanyalah untuk menghasilkan bunyi yang berbeda, otak-atik gatuk atas pengolahan kreativitasnya. Vibraphone yang digesek dengan bow adalah suatu perlakuan 'coba-coba' yang menarik, sama ketika Jimy Page (Led Zepellin) pada tahun 70-an sudah memperlakukan gitar elektriknya, menggesek senar keras-keras dengan bow. Dody Satya memperlakukan sitar dengan cara petik yang dibantu putaran roda tamiya, atau Motohide yang menggesek simbal juga dengan bow, semua telah dilakukan. Namun, parameter kreativitas di sini bukan hanya berlomba-lomba untuk memunculkan kebaruan pada suatu karya. Sejarah telah dilahirkan dan kita tinggal melanjutkannya atau ingin menjadi bagian penting dalam sejarah. Rasanya kurang tepat jika pada posisinya komponis selalu mencari kebaruan. Suatu karya adalah (setidaknya) sudah menjadi bagian dari karya orang lain yang pernah dilakukan. Representasi atas kebekuan sejarah telah digedor habishabisan oleh komposer-komposer revolusioner generasi awal perintis musik perkusif baru: John Cage, Edgard Varèse, Carlos Chavez, maupun John Becker. Kategori komposer lain, avantgardis yang terkenal dengan karya perkusinya seperti Karlheinz Stockhausen, Larry Austin, Frederic Rzewski, Harry Partch, Edward Miller, Mario Bertoncini, Peter Garland, William SMS: Short Music Service 81 Kraft, dll, telah banyak melakukan eksperimen yang menghentakkan jantung. Bahwa 'kepusingan-kepusingan' naluri, imajinasi, néko-néko, keanehan-keanehan telah melanda peradaban musikal sejak paruh kedua abad ke-20. Saat ini semua serba menjanjikan, semua mengijinkan, hampir semua telah men-sahkan. Tetapi hati-hati, Frederic Jameson pernah berkata demikian, “Ciri utama (posmodernisme) adalah munculnya bentuk baru kedataran dan kedangkalan, sebuah bentuk baru kecintaan akan permukaan saja !” Yogya, Des. 2005 Persoalan (Ilmu) Musik J aques Atalli pernah mengatakan bahwa musik berada dalam dua wilayah. Pertama, musik sebagai seni; kedua, musik sebagai ilmu. Tidak semua musik dapat dikategorikan sebagai seni. Dalam beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh Jakob Sumardjo dalam bukunya Filsafat Seni (2000) terdapat beberapa pendapat yang menegaskan bahwa ilmu dan seni adalah (jelas) suatu hal yang sangat berlainan. “Ilmu seni harus dibedakan dengan seni. Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk dinikmati, sementara ilmu seni untuk memahami.” Pengetahuan tentang seni bukan hanya berhubungan dengan penciptaan karya seni dan penghayatan karya seni, tetapi juga pemahaman tentang karya seni. Peran Kritikus Musik seringkali mendapat tempat di sini. Uraian-uraian yang menjembatani karya seni dengan publik disampaikan oleh Kritikus. Tidak sepenuhnya Kritikus berposisi sebagai pencela SMS: Short Music Service 84 dalam setiap ruang gerak pengembaraannya. Kritikus Musik menjadi mediator untuk pemahaman-pemahaman seni. Tumpul-runcingnya perkembangan musik dapat dilihat melalui peran Kritikus Musik dalam memberikan wacana 'pembenahan' dalam segala kekurangan yang ada pada karya seni sebagai obyek maupun publik seni sebagai subyek (apresian). Seringkali publik, sebagai manusia yang terlibat dalam tumbuhnya kebudayaan musik, hanyalah berposisi sebagai penikmat yang dangkal. Musik sebagai hiburan adalah tren yang telah menggejala di banyak sendi-sendi kebudayaan dalam banyak wilayah/negara. Pop, sebagai salah satu jenis musik yang ada di dunia ini, banyak memberi kesempatan ruang hiburan bagi penikmatnya dibanding art music yang menempatkan konteks filsafati dalam setiap ruang eksistensinya. Parameter yang terjadi sekarang ini, bagi perkembangan musik di Indonesia, hanyalah—dalam bahasa—ekstrimnya melulu diukur dari suksesnya penjualan album pelaku musik pop. Platinum, Double Platinum; dan sejenisnya. Prestasi-prestasi tersebut hanyalah bersifat artifisial, yang mengabaikan segi-segi kualitatif-prestasi yang mestinya menjadi bagian utama dalam mempelajari dan mengembangkan kebudayaan suatu bangsa. Hipotesa ini bukan berarti menyudutkan seni pop dalam kerangka kebudayaan. Dalam budaya pop, ada kategori tertentu yang disebut seni pop. Seni pop bukanlah seni yang gagal menjadi seni “riil”, tetapi seni yang berlaku dalam lingkup umum. Marie Lloyd (pemikir Charles Dickens, Charlie Chaplin dan musisi jazz) mendefinisikan seni pop sebagai berikut: SMS: Short Music Service 85 Jika ia memiliki banyak kesamaan dengan seni lokal maka ia akan menjadi seni individual yang ada dalam budaya sastra komersial. Unsur “lokal” tertentu terbawa, bahkan seniman itu menggantinya dengan seniman anonim, “gaya” itu akan lebih tampak pada pembuatnya dibandingkan dengan gaya komunal. Hubungan di sini lebih kompleks seni tidak lagi dibuat oleh orang bawah dalam interaksi, dengan cara pengaturan perwujudan dan perasaan, pemantapan kembali hubungan. Meskipun seni ini tidak lagi mengarahkan penciptaan “pandangan hidup” suatu “komunitas organis” dan ia bukan lagi “dibuat oleh orang-orang”, namun ia masih menjadi masalah yang tidak bisa diterapkan pada seni tinggi, seni pop untuk rakyat. Tidak ada suatu batasan yang memberikan justifikasi bahwa musik pop merupakan citra buruk peradaban musik sampai abad ini. Apa yang mencirikan image yang terkesan buruk pada musik pop terletak pada pendangkalanpendangkalan kreativitas. Orientasinya bukan pada penciptaan seni otonom, melainkan sudah memasuki wilayah take and give dalam kerangka bisnis mahaluas yang kian digemari. Pop mencirikan ada uang dibalik penjualan kaset; royalti; laba konser yang besar, dsb. Inilah yang dinamakan golabalisasi-industri, musik seperti laiknya barang saja, dan bukan roh atas ungkapan jiwa yang sejujurnya, menjadi bukan ekspresi (ke)manusia(an). Terutama musik pop, sangat terkait dengan perkembangan teknologi. Kemunculan teknologi rekaman membantu begitu pesat kemajuan pendistribusian/produksi kaset-kaset yang bisa dengan cepat disebarluaskan ke penjuru dunia. Orang lantas tertarik, membeli, dan menonton konser, akhirnya jadi SMS: Short Music Service 86 seorang pemuja. Industri musik yang naik daun sejak ditemukannya teknologi rekaman, memaksa para masyarakat untuk menikmati sisi “dunia yang dilipat” (meminjam istilah Yasraf Amir Piliang). Satu kilometer menjadi satu centimeter. Pada abad-abad sebelum abad ke-20 (baca: > abad ke-19), untuk menyaksikan sebuah konser musik, masyarakat harus rela berjalan kaki sejauh puluhan kilometer, untuk menonton pementasan musik yang tidak bisa diulang lagi. Bandingkan dengan, apabila kita memutar kaset yang berisi rekaman konser musik, hari ini kita tidak usah pergi jauh, cukup di kamar tidur, memutarnya, dan jika kita ingin, esok pagi kita bisa memutarnya kembali. Istilah ini, oleh Dr. Suhardjo Parto yang mengutip pandangan Otto Karolyi, disebut modus pengulangan. Roy Suryo mengatakan bahwa perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan moral, etika, sosial, dsb. Pendapat Roy memang benar. Bahwa teknologi setiap detik terus berkembang, dengan munculnya internet yang “on-line”, setiap orang diijinkan mengakses apa saja yang ada di dunia. Semua nyaris bisa terakses. Teknologi berkembang pada setiap detiknya. Memunculkan keuntungan tersendiri bagi banyak orang. Sekaligus, teknologi, jika tidak dimanfaatkan dengan wajar dan sebenar-benarnya, akan menimbulkan “cedera” bagi masysrakat. Teknologi bisa pula membahayakan. Karya seni sebagai kekuatan untuk keberlangsungan kebudayaan di Indonesia, harus diakui pula, masih berada dalam tataran minor. Persepsi mengenai keterbelakangan posisi dalam lini kebudayaan menyebabkan kehidupan kesenian sebagai faktor sampingan yang tidak layak disebut sebagai 'elemen inti' kebudayaan. Kemajuan peradaban bangsa masih saja dilihat dari kemajuan politik dan ekonomi SMS: Short Music Service 87 semata. Plato pernah berpendapat bahwa seni memiliki peran utama untuk kemajuan suatu negara, dan ini belum terbukti secara menyeluruh di Indonesia. Wacana yang dapat mengkaji hal ini salah satunya adalah cultural studies. Kajian budaya atau cultural studies adalah gerakan keilmuan atau praksis kebudayaan yang mencoba secara cerdas dan kritis menangkap semangat teori-teori budaya, “kepentingan elite budaya dan kekuasaan”, sembari mengkukuhkan perhatiannya pada budaya-budaya yang selama ini tidak terjamah atau tak diakui oleh ilmu-ilmu sosial humaniora tradisional yang telah mapan. Karena sifatnya yang kritis, tak mengherankan jika kemudian teori budaya atau kajian budaya memiliki sifat disiplin dan metodologi yang sangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang sudah mapan yang umumnya disipliner. Kajian budaya dalam hal ini bersifat eklektis. (Melani Budianta, 2002). Harus diakui, bahwa Musikologi, sebagai ilmu seni, bukan penghayatan, memang tidak begitu berkembang di Indonesia. Dalam konteks ilmu sejarah, hal ini agaknya kurang diminati. Hipotesa ini semakin kuat apabila ditinjau mengenai kompleksitas wacana yang ada pada kehidupan musik Indonesia saat ini, apa yang menjadi mayoritas? Barangkali, yang menjadi kegamangan banyak masyarakat, adalah dalam konteks perkembangan budaya musik akhir-akhir ini. Suka Hardjana mengatakan, kalau mau tahu perkembangan musik Indonesia lihatlah televisi. Musikologi—sebagai ilmu seni (musik) hampir serupa dengan art music yang kurang memiliki tempat layak dalam urusan publishing dan apresiasi pada masyarakat luas. Di tivi jarang muncul konser klasik misalnya, dan kebanyakan pop. Dalam kerangka industri, klasik itu tidak laku. Masyarakat SMS: Short Music Service 88 banyak tidak tahu apalagi apa itu Musikologi? Bagaimana implikasinya dalam perkembangan musik Indonesia di abad ini. Apakah Musikologi menjadi wilayah ilmu minor yang kurang sesuai dengan 'perubahan jaman' jika dipelajari? Disamping mempelajari sejarah, konteks zaman, analisis, teori musik, kritik musik, dll., musikologi meluaskan pandangan kita untuk 'membaca' fenomen musik apa pun yang sedang berkembang. Musikologi adalah ilmu yang luas, seperti ilmu filsafat. Kebutuhan akan seni dan kebutuhan akan ilmu seni menjadi poin yang proporsional untuk masyarakat. Jika keduanya seimbang, kehidupan musik ini akan menjadi lebih dinamis dan tidak (semakin) terjebak dalam kondisi artifisial saja. Yogyakarta, 2005 Jagad Perbukuan Musik di Indonesia M usik telah menjadi kebudayaan yang dijalankan manusia dari zaman pra-sejarah hingga saat ini. Oleh sebab itu, keberadaan musik menjadi kebutuhan bagi hampir semua orang di dunia. Musik hanyalah persoalan pendengaran, sementara, sisi lain untuk mengetahui informasi seputar musik—salah satunya—bisa kita dapatkan melalui buku musik. Buku adalah jendela dunia, demikianlah kata pepatah yang sangat populer. Dengan buku, kita bisa mengetahui dunia. Sedangkan, buku musik adalah jendela 'dunia musik'. Buku musik berisi informasi musik, antara lain mengenai sejarah musik, sifat dan fungsi musik, ketokohan, jenis dan teknik bermain instrumen, teknik menulis komposisi, atau seputar wacana musik yang sedang berkembang. Di banyak toko buku, kita sering menjumpai buku-buku musik yang mayoritas berisi informasi tentang cara cepat belajar alat musik seperti gitar, drum, bass, serta informasi SMS: Short Music Service 90 seputar lagu dan akor, yang sedikit-sedikit juga disisipi informasi tokoh musik (pop); atau pun, informasi tentang bagaimana mengelola pertunjukan musik. Yang sering kita jumpai tersebut adalah buku kategori populer (baca: berisi informasi praktis dan tepat guna). Adakah buku musik yang berbicara lain? Tentu ada. Dalam tulisan ini saya akan memaparkan ringkasan perjalanan acak penulisan buku musik non-populer. Untuk memudahkan, saya menyebutnya dengan istilah buku musik ilmiah, karena beberapa buku ditulis dengan berdasarkan ilmu musikologi, psikologi, sosial, yang rata-rata ditulis oleh para akademisi dan pakar musik. Di Indonesia, dekade 70-80-an, misalnya, pemikir musik seperti Amir Pasaribu, Sumaryo L.E, Suka Hardjana, Binsar Sitompul, telah membuat catatan-catatan bersejarah mengenai musik seni (art music), entah suatu peristiwa yang terjadi di Barat maupun Indonesia. Musik, pada saat itu telah menjadi kegiatan budaya yang banyak diminati, khususnya dengan banyak didirikannya pendidikan musik. Misalnya, Sumaryo L.E., telah menulis buku berjudul Komponis, Pemain Musik dan Publik (Pustaka Jaya Jakarta, 1978), yang menjelaskan cukup detail mengenai bidang penciptaan musik, penyajian musik, serta mengenai publik. Dalam buku setebal 134 halaman itu kita dapat mencari banyak informasi musik yang berguna, seperti sekilas sejarah pendidikan musik di Indonesia, jenis dan karakter alat musik, serta sifat-sifat yang lebih khusus dalam musik. Amir Pasaribu juga menulis buku Analisis Musik Indonesia (Pantja Simpati Jakarta, 1986), yang berisi banyak kritik tentang kegiatan musik. Amir Pasaribu juga menganalisis lagu Indonesia Raya, menjelaskan tentang apa arti musik, menjelaskan pula tentang tokoh-tokoh musik seperti Johann Sebastian Bach, SMS: Short Music Service 91 Zoltan Kodaly, Sergei Prokofiev, sampai Debbusy; serta hal lain yang lebih spesifik dan menarik. Binsar Sitompul menulis: Cornel Simanjuntak: Komponis, Penyanyi, dan Pejuang (Pustaka Jaya Jakarta, 1987), yang memaparkan detail kehidupan Cornel Simanjuntak, salah satu tokoh penting musik Indonesia. Suka Hardjana juga menulis buku yang sangat penting berjudul Estetika Musik (Depdiknas, 1983), yang menguraikan dengan detail arti dan sifat musik, keindahan musik, dan manfaat musik. Selain nama-nama yang dicontohkan di atas, kita juga harus mengetahui keberadaan Liberty Manik, J.A. Dungga, Yapi Tembayong, yang pernah pula menulis buku-buku serupa demi keperluan (khususnya) pendidikan musik negeri ini pada saat itu. Yapi Tembayong adalah orang pertama yang menulis buku Ensiklopedi Musik Indonesia (1992) sebanyak dua jilid. Ponoe Banoe pernah pula menulis Pengantar Pengetahuan Alat Musik (CV. Baru Jakarta, 1986), yang berisi informasi seputar alat musik dari berbagai jaman. Lalu, di tahun 1990-an, adalah Karl. Edmund Prier, SJ (Romo Prier), dari Puskat Yogyakarta yang kemudian menulis buku penting yang jadi pegangan mahasiswa musik hingga saat ini, yaitu Sejarah Musik jilid 1 dan 2 (PML Yogyakarta, 1994). Disusul, Dieter Mack menulis Sejarah Musik jilid 3 dan 4 (PML Yogyakarta, 1995). Kedua pemikir tersebut samasama menulis sejarah musik yang sangat berguna bagi kehidupan musik seni di Indonesia. Mereka menulis sejarah musik dari jaman pra-sejarah hingga tahun 1990-an. Di wilayah penciptaan musik seni Indonesia, tahun 1970-an muncul nama-nama seperti Slamet Abdul Syukur, Paul Goetama, Trisutji Kamal, Tony Prabowo, dll. Selain itu, mereka berdua juga menulis banyak buku musik SMS: Short Music Service 92 non-sejarah yang keberadaannya juga sangat penting. Dieter Mack telah menulis beberapa buku penting seperti Apresiasi Musik Populer (IKIP Bandung, 1995); Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural (ArtiLine, 2001), dan Pendidikan Musik, Antara Harapan dan Realitas (UPI Bandung, 1997), maupun Ilmu Melodi (PML Yogyakarta, 1996). Romo Prier juga banyak menulis buku musik rohani, teknik bermain organ, dan teknik memimpin paduan suara. Buku sejarah musik lain yang bisa kita temui adalah tulisan Roderick J. Mc.Neill: Sejarah Musik 1 (PT. Gunung Mulia Jakarta, 1996) dan Sejarah Musik 2 (idem, 2001). Buku ini juga sangat menarik dan perlu, meski saat ini susah ditemui. Penulis sejarah musik ini justru berasal dari luar Indonesia, namun perhatian mereka terhadap kehidupan musik negeri ini pantas dihargai. Maka, jasanya adalah besar bagi perkembangan musik seni di negeri ini. Di tahun 2000-an, muncul nama seperti Djohan Salim, yang tiga kali berturut-turut menulis buku: Psikologi Musik (Buku Baik, 2003), Terapi Musik (Galang Press, 2006), Matinya Efek Mozart (Galang Press, 2007). Djohan memberi kontribusi penting bagi wacana psikologi musik di Indonesia, sebuah bidang yang belum begitu populer. Triyono Bramantyo menulis, Disseminasi Musik Barat di Timur (Tarawang Press Yogyakarta, 2004); buku ini penting karena memaparkan sejarah masuknya musik barat ke timur (Jepang dan Indonesia), yang secara khusus disebarkan melalui aktifitas misionaris di abad ke-16. Suka Hardjana, salah satu ilmuwan musik penting yang kita miliki, juga menerbitkan kumpulan tulisannya menjadi buku berjudul Musik, Antara Kritik dan Apresiasi (Buku Kompas, 2004), Esai dan Kritik Musik (Galang Press, 2003), Corat-Coret Musik Kontemporer (MSPI, 2003). Keberadaan buku Suka Hardjana tersebut menjadi sangat SMS: Short Music Service 93 penting karena di situ tertulis peristiwa-peristiwa musik seni dari tahun 1970 hingga 2000-an yang bisa dijadikan parameter untuk membaca sejarah musik seni di negeri ini. Kita bisa menyimak siapa saja pemusik-pemusik penting dari berbagai negara yang pernah berpentas di Indonesia. Tulisan ini memang tidak memaparkan secara tuntas mengenai siapa saja yang pernah menorehkan sejarah di bidang penulisan buku musik kategori ilmiah. Dan, saya yakin masih banyak nama-nama lain yang belum tersebutkan di sini. Namun, setidaknya, sekilas rentetan acak wacana perbukuan musik ini bisa membantu kita mengenal wacana musik yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika Anda mencari dan membaca buku-buku tersebut. Semuanya pasti bermanfaat untuk menambah kepustakaan Anda, sekaligus wawasan musik tentu bertambah. Jurusan Musik SMK 8 Solo: Sejarahmu Kini dan Esok J urusan Musik (Diatonis) SMKN 8 Surakarta sudah menginjak usianya yang ke-8 tahun dalam menjalankan pendidikannya, tepatnya pada tahun 2005/2006 ini. Bukan perkara yang mudah untuk (sekadar) mewujudkan judul sederhana di atas, yang (mungkin) penuh tantangan dan sulit untuk dilakukan. Satu prioritas utama bagi penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk sekolah kejuruan, adalah upaya memikirkan kesinambungan kompetensi yang dipelajari, serta mempersiapkan para siswa-siswinya untuk mampu terjun di dunia kerja seni, tentunya musik sebagai spesifikasi utama. Keberlangsungan suatu pendidikan di sekolah manapun, keberhasilannya, tidak bisa terlepas dari peran kontinu yang dilakukan guru, murid, dan segenap pengelola sekolah. Guru dan murid adalah dua elemen paling vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Murid belajar dari guru, dan sebaliknya, guru juga harus dengan rendah hati mau belajar SMS: Short Music Service 96 dari murid. Interaksi yang kondusif antar guru dan murid akan menyebabkan pendidikan berjalan dengan dinamis. Satu sekolah adalah satu tubuh, satu kerja, dan satu penggerak. Apa yang diyakini sebagai penggerak, adalah terletak pada kekonsistenan masing-masing elemen sekolah dalam merealisasikan pengajaran dengan profesional, memberikan pendidikan yang betul, dan berupaya keras mewujudkan citacita masa depan. Salah satu bahaya yang muncul di Jurusan Musik sekarang ini, adalah semakin berkurangnya guru, karena baru saja ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bagi mayoritas guru (GTT) yang ada. Yang telah berlalu, tahun ke-1 sampai ke-7, perkembangan Jurursan Musik belum mampu dibaca secara gradual (tidak selalu ada peningkatan berarti setiap tahunnya), atau cenderung statis. Hal ini adalah sorotan yang harus segera dibenahi, mumpung belum terlanjur. Memang, usia Jurusan ini baru seumur jagung. Keterbatasan guru, kesejahteraan yang kurang mencukupi bagi para guru (yang mayoritas GTT), juga salah satu penyebab, perkembangan jurusan itu terasa seret, selain terbatasnya fasilitas yang ada. Tentu, kita tidak bisa dengan mudahnya menilai bahwa semua guru yang menjadi penentu laju pendidikan adalah orang yang kesemuanya berkompeten dan profesional. Kita perlu memberdayakan kewaspadaan agar kontinuitas profesional kerja selalu terjaga dengan menilik kompetensi para pengajar pula. Lebih berbahaya lagi, apabila orientasi para pengajar hanyalah bekerja sambil lalu, tanpa menilik beberapa “cedera” yang menempel di Jurusan Musik selama ini dan berusaha memperbaikinya secara kontinu. Kita tentu jelas ingin menghindari cedera-cedera yang ada, dengan berorientasi mencetak serta menghasilkan lulusan yang SMS: Short Music Service 97 berkompeten. Yang terjadi selama ini, suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, ada saja siswa yang tidak bisa sama sekali membaca notasi (balok) setelah mereka lulus sekolah! Ini kesalahan guru atau siswa? Apalagi sekarang, dengan berkurangnya guru, ataukah tidak lebih berbahaya dari yang lalu-lalu? Mampukah (hanya) 7 guru yang ada mengelola Jurusan Musik dengan baik dan maksimal? Mengurus 3 kelas yang ada (lebih dari 60 murid?) menjamin pendidikan yang layak dan maksimal kepada orang tua murid yang menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal? Apabila guru yang ada sanggup mengelola sekolah ini, hal ini tentunya adalah suatu kerja keras yang sangat-sangat berat! Permasalahan kompetensi minat? Kenakalan murid? Apakah bisa dengan mudah diurusi semudah meniup kapas? Kadang kala atau bahkan seringkali terjadi, suatu pemikiran guru revolusioner bisa membawa dampak baik bagi kemajuan penekunan bidang tertentu. Setiap elemen revolusioner pendidikan akan mencoba mempertahankan eksistensi sekolah secara tekun dan selalu ingin berupaya mengoreksi setiap kesalahan yang muncul, kemudian mencari solusi dan memecahkannya bersama-sama. Tetapi, tidak semua guru harus revolusioner. Karena hal itu hanya akan menjadi ketegangan yang tak pernah usai. Guru yang bekerja adem ayem saja adalah penenang dari setiap ketegangan yang muncul. Revolusi, secara sederhana adalah upaya merubah keadaan dengan suatu jalan yang berisiko (mungkin dengan risiko besar). Sudah barang tentu, mengelola suatu sekolah adalah kerumitan yang unik, karena yang dilalui adalah kompleksitas yang selalu bergantian setiap tahunnya. Murid yang memiliki bermacam-macam karakter, kepala sekolah SMS: Short Music Service 98 yang unik,kehidupan kesenian di kota tempat sekolah itu berdiri, dsb, tidak bisa semena-mena dikesampingkan. Mata harus jeli untuk menengok setiap detail-detail kekurangan yang muncul di sekolah. Mana mungkin sampai ada KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang sama sekali tidak bisa berjalan lancar selama tiga tahun berturut-turut selain di Jurusan Musik, karena tidak ada guru yang berkompeten, padahal ada fasilitasnya. Apa jadinya? Adalah kerugian yang dirasakan murid, dan tentunya, guru yang merasa tidak bisa memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Oleh sebab itu, melihat beberapa paparan di atas, kiranya perlu diambil langkah yang terbaik untuk menyikapi keadaan. Pertama, setelah pihak sekolah memberikan SK PHK kepada GTT Jurusan Musik, maka konsekuensinya adalah mencari tenaga pengajar pengganti yang lain. Pertimbangan ini, berdasarkan keyakinan bahwa tidak mungkin satu Jurusan hanya ditangani oleh sedikit sekali guru. Meskipun bisa dikelola, itu adalah kerja yang sangat super berat. Penambahan guru adalah demi efisiensi tenaga, untuk membagi tugas, dan apa yang dikerjakan juga tidak terlampau terforsir. Tenaga pengajar yang dicari juga harus berkualitas. Paling tidak sesuai untuk memberi pengajaran di tingkat SMK. Kedua, penekanan spesifikasi kurikulum (klasik/nonklasik). Jika berlaku kurikulum klasik, harus segera dibenahi sebaran mata pelajarannya, untuk memberi bobot muatan pada jenjang-jenjang pembelajaran musik klasik. Jika nonklasik akan menjadi kemantapan studi, maka dari itu perlu upaya untuk memetakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan bidang non-klasik, sekaligus wawasan arah profesinya. Ketiga, pengadaan ruang-ruang praktek individual yang SMS: Short Music Service 99 memungkinkan siswa belajar secara privat, tanpa terganggu teman lain. Pengadaan ruang praktek, juga akan lebih menarik minat siswa siswi karena mereka akan merasakan ketenangan dalam belajar, dibandingkan apabila siswa-siswi harus dituntut belajar secara bersama-sama, padahal pelajaran yang dipelajari adalah PIIP (praktek, yang sangat bersifat individual). Keempat, penerapan budaya disiplin memiliki alat musik pribadi untuk spesifikasi instrumen mayor bagi para siswa. Untuk instrumen gitar (klasik), tidak sepantasnya sekolah menyediakannya sebagai fasilitas, karena itu akan menyebabkan siswa malas untuk memiliki alat musik sendiri. Setidaknya, paparan tawaran solusi di ataslah yang sampai sekarang ini mendesak dan harus segera diupayakan. Bila tidak segera dilaksanakan, laju pendidikan musik di SMK N 8 akan terhambat dan tidak akan memberi dampak ke arah kemajuan. Tulisan sederhana ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama. Mohon maaf bila ada salah kata. Catatatan: Esai ini ditulis tahun 2005, saat penulis masih menjadi GTT di SMK N 8 Surakarta. Saat ini Jurusan Musik SMKN 8 Surakarta mengalami peningkatan yang cukup berarti. Memiliki sekitar 100-an murid. GTT yang dulu di-PHK sudah diganti para PNS baru, yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Berbagai event musik unggulan skala lokal maupun nasional juga selalu diikuti oleh siswa-siswi. Jazz dan Selera Wong Solo B erbeda dengan musik-musik yang umumnya selalu bergaung di telinga kita dari pagi hingga malam (baca: musik pop semacam Nidji, Samsons, atau Letto), jazz ternyata masih menjadi sesuatu yang cukup terasing di antara genre musik populer yang beredar dan berkembang saat ini. Khususnya di Solo, jazz masih terasing. Sejak munculnya Big Band, di awal 1920-an, orang kulit hitam (Amerika) mulai mengekspresikan isi hati melalui musik yang menghentakhentak, dengan instrumen tiup (brass) yang dominan, dengan vokal yang merengek-rengek dan semangat yang membara. Yang sebelumnya, di abad ke-19, hal seperti itu tak pernah ada, karena kehidupan musik masih terbatas pada musik orkestra (lanjutan dari periode klasik maupun romantik yang telah memuncak di Eropa). Apresiasi pun hanya oleh kalangan terbatas. Saat Big Band muncul itulah, kepopuleran musik untuk SMS: Short Music Service 102 semua kalangan mulai merambah ke permukaan. Jazz mulai dikenal di kafe, bar, hotel-hotel, serta pentas umum di Amerika (misalnya: New Orleans), dengan gaya-gaya awal semisal ragtime, swing dan be-bob. Setelah teknologi rekaman muncul, mulai beredar piringan hitam dan kaset. Orang dapat dengan mudah mengakses musik, mendengarkannya di kamar tidur sembari membaca majalah, menjadi kenikmatan yang ketika itu sangat mahal harganya. Kini, jazz sudah menjadi milik semua, karena teknologi tanpa batas. Di Indonesia, pergelaran jazz digelar rutin. Mulai dari Java Jazz, Bali Jazz, JakJazz, dll. Event itu menyita banyak perhatian. Banyak kalangan datang untuk menyaksikan festival-festival akbar tersebut. Untuk sekadar melihat idola kesayangan, belajar dari mereka, maupun sekadar iseng mengisi liburan. Di Solo, kota kecil di Jawa Tengah, akhir-akhir ini nampak geliat yang pantas dicermati mengenai keberadaan jazz, komunitas, publik dan musisinya. Titik Berangkat Berawal dari Explo Jazz yang digagas pemusik Yasudah, berlanjut lewat Jazz in Sriwedari, Segaran, Museum, Sar Gede, dll., adalah contoh adanya gairah jazz yang mulai merangkak. “Jazz adalah kebebasan persepsi yang harus diserahkan sepenuhnya kepada pendengar dan musisinya, biarkan publik dan musisinya berpendapat”, demikian pendapat Yasudah. Kendati demikian, upaya komponis kontemporer Solo ini patut dihargai. Lewat ajang rutin yang digelar Mataya Production tersebut, lahirlah band-band jazz baru yang anggotanya masih tergolong muda-muda, semisal Mid Session, Siku 4X4, Arcadea, Blue Skin, Foggy, Bagaskara, Hat n' Friends, dan lainnya. SMS: Short Music Service 103 Dalam pergelaran akbar di puncak tahun 2006 yang lalu, hadir sepuluh band yang meramaikan pentas jazz tutup tahun, termasuk B'All Stars, band kawakan yang sudah lebih dulu berpetualang dari panggung ke panggung. Ini adalah gejala baru yang sebelumnya tak pernah ada di Solo. Heru Prasetya, dari Mataya Production punya visi, bahwa penyelenggaraan event jazz tersebut tidak hanya sebagai ajang bertemunya musisi jazz, namun juga apresiasi terhadap tempat bersejarah di Solo, misalnya Taman Sriwedari, Museum Radyapustaka, Pasar Gedhe, dll. Hal ini kiranya sangat positif. Selera Jazz tidak begitu saja diterima oleh wong Solo. Kendatipun jazz termasuk salah satu genre musik populer, di Solo ini—tak bisa dipungkiri—jazz masih menjadi sesuatu yang terasing. Sering sekali pertanyaan seperti ini muncul: mengapa musik jazz susah dinikmati? Mengapa jazz hanya instrumental saja, (kok) tanpa vokal? Selama ini jazz dianggap musiknya orang eksklusif (padahal tidak), yang sering ke kafe dan hotel, jadi orang awam susah menerimanya, tidak mampu bayar(?) Yang lebih ironis, mengapa jazz tidak menjadi cepat membumi dengan masyarakat seperti musik Samsons, Letto, Nidji, Ratu, dsb. Seperti kita tahu, MTV adalah ikon musik pop yang setiap detik menayangkan musik pop, bukan jazz. Stasiun TV yang lain, kecuali Metro TV atau TVRI (yang ada serpihan jazznya), selalu menayangkan acara pop yang luar biasa fantastis. Konser ini, konser itu, lomba ini lomba itu, sinetron ini itu yang ilustrasinya pop, yang semuanya serba pop. Penonton dipaksa untuk duduk diam (setiap saat) di depan TV dengan nikmat, SMS: Short Music Service 104 tanpa perlu merasa mengapresiasi. Semuanya hanya demi hiburan belaka. Itulah sesungguhnya pop, tanpa berpikir panjang kita bisa tahu segalanya. Sesungguhnya, jazz juga termasuk pop, karena jazz adalah seni populer yang bisa didengar di mana-mana. Namun secara hakekat, jazz bukan pop. Ciri seni (musik) populer adalah, “membuka diri bagi siapa saja tanpa terkecuali—dan mencoba membuka diri dalam semangat komunikasi dengan publik. Seni yang bersifat massal diupayakan untuk memenuhi kebutuhan selera masyarakat dengan material yang mudah dicerna, mudah diingat dan gampang diterima, tetapi sebenarnya juga mudah dilupa.” (Suka Hardjana: 2007). Ada tujuan lain yang diharapkan oleh 'musik jazz' yang membedakannya dengan musik pop, yaitu adanya permainan improvisasi (bermain atau bernyanyi spontan, yang mungkin membuat jazz susah diterima karena kadang-kadang improvisasi terasa sangat kompleks, terutama improvisasi musisi profesional). Dalam musik pop yang umumnya kita tahu, improvisasi sama sekali bukan menjadi faktor penting. Dalam jazz, improvisasi adalah hal wajib yang menjadi watak, karakteristik dan ciri. Dari panggung ke panggung, permainan musisi jazz akan selalu berbeda. Semangat akan selalu berbeda. Improvisasi akan terus berkembang seiring apresiasi telinga terhadap musik, dan skill terhadap ribuan teori tentang musik jazz. Solo, antara Campur Sari dan Jazz Oleh sebab itu, kiranya saya juga harus membatasi bahasan ini dengan hanya menyinggung soal musik yang SMS: Short Music Service 105 populer saja, yang turun langsung dari Amerika itu, yang dulu dikatakan Bung Karno sebagai musik ngak-ngik-ngok. Seperti halnya jazz, campur sari adalah pop. Satu hal yang musti kita pahami sungguh-sungguh adalah, hampir sebagian besar masyarakat Solo adalah penggemar Didi Kempot dan Cak Diqin, yang kental campur sarinya. (Mantan Walikota Solo, Slamet Suryanto aja pernah bikin album campur sari!). Selebihnya, wong Solo adalah penggemar keroncong, dangdut, pop, rock, jazz, klasik, reggae, country, dan puluhan musik lain. Untuk mengharapkan jazz sampai ke telinga pendengar yang luas, di Solo ini, adalah kerja keras yang kesannya (memang) masih babat alas. Permasalahan selera dan latar belakang budaya ternyata menjadi faktor utama. Karena, kita murni mengadopsi Amerikana minded—karena jazz adalah serpihan budaya Amerika. Selera bisa mempengaruhi perkembangan. Kita bisa mengidentifikasi perkembangan jazz di Solo dari beberapa faktor. (1) ada musisi plus pengamatnya, (2) ada media yang memberitakannya, (3) ada komunitas sekaligus penikmatnya, (4) ada album rekaman dari para kreatornya, (5) ada pentas, diskusi dan ada seminarnya. Semua itu harus dengan regulasi yang stabil dan semangat yang dinamis. Adanya event yang rutin diselenggarakan Mataya, adanya beberapa radio di Solo (contoh: Metta, Solo Radio, RRI, Karavan), yang menyiarkan musik jazz secara rutin, juga adanya koran Solo Pos yang terus-menerus memberitakan pentas jazz, juga tak ketinggalan adanya banyak musisi muda yang sudah mulai lahir, adalah bukti nyata bahwa masih ada harapan yang cerah untuk bersama-sama membumikan musik jazz di Solo, yang tak boleh disertai sikap pesimis. SMS: Short Music Service 106 Karena, banyak sekali hal kreatif yang bisa ditemukan dalam musik jazz. Biar saja musik jazz tumbuh tidak seperti musik-musik pop yang luar biasa fantastis. Biarlah penikmatnya terbatas. Namun, jika jazz dihayati betul, walau hanya dalam komunitas kecil, tetap akan ada manfaatnya, seperti kata Plato, “Musik dapat membuat manusia lebih manusiawi.” Sekian. Wadah Pecinta Jazz di Solo T ulisan-tulisan yang beredar di media biasanya menyoroti tentang sastra dan seni rupa. Musik jarang mendapat tempat karena jarang penulisnya. Jarang kita menemui tulisan yang berbicara secara khusus soal musik dan kehidupannya. Mengapa hal ini terjadi? Kemana perginya wacana musik? Apakah ini menunjukkan bahwa kehidupan musik (di Solo ini khususnya) telah sekarat? Dalam sebuah kesempatan, sekelompok anak muda kota Solo yang gemar musik jazz berkumpul. Mereka membicarakan soal perlunya dibentuk suatu komunitas: di situ harus ada praktisi (pemain), penggemar, dan siapa pun yang minat pada jazz. Mereka sepakat berada dalam satu 'payung' yang akhirnya dinamai Solo Jazz Society (SJS). Tidak hanya itu, mereka—yang salah satunya adalah penulis—membicarakan visi dan misi, soal rencana ke depan, serta pentingnya membangun dialog secara lebih luas: dengan pemusik, publik, lembaga-lembaga, maupun institusi SMS: Short Music Service 108 dan instansi terkait. Di komunitas ini jelas ada agenda rutin berupa diskusi, workshop, apresiasi musik (nonton film dan diskusi), konser, sampai dengan jam session bagi mereka yang konsen pada skill. Semua bertujuan positif meski kini masih dalam aktualisasi rencana. Yang menarik, penggagas SJS pada umumnya berangkat dari berbagai konsentrasi. Pemain, penggemar, pendengar, bahkan ada yang belum mengerti sama sekali tentang jazz. Namun, mereka semua berbicara, tidak ada yang diam. Ini berarti, niat ini disambut antusias. Setidaknya oleh para penggagasnya terlebih dahulu. Jazz adalah kebebasan berekspresi. Dalam tataran genre musik populer, 'drajat' jazz adalah paling tinggi. Karena, jazz memberikan 'ruang' yang lebar dalam hal improvisasi yang menuntut pemain bermain secara spontan dalam kesempatan tertentu, hingga 'ruang' yang tak terbatas. Improvisasi takkan habis jika dipelajari. Pun, berbagai teori musik jazz yang melatarbelakangi munculnya banyak gaya dalam jazz. Berbeda dengan improvisasi dalam musik pop yang lebih bersifat terencana. Konon, ketika pemusik jazz sedang trans (dalam kondisi puncak) saat memainkan alat musik, kenikmatan yang didapat melebihi ketika melakukan hubungan badani. Jack Lesmana, Indra Lesmana, Oelle Patiselano, Bubi Chen, adalah tokoh-tokoh jazz kawakan Indonesia yang pernah mengalami 'kenikmatan' itu. Mereka-mereka itu tidak sadar bahwa mereka tengah 'memunculkan' nada-nada yang sangat enak di kuping. Pengalaman seperti itu baru didapat setelah puluhan tahun menggumuli jazz secara serius. Kini, dinamika musik Indonesia memang tergilas oleh arus komersialisasi yang luar biasa. Dalam tayangan televisi — SMS: Short Music Service 109 setiap hari—kita hanya menyaksikan fenomena musik pop yang terus menerus dijadikan hiburan: komoditas. Pagi hingga pagi buta, Ungu hingga Keris Patih. Jazz jarang mendapat tempat. Padahal, jazz lebih dari sekadar musik penghibur. Jazz sarat akan makna musikal: jazz adalah tulang punggung apresiasi musik populer. Sifat musik ini di negara tempatnya berkembang sangatlah merakyat. Di Indonesia musik ini menjadi ekslusif, dan fakta ini menjadi masalah sosiologis. Konon, kata almarhum pelawak Srimulat, saat beliau memberi pelajaran kepada murid-muridnya, ia berujar demikian, “Sebelum kamu melawak, belajarlah (dan bermainlah) musik jazz terlebih dulu. Di situ kamu akan belajar yang namanya improvisasi (spontanitas) yang bisa jadi bekal baik saat kamu melawak di atas pentas. Ingat, hal tidak terduga selalu akan muncul. Jika kamu tidak siap maka kamu akan kwalahan. Jazz itu musik yang sangat penting.” Oleh alm. Srimulat, seorang pelawak pun diharuskan untuk kenal (kalau bisa paham) tentang musik jazz. Dan ternyata memang benar demikian. Dalam forum maupun komunitas lain yang kini marak, selalu menjadi ajang kumpul-kumpul yang lebih banyak segi positifnya dibanding negatifnya. Di Solo, semisal contoh kita bisa menemui komunitas sastra semacam Meja Bolong atau Kabut Institut. Sanggar Sarotama di Palur juga sebagai tempat berkreasi para praktisi tari, gamelan, dan wayang yang rutin mengadakan berbagai kegiatan. Tak ketinggalan, SJS juga berniat untuk membentuk suatu 'ajang dialog' yang berfungsi menampung aspirasi, ide, dan gagasan bagi para penggemar musik jazz (khususnya) di Solo. Sekaligus—ke depan—bagi pecinta Jazz Solo, komunitas ini bisa menjadi pusat info SMS: Short Music Service 110 tentang jazz. Wartajazz.com misalnya, telah memulai persemaian untuk masalah-masalah seperti ini sejak lama dan menjadi pusat informasi dan hubungan “kultur” yang cukup menjanjikan untuk perkembangan musik (jazz) di negara ini. Jika Mataya Production yang dikepalai Heru Prasetya lebih konsen ke penyelenggaraan event (konser) jazz, SJS akan menjebatani lewat hal yang lebih bersifat dialogis-informatif, bertukar referensi, informasi, serta bersama-sama mengakses info dan isu seputar jazz yang sedang beredar hingga detik ini. Kecanggihan teknologi yang ada harus segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia penggunanya. Oleh karena itu, akan terjadi sinkronisasi antara event 'dalam ruang' dan event 'luar ruang'. Dalam ruang adalah semacam seminar, diskusi, workshop, dan semacamnya. Sedangkan luar ruang adalah konser musik, yang harus disaksikan oleh berbagai publik tanpa sekat. Dengan demikian, di Solo ini khususnya, musik jazz akan berkembang lebih luas, bersemi bagai bunga-bunga yang mekar. “Mendengarkan” Orska K onser Orska kali ini (25/2/06), sangat berbeda dengan tahun lalu. Tidak menutup kemungkinan, ini adalah upaya 'revolusi' untuk mendekati makna sesungguhnya dari kata 'Orkestra'; suatu beban berat untuk jenis musik yang tidak bisa dimainkan dengan 'main-main'. Pertunjukan yang Sukses ? Apa sebetulnya yang menjadi ukuran suksesnya suatu pertunjukan musik? Banyak yang meyakini, bahwa salah satu kesuksesan (kuantitas) dapat dilihat dari, pertama, jumlah penonton. Semakin banyak jumlah penonton berarti pertunjukan semakin sukses, tiket habis pemasukan banyak. Kedua, bahwa materi atau suguhan lagu yang ditampilkan menarik, setidaknya—paling sederhana—akrab di telinga pendengar. Kalaupun pendengar belum pernah sekalipun mendengarkan musik atau lagu yang disuguhkan, namun jika lagu itu ternyata memiliki kandungan melodi yang unik, ritme SMS: Short Music Service 112 a t r a k t i f , g a y a - g a y a y a n g p o p u l i s , f a m i l l i e r, ataubahkanpenyanyi yang memiliki suara bagus seperti Christoper Abimanyu, pastilah mendapat sambutan yang meriah. Ketiga, setelah penonton pergi dari ruang konser, ada sisa bunyi yang terngiang di kuping, suatu saat ada keinginan menonton itu lagi. Kesuksesan dapat pula diukur dari “skenario” pertunjukan. Penyusunan urutan lagu (yang tentu sudah diprediksikan) akan membawa penonton 'lebur' dalam suguhan yang ditawarkan. Hal itu akan menjadi kunci pokok selama pertunjukan berlangsung, dari awal ketika artis naik pentas, musik berbunyi, hingga akhir lagu sampai balon meletus, kertas warna-warni bertebaran, dan kembang api 'muncrat' dari muaranya. Penonton yang jeli akan menilai suksesnya suatu pertunjukan salah satunya dari segi “skenario” tersebut. Pada saat penonton masuk ruang konser, mereka belum punya persepsi atau gambaran apapun mengenai 'apa yang akan terjadi di atas pentas'. Penonton hanya mengantongi satu kegelisahan yang lebih mirip sebagai rasa penasaran. Apakah si artis nantinya tampil memukau? Apakah Konduktor bisa menjalankan tugas dengan baik? Apakah lagu yang ditawarkan menarik? Siapa saja artis yang tampil? Jaya Suprana kok tidak jadi main? Tentu menjadi satu kekecewaan bagi penonton yang malam itu (ternyata) hanya ingin menonton Jaya Suprana: juragan jamu, pianis, dan komponis lulusan Jerman itu. Sisi lain kesuksesan pertunjukan musik bisa dilihat juga dari tidak adanya gangguan teknis maupun non-teknis saat pertunjukan berlangsung. Persoalan sound yang sempat membuat 'panik' selama gladi bersih menyebabkan outgoing SMS: Short Music Service 113 dari pemain saat pentas juga tidak bisa maksimal, mereka masih dihiasi kegelisahan dan rasa kurang nyaman. Untung saja ketika itu ada Memet Chairul Slamet (komponis) yang segera memberi solusi atas permasalahan itu. Kesuksesan juga bisa dilihat dari proses produksi, persiapan yang matang serta latihan yang efektif. Pertanyaan selanjutnya, apakah konser Orska malam itu bisa dikatakan sukses? Menit-menit awal pertunjukan itu dihiasi 'kegagalan dan kecelakaan' yang tak terperikan. Lagu Esterellita dan Fly Me Too The Moon menemui 'naasnya', tidak berhasil sebagai suguhan yang menarik. Peran 'soli' Orska Junior dalam lagu Do Re Mi ataupun Congratulation juga dirasa masih jauh dari akurat. Ada beberapa alasan, selain mereka hanyalah 'kumpulan' anak-anak yang dituntut untuk tampil ke publik, masih ada pertimbangan lain, yaitu: menampilkan regenerasi yang sudah 'dicetak'. Kelak, kalau personel Orska sudah tidak lagi remaja, mereka bisa menggantikannya. Setidaknya ini hanya dugaan. Pentas Orska memang tidak memudahkan penonton untuk menikmati pertunjukan secara lebih leluasa akibat 16 Soko yang menghalangi. Kepala penonton harus tengok kiri-kanan, tidak rileks, tidak nyaman, tidak plong dan tidak berhasil secara visual. Bantuan penikmatan dari white screen tidak seperti ketika penonton melihat secara langsung. Karena, white screen adalah 'tipuan atas realitas', mata hanya dituntun kamera, penonton hanya manut saja dan mengikuti apa yang sedang ditampilkan di white screen seperti saat kita menonton televisi. Kita harus 'patuh' pada layar, bukan kehidupan sesungguhnya yang sedang terjadi. Jika suatu saat yang nampak di white screen hanyalah wajah Boni (biola) yang di-shoot selama satu menit, namun penonton menginginkan SMS: Short Music Service 114 Haryanto dan Dea (oboe), penonton harus menunggu Cameraman memindahkan obyek hingga terlihat gambar yang diinginkan. Pemilihan ruang pertunjukan yang terlalu dipaksakan untuk 'disulap' menjadi 'ruang konser' juga menjadi penyebab proses dan hasil terlampau rumit. Contoh gedung yang didesain khusus untuk pertunjukan musik klasik Siapa Yang Berhak Bermain dan Mendengar Musik ? Kita tidak bisa menuntut lebih banyak dari apa yang telah dilakukan. Usaha-usaha yang telah berlangsung selama latihan, proses administrasi, lobi sana-sini, pendanaan, kostum, performance, sampai persoalan menghitung birama dan menjaga tempo telah dicurahkan semua pada tanggal 25 Februari yang lalu. Itu berarti, kesempatan konser menjadi pilar utama untuk menjangkau publik. TA TV menyiarkan secara langsung, dan seluruh publik se-Solo dan sekitarnya telah mengerti kehadiran Orska, Orkestra Remaja Surakarta. Tanggung jawab di masa mendatang memang terletak pada konsistensi pemain musik atau pun orang-orang di belakang layar untuk menyampaikan kembali kepada publik, tentang apa potensi, bakat, ketrampilan, keberanian bermusik, demi suatu penghidupan bagi nilai karya seni SMS: Short Music Service 115 melalui pertunjukan yang bisa menjangkau semua publik tanpa terkecuali. Karena, musik milik semua orang. Tidak untuk komunitas tertentu yang mampu membeli 'musik' dengan harga yang terlampau mahal! Semua orang tentu berhak mengapresiasi musik atas dasar kebutuhan akan keindahan. Sangat beruntung bahwa di lagu-lagu selanjutnya pada pertunjukan itu sudah jarang terjadi 'kecelakaan' di atas pentas. Materi yang digagas untuk ditampilkan memang terlampau variatif. Pop, Rock, Klasik dan Tradisi lebur jadi satu. Lagu Medley garapan Indra Permana adalah sebuah 'kejeniusan' yang sebetulnya bisa diolah lebih menarik lagi, namun karena keterbatasan waktu latihan, akhirnya lagu tersebut hanya mampu tampil seadanya, dengan persiapannya yang kurang maksimal. Sinkopisasi ritme, aksentuasi, ekspresi dan ketepatan tempo masih dirasa sangat ragu-ragu. Namun, keberanian menampilkan lagu ini pantas mendapat penghargaan, dibuat di tengah kesibukan 'Mas Man' yang berjubel, berdesak-desakan: dari administrasi, properti, musik, sampai konsumsi! Ketika Haryanto ataupun Jogja Cello Ensamble tampil di atas pentas, yang ada hanya ketercenungan menyaksikan 'bunyi baru' bagi mereka (penonton) yang belum pernah menyaksikan lagu model begituan (klasik). Ternyata, justru satu contoh penampilan ini bisa menjadi pilar untuk 'berkenalan dengan musik klasik'. Dari keduapuluh lagu yang ditampilkan, mayoritas memang lagu instrumental: tanpa lirik. Dengan demikian, ada beberapa dugaan yang bisa disimpulkan dari respon penonton. Ketika musik tanpa lirik mengalun, persepsi penonton hanyalah berada dalam tataran bunyi (non-verbal), yang mengandung unsur nada, melodi, SMS: Short Music Service 116 harmoni dan irama. Berusaha meraih penikmatan akan melodi bukan merupakan penjelasan seperti 'bahasa komunikasi sehari-hari'. Kita merasa lebih tertarik pada suatu pernyataan musik tertentu kalau terutama melodinya dapat kita kenal kembali dan tetap tinggal dalam ingatan kita. Maka dari itu, musik vokal yang dapat ikut kita nyanyikan biasanya lebih populer daripada musik instrumental, yang dapat menghasilkan melodi yang kadang-kadang melebihi batas jangkauan suara manusia. Sebaliknya, musik instrumental yang nada-nadanya termasuk batas jangkauan suara kita sendiriyang dapat kita nyanyikan dan ingat-ingatdapat juga menjadi populer. Apakah masyarakat Solo terbiasa mendengar musik instrumental? Apakah masyarakat Solo (harus dituntut) mempunyai wilayah dengar 'masing-masing'? Maksudnya, suatu komunitas pendengar jazz, klasik, rock, blues, pop, reggae, apakah diusahakan memiliki tempatnya? Cita rasa penonton adalah perbedaan yang signifikan, kompleks, dan ribuan 'rasa dan pikir' bisa menjadi satu di ruang konser, 'berebut tempat' untuk mendapatkan satu kesepahaman. Ada penonton yang musikal, setengah musikal, dan tidak musikal. Suguhan Orska memang apresiatif dan menuntut publik untuk menghargai apa pun yang telah diusahakan dan disuguhkan, tanpa harus menolak dengan sinis. Pengaruh melodi pada publik yang mendengarkan akan berbeda satu sama lain, sesuai dengan daya tangkap masing-masing. Maka, menghadirkan suatu suguhan musik instrumental adalah sah-sah saja. Kita tidak harus 'mengabdi' sepenuhnya pada selera publik, karena hal itu akan mengungkung kreativitas. Otoritas kreator seni menjadi dikendalikan bahkan bisa kerdil. Hati-hati. SMS: Short Music Service 117 Ensambleship dan Evaluasi Yang menjadi pertanyaan menarik lagi adalah, apakah kaidah ensambleship sudah benar-benar dibangun di lingkungan Orska dalam keseharian, latihan, maupun konser? Suatu ensembel adalah kerja sama kelompok. Saling mengerti satu sama lain adalah kunci yang paling utama. Apalagi persoalan ketrampilan, sebisa mungkin harus seimbang. Dalam suatu kelompok musik tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang tidak penting. Selanjutnya, jika setiap selesai latihan tidak ada evaluasi yang melibatkan pelatih, konduktor, pemain, pakar, dsb., akan sulit mendapatkan masukan-masukan, dan pelajaran yang bermanfaat. Pemain berhak bicara, pelatih berhak bicara, apalagi konduktor. Orang yang menonton latihan pun berhak bicara, jika mau. Orska adalah sekolah. Adalah ruang berbagi ilmu. Adalah ruang dengar dan bermain musik dalam berbagai suasana yang menyenangkan, bahkan sering piknik. Yang lebih dibutuhkan adalah persamaan hak dan kewajiban, bukan otoritas suatu keputusan yang 'dirasa' lebih berwenang dalam soal musik (feodal). Dalam suatu kelas di pelajaran sekolah, siswa bebas bertanya, mendebat, atau bahkan tidak setuju dengan ajaran gurunya jika ternyata ajarannya adalah suatu hal yang keliru, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sah-sah saja. Sekarang sudah zamannya 'Demokrasi Bunyi dan Pendapat'. Lagu yang tampak sedemikian menarik pada malam itu, dengan penampilan yang rileks, adalah Can't Smile Without You. Ketegangan yang dirasakan pemain di awal-awal lagu sudah mulai mengendur berkat hadirnya lagu itu. Satu senyuman dari solis sebenarnya sudah cukup mewakili SMS: Short Music Service 118 pengenduran atas ketegangan bermusik. Menunjukkan bahwa pemain pun bisa dan harus menikmati musik yang dimainkan. Kadang-kadang, suatu ekspresi (mimik wajah), bisa saja menipu. Pura-pura senyum. Pura-pura gerak. Purapura ekspresi tapi ada paksaan, entah dari orang lain atau tuntutan entertainment. Seni tidak bisa di'pura-pura'kan. Mei Djing, seorang ahli er-hu (alat musik Cina) yang malam itu tampil memukau lewat Jie Qian Ying Ye dan Sai Ma, adalah contoh riil pengadaptasian dan aplikasi imajiner kisah kehidupan nyata ke dalam ekspresi musikal yang bernilai. Ia t i d a k m e m b u a t - b u a t e k s p r e s i d a n b e n a r- b e n a r membayangkan apa yang sedang terjadi di balik rajutan kompositoris musik, suatu maksud komponis, arti setiap gesekan, arti senyum, mimik, gerak badan, melodi yang 'menggigit', serta macam-macam kebutuhan 'latar belakang' yang mestinya diusahakan oleh semua pemain musik. Hanifah malam itu menyanyi The Prayer dengan nafas, range, dan power yang 'amat sangat tercekik'. Ternyata, The Prayer bukan lagu anak-anak. Orkestra dan Pemimpinnya Perumpamaan Suka Hardjana (Musikolog), sebuah orkes itu ibarat sebuah pasukan tentara. Berhasil tidaknya gempuran, banyak ditentukan oleh faktor kondisi medan, target yang hendak dicapai dan siapa yang memimpin para serdadu itu sebagai komandan. Tentu kualitas individu pasukan juga sangat mempengaruhi, tetapi komandanlah yang kemudian bertanggung jawab pada hasil finalnya. Di sinilah, pada saatnya peran konduktor penjadi penentu yang amat penting. Agus Murtono punya pengalaman yang panjang sebagai pemain musik yang mumpuni dan assisten SMS: Short Music Service 119 konduktor di berbagai event, begitu juga Adhi Satria yang meski masih muda namun pengalamannya berderet. Berbeda sekali ketika yang di kondukt itu memang sebuah orkestra yang sesuai dengan kaidahnya (orkes musik klasik). Tuntutan keakuratan yang serba 'macam-macam' mulai dari tempo, dinamika, ritme, ekspresi, intonasi, kedetailan bidikan nada, 'dongeng' untuk menceriterakan maksud lagu kepada pemain agar lebih 'greng', akan menjadi tujuan yang harus digarap dengan sempurna. Orska bukan (atau belum menjadi) Orkes Simfoni. Maka, meng-kondukt dengan gaya-gaya yang ringan dan santai saja menjadi suatu kewajaran. Belum ada keseriusan yang harus diusahakan bagi Orska seperti bermain di Orkes Simfoni. Meng-kondukt di Orska yang penting menghitung dulu, menghitung saja cukup dan menuntun pemain agar tidak 'lari' tak karuan keluar tempo dan bisa kompak terus. Mungkin, selain itu belum ada hal lain yang lebih detail. Apakah benar begitu, Pak Agus Murtono, Mas Adhi? Kalau salah ngomong tolong dikoreksi biar tulisan ini tidak 'bicara' seenaknya saja. Musik dan Puisi ? The Swan From The Carnival of the Animals karya komponis Perancis Camille Saint-Saens (1835-1921), menjadi karya yang tidak sepenuhnya hadir sebagai sebuah 'komposisi musik yang otentik'. Musik itu hadir (hanya) untuk mengiringi Ratih Sanggarwati berpuisi. Yang jadi pusat perhatian tentu lebih ke Ratih, bukan musik. The Swan, maksud Saint-Saens menciptakan lagu ini berdasarkan 'fantasi tentang dunia binatang' yang kemudian diwujudkan lewat musik (versi cello dan dua piano; versi orkes dan dua piano). Cello sebagai melodi pokok membawakan tema terus menerus, melodinya SMS: Short Music Service 120 memang terkesan sedih. Video Art dari lagu ini juga pernah dikerjakan oleh Walt Disney dengan sangat apik, dengan gambar-gambar hewan yang lucu, lincah, dan sesekali bersedih. Jadi, apa jadinya kalau lagu ini digunakan sebagai pengiring puisi yang bertema Ibu? Antara musik dan puisi sudah tidak terjadi 'peleburan'. Padahal, jaman sekarang ini musikalisasi puisi sedang dalam perbincangan hangat. Ratih bercerita soal Ibu, sementara The Swan bercerita tentang binatang angsa: Wah, Ibu angsa kali yee.. 'Ruang kesempatan improvisasi' yang diberikan pada Banu (gitar) pada lagu Kopi Dangdut terasa masih kurang panjang durasinya, seharusnya bisa ditambah dua atau tiga putaran lagi. Pertama untuk yang normal-normal saja, kedua untuk jelajah modus dan pengembangan tema, ketiga untuk yang speed-speed atau apapun 'sesuka hati', biar tambah 'kentèl kopi-nya'. Jangan mau kalah sama 'Star Way To Heaven', dong! Sudah, itu saja ya...Katanya nggak boleh dikritik. Padahal pingin ngomong banyak, nih... Epilog Balon meletus, We Are The Champion tanpa lirik berkumandang, menandai bahwa konser malam itu pun bubar dengan tepukan, kegembiraan, kejengkelan, kelegaan, kepuasan, kesenangan, kebahagiaan dan macam-macam 'ke-an' yang bisa disebutkan lagi. Penghargaan yang sedalamdalamnya untuk siapa saja yang 'bertindak, berbuat dan bekerja' demi terselenggaranya konser ini. Terima kasih untuk sponsor yang 'membanjir' di booklet hingga tidak ada ruang untuk sinopsis lagu. Semua yang bekerja di belakang layar maupun di depan layar pantas mendapat jabat tangan ucapan selamat, pelukan, pujian, sanjungan, applaus, dan tidak SMS: Short Music Service 121 menutup kemungkinan mendapat saran dan kritik jika memang mau didengar. Cita-cita Orkestra Remaja Surakarta adalah membentuk Orkes Simfoni di tahun 2010, sebuah obsesi yang pantas dihargai dan diacungi jempol. Hal ini, tentu bukan lagi mainmain. Bukan lagi 'me-langgeng-kan' suasana canda mirip 'play group' saat latihan, suasana ensembel-ship yang rasanya masih kurang sadar untuk diemban. Membentuk Orkes Simfoni butuh keseriusan yang berlipatlipat. Pendanaan untuk administrasi dan pengadaan alat musik yang luar biasa banyak, makan biaya ratusan juta. 2 Mengusahakan ruang latihan, paling tidak seluas 120 m dan ruang konser dengan akustik khusus. Mengusahakan perpustakaan untuk dokumentasi ribuan score dan partitur tulisan berbagai komposer, serta pengadaan buku-buku musik untuk referensi. Belum lagi pengadaan 'perpustakaan audio' yang tidak kalah pentingnya. Konduktor Orkes Simfoni mesti yang mumpuni, serta pemain musik yang siap akan segala risiko untuk bermusik orkes di wilayah 'publik dengar' Indonesia yang sebetulnya lebih memiliki cita rasa 'nge-pop' daripada 'nglasik'. Namun, itu bukan suatu persoalan. Keberanian mewujudkan cita-cita, sekali lagi, adalah obsesi yang pantas dihargai. Tinggal ber'main-main' saja bersama tantangan yang (mungkin) berat. Tentu, tantangan itu sudah ada di depan mata. Piknik Musikal bersama Amari Catatan Kecil Konser Tunggal Perdana Amari Solo Bila aku memiliki kesempatan hidup sekali lagi, aku akan membuat jadwal untuk...mendengar musik paling tidak sekali setiap minggu; agar bagian dari otakku yang mengalami Atrophia dapat selalu diaktifkan (Charles Darwin). Music attend moment played. If someone only skillful read good imagination and tone, unanswerable that he will not attend. Music really attend only if played. (Kiergaard). K onser Tunggal Perdana Amari Solo (Auditorium UNS, 18/02/06) banyak menuai pujian, sekaligus membawa kekaguman bagi banyak publik. Mungkinkah ada kritik? Tentu ada beberapa penyebab yang bisa disimpulkan mengapa konser itu tergolong sukses? Pertama, banyak publik yang hadir. Kedua, sajian yang cukup variatif dan menarik. Ketiga, nyaris tidak ada gangguan teknis selama SMS: Short Music Service 124 pertunjukan berlangsung. Keempat, yang paling penting: persiapan (proses) yang matang. Meski pertunjukan sempat mulur beberapa saat dari jadwal, dan terjadi sedikit miskoordinasi mobilitas di stage, bagaimanapun juga pertunjukan itu tetap berjalan hingga tuntas bersamaan dengan berakhirnya lagu We Are The Champion, lagu Rock legendaris Freddy Mercury yang sangat agung: maestoso. Penonton pun pulang satu persatu dengan senyuman, mereka tidak merasa rugi meski mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli tiket. Untuk ukuran anak, bermain musik dua jam penuh dengan membawakan lebih dari 20 lagu dengan interpretasi, ekspresi, intonasi, mental, ketrampilan, keberanian, stamina sesuai kapasitas mereka, adalah suatu prestasi yang tidak mudah dicapai. Dalam suatu proses yang dikehendaki, tentu ada suatu pendidikan kedisiplinan di balik hasil yang telah dicapai. Bagi Drs. Murtidjono dalam kata sambutannya mengatakan, “fenomena Amari, dalam kaitannya dengan pelatihan kedisiplinan, mungkin lebih penting di tengah situasi sosial dewasa ini.” Anak-anak dan remaja adalah fase yang tepat untuk pelatihan kedisiplinan. Materi? Ada Apa? Berbicara tentang (sebagian besar) materi yang ditampilkan Amari, sesungguhnya hanyalah berkadar hiburan, bukan wacana musik yang apresiatif. Pementasan itu menjadi apresiatif tatkala ada beberapa lagu yang memang dibuat (bukan hanya) sekedar untuk menghibur (contoh: Zamrud Katulistiwa, Indonesia Permai). Kedua lagu itu mengenalkan penonton pada citra ke-Indonesia-an. Ada bermacam tanggapan ketika publik mendengarkan SMS: Short Music Service 125 musik. Pembedaan yang umum adalah: musik yang bersyair dan musik yang tidak bersyair. Musik bersyair telah berhenti pada pemahaman akan apa yang diketahui dari syair. Lagu Cinta Dari Hati jelas menggambarkan peristiwa cinta. Begitu pula Ayo Ngguyu—yang pada malam itu Waldjinah banyak terpeleset — juga jelas menggambarkan peristiwa humor. Bagaimana dengan Winter Game? 'Permainan Musim Dingin', yang malam itu hadir sebagai komposisi instrumental? Permainan musim dingin itu seperti apa? Tentu ada beragam persepsi. Di sinilah sebetulnya, usaha manusia memahami musik adalah usaha untuk 'membongkar' apa sesungguhnya yang bisa didapat dan diketahui dari musik (membaca idenya). Ini bisa dilakukan melalui banyak hal. Mencermati nada, melodi, lirik, ekspresi, ketrampilan, latar belakang pembuatnya, peristiwa dan realitasnya, dari apapun yang bisa dimungkinkan melalui musik. Satu hal yang tidak disampaikan kepada publik di booklet Amari adalah: pencipta lagu! Publik tidak tahu, Contra Dance itu lagunya siapa? Siapa pembuat lagu Matahari? Explosive itu lagu siapa? Bagi publik yang sudah kenyang mendengar musik puluhan tahun tentu akan mengerti 'rahasia' itu tanpa harus membuka song book atau bertanya teman. Namun, bagi publik yang tidak mengerti? Mereka akan mengira bahwa lagu Winter Game adalah karya Amari (?). Tentu yang diharapkan tidak demikian. Maka dari itu sangat perlu apresiasi. Tidak salah juga, andaikata ruang di booklet memungkinkan, disertai sinopsis masing-masing lagu, meski hanya satu-dua kalimat. Karena, musik yang dicipta tentu punya maksud, ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Sebagian besar —hal yang menyangkut penampilan — telah diusahakan Amari dengan maksimal. Mursid Hananto yang SMS: Short Music Service 126 bertindak sebagai Konduktor dan Arranger juga telah mengupayakan proses itu dengan semaksimal mungkin: membawa stage menjadi punya aura, tidak vakum, dan ekspresi musikal selalu berusaha diraih dengan kerja keras, sekeras-kerasnya. Hal ini pantas dihargai. Mungkin, ada beberapa pemain yang masih merasa 'ketakutan' ketika menggesek biola, entah takut publik, takut salah, atau merasa tidak nyaman. Itu hal yang wajar. Bermain di hadapan ratusan publik tidak seperti berlatih sendirian di dalam kamar dengan rasa yang 'super nyaman'. Dalam parameter ketrampilan bermusik, memang segalanya bisa dilatih, termasuk mental. Ketika artis sudah berada di atas pentas, yang ada hanyalah 'dirinya' sendiri yang bermusik tanpa harus mengemban beban apa-apa. Esensi musik adalah 'bermain' dalam wilayah 'taste' (rasa). Genssly Ediansyah Syams (Pianis Indonesia yang memenangkan IBLA Grand Prix di Ragusa, Italia: kompetisi piano) pernah memberi kesaksian bahwa, ketika ia tampil bermain piano di hadapan banyak publik dan juri, yang terpikirkan hanyalah usaha untuk memasuki jiwa Komponis. Saat Genssly bermain piano, ia sudah tidak memikirkan apapun kecuali musik! Ia memikirkan bagaimana menghargai usaha Komponis yang sudah menciptakan karya agung untuk diinterpretasikan sekuat talenta hingga membuat karya musik menjadi lebih bernilai. Maka dari itu, ternyata, urusan performance yang menyangkut banyak aspek, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Butuh waktu tahunan. Sedangkan, jika kita menengok usia Amari yang belum ada satu tahun, apa sebaiknya komentar kita? Yang paling 'aman' adalah memberi penghargaan sedalam-dalamnya meski hanya berupa tepuk SMS: Short Music Service 127 tangan dan ucapan selamat. Pada awal-awal eksistensinya ini, Amari telah menunjukkan suatu keberanian yang menjanjikan masa depan musik menjadi lebih tepat, atau setidaknya ada aspek yang positif. Tentu, yang ada hanyalah tantangan agar kelompok ini tetap bertahan hingga tahun-tahun mendatang. Satu Level Suatu ansambel, idealnya digawangi oleh pemain musik yang 'se-level'. Artinya, untuk mencapai tingkat efektifitas yang lebih baik antara pemain satu dan yang lainnya sebaiknya memiliki ketrampilan yang seimbang (bukan harus sama). Jika tidak demikian, coba bandingkan, pemain musik yang baru belajar musik selama sebulan lalu bermain bersama dengan pemusik yang sudah belajar lima tahunan. Meski sama-sama bisa memainkan satu rangkaian melodi, namun tingkat ketepatan, keakuratan, pembawaan dan interpretasinya tentu sangat berbeda. Akibatnya, permainan musik menjadi tidak bisa melebur untuk mencapai satu kekuatan yang seimbang, satu kekuatan bunyi yang sonor. Ibarat pembalap kelas Standard yang tiba-tiba bergabung dengan pembalap kelas Tune-Up, bertarung di Road. Meski si pembalap kelas Standard bisa menyaingi pembalap kelas Tune-Up, namun usaha pembalap kelas Standard akan terlampau 'ngongso' dan tidak efektif. 100 KM/jam pembalap kelas Tune-Up tentu beda dengan 100 KM/jam pembalap kelas Standard. Mencapai kemahiran bermusik adalah kebiasaan latihan, mendengar, menonton pertunjukan musik dan banyak membaca buku yang mendukung. Apabila suatu ansambel ditemukan ketidaksetaraan level maka hal ini perlu dicari solusi. Salah satunya adalah saling menghargai antar sesama pemain. SMS: Short Music Service 128 Pertunjukan Amari pada malam itu memang belum bisa dikatakan seratus persen maksimal. Sebagai pemusik (yang tentu juga manusia), mempunyai kekurangan adalah kewajaran yang berlaku sepanjang masa. Nada-nada fals dari paduan belasan pemain biola masih sering terdengar, itu biasa, dan belum menjadi persoalan vital. Karena kita sudah tahu, bahwa hal inilah sebagai akibat dari ketidaksetaraan ketrampilan pemusik dalam suatu ansambel. Atau bisa jadi, permasalahan tuning (stem) belum diselesaikan dengan tuntas, kalau demikian adanya, hal ini sangatlah vital. Amari memang beranggotakan kebanyakan siswa-siswi berprestasi. Entah di sekolah maupun dalam kesenian. Hadir pula beberapa vokalis yang pernah menjuarai lomba vokal berulang kali. Dengan adanya 'kekuatan' ini, akan semakin memudahkan Amari untuk terus menjalani kiprah sebagai ansambel yang berkualitas di masa mendatang. Namun, kita juga belum tahu, apakah musik sudah menjadi pilihan utama dari semua anggota Amari? Siapa tahu mereka bermusik hanya sekedar hobi, sampingan, maupun mengisi waktu kosong. Menurut Sumaryo L.E, pemusik non-hobi adalah pemusik profesional. Oleh sebab itu, mereka bukan lagi amatir. Musik bagi Profesional Musician adalah profesi, pekerjaan sehari-hari, dan musik adalah (nafas) kehidupan itu sendiri. Jika semua anggota Amari berniat menjadi pemusik profesional, itu berarti bidang musik sudah menjadi pilihan hidupnya. Apapun risikonya, mereka harus tetap berpengalaman lewat musik sampai mati! Semoga demikian adanya. *** Hadirnya salah satu bintang tamu: Sheilla Sanjaya, ternyata SMS: Short Music Service 129 belum bisa menampilkan pertunjukan yang maksimal. Banyak terdengar ketidakakuratan nada dari gesekan Contra Dance-nya. Mungkin Sheilla kurang persiapan, atau memang Sheilla kurang memiliki mental Solis? Bermain musik dengan banyak gerak tidak semudah yang dibayangkan. Sementara kaki berjalan-jalan, jari-jemari masih sibuk di atas neck. Konsentrasi buyar, meleset...dan akhirnya terjatuh juga. Masih butuh banyak latihan untuk Sheilla. Terkecuali Singgih Sanjaya yang memahami betul faktorfaktor demikian, meski Singgih sebetulnya bukan Solis. Namun, dari pengalamannya puluhan tahun bermusik, ia lebih paham bagaimana cara menjaga kondisi, tempo, keakuratan nada, dan memilih saat yang tepat untuk berimprovisasi sesuai karakteristik lagu yang ditampilkan. Pradipta Bagaskara 'melesat' bersama suasana panggung yang agak berbeda baginya. Namun sepertinya, ekspresi musikalnya masih belum maksimal, iringan dan solist belum menyatu. Ekspresi Pradipta hanyalah ekspresi tubuh yang penuh emosi, belum sampai ke ekspresi musikal dengan pertimbangan yang matang! *** Berbeda lagi apabila eksistensi (keberadaan) Amari diamati dari sudut pandang pendidikan musik anak. Bagi A.T Mahmud, musik anak merupakan wacana bagi anak untuk mengungkapkan gagasan dan perasaannya sesuai dengan ciri khas setiap perkembangan mereka. Antara anak dengan musik (nyanyian) ada keselarasan kaitan timbal balik yang harus dilihat dari dua sisi: sisi subjek adalah anak, dan sisi objek adalah lagu. Dengan memperlakukan anak sebagai subjek, anak akan menghayati nilai dan sikap yang berguna SMS: Short Music Service 130 bagi perkembangan dirinya menuju kedewasaan, sekaligus dapat mengembangkan kepekaan musikalnya secara sehat dan wajar. Dalam kutipan tulisan tersebut AT Mahmud mengkritisi lagu anak zaman sekarang, yang tidak mencerminkan kepribadian anak. Anak justru menjadi objek, bukan subjek yang penting. Dalam arti, lagu anak zaman ini tidak menanamkan pola kehidupan anak yang lugu, spontan, dan ceria, tetapi sebaliknya, malah menggambarkan gagasan orang dewasa. Amari memang tidak mewacanakan musik atau lagu anak karena mungkin ini memang kehendak mereka. Hampir semua lagu yang dibawakan Amari adalah lagu orang dewasa. Bukanlah hal yang baru bahwa melalui pendidikan musik sejak dini membuat perbedaan yang nyata terhadap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak. Karena musik adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan anak. Berbagai penelitian yang dilakukan di luar negeri membuktikan bahwa bila anak berinteraksi dengan musik sejak dini akan memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup anak. Oleh karena itu dikatakan bahwa musik adalah sesuatu yang alamiah dan merupakan bagian penting dalam perkembangan anak. (Rien Safriena: 2003). Sebuah lagu bisa mempengaruhi pendengarnya, apalagi jika pendengarnya adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Bagi anak, menyanyi adalah hal yang menyenangkan dan merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri, sementara lirik lagu ibarat sumber pengetahuan (informasi) yang mampu mengajarkan tentang keindahan alam, macam-macam binatang, lingkungan keluarga maupun lainnya yang SMS: Short Music Service 131 berkaitan dengan lingkungan dimana mereka tinggal. (Syahrul Syah Sinaga: 2003) Dengan demikian, pendidikan musik anak memang ada dan keberadaannya sungguhlah penting. Fenomena hadirnya Amari pada malam itu memang kurang sesuai dengan 'visi misi pendidikan musik anak', dan biarlah problematika itu dibongkar oleh pakar pendidikan musik yang berkompeten atau oleh para anggota Amari sendiri. Suatu ketika mungkin tidak terdengar lagi: Saya si putri...datang kemari menurut panggilan abang... Bagaimana dengan remaja? Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja, luar dan dalam itu, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja. Dengan demikian, remaja tentu berbeda dengan anak. Amari, sesuai dengan kepanjangannya: Ansambel Musik Anak dan Remaja Indonesia, adalah gabungan anak dan remaja dalam satu komunitas. Dua fase yang berlainan, antara anak dan remaja, terutama kadar-kadar responnya terhadap musik, adalah upaya yang meski dikuak dan dijadikan satu kesepahaman. Jawabannya: anak dan remaja sama-sama mengupayakan kreativitas bermusik yang ideal, tidak harus menuntut kebenaran. Bagi Dr. Djohan Salim (psikolog musik), musik tidak untuk dinilai jelek atau bagus. Sedangkan, musik apa yang kira-kira pantas dan cocok untuk remaja? Menongkrongi Global TV selama 24 jam adalah jawabannya. Mendengar Simphony karya Mozart, Haydn, Beethoven, Mahler, Schubert, Grieg, Mendelssohn, juga tidak SMS: Short Music Service 132 keliru. Mendengar musik Pat Matheny, Yanni, Deep Forest, Kitaro, Celiene Dion, Mayang Sari, Slipknot, GodBless, Led Zeppelin, Uriah Heep? Boleh-boleh saja. Apalagi mendengar Sheila On 7! Remaja memang menempati posisi wilayah dengar yang paling aman: musik apa saja bisa masuk! Silakan menjadi remaja terus. Jika sudah tua, kita akan malu jika setiap hari mendengar lagu Marshanda, apalagi menyanyi Ambilkan Bulan sambil menggerakkan tangan seraya menatap bulan di langit (?). Anak dan remaja adalah kebebasan berkehendak untuk mengekspresikan diri lewat jalur musik. Namun, sebaiknya kebebasan ekspresi tersebut masuk dalam koridor yang 'tidak membahayakan' perkembangan kepribadian anak dan remaja, apalagi membahayakan peradaban. Hal ini memang butuh selektifitas yang akurat. Apa yang telah diusahakan Amari beserta kerabat kerja, penata musik, dan siapa saja yang bertindak penuh 'di belakang layar' atas terlaksananya konser pada malam itu, pantas mendapat penghargaan, sanjungan, pujian, kritik, dan applaus yang meriah. Selamat dan sukses untuk Amari: di hari selanjutnya dan di masa depan! Sewon, 21 Februari 2006 Surat Cintaku Buat Kiai Kanjeng A khir-akhir ini, di banyak media, mencuat persoalan mengenai pluralisme, multi-kulturalisme, dan yang sejenis. Banyak ahli sosial gelisah, berpendapat dan akhirnya turun tangan. Salah satu masalah (dalam) pluralisme adalah semakin pudarnya toleransi antar umat beragama, seperti diungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X (Kompas, 8/08/07). Oleh sebab itu, berbagai kegiatan dilakukan untuk mendongkrak kembali kerukunan. Salah satunya adalah dialog antar agama secara jujur dan terbuka. Lalu, apa peran kesenian untuk solidaritas antar umat beragama? Malam itu (8 Agustus 2007), Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) beserta Kiai Kanjeng didaulat untuk memberi siraman rohani dalam sebuah acara peringatan 73 Tahun Paroki Pugeran, dengan tema Syukur atas Kebersamaan dalam Perbedaan: Mewujudkan Habitus Baru. Acara ini diselenggarakan di area Wisma Losari, Gereja HKTY Paroki Pugeran Yogyakarta. SMS: Short Music Service 134 Dibanjiri lebih dari 500 orang. Selanjutnya, tulisan ini akan menyoroti makna kesenian sebagai proses komunikasi (baca: antar umat beragama). Musik = Komunikasi Sejak awal naik pentas, Cak Nun tidak mengatakan Kiai Kanjeng ini berpentas. Melainkan, seperti diakuinya, “di sini kami tidak berpentas, dan musik Kiai Kanjeng adalah sarana komunikasi, “ ungkapnya. Maka dari itu, jika kita mengamati musik Kiai Kanjeng, mereka selalu fleksibel dan (selalu) bisa diterima semua kalangan. Fakta ini sejalan dengan apa yang diberitakan Harian Republika (Senin, 25/07/07), bahwa sejak Juni 1998 hingga Desember 2005 saja, Kiai Kanjeng telah mengunjungi lebih dari 1.300 desa, 930 kecamatan, 376 kabupaten, 21 provinsi. Kiai Kanjeng juga kerap diundang berbagai negara, semisal: Mesir, Italia, Jerman, Belanda, Finlandia, Skotlandia, Malaysia, dll. Sebuah peristiwa dan prestasi luar biasa dalam sejarah (pertunjukan musik) di Indonesia. Kehadiran Cak Nun dan Kiai Kanjeng ke berbagai wilayah di negeri Indonesia, selalu menjadi penyejuk dan pencerahan yang menguatkan rakyat berbagai kalangan, dari supir becak, petani, hingga para pejabat. “Ia tokoh yang berpijak pada rakyat dan memperjuangkan rakyat”, ungkap Budayawan Muhammad Sobary. Acara malam itu dimeriahkan pula oleh Novia Kolopaking, Untung Basuki (Sanggar Bambu), Shalawatan Gedung Kiwa, dan Paduan Suara Wilayah Kraton. Mereka memeriahkan acara dengan dipandu MC 'dagelan' Susilo (Den Baguse), yang penuh canda, dengan atmosfir yang meriah. SMS: Short Music Service 135 Kolaborasi dan Keteguhan Hadirin didaulat Cak Nun untuk ikut bernyanyi, sementara, hadirin belum tahu apa yang hendak dinyanyikan. Bayangan mereka, Cak Nun akan bernyanyi lagu-lagu Islami. Yang mengejutkan, setelah mempersilahkan para bapak ibu paduan suara dari Wilayah Kraton naik pentas, musik mulai berkumandang. Tak disangka, Kiai Kanjeng mengiringi bermacam lagu yang digarap secara medley (sambungmenyambung), antara lain: Tanah Airku, Yamko Rambe Yamko, Angin Mamiri, sebuah lagu Cina, You Rise Me Up, dan lagu rohani Katholik Ave Maria yang dimedley lagu-lagu Islami secara bergantian. Maka, ratusan hadirin sontak bernyanyi bersama karena sudah familier dengan lagu-lagu di atas. Mereka saling menghormati meski dalam perbedaan yang paling krusial. “Bapak ibu, saya mau tanya, apakah dengan digabunggabungkannya lagu Islam dan katholik ini iman khatolik bapak-ibu berkurang?”, tanya Cak Nun kepada hadirin. Mereka yang tertegun pun menjawab, “Tidak!”. Bagi Cak Nun, begitu juga sebaliknya. Pada prinsipnya, perbedaan hadir bukan untuk saling merugikan. Teguh prinsip itu sangat penting. 'Pagar' yang sudah dibangun hendaknya dijaga dan tidak dirusak. “Buat saya, perbedaan tidak menjadi masalah. Jika kita saling menghargai, itu tidak menjadi persoalan. Nggak ada masalah kok! Tenan! Bapak-ibu, wedus dan sapi itu beda. Namun, pada saatnya mereka akan berkumpul di ladang yang sama untuk mencari rumput! Oleh sebab itu marilah saling menghargai perbedaan dan berjalan satu tujuan. Kuncinya cuma satu: mari kita berbuat baik. Titik”, tegas Cak Nun yang disambut tepuk tangan meriah. SMS: Short Music Service 136 Ketika diminta memberi komentar untuk usaha kolaboratif tadi, Romo Paroki Pugeran, Antonius Dodit Haryono Pr. mengungkap, “Bahwa ini ekspresi paling jelas.100% kita orang Indonesia, 100% orang Katolik, atau 100% orang Islam, dan 100% menjadi warga etnis masing-masing, yang bisa menjadi satu.” Yang lain, Romo Yulius Blasius Fitri Gutanto Pr., memberi komentar tentang syukur atas keindahan (musik) yang diciptakan Tuhan. Ia merasa nyaman dan trenyuh ketika yang beda itu menjadi satu. Tidak dipermasalahkan. Bukan dakwah Cak Nun selalu beranggapan bahwa yang dilakukannya selama ini bukan dakwah. Dakwah yang sesungguhnya adalah perilaku yang konkrit dan riil. Ia selalu enggan disebut Budayawan, meski pemikiran dan tindakannya berpengaruh bagi kebudayaan. Bagi Cak Nun, ketika terjun di masyarakat, kita berbagi, tanpa peduli kamu siapa, dari mana, agamanya apa. Dalam Kiai Kanjeng, kesenian hadir sebagai media penyejuk iman, untuk menggelorakan semangat. Ini lebih efektif dibandingkan 'dakwah' dalam pengertian verbal, bukan auditif. Oleh sebab itu, proses komunikasi yang dicapai melalui acara ini adalah sinergi yang take and give, dan tidak berjalan satu arah, ada dialog dengan penonton. Malam itu Cak Nun berpandangan mengenai teori pluralisme, "Pluralisme yang berkembang selama ini bukan berpenger tian bahwa orang Islam jangan terlalu menampakkan dirinya Islam, nanti malah jadi setengahsetengah. Saya Islam, Anda bukan orang Islam, harus dicari celah menuju kebaikan bersama. Itulah pluralisme," jelas Cak Nun. SMS: Short Music Service 137 Berbagai pandangan hidup dan pemikiran dilontarkan Cak Nun. Ia menjelaskan bermacam hal yang memberi wawasan baru bagi hadirin yang mayoritas beragama katholik. Konsep jihad, perbedaan antara Kiai, Gus, Ustadz, dan Ulama; juga konsep 46 Piagam Madinah yang luar biasa. Ia menjelaskan kata Assalamualaikum dari subtansi, etimologi, hingga maknanya. “Kalau sudah Assalamualaikum berarti dalam hati kita berjanji tidak menyakiti orang lain yang diberi salam,” ujarnya. Saling Menghargai Kesimpulan dari pertemuan antar umat beragama ini adalah menyadarkan bahwa perbedaan itu bukan suatu masalah. Menyusutnya toleransi antar umat beragama yang akhir-akhir ini mencuat, dapat menjadi cambuk untuk bangkit. Apalagi di Yogyakarta, sebuah kota yang majemuk dan dihuni oleh beragam etnis. Jangan sampai, karena etnisitasnya, kita jadi enggan bersatu. Pada prinsipnya, kita tetap teguh pada benteng kita masing-masing, saling menghormati. “Yang Islam makin kuat Islamnya, yang Katholik makin kuat Katholiknya”, jelas Cak Nun. Baik Kiai Kanjeng, SABU, yang membawakan Iqra', Saudara-saudaraku, dan Lepas-lepas, maupun pengisi acara lain, telah ikut membantu memberi pencerahan lewat kesenian. Meneguhkan subtansi seni untuk komunikasi dan menumbuhkan sikap saling berbagi. Acara ini pun berlangsung sangat meriah dan sukses. Suasana humoris yang digawangi Den Baguse maupun Cak Nun mampu membuat hadirin betah menikmati acara itu selama kurang lebih 4 jam. SMS: Short Music Service 138 Peringatan Tuhan lewat Gempa Tulisan ini belumlah selesai, ada satu lagi peristiwa mengesankan. Setelah Shalawat al-Bushiri berkumandang untuk menutup acara, tiba-tiba terjadi goncangan yang cukup lama, sekitar pukul 12 malam. Gempa Bumi! Kepanikan pun merambah... Hadirin pun saling pandang, berdiri, terasa panik. Mereka berdoa. Cak Nun melantunkan Ayat Kursi. Ia bilang, “Tuhan hadir, Tuhan hadir. Ini mempersatukan kita”. Barangkali, ini adalah peringatan Tuhan, bahwa masalah pluralisme dan toleransi antar umat beragama tak cukup diomongkan. Kita harus bertindak riil dan konkrit. Sekaranglah saatnya. Agustus, 2007 Catatan: Baru-baru ini, dalam Pengajian bersama Emha Ainun Nadjib (17 Desember 2007) di Bantul, dibahas mengenai Letak, Peran dan Perjalanan Kiai Kanjeng. Pertanyaan seputar itu dilontarkan oleh Sabrang Mowo Damar Panuluh. Secara umum, tidak ada Letak yang bisa diidentifikasi, Kiai Kanjeng “duduk” di wilayah mana dalam konstelasi musik di Indonesia. Perannya lebih sebagai komunikasi sosial, dan bisa sebagai siapa saja. Perjalanannya adalah merefleksikan sejauh mana tugas-tugas yang telah dijalankan sampai sejauh ini. Renungan 62 Tahun Musik Indonesia Catatan: ini adalah makalah diskusi yang pernah dipresentasikan dalam kelompok diskusi Forum Studi Musik Turanggalila. Ini merupakan suatu catatan khusus yang merefleksikan situasi musik sejalan dengan pengalaman yang dialami penulis saja. Berisi fragmen pertanyaan yang berhak dijawab siapa pun. *** ini stanza satu: pertarungan kian larut, mari kita tidur saja agar terjaga pagi buta lihat kabut, sambil ngobrol ngopi, ngemut udut daripada kalang kabut lari terbirit sampai mungkid, mendut SMS: Short Music Service 140 tambahan: aku sekarang kuliah di institut setan fakultas iblis jurusan mayit semua menakutkan. biarpun takut aku tetap berjalan, (erie, jgj. 2007) baiklah, aku mulai bercerita: (1) Kita kini tidak sedang membicarakan rentang linier seperti rangkaian gerbong. Hanya saja, kita diajak menikmati mainan anak bernama odong-odong. 62 tahun (musik) Indonesia tidak bicara sejarah, namun bicara pencapaian dan prestasi (kualitatif, bukan kuantitatif). Ada apa sesungguhnya? Adakah persoalan atau aman-aman saja? (2) Yon Koeswoyo menyesalkan sikap Bung Karno: presiden bilang, pop itu ngak-ngik-ngok, tidak baik untuk “revolusi yang belum selesai”. Kreativitas yang marak pada masa itu dicekal. Koes Bersaudara pun masuk penjara. Itu tahun 1965. Kini, pop (malah) menjadi dominan di penjuru negeri, dikonsumsi, bukan diapresiasi. Industri dianggap gerbang meraih harta karun. (3) Belum lama ini Emha Ainun Nadjib bilang, bahwa kekuatan industri mengalahkan kekuatan negara. Di tahun 2100 barangkali, kekuatan perusahaan akan lebih besar dari negara. Dr. Faruk kurang setuju dan bilang bahwa industri juga SMS: Short Music Service 141 menguntungkan. Terserah, bagi Emha perbedaan pendapat itu wajar, asal sama-sama menguntungkan. Kini, selalu saja kita merasa deg-deg sir atas itu. Tapi, kenapa kita masih menjadi penikmat pasif, sulit lepas dari terkaman 'energi' industri yang gila? Apakah memang demikian adanya? Harus dibagi berapa porsi? (4) Musik, dan seni yang lain, selalu mencoba lepas dari hasil akhir: ia bicara proses, bisa berubah dan berganti setiap saat. Adakah perubahan penting atas kekaryaan musik selama kurun waktu 62 tahun? Setelah rapat besar para tokoh musik untuk pertama kalinya (Pesta Seni 1974), Indonesia mencatat banyak karya musik (klasik) terutama seriosa (musik vokal). Sementara, yang pop semacam Dara Puspita, Panbers, KoesPlus, Titiek Puspa, Bob Tutupoli juga berjalan beriringan. Ketika itu, Slamet Abdul Sjukur masih di Paris, karena ia baru pulang 1976. Musik Indonesia belum (jadi) kontemporer. Pak Suka Hardjana masih 34 tahun, baru panas-panasnya mengkritik, banyak nulis di koran-koran seluruh Indonesia. Trisutji Kamal masih cantik, Iravati Soediarso juga demikian. Dalam Pesta Seni itu, kalau boleh berpendapat, sebenarnya 'denyut jantung' pemikiran (masa depan) musik Indonesia baru awal-awalnya dimulai, setelah sebelumnya beberapa lembaga pendidikan musik (formal) berdiri. (5) Sebagian dari kita, saya yakin kurang berminat mempelajari pemikiran pribumi yang sesungguhnya super cerdas dan luar biasa, tapi kita justru memilih “mengobrakabrik” kekaryaan manca (Barat!) yang kadang-kadang kurang aplikatif dan kurang sesuai konteks. Belum kuat konsep dalam, sudah keluar secara liar, lupa tanah kelahiran. Belum SMS: Short Music Service 142 siap uang, pingin jalan-jalan beli buku belasan. Ini kurang tepat, karena kita (seolah) mengingkari pencapaian yang terjadi di negeri sendiri. Sah-sah saja. Tapi ada tapinya. Kalau kita hidup di Hongaria dan kenal almarhum Bela Bartók, kita pasti mengenal 16.000 lagu rakyat Hongaria yang ditelitinya bersama Zoltan Kodaly. Di Indonesia, Phillip Yampolsky hingga kini masih tetap keliling mencatat berbagai serpihan kekayaan musik (tradisi) di penjuru negeri (baca Kompas, 9 Agustus 2007). (6) Cornel Simanjuntak mati muda (26 tahun). Binsar Sitompul sahabatnya bilang, “kita harus menghargai peninggalannya bagi bangsa dengan rasa syukur”. Sejauh saya mengamati selama ini, tidak ada seni lain yang sanggup membangkitkan bangsa ini dalam semangat nasionalisme yang gagah, kecuali musik. Misalnya, dengarlah Maju Tak Gentar, Sorak-Sorak Bergembira. Atau, lihat saja presiden kita SBY, ia tertegun saat mendengar 'Nyanyian Negeriku' berkumandang di upacara 17 Agustus yang lalu. Saya tidak bicara soal terharunya presiden SBY itu, juga tidak mau bahas kualitas sound system atau kualitas pemusik yang masih belum siap (skill dan mental!) itu. Namun, saya hendak bicara tentang kesadaran nasionalisme: mentalitas. Lalu mau apa mereka bermain musik? Bicara honor atau roh-nya? Semua penting, tapi pasti ada yang (lebih) penting, yang lebih manusiawi, nuraniah, inderawi, dan jujur. Terus terang, selama ini, yang gagal di kita, adalah pendidikan mental! Skill oke tampang oke, nggak punya mental sama artinya tak punya strategi, jadinya (cuma) ikut arus. Diajak masuk sumur ya ngikut saja. Tentara berperang itu bukan soal banyaknya peluru, lengkapnya atribut dan SMS: Short Music Service 143 senjata, tapi bagaimana mengatur strateginya. Kalau bisa, sehari bisa maju 14 kilometer hingga menabrak pertahanan lawan. ini stanza dua: perjuangan belum selesai, mari kita tutup saja agar pembeli nggak kecilik lihat kita laris, bilang apik-apik... pulang mata mendelik, kecewa ndakik-dakik (erie, yogya 2007) (7) selama berdirinya hingga kini, sudahkah institusi menjadi barometer ilmu pengetahuan? Sudahkah institusi menjadi suatu kebutuhan berseminya intelektualisme musik bagi masyarakat? Di buku Tahta Berkaki Tiga (2005) St. Sunardi bilang, tahta kepemimpinan perguruan tinggi itu intelektualitas, moralitas, dan keberanian. Sesungguhnya kita punya itu semua, tapi selalu bingung karena realitas (kadang) bicara lain. Bagaimana menanggulanginya? (8) yang manual itu membosankan sekaligus mengasyikkan. Yang digital itu mengasyikkan sekaligus membosankan. Manual ke teknologi, itu kemajuan. Sejak munculnya teknologi rekaman misalnya, hingga kini, manusia memproduksi audio, memanipulasinya dalam waktu amat singkat. Mau bikin karya elektronik, konkrit, fluxus, sound-art, visual-art, atau videoart? Boleh. Semua sudah masuk Indonesia dan ramai dalam SMS: Short Music Service 144 2-3 dekade terakhir. Yogya, Jakarta, Bandung, sudah cukup lama bermain-main itu. Dari Yogyakarta, saya tetap menjagokan Tony Maryana dan Gatot D. Sulistiyanto, sama seperti heboh sastra 1980-an. Ada dua pendekar bernama Linus Suryadi dan Emha Ainun Najib. Kini, siapa yang jadi pendekar muda? Di tangan siapa 62 tahun musik Indonesia dan seterusnya? Sebagai kreator kebudayaan, dalam berkarya apapun, kita akan bicara kedalaman, bukan permukaan. (9) Kunci jawaban: cuma optimis dan terus berkarya. Namun, berkarya saja tidaklah cukup, kita harus berkarya bakti. Yogyakarta, 20 Agustus 2007 Menonton (Konser) Musik M enonton adalah sebuah aktifitas yang melibatkan beberapa unsur sekaligus. Jika kita menonton pertandingan sepak bola, kita akan berharap tim yang kita dukung meraih kemenangan. Itu berarti, selain sepak bola sebagai tontonan yang tak berarti apa-apa, ternyata justru menjadi bagian dari 'harapan' kita: semoga yang dijagokan menang, lantas membawa kebahagiaan hati. Aktifitas 'menonton' kerumunan orang berlalu-lalang di tengah pasar juga dapat menjadi keasyikan tersendiri, namun hal itu belum tentu bermanfaat bagi kita. Setiap hari kita diperkenankan menonton televisi dengan beragam acara yang ditawarkan. Tentu, tidak semua acara menarik perhatian. Kita perlu memilihnya. Arak-arakan Kebo Kiai Slamet yang selalu dilakukan pada malam 1 Suro (Tahun Baru Jawa) di Surakarta, hadir untuk memberikan tontonan kepada masyarakat, sekaligus dipercayai bisa membawa berkah apabila kita mengambil kotoran kebo (tai) itu. Masyarakat SMS: Short Music Service 146 sering berduyun-duyun pergi ke kota untuk menonton 'pawai pembangunan' memperingati kemerdekaan. Kita pernah, meski sekali dua kali, pergi ke bioskop untuk menonton film yang kita sukai; kita ingin menonton artis yang diharapkan muncul di layar yang amat lebar. Masih banyak lagi aktifitas tontonan yang bisa disebutkan sesuai dengan pengalaman kita. Aktifitas menonton ternyata menarik perhatian. Hampir semua yang ada di sekitar kehidupan kita seolah memaksa untuk ditonton. Mata, sebagai medium transformasi dan otak sebagai medium persepsi, adalah dua unsur pokok yang kita gunakan ketika kita menonton. Kita tidak akan tahu apa-apa apabila kita tidak mencoba mempelajari, atau setidaknya menangkap maksud dari apa yang dipertontonkan pada kita. Untuk urusan musik, kita mengenal apa yang dinamakan pertunjukan musik. Kita semua telah menontonnya. Apa yang ingin dikuak dari aktifitas menonton pertunjukan musik? Teori tentang filosofi menonton pertunjukan musik agaknya belum pernah ditulis. Hal yang paling sederhana—yang berkaitan dengan persepsi yang kita miliki—sangat bergantung pada tingkat pemahaman/latar belakang pengetahuan kita, dengan tidak bermaksud mengatakannya latar belakang pendidikan. Kita akan merasa takjub tatkala menonton keahlian Ananda Sukarlan di atas pentas karena sebelumnya kita tahu bahwa dia adalah seorang virtuoso, komposisi yang dibawakannya tergolong amat berat dengan teknik advance. Kita tidak bisa mempercayai orang lain yang akan mempertontonkan keahlian bermusik sebelum menyaksikannya secara langsung di gedung konser atau 'lapangan' tempat digelarnya pertunjukan. SMS: Short Music Service 147 Sebelum berniat menonton pertunjukan musik, biasanya kita mempertimbangkan banyak hal. Pertama, siapa yang akan tampil. Kedua, jenis musik apa yang akan dipertontonkan. Ketiga, kapan, dimana dan berapa harga tiket. Keempat, apakah yang akan kita tonton bisa bermanfaat. Keempat pertimbangan tersebut, bagi saya adalah yang paling ideal. Berbeda lagi apabila kita diajak seorang teman untuk menonton pertunjukan musik dengan tiba-tiba. Kita tidak mempertimbangkan apa pun. Setelah sampai di gedung konser, ternyata kita kecewa, harga tiket terlampau mahal atau kita belum mengenal reputasi performer yang akan tampil. Beberapa pertimbangan tersebut, barulah sampai pada taraf 'merencanakan menonton pertunjukan musik', belum sampai pada 'menonton pertunjukan musik'. Hal yang filosofis, adalah hal yang berusaha dikuak atau dianalisis dari pertunjukan musik dalam konteks pemenuhan akan ilmu pengetahuan. Di sini, tidak ada pembedaan bahwa sebagai 'orang yang tengah belajar musik serius', melulu harus menonton pertunjukan musik seirus. Musik pop pun, yang bagi Raymod Williams adalah kebudayaan 'orang banyak', ternyata amat memungkinkan untuk dibedah ataupun dianalisis. Di sini, musik pop tidak dipandang sebagai sesuatu yang rendah. Dalam dunia wayang, kita mengenal dua unsur pokok, yaitu tontonan dan tuntunan. Misalnya, kita suka dengan gaya dalang Anom Suroto atau Manteb, tentulah ini satu hal yang membuat kita ingin menontonnya. Ini baru satu sisi. Ada pelajaran apa? Wayang, adalah seni yang tiada tanding. Cerita yang disampaikan selalu penuh muatan filosofis, bicara budi pekerti, pengetahuan, dll. Ada yang bilang, jika ingin 'kuliah', SMS: Short Music Service 148 simaklah pagelaran wayang kulit saja, ia adalah guru kehidupan. Oleh sebab itu, inilah sisi tuntunannya. Nah, bagaimana di musik? Apakah bisa begitu saja disamakan keberadaannya dengan wayang? Tentu tidak. Pertama, yang harus diingat, musik bersifat auditif (pendengaran), bukan visual. Kedua, musik tidak begitu menjamin adanya unsur filosofis. Lalu? Apa yang hendak dicapai ketika menonton pertunjukan musik? Persoalan ini, pada prinsipnya hampir sama dengan wayang. Musik itu (juga) tidak cuma tontonan, tapi juga tuntunan. Bedanya, tidak semua musik bercerita tentang filosofi kehidupan seperti halnya wayang. Musik cuma menuntun kita menghargai penghayatan, penikmatan, dan suatu konsepsi dasar mengenai rasa (auditif) dalam konteks psikologis, bukan logis saja. Nah, wayang tidak menjamin pengungkapan ekspresi seperti musik, karena kita cuma mendengar, melihat, menyimak, dan memahami apa yang disampaikan saja, sama seperti kuliah. Musik bicara soal penghayatan rasa ngeng yang mengendap. Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa musik itu (juga) tidak sekadar ditonton dan disamakan seperti nonton sepak bola. Musik membuka kemungkinan untuk menghayati nilai estetis yang unik, yang tidak bisa ditemukan di seni lain seperti tari, seni rupa, teater. Dan, masing-masing seni juga akan memiliki cita-rasa khas yang masing-masing unik dan berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika menonton pertunjukan musik, sebenarnya yang 'bermain' bukan cuma mata, tapi indera penghayatan berupa rasa, untuk menghargai konteks manusia pencipta, mengurai satu demi satu masalah ke-manusia-an (ekspresi) dalam tataran mendasar. Kelemahannya, pembicaraan atas ke-manusia-an SMS: Short Music Service 149 sebagai ekspresi itu memang belum memungkinkan adanya lanjutan yang konkrit, karena musik bukan bicara hal konkrit tapi musik adalah sarana penting untuk menghargai kemanusiaan. Yogyakarta, 2005 Kepadamu Seniman Jalanan S ungguh patut dibanggakan apabila kehadiran pengamen mampu memberikan pengaruh positif serta mampu menghibur dengan segenap hati dan perasaannya kepada masyarakat khususnya para pengguna transportasi umum. Mungkinkah pengamen tidak lagi menjadi simbol anarkisme, namun justru dapat menjadi sumber daya manusia (SDM) baru yang berkemampuan seni sehingga diharapkan dapat menjadi sosok seniman yang berguna dalam kehidupan berkesenian. Namun, ketika kehadiran pengamen dinilai memberikan dampak negatif dengan tindakan anarkisnya, ini sungguh patut disayangkan. Terlebih apabila kehadiran sosok pengamen telah merusak kaidah kesenimanannya, yang kebanyakan orang menyebutnya sebagai seniman jalanan. Arti kata seniman adalah orang yang berbuat seni (contoh: musik, tari, teater, dsb.) dan berkecimpung di dunia seni. Seniman yang dapat dikatakan sebagai seniman yang baik SMS: Short Music Service 152 ialah yang benar-benar menghargai profesinya. Antara lain selalu berusaha memelihara dan menjaga estetika seninya. Apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seniman, maka konsekuensinya selalu berkarya dengan seninya guna mendapatkan hasil untuk kebutuhan hidupnya. Hasil tersebut daat berupa pengalaman, pengetahuan, ilmu, maupun yang bersifat finansial. Hidup di Jalan Memang hampir seluruh waktunya pengamen hidup di jalanan. Ini merupakan alasan orang mengapa pengamen disebut-sebut sebagai seniman jalanan. Bila dikatakan pengamen adalah seniman jalanan, tentunya harus memenuhi dulu beberapa kriteria yang disebut di atas. Jadi, tidak semua pengamen dapat dikatakan mereka seniman jalanan. Mengapa demikian? Persoalannya sekarang, sejauh mana seorang pengamen benar-benar menghargai profesinya sendiri. Sosok pengamen yang bagaimanakah dapat dikatakan memiliki jiwa seni sehingga sangat memungkinkan ia menghargai profesinya sebagai seniman jalanan, bukan justru meresahkan masyarakat. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar yang takkan mungkin terjawab apabila tidak ada peran serta masyarakat, aparat keamanan dan pengamen itu sendiri. Penyuluhan yang Tepat Tentu aparat keamanan dapat memberikan penyuluhan yang baik menyangkut aspek-aspek kesenimanan yang tepat bila akan merazia sekelompok pengamen yang dinilai memang meresahkan masyarakat tersebut. Tanpa diberi SMS: Short Music Service 153 pengertian tentang bagaimana menjadi seniman jalanan yang baik, mustahil semua akan berubah menjadi baik. Mereka (para pengamen) akan tetap menghiasi kehidupan dengan lagu dan tindak kejahatannya. Dari pengamatan saya selama enam bulan terakhir ini, karena saya sering mengadakan perjalanan keluar kota maupun kedalam kota dengan kendaraan umum, sangat sedikit pengamen yang berprofesi dengan baik. Berdasarkan pantauan saya tersebut, dari sekitar 50 pengamen lebih, tidak sampai separonya yang bisa menghibur dengan baik, segenap hati dan memiliki jiwa kesenimanan yang tinggi, selebihnya hanya pengamen yang asal berdendang. Menurut saya, seorang seniman jalanan yang memiliki jiwa seni tinggi adalah mereka yang dapat menghibur dengan bernyanyi sungguh-sungguh, dengan memainkan musik secara baik pula, serta dapat menerima keadaan atau tanggapan orang lain yang turut menyaksikan dengan ikhlas. Mereka (para pengamen) dapat mengerti bahwa kehadiran dia dengan lagunya belum dapat diterima orang lain. Maka, dengan segenap hati, pengamen tersebut akan memakluminya dan merasa tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa, merampas, mengompas dan berbuat kejahatan lainnya. Pengamen yang memiliki jiwa kesenimanan yang tinggi selalu akan berusaha untuk menghibur orang lain dengan sebaik-baiknya. Lagu-lagu yang dinyanyikan akan terdengar indah dengan musik yang harmonis sehingga tak segan-segan orang yang mendengarnya memberi upah sebagai rasa terima kasih karena telah dihibur. Pengamen seperti inilah cerminan kehidupan berkesenian yang baik. Jadi, antara seniman jalanan yang benar-benar nyenimani SMS: Short Music Service 154 dan seniman jalanan yang hanya etok-etok'an harus dibedakan. Ini untuk memudahkan kita mengerti dalam memberikan penilaian terhadap pengamen. Jangan lantas menilai semua pengamen adalah buruk dan meresahkan masyarakat. Bahkan, kalau boleh disinggung, artis sekaliber Iwan Fals, Didi Kempot, dan sebagainya juga pernah menjadi pengamen dalam awal-awal karirnya. Namun mereka menghibur dengan segala jiwa kesenimanannya. Mereka justru dapat sukses dan tetap konsisten untuk selalu mewarnai blantika musik (pop) Indonesia. Sudah selayaknya para pengamen mengerti arti profesi mencari nafkah sebagai seniman jalanan dan mengerti arti kesenimanannya, bukan malah merusak kaidah seni dengan tindakan yang berbau anarkistis. Ini semua demi menciptakan kehidupan berkesenian jalanan yang kondusif serta meningkatkan harkat dan martabat pengamen hingga mereka tidak lagi keras dan kencang disebut sebagai sososk yang meresahkan masyarakat dan justru dapat berguna demi menciptakan kehidupan berkesenian yang sehat dan dinamis. Solo, 2003 Borobudur Live in Concert: Antara Potensi dan Politisi D alam budaya mutakhir dimana produksi komoditas bersanding dengan produksi simbolik makna dan penggairahan provokatif lewat iklan yang merangsang basic instinct untuk mengkonsumsi terus-menerus dan menuruti selera yang diciptakan oleh penguasa pasar, pemahaman dan penulisan kritik seni mesti bisa melihat sisi the sacred dalam komoditas konsumtif sekaligus yang simbolik dari citraancitraan dunia hiburan agar erosi nilai pembendaan diketahui kapan mulainya. Mampukah kritik seni keluar dari makian dan menuding kapitalisme sebagai biang tandingan mencoba menanggapi secara cerdas, kultural, dan alternatif yang memaksa penguasa pasar menghargai sumber berkesenian sebagai perayaan hidup dalam festival? (Kompas Minggu, 24/4/05). Pernyataan Mudji Sutrisno di atas boleh diakui kebenarannya. Budaya popular memang merupakan tantangan terbesar bagi pertahanan nilai-nilai yang tumbuh di SMS: Short Music Service 156 sisi lain lewat budaya “non-populer” (seni yang hidup di festival)—yang berorientasi mewacanakan simbolik makna. Menyikapi hal itu, Mudji menyarankan agar kritikus tidak semata-mata menuduh kapitalisme (sebagai ideologi-nya budaya massa), tanpa disertai tanggapan yang cerdas. Pe r nya t a a n i t u m e n a r i k n a m u n s e ka l i g u s j u g a membingungkan. Kalangan kritikus, seniman, atau artis sekali pun, tidak bisa sanksi terhadap kecenderungan seni populis yang akhirakhir ini mencuat tajam di media televisi. Seni yang kerap kali ditampilkan secara mewah dengan kemasan yang menarik, mau tidak mau tetap menggoda para penonton untuk duduk diam melihat sang idola atau pun sekadar mengisi waktu luang. Televisi menggoda 'ratusan juta' pasang mata. Televisi turut membantu me-lena-kan jutaan orang untuk mudah berkecimpung pada “budaya tontonan” daripada “budaya membaca”. Agaknya, asumsi itu pula yang memaksa kalangan pemerhati seni me-meta-kan, mana yang seharusnya dipilih: menonton atau 'membaca'? Dua tawaran pilihan itu tidak akan bisa terjawab jika ternyata ada pembedaan signifikan yang menarik garis batas antara kedua istilah itu. Berbeda dengan membaca, menonton adalah suatu kegiatan pasif yang dilakukan oleh orang; belum tentu dimungkinkan adanya suatu respon aktif bagi tindak pengetahuan yang ber-implikasi pada realitas. Sedangkan membaca adalah kegiatan aktif yang memaksa pembaca berpikir ulang atas yang dibacanya kemudian mencocokkan-nya dengan realitas, sekaligus agar bisa lebur dalam realitas tersebut. Televisi adalah realitas (semu) itu sendiri. Baca-an adalah realitas yang masih dalam tataran verbal (non-gerak). Tetapi, SMS: Short Music Service 157 argumen itu bukan titik final. Setiap orang yang menonton sesuatu, mereka sesungguhnya turut pula membaca. Obyek yang dibaca bukanlah bahasa verbal seperti di buku, namun merupakan suatu tampilan simbolik yang seolah-olah menawarkan gagasan bagi penonton yang 'membaca', agar kemudian menyikapinya sesuai kehendak hati (respon). Tindakan fans yang tergila-gila pada artis adalah salah satu contoh kasus ini, atau biasa disebut histeria massa. Seperti dilontarkan novelis Nh. Dini baru-baru ini, budaya membaca bangsa ini memang belum tumbuh sekuat budaya menonton-nya. Dengan begitu, bangsa ini sebenarnya telah terkecoh oleh satu nilai yang mustinya dihargai demi pertumbuhan intelektualitas bangsanya. Namun justru sebaliknya, itu cenderung tidak dihargai. Membaca menjadi sesuatu yang agaknya sulit dilakukan. Menonton adalah pilihan tepat, karena tidak perlu membolak-balik halaman, berpikir, atau pun menerjemahkan istilah asing lewat kamus ilmiah yang tebal. Remoute telah membantu penonton sepenuhnya untuk menuruti keinginan yang serba instan, tinggal tekan, klik, jalan. Jawaban “sah” akan tepat apabila realitas itu akan disikapi dengan dua pertanyaan (sah atau tidak?). Namun agaknya, ada yang salah dari semua ini. Kegawatan bangsa ini dalam menyusuri lorong hidupnya adalah ketika berhadapan dengan budaya yang salah. Menonton adalah suatu kegiatan yang wajar. Begitu pula dengan membaca. Menonton dengan sekaligus 'membaca' adalah titik kegawatan yang belum dilakukan secara penuh oleh bangsa ini. Oleh sebab itu, bangsa ini sebenarnya perlu menonton segala yang ada dan mencuat ke permukaan yang timbul lewat media, sekaligus membaca makna simbolik (ide) dari obyek yang ditontonnya SMS: Short Music Service 158 sebagai suatu sinergi (komparasi) untuk pembanding hidup (penonton)sebagai upaya koreksi, apakah yang ditontonnya merupakan sesuatu yang salah, benar, baik, atau menjerumuskan. Orang akan terpredikati “salah besar” apabila sematamata hanya memanfaatkan media sebagai cermin diri dan meniru segala sesuatunya tanpa pertimbangan yang matang. Sebagai contoh, kasus perkosaan kini (seolah) menjadi suatu tren. Salah satu sebabnya adalah televisi sering mengeskposnya. Image, tindakan meniru ungkapan (katakata) di iklan televisi juga demikian adanya: menjadi tren yang berkepanjangan bagi ibu-ibu atau remaja. Memberi dukungan SMS bagi idola adalah kegiatan asyik yang semakin sulit ditinggalkan banyak orang, tanpa memperhatikan bahwa itu sesungguhnya suatu keborosan yang tidak berguna karena hanya menuruti keinginan emosi sesaat. Beberapa contoh sederhana tersebut bisa menjadi bukti bahwa bangsa ini enggan melakukan keoreksi terlebih dahulu terhadap apa yang ditontonnya di televisi sebelum melakukan tindakan yang berguna atau tidak (mereka cenderung menafikkan). Bisa dilihat sekarang, bahwa yang terjadi, atau dampak yang menyembul adalah budaya baru: miskin jati diri bagi kehidupan manusia. Oleh sebab awal manusia diciptakan untuk mencari jati diri, telah kalah oleh terpaan simbolisme budaya media yang menggebu-gebu bagai meriam yang sulit tertandingi. Orang lebih memilih menonton daripada membaca; meniru daripada berkreativitas sendiri; dan bahayanya, jika orang lebih terlena oleh sindrom budaya populis, nantinya (lama-kelamaan) orang tersebut tidak akan tahu siapa sesungguhnya dirinya. Oleh karena itu, manusia sulit hidup dan berkembang sebagai “manusia” yang SMS: Short Music Service 159 berbudaya secara benar. Sulit mengerti dirinya sendiri. Sebetulnya, suatu kritik menjembatani secara kompeherensif akan hal ini. Mudji Surtisno menyarankan, “...resensi seni pertama-tama harus kembali pada tempat seni itu diproses, yaitu dalam ritus untuk melahirkan, merawat, dan membuahi kehidupan, dan festival atau perayaan kehidupan dari oasis dan ruang pemuliaan gairah hidup dan motivasi hidup”. Seni ber-kualitas yang dapat dikatakan 'baik' untuk dikonsumsi adalah seni yang diciptakan melalui proses yang benar (tidak instan), karena di situ akan ada kelahiran, tindakan merawat dan membuahi kehidupan. Saran Mudji selanjutnya sangat bagus: perayaan kehidupan dari oasis dan ruang pemuliaan gairah hidup dan motivasi hidup. Harap dicatat, bahwa instan adalah salah satu ciri untuk mengidentifikasi pop. *** Ketika menyaksikan Borobudur Live in Concert dengan tema “Pesan Damai dari Satu Keajaiban Dunia” yang digelar di Lapangan Gunadharma kompleks Candi Borobudur (Sabtu, 23/4/05), ada beberapa catatan yang bisa dicermati untuk tidak lebih dari sekadar pesan dan kesan sepengetahuan saya saja. Acara yang boleh disebut “spektakuler” itu menampilkan tiga sinergi sekaligus. Pertama, Pariwisata (Candi Borobudur). Kedua, Seni dan Budaya (Materi acara). Ketiga, Ekonomi. Alasan dari sinergi yang ketiga itu adalah adanya sebuah propaganda produk teknologi informasi komersial (Telkomsel) yang mem-back up sepenuhnya acara “wah” tersebut. Acara ini memang menarik, terutama apabila kita menyaksikan stage yang dilatarbelakangi oleh kemegahan Candi Borobudur warisan Dinasti Syailendra di abad ke-9 yang SMS: Short Music Service 160 begitu dahsyat itu. Menariknya, acara itu juga bisa dilihat dari banyaknya wisatawan asing yang datang. Potensi wisata yang ada, dipamerkan sebagai aset ekonomi nasional, dan kekayaan akan nilai budaya yang dimiliki Indonesia. Pemilihan tempat untuk pergelaran telah berhasil disiasati dengan gemilang. Namun, tidak secara keseluruhan acara itu berhasil. Jauh hari sebelum acara itu berlangsung, di sebuah surat kabar nasional, Sutanto Mendut melontarkan kritik bahwa acara itu terkesan terlalu elit. Bayangkan, konon tiket dihargai Rp. 250.000,00. Jumlah uang yang tentunya tidak sedikit. Lebih lanjut, hal ini akan menyebabkan rakyat kecil yang berkeinginan menonton tidak terwujud. Jadi, acara itu menjadi kesempatan bagi “pesta”-nya kalangan berstatus sosial tingkat atas. Acara itu menampilkan sederet artis yang menyandang predikat papan atas. Antara lain, Ruth Sahanaya, Christoper Abimanyu, Katon, Nugie, Tasya, Mollucas, Iyeth Bustami, dan diiringi oleh Vista Simfoni Orkestra dengan konduktor Paulus Surya. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto, dan Menteri Pariwisata Jero Wacik. Acara itu diawali oleh sambutan pembuka dari Miss Indonesia Imelda Fransisca, dibuka oleh Gubernur, dan selanjutnya dipandu oleh Farhan dan Astrid sebagai MC. Acara yang berlangsung sekitar dua jam itu memang diakui baru pertama kali digelar. Dengan bendera Vista Simfoni Orkestra lewat ekspresi 150 musisi mudanya (dari SMM!) dan 140 vokalia, Paulus Surya mencoba membawa emosi penonton dengan susah payah. Ada ketidakberhasilan yang tanpa terduga muncul. Ternyata, artis yang diberi applaus adalah artis yang sudah lebih dulu dikenal publik. Karena, di SMS: Short Music Service 161 samping artis top, malam itu muncul juga artis lokal yang turut menyanyi. Meraka itu tidak begitu terkenal, jadinya tidak mendapat applaus meriah. Lho! Padahal suaranya bagus, penampilan juga oke. Kok kalah sama Ruth Sahanaya atau Katon Bagaskara? Emosi penonton menjadi naik turun. Habis mendengar yang bagus (atau terkenal?) lalu mendengar yang bagus lagi (tapi tidak terkenal?). Salah siapa ini? Paulus Surya atau penonton? Oleh sebab itu, emosi penonton kurang bisa dibangun secara gradual. Mungkin, konser malam itu tidak terlalu bisa kontinu alias terputus-putus. Ketidaksigapan sound engineer dalam mengatur keseimbangan soundsystem juga mengakibatkan sound menjadi kurang bagus. Apalagi, desis noise mikrofon selalu muncul berkepanjangan. Ha...ha...ha..., konduktor sudah siap-siap mengangkat tangan tanda aba-aba lagu akan dimulai, eee...di white screen muncul iklan Telkomsel dengan suara yang keras. Kedua tangan Paulus Surya turun lagi. Mubazir deh... Terlepas dari faktor musikal, seperti dituturkan Gubernur, bahwa Candi Borobudur telah dikenal masyarakat sebagai salah satu keajaiban dunia. Kemegahan candi yang terpantul melalui arsitektur bangunan dan relief yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha dan masyarakat, menjadikan Candi Borobudur sebagai bangunan bersejarah yang bernilai tinggi, pusat budaya, pusat kegiatan keagamaan, tujuan wisata, dan lain sebagainya. Memanfaatkan ikon budaya (Candi Borobudur) sebagai tempat untuk berlangsungnya pergelaran (juga seperti di Stage Ramayana Prambanan), adalah suatu kesempatan berharga yang banyak mengandung manfaat. Terutama bagi promosi pariwisata. Bagi kesenian, setidaknya itu merupakan usaha menanamkan fungsi tersendiri. Kemegahan Candi Borobudur SMS: Short Music Service 162 menjadi obyek wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan Jawa Tengah, sudah barang tentu Candi Borobudur sebagai obyek wisata “given” tidak harus didiamkan begitu saja melainkan perlu dikreasi dengan berbagai event agar lebih bermakna dan atraktif, seperti yang dikemukakan Agus Suryono selaku ketua panitia. Munculnya Telkomsel secara berlebihan memang membuat acara ini menjadi setengah bisnis. Maksud konsep acara yang berkenaan dengan misi adalah, (1)mengajak penonton untuk menikmati pertunjukan; (2)menyuarakan pesan damai bagi dunia internasional (lewat tema); (3)mempromosikan potensi wisata; (4) menguak potensi seni dan budaya; dan (5)bisnis, bung! Dari kelima misi itu, bolehlah ditarik kesimpulan, bahwa acara ini punya banyak maksud yang kompleks. Saya tidak menemukan penekanan yang signifikan dari maksud-maksud tersebut tatkala menonton acara itu. Dengan kemegahan Candi Borobudur “saya” tertarik, dengan telkomsel “saya” terpikat, dengan seni budaya sebagai materi acara “saya” juga terlena. Demikianlah kira-kira kesan penonton yang bisa saya tangkap. Penekanan paling tajam dari maksud itu bagi saya lebih pada potensi pariwisatanya. Mengadakan pergelaran seni di gedung konser tentu beda dengan di tempat umum, apalagi di daerah wisata yang dikenal meng-internasional seperti Borobudur. Tulisan ini memang bukan bermaksud membedah segi tekstual pertunjukan itu. Yang lebih menarik adalah lingkaran faktor kontekstualnya: baik sosiologis maupun budaya. Namun, bolehlah disinggung sedikit bahwa acara pada malam itu—dari segi tekstual—sudah cukup berhasil, meskipun ada sedikit kesombongan yang tidak perlu dan klise (dengan adanya kata terbesar dan termegah di buklet!? ). Sungguh SMS: Short Music Service 163 sayang jika kemasan 'luar'nya saja yang besar dan megah, tetapi isinya jauh dari maksimal. Jika dilihat bahwa ternyata persiapan acara itu terbatas, inilah yang menyebabkan acara itu kurang berhasil. Dari tulisan inilah tentunya bisa disikapi lebih jauh oleh berbagai pihak yang merasa peduli terhadap bangsa ini, agar seni budaya dan pariwisata gagal menjadi propaganda kepentingan politis yang berkelanjutan, tetapi lebih pada kreasi potensi yang dikembangkan secara jujur dan bermakna! Surakarta Hadiningrat, 24 April 2005 Demonya si Tukang Bonang P ementasan Dedek Wahyudi masih sarat dengan unsur konvensional. Unsur menariknya adalah gerak-gerak tubuh pengrawit yang dimodifikasi sedemikian rupa, cantikcantik pendukungnya, dan kemunculan kolaborasi aneka warna. Sedangkan media (alat musik yang digunakan) tetap sama (gamelan), hanya berbeda sedikit cara memperlakukannya. Pementasan itu cukup bagus karena mengandung muatan-muatan kritik terhadap situasi yang sedang terjadi di Tanah Air, suatu kritik sosial yang menggugah, dipadu dengan humor yang cukup segar. Lakon pertunjukan itu adalah “Demonya Si Tukang Bonang”. Konon ceritanya begini: Di sebuah pondok gamelan, seorang tukang bonang melakukan aksi protes menuntut adanya perubahan di dalam sajian gamelan konvensional. Kendang sebagai penguasa (irama) tidak menggubris tuntutan itu. Akhirya tukang bonang memutuskan walkout dari keanggotaan, kemudian membuat SMS: Short Music Service 166 pondok gamelan tandingan. Di pondoknya yang baru, tukang bonang berusaha mencari dukungan. Berkat kegigihan serta janji perubahan yang ditawarkan membuat banyak orang ingin bergabung. Seperti tukang demung, saron, suling, rebab, terbang, bersedia untuk berkoalisi. Tidak hanya dari kalangan pengrawit, bahkan penari, dalang, pemain sinetron, tukang lampu, menyatakan diri untuk mendukung. Dalam menunjukkan eksistensinya, tukang bonang kadang-kadang berpenampilan ekstrim, e k s e n t r i k b a h k a n c e n d e r u n g k a s a r. Te r k a d a n g penampilannya lembut layaknya seorang Da'i yang sedang berdakwah. Menurutnya penampilan tidaklah penting, yang penting adalah niat baiknya, memperjuangkan kebajikan dan memerangi kejahatan. Akibat dari penampilannya itu, kelompok pondok gamelannya sering didatangi orang yang tidak dikenal, tamu misterius yang mencoba mencari tahu maksud kegiatan demo-demonya. Dedek Wahyudi, dalam perannya sebagai komponis, memiliki peran vital dalam pertunjukan berdurasi satu jam itu. Mengamatinya dari dekat, tentu tidak hanya eksplorasi gamelan saja yang dilakukan Dedek, melainkan ada sentuhan eksplorasi gerak (Eko Supriyanto) dan dalang (Slamet Gundono), yang membuat pertunjukan itu menjadi karya warna. Dedek Wahyudi dikenal sebagai komponis (terutama untuk iringan tari) yang cukup berbakat di negri ini. Ia banyak membantu pementasan karya tari koreografer terkenal seperti Sardono W. Kusumo, Dedy Luthan, dll. Selain aktifitas kreatifnya sebagai pencipta musik iringan tari, ia juga tergolong produktif berkarya (menciptakan komposisi otonom) dan pernah beberapa kali menggelar pertunjukan di SMS: Short Music Service 167 luar negeri (Inggris, Jerman, Belanda, dsb.) Saya tidak merasa menemukan ada gagasan baru yang disampaikan Dedek lewat pementasan “Demonya Si Tukang Bonang” ini. Semua eksplorasi Dedek saya anggap sudah pernah dilakukan oleh banyak seniman (khususnya yang fleksibel). Jika Slamet Gundono mengatakan, “pentas ini termasuk apa? Tradisional atau kontemporer? Jika kontemporer, kok pengrawitnya masih pada duduk bersila semua; kalau dikatakan tradisional, kok…” Melihat suatu pertunjukan, asal menarik dan enak, kebanyakan orang cukup akan menilai dengan satu kata saja, bagus atau jelek. Pada kasus ini, penonton yang nonapresiatif akan menarik kesimpulan bahwa apa yang mereka lihat mampu membawa aura keasyikan yang membahagiakan, dan cukup sampai di situ. Tidaklah mudah bagi para pengkaji-pengkaji seni yang “menawar dahulu baru menilai”. Sangat membingungkan memang. Apabila kata kebanyakan penonton itu adalah pertunjukan bagus, bisa jadi sebaliknya bagi kritikus, ia bisa “mencela” dan mengatakan pertunjukan itu tidak ada “garam”nya sama sekali. Oh, ini tentu sangat kontradiktif. Siapa yang tidak menghendaki suatu pertunjukan yang digelar oleh seniman bisa dinikmati publik luas? Semua saya kira menghendaki. Kritikus menilai “salah betulnya” pertunjukan, atau hanya “ngikut” apa kata penonton? Bagus ya ngikut bagus; jelek ya ngikut jelek; biasa saja ya ngikut biasa saja; atau bagaimana? Tawar menawar berbagai kesimpulan yang diungkapkan oleh semua penikmat seni—baik penonton maupun kritikus — adalah gejala fenomena dinamisme budaya di dalam masyarakat dalam mengapresiasi keseniannya. Boleh saja berkehendak sesuka hati dalam memvonis suatu pertunjukan SMS: Short Music Service 168 yang ditontonnya, asal punya alasan kuat dalam berargumen, semua akan selesai. Penonton tidak bisa dengan mudahnya di-cap harus patuh terhadap gejala kebaruan yang muncul! Justru karena rasa-rasa “pop” yang masih melekat di benak kebanyakan orang, pertunjukan Dedek malam itu menjadi suatu “rasa” yang khas untuk dikagumi kebanyakan orang. Do mi sol do mi sol, dalam harmoni dua suara; parodi gaya Tegal Slamet Gundono yang unggul; bonang yang diangkatangkat; tata artistik yang unik (hanya bermodalkan daun pisang); serta kolaborasi dengan performa tari Eko Supriyanto yang cukup memiliki bobot, menjadi bagian penting dari sisisisi pengolahan kompositoris Dedek tatkala menggarap “Demonya Si Tukang Bonang”. Seperti yang diungkapkan I Wayan Sadra, Dedek mendekati gamelan dengan sikap yang lebih mengkini. Bicara tentang kar ya Dedek , barangkali tidak relevan membandingkannya dengan karawitan tradisi. Namun, sebagai wacana untuk mengungkap tentang fakta genetika kelahiran suatu karya baru, rasanya masih tetap perlu. Dedek bukan seorang seniman penjaga tradisi yang patuh. Banyak sekali gejolak-gejolak yang muncul ketika dihadapkan pada fenomena ketidak patuhan seniman terhadap tradisi. Bagaimanakah seniman menghadapi fakta yang sudah banyak dilirik orang ini? Persepsi atas ragam bentuk kemandirian suatu karya otonom yang tidak patuh pada tradisi memang akan membimbing seniman untuk berupaya bereksplorasi sekehendaknya, tetapi bukan semuanya. Apa yang dilakukan Dedek sudah tergolong cukup baik dan sempurna dalam penelusuran jejak-jejak eksplorasi kompositoris. Buktinya, apa yang dipentaskan Dedek, terlepas dari muatan kualitatifnya, sungguh mampu memikat banyak SMS: Short Music Service 169 orang. Semua orang berkunjung hanya untuk menyaksikan karya Dedek. Kata Dedek, “Kalau ingin masuk surga, belajarlah gamelan.” Solo, 4 Agustus 2005 Dari Sarasehan ‘Jalin Bapilin’: Hari Gini Ngomongin Tradisi Catatan: esai berikut ini tidak secara khusus bicara mengenai musik. Namun, musik juga sebagai tradisi yang menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Atas pertimbangan tersebut, esai ini turut disertakan di buku ini. J udul di atas adalah tema yang diangkat oleh Forum Mahasiswa Minang ISI Yogyakarta (FORMISI) ketika menyelenggarakan sarasehan di Benteng Vredeburg Yogyakarta (Selasa, 16 Mei 2006). Hadir tiga pemakalah: Prof. Dr. Sjafri Sairin, Mamannoor dan Djohan Salim, dengan dipandu moderator Risman Marah dan Raudal Tanjung Banua. Selama 4 jam penuh pembicaraan seputar tradisi mengalir begitu saja di dalam ruangan peninggalan Belanda berkapasitas sekitar 100-an orang itu. Tema tentang tradisi, apalagi dengan judul gaul gaya Jakarta: “Hari Gini Ngomongin Tradisi?”, memang sangat menggelitik dan menarik. Kursi yang disediakan panitia penuh tak bersisa kecuali barisan SMS: Short Music Service 172 paling depan. Suasana memang begitu cair, hal ini disebabkan karena masing-masing pemakalah mempunyai gaya bahasa, pengungkapan, mimik, serta trik yang cerdas dan segar dalam menyampaikan pembahasan; sangat terasa tidak menjemukan. Berbeda dengan seminar atau diskusi, dalam sarasehan ini suasana terasa lebih rileks. Tidak ada kemungkinan yang valid untuk berusaha memecahkan persoalan dengan teori-teori tentang tradisi yang beredar. Persoalan tradisi memang sebaiknya tidak untuk dibicarakan apalagi dipersoalkan. Tradisi adalah hasil dari kebudayaan yang sedang dan terus berjalan di semua lini kehidupan masyarakat; tradisi adalah kebiasaan yang turuntemurun. Tidak akan ditemui rumusan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan (makna) tradisi, meski ribuan kamus mendefinisikannya. Hingga kini, pemaknaan atas kata 'tradisi' menjadi sedemikian luas, apalagi di tanah air yang amat plural ini, yang hampir semua kebudayaan kita adalah hasil dari asimilasi maupun akulturasi. Negeri Cina, India dan Arab selama ribuan tahun mempengaruhi bahkan mewarnai kelahiran kebudayaan kita. Jika Rene Girard, dalam buku 'Kambing Hitam' tulisan Sindhunata, bilang bahwa differensiasi (keberagaman: pluralitas) justru mampu menghasilkan pandangan hidup yang cerdas, maka demikian pula di Indonesia, kata tradisi harus dimaknai sebagai buah kultur dan budaya yang bisa melahirkan gagasan dan pemikiran yang lebih baik, bukan untuk saling dipertentangkan. Menurut Mamannoor, yang ketika itu berbicara tentang (tradisi) seni rupa, membedakan dua terminologi penting mengenai tradisi, (1) Tradisi Seni Rupa; (2) Seni Rupa SMS: Short Music Service 173 Tradisional. Penggunan istilah tradisi dalam seni rupa, apabila ditempatkan sebagai awal istilah (baca: Tradisi Seni Rupa, bukan Seni Rupa Tradisi), maka dapat dipahami sebagai kebiasaan (adat) dasar yang umum di dalam perilaku berseni rupa. Tradisi seni rupa membangun sikap, konsep, bentuk dan orientasinya. Demikianlah yang terungkap dalam makalah tulisan Mamannoor. Dengan slide, Mamannoor mencontohkan berbagai karya seni rupa banyak negara (khususnya Asia) yang mencirikan tradisi menurut pandangannya. Bagi Mamannoor, yang tidak setuju atas pernyataan 'pencarian identitas' (karena kita sudah punya identitas), menjelaskan dengan argumen yang didasarkan atas kebudayaan Indonesia yang tidak original. Dalam ceritanya mengenai pengalaman berdiskusi tentang tradisi di Palembang, ia memberikan penegasan bahwa tradisi (baca: identitas) kita itu adalah 'turunan' bangsa lain. Bisa jadi, tradisi dari bangsa lain itu berasal dari bangsa yang lain lagi. Dengan demikian, kata original amatlah berat jika diungkapkan di Indonesia ini, yang menurut Mamannoor sangatlah bersifat indo (baca: campuran). Seniman, dalam konteks kekaryaan, menurutnya tidak perlu repot-repot mencari identitas. Hal ini dikuatkan pula oleh Djohan Salim (sebagai pembicara kedua) yang amat meyakini, bahwa dalam psikologi, usia 0 5 tahun adalah bawaan kultur (memori paten) yang akan dipegang manusia selama menjalankan kebudayaan. Untuk pernyataan ini, Sigmund Freud (tokoh psikoanalisis) juga menegaskan, bahwa 'jati diri' (sifat, karakter, watak) manusia akan berhenti sampai usia 5 tahun, selanjutnya adalah pengulangan-pengulangan saja, begitu seterusnya. Djohan amat mempercayai bahwa manusia, notebene kita, mempunyai tradisi 'bawaan' yang selalu kita bawa untuk 'membahagiakan' diri kita, meskipun di SMS: Short Music Service 174 depan mata kita selalu menemui banyak differensiasi tradisi. Artinya, Djohan tidak mempersoalkan hal tersebut (tradisi), namun menghargainya sebagai suatu kehidupan yang terus move, yang dimaknai dengan modal strategi, bahwa manusia harus mensikapi sesuatu yang sedang berjalan dengan terus belajar. Djohan, sebagai orang Palembang yang sudah duapuluhan tahun tinggal di Yogyakarta, bisa berkomunikasi memakai bahasa Jawa dengan Risman Marah yang juga trah Sumatra. Namun, bagi Djohan, alangkah membahagiakan apabila keduanya berkomunikasi dengan dialek Sumatra meski sama-sama di Yogyakarta. Djohan juga memberi contoh slide foto-foto seni tradisi dari berbagai daerah di Indonesia yang amat menarik dan memberikan penjelasan yang cenderung singkat dan tidak bertele-tele. Djohan mengungkapkan pula, bahwa tradisi di jaman ini sering dioposisi binerkan dengan kata 'modern'. Mengapa anak muda jaman sekarang lebih menyukai seni modern (band) dari pada kesenian tradisi? Jawaban ini terlalu kompleks. Globalisasi juga memunculkan 'kebudayaan voyeristik', bagi St. Sunardi merupakan kebiasaan (tradisi) hidup yang dikuasai tontonan dengan 'ritme' yang amat cepat. Dalam sarasehan yang riuh dan 'cair' oleh gurauan moderator (Risman Marah) itu, salah seorang peserta berkata, 'bahwa dalam masa sekarang, korupsi pun sudah menjadi tradisi'. Dengan demikian, persoalan tradisi tidak hanya berada dalam wilayah manusia (antropologi), sosial, geografis, namun juga sampai ke politik, apalagi kehidupan sehari-hari saat bangun tidur sampai mau tidur; semua adalah tradisi. Tradisi 'keterlambatan berkencan' juga selalu dipunyai Indonesia. Janji jam 7 datangnya jam 8 itu biasa: jam karet. Itu SMS: Short Music Service 175 tradisi (kebiasaan). Meskipun dalam kesempatan sarasehan tersebut hampir secara keseluruhan pembicaraan berkutat di wilayah kesenian, namun mestinya, kata tradisi dimaknai sebagai hal yang menjangkau berbagai aspek. Prof. Dr. Syafri Sairin, yang pada waktu itu berbicara mengenai sejarah dan budaya Minangkabau dengan amat kompleks, menulis dan menegaskan bahwa gejala yang ada di masyarakat Minang saat ini, harus disikapi masyarakatnya dengan menempatkan diri pada posisi yang berbeda-beda tetapi tidak berbenturan dan malah saling mengisi dan tunjang menunjang antara satu sama lain. Dengan sikap terbuka dan lapang dada, orang Minang akan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Tidak semua hal-ikhwal tentang tradisi bisa tersentuh dan terpecahkan dalam sarasehan itu meski feedback dari peserta amatlah berlangsung kondusif dan meriah. Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil selain mensikapi tradisi sebagai sesuatu yang berjalan dalam kebudayaan masyarakat; sesuai kebutuhan masyarakat. Memperjuangkan, mengembangkan ataupun memelihara tradisi sangat tergantung pilihan. Aneh, Musik Serius Jadi Guyonan! S ebuah kesalahan besar ketika sesuatu yang serius justru menjadi obyek humor yang kampungan. Pelawak Asmuni, Timbul atau Doyok akan merasa bangga jika dapat memberikan penghiburan kepada publik karena memang porsinya sebagai pelawak, itu jelas pada tempatnya. Welcome Concert 2006, sebuah tradisi tahunan di lingkungan Jurusan Musik ISI Yogyakarya, yang sebetulnya adalah momen musikal untuk membangunan 'image' konseristik menjadi terkesan kacau balau karena ulah beberapa penonton yang (terkesan) kampungan. Kultur Tertawa PSM (Paduan Suara Mahasiswa) ISI Yogyakarta adalah sebuah kelompok baru yang berusaha 'babat alas' untuk urusan musik vokal di Yogyakarta. Kehadirannya pada malam itu kok justru menjadi guyonan yang tidak pada tempatnya (?). Kuping penonton 'serius' menjadi merah karena beberapa SMS: Short Music Service 178 penonton kategori 'pecinta humor' selalu menganggap 'sesuatu' yang terjadi di stage (performer maupun crew) pantas untuk jadi obyek tertawaan. Ketika sudah bisa membuat tawa di antara ratusan orang di gedung pertunjukan, seolah-olah ada kebanggaan tersendiri. Sangat ironis! Apa yang mengkondisikan hal seperti ini? Pada wilayah penonton, yang duduk di tribun, tangga, maupun kursi, sepenuhnya adalah audience yang berposisi sebagai penikmat musik. Mereka, para penonton itu, tidak berhak apaapa selain menyimak apa yang menjadi tontonan, bertepuk tangan atau memberikan standing ovation sekadar rasa penghargaan kepada performer. Selain itu, saat jeda pun, mereka berhak diam sambil menunggu pergantian lagu. Penonton dirasa tidak berhak berceloteh karena sangat mengganggu konsentrasi audience dalam wilayah yang lebih komunal ketika mencoba khusyu dalam ruang dengar musikal. Apalagi untuk urusan pertunjukan musik serius (klasik), ketenangan selama pertunjukan lebih diutamakan. Mobilitas di atas stage (yang dilakukan crew saat setting) adalah kerja yang butuh waktu cepat, cekatan dan penuh konsentrasi. Yang terjadi, ternyata stage crew justru menjadi obyek guyonan! Rasa penghargaan kepada crew maupun performer menjadi sesuatu yang rasanya kok haram untuk dilakukan. Sebagian penonton sepertinya memilih bergaya kampungan, ala penonton band-bandnan di lapangan balbalan. Padahal ini pertunjukan musik serius!? Astaga, kok jadi begini... Ideal Beberapa kali dalam ruang pertunjukan live musik humor SMS: Short Music Service 179 Team-Lo, Pecas Ndahe atau Sri Redjeki, saya selalu dibuat terpingkal-pingkal. Pada satu sisi, penonton yang hadir untuk menontonnya memang berharap akan hadirnya tawa, bukan sekadar diam menyimak dan bertepuk tangan. Ada beberapa sinergi yang kait-mengkait untuk menghasilkan tujuan ke arah penikmatan akan sesuatu yang ditampilkan; penikmatan akan penghiburan yang ber-esensi lawakan, mengangkat derajat tawa hingga punya makna. Itu jelas pada porsinya. Tawa memang bukan sesuatu yang ketat, pada saat tertentu (mungkin) tawa harus ada. Sebuah contoh, Ananda Sukarlan, dalam resital yang saya saksikan beberapa waktu yang lalu, seringkali sengaja membuat penonton ketawa, penonton pun tertawa karena Ananda. Ia mencoba menciptakan suasana humor dengan gayanya yang khas untuk sekadar menetralisir ketegangan penonton pada saat tertentu. Maklum, beberapa lagu yang dibawakan Ananda termasuk lagu dengan teknik permainan yang sangat tinggi, amat berat. Hadirnya Ananda, dengan strateginya untuk menciptakan humor di hadapan penonton, menjadi sesuatu yang lumrah. Setelah merasa siap bermain kembali, Ananda menghentikan humor itu. Ketika lagu selesai, standing ovation dari penonton dalam waktu yang cukup lama menandakan bahwa audience memberi penghargaan untuk Ananda, untuk perjuangannya sebagai penafsir musik, dan yang paling penting adalah penghargaan terhadap nilai-nilai seni. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, menjadi kesalahan besar yang pantas mendapat kritik tajam tatkala sesuatu yang serius di atas pentas justru menjadi sebuah obyek guyonan yang tak masuk akal. Crew dan Performer yang susah payah membangun SMS: Short Music Service 180 kaidah pertunjukan musik agar menjadi sesuatu yang lebih bernilai, malah menjadi obyek tertawaan yang kampungan. Sekali lagi tidak masuk akal. Rieko Suzuki: “Tak Cukup Memahami Notasi” P ada tanggal 11 s.d. 13 September 2007 di Yogyakarta berlangsung sebuah hajatan musik tahunan bertajuk Yogyakarta Contemporary Music Festival 2007 (YCMF). Hadir sebagai pemusik tamu dalam event tersebut pemain biola cantik dari Jepang, Rieko Suzuki. Ia menyajikan performa yang luar biasa. YCMF adalah kemasan acara musik yang menampilkan komposisi-komposisi baru yang diciptakan kisaran paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21. Banyak komponis ambil bagian dalam acara ini, terutama komponis-komponis muda dari Yogyakarta dan Jakarta yang lahir sesudah dekade 1970-an. Acara tersebut berlangsung di tiga tempat terpisah: Teater Arena ISI Yogyakarta (workshop), Benteng Vredeburg dan Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta (diskusi dan konser). Acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Musik ISI Yogyakarta dan Independent Composers Community Yogyakarta (ICCY) ini SMS: Short Music Service 182 berlangsung sukses dan dihadiri ratusan penikmat. Meski pementasan musik kontemporer tergolong belum terbiasa di telinga awam, namun, bukan berar ti keberadaannya menjadi tidak penting. Berbagai suguhan yang ditampilkan cukup memberi angin segar apresiasi baru terhadap berbagai kalangan. Rieko Suzuki, pemain biola lulusan Toho Gakuen School of Music Tokyo ini bermain dua komposisi solo di hari pertama pementasan, Koningliches Theme karya Isang Yun (19171995) dari Korea dan Perspectives karya Toshi Ichiyanagi (Jepang). Sebelumnya, Rieko Suzuki juga memberi workshop bagi performers yang akan tampil di YCMF dan responnya mengenai para peserta sangat baik. “Mereka begitu luar biasa, mereka mengerti, dan benar-benar memberikan kemajuan.”, begitulah kesan Rieko. Karena banyak sekali teknik permainan baru dalam karyakarya baru, interpretasi atas musik tersebut juga menjadi lain dari yang pernah ada, yang menjadi standar pada umumnya. Secara keseluruhan, yang kontemporer dalam pengertian ini (belum) tentu terasa aneh seperti anggapan orang pada umumnya. Justru, Rieko Suzuki bermain sangat konvensional. Ketika saya menemui Rieko Suzuki seusai pentas dan bertanya mengenai bagaimana proses dia bermain karya baru, jawabannya yang ramah adalah demikian, “tentu pada dasarnya saya harus menguasai komposisinya terlebih dahulu, mulai dari nada, ritme, tempo, dll. Saya harus menemukan keinginan komponis atas karyanya. Seperti contoh, Yuji Takahashi menginginkan percampuran tempo dan pergantian karakter, Mamoru Fujieda menginginkan sebuah karya yang begitu tenang dan menggambarkan mengenai alam. Tidak hanya sekadar memahami notasinya saja, namun juga keinginan dari komponisnya.” Oleh SMS: Short Music Service 183 karenanya, sebelum bermain musik, ia selalu menjelaskan konsep-konsep yang terkandung dalam karya dan ini menjadi salah satu ketrampilan yang mutlak dipunyai pemain musik. Selain ketrampilan psikomotorik, pemusik juga harus mampu menyampaikan secara verbal mengenai apa yang ada di balik karya musik. Dari sini nampak, bahwa ada hubungan yang begitu dekat (personal) antara komponis dan pemusik. Keinginan komponis menjadi faktor yang utama. Hal tersebut tidak akan ditemui ketika bermain karya-karya lama yang diciptakan oleh maha-komponis yang telah wafat semacam Bach, Mozart, Rossini, Wagner, dll, karena pemain musik belum tentu bisa dengan cerdik dan tepat menafsir apa yang dikehendaki komponis, selain cuma mentaati bahasa ekspresi yang tertulis di partitur. Oleh sebab itu, seringkali, konduktor orkestra satu dengan yang lain akan mempunyai cara tafsir yang berbeda meskipun bermain karya yang sama. Dari pengalamannya bermain di banyak orkestra di Jepang dan negara lain, Rieko Suzuki menjadi pemusik yang terasah dan tenang menghadapi 'medan tempur' apa pun. Ia misalnya, pernah tampil sebagai concert missters di Malmo Opera Theatre Orchestra di Swedia dan New Japan Philharmonic Orchestra. Ia juga telah mengunjungi negara seperti Perancis, USA, Selandia Baru, Thailand, dan tentu Indonesia. Rieko Suzuki adalah seorang pemain biola berbakat yang tidak hanya bermain karya klasik tetapi juga bermain musik tradisional Jepang, soundtrack, pop standar, etnik dan musik terapi. Rieko Suzuki juga telah merilis beberapa album, antara lain: Vivaldi's The Four Seasons bersama Czech Philharmonic Chamber Orchestra (1996), Solo CD Rave d'une nuit de'te (1999), dan satu album yang sangat penting yaitu From the SMS: Short Music Service 184 Orient (2002), yang menggabungkan secara apik gaya Barat dan Timur (oriental). Di tahun 2005, Rieko Suzuki juga merekam violin concerto karya Stephen Melillo. Yang terakhir, 2006 ia merilis album solo Winter Garden yang berkonsep musik sinema karya komponis Joe Hisaishi. Bulan Mei 2007 silam dia memainkan karya Jack Body untuk violin solo di di Minatomirai Hall Jepang dan mendapat sambutan meriah. Sementara di hari kedua, Rieko Suzuki berduet dengan Ike Kusumawati (piano), memainkan Distance de Fee karya Toru Takemitsu (19301996) dan Nobara karya Kosçaku Yamada (18861965), keduanya adalah komponis dari Jepang. Dua karya tersebut hadir cukup sempurna dan menghangatkan suasana di ruang dingin Auditorium Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta. Meskipun ada sedikit ke-tidakbiasa-an dalam mencerna karya baru bagi awam, namun, justru di sinilah publik diminta terbuka untuk mengapresiasi karyakarya baru yang muncul dan mewarnai perjalanan sejarah musik mutakhir. Meskipun pada umumnya, yang hadir pada acara tersebut adalah penikmat yang telah cukup mengerti atau setidaknya pernah mendengar musik klasik. Pada kesempatan terakhir, Rieko Suzuki bermain tiga karya berturut-turut: Patters of Planets karya Mamoru Fujeida (Jepang), Aeolian Harp karya Jack Body (New Zealand) dan terakhir Vom Erde voller Kaltem Wind karya Yuji Takahashi (Jepang). Secara umum, performa yang ditampilkan Rieko Suzuki berhasil dengan baik. Ia bermain dengan berbagai kecermatan artikulasi, kemurnian ekspresi, dan ketenangan dalam membawakan karya sulit sekalipun, membuat applaus penonton tak kunjung berhenti di akhir acara. Encore yang ditampilkan Rieko Suzuki cuma dua kata, “thank you, terima SMS: Short Music Service 185 kasih”. Penonton pun tertawa dan sebenarnya agak kecewa karena encore dalam pengertian sesungguhnya tidak hadir, agaknya Rieko sudah terlalu capek. Secara umum, visi YCMF, seperti yang disampaikan Michael Asmara (ketua penyelenggara) adalah, “bahwa peristiwa ini diharapkan dapat menjadi barometer perkembangan dunia musik yang mutakhir, terutama mengenai isu-isu yang berkembang saat ini, baik mengenai teknik, gaya, estetika, maupun ideologi dalam perspektif kebudayaan secara global.” Sekadar informasi, bahwa nama-nama komponis yang menyajikan karya dalam YCMF kali ketiga ini adalah komponiskomponis dari Asia Pasifik dan Amerika. Mereka antara lain: Toshi Ichiyanagi, Yuji Takahasi, Joji Yuasa, Mamoru Fujieda, Toru Takemitsu, Koscaku Yamada (Jepang), Jack Body, Lisa Eui-Yeon Kim, Ross James Carey, Ross Harris (New Zealand), Tony Maryana, Veritha S. Koapaha, Diwani Indraningsri, Gatot D. Sulistiyanto, Gozaldi NM, Abdul Rosyid Al Karomi, Patrick G. Hartono, Dian Permana (Indonesia), Alex Dea (USA), dan Kam Kee Young (Malaysia). Musik-musik yang termasuk kategori baru memang harus selalu dikampanyekan. Kreativitas-kreativitas baru yang muncul dari komponis era sekarang akan menjadi petanda bahwa kekaryaan art music, adalah juga sebagai perjalanan sejarah musik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk mengapresiasinya dibutuhkan keterbukaan bagi masyarakat. “Saya sangat terkesan dan bangga dengan festival ini. Di Jepang sendiri tidak mudah lho mengadakan festival musik seperti ini. Saya juga bangga terhadap para komponis dan para musisi muda berbakat pada festival kali ini.”, demikianlah ucap Rieko Suzuki ketika ditanya komentar SMS: Short Music Service 186 mengenai YCMF 2007. Bravo Rieko Suzuki dalam Spectrum, between sound and silence... Yogyakarta, 20 Sept. 2007 Sekali Klik Dengar Musik Fakta Mau tidak mau, sekarang kita dihadapkan pada kepungan musik (komersial) yang hadirnya nyaris tanpa sekat, di ruang manapun, kapanpun. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi baru, semacam ponsel (dengan fasilitas musik) atau MP 4, anytime anywhere orang bisa mendengar musik. Bahkan di toilet sekalipun. Pada umumnya, musik hanya menjadi pelengkap di tengah rutinitas kerja yang padat. Taruhlah misal, saat pekerjapekerja proyek bangunan lelah di siang bolong, mereka rolasan (makan siang) sambil dengar musik di radio. Para remaja yang doyan ke mall selalu tidak lepas dari ponsel dan headphone—sambil jalan-jalan lihat kiri kanan musik tetap berdengung di telinga. Pagi, siang, sore, malam, dini hari, musik mengepung telinga lewat radio atau televisi. Munculnya berbagai kemajuan teknologi media yang menyediakan fasilitas dengar musik membuat masyarakat menjadi SMS: Short Music Service 188 termudahkan, tidak perlu repot tidak perlu susah-susah. Intinya, sekali klik dengar musik. Musik = Logika Dagang Barangkali, tidak semua musik layak dikonsumsi, seperti halnya tidak semua makanan layak dimakan. Ada yang sudah kadaluarsa, mengandung pengawet, menggunakan bahan kimia yang tidak menyehatkan, dll. Logika para pelaku di balik industri musik adalah kepiawaian membentuk citra bagi pendengar agar menjadi mudah lekat dalam sekejap. Misalkan, kita bisa belajar dari kepopuleran lagu Peterpan Ada Apa Denganmu kala itu. Semua usia bernyanyi. Muncul versi dangdutnya, ganti gaya, ganti suasana. Tua muda anakanak tetap menyanyi. Belakangan, lagu Ketahuan yang dipopulerkan Matta Band membius semua kalangan. Masyarakat percaya ini 'keajaiban'. Dewi Persik lantas bernyanyi versi ndangdut-nya. Ternyata justru lebih menarik dari aslinya. Ada semacam tak-tik yang sungguh misterius dibalik games-nya orang-orang media itu. Ini sangat sulit dimengerti. Anak-anak zaman sekarang tidak dekat lagi dengan lagulagu karangan AT Mahmud, Pak Kasur, Ibu Sud atau Papa T. Bob. Industri musik seolah menjadi bias dalam hal ini. Pengertian, kepentingan dan kebutuhan menjadi berbalik. Orang tua justru bangga mendengar anaknya yang masih kecil bernyanyi: “kamu ketahuan...pacaran lagi...”, padahal lirik tersebut jelas-jelas jauh dari dunia anak-anak. Tetapi jika ini menyenangkan dan bikin anak makin pintar, kenapa tidak? Masalah Pertanyaannya kemudian, lalu musik apa yang layak SMS: Short Music Service 189 dikonsumsi di zaman sekarang? Apakah harus ada aturan ideal? Misalnya, kita harus dengar lagu yang sama berapa kali sehari? Apa batasan-batasan agar kepungan musik tidak semakin menjerumuskan kita dalam superstar syndrom, pengidolaan, keterlenaan, yang sejatinya tidak semakin membentuk pribadi yang matang, namun malah menjerumuskan dalam sintesa-sintesa jiwa yang tidak lagi tangguh. Logika industri merakit garis “biusan” pola konsumsi dan manfaat ketika orang melihat sesuatu (barang), maka ia berniat membeli. Musik, dalam logika industri, bukan menjadi musik lagi dalam pengertian sebenarnya. Musik telah menjadi barang dagangan, bukan sarana mencapai kenikmatan spiritual atau pemahaman inderawi yang diresapi sungguhsungguh. Oleh sebab itu, dalam logika industri, musik tidak beda dengan kripik singkong, teh botol, minuman suplemen, atau apa pun produk lain. Dijual, dibeli, dimakan, selesai. Apabila dalam sehari kita mendengar musik yang sama 12 kali tanpa penghayatan (dan pemahaman) apa-apa, maka logikanya akan sama seperti kita meminum minuman suplemen 12 botol sehari tanpa tahu bahayanya. Ini memabukkan dan tidak baik. Musik yang layak dikonsumsi adalah yang sesuai dengan realitas kehidupan, tidak mengada-ada dan sejatinya ia harus bermanfaat lahir batin. Dalam istilah yang populer, ini disebut edutainment, menghibur sekaligus mendidik. Sementara yang terjadi di Indonesia, nyaris 90% musik industri itu menghibur, dan kurang mendidik. Jadinya, daya pikir remaja bangsa ini menjadi kian lemah dari hari ke hari. Apa yang diinginkan oleh para “mafia-mafia” industri musik seringkali berseberangan dengan niat tulus masyarakatnya ketika SMS: Short Music Service 190 mendengarkan musik. Jadi, masyarakat seringkali bagai kejatuhan “bencana” begitu saja. Tidak ada hal lain selain pengecapan indera dengar yang kita perjuangkan ketika menikmati musik. Para artis hadir sejatinya juga bukan untuk diidolakan. Mereka hanya mediator penyampai musik. Kita tidak boleh terpana begitu saja dalam histeria massa. Kita dan artis punya derajat yang sama: sebagai manusia. Oleh sebab itu mereka tidak selayaknya dipuja dan diagung-agungkan. Sekadar suka boleh tetapi jangan sampai terlena. Ini juga akan berbahaya, sama seperti ketagihan narkoba. Filsuf TW Adorno dalam buku Philosophy of Modern Music (1973) membagi 8 jenis pendengar musik: 1. ahli, 2. pendengar yang baik, 3. konsumen budaya, 4. pendengar emosional, 5. tidak dapat diam, 6. penggembira, 7. pendengar hiburan, 8. pendengar tidak musikal. Dalam konteks Indonesia, nyaris semua remaja agaknya menduduki posisi sebagai pendengar hiburan (7). Menurut Adorno, pendengar hiburan adalah sebagai obyek budaya industri. Jarang sekali ditemui pendengar nomer 2 atau pendengar yang baik. Bagi Adorno, pendengar yang baik itu bisa mendengar dengan detil dan mengambil keputusan logis atas musik yang didengar. Bisa bercerita dengan tidak hanya mengagung-agungkan perasaan saja. Kira-kira begitu. Solusi Selektif Maka dari itu, yang diperlukan sekarang adalah sikap selektif memilih bunyi (musik) seperti halnya sikap selektif kita memilih sayuran ketika di pasar. Yang tidak sehat atau basi pasti kita singkirkan. Kita harus membiasakan diri mencermati musik yang didengar dengan sikap yang tidak SMS: Short Music Service 191 terlampau emosional namun penuh kehati-hatian. Bukan berarti menjadikan kita tidak bebas karenanya. Ekspresi — secara psikologis sebagai faktor kejiwaan—tetap menjadi pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung dari musik. Ingat maksud semula, bahwa musik bertujuan membuat manusia lebih manusiawi karena musik menghubungkan kita dengan cita-rasa, dimensi perasaan, dan musik hadir sebagai stimulan guna merangsang tumbuhnya kreatifitas sebuah hal positif yang makin mahal harganya di abad ini. Semuanya tetap kembali pada manusia, bukan manusia yang berkiblat pada teknologi dunia citra, jika tidak ingin menjemput bahaya perubahan zaman di masa depan. Karya Baru Musik Keroncong S ementara ini, khususnya di Jawa Tengah, menurut praktisi dan provokator keroncong, Imoeng CR, kehidupan keroncong cukup membawa kesegaran baru dengan banyak munculnya generasi muda yang memainkan musik ini. Hal ini dapat dilihat dari peran serta generasi muda tatkala mengikuti berbagai Festival Musik Keroncong yang diadakan oleh berbagai daerah, misalnya di Yogyakarta, Solo, Ungaran, Purbalingga, dll, yang ramai beberapa tahun terakhir. Tidak benar jika ada pendapat bahwa keroncong milik orang tua saja. Pernyataan itu harus segera dihapuskan jika ingin musik ini berkembang. Seiring perkembangan zaman, dengan segala variasinya yang kompleks, musik keroncong pun berkembang secara dinamis. Dengan pola penggarapan (aransemen) yang baru, serta mengikut-sertakan, misalnya, instrumen orkestra ke dalam penggarapannya. Meskipun ini menjadi sesuatu yang kontroversial, namun justru pemikiran kreatif inilah yang membawa keroncong mampu bertahan di SMS: Short Music Service 194 tengah arus industri musik pop yang sesak dan padat. Sebetulnya, penggunaan orkestra sebagai elemen ke dalam aransemen musik keroncong sudah ada sejak dekade 1950-an ketika di Solo muncul kelompuk Radio Orkes Surakarta (Radio Republik Indonesia). Kelompok tersebut merekam beberapa lagu keroncong asli dengan format “keroncong orkestra”. Namun, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki penata musik yang bekerja di balik layar, menjadikan beberapa karya itu kurang menarik. Lalu, barubaru ini, di Yogyakarta misalnya, muncul 'gerakan' baru yang dipelopori Singgih Sanjaya dengan Light Keroncong Orchestra, yang memadukan keroncong dengan orkestra secara lebih menarik dan segar. Selain latar belakang Singgih sebagai seniman keroncong dan Arranger berbakat yang dimiliki negeri ini, peran serta pendukung musik ini turut membawa keroncong naik ke permukaan dengan pemaknaan yang lebih kreatif. Yang menjadi permasalahan adalah justru pada produktifitas kekaryaan baru, yang ternyata terputus lebih dari empat generasi, sejak tahun 1980-an. Berbeda dengan musik rakyat lain, semisal campur sari, yang populer dan banyak digemari masyarakat, yang selalu ada lagu-lagu baru. Kekaryaan lagu-lagu keroncong dari penggubah baru kurang mendapat perhatian untuk dipublikasikan. Singkatnya, banyak grup keroncong masih memainkan karya-karya lama yang diciptakan oleh maha-seniman Ismail Marzuki, Kusbini, Gesang, Ismanto, R. Maladi, WS Nardi, Sapari, S. Dharmanto, dibanding karya baru ciptaan seniman baru. Hal ini menyebabkan perkembangan keroncong justru berjalan statis, karena para praktisi hanya mengabdi sejarah, tanpa kreatif dan memaknai sejarah dengan karya-karya baru. SMS: Short Music Service 195 Kalau cuma aransemen saja yang diperbaharui, sama seperti kita bersolek untuk lebih tampan namun tidak peduli kecantikan rohani. Semenjak musik keroncong mulai banyak dikenal di penjuru negeri, yang pada mulanya, konon dibawa oleh para misionaris Portugis di Maluku pada abad ke-16, kini keroncong menempati suatu strata kebudayaan musik yang memiliki khasanah pendukung yang luas dan unik. Di banyak kota, terutama di Jawa, musik ini tampil sebagai klangenan (kumpul-kumpul menghibur) pada saat tertentu. Keroncong juga tampil sebagai hiburan dalam acara kerakyatan, maupun sebagai apresiasi positif di berbagai media. Berkarya adalah parameter eksistensi seniman. Oleh sebab itu, titik berangkat yang harus dipahami oleh para praktisi keroncong dan masyarakat pendukungnya, bukan cuma terletak pada: bagaimana melestarikan musik keroncong saja. Namun, hal ini juga harus didukung penciptaan karya-karya baru yang akan menambah perbendaharaan lagu keroncong. Para praktisi bisa merekamnya, memproduksinya, dan mempublikasikannya seperti laiknya di industri musik pop. Sehingga, musik ini dikenal lebih luas melalui karya baru dan pemaknaan yang lebih cerdas, bukan pada perjalanan yang mandeg dan statis. Solo, 8 Juli 2007 Disco-nya Kaum Spiritualis M usik bisa jadi merupakan persepsi dengar atau cuma pengecapan inderawi yang tak harus berujud (bunyi). Pada akhirnya, musik akan kembali ke dalam musik itu sendiri. Meski sebelumnya, 'teka-teki' peradaban sejarah musik, perkembangan gaya, genre, dan lain sebagainya selalu menjadi dinamika dari zaman ke zaman. Penikmatan akan musik, bagi orang yang merasa mendalami musik, adalah perjalanan hidup yang mengagumkan. Mengalami musik dan mengerti musik memang ua hal yang tak habis dipelajari. Tulisan ini sedikit berpendapat soal rumus mengalami dan mempelajari (mengerti), terlepas dari dengar musik apa dan untuk siapa musik diperdengarkan. Ini pun akan bersifat relatif. Mempelajari musik belum berarti mengalami musik. Mempelajari musik berada di kapasitas pemahaman verbalisme, semisal: berkutat pada wilayah bacaan, teknis, tanpa tujuan rasa yang ngeng, mat, dan nyaman. Tanpa sadar, SMS: Short Music Service 198 setelah berlatih musik (klasik) berjam-jam ternyata kita tidak mendapatkan sesuatu apa pun dan justru bertambah sebal karena tak kunjung menguasai apa yang kita pelajari. Setelah menguasai dan mendapatkan 'secuil' kepuasan ketika memainkannya ataupun memertunjukkan kepada publik— lantas sesudah dua bulan—partitur kita letakkan di meja begitu saja tanpa mau menyentuhnya lagi, apa jadinya? Pada saat kita mencoba memainkannya kembali tanpa notasi, mustahil kita akan mengingat semuanya dengan sempurna, pasti ada yang terlupakan meski hanya satu nada! Dalam wilayah ini kita seringkali dirong-rong habis-habisan oleh “mazhab verbal” (semacam notasi, simbol, dll yang sebetulnya adalah bahasa mati) yang harus ditaati penuh namun kita menisbikan (mengesampingkan) penikmatanpenikmatan batiniah (interpretasi) di balik bahasa verbal yang sebetulnya akan banyak kita dapati. Aaron Copland, dalam bukunya Music and Imagination, kurang lebih berkata demikian, “dalam seni musik, ciptaan dan interpretasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan” (1964:60). Ciptaan/kreativitas erat dengan interpretasi, dan sekaligus, suatu maksud penciptaan musik bersinergi dengan pikiranpikiran imajinatif. Tidak mungkin, dalam usaha menikmati musik, kita mematahkan interpretasi, penafsiran akan bahasa-bahasa terpendam yang disampaikan komponis, yang kadang-kadang tak cukup diketahui lewat simbol verbal berupa notasi. Pemain musik tidak hanya mematahkan kendala teknis di balik rentetan notasi, namun seorang pemain musik akan berusaha menghargai setiap detail persepsi menuju ke arah penikmatan akan musik. Keseimbangan keduanya, antara sisi hayat (seni) dan sisi paham (ilmu seni), akan membaca SMS: Short Music Service 199 suatu keistimewaan bagi pengalaman musik. Di sinilah seni benar-benar dialami sebagai koherensi yang utuh. Yogya, 2006 Bab III Retrospeksi Catatan: Bab 3 buku ini secara khusus berisi mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi di Jurusan Musik ISI Yogyakarta. Pemaparan yang disampaikan hanya bersifat faktual dan umum, bukan suatu penjelasan ilmiah. Hanya merupakan suatu pengamatan, terutama terhadap kondisi sosial dan belajar. Sekaligus, tulisan di bab ini juga merupakan retrospeksi, renungan dari sudut pandang penulis yang lahir atas pengalaman batin, pikiran, dan segala efek persinggungan belajar yang pernah terjadi selama 5 tahun (2002-2007), juga disampaikan beberapa oto-kritik. Tulisan ini merupakan studi kasus yang mencoba memberi wacana kepada siapa saja tidak hanya di lingkup internal Jurusan Musik. Informasi mengenai Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat dilihat di www.isi.ac.id Retrospeksi Prolog Ketika melangkah memasuki ruang baru bernama kampus, adakah yang lebih mengesankan kecuali fase perpindahan pola pikir gaya SMA (manja), kini mandiri? Adakah yang lebih “menegangkan” selain proses adaptasi terhadap gaya belajar yang baru, pola hubungan sosialkomunitas yang baru, serta tantangan hidup (berkesenian) yang baru? Karena kampus, cakrawala terbuka, bahwa dunia ini terasa semakin luas saja. Aku bagaikan piknik keliling Asia Eropa. Faktanya, lini kehidupan yang memungkinkan belajar lebih dewasa untuk saling melengkapi dan memberi kontribusi pengetahuan satu sama lain lahir dari kampus. Lewat pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam jeruji penjara yang tidak membebaskan pikiran maupun kreativitas. Sebaliknya, di kampus inilah SMS: Short Music Service 204 mahasiswa mencoba mempertaruhkan apa pun, bahkan nyawa, demi kesejahteraan mengangkat martabat manusia. Menjelajahi sisi kemanusiaan, mewarnai kehidupan dengan dimensi estetis-humanis. Tetapi, yang perlu dicermati, bahwa watak kampus seni akan sangat berbeda dari kampus-kampus lain. Gaya pengungkapan ide dari kampus seni bersifat unik, bukan politik. Bahkan, gaya pergaulannya pun akan terasa sangat berbeda. Dalam kampus seni banyak 'orang gila', nyeleneh, tapi ternyata cerdas dalam berpikir. Kampus seni lebih merupakan ruang pikiran kreativitas dan humanitas, yang sifatnya kolektif, relationship, manusiawi, sederhana dan tidak frontal. Ruang belajar kampus seni adalah ruang kekaryaan seni, meski belum sepenuhnya menjadi jaminan kesejahteraan hidup. Karya seni akan hidup jika ia menjadi bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu yang diperoleh di kampus masih merupakan sepenggal fase kecil yang tidak berarti apaapa jika tidak diterapkan. Ilmu harus dibuktikan di lapangan, di-implementasikan dengan jalan apresiasi kepada masyarakat luas. Di situlah kampus akan terbukti ikut mewarnai perkembangan pendidikan untuk turut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam usaha mencerdaskan bangsa. Mahasiswa adalah jantung kehidupan ilmu pengetahuan yang mewakili sifat kemandirian. Belajar mandiri, yaitu aktifitas perencanaan belajar (menentukan tujuan, target nilai atau strategi belajar yang akan dilakukan, menentukan waktu belajar yang sesuai dengan kegiatan lainnya) dilakukan secara mandiri. Mahasiswa tidak bisa ndompleng ngikut sana ngikut sini. Yang menjadi sari patinya adalah kekuatan dan SMS: Short Music Service 205 tekad untuk berbuat sesuatu dengan inisiatif dan inovatif, melakukan perubahan, menorehkan sejarah, mengubah lingkungan menjadi kondusif. Bahkan sampai membawa ilmunya ke meja percaturan tingkat internasional. Kampus pada sisi tertentu merupakan ruang belajar, meskipun pada konteks kesenian, seperti tadi telah disinggung, kampus tidak sepenuhnya menjadi ruang kreativitas. Maka dari itu, segala yang dicapai semasa studi haruslah diterapkan di lapangan, dalam konteks (realitas) yang lebih terbuka. Karena hal ini memungkinkan pertaruhan atas wacana, apresiasi, kritik, kehidupan menjadi dinamis, ada kemajuan. Mahasiswa menjadi tonggak sejarah, bahkan yang lebih penting, sejatinya ia manusia pemikir, yang tidak hanya duduk diam, santai, tenang, bercanda, nggosip, menggerutu dan mengeluh tanpa mencari solusi yang jelas atau melakukan koneksitas dengan lingkungan belajarnya ataupun masyarakat luas. Mahasiswa harus sanggup menjuntai satupersatu persoalan yang melilit di sekitarnya: problem diri, problem kampus, problem sosial sampai problem lokal-global, nasional-internasional. Jika gagal, pada akhirnya, mahasiswa yang putus asa memilih meninggalkan kampus secara sporadis, karena tidak betah atas segala kondisi yang menekannya. Untuk membaca persoalan dengan segala dinamika yang ada di kampus Jurusan Musik ISI Yogyakarta ini jelas dibutuhkan tenaga dan pikiran yang berlipat-lipat. Menghabiskan waktu untuk berdiskusi bersama teman-teman sekampus selalu dilakukan ratusan kali. Kamar. Kantin. Lobi. Burjo. Angkringan. Jalanan. Gedung konser. Sudah biasa. Tidak tidur sampai matahari terbit. Waktu menjadi terbalik. SMS: Short Music Service 206 Rokok dan kopi habis kami ngutang di warung dulu. Sangat biasa. Tidak lain, diskusi itu cuma ajang curhat untuk menyampaikan gagasan demi gagasan meraih solusi terbaik. Ruang kampus yang 24 jam ini akan memungkinkan mengoptimalkan tugas belajar mengenai banyak hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan, yang sifatnya angin lalu, terlewatkan begitu saja, tetapi ternyata justru itulah yang penting. Justru dari tongkrongan kecil itulah lahir pemikiran besar yang bisa mengubah sejarah. Inilah yang dinamakan filosofi tongkrongan. Oleh sebab itulah saya berniat menuliskan catatan-catatan ini menjadi buku. Tonggak Awal, Guyub dan Ajang Silaturahmi Sebuah makalah yang tidak begitu panjang ditulis oleh Drs. Yc. Budi Santosa, M.Hum (ketika itu Ketua Jurusan Musik). Tulisan ini diberi judul Menyimak Wawasan Kampus Jurusan Musik (Musyawarah Mahasiswa V). Pemikiran dalam tulisan itu adalah tonggak awal acuan pemikiran saya mengenai kampus. Gaya bahasa tutur dari Mbah Budi, begitulah sapaan akrabnya, amatlah sederhana, polos tetapi menarik. Dalam pendahuluan tulisan itu, ia mengungkap demikian, “dewasa ini, hampir sebagian besar di tengah kampuskampus, mencuat keprihatinan terutama menyempitnya wawasan kampus. Seminar-seminar, tulisan-tulisan, banyak yang mengungkapkan adanya krisis solidaritas, yang menjurus ke arah dis-integrasi atas tatanan kehidupan di kampus-kampus, di antaranya telah tampak adanya pergeseran nilai, salah satunya contoh adalah masalah SMS: Short Music Service 207 hubungan sosial antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan pegawai dan atau siklus kebalikannya, yang tampak dalam kiprahnya bersifat sekularisme, sektarian, primordial, dan sempit. Hal ini lamalama tentu akan mempengaruhi proses kebijakan dan sudah pasti akan mengarah merusak dan merapuhkan persatuan kesatuan di dalam kehidupan berkampus. Di dalam konteks kekaburan wawasan kampus tersebut, kiranya perlu untuk diatasi dengan pola gerakan baru, minimal perlunya penyadaran makna sejarah, yang perjalannya: [1] dimulai dari kelahiran kampus musik AMI Suryodiningratan (keteduhan kampus mampu merangsang semangat belajar, keakraban); [2] kemudian menuju kenyataan keberadaan yang lebih luas atau setelah integral di FSP ISI Yogyakarta (alat tak tambah, panas, loyo); [3] kemudian puncaknya adalah pada kesadaran wawasan kampus saat ini (demo, alat hilang, egoisme, cuek)”. Fakta yang dipaparkan adalah sekumpulan krisis-krisis yang menghantam tubuh kampus ini, sekaligus tulang-tulang pembentuknya. Perjalanan Jurusan Musik dari “gedung ke gedung” adalah penyadaran akan sejarah. Manusia yang unggul adalah manusia yang ingat akan sejarahnya, anak yang baik ingat jasa orang tuanya. Dengan begitu ia bisa belajar dari masa lalu sebagai bekal masa depan. Pada kenyataannya, ada semacam grafik menurun dari catatan tersebut. Yaitu, melemahnya solidaritas yang terbangun dari tahun ke tahun. Jika kini mahasiswa terbiasa cuek dengan lingkungan, egois, acuh tak acuh, individualisme semakin tinggi, ini tentu bukan tanpa sebab, barangkali mereka tidak sadar sejarah SMS: Short Music Service 208 dan tidak berusaha melakukan oto-kritik (kritik diri) secara kontinu. Seperti diketahui, kondisi sekarang memang berbeda dengan dulu ketika kampus ini masih berada di Suryodiningratan, yang konon dalam banyak perbincangan, dalam rekaman foto-foto, merupakan kampus yang nyaman, rindang, keguyuban terjaga baik, suasana belajar kondusif, jauh dari kebisingan, tidak seperti sekarang. Melihat kondisi itu elemen kampus ini memilih diam atau berbuat sesuatu? Memang, pendekatan untuk mengenali kampus ini di masa sekarang tentu jauh berbeda dengan kondisi masa itu. Tingkat kepadatan, overload, dengan ruang sempit yang dihuni banyak orang ini membuat sesak, nafas tersedak, jantung kencang berdetak. Maunya buru-buru saja. Suasana bising dan tidak nyaman, membludak, banyak kepala, runyam, barangkali menjadikan mahasiswa memilih hengkang satupersatu, menyendiri dalam kenikmatannya, memilih tidak berpikir apa-apa saja. Tetapi, tentunya bukan itu yang diinginkan. Kemenangan suatu team sepak bola adalah kekompakan pemain dalam menentukan strategi. Keberhasilan kampus ini amat bergantung kekompakan semua elemen dalam menjalankan visi dan misi. Dari masalah krisis yang ada, Mbah Budi menawarkan solusi sederhana, bahwa penerapan 'teori kemitraan' dalam kampus Jurusan Musik ini menjadi penting. Kemitraan kirakira dijelaskan sebagai perihal hubungan (jalinan kerjasama), misal: berteman, bersahabat, berkawan kerja. Untuk kepentingan kemitraan ini, bagi Mbah Budi, ada beberapa prinsip yang perlu diketahui. Realisasi kemitraan diperlukan sarana-sarana penunjang yang harus timbul dari masingmasing individu, antara lain: SMS: Short Music Service 209 (1) Tekad dan niat: Setiap individu harus bertekad mau melepas egoisme masing-masing, ketika bertemu sesama manusia baik di kampus, di masyarakat. Tekad tersebut akan membantu kita untuk mau “belajar mendengarkan” orang lain selagi berbicara, mendengarkan keluhan dan menghargai kebutuhan klien atau orang lain dengan penuh perhatian (hindari serba “ku”, atau “aku”, “pokoknya”,dsb.) (2) Keyakinan Tidak ragu dalam bersikap karena kemitraan adalah kunci utama untuk berteman, bermitra, tunjukkan sikap kita untuk selalu positif thinking, jujur, familier, dsb. (3) Kesabaran Jauhkan rasa dan pikiran emosional, jawablah sesuai dengan pola pikir rasional, pola kebijakan, kewibawaan, cinta kasih (perlu inspirasi dan kreatif) Kesimpulan secara umum, bahwa kuantitas (banyaknya mahasiswa) tidak akan menjamin kemajuan apa-apa tanpa adanya solidaritas yang terbangun di kampus ini. Kita tak akan sampai ke percaturan internasional jika tidak berani kompak. Manusia melakukan hubungan harmonis dengan sesamanya untuk menjaga tradisi olah pikir perguruan tinggi yang tidak bisa dicapai begitu saja. Korelasi atau sinergi sosial (manusia antar manusia), sebelum lebih jauh ke persoalan musikal atau studi minat utama misalnya, ternyata menjadi elemen penting (fondasi) yang harus lebih dulu dibangun. Barangkali, ini dasar dari semuanya. Bahwa dalam konteks Jawa misalnya, kita tidak bisa hidup sendiri, sebaliknya, SMS: Short Music Service 210 gotong royong itu adalah faktor penentu laju kebudayaan. Apakah melihat kondisi yang semakin terpecah belah ini kita cuma bisa terdiam? Dalam dan Luar Tembok Pada sebuah kesempatan di bulan November 2003, saya dan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa mengikuti Forum Dialog Mahasiswa yang digagas mahasiswa FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Forum tersebut diikuti perwakilan dari UNY, ISI dan UKRIM. Dalam kesempatan itu, Gatot D. Sulistiyanto (Ketua HIMA musik) tampil sebagai pembicara. Saya, yang ketika itu menjabat sebagai koordinator Divisi Keilmuan HIMA, merasa harus banyak belajar membuka pikiran untuk mengenali atmosfir seminar atau diskusi. Tiba saatnya, seperti yang disampaikan mBah Budi mengenai ilmu “belajar mendengarkan orang lain” akhirnya bisa saya terapkan, bahkan hingga kini. Ketika itu, HIMA Jurusan Musik menyoal masalah Problematika Kampus Seni. Secara umum, pembicaraan ini membahas paradoks berkesenian di dalam tembok (kampus) dan di luar tembok (realitas). Bagaimana mengatur strategi seimbang antara proses belajar dan proses berkesenian (bermusik)? Adakah masalah di antara keduanya? Pengalaman belajar ini sungguh menarik untuk ditulis. Sebaran mata kuliah yang terlalu banyak dan mungkin memusingkan, meskipun itu merupakan pijakan studi, ternyata, bukanlah esensi (inti sari). Ilmu yang didapatkan di kampus hanyalah 10%, demikian kata kebanyakan dosen. Selebihnya mahasiswa harus mencari dan mengembangkannya di dunia luar yang lebih terbuka, apalagi dalam konteks kesenian. SMS: Short Music Service 211 Kurikulum sebagai obyek teori yang menjadi materi dasar pengajaran, ternyata menemui situasi yang unik ketika diaplikasikan. Hal ini menyangkut masalah minat utama yang diselenggarakan oleh kampus. Walaupun perbedaan sebaran mata kuliah Minat Utama (MU) Musik Pendidikan dan Pengkajian Musik ketika itu terlihat jelas, namun dalam kondisi di lapangan hampir tidak ditemui batas yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan (ketidaksadaran) mahasiswa pada umumnya terhadap minat utama yang dipilih. Ketika itu, mahasiswa MU Musik Pendidikan maupun Pengkajian Musik sama-sama terbebani praktek instrumen mayor dengan tingkat ketrampilan yang relatif sulit. Dampaknya, bahwa sasaran sesungguhnya dari Musik Pendidikan (menjadi pedagog misalnya), atau Pengkajian Musik (menjadi peneliti, penulis, musikolog), dirasa tidak berhasil, bahkan kesalahan persepsi ini cenderung dipertahankan. Sebagai akibatnya, mahasiswa dihadapkan pada situasi “mendua” yang berkepanjangan, tidak ada satu konsentrasi yang diperjuangkan sampai ke masalah dedikasi kesenian. Faktanya, banyak mahasiswa memilih bermain musik namun kurang berpikir strategi mengembangkan potensi, mereka banyak terjebak, mengeluh stres karena mayor, tetapi kurang berpikir kolektifitas, atau masalah pengabdian untuk masyarakat, penelitian misalnya. Bahkan ironisnya, nyaris tidak ada sumbangsih yang berarti bagi kehidupan musik bagi bangsa dan negara ini (dedikasi). Relitasnya, banyak elemen kampus ini memilih bekerja “di luar”, yang barangkali untuk kepentingan masing-masing. Kepentingan musik dan institusi justru menjadi kurang. Ini adalah kesan yang SMS: Short Music Service 212 membuat saya harus merenung kembali. Di bawah bayang-bayang 4 Minat Utama Di Jurusan Musik saat ini sedang dijalankan 4 MU, yaitu Musik Pendidikan, Musikologi, Musik Pertunjukan, dan Komposisi. Setelah kampus menawarkan ini pun, minat Musik Pertunjukan, yang mengkhususkan bagi para pemain musik, juga tidak ramai 'dikunjungi' karena dirasa mempunyai grade yang lebih berat dari MU lain. Jalan yang sepertinya “paling aman” adalah masuk Musik Pendidikan. Oleh sebab itu mahasiswa Musik Pendidikan (dari tahun ke tahun) selalu membanjir. Dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Tetapi yang kuantitatif jelas belum menjamin kualitas. Yang ramai dikunjungi itu juga belum tentu sebagai indikasi kemajuan. Ketika dihadapkan pada realitas kesenian sesungguhnya, bulu kuduk malah berdiri, tidak siap mental. Resital dan konser misalnya, menjadi momok karena takut gagal. Menjadi langka. Padahal kemajuan diukur dari seringnya, bukan jarangnya. Yang mengherankan, bahwa studi di dalam tembok kampus malah dijadikan sesuatu yang mengungkung dan tidak menjadikan mahasiswa terbuka terhadap dinamika kehidupan (seni) yang lebih lebar. Jalan keluar dari persoalan ini perlu dicari, agar, meminjam istilah Suka Hardjana, bakat-bakat itu tidak menjadi tua di kampus. Ironisnya, banyak rekan mahasiswa yang bingung ketika ditanya cita-citanya apa? Pada saat kita kecil, ketika ditanya cita-cita, kita yakin menjawab: pilot, dokter, guru, nahkoda, masinis, nelayan, profesor, sampai presiden! Tetapi ketika sudah semakin dewasa banyak yang tidak punya keyakinan dan kemantapan. Berkali-kali saya menanyakan seputar cita-cita (musik) kepada rekan mahasiswa. Sebagian SMS: Short Music Service 213 besar menjawab dalam kubangan dan genangan ketidakpastian. Dampaknya, setelah lulus kebingungan, banyak alumni lebih memilih “jalur” cepat, kilat dan aman, misalnya jadi guru kursusan, main di pub, orkestra populer, bahkan menjadi pedagang tanaman. Tidak ada hubungan signifikan dengan konsentrasi studi (MU) yang telah dipilih. Dengan demikian, orientasi studi (barangkali) dihadapkan pada sejumlah kewaspadaan, ke(tidak)berhasilan. Ini terjadi bertahun-tahun. Secara umum, ada beberapa pendapat mengenai minat. Istilah minat terkait dengan motivasi. Banyak ahli psikologi yang menyebutkan bahwa minat merupakan aspek penting motivasi yang mempengaruhi perhatian, belajar, berpikir dan berprestasi (Pintrich Schunk, 1996). Pendapat dari Blair, Jones, Simpson (1975) tentang minat adalah suatu perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu kegiatan. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kesadaran memilih, kesadaran berbuat, kesadaran menentukan pilihan. Menjatuhkan pilihan pada institusi ini, pada MU misalnya (bukan pada mayor saja!) Berarti siap menanggung segala konsekuensinya. Artinya, mahasiswa dilarang keras untuk mengingkari pernyataan yang telah ditorehkan di awal studi. Bahwa dalam setiap tes masuk (wawancara), sebagian besar mahasiswa, ketika ditanya soal kenapa alasan masuk Jurusan Musik, pasti jawabannya untuk belajar, menambah ilmu, jadi pemusik. Tetapi pada kenyataannya, setelah menjalani masa studi, mahasiswa tidak belajar sungguhsungguh, ilmu tidak diperdalam kebanyakan dolan, main PS atau pacaran, dari tahun ke tahun ilmu-ilmu yang seharusnya semakin banyak malah semakin susut, surut. Diet kok ilmu? Akhirnya, mahasiswa yang berhasil dan tidak, bisa SMS: Short Music Service 214 diperkirakan banyak yang tidak berhasil (sesuai maksud institusi). Kalau berhasil menuruti maunya sendiri ya mungkin banyak. Banyak sekali lah... Hal ini tentu menjadi koreksi bersama, sejauh manakah kita berperan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian negara ini? Apabila tidak sanggup belajar, dan kampus cuma (semata-mata) menjadi “jembatan” cari rejeki saja tanpa pendalaman studi dan dedikasi apa-apa, ya lebih baik tidak usah ke perguruan tinggi saja, itu malah lebih dihormati dan dihargai. Persoalan problematika kampus seni tersebut kiranya cukup menjadi renungan bagi masyarakat kampus ini. Selagi semuanya masih bisa diperbaiki kenapa harus menyerah? Habitat Baca Habitat Nulis Budayawan Wilson Nadeak (Kompas, 10/4/2005) mengungkap, bahwa membaca bukan sekadar ketrampilan. Lebih dari itu, membaca adalah sebuah kegiatan kreatif. Saat membaca, seseorang berdialog dengan dirinya sendiri dan hal-hal atau tokoh-tokoh yang terkandung di dalam bacaan, saling mengasah intelek dengan pengarang dalam bayangbayang rasa ingin tahu, sanggahan, dan menjaring gagasan baru. Sementara menulis adalah ujung dari sebuah pencarian tonggak kecendekiaan. Menulis berarti seseorang menyarikan sesuatu yang dicerna ke dalam sebuah wacana yang terseleksi, dapat dipahami dan mengandung pemikiran yang menantang. Menulis adalah sebuah kegiatan kreatifitas pengungkapan diri, pencarian ide yang autentik dengan pengungkapan yang autentik, dari simpul-simpul penemuan para pendahulu yang telah teruji oleh waktu. Dengan demikian membaca dan menulis adalah dua hal yang tak mampu SMS: Short Music Service 215 dipisahkan. Intelektualitas ditopang oleh kedua hal itu. Cinta buku cinta menulis. Slogan ini mustinya diusulkan menjadi basic penggemblengan pola pikir bagi semua mahasiswa (4 Minat Utama). Di kampus ini, terus terang saja, tradisi itu belum, bahkan semakin tidak terbangun. Hal ini saya buktikan ketika mengelola majalah dinding Jurasik Today misalnya. Kami redaksi selalu mengeluh, sedikit sekali yang berminat membacanya, apalagi menyumbangkan tulisannya (aspirasi dan pikirannya). Walaupun demikian kami sungguh berbahagia bisa menerbitkan kumpulan tulisan (Bundel), meskipun minim dana. Asalkan kreatifitas ada di kepala, jalan tidak tersumbat. “Denah sukses” bisa digambar sendiri. Sebagian besar rekan mahasiswa punya gagasan cemerlang dan konstruktif, namun ketika sampai pada penuangan gagasan terjadi kesulitan. Jika kesulitan demi kesulitan itu tetap dibiarkan, tidak akan ada jalan keluar. Oleh sebab itu solusi yang perlu dicari adalah mencoba dan terus berlatih, membaca dan menulis, karena itu tugas utama akademisi, demi pengejawantahan pola pikir sebelum melangkah ke lingkup pergaulan yang lebih luas. Bahwa yang terpenting bukan tulis-menulisnya, tetapi kesanggupan untuk menuangkan gagasan dan ide-ide yang membawa perubahan bagi masa depan. Perubahan yang (tentunya) positif. Penyebab dari ketertinggalan wacana perguruan tinggi barangkali adalah gagap membaca. Buku belum dianggap sebagai pembentuk pemikiran dan menulis belum dianggap sebagai media yang paling tepat sasaran untuk menyampaikan ide dan gagasan, mengusahakan perubahan. Banyak mahasiswa di sini tidak suka membaca, apalagi menulis. Padahal ini elemen dasar atau fondasi yang menurut saya cukup tepat untuk menuangkan ide, berkomunikasi, SMS: Short Music Service 216 membina korelasi sosial, kontrol sosial, kemungkinan dialog yang sehat, eksistensi, mengangkat pamor, membuka link, serta untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang konstruktif. Di kampus ini, menulis sering diidentikan hanya sebagai tugas bagi para musikolog (pemikir) saja. Padahal tidak demikian adanya. Sekadar menyebut contoh, bahwa namanama yang disebut di bawah ini bukan para musikolog, tetapi mereka komponis, pedagog, dan pemain. Namun para tokohtokoh ini semuanya menulis, baik artikel maupun buku. Mereka adalah Vincent Persichetti, F. Bussoni, Zoltan Kodaly, A. Zemlinsky, Elie Siegmester, Arthur Lourié, Arnold Schoenberg, Amir Pasaribu, Djohan Salim, dan tentu masih banyak contoh lain yang bisa ditemukan dalam berbagai publikasi. Mahasiswa termasuk makhluk pilihan yang pintar dan potensial, tergantung bagaimana mengoptimalkan ketrampilannya, bagaimana belajar percaya pada otaknya sendiri. Salah satu sebab pola pikir tidak terbentuk dengan baik karena tidak suka membaca buku. Jika tidak suka membaca buku, bisa dikatakan tidak mencintai ilmu pengetahuan. Jika tidak cinta ilmu pengetahuan, berarti tidak cinta perguruan tinggi, itu sama halnya (maaf) tidak mencintai kampusnya sendiri. “Bermain musik itu pilihan, tetapi berpikir tentang musik itu pasti”. Demikian teori Gatot D. Sulistiyanto. Senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, adalah buku. Begitu ujar Mochtar Lubis. Republik Indonesia banyak memiliki tokoh pergerakan yang bersenjatakan buku dalam mengusir penjajah (Majalah Inti Sari, Mei 2005). SMS: Short Music Service 217 Kenapa Membaca? Kemampuan membaca (sudah tentu) besar peranannya dalam pendidikan tinggi. Sebagian besar pengetahuan mahasiswa, misalnya, diperoleh dari media cetak, terutama dari buku dan majalah-majalah ilmu pengetahuan (serta jurnal ilmiah). Oleh karena itu, agar dapat belajar secara efisien, kemampuan membaca mahasiswa perlu ditingkatkan. Cara kita membaca ditentukan oleh maksud kita membaca. Ada lima alasan mengapa kita membaca, yaitu untuk memperoleh informasi, untuk memahami informasi, untuk mendalami bahan bacaan, untuk mengenal atau menilai dan untuk mencipta. Dengan membaca, sesungguhnya orang belajar menghargai pemikiran orang lain, perjalanan hidup orang lain. Menyimak lembar demi lembar sejarah yang berjalan. Meluaskan cakrawala. Mendekati kisi-kisi menjadi cendekiawan, dan tentu masih banyak manfaat lain yang bisa kita simpulkan sendiri. Kita cuma berusaha mengingat slogan populer: buku adalah jendela dunia. Adanya berbagai buku (musik) yang pernah terbit, hendaknya juga dibaca tidak hanya pada saat mau ujian semester atau skripsi saja, namun membaca dan menulis adalah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Selama S1, paling tidak mahasiswa (mampu) membaca minimal 100 buku, syukur-syukur bisa lebih, demikian nasihat Drs. Hari Martopo, M. Sn. Membaca buku tidak harus mempunyai buku! Perpustakaan itu maha bijaksana, di situlah mahasiswa belajar tentang semua tanpa dipungut biaya. Komponis, pemain, pedagog, musikolog, mereka semua adalah jantung kehidupan musik yang tugas sama-ratanya SMS: Short Music Service 218 adalah menyumbangkan ide, gagasan dan pikiran mereka dengan cara apa pun, termasuk menulis. Pernyataan itu tidak bisa lepas dalam benak, karena di tangan merekalah nyawa kampus ini akan bertahan selama-lamanya. Apabila tidak dioptimalkan, potensi itu hanya menjadi angin lalu. Belajar Kepada Semua Tulisan demi tulisan di bab ini sengaja tidak didominasi dengan asumsi teori ilmiah. Nyaris semuanya berdasarkan fakta, serta berbagai argumen yang didasarkan atas pengalaman. Apa yang saya alami selama studi di kampus ini membawa suatu kesan tersendiri yang sulit dirumuskan dengan bahasa ungkap teoritis. Berbagai uraian cuma menjadi pendapat yang (harus) dilanjut menjadi diskusidiskusi yang lebih terbuka, secara sehat dan dinamis. Segala ide tentang kampus ini mengalir dengan apa adanya, seperti sungai bengawan solo. Tidak ada klasifikasi pasti, bahwa ketika manusia belajar, ia harus secara khusus mencari guru yang tepat baginya, kecuali untuk pendidikan supranatural atau spiritual yang barangkali membutuhkan rumus-rumus khusus yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Belajar bisa dilakukan dengan siapa saja. Kapan pun dan dimana pun. Di kampus, secara struktural, mahasiswa belajar pada dosen. Tetapi, mahasiswa juga bisa belajar dari karyawan, dan dosen pun juga harus senantiasa membuka diri untuk belajar kepada mahasiswa. Bukan pada tempatnya dosen merasa menjadi gudang pembenaran. “Ragukan omongan dosenmu”, demikian anekdot dosen filsafat, Dra. Sukatmi Susantina, M.Hum. Pengalaman yang dimiliki satu sama lain tentulah berbeda menurut kadarnya masing-masing. Berdasarkan hal SMS: Short Music Service 219 inilah, prinsip saling melengkapi akan menjadi sinergi yang menarik. Belajar kepada semua, kepada siapa saja. Tidak ada stratifikasi pembedaan kelas yang menyebabkan mahasiswa menjadi sulit belajar. Pada hakekatnya, ilmu itu bersifat terbuka. Kita tidak hidup di masa peperangan atau zaman silat-silatan, yang kadang-kadang, ada ilmu yang disembunyikan. Tidak semua ilmu bisa dibocorkan sang guru kepada murid. Intelektualitas itu akan terbangun melalui jalinan komunikasi yang akrab, terbuka, dan komunikatif. Kepada siapapun manusia boleh saling belajar, tidak perlu ada ilmu yang disembunyikan. Senantiasa semua elemen harus belajar kepada semua, tidak harus melulu yang muda kepada yang tua. Selamat belajar. Kultur Kedisiplinan Perbincangan kian hangat ketika sampai pada masalah sulitnya menerapkan kedisiplinan di kampus Jurusan Musik ini. Nah, selanjutnya kita semua pasti akan berkata: ya ampun…sulitnya minta ampun untuk menerapkan satu kata itu. Disiplin Belajar dan Komunikasi Pada umumnya, barangkali semua setuju bahwa disiplin musikal dapat dicapai melalui latihan (belajar) secara intensif, dengan pola latihan yang tepat dan efektif, juga efisien. Sadar hidup di musik berarti sadar belajar dan berlatih, misalnya: memainkan, mendengarkan, menonton konser, membaca, menulis, berpikir, sampai tahap manajemen diri, aktualisasi diri, membuka link (publikasi) demi eksistensi (pribadi dan institusi). Dalam kasus tertentu, seringkali mahasiswa terjebak oleh SMS: Short Music Service 220 hal yang entah apa sebabnya, yang menjadikan kegiatan belajar menjadi tidak kontinu, putus di tengah jalan. Pada saat memasuki babak baru perguruan tinggi (semester awal) banyak mahasiswa sibuk berlatih di kampus hingga tengah malam. Kampus ramai dikunjungi, bahkan sampai pagi. 1-2 tahun berikutnya mereka ternyata limbung, hilang tak tentu arah, studinya mengalami kekacauan. Rekan mahasiswa yang seperti ini memilih hilang dari kampus skala tahunan. Mungkin stres kali ye! Ee...tahu-tahu sudah nikah, ke kampus bawa berkah (anak!). Hal ini barangkali, salah satunya, disebabkan oleh kurang adanya disiplin belajar dan komunikasi (secara intensif) antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa seringkali kehilangan arah akibat bingung menentukan langkah. Kurang ada bimbingan intensif, cuma sebatas kelas saja. Padahal itu sangat kurang. Menurut saya, dosenlah orang yang paling tepat untuk mengarahkan studi anak didiknya, membaca potensi yang ada pada anak didik, menolong menemukan jalan bagi minatnya sendiri. Mahasiswa kadang tidak percaya diri ketika harus selalu mendekati dosen dan berguru sepanjang waktu. Menghadapi mahasiswa tipe kurang pede itu, seharusnya dosen berjiwa ngemong, yang tua membimbing yang muda. Orang tua membimbing anaknya. Istilah Jawanya ngalahi. Asal anak didiknya maju. Kalau semua mahasiswa punya inisiatif ya tidak perlu seperti itu, namun yang terjadi di sini sebaliknya, jadi (sepertinya) perlu pendekatan berbeda. Di kampus ini, disiplin komunikasi jelas kurang terjalin dengan baik. Hanya segelintir dosen yang menurut saya dedikatif, serta mampu menjalankan tugasnya dengan baik, SMS: Short Music Service 221 sisanya cuma menjadi pengajar kelas. Ketika ada mahasiswa putus studi di tengah jalan, hilang tak tentu arah, DO misalnya, seolah-olah hal demikian murni kesalahan mahasiswa. Bisa jadi, mahasiswa tertekan dengan sistem pendidikan, tertekan dengan iklim belajar kelas yang tidak kondusif, pelayanan akademik yang kurang memuaskan, kecewa karena minat-minat yang dipupuk tidak tersalurkan, kecewa karena pengajarnya kurang kompeten di mata kuliah tertentu, kecewa karena dosen tidak menjadi figur bagi anak didiknya, dan sebab lain yang tentu bisa dicari. Disiplin Merawat Alat Musik Contoh lain adalah disiplin merawat alat musik. Dalam banyak gurauan alat musik itu tak ubahnya seperti kekasih. Oleh sebab itu kita menyayangi dan menjaganya sepenuh hati. Perlakuan dalam perawatan (maintenance) terhadap alat musik, selayaknya seiring pula dengan perlakuan perbaikannya (repair). Dalam perlakuan tersebut perlu adanya hal yang mendasarkan pada pengetahuan organologi alat musik, dan perangkat alat perawatan serta alat perbaikan (R. Agus Sri Widjadadi, 2005). Untuk sanggup mencintai alat musik masing-masing memang dibutuhkan pengorbanan. Disiplin pada titik ini adalah upaya “bersetubuh” lahir batin dengan alat musik, menjadikannya media paling sakral dan kudus yang harus menjadi tanggungan dedikasi, terutama bagi para pemain. Disiplin Waktu Ini masalah klasik yang semua tahu. Masalah kuno, zaman purba. Baheulak. Sampai kini susah untuk dijalankan: disiplin waktu! Ada anekdot, Indonesia itu dalam sehari punya 25 jam SMS: Short Music Service 222 (selalu molor minimal 1 jam). Ada jadwal latihan, rapat, diskusi, undangan, konser, tertulis jam 3 datang jam 4. Sudah biasa, mas! Kuliah molor, harusnya pukul 07.30 menjadi 08.30 juga biasa. Jika ini dijaga, berarti sama halnya menjaga yang payah, meski itu kadang-kadang nikmat dijalankan. Ah, telat saja ah...palingpaling juga molor... Disiplin waktu tidak membudaya di kampus ini. Manajemen diri mendisiplinkan waktu menjadi berat untuk dijalankan. Jika para dosen dan mahasiswa menjadi makhluk teladan, cinta disiplin, itu bakal menjamin kampus ini maju. Prospek cerah akan terbuka di masa depan. Yang perlu dicatat, bahwa kedisiplinan dosen dan mahasiswa masih kalah dengan kedisiplinan para karyawan yang kerjanya hanya bersihbersih! Disiplin Kreativitas: Mencipta! Leonardo da Vinci (1452-1519), jenius zaman Renaisans, secara tegas menggunakan istilah kreatif untuk para seniman. Kemampuan kreatif manusia adalah kemampuan yang membantunya untuk dapat berbuat lebih dari kemungkinan rasional dari data dan pengetahuan yang dimilikinya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang lengkap, yang memiliki kreativitas pasif dan aktif. Tentang hubungan kreativitas dengan proses kreasi, Irving A. Taylor (1959) berpendapat bahwa perkembangan seni dan ilmu bergantung kepada usaha kreatif. Kemajuan pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kreativitas manusia. Kampus ini, secara ideal adalah kampus yang akan menghasilkan banyak kreator, yang pekerjaannya berkreasi, berkarya, berkarya dan berkarya. Bukan menunggu, tetapi SMS: Short Music Service 223 selalu ada hasrat ingin tahu dan mencari sesuatu. Pada titik ini, seniman memang dituntut disiplin dan kerja keras. Pemikiran harus selalu stand by, ini barangkali susah. Dalam kreativitas berkomposisi misalnya, komponis tidak hanya piawai merangkai nada saja. Berbagai gejala sosial yang melingkupinya juga harus dicermati dengan jeli sampai pada keadaan paling up to date. Kondisi politik, sosial, negara, konflik, sampai inovasi kemungkinkan teknologi terbaru misalnya, akan mewarnai dinamika pikir, yang lantas direduksi menjadi sebuah karya (ingat karya Beethoven Shympony No.3). Kreativitas bagi para performer adalah semangat menyulap panggung menjadi dunia yang mewakili berbagai dimensi. Panggung adalah (juga) dimensi kultural, humanis, sosial. Panggung tidak cukup menjadi tempat pentas (aksi!) para pemusik, tetapi menjadi bagian dari budaya. Bahwa di situlah performer menggantungkan nyali dengan beribu tingkah nafas kreatifnya, berusaha menjalin interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat, sampai pada titik puncak karir. Di biodatanya berjejer diskografi. Jika kampus ini tidak ingin mandeg (statis), maka elemen di dalamnya selalu merasa perlu melakukan inovasi. Dibutuhkan semangat mencipta. Semangat kebaruan. Dilandasi dengan kreativitas. Bahwa mencipta, yang dilandasai semangat berkreativitas, bukan tugas para komponis saja. Tetapi, para pedagog, pemain dan musikolog adalah muara adanya think creative di kampus ini. Kreativitas adalah upaya pembaruan, yang tidak cukup dicapai dalam kurun temporal. Kepada kreativitaslah seni itu bertumpu, seni itu menjadi hidup. Komunitas: Usaha Belajar Bersama Di kampus ini, ada mahasiswa yang suka belajar sendiri, SMS: Short Music Service 224 tapi ada juga yang nyantol ketika belajar secara kelompok. Bersama-sama menemukan kesepakatan, meraih solusi atas permasalahan (ajang curhat!). Pentingnya komunitas belajar bagi masyarakat kampus ini adalah upaya mencari kesamaan visi-misi edukatif, yang mensinergikan aspek moral, kreatif yang kadang-kadang diiringi parodi, guyonan khas. Didirikannya Turanggalila misalnya, sebuah komunitas belajar (indie: luar kampus), adalah sebuah usaha untuk mencari, menemukan, dan memecahkan masalah bersama-sama. Komunitas ini melatih olah pikir, bersifat komunikatif, tidak struktural atau pragmatis. Ilmu dan kolektifitas menjadi dasar, ilmu (musik) menjadi teka-teki untuk dikuak. Turanggalila adalah organisasi alternatif, bersifat independen, tidak feodal ataupun demokratis. Gaya bebas menjadi ciri komunitas tanpa struktur dan rileks ini. Namun yang kami prihatinkan dari koordinator Turanggalila, bahwa kegiatan berpikir di kampus ini masih dianggap hal yang 'mengerikan'. Rekan mahasiswa yang tidak suka baca buku, bergaul dan berpikir akan merasa minder dengan Turanggalila karena dianggapnya berat. Padahal tonggak kemajuan diukur dari adanya pemikiran, bukan banyaknya yang main (tapi tidak “mikir”). Suatu ketika, bahkan sering, saya menemukan joki begini: “itu golongan orang-orang pinter ya, ngeri ah!” (pinter bohong kali ye...). Padahal komunitas ini, menurut Agus Bing belum pernah ada (secara kontinu) sebelumnya. Kegiatan belajar dijalani secara rileks dan santai, bahkan cenderung celelek'an dan “kampungan”. Komunitas ini gratis, datang dapat snack, dapat minum, dapat ilmu. Pertanyaan yang akan saya lontarkan di buku ini adalah kenapa sebagian besar dari kita (mahasiswa) merasa bahwa berpikir itu berat? Ini terbukti SMS: Short Music Service 225 sangat sedikit sekali yang berminat bergabung di komunitas ini. Adanya Kelompok Belajar Mahasiswa, yang di kampus ini dikenal sebagai KBM, juga sebagai media belajar alternatif yang hendaknya selalu dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Klasifikasi per-instrumen mayor menjadi dasar bagi setiap KBM. Dari sinilah interaksi antar mahasiswa dapat terjalin erat, ada kerja sama. Mahasiswa mustinya minat dan membutuhkan wadah seperti ini, yang menjamin pemantapan di lingkup kampus, sebelum pede bergaul di dunia luar, suatu tujuan esensial yang hendak kita capai. Hal yang berhubungan dengan kreativitas adalah bagian dari usaha pendisiplinan mencipta ruang kreatif, sekaligus mencipta ide-ide dan gagasan cemerlang. Jika usaha-usaha yang telah dicapai sebelumnya, dengan hasil (dinamika) yang sudah menunjukkan grafik meningkat, ini perlu diupayakan secara serius, ditingkatkan lagi. Organisasi kampusan memang tidak bisa dikatakan profesional, namun juga tidak amatir. Ada strategi khusus agar kelompok belajar tersebut tidak terkungkung dalam temaram labirin tembok baja yang menyekat. Organisasi kampusan adalah pintu gerbang menuju relaitas kesenian. Kuncinya adalah membuka diri terhadap belantara luar, belajar pede ketemu orang-orang di luar kampus, melakukan dialog, saling terbuka. Dengan begitu kampus ini akan maju. Percaya deh... Gosip Seputar Figur (Dosen Cepat Saji) Tulisan Vina Yulia (mhs. 2005), Ya Dosen Ya Performer, Mungkinkah?, termuat di Bundel Jurasik Today (2007) mengingatkan kita semua akan pentingnya figur (dosen) sebagai sosok suri tauladan bagi mahasiswa. Lebih lanjut, SMS: Short Music Service 226 Vina menulis demikian, “idealnya seorang pengajar, terutama dosen mayor, harus mengadakan resital rutin entah itu satu semester sekali atau setahun sekali. Alangkah bangga dan bahagianya jika kita dapat saksikan dosen berunjuk kebolehan memainkan alat musik dengan gaya dan ekspresi mereka.” Itu sekadar uneg-uneg yang terlampau polos namun realistis---meskipun---dosen mayor juga tidak musti sebagai performer yang handal. Namun ada beberapa catatan yang ingin dicermati lebih jauh. Keprihatinan ini barangkali terletak pada persoalan garis dedikasi pengajar. Segala mata kuliah (ilmu) yang diasup mahasiswa adalah makanan (gizi: baik atau buruk?) tiap harinya. Andaikan kita ke warung, ada harapan untuk mencicipi masakan enak, atau minimal layak dikonsumsi. Faktor lain, ada harapan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari penjaga warung. Lebih menyenangkan ketika penjaga itu juga sebagai koki yang handal, yang mengerti betul cara memanjakan lidah pelanggan. Kita menyaksikan cara koki memasak dengan lihainya, hingga sampai ke piring saji dengan uap khas yang mengepul. Aroma sedap terasa, koki menjanjikan, kepuasan datang. Suatu ketika pelanggan merindukan makan di warung itu lagi. Itu sekadar perumpamaan. Yang menjadi pokok persoalan sebetulnya adalah penguasaan (kompetensi) dosen. Pengampu mata kuliah A juga seharusnya menger ti dengan baik ilmu A (mengaplikasikannya di lapangan?) dan bukan sebagai pengajar text-book semata. Yang agaknya disayangkan, ada sebagian pengajar 'dadakan' (dosen cepat saji) yang kurang memahami mata kuliah dengan baik. Faktanya, beberapa mahasiswa terlihat protes. SMS: Short Music Service 227 Contohnya seperti ini: 1. “koq dosen itu mengajar ini, sih?” 2. “lho, dosen itu kan biasanya begitu, koq tiba-tiba ngajar ini?” 3. “ah, dosenku nggak mau nyontoni (memberi contoh: main), apalagi resital. Bagaimana aku tahu dia bisa main? Mengajarnya juga kurang baik”. Kira-kira seperti itu faktanya. Tulisan Vina Yulia, atau sebagian tulisan yang lain dan dalam berbagai obrolan seputar ini, cukup memberikan data dan sumber yang akurat. Ini cukup membawa bukti bahwa dosen (atau penentu kebijakan?) melakukan hal yang kurang tepat bagi anak didik. Imbasnya adalah protes dari mereka. Bahwa pengajar mata kuliah A ternyata tidak mempunyai kompetensi mata kuliah A. Jadinya cuma “A'A”-nan doang. Permasalahan ini sangat umum. Di kampus-kampus lain juga mengalaminya. Memang dosen tidak bisa kita tuntut menguasai secara sempurna bahan atau ilmu yang diajarkan. Karena ciri khas ilmu itu sendiri adalah dinamis, tidak abadi, bisa “goyang” setiap saat. Namun setidaknya, ada standar kompetensi (kelas dan lapangan!) yang dijalani oleh dosen. Tidak harus semua. Bagaimana pun juga, mahasiswa adalah penerima dan pembuat ilmu itu sendiri, yang kedudukannya sebagai jantung di perguruan tinggi. Kepada mahasiswa ilmu itu bertumpu. Dosen mengajarkan apa pun yang dimilikinya, syukur-syukur, sesuai dengan dedikasinya di lapangan kesenian. Itu memang tidak mutlak tetapi paling tidak bisa membahagiakan mahasiswa (sebagai pelanggan ilmu). Tetapi bayangkan saja jika ada mahasiswa yang mengeluh akan hal ini. Siapa yang menimpa kerugian terbesar? Adalah kedua- SMS: Short Music Service 228 duanya. Adalah juga Institusi. Atau memang kita kekurangan tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya sendiri? Apakah dalam skala mayoritas dosen cuma menjadi pengajar text-book? Ah, saya tak cukup tahu untuk menjawab persoalan ini. Tolong dibantu. Semacam Pamali bagi Para Durhaka Ibu melahirkan kita. Dialah yang repot mengandung, melahirkan, membasuh, nyeboki, menyusui, menyuapi, menyayangi, melindungi, memberi jalan, mengajari bahasa, retorika, ilmu komunikasi, hukum-hukum hidup sejak bayi, jadi anak, jadi remaja, dewasa, tua. Banyak hal diasup dari ibu. “Pembalasan-pembalasan” kepadanya haruslah setimpal. Jika anak tidak hormat atau durhaka pada ibu kandungnya bisa pamali. Bakalan menanggung risiko yang teramat besar. Sekarang begini, jika kata ibu diganti Institusi. Hukumnya sama saja. Lalu apa bedanya? Bedanya ada pada: sang Ibulah yang menghendaki hadirnya kita, selain tentu Allah yang berkuasa atas ini. Sementara Insititusi itu adalah ruang yang kita pilih untuk belajar, untuk menjadi ibu yang baik buat mendidik kita. Rahim Institusi adalah rahim ibu, yang akan melahirkan sosok-sosok penting bagi kehidupan ilmu pengetahuan dan seni. Lahir ceprot dari rahim ibu belum menjadi apa-apa selain bayi putih dengan rengek keras mengganggu tetangga. Lahir ceprot dari Institusi adalah menggunakan tabungan ilmu, yang minimal selama 4,5 tahun dikumpulkan. Logikanya sama. Kepada ibu dan Insitusi kita harus mengabdi, hormat dan menjunjung tinggi. Jika mainmain dan menganggap remeh pasti kuwalat, pamali. Banyak mahasiswa kurang sadar akan hal ini. Kerjanya ngejob jarang belajar. Hilang lama. Mendadak kaya, tapi tak SMS: Short Music Service 229 ada sumbangsih apa-apa bagi Institusi, bagi ilmu, bagi komunitas, bagi masa depan semua, masa depan rakyat dan bangsa, masa depan musik. Jarang sekali berpikir, cuma suka cari uang, bukan cari ilmu. Sangkuriang telah dibenci Tuhan, dibenci langit dan bumi. Ini memang abstrak, tak cukup dibaca sekali-dua kali. Perjalanan, Pencarian, Kesasar, atau Kepepet ? Indonesia selalu punya seabrek masalah, apalagi ekonomi yang semakin terpuruk, kemiskinan semakin bertaburan dimana-mana. Kesempatan untuk bernafas bahagia kian sempit. Jakarta dilanda macet. Tingkat emosional penduduk jelas semakin tinggi. Di antara dua kebimbangan. Di media dan birokrat kita saksikan sedang hura-hura, sementara rakyat semakin tidak jelas nasibnya. Ekonomi. Lagi-lagi ekonomi menjadi persoalan yang tak cukup menjadi persoalan, tapi ironi. Jika ini penyakit, pastilah tak henti-henti kita berpikir: apa obat yang paling mujarab. Kisah yang satu ini agak lucu, selain tentu unik. Logika Institusi Seni adalah mencetak para seniman, ilmuwan, yang kompeten sekaligus disegani di masyarakat. Bukan mencetak pedagang. Rentang studi, perjalanan, dan nasib kita diadu: dengan bunyi-bunyian, buku, pergaulan, musik, ilmu, karya, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, nurani selalu mencita-citakan untuk tetap berada di satu rel, tidak mencabang. Rel itu adalah jalan ilmu yang kita pilih: musik. Apa pun dinamika proses belajar, yang harus diusahakan adalah menguak apa pun yang belum pernah diungkap, atau menelaah berbagai permasalahan. Mengais akal budi, SMS: Short Music Service 230 kedinamisan pola pikir, serta merakit jantung, yang sebelumnya cuma embrio yang belum jadi. Jantung kita ini bisa dianalogikan sebagai nafas hidup-mati Institusi. Proses itu adalah jungkir baliknya mahasiswa ketika tak hentihentinya mencari alternatif, mana yang tepat, pas, sreg, menjamin, yang musti diusahakan, dilakukan, tak cuma dipikir. Intinya, mencari apa pun yang belum terkuak dari musik, musik, dan musik. Nah, jika ternyata di tengah jalan tidak kuat dengan seabrek tuntutan kurikulum Institusi, mahasiswa mau apa? Jika di tengah jalan kecantol cewek cantik lalu married, dengan apa menghidupi keluarga? Apa mungkin ini beberapa contoh mahasiswa keblinger? Apa mereka memang mencitacitakan untuk menjadi kesasar seperti ini? Apakah ini cuma tujuan mencari jalan, biar bisa makan, bisa hidup, orang tua tak lagi menanggung biaya. Atau barangkali cuma iseng-iseng berhadiah? Apa pun alasannya itu menjadi logis: karena siapapun bebas memilih, menentukan dan memutuskan pilihan, jalan hidup sendiri-sendiri. Makanya, jangan heran ketika banyak mahasiswa kategori keblinger itu memilih menjalani garis bisnis yang sama sekali tidak berhubungan dengan profesi seni. Contohnya: jual voucher, buka angkringan, jual kaos, bisnis laundry, jual-beli tanaman, pakaian, alat musik, dll. Mereka-mereka ada dan hidup di sekitar kita. Musik bagi mereka barangkali menjadi antrian paling belakang. Namun ini menjadi kisah unik yang harus dicatat dalam kalbu. Kita akan menjaga mereka dengan ketulusan hati agar mereka tetap ada dan tetap berjualan. Biarkan mereka hidup dengan perjuangan mereka, karena negara tidak menjamin hal ini. Persoalan ekonomi barangkali menjadi alasan paling SMS: Short Music Service 231 kuat. Mereka mencoba mengatasi hal itu. Saya merasa yakin mereka tetap mencintai musik meski tidak lagi berjuang untuk musik. Salut. Dialog Bapak Anak di Keluarga Paris 6,5 Andaikan kita ini merasa satu keluarga ya mustinya kita saling berdialog. Konsensus. Menuju kesepahaman. Keluarga yang maju berisi bapak dan anak yang selalu berdialog, ibu dan bapak mesra. Siapa yang menjadi bapak dan ibu dalam Institusi? Ini bisa dijawab sendiri-sendiri. Tetapi saya yakin jawaban itu sama. Yaitu para elemen birokrasi dan dosen. Merekalah yang memberi inspirasi dan gizi buat kehidupan kita di Institusi. Jadi teman-teman, bapak kita itu banyak. Semua jadi bapak kandung, jangan dibeda-bedakan. Tidak ada bapak tiri di sini. Makanya, jika kampus ini mau maju ya sering-seringlah berdialog dengan mereka. Tetapi, kita tuh punya kebiasaan grogi kalau ketemu mereka. Sulit bicara saat bertemu mereka. Pokoknya minderlah. Termasuk saya ini orang yang minderan. Untuk membuka dialog, biar kita cair ketemu mereka, siapa yang harus memulai? Anak atau bapaknya? Mustinya ya bapak. Karena secara manusiawi bapak punya sifat ngemong anaknya. Membimbing. Bapak bertanya pada anak. Sudah sampai mana perjalanan (ilmu musik) mu, nak? Juga diperhatikan, mana saja anak-anak yang berprestasi, punya reputasi, pintar. Anak-anak itu harus disantuni, dibiayai (bukan beasiswa PPA, lho!) dengan harapan termotivasi, maju, membawa nama indah bagi institusi. Anak-anak harus “disentuh” secara langsung. Menjadi satu, menjadi cair. Bapak akan mencintai tulus (perkembangan) anaknya. Lima tahun saya belajar di sini, saya sangat kurang SMS: Short Music Service 232 mendapat perhatian dari Bapak saya yang jumlahnya banyak itu. Ah, alangkah sedihnya saya. Atau jangan-jangan saya terlalu menutup diri dan tidak pandai bergaul dan bertanya? Mungkin saja. Kalau benar begitu, saya minta beribu maaf. Tolong maafkan saya ya, pak? Kenal Pura-pura versus Kenal Beneran Saya tidak tahu, yang tertulis di sub-bab ini perlu ditulis apa tidak, menjadi persoalan atau bukan. Kalau suatu persoalan, ini vital atau ringan. Atau jangan-jangan saya cuma menjadi budak atas emosi saya sendiri? Akal sehat sama sekali tidak bermain. Ah, tak tahu lah. Atas dasar kata hati yang kuat saja saya berani menuliskannya. Seperti yang telah saya tulis tentang masalah guyub, silaturahmi, meraih kehangatan sosial di atas, hal ini menduduki pandangan yang lebih personal, subyektif. Hubungan aku dan kamu, seperti pacaran. Topik bagian ini sengaja bukan menekankan pada kolektifitas koheren. Secara sosiologis, dalam Institusi ini, kita satu keluarga; secara biologis saja kita berlainan. Ada orang-orang pilihan yang musti saya pilih untuk ruang tohokan keluh kesah, dikala saya sambat (mengeluh) berbagai hal: studi, karir, masa depan, cinta, ekonomi, dll. Singkatnya, para sahabat terdekat, yang lahir batin membahana dalam ruang-ruang protes dan amarah saya mengenai apa pun yang pernah saya pelajari di dunia ini. Adakah mereka dalam satu ruang ini? Adakah mereka bisa ditemui dimana-mana? Karena orang-orang pilihan, maka tidak begitu mengherankan mereka saya sebut sebagai sahabat terpilih, yang ikhlas lahir batin, kekancan sungguh-sungguh, tanpa kedok apa-apa, tanpa tujuan menjilat, menghasut, politik, “punya maunya”, iseng. Tidak. SMS: Short Music Service 233 Mereka ini adalah orang “sungguhan” yang bicara ikhlas, bergaul lahir batin. Bukan orang individual dan egois. Saya tidak akan menyebut nama-namanya, namun fakta sosial-lah yang akan mencoba saya tuliskan di sini. Kultur kampus ini kurang begitu menjanjikan untuk bisa bersilaturahmi lahir batin kepada banyak orang. Banyak orang masih mementingkan ambisi pribadi, egois, memuliakan individualisme. Selama lima tahun terakhir malah tidak semakin baik, malah kondisinya semakin tak karuan saja. Makanya, harus ada orang-orang pilihan yang saya amini sebagai kawan lahir batin, kawan yang beneran, bukan etoketokan (pura-pura). Untuk menyebut contoh yang faktual saja, banyak 'kawan pura-pura' itu obrolannya tak lebih sekadar say hallo saja: piye dab, mayor sudah lulus belum?, njikuk pirang SKS ki, wis ya tak mulih sik, dsb. Pokok'nya gitu lah. Saya tak bakalan betah ngobrol dengan mereka-mereka ini. Paling lama 1 menit. Merasa agak tidak nyambung. Cuma kawan pura-pura. Sama sekali tidak terasa hubungan emosional yang menandakan bahwa kita ini satu keluarga yang saling berkomunikasi. Kalau saya bicara dengan kawan beneran, minimal 1 jam, maksimal bisa 12 jam; dan itu sangat menyenangkan. Lahir batin. Enjoy. Rileks. Tidak lagi bilang, “piye dab?”, atau katakata serupa yang cuma klise saja. Kawan beneran selalu ngobrol sungguh-sungguh, bicara masa depan, diskusi, belajar bersama, dengan tanpa simbolisasi-simbolisasi yang tak perlu. Makanya, mohon maaf, saya sering nggak konek ketika ngobrol dengan kawan tipe pura-pura. Saya tidak bisa menyalahkan kawan pura-pura itu. Di satu sisi, mereka itu bisa jadi merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di hatinya. Sementara di sisi lain sebenarnya SMS: Short Music Service 234 untuk apa saya mengupas ini. Toh, sudah banyak yang bilang, bahwa hubungan solidaritas kita satu sama lain sudah semakin pudar karena didomplengi oleh berbagai kepentingan yang bukan kemanusiaan lagi. Saya memilih mempertahankan komunitas kawan beneran saja. Dalam ruang terasing tidak menjadi masalah. Minoritas, sempit, kerdil, kecil, tidak masalah. Asalkan kawan-kawan saya yang satu ini memang benar-benar menjadi senasib dan sepenanggungan. Satu gaya. Jujur. Rukun. Ikhlas. Guyub. Lahir batin. Mengerti satu sama lain. Saling membantu. Tepa salira. Suka menolong. Dan predikat serupa yang bisa disebutkan. Sampai sejauh ini kawan-kawan saya itu jumlahnya sudah 20-an orang. Bukankah ini kebahagiaan? Alienasi Pernahkah suatu ketika kita berpikir: apakah masyarakat semakin bisa percaya pada Institusi ini? Percaya penuh bahwa out-put yang dihasilkan memang menguasai bidang? Percaya kalau Jurusan Musik ini bukan mencetak “tukang” tapi seniman, ilmuwan, yang melakukan pemikiran dan inovasi? Percaya bahwa dengan menyekolahkan anaknya, pakai jutaan duit, akan mendapat pendidikan yang layak, lulus bisa diandalkan? Percaya bahwa masyarakat menaruh harapan penuh pada Institusi ini agar bisa memajukan kehidupan musik di negeri ini? Mencerdaskan akhlak bangsa? Mencetak manusia kreatif? Apakah masyarakat percaya hal itu? Atau justru sebaliknya, kita menjadi elemen yang sama sekali tidak diharapkan kehadirannya? Bahwa yang harus dicatat, kita ini juga bagian dari masyarakat itu. Hanya bedanya, kita berada dalam suatu ruang formal yang terkonstelasi oleh sekat-sekat. Artinya, kita SMS: Short Music Service 235 tidak dimungkinkan menjadi terbuka dan menjalin dialog langsung dengan masyarakat luar, selain dalam “uji lapangan” ketika kita benar-benar menjadi bagian hidupmatinya masyarakat (kesenian). Institusi itu cuma fasilitator saja. Sementara, yang menjadi inti adalah terbukanya dialog dengan masyarakat bahwa Jurusan Musik ini juga menjadi jantung yang dipercaya memajukan pendidikan musik di Indonesia, bukan semakin memundurkan seratus kilo pertahun. Sudah puluhan kali para ahli musik mengeluh, entah itu Amir Pasaribu, L. Manik, Binsar Sitompul, Suka Hardjana, Suhastjarja MA, Dieter Mack, dan sebagainya. Intinya bahwa pendidikan musik tidak semakin maju. Ini karena apa? Kesalahan sistem Institusi? Media? SDM-nya? Arah profesi yang tidak jelas? Barangkali saya adalah orang yang ke-100 kali yang membicarakan ini. Menurut Dr. Victor Ganap, sistem pendidikan musik seyogyanya mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, sesuai Undang Undang No.2 Tahun 1989. Artinya pendidikan tinggi musik harus mampu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam hal menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan musik. Wadah Institut (ISI, IKJ, UNY, misalnya) cukup memadai dalam pengertian sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Pendidikan musik seyogyanya bersifat lebih terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik. Bahwa yang dimaksud dari pemaparan itu adalah, goalnya mahasiswa seni adalah juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui Institusi para mahasiswa nyicil, menabung ilmu, dan melalui pengalaman di masyarakat ilmu itu diterapkan, diuji. Bukan pada “panggung- SMS: Short Music Service 236 panggung berhadiah” versi kapitalis, tetapi benar-benar diuji di pentas kemasyarakatan, yang memperjuangkan akhlak bangsa. Institusi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Maju tidaknya kehidupan (pendidikan) musik amatlah tergantung akan peran serta elemen Institusi. Jika selama ini banyak yang sembrono, dampaknya akan “membahayakan” Institusi. Lebih kacau lagi jika masyarakat merasakan dampak (buruk) itu. Optimis dan percaya diri saja, asal berusaha dengan sungguh-sungguh, tulus dan jujur kita pasti diberi jalan oleh Allah. Tidak usah khawatir. Saya percaya Intitusi ini tidak bakalan ter-alienasi (terasing) dari masyarakatnya sendiri dan kehadirannya akan dibutuhkan sebagai penyejuk yang didambakan seperti menantikan Idul Fitri atau Natal. Serius. Saya masih 100% percaya bahwa Jurusan Musik ini gudangnya para pengabdi masyarakat. Bule Bule Datang, Mari Kita Sambut Kita semua, para mahasiswa maksudnya, tentu berbahagia atas kedatangan para musisi asing yang kita pandang lebih hebat dan akan memberi ilmu pada kita. Kepada Tuhan kita bersyukur tiada habisnya. Dr. Djohan Salim, sosok yang saya hormati, melontarkan anekdot saat saya bertandang ke rumahnya, “kalau belajar musik Barat sebaiknya langsung sama orang Barat”. Ini artinya kita disuruh ke Barat atau kita menunggu saja orang Barat datang ke Jurusan Musik, ke Sewon, ke pinggir sawah? Lewat buku ini, saya tulis beberapa nama musisi asing yang pernah berkunjung ke Jurusan Musik memberi workshop sampai “petuah bijak”. Saya tulis seingat saya saja, kurang lebih 5 tahun terakhir. Mereka adalah: SMS: Short Music Service 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 237 Jack Body (New Zealand/Komponis) Edward C. Van Ness (Belanda/Violinist) Duo Groningen (Belanda/Gitaris) Vincent McDermott (Amerika/Komponis) Kees Weringa (Amerika/Pianis) Rieko Suzuki (Jepang/Violinist) New Zealand Trio (New Zealand/Chamber Music) Dutch Brass Quintet (Belanda) New Dutch Academy (Chamber dari Belanda) Carlos Michan (Belanda/Komponis) Prof. Dieter Mack (Jerman/Musikolog) Wilfried Jentzsch (Wina/Komponis) Kim Sanders (Australia/Komponis) Geizer-Mazzolla Duo (Switzerland, duo: piano dan drum) Eriko Takezawa (Pianis/Jepang) Pieter Ypma (Belanda/Drumer) Roderik de Man (Belanda/Komponis) Prof. Nakamura (Jepang/Violinist) Epocus (band dari Jepang) Motohide Taguchi (Jepang/Komponis) Disamping nama-nama di atas jelas ada nama yang belum tersebut dan hilang dari memori. Yang terpenting dari kedatangan mereka, entah itu siapa, dari mana asalnya, bukan hanya memberi stimulus kepada para calon musisi profesional kita untuk lebih terpacu bermusik, tetapi juga sebagai jaringan kerja dan kebudayaan yang harus dipelihara baik-baik. Mereka bukan para dewa yang harus kita junjung tinggi. Sama seperti kita, mereka itu manusia biasa. Hanya saja, mereka adalah orang-orang SMS: Short Music Service 238 tekun, yang memetik kesuksesan di berbagai panggung musik. Lahir dari sekolah musik yang unggul. Mereka lebih terbiasa membumi dengan kultur musik Barat dibanding kita yang punya banyak permasalahan dan terlalu bingung harus gimana langkah ini. Beruntung mereka datang ke Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Belanda, Jepang, Amerika, Switzerland, Selandia Baru, Australia, Jerman, dll. Maka, persahabatan yang mesra ini memang selayaknya dipelihara. Jika mereka disakiti dengan cara tidak dihargai, diterlantarkan, dibohongi, dijilat, dsb., maka mereka akan marah dan tidak akan balik lagi ke Sewon. Rugilah kita semua. Ayo siapa lagi yang mau datang? Mari rame-rame bule-bule itu dikalungi kembang. Relativitas Penyadaran (Epilog) Sadar atau tidak, menyoal perkara “sadar” adalah urusan pribadi masing-masing, yang sebetulnya sangat tidak bisa dipaksakan. Berubah atau tidaknya suatu kondisi disebabkan oleh adanya kesadaran bersama untuk berani menghadapi situasi sulit, yang terkadang menjebak. Dihantam krisis di sana-sini, termasuk “penghantaman” dan kritik terhadap kampus ini, bukan terpaan yang membuat kita tak bisa berkutik sedikit pun. Jika pada kenyataannya, mahasiswa atau dosen tidak menyadari ketertinggalan, tidak sadar perjuangan sampai dimana, dan tidak sadar menghadapi titik nadir yang amat mencekam, maka hal inilah situasi paling sulit tersebut. Kesadaran menjadi hilang. Sebenarnya, kampus ini mau dianggap Mall, Taman Bermain, atau tempat Akumulasi Pemikiran? Jika kampus ini Mall, yang datang cuma ingin membeli sesuatu (ilmu) saja, habis itu pulang tanpa berpikir apa-apa selain memanfaatkan SMS: Short Music Service 239 barang yang dibeli untuk kepentingan pembeli dengan semaunya sendiri. Jika mall tiba-tiba terbakar, pelanggan tidak akan pernah merasa iba, cuma sedih sebentar dan tidak akan membantu memadamkan apinya. Jika kampus dianggap Taman Bermain, berarti tidak ada sesuatu yang serius, selain menghapus retorika penat dan “kamus bosan” menjadi happy. Tidak ada kesan, pengendapan dan renungan apa-apa selain keisengan membunuh waktu. Bermain adalah “ujinyali” pengalaman yang tidak ada hubungannya dengan garis masa depan. Dilakukan hari ini hilang juga hari ini. Kecuali games itu ada muatan mendidik? Jika hanya seperti Dunia Fantasi, lha kita mau apa? Sampailah kita pada alam pemikiran yang tak pernah selesai sepanjang zaman. Bahkan, jika kampus ini runtuh atau hancur diamuk gempa sekalipun, buih pemikiran itu akan tetap ada. Orang-orangnya belum mati, meski kampusnya mati. Karena yang menjadi inti perjalanan kampus bukan tembok kampus dengan akustik yang harus banyak direvisi lagi ini, tapi otak-otak yang setia bersemayam di dalamnya. Jika kampus dianggap tempat Akumulasi Pemikiran, maka sebaiknya sebagian besar masyarakat kampus ini suka berpikir dan berkarya. Tidak harus semua berpikir, nanti kebanyakan. Yang paling menjamin masa depan kehidupan musik bukan pada banyaknya pemusik saja, bukan banyaknya grup-grup musik, bukan banyaknya seniman-seniwati, pencipta, pedagog, publik, kreator, pemikir. Bukan pada banyaknya (kuantitas) siapa pun yang mewarisi musik. Namun, masa depan kehidupan musik ya tergantung intensitas dan konsistensinya. Anehnya, banyak yang suka musik, suka main musik, tetapi tidak suka berpikir. Sukanya berpikir bisnis saja. Bagaimana cara lakunya, meraup untung SMS: Short Music Service 240 besar “di panggung massif saja” (meninjam istilah Agus Bing) tapi menihilkan kualitas, penghayatan, otoritas, keyakinan, link, dan kreativitas. Menurut saya, kemajuan itu ditopang oleh endapan pemikiran, pencurahan pemikiran yang mengarah ke perubahan. Intinya, semua yang merasa mewarisi musik dari para leluhurnya ya wajib berpikir tentang itu. Dengan demikian penyadaran menjadi tidak relatif, tetapi merupakan elemen yang benar-benar nyata. Tidak semu. Baiklah, untuk menutup akan saya kutip nasihat ini: Mantan Rektor ISI Yogyakarta, Prof. Dr. I Made Bandem punya petuah begini, “...seorang seniman yang terus memelihara daya kreasi dan semangat inovasi, serta membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Seorang seniman memiliki komitmen ser ta integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang seniman memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kesenian, bagi kehidupan dan kemanusiaan.” Rektor ISI Yogyakarta sekarang, Dr. Suprapto Soedjono, petuahnya begini, “Kesenian tidaklah sekadar ungkapan rasa, emosi, dan pemikiran yang tertampilkan melalui proses estetis-kreatif yang bisa dinikmati sekadar sebagai 'tontonan' saja, tetapi juga bisa dimuati pesanpesan makna yang berwujud dalam bentuk-bentuk 'tuntunan' bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat.” SMS: Short Music Service 241 Tulisan di bab ini hanya sebagai retrospeksi saja, yang memungkinkan dibaca siapa saja yang berminat belajar melalui pengalaman dan melalui sejarah. Usaha untuk kembali merenung dan merenung lagi demi bangsa ini. Keyakinan bahwa masih banyak harapan cerah untuk hari esok harus dijunjung tinggi hingga ke langit. Keyakinan dan optimisme harus tetap abadi dalam ruang dan waktu. Bahan Bacaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sukses Belajar di Perguruan Tinggi. ed. Evita E. Singgih-Salim dan Soetarlinah Sukadji. Panduan. Yogyakarta. 2006 Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan. Edgar Morin. Kanisius. 2005 Bundel Jurasik Today. HIMA Musik ISI Yogyakarta. 2007 P e n i n g ka t a n Ku a l i t a s B e rke s e n i a n : S u a t u Keniscayaan Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Dr. Soeprapto Soedjono. Makalah Dies Natalis XXIII ISI Yogyakarta. Debat Tentang ISI: Peran, Kenyataan, dan Tantangannya. Prof. Dr. I Made Bandem. Harian Kedaulatan Rakyat. 23 Juli 2004. Problematika Kampus Seni. Situasi di Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta. Tim HIMA Musik ISI Yogyakarta. Makalah Seminar Musik dan Forum Dialog Mahasiswa. 4 November 2003. Universitas Negeri Yogyakarta. Menyimak Wawasan Kampus Jurusan Musik. Drs. YC. Budi Santosa, M.Hum. Makalah dalam Musyawarah Mahasiswa V Jurusan Musik ISI Yogyakarta. 2003. SMS: Short Music Service 8. 242 Perawatan Alat Musik: Sebuah Wacana Menjadikan Pemain yang Baik. R. Agoes Sri Widjajadi. Makalah Pelatihan Perawatan Alat Musik. Jurusan Musik ISI Yogyakarta. 2005 9. Membaca, Menulis dan Tradisi. Wilson Nadeak. Artikel dalam Kompas Minggu, 10 April 2005. 10. Kreativitas dan Humanitas: Sebuah Studi Tentang Peranan Kreativitas dalam Perikehidupan Manusia. Primadi Tabrani. Jalasutra. 2006 11. Majalah Intisari. Mei 2005. Komentar Pembaca Pertama 1. “Erie sangat keras dalam semangat menulis. Terutama dalam memacu iklim menulis (musik) di komunitasnya, atau sekadar corat-coret menawarkan gagasan yang segar-segar.” (Tony Maryana, Komponis) 2. “Tulisan-tulisan Erie lugas, kritis, motivatif dan pokoknya kerenlah...” (Maslikhatun Nisa, S.Sn, Terapis Musik) 3. “Komunitas Jurasik Today, Turanggalila, tulisan-tulisannya yang tersebar, serta karya (di buku) ini menunjukkan suatu metamorfosa yang bertahap. Tetap semangat!” (Reza Amaludin, Event Organizer) 4. ”Buku ini sebagai monumen peristiwa musik yang penting untuk dibaca!” (Gatot D. Sulistiyanto, Komponis) SMS: Short Music Service 244 5. “Wawasannya luas, orangnya menarik dan nyeleneh, namun Erie mempunyai kontribusi nyata. Anda dapat mengetahuinya setelah membaca buku ini. (Ag. Joko Prayitno, Pembaca Kritis) 6. “Tulisan-tulisan Erie langsung menyeret kita untuk tahu akan wacana, tersadar, dan membayangkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Selain itu, gaya tulisannya nyeleneh dan rock'n'roll abis...” (Muslim, Pemain Kecapi) 7. “Seperti kata pepatah: malu bertanya setelah sampai di “rumah”daripada tersesat lebih bagus pulang ke rumah; manusia itu yang tahu adalah manusianya sendiri. Bukan ia, dia, mereka, atau siapa saja. Sebab, kalau Anda bilang bagus saya bilang tidak bagus, Anda mau apa? Ini mengajarkan kita percaya diri. Jadikanlah obsesimu setinggi langit tetapi jangan melebihi Tuhanmu. (Rafael Antonio Montoya, Pekerja Audio) 8. “Semoga buku ini bisa menjadi motivasi untuk siapa saja, khususnya teman-teman Jurusan Musik ISI Yogyakarta. Sukses!” (Kuncoro Hadi, Pekerja Seni) TENTANG PENULIS Erie Setiawan. Lahir di Solo, 11 Januari 1984. Belajar musik secara formal di SMK N 8 Surakarta, lulus tahun 2002 dan mengantongi predikat Tamatan Terbaik. Kemudian ia menempuh studi Musikologi di Jurusan Musik ISI Yogyakarta. Tahun 2003 s.d. 2005 pernah “nyambi” bekerja sebagai guru honorer di SMK Negeri 8 Surakarta. Keaktivannya di kegiatan organisasi kampus dimulai dengan menjabat sebagai koordinator Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Musik ISI Yogyakarta. Tahun 2006 hingga kini dipercaya sebagai Pemimpin Redaksi Kabar Kampus Jurasik Today. Tahun 2007 ia mendirikan Forum Studi Musik Turanggalila, yang merupakan komunitas belajar (musik) independen. Kegemarannya membaca untuk mengetahui banyak “misteri” di dunia ini menyeretnya ke dalam rimba pemikiran SMS: Short Music Service 246 dan tulis-menulis. Buku SMS : Short Music Service (Prophetic Freedom, 2008) ini adalah buku keduanya, setelah pada tahun 2003 ia mencoba menulis buku saku berjudul Diatonis, 6 Tahun Meniti Melodi, yang diedarkan terbatas untuk muridmuridnya. Tahun 2007 bersama rekan-rekan Jurusan Musik menerbitkan Bundel Jurasik Today. Segelintir tulisannya juga pernah dimuat antara lain di Harian Suara Merdeka, Kompas, Majalah Gong, Solo Pos, dan beberapa media massa lainnya. Selain aktivitas menulis, bermain di group band sebagai gitaris adalah hobi yang tak bisa ditinggalkannya. Sejak pertama kali bermusik pada 1997, setidaknya sudah 10 band dibentuknya. Namun ia dan group bandnya tak pernah bercitacita menjadi artis. Salah satu band yang sampai kini masih “dijaganya” di Solo adalah Blue Skin, sebuah band instrumental yang memainkan musik jazz. Ia juga tergabung di komunitas Solo Jazz Society. Ia juga kerap diminta menjadi Juri untuk Festival Band, menulis komposisi musik dan mementaskan karyanya, memberi ceramah ilmiah, kurator independen, dan sedang belajar menjadi pengamat musik. Saat ini tengah bersiap menyelesaikan studi S-1nya yang sebentar lagi (harus) diselesaikannya. Bagi yang ingin mengobrol dengan santai, Erie bisa dihubungi di 0815 486 22425. Kritik dan saran mengenai buku ini silahkan disampaikan melalui e-mail: [email protected]