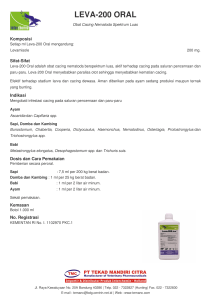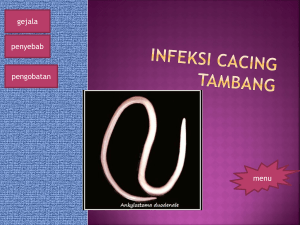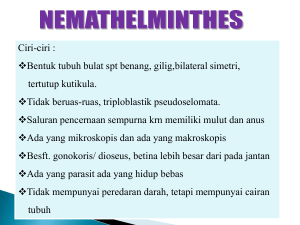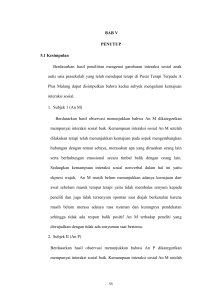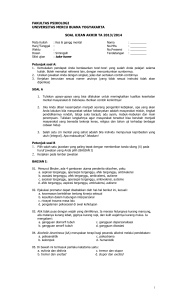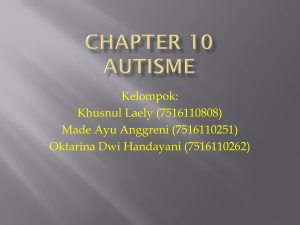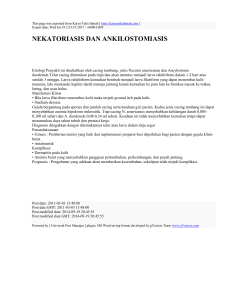Nyeri Neuropatik
advertisement

DARI REDAKSI Sidang Pembaca yang terhormat, Penasehat Ir. Ferry A. Soetikno, M.Sc., M.B.A. Ketua Pengarah/Penanggung Jawab Dr. Raymond R. Tjandrawinata Pemimpin Redaksi dr. Grace V.J., M.M. Pada edisi terakhir di penghujung tahun 2006 ini, Dexa Media menampilkan tema utama, yaitu dengan judul artikel “Penggunaan Obat Antiepilepsi sebagai Terapi Nyeri Neuropatik”, yang menjelaskan bahwa penggunaan lamotrigine yang pada awalnya sebagai antiepilepsi, sekarang ini digunakan sebagai analgesik adjuvant untuk nyeri neuropatik. Beberapa artikel dari rubrik tinjauan pustaka antara lain membahas mengenai Redaktur Pelaksana Tri Galih Arviyani, S.Kom. austistik, manajemen gagal jantung kronik, diagnosis dan penatalaksanaan gagal Staf Redaksi dr. Della Manik Worowerdi Cintakaweni Gelly Eka Prasasti, S.Si., Apt. Herninta Pramitasari, S.Si., Apt Gunawan Raharja, S.Si., Apt. Drs. Karyanto, MM dr. Marini Johan Puji Rahayu, S.Farm, Apt. dr. Ratna Kumalasari dr. Lydia Fransisca H. Tambunan Yosi Krisyanti, S.Si, Apt Peer Review Prof. dr. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D., Sp.And. Prof. Dr. dr. Darmono, Sp.PD-KEMD Prof. Dr. dr. Djokomoeljanto, Sp.PD-KEMD Jan Sudir Purba, M.D., Ph.D. Prof. Dr. Med. Puruhito, M.D., F.I.C.S., F.C.T.S. Prof. dr. Sudradji Soemapraja, Sp.OG. Prof. Dr. dr. H. Sidartawan Soegondo, Sp.PD-KEMD, FACE Prof. dr. Wiguno Prodjosudjadi, Ph.D., Sp.PD-KGH Redaksi/Tata Usaha Jl. R.S. Fatmawati Kav. 33 Telp. (021) 7509575 Fax. (021) 75816588 Email: [email protected] Rekomendasi Depkes RI 0358/AA/III/88 Ijin Terbit 1289/SK/Ditjen PPG/STT/1988 jantung diastolik, infeksi cacing tambang, patogenesis dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami persilahkan untuk membacanya. Penelusuran jurnal yang memuat artikel-artikel terbaru sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk pembaca dan Kalendar Peristiwa yang memuat jadwal simposium yang diadakan pada tahun 2006 ini tetap kami tampilkan tiap edisinya. Tak lupa kami terus mengundang para pembaca untuk berpartisipasi mengisi lembaran Dexa Media dengan memberikan tulisan berupa Tinjauan Pustaka, Case Report, Artikel Penelitian. Akhir kata kami redaksi Dexa Media mengucapkan selamat Idul Fitri 1427 H dan selamat Natal dan Tahun Baru 2007. Salam! DAFTAR ISI Pengantar Redaksi Petunjuk untuk Penulisan Dexa Media 161 162 Artikel Utama: Penggunaan obat antiepilepsi sebagai terapi nyeri neuropatik 163 Tinjauan Pustaka: Tatalaksana farmakologis gangguan spektrum autistik: Telaah pustaka terkini Peran serotonin pada gangguan spektrum autistik Konsep baru kortikosteroid pada penanganan sepsis Patogenesis dan respon imun tubuh terhadap infeksi virus Herpes simpleks Infeksi cacing tambang 167 173 177 182 187 Artikel Penelitian: Pemberian glutamin menurunkan kadar bilirubin darah serta Mengurangi nekrosis sel-sel hati setelah pemberian aktivitas Fisik maksimal dan parasetamol pada mencit Diagnosis dan penatalaksanaan gagal jantung diastolik Manajemen gagal jantung kronik Cover: NEURON SUMBANGAN TULISAN Redaksi menerima partisipasi berupa tulisan, foto, dan materi lainnya sesuai dengan misi majalah ini. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan. Redaksi berhak mengedit atau mengubah metode penulisan, tanpa mengubah tulisan yang dimuat apabila dipandang perlu. No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 192 196 200 Sekilas Dexa Medica Group Berkibarlah Merah Putih-ku OGBdexa, Segitiga Merahnya, Bikin Hemat Delon semarakkan peluncuran TOXILITE 207 207 208 Penelusuran Jurnal Kalender Peristiwa Daftar Iklan: Lamictal, Raivas, Dobuject, Toxilite, Tripoten, Generik 211 212 161 PETUNJUK PENULISAN Redaksi menerima tulisan asli/tinjauan pustaka, penelitian atau laporan kasus dengan foto-foto asli dalam bidang Kedokteran dan Farmasi. 1. Tulisan yang dikirimkan kepada Redaksi adalah tulisan yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dalam bentuk cetakan. 2. Tulisan berupa ketikan dan diserahkan dalam bentuk disket, diketik di program MS Word dan print-out dan dikirimkan ke alamat redaksi atau melalui e-mail kami. 3. Pengetikan dengan point 12 spasi ganda pada kertas ukuran kuarto (A4) dan tidak timbal balik. 4. Semua tulisan disertai abstrak dan kata kunci (key words). Abstrak hendaknya tidak melebihi 200 kata. 5. Judul tulisan tidak melebihi 16 kata, bila panjang harap dipecah menjadi anak judul. 6. Nama penulis harap disertai alamat kerja yang jelas. 7. Harap menghindari penggunaan singkatan-singkatan 8. Penulisan rujukan memakai sistem nomor (Vancouver style), lihat contoh penulisan daftar pustaka. 9. Bila ada tabel atau gambar harap diberi judul dan keterangan yang cukup. 10. Untuk foto, harap jangan ditempel atau di jepit di kertas tetapi dimasukkan ke dalam sampul khusus. Beri judul dan keterangan yang lengkap pada tulisan. 11. Tulisan yang sudah diedit apabila perlu akan kami konsultasikan kepada peer reviewer. 12. Tulisan disertai data penulis/curriculum vitae, juga alamat email (jika ada), no. telp/fax yang dapat dihubungi dengan cepat. Contoh Penulisan Daftar Pustaka Daftar pustaka di tulis sesuai aturan Vancouver, diberi nomor sesuai urutan pemunculan dalam keseluruhan tulisan, bukan menurut abjad. Bila nama penulis lebih dari 6 orang, tulis nama 6 orang pertama diikuti et al. Jumlah daftar pustaka dibatasi tidak lebih dari 25 buah dan terbitan satu dekade terakhir. Artikel dalam jurnal 1. Artikel standar Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11):980-3. Lebih dari 6 penulis: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Freidl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years follow-up. Br J Cancer 1996; 73:1006-12 2. Suatu organisasi sebagai penulis The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164:282-4 3. Tanpa nama penulis Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J 1994; 84:15 4. Artikel tidak dalam bahasa Inggris Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116:41-2 5. Volum dengan suplemen Shen HM, Zhang QE. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82 6. Edisi dengan suplemen Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2):89-97 7. Volum dengan bagian Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6 8. Edisi dengan bagian Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1990; 107(986 Pt 1):377-8 9. Edisi tanpa volum Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrode-sis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320):110-4 10.Tanpa edisi atau volum Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993;325-33 162 11. Nomor halaman dalam angka romawi Fischer GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction Hematol Oncol Clin North Am 1995; Apr; 9(2):xi-xii Buku dan monograf lain 12. Penulis perseorangan Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):Delmar Publishers; 1996 13. Editor sebagai penulis Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for eldery people. New York:Churchill Livingstone; 1996 14. Organisasi sebagai penulis Institute of Medicine (US). Looking at the future of the medicaid program. Washington:The Institute; 1992 15. Bab dalam buku Catatan: menurut pola Vancouver ini untuk halaman diberi tanda p, bukan tanda baca titik dua seperti pola sebelumnya). Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Patophysiology, Diagnosis and Management. 2nded. New York:Raven Press; 1995.p.465-78 16. Prosiding konferensi Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent Advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam:Elsevier; 1996 17. Makalah dalam konferensi Bengstsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical information. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:North-Hollan; 1992. p.1561-5 18. Laporan ilmiah atau laporan teknis Diterbitkan oleh badan penyandang dana/sponsor: Smith P, Golladay K. Payment for durable medi-cal equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas(TX):Dept.of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860 Diterbitkan oleh unit pelaksana: Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health Services Research: Work Force and Education Issues. Washington:National Academy Press; 1995. Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and Research 19. Disertasi Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The eldery’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995 20. Artikel dalam koran Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sept A:3 (col.5) 21. Materi audio visual HIV + AIDS: The facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995 Materi elektronik 22. Artikel jurnal dalam format elektronik Morse SS. Factors in the emergence of infection diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL:HYPERLINK 23. Monograf dalam format elektronik CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995 24. Arsip komputer Hemodynamics III: The ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando [FL]: Computerized Educational Systems No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL UTAMA Penggunaan Obat Antiepilepsi sebagai terapi Nyeri Neuropatik Jan Sudir Purba Departemen Neurologi FKUI/RSCM, Jakarta Abstrak. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri neuroaptik yang tergolong pada tipe nyeri kronik diakibatkan oleh lesi di jaringan susunan saraf baik perifer maupun pusat. Penggunaan obat antiepilepsi pada nyeri neuropatik didasari oleh keidentikan dalam neuropatofisiologik antara nyeri neuropatik dan epilepsi. Keidentikan ini termasuk kepekaan yang abnormal dari neuron-neuron sebagai akibat kelainan pada reseptor seperti NMDA, AMPA/kainat yang pada saatnya nanti bisa memicu plastisitas reseptor tersebut di post-sinaptik. Kepekaan yang abnormal inilah yang mengakibatkan tarjadinya perubahan elektrik potensial di otak yang disebut sebagai bangkitan epilepsi. Obat antiepilepsi merupakan obat yang berkemampuan untuk menekankepekaan yang abnormal dari neuron-neuron sehingga dengan demikian bisa menekan bangkitan epilepsi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa obat antiepilepsi digunakan sebagai analgesik adjuvant untuk terapi nyeri neuropatik. Ternyata obat antiepilepsi lamotrigine sangat efektif dalam penanggulangan nyeri neuropatik terutama trigeminal neuralgia, nyeri neuropatik pada penderita HIV, nyeri sentral pada penderita pasca stroke ataupun nyeri neuropatik yang intracktable. Cara kerja dari lamotrigine adalah berperan dalam stabilisasi membrane sel neuron dengan memblok aktivitas kanal voltage-sensitive natrium serta mencegah sekresi glutamate dan menstimulasi sekresi GABA di presinaptik ke sinaps. Pendahuluan yeri seperti didefinisikan oleh International Association for Study of Pain (IASP), adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut.1,2 Nyeri bisa bervariasi berdasarkan: waktu dan lamaya berlangsung (transient, intermittent, atau persisten), intensitas (ringan, sedang dan berat), kualitas (tajam, tumpul, dan terbakar), penjalarannya (superficial, dalam, local atau difus).3 Di samping itu nyeri pada umumnya memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan sebagai penderitaan. Selain itu nyeri juga dihubungkan dengan refleks motorik menghindar dan gangguan otonom yang oleh Woolf (2004)3 disebut sebagai pengalaman nyeri. Secara patologik nyeri dikelompokkan pada nyeri adaptif atau nyeri nosiseptif, atau nyeri akut dan nyeri maladaptif sebagai nyeri kronik juga disebut sebagai nyeri neuropatik serta nyeri psikologik atau nyeri idiopatik. Nyeri akut atau nosiseptif yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan, merupakan salah satu signal untuk mempercepat perbaikan dari jaringan yang rusak.3 Sedangkan nyeri neuropatik disebut sebagai nyeri fungsional merupakan proses sensorik abnormal yang disebut N DEXA MEDIA No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 juga sebagai gangguan sistem alarm.3 Nyeri idiopatik yang tidak berhubungan dengan patologi baik neuropatik maupun nosiseptif dan memunculkan simptom gangguan psikologik memenuhi somatofovrm seperti stres, depresi, ansietas dan sebagainya.4,5 Dalam tulisan ini dibahas nyeri neuropatik dan penanggulangannya dengan penggunaan obat antiepilepsi lamotrigine. Neuropatologi dan Mekanisme Nyeri Neuropatik Nyeri neuropatik yang didefinisikan sebagai nyeri akibat lesi jaringan saraf baik perifer maupun sentral bisa diakibatkan oleh beberapa penyebab seperti amputasi, toksis (akibat khemoterapi) metabolik (diabetik neuropati) atau juga infeksi misalnya herpes zoster pada neuralgia pasca herpes dan lainlain. Nyeri pada neuropatik bisa muncul spontan (tanpa stimulus) maupun dengan stimulus atau juga kombinasi.6 Nyeri neuropatik juga disebut sebagai nyeri kronik berbeda dengan nyeri akut atau nosiseptif dalam hal etiologi, patofisiologi, diagnosis dan terapi. Nyeri akut adalah nyeri yang sifatnya self-limiting dan dianggap sebagai proteksi biologik melalui signal nyeri pada proses kerusakan jaringan. Nyeri pada tipe akut merupakan simptoma akibat kerusakan jaringan itu sendiri dan berlokasi disekitar kerusakan jaringan 163 ARTIKEL UTAMA dan mempunyai efek psikologis sangat minimal dibanding dengan nyeri kronik. Nyeri ini di picu oleh keberadaan neurotransmiter sebagai reaksi stimulasi terhadap reseptor serabut alfa-delta dan C polimodal yang berlokasi di kulit, tulang, jaringan ikat otot dan organ viskera. Stimulus ini bisa berupa mekhanik, kimia dan termis, demikian juga infeksi dan tumor.6,7 Reaksi stimulus ini berakibat pada sekresi neurotransmiter seperti prostaglandin, histamin, serotonin, substansi P, juga somatostatin (SS), cholecystokinin (CCK), vasoactive intestinal peptide (VIP), calcitoningenen-related peptide (CGRP) dan lain sebagainya.8 Nyeri neuropatik adalah non-self-limiting dan nyeri yang dialami bukan bersifat sebagai protektif biologis namun adalah nyeri yang berlangsung dalam proses patologi penyakit itu sendiri.6 Nyeri bisa bertahan beberapa lama yakni bulan sampai tahun sesudah cedera sembuh sehingga juga berdampak luas dalam strategi pengobatan termasuk terapi gangguan psikologik. Baik nyeri neuropatik perifer maupun sentral berawal dari sensitisasi neuron sebagai stimulus noksious melalui jaras nyeri sampai ke sentral. Bagian dari jaras ini dimulai dari kornu dorsalis, traktus spinotalamikus (struktur somatik) dan kolum dorsalis (untuk viskeral), sampai talamus sensomotorik, limbik, korteks prefrontal dan korteks insula.6 Karakteristik sensitisasi neuron bergantung pada: meningkatnya aktivitas neuron; rendahnya ambang batas stimulus terhadap aktivitas neuron itu sendiri misalnya terhadap stimulus yang nonnoksious, dan luasnya penyebaran areal yang mengandung reseptor yang mengakibatkan peningkatan letupan-letupan dari berbagai neuron.6 Sensitisasi ini pada umumnya berasosiasi dengan terjadinya denervasi jaringan saraf akibat lesi ditambah dengan stimulasi yang terus menerus dan inpuls aferen baik yang berasal dari perifer maupun sentral dan juga bergantung pada aktivasi kanal ion di akson yang berkaitan dengan reseptor AMPA/kainat dan NMDA.9 Sejalan dengan berkembangnya penelitian secara molekuler maka ditemukan beberapa kebersamaan antara nyeri neuropatik dengan epilepsi dalam hal patologinya tentang keterlibatan reseptor misalnya NMDA dan AMPA dan plastisitas disinapsis, immediate early gene changes. Yang berbeda hanyalah dalam hal burst discharge secara paroksismal pada epilepsi sementara pada neuropatik yang terjadi adalah ectopic discharge. Nyeri neuropatik muncul akibat proses patologi yang berlangsung berupa perubahan sensitisasi baik perifer maupun sentral yang berdampak pada fungsi sistem inhibitorik serta gangguan interaksi antara somatik dan simpatetik. Keadaan ini memberikan gambaran umum berupa alodinia dan hiperalgesia.10 Permasalahan pada nyeri neuropatik adalah menyangkut terapi yang berkaitan dengan kerusakan neuron dan sifatnya ireversibel. Pada umumnya hal ini terjadi akibat proses apoptosis yang dipicu baik melalui modulasi intrinsik kalsium di neuron sendiri maupun akibat proses inflamasi sebagai faktor ekstrinsik.6 Kejadian inilah yang mendasari konsep nyeri kronik yang ireversibel pada 164 sistem saraf. Atas dasar ini jugalah maka nyeri neuropatik harus secepat mungkin di terapi untuk menghindari proses mengarah ke plastisitas sebagai nyeri kronik.6 Penanggulangan Nyeri neuropatik merupakan masalah dalam dunia kedokteran karena bukan hanya menyangkut kerusakan atau lesi dari jaringan saraf itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut efek dari penderitaan yang kronik terhadap quality of life si penderita. Nyeri neuropatik yang tergolong dalam nyeri kronik menimbulkan tantangan yang berat dalam hal pengobatan karena tidak berespons terhadap pengobatan nyeri tradisional. Oleh sebab itu penanggulangan nyeri neuropatik membutuhkan tim yang multi disipliner baik menyangkut terapi non-farmaka maupun terapi farmaka. Penanggulangan secara farmakologik bukan hanya sebatas pada tingkat reseptor dan perbaikan lesi jaringan saraf saja, tapi juga yang berkaitan dengan efek kronik dari nyeri tersebut misalnya efek psikologik.11 Penelitian tentang nyeri termasuk klasifikasi berkembang terus. Sejajar dengan itu maka penelitian untuk menemukan obat juga berkembang tidak henti-hentinya. Antiepilepsi sebagai terapi Nyeri Neuropatik Seperti diketahui dari sejumlah hasil penelitian baik itu malalui hewan percobaan maupun pada manusia ditemukan bahwa nyeri neuropatik mendasar pada kelainan jaringan saraf yang mengakibatkan perobahan komposisi biokimiawi atau neurotransmiter terhadap sistem saraf perifer maupun di sentral.12,13 Oleh sebab itu, penanggulangan nyeri neuropatik juga mendasar pada kelainan atau patologi jaringan saraf yang disertai oleh perobahan pada biokimiawi atau neurotransmiter baik di perifer maupun di sentral. Dengan kata lain tindakan yang memfokus pada pengurangan input neuronal dengan tujuan mengembalikan ke keadaan normal dengan cara menekan fungsi akson misalnya memblok kanal natrium atau mengurangi sekresi eksitatorik serta meningkatkan sekresi inhibitorik.14 Penggunaan obat antiepilepsi pada nyeri neuropatik didasari oleh keidentikan dalam hal neuropatofisiologik pada nyeri neuropatik dan epilepsi.15 Secara neurofarmakologi molekuler, diketahui bahwa standar penanggulangan epilepsi mendasar pada blok kanal natrium, sementara obat-obat antiepilepsi yang baru selain blok kanal natrium juga blok kanal Ca2+ secara spesifik di post sinaptik, yakni reseptor NMDA dan AMPA, stimulasi sekresi GABA di presinaptik, reduksi sekresi glutamate di presinaptik. Hal ini juga telah dibuktikan melalui beberapa penelitian. Dengan demikian disimpulkan bahwa obat antiepilepsi digunakan juga sebagai obat standar untuk nyeri neuropatik.12,13 Epilepsi dan nyeri neuropatik timbul karena munculnya aktivitas abnormal dari sistem saraf sentral. Patologi nyeri neuropatik mendasar pada sensitisasi perifer, ectopic discharge, sprouting, dan berakhir pada kelainan patologi di neuron berupa sensitisasi dan disinhibisi sentral. Epilepsi yang dipicu DEXA MEDIA No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL UTAMA oleh hipereksitabilitas sistem saraf sentral mengakibatkan bangkitan spontan dan paroksismal dan mirip dengan nyeri spontan dan paroksismal pada nyeri neuropatik.16 Dalam keadaan ini peran reseptor NMDA terhadap influks Ca2+ merupakan proses dasar terhadap kindling pada epilepsi serupa halnya dengan kejadian wind-up pada nyeri neuropatik. Atas dasar patologi ini maka antiepilepsi merupakan obat yang berkemampuan untuk menekan kepekaan yang abnormal dari neuron-neuron di sistem saraf pusat dengan memblokade reseptor NMDA, AMPA/kainat.16 Hal ini disimpulkan oleh Markman and Dworkin, (2006)17 bahwa permasalahan nyeri neuropatik adalah di kanal ion sebagaimana juga pada epilepsi. Oleh sebab itu target terapi adalah tertuju pada voltage-gate kanal Na+ dan Ca2+.17 Dari hasil penelitian ternyata bahwa obat antiepilepsi seperti lamotrigine mempunyai sifat analgesik dalam lingkup yang luas. Lamotrigine membatasi influks kalsium melalui penekanan voltage-gate.18 Pada percobaan hewan menyangkut hiperalgesia pemberian lamotrigine berefek sebagai analgesik.19 Lamotrigine dengan dosis di atas 200 mg/hari sangat efektif dalam penanggulangan nyeri neuropatik terutama trigeminal neuralgia, nyeri neuropatik pada penderita HIV, nyeri sentral pada penderita post stroke ataupun nyeri neuropatik yang intracktable.12,13,20-23 Prinsip kerja dari lamotrigine yang diketahui sampai sekarang ini berperan aktif terhadap neurotransmiter eksitatorik glutamate dalam hal mencegah sekresi glutamate di presinaptik serta berperan dalam inhibisi reuptake serotonin oleh presinaptik yang berefek pada stabilisasi membrane sel neuron dengan memblok aktivitas kanal voltage-sensitive natrium.24,25 Efek samping bisa muncul dengan dosis tinggi berupa dizziness, ruam, mual, insomnia.26 Kesimpulan Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang sangat sulit diterapi dengan obat analgesik biasa. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya kerusakan jaringan saraf baik di perifer maupun di sentral. Oleh karena nyeri neuropatik bukan nyeri adaptif akan tetapi merupakan proses patologi yang berjalan di mana adanya perubahan struktur reseptor di membrane neuron baik itu di perifer maupun di sentral. Kelainan reseptor ini mengakibatkan perubahan pada influks dan dari ion-ion seperti kalsium, natrium yang berperan dalam perobahan elektrik potensial saraf. Perubahan ini merupakan signal berupa stimulus yang akan sampai ke korteks sensorik yang diterjemahkan dengan nyeri. Obat antiepilepsi berperan sebagai inhibitorik terhadap reseptor NMDA maupun AMPA/kainat akibat peran glutamate dengan demikian mencegah masuknya ion kalsium dan natrium yang berlebihan ke dalam sel. Mendasar pada cara kerja dari obat antiepilepsi ini maka obat antiepilepsi ini digunakan sebagai standard obat nyeri neuropatik yang secara neuropatologik mempunyai kesamaan dengan epilepsi. Penggunaan lamotrigine yang pada awalnya sebagai antiepilepsi, sekarang ini digunakan sebagai analgesik DEXA MEDIA No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 adjuvant untuk nyeri neuropatik. Hal ini telah terbukti karena lamotrigine berperan dalam inhibisi ion natrium, juga inhibisi sekresi glutamat serta sekresi GABA yang berefek terhadap stabilisasi membrane neuron. Daftar Pustaka 11. Pain Terms: a list with definitions and notes on usage. Pain 1979;6:49-252 12. Merksey H, Bogduk N, editors. Classification of chronic pain: description of chronic pain syndromes and definition of pain terms. 2nd edition. Seattle: International Association for the Study of Pain;1994 13. Woolf CJ. Pain: Moving from symptom control towards mechanisms- specific pharmacologic management. Ann Internal Med 2004;140:441-51 14. Eccleston C. Role of psychology in pain management. Br J Anaestesia 2001;87:144-52 15. Ludwick-Rosenthal R and Neufeld R. Stress management during noxious medical procedures. Psychological Bulletin 1988;104:326-42 16. Helme RD. Drug treatment of neuropathic pain. Austr Prescr 2006;29:72-5 17. Price DD and Harkins SW. Combined use of experimental pain and visual analogue scale in providing standardized measurement of clinical pain. Clin J Pain 1987;3:1-8 18. Agnati LF, Tiengo M, Ferragutti F. Pain, analgesia, and stress: an integrated view. Clin J Pain 1991;7(S):S23-S37 19. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, et al. Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanisms, and treatment recommendations. Arch Neurol 2003;60:1524-34 10. Dogrul A, Gardell LR, Ossipov MH, et al. Reversal of experimental neuropathic pain by t-type calcium channel blockers. Pain 2003;105:159-68 11. Teng J and Makhael N. Neuropathic pain: Mechanisms and treatment option. Pain Practice 2003;3:388-98 12. Backonja MM. Use of anticonvulsants for treatment of neuropathic pain. Neurology 2002; 59:S14-S17 13.Tremont-Lukts IW, Megeff C, Backonja MM. Anticonvulsants for neuropathic pain syndromes : mechanisms of action and place in therapy. Drugs 2000;60:1029-52 14. Finnerup NB, Otto M, Mc Quuay HJ, et al. Algorithm for neuropathic pain treatment: and evidence based proposal. Pain 2005; 118:289-305 15. Attal N. Antiepileptic drugs in the treatment of neuropathic pain. Ex Rev Neurotherapeut 2001;1:199-206 16. Chong MS, Smith TE. Anticonvulsants for the management of pain. Pain Rev 2000;7:129-49 17. Markman JD and Dworkin RH. Ion channel targets and treatment efficacy in neuropathic pain. J Pain 2006;7:S38-S47 18. Wang SJ, Shira TS, Gean PW. Lamotrigine inhibition of glutamate release from isolated cerebrocortical nerve terminals (sinaptosomes) by suppression of voltageactivated Ca2+ channels activity. Neuroreport 2001;12:2255-8 19. Von WagenerJ, Hesslinger B, Berger M, et al. A Ca2+ antagonistic effect of the new antiepileptic drug lamotrigeine. Eur Neuropsychopharmacol 1997;7:77-8 20. Devulder J, De Laat M. Lamotrigine in the treatment of chronic refractory neuropathic pain. J Pain Symptom Manage 2000;19:398-403 21. Kelompok studi Nyeri Perhimpunan Dokter spesialis saraf Indonesia (PErDOssI). Konsensus Nasional Penanganan Nyeri Neuropatik. Dalam: Meliala L, Suryamiharja A, Purba JS (Eds.) 2000.p.15, PERDOSSI, Jakarta 22. Vestergaard K, Andersen G, Gottrup H, et al. Lamotrigine for central poststroke pain: a randomized controlled trial. Neurology 2001;56:184-90 23. Zarzewska JM, Chaudry Z, Nurmikko TJ, et al. Lamotrigine in refractory trigeminal neuralgia in Ms patients. Neurology 2000;55:1587-88 24. Di Vadi PP, Hamann W. The use of lamotrigine in neuropathic pain. Anastesia 1998;53:808-9 25. Eisenberg E, Shifrin A, Krivoy N. Lamotrigine for neuropathic pain. Expert Rev Neurother 2005;5:729-35 26. Elsworth, Allan J (Eds.). Mosby’s Medical Drug reference. St Louis, MO; Mosby, Inc, 1999. 165 SEKILAS PRODUK Lamictal mengandung Lamotrigine 50 mg dan 100 mg. Lamictal sudah digunakan di dunia oleh lebih dari 5 juta orang lebih dari 15 tahun dan dilaunch di Indonesia pada bulan Desember 1994 dengan indikasi obat anti-epilepsi (AED). Lamictal adalah AED yang dapat digunakan sebagai monoterapi maupun kombinasi dengan AED lain. Indikasi Lamictal yang didaftarkan adalah untuk: - Partial seizures (simple dan kompleks) - Secondary general tonic-clonic seizure - Primary general tonic-clonic seizure - Lennox-Gastaut syndrome Epilepsi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penghambatan neurotransmitters. Lamictal bekerja dengan menstabilkan membran saraf dengan cara menghambat saluran natrium dan mengurangi pelepasan neurotransmitter glutamat. Glutamat diketahui sebagai penyebab utama dalam epileptogenesis 1,2. 3.0 160 140 2.0 120 100 80 1.0 60 40 20 0 30 60 Dose (mg) 120 240 0 Hubungan linear antara dosis Lamictal dan konsentrasi plasma membuat tidak diperlukannya monitoring konsentrasi plasma berulang untuk identifikasi dosis individu. Titrasi dosis dapat berdasarkan respons daripada konsentrasi plasma darah. Monitoring terapi obat yang rutin tidak dianjurkan pada penggunaan Lamictal. Bioavailabilitas Lamictal setelah administrasi 75 mg dosis tunggal adalah 98%3. Konsentrasi plasma tertinggi tercapai dalam waktu 1 – 3 jam. Absorpsi tidak dipengaruhi oleh makanan, oleh karena itu pasien dapat minum obat sebelum atau setelah makan. Beberapa dokter menyadari perlunya monitoring konsentrasi plasma pada penggunaan carbamazepine atau phenytoin5. Carbamazepine menunjukkan farmakokinetik non-linear dan phenytoin menunjukkan hubungan konsentrasi erratic, pada penggunaan dosis tinggi memperlihatkan peningkatan konsentrasi plasma yang tidak terkontrol. Lamictal memiliki farmakokinetik linear dengan margin dosis terapi, interaksi dengan obat lain yang rendah dan eliminasi watu paruh yang panjang (rata-rata 29 jam)3,4. Antara individu yang satu dengan yang lain dapat terjadi perbedaan waktu eliminasi obat, hal ini disebabkan adanya perbedaan pada klirens metabolisme pada masing-masing individu. Kesimpulannya Lamictal memberikan keuntungan pada pasien penderita epilepsi, yaitu: - Telah digunakan oleh jutaan orang di dunia untuk mengatasi gangguan kejang - Memiliki profil tolerabilitas yang baik - Tidak memerlukan blood monitoring - Absorpsi tidak dipengaruhi oleh makanan Lamictal menunjukan farmakokinetik linear setelah pemberian oral dosis tunggal 30 – 450 mg pada sukarelawan sehat dan pasien yang menerima obat sebagai monoterapi atau kombinasi (add-on)3. Lamictal dalam plasma meningkat berbanding lurus dengan dosis Lamictal (gb.1). Lamictal dapat diberikan sebagai monoterapi dan kombinasi (add-on) - Monoterapi untuk pasien epilepsi dari usia 12 tahun hingga dewasa. - Kombinasi untuk epilepsi anak dari usia 2 tahun. 166 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 SEKILAS PRODUK Dosis Lamictal untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun: Minggu 1 & 2 Minggu 3 & 4 Dosis Pemeliharaan add-on Lamictal dengan sodium valproate 12,5 mg/hari 25 mg/hari (diberikan 25 mg/hari (sekali sehari) 2 hari sekali/selang sehari) 100-200 mg/hari (sekali sehari atau di bagi dalam 2 kali pemberian) Monoterapi Lamictal 25 mg/hari (sekali sehari) 50 mg/hari (sekali sehari) 100-200 mg/hari (sekali sehari atau di bagi dalam 2 kali pemberian) add-on Lamictal tanpa sodium valproate 50 mg/hari (sekali sehari) 100 mg/hari (sekali sehari) 200-400 mg/hari (di bagi dalam 2 kali pemberian) Dosis Lamictal untuk anak-anak dari usia 2 – 12 tahun: Minggu 1 & 2 Minggu 3 & 4 Dosis Pemeliharaan Add-on Lamictal dengan sodium valproate 0,2 mg/kg/hari (sekali sehari) 0,5 mg/kg/hari (sekali sehari) 1-5 mg/kg/hari (sekali sehari atau di bagi dalam 2 kali pemberian) Monoterapi Lamictal 0,5 mg/kg/hari (sekali sehari) 1 mg/kg/hari (sekali sehari) 2-10 mg/kg/hari (sekali sehari atau di bagi dalam 2 kali pemberian) Add-on Lamictal tanpa sodium valproate 2 mg/kg/hari (di bagi dalam 2 kali pemberian) 5 mg/kg/day di bagi dalam 2 kali pemberian) 5-15 mg/kg/hari (di bagi dalam 2 kali pemberian) No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Dosis titrasi pada Lamictal dapat meminimalkan insiden terjadinya rash. Rash yang terlihat pada penggunaan Lamictal dapat berupa reaksi kelainan kulit dari yang ringan hingga berat dengan kejadian 2% dari yang diterapi. Sedangkan yang menghentikan terapi kurang dari 3% pasien. Referensi: 1. Leach MJ et al. Lamotrigine: mechanism of action. In: Levy RH et al (eds). Antiepileptic Drugs (4th ed.). New York Raven Press; 1995. p.861 – 69 2. Xinmin X et al. Interaction of the antiepileptic drug lamotrigine with recombinant rat type IIA Na+ channels and with native Na+ channels in rat hippocampal neurones. Pflugers Arch – Eur J Physiol 1995; 430: 437 – 46 3. Pisani F. In: Reynolds EH (ed). Lamotrigine – a new advance in the treatment of epilepsy. London Royal Society of Medicine Service; 1993, p.15-24. 4. Cohen AF et al. Lamotrigine, a new anticonvulsant: pharmacokinetics in normal humans. Clin Pharmacol Ther 1987; 42 (suppl 5): 535 – 41 5. Pugh CB, Garnet WR. Current issues in the treatment of epilepsy. Clin Pharm 1991; 10; 335 – 58 167 TINJAUAN PUSTAKA Tatalaksana Farmakologis Gangguan Spektrum Autistik: Telaah Pustaka Terkini Rizaldy Pinzon SMF Saraf RSUD Dr. M. Haulussy Ambon Abstrak. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif. Penelitian terdahulu menunjukkan kelainan neurotransmiter pada autisme. Penatalaksanaan farmakologis dengan prinsip menyeimbangkan fungsi neurotransmiter merupakan dasar pendekatan terapi yang rasional. Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan terapi antagonis sistem dopaminergik, pemacu sistem serotoninergik, antagonis opioid, dan pemacu GABA. Beberapa modalitas terapi lain seperti penggunaan suplemen vitamin dan mineral dan penggunaan terapi imunologis telah dilaporkan pula. Hasil kajian sistematis ini mendapatkan bahwa antagonis sistem dopaminergik merupakan modalitas terapi yang cukup didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang baik. Kata kunci: Autisme, treatment, randomized controlled trial, dopamine, serotonin, GABA (Gammaaminobutyric acid) Pendahuluan utisme merupakan gangguan perkembangan yang terutama ditandai oleh ketidakmampuan dalam komunikasi, sosialisasi, dan imajinasi.1 Penderita autisme akan menunjukkan disabilitas dalam interaksi sosial, disabilitas komunikasi dan kelambatan fungsi berbahasa, perilaku yang terbatas dan stereotipik, dengan onset sebelum usia 3 tahun.2 Tatalaksana farmakologis tidak akan mengubah riwayat keadaan atau perjalanan gangguan autistik.3 Terapi farmakologi bukan merupakan pendekatan terapi yang utama, namun penggunaan terapi farmaka untuk gejala-gejala tertentu dapat membantu secara signifikan program terapi dan edukasi.4 Penggunaan terapi farmakologis yang memperbaiki keseimbangan neurotransmiter merupakan pendekatan yang rasional pada penderita autisme.3 Kajian Rapin4 menunjukkan bahwa obat-obat diberikan secara spesifik untuk gejala tertentu sebagai berikut: (1) obat yang bekerja sistem noradrenergik terutama ditujukan untuk mengatasi gejala agresif dan perilaku eksplosif, (2) obat-obat antidepresan dan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ditujukan untuk mengatasi obsesif, agresivitas, dan depresi, (3) obatobat penghambat dopamin ditujukan untuk gejala destruktif, agresi, dan melukai diri sendiri, (4) obat-obat antagonis opioid untuk gejala stereotipik dan melukai diri sendiri, (5) golongan antikonvulsan untuk mengobati epilepsi, agresivitas, dan regresi yang berhubungan dengan gelombang epileptiformis subklinis. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bukti ilmiah tatalaksana farmakologis gangguan spektrum autistik. Tujuan penulisan makalah adalah mengkaji secara A No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 kritis bukti-bukti ilmiah terapi farmaka untuk autisme. Metode Pelacakan Kepustakaan Pelacakan kepustakaan dilakukan dengan menggunakan internet, MEDLINE database, dan pelacakan manual pada berbagai penelitian dan kajian tentang tatalaksana farmakologis autisme dengan tahun publikasi 1995-2003. Kata kunci yang dipergunakan adalah: autism, treatment, randomized controlled trial, mechanism, dan pathophysiology. Tingkat Bukti Ilmiah Penetapan tingkat bukti ilmiah terhadap berbagai penelitian terapi yang ada didasarkan sesuai dengan panduan Scotish Intercollegiate Guidelines Network5 sebagai berikut: Tabel 1. Derajat bukti ilmiah artikel terapi (SIGN, 2000) Levels Kejadian Deskripsi IA Bukti diambil dari suatu penelitian meta-analysis IB Bukti diambil minimal dari suatu penelitian randomized controlled trial IIA Bukti diambil minimal dari suatu penelitian welldesigned controlled study without randomization IIB Bukti diambil minimal dari suatu penelitian tipe lain dari well-designed quasi-experimental III Bukti diambil minimal dari suatu penelitian well-designed non-experimental descriptive, seperti comparative studies, correlation studies dan case studies IV Bukti diambil dari suatu laporan komite ahli dan/atau pengalaman klinis pakar 169 TINJAUAN PUSTAKA Pembahasan Hasil Pelacakan Pustaka Hasil pelacakan kepustakaan secara manual dan elektronik mendapatkan berbagai artikel terapi farmakologis untuk autisme. Tabel 2 memperlihatkan berbagai artikel yang diperoleh dan tingkat bukti ilmiahnya, sbb: Tabel 2. Peringkat bukti ilmiah hasil pelacakan pustaka Peneliti (tahun) Fankhauser (1992) Jaselskis (1992) Sophie (1996) Delong (1998) McDougle (1998) Fatemi (1998) Owley dkk (1999) Sandler (1999) Adams (2000) Pertejo (2000) Lightdale (2001) Roberts (2001) McCracken (2002) Chez (2002) DeLong (2003) Nye (2004) Modalitas terapi Derajat bukti ilmiah Clonidine Clonidine Naltrexone Fluoxetine Risperidone Fluoxetine Secretin Secretin Suplemen vitamin dan mineral Fluoxetine Secretin Secretin Risperidone L-Carnosine Fluoxetine Vitamin B6-Magnesium IB IIA IB IIB IB III IB IB IB IIB IIB IB IB IB IIB IA Antagonis Dopamin Tipikal (haloperidol) Sistem dopaminergik berperan dalam pengaturan perilaku motorik. Dopamin yang berlebih akan menyebabkan munculnya gerakan motorik berlebih, stereotipik seperti yang diamati pada penderita autisme. Penggunaan antagonis dopamin diharapkan memperbaiki gejala-gejala motorik seperti hiperaktivitas dan stereotipik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif.6 Obat-obat neuroleptik merupakan golongan obat yang secara luas digunakan pada autisme. Tabel 3 menunjukkan kajian terhadap penggunaan haloperidol dalam terapi autisme. Tabel 3. Uji klinik haloperidol untuk terapi autisme6 Peneliti (tahun) Rancangan Dosis Subjek Hasil 40 anak autisme, - Terdapat perbaikan dalam skor Corner usia antara 2-7 Parent-Teacher Questonaire, Global tahun Improvement, dan Children's Rating Scale - Penurunan perilaku maladaptif - 36 tetap meneruskan haloperidol Anderson Uji klinik (1984) randomisasi, double blind cross over 0,5–3,0 mg/hari Anderson Uji klinik (1988) randomisasi, double blind, cross over 0,25-0,40 45 anak autisme, - Terdapat perbaikan dalam skor Corner mg/hari usia antara 2-7 Parent-Teacher Questonaire, Global tahun Improvement, dan Children's Rating Scale - Penurunan hiperaktivitas dan stereotipik Efek samping utama penggunaan haloperidol adalah diskinesia. Diskinesia muncul pada 25% kasus setelah 11 bulan terapi, dan 75% kasus setelah 3,5 tahun terapi.6 Antagonis Dopamin Atipikal Antipsikotik atipikal memblokade pula reseptor serotonin postsinaptik, sehingga melindungi terhadap munculnya efek samping ekstrapiramidal.7 Penelitian uji klinik dengan 170 randomisasi dilakukan oleh McDougle, dkk8 pada 31 penderita gangguan autisme dewasa. Respon terapi diukur dengan Global Improvement Scale dengan skala likert. Perbaikan gejala didapatkan secara bermakna pada kelompok terapi risperidone dibanding plasebo (57% VS 0%, p <0,002). Penelitian uji klinik acak buta ganda (randomized clinical trial) risperidone lebih baru dilakukan oleh McCracken, dkk7 dengan subjek 101 anak autisme yang berusia antara 2-8 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon positif secara bermakna didapatkan pada kelompok terapi risperidone dibanding kelompok plasebo (69% vs 12%, p<0,01). Tabel 4 menunjukkan karakteristik dan hasil penelitian uji klinik penggunaan Risperidone untuk terapi autisme. Tabel 4. Hasil penelitian terapi risperidone pada autisme Peneliti (tahun) Metode Subjek Hasil McDougle RCT dengan dosis (1998) risperidone harian 2,9 ±1,4 mg/hari 31 penderita - Perbaikan gejala didapatkan secara autisme dewasa bermakna pada kelompok terapi Risperidone dibanding plasebo (57% vs 0%, p<0,002) McCracken RCT dengan dosis (2002) risperidone harian 0,25 mg/hari - Respon positif secara bermakna didapatkan 101 anak dengan autisme pada kelompok terapi risperidone dibanding kelompok plasebo (69% vs 12%, p<0,01) - Efek samping utama sedasi ringan Penelitian McCracken, dkk7 memperlihatkan terjadinya efek samping akibat terapi yang ringan, yang akan menghilang dengan sendirinya setelah beberapa minggu. Efek samping konstipasi, pandangan kabur, mulut kering, dan mengantuk disebabkan oleh perangsangan sistem antikolinergik. Perangsangan anti histamin akan menyebabkan penambahan berat badan dan mengantuk. Sifat antagonistik pada reseptor alfa satu akan menyebabkan penurunan tekanan darah, dizziness, dan mengantuk.9 Opioid Kadar opiat yang tinggi dalam LCS dan urine sering dijumpai pada penderita autisme. Opioid dalam konsentrasi yang tinggi akan menghambat faktor pertumbuhan neuronal. Opioid berperan pula dalam perilaku maladaptif, seperti impulsivitas, perilaku berisiko abnormal, gangguan belajar, gangguan perhatian, dan gangguan mood. Pasien-pasien dengan perilaku melukai diri sendiri sering mengalami insensitivitas nyeri. Penderita dengan perilaku melukai diri sendiri cenderung menunjukkan peningkatan kadar metenkephalin dan β endorfin plasma.10 Sophie, dkk11 melakukan penelitian uji klinik pada 23 anak autisme (usia berkisar antara 3-7 tahun). Terapi naltrexone diberikan dengan dosis 1 mg/kgBB selama 4 minggu. Efek terapi dipantau dengan kuisioner yang diisi oleh orang tua dan guru, serta observasi saat bermain. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa para guru melaporkan adanya perbaikan perilaku (hiperaktivitas dan iritabilitas) secara signifikan. Pemberian naltrexone tidak memperbaiki kontak sosial dan perilaku stereotipik. Kajian Perry dan Kuperman6 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA menyatakan bahwa penggunaan naltrexone tidak dianjurkan sebagai terapi lini pertama untuk autisme. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Obat-obat Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) bekerja terutama pada terminal akson pre sinaptik dengan menghambat ambilan kembali serotonin. Hal tersebut akan menyebabkan serotonin bertahan lebih lama di celah sinaps.9 Tabel 5 memperlihatkan penelitian penggunaan fluoxetine dalam terapi autisme. Tabel 5. Penelitian-penelitian penggunaan fluoxetine untuk terapi autisme Peneliti (tahun) Disain Cook, dkk Open label trial fluoxetine 20-80 mg/hari 23 penderita Perbaikan pada Global autisme Clinical Impressions pada 15 (65%) subjek DeLong, dkk13 Open label trial fluoxetine 37 anak autisme usia antara 2-7 tahun Perbaikan pada Independent Developmental Testing pada 22 (59%) subjek Fatemi, dkk14 fluoxetine 20-80 mg/hari 7 pasien usia 9-20 tahun Perbaikan Abberant Behaviour Checklist dalam hal iritabilitas 21%, letargi 37%, stereotipik 27%, dan gangguan bicara 21% fluoxetine 0,15-0,5 mg/kg 129 anak autisme (2-8 tahun) 12 Kajian data retrospektif DeLong, dkk15 Open label trial (post hoc analysis) selamarata-rata 32-36 bulan Terapi Subjek Tabel 6. Kajian hasil penelitian penggunaan secretin sebagai terapi autisme Peneliti (tahun) Sandler17 Penelitian Buchsbaum, dkk16 mengukur efek pemberian fluoxetine terhadap aliran darah regional dan tingkat metabolisme otak. Penelitian dilakukan pada 6 pasien dewasa dengan autisme dengan penggunaan possitron emission tomography. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat metabolisme di regio frontal kanan (terutama gyrus cinguli anterior dan korteks orbito-frontal) pada penderita yang diberikan terapi fluoxetine. Secretin Secretin merupakan suatu hormon peptida yang terdiri dari 27 asam amino yang befungsi untuk menstimulasi sekresi pankreas. Penggunaan secretin sebagai terapi autisme dimulai pada saat muncul laporan kasus serial tentang efek secretin. Laporan tersebut menyebutkan adanya perbaikan gejala pada beberapa penyandang autisme yang menjalani pemeriksaan fungsi gastrointestinal dengan Secretin.17 Tabel 6 memperlihatkan telaah hasil-hasil penelitian secretin dalam terapi autisme. Terapi farmakologi bukan merupakan pendekatan terapi yang utama, namun penggunaan terapi farmaka untuk gejalagejala tertentu dapat membantu secara signifikan program terapi dan edukasi. No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Subjek RCT 60 anak autisme Hasil - Tidak ada perubahan bermakna pada skorAutism Behavior Checklist dan Clinical Global Impression Scale - Tidak didapatkan efek samping Owley RCT 20 anak autisme, usia antara 3-12 tahun Lightdale, dkk19 Penelitian prospektif open label 20 penderita autisme, usia rata-rata 5 tahun 18 Hasil penelitian Respon pada Autism Disgnostic Observation Schedule - Sangat baik pada 17% kasus - Baik pada 52% kasus - Buruk pada 31% kasus Metode Roberts20 RCT 64 anak autisme, usia antara 2-7 tahun Tidak berbeda bermakna antara kelompok terapi dan plasebo dalam skor komunikasi sosial setelah 4 minggu terapi (p=0,74) - Tidak dijumpai perbaikan bermakna pada fungsi berbahasa dan perilaku - 70% orang tua secara subjektif melaporkan adanya perbaikan gejala setelah infus secretin Tidak ada beda efek terapi yang berbeda bermakna pada fungsi kognitif, perilaku, dan gejala gastrointestinal antara kedua kelompok Obat Antiepilepsi pada Autisme Epilepsi dan abnormalitas gelombang otak sering dijumpai pada penderita autisme. Kajian Martino dan Tuchman21 memperkirakan adanya hubungan antara adanya epilepsi dan gelombang otak abnormal dengan gangguan fungsi kognitif, berbahasa, perilaku, dan mood. Terminologi yang sering dipergunakan adalah Transient Cognitive Impairment untuk menunjukkan gangguan adaptif fungsi serebral akibat gelombang epileptiform di otak. Gelombang paku (spike) fokal interiktal dapat mengganggu fungsi kortikal sesuai dengan lokasi munculnya spike tersebut. Sampai saat ini masih ada kontroversi dalam penggunaan obat antiepilepsi pada kelompok penderita autisme dengan pola EEG yang abnormal tanpa bangkitan epilepsi. Penggunaan antiepilepsi pada penderita autisme ditujukan untuk: (1) mengendalikan bangkitan epilepsi, (2) mengendalikan gelombang abnormal epileptiform, dan (3) memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial. Penggunaan obat anti epilepsi untuk autisme didasarkan pada 2 mekanisme, yaitu: (1) mengatasi bangkitan epilepsi dengan peningkatan GABA, dan (2) perangsangan GABA akan meningkatkan kadar serotonin di sistem limbik.22 Suplemen Vitamin dan Mineral Dasar pemikiran pemberian suplemen vitamin dan mineral pada penderita autisme adalah: (1) penderita autisme sering kali memiliki asupan vitamin dan mineral yang terbatas atau picky eaters, (2) penderita autisme sering kali memiliki fungsi pencernaan yang buruk (25% penderita dengan diare kronik), dan (3) berbagai penelitian terdahulu menunjukkan berkurangnya flora normal usus yang ikut berperan dalam penyerapan vitamin.23 Penelitian terdahulu tentang penggunaan suplemen vitamin dan mineral dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 171 TINJAUAN PUSTAKA Tabel 7. Penelitian terdahulu tentang penggunaan suplemen vitamin dan mineral untuk terapi autisme. Peneliti (tahun) Disain Subjek (n) Terapi Hasil Dolske, dkk (1993) Uji klinik, buta ganda, cross over, 10 minggu 18 Vitamin C, 8 g/70 kg/hari Penurunan subjektif gangguan perilaku dan stereotipik Finding, dkk (1997) Uji klinik, buta ganda, cross over, 4 minggu 10 Vitamin B6 30 mg/kg/hari dan Mg 10 mg/kg/hari Tidak ada perbedaan efek terapi,sampel terlalu kecil Tolbert, dkk (1993) Uji klinik, buta ganda, cross over, 10 minggu 15 Vitamin B6 200 mg/ Tidak ada perbedaan 70kg dan Mg 100 efek terapi mg/ 70 kg Martineau, dkk (1988) Systematic assignment, control group 11 Vitamin B6 30 mg/ kg/hari dan Mg 10 mg/kg/hari Penurunan dopamin di urin, respon klinis tidak jelas dengan skala pengukuran yang tidak sesuai Martineau, dkk (1988) Random assignment 6 Vitamin B6 30 mg/kg/hari dan Mg 10 mg/kg/hari Tidak ada perubahan pada metabolit dopamin di urin Bolman, dkk (1999) Uji klinik, buta ganda, dengan kontrol plasebo 8 Dimethylglisine 125 Tidak ada perubahan mg-350 mg/hari dalam observasi Penggunaan suplemen vitamin dan mineral dalam terapi autisme didasarkan pada pemikiran bahwa vitamin dapat memperkuat aksi neurotransmiter dengan meningkatkan aviabilitasnya dan bertindak sebagai kofaktor. Vitamin C dalam penelitian eksperimental dapat menghambat efek dopamin sentral. Vitamin B6 berperan dalam pembentukan beberapa neurotransmiter seperti serotonin, dopamin, GABA, dan norepinefrin. Dimethylglisine merupakan suplemen nutrisi yang memiliki efek neuroaktif serupa dengan Glysin.24 Penelitian uji klinik double blind oleh Adams, dkk23 melibatkan 18 anak dengan rata-rata umur 5,5 tahun dengan diagnosis klinis autisme. Sebanyak 9 orang anak terdiri atas 8 laki-laki dan 1 perempuan mendapat terapi suplemen multivitamin dan mineral, dan 9 orang lainnya mendapat plasebo. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kadar vitamin C yang berbeda bermakna pada kelompok terapi serta perbaikan dalam pola tidur dan gejala gastrointestinal yang bermakna, namun pada perilaku dan kemampuan bahasa tidak berbeda bermakna (p>0,05) Kajian sistematis yang dilakukan oleh Nye dan Bryce25 menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk penggunaan kombinasi vitamin B6 dan magnesium untuk terapi gangguan spektrum autisme. Hal ini disebabkan karena berbagai penelitian yang ada saat ini memiliki keterbatasan metodologi dan jumlah sampel yang kecil. Kesimpulan Autisme merupakan kelainan yang kompleks, terutama ditandai oleh gangguan fungsi berbahasa, interaksi sosial, dan gangguan perilaku. Penatalaksanaan farmakologis dengan prinsip menyeimbangkan fungsi neurotransmiter merupakan dasar pendekatan terapi yang rasional. Penelitianpenelitian terdahulu menggunakan terapi antagonis sistem dopaminergik, pemacu sistem serotoninergik, antagonis opioid, dan pemacu GABA. Beberapa modalitas terapi lain seperti penggunaan suplemen vitamin dan mineral dan 172 penggunaan terapi imunologis telah dilaporkan pula. Hasil kajian sistematis ini mendapatkan bahwa antagonis sistem dopaminergik merupakan modalitas terapi yang cukup didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang baik. Daftar Pustaka 1. Herman A. Neurobiological insights into infantile autism. The Harvard Brain 1996:9-25 2. Tonge BJ. Autism, autistic spectrum and the need for better definition. MJA 2002;176:412-3 3. Ratcliff J. Treatment and education for autistic and related communication handicapped children. Autism Course Section 5. Bexley; 2002 4. Rapin I. Autism: current concept. N Engl J Med 1997;337(2):97-104 5. SIGN. Classification of evidence levels and grades of recommendation.Scotish Intercolligiate Guideline Network; 2000 6. Perry P, Kuperman S. Pediatric psychopharmacology: autism. Clinical Psychopharmacology Seminar, University of Iowa; 2003 7. McCracken JT, McGough J, Shah B, et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. N Eng J Med 2002; 347(5):314-21 8. McDougle CJ, Holmes JP, et al. A double-blind, placebocontrolled study of risperidone in adults with autistic disorder and other pervasive developmental disorders. Ach Gen Psychiatry 1998;53:633-41 9. Stahl SM. Essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. Cambridge University Press; 2000 10. Villalba R, Harrington C. Repetitive self-injurious behavior: the emerging potential of psychotropic intervention.Psychiatric Times 2003; 20(2) 11. Sophie HN, Swinkels W, et al. the effect of chronic naltrexone treatment in young autistic children: a double-blind placebo controlled crossover trial. Biol Psychiatry 1996;39:1023-31 12. Cook EH, Rowlett R, Jaselkis C. Fluoxetine treatment of children and adults with autistic disorder and mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1992;31(4):734-45 13. DeLong GR, Teagoe LA, Kamran M. Effect of fluoxetine treatment in young children with idiopathic autism. Dev Med Child Neurol 1998; 40(8):551-62 14. Fatemi SH, Realmuto Gm, Khan L, et al. Fluoxetine in treatment of adolescent patients with autism: a longutudinal open trial. J Autism Dev Disord 1998;28(4):303-7 15. DeLongGR, Ritch CR, Burch S. Fluoxetine response in children with autistic spectrum disorders: correlation with familial major affective disorder and intelectual achivement. Dev Med Child Neurol 2002;44(10):652-9 16. Buchsbaum MS, Hollander E, Hazneder MM. Effect of fluoxetine on regional cerebral metabolism in autistic spectrum disorder: a pilot study. Int J Neuropsychopharmacol 2001; 4(2):119-25 17. Sandler AD, Sutton KA, DeWeese J, et al. Lack of benefit of a single dose of synthetic human secretin in the treatment of autism and pervasive developmental disorder. N Engl J Med 1999;341:1801-6 18. Owley T, Steele E, Corsello C, et al. A double-blind, placebocontrolled trial of secretin for the treatment of autistic disorder. Med Gen 1999 19. Lightdale JR, Hayer C, Duer A, et al. Effects of intravenous secretin on language and behaviour of children with autism and gastrointestinal symptoms: a single blinded, open-label pilot study. Pediatrics 2001;108(5) 20. Roberts W, Weaver L, Brian J, et al. Repeated doses of porcine secretin in the treatment of autism: a randomized, placebo-controlled trial. Pediatrics 2001;107(5) 21. Martino AD, Tuchmann RF. Antiepileptic drugs: affective use in autism spectrum disorders. Pediatr Neurol 2001; 25:199-207 22. Esles L. the role of serotonin in autism. University of California;2000 23. Adams JB, Fabes R, Johnston C. Effect of vitamin/mineral supplements on children with autism. Arizona State University; 2000 24. Hyman SL, Levy SE. Autistic spectrum disorders: when traditional medicine is not enough, contemporary. Pediatrics 2000; 10:101-23 25. Nye C, Brice A. Combined vitamin B6-magnesium treatment in autism spectrum isorder (Cochrane review). In: The Cochrane Library. Issue 2. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.; 2004 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Peran serotonin pada Gangguan spektrum Autistik Rizaldy Pinzon*, Lucas Meliala**, Sri Sutarni** * SMF Saraf RSUD Dr. M. Haulussy Ambon ** Bagian IP Saraf FK UGM Abstrak. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif. Penelitian terdahulu menunjukkan kelainan neurotransmiter pada autisme. Telaah pustaka ini membahas peran serotonin pada autisme. Serotonin merupakan neurotransmiter yang berperan besar dalam perkembangan otak. Berbagai penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar penderita autisme adalah hiperserotonemia. Hal ini mungkin berhubungan dengan kadar serotonin yang rendah di sistem limbik, dan penurunan sintesis serotonin di nukleus raphe. Berbagai uji klinik terdahulu menunjukkan bahwa pemberian obat-obat yang meningkatkan serotonin di sistem limbik akan memperbaiki gejala autisme. Kata kunci: Autisme, serotonin, hiperserotonemia, ssrI Pendahuluan utisme merupakan gangguan perkembangan yang terutama ditandai oleh ketidakmampuan dalam komunikasi, sosialisasi, dan imajinasi.1 Terminologi yang sering digunakan adalah gangguan spektrum autistik/ autistic spectrum disorder, yang terdiri dari autisme, sindrom Asperger atau Asperger’s Syndrome, dan Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified/PDD-NOS.2,3 Gangguan spektrum autisme dinyatakan sebagai gangguan dalam empati dan defisit pada fungsi perhatian, kontrol motorik dan persepsi. Penderita autisme akan menunjukkan disabilitas dalam interaksi sosial, disabilitas komunikasi dan kelambatan fungsi berbahasa, perilaku yang terbatas dan stereotipik, dengan onset sebelum usia 3 tahun.2 Berbagai bukti dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disfungsi otak dijumpai pada anak-anak dengan A No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 autisme.1 Faktor genetik diperkirakan berperan penting pada kejadian autisme.1,4 Hal ini didasarkan pada penemuan autisme yang lebih sering pada anak laki-laki dibanding perempuan (4:1).1 Faktor paparan zat kimiawi dianggap berperan pula dalam kejadian autisme. Ada 2 faktor zat kimiawi yang berperan pada autisme dan didukung oleh bukti ilmiah, yaitu pemakaian thalidomide dan antikonvulsan selama kehamilan.4 Saat ini telah disepakati secara luas bahwa autisme merupakan kelainan neurobiologik.1 Pengetahuan tentang aspek neuroanatomi autisme sangat dibantu oleh hasil pemeriksaan histopatologis berbagai penelitian terdahulu. Pengetahuan tentang kelainan neuroanatomi, neurokimiawi, dan perubahan molekuler pada autisme akan membantu dalam formulasi uji diagnosa dan terapi farmakologi pada autisme.5 173 TINJAUAN PUSTAKA Gangguan sistem neurotransmiter sering dijumpai pada penderita autisme, dan berhubungan dengan munculnya gejala gangguan perilaku. Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya disfungsi sistem neurokimiawi pada penderita autisme yang meliputi sistem serotonin, norefinefrin, GABA, dan dopamin.5,6 Gangguan sistem neurokimiawi tersebut berhubungan dengan perilaku agresif, obsesif kompulsif, dan stimulasi diri sendiri (self stimulating) yang berlebih.6 Permasalahan yang ada adalah bagaimana keterlibatan disfungsi sistem serotonin pada gangguan spektrum autistik. Tinjauan pustaka ini secara mendalam akan membahas peran disfungsi sistem serotonin pada autisme. Berbagai terapi farmaka yang bekerja pada sistem serotonin akan dibahas pula. Pembahasan dititikberatkan pada peran obatobat tersebut pada gangguan spektrum autistik. Metode Studi pustaka ini dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai penelitian terkini. Pelacakan kepustakaan dilakukan dengan menggunakan internet, MEDLINE database, dan pelacakan manual pada berbagai penelitian dan kajian tentang hubungan disfungsi serotonin dan autisme. Kata kunci yang dipergunakan adalah: autism, serotonin, antidepressant drugs, treatment, mechanism, dan pathophysiology. Pembahasan Gangguan fungsi serotonin pada penderita autisme Serotonin dikenal juga dengan nama 5-hydroxytryptamine (5HT), suatu neurotransmiter yang dibentuk dari asam amino tryptophan. Serotonin dimetabolisme oleh enzim monoamine oxidase menjadi 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), sebuah metabolit yang dapat digunakan untuk menilai fungsi serotonergik sentral.7 Sistem serotoninergik pada otak manusia terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu pada bagian rostral dan kaudal. Nukleus bagian rostral meliputi nukleus linearis, raphe dorsalis, raphe medialis, dan raphe pontis, yang berproyeksi hampir ke seluruh bagian otak termasuk serebelum. Sementara nukleus bagian kaudal terdiri dari raphe magnus, raphe pallidus, dan raphe obscuris dengan proyeksi yang lebih terbatas pada serebelum, batang otak, dan medula spinalis.7 Serotonin disintesa dari asam amino tryptophan, tryptophan akan dihidroksilasi oleh enzim tryptophan hydroxylase (TPH) menjadi 5-Hydroxytryptophan yang kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi serotonin oleh enzim L-aromatic amino acid decarboxylase. Metabolisme serotonin terutama diperantarai oleh enzim MAO (Mono Amine Oxidase) menjadi 5-hydroxyindoleactic acid (5-HIAA).7 Serotonin yang dilepaskan ke celah sinaps akan mengalami satu atau lebih kejadian berikut: (1) difusi dari sinaps, (2) dimetabolisme oleh enzim MAO, (3) mengaktivasi reseptor 174 presinaptik, (4) mengaktivasi reseptor post sinaptik, dan (5) mengalami ambilan kembali (reuptake) ke pre sinaptik.7 Neurotransmiter serotonin memiliki 14 reseptor yang berbeda berdasar pada susunan protein dan lokasinya. Sebagian reseptor serotonin berperan sebagai autoreseptor (misalnya: 5HT1A dan 5-HT1D), perangsangan autoreseptor akan mengurangi sintesa dan pelepasan serotonin.7 Serotonin berperan dalam perkembangan otak (neurodevelopmental) dengan cara menstimulasi neurogenesis, berperan pada diferensiasi neuronal, perkembangan dendrit, sinaptogenesis, dan mielinisasi akson. Kadar serotonin diatur melalui mekanisme umpan balik, kadar serotonin yang berlebihan akan menghentikan produksi dan pelepasan serotonin.8 Fungsi sistem serotonin di otak ditentukan oleh lokasi sistem proyeksinya. Proyeksi pada korteks frontal diperlukan untuk pengaturan mood, proyeksi pada ganglia basalis bertanggung jawab pada gangguan obsesif kompulsif. Kecemasan dan panik diperantarai oleh fungsi serotonin pada sistem limbik, dan gangguan tidur diperantarai oleh kurangnya serotonin pada pusat tidur di batang otak.9 Kajian Wiznitzer10 menunjukkan bahwa serotonin berperan dalam hal-hal berikut: (1) perkembangan sistem saraf pusat, (2) perilaku sosial, (3) tidur, (4) agresi, (5) ansietas, dan (6) gangguan afektif. Berbagai penemuan yang menunjukkan adanya peran sistem serotonin pada autisme adalah sebagai berikut:(1) dijumpai adanya hiperserotonemia pada 25%-30% kasus autisme, (2) kadar serotonin dalam darah yang lebih tinggi pada saudara kandung penderita autisme, (3) deplesi kadar triptofan akan memperburuk gejala, (4) peningkatan antibodi terhadap reseptor serotonin, (5) fungsi serotonin yang abnormal pada pemeriksaan pencitraan (PET), dan (6) dijumpai adanya perbaikan gejala dengan pemberian Serotonin Selective Reuptake Inhibitor (SSRI) pada penderita autisme.10 Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa disfungsi sistem serotonin pada autisme dapat disebabkan oleh halhal berikut: (1) menurunnya sintesa, (2) menurunnya pelepasan serotonin, (3) peningkatan ambilan kembali, (4) menurunnya sensitivitas postsinaps, dan (5) berkurangnya efek postsinaptik.10 Pada sebagian penderita dijumpai adanya hiperserotonemia. Hiperserotonemia yang terjadi tidak berhubungan dengan peningkatan volume platelet, peningkatan ambilan platelet, peningkatan sintesis 5-HT, dan penurunan katabolisme 5-HT. Pada penderita autisme diamati pula adanya antibodi yang bersirkulasi dan merusak reseptor serotonin. Faktor genetik dianggap berperan besar dalam kejadian hiperserotonemia.1 Penelitian Leboyer, dkk11 pada penderita autisme dan keluarganya memperlihatkan bahwa hiperserotonemia terdapat pada 51% ibu penderita, 45% ayah penderita, dan 87% dari saudara kandung penderita. Peningkatan kadar serotonin di dalam darah (hiperserotonemia) akan menyebabkan penurunan sistesis serotonin No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA di raphe nuclei. Hyperserotonemia pada penderita autisme terutama dijumpai dengan adanya peningkatan serotonin pada platelet. Peningkatan serotonin pada platelet dapat disebabkan oleh karena ambilan atau uptake platelet yang berlebih atau karena pelepasan atau release serotonin dari platelet yang kurang. Kadar serotonin yang kurang di sinaps atau neuron serotoninergik dapat pula disebabkan oleh karena ambilan berlebih dari platelet.8 Perilaku melukai diri sendiri atau self injurious behaviors merupakan masalah yang sering dijumpai pada gangguan perkembangan pervasif atau autisme. Gangguan sistem serotonin diduga berperan dalam perilaku melukai diri sendiri dengan cara mengganggu pengendalian impuls. Gangguan pengendalian impuls disebabkan oleh menurunnya aktivitas dan fungsi 5-HT impuls. Sistem serotonin yang hiperaktif dihubungkan dengan perilaku eksplorasi, mengambil risiko, ide bunuh diri, perilaku impulsif dan agresif, sementara sistem serotonin yang hipoaktif menyebabkan temperamen yang pasif impuls.12 Isolasi sosial pada awal kehidupan akan memicu perilaku melukai diri sendiri, hal ini dihubungkan dengan berkurangnya cabang-cabang dendrit pada korteks dan serebelum, perubahan anatomis pada striatum dan hipokampus, dan menimbulkan gangguan pada kadar regional neurotransmiter norepinefrin, dopamin, serotonin, substansia P, dan leucine-enkephalin.12 Berbagai penelitian eksperimental memperlihatkan adanya hubungan terbalik antara kadar asam 5-hydroxyindole acetic acid sebagai metabolit serotonin dengan perilaku kekerasan, mengambil risiko, dan mencederai diri sendiri impuls.12,13 Serotonin berperan dalam pengaturan perkembangan otak, dengan mengatur divisi sel, diferensiasi sel, pertumbuhan neuron dan sinaps, dan pengaturan faktorfaktor neurotropik.14 Peranan neurotransmiter serotonin pada autisme ditunjukkan dengan hiperserotonemia pada penderita autisme, perbaikan gejala regresi dan stereotipi dengan pemberian obat-obat penghambat reuptake serotonin, dan pengurangan tryptopan akan memperburuk gejala autisme. Penderita autisme mengalami gangguan dalam kapasitas sintesis serotonin pada masa anak-anak.14 Pada penderita epilepsi dengan autisme, serotonin memiliki peran tersendiri dalam munculnya gangguan perilaku. Timbulnya gangguan perilaku dan afektif pada penderita autisme dengan epilepsi atau abnormalitas gelombang EEG diperkirakan terjadi melalui mekanisme kindling seizure pada amigdala. Kindling memperlihatkan sebuah model progresivitas kerusakan neuron akibat pacuan berulang baik subkonvulsif maupun konvulsif.15 Neurotransmiter serotoninergik diperkirakan ikut berperan dalam terjadinya kindling pada amygdala, pemberian agonis 5-HT1A akan menghambat pembentukan kindling, sementara percepatan kindling teramati setelah pemberian 5-HT2A. Serotonin berperan dalam pembentukan kindling No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 dengan cara memodulasi munculnya discharge pada amygdala melalui fungsi reseptor glutamat NMDA (NMethyl DAspartate). Berbagai obat antiepilepsi memiliki efek yang poten terhadap sistem serotoninergik.15 Penggunaan terapi farmakologi yang berperan pada sistem serotoninergik Agonis 5-Ht Kelompok agonis 5-HT yang paling banyak digunakan dalam penelitian terapi autisme adalah fenfluramine. Fenfluramine merupakan kelompok agonis 5-HT indirek yang memacu pelepasan 5-HT presinaps dan menghambat ambilan kembali (reuptake) oleh neuron 5-HT.7 Fenfluramine juga mempercepat pemecahan dopamin yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekskresi metabolit utama dopamin, yaitu homovanilic acid (HVA).6 Fenfluramine akan menginduksi pelepasan cepat serotonin dari neuron. Pemakaian fenfluramine jangka panjang akan menyebabkan deplesi serotonin di neuron dan penurunan fungsi enzim tryptophan hydroxylase (TPH), dengan mekanisme yang tidak diketahui secara pasti. Saat ini fenfluramine telah ditarik dari pasaran obat di Amerika Serikat karena efek samping kerusakan katup jantung dan hipertensi pulmoner.7 Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Obat-obat Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) bekerja terutama pada terminal akson presinaptik dengan menghambat ambilan kembali serotonin. Penghambatan ambilan kembali serotonin diakibatkan oleh ikatan obat (misalnya: fluoxetine) pada transporter ambilan kembali yang spesifik, sehingga tidak ada lagi neurotransmiter serotonin yang dapat berikatan dengan transporter. Hal tersebut akan menyebabkan serotonin bertahan lebih lama di celah sinaps. Penggunaan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) terutama ditujukan untuk memperbaiki perilaku stereotipik, perilaku melukai diri sendiri, resisten terhadap perubahan halhal rutin, dan ritual obsesif dengan ansietas yang tinggi.16 Salah satu alasan utama pemilihan obat-obat penghambat reuptake serotonin yang selektif adalah keamanan terapi.17 Efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian fluoxetine adalah nausea, disfungsi seksual, nyeri kepala, dan mulut kering. Tolerabilitas SSRI yang relatif baik disebabkan oleh karena sifat selektivitasnya. Obat SSRI tidak banyak berinteraksi dengan reseptor neurotransmiter lainnya.18 Penelitian Awad17 dengan metode pengamatan kasus serial atau case series terhadap 8 subjek. Tindakan terapi ditujukan untuk mengatasi gejala-gejala disruptif, dan dimulai dengan fluoxetine dosis 10 mg/hari dengan pengamatan selama 1 bulan. Perbaikan paling nyata dijumpai pada gangguan obsesif dan gejala cemas. Tabel 1 memperlihatkan penelitianpenelitian terdahulu tentang penggunaan fluoxetine dalam terapi autisme. 175 TINJAUAN PUSTAKA Tabel 1. Penelitian-penelitian terdahulu tentang penggunaan fluoxetine untuk terapi autisme19-22 Disain Terapi Subjek Hasil penelitian Perbaikan pada Global Clinical Impressions pada 15 (65%) subjek Open label trial Fluoxetine 20-80 mg/hari 23 penderita autisme Open label trial Fluoxetine 37 anak Perbaikan pada Independent autisme usia Developmental Testing antara 2-7 tahun pada 22 (59%) subjek Kajian data retrospektif Fluoxetine 20-80 mg/hari 7 pasien usia 9-20 tahun Perbaikan Abberant Behaviour Checklist dalam hal iritabiltas 21%, letargi 37%, stereotipik 27%, dan gangguan bicara 21% Open label trial selama 1 tahun Fluoxetine 20 mg/hari 12 pasien usia 3-13 tahun Open label trial Fluoxetine (post hoc analysis) 0,15-0,5 mg/kg selama rata-rata 32-36 bulan 129 anak autisme usia 2-8 tahun Perbaikan pada Global Clinical Impressions Respon pada Autism Diagnostic Observation Schedule - Sangat baik pada 17% kasus - Baik pada 52% kasus - Buruk pada 31% kasus Penelitian Buchsbaum, dkk23 mengukur efek pemberian fluoxetine terhadap aliran darah regional dan tingkat metabolisme otak. Penelitian dilakukan pada 6 pasien dewasa autisme dengan penggunaan Possitron Emission Tomography. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat metabolisme di regio frontal kanan (terutama gyrus cinguli anterior dan korteks orbito-frontal) pada penderita yang diberikan terapi fluoxetine. Antidepresan trisiklik Clomipramine merupakan golongan antidepresan trisiklik yang digunakan sebagai terapi gangguan obsesif-kompulsif dan autisme. Agen terapi obsesif-kompulsif pada autisme terutama digunakan untuk mengurangi perilaku stereotipik dan gerakan yang berulang-ulang, meningkatkan interaksi sosial, dan menurunkan kecenderungan agresivitas.8 Mekanisme kerja utama clomipramine adalah menghambat ambilan kembali (reuptake) 5-HT dan norepinefrine. Lima penelitian terdahulu tentang clomipramine sebagai terapi autisme masih bervariasi dan belum konklusif. Perbaikan gejala hiperaktivitas, stereotipik, kompulsif, perilaku yang ritual, dan kemarahan diamati pada sebagian besar kasus, namun ada pula penderita yang menunjukkan perburukan gejala. Pada kelompok anak-anak pemberian clomipramine memerlukan monitor EKG yang ketat karena kemungkinan efek samping takikardia dan perpanjangan interval QT.6 Kesimpulan Autisme merupakan kelainan yang kompleks, terutama ditandai oleh gangguan fungsi berbahasa, interaksi sosial, dan gangguan perilaku. Morbiditas epilepsi dan retardasi mental dilaporkan tinggi pula. Aspek neuroanatomi yang mendasari munculnya autisme sangat kompleks. Gangguan neurotransmiter dianggap berperan pula dalam patofisiologi autisme. Gangguan yang terjadi terutama pada sistem dopaminergik, serotoninergik, dan GABA. Gangguan pada sistem neurotransmiter dianggap bertanggung jawab pada 176 berbagai gangguan perilaku yang muncul pada autisme. Peranan neurotransmiter serotonin pada autisme ditunjukkan dengan hiperserotonemia pada penderita autisme, perbaikan gejala regresi dan stereotipi dengan pemberian obat-obat penghambat reuptake serotonin, dan pengurangan tryptophan akan memperburuk gejala autisme. Obat-obat yang bekerja pada sistem serotonin banyak dipergunakan dalam terapi autisme. Namun bukti-bukti ilmiah yang mendukungnya kurang kuat, sehingga diperlukan suatu uji klinik double blind randomisasi di waktu mendatang. Daftar Pustaka 1. Herman A. Neurobiological insights into infantile autism. The Harvard Brain 1996:19-25 2. Tonge BJ. Autism, autistic spectrum and the need for better definition. MJA 2002; 176:412-3 3. Pusponegoro HD. Pandangan umum mengenai klasifikasi spektrum gangguan autistik dan kelainan susunan saraf pusat. Konferensi Nasional Autisme Pertama. Jakarta; 2003 4. Szatmari P. the causes of autism spectrum disorder: multiple factors has been identified, but a unifying cascade of events is still elusive. BMJ 2003; 326:173-4 5. Rapin I. Autism: current concept. N Engl J Med 1997; 337(2):97-104 6. Perry P, Kuperman S. Pediatric psychopharmacology: autism, clinical psychopharmacology seminar. University of Iowa; 2003 7. Nestler EJ, Hyman SE, Malenka RC. Molecular neuropharmacology: a foundation for clinical neuroscience. McGraw-Hill Companies; 2001 8. Esles L. the role of serotonin in autism. University of California;2000 9. Stahl SM. Essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. Cambridge University Press; 2000 10. Wiznitzer M. Autism spectrum disorder in 2002: an update. Cleveland Ohio, USA:Western Reserve University; 2002 11. Leboyer M, Philippe A, Bouvard M, et al. Whole blood serotonin and plasma beta endorphin in autistic probands and their first degree relatives. Biol Psychiatry 1999; 45:158-63 12. Villalba R, Harrington C, repetitive self-injurious behavior: the emerging potential of psychotropic intervention. Psychiatric Times 2003; 20(2) 13. Levin AL. Neurobiological aspects of agression. Neuropsychiatry Bulletin 2002 14. Schultz RT. The Neural basis of autism. International Encylopedia of the Social and Behavioral SciencesNew York: Elsevier Science, 2001.p.983-7 15. Martino AD, Tuchmann RF. Antiepileptic drugs: affective use in autism spectrum disorders. Pediatr Neurol 2001; 25:199-207 16. Widyawati I. Manajemen multidisiplin pada individu dengan autistic spectrum disorder. Konferensi Nasional Autisme Pertama. Jakarta; 2003 17. Awad GA. the use of selective serotonin reuptake inhibitors in young children with pervasive developmental disorders: some clinical observations. Can J Psychiatry 1996; 41(6):361-6 18. Ferguson JM. ssrI, anti depressant medications, adverse effects and tolerability. J Clin Psychiatry 2001; 3:22-7 19. Cook EH, Rowlett R, Jaselkis C. fluoxetine treatment of children and adults with autistic disorder and mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1992; 31(4):734-45 20. DeLong GR, Teagoe LA, Kamran M. Effect of fluoxetine treatment in young children with idiopathic autism. Dev Med Child Neurol 1998; 40(8):551-62 21. Fatemi SH, Realmuto Gm, Khan L, et al. fluoxetine in treatment of adolescent patients with autism: a longutudinal open trial. J Autism Dev Disord 1998; 28(4):303-7 22. DeLongGR, Ritch CR, Burch S. fluoxetine response in children with autistic spectrum disorders: correlation with familial major affective disorder and intelectual achivement. Dev Med Child Neurol 2002; 44(10): 652-9 23. Buchsbaum MS, Hollander E, Hazneder MM. Effect of fluoxetine on regional cerebral metabolism in autistic spectrum disorder: a pilot study. Int J Neuropsychopharmacol 2001; 4(2):119-25 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Konsep Baru Kortikosteroid Pada Penanganan Sepsis IGP Suka Aryana, Sjaiful I Biran Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam FK UNUD/RS Sanglah Denpasar - Bali Abstrak. Sepsis adalah respon inflamasi sistemik akibat infeksi. Mekanisme terjadinya sepsis masih merupakan mekanisme yang tidak sepenuhnya jelas. Sepsis yang sebelumnya dianggap sebagai peningkatan respon inflamasi ternyata juga peningkatan respon antiinflamasi. Pada sepsis ternyata terjadi keadaan imunosupresif di mana didapatkan peningkatan respon antiinflamasi, anergi dan apoptosis sel imun. Peranan genetik juga berpengaruh pada prognosis dari sepsis. Pengobatan kortikosteroid masih merupakan kontroversi. Penelitian-penelitian terbaru membuktikan bahwa penggunaan kortikosteroid dosis tinggi tidak ada manfaatnya pada terapi sepsis dan syok sepsis. Beberapa penelitian baru menunjukkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah, dosis fisiologis dapat mengembalikan stabilitas hemodinamik, perbaikan fungsi organ dan menurunkan mortalitas. Tetapi belum banyak studi yang membuktikan hal tersebut. Pengobatan kortikosteroid dosis rendah sebaiknya diberikan pada penderita sepsis dengan disertai adanya adrenal insufisiensi. Kata kunci: sepsis, kortikosteroid, proinflamsi, antiinflamasi Pendahuluan epsis adalah merupakan respon inflamasi yang bersifat sistemik akibat adanya infeksi berat. Respon imun sistemik muncul setelah respon imun lokal tidak berhasil mengeliminasi antigen dengan baik. Respon ini dikenal sebagai istilah Systemic Inflammatory Responses Syndrome (SIRS). Keberhasilan dari respon ini ditentukan oleh kekuatan proses inflamasi dan keseimbangan antara respon inflamasi dan kompensasi respon antiinflamasi.1,2 Beberapa istilah yang harus dipahami sehubungan dengan sepsis antara lain infeksi, bakterimia, SIRS, sepsis, severe sepsis, syok sepsis, dan Multiorgan Dysfunction (MOD). Infeksi adalah respon inflamasi akibat adanya mikroorganisme atau invasi mikroorganisme ke jaringan yang seharusnya steril. Bakterimia adalah ditemukannya bakteri pada darah. Systemic Inflammatory Responses Syndrome adalah respon inflamasi sistemik akibat berbagai sebab dengan 2 atau lebih manifestasi berikut: temperatur >38oC atau <36oC, denyut jantung >90 kali/menit, respirasi >20 kali/menit atau PaCO2 <32 mmHg, dan leukosit >12.000/mm2, <4.000/mm2 atau >10% bentuk (band) immature. Sepsis adalah respon inflamasi sistemik S No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 akibat infeksi dengan manifestasi SIRS. Severe sepsis adalah sepsis yang disertai dengan disfungsi organ, hipoperfusi, atau hipotensi dan kadang disertai laktoasidosis, oligouri dan penurunan kesadaran. Syok sepsis adalah bagian dari severe sepsis yang disertai dengan hipotensi. Multiorgan Dysfunction adalah sepsis yang disertai dengan adanya gangguan fungsi organ akibat homeostasis tidak bisa dipertahankan.1-3 Insiden sepsis mempunyai kecenderungan terus meningkat. Sepsis merupakan penyebab kematian terpenting pasien-pasien yang di rawat di ruang intensif. Laporan Central Disease Control (CDC) di Amerika, insiden septikemia meningkat dari 73,6 per 100.000 pasien pada tahun 1979 menjadi 175,9 per 100.000 pasien pada tahun 1987. Laporan terakhir tahun 1990 insiden septikemia di Amerika 450.000 kasus pertahun dengan angka kematian lebih dari 100.000 orang.2,4 Di Eropa didapatkan 2-11% pasien yang dirawat di Intensive Care Unit (ICU) menderita severe sepsis. Angka mortalitas dari syok sepsis berkisar 40%. Angka kematian sepsis di Amerika didapatkan lebih rendah, yaitu 9,3% pada tahun 1995. Total biaya yang diperlukan per kasus berkisar 22.10 dolar. Tingginya angka mortalitas membuat sepsis 177 TINJAUAN PUSTAKA semakin diperdebatkan dalam hal patogenesis dan terapi yang terus berkembang. Terapi kortikosteroid telah dimulai sejak tahun 1950 ternyata masih menjadi perdebatan. Pada tinjauan pustaka ini akan kami uraikan secara praktis penggunaan kortikosteroid dalam terapi sepsis.1,2,5 Patofisiologi Sepsis Sistem kekebalan alami (nonspesifik) adalah pertahanan lini pertama tubuh terhadap infeksi yang diaktifkan bila ada patogen masuk melewati pertahanan fisik, mekanik dan kimiawi tubuh. Sistem kekebalan alami bisa berupa seluler yang terdiri dari sel monosit, makrofag, neutrofil, eosinofil dan sel Natural Killer (NK) dan humoral berupa protein terlarut seperti komplemen, C Reactive Protein (CRP) dan sitokin. Sistem kekebalan yang didapat (spesifik) akan membantu sistem kekebalan alami melalui aktivitas dari sel limfosit. Limfosit T bersifat seluler dan limfosit B bersifat humoral. Sistem imun akan diaktifkan oleh protein patogen yang dapat berasal dari berbagai jenis mikroorganisme, misalnya endotoksin (lipopolysaccharide), peptidoglycan, lipoechoic acid, lipopeptide, flagelin, mannan dan RNA virus. Kegagalan sistem imun mengatasi infeksi dan menimbulkan reaksi imun yang tidak sesuai dikatakan sebagai sepsis.4 Elemen kunci pada patofisiologi sepsis adalah sitokin. Sitokin yang dihasilkan oleh sel yang mengalami injuri bersifat sebagai peptida imunoregulator yang polimorfik. Sitokin Tumor Necrosing Factor (TNF), interleukin(IL)-1 dan IL-8 sebagai sitokin proinflamasi dan IL-6, IL-10 sebagai sitokin antiinflamasi.6 Toksin mikroba akan merangsang produksi TNF dan IL-1 menyebabkan terjadinya adhesi dari lekosit pada endotel dan mensekresi protese dan metabolit arakidonat. Hal ini akan mengaktifasi sistem pembekuan.6 Jadi ada beberapa faktor yang berperan pada proses ini, yaitu: respon tubuh, peranan sel endotel dan monosit dan aktivasi sistem inflamasi dan koagulasi. Ketiga hal ini berperan dalam menentukan prognosis dari pasien sepsis. Inflamasi dan koagulasi merupakan 2 keadaan yang akan saling berpengaruh untuk menentukan prognosis pasien yang mengalami infeksi. Elemen kunci pada patofisiologi sepsis adalah sitokin. Sitokin yang dihasilkan oleh sel yang mengalami injuri bersifat sebagai peptida imunoregulator yang polimorfik. Adanya infeksi menghasilkan endotoksin atau toksin akan meningkatkan sitokin proinflamasi. Reaksi dari sitokin proinflamasi ini yang bermanifestasi sistemik sebagai (Systemic 178 Inflamatory Responses Syndrome) SIRS. SIRS ditandai dengan adanya hipersitokinemia. Peningkatan respon imun berlebihan ternyata berakibat buruk pada pasien. Pasien dapat mengalami fase syok dan MOD dan berakhir pada Multiple Organ Faillure (MOF) dan kematian. Pada SIRS terjadi patogenesis yang sangat kompleks, melibatkan banyak sel, dan merangsang sekresi berbagai hormon. Terapi tidak akan berhasil jika berkerja hanya pada satu titik saja. Terapi dengan antibodi antiTNF gagal menunjukan hasil bermakna pada peningkatan angka harapan hidup pasien dengan sepsis berat.1,7 Hal ini menimbulkan munculnya teori baru tentang sepsis tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa ternyata pada sepsis tidak ada bukti bahwa peran reaksi proinflamasi lebih dominan. Hal ini yang menyebabkan kita harus lebih banyak mengerti konsep baru di mana ditambahkan 2 istilah baru yang dapat terjadi pada sepsis, yaitu Compensatory Anti Inflammatory Responses (CARS) dan Mixed Proinflammatory and Antiinflammatory Responses (MARS).1,7 Respon proinflamasi lokal Respon antiinflamasi lokal Luka awal (bakteri, virus, kondisi traumatis, termal) Sebaran sistemik mediator proinflamasi Sebaran sistemik mediator antiinflamasi Reaksi sistemik: SIRS (proinflamasi) CARS (antiinflamasi) MARS (campuran) C Cardiovascular compromise (syok) SIRS Predominate H Homeostatis A Apoptosis (sel-sel mati) Kematian Keseimbangan dengan inflamasi CARS dan SIRS minimal O Disfungsi organ S Supresi sistem organ SIRS mendominasi CARS mendominasi Gambar 1. Konsep baru sepsis Imunomodulasi pada sepsis sangat kompleks dan saling tumpang tindih. Konsep baru ini menjelaskan bahwa ada 5 tahapan terjadinya MOD pada sepsis, yaitu:2 1. Stadium reaksi lokal Respon awal tubuh adalah menginduksi mediator proinflamasi untuk menghancurkan jaringan yang rusak, benda asing, kuman dan merangsang pertumbuhan jaringan baru. Kompensasi mediator antiinflamasi segera muncul untuk mencegah agar proinflamasi tidak terlalu destruktif. IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, reseptor TNFa terlarut, antagonis reseptor IL-1, tumor growth factor No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Beberapa penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa ternyata pada sepsis tidak ada bukti bahwa peran reaksi proinflamasi lebih dominan. (TGF)b dan mediator lainnya bertujuan mengurangi ekspresi Major Histocompability Complex (MHC) klas II, menurunkan aktivitas Antigen Precipating Cell (APC), dan menurunkan aktivitas sel untuk memproduksi sitokin inflamasi. Semua reaksi ini berlangsung lokal tanpa reaksi sistemik berlebihan. 2. Stadium respon sistemik awal Bila mediator proinflamasi didapatkan dalam sirkulasi menandakan bahwa kerusakan/kuman tidak dapat dikontrol oleh reaksi lokal saja. Mediator proinflamasi bertujuan membantu menarik neutrofil, sel limfosit T, dan B, trombosit dan faktor koagulasi untuk datang ke injury location atau infeksi. Reaksi ini akan merangsang respon kompensasi sistemik antiinflamasi. Tetapi respon ini akan segera menurunkan respon sistemik proinflamasi. Manifestasi klinis akan muncul tetapi tidak berat dan jarang menimbulkan disfungsi organ. 3. Stadium inflamasi sistemik masif Pada stadium ini terjadi kehilangan mekanisme regulasi respon proinflamasi sehingga timbul manifestasi klinis SIRS. Hal ini terjadi akibat dari: (1) progresivitas disfungsi endotel sehingga terjadi peningkatan permiabilitas mikrokapiler; (2) Trombosit yang memblok mikrosirkulasi sehingga timbul iskemia atau injuri reperfusi dan menginduksi Heat Shock Protein (HSP); (3) aktivasi sistem koagulasi dan gangguan jalur inhibisi protein C dan protein S; (4) adanya vasodilatasi dan maldistribusi aliran darah sehingga pasien jatuh pada fase syok. Pada stadium ini merupakan ancaman terjadinya disfungsi organ dan MOF bila homeostasis tidak segera diatasi. 4. Stadium imunosupresi masif Pada keadaan ini terjadi reaksi antiinflamasi kompensasi yang tidak efektif dan menyebabkan terjadinya imunodefisiensi. Keadaan ini sering disebut sebagai immune paralysis atau CARS. Pada suatu penelitian didapatkan bahwa pada pasien dengan SIRS. Pada CARS No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 didapatkan ekspresi human leucocyte antigen (HLA) DR monosit menurun kurang dari 30%. Penambahan interferon (IFN) g-1b dapat meningkatkan ekspresi HLA DR pada permukaan monosit sehingga memperbaiki fungsi monosit dan sekresi IL-6 dan TNFa sehingga kondisi pasien membaik. 5. Stadium imunologi dissonance Stadium akhir dari sepsis adalah imunologis dissonance, jadi terjadi ketidaksesuaian atau sistem imunomodulator berada di luar keseimbangan. Keadaan ini sering dianggap sebagai keadaan yang persisten sehingga mempunyai angka kematian yang tinggi. Adanya kenyataan seperti ini berarti masih banyak misteri sepsis yang belum terungkap dengan jelas. Sepsis yang didefinisikan sebagai respon inflamasi sistemik ternyata tidak sepenuhnya terjadi respon inflamasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang mencoba memberikan terapi antiinflamasi dengan kortikosteroid, antibodi antiendotoksin, antagonis TNF, antagonis reseptor IL-1 dan lainnya ternyata gagal sebagai terapi pada sepsis. Penelitian lain mendapatkan bahwa ternyata sepsis adalah suatu kondisi imunosupresif. Hal ini didasari oleh didapatkannya bukti bahwa pada sepsis terjadi kehilangan kemampuan pada reaksi hipersensitivitas tipe lambat dan kemampuan eliminasi infeksi sehingga pada sepsis mudah terjadi infeksi nosokomial. Ada beberapa teori yang menjelaskan terjadinya imunosupresif pada sepsis, yaitu: (1) perubahan/pergantian sitokin yang mulanya proinflamasi menjadi antiinflamasi, (2) anergi: penurunan respon terhadap antigen akibat kegagalan proliferasi dan sekresi sitokin sehubungan dengan terjadinya apoptosis limfosit akibat sepsis, (3) kematian sel imun akibat terjadinya apoptosis baik pada sel B, sel T CD4 maupun sel dentritik folikular. Peranan genetik dikatakan ikut mempengaruhi prognosis pasien. Neutrofil yang sebelumnya diduga dapat mengeradikasi kuman patogen ternyata juga dapat berakibat kerusakan jaringan yang lebih luas karena produksi oksidan dan protease yang berlebihan.8 Karena mekanisme sepsis yang masih belum jelas diketahui, maka terapi kortikosteroid juga masih merupakan kontroversi dan masih diperdebatkan. Beberapa penelitian baru telah menunjukkan adanya manfaat dari terapi kortikosteroid tersebut. Perkembangan Pemakaian Kortikosteroid pada Terapi Sepsis Kortikosteroid telah banyak digunakan pada beberapa penyakit yang ditandai dengan peningkatan respon inflamasi seperti asma, penyakit kolagen, vaskulitis, sarcoidosis dan penyakit lainnya. Pada syok sepsis terjadi peningkatan respon inflamasi yang disertai dengan manifestasi syok dengan penurunan kesadaran, laktoasidosis, dan penurunan produksi urin. Kortikosteroid dikatakan dapat mengatasi respon inflamasi ini melalui beberapa cara seperti terlihat pada tabel 1.1 179 TINJAUAN PUSTAKA Tabel 1. Efek kortikosteroid sebagai antiinflamasi1 Efek pada lipokortin: 1. Meningkatkan respon PMN pada rangsangan 2. Hambatan phospholipase A2 dan cegah aktivasi prostaglandin 3. Perubahan membran sel pada pengikatan kalsium 4. Hambat kemampuan netrofil untuk melepaskan metabolit oksigen aktif Efek pada interleukin: 1. Hambat sintesis IL-1 dan hambat IL-6 2. Menurunkan waktu paruh mRNA IL-3 3. Down egulasi sitokin dan growth factor 4. Cegah TNF dan IL-1 dilepas oleh sel mononuklear Efek pada netrofil: 1. Stabilisasi lisosom neutrofil 2. Hambat pelepasan enzim lisosom 3. Menormalkan respon inflamasi 4. Cegah hiperagregasi dan adesi lekosit oleh endotoksin Lain-lain: 1. Cegah aktivitas kaskade koagulasi 2. Hambat sintesis NO eksogen 3. Menurunkan platelet-activating factor selama rangsangan endotoksin Kortisol bentuk kortikosteroid yang disekresi oleh kortek adrenal pada orang sehat tanpa stress mempunyai kadar diurnal sesuai dengan rangsangan kortikotropin yang disekresi oleh kelenjar pituitaria. Sekresi kortikotropin dirangsang oleh Corticotropin Releasing Hormone (CRH) yang berasal dari hipotalamus (gambar 3). Kedua hormon ini mempunyai negative feedback control. Kortisol dalam darah terikat dengan Corticosteroid Binding Globulin (CBG), di mana <10% dalam bentuk bebas. Pada keadaan infeksi berat/sepsis, trauma, luka bakar, dan operasi akan terjadi peningkatan sekresi kortisol akibat peningkatan sekresi hormon kortikotropin dan CRH. Mekanisme feed back tidak bekerja maksimal sehingga variasi diurnal sekresi kortisol tidak normal. Gangguan pada mekanisme aksis hipotalamus-pituitaria-adrenal dikatakan disebabkan oleh banyaknya sitokin di dalam sirkulasi pada keadaan tersebut. Pada keadaan ini juga terjadi penurunan CGB sehingga kortisol bebas akan semakin tinggi. Proses inflamasi dikatakan dapat memecah ikatan CBG dengan kortisol oleh enzim neutrofil elastase. Sitokin inflamasi juga dapat meningkatkan kortisol di jaringan karena sitokin ini dapat merubah metabolisme kortisol perifer dan meningkatkan afinitas reseptor glukokortikoid terhadap kortisol. Tetapi tingginya kadar sitokin inflamasi pada sepsis secara langsung dapat menghambat sintesis kortisol oleh adrenal. Pemberian terapi kortikosteroid jangka lama dapat menekan sekresi kortikotropin dan CRH akan menimbulkan atropi adrenal terutama jika mendapat hidrokortison 30 mg perhari selama lebih dari 3 minggu. Pada keadaan kadar sitokin yang rendah dalam darah jaringan akan lebih sensitif terhadap kortisol dibandingkan dengan keadaan sitokin tinggi yang akan menyebabkan terjadi resistensi. Hal ini menandakan perlukan respon adrenal yang normal untuk 180 dapat mengontrol inflamasi. Hal ini sering disebut sebagai functional adrenal insufficiency atau relative adrenal insufficiency artinya walaupun kadar kortisol tinggi tetapi belum cukup untuk menekan proses inflamasi.1,9 A B Fungsi nonstres normal hipofisis andrenal Hipotalamus Corticotropin releasing hormonie C Fungsi normal aksis hipotalamushipofisis-adrenal selama sakit Fungsi normal aksis hipotalamushipofisis-adrenal selama sakit Mengurangi asupan balik Kortikotropin melepaskan hormon Stress sitokin Pelepasan hormon kortikotropin penyakit sistem saraf pusat, kortikostroid Apoplexy hipofisis, kortikosteroid Hipofisis Kortikotropin Kortikotropin Kortikotropin Andrenal Terikatnya kortisol dengan kortikosteroid - mengikat globulin Meningkatkan kortisol dan menurunkan kortikostenoid-mengikat globulin Sitokin anastesi, antiinfeksi, kortikosteroid hemorrhage infeksi termasuk infutrasi HIV Menurunkan kortisol dan menurunkan kortikosteroid-mengikat globulin Sitokin, aktivasi kortikostenoid lokal Aksis normal pada jaringan Meningkatkan aksi pada jaringan Menurunkan aksi pada jaringan Gambar 2. Aksis hipotalamus-pituitaria-adrenal Konsep Lama Pemakaian Kortikosteroid pada Terapi Sepsis Sejak tahun 1950 penggunaan kortikosteroid pada sepsis sudah diperdebatkan.1 Beberapa penelitian yang dilakukan dari tahun 1950 sampai tahun 1971 menunjukkan banyaknya kortikosteroid digunakan pada sepsis oleh karena bakteri. Hasil-hasil penelitian ini sulit dievaluasi karena banyaknya data-data dan metode yang tidak valid.5 Pada tahun 1970-an beberapa penelitian menggunakan kortikosteroid dosis tinggi pada sepsis berat dan syok sepsis. Schumer dkk., mendapatkan pada studi prospektifnya bahwa pemberian metilprednisolon 30 mg/kg berat badan (BB) atau deksametason 3 mg/kg BB diberikan 1 atau 2 kali dalam 24 jam dapat menurunkan angka kematian dari 38,4% menjadi 10,5%. Pemberian kortikosteroid dosis tinggi didasarkan pada asumsi bahwa pemberian kortikosteroid dosis tinggi akan dapat menguatkan efek antiinflamasi untuk melawan efek proinflamasi yang tidak terkontrol. Pemberian kortikosteroid juga diharapkan dapat mengobati relative adrenal insufficiency yang biasanya terjadi pada pasien sepsis.1,10-13 Konsep Baru Pemakaian Kortikosteroid pada Terapi Sepsis Banyak studi mendapatkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis tinggi pada sepsis tidak bermanfaat bahkan dapat merugikan karena dapat menimbulkan infeksi sekunder, perdarahan saluran cerna dan peningkatan gula darah. Penggunaan kortikosteroid dosis rendah masih diharapkan bermanfaat karena dapat menurunkan efek kerusakan sistem imunologis dan menurunkan insiden No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Pemberian kortikosteroid dosis tinggi didasarkan pada asumsi bahwa pemberian kortikosteroid dosis tinggi akan dapat menguatkan efek antiinflamasi untuk melawan efek proinflamasi yang tidak terkontrol. antiinflamasi, dan genetik. Pengobatan kortikosteroid masih merupakan kontroversi. Beberapa penelitian baru menunjukkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah, dosis fisiologis dapat mengembalikan stabilitas hemodinamik, perbaikan fungsi organ dan menurunkan mortalitas. Daftar Pustaka 1. Chacko J. Steroid in sepsis. Crit Care & Shock 2004; 7:129-33 2. Aird WC. The role of the endothelium in severe sepsis and multiple dysfunction syndrome. Blood 2003; 101:3765-77 3. Abraham E, Matthay MA, Dinarello CA, et al. Consensus conference definitions for sepsis septic shock, acute lung injury, and acute respiratory distress syndrome: time for a reevaluation. Crit Care Med 2000;28:232-5. 4. Bochud PY, Calandra. Pathogenesis of sepsis: new concepts and implications for future treatment. BMJ 2003; 326:262-6 terjadinya infeksi sekunder. Terapi ini menjadi rasional karena dianggap pada keadaan sepsis terjadi relatif defisiensi adrenal. Terapi ini sering disebut sebagai terapi fisiologi/replacement dari kortikosteroid.5 Metaanalisis terakhir oleh Minneci mendapatkan bahwa terapi kortikosteroid dosis tinggi dalam waktu pendek dapat menurunkan harapan hidup, sedangkan terapi kortikosteroid dosis selama 5-7 hari dapat meningkatan umur harapan hidup, dapat memperbaiki kondisi syok dan meningkatkan respon vaskular terhadap vasopresor.11,14,15 Kelenjar adrenal mensekresi kortisol pada saat ada stressor seperti pada sepsis. Baik tinggi maupun rendahnya kadar kortisol endogen yang disekresi akan berhubungan dengan mortalitas yang terjadi pada penderita sepsis. Manfaat dari kortisol adalah dapat sebagai antiinflamasi (menghambat sekresi sitokin dan migrasi sel radang) dan efek kardiovaskularnya dapat menghambat rangsangan sintesis Nitric Oxide (NO) dan meningkatkan respon vasokonstriksi vaskular terhadap katekolamin.16 Pemberian kortikosteroid dosis tinggi tidak dianjurkan karena lebih banyak merugikan. Pemberian kortikosteroid dosis rendah dikatakan lebih memberikan manfaat tetapi masih belum disepakati. Penelitian terbaru yang sedang berjalan dilakukan oleh Sprung dkk., dalam studi yang disebut CORTICUS akan menjawab pertanyaan penggunaan steroid pada sepsis. Sementara menunggu hasil studi pemberian kortikosteroid dosis rendah hanya direkomendasi apabila didapatkan adanya adrenal insufisiensi pada sepsis.12-14,17 Kesimpulan Sepsis adalah respon inflamasi sistemik akibat infeksi. Mekanisme terjadinya sepsis masih merupakan mekanisme yang tidak sepenuhnya jelas. Sepsis merupakan kombinasi kompleks peningkatan respon inflamasi, peningkatan respon No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 5. Sessler CN. Steroid for septic shock. Back from the dead?(Con). Chest 2003; 123:482S-489S 6. Wheeler AP, Bernard GR. Treating patients with severe sepsis. N Engl J Med 1999; 340:207-14 7. Bone RC, Grodzin CJ, Balk RA. Sepsis: a new hypothesis for pathogenesis of the disease process. Chest 1997; 112:235-43 8. Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. N Engl J Med 2003; 384:138-50 9. Cooper MS, Stewart. Coricosteroid insuffeciency in acutle ill patients. N Engl J Med 2003; 348:727-34 10. Lamberts SW, Bruining HA, DeJong FH. Corticosteroid therapy in severe illness. N Engl J Med 1997; 337:1285-92 11. Minneci PC, Deans KJ, Banks SM, et al. Meta-analysis: the effect of steroid on survival and shock during sepsis depends on the dose. Ann Intern Med 2004; 141:47-56 12. Luce MJ. Physician should administer low dose corticosteroid selectively to septic patients untill an ongoing trial is completed. Ann Intern Med 2004; 141:70-2 13. Bornstein SR. A new role for glucocorticoid in septic shock. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167:485-9 14. Balk RA. Steroid for septic shock. Back from the dead?(pro). Chest 2003; 123:490S-499S 15. VanAmersfoort ES, VanBerkel TJ, Kuiper J. Receptors, mediators, and mechanism involved in bacterial sepsis and septic shock. Clin Microbiol R 2003; 16:379-414 16. Burry LD, Pharm B. Role of corticosteroids in septic shock. Annals Pharm 2004; 38:464-72(abstract) 17. Annene D, Bellisant E, Bollaert PE, et al. Corticosteroid for severe sepsis and septic shock: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2004; 329:480 181 TINJAUAN PUSTAKA Patogenesis dan Respon Imun Tubuh terhadap Infeksi Virus Herpes Simpleks Ary Widhyasti Bandem, Satiti Retno Pudjiati Bagian/SMF Ilmu Penyakit Kulit Kelamin Fakultas Kedokteran UGM/RS Dr. Sardjito Yogyakarta Abstrak. Herpes genital (HG) disebabkan oleh virus herpes simpleks (VHS) yang bermanifestasi sebagai papule vesicle yang dengan mudah menjadi ulkus dangkal pada genital. Infeksi HG dapat berupa infeksi primer, rekuren dan bahkan asimptomatis sehingga dengan mudah dapat menular kepada orang lain. Infeksi HG prevalensinya makin meningkat dan memudahkan transmisi infeksi HIV maupun penyakit menular seksual lainnya. Manifestasinya dapat ringan maupun berat pada penderita imunocompromise sehingga penting untuk diketahui patogenesis dan respon imun tubuh terhadap infeksi VHS. Pada tulisan ini akan diuraikan tentang karakteristik VHS, patogenesis infeksi VHS pada mukokutan, diagnosis HG serta respon imun tubuh terhadap infeksi VHS baik yang bersifat alamiah dan adaptif. Kata kunci: Herpes genital, patogenesis, diagnosis, karakteristik, respon imun Pendahuluan erpes Genitalis (HG) adalah infeksi genital yang disebabkan oleh virus herpes simpleks (VHS) ditandai secara klasik dengan timbulnya erupsi papulovesikular dengan dasar eritema pada kulit, dan pada mukosa dengan mudah menjadi ulkus dangkal. Virus Herpes Simpleks merupakan virus DNA dari famili Herpesviridae dan menginfeksi epitel mukokutan secara inokulasi langsung melalui lesi abrasi. Pada saat terjadinya infeksi di mukokutan, VHS juga menginfeksi sel saraf sensoris, menuju ganglion sakralis (S2-S4), selanjutnya menetap sebagai infeksi laten. Pada beberapa keadaan seperti adanya trauma lokal, menstruasi, stres emosi, demam, dan paparan sinar ultraviolet, VHS ini mengalami reaktivasi, secara axonal kembali ke mukokutan dan memberikan gambaran klinis sebagai infeksi rekuren.1-8 Prevalensi HG di Amerika Serikat meningkat dari 100.000 di tahun 1970-an menjadi 200.000 di tahun 1990. Hal ini di samping karena jumlah kasus yang memang meningkat, juga disebabkan karena perbaikan dalam menegakkan diagnosis dan meningkatnya kepedulian pasien.9 Pada tahun 1988-1994, seroprevalensi VHS-2 pada penduduk Amerika Serikat yang berusia di atas 12 tahun sebesar 21,9% dari 45 juta penduduk yang terinfeksi. Saat ini secara nasional di Amerika Serikat dideteksi VHS-2 positif pada 1 dari 5 orang yang berusia di atas 12 tahun.6 VHS-1 sebagai penyebab HG di Amerika Serikat H 182 telah didapatkan meningkat sampai 20% dan disebabkan karena dari hubungan oral-genital.10 Manifestasi klinis HG bervariasi, dikenal dengan infeksi primer, infeksi rekuren, dan bahkan infeksi dapat tidak dirasakan penderita (asimptomatis) tetapi terjadi viral shedding yang dapat menularkan kepada orang lain. Tentunya transmisi ini berbahaya apalagi dengan adanya infeksi HG juga memudahkan transmisi HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya.11-13 Manifestasi klinis yang bervariasi, rekureni yang tinggi dan komplikasi berat pada penderita imunocompromise, serta kesembuhan permanen yang tidak pernah terjadi, maka diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang patogenesis dan respon imun tubuh terhadap infeksi VHS. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan yang lebih tepat untuk penderita HG. Pada makalah ini akan dibahas mengenai karakteristik VHS, patogensis infeksi VHS pada mukokutan, diagnosis HG serta respon imun tubuh terhadap infeksi VHS baik yang bersifat alamiah dan adaptif. Karakteristik VHS Virus herpes simpleks tergolong ke dalam virus Herpes tipe alfa yang mempunyai sifat neurotropik dan replikasi virus yang relatif cepat serta dapat menginfeksi berbagai sel pada kultur. Sejak tahun 1960 dikenal ada dua serotipe, yaitu VHS-1 dan No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA VHS-2. Strain VHS-1 umumnya diisolasi dari labia, fasial dan okular sedangkan strain VHS-2 dari lesi genital dan dari bayi baru lahir yang terinfeksi lewat jalan lahir. Akan tetapi kedua strain ini dapat dijumpai pada tempat yang sebaliknya. Kedua strain ini sulit dibedakan dari patogenesisnya, hanya disebutkan bahwa VHS-2 lebih sering menimbulkan infeksi rekuren pada daerah genital daripada oral dan demikian sebaliknya.2,3 VHS mempunyai genom yang linier, double stranded DNA, dengan ukuran 160 x 103 kDa, dikelilingi selubung protein dan amplop lipid. Virion VHS terdiri dari inti DNA, kapsid ikosahedral berdiameter 100 nm dengan permukaannya ditutupi Manifestasi klinis yang bervariasi, rekureni yang tinggi dan komplikasi berat pada penderita imunokompromais, serta kesembuhan permanen yang tidak pernah terjadi, maka diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang patogenesis dan respon imun tubuh terhadap infeksi VHS. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan yang lebih tepat untuk penderita HG. 162 kapsomer serta dibatasi oleh amplop yang mengandung lipid. Antara nukleokapsid dan amplop dipisahkan oleh tegumen. Genom VHS-1 dan VHS-2 mempunyai 50% sekuen nukleotida yang sama (homolog) sedangkan 50% lainnya berbeda. Genom virus mengkode 50 protein virus spesifik termasuk 5-6 glikoprotein spesifik yang dipresentasikan pada permukaan virus dan pada permukaan sel yang terinfeksi virus. Glikoprotein VHS ditemukan ada 11 dan yang berfungsi sebagai attachment pada hospes adalah glikoprotein B dan C, sedangkan untuk entry dan terpenting dalam menginduksi antibodi netralisir terhadap virus adalah glikoprotein D. dari 56 glikoprotein pada VHS tersebut, hanya satu dari glikoprotein permukaan ini yang bersifat spesifik, gG1 untuk VHS-1 dan gG2 untuk VHS-2. Secara signifikan didapatkan adanya reaktivitas silang pada antibodi yang terbentuk di antara kedua tipe virus tersebut.1,14-16 Genom VHS juga menyandi sejumlah protein non-struktural yang penting untuk replikasi DNA virus, termasuk virus timidin kinase, DNA polimerase, ribonukleotida reduktase dan alkaline DNase. Enzim virus ini berbeda dengan enzim sel yang terinfeksi dan menjadi dasar penghambat obat antivirus.1 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Patogenesis VHS masuk ke dalam tubuh manusia untuk pertama kali (infeksi inisial, infeksi primer) melalui kontak virus dengan mukosa atau lesi abrasi. VHS-2 menginfeksi pejamu di mukosa genital dan mengadakan replikasi dalam sel epitel. Virus memasuki sel secara fusi dimulai dengan glikoprotein amplop VHS mengikat reseptor spesifik sel pejamu, yaitu heparin sulfat permukaan sel. Nukleokapsid ditransfer ke inti sel pejamu melewati sitoplasma, terjadi uncoating (selubung VHS lepas), dan akhirnya genom (DNA) VHS ditransfer ke inti sel pejamu. Setelah terjadi fusi amplop virion dengan membran sel pejamu, beberapa protein virus dilepaskan dari virion VHS. Beberapa protein tersebut menghentikan sintesa protein pejamu dan yang lainnya menghidupkan transkripsi early-genes untuk replikasi VHS. Early genes atau gen alfa diperlukan untuk sintesis kelompok polipetida, atau gen beta yang merupakan protein regulator dan enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA. Kelompok gen VHS yang ketiga adalah gen gamma yang dibutuhkan untuk replikasi DNA, yaitu untuk ekspresi dan penggantian protein struktural virus. Setelah replikasi genom virus dan pembentukan protein struktural virus, nukleokapsid di susun di inti sel pejamu. Pembentukan amplop melalui budding melewati membrana inti, ruang perinuclear dan akhirnya virion ditransfer melalui retikulum endoplasma dan apparatus golgi ke permukaan sel. Seluruh siklus replikasi ini membutuhkan waktu 12-16 jam.14,15 Replikasi VHS dalam sel epidermis dan dermis menghasilkan kerusakan sel dan inflamasi. Secara klinis tampak lesi vesikular di atas kulit eritem dan secara mikroskopis dijumpai multinucleated giant cells, nekrosis sel setempat dan degenerasi balon pada sel yang terinfeksi. Infeksi virus menyebabkan degenerasi balon dengan kromatin yang padat di dalam inti sel, diikuti degenerasi selular inti sel parabasal dan sel intermediate. Sel yang terinfeksi kehilangan kontak dengan plasma membran dan membentuk multinucleated giant cells. Bila sel mengalami lisis akan terlihat sebagai vesikel pada lapisan epidermis dan dermis. Cairan vesikel mengandung depris sel, sel-sel inflamasi, dan multinucleated giant cell. Pada lapisan subdermis terjadi respon inflamasi yang intens dan penyembuhan pada kulit di mulai dengan vesikel menjadi pustul dan akhirnya menjadi krusta. Pada mukosa tidak terbentuk krusta tetapi mudah menjadi ulkus dangkal. Pada infeksi inisial penyebaran infeksi virus dapat melalui sistem limfatik ke limfonodi regional. Saat infeksi inisial, virus secara asenden mencapai neuron sensoris perifer dan mengalami latensi pada ganglia saraf sensoris maupun autonom serta mempunyai hubungan permanen antara virus dengan pejamu. Saat latensi di ganglion dorsalis, virus melakukan replikasi dalam jumlah sangat terbatas dan transkripsi yang terjadi dikenal dengan LAT (latentcy associated transcripts).2,8,15-17 Pada model binatang percobaan, VHS terdeteksi di neuron ganglion 2 hari setelah infeksi. Replikasi virus dalam jaringan saraf terbatas tetapi mempunyai kemampuan untuk migrasi 183 TINJAUAN PUSTAKA kembali ke akson dekat tempat inokulasi awal sehingga dapat memperjelas luasnya area permukaan yang terlibat pada infeksi primer. Pada penderita yang imunokompeten replikasi virus ini terkendali dan terjadi penyembuhan (reepitealisasi).3 Reaktivasi dan replikasi VHS laten (infeksi rekuren) terjadi karena adanya stimuli multipel seperti dengan adanya pajanan sinar ultraviolet, immunsupreisan, demam, infeksi dan trauma pada neuron yang terinfeksi. Virus diantarkan di kulit kembali melalui saraf sensoris tepi dan mengadakan replikasi lagi di epidermis. Gejala yang timbul lebih ringan dibandingkan infeksi inisial, tergantung dari jumlah virus yang mengalami replikasi, virulensi strain VHS dan status imun penderita. Reaktivasi dan replikasi virus dapat terjadi secara periodik pada penderita asimtomatis dan pada fase ini virus dapat dideteksi walaupun tanpa gejala dan tanda dari penyakit.10,15 Respon Alamiah dan Adaptif Tubuh terhadap Infeksi VHS Virus adalah mikroorganisme obligat intraselular dan saat masuk ke dalam sel epitel, pertama kali direspon tubuh pejamu melalui barier mekanis, misalnya pada genitalia wanita, dengan adanya mukus, flora normal dan glikokaliks. Sekresi tersebut mengandung pula komplemen dan IgM alamiah yang akan mengurangi jumlah sel yang terinfeksi akan tetapi bila virus dapat menembus pertahanan ini tubuh berespon dengan stimulasi respon imun alamiah lainnya. Replikasi virus mengaktifkan komplemen, stimulasi kemokins dan interferon (IFNab). Substansi-substansi ini mengaktifkan endotel kapiler, menjadi bocor (leaky) dan mengekspresikan molekul adesi. Substansi tersebut pula yang mengaktifkan sel dentritik dan makrofag residen untuk mempresentasikan patogen. Sel dentritik imatur memakan antigen atau partikel VHS dan mengantarkan ke limfonodi regional untuk aktivasi sel T sebagai permulaan respon imun adaptif. Saat sel dentritik keluar dari mukosa yang terinfeksi, terjadi influks neutrofil, monosit dan sel pembunuh alami, atau sel NK (natural killer). Sel-sel ini melewati kapiler endotel yang teraktifasi dan mengikuti kemokins di tempat yang terinfeksi. Sel- sel ini berusaha untuk memfagositosis partikel virus dan sel-sel yang terinfeksi.13 Respon imun alamiah (innate) yang paling berperan terhadap infeksi virus adalah interferon tipe I (IFN) dan dimediasi oleh sel NK. Sel yang terinfeksi virus secara langsung memproduksi IFN dan menginduksi sel yang belum terinfeksi virus ke dalam antiviral state (keadaan di mana sel-sel pejamu mendapatkan kekebalan terhadap infeksi virus). IFN gamma mengaktifkan sel NK dan memfokuskan sel ini pada tempat infeksi. Sel NK juga merupakan mediator utama dalam antibodydependent cellular cytotoxicity (ADDC), yaitu sitotoksisitas sel yang tergantung antibodi. Sel NK melisiskan sel yang telah terinfeksi dan berperan penting sebelum terbentuknya respon imun yang adaptif. Sel NK aktif dapat terdeteksi 2 hari setelah infeksi virus. Sel NK mengenali sel yang terinfeksi karena tidak terekspresikan MHC kelas I.13,18-21 Respon imun adaptif dimulai dengan adanya sel 184 dentritik membawa antigen atau partikel virus ke limfonodi, mempresentasikan MHC (Major Histocompability Complex), mensekresikan sitokin dan menstimulasi sel T untuk berdiferensiasi menjadi sel Th1 dan Th2.13 Respon imun adaptif diperankan oleh antibodi dan sel limfosit sitotoksik. Antibodi berperan saat virus berada di ektraseluler, yaitu saat virus akan masuk ke dalam sel pejamu atau saat virus berada di luar sel, saat sel pejamu lisis akibat efek sitopatik virus. Antibodi berfungsi sebagai antiviral dengan atau tanpa bantuan komplemen. Antibodi antiviral ini berfungsi sebagai antibodi netralisir yang mencegah attachment dan entry ke dalam sel pejamu. Antibodi netralisir ini menyatu dengan amplop virus atau antigen kapsid. Antibodi netralisir menghambat terjadinya infeksi virus dan penyebaran virus dari sel ke sel, tetapi bila virus dapat masuk ke dalam sel, antibodi sudah tidak berperan. Sehingga pemberian vaksinasi ataupun imunitas humoral yang terbentuk dari infeksi sebelumnya hanya dapat memproteksi dengan mencegah terjadinya infeksi tetapi tidak dapat mengeliminasi infeksi virus yang telah terjadi.20 Untuk virus yang dapat masuk ke dalam sel pejamu (intraseluler), diatasi oleh respon imun adaptif yang diperankan oleh sel T sitotoksik (CD8). Sel T (CD8) mengenali sel terinfeksi karena adanya presentasi antigen oleh sel panyaji antigen, yaitu adanya ekspresi MHC kelas I. Diferensiasi sel CD8 juga memerlukan sitokin yang dihasilkan oleh sel CD4 T helper. Efek antiviral CD8 dengan cara melisiskan sel yang terinfeksi dan aktivasi enzim nuklease di dalam sel terinfeksi sehingga genom virus terdegradasi dan tersekresi sitokin dengan aktivitas IFN. Virus Herpes Simpleks tetap mengadakan upaya untuk menghindarkan diri dari pengenalan oleh CD8, yaitu dengan menghasilkan protein ICP-47 yang mengikat pada TAP (transporter associated within antigen processing). Hal ini akan mencegah transporter menangkap peptida sitosolik yang dibawa ke dalam retikulum endoplasma untuk pengikatan molekul kelas I. Ini dikenal dengan mekanisme shutt off MHC kelas I. (bagan pathway class I MHC). Dengan demikian MHC kelas I tidak terekspresikan sehingga sel terinfeksi tersebut tidak dikenali oleh sel CD8. Akan tetapi tubuh mengatasi hal ini dengan adanya sel NK yang dapat berespon melawan sel terinfeksi virus tersebut walaupun tidak mengekspresikan MHC kelas I.19,20 Pada fase laten, virus di neuron tidak melakukan replikasi dan tidak menimbulkan penyakit (infeksius). Sel neuron sensoris tetap terinfeksi namun virus dalam keadaan quiescent (diam, tanpa gerak) dan peptida yang dihasilkan sedikit, sehingga hanya sedikit pula yang dipresentasikan sebagai MHC kelas I. Neuron yang tidak mengekspresikan MHC kelas I membuat sel T sitotoksik (CD8) tidak mengenalinya. Keadaan ini menguntungkan, karena sel T (CD8) tidak merusak neuron yang mempunyai regenerasinya memang lambat. Pada keadaan tertentu virus dapat menjadi aktif, menuju ke sel epidermis yang diinervasi saraf terinfeksi tersebut dan mengadakan replikasi sehingga siklus berulang kembali dan menjadi infeksius yang No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA disebut infeksi rekuren.22,23 Pada infeksi rekuren, 90% didahului adanya gejala prodromal sebelum timbul erupsi. Gejala prodromal hanya berupa rasa tingling selama 0,5 sampai 48 jam, akan tetapi dapat pula disertai nyeri menusuk pada pantat, paha dan pinggang yang dapat berlangsung 1-5 hari sebelum timbal erupsi. Diagnosis 1. Manifestasi klinis Gambaran klinis HG primer dan HG rekuren sangat berbeda. Pada infeksi primer disertai dengan adanya gejala sistemik (demam, nyeri kepala, malaise dan myalgia), durasi penyakit lebih lama (bisa sampai 20 hari), lesi genital yang multipel dan disertai lesi ektragenital. Gejala lokal antara lain: nyeri, gatal, disuria, discar uretra atau vagina, dan pembengkakan limfonodi inguinal. Lesi klasik dimulai dengan makula dan papul yang berkembang menjadi vesikel, pustul dan ulkus. Kulit akan menjadi krusta sedangkan pada mukosa terjadi ulkus dangkal.10 Penderita yang mengalami infeksi primer (baik infeksi VHS1 atau VHS2) mengalami gejala penyakit yang lebih berat dibandingkan yang secara klinis ataupun serologis telah terinfeksi VHS-1 sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada infeksi berikutnya sudah terbentuk antibodi spesifik dan infeksi VHS-1 dapat memberikan proteksi parsial terhadap infeksi VHS-2.24 Gambaran klinis herpes genitalis rekuren lebih terlokalisasi di genital area. Gejala nyeri, gatal lebih ringan dibandingkan pada infeksi primer. Pada infeksi rekuren, 90% didahului adanya gejala prodromal sebelum timbul erupsi. Gejala prodromal hanya berupa rasa tingling selama 0,5 sampai 48 jam, akan tetapi dapat pula disertai nyeri menusuk pada pantat, paha dan pinggang yang dapat berlangsung 1-5 hari sebelum timbul erupsi. 2. Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang sangat diperlukan bila secara klinis tidak menunjukkan gejala dan tanda khas (klasik) apalagi pada herpes genitalis dapat bersifat asimtomatis sehingga penderita tidak menyadari menjadi sumber penularan. Kultur viral dan viral typing masih merupakan baku emas dalam mendiagnosis infeksi herpes dengan spesifisitas 100% akan tetapi sensitivitasnya tergantung dari episode infeksinya. Pada infeksi primer sensitivitasnya 74% dan 50% pada infeksi rekuren. Sampel sebaiknya diambil pada awal penyakit dan tidak melewati fase erupsi vesikuler. Sel yang terinfeksi virus banyak didapatkan pada tepi dan di dasar lesi. VHS adalah virus yang tumbuh cepat dan memperlihatkan efek sitopatik pada kultur sel dalam 24 jam. Virus ini dapat diisolasi dalam berbagai sel, seperti sel embrionik paru manusia, ginjal kelinci, HEp2 (berasal dari karsinoma laring manusia) dan A549 (karsinoma paru manusia).4,15,17,25 Deteksi antigen VHS dapat dilakukan dengan metode PCR (polymerase chain reaction) walaupun penggunaannya masih terbatas untuk penelitian. Metode ini mempunyai spesifisitas dan sensitivitas yang lebih tinggi dari kultur. Pemeriksaan ini berdasarkan amplifikasi DNA VHS dan hasil dapat diketahui dalam 2 hari.18,26,27 Tes Tzanck (pemeriksaan sitologi) bertujuan untuk No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 melihat efek sitopatik pada sel epitel. Sel membesar, dengan intranuclear inclusion dan sering terjadi fusi sel yang memberi gambaran multinucleated giant cell. Pemeriksaan Tzanck mempunyai sensitivitas yang rendah dan tidak dapat membedakan VHS-1 dan VHS-2 ataupun virus varisela-zoster.24,28 Pemeriksaan penunjang secara indirek (serologis) saat ini ada 3 macam yang telah disetujui oleh FDA (Food and Drug Association), yaitu Herpes Western Blot, Herpect Select (Elisa dan Immnublot Kit) dan POC Rapid Test. Herpes Western Blot merupakan baku emas dalam mendeteksi antibodi terhadap VHS dan dengan pemeriksaan ini dapat membedakan VHS-1 dan atau VHS-2. Dengan demikian tes ini dapat mengetahui adanya serokonversi awal VHS2 pada penderita yang sebelumnya terinfeksi VHS-1. Kekurangan pemeriksaan ini adalah harganya mahal, tidak tersedia secara komersil (University of Washington, Amerika Serikat) dan masih memerlukan 2-5 hari untuk mengetahui hasil.26-29 Pemeriksaan EIAs (enzyme-linked immunosorbent assays) berdasarkan deteksi glikoprotein yang spesifik seperti glikoprotein G meningkatkan sensitivitas dan spesifitasnya menjadi 93-98%. Test ini masing-masing untuk VHS-1 dan ada untuk VHS-2. Tes ini diproduksi oleh Focus Technologies, dengan nama ELISA Kits dan Immunoblot Kit.24,26,27 Saat ini juga tersedia pemeriksaan yang dapat dipakai mendeteksi antibodi secara lebih cepat dan dapat dipakai langsung di klinik. Contoh yang telah mendapatkan persetujuan FDA dan khusus untuk mendeteksi antibodi terhadap VHS-2 adalah POCkit HSV-2 Rapid Test (Diagnology Incoporation) yang mempunyai sensitivitas 96% 185 TINJAUAN PUSTAKA dan spesifisitas 87-98%.15,16,18 Tes ini lebih cepat hasilnya karena memerlukan hanya kurang dari 10 menit dan darah diambil dari tusukan jari saja.30,31 Tes serologis berguna pada penderita dengan manifestasi klinis yang tidak klasik (konfirmasi diagnosis), untuk skrining pada yang orang yang berisiko tinggi terinfeksi VHS seperti pada penderita HIV, penderita dengan penyakit menular seksual lainnya, atau penderita dengan partner dengan riwayat herpes. Semua tes ini direkomendasikan untuk dikerjakan 12-18 minggu setelah paparan VHS, karena pada saat itu telah melewati window period dan telah terbentuk antibodi.30,31 Kesimpulan Virus herpes simpleks (VHS) adalah virus double standed DNA yang terdiri dari dua serotipe VHS1 dan VHS2. VHS sebagai penyebab herpes genital menginfeksi tubuh melalui lesi abrasi yang secara klinis dapat ditegakkan dengan dijumpai lesi papul vesikel yang menjadi ulkus dangkal pada area genital. Pemeriksaan penunjang sederhana yang dapat dikerjakan adalah tes Tzanck dengan menemukan multinucleated giant cell sedangkan secara serologis dengan pemeriksaan Herpes Western Blot, Herpect Select (Elisa dan Immunublot Kit) dan POC Rapid Test. Herpes genital masih merupakan penyakit menular seksual yang tidak dapat sembuh permanen. Berat ringannya penyakit yang diakibatkan virus ini tergantung oleh respon imun tubuh dalam usahanya mengeliminasi virus. Respon imun pada penderita dengan infeksi VHS terdiri dari respon imun alamiah dan adaptif, baik selular maupun humoral. Virus yang berada di ekstraselular dihambat oleh INF dan antibodi netralisir sedangkan yang berperan dalam menghambat virus intraselular adalah sel NK dan sel CD8 sitotoksik. Akan tetapi infeksi VHS tetap dapat berlangsung seumur hidup karena selalu adanya upaya penghindaran VHS terhadap sistem imun pejamu. Daftar Pustaka 1. Crumpacker CS. Herpes simplex. In: Freeberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, et al.(eds). Dermatology in General Medicine. 4th ed. New York:McGraw-Hill, 1999.p.2414-25 2. Pertel PE and Spear PG. Biology of herpesviruses. In: Holmes KK, Sparling PF, Mardh PA, et al.(eds). Sexually Transmitted Diseases. 3rd ed. New York:McGraw-Hill; 1999.p.269-78 3. Corey L and Wald Ann. Genital herpes. In: Holmes KK, Sparling PF, Mardh PA, et al.(eds). Sexually Transmitted Diseases. 3rd ed. New York:McGraw-Hill; 1999.p.285-306 4. Oates JK. Anogenital herpes. In: Csonka and Oates (eds). Sexually Transmitted Diseases. A Textbook of Genitourinary Medicine. London: Bailleire Tindall; 1990.p.129-51 5. Berger TG, James WD, and Odom RB (eds). Herpes simplex. In: Andrew’s Diseases of the Skin. 9th ed. Philadelphia:WB Saunders Company; 2001.p.473-82 6. Habib TP. Genital herpes simplex. In: Clinical Dermatology. 4th ed. Edinburgh:Mosby; 2004.p.346-55 7. Heaton CL. Herpes simplex. In: Moschella SL and Hurley HJ (eds). Dermatology. 3rd ed. Philadelphia:WB Saunders Company; 1992. 186 p.791-6 8. Patel R. Genital Herpes. In: Medicine International. Vol 36; 1996.p.80-2 9. Patrick TB, Johnson RA, Surmond D, et al. Herpes simplex virus: Genital infection. In: Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, 4th ed. International Edition; 2001.p.874-81 10. Kimberlin DW and Rouse DJ. Genital herpes. N Engl J Med 2004; 350:1970-7 11. Arvin AM. Herpes simplex virus type 2. A persistent problem. N Engl J Med 1997; 337:1158-9 12. Roe VA. Living with genital herpes. How effective is antiviral therapy? J Perinat Neonat Nurs 2004; 18(3):206-15 13. Ashley RL and Wald A. Genital herpes: Review of the epidemic and potensial use of type-spesific serology. Clinical Microbiology Review 1999; 12(1):1-8 14. Brooks GF, Butel JS, and Ornston LN. Herpes viruses. In: Jawets, Melnick and Adelberg’s. Medical Microbiology. 20th ed. London: Prentice International Hall; 1995.p. 358-67 15. Duerst RJ and Morrison LA. Review innate immunity to herpes simples virus type 2. Viral Immunology 2003; 16(4):475-90 16. Whitley RJ, Kimbelin DW, and Roizman B. Herpes simples virus. Clinical Infectious Diseases 1998; 26:541-55 17. Morrison LA. Vaccine against genital herpes. Drugs 2002; 62(8):1119-29 18. Bellanti JA. Mechanisms of immunity to viral diseases. In: Immunology III. 2nd ed. Philadelphia:Saunders Co.; 1985.p.283-305 19. Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunity to viruses. In: Immunology. 6th ed. London:Mosby; 2001.p.235-42 20. Abbas AK, Lichtman AH, and Pober JS. Immunity to microbes. In: Cellular and Molecular Immunology. 4th ed. Philadelphia:WB Saunders Company; 2000.p.343-62 21. Mary Norval. Viral infection. In: Bos JD (ed). Skin Immune System (SIS). 2nd edition. New York:CRP Press; 1997.p.555-68 22. Lemon SM and Sparling PF. Pathogénesis of sexually transmitted viral and bacterial infections. In: Holmes KK, Sparling PF, Mardh PA, et al.(eds). Sexually Transmitted Diseases. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1999.p.205-11 23. Janeway CA, Travers P, Walport M, et al. Failure of host defence mechanism. In: Janeway (ed), Immunobiology. 4th ed. New York: Garland Publishining; 2001.p.425-65 24. Xu F, Schillinger JA, Stenberg MR, et al. Seroprevalence and co infection with herpes simples virus type 1 and type 2 in the United Status, 1988-1994. The Journal Infectious Diseases 2002; 185:1094-24 25. Barton S, Brown D, Cowan FM, et al. National guidelines for management of genital herpes. Diakses melalui internet http:// search epnet.com 26. Davison VE and Alderson GL. Clinical virology. In: Mahon CR (eds). Textbook of diagnostic microbiology. Philadelphia. WB Saunders, 1995.p.796-826 27. Lowy, DR. Viral diseases: General considerations. In: Freeberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al.(eds) Dermatology in General Medicine. 4th ed. New York:McGraw-Hill; 1999.p.2389-2394 28. Cusini M and Ghislanzoni M. The importance of diagnosing genital herpes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2001;47:9-16 29. Stanberry L, Cunningham A, Mertz G, et al. Mini review: New developments in the epidemiology, natural history and management of genital herpes. Antiviral Research 1999; 42:1-14 30. Mark HD, Hanahan AP and Stender SC. Herpes simplex virus type 2: An update. The Nurse Practioner 2003; 28(11):34-40 31. Wald A and Asley-Morrow R. Serological testing for herpes simplex virus (HSV)-1 and HSV-2 infection. Clinical Infectious Diseases 2002; 35:S173-82 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Infeksi Cacing Tambang Mangatas SM Manalu*, SI Biran** * Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam ** Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Bagian/SMF ilmu Penyakit Dalam FK UNUD/RS Sanglah Denpasar - Bali Abstrak. Infeksi cacing tambang masih menjadi masalah kesehatan yang besar di Indonesia karena merupakan salah satu penyebab utama anemia defisiensi besi. Dan juga menyebabkan kekurangan protein. Pada akhirnya infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pada neonatus, hambatan tumbuh kembang balita dan penurunan kecerdasan anak usia sekolah serta produktivitas kerja orang dewasa. Pengenalan dan pemahaman akan penyakit yang “sederhana” ini serta pengkajian terapinya diharapkan akan membantu para klinisi untuk dapat melakukan pencegahan dan diagnosis, mengingat belum ditemukannya vaksinasi dan terapi imunologis yang efektif untuk infeksi cacing tambang. Kata kunci: Infeksi cacing tambang, anemia, diagnosis, pencegahan Pendahuluan nfeksi cacing tambang pada manusia terutama disebabkan oleh Ancylostoma duodenale (A. duodenale) dan Necator americanus (N. americanus).1,2 Kedua spesies ini termasuk dalam famili Ancylostomidae dari filum Nematoda.3 Selain kedua spesies tesebut, dilaporkan juga infeksi zoonosis oleh A. braziliense dan A. caninum yang ditemukan pada berbagai jenis karnivora dengan manifestasi klinik yang relatif lebih ringan, yaitu creeping eruption akibat cutaneus larva migrans. Terdapat juga infeksi A. ceylanum yang diduga menyebabkan enteritis eosinofilik pada manusia.2 Diperkirakan terdapat 1 miliar orang di seluruh dunia yang menderita infeksi cacing tambang dengan populasi penderita terbanyak di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia dan subsahara Afrika. Infeksi N. americanus lebih luas penyebarannya dibandingkan A. duodenale, dan spesies ini juga merupakan penyebab utama infeksi cacing tambang di Indonesia.1 Infeksi A. duodenale dan N. americanus merupakan penyebab terpenting dari anemia defisiensi besi. Selain itu infeksi cacing tambang juga merupakan penyebab hipoproteinemia yang terjadi akibat kehilangan albumin karena perdarahan kronik pada saluran cerna. Anemia defisiensi besi dan hipoproteinemia sangat merugikan proses I No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 tumbuh kembang anak dan berperan besar dalam mengganggu kecerdasan anak usia sekolah.1,2 Penyakit akibat cacing tambang lebih banyak didapatkan pada pria yang umumnya sebagai pekerja di keluarga. Hal ini terjadi karena kemungkinan paparan yang lebih besar terhadap tanah terkontaminasi larva cacing.2,4,5 Sampai saat ini infeksi cacing tambang masih merupakan salah satu penyakit tropis terpenting. Penurunan produktivitas sebagai indikator beratnya gangguan penyakit ini, menempatkan infeksi cacing tambang di atas tripanosomiasis, demam dengue, penyakit chagas, schisostomiasis dan lepra.2 Siklus Biologis Cacing Tambang Cacing tambang jantan berukuran 8-11 mm sedangkan yang betina berukuran 10-13 mm. Cacing betina menghasilkan telur yang keluar bersama feses pejamu (host) dan mengalami pematangan di tanah. Setelah 24 jam telur akan berubah menjadi larva tingkat pertama (L1) yang selanjutnya berkembang menjadi larva tingkat kedua (L2) atau larva rhabditiform dan akhirnya menjadi larva tingkat ketiga (L3) yang bersifat infeksius. Larva tingkat ketiga disebut sebagai larva filariform. Proses perubahan telur sampai menjadi larva filariform terjadi dalam 24 jam.3,5 Larva filariform kemudian menembus kulit terutama kulit tangan 187 TINJAUAN PUSTAKA dan kaki, meskipun dikatakan dapat juga menembus kulit perioral dan transmamaria. Adanya paparan berulang dengan larva filariform dapat berlanjut dengan menetapnya cacing di bawah kulit (subdermal). Secara klinis hal ini menyebabkan rasa gatal serta timbulnya lesi papulovesikular dan eritematus yang disebut sebagai ground itch.2,4,6 Dalam 10 hari setelah penetrasi perkutan, terjadi migrasi larva filariform ke paru-paru setelah melewati sirkulasi ventrikel kanan. Larva kemudian memasuki parenkim paruparu lalu naik ke saluran nafas sampai di trakea, dibatukkan, dan tertelan sehingga masuk ke saluran cerna lalu bersarang terutama pada daerah 1/3 proksimal usus halus. Pematangan larva menjadi cacing dewasa terjadi disini. Proses dari mulai penetrasi kulit oleh larva sampai terjadinya cacing dewasa memerlukan waktu 6-8 minggu. Cacing jantan dan betina berkopulasi di saluran cerna selanjutnya cacing betina memproduksi telur yang akan dikeluarkan bersama dengan feses manusia. Pematangan telur menjadi larva terutama terjadi pada lingkungan pedesaan dengan tanah liat dan lembab dengan suhu antara 23-33o C. Penularan A. duodenale selain terjadi melalui penetrasi kulit juga melalui jalur orofekal, akibat kontaminasi feses pada makanan. Didapatkan juga bentuk penularan melalui hewan vektor (zoonosis) seperti pada anjing yang menularkan A. brazilienze dan A. caninum. Hewan kucing dan anjing juga menularkan A. ceylanum. Jenis cacing yang yang ditularkan melalui hewan vektor tersebut tidak mengalami maturasi dalam usus manusia.2,5,6 Cacing N. americanus dewasa dapat memproduksi 5.00010.000 telur/hari dan masa hidup cacing ini mencapai 3-5 tahun, sedangkan A. duodenale menghasilkan 10.000-30.000 telur/hari, dengan masa hidup sekitar 1 tahun.4,5 Selengkapnya siklus biologis cacing tambang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: Larva masuk/ penetrasi ke kulit, masuk ke aliran darah Larva di atas rumput Larva menetas dan berkembang didalam Larva Telur dikeluarkan bersama dengan feces Telur Cacing dewasa Larva dewasa masuk ke usus halus Larva dibatukkan dan tertelan Gambar 1. Siklus biologis cacing tambang2 188 Masa inkubasi mulai dari bentuk dewasa pada usus sampai dengan timbulnya gejala klinis seperti nyeri perut, berkisar antara 1-3 bulan. Untuk meyebabkan anemia diperlukan kurang lebih 500 cacing dewasa. Pada infeksi yang berat dapat terjadi kehilangan darah sampai 200 ml/ hari, meskipun pada umumnya didapatkan perdarahan intestinal kronik yang terjadi perlahan-lahan Patofisiologi Cacing tambang memiliki alat pengait seperti gunting yang membantu melekatkan dirinya pada mukosa dan submukosa jaringan intestinal. Setelah terjadi pelekatan, otot esofagus cacing menyebabkan tekanan negatif yang menyedot gumpalan jaringan intestinal ke dalam kapsul bukal cacing. Akibat kaitan ini terjadi ruptur kapiler dan arteriol yang menyebabkan perdarahan. Pelepasan enzim hidrolitik oleh cacing tambang akan memperberat kerusakan pembuluh darah. Hal itu ditambah lagi dengan sekresi berbagai antikoagulan termasuk diantaranya inhibitor faktor VIIa (tissue inhibitory factor). Cacing ini kemudian mencerna sebagian darah yang dihisapnya dengan bantuan enzim hemoglobinase, sedangkan sebagian lagi dari darah tersebut akan keluar melalui saluran cerna.2,4,5 Masa inkubasi mulai dari bentuk dewasa pada usus sampai dengan timbulnya gejala klinis seperti nyeri perut, berkisar antara 1-3 bulan. Untuk meyebabkan anemia diperlukan kurang lebih 500 cacing dewasa. Pada infeksi yang berat dapat terjadi kehilangan darah sampai 200 ml/hari, meskipun pada umumnya didapatkan perdarahan intestinal kronik yang terjadi perlahan-lahan.1,2,4,5 Terjadinya anemia defisiensi besi pada infeksi cacing tambang tergantung pada status besi tubuh dan gizi pejamu, beratnya infeksi (jumlah cacing dalam usus penderita), serta spesies cacing tambang dalam usus. Infeksi A. duodenale menyebabkan perdarahan yang lebih banyak dibandingkan N. americanus.2,4,5 Manifestasi Klinis Anemia defisiensi besi akibat infeksi cacing tambang menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Pada wanita yang mengandung, anemia defisiensi besi menyebabkan peningkatan mortalitas maternal, gangguan No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA laktasi dan prematuritas. Infeksi cacing tambang pada wanita hamil dapat menyebabkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Diduga dapat terjadi transmisi vertikal larva filariform A. duodenale melalui air susu ibu.1,2,5 Pada daerah subsahara Afrika sering terjadi infeksi campuran cacing tambang dan malaria falsiparum. Diduga infeksi cacing tambang menyebabkan eksaserbasi anemia akibat malaria falsiparum dan sebaliknya.2 Kebanyakan infeksi cacing tambang bersifat ringan bahkan asimtomatik. Dalam 7-14 hari setelah infeksi terjadi ground itch. Pada fase awal, yaitu fase migrasi larva, dapat terjadi nyeri tenggorokan, demam subfebril, batuk, pneumonia dan pneumonitis. Kelainan paru-paru biasanya ringan kecuali pada infeksi berat, yaitu bila terdapat lebih dari 200 cacing dewasa. Saat larva tertelan dapat terjadi gatal kerongkongan, suara serak, mual, dan muntah. Pada fase selanjutnya, saat cacing dewasa berkembang biak dalam saluran cerna, timbul rasa nyeri perut yang sering tidak khas (abdominal discomfort). Karena cacing tambang menghisap darah dan menyebabkan perdarahan kronik, maka dapat terjadi hipoproteinemia yang bermanifestasi sebagai edema pada wajah, ekstremitas atau perut, bahkan edema anasarka.1,2,4,5 Anemia defisiensi besi yang terjadi akibat infeksi cacing tambang selain memiliki gejala dan tanda umum anemia, juga memiliki manifestasi khas seperti atrofi papil lidah, telapak tangan berwarna jerami, serta kuku sendok. Juga terjadi pengurangan kapasitas kerja, bahkan dapat terjadi gagal jantung akibat penyakit jantung anemia.3 Respons Imun Terhadap Infeksi Cacing Tambang a. Terhadap larva filariform Saat menembus kulit, larva filariform melepaskan bagian luar kutikula dan mensekresi berbagai enzim yang mempermudah migrasinya. Pada proses ini banyak larva yang mati dan mengakibatkan pelepasan berbagai molekul imunoreaktif oleh tubuh. Saat memasuki sirkulasi, terutama sirkulasi peparu, larva filariform menghasilkan berbagai antigen yang bereaksi dengan sistem imun peparu dan menyebabkan penembusan sejumlah kecil alveoli. Pada infeksi zoonotik (melalui vektor), terjadi creeping eruption atau ground itch akibat terperangkapnya larva dalam lapisan kulit, yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe I (alergi). Jumlah larva yang masuk ke sirkulasi jauh lebih banyak dari yang berdiam di kulit. Pada infeksi antropofilik (langsung pada manusia) tidak terjadi kumpulan larva di kulit.3 Antibodi humoral terhadap N. americanus hanya reaktif terhadap lapisan dalam kutikula, hal ini menjelaskan mengenai minimnya reaksi kulit terhadap parasit ini. Antibodi yang berperan ialah Imunoglobulin M (IgM), IgG1 dan IgE. Yang paling spesifik ialah IgE yang bersifat cross reactive. Diduga reaksi hipersensitivitas tipe II (antibody dependent cell mediated cytotoxicity) juga berperan No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 disini.2,3 Sistem kekebalan seluler pada infeksi cacing tambang terutama dilakukan oleh eosinofil. Hal ini dicerminkan oleh tingginya kadar eosinofil darah tepi. Eosinofil melepaskan superoksida yang dapat membunuh larva filariform. Jumlah eosinofil makin meningkat saat larva berkembang menjadi bentuk dewasa (cacing) di saluran cerna. Sistem komplemen berperan dalam perlekatan larva pada eosinofil.3,7 Bukti-bukti penelitian menunjukkan bahwa eosinofil lebih berperan dalam membunuh larva filariform, bukan terhadap bentuk dewasa. Interleukin-5 (IL-5) yang berperan dalam pertumbuhan dan diferensiasi eosinofil meningkat pada infeksi larva yang diinokulasikan pada tikus percobaan. Pada manusia hal tersebut belum terbukti.3 b. Respons terhadap infeksi cacing tambang dewasa Respons humoral dilakukan oleh IgG1, IgG4 dan IgE, yang dikontrol oleh pelepasan sitokin pengatur sel Th2. Sitokin yang utama, ialah IL-4. Pada percobaan, setelah 1 tahun pemberian terapi terhadap infeksi N. americanus, didapatkan bahwa kadar IgG terus menurun sementara kadar IgM dapat meningkat kembali meskipun tidak setinggi seperti sebelum dilakukan terapi. Di sini kadar IgE hanya menurun sedikit, sedangkan kadar IgA dan IgD meningkat setelah 2 tahun pasca terapi. Para pakar menyimpulkan bahwa dibutuhkan lebih sedikit paparan antigen untuk meningkatkan IgE, IgA dan IgD dibandingkan untuk meningkatkan IgG dan IgM. Selain itu disimpulkan bahwa kadar IgG dan IgM merupakan indikator terbaik untuk infeksi cacing tambang dewasa dan untuk menilai efikasi pengobatan. Hanya sedikit bukti yang menyatakan bahwa kadar antibodi berhubungan dengan imunoproteksi terhadap infeksi cacing tambang Anemia defisiensi besi yang terjadi akibat infeksi cacing tambang selain memiliki gejala dan tanda umum anemia, memiliki manifestasi khas seperti atrofi papil lidah, telapak tangan berwarna jerami, serta kuku sendok. Terjadi pengurangan kapasitas kerja, bahkan dapat terjadi gagal jantung akibat penyakit jantung anemia. 189 TINJAUAN PUSTAKA dewasa.3 Sitokin perangsang sel T helper 2 (Th2), yaitu IL-4, IL-5 dan IL-13 yang merangsang sintesis IgE, merupakan sitokin yang predominan, sedangkan sitokin perangsang sel Th1 seperti interferon yang menghambat produksi IgE, lebih sedikit ditemukan. Para peneliti membuktikan bahwa IgE lebih sensitif untuk menentukan adanya infeksi baik infeksi larva maupun cacing tambang dewasa, sedangkan IgG4 lebih spesifik sebagai marker infeksi cacing dewasa N. americanus. Pada infeksi A. caninum, ternyata IgE lebih spesifik dibandingkan IgG4.2,3 Peran IgG4 belum diketahui sepenuhnya. Kemungkinan IgG4 berperan menghambat respons imun dengan inhibisi kompetitif terhadap mekanisme kekebalan tubuh yang dimediasi oleg IgE, misalnya aktivasi sel mast. Imunoglobulin G4 tidak mengikat komplemen dan hanya mengikat reseptor Fc-g secara lemah. Pada infeksi cacing tambang didapatkan fenomena pembentukan autoantibodi IgG terhadap IgE.3 Respons imun seluler terhadap infeksi cacing tambang dewasa adalah terutama oleh adanya respons sel Th2 yang mengatur produksi IgE dan menyebabkan eosinofilia. Terjadinya eosinofilia dimulai segera setelah L3 menembus kulit dengan puncak pada hari ke 38 sampai hari ke 64 setelah infeksi. Sel mast yang terdegradasi akibat pengaruh IgE melepaskan berbagai protease terhadap kutikula kolagen N. americanus. Selain itu terjadi pelepasan neutralizing antibody terhadap IL-9, yang akan menghambat perusakan sel mast oleh enzim mast cells protease I. Cacing tambang tampaknya lebih tahan terhadap reaksi inflamasi dibandingkan dengan famili nematoda lainnya.3,7 c. Bentuk larva hipobiosis Pada infeksi A. duodenale dapat terjadi bentuk hipobiosis di mana terjadi penghentian pertumbuhan larva pada jaringan otot. Pada waktu tertentu, misalnya saat mulai bersinarnya bulan ini, merupakan saat yang optimal untuk pelepasan larva A. doudenale. Penyebab fenomena tersebut tidak diketahui. Pada bentuk hipobiosis pelepasan telur cacing melalui feses baru terjadi 40 minggu setelah masuknya larva A. duodenale melalui kulit. Fenomena ini juga terjadi pada infeksi A. caninum pada anjing. Buktibukti menunjukkan bahwa aktivasi bentuk hipobiosis pada akhir kehamilan yang berakhir dengan penularan transmamaria/transplasental dari A. duodenale.3 Proteksi Sistem Imun Terhadap Infeksi Cacing Tambang Tidak terdapat bukti yang jelas mengenai proteksi imunologis tubuh terhadap infeksi cacing tambang. Beberapa penelitian di Papua New Guinea menunjukkan bahwa penderita yang memiliki titer IgE lebih tinggi, lebih jarang mengalami reinfeksi N. americanus.3,7 190 Diagnosis Cacing Tambang I. Secara klinis dan epidemiologis II. Pemeriksaan penunjang saat awal infeksi (fase migrasi larva) mendapatkan: a. eosinofilia (1.000-4.000 sel/ml) b. feses normal c. infiltrat patchy pada foto toraks d. peningkatan kadar IgE Pemeriksaan feses basah dengan fiksasi formalin 10% dilakukan secara langsung dengan mikroskop cahaya. Pemeriksaan ini tidak dapat membedakan N. americanus dan A. duodenale. Pemeriksaan yang dapat membedakan kedua spesies ini ialah dengan faecal smear pada filter paper strip Harada-Mori. Kadang-kadang perlu dibedakan secara mikroskopis antara infeksi larva rhabditiform (L2) cacing tambang dengan larva cacing strongyloides stercoralis.4-6,8 III. Pemeriksaan penunjang pada cacing tambang dewasa 1. Didapatkan telur cacing dan atau cacing dewasa pada pemeriksaan feses. 2. Tanda-tanda anemia defisiensi besi yang sering dijumpai adalah anemia mikrositik-hipokrom, kadar besi serum yang rendah, kadar total iron binding capacity yang tinggi. Di sini perlu dieksklusi penyebab anemia hipokrom mikrositer lainnya. 3. Dapat ditemukan peningkatan IgE dan IgG4, tetapi pemeriksaan IgG4 tidak direkomendasikan karena tinggi biayanya.2,4,5,8 Pengobatan Infeksi Cacing Tambang 1. Pada fase migrasi larva Batuk-batuk dan bronkokonstriksi diatasi dengan agonis b2 inhalasi. Pemberian inhalasi steroid dapat menyebabkan eksaserbasi gejala pulmonal, terutama bila terdapat ko-infeksi cacing strongyloides stercoralis.2,4 2. Fase infeksi awal (ground itch) Diatasi terutama dengan thiabendazole topikal 3. Fase infeksi lanjut Diet tinggi protein dan suplemen besi diperlukan untuk mengatasi anemia dan hipoproteinemia. Jika terjadi perdarahan yang hebat (>200 ml/hari) diperlukan transfusi darah, demikian juga jika terjadi penyakit jantung anemia.2,4,8 Badan kesehatan dunia (WHO) menganjurkan pemberian mebendazole dan pirantel pamoate, dengan pemberian ½ dosis dewasa untuk anak-anak usia 2-12 tahun. Pemberian obat antihelmintik untuk anak berusia di bawah 2 tahun belum direkomendasikan keamanannya, sedangkan untuk wanita hamil, obat cacing tambang dapat diberikan pada trimester II dan III. Selengkapnya obat-obatan anti cacing tambang terdapat pada tabel 1 berikut ini. No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 TINJAUAN PUSTAKA Tabel 1. Obat yang direkomendasikan WHO untuk infeksi cacing tambang.4 Nama Obat Pyrantel pamoate (Antimint, Pin-Rid, Pin-X) agen penghambat depolarisasi neoromuskular. Menghambat kolinesterase, sehingga menyebabkan poralisis spastik pada cacing. Aktif melawan Enterobius Vermicularis (pinworm), ascaris lumbricoides (round-worm), A.duodenale (hook worm) obat pencahar tidak dibutuhkan dan boleh diminum dengan susu atau Jus buah. Dosis dewasa 11 mg/kg/hari peroral selama 3 hari, tidak lebih dari 1 gr/hari. Dosis anak 11 mg/kg/hari peroral selama 3 hari, tidak lebih dari 500 gr/hari. Kontraindikasi Hipersensitif, penyakit hati Interaksi Kadar serum teofilin dapat meningkat pada pasien anak-anak setelah pemberian pirantel pamoet Kehamilan C - keamanan untuk penggunaan pada wanita hamil belum ditetapkan Perhatian perhatian pada kerusakan hati, anemia dan mal nutrisi Nama Obat Mebendazole (vermox) menyebabkan kematian cacing secara efektif dan secara irreversible menghambat uptake glukosa dan nutrien lain pada usus manusia yang rentan , yang menjadi tempat tinggal bagi cacing Dosis dewasa 100 mg per oral, 2 kali sehari selama 3 hari atau 500 mg per oral sekali Dosis anak < 2 tahun : belum ditentukan > 2 tahun : berikan seperti orang dewasa Kontraindikasi hipersensitif Interaksi Kehamilan Perhatian Nama Obat karbamazepin dan fenitroin dapat menurunkan efek mebendazole cimeditin dapat meningkatkan kadar mebendezole C – keamanan untuk penggunaan pada wanita hamil belum ditetapkan. Penyesuaian dosis pada gangguan hati Albendazole (Albenza) – menurunkan produksi atp pada cacing, menyebabkan penurunan energi, immobilisasi, dan akhirnya cacing menjadi mati Dosis dewasa 400 mg sekali per oral Dosis anak 200 – 400 mg sekali per oral Kontraindikasi Hipersensitif Interactions Pregnancy Perhatian Nama Obat Pemberian bersamaan dengan karbamazepin dapat menurunkan efikasi, deksametason, cimisidine dan praziquantel dapat meningkatkan toksisitas C – Kehamilan untuk penggunaan pada wanita hamil belum ditetapkan Hentikan jika terjadi peningkatan LFTs yang signifikan (lanjutan pengobatan jika kadar menurun untuk menilai protest) Thiabendazole (Mintezol) – menghambat cacing yang spesifik pada microchondria fumarate reductase dan mengurangi gejala trikinosis selama fase infasiv untuk penggunaan topical. Dosis dewasa 0.25 – 1.5 g per oral 2 kali sehari selama 2 hari, tidak lebih dari 3 g/hari Dosis anak 50 mg /kg/hari per oral, dibagi dalam 2 dosis selama 2 hari, tidak lebih dari 3 g/hari Kontraindikasi Hipersensitif Interaksi Dapat meningkatkan kadar serum teofillin , meningkatkan toksisitas (amati kadar serum dan kurangi dosis bila perlu) Pregnancy C – Kehamilan untuk penggunaan pada wanita hamil belum ditetapkan Perhatian Pengawasan yang ketat pada disfungsi hati atau ginjal , sebelum memulai terapi, terapi suportif perlu dilakukan pada pasien anemia , dehidrasi , atau mal nutrisi digunakan bila benar ada parasit cacing (bukan profilaksis), dapat menyebabkan mual, muntah dan depresi susunan saraf pusat. Dalam 2-3 minggu setelah terapi selesai, dilakukan pemeriksaan ulang feses. Jika masih terdapat telur maupun cacing dewasa, dilakukan terapi ulang. Pencegahan dan Imunisasi Perbaikan lingkungan dengan meniadakan tanah berlumpur serta pemakaian alas kaki saat melewati daerah habitat cacing tambang, sangat dianjurkan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan menurunkan kemungkinan infeksi A. duodenale. Belum terdapat vaksin cacing tambang yang efektif untuk manusia.2,3 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Perbaikan lingkungan dengan meniadakan tanah berlumpur serta pemakaian alas kaki saat melewati daerah habitat cacing tambang, sangat dianjurkan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan menurunkan kemungkinan infeksi A. duodenale. Belum terdapat vaksin cacing tambang yang efektif untuk manusia. Kesimpulan Infeksi cacing tambang masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, karena menyebabkan anemia defisiensi besi dan hipoproteinemia. Spesies cacing tambang yang terutama di Indonesia ialah N. americanus. Siklus biologis cacing tambang berupa perubahan telur menjadi larva (L1) sampai bentuk filariform (L3) di tanah, yang kemudian menembus kulit manusia sampai akhirnya masuk ke saluran cerna dan menjadi dewasa di sini. Terdapat penularan melalui hewan vektor (zoonosis) dengan gejala klinis berupa ground itch dan creeping eruption. Pneumonitis, abdominal discomfort, hipoproteinemia dan anemia defisiensi besi merupakan manifestasi infeksi antropofilik. Komponen sistim imun yang berperan utama ialah eosinofil, IgE, IgG4 dan sel Th2. Tidak terdapat kekebalan yang permanen dan adekuat terhadap infeksi cacing tambang. Diagnosis data epidemiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang termasuk pemeriksaan imunologis. Pengobatan dilakukan dengan mebendazole, albendazole, pirantel pamoat dan berbagai terapi suportif. Belum ada vaksin yang efektif terhadap cacing tambang sehingga perbaikan higiene dan sanitasi adalah hal yang terutama. Daftar Pustaka 1. Pohan HT. Penyakit cacing yang ditularkan melalui tanah. In: Noer HMS editor. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jilid I, 3rd ed. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 1996.p.515-6 2. Hotez PJ, Broker S, Bethony JM, et al. Hookworm infection. N Engl J Med 2004; 351(8):799-807 3. Loukas A, Prociv P. Immune responses in hookworm infection. Clin Microbiol Rev 2001:689-703 4. Weiss EL. Hookworm. 2001. Available from:http://www.eMedicine.com. Downloaded in June 23, 2005 5. Keshavarz R. Hookworm infection. 2000. Available from: http://www. eMedicine.com. Downloaded in June 23, 2005 6. Montressor A, Sanioli L. Ancylostomiasis. 2004. Available from: http:// www.orphanet.com. Downloaded in July 2, 2005 7. MacDonald AS, Araujo MI, Pearce EJ. Immunology of parasitic helminth infections. Infect and Immun 2002; 70(2):427-33 8. Mahmoud AAF. Intestinal Nematodes. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, editors. Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th ed. New York:Churchill Livingstone; 1995.p.2529-31 191 ARTIKEL PENELITIAN Pemberian Glutamin Menurunkan Kadar Bilirubin Darah serta Mengurangi Nekrosis Sel-Sel Hati setelah Pemberian Aktivitas Fisik Maksimal dan Parasetamol pada Mencit I Made Jawi*, I B Rai Manuaba**, I W P Sutirtayasa*** dan Gopinath Muruti**** * ** *** **** Staf Pengajar Bagian Farmakologi - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Staf Pengajar Bagian Patologik Anatomi - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Staf Pengajar Bagian Patologi Klinik - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Mahasiswa Semester VIII - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Abstrak.Stres oksidatif dapat terjadi akibat pemberian beban maksimal dan parasetamol secara bersamaan, yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel dan organel sel, termasuk sel hati. Banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat kerusakan sel hati akibat beban maksimal dengan mengukur kadar bilirubin dan SGPT darah. Penelitian yang melihat pengaruh beban maksimal dan parasetamol serta efeknya terhadap gambaran histologis hati yang diawali pemberian glutamin yang merupakan bahan baku glutathione nampaknya belum ada. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh glutamin terhadap kadar bilirubin dan gambaran histologis hati setelah pemberian parasetamol dan beban maksimal pada mencit. Penelitian dilakukan terhadap 40 ekor mencit jantan umur 4–5 bulan jenis Balb/C yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok glutamin dan non-glutamin masing-masing 20 ekor. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu kelompok kontrol, kelompok renang maksimal dengan parasetamol, masing-masing terdiri dari 10 ekor, dengan rancangan randomized control group post test only design. Terhadap semua kelompok dilakukan pengamatan kadar bilirubin dan gambaran histologis hati setelah perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji T untuk bilirubin, dan data tentang gambaran histologis hati dianalisis secara nonparametrik, yaitu dengan Mann-Whitney U dengan program SPSS. Hasil yang didapat menunjukan terjadi peningkatan kadar bilirubin yang bermakna (p<0,05) pada kelompok glutamin dan non-glutamin setelah perlakuan. Peningkatan bilirubin lebih tinggi pada kelompok non-glutamin dibandingkan kelompok dengan glutamin (p<0,05). Sel hepatosit menunjukkan tingkat degenerasi, nekrosis yang lebih banyak dan peningkatan sel-sel radang setelah perlakuan dengan glutamin dan non-glutamin (p<0,05). Kelompok non-glutamin mengalami peningkatan sel nekrosis dan sel radang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok glutamin (p<0,05). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan glutamin dapat melindungi fungsi hati pada pemberian parasetamol dan beban maksimal pada mencit. Kata kunci: Renang maksimal, glutamin, parasetamol, radikal bebas, kerusakan sel hati, mencit Pendahuluan ati merupakan organ tubuh yang penting dalam menjaga dan menentukan derajat kesehatan seseorang. Dalam menjalankan fungsi tersebut hati akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menyebabkan perubahan lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hati. Penggunaan berbagai zat kimia baik berupa food additive maupun berupa pestisida serta obat-obatan, akan ikut memperberat kerja hati. Di samping itu kehidupan yang semakin susah dan selalu dituntut untuk bekerja keras dalam mempertahankan kehidupan, sering menyebabkan lupa untuk mengatur waktu istirahat. Kerja keras tanpa istirahat pada akhirnya akan membebani hati. Aktivitas fisik yang berat ternyata akan menimbulkan perubahan metabolisme dalam H 192 tubuh yang akan menghasilkan radikal bebas (oxidant) yang merusak sel-sel termasuk sel-sel hati. Pada penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti, ditemukan peningkatan produksi reactive oxygen species (ROS) yang akan menimbulkan oxidative damage setelah melakukan latihan fisik yang berat.1 Pada latihan fisik berat berupa lari 80 km terjadi ketidakseimbangan antara prooksidan dan antioksidan intraselular yang dapat menimbulkan kerusakan sel hati sehingga terjadi peningkatan plasma aspartat transaminase (AST/SGOT) 4 kali lipat dan peningkatan kadar bilirubin yang merupakan tanda dari gangguan fungsi hati.2 Setelah melakukan lari jarak jauh terjadi peningkatan yang signifikan dari SGOT/AST 193% dan SGPT/ALT 42% serta bilirubin total 106%. Hal ini terjadi karena kerusakan hati dan kerusakan otot serta terjadi hemolisis.3 Pada No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL PENELITIAN penelitian terhadap pelari maraton ditemukan peningkatan yang signifikan dari SGOT, SGPT dan bilirubin.4 Latihan yang dilakukan sesaat, juga dapat meningkatkan AST/ SGOT dan Alanin aminotransaminase (ALT/SGPT) dalam darah.5 Latihan fisik berat akut meningkatkan kadar malandialdehyde (MDA) sangat bermakna pada hati, yang merupakan pertanda dari meningkatnya oxidative stress akibat oxidant/radikal bebas.6 Penelitian yang dilakukan pada mencit dengan memberikan beban aktivitas fisik berupa gerakan cepat 10 m/menit selama 2 jam dalam suatu rotating cage yang diikuti pemberian paracetamol/ acetaminophen 700 mg/Kg BB, terjadi peningkatan efek hepatotoksik dibandingkan dengan tanpa beban maksimal. Pada penelitian tersebut terjadi peningkatan kadar SGOT dan SGPT yang diukur setelah 24 jam kemudian.7 Peningkatan SGPT, SGOT dan bilirubin setelah aktivitas fisik dan setelah pemberian acetominophen adalah akibat menurunnya kadar glutathione yang merupakan antioksidan8 yang melindungi sel-sel hati.9 Glutathione adalah suatu tripeptida yang terdiri dari glycine-glutamate-cysteine.10 Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kadar glutathione sehingga efek hepatotoksik dari radikal bebas dapat diatasi. Pemberian n-acetylcystein pada saat melakukan aktivitas fisik berat ternyata dapat meningkatkan kadar glutathione tapi tidak dapat mengurangi kelelahan.9 Penelitian lain yang meneliti pengaruh pemberian nacetylcystein pada penderita hepatitis oleh karena virus ternyata tidak mampu meningkatkan kadar glutathione dalam sirkulasi.11 Meskipun peran glutathione dalam mengatasi keracunan hati oleh parasetamol/acetaminophen telah jelas12,13 namun pemberian enzim glutathione sintetase pada mencit yang diberikan parasetamol/acetaminophen ternyata tidak mampu meningkatkan kadar glutathione.14 Nampaknya perlu dicari usaha lain untuk dapat meningkatkan kadar glutathione saat melakukan aktivitas fisik berat dan setelah pemberian acetaminophen. Glutamin adalah salah satu asam amino yang diperlukan untuk sintesa glutathione dalam sel. Glutamat yang merupakan salah satu komponen dari glutathione baru bisa terpenuhi bila ada glutamin yang cukup dalam darah.10 Peran glutamin dalam mempercepat waktu pemulihan jumlah limfosit lien dan limfosit darah setelah beban aktivitas fisik berat pada mencit telah terbukti.15 Sehingga perlu diteliti peran glutamin dalam mencegah gangguan fungsi hati akibat pemberian parasetamol dan beban aktivitas fisik maksimal, dengan mengukur kadar bilirubin darah dan melihat gambaran histologis jaringan hati. Masalah dalam penelitian ini apakah pemberian glutamin dapat memperkecil kenaikan bilirubin darah akibat olahraga berat/aktivitas fisik maksimal dan parasetamol? Masalah lain apakah pemberian glutamin dapat mengurangi terjadinya perubahan gambaran histologis hepar akibat olahraga berat/aktivitas fisik maksimal dan parasetamol? Tujuan dari penelitian ini mengetahui efek glutamin terhadap No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 kadar bilirubin darah setelah melakukan aktivitas fisik renang maksimal dan pemberian parasetamol pada mencit, mengetahui efek glutamin terhadap perubahan gambaran histologis hati setelah pemberian beban aktivitas fisik renang maksimal dan parasetamol pada mencit. Bahan dan Cara Kerja Penelitian ini adalah eksperimental laboratorik dengan rancangan randomized control group posttest only. Sampel dalam penelitian ini adalah mencit Balb/C jantan dengan umur 4-5 bulan yang diperoleh dari kandang hewan coba Lab. Farmakologi FK Unud. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 40 ekor. Sampel dibagi menjadi 4 kelompok masingmasing 10 ekor mencit. Kelompok 1 atau kelompok kontrol tanpa diberi perlakuan. Kelompok 2 adalah kelompok kontrol dengan glutamin secara oral dengan dosis 3,2 mg/hari/ekor selama satu minggu. Kelompok 3 diberi perlakuan parasetamol secara oral 7,5 mg/ekor dan latihan fisik berupa renang sekuatkuatnya sampai hampir tenggelam atau nampak tandatanda kelelahan berupa tenggelamnya hampir semua badan kecuali hidung dan melemahnya gerakan anggota gerak serta menurunnya waktu reaksi. Lamanya renang berkisar antara 45-50 menit. Perlakuan ini dilakukan di Lab. Farmakologi FK Unud, hanya satu kali dilanjutkan dengan pengambilan darah secara intrakardial sehingga mencit mati. Darah dikirim ke Lab. Patologi Klinik FK Unud untuk dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin. Setelah mencit mati dilakukan pembedahan laparatomi untuk mengambil hati. Hati direndam dengan formalin 10% lalu dikirim ke Lab. Patologi Anatomi FK Unud untuk dibuat sediaan PA. Kelompok 4 diberikan glutamin secara oral dengan dosis 3,2 mg/ekor/hari selama seminggu sebelum perlakuan renang maksimal. Setelah seminggu mencit diberi perlakuan seperti kelompok 3. Terhadap kelompok kontrol dilakukan pengambilan darah dan pengambilan hati tanpa diawali dengan renang. Variabel dalam penelitian ini meliputi: (a) variabel bebas, yaitu renang sekuat-kuatnya sampai hampir tenggelam, dengan parasetamol dan glutamin serta tanpa glutamin, (b) Variabel tergantung, yaitu kadar bilirubin darah serta gambaran histologis hati, (c) Variabel kendali, yaitu jenis hewan coba, umur, kandang hewan coba. Variabel gambaran histologis hati adalah keadaan sel-sel hati serta adanya tanda-tanda degenerasi yang dilihat dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali pada 10 lapangan pandang untuk setiap sediaan, dan dilakukan oleh seorang ahli patologi. Uji statistik yang digunakan adalah uji T dan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann Whitney. Hasil Penelitian Hasil penelitian berupa kadar bilirubin darah dapat dilihat pada tabel 1,dan gambaran histopatologi jaringan hati dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 serta tabel 2. 193 ARTIKEL PENELITIAN Tabel 1. Rata-rata kadar bilirubin dari ke empat kelompok percobaan Kelompok Std Deviasi N Rata-rata I. 0,3557 10 0,7370 II. 0,3554 10 0,7350 III. 0,4889 10 1,2450 IV. 0,2884 10 0,8200 Keterangan: Kelompok I: Kelompok kontrol tanpa glutamin yang mengalami nekrosis lebih banyak pada kelompok tanpa glutamin, dan secara statistik signifikan (p<0,05). Sel-sel yang mengalami degenerasi tidak berbeda secara statistik(p>0,05). Kelompok II: Kelompok kontrol dengan glutamin Kelompok III: Kelompok perlakuan yang diberikan parasetamol dan aktivitas fisik maksimal Kelompok IV: Kelompok perlakuan yang diberikan glutamin, parasetamol dan aktivitas fisik maksimal Pada tabel 1 terlihat terjadi kenaikan bilirubin darah setelah pemberian parasetamol dan aktivitas fisik maksimal. Pada ratarata kontrol bilirubin darah baik yang diberikan glutamin dan tanpa glutamin hampir sama, yaitu 0,7370 dan 0,7350. Setelah diberikan perlakuan parasetamol dan aktivitas fisik maksimal tanpa glutamin menjadi 1,2450. Secara statistik perbedaan ini bermakna (p<0,05). Sedangkan pada kelompok yang diberikan glutamin, parasetamol dan aktivitas fisik maksimal kadar bilirubin darah naik menjadi 0,8200, secara statistik tidak berbeda dibandingkan kontrol (p>0,05). Perbandingan keadaan sel-sel jaringan hati dapat dilihat pada grafik 1 dan 2. Grafik 2. Perbandingan sel yang mengalami degenerasi dan nekrosis serta PMN dan sel limfosit pada kelompok tanpa glutamin dan kelompok dengan glutamin Keterangan: Skala degenerasi dan nekrosis 0= tidak ada, 1=1%-25 %, =26%50%, 3=51%-75%, 4=76%-100%. (dalam lapangan pandang 10 x) Skala PMN dan Limfosit: 0= tidak ada, 1=1 sel-25 sel, 2=26 sel-50 sel, 3=51 sel-75 sel, 4=76 sel-100 sel. (dalam lapangan pandang 10x) Pada Grafik 2 terlihat tidak ada perbedaan sel yang mengalami degenerasi pada kelompok glutamin dengan kelompok tanpa glutamin (P>0,05). Sel yang mengalami nekrosis dan sel-sel radang lebih tinggi pada kelompok tanpa glutamin. Dengan uji Mann-Whitney perbedaan tersebut bermakna (p<0,05). Gambaran jaringan hati pada ke-4 perlakuan dapat dilihat pada gambar 1 berikut. A. Grafik 1. Perbandingan gambaran PA pada kelompok tanpa glutamin dan kelompok dengan glutamin Keterangan: Skala degenerasi dan nekrosis 0= tidak ada, 1=1%-25%, 2=26%50%, 3=51%-75%, 4= 76%-100%. (dalam lapangan pandang 10x) Skala PMN dan Limfosit: 0= tidak ada, 1=1 sel-25 sel, 2= 26 sel-50 sel, 3=51 sel-75 sel, 4=76 sel-100 sel. (dalam 10 lapangan pandang) Pada Grafik 1 terlihat perbandingan fokus degenerasi dan nekrosis pada kontrol adalah 0 baik tanpa glutamin maupun dengan glutamin (tidak ada degenerasi dan nekrosis). Setelah pemberian beban renang maksimal terjadi peningkatan jumlah degenerasi dan nekrosis sel pada kelompok tanpa glutamin maupun dengan glutamin. Secara statistik perbedaan tersebut bermakna dibandingkan dengan kontrol (p<0,05). Begitu juga sel-sel PMN dan limfosit (p<0,05). Kalau dibandingkan antara kelompok tanpa glutamin dengan kelompok dengan glutamin setelah diberikan beban maksimal terlihat perbedaan jumlah selsel yang mengalami degenerasi dan nekrosis. Terlihat sel-sel 194 B. C. No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL PENELITIAN Seperti telah disebutkan bahwa glutathione merupakan antioksidan yang penting dalam sel hati yang akan mengikat radikal bebas serta metabolit toksik parasetamol.16 Glutamin adalah salah satu asam amino yang diperlukan untuk sintesa glutathione dalam sel. Glutamate yang merupakan salah satu komponen dari glutathione baru bisa terpenuhi bila ada glutamin yang cukup dalam darah.10 D. Gambar 1. Gambaran histologis hati mencit kontrol dan setelah perlakuan dengan pembesaran 400x Keterangan: A. Kontrol tanpa glutamin nampak sel hepatosit normal B. Kontrol dengan glutamin nampak sel hepatosit normal C. Renang, parasetamol tanpa glutamin nampak degenerasi dan nekrosis yang banyak D. Renang, parasetamol dengan glutamin nampak degenerasi dan nekrosis yang lebih jarang dibandingkan tanpa glutamin. Pembahasan Pada penelitian ini terjadi peningkatan kadar bilirubin darah setelah pemberian parasetamol dan aktivitas fisik maksimal. Parasetamol dosis tinggi akan menyebabkan kerusakan jaringan hati melalui beberapa mekanisme, yaitu akibat dari terbentuknya metabolit toksik atau metabolit reaktif dari parasetamol, yaitu N-acetyl-p-benzoquinon imine (NAPQI) yang terjadi akibat dari aktivasi enzim cytochrom P450. NAPQI akan ditoksifiksi oleh glutathion (GSH) menjadi acetaminophen-GSH. Pada keracunan parasetamol GSH menurun hingga 90%. Akibatnya metabolit reaktif NAPQI akan berikatan dengan cystein group protein membentuk acetaminophen-protein adducts baik dengan enzim maupun protein dalam sel maupun dalam mitochondria sehingga terjadi gangguan fungsi pada akhirnya terjadi kerusakan sel/lisis/nekrosis. Gangguan pada mitochondria menyebabkan kekurangan ATP. Gangguan tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan ion dalam sel dan mitokondria sehingga terjadi peningkatan kalsium sitosolik pada akhirnya menyebabkan aktivasi protease, endonuklease dan kerusakan DNA.16 Selain mekanisme tersebut akibat pemberian parasetamol dosis tinggi menyebabkan stres oksidatif. Selama pembentukan NAPQI oleh Cytochrome P450 juga terbentuk ion superoksida yang sangat reaktif. Kurangnya glutathion akibat NAPQI akan menyebabkan ion superoksida tidak dapat dinetralisir sehingga terjadi stres oksidatif. Aktivitas fisik berat yang diberikan berupa renang maksimal pada mencit akan memperberat terjadinya stres oksidatif karena meningkatkan terbentuknya radikal bebas2 sehingga terjadi kerusakan sel-sel hati yang terlihat dari meningkatnya SGOT, SGPT dan bilirubin.4,17 Meningkatnya bilirubin juga disebabkan oleh karena terjadi kerusakan otot dan hemolisis akibat aktivitas fisik berat.3,17 Pemberian glutamin sebelum pemberian parasetamol dan beban maksimal dapat memperingan kerusakan jaringan hati sehingga kadar bilirubin darah lebih rendah dibandingkan dengan tanpa glutamin. No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Kesimpulan dan Saran Pembebanan aktivitas fisik maksimal dan parasetamol dapat meningkatkan kadar bilirubin darah dan dapat meningkatkan degenerasi serta nekrosis sel hati mencit. Pemberian glutamin sebelum pembebanan aktivitas fisik dan parasetamol dapat melindungi fungsi hati serta mengurangi nekrosis sel hati mencit. Agar hasil penelitian ini dapat diaplikasikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melihat kadar radikal bebas pada jaringan hati setelah aktivitas fisik dengan pemberian parasetamol dan dilindungi dengan glutamin. Daftar Pustaka 1. Li Li Ji. Antioxidants and oxidative stress in exercise. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 1999;222:283-92 2. Chevion S, Molan DS, Heled Y, et al. Plasma antioxidant status and cell injury after severe physical exercise. PNAS 2003;100(9):5119-23 3. De Paz JA, Villa JG, Lopez P, et al. 1995. Effect of long-distance running on serum bilirubin. Med Sci Sports Exerc 1995;27(12):1590-4 4. Wu HJ, Chen KT, Shee BW, et al. Effect of ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. World J Gastroenterol 2004;15; 10(18):2711-4 5. Koutedakis Y, Raafat A, Sharp NC, et al. Serum enzyme activities in individuals with different levels of physical fitness. J Spotts Med phys Fitness 1993;33(3):252–7 6. Liu J, Yeo HC, Hagen T, et al. Chronically and acutely exercised rats: biomarkers of oxidative stress and endogenous antioxidants. J Appl Physiol 2000;89: 21-8 7. Yoon MY, Kim SN, Kim YC. Potentiation of acetaminophen hepatotoxicity by acute physical exercise in rats. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1997;96(1):35-44 8. Phels DT, Deneke SM, Daley DL, et al. Elevation of glutathione levels in bovine pulmonary artery endothelial cells by N-acetylcysteine. J Appl Physiol 1992;7(3):293-9 9. Medved, Brown MJ, Bjorksten AR, et al. N-acetylcysteine infusion alters blood redox status but not time to fatigue during intense exercise in humans. J Appl Physiol 2003;94:1572-82 10. Frick R. Function of glutamine. Available at: http://www.medfaq.com/glulong 3.htm 11. Bernhard MC, Junker E, Hettinger A, et al. Time Course of total cystein, glutathione and homocysteine in plasma of patients with chrinic hepatitis C treated with interferon-alpha with and without supplementation with N-acetylcysteine. J Hepatol 1998; 28(5):751-5 12. Song H, Chen TS. p-Aminophenol-induced liver toxicity: tentative evidence of a role for acetaminophen. J Biochem Mol Toxicol 2001; 15(1):34-40 13. Chen TS, Richie JP, Nagasawa HT, et al. Glutathione monoethyl ester protects against glutathione deficiencies due to aging and acetaminophen in mice. Mech Ageing Dev 2000;120(1-3):127-39 14. Rzucidlo SJ, Bounous DI, Jones DP, et al. Acute acetaminophen toxicity in transgenic mice with elevated hepatic glutathione. Vet Hum Toxicol 2000; 42(3):146-50 15. Jawi M. Glutamin mempercepat waktu pemulihan limfosit darah dan limfosit lien setelah pemberian beban aktivitas fisik maksimal pada mencit. Penelitian Duelike 2002. Konas Ikafi XI Denpasar 2004 16. James LP, Mayyeux PR, Hinson JA. Acetaminophen-induced hepatotoxicity. Drug Metabolism and Disposition 2003;31:1499-506 17. Fallon KE, Sivyer G, Sivyer K, et al. The biochemistry of runners in a 1600 km ultramarathon. Br J Sports Med 1999;33(4):264-9 195 ARTIKEL PENELITIAN Diagnosis dan Penatalaksanaan Gagal Jantung Diastolik L. Liza Nellyta* , Eko Purnomo** * Alumni FKUP/RSHS ** RSPAD Gatot Subroto Abstrak.Tiga juta penduduk Amerika terdiagnosis gagal jantung kongesti dan tidak kurang dari setengah juta penderita baru dirawat di rumah sakit setiap tahun. Sayangnya data tentang prevalensi kasus gagal jantung di Indonesia belum tersedia. Padahal angka kematian akibat gagal jantung cukup tinggi. Lebih dari 50% penderita gagal jantung meninggal dalam kurun waktu 5 tahun setelah diagnosis. Penyakit gagal jantung dijuluki pula sebagai heart cancer karena risikonya setara dengan bahaya penyakit kanker. Insidensi gagal jantung diastolik meningkat sesuai pertambahan umur; oleh karena itu, 50% pasien yang berusia >65 tahun dengan gagal jantung mempunyai ”Isolated Diastolic Dysfunction (IDD)”. Gagal jantung diastolik diperkirakan 40-60% dari pasien gagal jantung kongesti, pasien ini mempunyai prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan gagal jantung sistolik. Gagal jantung diastolik adalah suatu sindroma klinis yang ditandai dengan keluhan dan tanda gagal jantung di mana fungsi sistolik ventrikel kiri normal (ejeksi fraksi >45%) dengan fungsi diastolik yang abnormal. Membedakan gagal jantung diastolik dari sistolik penting sebab terdapat perbedaan patogenesis, prognosis dan penanganannya. Terapi farmakologi yang merupakan pilihan untuk gagal jantung diastolik adalah angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin reseptor blockers, diuretics dan beta blockers. Kata kunci: Gagal jantung diastolik, gagal jantung sistolik, ejeksi fraksi Pendahuluan iga juta penduduk Amerika terdiagnosis gagal jantung kongesti dan terdapat 500.000 kasus baru tiap tahun. Diagnosis tersebut paling sering ditemukan pada pasien dengan usia >65 tahun.15 Gagal jantung diastolik diperkirakan terjadi pada 40-60% dari pasien gagal jantung kongesti, pasien ini mempunyai prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan gagal jantung sistolik.13 Insidensi gagal jantung diastolik meningkat sesuai pertambahan umur. Lima puluh persen pasien yang berusia >65 tahun dengan gagal jantung mempunyai ”Isolated Diastolic Dysfunction (IDD)”. Dengan diagnosis dini dan penanganan yang tepat, prognosis disfungsi diastolik lebih baik daripada disfungsi sistolik.12 Baik disfungsi diastolik maupun sistolik dapat menyebabkan gagal jantung kongesti. Oleh karena itu, pasien tidak hanya mempunyai gagal jantung sistolik murni. Meskipun penyakit kardiovaskular tertentu seperti hipertensi dapat menyebabkan disfungsi diastolik tanpa disertai disfungsi sistolik.17 Terapi farmakologi yang menjadi pilihan untuk gagal jantung diastolik adalah angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin reseptor blockers, diuretik dan beta blocker.12 Gagal jantung diastolik tidak dapat dibedakan dari T 196 gagal jantung sistolik baik secara klinis dan radiografi, oleh karena itu perlu pemeriksaan penunjang lainnya, seperti ekokardiografi dua dimensi (alat noninvasif terbaik untuk menegakkan diagnosis)/radionuclide angiography (digunakan pada pasien yang secara teknis sulit dilakukan ekokardiografi), namun kateterisasi jantung tetap merupakan metode yang disarankan untuk mendiagnosis disfungsi diastolik.11,12 Oleh karena itu sangatlah penting bagi seorang dokter untuk mengenali perbedaan gagal jantung diastolik dan gagal jantung sistolik, serta memperbaiki penatalaksanaan pengobatan pada pasien gagal jantung diastolik. Definisi dan Kriteria Diagnosis Gagal jantung diastolik adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan keluhan dan tanda gagal jantung (dyspnea on exertion, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, pulmonary edema, jugular venous distension, rales, third or fourth heart sounds, edema perifer, kardiomegali) di mana fungsi sistolik ventrikel kiri normal (efeksi fraksi >45%) dengan fungsi diastolik yang abnormal.2,3,12,18 Suatu penelitian menyarankan para dokter mengkombinasikan informasi klinis dan ekokardiografi untuk mengkategorikan pasien gagal jantung diastolik berdasarkan No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL PENELITIAN tingkat kepastian diagnostik (tabel 1).16 Tabel 1. Kriteria diagnostik gagal jantung diastolik16 Kriteria Definitif Kriteria Probable* Kriteria Possible Bukti definitif gagal jantung kongesti** Dan Dan Bukti objektif fungsi sistolik ventrikel kiri normal Φ Dan Dan Bukti objektif disfungsi diastolik ventrikel kiri Ψ normal Φ Dan Ejeksi fraksi ventrikel kiri ≥50% tidak dalam 72 jam kejadian CHF berat, ventrikel menjadi kaku sehingga otot atrium gagal mengkompensasi dan volume akhir diastolik tidak dapat dinormalisasi dengan peningkatan tekanan pengisian. Proses ini mengurangi stroke volume dan cardiac output, sehingga menyebabkan effort intollerance.8 Tabel 2. Patofisiologi gagal jantung diastolik8 Dan Tidak ada informasi yang menyimpulkan fungsi diastolik ventrikel kiri Kelebihan tekanan iskemia Relaksasi abnormal * Pasien yang memiliki bukti definitif gagal jantung kongesti dan bukti objektif fungsi sistolik ventrikel kiri normal pada saat kejadian CHF, mempunyai kemungkinan gagal jantung diastolik setelah penyakit katup mitral, cor pulmonale, primary volume overload dan penyebab di luar jantung telah disingkirkan. ** Gejala-gejala dan tanda-tanda klinis, radiografi toraks yang mendukung dan respon klinis yang spesifik terhadap diuretik dengan atau tanpa peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri atau indeks jantung yang rendah. F Ejeksi fraksi ventrikel kiri lebih besar sama dengan 50% dalam 72 jam kejadian CHF Y Relaksasi/pengisian/peregangan ventrikel kiri abnormal merupakan indikator kateterisasi jantung. Prevalensi dan Etiologi 40% pasien gagal jantung mempunyai fungsi sistolik yang baik.14 Insidensi gagal jantung diastole meningkat dengan pertambahan umur, dan lebih banyak ditemukan pada wanita lansia.1,9 Hipertensi dan penyakit jantung iskemik merupakan penyebab tersering gagal jantung diastolik. Faktor presipitasi tersering meliputi kelebihan volume; takikardi; hipertensi; iskemik; stressor sistemik (seperti anemia, demam, infeksi, tirotoksikosis); arritmia (seperti atrial fibrilasi, AV blok); meningkatnya konsumsi garam dan penggunaan obat anti inflamasi nonsteroid.12 Patofosiologi Diastol merupakan proses dimana jantung kembali pada keadaan relaksasi. Secara konvensional, diastol dapat dibagi menjadi 4 fase: isovolumetric relaxation, ditandai oleh penutupan katup aorta sampai pembukaan katup mitral; early rapid ventricular filling, setelah pembukaan katup mitral; diastasis, merupakan suatu periode aliran lambat selama middiastol; dan late rapid filling selama kontraksi atrial.6 Secara luas isolated diastolic dysfunction dapat didefinisikan sebagai gangguan relaksasi isovolumetrik ventrikular dan penurunan compliance ventrikel kiri. Dengan disfungsi diastolik, jantung dapat memenuhi kebutuhan metabolik tubuh baik saat istirahat atau selama bekerja, tetapi dengan peningkatan tekanan pengisian. Transmisi tekanan akhir diastolik yang tinggi ke sirkulasi pulmonal menyebabkan kongesti pulmonal. Dengan disfungsi ringan, late filling meningkat sampai volume akhir diastolik ventrikel kembali ke normal. Pada kasus yang No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Hipertrofi infark otot jantung Relaksasi abnormal dan Kekakuan Kekakuan Tekanan pengisian ventrikel kiri Pengisian awal abnormal Tekanan dan ukuran atrium kiri Tekanan paru-paru selama aktivitas fisik Fibrilasi atrium dan curah jantung Toleransi aktivitas fisik normal Toleransi aktivitas fisik Toleransi aktivitas fisik dan tanda-tanda gagal jantung Gagal jantung diastolik Disfungsi diastolik Abnormalitas diastolik Diagnosis Gagal jantung dapat menyebabkan kelelahan, dyspnea on exertion, paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea, distensi vena jugularis, ronki, takikardi, bunyi jantung tiga atau empat, hepatomegali dan edema. Kardiomegali dan kongesti vena pulmonalis sering ditemukan pada rontgen toraks. Namun penemuan klinis ini tidak spesifik dan sering ditemukan pada penyakit di luar jantung seperti penyakit paru, anemia, hipotiroidisme dan obesitas. Lebih jauh lagi sulit untuk membedakan gagal jantung diastolik dari gagal jantung sistolik hanya berdasarkan klinis saja.12 Test serum brain natriuretic peptide (BNP) dapat membedakan secara akurat gagal jantung dari penyakit di luar jantung pada pasien dengan sesak nafas, namun tidak dapat membedakan gagal jantung diastolik dari sistolik.7 Tabel 3. Keakuratan kadar BNP dalam mendiagnosis gagal jantung7 Gagal jantung kongesti vs nonkongesti Spesifisitas LR+ (%) Gagal jantung sistolik vs nonsistolik Kadar BNP (pg per mL) Sensitivitas (%) 100 90 73 4.5 0.12 95 200 81 85 5.4 0.22 89 300 73 89 6.6 0.3 400 63 91 7 0.41 LR- Sensitivitas Spesifisitas (%) (%) LR+ LR- 14 1.1 0.36 27 1.2 0.41 83 29 1.4 0.44 74 50 1.48 0.52 BNP= Brain Natriuretic Peptide; LR+= positive likelihood ratio; LR-= negative likelihood ratio 197 ARTIKEL PENELITIAN Sebagai tambahan untuk memperoleh informasi tentang chamber size, ketebalan dinding dan pergerakan, fungsi sistolik, katup dan perikardium, ekokardiografi dua dimensi dengan doppler dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik transmitral diastolik dan pola aliran vena pulmonalis.10 Pada ekokardiografi, kecepatan puncak aliran darah melewati katup mitral selama early diastolic filing dinyatakan sebagai gelombang E dan kontraksi atrial dinyatakan sebagai gelombang A. Oleh karena itu ratio E/A dapat dihitung. Pada keadaan normal, E lebih besar dari A dan ratio E/A mendekati 1,5.12 Pada disfungsi diastolik awal, relaksasi terganggu dengan kontraksi atrial kuat, ratio E/A menurun sampai <1. Selama perjalanan penyakit, compliance ventrikel kiri berkurang, di mana terdapat peningkatan tekanan atrial dan akhirnya terdapat peningkatan early left ventricular filling selain gangguan relaksasi. Keadaan ini disebut pseudonormalisasi. Pada pasien dengan disfungsi diastolik berat, pengisian ventrikel kiri terjadi pada awal diastol, sehingga membuat ratio E/A>2. Kecepatan gelombang E dan A dipengaruhi oleh volume darah, anatomi katup mitral, fungsi katup mitral dan atrial fibrilasi, hal ini membuat standard ekokardiografi kurang dapat dipercaya. Pada kasus ini, tissue doppler imaging sangat berguna untuk mengukur mitral annular motion (pengukuran aliran transmital bergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan).12 Kateterisasi jantung tetap merupakan metode yang disarankan untuk mendiagnosis disfungsi diastolik. Namun dalam prakteknya, ekokardiografi dua dimensi dengan doppler merupakan alat noninvasif terbaik untuk menegakkan diagnosis. Walaupun sangat jarang, radionuclide angiography digunakan pada pasien yang secara teknis sulit dilakukan ekokardiografi.12 Penatalaksanaan Pencegahan primer gagal jantung diastolik meliputi berhenti merokok dan penanganan agresif hipertensi, hiperkolesterolemia dan penyakit arteri koroner. Modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan, berhenti merokok, perubahan pola makan, pembatasan asupan alkohol dan olahraga, efektif dalam mencegah gagal jantung diastolik dan sistolik. Disfungsi diastolik dapat muncul beberapa tahun sebelum terdapat bukti klinis.8 Diagnosis dan pengobatan dini sangat penting dalam mencegah perubahan struktural ireversibel dan disfungsi sistolik. Namun tidak ada obat tunggal yang murni lusitropic properties (selektif meningkatkan relaksasi otot jantung tanpa menghambat fungsi atau kontraktilitas ventrikel kiri). Oleh karena itu, terapi medis untuk disfungsi diastolik dan gagal jantung diastolik sering empiris dan tidak sebaik terapi gagal jantung sistolik. Pada permukaan tampaknya terapi farmako untuk gagal jantung sistolik dan diastolik tidak berbeda jauh.12 American College of Cardiology dan American Heart 198 Association mengeluarkan panduan yang menyarankan dokter untuk mengontrol tekanan darah, denyut jantung, pengurangan volume darah sentral dan mengurangi iskemia otot jantung. Target panduan ini adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, meningkatkan fungsi ventrikel kiri dan mengoptimalkan hemodinamik.5 Adapun tujuan penanganan gagal jantung diastolik dapat dilihat pada tabel 4.12 Tabel 4. Tujuan penanganan gagal jantung diastolik12 Mengobati faktor-faktor presipitasi dan penyakit yang mendasarinya. Mencegah dan mengobati hipertensi dan penyakit jantung iskemik. Menghilangkan secara bedah penyakit perikardium. Memperbaiki relaksasi ventrikel kiri. ACE inhibitors Calcium channel blokers Mengurangi hipertropi ventrikel kiri(mengurangi penebalan dinding dan menghilangkan kolagen yang berlebih). ACE inhibitors dan ARBs Aldosterone antagonists Beta blocker Calcium channel blockers Menjaga sinkronikasi atrioventrikular dengan menangani takikardi (takiaritmia). Beta blocker (pilihan) Calcium channel blockers (obat golongan kedua) Digoksin (kontroversial) Ablasi nodus atrioventrikular (kasusnya jarang) Optimalisasi volume sirkulasi (hemodinamik). ACE inhibitors Aldosterone antagonists (bermanfaat secara teoritis) Pembatasan garam dan air Diuresis, dialisis, atau plasmapheresis Meningkatkan harapan hidup. Beta blocker ACE inibitors Mencegah relaps dengan menekankan follow-up pada pasien rawat jalan. Kontrol tekanan darah Konsultasi gizi (garam) Memonitor status volume (daily weights dan diuretic adjustment) Program aktivitas fisik (olahraga) oleh suatu institusi ACE= Angiotensin-Converting Enzyme; ARB= Angiotensin Receptor Blocker Memperbaiki Fungsi Ventrikel Kiri Ketika menangani pasien dengan disfungsi diastolik, penting untuk mengontrol denyut jantung dan mencegah takikardi untuk memaksimumkan periode pengisian diastolik. Beta bloker berguna untuk tujuan ini, namun tidak secara langsung menyebabkan relaksasi otot jantung. Dalam memperlambat denyut jantung, beta bloker terbukti bermanfaat dalam mengurangi tekanan darah dan iskemia otot jantung, mengurangi hipertropi ventrikel kiri dan mengurangi stimulasi adrenergik berlebihan selama gagal jantung. Beta bloker dapat memperbaiki harapan hidup pada pasien dengan gagal jantung diastolik, khususnya bila terdapat hipertensi, penyakit arteri koroner atau aritmia.12 Optimalisasi Hemodinamik Optimalisasi hemodinamik terutama dicapai dengan mengurangi preload dan afterload. Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor dan Angiotensin Receptor Blockers (ARB) secara langsung mempengaruhi compliance dan relaksasi otot jantung dengan menghambat produksi atau memblok reseptor No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 ARTIKEL PENELITIAN angiotensin II, dengan cara mengurangi cadangan kolagen interstitial dan fibrosis. Manfaat tidak langsung dari optimalisasi hemodinamik meliputi perbaikan pengisian ventrikel kiri dan mengurangi tekanan darah. Lebih penting lagi, terdapat perbaikan kapasitas kerja dan kualitas hidup.12,19 Diuretik efektif dalam penanganan optimal volume intravaskular dan mengurangi sesak nafas dan mencegah gagal jantung akut pada pasien dengan disfungsi diastolik. Meskipun diuretik mengontrol tekanan darah, memperbaiki hipertropi ventrikel kiri dan mengurangi kekakuan ventrikel kiri, beberapa pasien dengan gagal jantung diastolik sensitif terhadap pengurangan preload dan dapat mengakibatkan hipotensi dan azotemia prerenal berat. Diuretik intravena seharusnya hanya digunakan untuk mengurangi gejala akut.12 Hormon aldosteron menyebabkan fibrosis jantung dan berperan dalam kekakuan diastolik. Efek antagonis aldosteron, spironolactone (Aldactone®) pada gagal jantung sistolik menunjukkan penurunan angka mortalitas, sedangkan efeknya pada disfungsi diastolik tidak jelas.12 Calcium channel blockers telah menunjukkan dapat memperbaiki fungsi diastolik secara langsung dengan mengurangi konsentrasi kalsium sitoplasmik dan menyebabkan relaksasi otot jantung atau secara tidak langsung mengurangi tekanan darah, mencegah atau mengurangi iskemik otot jantung, mengurangi hipertropi ventrikel kiri dan memperlambat denyut jantung. Bagaimanapun juga nondihydropyrimidine calcium channel blockers (seperti verapamil (Calan®)), diltiazem (Cardizem®) seharusnya tidak digunakan pada pasien dengan gangguan disfungsi ventrikel kiri. Long-acting dihydropyrimidine (seperti amlodipine (Norvasc®) seharusnya hanya digunakan untuk mengontrol irama dan angina ketika beta bloker kontraindikasi atau tidak efektif. Akhirnya pada penelitian random terkontrol berskala besar, calcium channel blockers belum terbukti menurunkan angka kematian pada pasien dengan isolated diastolic dysfunction.4,12 Vasodilator (seperti nitrat, hydralazine (Apresoline®)) mungkin berguna karena menurunkan preload dan efek antiiskemik, khususnya ketika ACE inhibitor tidak dapat digunakan. Vasodilator digunakan secara hati-hati karena penurunan preload dapat memperburuk cardiac output. Tidak seperti obat lain yang digunakan untuk gagal jantung diastolik, vasodilator tidak mempunyai efek regresi ventrikel kiri. Penelitian gagal jantung dengan vasodilator tidak menunjukkan manfaat harapan hidup yang signifikan pada pasien gagal jantung diastolik.12 Peranan digoksin masih kontroversial dalam penanganan pasien dengan gagal jantung diastolik. Pada pasien dengan ejeksi fraksi normal, digoksin dapat merusak fungsi jantung dengan meningkatkan kontraktilitas dan konsumsi oksigen, dimana oksigen menghambat kalsium klirens intraselular saat diastolik sehingga mengganggu relaksasi diastolik. Digoksin berperan untuk mengontrol laju ventrikel pada pasien atrial fibrilasi atau flutter.12 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 Kesimpulan Terdapat perbedaan patogenesis, prognosis dan penanganan antara gagal jantung diastolik dan gagal jantung sistolik. Dokter perlu mengkombinasikan informasi klinis dan ekokardiografi untuk mengkategorikan pasien gagal jantung diastolik. Gagal jantung diastolik diperkirakan 40-60% dari pasien gagal jantung kongesti, pasien ini mempunyai prognosis yang lebih baik dibanding gagal jantung sistolik. Terapi farmakologi yang merupakan pilihan untuk gagal jantung diastolik adalah angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin reseptor blockers, diuretics dan beta blockers. Daftar Pustaka 1. Ahmed A, Nanda NC, Weaver MT, et al. Clinical correlates of isolated left ventricular diastolic dysfunction among hospitalized older heart failure patient. Am J Geriatr Cardiol 2003;12:82-9 2. Braunwald E, Michael JG, Wilson SC. Clinical aspect of heart failure. In: Heart Disease: Textbook of Cardiovascular Medicine 6th edition. Philadelphia:Saunders; 2001.p.534-62 3. Grossman W. Defining diastolic dysfunction. Circulation 2000;101:2020-1 4. Gutierrez C, Blanchard DG. Diastolic heart failure: challenges of diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2004;69:2609-16 5. Hunt SA, Baker DW, Chin MH, et al. ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary. A report of the american college of cardiology/american heart association task force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol 2001;38:2101-13 6. Kovacs SJ, Meisner JS, Yellin EL. Modelling of distole. Cardiol Clin 2000;18:459-87 7. Maisel AS, McCord J, Nowak RM, et al. Bedside B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure with reduced or perseved efection fraction. Results from the breathing not properly multinational study. J Am Coll Cardiol 2003; 41:2010-7 8. Mandinov L, Eberli FR, Seiler C, et al. Diastolic heart failure. Cardiovascular Research 2000;45:813-25 9. McCullough PA, Philbin EF, Spertus JA, et al. Confirmation of a heart failure epidemic: findings from the resource utilization among congestive heart failure (REACH) study. J Am Coll Cardiol 2000;39:60-9 10. Naqvi TZ. Diastolic function assessment incorporating new techniques in doppler echocardiography. Rev Cardiovasc Med 2003;4:81-99 11. Philbin EF, Hunsberger S, Garg R, et al. Usefulness of clinical information to distinguish patients with normal from those with low ejection fractions in heart failure. Am J Cardiol 2002;89:1218-21 12. Satpathy C, Mishra TK, Satpathy R, et al. Diagnosis and management of diastolic dysfunction and heart failure. Am Fam Physician 2006; 73:841-6 13. Senni M, Redfield MM. Heart failure with preserved systolic function. A different natural history? J Am Coll Cardiol 2001;38:1277-82 14. Tecce MA, Pennington JA, Segal BL, et al. Heart failure: clinical implications of systolic and diastolic dysfunction. Geriatrics 1999;54:24-8, 31-3 15. van Kraaij DJ, van Pol PE, Ruiters AW, et al. Diagnosing diastolic heart failure. Eur J Heart Fail 2002;4:419-30 16. Vasan RS, Larson MG, Benjamin EJ, et al. Congestive heart failure in subjects with normal versus reduced left ventricular efection fraction: prevalence and mortality in a population-based cohort. J Am Coll Cardiol 1999;33:1948-55 17. Vasan RS, Levy D. Defining diastolic heart failure: a call for standardized diagnostic criteria. Circulation 2000;101:2118-21 18. Warner JG, Metzger DC, Kitzman DW, et al. Losartan improves exercise tolerance in patients with diastolic dysfunction and a hypertensive response to exercise. J Am Coll Cardiol 1999;33:1567-72 199 SEKILAS DEXA MEDICA GROUP Berkibarlah Merah Putih-Ku Dexa Media. Keheningan saat merah putih dikibarkan oleh petugas upacara, seolah meneguhkan kembali tingginya rasa nasionalisme warga Dexa Medica Group (DXG). Diiringi lagu Indonesia Raya, sang Merah Putih berkibar, melambai ditiup sang bayu…! Gelanggang Olah Raga Ragunan Jakarta, 17 Agustus 2006, pukul 08.10 WIB, menjadi saksi kebersamaan warga Dexa Group di dalam memperingati HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-61. Sekitar 650 warga DXG dari kantor pusat dan perwakilan Jabotabek berbaris berbanjar, khidmat mengikuti prosesi upacara bendera.Usai upacara bendera, dilanjutkan pertandingan DXG CUP II, yang berjalan meriah dan penuh persaudaraan. Bapak Ir. Ferry A. Soetikno, MSc,MBA, Corporate Managing Director DXG, selaku Pembina Upacara, pagi itu tampil mempesona, selaras dengan kostum para petugas upacara bendera yang tampil gagah layaknya pasukan pengibar bendera. Dalam amanatnya, Pak Ferry mengingatkan agar warga DXG terus berkarya demi nusa dan bangsa. “Setiap niatan yang baik, dan diproses dengan baik akan memberikan hasil yang baik,” demikian salah satu amanat yang penting dari Pak Ferry Soetikno. Karyanto OGBdexa, Segitiga Merahnya, Bikin Hemat Dexa Media. Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2006, Tim OGB Dexa di seluruh Indonesia mengadakan perhelatan bertajuk “Sehari Bersama OGBdexa”. Sejak pagi hari itu, kesibukan rekan-rekan Tim OGB Dexa di tiap-tiap cabang mulai bergulir. Sekitar pukul 8.30, rekan-rekan Tim OGB Dexa bergerak menuju Rumah Sakit Umum, baik swasta maupun pemerintah yang telah ditetapkan. Kegiatan di tiap lokasi diawali dengan membagi brosur “Kenali OGB” kepada pasien dan pegawai apotek di Rumah Sakit. Tim OGB Dexa juga melakukan survei dengan mewawancarai pasien untuk mengetahui awareness masyarakat terhadap obat generik berlogo dan sekaligus mengenalkan brand OGBdexa di kalangan awam. Secara keseluruhan acara berjalan lancar dan mendapatkan respon positif dari Rumah Sakit maupun masyarakat luas. OGBdexa: Segitiga Merahnya, Bikin Hemat. Natalia No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 207 SEKILAS DEXA MEDICA GROUP Delon Semarakkan Peluncuran TOXILITE Dexa Media. Komitmen Dexa Medica Group untuk terus mengembangkan produk-produk non-konvensional semakin nyata. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran Toxilite di Hard Rock Café Jakarta, 12 September 2006. Penyanyi Dellon dan presenter Novita Angie, menjadi bintang tamu yang menghangatkan suasana. Toxilite mengandung bahan–bahan alami seperti ekstrak Curcuma xanthorizza (100 mg), Lecithin(25 mg), dan Vitamin E (100 mg). Toxilite bekerja membantu memperbaiki sel-sel hati (liver), sehingga dapat mengoptimalkan fungsi detoksifikasi yang dilakukan oleh hati terhadap toxin (racun) yang diserap tubuh. Toxin tersebut bisa berasal dari lingkungan disekitar kita, seperti: asap rokok, obat serangga, zat pengawet, zat pewarna, pestisida, alkohol, ataupun polusi kendaraan bermotor. Grand Launching Toxilite dikemas atraktif, dihadiri perwakilan outlet wilayah Jabodetabek, rekan-rekan Dexa Medica Group, dan sekitar 30 media cetak dan elektronik. Sebelum grand launching digelar, diawali dengan Konferensi Pers. Rekan-rekan media diajak berbagi wawasan mengenai Kiat Menetralkan Racun dalam Tubuh Secara Sehat dan Alami. Saat itu, Bapak Ferry A. Soetikno, Corporate Managing Director Dexa Medica Group, dan Ibu Sylvia A. Rizal, Head of Marketing and Sales OTC Dexa Medica sebagai narasumber, dipandu Bapak Karyanto, Corporate 208 Communications Manager DXG. Menjelang puncak acara, Novita Angie selaku MC, mengundang sejumlah dancer untuk menyajikan komposisi tarian unik dari Toxic Dancers. Dalam tarian itu digambarkan toxin–toxin itu akhirnya mati, berguguran, saat Toxilite menggempur mereka. Sebelum Delon menampilkan sejumlah lagu-lagu manis, talkshow singkat digelar dengan topik mengenai apa dan bagaimana Toxilite bekerja memkasimalkan proses penetralan racun tubuh. Serta keunggulan Toxilite. Talkshow menampilkan Bapak Raymond R. Tjandrawinata, Director of Scientific Affairs & Corporate Development Dexa Medica, dan dokter spesialis Hepatologi, Dr. Rino A Gani, Sp.PD,KGEH. Indriana No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 PROFIL PENELUSURAN JURNAL Pembaca yang budiman, Mulai edisi ini Dexa Media melayani permintaan penelusuran jurnal hanya dengan melalui Tim Promosi Dexa Medica Group, apabila tidak melalui Tim Promosi Dexa Medica Group, kami tidak melayani permintaan. Di bawah ini akan diberikan daftar isi beberapa jurnal terbaru yang dapat anda pilih. Bila anda menginginkannya, mohon halaman ini difotokopi, artikel yang dimaksud diberi tanda p dan dikirimkan ke alamat redaksi. Avian influenza: Preparing for a pandemic. American Academy of Family Physicians 2006;74:783-90 Cognitive impairment in bipolar II disorder. British Journal of Psychiatry 2006;189:254-9 Effect of celecoxib on cardiovascular eventsand blood pressure in two trials for the prevention of colorectal adenomas. Circulation 2006;114:1028-35 Hypoglycemia in type 1 and type 2 diabetes:Physiology, pathophysiology, and management. Clinical Diabetes 2006; 24(3):115-21 Ferritin and transferrin are both predictive ofthe onset of hyperglycemia in men and women over 3 years. Diabetes Care 2006; 29:2090-4 Effect of weight loss with lifestle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7 Oral anticoagulations in development. Focus on thromboprophylaxis in patients undergoing orthopaedic surgery. Drugs 2006; 66(11):1411-29 Pharmacological approaches to the management of cognitive dysfunction in schizophrenia. Drugs 2006;66(11):1465-73 Risk for tuberculosis among children. Emerging Infectious Diseases 2006;12(9):1383-8 Clinical events in high-risk hypertensive patients randomly assigned to calcium channel blocker versus angiotensin-converting enzyme inhibitor in the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial. Hypertension 2006;48:374-84 Topical ciprofloxacin/dexamethasone superior to oral amoxicillin/clavulanic acid in acute otitis media with otorrhea through tympanostomy tubes. Pediatrics 2006;118:561-9 Mycoplasma genitalium as a sexually transmitted infection: implications for screening, testing, and treatment. Sexually Transmitted Infections 2006;82:269-71 Role of minimally invasive surgery in gynecologic cancers. The Oncologist 2006;11:895-901 Celecoxib for the prevention of sporadic colorectal adenomas. The New England Journal of Medicine 2006;355(9):873-84 Cerebral aneurysms. The New England Journal of Medicine 2006;355(9):928-39 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006 211 KALENDER PERISTIWA 1) Biennial Symposium DIGM: “Geriatri Update 2006” Tempat: Hotel Le Meridien, Jakarta Tanggal: 04-05 November 2006 Sekretariat: Global Medica Communications, Jakarta E-mail: [email protected] Telp: 021-30042089 Faks: 021-30041027 2) XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics Tempat: Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia Tanggal: 5-10 November 2006 Sekretariat: AOS Convention & Events Sdn Bhd No. 39240, Jl. Mamandan 9, Ampang Point 68000, Ampang Kuala Lumpur - Malaysia E-mail: [email protected] Telp: +60 3 4252 9100 Faks: +60 3 4257 1133 Website: http://www.figo2006kl.com 3) The 6th Asian & Oceanian Epilepsy Congress Tempat: Kuala Lumpur, Malaysia Tanggal: 16-19 November 2006 Sekretariat: ILAE/IBE Congress Secretariat 7 Priory Hall, Stillorgan, Dublin 18, Ireland Telp: +353 1 2059720 Faks: +353 1 2056156 Website: http://www.epilepsykualalumpur2006.org 4) World Menopause Day: Menopause and Aging Quality of Life and Sexual Tempat: Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal: 16-19 November 2006 Sekretariat: Yayasan Sehat Wanita Indonesia PERMI Jl. Saharjo 120 Jakarta 12960 Indonesia E-mail: [email protected] Telp: 021-8292672 / 8312378 Faks: 021-830190 Contact person: Nelly Hutajulu, SKM 5) The 2nd International Symposium Jakarta for Healthy Travellers Tempat: Jakarta Tanggal: 18-19 November 2006 Sekretariat: Global Medica Communications, Jakarta E-mail: [email protected] Telp: 021-30042089 Faks: 021-30041027 212 6) WFAS International Symposium on Acupuncture Tempat: Sanur Paradise Plaza, Sanur, Bali Tanggal: 22-26 November 2006 Sekretariat: Pacto Convex Lagoon Tower, Level B-1 Jakarta Hilton Int’l, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270 E-mail: [email protected] Telp: 62-21-5705800 ext 420 Faks: 62-21-5705798 Contact: Reny Yetri 7) Kongres I PERKAPI (Perhimpunan Kedokteran Anti Penuaan Indonesia) Anti Aging: New Challenge in Medicine Tempat: Jakarta Convention Center, Jakarta Tanggal: 24-25 November 2006 Sekretariat: Sekretariat Kongres Nasional I PERKAPI Perkantoran Kebun Jeruk Baru Blok A No. 13-14 Jl. Arjuna Selatan, Jakarta 11530 E-mail: [email protected] Telp: 021-5367 7981-82 Faks: 021-5367 7983 8) Seminar & Workshop PASTI (Perkumpulan Awet Sehat Indonesia) Restoring Youthful Hormone Level Tempat: Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal: 25 November 2006 Sekretariat: PASTI Jl. Sultan Iskandar Muda No. 30 A-B Jakarta 12240 Telp: 021-729 0623 Faks: 021-7289 5871 Contact: dr. Fredy Wilmana / dr. Arjati Daud 9) 11th Asian Symposium on Rhinology Tempat: Kuala Lumpur, Malaysia Tanggal: 02-04 Desember 2006 Sekretariat: Academy of Medicine E-mail: [email protected] 10) PIN PAPDI Tempat: Hotel Mercure, Ancol - Jakarta Tanggal: 15-17 Desember 2006 Sekretariat: E-mail: [email protected] Telp: 021-3910294, 31931384, 3193808 pswt: 6703 Faks: 021-3148163 No. 4, Vol. 19, Oktober - Desember 2006