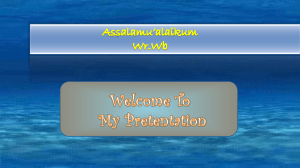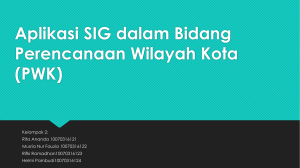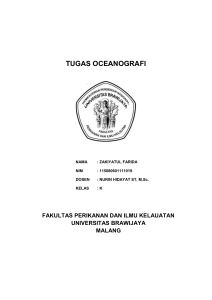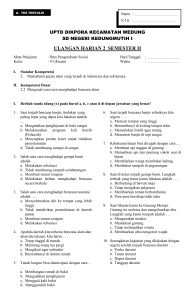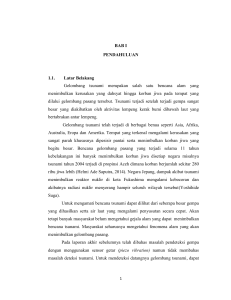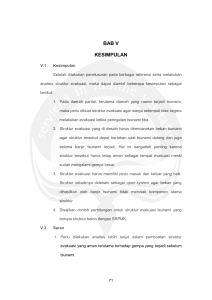Arahan pemanfaatan ruang dalam pengembangan
advertisement

6 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tsunami Tsunami merupakan kosa-kata yang berasal dari jepang, yaitu “tsu” berarti pelabuhan dan “nami” berarti gelombang/ombak. Kedua kata tersebut digabungkan dan dapat diartikan sebagai “gelombang pelabuhan yang besar”. Pengertian ini diambil dari akibat gelombang raksasa yang sering menyebabkan kematian dan kerusakan pada pelabuhan-pelabuhan dan pedesaan yang terletak di pantai Jepang (Diposaptono, 2005). 2.1.2. Penyebab tsunami Tsunami dapat ditimbulkan oleh berbagai gangguan yang memindahkan massa air yang besar secara vertikal dari posisi kesetimbangannya. Gempa dengan patahan vertikal, baik patahan naik atau patahan turun yang terjadi secara mendadak di kedalaman ribuan meter, dapat memicu terjadinya tsunami. Keberadaan tersebut juga bisa terjadi akibat letusan gunung berapi bawah laut atau lingkungan laut, dimana gaya impulsif yang dihasilkan oleh letusan memindahkan kolam air dan menciptakan tsunami. Fenomena tersebut pernah terjadi di Indonesia pada saat gunung Krakatau meletus pada tanggal 27 Agustus 1883, yang telah memicu timbulnya gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter. Selain disebabkan oleh peristiwa alam yang bersumber dari bawah laut, tsunami dapat pula terjadi akibat longsoran gunung es seperti yang terjadi di Alaska pada tahun 1958 ( Diposaptono, 2005). Menurut Diposaptono (2005), kejadian tsunami di Aceh akhir tahun 2004 disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan gempa tektonik berkekuatan 9.0 SR, pada kedalaman 4 km di dasar laut. Disamping menyebabkan gempa, pergeseran tersebut menyebabkan patahan dan memicu dua gempa besar lainnya di kepulauan Andaman dan Nikobar (India) dengan kekuatan 6.3 dan 7.3 SR yang mengganggu keseimbangan air laut sehingga menimbulkan pergolakan air yang dahsyat dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di daerah pantai yang terletak di sekitar samudera Hindia. 7 2.1.3. Perambatan dan rayapan tsunami di daratan Di tengah lautan, ketinggian gelombang tsunami tidak lebih dari 3 meter, terlihat seperti gelombang laut normal pada umumnya, walaupun wujud fisik tsunami tidak kelihatan di permukaan laut dalam, sebenarnya kecepatan rambatan tsunami bisa mencapai 1000 km/jam di laut dalam, ia akan mengalami perubahan kenampakan gelombang ketika meninggalkan perairan laut dalam dan merambat ke perairan yang lebih dangkal di pesisir. Pada saat gelombang mencapai perairan yang dangkal, kecepatan tsunami akan berkurang tetapi energi total dari tsunami konstan sehingga ketinggian gelombang dapat mencapai ketinggian lebih dari 15 meter atau lebih. Pada kedalaman laut 4.000 meter, tsunami merambat dengan kecepatan 720 km/jam, sedangkan pada kedalaman laut 90 meter kecepatannya berkurang menjadi sekitar 25 – 100 km/jam. Terkadang tsunami bisa saja musnah jauh sebelum mencapai pantai. Namun bila mencapai pantai, tsunami dapat terlihat sebagai gelombang pasang naik maupun pasang turun yang meningkat drastis, rangkaian gelombang besar, atau bahkan sebuah bore yang menerjang hingga ke pedalaman (daratan) yang secara normal tidak pernah terjangkau oleh gelombang laut. Bore adalah gelombang yang mirip tangga dengan dengan sisi yang curam, yaitu ujung gelombang pasang yang mendesak air sungai ke hulu yang terjadi pada saat pasang laut naik, disebut juga tidal bore. Sebuah bore dapat terjadi apabila tsunami bergerak dari perairan dalam ke perairan teluk dangkal atau sungai. Terumbu karang, semenanjung, muara-muara, kenampakan-kenampakan bawah laut dan kelerengan pantai kesemuanya itu membantu untuk memodifikasi tsunami pada saat mencapai pantai. Tsunami yang bergerak naik ke daratan umumnya merayap dengan kecepatan sekitar 70 km/jam merupakan kekuatan yang sangat besar yang bisa mengangkat pasir di pantai, mencabut pepohonan dan menghancurkan bangunan apalagi manusia dan kapal-kapal tidak berdaya melawan turbulensinya. Kualitas air yang dibawa ke daratan mampu membanjiri daerah luas yang biasanya kering (dry land). Rayapan akibat gelombang tsunami dapat menimbulkan genangan banjir yang merambah daratan hingga 300 meter dari garis pantai atau lebih. 8 2.2. Penataan Ruang Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta kelangsungan hidupnya. Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta biaya, sementara itu pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Lebih jauh lagi pada pasal 2 undang–undang ini menyatakan bahwa penataan ruang berasaskan : a) Keterpaduan; b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) Keberlanjutan; d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) Keterbukaan; f) Kebersamaan dan kemitraan; g) Perlindungan kepentingan umum; h) Kepastian hukum dan keadilan; dan i) Akuntabilitas. Menurut Rustiadi et al. (2005), penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Dalam pemahamannya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang merupakan bagian dari proses pembangunan. Penataan ruang mempunyai tiga urgensi, yaitu : a) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktivitas dan efesiensi); b) Alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan) dan c) Keberlanjutan (prinsip sustainabilitas). Konsep penataan ruang dapat menjadi aktivitas yang mengarahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Penataan ruang bukanlah suatu tujuan akan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian kegiatan penataan ruang tidak boleh berhenti dengan diperda kannya rencana tata ruang kabupaten/kota, tetapi penataan ruang harus merupakan aktifitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan 9 masyarakat suatu wilayah untuk mencapai tujuan-tujuan pokoknya (Darwanto, 2000). Menurut UU 26/2007, pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Menurut Rustiadi (2004), tata ruang sebagai wujud pola dan struktur pemanfaatan ruang terbentuk secara alamiah dan merupakan wujud dari proses pembelajaran (learning process) yang terus menerus. Sebagai alat pendeskripsian, istilah pola spasial (ruang) erat dengan istilah-istilah kunci seperti pemusatan, penyebaran, pencampuran dan keterkaitan, posisi/lokasi, dan lain-lain. Pola pemanfaatan ruang selalu berkaitan dengan aspek-aspek sebaran sumberdaya dan aktifitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap jenis aktifitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda, dan tingkat penyebaran yang berbeda-beda pula (Rustiadi 2004). Pola pemanfaatan ruang juga dicerminkan dengan gambaran pencampuran atau keterkaitan spasial antar sumberdaya dan pemanfaatannya. Kawasan pedesaan dicirikan dengan dominasi pencampuran antara aktifitas-aktifitas pertanian, penambangan, dan kawasan lindung. Sebaliknya, kawasan perkotaan dicirikan oleh pencampuran yang lebih rumit antara aktifitas jasa komersial dan pemukiman. Adapun, kawasan sub urban di daerah perbatasan perkotaan dan pedesaan dicirikan dengan kompleks pencampuran antara aktifitas pemukiman, industri dan pertanian. Peta penggunaan lahan dan peta penutupan lahan adalah bentuk deskriptif terbaik dalam menggambarkan pola pemanfaatan ruang yang ada (Rustiadi 2004). Hutabarat (2005), menyatakan bahwa dewasa ini penyelenggaraan penataan ruang senantiasa dikaitkan dengan upaya mewujudkan good governance, baik dalam konteks pembangunan wilayah administrasi maupun kawasan fungsional. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti keberlanjutan, keadilan, efesiensi, trasparansi, akuntabilitas, kepatian hukum, dan pelibatan masyarakat secara keseluruhan juga merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang. Dalam kata lain instrumen penataan ruang dapat dimanfaatkan oleh pengelola wilayah administrasif ataupun kawasan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terpadu untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, yang 10 didukung oleh pelayanan sosial-ekonomi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Rustiadi (2001), proses alih fungsi lahan dapat dipandang merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud tercermin dari adanya: (1) Pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita; dan (2) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor-sektor primer (sektor-sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam) ke aktivitas sektorsektor sekunder (industri manufaktur dan jasa). 2.3. Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah Wilayah menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan menurut Winoto (1999), wilayah sebagai area geografis yang mempunyai ciri tertentu dan merupakan wadah bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Sehingga wilayah dapat didefinisikan, dibatasi dan digambarkan berdasarkan ciri atau kandungan area geografis tersebut, namun ciri dan kandungan area geografis yang digunakan untuk mendefinisikan wilayah merupakan hal yang masih diperdebatkan. Dalam memahami wilayah, terdapat juga pengertian wilayah sebagai wilayah nodal. Wilayah nodal merupakan bentuk spesifik dari wilayah fungsional dan dianggap sebagai suatu sel yang terdiri dari satu inti (center) dan dikelilingi oleh plasma (hinterland). Inti merupakan daerah center of excellence dan memiliki sifat lebih majemuk daripada daerah hinterland. Inti atau pusat berfungsi sebagai tempat konsentrasi penduduk, pusat pasar, pusat perdagangan, pusat pelayanan masyarakat, pusat industri dan inovasi. Hinterland mempunyai fungsi spesifik sebagai pemasok bahan mentah, tenaga kerja dan sebagai tempat pemasaran produk yang dihasilkan oleh pusat serta berfungsi juga sebagai 11 penyeimbang ekologis. Pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah hinterland adalah hubungan fungsional yang berjenjang (hirarki) sehingga timbul ketergantungan hinterland kepada inti. Selanjutnya Winoto (1999), menjelaskan bahwa peubah-peubah yang digunakan untuk membatasi wilayah nodal adalah kepadatan penduduk, jenis dan jumlah sarana pelayanan serta sirkulasi kapital. Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu wilayah. Dalam tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam ( 3 ) tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (uniform/homogenous region), (2) wilayah nodal (nodal region), dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor yang dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor yang tidak dominan dapat beragam. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah, secara umum terdiri atas penyebab alamiah dan penyebab artifisial. Faktor alamiah yang dapat menyebakan homogenitas wilayah adalah kelas kemampuan lahan, iklim, dan berbagai faktor lainya. Sedangkan homogenitas yang bersifat artifisial adalah homogenitas yang didasarkan pada pengklasifikasian berdasarkan aspek tertentu yang dibuat oleh manusia. Contoh wilayah homogen artifisial adalah wilayah homogen dasar kemiskinan (peta kemiskinan). Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam, maka menurut Rustiadi et al., (2004), wilayah homogen sangat bermanfaat dalam: (1) penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung utama yang ada (comparative advantage), (2) pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai denga permasalahan masing-masing wilayah. Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu sel hidup yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman sedangkan plasma adalah daerah belakang (peripheri/hinterland) yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi et al., 2005). 12 Konsep wilayah perencanaan, merujuk pada wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terhadap sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bersifat alamiah maupun artifisial dimana keterkaitannya sangat menentukan sehingga perlu perencanaan secara integral. Sebagai contoh, secara alamiah suatu daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan matrik dasar kesatuan hidrologis yang perlu direncanakan secara integral. Perencanaan wilayah (regional planning) pada dasarnya merupakan upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah memiliki tiga tujuan pokok, yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, tujuan utamanya adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektoral dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada didalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Riyadi, 2002). Menurut Rustiadi et al. (2005) perencanaan pengembangan wilayah merupakan bidang kajian yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan didalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan serta aspek-aspek proses politik, manajemen dan administrasi perencanaan pembangunan yang berdimensi ruang dan wilayah. Proses kajian perencanaan dan pengembangan wilayah memerlukan pendekatan-pendekatan yang mencakup : (1) aspek pemahaman, yaitu aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem untuk mengenal potensi dan memahami permasalahan pembangunan wilayah; (2) aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknikteknik desain dan pemetaan hingga teknis perencanaan; dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan evaluasi, perumusan tujuan pembangunan dan proses pelaksanaan pembangunan seperti proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan. Bidang kajian ini tidak saja menjawab pertanyaan mengapa keadaan wilayah demikian adanya tetapi juga menjawab bagaimana wilayah di 13 bangun. Oleh karenanya mencakup aspek-aspek perencanaan yang bersifat spasial (spatial planning), tata guna lahan (land use planning) hingga perencanaan kelembagaan (Structural planning) dan proses perencanaan. Sebagai suatu ilmu yang mengkaji seluruh aspek-aspek kewilayahan dan mencakup aspek sumberdaya serta interaksi dan interelasi antar wilayah, maka kajian perencanaan dan pengembangan wilayah memiliki sifat: (1) berorientasi kewilayahan; (2) futuristik; dan (3) berorientasi publik. Secara umum perencanaan pengembangan wilayah ditunjang oleh empat pilar pokok, yaitu: (1) inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi sumberdaya; (2) aspek ekonomi; (3) aspek kelembagaan (institusional) dan; (4) aspek spasial/lokasi. Menurut Triutomo (2001), tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Disisi sosial-ekonomi, pengembangan wilayah adalah upaya memberi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana, dan sebagainya. Disisi lain secara ekologis pengembangan wilayah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan. Berkembangnya suatu wilayah sangat terkait oleh tingkat pemanfaatan dari tiga sumberdaya yakni sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Kemudian Prod homme (1985), dalam Triutomo (2001), menyatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. 2.4. Kota dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan kota (urban) merupakan kawasan yang dinamis, dimana secara tetap terjadi perubahan. Kota merupakan sebuah hasil proses produksi yang permanen (Lefebvre (1990), diacu dalam Martokusumo, 2006). 14 Perubahan ini bisa bersifat ekspansif (perluasan) atau intensifikasi (restrukturisasi internal) sebagai respon dari kebijakan ekonomi atau tekanan sosial yang timbul. Desain urban dapat dilihat sebagai sebuah alat untuk mengontrol perubahan, sebagai konsekuensi terhadap perkembangan dan pembangunan perkotaan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Desain urban bukanlah merupakan suatu produk akhir. Namun, desain urban akan sangat turut menentukan kualitas dari produk akhirnya, yaitu lingkungan binaan yang dihuni. Dengan demikian desain urban harus dipahami sebagai suatu proses yang mengarahkan perwujudan suatu lingkungan binaan fisik yang layak, sesuai dengan aspirasi masyarakat, ramah terhadap lingkungan, termasuk kepada kemampuan sumberdaya setempat dan daya dukung lahan serta merujuk kepada aspek lokal (Martokusumo, 2006). Menurut Budiharjo (1997), kota adalah kumpulan orang-orang yang berdomisili dalam jangka waktu lama maupun sementara. Sebuah kota tidak akan nyaman jika orang-orangnya tidak menciptakan kenyamanan bagi lingkungannya. Kota yang baik dan berkesan adalah kota-kota dimana masyarakatnya memberikan kenyamanan terhadap eksistensi lingkungannya. Jadi dengan membicarakan kenyamanan berarti sebuah kota adalah kumpulan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya. Kota dari pandangan yuridis administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah negara, dimana keberadaannya diatur oleh undangundang (peraturan tertentu) daerah, dimana dibatasi oleh batas-batas administratif yang jelas yang keberadaannya diatur oleh undang-undang/peraturan tertentu dan ditetapkan berstatus sebagai kota dan berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengatur wilayah kewenangannya (Yunus, 2005). Sementara itu menurut Sujarto (1970), yang dikutip Yunus (2005), kota adalah suatu wilayah negara/suatu areal yang dibatasi oleh batas-batas administrasi tertentu, baik berupa garis yang bersifat maya/abstrak ataupun batas-batas fisikal, misalnya sungai, jalan raya, lembah, barisan pegunungan dan lain sebagainya yang berada di dalam wewenang suatu tingkat pemerintahan tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga di wilayah tersebut. 15 Kota di tinjau dari morfologi kota, dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan non pertanian, pemanfaatan sebagian besar tertutup oleh bangunan baik bersifat residensial maupun non residensial, kepadatan bangunan khususnya perumahan yang tinggi, pola jaringan jalan yang kompleks, dalam satuan permukiman yang kompak dan relatif lebih besar dari satuan permukiman kedesaan di sekitarnya. Sementara itu daerah yang bersangkutan sudah/mulai terjamah fasilitas kota (Yunus, 2005). Kriteria Umum Kawasan Perkotaan menurut Kepmen Kimpraswil 327/2002 adalah: (1) memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan; (2) memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; (3) memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar; (4) memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi. Budiharjo (1997), mengatakan bahwa fungsi kota sebagai pusat pelayanan (service center) membawa konsekuensi areal kota akan dipenuhi oleh kegiatankegiatan komersial dan sosial, selain kawasan perumahan dan permukiman. Pembangunan ruang kota bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas; dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera. Berkenaan dengan hal tersebut pembangunan kota harus ditujukan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang selanjutnya akan dapat mendorong sektor perekonomian. Namun dalam pengembangannya, tentu perlu diperhatikan ketersediaan sumberdaya, sehingga perlu dicermati efisiensi pemanfaatan sumberdaya maupun efisiensi pelayanan prasarana dan sarana kota. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Selain itu juga diharapkan untuk selalu mengarah kepada terciptanya keadilan yang tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh penghidupan perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan. 16 Menurut Rustiadi et al. (2005) dilihat dari konsep keruangan (spasial) dan ekologis, urbanisasi merupakan gejala geografis yakni; a) adanya perpindahan penduduk keluar wilayah ; b) gerakan/perpindahan penduduk yang terjadi disebabkan adanya salah satu komponen dari ekosistem kurang/tidak berfungsi secara baik sehingga terjadi ketimpangan dalam ekosistem setempat; c) terjadinya adaptasi ekologis yang baru bagi penduduk yang pindah dari daerah asal ke daerah yang baru, dalam hal ini kota. Sehingga urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu proses dalam artian : (1) meningkatkan jumlah dan kepadatan penduduk kota menjadi lebih menggelembung; (2) bertambahnya kota dalam suatu negara atau wilayah akibat dari perkembangan ekonomi, budaya dan tehnologi baru; (3) merubah kehidupan desa atau nuansa desa menjadi suasana kehidupan kota. Yunus (2006), ada dua dimensi dalam membahas urbanisasi yaitu; (1) dimensi fisiko-spasial dan (2) dimensi non fisikal. Dalam dimensi fisiko-spasial, urbanisasi berarti berubahnya kenampakan fisiko spasial kedesaan menjadi kenampakan fisiko-spasial kekotaan. Jadi urbanisasi merupakan proses berubahnya ketiga elemen morfologi kekotaan (land use characteristics; building characteristics dan circulation characteristics). Sedangkan dimensi non fisikal merupakan berubahnya keseluruhan dimensi kehidupan manusia (perilaku ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi) dari sifat kedesaan menjadi bersifat kekotaan. Sub-urban diartikan sebagai proses terbentuknya pemukiman-pemukiman baru dan juga kawasan industri di pinggir wilayah perkotaan, terutama sebagai perpindahan penduduk kota yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri. Sub urban telah melahirkan fenomena yang kompleks di wilayah sub urban yaitu akulturasi budaya, konversi lahan pertanian di perkotaan, spekulasi lahan dan lain-lain. Proses sub urbanisasi adalah salah satu proses pengembangan wilayah yang semakin menonjol dan semakin berpengaruh nyata di dalam proses penataan ruang disekitar wilayah perkotaan (Rustiadi et al., 2005). Disatu sisi proses ini dipandang sebagai perluasan wilayah ke wilayah pinggir kota yang berdampak meluasnya skala manajemen wilayah urban secara riil, dilain sisi proses ini sering 17 dinilai sebagai proses yang kontradiktif mengingat prosesnya selalu diiringi dengan proses konversi lahan pertanian yang sangat prodiktif. 2.5. Teori Lokasi dan Pemusatan Kegiatan Menurut Hanafiah (1989), pemerintah sebagai penentu lokasi mempunyai kekuatan atau kewenangan yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan melalui kegiatan masyarakat yang tersebar secara spasial, dan bertujuan untuk memaksimumkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyebaran fasilitas pelayanan secara merata. Kajian tentang teori lokasi secara komprehensif dilaksanakan oleh Alfred Weber pada tahun 1909 (Tarigan, 2005). Apabila Von Thunen menganalisis lokasi kegiatan pertanian, maka Weber menganalisis lokasi kegiatan industri atas prinsip minimisasi biaya. Weber mengemukakan teori lokasinya berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1. Lokasi kajian adalah suatu wilayah yang terisolasi, mempunyai iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat aktifitas, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna. 2. Beberapa sumberdaya alam, seperti tanah liat, pasir, dan air tersedia di manamana dalam jumlah yang memadai (ubiquitous). 3. Bahan-bahan lainnya tersedia secara sporadis pada tempat-tempat tertentu dengan jumlah terbatas. 4. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, tetapi terbatas pada beberapa lokasi dengan mobilitas yang tetap. Teori lokasi Weber lebih menekankan pada lokasi industri, dengan anggapan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi tersebut adalah: 1. Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental berpengaruh dalam penentuan lokasi kegiatan industri, biaya transportasi berbanding lurus dengan dengan jarak tempuh, dan ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang rendah di lokasi tertentu akan mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi. 18 2. Kekuatan aglomerasi dan deglomerasi (aglomerative and deglomerative force). Kekuatan aglomerasi dan deglomerasi adalah faktor yang juga turut menentukan konsentrasi atau penyebaran berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu pola tata ruang. Sampai pada tingkat tertentu kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi atau mengumpul pada suatu lokasi tertentu. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan timbul kejenuhan ekonomi pasar lokal yang ditandai oleh dis-economic of scale, dan ini akan mengakibatkan menyebarnya kegiatan ekonomi ke wilayah lain di sekitarnya. Berdasarkan faktor tersebut di atas, maka lokasi industri akan cenderung akan memilih lokasi dengan biaya input yang paling minimum. Weber menyatakan bahwa biaya transportasi merupakan faktor utama dalam determinasi lokasi, asumsinya adalah bahwa biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan bertambahnya jarak angkut, sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Salah satu kelemahan dari teori Weber adalah hanya menekankan pada biaya input, dan kurang memperhatikan aspek permintaan pasar, padahal pasar adalah termasuk salah satu variabel dalam menentukan lokasi industri. Konsumen tersebar di wilayah yang luas dengan intensitas permintaan yang berbeda-beda, sehingga pasar menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi yang optimum, yaitu lokasi di mana dapat diperoleh laba maksimum. Hal ini dikemukakan oleh Losch pada tahun 1939, seperti dikutip oleh Hanafiah (1989). Dalam konsep teori lokasinya, Losch mendasarkan pada asumsi: 1. Tidak ada perbedaan spasial dalam distribusi input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal pada suatu wilayah yang homogen 2. Kepadatan penduduk yang seragam dan dengan selera yang konstan. 3. Tidak ada interdependensi antara perusahaan. Apabila Weber melihat persoalan dari sisi produksi, maka Losch melihat persoalan dari sisi permintaan pasar atas dasar prinsip lokasi yang dapat memaksimumkan laba. Losch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk 19 mendatangi tempat penjual semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini mengikuti pandangan Christaller. Atas dasar pandangan tersebut Losch cenderung menyarankan lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar (Tarigan, 2005). Menurut Isard (1960), dalam Tarigan (2005), masalah lokasi merupakan masalah penyeimbangan antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidak pastian yang berbeda-beda. Keuntungan relatif dari lokasi sangat dipengaruhi oleh faktor dasar: (a) biaya input atau bahan baku; (b) biaya transportasi; dan (c) keuntungan aglomerasi. Perkembangan dari teori Losch dikembangkan lebih lanjut oleh Isaard pada tahun 1956 dengan konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi Isard adalah: 1. Faktor skala usaha yang ekonomis, yaitu suatu besaran skala usaha dari suatu perusahaan tertentu, sebagai konsekuensi dari perluasan perusahaan di suatu lokasi. 2. Faktor lokalisasi yang ekonomis, yaitu lokasi yang ekonomis bagi sekelompok perusahaan industri yang sejenis, sebagai konsekuensi dari peningkatan produksi total pada suatu lokasi. 3. Faktor urbanisasi yang ekonomis, yaitu suatu lokasi yang ekonomis bagi semua perusahaan dari berbagai jenis industri, sebagai konsekuensi kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu tempat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, produksi dan tingkat kesejahteraan setempat. Secara alamiah, terdapat kecenderungan pada setiap individu penduduk dan perusahaan untuk memilih lokasi pada daerah-daerah yang relatif sudah berkembang atau daerah-daerah yang menjadi pemusatan di dalam wilayah yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena adanya berbagai keuntungan yang dihasilkan oleh daerah-daerah pemusatan yang menjadi daya tarik bagi penduduk dan perusahaan atau aktifitas ekonomi untuk memilih lokasi pada daerah-daerah tersebut. Keuntungan-keuntungan tersebut dinamakan dengan keuntungan aglomerasi. 20 Keuntungan aglomerasi, dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh individu penduduk atau perusahaan, dan oleh masyarakat dan industri secara keseluruhan pada suatu daerah di mana terjadi pemusatan kegiatan. Keuntungan ini merupakan keuntungan eksternal yang diakibatkan oleh adanya pemusatan geografi kependudukan, perusahaan, aktifitas sosial ekonomi, ketersediaan sarana dan prasaran fasilitas pelayanan umum dari berbagai institusi dan kelembagaan baik pemerintah maupun swasta. Konsep aglomerasi dapat timbul pada berbagai skala, di mana pusat-pusat aglomerasi yang lebih kecil akan cenderung mengitari pusat aglomerasi yang lebih besar. Pusat dengan tingkat terendah akan melaksanakan berbagai fungsi atau menyediakan berbagai barang dan jasa yang jumlah dan jenisnya terbatas oleh terbatasnya jumlah penduduk ataupun sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut. Pada umumnya aglomerasi terjadi pada bidang pelayanan administrasi, kesehatan, sosial, keuangan, perdagangan, tenaga kerja, dan lalu lintas perhubungan. Setiap pemusatan akan menghasilkan pengaruh positif dan negatif sekaligus. Adanya pemusatan yang berlebihan pada daerah-daerah tertentu, di samping akan menimbulkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan hidup, juga akan menyebabkan dana dan sumberdaya untuk pembangunan wilayah lain menjadi terbatas. Apalagi dengan adanya aktifitas lembaga pemerintahan yang berhirarki lebih tinggi di suatu wilayah, maka perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut cenderung lebih besar dibandingkan terhadap wilayah lainnya. Dusseldorp (1971), diacu dalam Prakoso (2005), mengemukakan bahwa konsep dasar teori pusat pelayanan adalah pemusatan dan fungsi pemusatan, batas ambang dan hirarki. Dengan adanya kristalisasi penduduk pada daerah inti akan berimplikasi pada terjadinya pemusatan fasilitas pelayanan sekaligus menobatkan daerah inti ini menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Pemusatan pusat pelayanan akan memberikan keuntungan antara lain: 1. Pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pelayanan akan lebih intensif daripada tidak dipusatkan; 2. Fungsi dari setiap fasilitas pelayanan akan lebih efisien; 21 3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan social capital masyarakat. Usaha penekanan biaya operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi fasilitas pelayanan atau untuk mendapatkan pasar dan jumlah konsumen yang cukup besar bagi fasilitas pelayanan, cenderung dapat mengurangi banyaknya pusat-pusat pelayanan, sehingga dapat meningkatkan biaya perjalanan konsumen. Jika ditinjau dari segi usaha untuk meningkatkan kesamaan jarak maksimum yang bersedia ditempuh oleh setiap konsumen, maka jumlah pusat-pusat pelayanan perlu ditambah sehingga biaya perjalanan atau jarak ekonomi dapat dikurangi. Hakimi (1964), diacu dalam Rushton (1979), menyatakan bagaimana menemukan satu titik optimum dalam satu jaringan. Dengan adanya jarak yang tetap di antara simpul-simpul yang ada dalam jaringan, maka akan ditemukan satu simpul di antara semua simpul yang ada yang memiliki jarak terpendek dan memiliki kriteria bobot yang ditetapkan. Simpul atau titik yang dimaksud adalah titik tengah dari jaringan, ini merupakan teori yang penting karena dapat digunakan untuk menyelesaikan permasahan-permasalahan penaksiran simpul-simpul alternatif pada jalur jaringan. Hakimi mengatakan, bahwa ada satu simpul dalam jaringan yang meminimumkan jarak terpendek yang berbobot dari semua simpul terhadap satu simpul tertentu di mana simpul tersebut juga merupakan bagian dari jaringan tersebut. Pemukiman penduduk yang tidak tersebar merata di semua wilayah akan menyebabkan setiap individu akan berusaha untuk mendapatkan berbagai jenis barang, jasa, dan pelayanan terbaik yang juga tersebar di berbagai lokasi yang dapat dijangkau berdasarkan biaya yang harus dikeluarkannya. Lokasi yang dapat dijangkau memiliki banyak pilihan dan masyarakat akan memilih yang berada pada posisi most accessible bagi mereka. Suatu lokasi dapat dikatakan most accessible apabila mempunyai kriteria berikut (Rushton 1979): 1. Kriteria jarak rata-rata minimum, yaitu jarak total dari semua penduduk yang akan dilayani ke pusat pelayanan terdekat adalah minimum, disebut juga jarak agregat minimum; 22 2. Kriteria jarak maksimal, yaitu apabila jarak terjauh dari tempat penduduk yang akan dilayani ke pusat pelayanan adalah minimum yang disebut dengan jarak minimax; 3. Kriteria penetapan berdasarkan kesamaan, yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan terdekat selalu sama dengan jumlah yang ditentukan; 4. Kriteria ambang batas (population treshold), yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan terdekat selalu lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan; dan 5. Kriteria kapasitas atau daya tampung, yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan teredekat selalu lebih kecil dari jumlah yang ditentukan. Rushton (1979), mengungkapkan permasalahan lokasi yang terjadi di negara berkembang, yaitu: 1. Belum berkembangnya sistem transportasi. Sistem transportasi yang ada belum terintegrasi dengan lokasi fasilitas pelayanan masyarakat sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayan. 2. Fasilitas pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sering terjadi fasilitas yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam ukuran tata ruang, sehingga keberadaan fasilitas yang telah ada tidak dapat memenuhi suatu permintaan yang sesuai dengan yang diperlukan. 3. Kesalahan lokasi akibat pengaruh sistem kolonial. Perlunya perbaikan pada sistem pola lokasi yang dibangun oleh sistem kolonial karena hal ini sering menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan di masa sekarang dan akan datang, seperti diketahui bahwa sistem kolonial dibangun untuk tujuan dan sesuai dengan keperluan dan kepentingan pemerintah kolonial pada saat itu. 4. Ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah perlu dijadikan perhatian, sehingga perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan di suatu wilayah dapat mengarah kepada pencapaian tujuan untuk meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. 23 Penetapan lokasi dari suatu jenis kegiatan hendaknya tidak hanya sekedar menerangkan kegiatan tersebut sebagaimana adanya, melainkan harus dibuat keputusan yang rasional serta dikemukakan alasan mengapa kegiatan tersebut berada di suatu tempat. Cara terbaik untuk menyediakan pusat pelayanan kepada penduduk yang mendasarkan pada aspek keruangan adalah dengan menempatkan lokasi kegiatan pada hirarki wilayah yang luasnya makin meningkat dan berada pada tempat sentral. 2.6. Hirarki Pusat Aktivitas Keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan aspek lokasi dalam suatu ruang sudah mulai dipelajari sejak era Von Thunen yang menjelaskan tentang pola spasial dari aktivitas produksi pertanian. Von thunen dari suatu pemikiran sederhana, bahwa pola penggunaan lahan dalam suatu ruang merupakan fungsi dari perbedaan harga produksi pertanian yang dihasilkan dan perbedaan biaya produksinya, dimana jarak dari pusat pasar merupakan faktor penentu besarnya biaya produksi. Pemikiran ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa : (1) biaya hanya ditentukan oleh jarak dari pasar, (2) karakteristik wilayah dianggap homogen, (3) harga di pusat pasar ditentukan oleh mekanisme suplai dan demand yang normal, (4) tidak ada halangan untuk melakukan perdagangan (no barrier to trade) seperti biaya tarif, kebijakan harga, labor immobility, dan tidak dapat menggambarkan dengan cukup baik aktivitas ekonomi riil yang terjadi. Kemudian Christaller (1966), dan Losch (1954), dalam Smith (1976), dengan “teori lokasi pusat” yang mulai mencoba untuk menjelaskan mengapa dalam suatu wilayah bisa muncul pusat-pusat aktivitas. Menurut Christaller (1966), setiap produsen mempunyai skala ekonomi yang berbeda sehingga aktivitasnya akan menjadi efesien apabila jumlah konsumennya mencukupi. Karena itu lokasional aktivitas dari suatu produsen ditujuakan untuk melayani wilayah konsumen yang berada dalam suatu jarak atau range tertentu. Dengan demikian wilayah cakupan dari produk yang dihasilkan akan sangat tergantung kepada seberapa jauh keinginan konsumen melakukan perjalanan untuk memperolehnya, elastisitas demand, harga produk, biaya trasport dan frekwensi penggunaannya. 24 Lokasi di sekitar produsen atau suplier yang memiliki tingkat demand konsumen yang mencakupi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan disebut dengan istilah treshold. Setiap produk yang dihasilkan, termasuk dalam hal ini fasilitas umum, mempunyai wilayah treshold-nya sendiri. Karena itu distribusi spasial dari aktivitas produksi bisa diprediksi berdasarkan wilayah treshold-nya. Dari sisi karakteristik suplai, aktivitas ekonomi skala besar akan berada di pusat pelayana hirarki I karena wilayah treshold-nya luas. Sementara dari sisi karakteristik demand, produk yang sifatnya inelastis dan frekwensi penggunaannya tidak terlalu sering juga akan berada di pusat pelayanan hirarki I, sebagai upaya untuk mengoptimalkan keuntungan melalui maksimalisasi jumlah konsumen yang harus dilayani. Sistem lokasi pusat-pusat pelayanan dapat diidentifikasi melalui pendekatan top down, yaitu dari aktivitas produksi dengan treshold tinggi ke rendah atau bottom up, yaitu dari aktivitas produksi dengan treshold rendah ke tinggi. Christaller (1966), diacu Smith (1976), melakukan identifikasi melalui pendekatan top down. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa lokasi pusat utama akan menjadi semakin besar dan meyebar daripada lokasi pusat yang lebih rendah. Lokasi pusat utama ini akan menyediakan barang dan jasa utama, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang treshold-nya tinggi, dan sekaligus menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang treshold-nya rendah. Keberadaan barang dan jasa yang lebih rendah di lokasi pusat utama disebabkan karena produsen dengan treshold-nya rendah ingin medapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari treshold-nya itu sendiri. Sementara itu lokasi pusat pelayanan yang lebih rendah hanya akan menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah. Sedangakan Losch (1954), diacu Smith (1976), melakukan identifikasi melalui pendekatan bottom up. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa lokasi pusat utama hanya akan menyediakan barang dan jasa utama, sedangkan lokasi pusat yang lebih rendah hanya akan meyediakan barang dan jasa yang lebih rendah. Menurut Smith (1976), pemikiran Losch ini banyak ditentang oleh para peneliti, karena dengan menggunakan teknik skalogram berdasarkan skala Gutman, secara 25 empiris tidak pernah ditemukan lokasi pusat pelayanan yang hanya menyediakan barang dan jasa utama saja. Pada perkembangan selanjutnya, Isard (1975), mulai mempertanyakan kegunaan dari teori yang tidak mampu melakukan prediksi karena asumsinya yang kurang realistis. Berkaitan dengan teori lokasi pusat, asumsi-asumsi yang dikritisi mencakup kondisi wilayah yang homogen, terjadinya persaingan sempurna antara produsen/suplier, lokasi produsen/suplier hanya didasarkan pada treshold, hanya ada satu produsen/suplier pada satu pusat, dan konsumen melakukan perjalanan hanya untuk satu tujuan saja. Berdasarka hasil temuan empiris, produsen/suplier selain menyediakan jasa untuk konsumen, pada dasarnya juga menjadi konsumen bagi produsen/suplier yang lain. Karena itu antara produsen/suplier pun saling terkait dalam kerangka sistem supply dan demand. Dengan demikian sebenarnya para produsen/suplier akan muncul di satu lokasi apabila terjadi konsentrasi demand di lokasi tersebut. Menurut Isard (1975), teori lokasi pusat tidak mempertimbangkan adanya konsentrasi demand, dan munculnya lokasi pusat utama dalam kondisi wilayah yang relatif homogen justru mengganggu asumsi dasar dari teorinya. Selain itu, berdasarkan hasil temuan empiris konsumen biasanya akan membeli lebih dari satu jenis barang dan jasa dalam satu kali perjalanan. Karena itu ketersediaan jenis barang dan jasa yang beragam akan mendorong konsumen untuk melakukan perjalanan. Fakta empiris ini menggugurkan asumsi bahwa konsumen melakukan perjalanan hanya untuk satu tujuan, dan sekaligus membuat asumsi bahwa lokasi produsen/suplier hanya ditentukan oleh treshold-nya menjadi tidak realistis. Apabila produsen/suplier memilih lokasi yang lebih jauh untuk bisa melayani wilayah konsumen yang lebih luas. Tetapi karena bagi konsumen membeli berbagai barang dalam satu kali perjalanan membuat ongkos transport menjadi lebih murah, maka produsen/suplier yang berbeda akan memilih lokasi yang berdekatan untuk melayani keinginan konsumen. Selanjutnya menurut Smith (1976), teori lokasi pusat ini akan sangat membantu dalam menganalisa sistem hirarki pusat wilayah yang terjadi di lapangan secara empiris. Fakta empiris pertama yang dijumpai adalah sistem hirarki pusat yang berjenjang seperti distribusi log-normal (rank-size distribution 26 of urban center). Menurut Berry (1961), diacu dalam Smith (1976), hal ini terjadi karena proses trickle down effect dapat berjalan dengan baik. Tenaga kerja di kota-kota besar akan menuntut upah yang lebih tinggi, sehingga industri akan bergeser ke wilayah-wilayah yang upah tenaga kerjanya lebih rendah. Karena itu industri akan bergeser dari kota-kota besar ke kota-kota yang lebih kecil dan multiplier effect dari bergesernya lokasi industri ini akan mendorong proses trickle down effect terus berjalan. Namun terjadinya proses ini mensyaratkan adanya 2 hal, yaitu adanya pertumbuhan yang berimbang dan berkelanjutan dalam waktu yang relatif lama dan adanya kompetisi diantara perusahaan dalam memperoleh faktor produksi dan tenaga kerja. Faktor empiris kedua adalah sistem hirarki pusat, dimana lokasi pusat utama sangat dominan (primate system). Dalam primate system, tidak semua bagian dari suatu wilayah mendapatkan pelayanan yang sama, tetapi ada satu pusat yang dipilih untuk dikembangkan melebihi share dari produsen/suplier yang secara riil ada di lokasi tersebut memonopoli aktivitas ekonomi seluruh wilayah, dan meninggalkan wilayah hinterland yang jauh menjaditidak terlayani. Banyak orang berpikir bahwa fakta empiris ini mirip dengan model Von Thunen, dimana munculnya primate center justru akan mendorong komersialisasi dan intensifikasi di wilayah hinterland-nya. Tetapi perlu diingat bahwa model Von Thunen tidak mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi bisa bergerak bebas. Menurut Smith (1976), apabila jaringan transportasi, modal, dan industri terkonsentrasi di suatu pusat (primate center), intensifikasi produksi di daerah periphery hanya akan menyebabkab harga yang lebih rendah bagi produk periphery yang dihasilkan (term of trade-nya rendah). Menurut Berry (1961), diacu dalam Smith (1976), primate system ini terjadi karena suatu wilayah sedang dalam proses menuju masyarakat maju atau masyarakat industri, atau karena bargaining politik yang jauh tidak berimbang, dimana lokasi pusat biasanya dihuni oleh para elite dengan kekuatan politik yang jauh lebih besar. Tetapi menurut Smith (1976), ada satu hal yang dilupakan Berry bahwa di negara-negara Amerika Latin primate system terus berlangsung hingga saat ini. Dalam kondisi ini primate system terjadi bukan karena proses pembangunan ekonomi yang sedang berjalan atau karena keberadaan elit politik 27 di pusat kota, tetapi ini merupakan produk dari sistem ekonomi non kompetitif. Artinya perusahaan di primate center mempunyai keuntungan dari kondisi pasar monopsony dalam memperoleh faktor produksi dan tenaga kerja. Dari berbagai uraian di atas, diketahui bahwa berkembangnya suatu lokasi menjadi pusat pelayanan, secara alamiah terjadi karena adanya proses aglomerasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan economic of scale ( biaya per satuan input menjadi lebih murah apabila skala aktivitasnya menjadi lebih besar dan economic of scope (nilai tambah akan meningkat apabila berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda digabungkan). 2.7. Citra Satelit Resolusi Tinggi Kenampakan wilayah perkotaan jauh lebih rumit dari pada kenampakan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan persil lahan kota pada umumnya sempit, bangunan padat dan fungsi bangunannya beraneka. Oleh karena itu sistem penginderaan jauh yang diperlukan untuk menyusun tata ruang harus disesuaikan dengan resolusi spasial yang sepadan, untuk keperluan perencanaan tata ruang detail, maka resolusi spasial yang tinggi akan mampumenyajikan data spasial secara rinci. Untuk keperluan klasifikasi penutup lahan dapat digunakan berbagai citra, dimana ada beberapa citra yang mempunyai resolusi tinggi sehingga mampu menunjukkan perbedaan antara perumahan teratur dengan perumahan tidak teratur atau pemukiman padat dan pemukiman tidak padat. Berbagai data satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 0.7 – 10 m, dapat digunakan untuk memperoleh data penggunaan lahan dengan tingkat kerincian skala 1 : 5000 atau 1 : 10000. Citra satelit resolusi tinggi yang dapat digunakan antara lain SPOT 5, Ikonos, ALOS, Quick Bird, Formosat 2, Orbview 3 dan lain-lain (Martono. 2006). Citra Ikonos merupakan salah satu citra yang beresolusi tinggi. Citra merupakan gambaran yang terekam oleh sensor, sedangkan kata Ikonos berasal dari bahasa Yunani yaitu “Eye-Kohnos” yang artinya sama dengan citra (image). Ikonos merupakan nama satelit sekaligus sensor yang digunakan untuk merekam gambar/obyek permukaan bumi. Satelit Ikonos mengorbit bumi pada orbit Sunsynchronous, 14 kali per hari, atau setiap 98 menit (Hildamus, 2002). 28 Saluran spektral 1, 2 dan 3 dari citra Ikonos multispektral secara berurutan mengukur reflektansi spektrum elektromagnetik pada bagian biru, hijau, dan merah. Pita-pita tersebut untuk mengukur karakteristik spektral yang tampak oleh mata. Saluran mengukur reflektansi spektrum elektromagnetik pada bagian infra merah dekat, dan sangat membantu dalam mengklasifikasi vegetasi. Resolusi Ikonos yang tinggi tersebut memberikan peluang untuk dapat mendeteksi penggunaan lahan secara rinci. Rekaman citra satelit Ikonos menggunakan saluran atau panjang gelombang pankromatik (sinar tampak) dan saluran infra merah dengan pantulan (infra merah dekat) kombinasi saluran menghasilkan warna palsu yang dapat digunakan untuk identifikasi permukaan bumi secara rinci. Citra Ikonos dapat dikoraksi geometri secara presisi, sehingga layak untuk pembuatan peta dasar maupun peta tematik. Resolusi spasial citra Ikonos pankromatik 1 meter, memungkinkan pembuatan peta skala dengan besar yaitu peta skala 1 : 2000, sedangkan citra Ikonos multispektral 4 meter memungkinkan membuat peta skala 1 : 5000, dengan ketelitian pemetaan lebih dari 95 %. Hasil pengecekan lapang di berbagai tempat dapat meningkatkan ketelitian peta menjadi 100 % dengan kaidah kartografi standar. Di bawah ini dapat dilihat spesifikasi citra Ikonos pada Tabel 1. Tabel 1. Spesifikasi Citra Ikonos. Waktu Peluncuran 24 September 1999 Lokasi Peluncuran Venderberg Air Forces Base, California Resolusi Resolusi setiap pita spektral : • Pankromatik : 1 meter (nominal < 260 off nadir) • Multispektral : 4 meter (nominal < 260 off nadir) Respon Spektral Citra • Pankromatik : 0.45-0.90 mikron • Multispektral : 4 meter Lebar Swath dan ukuran • Lebar Swath : 13 km pada nadir Scene • Areas of interest : Citra tunggal 13 km x 13 km Ketinggian 423 mil / 681 km Inklinasi 98,10 Kecepatan 4 mil per detik / 7 km per detik Waktu Orbit 98 menit Tipe Orbit Sun-synchronous Sumber : Hildanus, 2002