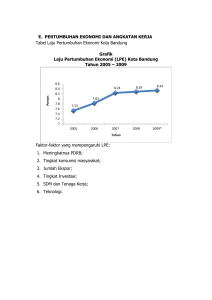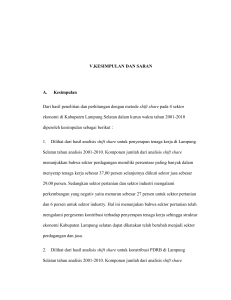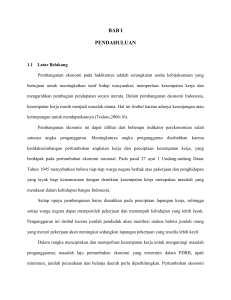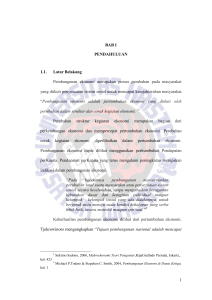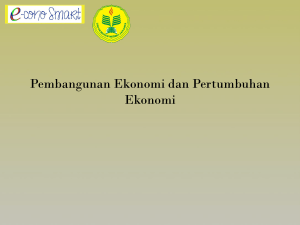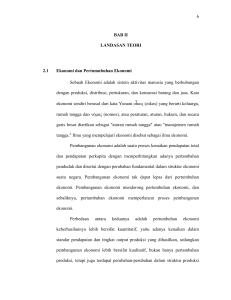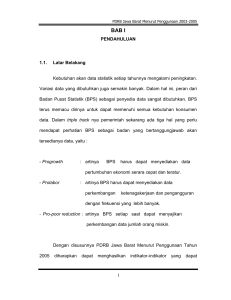analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap produk
advertisement
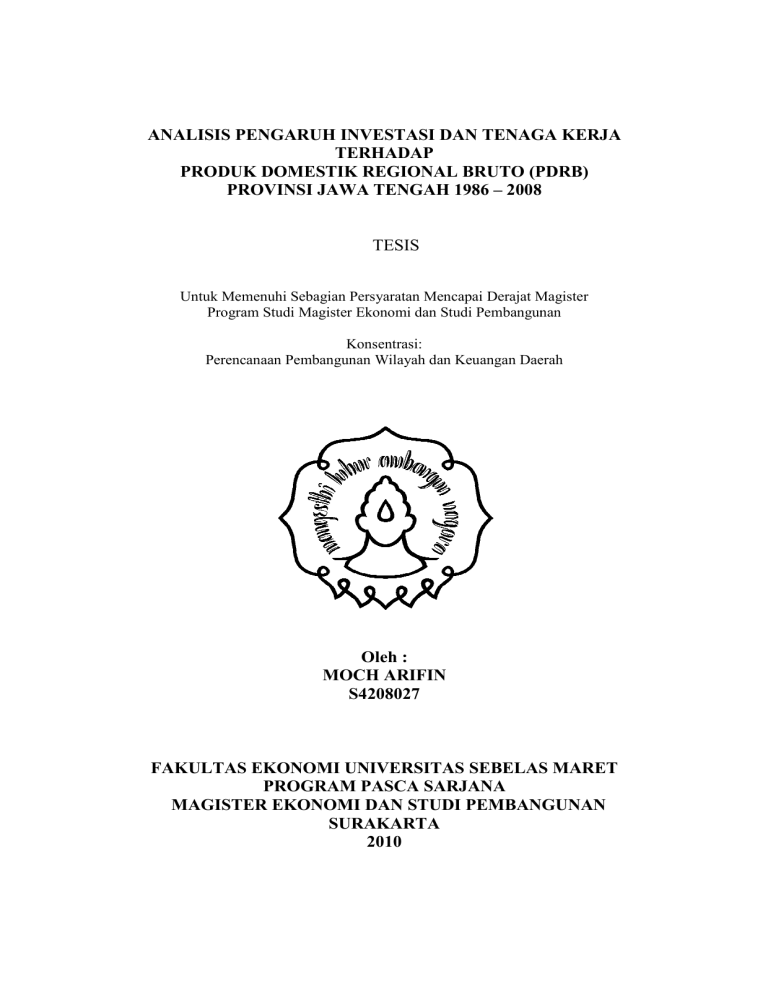
ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH 1986 – 2008 TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi: Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah Oleh : MOCH ARIFIN S4208027 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA 2010 ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH 1986 – 2008. Disusun oleh: MOCH ARIFIN S4208027 Telah disetujui pembimbing Dosen Pembimbing I Dr. AM. Soesilo, M.Sc. 19590328 198803 1 001 Dosen Pembimbing II Drs. Akhmad Daerobi. M.S. NIP: NIP:19570804 198601 1 002 Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Dr. J.J. Sarungu, MS. NIP:19510701 198010 1 001 ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH 1986 – 2008. Disusun oleh: MOCH ARIFIN S4208027 Telah disetujui oleh Tim Penguji: Pada tanggal, Jabatan Ketua Tim Penguji Nama Tanda tangan Dr. J.J. Sarungu, MS. ......................... Pembimbing Utama Dr. AM. Soesilo, M.Sc. ........................ Pembimbing Pendamping Drs. Akhmad Daerobi. M.S. ......................... Mengetahui: Direktur PPs UNS Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Prof. Drs. Suranto, M.Sc. Ph.D NIP. 19570820 198503 1 004 Dr. JJ. Sarungu, MS NIP. 19510701 198010 1 001 HALAMAN PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : MOCH ARIFIN NIM : S4208027 Program Study : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya. Surakarta, 5 Mei 2010 Tertanda, MOCH ARIFIN S4208027 ABSTRACT Moch Arifin NIM S4208027 This research aims to find out the effect of investment and labor on the PDRB of Central Java Province during 1986-2008 period. In line with such problems, the following hypothesis is proposed: It is hypothesized that investment and labor affect investment and labor on the PDRB of Central Java Province during 1986-2008 period. In line with the problem and hypothesis of research, the research took the secondary data derived from Central Statistical Bureau (BPS) of Central Java Province; the data taken in this research consisting of data on investment, labor and PDRB of Central Java Province. The data employed was the one with 23 scale from 1986-2008, then the data collected was put onto the multiple linear regression, and after the estimation parameter obtained, the examination was done using statistic and classical assumption tests. The result of statistic test in this research shows that the independent variable of investment affects positively and significantly the PDRB of Central Java Province, Similarly, the labor affects positively and significantly the PDRB of Central Java Province. Meanwhile based on the result of F-test, investment and labor simultaneously affects the PDRB of Central Java Province. The result of econometric test shows the absence of multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation distractions. Considering the result of data analysis, it is recommended that the government should create conducive climate for the implementation of various investment projects in Central Java Province. The labor has substantial effect on PDRB so that there should be the use of intensive-labor technology to absorb the labor more optimally in the production process. Keywords: Investment, Labor, and PDRB KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjakan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga Thesis yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986 – 2008”. ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa terselesainya penelitian ini adalah atas bimbingan, petunjuk, serta nasehat dari Bapak-Bapak pembimbing dan Bapak/ Ibu Dosen serta Sekretariat Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, maka pada kesempatan ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para beliau. Selanjutnya penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu Dosen serta dari rekan rekan sekalian guna perbaikan penelitian ini. Demikian semoga penelitian ini bermanfa’at. Surakarta, 5 Mei 2010 Peneliti Moch Arifin NIM: S 4208027 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN .................................................................. iv ABSTRAKSI……………………………………………………………... v KATA PENGANTAR ............................................................................ vi DAFTAR ISI .............................................................................................. vii DAFTAR TABEL...................................................................................... x DAFTAR GAMBAR................................................................................ . xi BAB I BAB II PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1 B. Perumusan Masalah .......................................................... 7 C. Tujuan Penelitian ............................................................... 7 D. Manfaat Penelitian ............................................................ 8 TINJAUAN PUSTAKA A. Investasi ............................................................................ 9 1. Definisi Investasi……………………………………. 9 2. Macam-macam Investasi…………………………….. 12 3. Peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. 14 B. Tenaga Kerja ......................................…………………… 16 1. Pengertian Tenaga Kerja............................................... 16 2. Permintaan Tenaga Kerja ……………………………. 18 3. Penawaran Tenaga Kerja................................................. 31 C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ....................... 1 Definisi PDRB............................................................... 34 34 2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi……………………. 38 3. Model Pertumbuhan Ekonomi…………………………. 40 a. Teori pertumbuhan Harrod-Domar ………………. 41 b. Pendekatan Neo-Klasik…………………………….. 50 c.Teori Pertumbuhan Baru (new growth theory)…… 58 D. Peneliti Terdahulu ............................................................. 54 E. Kerangka Pemikiran .......................................................... 64 F. Hipotesis ............................................................................ 67 BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian……………………………………………. 71 B. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………... C. Definisi Operasional Variabel ………………………… .. 71 72 1.Variabel Dependen............................................................ 72 2..Variabel Independen......................................................... 72 D Teknik Analisis Data ........................................................... 73 1. Uji Statistik…………………………………… ……. 74 2. Uji Asumsi Klasik……………………………………….. 78 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Wilayah………………………………………….. 1. Keadaan Geografis………………………………………. 80 80 2. Keadaan Penduduk………………………………………. 84 3. Kondisi Perekonomian................................................... B. Analisis Data ....................................................................... 88 93 1. Persamaan Regresi Linier Berganda Hasil Penelitian…. 93 2. Uji Statistik………………………………………………. 94 3. Pengujian Asumsi Klasik……………………………….. 98 4. Analisis Hasil Regresi ………….……………………….. 102 5. Uji Hipotesa (Teori) ………….…………………………. 103 6. Intepretasi ekonomi .......................................................... 104 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………… 106 B. Saran-saran............................................................................. .106 DAFTAR PUSTAKA................................................................................ ... LAMPIRAN 108 DAFTAR TABEL Tabel Uraian Hal 4.1 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah 84 4.2 Jumlah Penduduk, Kepadatan dan LPP Jawa Tengah Tahun 2008 87 4.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1986-2008 89 4.4 Pembetukan Modal Tetap Provinsi Jawa Tengan Tahun 19862008 91 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 1986-2008 93 4.6 Hasil Estimasi FaktorFaktor PDRB Provinsi Jawa Tengah 94 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas 98 4.8 Uji Heteroskedastisitas 100 yang Berpengaruh Terhadap DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kurva Fungsi investasi............................................................ 10 2.2 Permintaan terhadap tenaga kerja........................................ 19 2.3 Kurve fungsi produksi............................................................ 20 2.4 Kurve nilai produk marjinal.................................................... 21 2.5 Kurve ekuilibrum permintaan tenaga kerja............................. 23 2.6 Kurve maksimasi keuntungan................................................. 24 2.7 Kurve total permintaan total beaya.......................................... 25 2.8 Kurve VMPL............................................................................ 27 2.9 Efek perubahan upah .............................................................. 29 2.10 Kurve perubahan tingkat upah.............................................. .. 32 2.11 Kurve Fungsi Penawaran Tenaga Kerja .............................. ....33 2.12 Kueve laju pertumbuhan…………………………………….. 49 2.13 Ekuelibrum dalam model pertumbuhan Solow……………... 54 2.14 Efek jangha panjang dari perubahan tingkat tabungan............ 56 2.15 Gambar kerangka pemikiran PDRB....................................... 58 3.1 Daerah terima dan daerah tolak uji t… …………………….…76 3.2 Daerah terima dan daerah tolak uji F……………………….. 77 3.3 Autokorelasi…………………………………………….. . 79 4.1 Daerah terima dan daerah tolak uji F………………………… 96 4.2 Grafik Uji Autokorelasi……………………………..............101 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kegiatan pembangunan nasional Indonesia secara nyata membawa pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut antara lain di tunjukan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi dan disertai semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter telah melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan sehingga menguncang dan membawa perubahan mendasar pada sendi-sendi kehidupan politik bangsa dan negara serta perekonomian nasional. Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi perlu kerja keras, ketekunan dan perjuangan tidak ringan serta kerja sama semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pembangunan ekonomi dengan tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai agar dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Kegiatan dalam suatu perekonomian selalu mengalami perubahan. Adakalanya perubahannya sangat nyata dan dapat dirasakan dengan jelas oleh masyarakat yaitu pada saat perekonomian mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi atau keadaan perekonomian yang sedang mengalami kemerosotan serius. Namun demikian, menilai prestasi kegiatan perekonomian dengan cara mengamati apa yang dialami oleh masyarakat bukanlah cara yang terbaik. Cara paling baik adalah dengan memperhatikan data tertentu mengenai kegiatan sesuatu perekonomian dan data ini dikenal sebagai indikator makro ekonomi. Data yang selalu digunakan untuk mengamati kegiatan suatu perekonomian suatu negara antara lain adalah pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kestabilan harga-harga, kesempatan kerja dan pengangguran, neraca pembayaran, kurs valuta asing, suku bunga dan perkembangan pasar saham (Sadono Sukirno, 1999 ). Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara. Produk Domestik Bruto mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Nilai dari Produk Domestik Bruto mengandung dua macam persepsi yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang didalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 1997). Secara lebih jelas, pengertian Produksi Domestik Bruto adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan dinyatakan dalam harga pasar (Suparmoko, 1998 ). Pendekatan fungsi produk untuk menganalisis output secara agregat dapat menggunakan konsep fungsi produksi dari teori ekonomi perusahaan/mikro. Di dalam fungsi produksi disebutkan bahwa output merupakan fungsi dari faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal dan tingkat teknologi (faktor efisien). Sedangkan fungsi produksi agregrat menunjukkan hubungan fungsional antara output agregat atau disebut juga dengan produk domestik bruto dengan stok input. Jika faktor produksi tanah merupakan bagian dari faktor produksi, modal dan teknologi dianggap konstan, maka hanya ada dua jenis faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah diperlukan alat pengukur yang tepat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto bagi suatu daerah dapat dimanfaatkan : 1. Sebagi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara sektoral maupun secara struktural 2. Untuk mengetahui struktur perekonomian dan perubahan-perubahan di suatu daerah 3. Sebagai data dasar untuk menganalisis elastisitas kesemaptan kerja dengan dukungan data ketenagakerjaan 4. Dengan PDRB perencanaan pembangunan suatu daerah bisa lebih terarah, misalnya dengan mengetahui Capital Output Ratio (COR) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 5. Dalam suatu negara atau daerah bisa dihitung berapa jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mencapai perkiraan / proyeksi PDB atau PDRB dari target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran. Perannya ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat. Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa yang akan datang dan perkembangan ini akan merangsang pertambahan produksi nasional. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perekembangan ini akan memberi sumbangan penting keatas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat (Sadono Sukirno, 1999). Investasi itu sendiri merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barangbarang modal dan peralatan-peralatan produksi untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Penanaman modal atau investasi di daerah memegang dua macam fungsi yaitu untuk menciptakan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan untuk menambah kapasitas produksi dari daerah yang bersangkutan. Sebagai faktor untuk menbambah permintaan masyarakat, sejumlah tertentu penanaman modal akan menciptakan pendapatan daerah beberapa kali lipat dari besarnya penanaman modal itu sendiri, karena penanaman modal akan menciptakan proses multiplier yaitu menimbulkan pendapatan dan pengeluaran baru dalam masyarakat sehingga akhirnya menciptakan pertambahan pendapatan beberapa kali lipat lebih besar dari besarnya penanaman modal itu sendiri (Sadono Sukirno, 1999). Investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 tumbuh rata-rata 8,08 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 16.20 persen. Dalan beberapa kurun waktu, yaitu antara tahun 1997 s/d 1999, 2001, dan 2005 nilai investasi mengalami penurunan , hal ini disebabkan oleh situasi politik yang kurang kondusif. Faktor tenaga kerja secara tradisonal dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mampu meningkatkan pendapatan nasional. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif, sehingga apabila kuantitas tenaga kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat pula (Todaro, 2000). Besarnya penawaran tenaga kerja dalam perekonomian adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Golongan tersebut terdiri dari mereka yan sudah aktif dalam memproduski barang dan jasa (bekerja) dan mereka yan sudah siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja. Dengan kata lain angkatan kerja dapat diartikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benarbenar mau bekerja memproduksi barang dan jasa (Payaman Simanjuntak, 2001). Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami fluktuasi tiap tahunnya namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 tenaga kerja Jawa Tengah mencapai angka 15463658 orang. Angka pertumbuhan tenaga kerja rata rata 0.89 persen dan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebesar 7.19 persen. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 dan adanya krisis keuangan global sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dampak secara makro terhadap Indonesia adalah antara lain turunnya nilai investasi asing dan domestik, turunnya nilai ekspor, tutupnya perusahaan, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan hal ini secara tidak langsung dapat mengakibatkan turunnya Produk Domestik Bruto termasuk di dalamnya Produk Domestik Regional Bruto. Berikut ini sedikit ulasan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Nilai PDRB Jawa Tengah selama periode tahun 1986 sampai dengan 2008 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.27 persen. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2000 yaitu sebesar 19.13 persen. Krisis moneter yang dimulai pada pertengahan 1997 mengakibatkan kondisi perekonomian Jawa Tengah mengalami saat paling buruk sepanjang satu dasa warsa terakhir. PDRB mengalami laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar 11,74 persen di tahun 1998. Pada tahun 1999 perekonomian sedikit mengalami perbaikan yang ditandai dari nilai PDRB yang tumbuh 3,5 persen. Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008? B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008 ? 2. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008 ? 3. Bagaimana pengaruh Investasi dan Tenaga kerja secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008 2. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun. 1986 – 2008 3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008 D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terbaik. Sehingga PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat lebih meningkat. 2. Bagi Lingkungan Akademis Untuk menambah khasanah ilmu tentang penelitian yang berhubungan dengan Perekonomian Indonesia serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. 3. Bagi Masyarakat Memberikan sumbangsih bagi masyarakat umum untuk lebih mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi . BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Investasi 1. Definisi Investasi Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku (i), tingkat pengembalian (rate or return), dari barang modal, dan prospek proyek investasi Menurut Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi dan sebaliknya. Penjelasan diatas dapat diringkas dengan persamaan sebagai berikut : I=ƒ(r) (1) Bunga merupakan fungsi Investasi Gambar dibawah ini menunjukkan fungsi investasi. Fungsi itu berbentuk miring ke bawah, karena ketika tingkat bunga naik, jumlah investasi yang diminta turun. Gambar 2.1 Fungsi investasi Tingkat Bunga riil Fungsi Investigasi, 1 ( r ) Kuantitas investasi Sumber: Mankiw, 2000 Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi pada tingkat bunga riil r. Investasi bergantung pada tingkat bunga riil karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi miring ke bawah: ketika tingkat bunga naik, semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan ( Mankiw, 2000). Mengenai pembentukan kapital yang dianggap penting untuk adanya perkembangan, adalah sebagai berikut : Misalnya kesempatan untuk investasi bertambahkatakanlah karena ada kemajuan teknologi. Tambahnya permintaan untuk investasi akan menyebabkan tingkat bunga naik yang selanjutnya akan menaikkan jumlah tabungan. Dengan adanya kenaikan investasi, harga-harga barang kapital juga akan naik. Selanjutnya karena kenaikan-kenaikan tingkat bunga dan harga-harga barang kapital, maka investasi selanjutnya terbatas pada proyek-proyek yang dapat memberikan keuntungan terbesar. Bila proyek-proyek tersebut telah terlaksana maka permintaan terhadap investasi berkurang sehingga tingkat bunga dan harga barang-barang kapital turun kembali. Setelah itu maka proyek-proyek yang kurang menguntungkan menjadi menguntungkan lagi dan seterusnya. Akhirnya tingkat bunga sudah menjadi begitu rendahnya, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menabung. Pada tingkat perkembangan itu akumulasi kapital berakhir dan perekonomian mengalami suatu keadaan yang statis. Dengan tidak adanya akumulasi kapital berarti tidak ada perkembangan. Agar tidak mengalami keadaan yang statis tersebut, maka pengerjaan penuh (full employment) harus selalu dijaga selama proses akumulasi kapital. Pemerintah harus mengadakan proyek-proyek pekerjaan umum (public works). Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan perubahan teknologi menurut Neo-Klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangkan penggunaan tenaga buruh atau relatif lebih bersifat “penghematan buruh” (labor saving) daripada “penghematan kapital” (capital saving). Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang kapital. Investasi juga dapat diartikan berbagai cara atau upaya penambahan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada saatnya nanti pemilik modal tersebut akan mendapat sejumlah keuntungan yang diharapkan dari hasil penanaman modal tersebut. Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse (Jhingan, 1999 ), lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional. 2. Macam-macam Investasi Macam-macam investasi berdasarkan pelaku investasi dapat dibedakan sebagai berikut (Sobri, 1987 ) : a. Investasi Pemerintah (Public Investment) Public investment umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan dan sebagainya. Investasi-investasi seperti ini sering disebut dengan social overhead capital (SOC). Keuntungan bagi investasi-investasi ini baru terasa apabila muncul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, yang juga menaikkan pendapatan, akan memberikan keuntungan bagi produk investasi. b. Investasi Swasta (Private Investment) Private investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah dan pada akhirnya bertambah pula efektif demand. Investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang bersumber investment mungkin dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. c. Investasi Pemerintah dan Swasta Jenis investasi yang dilakukan oleh pihak publik dan swasta adalah investasi luar negeri (foreign investment). Foreign investment terjual dari selisih antara ekspor di atas impor (X-M), induced investment dalam hal (X-M) adalah disebabkan oleh dari penambahan permintaan disebut induced investment. Induced perkembangan ekonomi di luar negeri. Istilah investasi asing menurut definisi IMF Balance of Payment Manual (Edisi, yang juga digunakan Bank Indonesia adalah investasi langsung yang mengarah pada investasi asing untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dari penanaman modal tersebut). Sementara penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Istilah “manfaat yang cukup lama tersebut” merupakan investasi yang pengelolaannya hanya memerlukan pengawasan. Dalam definisi tersebut tidak termasuk investasi portofolio di Indonesia, investasi seperti ini masih sangat kecil dan modal pinjaman yang telah masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sejak 1996. (Jhingan 1999) 3. Peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi Di berbagai negara, terutama di negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat volatile yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dari fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Di samping itu perlu diingat kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja meningkat pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jhingan 1999) . Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian : a. Investasi merupakan salah satu komponen agregat maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa depan, dan perkembangan ini akan menstimular pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga perkembangan teknologi akan memberikan sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah : 1) Suku Bunga Untuk memperoleh modal diperlukan bunga, perusahaan mempunyai dua sumber pembiayaan yaitu dari keuntungan yang tidak dibagikan dan dari meminjam. Apabila keuntungan yang tidak dibagikan tersebut tidak diinvestasikan tetapi didepositokan maka perusahaan akan mendapatkan bunga, sedangkan bila perusahaan melakukan investasi dengan meminjam di bank maka ia harus membayar bunga. Dengan demikian apakah ia akan meminjam pada bank ataukah menggunakan dana sendiri. Oleh karena itu bunga perlu dipandang sebagai suatu biaya penting untuk memperoleh barang modal. 2) Depresiasi Setiap barang modal akan didepresiasikan, dalam prakteknya depresiasi dilakukan secara bertahap yaitu barang modal dikurangi sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Pengurangan barang modal ini merupakan biaya bagi perusahaan. 3) Pendapatan Nasional Pendapatan nasional yang semakin meningkat akan memerlukan barang modal yang semakin banyak. Dengan demikian perusahaan harus melakukan investasi yang lebih tinggi dan lebih banyak modal yang diperlukan. 4) Kebijakan Pemerintah Sikap pemerintah dalam kegiatan usaha sangat penting perannya dalam kegiatan investasi pemerintah. Pajak, keuntungan yang tinggi, hambatan dalam memperoleh pinjaman/devisa untuk mengimpor barang modal akan mengurangi gairah sektor perusahaan untuk berinvestasi. B Tenaga Kerja 1. Pengertian Tenaga Kerja Usia kerja adalah penduduk yang sudah mencapai usia kerja yaitu penduduk yang sudah ikut dan dapat diikurtsertakan dalam proses produksi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlihat dalam kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja tetapi tidak melakukan usaha produktif dan tidak sedang mencari pekerjaan karena alasan tertentu misalnya mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain. Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya disebut pengangguran ( Sadono Sukirno, 1999 ). Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan. Secara praktis pengertian tenaga kerja dibedakan oleh batasan umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda-beda. Di Indonesia dipilih batasan umur minimum sepuluh tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. Pemilihan sepuluh tahun sebagai batas umur minimun adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk muda terutama di desadesa yang sudah bekerja/mencari pekerjaan. Di Indonesia juga tidak menganut batas umur maksimum, alasannya adalah karena di Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua (Payaman Simanjuntak, 1985 ) Sedangkan yang dimaksud pekerja itu sendiri adalah bagian dari angkatan kerja yang benar-benar atau telah memproduksi barang dan jasa. Menurut BPS (2000 ), konsep bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi). 2. Permintaan Tenaga Kerja a. Pasar persaingan sempurna Berikut ini analisis permintaan tenaga kerja dalam dua kasus, yaitu: (1) apabila tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, (2) apabila ada beberapa faktor produksi. 1). Permintaan perusahaan terhadap satu faktor produksi Asumsi berikut ini mendasari analisis ini: a). Sebuah komoditas X diproduksi di pasar persaingan sempurna. Maka dari itu, Px ditetapkan oleh semua perusahaan di pasar. b). Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. c). Terdapat satu faktor, yaitu tenaga kerja di pasar persaingan sempurna. Pada gambar di bawah ini, w adalah upah tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini menyiratkan bahwa persediaan tenaga kerja untuk masing-masing perusahaan sangat elastis. Hal ini dapat dinyatakan dengan sebuah garis lurus w yang sejajar dengan sumbu horizontal. Pada tarif upah tersebut perusahaan dapat mempekerjakan sejumlah tenaga kerja yang diinginkan. Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja w w SL L 0 d). Teknologi diberikan. Bagian yang relevan dari fungsi produksi ditunjukkan pada gambar 2.2. Lerengan fungsi produksi adalah produk fisik marjinal tenaga kerja. dX MPPL dL MPPL menurun pada tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, dengan hukum proporsi variabel. Jika kita mengalikan MPPL pada setiap tingkat pekerjaan dengan harga output tertentu, Px , kita memperoleh kurva nilai produk marjinal VMPL (gambar 2.3). Kurva ini menunjukkan nilai output yang dihasilkan oleh unit tenaga kerja tambahan yang dipekerjakan. Gambar 2.3 Kuva fungsi produksi w X = f(L)k L 0 Gambar 2.4 Kurva nilai produk marjinal W MPPL VMPL MPPL VMPL = MPPL.Pk 0 L Perusahaan akan memaksimalkan keuntungan, jika selama penambahan akan menghasilkan lebih banyak penerimaan total daripada biaya total. Maka dari itu, suatu perusahaan akan mempergunakan sumberdaya sampai ke pada titik di mana unit yang terakhir menyumbangkan kepada total biaya sebanyak total penerimaan, karena Dengan kata lain, syarat keseimbangan dari perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan adalah MCL = VMPL (2) Dimana MCL = biaya marginal tenaga kerja, w& = VMPL atau (3) karena MC L = w& (4) Pada gambar 2.4 keseimbangan perusahaan dinyatakan dengan e. Pada tarif upah pasar w& perusahaan akan memaksimalkan keuntungannya dengan mempekerjakan unit tenaga kerja l*. Hal ini juga karena di bagian sebelah kiri setiap unit l* biaya tenaga kerja yang lebih kecil dari nilai produknya (VMPL > w& ), maka keuntungan perusahaan akan meningkat dengan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Sebaliknya pada bagian kanan l* VMPL < w& , dan oleh karena itu keuntungan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan berada pada tingkat maksimal apabila VMPL = w& . Fungsi produksi adalah X = f ( L) K (5) Total biaya terdiri atas biaya variabel w& .L dan biaya tetap F C = w& ⋅ L + F (6) Penerimaan perusahaan adalah R = Px ⋅ [ f (L )] Perusahaan ingin memaksimalisasi labanya Π = R −C (7) Π = Px [ f ( L )] − (w& ⋅ L + F ) (8) Dengan menetapkan turunan fungsi keuntungan dalam kaitannya dengan tenaga kerja sama dengan nol kita memperoleh dΠ dX = Px ⋅ − w& = 0 dL dL (9) Dengan menyusun kembali dX Px ⋅ ( MPPL ) = w& karena = MPPL dL ( 10 ) Atau VMPL = w& ( 11 ) Gambar 2.5 Kurva ekuilibrum permintaan tenaga kerja VMPL w _ w e SL VMPL 0 L* L Gambar 2.6 Kurva maksimasi keuntungan VMPL w w1 S l1 e1 _ w e SL e2 w2 S l2 VMP L 0 L1 L* L2 L Apabila upah di pasar tenaga kerja naik menjadi w1, maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja menjadi l1 (gambar 2.5) untuk memaksimalkan keuntungan (pada e1 pada gambar 2.5 w1 = VMPL). Demikian halnya, jika upah turun menjadi w2, perusahaan akan memaksimalkan keuntungannya dengan menambah pekerjanya menjadi l2. Permintaan tenaga kerja yang memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat ditentukan baik dengan menggunakan total penerimaan maupun kurva total biaya, atau dengan menggunakan jadwal VMPL dan tarif upah tertentu, yang menentukan persediaan tenaga kerja bagi masing-masing perusahaan. a. Pendekatan total penerimaan-total biaya Keuntungan mencapai tingkat maksimum apabila selisih antara total penerimaan dengan total biaya paling besar. Pendekatan total penerimaan-total biaya ditunjukkan pada gambar 2.7 Lerengan kurva penerimaan adalah penerimaan marginal per unit tambahan tenaga kerja, dan lerengan kurva total biaya adalah tarif upah, yang di pasar persaingan sempurna sama dengan biaya marginal tenaga kerja. Maka dari itu, kondisi untuk keseimbangan perusahaan di pasar adalah MRPL = w = MCL ( 12 ) Karena MRPL = ∂R ∂ ( X ⋅ Px ) ∂X = = Px ⋅ = Px ⋅ ( MPPL ) ( 13 ) ∂L ∂L ∂L Gambar 2.7 Kurve total penerimaan-total biaya TR TC TR MPP L TC TVC 0 9 L dan menurut definisi Px ⋅ ( MPPL ) = VMPL ( 14 ) dapat ditulis syarat keseimbangan sebagai VMPL = w ( 15 ) yang merupakan hasil yang sama seperti hasil yang telah dicapai diatas. b. Pendekatan VMPL Gambar 2.8 adalah contoh VMPL yang menunjukkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Kebutuhan tenaga kerja bagi masing-masing perusahaan adalah garis lurus S1 yang melewati tarif upah yang ditentukan sebesar $40. Kedua kurva tersebut berpotongan pada titik e, yang menentukan permintaan akan tenaga kerja (l = 9) dimana laba perusahaan berada mencapai kedudukan maksimal Gambar 28 Kurve VMPL w 200 100 e1 w1 $40 = w e SL e2 w2 VMPL 0 9 L Perusahaan mencapai keseimbangan dengan menyamakan VMPL dengan tarif upah pasar. Jika upah pasar naik, maka kesetaraan antara w1 dengan VMPL terjadi pada bagian sebelah kiri e. Sebaliknya jika tarif upah turun menjadi w2 maka kesetaraan dengan urva VMPL terjadi pada sebelah kanan e. Dengan demikian, kurva produk nilai produk marginal adalah kurva permintaan tenaga kerja di masing-masing perusahaan. 2). Permintaan perusahaan terhadap beberapa faktor produksi Apabila ada lebih dari satu faktor produksi maka kurva VMP dari sebuah input bukan kurva permintaannya. Hal ini karena berbagai sumber digunakan secara serentak dalam memproduksi barang-barang sehingga suatu perubahan pada harga satu faktor mengakibatkan perubahan pada penggunaan faktor yang lain. Hal itu nantinya menggeser kurva MPP input yang harganya berubah sejak awal. Diasumsikan tarif upah turun, akan diperoleh permintaan baru untuk tenaga kerja, dengan menggunakan analisis isoquant. Perubahan pada tarif upah secara umum memiliki tiga efek yaitu: efek substitusi, efek output, dan efek memaksimalkan keuntungan. Di bawah ini akan dikaji efek tersebut, dengan menggunakan gambar 2.9. Gambar 2.9 Efek perubahan upah K A K2 K1 e2 e1 x2 a B 0 L1 L’1 L 2 x1 B’ K Diasumsikan sejak awal perusahaan menghasilkan output memaksimalkan keuntungan X1 dengan kombinasi antara faktor K1, L1, karena harga factor produksi (awal) w1 dan r1, yang rasionya menentukan kemiringan garis isocost AB. Sekarang diasumsikan bahwa tarif upah turun (w2) sehingga garis isocost yang baru adalah AB (harga modal tetap konstan). Perusahaan, dengan menggunakan pengeluaran biaya yang sama, sekarang dapat menghasilkan output lebih tinggi yang dilambangkan dengan isoquant X2, dengan menggunakan K2 dan L2, yaitu masingmasing adalah jumlah modal dan tenaga kerja. Hasil ini diperoleh dari tangen garis isocost yang baru AB dengan isoquant tertinggi, yang pada contoh, adalah X2. Perubahan dari e1 ke e2 dapat dibagi menjdi dua efek yang berbeda yaitu: efek substitusi dan efek output (hasil). Untuk memahami kedua efek tersebut akan ditarik sebuah garis isocost sejajar dengan garis yang baru (AB) sehingga hal itu merefleksikan rasio harga baru, tetapi tangen terhadap isoquant yang lama X1. Tangen terjadi pada titik a pada gambar 2.8. Perubahan dari e1menjadi a merupakan efek substitusi: perusahaan akan mensubtitusi modal yang relatif lebih mahal dengan tenaga kerja yang lebih murah, bahkan meskipun ia harus memproduksi tingkat output awal X1. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja naik dari L1 ke L`1. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak akan tetap berada pada a. Karena, apabila upah turun, maka perusahaan, dengan total biaya pengeluaran yang sama, dapat membeli lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak modal, atau lebih banyak keduanya. Akibatnya, perusahaan tersebut dapat memproduksi output yang lebih tinggi X2, yang mempergunakan K2 modal dan L2 tenaga kerja. Peningkatan pekerjaan dari L`1 ke L2, yang sesuai dengan perubahan dari a ke e2, adalah efek output. b. Pasar persaingan tidak sempurna Dalam kondisi pasar persaingan tidak sempurna, menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan kurva Produk Penerimaan Marjinal Tenaga kerja ( Marginal Revenue Product / MRPL ) yang ditentukan dengan mengalikan Produk Marjinal Tenaga kerja ( Marginal Product of Labour/MPL) dengan Penerimaan Marjinal ( Maginal Revenue/ MR) dari penjualan komoditas yang diproduksi: MRPL = MPL .MRx (16) Turunan matematika dari kurva MRPL: Dapat dilihat bahwa MRPL = MPL.MR 1) (17) Diketahui fungsi permintaan untuk produk adalah Px = f1 (Qx ) (18) Total penerimaan perusahaan adalah TR = Px . Qx (19) dan penerimaan marjinal dQ x dP d (TR ) = Px ⋅ + Qx ⋅ x dQ x dQ x dQ x MR x = Px + Q x atau (20) dPx dQ x (21) 2). Fungsi produksi dengan tenaga kerja sebagai satu-satunya variabel adalah Q x = f 2 ( L) (22) MPPL adalah dQ x = MPPL dL (23) 3). Menurut definisi, produk penerimaan marginal tenaga kerja adalah penambahan penerimaan yang didapat atas penambahan satu unit tenaga kerja. MRPL = d (TR ) dL (24) Dengan TR = Px · Qx, turunan total penerimaan dalam kaitannya dengan L adalah dP dQ x dQ d (TR) = Px ⋅ x + Qx x ⋅ dL dL dQx dL atau MRPL = dQ x dL dPx Px + Q x ⋅ dQ x (25) (26) dari (10) dPx = MPPL dQ x (27) dan dari (8) dPx Px + Q x ⋅ = MRx dQ x Maka dari itu, MRPL = (MRL).(MPx) (28) (29) 3. Penawaran Tenaga Kerja Menurut teori, penawaran kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Sebetulnya penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak ? keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya. Kenaikan tingkat upah berarti pertambahan pendapatan. Dengan status ekonomi lebih tinggi, seseorang cenderung untuk meningkatkan konsumsi dan menikmati waktu senggang lebih banyak, yang berarti mengurangi jam kerja (income effect). Di pihak lain kenaikan tingkat upah juga berarti harga waktu menjadi lebih mahal. Nilai waktu yang lebih tinggi mendorong keluarga mensubstitusikan waktu senggangnya untuk lebih banyak bekerja menambah konsumsi barang. Penambahan waktu bekerja tersebut dinamakan substitution effect dari kenaikan tingkat upah. Gambar : 2.10 Kurve Perubahan tingkat upah Upah A2 A1 C Kerja O 12 24 jam 12 Laisure OA1 : Jumlah upah bila bekerja selama 24 jam OA2 : Upah per jam naik bekerja 24 jam Titik C : Bila upah maksimum OA mau bekerja 12 jam dan istirahat 12 jam Sebaliknya tingkat upah akan mengakibatkan pengurangan waktu bekerja bila substitution effect lebih kecil dari income effect. Grafik fungsi penawaran tersebut dapat dilukiskan dengan cara lain seperti dalam gambar dibawah ini. Gambar : 2.11 Kurve Fungsi Penawaran Tenaga Kerja Wage S3 S2 S1 H D Laisure Sampai dengan jumlah jam kerja HD, waktu yang disediakan untuk bekerja bertambah sehubungan dengan pertambahan tingkat upah. Sesudah mencapai jumlah waktu bekerja HD jam, keluarga mengurangi jam kerjanya bila tingkat upah naik. Penurunan jam kerja sehubungan pertambahan tingkat upah (penggal grafik S2S3) dinamakan backward-bending. Penawaran (supply) tenagakerja keseluruhan adalah penjumlahan jumlah jam kerja (supply) dari seluruh keluarga-keluarga. Hal ini dapat dilukiskan dengan menambahkan grafik penawaran dari tiap-tiap keluarga secara horizontal C Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1 Definisi PDRB PDRB di artikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDRB berbeda dari Produk Domestik Regional Netto karena tidak menghitung perpindahan pendapatan antar negara, dan dengan itu menilai sebuah wilayah berdasarkan produksi yang dilakukannya dari pendapatan yang diterimanya. PDRB nominal merujuk kepada jumlah nilai uang yang dihabiskan untuk PDRB, PDRB asli merujuk kepada suatu langkah untuk mengoreksi angka tersebut dengan melibatkan efek dari inflasi agar dapat memperkirakan jumlah barang dan jasa yang sebenarnya menjadi basis perhitungan PDRB. Produk Domestik Regional bruto atau Gross Domestic Product adalah suatu alat ukur pertumbuhan ekonomi bagi suatu Provinsi ataupun Provinsi/Kota. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat angka ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari nilai pendapatan nasionalnya. Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri atau dari warga negara asing (Al Gifari, 1998 ). Pengertian Produk Domestik Regional Bruto menurut kantor statistik Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi 3 bagian : 1. Pengertian Menurut Produksi Menurut pengertian produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu menjadi 9 lapangan usaha : a. Sektor Pertanian b. Sektor Pertambangan c. Sektor Industri Pengolahan d. Sektor Listrik, Gas dan Air e. Sektor Bangunan f. Sektor Perdagangan g. Sektor Lembaga Keuangan Persewaan dan Jasa h. Sektor Jasa-jasa 2. Pengertian Menurut Pendapatan Menurut pengertian pendapatan PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam rangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan di atas termasuk pula komponen jangka waktu tertentu (satu tahun). 3. Pengertian Menurut Pengeluaran Menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga di lembaga swasta tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto yang lain adalah PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. 1) PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan. 2) PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atas pendapatan atau pengeluaran yang nilai atas harga tetap suatu tahun tertentu. 3) PDRB perkapita yaitu PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Perhitungan PDRB atas harga konstan satu tahun dasar sangat penting karena bisa untuk melihat perubahan riil dari tahun ke tahun dari agregat ekonomi yang diamati. Hal ini berarti dapat pula melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang besar berati ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara berkembang, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kelebihan tenaga kerja benar-benar akan memberikan dampak positif, justru negatif. Dari pernyataan diatas, menurut (Todaro, 1998). Menyatakan bahwa positif atau negatif pertambahan penduduk yang akan menjadi angkatan kerja bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor pendukung, seperti kecakapan, manajerial dan pengadministrasian. 2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1997). Suatu perekonomian harus dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderung jangka panjang yang meningkat. Namun demikian tidak berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan suatu perekonomian menurun pada tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi modern pertanda penting dalam kehidupan perekonomian. Simon Kuznets menyatakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern melalui (Jhingan, 1993 ) : a. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Perkapita Pertumbuhan ekonomi modern, sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal ke-19, ditandai dengan kenaikan produk perkapita yang dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju pertumbuhan yang luar biasa ini paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sekali untuk produksi. b. Peningkatan Produktivitas Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-kedunya. Kenaikan efisiensi berarti perolehan hasil output yang lebih besar dari setiap unit input yang digunakan. Menurut Kuznes laju kenaikan produktivitas tetap dapat menjelaskan keseluruhan pertumbuhan produk perkapita di negara maju. Bahkan dengan beberapa penyesuaian untuk menampung biaya dan input yang tersembunyi, pertumbuhan produktivitas tetap dapat menjelaskan lebih dari separuh pertumbuhan dalam produk perkapita. c. Laju Pertumbuhan Struktural Yang Tinggi Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa. Perubahan dalam skala unit-unit produktif dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status buruh. d. Urbanisasi Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan banyaknya penduduk di negara maju berpindah dari desa ke perkotaan yang disebut urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi, skala ekonomi yang timbul dalam usaha non agraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan. Karena secara teknik transportasi, komunikasi berkembang menjadi efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skala optimum. Semua proses ini mempengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar perikehidupan. e. Arus Barang, Modal dan Orang Antar Bangsa Arus barang, modal dan orang antara bangsa kian meningkat sejak abad ke19 sampai perang dunia ke-1, tetapi memudar pada perang dunia ke-1 dan berlanjut sampai akhir perang dunia ke-2. namun kemudian sejak abad ini terjadi peningkatan. 3. Model Pertumbuhan Ekonomi Teori-teori pertumbuhan yang termasuk dalam kajian ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat asas (konsisten), tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris (historis)-nya dan bersifat deduksi teoritis. Adapun pendekatan yang dimaksud dan menjadi model pertumbuhan ekonomi dalam kajian penelitian ini yaitu pendekatan Neo-Keynesian ( model Harrod-Domar ) dan dari pendekatan Neo Klasik ( Model Solow ). c. Teori pertumbuhan Harrod-Domar Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh Evsey Domar ( Massachussets Institute of Technology ) dan Sir Roy F. Harrod ( Oxford University ) Teori ini mengembangkan analisis Keynes dengan mamasukkan masalah-masalah ekonomi jangka panjang serta menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bias tumbuh dan berkembang dengan mantap (steady growth). Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua “dampak penawaran” investasi. Pekerjaan dipertahankan dalam jangka panjang, dengan memperbesar investasi. Hal ini lebih lanjut memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus-menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh, tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut sebagai “tingkat pertumbuhan terjamin” (warranted rate of growth) atau “tingkat pertumbuhan kapasitas penuh”. Model yang dibuat oleh Harrod dan Domar didasarkan pada asumsi sebagai berikut : 1. Ada ekulibrium awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh 2. Tidak ada campur tangan pemerintah 3. Model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri 4. Tidak ada kesulitan didalam penyesuaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produktif 5. Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung marginal 6. Kecenderungan menabung marginal tetap konstan 7. Koefisien modal, yaitu rasio stok modal terhadap pendapatan, diasumsikan tetap (fixed) 8. Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai seumur hidup 9. Tabungan dan invesatsi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama 10. Tingkat harga umum konstan, yaitu upah uang sama dengan pendapatan nyata 11. Tidak ada perubahan tingkat suku bunga 12. Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi 13. Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal. Terakhir di dalam perekonomian itu hanya terdapat satu jenis produk. Kesemua asumsi ini tidak penting bagi kesimpulan akhir permasalahannya, namun dimaksudkan untuk menyederhakan analisanya. Model Domar Investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produktif, agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan di dalam kapasitas produktif, maka perlu mempererat kaitan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat melalui investasi. Kenaikan kapasitas produksi; Domar menjelaskan sisi penawaran tersebut sebagai berikut. Kita anggap laju investasi tahunan adalah I, dan kapasitas produksi tahunan per dolar modal yang baru ditanam rata-rata sama dengan s (yang menggambarkan rasio kenaikan pendapatan nyata atau output terhadap kenaikan modal output marginal). Jadi kapasitas produktif dolar I yang diinvestasikan adalah I.s dollar per tahun. Kenaikan yang diperlukan dalam permintaan agregat; Sisi permintaan dalam sistem Domar dijelaskan dengan pengali (multiplier) Keynesian. Misalnya kenaikan rata-rata pendapatan kita nyatakan dengan Y dan kenaikan dalam investasi dengan I dan kecenderungan menabung dengan α(alpha) (=∆S/∆Y). Maka kenaikan pendapatan itu akan sama dengan multiplikator (I/α) kali kenaikan dalam investasi. ∆Y = ∆I 1 α ( 30 ) Ekuilibrium; Untuk mempertahankan tingkat ekulibrium pendapatan pada pekerjaan penuh, permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Dengan ini kita sampai pada persamaan dasar model tersebut : ∆I 1 α = Iσ ( 31 ) Dengan membagi kedua ruas persamaan dengan I dan mengalikannya dengan σ kita mendapatkan : ∆I = ασ I ( 32 ) Persamaan ini menunjukan bahwa untuk mempertahankan pekerjaan penuh laju pertumbuhan investasi autonomous netto (∆I/I) harus sama dengan (MPS kali produktivitas modal). Inilah batas kecepatan laju investasi yang diperlukan untuk menjamin penggunaan kapasitas potensial dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang mantap pada keadaan pekerjaan penuh. Domar memberikan contoh angka untuk menjelaskan hal ini. Model Harrod: Prof. R.F. Harrod mencoba menunjukkan dalam model bagaimana pertumbuhan mantap (yaitu ekuilibrium) dapat terjadi dalam perekonomian. Sekali laju pertumbuhan mantap itu terganggu dan perekonomian jatuh ke dalam disekuilibrium, kekuatan-kekuatan kumulatif cenderung mengabaikan perbedaan tersebut yang selanjutnya akan membawanya ke deflasi jangka panjang atau inflasi jangka panjang. Model Harrod didasarkan pada 3 (tiga) macam laju pertumbuhan. Pertama, laju pertumbuhan aktual, dinyatakan dengan G, yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal-output. Laju ini menunjukkan variasi siklis jangka pendek dalam laju pertumbuhan. Kedua, laju pertumbuhan terjamin, yang dinyatakan dengan Gw, yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. Terakhir, laju pertumbuhan alamiah (natural growth rate), dinyatakan dengan Gn, yang oleh Harrod dianggap sebagai “optimum kesejahteraan”. Ia dapat juga disebut sebagai laju pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh. Laju pertumbuhan aktual. Di dalam model Harrod persamaan dasarnya yang pertama ialah : GC = S ( 33 ) dimana G merupakan laju pertumbuhan output dalam jangka periode waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai ∆Y/Y; C adalah tambahan netto terhadap modal yang didefinisikan sebagai rasio investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu I/∆Y; dan S adalah kecenderungan menabung rata-rata yaitu S/Y. Dengan memasukkan rasio-rasio ini kedalam persamaan diatas kita peroleh: ∆Y I S I S x = atau = atau I = S Y ∆Y Y Y Y ( 34 ) Persamaan ini hanyalah pernyataan kembali kebenaran bahwa tabungan expost (aktual, terealisasi) sama dengan investasi expost. Hubungan di atas terungkap perilaku pendapatan. Sementara S tergantung pada Y, I tergantung pada tambahan pendapatan (∆Y), yang terakhir tidak lain adalah prinsip percepatan (akselerasi). Laju pertumbuhan terjamin; Laju pertumbuhan terjamin, menurut Harrod, adalah laju pertumbuhan “dimana para produsen merasa puas atas apa yang dikerjakan”. Persamaan untuk laju terjamin ini ialah : Gw Cr = s ( 35 ) dimana Gw merupakan “laju pertumbuhan terjamin” Jadi, Gw dalam hal ini adalah nilai ∆Y/Y. Cr, atau modal yang dibutuhkan, menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan terjamin tersebut yaitu rasio modal-output yang diperlukan. s adalah sama dengan s dalam persamaan pertama yaitu S/Y. Persamaan itu dengan demikian menunjukkan bahwa apabila perekonomian dimaksudkan untuk maju dengan laju pertumbuhan mantap Gw yang akan menggunakan kapasitasnya secara penuh, Asal muasal Dis-ekuilibrium jangka panjang. Bagi pertumbuhan ekuilibrium pekerjaan penuh, laju pertumbuhan aktual G harus menyamai Gw yaitu laju pertumbuhan terjamin yang akan memberikan kemajuan mantap kepada perekonomian tersebut, dan C (barang modal aktual) harus menyamai Cr (barang modal yang diperlukan bagi pertumbuhan mantap). Jika G dan Gw tidak sama, perekonomian akan berada dalam disekuilibrium. Misalnya, jika G melebihi Gw maka C akan lebih kecil daripada Cr. Apabila G > Gw, timbul kelangkaan. “Akan terjadi kekurangan barang di pasaran dan atau kekurangan peralatan”. Situasi semacam ini membawa ke arah inflasi jangka panjang sebab pendapatan aktual berkembang dalam laju yang lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh pertumbuhan kapasitas produktif perekonomiannya. Ini akan lebih lanjut membawa ke arah kekurangan barang modal (C < Cr). Dalam situasi seperti ini Cr, investasi yang diinginkan (direncanakan, dimaksudkan atau ex-ante) akan lebih besar daripada C, investasi yang terlaksana agregat. Dengan demikian akan terjadi inflasi kronis. Pada fihak lain, apabila G lebih kecil daripada Gw, maka C lebih besar daripada Gr, situasi semacam ini membawa kepada depresi jangka panjang sebab pendapatan aktual tumbuh lebih lamban daripada apa yang diperlukan oleh kapasitas produksi perekonomiannya. Ini akan menyebabkan timbulnya ekses barang modal (C >Cr), yang berarti bahwa investasi yang diperlukan lebih kecil daripada investsi yang teralisir dan bahwa permintaan agregat mengalami kekurangan penawaran agregat. Akibatnya ialah jatuhnya output, pekerjaan dan pendapatan. Demikian yang akan terjadi situasi itu ialah depresi kronis. Laju pertumbuhan alamiah. Laju pertumbuhan alamiah “adalah laju kemajuan dimana pertumbuhan penduduk dan perbaikan teknologi berjalan lamban”. Laju ini tergantung pada variabel-variabel makro seperti penduduk, teknologi, sumber alam dan peralatan modal. Persamaan untuk laju pertumbuhan alamiah adalah : Gn . Cr = atau ≠ S ( 36 ) Gn adalah apa yang disebut laju pertumbuhan pekerjaan penuh atau alamiah tersebut di atas. Perbedaan antara G, Gw, dan Gn Sekarang bagi pertumbuhan ekuilibrium pekerjaan penuh Gn = Gw = G. Tetapi keseimbangan ini merupakan “keseimbangan sempurna”. Karena, sekali timbul perbedaan antara laju pertumbuhan alamiah, terjamin dan aktual, akan tercipta kondisi stagnasi atau inflasi jangka panjang. Jika G > Gw, investasi meningkat lebih cepat daripada tabungan. Dan pendapatan naik lebih cepat daripada Gw. Apabila G < Gw, tabungan naik lebih cepat daripada investasi dan kenaikan pendapatan lebih kecil daripada Gw. Jadi Harrod menunjukkan bahwa jika Gw > Gn stagnasi sekuler akan terjadi. Dalam situasi seperti itu Gw juga lebih besar daripada G sebab batas atas laju aktual ditentukan oleh laju alamiah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.12 (A), pada waktu Gw melampaui Gn > Cr dan barang-barang modal menjadi berlebihan karena buruh langka. Kelangkaan buruh ini menyebabkan laju kenaikan output tetap ada pada tingkat yang lebih rendah dari pada Gw. Mesin-mesin menjadi ngangur (idle) dan terjadi ekses kapasitas. Ini lebih lanjut menghambat investasi, output, pekerjaan dan pendapatan. Laju, perekonomian akan tercengkeram depresi kronis. Di bawah keadaan seperti ini tabungan merupakan sesuatu hal yang buruk. Gambar 2.12 Kurve laju pertumbuhan Apabila Gw < Gn, Gw juga lebih kecil daripada G seperti terlihat dalam gambar 2.12 (B). Dalam perekonomian seperti itu ada kecenderungan terjadinya inflasi jangka panjang, jika Gw lebih kecil daripada Gn, C < Cr. Disini barangbarang modal menjadi langka dan buruh melimpah ruah. Keuntungan begitu tinggi karena investasi yang teralisir lebih kecil daripada investasi yang direncanakan dan para pengusaha cenderung untuk meningkatkan stok modal mereka. Ini akan membawa ke arah inflasi jangka panjang. Dalam situasi seperti itu tabungan merupakan hal yang baik karena akan memungkinkan laju terjamin tersebut naik. d. Pendekatan Neo-Klasik Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara Gw dan Gn tersebut timbul dari asumsi pokok pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi ini dilepaskan, keseimbangan tajam antara Gw dan Gn juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap seperti itu. Asumsi Solow membangun modelnya disekitar asumsi berikut : 1. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi 2. Yang dimaksud output ialah output netto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal 3. Returns to scale bersifat konstan. Dengan kata lain fungsi produksi adalah homogen pada derajat pertama 4. Dua faktor produksi buruh dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka 5. Harga dan upah fleksibel 6. Buruh terperkerjakan secara penuhj 7. Stok modal yang ada juga terperkerjakan secara penuh k 8. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain 9. Kemajuan teknik bersifat netral Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam modelnya bahwa dengan koefisen teknik yang bersifat variabel, rata-rata modal buruh akan cenderung menyesuaikan dirinya, dalam perjalanan waktu, kearah rasio keseimbangan. Jika rasio sebelumnya antara mdoal terhadap buruh lebih besar, modal dan output akan tumbuh lebih lamban daripada tenaga buruh, dan sebaliknya. Analisa Solow berakhir pada jalur keseimbangan (keadaan mantap) yang berangkat dari sembarang rasio modal buruh. Model Solow Model pertumbuhan neoklasik Solow, mungkin merupakan model pertumbuhan ekonomi yang paling terkenal. Meskipun dalam hal tertentu model Solow menggambarkan perekonomian negara maju secara lebih baik daripada kemampuannya dalam menjelaskan perekonomian negara berkembang. Model ini menyatakan bahwa secara kondisional, perekonomian berbagai negara akan bertemu (converge) pada tingkat pendapatan yang sama, dengan syarat bahwa negara-negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan produktivitas yang sama. Karena itu, model Solow adalah kerangka dasar bagi penelitian tentang konvergensi antaranegara. Modifikasi penting dari model pertumbuhan Harrod-Domar (atau model pertumbuhan AK), adalah model Solow membolehkan substitusi antara model dan tenaga kerja. Dalam proses produksi, model ini mengasumsikan bahwa terdapat tambahan hasil yang semakin berkurang dalam penggunaan input-input ini. Fungsi produksi agregat, Y = F(K,L) mengasumsikan skala hasil yang konstan (constant returns to scale). Sebagai contoh, dalam kasus khusus yang dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas pada waktu t didapatkan. Y(t) = K(t)α(A(t)L(t)1-α ( 37 ) Dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang dapat mencakup modal manusia maupun modal fisik), L adalah tenaga kerja, dan A(t) adalah produktivitas tenaga kerja, yang tumbuh selamanya pada tingkat eksogen. Karena adanya skala hasil yang konstan, jika semua input dinaikkan dengan jumlah yang sama, katakanlah 10%, maka output akan naik dengan jumlah yang sama (10% dalam hal ini) Notasinya adalah : γY = F(γK, γL) ( 38 ) Di mana γ adalah positif (1,1 jika kenaikannya 10%). Karena γ dapat berupa angka riil positif berapa pun, sebuah “trik” matematis yang bermanfaat untuk menganalisis implikasi model tersebut adalah dengan menetapkan nilai γ = 1 / L, sehingga Y/L = f(K/L, 1) ( 29 ) atau y = f(k) ( 39 ) Penyederhanaan ini membuat hanya berurusan dengan satu variabel dalam fungsi produksi. Misalnya, dalam kasus Coba-Douglas. Y = Akα ( 40 ) Hal ini mencerminkan sebuah cara alternatif mengenai fungsi produksi, dimana segala sesuatu dihitung dalam kuantitas per tenaga kerja. Persamaan ( 40 ) menyatakan bahwa output per pekerja adalah fungsi yang tergantung pada jumlah modal per tenaga kerja. Semakin banyak jumlah modal yang harus ditangani masing-masing pekerja, maka semakin banyak pula output yang dapat dihasilkan per pekerja. Katakanlah angkatan kerja tumbuh pada tingkat sebesar n per tahun, dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (yaitu tingkat kenaikan nilai A dalam fungsi produksi) meningkat sebesar γ. Persediaan modal total tumbuh ketika tabungan tumbuh lebih cepat dibandingkan depresi, namun modal per tenaga kerja tumbuh ketika tabungan juga lebih besar dari pada yang diperlukan untuk memasok para pekerja baru dengan jumlah modal yang sama dengan yang dimiliki pekerja yang sudah ada. Gambar 2.13 Ekuilibrium dalam Model Pertumbuhan Solow Persamaan Solow (Gambar 2.13) menunjukkan rasio pertumbuhan modal tenaga kerja, k (disebut sebagai pendalaman modal atau capital deepening), dan menunjukkan bahwa pertumbuhan k tergantung pada tabungan sf(k), setelah memperhitungkan jumlah modal yang ada per tenaga kerja kepada tenaga kerja baru neto yang memasuki angkatan kerja, nk, yaitu : ∆k = sf(k) – (δ + n)k ( 41 ) Versi lain dari persamaan Solow juga valid untuk model pertumbuhan yang lain, seperti dalam model Harrod – Domar. Untuk penyederhanaan, kita mengasumsikan sekarang bahwa A tetap konstan. Dalam hal ini, akan terjadi keadaan dimana output dan modal per tenaga kerja tidak lagi berubah, yang dikenal sebagai kondisi mapan (steady state). (Jika A meningkat, kondisi yang mengikutinya adalah kondisi di mana modal per pekerja yang efektif tidak lagi berubah, jika demikian, jumlah pekerja yang efektif meningkat jika A meningkat, karena jika para pekerja mempunyai produktivitas yang lebih tinggi, hal ini serupa dengan adanya pekerja tambahan yang mengerjakan pekerjaan tersebut). Untuk menemukan kondisi mapan ini, ∆k ditetapkan sama dengan 0 : sf(k*) = ( + n)k* ( 42 ) Notasi k* berarti bahwa tingkat modal per pekerja ketika perekonomian berada pada kondisi mapan. Sehingga ekuilibrium ini stabil, seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 2.12 Modal per pekerja k* mencerminkan kondisi mapan, jika k lebih tinggi atau lebih rendah daripada k*, perekonomian akan kembali ke kondisi mapan tersebut; sehingga k* merupakan ekuilibrium yang stabil. Stabilitas ini terlihat di dalam peraga dengan mencatat bahwa disebelah kiri k* , k < k*. Pada peraga, kita lihat bahwa dalam hal ini, (n+δ)k < sf(k). Ketika (n+δ)k < sf(k), ∆k > 0. Hasilnya, k dalam perekonomian bergerak menuju titik lihat bahwa ketika (n + d)k > sf(k), k < 0. Hasilnya, k dalam perekonomian bergerak menuju titik ekuilibrium k*. Dengan penalaran yang sama, di sebelah kanan k*, (n+d)k > sf(k) dan hasilnya k 0, dan modal per tenaga kerja menyusut menuju ekuilibrium k*. Perlu untuk dipertimbangkan apa yang akan terjadi pada model ini jika meningkatkan tingkat tabungan s. Peningkatan sementara dalam tingkat pertumbuhan output terjadi ketika k ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat tabungan.. Dalam model Solow, tidak seperti dalam analisis, implikasi kuncinya adalah bahwa peningkatan s tidak akan meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang, namun hanya akan meningkatkan keseimbangan k*. Sehingga, setelah perekonomian mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri, rasio modal-tenaga kerja meningkat, dan demikian pula rasio output-tenaga kerja, namun bukan tingkat pertumbuhan. Efeknya terlihat pada Gambar 2.14 Gambar 2.14 Efek jangka panjang dari perubahan tingkat tabungan Kalau di perhatikan, peningkatan s memang menaikkan output ekuilibrium per kapita yang tentunya merupakan kontribusi yang sangat bernilai untuk pembangunan. Dan tingkat pertumbuhan memang naik sementara, seiring dengan meningkatnya ekuilibrium ke ekuilibrium modal per pekerja yang lebih tinggi. Lebih jauh, simulasi yang didasarkan pada data antarnegara menyatakan bahwa jika s ditingkatkan, perekonomian mungkin tidak akan kembali ke setengahnya kondisi mapan selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga, untuk tujuan praktis pembuatan kebijakan di negara berkembang, bahkan jika model Solow merupakan penggambaran perekonomian yang akurat, peningkatan tabungan dapat menaikkan tingkat pertumbuhan secara substansi selama beberapa dekade ke depan. Akhirnya, adalah mungkin bahwa tingkat tabungan berhubungan secara positif dengan tingkat kemajuan teknologi itu sendiri, sehingga pertumbuhan A bergantung pada s. Hal ini dapat terjadi jika investasi menggunakan modal unggulan yang lebih baru dan karenanya lebih produktif, jika investasi mencerminkan inovasi yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, dan jika perusahaan yang lain melihat investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan menirunya (learning by watching), dan menghasilkan eksternalitas. Hal ini menyebabkan munculnya sebuah model yang merupakan perpaduan antara model Solow yang standar dengan model pertumbuhan endogen c. Teori Pertumbuhan Baru (new growth theory): Pertumbuhan Endogen Menurut teori neoklasik, rasio modal tenaga kerja yang rendah pada negaranegara berkembang menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang luar biasa tinggi. Karenanya, reformasi pasar bebas yang dibebankan pada Negara-negara yang mempunyai banyak utang oleh Bank Dunia dan IMF seharusnya akan memicu investasi yang lebih tinggi, meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan standar kehidupan. Namun, bahkan setelah menerapkan liberalisasi dalam perdagangan dan pasar domestik, banyak negara berkembang yang tidak tumbuh atau hanya tumbuh sedikit dan gagal menarik investasi asing, atau gagal mencegah larinya modal domestik ke luar negeri. Perilaku aliran modal negara-negara berkembang yang aneh (dari negara miskin ke negara kaya) turut memicu konsep pertumbuhan endogen (endogenous growth) atau dengan kata lain yang lebih sederhana, teori pertumbuhan baru (new growth theory). Teori pertumbuhan baru ini mencerminkan komponen kunci dari teori pembangunan yang muncul. Teori pertumbuhan baru tersebut memberikan kerangka teoritis untuk menganalisi pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP yang persisten, yang ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi dan bukan oleh kekuatankekuatan di luar sistem. Berlawanan dengan teori neoklasik tradisional, model-model ini menganggap bahwa pertumbuhan GNP merupakan konsekuensi alamiah dari keseimbangan jangka panjang. Motivasi utama dari teori pertumbuhan baru ini adalah untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam pertumbuhan yang diobservasi. Lebih jelasnya lagi teori pertumbuhan endogen berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam pertumbuhan yang diobservasi. Lebih jelasnya lagi, teori pertumbuhan endogen berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besaran λ, yaitu tingkat pertumbuhan GDP yang tidak dijelaskan dan dianggap sebagai variabel eksogen dalam perhitungan teori pertumbuhan neoklasik Solow (residu Solow). Model pertumbuhan endogen mempunyai kemiripan struktural dengan model neoklasik, namun sangat berbeda dalam hal asumsi yang mendasarinya dan kesimpulan yang ditarik darinya. Perbedaan teoristis yang paling signifikan berasal dari dikeluarkannya asumsi neoklasik tentang hasil marjinal yang semakin menurun atas investasi modal, memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat (increasing returns to scale) dalam produksi agregat, dan sering kali berfokus pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian investasi modal. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antarnegara. Dan karena teknologi masih memainkan peran penting dalam modelmodel ini, tidak ada perlunya lagi untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Dalam membandingkan teori pertumbuhan (endogen) yang baru dengan teori neoklasik tradisional, sangat bermanfaat jika kita mengetahui bahwa banyak teori pertumbuhan endogen yang dapat dinyatakan oleh persamaan sederhana Y= AK, seperti yang terdapat dalam model Harrod-Domar. Dalam formulasi ini, A dianggap mewakili semua faktor yang mempengaruhi teknologi, dan K mencerminkan modal fisik dan sumber daya manusia. Namun dalam rumus ini tidak terdapat hasil yang semakin menurun atas modal; sehingga terdapat kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia dapat menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang melebihi keuntungan pribadi dalam jumlah yang cukup untuk membalikkan efek hasil semakin berkurang. Hasil akhirnya adalah pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan sebuah hasil yang ditabukan oleh teori pertumbuhan neoklasik tradisional. Sehingga meskipun teori pertumbuhan baru tersebut menekankan kembali pentingnya tabungan dan investasi modal manusia untuk mempercepat pertumbuhan, teori ini juga membawa beberapa implikasi pertumbuhan yang sama sekali berlawanan dengan teori tradisional. Pertama, tidak terdapat kekuatan yang mengarahkan terciptanya persamaan tingkat pertumbuhan antar negara yang perekonomiannya tertutup; tingkat pertumbuhan nasional tetap konstan dan berbeda antar negara tergantung pada tingkat pertumbuhan nasional dan tingkat teknologinya. Selanjutnya, tidak terdapat kecenderungan bahwa level pandapatan perkapita di negara-negara kaya meskipun tingkat pertumbuhan tabungan dan tingkat pertumbuhan populasinya serupa. Konsekuensi serius dari fakta ini adalah bahwa resesi yang berlangsung sementara atau lama disebuah negara dapat menyebabkan semakin melebarnya jurang pendapatan yang permanent di dalam negara tersebut dan dengan negara-negara lain yang lebih kaya. Model Romer Model Romer dimulai dengan mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang konstan, sehingga model tersebut konstan dengan asumsi persaingan sempurna; dan sampai titik ini asumsinya serupa dengan Solow, namun berbeda dengan Solow, Romer mengasumsikan bahwa cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian, K , secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri, sehingga terdapat kemungkinan skala hasil semakin meningkat (incerasiung return to scale – IRS) pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Cadangan modal setiap perusahan meliputi pengetahuan yang dimilikinya juga, bagian pengetahuan yang terdapat dalam cadangan modal setiap perusahaan secara esensial adalah sebuah barang publik (public good), seperti A didalam model Solow, yang merembes ke perusahaan lain di dalam perekonomian secara instan. Hasilnya, model ini memperlakukan belajar dari pengalaman (learning by doing) sebagai “belajar dari investasi (learning by investing)”. Model Romer dapat dianggap – endogenisasi – sebagai cara untuk memahami alasan mengapa pertumbuhan tergantung kepada tingkat investasi. Dalam model yang disederhanakan ini, berangkat dari sektor rumah tangga, yang merupakan fitur penting dari model aslinya, untuk memusatkan perhatian pada berbagai masalah yang menyangkut industrialisasi. Rumusnya dinyatakan sebagai berikut : Yi = AK αi L 1i −α K β ( 44 ) Diasumsikan kesimetrisan antarindustri untuk menyederhanakan masalah, sehingga setiap industri akan menggunakan modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama. Kemudian, diagregasi fungsi produksi : Y = AK α + β L 1−α ( 45 ) Untuk memperjelas model pertumbuhan endogen, di asumsikan bahwa A bersifat konstan dan bukan meningkat sepanjang waktu; sehingga pada saat ini diasumsikan bahwa tidak terdapat kemajuan teknologi. Dengan bantuan sedikit kalkulus, akan diperhatikan bahwa hasil tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di dalam perekonomian akan menjadi : g – n = β / [1 - α + β] ( 46 ) Di mana g adalah tingkat pertumbuhan output dan n adalah tingkat pertumbuhan populasi. Tanpa adanya imbasan, seperti dalam model Solow dengan skala hasil konstan, β = 0, maka pertumbuhan per kapita akan menjadi nol (tanpa kemajuan teknologi). Namun Romer mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan ketiga faktor, termasuk eksternalitas modal, β > 0; sehingga g – n > 0, dan Y / L tumbuh. D. Penelitian Terdahulu 1. Ida Bagus Putu Purbadharmaja ( 2002 ) Ida Bagus Putu Purbadharmaja meneliti Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data deret waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2002. variabel yang berpengaruh nyata terhadap PDRB adalah variabel pengeluaran dengan nilai t statistik sebesar 19.79 (signifikan), sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi PDRB secara nyata adalah variabel investasi dengan nilai t statistik sebesar 0.75 (nonsignifikan). Variabel investasi tidak signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh investasi yang dilakukan di Bali tidak efisien. 2. Jamzani Sodik & Didi Nuryadin ( 2005 ) Jamzani Sodik & Didi Nuryadin meneliti Investasi dan pertumbuhan Ekonomi Regional ( Studi kasus pada 26 Provinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi ) bahwa variabel penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun investasi (baik PMA maupun PMDN) sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. 3. Jamzani Sodik ( 2003 ) Jamzani Sodik meneliti Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional, selama periode penelitian ditemukan bahwa Variabel Investasi Swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi Regional, sedangkan Pengeluaran Pemerintah ( baik pengeluaran Pembangunan maupun Pengeluaran Rutin ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. Ini mengindikasikan bahwa Pengeluaran Pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerahuntuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan sendiri. Variabel Keterbukaan Ekonomi ( ekspor netto ) memiliki hubungan yang konsisten dengan teori ( baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah ) tetapi tidak signifikan. Sekaligus menunjukkan bahwa keterbukaan perekonomian suatu daerah belum berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negative untuk tahun1993-2003 dan tahun 1998- 2000 ( sebelum era otonomi ) ini menunjukkan bahwa daerah belum bias menyerapangkatan kerja tang ada di daerah tersebut sehingga bias meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sedangkan untuk periode 20012003 ( setelah otonomi daerah ) variable ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 4. Waloejo Wirjo Wijono (2005) Waloejo Wirjo Wijono meneliti Mengungkap Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir yang bersifat diskriptif, dengan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor industry pengolahan ( yang bersifat padat modal serta tehnologi tinggi ) menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh sector keuangan dan jasa serta sector pertanian. Begitu pula belanja konsumsi swasta menyumbang terbesar dari sisi pengeluaran dari pada pembetukan modal tetap domestic , dengan kecenderungan semakin merurunnya foreigh direct investment . Pertumbuhan ekonomi ternyata juga banyak didorong oleh factor eksternal yang terlihat pada tingginya kandungan impor yang digunakan olek sector industry dalam proses produksinya. 5. Makmun dan Akhmad Yasin ( 2002 ) Makmun dan Akhmad Yasin meneliti Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. Dalam Pembahasan ini, data yang dipakai adalah data time series periode 1980-2002 yang merupakan data sekunder dari BPS. Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh investasi dalam sektor pertanian dan krisis ekonomi pada pertengahan 1997 terhadap perkembangan PDB signifikan, sedangkan pengaruh tenaga kerja tidak sinifikan. Dilihat dari jenis investasinya, pengaruh PMDN signifikan, sedangkan untuk PMA tidak signifikan. Model juga menjelaskan bahwa variasi perubahan PDB sektor pertanian 91,70 persen (untuk model pertama) dan 91,20 persen (untuk model kedua) dipengaruhi variabel investasi, tenaga kerja dan krisis ekonomi. Tidak signifikannya pengaruh tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian bahkan koefisien ini bertanda negatif menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini sejalan pula dengan tingkat efisiensi (return on scale) menurun, karena β1+β2+β3+β4 < 1. 6. Victor Siagian ( 2004) Victor Siagian meneliti Analisa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Filipina periode :1994-2003, variable pengukuran yang diteliti adalah meliputi;Tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variable dependen, sedang variaberl independennya adalah; ekspor barang, impor barang, realisasi investasi swasta asing, investasi swasta domestic yang disetujui, tabungan pemerintah dan swasta, aliran netto utang luar negri pemerintah dan swasta, utang pemerinyah pusat pada pinjaman dalam negri, dan pengeluaran pemerintah. Metode analisis dengan menggunakan Error Correction Model ( ECM ), dengan hasil penelitian sebagai berikut ; 1. Dalam jangka panjang, kontribusi positif dan signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina diberikan oleh variabel: ekspor, impor, investasi dalam negri, tabungan, dan pengeluaran pemerintah. 2. kontribusi positif dan tidak signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina diberikan oleh variable investasi asing. 3. Variabel utang luar negri dan utang dalam negri berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina namun tidak signifikan. E Kerangka Pemikiran Berdasarkan dari landasan teori yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bekerja dengan kerangka pemikiran bahwa Investasi dan Tenaga Kerja secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto ). Gambar 2.15 ( PDRB Gambar Kerangka Pemikiran PDRB Investasi PDRB Tenaga Kerja Keterangan : Untuk memberikan arahan yang jelas dalam memecahkan masalah, perlu disusun suatu kerangka pemikiran sebagai dasar yang dipakai dalam menganalisa data. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut : Investasi merupakan salah satu komponen faktor produksi sehingga perubahan jumlah investasi akan mempengaruhi tingkat produksi. Pengadaan peralatan dan bahan baku akan meningkatkan stok modal secara fisik (yaitu nilai riil “netto” atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal ini jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang. Kegiatan investasi bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal dimana akumulasi modal akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada. (Todaro, 2000 ) Perubahan kuantitas tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat produksi karena tenaga kerja merupakan salah satu komponen dari faktor produksi. Bila kuantitas tenaga kerja meningkat, maka hasil produksi (PDB) akan meningkat pula. Dari kerangka pemikiran tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa investasi dan Tenaga Kerja ternyata dapat mempengaruhi PDRB baik secara individual ataupun secara bersama-sama. F. Hipotesis Adapun pengertian dari hipotesis adalah suatu pernyataan yang harus diuji kebenarannya (Djawanto, PS dan Pangestu Subagyo, 1998). Maka hipotesis masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisaan data. Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut bahwa: 1. Investasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah 2. Tenaga Kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. 3. Investasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Jawa Tengah tahun 1986 – 2008. Pokok-pokok pikiran yang ada didasarkan pada teori,. penggalian data, dan referensi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dilakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari laporan, dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dikeluarkan oleh instansi atau badan-badan tertentu. Data sekunder tersebut diperoleh dari BPS, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah; Investasi, Tenaga Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data berskala 23 yaitu tahun 1986 – 2008. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. B. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan analisis mengenai Pengaruh Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah, selama tahun 1986 – 2008. Penelitian ini sengaja mengambil obyek di Provinsi Jawa Tengah, karena Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang mempunyai laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 ( Statistik Indonesia ). C. Definisi Operasional Variabel Definisi operasional adalah pernyataan tentang definisi, batasan, pengertian dan pengambilan variabel dalam penelitian. 1.Variabel Dependen Variabel terikat (Y) disini adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Jawa Tengah. yaitu total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah Provinsi Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) di sini mewakili pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000 dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Data PDRB diambil dari Jawa Tengah Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Jawa Tengah terbitan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. ( beberapa edisi). 2. Variabel Independen, dibedakan menjadi 2 variabel : a). Investasi Variabel ini diukur dengan tingkat pembentukan modal tetap bruto yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan perhitungan dasar harga konstan, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000 dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Data investasi diambil dari Jawa Tengah Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Jawa Tengah terbitan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. ( beberapa edisi). b). Tenaga Kerja Variabel ini diukur dengan jumlah tenaga kerja usia 10 tahun. sampai dengan 65 tahun yang ikut memproduksi barang dan jasa (sudah bekerja) yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan dalam jiwa. Data Tenaga Kerja diambil dari Jawa Tengah Dalam Angka terbitan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. ( beberapa edisi) D. Teknik Analisis Data Alat analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan alat yang disebut dengan regresi, yaitu suatu model yang menyatakan suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam persamaan matematik. Karena pada penelitian ini variabel independen berjumlah lebih dari satu maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengertian linier dalam hal ini adalah bila penyajian variabel independen dan parameternya hanya satu indeks dan tidak dikalikan atau dibagi dengan variabel atau parameter lain Fungsi regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Ln Y = β1 + β2 Ln X1 + β3 Ln X2 + e1 (48) Dimana : Y = PDRB X1 = Investasi X2 = Tenaga Kerja Β1 = Konstanta β2, β3 = Koefisiensi regresi x1 dan x2 e1 = Variabel pengganggu, wakil semua pengaruh yang timbul dari variabel terikat akibat kesalahan peneliti 1. Uji Statistik Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependen, digunakan uji t test. Uji t test akan dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diambil. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : Ho : β1 = O : tidak pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual Ha : β1 ≠ 0 : ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual a. Uji t Yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (x1, x2 dan x3) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial atau individu. Menurut Gujarati (1995) Dengan langkah : 1). t hitung = β (49) SE (β ) Dimana : β = Nilai masing-masing koefisien regresi SE (β) = Standar error untuk masing-masing koefisien regresi 2). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (n-k-1), karena pengujian dua sisi maka pada penentu t tabel menggunakan a 2 = 0,025 Dimana : 3). n = Jumlah pengamatan k = jumlah variabel Ho : β1, β2, = 0 (secara parsial, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat) Ha : β1, β2, ≠ 0 (paling tidak salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat) 4). Uji t dipergunakan untuk mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut : a). Jika t hit >t tabel, atau t hit >-t tabel, maka Ho diterima dan ditolak. Berarti signifikasi atau variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependent. b). Jika t hit <t tabel atau t hit < -t tabel, maka Ho diterima dan ditolak. Berarti signifikasi atau variabel independ yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel dependent dengan = 0,05 Gambar 3.1 Daerah terima dan daerah tolak uji t Ho ditolak Ho diterima -1( a2 ; n –k) Ho ditolak 1( a2 ; n – k) b. Uji F Yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (x1, x2 dan x3) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama. Menurut Gujarati (1995) Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1). F hitung : F= R 2 / (K − 1) (1 − R )2 / (n − K − 1) Dimana : R2 : Koefisien determinan K : Jumlah variabel independent N : Jumlah data atau sampel (50) 2). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) pembilang (k-1) dan penyebut (n-k). Df = k – 1 ; n – k 3). Ho : β1, β2, = 0 (tidak ada pengaruh secara bersama-sama, antara variabel terikat dengan variabel bebas) Ha : β1, β2, ≠ 0 (ada pengaruh secara bersama-sama, antara variabel terikat dengan variabel bebas) 4). Uji F ini dipergunakan untuk mempengaruhi apakah Ho diterima dan ditolak dengan ketentuan sebagai berikut : a). Apabila Fhit > Ftabel, maka Ho ditolak dan diterima berarti signifikansi/variabel independent secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependent b). Apabila Fhit < Ftabel, maka Ho, ditolak dan diterima berarti tidak signifikan variabel independent secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Gambar 3.2. Daerah terima dan daerah tolak uji F Ho diterima Ho ditolak F( α ; k – 1 : n – k) c. Koefisien Determinasi (R2) Untuk mengukur kebaikan dari model regresi maka diperlukan perhitungan determinasi (R2), yaitu angka untuk persentase total variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan variabel independent dalam model. 2. Uji Asumsi Klasik a. Multikolinaritas Variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain, suatu variabel bebas merupakan tugas linier dari variabel bebas lainnya. Cara paling mudah untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas aalah dengan metode Auxillary Regresi, yaitu dengan melihat nilai R2 dan nilai r2. Apabila dari hasil pengujian statistik diperoleh r2 < R2 berarti tidak ada multikolinieritas, sedangkan jika b. r2 > R2 berarti terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar tapi masih tetap tidak bias dan konsisten Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 1) Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residualnya 2) Nilai residual dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut : e1 = α1X1 + α2X2 (51) Hasil regresi tahap dua dilakukan uji t Jika signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas, sedangkan jika tidak signifikasi maka tidak terjadi masalah heteroskedentisitas dalam model tersebut. a. Autokolerasi Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan percobaan d(darbin-Watson test). 1 − ∑ e1e1−1 D= 2 ∑ e1 (52) Gambar 3.3. Autokorelasi Ragu-ragu Ragu-ragu Autokorelasi Positif Autokorelasi Negatif Tidak ada autokorelasi 0 dL dU 2 4 – dU 4 – dL 4 Dengan Ho : tidak ada serial autokorelasi antara dua ujungnya baik yang positif maupun negatif, sehingga jika : 0 < d < dL : menolak Ho 4-dL < d < 4 : menolak Ho dU < d < 4 – dU : menerima Ho dL < d < dU atau 4 – dU < d < 4-dL: tidak meyakinkan BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Wilayah 1. Keadaan Geografis a. Letak Geografis Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya antara 5o40’ dan 8o30’ LS dan antara 108o30’ dan 111o30’ BT (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Batas-batas wilayah Jawa Tengah adalah : Sebelah utara : Laut Jawa Sebelah Selatan : DI Yogyakarta dan Samudra Indonesia Sebelah Barat Provinsi Jawa Barat : Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 35 Daerah Provinsi dan Kota yaitu 6 Daerah Kota dan 29 Daerah Kabupaten dengan 352 Kecamatan, yang meliputi 8.530 Desa dan 606 Kelurahan. b. Sumber Daya Alam 1). Iklim dam Suhu Udara Provinsi Jawa Tengah memiliki dua musim yaitu musin kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu rata-rata Jawa Tengah tahun 1999 berkisar antara 18oC sampai dengan 28oC. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi, sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 74 % sampai 95%. Jumlah curah hujan dalam satu tahun sebesar 200 mm, sehingga Jawa Tengah termasuk beriklim basah. Jumlah curah hujan rata-rata bulanan di Bagian Dataran Rendah Utara minimum 3 mm dan maksimum 663 mm, sedangkan di Bagian Dataran Rendah Selatan minimun 8 mm dan maksium 207 mm. 2). Keadaan Alam Provinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Daerah pegunungan dan dataran yang membujur sejajar dengan panjang Pulau Jawa, daerah dataran rendah yang hampir tersebar diseluruh Jawa Tengah serta daerah pantai yaitu pantai utara dan selatan. Ditinjau dari sisi topografinya Jawa Tengah mempunyai relief yang beragam meliputi daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Diukur dari permukaan laut, Jawa Tengah dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian, yaitu : 0 – 9 meter meliputi wilayah seluas 53.3 persen 100 – 499 meter meliputi wilayah seluas 27.4 persen 500 – 999 meter meliputi wilayah seluas 14.7 persen 1000 meter keatas meliputi wilayah seluas 4.6 persen Dari kemiringannya Jawa Tengah juga dibedakan menjadi empat golongan derajat kemiringan, yaitu : 0o – 2o meliputi wilayah seluas 41,3 persen 3o – 15o meliputi wilayah seluas 27,7 persen 16o – 39o meliputi wilayah seluas 21,2 persen 4o keatas meliputi wilayah seluas 4,8 persen Luas lahan yang terdapat di Jawa Tengah 64 persen dapat dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan 21,1 persen luas lahan hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan khusus. 3). Hutan Kelestarian hutan sangat penting artinya bagi kehidupan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari hutan antara lain sebagai pencegah bahaya banjir, pencegah polusi, habitat flora dan fauna, selain itu dapat diambil hasil hutannya dan secara umum adalah sebagai penyeimbang lingkungan. Menurut Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah luas di Jawa Tengah adalah 646.831,93 ha atau kurang lebih 28,80 persen dari luas wilayah Jawa Tengah, dimana 41.739,12 ha berfungsi sebagai hutan lindung 604.255,69 ha sebagai hutan produksi dan 867,12 ha sebagai hutan suaka alam dan wisata. 4). Gunung Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak dan empat diantaranya masih aktif, artinya gunung tersebut sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava atau gas beracun. Gunung-gunung yang masih aktif tersebut adalah : Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gunung Slamet yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes dan Tegal Gunung Sindoro yang terletak di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Pegunungan Dieng yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pekalongan. c. Luas Wilayah Luas daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.547 km2 atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 2.138,51 Km2, dan yang terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 18,12 Km2. 2. Keadaan Penduduk Penduduk memiliki fungsi ganda di dalam perekonomian. Dalam konteks pasar, penduduk berada di sisi permintaan sekaligus di sisi penawaran. Pada sisi permintaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang-barang dan jasa. Sedangkan di sisi penawaran penduduk adalah produsen, misalnya sebagai pengusaha atau tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap keberadaan penduduk terpecah menjadi dua yaitu penduduk pemacu pembangunan. Namun demikian, apakah penduduk merupakan pemacu atau penghambat pembangunan, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar/kecil jumlahnya, akan tetapi tergantung pada kapasitas penduduk tersebut, baik selaku konsumen ataupun produsen (Dumairy, 1997 : 68). Tabel 4.1. Jumlah, Kepadatan dan LPP Jawa Tengah Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2008 Keterangan 1980 1990 2000 2008 Jumlah (juta jiwa) 25,37 28,52 30,78 32.62 Laki-laki (juta jiwa) 12,47 14,08 15,25 16.19 Persentase (laki-laki) 49,15 49,37 49,55 49,63 Perempuan (juta jiwa) 12,9 14,44 15,52 16.43 Persentase (perempuan) 50,85 50,63 49,63 50,37 10 tahun ke atas(juta jiwa) 23,46 21,87 25,12 27.10 Berlanjut ke halaman 72 …………Lanjutan Tabel 4.1 Persentase (10 tahun ke atas) 10 tahun ke bawah (juta jiwa) Persentase (10 tahun ke bawah) Kepadatan (Jiwa per km2) Pertumbuhan(persen) 92,47 76,68 81,61 83.07 1,91 6,65 5,66 5,52 7,53 23,32 18,39 16.93 745 834 918,98 1002.53 1,18 0,75 1,24 0.55 Penduduk Pulau Jawa 91,27 107,53 121,20 (juta jiwa) Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi) 132.86 Dari Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk dalam jumlah yang besar. Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan Jawa Tengah Dalam Angka 2009 adalah sebesar 32.626.400 jiwa. Jumlah ini setara dengan 25 persen penduduk Pulau Jawa atau 15 persen jumlah penduduk Indonesia sehingga Jawa Tengah menempati urutan ketiga Provinsi yang memiliki penduduk terbesar dari seluruh Provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat besar bila dibandingkan pada tahun 2000 dimana penduduk Jawa Tengah adalah 30,78 juta jiwa dan pada tahun 2008 berjumlah 32.62 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 0.55 persen dimana pada tahun 2007 penduduk Jawa Tengah berjumlah 32.380.3000 jiwa. Angka pertumbuhan ini relatif lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2007 yang besarnya 0.52 persen. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki, dimana di tahun 2008 persentase jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 50,37 persen sedangkan persentase jumlah penduduk laki-laki adalah 49,63 persen. Sedangkan pada tahun 2000 penduduk Jawa Tengah menunjukkan persentase penduduk perempuan adalah sebesar 50,37 persen dan persentase penduduk laki-laki adalah 49,63 persen. Pada tahun 1990 proporsi penduduk perempuan sebesar 50,63 persen dan proporsi penduduk laki-laki adalah 49,37 persen. Selain memiliki masalah tentang besarnya jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi masalah sebaran penduduk yang tidak merata. Ketidakmerataan jumlah penduduk antar wilayah menimbulkan masalah urbanisasi. Urbanisasi dalam jumlah besar akan menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi, yang antara lain menyangkut penyediaan lapangan kerja, permukiman, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dimana 15 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Pada tahun 1980 kepadatan penduduk tercatat 745 jiwa per km2, tahun 1990 nilainya meningkat menjadi 834 jiwa per km2 dan pada tahun 2000 tercatat rata-rata sebesar 918 jiwa setiap kilometer persegi dan pada tahun 2008 tercatat rata-rata sebesar 1002 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di wilayah kota secara umum lebih tinggi dibandingkan di wilayah Provinsi (lihat tabel 4.2), wilayah terpadat terdapat di wilayah Kota Surakarta yaitu sekitar 11.876 orang setiap km2 dengan jumlah penduduk sebesar 522.935 jiwa atau 1,6 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Sedangkan wilayah dengan angka kepadatan terkecil di Kabupaten Blora yaitu sekitar 465 orang setiap km2 dengan jumlah penduduk sebesar 835.160 jiwa atau 2,6 persen dari jumlah Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah di Kabupaten Cilacap yaitu 0.22 persen , angka pertumbuhan penduduk terbesar di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang yaitu sebesar 1.84 persen. Tebel 4.2. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan LPP Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten / Kota Jumlah (jiwa) Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Jawa Tengah Klaten Sukoharjo 1626795 1503262 828125 869777 1215801 722293 757746 1170894 938469 1133012 826699 Pertumbuhan (%) 0.22 0.49 0.76 0.65 0.59 0.40 0.44 0.83 0.62 0.37 0.86 Pertambahan Penduduk 3619 7281 6255 5629 7085 2897 3299 9616 5771 4160 7078 Kepadatan 760 1132 1064 813 947 697 769 1078 924 1728 1171 Berlanjut ke halaman 88 …Lanjutan Tabel 4.2 Wonogiri Karanganyar Sragen 982730 812423 860509 0.27 0.86 0.31 2598 6961 2665 539 1052 909 Grobongan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanbgung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Selatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal 1336322 835160 575640 1171605 786269 1090839 1034286 911223 707707 952011 682561 851700 1375240 1415625 1788687 134615 522935 178451 1511236 275241 240502 0.75 0.39 0.48 0.34 1.48 1.60 0.87 1.20 0.98 1.48 0.54 0.89 1.20 0.38 0.72 1.84 1.04 2.15 1.52 0.69 0.27 9908 3251 2761 3984 11431 17208 8898 10803 6862 13896 3652 7472 16288 5335 12748 2438 5378 3752 22591 1899 642 676 465 567 785 1849 1086 1152 962 813 949 865 1018 1359 1609 1079 7429 11876 3369 4044 6121 6973 Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2009 diolah. 3. Kondisi Perekonomian Data mengenai PDRB dan Investasi yang diwujudkan dalam Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. serta data Tenaga Kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Seluruh nilai PDRB dan Investasi, telah dideflasikan dengan indeks harga konstan tahun dasar tahun 2000. a. Perkembangan PDRB Nilai PDRB Jawa Tengah selama periode tahun 1986 sampai dengan 2008 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.27 persen. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2000 yaitu sebesar 19.13 persen dari Rp. 96278664 juta di tahun 1999 menjadi Rp. 114701304 juta. Krisis moneter yang dimulai pada pertengahan 1997 mengakibatkan kondisi perekonomian Jawa Tengah mengalami saat paling buruk sepanjang satu dasa warsa terakhir. PDRB mengalami laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar 11,74 persen dari Rp. 105407654 juta ditahun 1997 menjadi Rp. 93030052 juta di tahun 1998. Pada tahun 1999 perekonomian sedikit mengalami perbaikan yang ditandai dari nilai PDRB yang tumbuh 3,5 persen dari Rp. 98030052 juta di tahun 1998 menjadi Rp. . 96278664 juta. Tabel 4.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1986-2008 ( Dalam Jutaan Rupiah ) NO TAHUN 1 2 1 1986 2 1987 3 1988 4 1989 5 1990 6 1991 7 1992 8 1993 9 BERDASARKAN BERDASARKAN HARGA DASAR HARGA TAHUN 1983 TAHUN 1993 TAHUN 2000 BERLAKU 3 4 5 7 PERTUM BUHAN PDRB 9 21.686.498,75 53.000.962,36 11.492.261,66 183.156.327,26 447.626.964,66 13.593.745,27 221.691.173,60 541.804.635,50 16.422.805,51 156.705.199,80 382.981.434,40 18.692.151,22 194.559.074,90 475.494.837,92 21.689.283,14 257.252.159,61 628.714.306,96 25.980.440,64 226.927.465,33 554.601.929,53 30.200.680,97 33.978.909,16 83.043.136,96 33.978.909,16 1994 36.145.114,48 88.337.258,80 39.303.565,03 10 1995 39.013.952,64 95.348.588,06 46.586.032,91 18,53 11 1996 41.862.203,72 102.309.603,31 52.505.360,63 12,71 12 1997 43.129.838,90 105.407.654,55 60.296.426,87 14,84 9.459.721,30 10.016.163,95 10.652.347,73 11.340.444,99 12.134.025,95 13.002.587,13 13.969.999,53 14.821.710,71 2,2925093 18,29 20,81 13,82 16,03 19,78 16,24 12,51 15,67 Berlanjut ke halaman 90 ………Lanjutan Tabel 4.3 13 1998 38.065.273,35 93.030.052,65 84.610.222,51 14 1999 39.394.513,74 96.278.664,64 101.509.193,76 19,97 15 2000 46.932.538,43 114.701.304,81 114.701.304,81 13,00 16 2001 118.816.400,29 133.227.558,11 16,15 17 2002 123.038.541,13 151.968.825,74 14,07 18 2003 129.166.462,45 171.881.877,04 13,10 19 2004 135.789.872,31 193.435.263,05 12,54 20 2005 145.051.213,88 234.435.323,30 21,20 21 2006 150.682.654,75 281.996.709,11 20,29 40,32 22 2007 151.362.625,34 312.428.807,09 10,79 23 2008 167.790.369,84 362.938.708,25 16,17 Sumber: Jawa Tengah dalam Angka dan PDRB Jawa Tengah diolah ( beberapa edisi ) b. Perkembangan Investasi Nilai investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 hampir selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan ratarata pertumbuhan sebesar 8,08 persen. Pertumbuhan investasi tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 16.20 persen dari Rp. 55,161,025.48 juta menjadi Rp. 67,171,292.57 juta. Hal ini menunjukkan terciptanya kondisi yang mendukung bagi kegiatan investasi di Provinsi Jawa Tengah pada saat itu. Dalan beberapa kurun waktu, yaitu antara tahun 1997 s/d 1999, 2001, dan 2005 nilai investasi mengalami penurunan , hal ini disebabkan oleh situasi politik yang kurang kondusif. Tabel 4.4 Pembetukan Modal Tetap Provinsi Jawa Tengan Tahun 1986-2008 ( Dalam Jutaan Rupiah ) NO TAHUN TAHUN 1983 3 BERDASARKAN INV BERDASARKAN HASIL HARGA DASAR PERT. HARGA DEFLATOR (%) BERLAKU 6 7 TAHUN TAHUN 1993 2000 4 5 1 2 1 1986 1,803,313.73 2 1987 1,724,794.81 (0.02) 2,555,276.66 3 1988 1,983,300.68 9.48 3,177,939.16 2,287,717.03 8 10,550,682.52 10,548,862.69 11,549,122.23 4 1989 2,157,027.31 9.89 3,733,459.08 5 1990 2,418,138.98 10.61 4,478,539.18 6 1991 2,768,823.96 10.22 5,517,888.00 7 1992 3,068,466.85 8.74 6,491,537.19 8 1993 8.94 7,499,519.12 9 1994 12.22 9,151,738.67 10 1995 3.81 10,432,268.67 11 1996 9.15 11,960,812.49 12 1997 (5.75) 12,565,527.25 13 1998 (8.80) 18,221,031.66 14 1999 (13.2) 18,326,349.73 15 2000 11.86 19,443,890.34 16 2001 (1.31) 21,515,843.51 17 2002 2.92 24,392,021.63 18 2003 5.30 27,672,216.45 19 2004 10.06 32,603,177.99 20 2005 (0.59) 36,772,031.93 21 2006 13.97 48,525,638.48 22 2007 3.06 55,161,025.48 23 2008 16.20 67,171,292.57 7,499,519.12 8,646,098.98 9,202,415.49 10,008,798.84 9,276,563.74 7,795,292.13 6,189,368.22 19,443,890.34 17,210,016.59 17,846,043.00 19,152,824.31 21,731,823.21 23,702,943.17 26,759,732.63 28,276,562.99 30,169,301.77 12,690,759.68 14,037,879.59 15,472,537.89 16,824,130.15 18,328,534.05 20,569,113.94 21,351,938.04 23,306,305.61 21,966,521.47 20,034,264.00 17,382,036.19 19,443,890.34 19,188,485.56 19,748,515.80 20,795,225.00 22,887,147.39 22,751,809.72 25,929,281.42 26,723,904.59 31,053,992.77 Sumber: Jawa Tengah dalam Angka dan PDRB Jawa Tengah ( beberapa edisi ) diolah c. Perkembangan Tenaga Kerja Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami fluktuasi tiap tahunnya namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh kenaiakan jumlah penduduk Jawa Tengah. Jumlah tenaga kerja cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 0.86 persen. Pada tahun 2008 tenaga kerja Jawa Tengah mencapai angka 15463658 orang atau tumbuh sekitar -5.15 persen dari tahun 2007 yang berjumlah 16304058 orang. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebesar 7.19 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya. Kondisi ini sangat mendukung bagi tercapainya tingkat Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah yang tinggi. Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 1986-2008 No Tahun Jumlah Tenaga kerja Pertumbuhan 1 2 3 4 1 1986 2 1987 3 1988 4 1989 5 1990 6 1991 7 1992 8 1993 12,837,119 12,866,665 0.23 12,504,593 -2.81 13,106,608 4.81 13,424,784 2.43 13,144,046 -2.09 14,022,669 6.68 13,871,820 -1.08 Berlanjut ke halaman 93 ………Lanjutan Tabel 4.5 9 1994 10 1995 11 1996 12 1997 13 1998 14 1999 15 2000 16 2001 17 2002 18 2003 19 2004 20 2005 21 2006 22 2007 13,850,929 -0.15 14,062,056 1.52 13,841,255 -1.57 13,805,930 -0.26 14,117,828 2.26 14,566,119 3.18 14,491,222 -0.51 15,066,542 3.97 15,154,856 0.59 15,124,082 -0.20 14,930,097 -1.28 15,655,303 4.86 15,210,931 -2.84 16,304,058 7.19 23 2008 -5.15 15,463,658 Sumber: Jawa Tengah dalam Angka ( beberapa edisi ) diolah. B. Analisis Data 1. Persamaan Regresi Log Linier Berganda Hasil Penelitian Perhitungan analisis regresi log linier berganda dilakukan dengan bantuan komputer Eviews 3.0. Adapun hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut : Tabel 4.6 Hasil Estimasi Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dependent Variable: Ln PDRB Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:00 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient C Ln INV Ln TK -34.31603 0.553125 2.638201 R-squared Adjusted Rsquared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.958381 0.954219 Mean dependent var S.D. dependent var 18.38898 0.340711 0.072900 0.106289 29.20088 1.608425 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -2.278337 -2.130229 230.2729 0.000000 Std. Error t-Statistic Prob. 5.315654 -6.455655 0.097651 5.664279 0.401262 6.574752 0.0000 0.0000 0.0000 Sumber : olah data Eviews 3.0 Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, hasil estimasi dengan menggunakan regresi Log Linier Berganda dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut: Ln PDRB = -34.31603+ 0.553125 Ln INV + 2.638201 Ln TK (53) 2. Uji Statistik a. Uji t ( Uji secara individu ) Uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi dari variabel independen secara individu yang bertujuan untuk melihat apakah variabel independen tersebut signifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika besarnya t hitung lebih besar dari pada t tabel ( t hitung > t tabel ) atau -t hitung lebih kecil dari pada t tabel ( -t hitung < t tabel ), maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara individu. 1). Variabel Investasi Koefisien regresi variabel investasi sebesar 0.553125 dengan nilai t 5.664279 yang lebih besar dari t tabel pada α = 0,05; α 2 hitung : 0,025 df : 20 yang bernilai 2,086. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai 0,0000 ( menunjukkan nilai yang sangat kecil) yang lebih kecil dari 0,05, maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel investasi di Provinsi Jawa Tengah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. 2). Variabel Tenaga Kerja Koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 2.638201 dengan nilai t 6.574752yang lebih besar dari t tabel pada α = 0,05; α 2 hitung : 0,025 df : 20 yang bernilai 2,086. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai 0,0000 ( menunjukkan nilai yang sangat kecil) yang lebih kecil dari 0,05, maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. b.Uji F Dari hasil pengolahan data pada table 4.6 diperoleh Fhitung = 230.2729 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 4.32. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (230.2729 > 4.32), maka Ho ditolak artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi investasi, dan Tenaga Kerja secara serentak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah sebagai berikut : 1) Ho : b = 0 (tidak ada pengaruh) Ha : b ≠ 0 (ada pengaruh) 2) α = 0,05 df pembilang : 1 df penyebut : 21 3) Perhitungan uji F nilai F tabel : 4.32 nilai F hitung : 230.2729 4) Daerah pengujian Gambar 4.1 Daerah terima dan daerah tolak uji F Ho ditolak Ho diterima 4.32 230.2729 Tingkat signifikansi dari nilai F statistic juga dapat dilihat dari probabilitas F statistiknya. Besarnya F Proob ( F statistik ) dalam model persamaan ini adalah 0,0000, maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi tersebut signifikan, bahwa sampai pada tingkat signifikansi 5 %. Ini berarti bahwa variabel investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah. c. Koefisien Determinasi (R2) Kemudian untuk mengetahui persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, maka digunakan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai adjusted R2 sebesar 0.958381; sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 95.84 % variasi dari variabel dependen dalam hal ini PDRB dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri investasi, dan Tenaga Kerja. Sedang 4.16 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 3. Pengujian Asumsi Klasik Model regresi yang digunakan akan menunjukkan hubungan yang representatif, apabila model regresi memenuhi asumsi dasar klasik regresi, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas uji autokorelasi. a. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat apakah ada hubungan diantara variabel yang menjelaskan. Cara paling mudah untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan metode Auxillary Regresi, yaitu dengan melihat nilai R2 dan nilai r2. Apabila dari hasil pengujian statistik diperoleh R2 > r2 berarti tidak ada multikolinieritas, sedangkan jika R2 < r2 berarti terjadi multikolinieritas. Selain itu juga menggunakan uji Klien. Berdasarkan uji Klien, maka untuk mendeteksi multikolinieritas pada beberapa variabel bebas, maka dilakukan auxillary regresi selama beberapa kali tergantung banyaknya variabel bebas tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut : Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas Keterkaitan antar variabel independen R2 Tanda r2 INV dgn TK 0.958381 > 0.701061 0.958381 > 0.701061 TK dgn INV Sumber: Hasil olah data Eviews 3.0 Keterangan Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa untuk semua korelasi antar variabel independent memiliki r2 yang lebih kecil daripada R2. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa semua variabel independent memberikan pengaruh bebas dari masalah multikolineritas. b. Heteroskedastisita Heteroskedastistitas terjadi bila variabel gangguan mempunyai varians yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar ( Modul Laboratorium Ekonomi Pembnangunan II ). Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 1).Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residualnya 2).Nilai residual dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut : Ln e2 = αo + α1 Ln INV+ α2 Ln TK (54) Dimana : α = Konstanta e2 = Residual INV = Investasi TK : Tenaga Kerja Meregres residual yang di kuadratkan dengan variable independen, dengan hasil sebagai berikut; Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas Dependent Variable: Ln e² Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:18 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 0.770687 1.526564 -0.754894 0.4499 0.1425 0.4591 C Ln INV Ln TK 79.34029 6.647721 -13.50767 102.9475 4.354697 17.89347 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.139626 0.053589 1.412147 39.88316 -38.96587 1.789792 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 31.04522 1.451576 3.649206 3.797314 1.622853 0.222266 Sumber: Hasil olah data Eviews 3.0 Hasil regresi tahap dua dilakukan uji t (dengan melihat probabilitasnya ) Investasi tidak signifikan pada tingkat α = 5 % Tenaga Kerja tidak signifikan pada tingkat α = 5 % Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada tingkat keyakinan 5 % semua koefisien regresi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model tersebut. Dengan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dapat disimpulkan : 1.Penaksir OLS tidak bias dan konsisten serta efisien baik dalam sampel besar maupun kecil 2.Varians minimum c. Uji Autokorelasi Pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai DurbinWatson yang diperoleh dari hasil regresi dengan batas bawah uji d (df), dan batas atas uji d (dU) dalam total statistik Durbin-Watson dan dengan (4-dL) dan (4-dU) (Damodar Gujarati, 1991 : 372). Sedangkan kriteria pengujian adalah sebagai berikut : Gambar 4.2 Grafik Uji Autokorelasi Ragu-ragu Ragu-ragu Autokorelasi positif Autokorelasi negatif Tidak ada korelasi 0 1,17 2,46 1,54 2,83 4 1.608425 Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai dL = 1,17, dU = 1,54, 4-dL = 2,83, 4-dU = 2,46 sedangkan DW = 1.608425 sehingga dU < d < (4-dU) maka menerima Ho berarti tidak ada autokorelasi. 4. Analisis Hasil Regresi Dari hasil estimasi dengan menggunakan regresi Ln Linier Berganda diperoleh datasebagai berikut: Ln PDRB = -34.31603+ 0.553125 Ln INV + 2.638201 Ln TK Model persamaan regresi di atas dapat di analisis sebagai berikut : a. Pengaruh Investasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dari hasil olah data diperoleh koefisien regresi variable investasi sebesar 0.553125 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variable investasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar satu persen maka akan menyebabkan kenaikan variable PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 0.55 persen dengan asumsi variable lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi pada variable investasi di Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh pula pada besarnya perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil uji signifikansi terbukti perubahan yang terjadi dalam variabel investasi mempunyai pengaruh yang signifikan pada perubahan variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 0.05 atau 5 %. Jumlah investasi yang tinggi akan akan meningkatkan PDRB di Provinsi Jawa Tengah dengan pengaruh yang signifikan. b. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dari hasil olah data diperoleh koefisien regresi variable tenaga kerja sebesar 2.638201 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variable tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah sebesar satu persen maka akan menyebabkan kenaikan variable PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.64 persen dengan asumsi variable lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi pada variable tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh pula pada besarnya perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil uji signifikansi terbukti perubahan yang terjadi dalam variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan pada perubahan variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 0.05 atau 5 %. Jumlah tenaga kerja yang tinggi akan akan meningkatkan PDRB di Provinsi Jawa Tengah dengan pengaruh yang signifikan. 5. Uji Hipotesa (Teori) a. Koefisien variabel investasi bernilai positif sebesar 0.553125 artinya jika nilai investasi meningkat maka PDRB cenderung mengalami peningkatan sesuai dengan hipotesa. b. Koefisien variabel tenaga kerja bernilai positif sebesar 2.638201 artinya jika penerimaan daerah meningkat maka PDRB cenderung mengalami peningkatan sesuai dengan hipotesa. c. Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 230.2729 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 4.32. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (230.2729 > 4.32), maka Ho ditolak artinya variabel investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. artinya investasi dan tenaga kerja maka PDRB cenderung mengalami peningkatan sesuai dengan hipotesa. 6. Intepretasi ekonomi a. Nilai Konstanta. Nilai konstanta persamaan regresi adalah -34.31603 berarti apabila Investasi dan tenaga kerja bernilai 1 maka nilai Produk Domestik Regional Bruto akan meningkat sebesar antilog -34.31603 atau sebesar 1,2495E-15 b. Nilai elastisitas Investasi terhadap PDRB. Nilai elastisitas Investasi terhadap PDRB ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel Investasi yaitu sebesar 0.553125. Jadi apabila Investasi meningkat sebesar satu persen maka produk domestik regional bruto akan meningkat pula sebesar 0.553125 persen. ( tidak elastis ) c. Nilai elastisitas Tenaga Kerja terhadap PDRB. Nilai elastisitas tenaga kerja terhadap PDRB ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja yaitu sebsar 2.638201. Hal ini berarti apabila ada peningkatan input tenaga kerja sebesar satu persen maka nilai produk domestik regional bruto akan meningkat sebesar 2.638201 persen. ( Elastis ) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan perumusan masalah, hipotesis dan hasil analisis yang diperoleh, di mana kesemuannya telah di kemukankan pada bab-bab sebelumnya. Hasil analisis tentang pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dalam analisis terbukti bahwa Investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 5 % terhadap PDRB. 2. Tenaga Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dalam analisis terbukti bahwa Tenaga Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 5 % terhadap PDRB. 3. Investasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB Jawa Tengah. Dalam analisis terbukti bahwa Investasi dan Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB Jawa Tengah dengan tingkat signifikansi 5 %. B. Saran-saran 1. Agar PDRB meningkat perlu usaha untuk meningkatkan nilai investasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah menciptakan iklim yang kondusif ( misalnya dengan mempermudah prosedur perijinan ) bagi terlaksananya berbagai proyek investasi. Stabilitas ekonomi dan keamanan merupakan faktor penting yang menjamin para investor menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Selain itu diupayakan berbagai macam insentif dari pemerintah daerah, akan dapat menarik minat para investor baik dari dalam maupun dari luar daerah/negri. 2. Faktor Tenga Kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap PDRB. Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat elastisitas sebesar satu ( elastis ), untuk itu disarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pertumbuhan PDRB meningkat, perlu lebih banyak menggunakan tehnologi yang bersifat padat tenaga. DAFTAR PUSTAKA Al Gifari, 1990 “Makro Ekonomi”. Yogyakarta STIE YKPN. Arsyad, Lincoln 1999, ”Pengantar Perncanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah”. BPPE : Yogyakarta Badan Pusat Statistik,2008”Statistik Indonesia” Badan Pusat Statistik,Jakarta. Badan Pusat Statistik, ”Jawa Tengah dalam Angka” BPS Semarang beberapa edisi. Badan Pusat Statistik, ”Produk Domestik Regional Bruto” BPS Semarang beberapa edisi. Boediono,1992”Teori Pertumbuhan Ekonomi” Yogyakarta. BPFE. Boediono, Noegroho, 1992 ”Pengatar Statistik Ekonomi dan Perusahaan” UPP YKPN Yogyakarta Djarwanto, PS dan Subagyo Pangestu. 1998. “Statistik Induktif”. Yogyakarta. BPFE. Dumairy,1997 ” Perekonomian Indonesia” Erlangga, Jakarta Gujarati Damodar, 1995. “Ekonometrika Dasar”. Terjemahan Edisi III. Jakarta : Erlangga Ida Bagus Putu Purbadharmaja, 2002 , Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bali. Buletin Studi Ekonomi. Volume 11 Nomor 1 tahun 2006. Halaman 79-91 Jamzani Sodik, 2007 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional, http:/uii/.ac.id/ Jamzani Sodik & Didi Nuryadin, 2005 Investasi dan pertumbuhan Ekonomi Regional ( Studi kasus pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi ) http://ejournal.unud.ac.id/ Jhingan ML. 1999. “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”. Diterjemahkan oleh Guritno. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. Koutsoyiannis A.,1989”Modern Microeconomics” Second Edition English Language Book Society, Macmillan Made Antara, 1996. Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan serta Investasi Swasta terhadap Kinerja Perekonomian Bali; Suatu Simulasi Model Social Accounting Matrix http://ejournal.unud.ac.id/ Makmun dan Akhmad Yasin, 2002. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. Kajian Ekonomi dan keuangan, Vol. VII No. 3. September 2003. Hal. 57-83 Mankiw, N. Gregory,2000 ” Teori Makro Ekonomi” Jakarta, Erlangga. Mardiasmo, 2002. “Otonomi dan Manajemn Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Andi Offset. Payaman J. Simanjuntak, 1985 ”Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” Jakarta: Lembaga Penerbut Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pindyck, Robert S.,2008” Mikro Ekonomi ” Jakarta , PT. Indeks. Sukirno Sadono, 1999. “Makro Ekonomi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suparmoko, 1998. “Pengantar Ekonom Makro”. BPFE Yogyakarta Simanjutak, Payaman J. 2001. “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”. Edisi 2001. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sobri. 1987. “Makro Ekonomi”. Yogyakarta: BPFE-UII. Todaro, 2000. “Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. Victor Siagian, 2004. “Analisis Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Filipina periode 1994-2003” http://ejournal.unud.ac.id/ Waloejo Wirjo Wijono, 2005. Mengungkap Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir, Jurnal Manejemen dan Fiskal, Volume V Nomor 2, Jakarta. http://ejournal.iei.or.id/ , Volume V, Nomor 2, Jakarta. Lampiran 1 Hasil Estimasi Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dependent Variable: LNPDRB Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:00 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C LNINV LNTK -34.31603 0.553125 2.638201 5.315654 0.097651 0.401262 -6.455655 5.664279 6.574752 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lampiran 2 0.958381 0.954219 0.072900 0.106289 29.20088 1.608425 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 18.38898 0.340711 -2.278337 -2.130229 230.2729 0.000000 Uji Multikolinieritas Ln INV dengan Ln TK Dependent Variable: LNTK Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:07 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C LNINV 13.05877 0.485996 0.203764 0.029036 26.87010 7.017722 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lampiran 3 0.701061 0.686826 0.039645 0.033007 42.64959 1.063632 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 16.46887 0.070843 -3.534747 -3.436008 49.24842 0.000001 Uji Multikolinieritas Ln TK dengan Ln INV Dependent Variable: LNINV Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:09 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C Ln TK -39.92645 3.440548 8.074192 0.490266 -4.944947 7.017722 0.0001 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lampiran 4 0.701061 0.686826 0.162908 0.557317 10.14574 0.949509 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 16.73548 0.291104 -0.708325 -0.609586 49.24842 0.000001 Uji Heteroskedastisitas Dependent Variable: Ln e² Method: Least Squares Date: 04/27/10 Time: 06:18 Sample: 1986 2008 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C Ln INV Ln TK 79.34029 6.647721 -13.50767 102.9475 4.354697 17.89347 0.770687 1.526564 -0.754894 0.4499 0.1425 0.4591 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lampiran 5 0.139626 0.053589 1.412147 39.88316 -38.96587 1.789792 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 31.04522 1.451576 3.649206 3.797314 1.622853 0.222266 PDRB PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986 - 2008 ( Dalam Jutaan Rupiah ) NO TAHUN BERDASARKAN BERDASARKAN DE HARGA DASAR HARGA FLA TAHUN 1983 TAHUN 1993 TAHUN 2000 BERLAKU TOR 3 4 5 7 8 1 2 1 1986 9,459,721.30 21,686,498.75 53,000,962.36 11,492,261.66 0.22 2 1987 10,016,163.95 22,962,148.68 56,118,601.35 13,593,745.27 0.24 3 1988 10,652,347.73 24,420,605.89 59,683,014.25 16,422,805.51 0.28 4 1989 11,340,444.99 25,998,075.23 63,538,288.18 18,692,151.22 0.29 5 1990 12,134,025.95 27,817,366.94 67,984,566.60 21,689,283.14 0.32 6 1991 13,002,587.13 29,808,551.49 72,850,944.47 25,980,440.64 0.36 7 1992 13,969,999.53 32,026,353.39 78,271,166.33 30,200,680.97 0.39 8 1993 14,821,710.71 33,978,909.16 83,043,136.96 33,978,909.16 0.41 9 1994 36,145,114.48 88,337,258.80 39,303,565.03 0.44 10 1995 39,013,952.64 95,348,588.06 46,586,032.91 0.49 11 1996 41,862,203.72 102,309,603.31 52,505,360.63 0.51 12 1997 43,129,838.90 105,407,654.55 60,296,426.87 0.57 13 1998 38,065,273.35 93,030,052.65 84,610,222.51 0.91 14 1999 39,394,513.74 96,278,664.64 101,509,193.76 1.05 15 2000 46,932,538.43 114,701,304.81 114,701,304.81 1.00 16 2001 118,816,400.29 133,227,558.11 1.12 17 2002 123,038,541.13 151,968,825.74 1.24 18 2003 129,166,462.45 171,881,877.04 1.33 19 2004 135,789,872.31 193,435,263.05 1.42 20 2005 145,051,213.88 234,435,323.30 1.62 21 2006 150,682,654.75 281,996,709.11 1.87 22 2007 151,362,625.34 312,428,807.09 2.06 23 2008 167,790,369.84 362,938,708.25 2.16 Lampiran 6 PEMBENTUKAN MODAL TETAP PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986 - 2008 ( Dalam Jutaan Rupiah ) NO TAHUN BERDASARKAN BERDASARKAN HASIL HARGA DASAR HARGA DEFLATOR TAHUN 1983 TAHUN 1993 TAHUN 2000 BERLAKU 3 4 5 7 1 2 1 1986 1,803,313.73 2,287,717.03 10,550,682.52 2 1987 1,724,794.81 2,555,276.66 10,548,862.69 3 1988 1,983,300.68 3,177,939.16 11,549,122.23 4 1989 2,157,027.31 3,733,459.08 12,690,759.68 5 1990 2,418,138.98 4,478,539.18 14,037,879.59 6 1991 2,768,823.96 5,517,888.00 15,472,537.89 7 1992 3,068,466.85 6,491,537.19 16,824,130.15 8 1993 7,499,519.12 7,499,519.12 18,328,534.05 9 1994 8,646,098.98 9,151,738.67 20,569,113.94 10 1995 9,202,415.49 10,432,268.67 21,351,938.04 11 1996 10,008,798.84 11,960,812.49 23,306,305.61 12 1997 9,276,563.74 12,565,527.25 21,966,521.47 13 1998 7,795,292.13 18,221,031.66 20,034,264.00 14 1999 6,189,368.22 18,326,349.73 17,382,036.19 15 2000 19,443,890.34 19,443,890.34 19,443,890.34 16 2001 17,210,016.59 21,515,843.51 19,188,485.56 17 2002 17,846,043.00 24,392,021.63 19,748,515.80 18 2003 19,152,824.31 27,672,216.45 20,795,225.00 19 2004 21,731,823.21 32,603,177.99 22,887,147.39 20 2005 23,702,943.17 36,772,031.93 22,751,809.72 21 2006 26,759,732.63 48,525,638.48 25,929,281.42 22 2007 28,276,562.99 55,161,025.48 26,723,904.59 23 2008 30,169,301.77 67,171,292.57 31,053,992.77 Lampiran 7 8 DATA JUMLAH TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986 - 2008 NO TAHUN JUMLAH TENAGA KERJA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 Lampiran 8 12,837,119 12,866,665 12,504,593 13,106,608 13,424,784 13,144,046 14,022,669 13,871,820 13,850,929 14,062,056 13,841,255 13,805,930 14,117,828 14,566,119 14,491,222 15,066,542 15,154,856 15,124,082 14,930,097 15,655,303 15,210,931 16,304,058 15,463,658 DATA PENELITIAN ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986-2008 PDRB INVESTASI TENAGA NO TAHUN (Dalam Jutaan Rp) (Dalam Jutaan Rp) KERJA 1 2 3 4 5 53,000,962.36 10,550,682.52 12,837,119 1 1986 56,118,601.35 10,548,862.69 12,866,665 2 1987 59,683,014.25 11,549,122.23 12,504,593 3 1988 63,538,288.18 12,690,759.68 13,106,608 4 1989 67,984,566.60 14,037,879.59 13,424,784 5 1990 72,850,944.47 15,472,537.89 13,144,046 6 1991 78,271,166.33 16,824,130.15 14,022,669 7 1992 83,043,136.96 18,328,534.05 13,871,820 8 1993 88,337,258.80 20,569,113.94 13,850,929 9 1994 95,348,588.06 21,351,938.04 14,062,056 10 1995 102,309,603.31 23,306,305.61 13,841,255 11 1996 105,407,654.55 21,966,521.47 13,805,930 12 1997 93,030,052.65 20,034,264.00 14,117,828 13 1998 96,278,664.64 17,382,036.19 14,566,119 14 1999 114,701,304.81 19,443,890.34 14,491,222 15 2000 118,816,400.29 19,188,485.56 15,066,542 16 2001 123,038,541.13 19,748,515.80 15,154,856 17 2002 129,166,462.45 20,795,225.00 15,124,082 18 2003 135,789,872.31 22,887,147.39 14,930,097 19 2004 145,051,213.88 22,751,809.72 15,655,303 20 2005 150,682,654.75 25,929,281.42 15,210,931 21 2006 151,362,625.34 26,723,904.59 16,304,058 22 2007 167,790,369.84 31,053,992.77 15,463,658 23 2008 Lampiran 9 Data Regresi Linier Berganda ( Ln ) DATA PENELITIAN ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1986-2008 NO TAHUN Ln PDRB Ln INV 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 4 Lampiran 10 Data Uji Heteroskedastisitas 17.79 17.84 17.90 17.97 18.03 18.10 18.18 18.23 18.30 18.37 18.44 18.47 18.35 18.38 18.56 18.59 18.63 18.68 18.73 18.79 18.83 18.84 18.94 Ln TK 5 16.17 16.17 16.26 16.36 16.46 16.55 16.64 16.72 16.84 16.88 16.96 16.91 16.81 16.67 16.78 16.77 16.80 16.85 16.95 16.94 17.07 17.10 17.25 16.37 16.37 16.34 16.39 16.41 16.39 16.46 16.45 16.44 16.46 16.44 16.44 16.46 16.49 16.49 16.53 16.53 16.53 16.52 16.57 16.54 16.61 16.55 DATA PENELITIAN DATA UJI HETEROSKEDASTISITAS NO TAHUN Ln e² 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 29.3275 30.8089 32.6741 28.5833 30.3265 29.2184 32.7466 32.1554 32.3067 32.1546 30.4414 30.1621 32.0663 31.4661 31.5533 27.7356 29.0085 31.1090 32.2310 31.1744 32.3891 32.5206 31.8807 Ln INV Ln TK 4 5 16.1717 16.1715 16.2621 16.3564 16.4573 16.5546 16.6383 16.7240 16.8393 16.8767 16.9642 16.9050 16.8130 16.6709 16.7830 16.7698 16.7986 16.8502 16.9461 16.9402 17.0709 17.1011 17.2512 16.3679 16.3702 16.3416 16.3886 16.4126 16.3915 16.4562 16.4454 16.4439 16.4590 16.4432 16.4406 16.4629 16.4942 16.4891 16.5280 16.5338 16.5318 16.5189 16.5663 16.5375 16.6069 16.5540