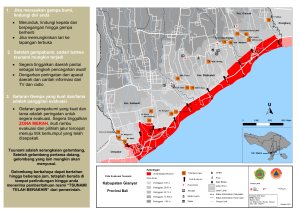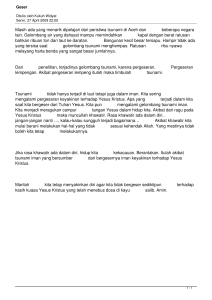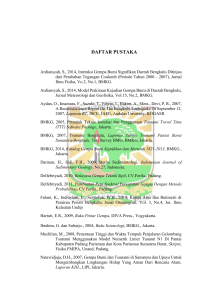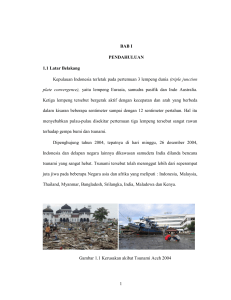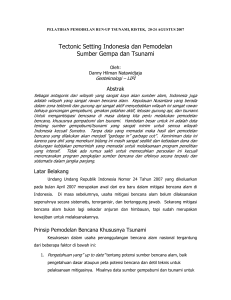4. hasil dan pembahasan
advertisement

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Karakteristik Pantai dan Pesisir Pangandaran 4.1.1 Elevasi daratan (Topografi) Hasil pemetaan topografi daratan menunjukan bawa kondisi topografi pesisir Pangandaran terdiri dari dataran rendah yang luas di sepanjang pantai dan pesisir. Dataran rendah nampak mulai dari Desa Sukaresik sampai Desa Babakan. Hal ini ditandai dengan warna ketinggian rendah yang hampir homogen disepanjang pesisir daerah tersebut. Dataran rendah pada umumnya membentang dalam radius 1500 m dari garis pantai. Daerah perbukitan berada di bagian selatan Desa Pangandaran dan menghadap langsung dengan Samudera Hindia. Pada jarak 500 m dari garis pantai wilayah ini didominasi oleh ketinggian 25 – 50 m, sedangkan pada jarak 1000 m dari garis pantai kondisi topografi didominasi oleh ketinggian 50 – 100 m. Perbukitan yang membentuk tanjung ini merupakan kawasan Cagar Alam. Berdasarkan survei lapang, perbukitan ini merupakan daerah kars (gamping/kapur). Di area ini banyak ditemukan cekungan-cekungan dan memiliki ketinggian lebih dari 100 m, selain itu daerah ini merupakan pantai berbatu/tebing batu. Wilayah pantai dan pesisir Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih memiliki topografi yang kompleks mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Wilayah bagian utara-timur Pangandaran merupakan wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Klasifikasi topografi daratan di wilayah penelitian disajikan pada Gambar 12. 48 49 Gambar 12. Kelas elevasi daratan (topografi) wilayah pesisir Pangandaran berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap bencana tsunami Berdasakan hasil pemetaan klasifikasi elevasi daratan menurut matriks risiko tsunami, dapat diketahui bahwa daerah dengan ketinggian daratan kurang dari 10 m memiliki jarak yang sangat dekat dengan laut. Luas area untuk kelas ini memiliki luas 3.044,92 Ha. Wilayah dengan ketinggian 10 – 25 m memiliki luas 1.979,02 Ha, daerah dengan ketinggian tersebut masih dominan berada di bagian utara Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih (Tabel 6). Daerah yang memiliki topografi lebih tinggi berada pada jarak yang lebih jauh dari garis pantai. Tabel 6. Luas daerah kelas elevasi daratan (topografi) No 1 2 3 4 5 Tingkat kerentanan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Total Kelas elevasi 0 – 10 m 10 – 25 m 25 – 50 m 50 – 100 m > 100 m Luas (Ha) 3.044,92 1.979,02 657,34 305,15 244,35 6.230,78 50 Mengacu pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya topografi pangandaran memiliki ketinggian kurang dari 10 m. Luas area untuk kelas ini lebih besar dari kelas-kelas yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah pantai dan pesisir di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih memiliki tingkat kerentanan tsunami yang sangat tinggi apabila dilihat dari segi elevasi daratannya. Elevasi daratan yang relatif rendah merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Hal ini menurut Oktariadi (2009b) akan lebih berpotensi untuk terkena limpasan tsunami dalam skala luas di bandingkan daerah yang memiliki topografi lebih tinggi. Rendahnya topografi daratan mempengaruhi seberapa luas masuknya tsunami ke daratan. 4.1.2 Kemiringan daratan (Slope) Kondisi kemiringan daratan pesisir Pangandaran terdiri dari dataran landai yang luas di sepanjang pantai dan pesisir. Sebaran dataran yang landai tersebut terlihat sama seperti sebaran topografi dimana dataran landai nampak mulai dari Desa Sukaresik sampai Desa Babakan. Daerah dengan kondisi kemiringan daratan yang landai pada umumnya membentang dalam radius 3000 m dari garis pantai. Daerah yang memiliki kemiringan daratan di atas 2% cenderung dominan di bagian utara mulai dari sebelah timur Desa Sukahurip sampai bagian barat Desa Cikalong. Daratan di atas 2% juga ditemukan di bagian selatan Desa Pangandaran (Tanjung Pangandaran). Daratan yang memiliki kemiringan di atas 2% berada pada jarak lebih dari 3000 m dari garis pantai kecuali untuk bagian selatan Desa 51 Pangandaran, kemiringan daratan di atas 2% berada pada jarak 500 – 1000 m (Gambar 13). Kemiringan daratan di lokasi penelitian didominasi oleh kelas kurang dari 2 % dengan luas mencapai 4.155,45 Ha. Kelas kemiringan daratan paling rendah berada pada kelas kemiringan daratan lebih besar 40 % dengan luas area hanya 293,78 Ha (Tabel 7). Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa wilayah pantai dan pesisir di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana tsunami apabila dilihat dari segi kemiringan daratannya. Daerah yang memiliki kemiringan landai akan berpotensi mengalami genangan gelombang tsunami lebih jauh ke arah darat. Pada pantai yang terjal atau curam, tsunami tidak akan terlalu jauh mencapai daratan karena tertahan dan dipantulkan kembali oleh tebing pantai (Oktariadi, 2009a). Gambar 13. Kelas kemiringan daratan (slope) wilayah pesisir Pangandaran berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap bencana tsunami 52 Tabel 7. Luas daerah kelas kemiringan daratan (slope) No 1 2 3 4 5 4.1.3 Tingkat kerentanan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Total Kelas slope 0 – 2% 2 – 10% 10 – 15% 15 – 40% > 40% Luas (Ha) 4.155,45 912,50 520,65 348,50 293,68 6.230,78 Jarak dari garis pantai Berdasarkan pengamatan di lapangan pada umumnya sarana-sarana penting seperti permukiman di lokasi penelitian memiliki jarak yang relatif dekat dengan garis pantai. Desa Pangandaran digolongkan sebagai daerah yang paling rentan karena berada pada dataran sempit diantara dua sisi teluk yang saling berhadapan (tanah genting). Desa Pangandaran merupakan lokasi wisata yang terkenal di Kabupaten Ciamis, sehingga tidak heran karena potensi daerahnya tersebut maka daerah ini menjadi kawasan padat penduduk. Masyarakat umumnya menempati bangunan yang sangat dekat dengan garis pantai, yaitu dalam jarak antara 100 m hingga 200 m dari garis pantai. Keadaan ini menjadikan permukiman di Desa Pangandaran tergolong sangat rentan terkena gelombang tsunami. Areal permukiman di daerah pesisir Pangandaran semakin lama semakin bertambah banyak dan semakin menjorok ke laut. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting sekali menerapkan penataan ruang yang baik untuk mengurangi risiko tsunami, khususnya di daerah pesisir. Jarak dari garis pantai menunjukan informasi jauh dekatnya suatu wilayah terhadap laut. Daerah yang berada pada jarak kurang dari 500 m dari garis pantai menunjukan daerah yang paling rentan 53 terhadap tsunami. Semakin dekat suatu wilayah terhadap laut maka semakin tinggi tingkat kerentanan dan risiko wilayah tersebut terkena dampak tsunami (NTHMP, 2001). Kelas jarak dari garis pantai wilayah pesisir Pangandaran diperlihatkan pada Gambar 14. Gambar 14. Kelas jarak dari garis pantai wilayah pesisir Pangandaran berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap bencana tsunami 4.1.4 Jarak dari sungai Wilayah Pangandaran yang mencakup Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih merupakan wilayah yang memiliki sungai-sungai besar yang sangat dekat dengan muaranya. Berdasarkan survei lapang dan analisis dari citra satelit Landsat TM diketahui setidaknya terdapat empat buah sungai besar yang melintasi wilayah penelitian. Sungai tersebut adalah Sungai Cikidang bagian barat, Sungai Cikidang bagian timur, Sungai Cikambulan dan Sungai Ciambulungan. 54 Sungai Cikidang terletak di sebelah barat dan timur Desa Babakan (Kecamatan Pangandaran) dan bermuara di muara Cikidang. Sungai Cikidang melewati beberapa desa mulai dari Desa Sukahurip, Desa Babakan, bagian utara Desa Wonoharjo, Desa Pananjung dan Desa Pangandaran. Sungai Cikambulan berada di sebelah timur Desa Cikembulan dan Sungai Ciambulungan berada di Desa Sukaresik, kedua sungai ini bermuara di muara Citonjong yang berada di Desa Sukaresik. Desa Sukaresik, Desa Cikembulan dan bagian timur Desa Pangandaran serta Desa Babakan dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi karena di daerah-daerah tersebut terlihat adanya sungai-sungai besar yang dekat dengan muaranya. Sungai-sungai tersebut saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya. Kondisi sungai yang demikian akan menyebabkan daerah yang terletak di antara sungai tersebut akan mempunyai tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana tsunami. Tsunami yang merambat melalui sungai dapat menimbulkan kerusakan yang lebih hebat dari yang diperkirakan. Keadaan ini terjadi karena dengan adanya sungai maka akan semakin mendorong tsunami untuk melintas lebih jauh ke daratan. Pada daerah yang menyempit seperti sungai dan kanal pengendali banjir akan terjadi peningkatan kecepatan dan ketinggian muka air. Hal ini disebabkan debit massa air yang sama harus menjalar melalui celah yang sempit (NTHMP, 2001). Berdasarkan hal tersebut maka penempatan daerah aman harus berada jauh dari sungai yang dekat dengan muarannya. Klasifikasi jarak dari sungai di wilayah penelitian diperlihatka pada Gambar 15. 55 Gambar 15. 4.1.5 Kelas jarak dari sungai wilayah pesisir Pangandaran berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap bencana tsunami Penggunaan lahan (Landuse) Wilayah pesisir termasuk dalam kerentanan yang tinggi terhadap bencana tsunami. Konsep penggunaan lahan harus melihat jarak dari garis pantai agar dapat melindungi daratan dari hantaman gelombang tsunami. Wilayah yang bisa dikategorikan rentan tsunami yaitu berdasarkan penggunaan lahannya bagi kepentingan masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui bahwa tipe penggunaan lahan di wilayah penelitian didominasi oleh vegetasi darat/hutan dan area permukiman. Penggunaan lahan berupa permukiman terlihat berada cukup padat di wilayah pesisir Kecamatan Pangandaran, khususnya Desa Pangandaran dan Desa Babakan (Gambar 16). Hasil survei lapang menunjukan bahwa jenis penutupan lahan untuk wilayah pesisir Pangandaran tidak mengalami banyak perubahan bila 56 dibandingkan dengan kondisi yang tergambar pada peta penutupan lahan pesisir Pangandaran dari Bappeda tahun 2004. Jenis penggunaan lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti permukiman,perkebunan dan sawah memiliki luas area yang cukup luas. Hal ini akan berdampak pada kerugian yang besar apabila gelombang tsunami melanda daerah tersebut. Luas area permukiman mencapai 1.285,50 Ha, keadaan ini menandakan bahwa wilayah pesisir Pangandaran tergolong daerah padat penduduk. Permukiman penduduk menggambarkan tingkat kepadatan penduduk dan sebaran tempat hunian yang akan mempengaruhi tingkat kerugian jiwa maupun harta benda. Luasan dari masing-masing penggunaan lahan disajikan pada Tabel 8. Gambar 16. Kelas jenis penggunaan lahan wilayah pesisir Pangandaran 57 Tabel 8. Luasan jenis penggunaan lahan (landuse) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis penggunaan lahan Danau Empang/Tambak Ladang/Teggalan Lahan kosong Perkebunan Permukiman Sawah Semak belukar Vegetasi darat/Hutan Total Luas (Ha) 14,71 135,64 90,55 325,20 785,65 1.285,50 480,50 521,55 2.584,45 6.230,78 Bencana tsunami dapat menyebabkan terjadinya perubahan lahan, oleh karena itu perlu dilihat tingkat kerentanan penggunaan lahan terhadap tsunami. Acuan klasifikasi tingkat penggunaan lahan terhadap tsunami pada penelitian ini dibagi berdasarkan klasifikasi Oktariadi (2009a) serta Diposaptono dan Budiman (2006). Selain itu pengklasifikasian parameter penggunaan lahan ini didasarkan dari hasil konsultasi pakar dan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Hasil klasifikasi jenis penggunaan lahan berdasarkan matriks risiko tsunami menunjukan daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi di Kecamatan Pangandaran dominan berada di Desa Pangandaran dan Desa Babakan. Sedangkan untuk Kecamatan Sidamulih daerah yang paling dominan memiliki kerentanan yang sangat tinggi berada di Desa Cikembulan. Hal ini disebabkan karena di daerah tersebut banyak dimanfaatkan sebagai area permukiman dan lahan-lahan terbangun yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Peta kerentanan penggunaan lahan di wilayah kajian selengkapnya disajikan pada Gambar 17. 58 Gambar 17. Kelas kerentanan penggunaan lahan wilayah pesisir Pangandaran berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap bencana tsunami Pada umumnya tingkat kerentanan penggunaan lahan terhadap bencana tsunami paling luas berada pada kelas dengan kerentanan sangat rendah dan sangat tinggi. Luas area dengan tingkat kerentanan penggunaan lahan sangat rendah mencapai 2.580,45 Ha. Sedangkan luas area dengan tingkat kerentanan penggunaan lahan sangat tinggi mencapai 1.773,03 Ha (Tabel 9). Kajian risiko tsunami dalam hal ini mengedepankan area permukiman sebagai area paling rentan. Sebagian besar daerah permukiman terletak di daerah pesisir dan dekat dengan laut sehingga berpotensi besar terhadap bahaya tsunami. Penggunaan lahan yang tidak banyak melibatkan manusia seperti lahan kosong, semak belukar dan vegetasi darat/hutan berada pada daerah yang aman. Atas dasar tersebut maka penggunaan lahan di wilayah pesisir harus memperlihatkan konsep penataan ruang yang berbasis bencana alam. 59 Tabel 9. Luas daerah tingkat kerentanan penggunaan lahan No 1 2 3 4 5 4.1.6 Tingkat kerentanan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Tipe Penggunaan lahan Permukiman dan Sawah Perkebunan, Empang/Tambak, Danau Ladang/Teggalan Semak belukar, Lahan kosong Vegetasi darat/Hutan Total Luas (Ha) 1.773,03 936,00 90,55 846,75 2.580,45 6.230,78 Kondisi batimetri wilayah pantai dan lepas pantai Kondisi batimetri wilayah lepas pantai (domain A) digambarkan dengan menggunakan data batimetri ETOPO 1. Data batimetri ini dikeluarkan oleh British Oceanographic Data Center. Data ETOPO 1 diperoleh dari hasil data satelit altimetri TOPEX. Berdasarkan pengolahan tiga dimensi dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper diketahui bahwa di dasar Samudera Hindia sebelah selatan Pulau Jawa terdapat palung yang sangat curam dengan kedalaman lereng lebih dari 7.500 meter. Palung ini memanjang dari ujung Pulau Sumatera sampai bagian timur Pulau Jawa. Keadaan tersebut menjadikan daerah di sepanjang palung memiliki risiko yang tinggi sebagai sumber tsunami. Hal ini dikarenakan bila terjadi gempa di daerah palung, maka ada kemungkinan hal itu mengganggu kestabilan lereng dan bila sampai roboh akan menimbulkan tsunami besar. Bagian selatan palung terlihat kondisi dasar laut yang hampir homogen membentuk basin dengan kedalaman yang besar. Hal ini akan megakibatkan gelombang tsunami akan mempunyai kecepatan tinggi apabila melitas di daerah tersebut. Kondisi batimetri di wilayah lepas pantai Pangandaran diperlihatkan pada Gambar 18. 60 Gambar 18. Profil tiga dimensi batimetri wilayah lepas pantai Pangandaran Profil batimetri untuk wilayah penelitian (Pangandaran) mengacu pada peta batimetri Dishidros TNI-AL. Hasil pemetaan batimetri wilayah penelitian menunjukan bahwa kedalaman dekat pantai umumnya dangkal dan semakin ke tengah laut kedalaman perairan semakin bertambah (Gambar 19). Gambar 19. Profil tiga dimensi batimetri wilayah pantai Pangandaran 61 Kondisi batimetri perairan Pangandaran memperlihatkan bahwa semakin mendekati pantai maka kondisi batimetri semakin dangkal dan hampir homogen. Kisaran kedalaman perairan di wilayah penelitian berkisar 0 – 40 m sehingga kondisi batimetri tergolong dangkal. Kondisi batimetri di sebelah barat (Desa Sukaresik dan Desa Cikembulan) relatif lebih dangkal. Keadaan ini terjadi karena di daerah tersebut terdapat muara Citonjong sehingga banyak terendapkan material sungai. Kondisi batimeti yang serupa berada di bagian timur Pangandaran (Desa Sukaresik), dimana di wilayah tersebut terdapat muara Cikidang. Kondisi batimetri yang dangkal menurut Yalciner et al. (2006) akan mempengaruhi kecepatan transportasi energi di laut yang lebih dalam sehingga kecepatan tsunami di laut yang lebih dalam akan lebih tinggi daripada kecepatan tsunami di laut yang lebih dangkal. Kondisi kemiringan dasar perairan di wilayah perairan Pangandaran didominasi oleh kemiringan dasar yang landai. Keadaan ini diketahui berdasarkan analisis profil batimetri dengan menggunakan menu 3D Path Profile/Line of Sight Tool pada perangkat lunak Global Mapper. Profil kemiringan dasar laut untuk setiap titik observasi disajikan pada Lampiran 4. Hasil identifikasi tersebut menunjukan bahwa kemiringan dasar perairan wilayah perairan Pangandaran berkisar antara 0,52o – 1,93o. Kemiringan dasar perairan cenderung menurun mulai dari bagian barat perairan Desa Sukaresik sampai wilayah barat perairan Desa Pangandaran. Keadaan berbeda diperlihatkan pada wilayah perairan sebelah timur tepatnya di perairan Desa Sukaresik. Wilayah perairan ini memiliki kemiringan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah 62 perairan disekitarnya. Berikut ini disajikan kemiringan dasar perairan di wilayah kajian untuk setiap titik observasi pada Tabel 10. Tabel 10. Kemiringan dasar perairan Pangandaran untuk setiap titik observasi Koordinat (o) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 From Pos To Pos 108,567 E – 7,687 S 108,581 E – 7,685 S 108,593 E – 7,684 S 108,599 E – 7,683 S 108,606 E – 7,684 S 108,618 E – 7,685 S 108,626 E – 7,685 S 108,634 E – 7,687 S 108,638 E – 7,687 S 108,642 E – 7,688 S 108,649 E – 7,693 S 108,655 E – 7,702 S 108,659 E – 7,701 S 108,664 E – 7,692 S 108,672 E – 7,686 S 108,681 E – 7,681 S 108,696 E – 7,677 S 108,567 E – 7,692 S 108,581 E – 7,689 S 108,593 E – 7,689 S 108,599 E – 7,688 S 108,606 E – 7,689 S 108,618 E – 7,689 S 108,626 E – 7,689 S 108,634 E – 7,691 S 108,638 E – 7,692 S 108,642 E – 7,692 S 108,649 E – 7,696 S 108,651 E – 7,702 S 108,664 E – 7,701 S 108,667 E – 7,696 S 108,675 E – 7,689 S 108,683 E – 7,684 S 108,696 E – 7,681 S Desa Kemiringan dasar perairan (o) Sukaresik Sukaresik Sukaresik Cikembulan Cikembulan Cikembulan Wonoharjo Wonoharjo Wonoharjo Pananjung Pananjung Pangandaran Pangandaran Pangandaran Babakan Babakan Babakan 1,14 0,89 0,83 0,77 0,70 0,78 0,76 0,74 0,66 0,59 0,55 0,52 0,66 0,83 1,29 1,93 1,02 Berdasarkan karakteristik batimetri dan kemiringan dasar perairan yang telah diuraikan di atas, maka gelombang tsunami akan lebih dulu tiba di wilayah pantai sebelah barat (Desa Sukaresik) dan disebelah timur (Desa babakan). Hal ini dikarenakan kedalaman perairan dan kemiringan dasar perairan di kedua wilayah tersebut cenderung lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Keadaan ini sesuai seperti yang dikemukan oleh Yudhicara (2008) dimana gelombang tsunami akan memiliki kecepatan lebih besar dan lebih dulu tiba di lokasi yang memiliki kontur batimetri yang lebih dalam. Menurut Mudhari (2009) kondisi 63 batimetri demikian akan mengakibatkan jarak daerah pecah gelombang dengan pantai menjadi semakin kecil. Pada penelitian ini kondisi batimetri dan kemiringan dasar perairan tidak dibobotkan kedalam matriks risiko tsunami. Hal ini dikarenakan parameter tersebut sudah terintegrasi di dalam hasil model. Pada dasarnya model tsunami yang dibangun sudah memperhitungkan kondisi batimetri dan kemiringan dasar perairan sehingga proses pembobotannya dilakukan terhadap hasil modelnya saja. 4.1.7 Morfometri pantai Pada penelitian ini bentuk morfometri pantai tidak digunakan dalam penentuan indeks kerentanan pantai. Hal ini dikarenakan bentuk morfometri pantai cenderung homogen, mengingat daerah yang diidentifikasi masih dalam skala kecil (skala kecamatan). Wilayah pesisir Pangandaran memiliki bentuk morfometri yang unik dan khas. Bentuk garis pantai Pangandaran membentuk air mata (teardrop) yang masuk ke Samudera Hindia. Bentuk seperti ini mengakibatkan garis pantai Pangandaran membentuk tanjung yang diapit dua sisi teluk yang hampir simetris. Teluk ini adalah Teluk Parigi di sisi sebalah barat dan Teluk Pangandaran di sisi sebelah timur Desa Pangandaran. Pangandaran merupakan daerah berteluk, pada dasarnya bentuk pantai berteluk akan memfokuskan gelombang tsunami yang sedang berjalan ke arahnya, sehingga energi gelombang tersebut terakumulasi pada cekungan tersebut dan mampu meningkatkan ketinggian gelombang tsunami yang sampai di pantai (Diposaptono dan Budiman, 2005). 64 4.1.8 Ekosistem pantai dan pesisir Pendugaan awal ekosistem pesisir dilakukan dengan penajaman citra. Penajaman citra untuk terumbu karang adalah komposit RGB 421, sedangkan untuk mangrove adalah komposit RGB 453. Berdasarkan penajaman dengan komposit RGB 421, keberadaan ekosistem terumbu karang tidak terdeteksi dalam citra Landsat TM tahun 2003, 2006 dan 2009. Hasil survei lapang memberikan penjelasan lain, dimana diketahui bahwa di perairan Pangandaran terdapat ekosistem terumbu karang. Berdasarkan hasil penelitian Wulandari (2002), diketahui terumbu karang dapat ditemukan pada kawasan Cagar Alam laut di pantai timur (Batu Nunggul dan Batu Layar) dan pantai barat Desa Pangandaran (Batu Mandi dan Pasir Putih). Tipe terumbu karang berupa karang tepi (fringing reef) yang mempunyai panjang 1,5 km dengan lebar hanya 50 m. Hasil penelitian Wulandari (2002) menunjukan bahwa persentasi penutupan karang hidup di Pangandaran secara keseluruhan termasuk dalam kategori buruk. Substrat dasar perairan sebagian besar ditutupi oleh rubble. Pengamatan pada tahun 1998 menunjukkan bahwa sebagian besar terumbu karang di Pangandaran dalam kondisi rusak (Wulandari, 2002). Survei lebih lanjut pada tahun 2005 memperlihatkan kerusakan terjadi semakin parah. Pengamatan terakhir pada tahun 2008 menunjukkan hasil tidak berbeda jauh. Tutupan karang hidup di pantai barat hanya sekitar 11,48 % , sedangkan di pantai timur 18,21 % sehingga dikategorikan rusak menurut kriteria baku Kementerian Lingkungan Hidup (Wulandari, 2002). 65 Kerusakan ini disebabkan baik oleh aktifitas penangkapan ikan maupun pariwisata seperti menginjak karang, mengambil karang, penangkapan ikan berlebih atau dengan racun, sampah, tertabrak perahu atau putaran baling baling mesin kapal yang mengaduk sedimen. Selain itu erosi di daerah sepanjang aliran sungai sungai bermuara di perairan Pangandaran menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi dan dapat merusak kehidupan terumbu karang. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa keberadaan ekosistem terumbu karang tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tingkat kerawanan bencana tsunami di Pangandaran. Hal ini disebabkan karena sebaran terumbu karang bersifat lokal dan sempit. Ekosistem mangrove ditemukan di kawasan penelitian dalam skala yang sangat kecil. Berdasarkan data spasial Bappeda Kab. Ciamis (2009) kemungkinan besar dahulu terdapat hutan mangrove di Pangandaran. Hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya muara muara sungai cukup lebar, tempat yang ideal bagi tumbuhan mangrove. Namun kini hanya sedikit yang tersisa, tinggal berupa deretan pohon nipah (Nypa fruticans) di sepanjang pinggiran sungai. Jenis jenis tumbuhan mangrove lainnya boleh dibilang telah hilang. Hal ini sangat disayangkan mengingat hutan ini memiliki manfaat sangat besar bagi kehidupan diantaranya sebagai pelindung pantai dari pukulan ombak dan menahan lumpur yang dibawa sungai atau abrasi akibat gelombang laut. Keadaan ini menjadikan ekosistem mangrove di kawasan penelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk menurunkan risiko bencana tsunami. 66 4.2. Kejadian Gempa Tektonik Berdasarkan catatan sejarah yang terangkum dalam katalog NEIC-USGS selama kurun waktu 1974 – Mei 2011 diketahui bahwa di wilayah lepas pantai Pangandaran umumnya terjadi gempa bumi berkekuatan 5 – 6 SM, gempa dengan kekuatan lebih kecil dari 5 SM lebih sering terjadi. Gempa terbesar yang pernah terjadi berkekuatan 7,7 SM. Gempa tersebut menimbulkan bencana tsunami yang melanda kawasan Pangandaran dan wilayah pesisir sekitarnya pada tahun 2006. Jumlah kejadian gempa yang terekam di wilayah penelitian pada rentang tahun 1974 – Mei 2011 terjadi sebanyak 683 kejadian dengan rentang kekuatan 3 – 7,7 SM. Pada rentang tahun ini gempa dengan kekuatan lebih kecil dari 5 SM terjadi sebanyak 585 kali, gempa berkekuatan 5,1 – 6 SM terjadi 94 kali, gempa berkekuatan 6,1 – 7 SM terjadi sebanyak 3 kali dan gempa dengan kekuatan di atas 7 SM hanya terjadi sekali. Bedasarkan hasil pemetaan pusat-pusat gempa (episentrum) yang terjadi di lepas pantai Pangandaran diketahui tipe sebaran pusat gempa-gempa dangkal terlihat rapat dan berkumpul di sekitar pusat gempa Pangandaran. Episentrum tersebut berada hampir tegak lurus dengan kawasan pesisir Pangandaran. Wilayah sebelah barat dari pusat gempa pangandaran memiliki frekuensi kegempaan yang lebih tinggi. Wilayah lepas pantai sebelah timur Pangandaran terlihat intensitas kegempaanya jauh lebih sedikit. Menurut Natawidjaja (2007) wilayah tersebut merupakan zona seismic gap yang membentang sepanjang 400 km. Seismic gap merupakan kawasan sepi gempa yang sangat berpotensi menjadi sumber gempa kuat/besar dan tsunami dimasa yang akan datang. Peta seismisitas di wilayah kajian diperlihatkan oleh Gambar 20. 67 Gambar 20. Tingkat seismisitas di wilayah kajian selang waktu 1974 – Mei 2011 (NEIC-USGS, 2011) Gempa-gempa yang terlihat pada peta seismisitas di atas merupakan gempa-gempa dangkal (≤ 40 km) yang terjadi di wilayah lepas pantai Pangandaran. Pusat gempa di perairan tersebut walaupun tergolong gempa-gempa dangkal belum tentu menjadi sumber pembangkit tsunami. Menurut Shuto (1993) tsunami akan terbentuk apabila terjadi gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 33 km (versi USGS < 48 km), magnitude gempa harus lebih besar dari 6 SR dan dan gempa menghasilkan deformasi vertikal yang besar di dasar laut, sehingga patahan sumber gempa berupa patahan naik (thrust fault) atau patahan turun (normal fault). Gempa Pangandaran serta gempa-gempa yang sering terjadi di selatan Jawa pada umumnya terjadi pada zona subduksi Jawa. Zona subduksi ini secara 68 kasat mata nampak sebagai palung Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Natawidjaja (2007) menjelaskan bahwa subduksi Jawa memiliki umur cukup tua yakni lebih dari 150 juta tahun sehingga sempat dianggap bersifat aseismik atau tidak menghasilkan gempa. Adanya peristiwa gempa Pancer (1994) dan Pangandaran (2006) dimana keduanya sama-sama memiliki momen magnitude lebih besar 7 SM, menunjukkan subduksi ini tetap harus diperhitungkan sebagai sumber potensial gempa besar di masa yang akan datang. Proses subduksi ini akan terus berlangsung dan terus menekan sehingga mengakibatkan terakumulasinya energi tekanan di daerah ini. Apabila batuan sedimen yang tertekan di wilayah tersebut sudah tidak kuat lagi menahan energi, maka energi tersebut akan dilepaskan berupa kejadian gempa bumi. Analisis parameter seismik pada penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menentukan zona tsunamigenik (sumber tsunami). Selain itu parameter seismik merupakan hal yang penting karena perubahan tingkat seimisitas suatu wilayah berhubungan erat dengan perubahan stress dan tekanan di bawah permukaan wilayah tersebut (Soehaimi, 2008). Hubungan antara jumlah kejadian gempa dan magnitude gempa untuk setiap wilayah kajian ditampilkan pada Gambar 21. Hasil analisis regresi linier menunjukan bahwa frekuensi kejadian gempa menurun secara eksponensial dengan meningkatnya kekuatan gempa. Berdasarkan hasil pengolahan regresi linier maka diperoleh nilai-b yang akan menentukan angka dimensi fraktal. Angka dimensi fraktal digunakan untuk melihat tingkat stress dan tekanan di bawah permukaan yang terjadi disuatu wilayah (Galih dan Handayani, 2007). 69 107o 108o BT dan 8o 11o LS (a) 1 y = -0,898x + 4,367 R² = 0,893 0,5 Log (N) 0 -0,5 0 2 4 6 8 6 8 -1 -1,5 -2 -2,5 (b) Magnitude (SM) 108o 109o BT dan 8o 11o LS 1 0,5 y = -0,858x + 4,206 R² = 0,952 Log (N) 0 -0,5 0 2 4 -1 -1,5 -2 -2,5 Magnitude (SM) 109o 110o BT dan 8o 11o LS (c) 1 0,5 y = -0,579x + 2,185 R² = 0,866 Log (N) 0 -0,5 0 2 4 6 8 -1 -1,5 -2 -2,5 Magnitude (SM) Gambar 21. Hubungan jumlah kejadian gempa dan magnitude gempa: (a) 107o – 108o BT dan 8o – 11o LS; (b) 108o – 109o BT dan 8o – 11o LS; (c) 109o – 110o BT dan 8o – 11o LS 70 Wilayah sebelah barat lepas pantai Pangandaran (107o – 108o BT dan 8o – 11o LS) memiliki angka dimensi fraktal sebesar 1,79. Nilai tersebut masih lebih besar apabila dibandingkan dengan angka dimensi fraktal untuk wilayah di bagian tengah (108o – 109o BT dan 8o – 11o LS) dan timur lepas pantai Pangandaran (109o – 110o BT dan 8o – 11o LS ) dimana nilainya masing-masing adalah 1,71 dan 1,15. Perairan sebelah barat lepas pantai Pangandaran memiliki angka dimensi fraktal paling besar. Keadaan ini menjelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah paling aktif gempa dibandingkan wilayah kajian lainnya. Hal ini sesuai dengan tingginya kejadian gempa di wilayah tersebut. Intensitas kejadian gempa yang rendah berada di bagian timur lepas pantai Pangandaran. Rohadi (2006) menyatakan bahwa bagian wilayah dengan intensitas gempa yang rendah biasanya berkorelasi dengan tingkat stress yang tinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah tersebut berpotensi lebih besar terjadi gempa bumi berkekuatan tinggi. Berdasarkan asumsi tersebut maka di sebelah timur lepas pantai Pangandaran pada saat ini tengah mengakumulasi energi tegangan akibat proses subduksi yang sewaktu-waktu akan dilepaskan berupa gempa bumi berkekuatan besar. 4.3. Hasil Pemodelan Tsunami 4.3.1 Skenario simulasi model Skenario simulasi pada pemodelan ini dilakukan dengan membuat sejumlah skenario yang dianggap paling sesuai dan paling mungkin terjadi. Pada penelitian ini dibangun empat buah skenario yang menjadi dasar dalam pemodelan tsunami. 71 Skenario pertama dibangkitkan oleh gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Pangandaran. Menurut Harvard CMT gempa tersebut memiliki kekuatan 7,7 SM atau 4,0 x 1027 dyne.cm. USGS menjelaskan posisi pusat gempa berada pada koordinat 9,295o LS dan 107,347o BT dengan kedalaman pusat gempa 6 km. Pusat gempa yang pernah terjadi pada tahun 2006 tersebut berada pada jarak 230 km dari arah utara Pulau Christmas, 235 km dari arah barat Tasikmalaya, 260 km dari arah selatan Bandung dan 355 km dari arah utara Jakarta (NEIC-USGS, 2006a). Skenario model ke-2 dibangun pada posisi episetrum gempa yang sama seperti pada skenario pertama. Besar gempa yang diterapkan pada skenario ke-2 adalah 8,5 SM. Pemilihan skenario ini dipilih sebagai pembanding pengaruh besarnya kekuatan gempa pada daerah/posisi pusat gempa yang sama. Posisi sumber tsunami untuk skenario ke-3 dan skenario ke-4 ditentukan berdasarkan analisis dari segi parameter seismik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa wilayah sebelah timur dari pusat gempa Pangandaran memiliki frekuensi kegempaan yang lebih sepi dibandingkan dengan di wilayah sebelah baratnya. Berdasarkan hal tersebut, maka model sumber tsunami untuk skenario ke-3 dan skenario ke-4 posisi episentrumnya berada pada batas tersebut. Daerah ini digunakan sebagai sumber tsunami walaupun kejadian gempa relatif sepi. Menurut Natawidjaja (2007) daerah yang relatif sepi gempa bukan berarti daerah tersebut aseismik (tidak aktif), justru hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sedang menimbun energi karena belum mengalami 72 pematahan. Pelepasan energi berupa gempa kuat disertai tsunami mendatang yang akan menerpa pesisir selatan Jawa berpotensi bersumber dari sini. Skenario ke-3 dibangkitkan oleh gempa bumi yang berada pada posisi 9,195o LS dan 108,500o BT. Pusat gempa tersebut memiliki jarak yang lebih dekat dengan Pangandaran yaitu sekitar 165 km dari arah selatan Pangandaran. Posisi episetrum pada skenario ke-4 posisinya lebih bergerak ke sebelah timur dari pusat gempa Pangandaran, yakni pada koordinat 10,280o LS dan 109,800o BT. Skenario ke-4 menggunakan parameter gempa Pancer. Hal ini untuk menyesuaikan arah tujaman (strike) dengan keadaan sebenarnya. Menurut Handayani dan Harjono (2008) semakin ke arah timur jalur konvergensi antara lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, arah tujaman semakin menujam dengan arah normal. Secara ringkas parameter-parameter yang menjadi dasar model pembangkit tsunami disajikan pada Tabel 11. Tabel 11. Parameter masukan untuk masing-masing skenario yang dibangun (NEIC-USGS, 2009b) Parameter Gempa o Lintang ( ) o Bujur( ) Hiposentrum (km) o Strike ( ) Dip (o) o Slip ( ) Momen Magnitude (Mw) Momen Seismik (dyne.cm) Skenario Gempa 1 2 3 4 -9,295 -9,295 -9,195 -10,280 107,347 107,347 108,500 109,800 6,0 6,0 6,0 6,0 289,0 289,0 289,0 276,0 10,0 10,0 10,0 89,0 95,0 95,0 95,0 79,0 7,7 8,5 8,5 8,9 27 28 28 2,4 x 1029 4 x 10 7 x 10 7 x 10 Panjang Patahan (km) 82,0 214,0 214,0 314,0 Lebar Patahan (km) 41,0 107,0 107,0 157,0 2,4 6,2 6,2 8,8 Dislokasi/Defomasi (m) 73 4.3.2 Simulasi gelombang tsunami awal Besar gempa yang diterapkan pada skenario ke-1 adalah 7,7 SM. Berdasarkan kekuatan gempa tersebut maka dengan formula empiris Emile A. Okal diperoleh panjang patahan sejauh 82 km, lebar patahan 41 km dan dislokasi atau pergeseran bidang patahan (deformasi) sebesar 2,4 m. Hal yang hampir serupa disampaikan oleh NEIC-USGS (2006a), dalam laporannya menyatakan bahwa lokasi patahan penyebab tsunami Pangandaran yang berjarak sekitar 50 km dari palung Jawa memiliki luas patahan seluas 5.600 km2 (80 x 70 m) dan pergeseran total (dislokasi) yang terjadi dalam patahan ini mencapai 1,97 meter. Gempa sebesar 8,5 SM yang diterapkan pada skenario ke-2 menghasilkan panjang patahan sepanjang 214 km dengan lebar patahan 107 km dan dislokasi 6,2 m. Skenario model ke-3 dan ke- 4 dibangun dengan kekuatan gempa sebesar 8,5 SM dan 8,9 SM. Bidang patahan yang terbentuk untuk kasus pada skenario ke-3 karakteristiknya sama seperti pada kasus skenario ke-2. Hal ini disebabkan besar kekuatan gempa yang digunakan memiliki energi yang sama yaitu sebesar 8,5 SM. Bidang patahan untuk kasus skenario ke-4 memiliki magnitude paling besar dan ekstrim. Pada skenario ke-4 diperoleh panjang patahan sepanjang 314 km dengan lebar 157 km dan dislokasi sebesar 8,8 m. Deformasi patahan di dasar laut merupakan efek dari kekuatan gempa. Hal ini akan menjadikan medan gelombang tsunami awal atau disebut juga sebagai gelombang tsunami awal. Hasil simulasi menunjukan adanya perubahan ketinggian muka air positif dan negatif. Muka air yang bernilai negatif atau lembah gelombang menghadap ke daerah pantai selatan Jawa Barat, tepatnya tegak lurus terhadap pesisir Pangandaran. Gelombang negatif ini menurut 74 Slawson dan Savage (1979) mengindikasikan sebagai pemicu terjadinya surutnya air laut di pantai sebelum gelombang tsunami tiba. Keadaan ini telah terbukti ketika terjadi tsunami di Pangandaran pada tahun 2006. Berdasarkan kesaksian saksi mata, air laut mengalami surut sekitar 50 sampai dengan 100 meter sampai akhirnya tsunami datang di kawasan pantai. Hasil simulasi di daerah pembangkitan gelombang tsunami diperlihatkan oleh Gambar 22. (a) 7,7 SM (b) 8,5 SM (c) 8,5 SM (d) 8,9 SM Elevasi (m) Gambar 22. Ketinggian muka air laut awal sesaat setelah terjadi gempa di dasar laut : (a) Skenario ke-1; (b) Skenario ke-2; (c) Skenario ke-3; dan (d) Skenario ke-4 Besarnya pergerakan yang terjadi dan luas atau panjangnya zona patahan gempa sebanding dengan besar magnitude gempanya. Semakin besar kekuatan gempa maka semakin besar pula pergerakan dan luas wilayah patahannya. 75 Keadaan ini seperti dikemukan Latief (2007) yang menyatakan bahwa parameter kekuatan gempa akan menentukan bidang patahan seperti panjang patahan, lebar patahan dan dislokasi. Semakin besar kekuatan gempa maka semakin luas bidang patahan yang terbentuk, selain itu sumber tsunami juga semakin luas. Hasil simulasi di daerah pembangkit gelombang tsunami menunjukan perubahan ketinggian muka air positif dan negatif. Bila dilakukan pemotongan melintang pada daerah sumber pembangkit tsunami sebagaimana garis A – A’, dapat dilihat dengan jelas profil muka air laut di daerah pembangkit. Potongan melintang perubahan elevasi muka air laut ditunjukan pada Gambar 23. -7 -7,3 -7,6 -7,9 -8,1 -8,4 -8,7 -9 -9,3 -9,6 -9,9 -10,1 -10,4 -10,7 Elevasi (m) A-A' (Skenario 2) 6 4 2 0 -2 -4 -6 -7 -7,3 -7,6 -7,9 -8,2 -8,5 -8,8 -9,2 -9,5 -9,8 -10,1 -10,4 -10,7 Koordinat (oLS) Koordinat (oLS) a) 7,7 SM b) 8,5 SM Elevasi (m) -7 -7,3 -7,6 -7,9 -8,1 -8,4 -8,7 -9 -9,3 -9,6 -9,9 -10,1 -10,4 -10,7 Elevasi (m) A-A' (Skenario 3) 6 4 2 0 -2 -4 -6 Koordinat (oLS) c) 8,5 SM 6 4 2 0 -2 -4 -6 A-A' (Skenario 4) -7 -7,3 -7,6 -7,9 -8,1 -8,4 -8,7 -9 -9,3 -9,6 -9,9 -10,1 -10,4 -10,7 Elevasi (m) A-A' (Skenario 1) 6 4 2 0 -2 -4 -6 Koordinat (oLS) d) 8,9 SM Gambar 23. Potongan melintang elevasi muka air laut : (a) Skenario 1; (b) Skenario 2; (c) Skenario 3; dan (d) Skenario 4 Perubahan ketinggian muka air positif dan negatif pada skenario ke-1 adalah kurang dari 1 m. Pada kasus skenario ke-2 dan skenario ke-3 perubahan 76 muka air laut sekitar 3 m, sedangkan untuk kasus terburuk yang diterapkan pada skenario ke-4 perubahan muka air adalah sekitar 4 m. Keadaan ini menjelaskan bahwa patahan naik dengan bidang patahan yang panjang akan menyebabkan volume kosong yang lebih besar, kemudian akan segera diisi oleh massa air laut secara sporadis sehingga gerakan balik dari massa air laut ini akan menyebabkan tsunami. 4.3.3 Waktu tempuh penjalaran gelombang tsunami Model penjalaran tsunami disimulasikan dengan hasil estimasi tinggi gelombang tsunami awal yang dibangkitkan oleh deformasi dasar laut akibat gempa tektonik. Simulasi ini dimulai dari sumber pembangkit hingga sampai sepanjang garis pantai yang terkena tsunami. Hasil simulasi berupa data matrik ketinggian muka air laut untuk setiap langkah waktu yang telah ditentukan besarannya. Simulasi yang diterapkan pada skenario pertama merupakan model penjalaran gelombang tsunami berdasarkan sejarah tsunami yang terjadi di Pangandaran. Kekuatan gempa dan posisi patahan yang disimulasikan sudah disesuaikan dengan kondisi pada waktu tsunami di Pangandaran. Gelombang tsunami yang dibangkitkan oleh deformasi dasar laut akibat gempa berkekuatan 7,7 SM menjalar dan sampai pertama kali di pesisir selatan Pangandaran (Tanjung Pangandaran) pada waktu ke-2600 detik (43 menit). Gelombang tsunami terus menjalar dan sampai di sisi sebelah barat (Teluk Parigi) serta sisi sebelah timur (Teluk Pangandaran) pada waktu ke-3080 detik (51 menit). Gelombang tsunami kemudian terrefleksikan sehingga gelombang muncul dari arah barat daya dan tenggara. Pada waktu ke-3360 detik (55 menit) 77 gelombang tsunami tiba di daratan pantai bagian barat Pangadaran (Desa Sukaresik dan Desa Cikembulan) dan daratan pantai timur Pangandaran (Desa Babakan). Hasil model penjalaran gelombang tsunami di wilayah pesisir Pangandaran (domain D) untuk skenario ke-1 diperlihatkan pada Gambar 24. 2600 detik 3080 detik 3360 detik 3600 detik Elevasi (m) Gambar 24. Simulasi penjalaran gelombang tsunami di pesisir Pangandaran (domain D) pada skenario ke-1 Berdasarkan catatan sejarah yang dilaporkan oleh IOC-ITIC (2006) dalam Summary of Event Information Timeline : July 17, 2006 Java, Indonesia Earthquake and Tsunami disampaikan bahwa pada menit ke-55 setelah terjadinya gempa, tsunami datang pertama kali dari arah sebelah barat daya. Hal ini memiliki kemiripan dengan model penjalaran tsunami yang telah dibangun. 78 Gelombang tsunami sudah tiba di sepanjang pantai Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih pada waktu kurang dari satu jam. Gelombang tsunami ini merendam sebagian kecil kawasan di sepanjang pantai. Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tsunami tersebut menjalar dari pusat gempa ke pantai secara keseluruhan membutuhkan waktu kurang dari satu jam setelah terjadinya gempa. Berdasarkan skenario yang dibangun dengan kekuatan gempa lebih besar dan posisi episentrum yang sama, maka dapat dilihat pada skenario ke-2 gelombang tsunami membutuhkan waktu 2480 detik (41 menit) untuk tiba pertama kali di bagian selatan Pangandaran. Gelombang tsunami kemudian datang dari arah barat daya dan tiba di pantai sebelah barat Pangandaran tepatnya di Desa Sukaresi pada detik ke-2840 (47 menit). Pada detik ke-3160 (52 menit) gelombang tsunami tiba di pesisir Desa Cikembulan, Desa Wonoharjo dan Desa Babakan serta terus merambat dari bagian barat daya Teluk Parigi sampai bagian tenggara Teluk Pangandaran. Gelombang tsunami tiba di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran pada detik ke-3240 (54 menit). Pada waktu ke-3600 detik (60 menit) gelombang tsunami sudah menerjang seluruh pantai di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih dan meredam lebih luas ke daratan disekitarnya. Pada skenario ke-2 ini waktu tempuh gelombang tsunami 2 – 3 menit lebih cepat dibandingkan gempa dengan kekuatan 7,7 SM. Keadaan ini menjelaskan bahwa pada posisi pusat gempa yang sama dengan kekuatan gempa yang berbeda, maka waktu tempuh gelombang tsunami mencapai ke pantai akan berbeda. Hal ini telah membuktikan bahwa semakin besar kekuatan gempa maka 79 waktu tempuh penjalaran tsunami untuk tiba di pantai akan semakin cepat. Semakin besar kekuatan gempa maka gelombang tsunami yang ditimbulkan akan semakin besar. Penjalaran gelombang tsunami untuk kasus skenario ke-2 diperlihatkan pada Gambar 25. 2480 detik 2840 detik 3160 detik 3600 detik Elevasi (m) Gambar 25. Simulasi penjalaran gelombang tsunami di pesisir Pangandaran (domain D) pada skenario ke-2 Model penjalaran gelombang tsunami untuk kasus pada skenario ke-3 menggunakan posisi sumber gempa yang berjarak lebih dekat terhadap pantai selatan Pangandaran. Jarak sumber tsunami terhadap pantai sekitar 165 km. Hasil model penjalaran tsunami yang dibangun memperlihatkan bahwa gelombang tsunami tiba pertama kali di selatan Pangandaran pada detik ke-2320 (39 menit). 80 Pada detik ke-2720 (45 menit) gelombang tsunami tiba di bagian barat Desa Sukaresik dan di bagian timur Desa Babakan. Gelombang tsunami kemudian bergerak ke timur dan tiba di Desa Cikembulan, Desa Wonoharjo dan bagian barat Desa Babakan pada detik ke-2960 (49 menit). Gelombang tsunami tiba di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran pada detik ke-3040 (50 menit). Pada detik ke3600 (60 menit) gelombang tsunami sudah menyebar keseluruh pantai di sepanjang garis pantai sebelah barat sampai ke timur. Model penjalaran gelombang tsunami untuk kasus skenario ke-3 ini dapat dilihat pada Gambar 26. 2320 detik 2720 detik 2960 detik 3600 detik Elevasi (m) Gambar 26. Simulasi penjalaran gelombang tsunami di pesisir Pangandaran (domain D) pada skenario ke-3 Gelombang tsunami pada skenario ke-3 ini memiliki kecepatan 2 – 3 menit lebih cepat dibandingkan dengan gempa yang dibangkitkan pada skenario 81 ke-2. Keadaan ini disebabkan oleh posisi sumber gempa yang cenderung lebih dekat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin dekat sumber gempa terhadap pantai maka waktu tempuh gelombang tsunami mencapai pantai akan semakin cepat. Berdasarkan hal tersebut maka daerah pantai yang mempunyai jarak yang semakin dekat dari sumber pembangkit tsunami akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai tingkat kerawanan bahaya tsunami yang tinggi, keadaan sebaliknya terjadi apabila daerah pantai memiliki jarak yang jauh terhadap sumber tsunami. Penjalaran gelombang tsunami untuk kasus terburuk dibangun pada skenario ke-4. Kasus terburuk yang dibangun pada model ini adalah kasus tsunami yang diakibatkan gempa berkekuatan 8,9 SM. Kekuatan gempa 8,9 SM merupakan kekuatan gempa yang pernah terjadi di Indonesia, gempa ini sekaligus merupakan peristiwa paling dasyat dan mengerikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Posisi pusat gempa pada skenario ke-4 berada di sebelah timur pusat gempa Pangandaran dengan jarak kurang lebih 310 km dari bagian selatan pantai Pangandaran. Skenario ini dibangun berdasarkan karakteristik gempa yang menimbulkan tsunami di Pancer (Banyuwangi) pada tahun 1994. Parameter sesar yang digunakan (dip, strike, slip) telah disesuaikan dengan keadaan sewaktu kejadian tsunami di Pancer, akan tetapi besarnya kekuatan gempa dan geomertri patahan dimodifikasi untuk mendapatkan keadaan yang lebih ekstrim. Penjalaran gelombang tsunami pada skenario ke-4 mengakibatkan gelombang tsunami menjalar dan mencapai bagian selatan Pangandaran pada waktu 2600 detik (43 menit). Gelombang tsunami kemudian tiba di bagian barat 82 Desa Sukaresik dan Bagian timur Desa Babakan pada detik ke-3000 (50 menit). Pada detik ke-3280 (55 menit) gelombang tsunami tiba di Desa Sukaresik, Wonoharjo dan bagian barat Desa Babakan. Satu jam setelah terjadi gempa, gelombang tsunami sudah menggenangi lebih jauh ke daratan. Model penjalaran gelombang tsunami untuk kasus skenario ke-4 disajikan pada Gambar 27. 2600 detik 3000 detik 3280 detik 3600 detik Elevasi (m) Gambar 27. Simulasi penjalaran gelombang tsunami di pesisir Pangandaran (domain D) pada skenario ke-4 Hasil model dari tiap skenario yang telah dibangun memperlihatkan bahwa gelombang tsunami awal akibat gempa bumi akan menjalar keseluruh arah. Perbedaan kontur kedalaman mengakibatkan gelombang tsunami mengalami pembelokan arah dan tinggi gelombang (refraksi). Arah datangnya tsunami di 83 daerah studi pertama kali datang dari arah selatan. Gelombang tsunami kemudian memasuki Teluk Pangandaran dari sisi barat daya dan Teluk Parigi dari sisi tenggara. Ketika memasuki Teluk Pangandaran dan Teluk Parigi gelombang tsunami menjadi terkurung karena memasuki wilayah berteluk, kemudian gelombang tsunami terefleksikan. Hal ini menyebabkan arah gelombang tsunami menyebar dan datang dari arah barat dan selatan serta timur perairan Pangandaran. Pada umumnya daerah yang pertama kali terkena limpasan gelombang tsunami adalah Tanjung Pangandaran yang letaknya di bagian selatan. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah yang paling depan dan menjorok ke laut lepas. Daerah yang selanjutnya paling awal terkena gelombang tsunami adalah pesisir barat Pangandaran (Desa Sukaresik) serta pesisir timur Pangandaran (Desa Babakan). Hal ini disebabkan perairan yang berbatasan dengan daerah tersebut memiliki kedalaman yang lebih besar dengan kelerengan dasar yang lebih curam jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Menurut Yudhicara (2008) karakteristik kontur batimetri demikian mengakibatkan gelombang tsunami akan memiliki kecepatan lebih besar dan lebih dulu tiba di lokasi tersebut. 4.3.4 Limpasan gelombang tsunami (run-up) Limpasan gelombang tsunami yang dihasilkan dari pemodelan tsunami untuk kasus skenario ke-1 pada umumnya masih dalam skala yang tidak terlalu luas. Hasil analisis berdasarkan measure tool pada perangkat lunak ArcGIS diketahui jarak limpasan gelombang tsunami yang masuk ke daratan Pangandaran berkisar antara 100 – 200 m dari garis pantai. Jarak limpasan maksimum gelombang tsunami ke daratan mencapai 200 m, dimana berada di Desa 84 Cikembulan. Hal ini berkolerasi dengan energi gelombang tsunami yang dibangkitkan pada skenario ini lebih kecil (7,7 SM). Keadaan ini menyebabkan penetrasi gelombang tsunami tidak cukup kuat untuk masuk lebih jauh ke daratan. Peta area limpasan tsunami untuk kasus skenario ke-1 disajikan pada Gambar 28. Gambar 28. Limpasan gelombang tsunami di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-1 Berdasarkan model yang dibangun pada skenario ke-1 total luas area yang tergenang tsunami untuk Kecamatan Pangandaran mencapai 225,60 Ha sedangkan untuk Kecamatan Sidamulih mencapai 105,68 Ha. Desa yang paling luas terkena limpasan gelombang tsunami adalah Desa Pangandaran. Luas area limpasan di Desa Pangandaran adalah 115,34 Ha. Limpasan tsunami yang menggenangi Desa Pangandaran mencapai 16,78% dari luas total daratannya. Hal ini dikarenakan kondisi daratan dan kemiringan daratannya sangat rendah sehingga dengan demikian penetrasi gelombang tsunami lebih mudah masuk sampai ke daratan. Desa Wonoharjo merupakan desa yang memperoleh limpasan paling rendah yaitu 85 hanya 5,43% dari keseluruhan daratannya. Luas area limpasan gelombang tsunami untuk setiap desa di wilayah penelitian selengkapnya disajikan pada Tabel 12. Tabel 12. Luas area limpasan tsunami di setiap desa pada skenario ke-1 Luas Luas Persentase daratan limpasan limpasan No Kecamatan Desa (Ha) (Ha) (%) 1 Pangandaran Babakan 638,58 56,64 8,87 2 Pangandaran Pananjung 360,47 21,08 5,85 3 Pangandaran Pangandaran 687,22 115,34 16,78 4 Pangandaran Wonoharjo 599,54 32,54 5,43 5 Sidamulih Sukaresik 844,51 68,73 8,14 6 Sidamulih Cikembulan 495,03 36,95 7,46 Pada kejadian tsunami Pangandaran 2006, wilayah yang paling luas terkena limpasan tsunami adalah Desa Cikembulan dan Desa Pangandaran (Kongko et al., 2006). Hasil model yang telah dibangun memperlihatkan hal yang serupa dengan kejadian sebenarnya. Keadaan yang berbeda terlihat pada jarak limpasan tsunami ke daratan. Menurut hasil pengukuran lapang diketaui bahwa jarak limpasan tsunami ke daratan mencapai 300 – 500 m (Kongko et al., 2006). Hasil model pada umumnya menghasilkan jarak limpasan yang lebih kecil dari kejadian yang sebenarnya. Pebedaan tersebut disebabkan karena tsunami Pangandaran termasuk kedalam jenis Tsunami Earthquake atau beberapa ilmuwan menyebutnya Slow Earthquake. Gempa tersebut hampir tidak terasa getarannya, tetapi tsunami yang dihasilkan jauh lebih besar seperti dibangkitkan oleh gempa yang lebih besar dari kekuatan gempa yang terukur saat itu (Ginanjar, 2010). Berdasarkan wawancara penulis dengan penduduk, mulai dari kawasan Cikembulan sampai Pananjung banyak penduduk yang sama sekali tidak merasakan getaran gempa sebelum terjadinya tsunami di Pangandaran tahun 2006 lalu, sehingga banyak yang tidak menyangka akan terjadi tsunami. Menurut 86 Ginanjar (2010), Tsunami Earthquake atau Slow Earthquake memiliki karakteristik getaran gempa yang lambat (slow shaking) yang dapat menimbulkan tsunami. Sifat slow shaking ini memberikan respon terhadap dinamika air yang lebih besar daripada getaran yang cepat (fast shaking). Respon besar inilah yang dapat membangkitkan gelombang tsunami. Getaran yang lambat ini salah satunya dapat disebabkan oleh tebalnya sedimen di sekitar pusat gempa di laut yang memberikan efek lubrikasi ketika gempa terjadi. Selain hal yang disebutkan di atas, perbedaan jarak limpasan tsunami diakibatkan pula oleh adanya arrival time yang dihasilkan model hanya didasarkan atas waktu pacu model selama 3 jam. Hal ini disebabkan tidak adanya data historis tsunami yang mencatat tsunami run-down (surutnya kembali gelombang tsunami) ketika kejadian tsunami di Pangandaran. Pada dasarnya model tsunami Tohoku University yang digunakan pada penelitian ini memiliki akurasi yang baik. Hal ini telah dibuktikan dengan pengukuran data tide gauge oleh peneliti BMG yang kemudian dibandingkan dengan hasil model. Hasil penelitian tersebut menghasilkan akurasi yang mencapai +1 (100%) (Gunawan, 2007). Salah satu kelemahan model tsunami ini adalah belum mampu memperhitungkan model tsunami dengan tipe Tsunami Earthquake. Gempa berkekuatan lebih besar (8,5 SM) yang diterapkan pada skenario ke-2 menghasilkan jarak limpasan tsunami yang lebih luas dibandingkan gempa berkekuatan 7,7 SM pada posisi pusat gempa yang sama. Jarak limpasan gelombang tsunami yang masuk ke daratan Pangandaran pada umumnya berkisar antara 400 – 1000 m dari garis pantai. Jarak limpasan maksimum gelombang 87 tsunami mencapai daratan adalah 1550 m dari garis pantai, sedangkan jarak limpasan minimum gelombang tsunami adalah 400 m (Gambar 29). Daerah yang paling jauh terkena limpasan dan genangan gelombang tsunami adalah Desa Sukaresik dan Desa Babakan. Penetrasi gelombang tsunami terjauh di Desa Sukaresik mencapai 1000 m, sedangkan di Desa Babakan jarak limpasan terjauh gelombang tsunami adalah 1550 m. Dampak tsunami pada skenario ke-2 yang dibangkitkan oleh gempa berkekuatan 8,5 SM menghasilkan area genangan yang lebih luas. Gambar 29. Limpasan gelombang tsunami di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-2 Total luas area yang tergenang gelombang tsunami di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih masing-masing adalah 907,34 Ha dan 452,45 Ha. Luas area genangan tsunami terbesar pada skenario ke-2 terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Gelombang tsunami di desa ini menggenangi setengah dari total luas daratannya. Desa Babakan merupakan daerah pesisir yang berada di bagian sebelah timur. Berdasarkan model yang 88 dibangun, ketinggian tsunami di bagian timur Pangandaran sangat tinggi, sehingga penetrasi gelombang tsunami cukup kuat untuk masuk lebih jauh ke daratan. Desa Sukaresik dan Cikembulan yang berada di bagian barat Pangandaran mengalami hal serupa. Ketinggian tsunami di lokasi ini maksimum sehingga luas area genangan di kedua desa ini juga sangat besar. Daratan Desa Cikembulan tergenang gelombang tsunami dengan persentase 34,84% dari total luas daratannya. Keadaan ini menyebabkan Desa Cikembulan menjadi daerah yang paling luas terkena limpasan gelombang tsunami untuk Kecamatan Sidamulih. Informasi selengkapnya mengenai luas limpasan tsunami pada skenario ke-2 disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Luas area limpasan tsunami di setiap desa pada skenario ke-2 Luas Luas Persentase No Kecamatan Desa daratan limpasan limpasan (Ha) (Ha) (%) 1 Pangandaran Babakan 638,58 363,15 56,87 2 Pangandaran Pananjung 360,47 108,20 30,02 3 Pangandaran Pangandaran 687,22 323,75 47,11 4 Pangandaran Wonoharjo 599,54 112,24 18,72 5 Sidamulih Sukaresik 844,51 279,97 33,15 6 Sidamulih Cikembulan 495,03 172,48 34,84 Penjalaran gelombang tsunami akibat gempa yang dibangun pada skenario ke-3 menjalar ke daerah pesisir yang lebih luas jika dibandingkan dengan dua skenario sebelumnya. Jarak limpasan gelombang tsunami yang masuk ke daratan Pangandaran pada umumnya berkisar antara 450 – 1000 m dari garis pantai. Jarak limpasan maksimum gelombang tsunami mencapai daratan adalah 1800 m dimana terjadi di Desa Babakan. 89 Daratan di Desa Pangandaran hampir seluruhnya terkena genangan akibat limpasan gelombang tsunami. Hal ini di sebebabkan karena topografi daratannya yang datar dan landai. Selain itu juga disebakan oleh adanya hempasan gelombang dari dua arah yang berbeda, yakni gelombang tsunami yang datang dari bagian barat dan timur. Kawasan selatan Pangandaran yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia mengalami limpasan yang tidak begitu luas karena faktor topografi wilayah tersebut yang berbukit. Kondisi daratan berbukit akan meminimalisir jangkauan tsunami ke daratan. Peta area limpasan tsunami untuk kasus skenario ke-3 disajikan pada Gambar 30. Gambar 30. Limpasan gelombang tsunami di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-3 Daerah yang paling luas terlanda gelombang tsunami untuk kasus pada skenario ke-3 masih sama seperti skenario-skenario sebelumnya yaitu Desa Babakan. Pada kasus skenario ke-3 yang dibangun oleh pusat gempa yang paling dekat dengan pantai mengakibatkan luas daerah genangan tsunami di Desa Babakan bertambah sebesar 95,14 Ha sehingga total luas genangannya menjadi 90 458,9 Ha. Keadaan yang serupa terjadi di desa-desa yang lainnya, seluruhnya mengalami peningkatan luas area genangan. Hal tersebut menggambarkan bahwa faktor jarak sumber gempa terhadap daratan sangat mempengaruhi besarnya tsunami yang dihasilkan. Informasi luasan limpasan gelombang tsunami untuk skenario ke-3 dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Luas area limpasan tsunami di setiap desa pada skenario ke-3 Luas Luas Persentase No Kecamatan Desa daratan limpasan limpasan (Ha) (Ha) (%) 1 Pangandaran Babakan 638,58 458,29 71,77 2 Pangandaran Pananjung 360,47 139,13 38,60 3 Pangandaran Pangandaran 687,22 343,88 50,04 4 Pangandaran Wonoharjo 599,54 158,56 26,45 5 Sidamulih Sukaresik 844,51 327,65 38,80 6 Sidamulih Cikembulan 495,03 215,65 43,56 Penjalaran gelombang tsunami akibat gempa berkekuatan 8,9 SM mampu menggenangi kawasan pesisir Pangandaran sampai beratus-ratus meter jauhnya dari garis pantai. Keadaan ini mengindikasikan bahwa gelombang tsunami yang yang dibangkitkan oleh kekuatan lebih besar akan lebih jauh menjalar sampai daratan pesisir yang lebih luas. Jarak limpasan gelombang tsunami terjauh pada skenario ke-4 adalah 2550 m. Daerah yang terlanda dengan jarak jangkauan tsunami tersebut adalah Desa Cikembulan dan Desa Babakan. Pada umumnya jarak limpasan gelombang tsunami ke daratan mencapai 1500 m di sepanjang wilayah yang dimodelkan. Beberapa daerah seperti Desa Pangandaran, Pananjung dan Babakan merupakan desa-desa yang hampir seluruh daratannya tergenang gelombang tsunami. Peta area genangan tsunami untuk kasus skenario ke-4 disajikan pada Gambar 31. 91 Gambar 31. Limpasan gelombang tsunami di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-4 Total luas area genangan tsunami untuk Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih pada skenario ini masing-masing seluas 1.690,04 Ha dan 883,48 Ha (Tabel 14). Jangkauan limpasan tsunami yang dibangkitkan gempa berkekuatan 8,9 SM ini meluas hingga ke beberapa desa. Beberapa desa yang sebelumnya tidak terkena limpasan tsunami seperti Desa Pejanten, Desa Purbahayu dan Desa Sukahurip pada skenario ini daerah-daerah tersebut ikut terkena dampak limpasan gelombang tsunami. Desa Babakan dan Desa Pananjung merupakan daerah yang paling luas terkena limpasan tsunami yaitu sekitar 94,56% dari total luas daratan Desa Babakan dan 96,17% dari total luas daratan Desa Pananjung. Kedua Desa ini hampir seluruh daratannya tergenang gelombang tsunami. Hal yang serupa dialami pada Desa Pangandaran, daratan yang menghubungkan daratan pulau jawa dengan tanjung Pangandaran (tanah genting) seluruhnya tergenang gelombang tsunami. 92 Pada umumnya desa-desa yang langsung berbatasan dengan laut hampir seluruhnya terkena limpasan gelombang tsunami yang paling tinggi. Desa-desa yang tidak berbatasan secara langsung dengan laut seperti Desa Pejanten, Desa Purbahayu dan Desa Sukahurip terkena limpasan dalam skala kecil. Informasi selengkapanya disajikan pada Tabel 15. Tabel 15. Luas area limpasan tsunami di setiap desa pada skenario ke-4 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Sidamulih Sidamulih Sidamulih Desa Babakan Pananjung Pangandaran Purbahayu Sukahurip Wonoharjo Cikembulan Pejanten Sukaresik Luas daratan (Ha) 638,58 360,47 687,22 1.012,32 1.433,05 599,54 495,03 606,73 1.433,05 Luas Persentase limpasan limpasan (Ha) (%) 603,82 94,56 346,66 96,17 375,20 54,60 4,77 0,47 11,25 0,79 348,34 58,10 396,80 80,16 52,70 8,69 433,98 30,29 Setiap wilayah memiliki jarak jangkauan dan luas genangan gelombang tsunami yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan di masing-masing wilayah tersebut serta besarnya kekuatan gempa yang menjadi sumber tsunami. Jika kerentanan lingkunganya tinggi, maka akan mudah untuk terpapar tsunami sehingga risikonya akan lebih besar. Desa-desa yang berada di sepanjang pantai dan pesisir Kecamatan Pangandaran serta Kecamatan Sidamulih pada umumnya didominasi oleh topografi dan kemiringan daratan yang rendah dan landai, dengan keadaan morfologi seperti itu maka jelas daerah-daerah tersebut terkena dampak yang paling parah dibandingkan daerahdaerah yang lainnya. 93 4.3.5 Ketinggian rendaman tsunami (Flowdepth) Klasifikasi kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami (flowdepth) dibangun untuk melihat tingkat bahayanya. Pada kasus skenario ke-1 ketinggian rendaman tsunami berkisar antara 0,5 – 2,7 m. Ketinggian rendaman tsunami cenderung lebih besar di daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Keadaan ini dikarenakan daerah tersebut mengalami dampak gelombang tsunami secara langsung. Berdasarkan hasil klasifikasi tingkat kerawanan terhadap ketinggian rendaman tsunami diketahui bahwa ketinggian rendaman tsunami pada skenario ke-1 menghasilkan tingkat kerawanan tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Peta kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami yang dibangkitkan oleh gempa berkekuatan 7,7 SM disajikan pada Gambar 32. Gambar 32. Kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami (flowdepth) di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-1 Daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berada di sepanjang pantai Kecamatan Sidamuli dan Kecamatan Pangandaran. Pada umumnya sebagian besar 94 tinggi rendaman tsunami yang dibangkitkan oleh gempa berkekuatan 7,7 SM tergolong sangat rendah, dimana ketinggian rendamanya rata-rata lebih kecil dari 0,5 m. Hal ini dapat diketahui dari luasan rendaman tsunami dengan kelas ketinggian rendaman 0 – 0,5 m memiliki luas area yang paling besar (Tabel 16). Keadaan ini menandakan bahwa tsunami yang diakibatkan gempa berkekuatan 7,7 SM tidak begitu membahayakan, dengan kata lain tingkat kerawanan pantai sangat rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kerusakan di wilayah pesisir Pangandaran. Secara lengkap mengenai luasan kelas ketinggian rendaman tsunami untuk setiap desa di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih disajikan pada Tabel 16. Tabel 16. Luasan kelas ketinggian rendaman tsunami di setiap desa pada skenario ke-1 Luas area kelas ketinggian rendaman tsunami (Ha) Nama Desa 0 – 0,5 m 0,5 – 1,5 m 1,5 – 2,5 m 2,5 – 2,7 m > 2,7 m Babakan 38,62 18,02 0 0 0 Pananjung 14,97 6,11 0 0 0 Pangandaran 53,40 57,32 3,68 0,94 0 Wonoharjo 20,11 12,43 0 0 Sukaresik 41,10 27,63 0 0 0 Cikembulan 21,87 15,08 0 0 0 Total 190,07 136,59 3,68 0,94 0 Hasil model yang dibangun pada skenario ke-2 menghasilkan ketinggian rendaman tsunami yang lebih besar dibandingkan skenario sebelumnya. Pada kasus skenario ke-1 ketinggian rendaman tsunami berkisar antara 0,5 – 7 m. Ketinggian rendaman tsunami cenderung maksimum pada jarak 100 m dari garis pantai menuju daratan (Gambar 33). Ketinggian rendaman tsunami semakin menurun seiring semakin jauh dari garis pantai menuju daratan. Keadaan ini disebabkan keadaan topografi daratan yang semakin meningkat. 95 Pada umumnya sebagian besar tinggi rendaman tsunami untuk kasus tsunami pada skenario ke-2 didominasi oleh kelas ketinggian redaman 2,5 – 5 m. Luasan rendaman tsunami dengan kelas ketinggian rendaman 2,5 – 5 m mencapai 452,82 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya ketinggian rendaman tsunami tergolong tinggi. Keadaan ini mengakibatkan wilayah pesisir Pangandaran memiliki tingkat kerawanan yang tinggi apabila terjadi tsunami yang diakibatkan gempa berkekuatan 8,5 SM. Kelas kerawanan tinggi merupakan daerah yang berisiko tinggi terhadap tsunami dan menjadi zona berbahaya untuk dijadikan kawasan permukiman ataupun aktivitas kependudukan. Gambar 33. Kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami (flowdepth) di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-2 Desa Pangandaran dan Desa Sukaresik merupakan daerah yang paling luas digenangi tsunami dengan kelas ketinggian rendaman 2,5 – 5 m, sehingga kedua desa ini tergolong memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ketinggian limpasan 96 tsunami untuk daerah di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih dominan digenangi tsunami dengan ketinggian 2,5 – 5 m, sedangkan ketinggian genangan tsunami > 5 m (tingkat kerawanan tsunami sangat tinggi) paling sedikit menggenangi lokasi kajian (Tabel 17). Tabel 17. Luasan kelas ketinggian rendaman tsunami di setiap desa pada skenario ke-2 Luas area kelas ketinggian rendaman tsunami (Ha) Nama Desa 0 – 0,5 m 0,5 – 1,5 m 1,5 – 2,5 m 2,5 – 5 m >5m Babakan 52,35 120,56 90,57 99,42 0,25 Pananjung 20,61 43,73 25,93 17,93 0 Pangandaran 13,85 51,09 69,76 138,28 50,77 Wonoharjo 19,70 27,59 34,56 30,39 0 Sukaresik 35,69 76,50 48,87 105,32 13,59 Cikembulan 25,53 40,75 44,10 61,48 0,62 Total 167,73 360,22 313,79 452,82 65,23 Hasil analisis dari model yang dibangun pada skenario ke-3 memperlihatkan ketinggian rendaman tsunami di setiap daerah mengalami peningkatan. Pada umumnya desa-desa di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih paling luas tergenangi gelombang tsunami dengan ketinggian 2,5 – 5 m. Hal ini menjadikan wilayah tersebut terggolong kedalam kelas yang memiliki kerawanan yang tinggi terhadap bencana tsunami. Pada umumnya daerah yang digenangi tsunami dengan ketinggian paling tinggi berada di sepanjang pantai Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Semakin jauh dari arah pantai ketinggian rendaman tsunami berangsur-angsur mengalami penurunan. Kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami untuk skenario ke-3 diperihatkan pada Gambar 34. Desa Pangandaran merupakan daerah yang paling luas tergenang gelombang tsunami dengan ketinggian 2,5 – 5 m. Luas area di daerah tersebut yang digenangi dengan ketinggian 2,5 – 5 m mencapai 156,56 Ha. Selain itu Desa 97 Pangandaran digenangi tsunami dengan ketinggian lebih besar dari 5 m, dimana luasnya mencapai 118,39 Ha. Keadaan ini menjadikan Desa Pangandaran memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi mengingat daerah tersebut memiliki populasi yang tinggi. Gambar 34. Kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami (flowdepth) di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-3 Hasil analisis terhadap ketinggian genangan tsunami memperlihatkan kelas yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi memiliki cakupan yang lebih luas. Tempat kedua yang memiliki cakupan paling luas adalah tingkat kerawanan sedang, disusul tingkat kerawanan rendah dan terakhir adalah tingkat kerawanan sangat tinggi dan sangat rendah. Tsunami yang diakibat gempa berkekuatan 8,5 SM dan memiliki episentrum paling dekat dengan daratan mengakibatkan wilayah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran tergolong kedalam kelas dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Informasi mengenai luasan kelas 98 ketinggian rendaman tsunami untuk setiap desa di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih secara lengkap disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Luasan kelas ketinggian rendaman tsunami di setiap desa pada skenario ke-3 Luas area kelas ketinggian rendaman tsunami (Ha) Nama Desa 0 – 0,5 m 0,5 – 1,5 m 1,5 – 2,5 m 2,5 – 5 m >5m Babakan 60,57 99,26 133,85 147,06 17,55 Pananjung 17,02 40,04 40,05 42,02 0 Pangandaran 8,79 21,67 38,47 156,56 118,39 Wonoharjo 23,02 47,05 31,08 55,92 1,49 Sukaresik 32,13 69,02 71,76 109,39 45,35 Cikembulan 25,92 53,46 44,33 81,77 10,17 Total 167,45 330,50 359,72 592,72 192,95 Prediksi tsunami yang dibangkitkkan oleh gempa yang berkekuatan 8,9 SM menunjukan tingkat kerawanan yang jauh lebih besar. Dapat dilihat bahwa daerah berwarna merah yang menunjukan daerak dengan tingkat kerawanan sangat tinggi meluas dari skenario-skenario sebelumnya. Semakin tinggi dan luas rendaman tsunami di daratan, maka tingkat kerentanan terhadap bahaya tsunami semakin besar. Semakin besar tingkat kerentanan, maka semakin besar risikonya dan sebaliknya. Terjadinya bencana tsunami akibat gempa tersebut menjadikan kawasan di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Luas limpasan tsunami tertinggi yang dibangun pada skenario ke-4 berada pada kelas ketinggian rendaman tsunami lebih besar dari 5 m. Tempat kedua berada pada kelas ketinggian rendaman tsunami 2,5 – 5 m, sedangkan luas limpasan tsunami paling rendah berada pada kelas ketinggian redaman tsunami kurang dari 0,5 m. Besarnya kekuatan gempa yang menjadi sumber tsunami mempengaruhi ketinggian rendaman tsunami di daratan. Kelas ketinggian rendaman tsunami di wilayah kajian untuk skenario ini disajikan pada Gambar 35. 99 Gambar 35. Kelas ketinggian rendaman gelombang tsunami (flowdepth) di berbagai lokasi pesisir Pangandaran pada skenario ke-4 Mengacu pada Tabel 18 diketahui bahwa daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran secara umum memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi apabila terjadi tsunami yang diakibatkan gempa berkekuatan 8,9 SM. Desa yang tergolong memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi terbesar berada di Desa Pangandaran, Desa Babakan, Desa Cikembulan dan Desa Sukaresik. Pada umumnya daerah yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi berada pada jarak 500 m dari arah pantai sedangkan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berada pada jarak 100 m dari arah pantai. Secara keseluruhan, tsunami yang dibangkitkan oleh gempa berkekuatan 8,9 SM akan mengakibatkan kerawanan yang sangat tinggi untuk daerah-daerah yang berada di sekitar pantai dan pesisir Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Luas kelas ketinggian rendaman tsunami di setiap desa pada skenario ke-4 ini secara lengkap disajikan pada Tabel 19. 100 Tabel 19. Luasan kelas ketinggian rendaman tsunami di setiap desa pada skenario ke-4 Nama Desa Babakan Pananjung Pangandaran Purbahayu Sukahurip Wonoharjo Cikembulan Pejanten Sukaresik Total 4.4. Luas area kelas ketinggian rendaman tsunami (Ha) 0 – 0,5 m 0,5 – 1,5 m 1,5 – 2,5 m 2,5 – 5 m >5m 8,68 30,35 56,30 229,00 279,49 15,82 52,97 73,43 126,88 77,56 6,93 9,72 8,89 39,84 309,82 1,66 2,78 0,33 0 0 4,04 7,01 0,20 0 0 45,36 58,98 62,81 120,66 60,53 14,43 30,67 54,27 170,90 126,53 25,55 26,03 1,12 0 0 22,75 60,15 73,60 145,05 132,43 145,22 278,66 330,95 832,33 986,36 Integrasi (Overlay) Morfologi Pantai dengan Model Tsunami Topografi yang relatif rendah merupakan wilayah dengan kelas kerentanan yang sangat tinggi. Hal ini akan lebih berpotensi untuk digenangi tsunami dalam skala luas di bandingkan daerah yang memiliki topografi lebih tinggi. Rendahnya topografi daratan mempengaruhi seberapa luas masuknya tsunami ke daratan. Keadaan ini telah terbukti, dimana berdasarkan hasil pemodelan diketahui daerah limpasan tsunami paling luas berada di daerah yang bertopografi rendah. Hasil overlay elevasi daratan (topografi) dengan model limpasan tsunami menunjukan bahwa pengaruh topografi terhadap luasan limpasan tsunami dapat dilihat pada Tabel 20. Berdasarkan Tabel 20, diketahui model yang dibangun baik pada skenario ke-1 sampai skenario ke-4 menunjukan kelas ketinggian daratan kurang dari 10 m adalah kelas yang paling banyak terkena limpasan gelombang tsunami. Topografi rendah memberikan limpasan tsunami dengan mudah sehingga mencapai ratusan meter. Hal ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki topografi yang relatif rendah lebih berpotensi untuk digenangi tsunami lebih luas dibandingkan daerah 101 yang memiliki topografi lebih tinggi. Kelas elevasi daratan lebih besar dari 50 m sama sekali tidak terkena limpasan gelombang tsunami. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki elevasi daratan lebih besar dari 50 m merupakan kawasan yang aman dari terjangan gelombang tsunami. Tabel 20. Luas area limpasan tsunami pada kelas elevasi daratan (topografi) Luas area limpasan tsunami (Ha) Kelas elevasi (m) Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 < 10 331,28 1.329,64 1.580,00 2.488,83 10 – 25 0 30,15 61,66 82,57 25 – 50 0 0 1,50 2,12 50 – 100 0 0 0 0 > 100 0 0 0 0 Total 331,28 1.359,79 1.643,16 2.573,52 Hasil overlay antara kemiringan daratan dengan model limpasan tsunami menghasilkan informasi bahwa limpasan tsunami terluas berada pada kelas kemiringan daratan kurang dari 2%. Luas limpasan tsunami terluas kedua berada pada kelas kemiringan daratan 2 – 10 % (Tabel 21). Hal tersebut membuktikan bahwa limpasan gelombang tsunami akan lebih luas merendam daratan pada daerah dengan kemiringan landai atau datar. Daerah tersebut akan berpotensi mengalami genangan gelombang tsunami lebih jauh ke arah darat. Pada pantai yang terjal atau curam, tsunami tidak akan terlalu jauh mencapai daratan karena tertahan dan dipantulkan kembali oleh tebing pantai (Oktariadi, 2009b). Tabel 21. Luas area limpasan tsunami pada kelas kemiringan daratan (slope) Luas area limpasan tsunami (Ha) Kelas slope (%) Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 <2 331,28 1.339,69 1603,16 2497,99 2 – 10 0 20,10 40,00 75,53 10 – 15 0 0 0 0 15 – 40 0 0 0 0 > 40 0 0 0 0 Total 331,28 1.359,79 1.643,16 2.573,52 102 Tabel 22 menyajikan luasan limpasan gelombang tsunami pada kelas jarak dari pantai. Berdasarkan tabel tersebut diketahui daerah yang berada dalam jarak 500 meter merupakan daerah yang paling luas terkena limpasan gelombang tsunami. Daerah yang semakin dekat dengan pantai merupakan daerah yang paling rentan dan begitu pula sebaliknya. Daerah yang terdekat dengan pantai akan mendapatkan dampak secara langsung dari gelombang tsunami. Hasil pemodelan yang dibangun dengan skenario paling ekstrim menghasilkan jarak limpasan tsunami di Pangandaran sejauh ± 3000 m. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang berda dalam jarak kurang dari 3000 m dari garis pantai merupakan daerah yang masih mendapat pengaruh dari limpasan gelombang tsunami. Daerah yang aman merupakan daerah yang terletak dalam jarak lebih dari 3000 m dari garis pantai. Tabel 22. Luas area limpasan tsunami pada kelas jarak dari garis pantai Kelas jarak Luas area limpasan tsunami (Ha) dari pantai Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 (m) 500 390,24 1.044,34 1.018,55 1.520,09 500 – 1000 0 227,37 450,26 550,26 1000 – 1500 0 53,34 166,46 168,45 1500 – 3000 0 1,08 7,89 334,72 > 3000 0 0 0 0 Total 331,28 1.359,79 1.643,16 2.573,52 Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tsunami terhadap masing-masih penggunaan lahan tidak sama. Hal ini karena masing-masing jenis penggunaan lahan memiliki tingkat reduksi tertentu saat terkena gelombang tsunami. Tabel 23 menunjukan hubungan kelas penggunaan lahan yang terkena limpasan tsunami dengan kelas luasan genangan tsunami. Kelas permukiman menjadi kelas pertama dalam penentuan area rawan tsunami. Hal ini disebabkan karena area permukiman 103 merupakan lahan yang paling penting dan akan menjadi rawan tsunami apabila area tersebut terkena tsunami. Tabel 23. Luas area limpasan tsunami pada kelas penggunaan lahan Jenis penggunaan lahan Danau Empang/Tambak Ladang/Teggalan Lahan kosong Perkebunan Permukiman Sawah Semak belukar Vegetasi darat Total Luas area limpasan tsunami (Ha) Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 0 0 0 2,78 0 15,57 30,17 85,73 0 10,80 12,14 23,48 50,89 103,06 142,84 212,31 16,80 212,51 259,09 344,12 85,60 376,55 466,98 713,23 0 51,2 101,85 230,77 110,20 286,62 315,54 350,92 62,93 298,40 303,69 605,32 331,28 1.359,79 1.643,16 2.573,52 Kelas penggunaan lahan yang paling luas terkena gelombang tsunami adalah kelas permukiman. Luas genangan tsunami terhadap permukiman untuk kasus skenario ke-1 sampai skenario ke-4 berturut-turut luasnya adalah 85,60 Ha, 376,55 Ha, 466,98 Ha dan 713,23 Ha. Keadaan ini mengindikasikan bahwa permukiman yang berada di wilayah Pangandaran sangat rawan dan rentan terkena hempasan gelombang tsunami. Jenis penggunaan lahan yang sangat vital terkena limpasan gelombang tsunami selain permukiman adalah empang/tambak dan sawah. Hal ini mengingat kedua jenis penggunaan lahan tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pada dasarnya empang/tambak dan sawah merupakan bagian dari aset dan aktivitas penduduk di wilayah Pangandaran dalam menunjang kehidupan penduduk sekitar sehingga apabila kedua jenis penggunaan lahan ini terkena tsunami akan sangat merugikan. Kebun atau perkebunan di wilayah Pangandaran juga tak lepas dari limpasan gelombang tsunami. Hal ini menunjukan bahwa 104 perkebunan di wilayah pangandaran berada di area yang memiliki topografi yang rendah. Pada umumnya perkebunan di wilayah Pangandaran di dominasi oleh perkebunan kelapa. 4.5. Indeks Kerentanan Pantai Akibat Bencana Tsunami Klasifikasi tingkat kerentanan pantai terhadap bencana tsunami membagi daerah menjadi lima kelas berdasakan tingkat kerentanan pantainya. Klasifikasi tersebut terdiri dari kelas kerentanan sangat rendah, kelas kerentanan rendah, kelas kerentanan sedang, kelas kerentanan tinggi dan kelas kerentanan sangat tinggi. Kelas kerentanan sangat rendah dan kelas kerentanan rendah dominan berada di bagian utara Pangandaran. Kedua kelas ini juga ditemukan berada di bagian selatan Pangandaran tepatnya di bagian Tanjung Pangandaran (Cagar Alam). Kelas kerentanan sedang dominan berada di bagian tengah wilayah penelitian. Zona ini berada pada jarak 3000 m dari garis pantai. Kelas kerentanan tinggi dan kelas kerentanan sangat tinggi umumnya berada di wilayah selatan Pangandaran. Zona ini berbatasan langsung dengan laut dimana jarak daratan sangat dekat dengan laut. Hal tersebut berdampak pada pengaruh langsung terhadap gelombang tsunami. Gradasi warna merah menunjukan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan sangat tinggi, sedangkan gradasi warna jingga menjelaskan zona kerentanan sedang, rendah dan sangat rendah. Zona kerentanan sangat tinggi merupakan daerah yang berpotensi paling besar dalam hal kerusakan atau kehancuran aset yang ditimbulkan apabila terlanda tsunami serta memiliki ancaman teradap risiko keselamatan penduduk yang lebih parah. Karakteristik 105 pantai dan pesisir di zona ini di tandai oleh dataran rendah yang landai dengan jarak dari pantai yang sangat dekat, berbatasan dengan sungai-sungai besar yang dekat dengan muaranya, selain itu ditambah dengan bentuk penggunaan lahan berupa permukiman dengan penduduk yang cukup padat. Sebaran spasial klasifikasi tingkat kerentanan wilayah Pangandaran diperlihatkan pada Gambar 36. Gambar 36. Sebaran spasial tingkat kerentanan pantai terhadap bencana tsunami di Pangandaran Zona kerentanan tinggi dan sangat tinggi umumnya berbatasan langsung dengan laut. Kedua kelas tersebut tergolong zona berbahaya terhadap limpasan gelombang tsunami. Zona kerentanan tinggi dan sangat tinggi pada umumnya berada pada jarak 1000 m dari garis pantai kecuali di bagian Tanjung Pangandaran. Wilayah Tanjung Pangandaran berbatasan secara langsung dengan laut dan berada dalam raidius 1000 m dari garis pantai, akan tetapi tingkat kerentanan di wilayah tersebut di dominasi oleh kelas kerentanan sangat rendah 106 dan kelas kerentanan rendah. Keadaan ini disebabkan morfologi wilayahnya yang betopogafi tinggi dengan slope yang besar dan tipe penggunaan lahan berupa vegetasi darat (hutan). Zona kerentanan sangat rendah merupakan daerah daerah paling aman atau sangat tahan terhadap bencana tsunami. Zona kerentanan sangat rendah ditandai oleh dataran tinggi atau berbukit dimana memiliki jarak yang paling jauh dari garis pantai serta tipe penggunaan lahan tidak banyak melibatkan manusia seperti lahan kosong, semak belukar dan vegetasi darat/hutan berada pada daerah yang aman. Desa Babakan, Desa Pangandaran dan Desa Cikembulan merupakan wilayah yang di dominasi oleh kelas kerentanan sangat tinggi. Wilayah-wilayah tersebut digolongkan sebagai wilayah yang paling berbahaya terhadap limpasan gelombang tsunami. Bentuk morfologi daerah pantai dan pesisirnya memberikan pengaruh yang tinggi terhadap risiko bencana sunami. Hal ini akan berdampak pada tingkat kerusakan yang lebih tinggi di wilayah-wilayah tersebut (Zona Bahaya Tsunami I). Desa Sukaresik dan Desa Pananjung di dominasi oleh tingkat kerentanan tinggi. Desa-desa ini menjadi daerah dengan peringkat kedua yang memiliki risiko kerusakan tertinggi (Zona Bahaya Tsunami II). Desa Wonoharjo di dominasi oleh tingkat kerentanan sedang sehingga Desa Wonoharjo digolongkan kedalam Zona Bahaya Tsunami III. Wilayah yang letaknya tidak berbatasan langsung dengan laut cenderung memiliki kerentanan yang rendah dan sangat rendah. Desa-desa yang tergolong dalam kelas tersebut antara lain Desa Cikalong, Sidamulih, Pejanten, Sidomulyo, Purbahayu, Sukahurip. Daerah ini berada dalam jangkauan lebih dari 3000 m dari garis pantai, sehingga penetrasi 107 gelombang tsunami tidak cukup kuat untuk masuk kedaratan sejauh itu (Gambar 36). Topografi di daerah tersebut juga memberikan pengaruh teradap penjalaran gelombang tsunami, topografi di daerah ini cenderung lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa terjal dan landainya morfologi pantai akan mempengaruhi jangkauan tsunami yang menghempasnya. Luas masing-masing kelas kerentanan di setiap wilayah disajikan pada Tabel 24. Tabel 24. Luas tingkat kerentanan pantai terhadap bencana tsunami di setiap desa Luas area tingkat kerentanan (Ha) Nama Desa Sangat Sangat Tinggi Sedang Rendah tinggi rendah Babakan 335,55 284,39 45,38 12,93 0 Cikalong 0 0 59,65 276,18 4,05 Cikembulan 227,22 135,67 104,34 155,59 0 Pananjung 106,13 203,36 50,92 10,61 0 Pangandaran 203,11 133,19 36,23 166,58 299,31 Pejanten 0 7,60 134,64 484,45 3,57 Purbahayu 0 0,33 60,10 296,03 200,76 Sidamulih 0 0 0 0,53 10,40 Sidomulyo 0 0 81,84 246,51 13,34 Sukahurip 0 2,60 14,25 190,22 201,70 Sukaresik 174,62 243,00 178,09 226,68 0 Wonoharjo 114,72 183,42 252,05 58,92 0 Total 1.161,35 1.193,56 1.017,49 2.125,23 733,15 Secara keluruhan, Desa Pangandaran yang terletak di bagian daratan yang menghubungkan daratan pulau jawa dengan tanjung Pangandaran (tanah genting) di tempatkan sebagai zona yang paling berbahaya karena merupakan daerah dengan permukiman terpadat. Sebaran dan kepadatan permukiman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi risiko bencana tsunami yang akan terjadi. Permukiman penduduk menggambarkan tingkat kepadatan penduduk dan sebaran tempat hunian yang akan mempengaruhi tingkat keugian jiwa maupun harta benda.