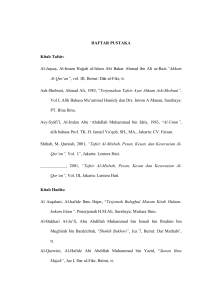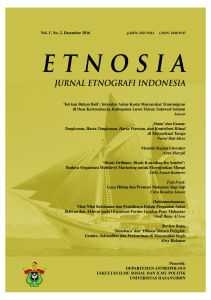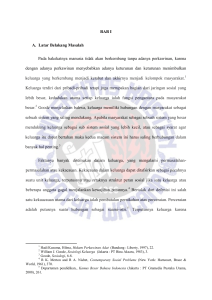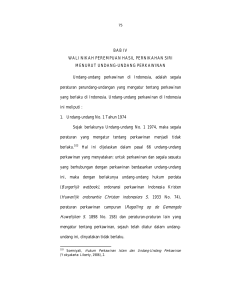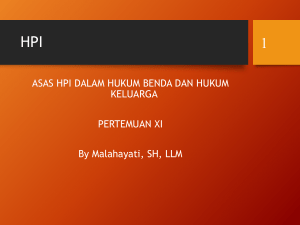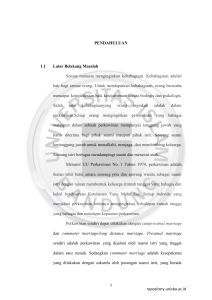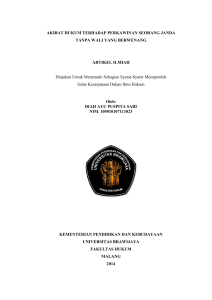Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia
advertisement

Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996 Yasin Baidi ∗ Abstrak Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan itu dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak, suami isteri. Dipahami oleh mayoritas ahli hakum bahwa kalimat ‘menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak’ berarti antara calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sama agamanya, harus seagama. Pemahaman ini dengan demikian berimplikasi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan isteri yang tidak seagama tidaklah sah. Namun demikian, secara faktual ada banyak masyarakat Indonesia yang melakukan nikah tidak seagama ini yang secara yuridis sangatlah problematis. Di tengah-tengah problematika ini muncullah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996 yang mencoba ‘menengahi’-nya. Namun, legalkah solusi ini? Problematika yuridis apa yang dimunculkannya? Tulisan ini menganalisisnya dari berbagai perspektif. Kata kunci: nikah beda agama, putusan MA, undang-undang A. Pendahuluan Semua agama secara normatif dan prinsipil tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama. Secara yuridis, dibuatlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan seperangkat aturan pelaksanaannya. Salah satu asas yang dikembangkan dalam U No. 1 Tahun 1974 itu adalah bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. UU No. 1 Tahun 1974 ini merupakan ‘kata akhir’ dan ‘penghapus berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP, Burgerlijk Wetbook/ BW), (2) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/ GHR), Stb. 1898 N0. 158, (3) Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesiers/ HOCI), Stb. 1933 No. 74, dan (4) Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Lebih lanjut, dalam bagian penjelasan dinyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal ∗ Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 672 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 2 (1) ini tidak ada lagi perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Seiring dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sagat majemuk dan heterogen—suku, adat, ras, bahasa, dan agama—serta semakin pesatnya perkembangan zaman, pergeseran pandangan dan nilai serta makna terhadap institusi keluarga semakin kuat. Maka, dengan kondisi kemajemukan dan hetrogenitas itu, ditambah lagi dengan mobilitas perikehidupan warga masyarakat yang semakin tinggi, fenomena nikah beda agama itu ternyata sudah semakin banyak dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah pernikahan beda agama dalam konstelasi global perikehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, jika tidak dicari jalan keluarnya, tidak saja akan menimbulkan ketidakjelasan status hukumnya, namun juga sangat dimungkinkan pada saatnya nanti akan memicu timbulnya instabilitas perikehidupan masyarakat warga negara Indonesia. Pemecahan terhadap permasalahan pernikahan beda agama ini jelas merupakan hal yang tidak bisa ditawartawar lagi. Muncul pro dan kontra tentang status hukumnya: sah-tidak sah, boleh-tidak boleh. Misalnya, MUI dan kaum ‘tradisionalis’ pada umumnya mengharamkan sementara Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Pengarusutamaan Gender (PuG) Depag RI membolehkan/mensahkan. Namun, pemikiran yang digagas dan ditawarkan oleh kedua lembaga di atas masih saja dipandang 'tidak benar' oleh sebagaian besar para juris dan para teolog di Indonesia sehingga pemikiran yang sebenarnya bisa dijadikan solusi alternatif itu masih berkutat dalam tingkatan wacana, belum bisa teraplikasikan dalam dataran praksis yakni dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, gagasan keduanya masih saja, secara praktis yuridis, belum memuaskan karena pada kenyataannya belum bisa mengentaskan problematika perkawinan beda agama yang semakin banyak dilakukan di Indonesia. Artinya, di satu sisi secara religius masih menimbulkan polemik pro dan kontra dan di sisi lain secara yuridis normatif terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) yang sudah barang tentu tidak kondisif dalam tata tertib hukum di Indonesia. Untuk itulah, sehubungan dengan adanya sebuah permohonan kasasi kasus nikah beda agama itu, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan pada gilirannya putusan Mahkamah Agung tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi dalam berbagai kasus nikah beda agama di Indonesia. Inti dari putusan tersebut adalah bahwa nikah beda agama di Indonesia itu boleh dilakukan dan tidak melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Paradigma yang dipakai SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 673 dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekosongan hukum itu agar tata tertib hukum bisa berjalan dengan baik. Meskipun demikian, polemik dalam masalah nikah beda agama tidaklah surut, masih saja menuai pro kontra yang semakin debatable. Maka menarik untuk dilihat apakah putusan Mahkamah Agung ini benar-benar “benar” secara yuridis konstitusional? Bagaimana kritik yang dapat diajukan kepada putusan Mahkamah Agung ini dalam perspektif hukum Islam? Kira-kira solusi alternatif apakah yang bisa ditawarkan? Inilah yang akan coba diangkat dan ditilik dalam tulisan ini. Oleh karena itu, muncul paling tidak tiga persoalan penting, yakni pertama, apa latar belakang Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat putusan itu; kedua, bagaimana paradigma interpretasi hukum melihat masalah ini; dan ketiga, solusi alternatif apakah yang dapat ditawarkan. Diharapkan, tulisan ini dapat menjelaskan latar belakang Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat putusan itu, mengetahui perspektif hukum Islam melihat masalah ini, dan berusaha mencari solusi alternatif yang dapat ditawarkan. Diharapkan pula, tulisan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengkritisi fenomena hukum perkawinan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sebagai sumbangan pemikiran terhadap dinamika hukum seputar hukum perkawinan di Indonesia, dan sebagai lemparan wacana yang diharapkan mengundang kritik konstruktif agar problematika nikah beda agama di Indonesia bisa teratasi secara yuridishumanis. B. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdata, tidak diberikan pengertian perkawinan itu. Oleh karena itu, untuk memahami arti perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Afandi mengatakan bahwa “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Scholten mengatakan bahwa perkawinan adalah “hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.1 Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya 1 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1985), p. 31. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 674 dalam hubungan-hubungan perdata.2 Hal ini berarti bahwa undangundang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal. Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. C. Hal-ihwal Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Ada beberapa aspek yang penting dikemukakan kaitannya dengan hal ihwal sebuah pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Pertama, hakekat. Pada Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.” Berangkat dari definisi ini tampak bawaha hakikat perkawinan menurut undang-undang bukanlah sekedar ikatan formal belaka tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa hakikat perkawinan adalah “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah”. Menurut KUHPerdata, hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat. Artinya, KUHPerdata melihat sebuah perkawinan lebih sebagai sekedar ikatan formal-lahiriah semata-mata. Kedua, asas. Menurut UU No. 1/1974 Pasal 3, asas perkawinan adalah monogami relatif atau sering disebut juga dengan monogami terbuka. Artinya, seorang suami idealnya hanya boleh beristeri satu orang saja. Namun, sepanjang ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta hukum dan agamanya mengizinkan, ia boleh beristeri lebih dari satu (poligami). Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI. Sedangkan KUHPerdata menganut asas monogami mutlak atau 2 Pasal 26 Kitab undang-undang Hukum Perdata SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 675 monogami tertutup. Artinya, seorang suami hanya boleh beristeri satu orang saja, tanpa kecuali. Secara histories, ketentuan dalam KUHPerdata ini berdasarkan kepada doktrin Kristen (Gereja). Ketiga, syarat sah. Dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI (Pasal 4) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, (Pasal 5) bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan, dan (Pasal 6) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 dijelaskan tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda. Syarat perkawinan menurut KUHPerdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Syarat material relatif yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Sementara menurut Pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta sighat akad nikah. Keempat, tujuan. Menurut pasal 1 UU No. 1/1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam KUHPerdata tidak ada satu pasalpun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Tampak bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata semata-mata. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 676 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... D. Perdebatan Pandangan tentang Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Perkawinan beda agama secara sederhana dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Kaitannya dengan masalah perkawinan beda agama ini paling tidak muncul empat kemungkinan, yaitu (1) perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, (2) perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, (3) perkawinan antara wanita muslim dengan pria Ahl al-Kitab, dan (4) perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik. Menanggapi model perkawinan yang pertama, sebagian ulama ada yang membolehkan (menghalalkan) namun sebagian yang lain mengharamkannya. Ulama yang membolehkan mendasarkan diri pada Q.S. al-Ma’idah (5): 5 yang artinya: “… [dan dihalalkan mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang ynag diberi Al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjaikannya gundik-gundik. …” Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah s.w.t. membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab yang muhsan, yakni wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain arti itu, ada juga ulama yang memahami kata muhsanât ketika dirangkaikan dengan ûtû al-kitâb dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang sudah kawin. Sementara ulama yang mengharamkan mendasarkan diri pada Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita-wanita musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanitawanita mukminah] hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak lakilaki yang mukmin itu lebih baik dari orang-orang musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat (perintah-perintah)-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Berdasarkan pada ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 677 begitu juga sebaliknya, wanita muslim pun dilarang menikahi pria musyrik. Golongan ulama yang mengharamkan nikan beda agama mengatakan bahwa QS al-Ma'idah (5): 5 di atas telah ‘dihapus’ (di-nasakh) oleh Q.S. alBaqarah (2): 221 ini. Ulama yang berpendirian seperti itu antara lain adalah Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Zaidiyyah.3 Abdullah ibn 'Umar r.a,. pernah ditanya tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab. Ia menjawab: “Allah mengharamkan wanita musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang berkata: 'Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah.” Bisa dipahami bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik karena Ahli Kitab berbuat syirik yang oleh karena itu ia pun masuk dalam kategori musyrik.4 Menurut kelompok yang membolehkan nikah beda agama, termasuk Muhammad Quraish Shihab, berdasar zahir teks ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. al-Ma'idah (5): 5 ‘dihapus’ (di-nasakh) oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221 adalah suatu kejanggalan. Hal ini disebabkan karena ayat yang disebut pertama (Q.S. al-Ma'idah (5): 5) turun belakangan daripada ayat yang disebut kedua (Q.S. al-Baqarah (2): 221). Jelas bahwa tidak logis (ma’qul) sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya.5 Golongan ulama yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan tabi'in yang yang pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Dari kalangan sahabat antara lain ialah Usman ibn Affan, Talhah, Ibn 'Abbas, dan Jabir ibn Huzaifah, sedangkan dari kalangan tabi’in antara lain Ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'bi dan ad-Dahhak. Selanjutnya, perkawinan bentuk kedua dan keempat umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai perkawinan yang diharamkan. Dasarnya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 221. Adapun perkawinan bentuk ketiga, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, menurut jumhur ulama adalah juga diharamkan. Walaupun pandangan mayoritas Ulama tidak memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria Ahli Kitab mengawini wanita muslimah. Bukankah mereka, walau tidak dinamai musyrik, dimasukkan dalam kelompok kafir. Berdasarkan Q.S. alMumtahanah (60): 10 dapat dipahami bahwa wanita-wanita muslimah 3 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an, jilid III, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), p. 29. 4 Ibid. 5 Ibid., I, p. 443. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 678 tidak diperkenankan mengawini atau dikawinkan dengan pria kafir, termasuk juga Ahli Kitab. Arti Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 adalah sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu perempuan-peremppuan yang beriman maka hendaklah kamu uji [keimanan] mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada [suami-suami] mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada [suami-suami] mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali [perkawinan] dengan wanita-wanita kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Berdasarkan paparan singkat di atas, maka tampak jelas bahwa Islam secara jelas membedakan antara beberapa kemungkinan bentuk perkawinan. Dengan adanya berbagai bentuk perkawinan tersebut, maka secara langsung akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda-beda pula. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan sah untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdi kepada Allah s.w.t.6 Di sisi lain, menurut Azhar Basyir, perkawinan memiliki tujuan pokok yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat begitu pentingnya arti dan makna perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu di antaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma, untuk mewujudkan cita-cita perkawinan tersebut, Islam menghendaki perkawinan dilakukan 6 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1974), pp. 47-48. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 679 antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam, penganut Kristen dengan sesama penganut Kristen, dan begitu seterusnya.7 Ahmad Sukarja, dalam artikelnya mengemukakan pendapat Yusuf al Qaradawi, bahwa akan muncul begitu banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan berbeda agama, di antaranya sebagai berikut.8 Pertama, akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara perempuan Islam dengan laki-laki Islam. Perempuan Muslim akan semakin banyak yang tidak kawin dengan laki-laki Muslim. Sementara itu, poligami diperketat dan malahan laki-laki Muslim tidak bisa melakukan hal itu disebabkan perkawinannya dengan Nasrani atau Yahudi akan membatasinya tidak boleh berpoligami dalam perkawinan. Kedua, suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya, demikian pula sebaliknya, juga anak-anaknya. Bila ini terjadi maka fitnah telah benar-benar terjadi. Ketiga, perkawinan berbeda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang harmonis, baik antara suami dan isteri, antara anak-anak mereka, terlebih lagi jika mereka berbeda kebangsaan, bahasa, kebudayaan dan tradisi maka akan lebih sulit lagi. Jadi perkawinan dalam Islam bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata akan tetapi sebagai perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan berarti ia telah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan dalam Islam termasuk katagori ibadah. Hal ini sesuai dengan prinsip umum dari Maqashid as-syari’ah atau tujuan syariat yaitu untuk menjaga agama serta keturunan. Berdasarkan beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka perbuatan yang menimbulkan kemudlaratan kepada manusia adalah dilarang untuk dilakukan, termasuk nikah beda agama. E. Pengertian Nikah Beda agama Dalam konteks era globalisasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini, pergaulan antar manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam satu lingkungan masyarakat kecil dan sempit semata-mata: suku, golongan, ras, dan agama. Dengan adanya nuansa era globalisasi dan komunikasi ini, maka dinding-dinding ‘batas’ itu telah tertembus dengan cepat. Dampak 7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama, cet-3, (Bandung: Bandar Maju, 2007), p. 25. 8 Ahmad Sukarja, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, (Ed) Chuzaimah T.Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), pp. 13-14. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 680 dari adanya kondisi ini antara lain adalah banyak dilangsungkannya perkawinan yang menembus batas-batans ‘dinding’ itu, misalnya perkawinan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang tidak seagama. Hal ini terutama terjadi pada titik-titik masyarakat perkotaan yang sarat dengan hiruk pikuk urbanisasi yang segala aspek sosiologisnya bernuansa heterogen.9 Secara umum, ada ada dua istilah yang terkait dengan masalah ini, yaitu perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Dinyatakan dalam pasal 57 UU No. 1/1974 bahwa perkawinan campuran adalah pernikahan yang dilakukan antara dua orang di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena beda warga negara, dan salah satu warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalan perkawinan campur adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganega-raan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Di sini, berlaku asas lex loci actus yaitu menunjuk di mana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Artinya, perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia. Sementara nikah beda agama yang dimaksudkan di sini adalah proses pernikahan (akad nikah) antara calon suami dengan calon istri yang salah satunya berlainan agama. Misalnya, calon mempelai laki-lakinya beragama Hindu sedangkan calon memperlai putrid beragama Katolik. Lebih lanjut, pemahaman terhadap makna perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. Pendapat kedua bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 66 UU No. 1/1974, maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. 9 Asmin, Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), p. 65. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 681 Selanjutnya, tampak adanya perbedaan pendapat di kalangan para pemerhati hukum perkawinan di Indonesia mengenai perkawinan beda agama khususnya terhadap petunjuk hukum Pasal 2 ayat (1) Undangundang Perkawinan. Sebagian kalangan mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pernikahan beda agama. Namun, sebagian yang lain berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Hilman Hadikusuma adalah contoh yang mengatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama.10 Ia mengatakan bahwa perkawinan yang dikehendaki Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Klausul dalam kalimat “…hukum masing-masing agamanya…” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Jadi, menurut Hilman, perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan jika terjadi perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri. Jika perkawinan telah dilakasanakan menurut hukum Islam, misalnya, kemudian dilakukan lagi menurut agama lain, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut Hilman menjelaskan bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di depan Kantor Catatan Sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan menurut prosesi agama tertentu jelas-jelas tidak sah menurut Undangundang Perkawinan. Sementara menurut peraturan perundangan atau KUHPerdata (BW), perkawinan tersebut sah, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 hal itu jelas-jelas menjadi tidak sah karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib agama. Hilman juga mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antar agama disebut anak “haram jadah” atau anak tidak sah. Berdasarkan petunjuk hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan itu juga, maka perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau di catatan sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah, juga tidak sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan 10 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan…, pp. 25-27. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 682 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katollik, Hindu, dan Budha di Indonesia. Hazairin memiliki pandangan yang agak berlainan. Ia mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ada kaitannya dengan Undang-undang Dasar sebagai landasan penyusunan Undang-undang di bawahnya. Menurutnya, meteri Pasal 2 ayat (1) yang berisi klausul “masing-masing agamanya” merupakan konsistensi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar yang mengatur tentang agama-agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ada ruang interpretasi perkawinan antara orang yang berbeda agama sebagaimana yang terjadi di masyarakat saat ini.11 Selanjutnya, Hazairin berpendapat bahwa terkait adanya indikasi kebolehan perkawinan beda agama yang disinyalir dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, maka perkawinan beda agama telah secara tegas diharamkan oleh agama Islam. Q.S. al-Baqarah (2): 221 telah secara jelas dan tegas menunjukkan tentang keharaman itu. Mengenai kontroversi pendapat tentang istilah ‘musyrik’ dan ‘kafir’ ia mengatakan bahwa istilah itu merupakan setali tiga uang, yakni memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama non-muslim. Oleh karena itu, perkawinan anatara orang yang berbeda agama dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak dimungkinkan adanya. Berbeda dengan Hadikusuma dan Hazairin, Munawir Sjadzali berpendapat lebih moderat bahkan liberal. Menurutnya, Undang-undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama. Sementara menurut Mudiarti Trisnaningsih, hukum Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Hukum Indonesia hanya mengenal perkawinan campuran. Antara perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran memiliki perbedaan mendasar. Perkawinan beda agama sudah jelas yaitu perkawinan antara orang yang berlainan agama. Perkawinan beda agama tersebut tidak dikenal dalam lapangan hukum Indonesia. Mengenai perkawinan campuran, Trisnaningsih mengatakan hal tersebut telah dikenal sejal Indonesia belum merdeka, namun dengan pengertian yang berbeda.12 Sebelum masa kemerdekaan Indonesia sampai keluarnya Undangundang tentang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, istilah ‘perkawinan campuran’ merujuk kepada perkawinan antargolongan penduduk 11 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, (Jakarta: UI Press, 1982), p. lampiran. 12 Mudiarti Trisnaningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indoneisa (The Relevance Of Certaintly Of Law Regulating Inter Religious Marriages In Indonesia), (Bandung: Utomo, 2007), p. 57. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 683 Indonesia, yaitu misalnya antara golongan penduduk Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Berkaitan dengan perkawinan campuran ini, kolonial Belanda secara khusus mengeluarkan regulasi tentang perkawinan campuran yang disebut Regeling Op De Gemengde Huwelijken, berdasarkan Koninklijk Besluit Van 29 December 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158 yang pada intinya apabila terjadi perkawinan antara golongan penduduk yang berbeda, maka berlakulah regulasi ini dengan menekankan pada pemberlakuan hukum dari status Golongan Penduduk pihak suami. Namun, setelah tahun 1974 atau setelah diundangkannya Undangundang Perkawinan, pengertian ‘perkawinan campuran’ mengacu pada perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Dalam Pasal 57 Undangundang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi jelas bahwa nikah beda agama tidak sama dengan perkawinan campuran. F. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 sebagai Yurisprudensi Merujuk pada Undang-undang No. 1/1974 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 57 ini, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak. Menurut Purwoto S. Gandasubrata, perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU No.1/1974 namun ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami. Jika dicermati secara saksama maka adanya ketidakjelasan dan ketidaktegas-an dalam masalah perkawinan antar agama adalah berangkat dari Pasal 2 yang bunyinya “…menurut hukum masing-masing agama atau SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 684 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... kepercaya-annya”. Artinya, jika agma kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tetapi jika agama atau kepercayaannya berbeda maka dalam hal adanya perbedaan kedua agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua. Hal ini berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya. Dalam praktiknya, perkawinan antar agama ini dapat dilaksanakan dengan salah satu calon ‘menganut’ agama pasangannya terlebih dahulu. Artinya, salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Oleh karena itu, tampak bahwa alasan mengapa Mahkamah Agung mencoba mengisi kekosongan hukum ini adalah karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas diatur tentang perkawinan antaragama. Menurut MA, UU No. 1/1974 tidak menyatakan (mengatur) bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. MA mendasarkan diri pada ‘semangat’ UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Semangat ini mencakup juga kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Untuk itu, selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masingmasing. Pertimbangan lainnya adalah bahwa meskipun ada ‘lampu hijau’ dari adanya GHR dan HOCI yang mengatur nikah antar agama namun kedua peraturan ini tetap tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Pertimbangan lainnya adalah bersifat factual empirical, yakni bahwa dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, tidak sedikit terjadi perkawinan antaragama. Oleh karenanya, MA berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut karena diasumsikan akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Untuk itu, solusi yang paling tepat menurut Mahkamah Agung adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan di mana kedua calon suami isteri berlainan agama. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 685 Tentu saja putusan MA ini senantiasa menuai pro dan kontra, kontroversial. Namun, itulah ‘ijtihad’ MA dalam mengisi kekosongan hukum dalam masalah ini. Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 ini pada gilirannya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Akibat hukum selanjutnya adalah dalam proses perkawinan antar agama maka paka para pihak dapat mengajukannya kepada Kantor Catatan Sipil. Jika itu terjadi maka, sebagai misal, bagi salah satu calon yang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai ‘tidak berkehendak’ untuk melangsungkan perkawinannya tidak secara Islam. Ini berarti pula bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya sehingga Pasal 8 point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya. Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antaragama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada Pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti (akte) perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya, perkawinan antaragama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan. G. Perspektif Interpretasi Hukum dan Perspektif Filosofis Setelah diuraikan latar belakang dan berbagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam menangani masalah nikah antaragama di atas tampak bahwa kesemuanya bermuara kepada penafsiran hukum. Dikarenankan model penafsiran hukum itu berbeda-beda dan variatif maka dampak pro-kontra terhadap hasil akhir dari sebuah penafsiran hukum pun tidak bisa terelakkan. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 686 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... Menurut hemat penulis, tampaknya Mahkamah Agung lebih cenderung menggunakan model penafsiran hukum secara teleologis (sosiologis) semata, tidak menghiraukan—apalagi mengelaborasikan— beberapa model penafsiran yang lainnya. Model penafsiran hukum secara teleologis (sosiologis) adalah menafsirkan (baca: memahami) undangundang dengan mengingat maksud dan tujuan dari sebuah undangundang, di mana bunyi undang-undang itu tetap sementara ‘kebutuhankebutuhan’ masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Maksud MA, mungkin pada masa-masa dulu nikah beda agama—karena berbagai alasan—sangat tidak mungkin dilakukan. Namun, pada masa-masa kini hal ketidakbolehan itu sudah tidak cocok lagi sehingga sudah semestinya nikah beda agama harus dibolehkan, terutama juga karena adanya alasan kekosongan hukum. Sementara Mahkamah Agung ‘lupa’ bahwa, pertama, jika ditilik menurut model penafsiran sahih (gramatikal), jelas bahwa Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan sudah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa nikah dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Maksudnya, kedua calon suami dan istri harus sama-sama seagama, agamanya sama, satu agamanya. Itu artinya, jika tidak sama agama dan kepercayaannya maka tidak sah. Kedua, jika ditilik memalui model penafsiran historis, nyata bahwa maksud (semangat) dari sejarah diundangkannya Undang-undang No.1/1974 itu adalah berbasis semangat religiusitas sesuai dengan jiwa sila pertama Pancasila. Ketiga, menurut model penafsiran a contrario, bahwa apa yang ‘sebaliknya’ tidak boleh/tidak sah. Jelas bahwa keabsahan pernikahan sebuah pasangan adalah menurut agama dan kepercayaannya. Ini artinya jika tidak sama agama dan kepercayaannya maka pernikahannya tidak sah. Berdasarkan analisis berbasis teori penafsiran hukum di atas tampak bahwa pilihan MA dalam menggunakan model penafsirannya kurang adil dan kurang komprehensif sehingga kesimpulan yang dimunculkannya terkesan timpang. Hal ini mungkin bisa dianalogkan dengan kasus lain, misalnya sudah maraknya kehidupan keluarga-tanpa-nikah di Indonesia. Keluarga-tanpa-nikah yang dimaksudkan di sini adalah sebuah ‘keluarga’ yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tetapi hanya dilakukan dengan dasar suka sama suka semata-mata, tanpa didahului oleh ikatan perkawinan. Tentu, sekali lagi, ini hanyalah sekedar contoh atu lebih tepatnya asumsi. Analoginya adalah seperti berikut ini. Apakah karena pertama, bahwa jelas-jelas UU No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang keluarga-tanpa-nikah secara tegas dan jelas; kedua, sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” sehingga tercakup di dalamnya kesamaan SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 687 hak asasi untuk hidup ‘berkeluarga’ dengan cara apapun yang ini berarti bahwa asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk menentukan cara hidup ‘berkeluarga’-nya masing-masing; ketiga, dengan tidak diaturnya keluarga-tanpa-nikah di dalam UU No. 1/1974 maupun dalam ketentuan peraturan perundangn-undangan lain; keempat, dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik sudah semakin banyak terjadi keluarga-tanpa-nikah, sehingga tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut karena pada gilirannya sangat dimungkinkan akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama; dan kelima, solusi hukum yang tepat bagi perkawinan antar agama adalah bahwa model keluarga-tanpa-nikah dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk itu, apakah dengan demikian perilaku dan model keluarga-tanpa-nikah di Indonesia harus dibolehkan dan dilegalkan? Menurut hemat penulis tentu tidak boleh. Kemudian untuk perspektif filosofisnya yang terkandung sekaligus mewarnai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat dalam kerangka pemikiran Abdul Ghofur Anshori. Menurutnya, ada dua hal yang sangat mendasar yang perlu dicermati dalam Undang-undang No.1/1974 ini. Pertama, sebenarnya undang-undang ini bermaksud untuk menata rakyat Indonesia agar ‘tertib-teratur’. Kedua,—dan ini yang paling utama—menilik Pasal 1-nya menandakan bahwa secara hakiki-substansial pernikahan di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang berdimensi transendental, bukan semata-mata hubungan keperdataan saja. Perkawinan harus dilandaskan pada nilai-nilai agama. Untuk mendukung kerangka dasar filosofi ini, maka diaturlah agar setiap pernikahan sebuah pasangan yang dilakukan di Indonesia itu diniscayakan harus seagama, agamanya sama.13 Kerangka normatif hukum positif suatu negara pada dasarnya adalah aturan yang diciptakan atas dasar kepentingan negara mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai, dan aman sesuai dengan asas bahwa setiap aturan hukum hendaknya dibentuk dengan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan keamanfaatan. Dalam hal hukum keluarga, maka bagaimana dan akan seperti apakah aturan hukum itu dirumuskan sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan an perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara dan dengan tetap mengacu pada landasan 13 Abdul Ghofur Anshori, “Orientasi Nilai Filsafat HukumKeluarga: Refleksi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada, 12 Desember 2005, Yogyakarta, p. 7. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 688 filosofinya. Landasan filosofis ini penting bagi suatu atuaran hukum karena sebuah aturan hukum positif akan berlaku efektif jika memenuhi tiga syarat pokok, yaitu keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan filosofis.14 Berdasarkan telaah filosofis-yuridis di atas, maka sebaiknya (1) yurisprudensi Mahkamah Agung itu dicabut karena sesungguhnya ‘kekosongan hukum’ itu tidak terjadi. Cukup dikembalikan dan menggunakan UU No. 1/1974 saja secara konsisten; (2) memberikan suatu ‘maklumat’ bahwa siapapun yang menikah dengan pasangan yang berlainan agama, apapun alasannya, adalah tidak sah; (3) melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa nilai dasar perkawinan di Indonesia—yang berbasis terutama kepada sila pertama Pancasila— adalah bersifat transendental, ada nilai-nilai religius-filofofis di dalamnya, bukan hanya hubungan keperdataan semata. Ini mensyaratkan bahwa tidak bisa tidak pernikahan harus dilakukan dengan pasangan yang seagama, sama agamanya. J. Penutup Setelah dilakukan pencermatan dan pengkajian di dalam Bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa latar belakang Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat putusan itu adalah untuk mengisi ‘kekosongan hukum’ sebagai akibat dai adanya interpretasi hukum yang beragam terhadap Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 di satu sisi dan maraknya kasus nikah beda agama di tengah-tengah rakyat Indonesia di sisi lain. Kedua, menurut paradigma hukum yang ada, Mahkamah Agung hanya menitik beratkan pada model penafsiran sosiologis semata-mata dan ‘lupa’ terhadap model penafsiran lainnya, terutama model penafsiran gramatikal dan historis. Ditambah lagi, Mahkamah Agung ‘melupakan’ semangat religiusitas-filosofis dari hukum pernikahan di Indonesia yang sangat transendental. Ketiga, solusi yang dapat ditawarkan adalah back to basics, kembali ke posisi semula. Artinya, semua pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia harus dikembalikan kepada asas transendensial yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 yakni bahwa antar calon suami isteri harus seagama, sama agamanya. Dengan demikian, harus secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh calon suami isteri yang tidak seagama, berbeda agama, agamanya tidak sama adalah tidak sah, ilegal, sehingga tidak ada satu pun lembaga di negeri ini yang berwenang untuk menikahkan pasangan yang seperti ini. 14 Ibid., p. 19. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010 Yasin Baidi: Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia... 689 Daftar Pustaka Anshori, Abdul Ghofur, “Orientasi Nilai Filsafat HukumKeluarga: Refleksi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12 Desember 2005. Asmin, Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama, cet-3, Bandung: Bandar Maju, 2007. Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Alumni, 1985. Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 1988. Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2001. Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999. Sukarja, Ahmad, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, dalam Chuzaimah T.Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta: UI Press, 1982. _______, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974. Trisnaningsih, Mudiarti, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indoneisa (The Relevance Of Certaintly Of Law Regulating Inter Religious Marriages In Indonesia), Bandung: Utomo, 2007. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010