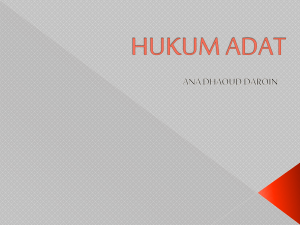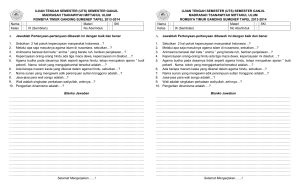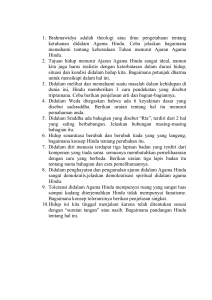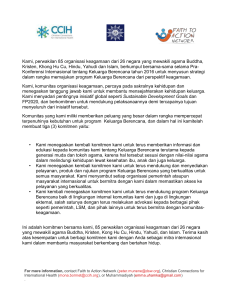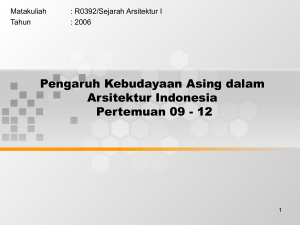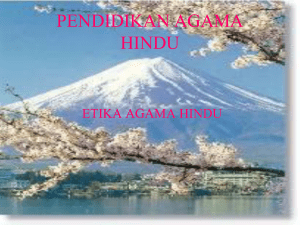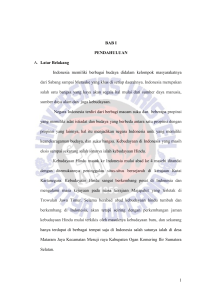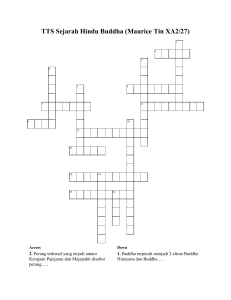50 PARADIGMA KOMUNIKASI HINDU = ETIKA KEUTAMAAN
advertisement

SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 PARADIGMA KOMUNIKASI HINDU = ETIKA KEUTAMAAN HINDU + KEARIFAN LOKAL Nengah Bawa Atmadja 1. Pendahuluan Agama Hindu sebagai agama dunia berasal dari India, masuk ke Indonesia sekitar awal abad masehi. Manurut Coedes (2010) hubungan antara India dan Indonesia terus mengalami meningkatan sehingga memunculkan indianisasi atau sanksekertaisasi, yakni “tersebarnya suatu kebudayaan yang terorganisir, yang berlandaskan konsep India tentang kerajaan, yang ciri-ciri khasnya adalah agama Hindu atau agama Buddha, mitologi Purana, kepatuhan pada Dharmasastra, dan yang cara pengungkapannya adalah bahasa Sansekerta” (Coedes, 2010: 43). Bukti-bukti bahwa indiaisasi semakin kuat adalah berdirinya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Aneka kerajaan ini merupakan tanda bahwa indianisasi semakin sukses, dan wajah kebudayaan lokal di berbagai daerah di Indonesia – terutama Jawa dan Bali sangat kental dengan pengaruh India (Poeponegoro dan Notosusanto, 1993; Lombard, 2005; Amadja, 2010). Dengan mengacu kepada Lombard (2005) banyak pakar yang menentang indiaisasi, mengingat bahwa pengaruh India tidak ditiru secara total, tetapi diolah sehingga menghasilkan corak kebudayaan yang berbeda daripada kebudayaan Hindu di India. Misalnya, kebudayaan Hindu Jawa dalam bentuk candi misalnya, tidak sama dengan bangunan suci agama Hindu di Jawa. Begitu pula pura di Bali, namannya memang memakai bahasa Sansekerta – tanda adanya sansekertaisasi, namun bentuk, fungsi, dan makna pura tidak sama dengan bangunan suci keagamaan di India. Jadi, di balik kesamaan ada perbedaaan sebagai hasil dari daya kreativitas bangsa Indonesia dalam menerima pengaruh India. Makalah ini mencoba memaparkan tentang bagaimana kebudayaan India, yakni agama Hindu, setelah masuk ke Indonesia – kasus Bali mengalami pengelohaan sehingga melahirkan ide yang mengakar pada kultur lokal. Ide-ide ini lazim disebut kearifan lokal. Kedudukannya amat penting, yakni sebagai resep bertindak yang tercermin dari tindakan sosial, termasuk di dalamnya komunikasi yang mereka lakukan secara meruang dan mewaktu. Untuk lebih jelasnya gagasan ini dapat digambar dalam suatu bagan, seperti terlihat pada Bagan 1. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 50 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Tabel 1 Lokalisasi Agama Hindu Berbentuk Kearifan Lokal Agama Hindu Tat Twam Asi Beberapa contoh butir etika keutamaan sebagai etika sosial (a) Maitri (persahabatan atau persaudaraan) (b) Karuna (welas asih atau belas kasih) (c) Mudita (simpatik atau bersimpati) (d) Upeksa (tenggang rasa atau toleran) (e) Ahimsa (nirkekerasan) (f) Adrobah (sikap ramah) (g) Acapalam (kesantunan, kejatmikan) (h) Advesa (tidak membenci) (i) Akrodah (tidak marah) (j) Priti (berpandangan bahwa semua manusia adalah sama) (k) Satya (jujur) (l) Ksama (mudah memberi maaf), dll. Kreativitas dan adaptivitas Lokalisasi Local genius Glokalisasi Akulturasi Sinkretisme Hibridisasi Manusia Rasional empirikal Pengalaman ekologis (keruangan) Pengalaman sosial budaya Pengalaman kewaktuan Kearifan Lokal Konsepsi abstrak yang dirumuskan secara padat, singkat, menarik, mudah diingat dan sarat makna Kearifan lokal bisa berbentuk kearifan sosial dan kearifan ekologi Digunakan sebagai habitus, skemata atau pedoman bertindak dalam berkomunikasi dan/atau berinteraksi sosial pada suatu arena (ranah) Komunikasi bisa antar pribadi atau non antar pribadi. Komunikatif memakai bahasa verbal dan/atau non-verbal dalam konteks kesalingpahaman guna mewujudkan suatu tujuan. Melahirkan artefak sebagai sarana komunikasi dan/atau simbol status sosial (nilai guna atau nilai tanda) 2. Esensi Agama Hindu Dengan mengacu kepada Gellner (2009) dan Koentjaraningrat (2015) agama memiliki banyak karakter antara lain kitab suci yang memuat etika (sila, susila). “Etika menyangkut sikap kita terhadap hidup, kita diharapkan berperilaku Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 51 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 yang baik, memiliki disiplin yang benar, moralitas, tidak melakukan perbuatan jahat” (Putra, 2014: ix). Gagasan ini mencerminkan bahwa etika selalu berkaitan dengan bagaimana manusia berperilaku terhadap orang lain – dalam agama Hindu tidak saja manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Dalam konteks inilah pertanyaan utama yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak etis terhadap orang lain menjadi penting. Adapun pertanyaannya adalah “Siapakah saya? “Siapa pula orang lain di luar diri saya?” Dengan berpegang pada Bagan 1, agama Hindu memiliki jawaban atas pertanyaan ini, yakni melalui filsafat manusia dengan rumusan Tat Twam Asi. Putra (2014) dan Visvanathan (2004) menjelaskan konsep Tat Twam Asi, yakni berkaitan dengan kondisi manusia bahwa secara ketubuhan adalah berbeda satu sama lainnya, namun secara esensial roh yang ada di dalamnya adalah jiwa universal yang sama di dalam semua makhluk. Jiwa universal adalah Brahman. Brahman sebagai jiwa universal bersifat transendental, namun berimanensi dalam tubuh manusia yang disebut Atman. Gagasan ini menimbulkan implikasi bahwa manusia berbeda secara ketubuhan, namun secara esensial – apa yang ada di dalam tubuhnya adalah sama, yakni Atman = Brahman. Dengan demikian Tat Twam Asi menekankan pada persaudaraan universal antarumat manusia –bahkan sesama makhluk hidup mengingat mereka pun memiliki Atman = Brahman. Bertolak dari gagasan ini maka agama Hindu mengembangkan etika tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang lain sebagai saudara agar hubungan saya dengan dia atau kita dengan mereka terbina secara baik yang ditandai oleh pola kehidupan yang damai atau shanty. Adapun yang dimaksud dengan etika meminjam gagasan Bertens (2011: 10) sebagai berikut. Dengan “etika” kita maksudkan pemikiran moral. Dalam konteks etika, kita memandang, mempertimbangkan, dan menilai aspek-aspek moral tingkah laku manusia, baik pada taraf individual maupun taraf sosial. Kita bertanya, apakah suatu perbuatan terpuji atau tercela, pantas dilakukan atau sebaliknya tidak pantas dilakukan. Kita memikirkan apa yang boleh diperbuat atau justru tidak boleh dilakukan. Karena mencari orientasi atau pegangan tingkah laku, etika bersifat normatif. Dalam etika, kita menyelidiki norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku atau barangkali tidak berlaku dalam situasi tertentu (Bertens, 2011: 10). Dengan kata lain bisa pula dikemukakan bahwa “etika ... dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 52 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak?” (Magnis-Suseno, 1991: 13). Pendek kata, etika memberikan kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini” (Salam, 1997: 1-2). Dengan mengacu kepada paparan Suhardana (2009), Putra (2014), Sandika (2014), dan kitab suci agama Hindu, misalnya Bhagavad Gita (Darmayasa, 2012; Ranganathannanda, 2000, 200a) sangat kaya dengan etika. Gagasan ini dapat dicermati pada Bagan 1. Butir-butir etika ini disebut etika keutamaan Hindu, dengan alasan, pertama, dia tidak saja penting sebagai orientasi bertindak secara etis, tetapi merupakan pula kewajiban karena dilegitimasi oleh fisafat manusia yang terumuskan dalam gagasan, yakni Tat Twam Asi. Kedua, butir-butir tersebut merupakan asas utama atau inti dari tindakan etis. Jika diterapkan secara konsisten maka tidak saja menjadikan seseorang sebagai makhluk paling utama daripada orang-orang lainnya, tetapi juga paling utama jika dibandingkan dengan hakhluk-mkahluk hidup lainnya. Ketiga, ide-ide tersebut berasal dari agama Hindu sehingga disebut etika keutamaan Hindu. 3. Lokalisasi Agama Hindu Konsep-konsep etika keutamaan yang tercantum pada Bagan 1 bisa jadi tidak dikenal pada masyarakat Hindu Jikalau pun dikenal, terbatas pada orangorang yang termasuk ke dalam kelompok elite agama tradisional (pedanda) atau mereka yang tergolong ke dalam kelompok agamawan yang ilmuwan atau ilmuwan yang agamawan. Walaupun demikian bukan berarti umat Hindu sama sekali tidak mengenal etika keutamaan, melainkan mengenalnya, namun dengan formulasi atau rumusan yang lain. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari daya kreatif dan daya adaptif yang dimiliki oleh agen budaya dalam masyarakat. Kemampuan seperti ini lazim disebut local genius. Istilah ini mengacu kepada kemampuan luar biasa yang tumbuh dan berkembang pada suatu komunitas yang secara kreatif mengolah dan mengadaptasikan unsur-unsur kebudayaan dari luar guna menghasilkan suatu kebudayaan baru yang memiliki karakteristik khas yang berbeda daripada kebudayaan aslinya (Atmadja, 2010). Ada pula yang memakai istilah yang berbeda, yakni Mulder (1999) memakai konsep apa yang disebut lokalisasi. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 53 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Konsep ini menyoroti inisiatif dan sumbangan masyarakat-masyarakat lokal sebagai jawaban dan penanggung jawab atas hasil-hasil pertemuan budaya. Dengan kata kain, budaya yang menerima pengaruh dari luarlah yang menyerap dan menyatakan kembali unsur-unsur asing, dengan cara menempa unsur-unsur asing itu sesuai dengan pandangan hidup. Dalam proses lokalisasi, unsur-unsur asing perlu menenukan akar-akar lokal, atau cabang asli daerah daerah tersebut, di mana unsur-unsur asing itu dapat dicangkokkan. Baru kemudian, melalui peresapan oleh getah budaya asli itu, cangkokan itu akan berkembang dan berbuah (Wolters, 1982: 52-5). Kalau kedua unsur itu tidak saling berinteraksi secara demikian itu, berbagai gagasan dan pengaruh asing boleh jadi akan tetap menjadi sesuatu yang berada di pinggiran budaya (Mulder, 1999: 5). Aneka istilah lain sebagaimana terlihat pada Bagan 1, bisa disejajarkan dengan lokal genius atau lokalisasi, yakni akulturasi (pencapuran budaya), sikretisme (percampuran agama) (Koentjaraningrat, 1985), hibridisasi budaya – (percampuran budaya sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru dan tidak asli lagi) (Atmadja 2015; Darmawan, 2014) atau Glokalisasi (melokalkan budaya global) (Ritzer, 2006, 2014; Ritzer dan Goodman, 2004). Dengan berpegang pada makna lokalisasi maka selalu bisa terjadi, etika keutamaan Hindu, seperti terlihat pada Bagan 1, bisa saja tidak dikenal secara tekstual pada masyarakat Hindu. Walaupun demikian bukan berarti umat Hindu sama sekali tidak mengenalnya atau sama sekali tidak mempraktikkannya, melainkan sebaliknya, yakni mereka mengenal dan sekaligus mempraktikkan atau mengontekstualkannya dalam kehidupan sehar-hari lewat suatu proses lokalisasi. Bagan 1 menunjukkan lokalisasi terhadap konsep-konsep etika keutamaan Hindu dikaitkan dan/atau dicangkokkan ke dalam pengalaman mereka dalam berinterakasi dengan sesama manusia lainnya dalam suatu ruang dan waktu. Dengan demikian secara esensial mereka tidak asing dengan etika keutamaan Hindu, melainkan sebaliknya, yakni mereka terbiasa melakukannya. Jadi, ada sinergi antara etika keutamaan Hindu dengan pengalaman keseharian mereka sehingga yang satu memperkuat yang lainnya. Walaupun demikian mereka tidak bisa memaknai dan/atau mengkaitkannya dengan butir-butir etika keutamaan Apalagi apa yang mereka lakukan adalah tradisi maka mereka pun tidak mempertanyakannya karena tradisi acapkali diasumsikan benar adanya. Kemampuan ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk rasional empirik sehingga mereka bisa memaknai dan mengolah pengalaman Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 54 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 ekologis, pengalaman kewaktuan, dan pengalaman sosial budaya menjadi kumpulan kognisi. Hal ini dipakai sebagai modal dasar untuk melakukan lokalisasi terhadap etika keutamaan Hindu. Baerkenaan dengan itu maka etika keutamaan Hindu tidak diterima secara tekstual – memakai istilah-istilah baku berbahasa Sansekerta seperti Bagan 1, melainkan dicangkokkan ke dalam kebudayaan lokal - diolah, diserap, dan konsep-konsep lokal yang disesuaikan dengan dengan kepribadian mereka. Dengan demikian terbentuk seperangkat ide milik bersama - meminjam pendapat Durkheim (dalam Samuel, 2010; Koentjaraningrat, 1992) disebut gagasan kolektif. Gagasan kolektif memiliki daya untuk mendorong bahkan memaksa manusia untuk bertindak sesuai dengan pesan yang terkandung di dalamnya. 4. Kearifan Lokal, Karakteristik dan Contohnya Bagan 1 menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam etika keutamaan Hindu merupakan konsekuensi dari gagasan Tat Twam Asi. Gagasan ini berimplikasi bahwa Tat Twam Asi dan etika keutamaan Hindu yang menyertainya tidak saja merupakan sarana orientasi bagi usaha manusia untuk bertindak secara etis, tetapi juga melegitmasinya. Artinya, ada argumentasi yang bisa dipertangungjawabkan dilihat dari filsafat manusia dan etika Hindu dalam konteks mengapa manusia melakukan tindakan etis. Pertanyaan ini dijawab oleh gagasan Tat Twam Asi dan etika keutamaan Hindu yang mengiringinya. Bagan 1 menunjukkan bahwa lokalisasi terhadap konsep-konsep etika keutamaan Hindu melahirkan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah konsepsi abstrak yang dirumuskan secara padat, singkat, menarik, mudah diingat dan sarat makna. Kearifan lokal bisa berbentuk kearifan sosial dan kearifan ekologi. Kearifan sosial mengacu kepada gagasan yang memberikan orientasi agar manusia menjadi insan bijaksana dalam berhubungan dengan manusia lainnya dalam sistem sosial. Kearifan ekologis mengacu kepada ide yang memberikan orientasi agar manusia menjadi insan yang arif dalam memperlakukan lingkungan alam biofisikal. Kearifan lokal merupakan habitus, skemata atau pedoman bertindak dalam berinteraksi sosial pada suatu arena (ranah) secara meruang dan mewaktu guna mewujudkan tujuan ideal, yakni kehidupan dunia yang damai. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 55 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Lokalisasi terhadap etika keutamaan Hindu bisa dicermati pada folklor Bali berbentuk ungkapan-ungkapan tradisional sebagimana dikemukakan Ginarsa (2009), Tinggen (1988) dan apa yang hidup pada masyarakat Bali. Gagasan ini terlihat misalnya pada etika keutamaan Hindu, yakni ahimsa (nirkekerasan). Manurut Visvanathan (2004: 196) ahimsa tidak saja berkaitan dengan gagasan bahwa manusia tidak melakukan kekerasan terhadap manusia dan segala makhluk hidup lainnya, tetapi di dalamnya mengadung pula “kelembutan, sopan santun, kebaikan, keramahan, kemanusiaan dan kasih”. Jadi, etika keutamaan Hindu yang ada pada Bagan 1, secara implisit tercakup dalam ahimsa sehingga ahimsa sering disebut sebagai kewajiban tertinggi dalam agama Hindu (Visvanathan (2004: 196). Ahimsa tidak saja bermakna menghindari kekerasan, tetapi bisa pula digunakan sebagai pusat orientasi guna memutus rantai kekerasan sehingga peluang adanya kedamian sebagai tujuan ideal menjadi lebih besar adanya. Walaupun ahimsa amat penting dalam agama Hindu, namun ahimsa tidak dikenal secara luas pada akar rumput. Jargon yang mereka kenal adalah kearifan lokal berbentuk ungkapan, yakni “yen timpuge aji tahi, de balese aji tahi, bales aji bunga (jika Anda dilempar dengan kontoran manusia maka jangan dibalas dengan kotoran manusia, tetapi dibalas dengan bunga)”. Ungkapan ini bisa saja naif, namun tidak bisa dipungkiri dia bermakna amat dalam – terkait dengan ahimsa, yakni kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Jika kekerasan dilawan dengan kekerasan maka terjadi lingkaran kekerasan yang sulit memutuskannya. Lingkaran kekerasan harus diputus melalui ahimsa, mengingat, jika tidak diputus maka kekerasan akan membawa korban, yakni kelas sosial terbawah pada suatu rantai hubungan sosial dalam masyarakat (Atmadja, 2010; 2010a). Etika keutamaan Hindu yang lainnya adalah kasih sayang. Atmadja (2014) yang mengutip dari berbagai sumber menujukkan bahwa inti dari belas kasih bisa dirumuskan melalui dua cara, yakni pertama, Kaidah Emas Negatif, yakni “Jangan berbuat terahadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak diinginkan akan diperbuat terhadap diri Anda”. Atau, “Jangan kaulakukan terhadap orang lain apa yang tidak kaumaui dilakukan terhadapmu”. Kedua, Kaidah Emas Positif, yakni”lakukan apa yang ingin orang lain lakukan untuk Anda”. Atau, “Hendaknya memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan” atau “Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri” (Atmadja, 2014: 209). Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 56 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Betapa pentingnya belas kasih dijelaskan pula oleh Swami Chinmayananda (dalam Bhalla, 2010: 4) yang menyatakan bahwa “Kasih adalah dasar dari agama Hindu. Bila Anda tahu cara mengasihi, Anda adalah seorang Hindu. Semua orang-orang hebat menjadi hebat karena rasa kasih mereka untuk sesama. Mereka menjadi hebat karena mereka belajar untuk mengasihi”. Begitu pula Kahril Gibran, kelahiran Libanon 6-1-1883, seorang penyair ternama yang karya-karyanya mencerminkan perpaduan budaya Timur dan Barat, sangat disukai di seantero dunia memberikan penilaian amat tinggi terhadap kasih sayang. Gagasan ini dapat dicermati pada ungkapan Kahril Gibran tentang cinta yang dikumpulkan Anjali Ratri (2015) yang menyatakan sebagai berikut. Kasih sayang dan kekerasan selalu berperang di hati manusia seperti malapetaka yang berperang di langit malam yang pekat. Tetapi kasih sayang selalu mengalahkan kekerasan Karena, ia adalah anugrah Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan malam ini akan berlalu dengan datangnya siang. (Kahlil Gibran dalam Ratri, 2015: 62). Gagasan ini memberikan petunjuk bahwa kasih sayang sangat penting, tidak saja dalam konteks hubungan antarmanusia, tetapi terkait pula dengan kemampuannya melawan kekerasan yang menyelimuti kehidupan manusia. Mengingat betapa pentingnya kasih sayang, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia pada tahun 2008 menandatangani Piagam Belas Kasih sebagai etika untuk menghindarkan umat manusia dari berbagai tindakan yang menhancurkan peradaban manusia antara lain berbagai bentuk tindakan kekerasan (Armstrong, 2013: 21-14). Agama Hindu merupakan agama dunia yang pertamatama dan selaligus sangat mengutamakan kasih sayang. Gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari filsafat manusia yang berlaku pada agama Hindu, yakni di dalam dirinya ada Atman = Brahman = Tuhan. Brahman adalah kekuatan adhidaya yang Mahapengasih dan Mahapenyayang. Berkenaan dengan itu maka manusia pun memiliki kodrat untuk memancarkan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup (Atmadja, 2014). Bagaimana pencerminan bahwa manusia memancarkan kasih sayang dalam kehidupannya? Pertanyaan inilah yang dijawab lewat butir-butir etika keutamaan Hindu seperti terlihat pada Bagan 1. Jadi, etika keutamaan Hindu Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 57 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 pada dasarnya merupakan patokan dan/atau pencerminan dari manusia yang berkomitmen untuk merepresentasikan kasih sayang, tidak saja untuk kedamaian dirinya sendiri, tetapi juga untuk kedamaian alam semesta. Gagasan ini dikenal pada masyarakat Bali, dengan rumusan, yakni “yen jimpite sakit, eda nyimpit anak len, karana ia pasti sakit (jika Anda dicubit terasa sakit, maka Anda jangan mencubit orang lain, karena dia pun pasti sakit)”. Rumusan ini secara esensial menekankan pada dalil bahwa jangan berbuat sesuatu terahadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak diinginkan akan diperbuat terhadap diri Anda. Jika Anda ingin orang lain memperlakukan Anda secara menyenankan dan/atau secara adil, maka Anda pun harus memperlakukan orang lain secara menyenangkan dan/atau secara adil pula. Tindakan ini merupakan wujud kasih guna menjamin terciptanya suatu kedamaian dalam masyarakat. Gagasan yang tidak kalah menariknya adalah etika keutamaan upeksa (tenggang rasa atau toleran). Gagasan ini berlaku pada ungkapan sebagai berikut. Belahan pane belahan paso (Pecahan pane [belanga kecil] pencahan paso [belanga] Celebingkah beten biu (Pecahan keramik di bawah pohon pisang) Artinya Ada kene ade keto (Ada begini ada begitu) Gumi linggah ajak liu (Dunia ini luas dan penghuninya banyak) Ungkapan ini merupakan kearifan sosial yang bermakna memberikan penyadaran kepada kita bahwa dunia sebagai ruang bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas sosial memang luas. Berkenaan dengan itu maka penduduknya banyak pula. Bahkan yang tidak kalah pentingnya sebagai implikasi dari dunia yang luas dan penghuninya yang banyak maka keragaman atau kepluralitasan menjadi tidak terhindarkan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan demikian kepluralitasan merupakan keniscayaan bagi kehidupan manusia sehingga upeksa tidak saja menjadi amat penting, tetapi merupakan pula suatu keharusan bagi umat manusia. Bahkan gagasan upeksa pada ungkapan tersebut tidak saja upeksa pasif (mengakui toleransi secara teoretis), tetapi juga upeksa aktif (mewujudkannya dalam tindakan). Toleransi Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 58 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 negatif dan toleransi positif amat penting guna mewujudkan terbentuknya masyarakat pluralistik yang berkedamaian (Baghi ed, 2012). Etika keutamaan lainnya, yakni ksama yang bermakna mudah memberi maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemberian maaf tidak saja bermakna bahwa yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan berjanji memperbaiki dirinya, tetapi kita yang memberikannya maaf secara tulus ikhlas, secara otomatis tidak memperpanjang lagi permasalahan. Pascapemberian maaf maka kedisharmonisan pada tataran psikologis dan sosial menjadi ternetralisir. Hal ini amat penting, mengingat, jika kita tidak memaafkannya dan kita secara terus-menerus memojokkan orang yang bersalah – apalagi yang bersangkutan telah meminta maaf, maka kearifan lokal berbentuk sesenggakan yang menyatakan “cicing kebelet (malikin negor)” bisa berlaku. Hal ini berkaitan dengan makna sesenggakan tersebut, yakni ibarat anjing terkepung bisa berbalik lalu menggigit. Dalam konteks ini orang bersalah, lalu dipojokkan secara terus-menerus bahkan disertai dengan kata-kata kasar, padahal yang bersangkutan telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Kondisi ini dapat menimbulkan kondisi cicing kebelet (malikin negor), yakni dia bisa berubah menjadi berani melawan, bahkan tidak menutup kemungkinan dia siap melakukan pembunuhan (Ginarsa, 2009). Walaupun sesenggakan cicing kebelet tidak secara langsung menyebutkan tentang ksama, namun secara implisit terkait dengan ksama. Gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari makna yang terkandung di dalam sesenggakan cicing kebelet bahwa seseorang tidak boleh memojokkan orang lain yang bersalah secara terusmenerus, melainkan memberikannya peluang untuk mengakui kesalahannya dan sekaligus memberikannya kesempatan untuk meminta maaf dan kitapun memaafkannya. Tindakan memaafkannya atau ksama merupakan tindakan yang lebih tepat daripada memojokkan orang bersalah secara terus-menerus. Sebab, sesenggakan cicing kebelet mengajarkan bahwa tindakan memojokkan seseorang yang bersalah secara berlebihan dapat mengakibatkan dia menjadi kehilangan rasa takut dan besamaan dengan itu dia pun bisa berubah menjadi agresif, yakni tak ubahnya seperti cicing keselek – akan menggigit orang yang memojokkannya. Beberapa contoh ini menunjukkan bahwa etika keutamaan Hindu seperti terlihat pada Bagan 1, setelah masuk ke suatu komunitas lokal melalui lokalisasi Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 59 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 sehingga melahirkan kearifan lokal sebagai skemata dalam kehidupan bermasyarakat. Pola ini tidak saja berlaku pada beberapa contoh etika keutamaan Hindu seperti dipaparkan di atas, tetapi bisa pula berlaku pada etika keutamaan yang lainnya (Bagan 1). Contoh aneka etika keutamaan, yakni ahimsa, karuna, upeksa, dan ksama seperti diuraikan di atas, tidak berdiri sendiri, tetapi bisa berkaitan dengan konsep-konsep etika keutamaan lainnya. Misalnya, jika seseorang menyatakan bahwa “yen timpuge aji tahi, de balese aji tahi, bales aji bunga” – pencerminan dari ahimsa, begitu pula ungkapan bahwa “yen jimpite sakit, eda nyimpit anak len, karana ia pasti sakit” – pencerminan dari karuna, maka tidak bisa dipungkiri bahwa butir-butir etika keutamaan lainnya, yakni maitri (persahabatan atau persaudaraan), mudita (simpatik atau bersimpati), adrobah (sikap ramah), acapalam (kesantunan, kejatmikan), advesa (tidak membenci), akrodah (tidak marah), priti (berpandangan bahwa semua manusia adalah sama) dan satya (jujur) secara otomatis menyertainya. Sebab, jika seseorang ingin mengembangkan kasih sayang misalnya, maka etika-etika keutamaan lainnya harus hadir sebagai akibat dan/atau sebagai aspek penting yang menyertainya. 5. Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal (Suatu Wacana Awal) Manusia adalah Homo socius, yakni selalu berada dalam interaksi sosial secara meruang dan mewaktu. Interaksi sosial tidak terlepas dari komunukasi, mengingat bahwa “... komunikasi merupakan hal yang terpenting atau vital bagi manusia. Tanpa komunikasi maka manusia bisa dikatakan ‘tersesat’ dalam belantara kehidupan ini” (Nasrullah, 2012: 1). Manurut Ruben dan Stewart (2013: 19) “komunikasi manusia adalah proses melalui mana individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungan”. Ada pula yang mendefinisikan komunikasi berarti “memberikan, menyampaikan, atau bertukar gagasan, pengetahuan, atau informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun melalui tanda-tanda” (Kamus Inggris Oxford dalam Ruben dan Stewart, 2013: 15). Dengan berpegang pada gagasan ini maka komunikasi mensyarakatkan ada agen yang berkomunikasi (komunikator), yakni mereka yang terlibat dalam Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 60 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 kegiatan bertukar informasi, ide atau pesan secara lisan, tulisan dan/atau melalui tanda-tanda. Mereka terikat oleh ruang, waktu, tujuan,` dan membentuk suatu tindakan berpola. Dengan meminjam gagasan Ibrahim (1992) kesemuanya ini tertikat pada tiga aspek, yakni: pertama, pengetahuan linguistik menyangkut kemampuan berbahasa, baik bahasa verbal maupun nonverbal, termasuk di dalamnya bahasa tubuh. Kedua, keterampilan interaksi, menyangkut menguasaan norma-norma interaksi dan interpretasi terhadap ruang, waktu, dan tindakan sosial dalam konteks pencapaian tujuan dalam suatu komunikasi. Ketiga, pengetahuan kebudayaan menyangkut penguasaan atas berbagai nilai yang digunakan sebagai habitus dalam bertindak termasuk di dalamnya berkomunikasi. Dengan berpegang pada gagasan ini tampak bahwa komunikasi tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan kebudayaan. Dalam konteks inilah seperti terlihat pada Bagan 1, etika keutamaan Hindu baik dalam bentuk teks asli – memakai bahasa Sansekerta maupun teks lokal dalam bentuk kearifan lokal – ungkapanungkapan tradisional sebagai hasil dari lokalisasi, memiliki kedudukan amat penting dalam komunikasi. Adapun kedudukannya, adalah pengetahuan kebudayaan yang tidak saja saja sebagai pusat orientasi, tetapi juga sebagai habitus dalam berkomunikasi pada suatu arena sosial – memijam gagasan Bourdieu (2010, 2011) – beberapa karya yang membahas gagasan Bourdieu (Haryatmoko, 2010, Jenkin, 2004, 2014). Dengan cara ini maka komunikasi sebagai suatu aktivitas prosesual yang di dalam tidak sekedar melibatkan manusia yang bertukar informasi, tetapi bisa pula bertarung untuk memperebutkan suatu modal dan sekaligus juga berkelas, menjadi jelas arahnya. Dalam konteks ini pertarungan memperebutkan modal sebagai suatu keniscayaan yang menyertai komunikasi dalam suatu arena, menjadi jadi terbebas dari berbagai bentuk tindakan kekarasan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya, karena seperti terlihat pada Bagan 1, ada habitus atau skemata yang mempedomaninya, yakni etika keutamaan Hindu dan/atau kearifan lokal sebagai hasil lokalisasi atas etika keutamaan Hndu. Jika gagasan ini bisa diwujudkan maka interaksi sosial dalam suatu arena – memuat aktivitas komunikasi maka secara fundamental harus berbingkaikan pada Tat Twam Asi. Artinya, siapapun yang berkomunikasi pada suatu arena maka habitus pertama dan utama yang harus dipegang adalah asas Tat Twam Asi. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 61 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Gagasan ini menimbulkan implikasi bahwa hubungan komunikatif antaragen yang bersaing memperebutkan suatu modal atau bahkan berkelas sosial seperti dikemukakan Bourdieu (2010, 2011), tidak boleh saling me-liyan-kan yang berujung pada yang satu meniadakan yang lainnya – kekerasan atau himsa, tetapi dilandasi oleh rasa persaudaraan. Persaudaraan terjadi karena secara esensial kita memiliki kesamaan dan pertalian satu sama lainnya, yakni berbentuk Atman dalam diri makhluk hidup adalah Brahman yang menubuh. Berdasarkan gagasan ini maka komunikasi berbingkai Tat Twam Asi seperti terlihat pada Bagan 1 secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari etika keutamaan Hindu dan/atau kearifan lokal. Aspek-aspeknya sebagai berikut. (a) Maitri, yakni komunikator tidak menempatkan dirinya sebagai lawan atau bahkan saling me-liyan-kan, tetapi mereka terikat pada suatu hubungan persahabatan atau persaudaraan. (b) Karuna, yakni komunikator terikat pada welas asih atau belas kasih, yakni menganut dalil, yakni “Jangan berbuat terahadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak diinginkan akan diperbuat terhadap diri Anda”, “Jangan kaulakukan terhadap orang lain apa yang tidak kaumaui dilakukan terhadapmu”, ”Lakukan apa yang ingin orang lain lakukan untuk Anda”, “Hendaknya memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan” atau “Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri”. (c) Mudita, yakni dalam berkomunikasi seseorang tidak saja mengembangkan sikap simpatik tetapi juga empatik terhadap orang yang diajak berkomunikasi. (d) Upeksa, yakni dalam berkomunikasi seseorang bersikap tenggang rasa atau toleransi terhadap perbedaan latar belakang fisikal, kebudayaan, agama, dll. Perbedaan tidak dianggap musibah, tetapi berkah bagi kehidupan, mengingat menurut asas rwa bhineda bahwa perbedaan memberikan peluang bagi terciptanya kehidupan yang berkomplementer. Penerimaan asas toleransi tidak saja bersifat pasif, tetapi juga bersifat aktif. (e) Ahimsa (nirkekerasan), yakni seseorang tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap orang yang diajak berkomunikasi, Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 62 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 misalnya kekerasan psikologis, kekerasan bahasa, kekerasan simbolik apalagi kekerasan fisik baik secara idividual dan/atau secara kolektif. Apa pun tindakan kekerasan (himsa) yang dilakukan terhadap manusia lainnya guna mencapai suatu tujuan tidak dibenarkan adanya. Adrobah, yakni dalam berkomunikasi seseorang bersikap (f) ramah sehingga suasana komunikasi menjadi sangat menyenangkan. Acapalam, (g) artinya dalam berkomunikasi seseorang mengikuti adat sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Advesa, yakni dalam berkomunikasi sseorang harus (h) membebaskan diri persaan membenci pihak lawan yang diajak berkomunikasi. Akrodah, (i) yakni dalam berkomunikasi seseorang hendaknya mampu membebaskan dirinya dari kemarahan mengingat kemarahan bisa mengalahkan asas rasionalitas. Priti, (j) yakni dalam berkomunikasi seseorang berpandangan bahwa semua manusia adalah sama sehingga tindakan yang mencedrai rasa keadilan secara otomatis tidak dibenarkan adanya. Satya, yakni dalam berkomunikasi seseorang harus jujur, (k) tidak saja dalam pikiran, tetapi juga dalam ucapan dan tindakan sosial. Ksama, yakni dalam berkomunikasi seseorang bersedia (l) mengakui kesalahan atas tindakan yang dilakukan dan sekaligus bisa saling memaafkan sehingga harmoni psikologis dan harmoni sosial terwujudkan. Pendek kata, butir-butir di atas hanya merupakan bagian kecil dari etika keutamaan Hindu yang bisa digunakan sebagai habitus dalam berkomunikasi pada suatu arena sosial. Jika gagasan ini bisa diwujudkan dalam tindakan berkomunikasi maka tidak saja asas Tat Twam Asi bisa diwujudkan, tetapi yang tidak kalah pentingnya ranah sebagai ruang pertarungan untuk memperebutkan modal dan sekaligus berkelas sosial akan terbebas dari tindakan kekerasan. Pencapaian sasaran ini dilakukan lewat tindakan komunikatif atau dialog yang melibatkan berbagai agen dengan berlandaskan pada etika keutamaan Hindu. Apapun tindakan yang dilakukan pada saat manusia berkomunikasi dalam suatu arena, sasarannya tidak sekedar mewujudkan apa yang menjadi tujuan seseorang, Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 63 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan kedamaian di dunia maupun di alam kelanggengan baik dalam bentuk pencapaian surga atau terminal akhir – tujuan tertinggi dan finalis dalam agama Hindu apa yang disebut moksha. Apa yang dikemukakan pada gagasan di atas tidak sekedar sebagai paradigma dalam membangun komunikasi yang sehat, tetapi yang tidak kalah pentingnya, bisa pula disebut komunikasi Hindu. Komunikasi Hindu tidak saja menyangkut mengapa dan bagaimana manusia berkomunikasi pada suatu arena guna memperebutkan suatu modal, tetapi yang tidak kalah pentingnya apa yang dilakukan adalah tunduk pada Tat Twam Asi dan etika keutamaan yang menyertainya, yakni maitri, mudita, adrobah, acapalam, advesa, akrodah, priti, satya, dll. Berbagai etika keutamaan Hindu ini, seperti terlihat pada contoh-contoh di atas acapkali mengalami lokalisasi dalam bentuk kearifan lokal. Dengan demikian berbicara tentang hakikat paradigma komunikasi Hindu, pada dasarnya tidak saja menekankan pada etika keutamaan Hindu, tetapi juga kearifan lokal. Kearifan lokal amat penting tidak saja karena kearifan lokal bisa jadi merupakan lokalisasi dari etika keutamaan Hindu, tetapi bisa pula sebagai hasil pengalaman kolektif yang teruji kemanfaatannya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jika gagasan ini dibuat formulasinya maka dapat digambarkan dalam suatu rumus atau bahkan bisa pula disebut dalil, yakni “Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan lokal”. Dengan rumusan lain gagasan tersebut bisa pula dikemukakan, yakni “Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal = Paradigma Komunikasi Hindu”. Budyatna dan Ganiem (2011) menunjukkan bahwa hubungan komunikasi pada tingkat sosiologis bisa dipilahkan menjadi dua, yakni hubungan sosiologis formal dan hubungan sosiologis informal. Hubungan sosiologis formal mengacu kepada suatu interaksi yang di dalamnya melibatkan suatu komunikasi yang formal yang ditandai oleh penerapan tata aturan yang ketat dan memakai sistem komonadom misalnya berlaku pada dinas militer. Hubungan sosiologis informal adalah interaksi sosial yang melibatkan suatu komunikasi yang kurang lebih sama dengan yang formal tetapi pada tingkat yang lebih longgar. Pola hubungan seperti ini terlihat misalnya pada berbagai lembaga di luar dinas militer. Pemberlakuan Paradigma Komunikasai Hindu yang bertumpu pada Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal, tidaklah menghilangkan kedua pola Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 64 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 hubungan sosiologis tersebut – karena telah melembaga, tetapi yang lebih penting, meminjam gagasan Budyatna dan Ganiem (2011) adalah terfokus pada usaha memberikan apa yang disebut keadaan kultural yang mengelilingi peristiwa komunikasi. “Konteks kultural meliputi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, sikapsikap, makna, hierarki sosial, agama, pemikiran mengenai waktu, dan peran dari para partisipan” (Samovar dan Porter dalam Budyatna dan Ganiem, 2011). Dengan berpegang pada gagasan ini maka Etika Keutamaan Hindu + Kerifan Lokal sebagai modal bagi pembentukan Paradigma Komunikasi Hindu, bisa diposisikan dalam konteks kultural atau meminjam gagasan Ibrahim (1992) bisa disebut sebagai pengetahuan kebudayaan. Gagasan ini menimbulkan implikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh para agen pada saat berkomunikasi, selain berpatokan pada tata aturan yang bersifat formal – bahkan bisa pula dilengkapi dengan kebiasaan, bisa pula diperkuat oleh konteks kultural, yakni Etika Keutamaan Hindu + Kerifan Lokal (lokalisasi dari etika keutamaan Hindu dalam bentuk uangkapan-ungkapan tradisional sebagai habitus yang melahirkan tindakan sosial dan/atau artefaktual). Butir-butir etika keutamaan Hindu seperti terlihat pada Tabel 1, jika dikaitkan dengan gagasan Swami Chinmayananda (dalam Bhalla, 2010: 4) tentang kasih adalah dasar dari agama Hindu maka substansinya bisa dikembalikan ke dasarnya, yakni kasih sayang. Dengan kata lain bisa pula dikemukakan bahwa butir-butir keutamaan Hindu seperti terlihat pada Bagan 1 pada dasarnya merupakan pencerminan dan/atau bermuara dari kasih sayang. Kasih sayang yang melahirkan melahirkan perilaku tidak melakukan kekerasan toleransi, persahabatan, empati dan/atau simpati, suka memaafkan, dll. Manusia tidak mungkin bertindak seperti ini jika mereka tidak berpegang pada kasis sayang. Kasih sayang bermuara pada Tat Twam Asi. Tat Twam Asi = Aham Brahman melahirkan gagasan bahwa semua makhluk hidup adalah bersaudara sehingga mereka harus mengembangkan belas kasih. Berbagai kajian menunjukkan pula bahwa belas kasih merupakan kebutuhan dasar manusia karena terkait dengan aspek biologis dan sosilogis (Atmadja, 2014: 209-210). Dengan demikian berbicara tentang etika keutamaan Hindu secara esensial ada dua aspek penting, yakni Tat Twam Asi dan belas kasih. Ibarat mata uang logam, keduanya tidak terpisahkan dalam konteks mewujudkan kedamian bagi umat manusia. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 65 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Bertolak dari gagasan ini maka berbicara tentang Paradigma Komunikasi Hindu bisa pula dirumuskan suatu formulasi lain, yakni Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu (Tat Twam Asi + Belas Kasih) + Kerifan Lokal atau Etika Keutamaan Hindu (Tat Twam Asi + Belas Kasih) + Kerifan = Paradigma Komunikasi Hindu. Artinya, komunikasi sebagai keniscayaan bagi manusia (umat Hindu) secara ideal harus berpegang pada habitus atau skemata, yakni apa yang sisebut etika keutamaan Hindu yang secara esensial mengacu kepada Tat Twam Asi dan belas kasih, tanpa mengabaikan kearifan lokal. Kearifan lokal amat penting mengingat bahwa banyak kearifan lokal secara esensial merupakan lokalisasi dari etika keutamaan Hindu. 6. Penutup Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa agama Hindu sebagai agama dunia, sesampainya di Indonesia (Jawa, Bali) maka konsepkonsepnya –khusunya etika keutamaan Hindu banyak yang mengalami lokalisasi dalam bentuk kearifan lokal. Etika keutamaan Hindu dan/atau kearifan lokal amat penting, karena bisa dipakai sebagai habitus atau skemata bagi tindakan sosial manusia, termasuk di dalamnya bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lainnya dalam suatu arena yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Bahkan yang tidak kalah pentingnya etika keutamaan Hindu dan/atau kearifan lokal bisa pula dipakai sebagai modal kultural untuk membangun paradigma komunikasi Hindu yang bisa diformulasikan ke dalam rumus, yakni Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu = Kearifan Lokal. Esensi etika keutamaan Hindu adalah Tat Twam Asi dan Kasih Sayang. Dengan demikian paradigma komunikasi Hindu bisa pula dirumuskan dengan suatu formula lain, yakni Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu (Tat Twam Asi + Belas Kasih) + Kerifan Lokal. Jika formula ini bisa diwujudkan dalam berkomunikasi atau secara luas dalam berbagai tindakan sosial dalam masyarakat maka kedamaian pada tataran individu dan/atau masyarakat secara otomatis terwujudkan secara baik dan benar. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 66 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 DAFTAR PUSTAKA Armstrong, Karen. 2013. Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih. [penerjemah T. Hermayah]. Bandung: Mizan. Atmadja, Nengah Bawa. 2001. Reformasi Ke Arah Kemajuan Yang Sempurna dan Holistik: Gagasab Perkumpulan Sura Kanta Tentang Bali di Masa Depan. Surabaya: Paramita. Atmadja, Nengah Bawa. 2010. Ajeg Bali: Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi. Yogyakarta: LKiS. Atmadja, Nengah Bawa. 2010a. Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Atmadja, Nengah Bawa. 2014. Saraswati Dan Ganesha Sebagai Simbol Paradigma Interpretativisme Dan Positivisme: Visi Integral Mewujudkan Iptek dari Pembawa Musibah Menjadi Berkah bagi Umat Manusia. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 67 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Denpasar: Pustaka Larasan bekerja sama dengan IBIKK BCCC Undiksha Singaraja dan Universitas Hindu Indonesia. Baghi, Felix [Ed.]. 2012. Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Maumere: Penerbit Ledalero. Bertens, K. 2011. Etika Biomedis. Yogyakarta: Kanisius. Bhalla, Prem P. 2010. Tata Cara, Ritual dan Tradisi Hindu. [penerjemah. Diah Sri Pandewi]. Surabaya: Paramita. Bourdieu, Pierre. 2010. Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. [penerjemah. Yudi Santosa]. Bantul: Kreasi Wacana. Bourdieu, Pierre. 2011. Choses Dites Uraian & Pemikiran. [penerjemah. Ninik Rochani Sjams]. Bantul: Kreasi Wacana. Budyatna, Muhammad dan Leila Mona Ganiem. 2011. Teori Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta: Kencana. Coedes, George. 2010. Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Darmawan, Darwin. 2014. Identitas Hibrid Orang Cina. Yogyakarta: Gading Publishing. Darmayasa. 2012. Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan). Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam. Fashri, Fauzi. 2014. Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasustra. Gellner, David N. 2009. “Pendekatan Antropologis”. Dalam Peter Connolly [ed]. Aneka Pendekatan Studi Agama. [penerjemah. Imam Khoiri]. Yogyakarta: LKiS. Ginarsa, Ketut. 1980. Paribasa Bali. Denpasar: Kayumas Agung. Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ibrahim, Abd. Syukur. 1994. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi. Surabaya: Usaha Nasional. Jendra, I Wayan. 2004. Karmaphala Pedoman dan tuntunan Moral Hidup Sejahtera, Bahagia, dan Damai. Denpasar: Deva. Jenkins, Richard. 2010. Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. [penerjemah. Nurhadi]. Bantul: Kreasi Wacana. Koentjaraningrat. 2015. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 68 SADHARANIKARAN- Volume 1, Nomor 1. Mei 2015 Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Magnis-Suseno, Franz. 1991. Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. Morissan. 2013. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Jakarta: Kencana. Nasrullah, Rulli. 2012. Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber. Jakarta: Kencana. Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka. Putra, Ngakan Putu. 2014. Kamu adalah Tuhan. Denpasar: Media Hindu. Ranganathananda, Swami. 2000. Pesan Universal Bhagavad Gita. [penerjemah. Dewa K. Suratnaya, dkk]. Denpasar: Media Hindu. Ratri, Anjali. 2015. Pesan Cinta Kahlil Gibran Kumpulan Syair & Mutiata Cinta dari Sang Guru Cinta Sejati Kahlil Gibran. Solo: Abata Press. Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2013. Komunikasi dan Perilaku Manusia. Jakarta: RajaGrafindo Pustaka. Salam, Burhanuddin. 1997. Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Samuel, Hanneman. 2010. Emile Durkheim: Riwayat, Pemikiran dan Warisan Bapak Sosiologi Modern. Depok: Kepik Ungu. Sandika, I Ketut. 2014. Membentuk Siswa Berkarakter Mulia Melalui Pola Pembelajaran Pendidikan agama Hindu: Telaah Teks Kitab Chandogya Upanisad. Surabaya: Paramita. Suhardana, K.M. 2009. Dharma Jalan Menuju Kebahagiaan & Moksa. Surabaya: Paramita. Suhardana, K.M. 2009. Catur & Sad Paramita Jalan Menuju Keluhuran Budi. Surabaya: Paramita. Tinggen, I Nengah. 1988. Aneka Rupa Paribasa Bali. Denpasar: Rika Dewata. Visvanathan, Ed. 2004. Apakah Saya Orang Hindu? [penerjemah. N.P. Putra & Sang Ayu Putu Renny. Denpasar: Pustaka Manik Geni. Nengah Bawa Atmadja : Paradigma Komunikasi Hindu = Etika Keutamaan Hindu + Kearifan Lokal 69