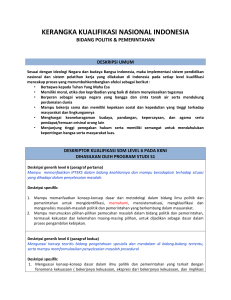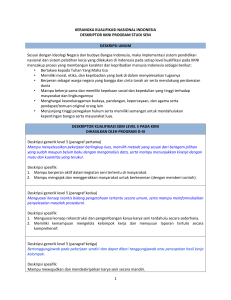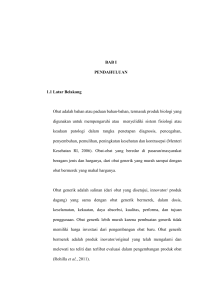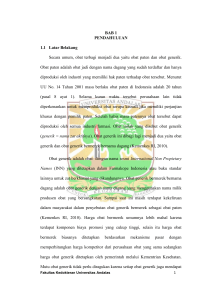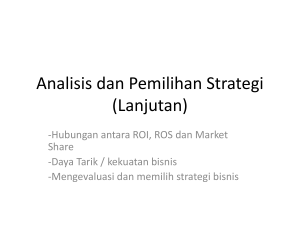09:12 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Pelepasan harga obat pada
advertisement

Obat Bermerek Kuasai Pasar Selasa, 23 Februari 2010 | 09:12 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Pelepasan harga obat pada mekanisme pasar mengakibatkan pasar dikuasai obat bermerek atau bernama dagang ketimbang obat generik. Padahal, obat bermerek dengan kandungan yang sama dengan obat generik harganya bisa jauh lebih mahal daripada obat generik. Berdasarkan pemantauan, Senin (22/2/2010), sejumlah dokter di beberapa puskesmas dan rumah sakit pemerintah masih tetap meresepkan obat bermerek untuk pasien. Kewajiban untuk meresepkan obat generik sesuai kondisi medis pasien belum sepenuhnya dipatuhi. Akibatnya, pasien dirugikan karena harus membayar obat dengan harga jauh lebih mahal. ”Pemerintah harus berperan besar dan tegas dalam mengatur harga obat sehingga masyarakat tidak dirugikan,” kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia sekaligus anggota Tim Rasionalisasi Harga Obat Generik Nasional di Kementerian Kesehatan Marius Widjajarta. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2005 pasar obat nasional yang mencapai Rp 21,07 triliun, pasar obat generik sangat minim hanya Rp 2,52 triliun. Adapun pada tahun 2009 pasar obat naik mencapai Rp 30,56 triliun. Meski demikian, pasar obat generik justru turun menjadi hanya Rp 2,37 triliun. Farmakolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof Iwan Dwiprahasto, mengatakan, obat generik sulit menjadi populer karena tidak didukung struktur yang memadai. ”Regulasi yang ada belum benar-benar kuat mengontrol dan mengawasi semua dokter untuk meresepkan obat generik,” kata Iwan. Dianggap tidak ampuh Sementara di masyarakat, obat generik masih dipandang sebagai obat untuk orang miskin, obat puskesmas, obat curah, dan dianggap tidak ampuh. ”Selain itu, obat generik juga tidak pernah diiklankan dan dokter lebih banyak mengetahui tentang obat bermerek karena kerap didatangi petugas penjual obat. Jaminan ketersediaan obat generik juga masih jadi masalah,” ujarnya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Anthony Ch Sunarjo mengatakan, perusahaan farmasi tentu mendukung program obat generik yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, murahnya harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah dan masih kecilnya pasar membuat obat generik tidak terlalu menarik. ”Perhitungan harga itu tidak sederhana dan begitu banyak faktornya,” ujarnya. Tidak hanya kalkulasi biaya produksi, promosi, dan distribusi, melainkan faktor psikologis harga. ”Sebagian masyarakat meyakini harga tidak menipu. Begitu harga obat bermerek terlalu murah malah dikira tidak ampuh atau tidak berkualitas,” ujarnya. Sekretaris Korporat PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius menjelaskan, pasar obat generik selama ini lebih banyak didorong pemerintah. ”Kelihatannya belum otomatis bergerak dalam saluran distribusi obat generik baik rumah sakit, apotek, dan dokter. Kalau hanya pemerintah yang mendorong, itu sulit dilakukan,” katanya. Sebagai pelaku usaha, pihaknya selalu melihat peluang pasar. Dari total volume penjualan obat, porsi untuk obat generik hanya 9-10 persen karena selama ini umumnya hanya bisa dipasarkan di sektor pemerintah, misalnya di rumah sakit umum daerah. Adapun penyedia layanan swasta bebas memilih antara peresepan obat generik ataupun jenis obat lain. Rasionalisasi harga Saat ini, setidaknya ada 8-12 produsen obat generik dan tiga di antaranya badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain, setidaknya ada 204 perusahaan farmasi yang terdiri dari 31 perusahaan asing, empat BUMN, dan sisanya perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau swasta nasional di Indonesia. Untuk mendorong minat produsen, pada 27 Januari 2010 pemerintah melakukan rasionalisasi harga obat. Dari 453 jenis obat generik, sebanyak 106 jenis obat harganya turun, 33 jenis obat harganya naik, dan 314 jenis obat harganya tetap. Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun di Serang mengatakan bahwa industri farmasi perlu mengoptimalkan produksi obat generik. ”Namun, ujung tombak pemanfaatan obat itu tetap di tangan dokter,” ujarnya. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo mengatakan sulit hanya mengandalkan niat baik dokter untuk meresepkan obat generik. Diperlukan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan menggiring peresepan obat ke arah generic 18 Persen Obat Generik Tidak Tersedia Kamis, 11 Februari 2010 | 04:02 WIB Jakarta, Kompas - Sekitar 18 persen atau lebih dari 80 item obat generik tidak tersedia di pasar sehingga terjadi kekosongan obat di unit-unit pelayanan kesehatan, terutama di kawasan Indonesia Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kekosongan terjadi sejak setahun lalu. Hal itu terungkap dalam pengarahan pers mengenai rasionalisasi harga obat generik, Rabu (10/2). Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawaty mengatakan, obat yang tidak tersedia itu sebagai besar merupakan obat yang paling dibutuhkan masyarakat (fast moving) dan obat untuk menyelamatkan nyawa (life saving), seperti antibiotik, cairan infus, serta obat sirup anak- anak. Kekosongan obat tersebut memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Kendala penyediaan obat itu, antara lain, disebabkan biaya distribusi yang tinggi untuk wilayah Indonesia timur dan Indonesia tengah sehingga produsen enggan mendistribusikannya. Lebih dari 98 persen industri farmasi berada di Pulau Jawa dan beberapa di Sumatera. Rasionalisasi harga Untuk menjamin ketersediaan obat, Kementerian Kesehatan merasionalisasi harga obat. Pemerintah telah menetapkan harga 453 item obat generik lewat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang harga obat generik. Setelah rasionalisasi ditetapkan, terjadi penurunan harga 106 item obat, kenaikan harga untuk 33 item, dan sisanya, 314 item dengan harga tetap. Pabrik obat atau pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generik kepada rumah sakit pemerintah, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya dapat memasukkan biaya distribusi 5-20 persen dari harga neto apotek (HNA) plus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga patokan tertinggi selama ini menggunakan HNA plus PPN. Persentase tambahan biaya distribusi itu tergantung regional. Regional I, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, dan Banten, tidak diperkenankan menambah biaya distribusi. Adapun Regional IV, mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, diberikan tambahan biaya distribusi hingga 20 persen. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita Hendardji mengatakan, pemerintah akan memantau harga dan ketersediaan obat setelah rasionalisasi. ”Kami mengupayakan keterjangkauan harga obat generik,” ujarnya. Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non-Propieritary Names (zat berkhasiat yang dikandung). Adapun obat generik bermerek atau bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang produsen. Masih Banyak Salah Persepsi soal Obat Generik Jumat, 18 Desember 2009 | 16:12 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Masih terdapat kesalahan persepsi dalam masyarakat soal obat generik. Masyarakat masih ada yang mengira obat generik bermerek sebagai obat paten. Padahal, sebetulnya hanya merek dagang saja yang dipatenkan sedangkan zat aktif obat sudah lepas paten sehingga bisa dikopi atau dikenal dengan nama obat generik. "Adakalanya, dokter menyarankan pasien menggunakan obat paten agar lebih cepat sembuh ketimbang obat generik. Padahal, yang dimaksud obat paten oleh oknum dokter tersebut ialah obat generik bermerek. Kemauan dari dokter untuk memberikan resep obat generik masih sangat penting," ujar Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) sekaligus anggota Tim Rasionalisasi Harga Obat Generik Nasional di Departemen Kesehatan, Marius Widjajarta, Jumat (18/12/2009). Padahal, dengan bahan serupa dan adanya standarstandar yang telah ditentukan dalam produksi obat, tidak ada perbedaan diantara obat generik, baik bermerek ataupun tidak. Pada dasarnya terdapat dua jenis obat yakni obat paten dan generik. Di Indonesia obat paten hanya sekitar 7-8 persen. Umumnya, berupa paten internasional seperti obat antiretroviral (HIV), kanker dan flu burung. Harga obat tersebut biasanya mahal karena riset sehingga harga sepenuhnya ditentukan produsen. Selebihnya ialah obat generik yakni obat generik berlogo dan generik bermerek (yang menggunakan merek dagang). Harga eceran tertinggi tertinggi obat generik berlogo ditentukan pemerintah. "Permasalahannya ialah harga obat generik bermerek yang perbedaan harganya berkisar 20-200 kali berdasarkan survei empat tahun lalu dan tidak terlalu berubah hingga kini," ujar Marius. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Huzna Gustiana Zahir, mengatakan, pasien punya hak memilih obat yang harganya sesuai kemampuan finansialnya. "Dulu pernah diwacanakan agar dokter meresepkan obat hanya dengan nama generik atau zat aktifnya sehingga pasien dapat memilih obat yang harganya lebih sesuai. Beberapa perusahaan obat terkadang menghasilkan obat yang persis sama dengan merek dan harga berbeda. Khasiat obat generik bermerek dan berlogo pun sama," ujarnya. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui jenis dan peruntukan masing-masing obat yang diberikan. "Kalau menginginkan obat generik, pasien dapat meyampaikan kepada dokter," katanya. Huzna juga menyoroti ketersediaan obat generik berlogo yang relatif masih terbatas. Mengenai hal itu, Marius mengatakan, perhitungan harga eceran tertinggi obat generik berlogo telah memperhitungkan keuntungan produsen sekitar 40 persen dan distributor sekitar 10-20 persen. Perhitungan berdasarkan Harga Jual Pabrik atau yang sering disebut dengan COGS (Cost Of Goods Sales) yang telah memperhitungkan komponen mulai dari bahan baku sampai dengan transportasi hingga obat sampai ke tangan konsumen dengan patokan daerah terjauh di Indonesia. "Tim menentukan harga obat generik berlogo dua tahun lalu dengan nilai tukar 1 dollar sama dengan Rp 11.000. Dengan menguatnya rupiah, tidak ada alasan produksi tersendat dan barang menjadi langka karena biaya," tambah Huzna.