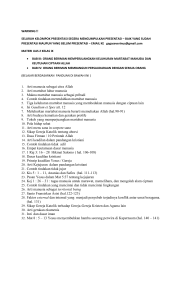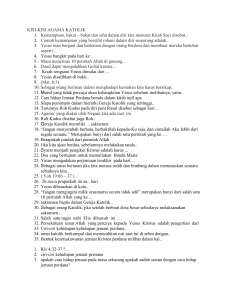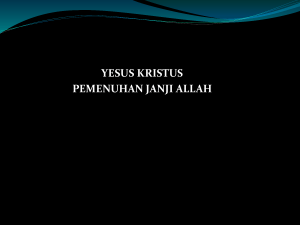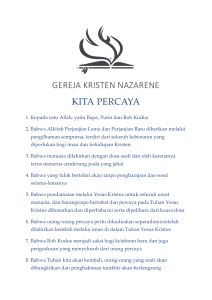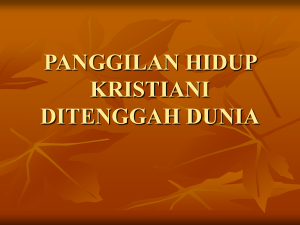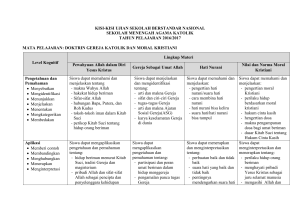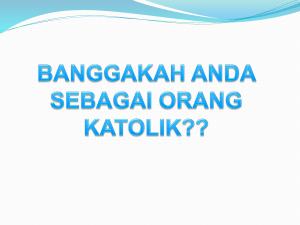KATOLISISME KATOLISISME Teologi bagi Kaum Awam Thomas P
advertisement

KATOLISISME KATOLISISME Teologi bagi Kaum Awam Thomas P. Rausch PENERBIT KANISIUS Katolisisme 015034 © Kanisius 2001 PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI) Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281 Kotak Pos 1125/Yk – Yogyakarta 55011 Telepon (0274) 588783, 565996, Fax (0274) 563349, 520549 E-Mail : [email protected] [email protected] Website : www.kanisius.co.id Diterjemahkan dari buku CATHOLICISM, At The Dawn of The Third Millennium, Thomas P. Rausch, The Liturgical Press, St. John’s Abbey, Collegeville, Minnesota 56321, 1996, oleh Agus M. Hardjana. Cetakan ke- 5 4 3 2 1 Tahun 05 04 03 02 01 Nihil Obstat : F. Hartono, SJ Yogyakarta, 7 Maret 2001 Imprimatur : J. Pujasumarta, Pr. Vikjen Semarang, 10 Maret 2001 ISBN 979-672-681-5 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta Kata Pengantar Buku ini dirancang sebagai buku antara katekismus bagi orang dewasa dan buku teologi. Buku ini disusun berdasarkan dua pertanyaan: apakah Katolisisme itu dan ke mana Gereja mengarah pada ambang abad ke-21, milenium ketiga? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sama, namun erat berkaitan. Katolisisme Secara umum istilah ”Katolisisme” digunakan untuk menyebut pengalaman Kristianitas yang dijalani bersama oleh orang-orang Kristiani dalam kesatuan dengan Gereja Roma. Secara populer ”Katolisisme” berarti komunitas umat beriman, Gereja historis yang kelihatan, dan tradisi yang hidup, yang seluruh akarnya berawal dari Gereja para Rasul. Dalam arti lebih luas, ”Katolisisme” kadang-kadang dimengerti mencakup Gereja-Gereja lain seperti Gereja Ortodoks dan Gereja-Gereja Anglikan, yang mempunyai tradisi amat dekat dengan tradisi Katolik. Tanpa mengingkari bahwa Gereja-Gereja Ortodoks dan Gereja-Gereja Anglikan memiliki tradisi yang serupa dengan tradisi Katolik, dalam buku ini pembahasan dipusatkan pada ”Katolisisme” dalam arti populer, yang berkaitan dengan Gereja yang disebut ”Katolik”. Kata sifat ”katolik” berasal dari kata Yunani kath’ holou, yang berarti ”menyangkut keseluruhan”. Kata itu diterapkan pada Gereja dalam arti ”seluruh” atau ”universal” oleh Ignasius dari Antiokhia sekitar tahun 115. Konsili Konstantinopel I (381) menambahkan kata itu pada syahadat dalam rumusannya tentang Gereja sebagai ”satu, kudus, katolik, dan apostolik.” Sesudah Kristianitas terbagi dua antara Kristianitas Barat dan Timur pada tahun 1054, Gereja-Gereja Timur mulai menyebut diri sebagai Gereja ”Ortodoks”, sementara Gereja Barat tetap dikenal sebagai ”Gereja Katolik”. Sejak zaman reformasi pada abad ke-16 menjadi semakin umum bahwa pada sebutan ”Gereja Katolik” ditambah dengan kata ”Roma”. Akan tetapi, Gereja itu sendiri terus menyebut diri dengan nama ”Gereja Katolik” saja dalam dokumen-dokumen resminya. Lalu apa arti ”Katolisisme” bagi mereka yang menjadi anggota Gereja Katolik sendiri? Bagi mereka, kata ”Katolisisme” pertama-tama berarti cara mengungkapkan iman Kristiani yang sifatnya khas eklesial. Gereja bagi orang Katolik jauh lebih dari sekadar lembaga religius yang kelihatan. Kata ”Katolisisme” mempunyai dimensi sakramental yang amat mistis, yang bagi dan melalui para anggotanya menjadi perantara hidup Ilahi yang penuh misteri. Sekurangkurangnya sejak abad ke-2 dan seterusnya, ciri perantaraan ini dikenal, sering digambarkan sebagai ibu yang melahirkan manusia melalui baptis, mengajar mereka melalui sabda, membawa mereka hidup dalam Kristus yang lebih dalam melalui sakramen-sakramen. ”Katolisisme” juga mempunyai arti universalitas atau katolisitas Gereja. Bila orang Katolik menyebut ”Gereja”, pada umumnya ia berpikir tentang seluruh Gereja. Gereja jauh lebih besar daripada umat lokal atau penjumlahan Gereja-Gereja setempat. Ecclesia catholica berarti baik kepenuhan Gereja maupun kesatuan Gereja-Gereja, karena Gereja yang satu itu ada dalam banyak Gereja. Paus sebagai Uskup Roma mengepalai kesatuan Gereja, dengan melambangkan universalitas dan katolisitasnya. Katolisitas Gereja bukan hanya menyangkut segi ruang atau geografi; ”katolisitas” mencakup keanggotaan dalam Gereja. ”Katolik” berarti ”di sini setiap orang diterima dengan baik”. Karena pengutusannya memaklumkan universalitas keselamatan dalam Yesus, Gereja harus memeluk dalam haribaannya segala bangsa, kelas, ras, dan budaya. ”Katolisitas” berarti bahwa Gereja merangkum dalam dirinya segala macam manusia – orang kudus dan orang berdosa, kaum kaya dan miskin, orang dewasa dan anak-anak, bahkan bayi. Gereja Katolik menjunjung tinggi keanekaragaman yang kaya ini. Gereja menampung dalam persekutuannya orang-orang yang suka berperang dan orang-orang yang memperjuangkan perdamaian, para teolog pembebasan dan para anggota Opus Dei, para Pekerja Katolik yang anarkis dan Kesatuan Katolik untuk Iman, kaum karismatik, kaum feminis, kaum tradisionalis, orang-orang yang hidup sendiri, orang-orang yang menikah, para rahib dan para rubiah, para pertapa, para imam, para penyembuh dan filsuf, kaum mistik, dan kaum aktivis. Ajaran tentang persekutuan para kudus memperluas persekutuan ini dan menjangkau semua orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, para kudus – yang dikanonisasi atau tidak – orang-orang suci dalam Kitab Suci Yahudi, dan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal namun belum masuk ke dalam kepenuhan hidup abadi. Daftar hal-hal yang oleh orang-orang Katolik diterima begitu saja sebagai ciri-ciri Katolisisme, meski tidak selalu khas baginya, meliputi: orang Katolik yang memiliki rasa kekhasan historis dari Gereja mereka, pelayanan hierarkis dan kewibawaan mengajarnya, dan penghormatan pada tradisinya. Iman Katolik bercirikan teologi inkarnasi, sakramentalitas, tradisi liturgis, berpusat pada Ekaristi, penghormatan kepada Maria dan penghormatan pada orang kudus, tradisi spiritualitas yang kaya, mistisisme, dan doa kontemplatif. Katolisisme mencakup hidup monastik, tarekat-tarekat religius, penghargaan atas nilai religius dalam seni, rasa mendalam tentang saling melengkapinya iman dan akal, pemahaman bersama baik tentang dosa dan penebusan, dan dengan demikian pentingnya komunitas, sistem persekolahan dan pelayanan kesehatan yang besar, ajaran sosial yang didasarkan atas martabat pribadi manusia, keterlibatan pada kegiatan misioner, dan tentu saja jabatan Paus. Dalam buku ini unsur-unsur Katolisisme itu akan dibahas. Setiap studi tentang Katolisisme mana pun, pertama, haruslah dimulai dengan menyajikan pandangan yang menyeluruh tentang iman dan ajaran Katolik. Tugas teologis kami yang sebenarnya adalah menunjukkan bagaimana iman Gereja muncul dari Kitab Suci dan sejarah Kristiani – yaitu, dari kehidupan umat Allah yang kudus – dan diungkapkan dalam lambang dan kisah, dalam ritual dan sakramen, dan pada akhirnya dalam bahasa teologis dan pernyataanpernyataan ajaran. Teologi yang baik membantu proses perkembangan ini menjadi jelas. Teologi yang baik juga harus mempunyai peranan penting untuk menyelidiki tradisi, menjelaskan bahasa religiusnya, menafsirkan kembali ajaran-ajaran yang telah kehilangan kekuatan untuk disajikan, dan menguji pernyataan-pernyataan imannya dari sudut pandang bidang ilmu lain dan keseluruhan tradisi Kristiani. Kedua, untuk mengerti Katolisisme sezaman, kita perlu mengetahui kekuatan-kekuatan dan gerakan-gerakan yang telah ikut membentuknya dalam abad ke-20. Katolisisme bukan hanya tradisi historis; Katolisisme adalah tradisi yang hidup, yang terus berkembang dan tumbuh, bahkan berubah. Khususnya kita perlu memperhitungkan pengaruh besar Konsili Vatikan II dalam membentuk Katolisisme. Menurut John O’Malley, ahli sejarah Gereja, ”tak pernah ada dalam sejarah Katolisisme sebelumnya sedemikian banyak perubahan dan sedemikian mendadak yang telah diundangkan dan dilaksanakan yang secara langsung mengenai kehidupan umat beriman, dan tak pernah ada sebelumnya penyesuaian pandangan yang sedemikian mendasar yang dituntut dari mereka.”1 O’Malley membandingkan Konsili Vatikan II dengan dua gerakan besar yang mendatangkan perubahan dalam sejarah Gereja, yaitu Reformasi Gregorius pada abad ke-9 dan Reformasi Luther pada abad ke-16. Reformasi Gregorius, dalam perjuangannya melawan penyalahgunaan penjualan jabatan-jabatan Gereja dan pengangkatan uskup-uskup, merupakan penolakan terhadap sistem feodal. Reformasi itu memberi kepada Gereja kemandirian besar dalam tata urusan duniawi dan mendatangkan pengembangan kepausan yang kuat yang memberi ciri pada Gereja Katolik dalam milenium kedua. Reformasi Luther mendatangkan perubahan paradigma teologis yang mengakibatkan perpecahan-perpecahan dalam Gereja Barat sampai dewasa ini. Diharapkan, Konsili Vatikan II, melalui pemeriksaan diri dan pembaruan yang diprakarsainya, pada suatu saat akan dilihat sebagai langkah menuju ke rekonsiliasi dan persiapan Gereja menyongsong milenium ketiga. Akan tetapi, pada waktu komunitas iman berusaha membaca ”tanda-tanda zaman” (GS 4) dan menegaskan kehadiran Allah yang penuh misteri berpangkal pada tantangan-tantangan baru dan keadaan-keadaan yang telah berubah, ada masalah-masalah serius yang menghadangnya. Dengan berbagai cara Gereja terbagi-bagi, dan ada banyak masalah yang jika tidak ditangani dengan bijak, dapat mendatangkan kerugian yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, kita juga perlu melihat masalah-masalah yang dihadapi Gereja dewasa ini dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Katolik pada saat ini. Untuk itu, dalam seri ini kita akan mulai uraian dengan Konsili Vatikan II dan mengakhiri dengan hal-hal yang dapat dianggap merupakan agenda Konsili yang belum selesai. Di sini, kita juga perlu menyampaikan sesuatu tentang budaya Katolisisme. Seperti budayabudaya lain, budaya Katolisisme merupakan lingkungan yang dibentuk bersama, dunia bentukbentuk lambang yang mengandung dan meneruskan makna dan nilai. Budaya mengubah dunia alamiah dan memungkinkan kita berhubungan satu sama lain secara manusiawi. Budaya Katolisisme mengubah budaya manusiawi kita, dengan menghubungkan kita dengan Allah dan kehadiran-Nya di dunia, terutama dalam komunitas manusia. Sebagai iman sakramental, Katolisisme ditampilkan baik oleh budaya yang diciptakannya – masa-masa liturgi, ruang-ruang kudus, lambang-lambang sakramental, pilihan-pilihan panggilan hidup, dan komunitas-komunitas yang beraneka ragam – maupun oleh teologi-teologi yang mengungkapkannya. Dengan demikian, kita harus berbicara tentang budaya Katolisisme, pandangannya tentang dunia, caracaranya mengalami yang kudus, pandangan-pandangan yang beraneka ragam tentang hidup Kristiani, perasaannya terhadap upacara keagamaan, cara-cara doanya, dan spiritualitasspiritualitas yang ber-beda. Menguraikan budaya ini mungkin merupakan tantangan yang nyata dewasa ini. Teologi selalu dapat ditemukan dalam buku, perpustakaan, dan diktat-diktat kuliah. Akan tetapi budaya Katolisisme merupakan perwujudan dari cara hidupnya. Budaya itu tidak sekadar menyangkut budi tetapi hati. Dewasa ini, budaya itu ada dalam bahaya untuk lenyap. Dalam tahun-tahun sesudah Konsili Vatikan II, kebanyakan orang Katolik terhanyut dalam budaya umum masyarakat yang beretos sekular dan tak banyak memberi ruang untuk yang kudus. Banyak tradisi devosional hilang, dan bersama hilangnya tradisi-tradisi itu, hilang juga Katolisisme kerakyatan. Di banyak lembaga pendidikan Katolik, pendidikan agama terbatas pada pelajaranpelajaran agama. Sementara anak-anak Katolik yang bersekolah atau berkuliah di lembagalembaga non-Katolik tidak selalu mendapat pelayanan pendidikan dalam agama mereka. Pendidikan lanjut kebanyakan orang Katolik terbatas pada khotbah dalam Ibadat hari Minggu. Banyak orang Katolik tidak lagi menjalankan agama dan iman mereka. Bersamaan dengan itu, banyak orang Katolik mau mempelajari iman mereka secara lebih mendalam. Di satu pihak, mereka malu lantaran tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang lain tentang ajaran iman mereka, dan di pihak lain, mereka mau mewariskan sesuatu kepada anak-anak mereka. Paroki-paroki yang menyelenggarakan program pendidikan agama tingkat lanjut, semacam kursus teologi bagi kaum awam, mendapatkan banyak peserta. Perayaan Ekaristi hari Minggu di lembaga-lembaga umum dan non-Katolik di kota-kota besar dihadiri banyak orang. Tidak sedikit orang Katolik bingung tentang iman mereka dan apa yang harus mereka percayai. Mereka terombang-ambing di antara orang-orang Katolik ”konservatif” dan ”progresif” atau di antara ajaran resmi Gereja dan pendapat-pendapat umum, terutama yang dilontarkan lewat media. Mereka tidak merasa nyaman terhadap kedua belah pihak. Sedang orang-orang Katolik lainnya berusaha menemukan jalan untuk menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dan diajarkan kepada mereka dengan ajaran-ajaran Gereja yang baru. Diharapkan, buku ini dapat membantu menyediakan hubungan-hubungan itu. Buku ini dimaksudkan bagi orang Katolik yang sudah akrab dengan Katolisisme, tetapi mau menggali lebih dalam lagi dalam tingkat yang lebih matang. Di antara mereka mungkin adalah orangorang Katolik muda yang tidak mendapat kesempatan studi teologi; mungkin orang Katolik yang mengalami pertobatan pada umur dewasa yang bertanya-tanya bagaimana mereka dapat memahami iman mereka lebih baik dan dapat menjelaskan kepada orang lain; mungkin orang yang hanya tertarik pada apa yang diimani oleh orang Katolik dan mengapa orang Katolik hidup dan berperilaku seperti itu. Untuk itu dengan sengaja buku ini disusun tak bersifat teknik, melainkan bersifat gabungan antara penyajian secara setia tradisi dan refleksi dan penafsiran teologis tentang di mana sekarang Gereja berada dan ke mana akan bergerak. Bapa Suci atas mandat Sinode Luar Biasa Para Uskup pada tahun 1985 telah menerbitkan Katekismus Gereja Katolik. Namun buku ini tidak disusun berdasarkan Katekismus itu. Buku ini bukan uraian resmi tentang iman Katolik, melainkan penyajian mengenai iman Katolik dalam konteks sezaman. Dengan demikian, sifatnya lebih historis, dan dengan demikian interpretatif. Buku ini membahas banyak topik yang tidak disinggung dalam Katekismus. Dalam penyusunan buku ini diusahakan agar catatan-catatan dibuat sesedikit mungkin. Dalam seluruh uraian, bahasa dibuat lancar dan kutipan-kutipan dimasukkan ke dalam teks. Namun demikian, ini tidak selalu mungkin dan teks-teks kutipan terpaksa disertakan. Untuk ini para pembaca dimohon memakluminya. Saya berterima kasih kepada Michael Glazier yang memberi saran kepada saya untuk menulis buku ini. Kepada Bill Cain, rekan Yesuit dan sahabat di Loyola Marymount, yang beberapa kali menekankan kepada saya tentang kebutuhan terbitnya buku semacam ini. Kebanyakan buku ini telah ditulis di Institute For Ecumenical and Intercultural Research di Collegeville pada musim gugur tahun 1994. Minat dan dukungan semua anggota Institute itu, baik rekan maupun staf, telah membuat saya senang selama saya tinggal dan bekerja di sana. Pada akhirnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Elizabeth Montgomery atas kerja pengetikannya dalam mempersiapkan penerbitan buku ini. Daftar Isi KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………… 5 DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………… 13 DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………………………………………… 17 I. GEREJA DAN KONSILI…………………………………………………………………… 19 1. 2. 3. 4. Katolisisme Pra–Vatikan II ……………………………………………………… Arus-Arus Pembaruan………………………………………………………………… Konsili Vatikan II: 1962-1965 ………………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 19 25 31 42 II. IMAN DAN JEMAAT YANG PERCAYA…………………………………… 45 1. 2. 3. 4. Hakikat Iman ………………………………………………………………………………… Umat Allah ……………………………………………………………………………………… Yesus dan Pemerintahan Allah……………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 45 55 64 76 III. GEREJA YANG KELIHATAN………………………………………………………… 79 1. Gereja dan Konsili ……………………………………………………………………… 80 2. Jemaat Para Murid……………………………………………………………………… 81 3. Pelayanan Resmi…………………………………………………………………………… 86 4. Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik…………………………………… 99 5. Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 111 IV. TRADISI YANG HIDUP …………………………………………………………………… 114 1. 2. 3. 4. Wahyu dan Tradisi ……………………………………………………………………… Ungkapan-Ungkapan Tradisi ………………………………………………… Tradisi Katolik ……………………………………………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 116 122 130 136 V. SAKRAMEN-SAKRAMEN DAN INISIASI KRISTIANI……… 139 1. 2. 3. 4. Prinsip Sakramental …………………………………………………………………… Sakramen Inisiasi………………………………………………………………………… Upacara Inisiasi Kristiani ………………………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 140 147 161 166 VI. HIDUP KRISTIANI DAN PANGGILAN MENJADI MURID ……………………………………………………………………………… 168 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panggilan Menjadi Murid ………………………………………………………… Perkawinan dalam Kristus ……………………………………………………… Imamat ……………………………………………………………………………………………… Komunitas Kristiani dan Hidup Religius ………………………… Hidup Sendiri, Tidak Menikah …………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 169 172 177 182 195 197 VII. DOSA, PENGAMPUNAN, DAN PENYEMBUHAN …………… 201 1. 2. 3. 4. 5. Dosa dalam Tradisi Kitab Suci……………………………………………… 203 Ajaran Tentang Dosa ………………………………………………………………… 209 Pengampunan dan Pendamaian……………………………………………219 Penyembuhan dan Pengurapan Orang Sakit………………… 226 Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 228 VIII. MORALITAS SEKSUAL DAN KEADILAN SOSIAL…………… 232 1. 2. 3. 4. Moralitas Seksual………………………………………………………………………… Keadilan Sosial……………………………………………………………………………… Hati Nurani dan Otoritas ………………………………………………………… Kesimpulan……………………………………………………………………………………… IX. DOA DAN SPIRITUALITAS 1. 2. 3. 4. 5. ………………………………………………………… 233 248 260 264 268 Jenis-Jenis Doa……………………………………………………………………………… 271 Spiritualitas……………………………………………………………………………………… 278 Spiritualitas-Spiritualitas Dewasa Ini…………………………………… 285 Mariologi ………………………………………………………………………………………… 294 Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 301 X. KEPENUHAN HARAPAN KRISTIANI ……………………………………… 304 1. Keselamatan dan Eskatologi……………………………………………………304 2. 3. 4. 5. Eskatologi Kristiani……………………………………………………………………… 309 Persekutuan Orang Kudus……………………………………………………… 320 Keselamatan di Luar Gereja…………………………………………………… 325 Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 327 XI. AGENDA YANG BELUM SELESAI…………………………………………… 330 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembaruan Liturgi ……………………………………………………………………… 332 Masalah Otoritas…………………………………………………………………………… 337 Wanita dalam Gereja ………………………………………………………………… 342 Ekumenisme…………………………………………………………………………………… 352 Dialog Antaragama……………………………………………………………………… 361 Kesimpulan……………………………………………………………………………………… 364 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………………… 368 DAFTAR SUMBER GAMBAR/FOTO …………………………………………………… 370 Daftar Singkatan Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II DH Dignitatis Humanae : Pernyataan tentang Kebebasan Beragama. DV Dei Verbum : Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi. GS Gaudium et Spes : Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern. LG Lumen Gentium : Konstitusi Dogmatis tentang Gereja. NA Nostra Aetate : Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristen. OE Orientalium Ecclesiarum : Dekrit tentang Gereja-Gereja Timur Katolik. PC Perfectae Caritatis : Dekrit tentang Pembaruan dan Penyesuaian Hidup Religius. PO Presbyterorum Ordinis : Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan para Imam. SL Sacrosanctum Concilium : Konstitusi tentang Liturgi Suci. UR Unitatis Redintegratio : Dekrit tentang Ekumenisme. Lain-Lain BEM Baptism, Eucharist and Ministry: Baptis, Ekaristi, dan Pelayanan DS Denzinger – Schönmetzer – Enchiridion Symbolorum – edisi ke-33 Freiburg: Herder, 1965 PL Patrilogia Latina WCC World Council of Churches: Dewan Gereja-Gereja Dunia I Gereja dan Konsili Pada waktu Paus Pius XII wafat pada tahun 1958, bagi para pengamat lepas, Gereja ada dalam keadaan bagus. Pada paruh abad ke-20 Gereja dipimpin oleh sejumlah Paus yang kuat, terutama Paus Pius XII sendiri, yang telah memimpin Gereja selama Perang Dunia II dan memusatkan energinya melawan ancaman komunisme pasca-Perang Dunia II. Gereja terus berkembang baik dalam jumlah maupun pengaruh. Seminari-seminari, biara-biara, dan pertapaan-pertapaan penuh penghuni sampai berkelebihan. Rumah-rumah religius didirikan di mana-mana di seluruh dunia. Teologi Katolik, jika tidak amat kreatif, amat ortodoks. Hampir tidak ada perbedaan pendapat, hampir tidak ada perselisihan. Orang-orang Katolik mengetahui siapa diri mereka. Mereka bangga akan Gereja dan memiliki identitas yang jelas tentang diri mereka. 1. Katolisisme Pra-Vatikan II Akan tetapi, ada sisi gelap dari gambaran di atas. Gereja Katolik pada pertengahan abad ke-20 melihat dirinya sebagai Gereja yang ada dalam keadaan terkepung bahaya. Karena kecurigaan terhadap dunia modern, Gereja mengambil sikap defensif. Keilmuan Katolik lumpuh oleh suasana curiga dan tidak percaya, yang mengikuti krisis Modernisme pada awal abad ke20. Buku-buku pengarang Katolik jarang diterbitkan tanpa sensor para penguasa Gereja. Para pengarang harus mendapatkan imprimatur (izin boleh terbit) dan nihil obstat (pernyataan yang menyebutkan isi buku tak berlawanan dengan ajaran Gereja) dari para petugas sensor resmi Gereja. Model satu-satunya yang dapat diterima untuk teologi adalah buku-buku pegangan dogmatik dari aliran Roma, buku-buku teologi yang bersandar pada neoskolastisisme yang abstrak dan ahistoris. Daripada mempersoalkan permasalahan-permasalahan baru dan menyelidiki sumber-sumber biblis dan historis, buku teks teologi itu menyajikan pendirian-pendirian tradisional dengan mengutip bukti-bukti biblis dan nomor-nomor Enchiridion Symbolorum oleh Denzinger, yang merupakan ringkasan ajaran-ajaran Paus dan Konsili-Konsili. Pada waktu Pius XII wafat menjelang akhir tahun 1950-an, sejumlah sarjana Katolik seperti Karl Rahner, Yves Congar, Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Teilhard de Chardin, dan John Courtney Murray dibungkam, dilarang menulis tentang topik-topik tertentu. Jika tidak taat, mereka dikenai sanksi disiplin. Ancaman bahwa buku-buku mereka ditaruh pada rak buku-buku yang dilarang membayang di atas kepala mereka. Profesor-profesor seminari dituntut mengucapkan sumpah melawan Modernisme setiap tahun. Gereja Katolik secara resmi tidak berminat pada ekumenisme, gerakan yang ditujukan untuk memulihkan kesatuan Gereja-Gereja yang terpecah-pecah. Gerakan ekumenis modern ini berasal dari pertemuan umat Kristiani Protestan dalam World Missionary Conference (Konferensi Pekabar Injil Dunia) di Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1910. Dari pertemuan itu, lahirlah Faith and Order Conference (Konferensi Iman dan Tata Dunia), yang untuk pertama kali berkumpul di Lausanne, Swiss, pada tahun 1928. Tidak lama kemudian, Paus Pius XII mengeluarkan ensiklik Mortalium Animos, yang melarang orang-orang Katolik ikut mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ekumenis yang diadakan oleh orang-orang non-Katolik. Pendekatan Katolik pada kesatuan Kristiani cukup jelas: ”Hanya ada satu jalan yang dapat memupuk kesatuan umat Kristiani, yaitu dengan mendorong kembalinya mereka yang sudah memisahkan diri dari kesatuan dengan Gereja Kristus yang benar.”2 Pendekatan ”kesatuan dengan Gereja yang benar” ini menjadi ciri pemikiran Katolik selama paruh pertama abad ke20. Orang-orang Katolik memandang orang-orang Kristiani di Gereja-Gereja lain sebagai orangorang baik, tetapi tersesat. Meskipun pada tahun 1949 Tahta Suci mengeluarkan surat yang memperbolehkan orang Katolik ikut serta dalam gerakan ekumenis dengan syarat yang amat ketat, dalam tahun-tahun sebelum Vatikan II kebanyakan orang Katolik diingatkan untuk tidak menghadiri ibadat Protestan atau bahkan memperbolehkan anak pergi menghadiri acara-acara pembinaan yang diadakan oleh umat Protestan. Teologi kaum awam yang asli baru mulai muncul. Gerakan awam yang dikenal dengan sebutan ”Catholic Action” (”Aksi Katolik”) berawal di Italia pada tahun 1930. Terutama melalui ungkapan Belgia dan Prancisnya, gerakan itu memberikan energi baru kepada Gereja Amerika Latin, dengan meletakkan dasar teologi pembebasan yang dikenal pada tahun 1960-an. Akan tetapi, Gereja resmi agaknya tidak dapat mengakui bahwa kaum awam juga ikut memiliki bagian dalam perutusan Gereja. Dalam dokumen-dokumen Gereja, ”kerasulan awam” dirumuskan sebagai ”kerja sama kaum awam dalam kerasulan hierarki.”3 Pelayanan merupakan hak istimewa para klerus. Secara liturgis, meski gerakan liturgi sudah berkembang di dalam Gereja sejak akhir abad ke-19, pada waktu wafatnya Pius XII, Roma berusaha melunakkan praktek ”Misa Dialog”. Dalam ”Misa Dialog”, umat berdoa dan menanggapi pemimpin ibadat dalam bahasa Inggris, sementara imam di altar berdoa dalam bahasa Latin. Gereja agaknya lebih memusatkan perhatian ke masa lampau daripada ke masa depan. Bukti-bukti untuk itu tak terbilang jumlahnya. Bagaimana Gereja Katolik dapat menjadi sedemikian mandeg? Dalam arti yang sebenarnya, Gereja belum pernah sembuh betul-betul dari keterkejutan yang diakibatkan oleh Reformasi pada abad ke-16. Sebagai akibat Reformasi, dalam waktu sekitar 40 tahun, separo Eropa telah menjadi Protestan. Namun, ada juga sebab-sebab lain yang membuat Gereja tidak mempercayai dunia modern. Revolusi ilmiah dan rasionalisme Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18 dengan serangan-serangan terhadap ajaran, kewibawaan, dan ritual Gereja membuat Gereja bersikap defensif. Kedua gerakan itu mengandaikan akal manusia yang otonom yang tidak memberi kemungkinan bagi wahyu atau yang transenden. Lalu, terjadilah revolusirevolusi pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19, termasuk revolusi Prancis. Revolusi itu berusaha mengubah pemerintahan Gereja dengan memaksa klerus untuk menaati undang-undang negara yang melepaskan otoritas yuridis atas Gereja di Prancis dari Paus. Akhirnya, revolusi itu berusaha membatasi praktek iman itu sendiri. Pada tahun 1863, Pius IX, yang dianggap cukup liberal pada awal masa kepausannya, menerbitkan Syllabus Errorum (Daftar Kesalahan-Kesalahan), daftar 80 konsep dan gerakan yang dianggapnya khas menjadi ciri peradaban modern. Di antara kesalahan-kesalahan yang dihukum adalah pernyataan bahwa ”Paus Roma dapat dan harus mendamaikan diri sendiri dan mencapai persetujuan dengan ’kemajuan’, Liberalisme, dan kebiasaan penjauhan diri dari masyarakat sipil yang belum lama mulai dipraktekkan” (DS 2980). Bahkan, wilayah yang oleh Gereja dipandang menjadi miliknya ikut diserang. Pada tahun 1870, Garibaldi menguasai Negara Kepausan untuk dimasukkan ke dalam negara Italia yang baru disatukan. Hilangnya daerah luas di Italia Tengah yang diperintah oleh para paus selama lebih dari 1000 tahun menciptakan trauma, luka batin yang mendalam. Modernisme Krisis Modernisme pada awal abad ke-20 semakin membuat Gereja resmi menjadi takut terhadap ilmu pengetahuan yang baru.4 Gerakan yang disebut dengan istilah ”Modernisme” tidak pernah merupakan sistem teologi yang sungguh-sungguh koheren. Apa yang ditampilkan adalah usaha beberapa ilmuwan Katolik untuk berdialog dengan modernitas dengan menggunakan metode-metode penyelidikan biblis dan historis. Metode-metode ”kritis” yang sebagian besar dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Protestan di Jerman, membuka dunia ilmu biblis baru yang kaya, yang memberi pengertian baru tidak hanya ke dalam teks-teks sendiri tetapi juga ke dalam cara wahyu Allah muncul dari sejarah umat Allah. Sayangnya, banyak yang menggunakan metode-metode itu, baik Protestan maupun Katolik, sampai tahap tertentu mewarisi pengandaian-pengandaian rasionalistis yang berasal dari Pencerahan. Dalam banyak hal mereka merelatifkan, merasionalkan apa saja yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, dan menyempitkan isi wahyu menjadi pengalaman subjektif manusia. Ajaran-ajaran menjadi lambang tanpa kebenaran, mukjizat disingkirkan, dan wahyu Kristiani ditafsirkan kembali sebagai tak berkaitan dengan pengaruh adikodrati, sebagai ungkapan khusus pengalaman religius umum yang dapat dialami oleh semua orang. Dengan demikian, dengan banyak cara, ”Modernisme” dapat dipandang sebagai versi Katolik dari Protestantisme Liberal. Yang khas pada semua pemikir itu adalah perhatian untuk memasukkan sejarah dan subjektivitas pada pemikiran teologi. Alfred Loisy (1857-1940), sarjana Kitab Suci Prancis, yang bukunya berjudul L’Evangile et L’Eglise (Injil dan Gereja) terbit tahun 1904, berusaha menunjukkan bagaimana Gereja merupakan hasil dari pelembagaan yang harus terjadi atas pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah. George Tyrell (1861-1909), seorang Yesuit Inggris adalah seorang filsuf agama. Minat utamanya ada pada wahyu sebagai pengalaman religius batin, sesuatu yang dapat diungkapkan secara simbolik tetapi tak pernah dapat dimengerti hanya sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan. Friedrich von Hügel (1852-1925), seorang teolog dan pembimbing rohani, menafsirkan Kristianitas dalam kerangka unsur kelembagaan, intelektual, dan mistiknya. Meskipun ia tidak menganggap diri sebagai seorang Modernis, namun ia kerap berhubungan dengan pemikir-pemikir Modernis dan kerap dikait-kaitkan dengan mereka. Gereja Katolik menanggapi dengan keras apa yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap imannya. Pada tahun 1907, dua dokumen dikeluarkan untuk menghukum Modernisme, yaitu Ensiklik Pius X Pascendi dan Dekrit Takhta Suci, Lamentabili. Ensiklik itu menunjukkan beberapa kesalahan nyata dalam Modernisme, meskipun para ilmuwan dewasa ini tidak sepakat tentang sejauh mana kesalahan-kesalahan itu ada pada pemikiran para ilmuwan yang dituju oleh ensiklik. Loisy dan Tyrell diekskomunikasikan; sedang von Hügel lepas dari hukuman. Selama 50 tahun berikutnya, keilmuan Katolik harus membayar mahal karena tindakantindakan yang diambil untuk meniadakan ancaman Modernisme dari Gereja. Pascendi mendorong terciptanya sensor yang ketat, pendirian panitia pengawasan keuskupan untuk menjaga ajaran Katolik, dan pelaporan nama-nama yang dicurigai menganut Modernisme kepada Takhta Suci. Atas persetujuan Paus, perkumpulan rahasia yang dikenal dengan nama Sodalitium Pianum didirikan untuk mengawasi bahkan anggota hierarki yang dicurigai condong ke Modernis.5 Apa yang terjadi selanjutnya adalah masa panjang dari kecurigaan dan penekanan. Para uskup dan profesor-profesor seminari dituntut untuk setiap tahun mengucapkan sumpah melawan Modernisme, seperti sudah disebut di atas. Setiap ajaran yang tidak sesuai dengan teologi buku-buku pegangan Roma dicurigai. Ilmuwan-ilmuwan tidak jarang dipecat dari jabatan mereka, dan ilmuwan-ilmuwan yang lain, buku-bukunya ditaruh pada rak buku-buku indeks. Kongregasi Kuria Roma, birokrasi Vatikan yang harus membantu Paus dalam memimpin Gereja, semakin berkuasa. Anggota-anggota kongregasi dan komisi kuria, sebagian besar klerus Italia, mengawasi ajaran dan moral, menetapkan pendirian-pendirian mana yang harus dipegang dan diajarkan oleh profesor-profesor Katolik, mendisiplinkan mereka yang berpendirian lain, mengawasi secara ketat seminari-seminari, menunjuk uskup-uskup dan mendirikan keuskupan-keuskupan baru. Mereka mengirim nuntius-nuntius dan delegat-delegat apostolik untuk mewakili Gereja dalam Gereja-Gereja nasional, mengawasi tarekat dan kongregasi religius, terutama tarekat dan kongregasi wanita, serta mengatur hidup sakramental dan liturgi Gereja. 2. Arus-Arus Pembaruan Gambarnya tidak seluruhnya suram. Segi yang paling cerah pada masa dari tahun 1920 sampai 1960 telah digambarkan dengan kata Prancis ressourcement, ”kembali ke sumber”, yaitu sumber Katolisisme dalam Kitab Suci, Bapa-Bapa Gereja, liturgi, dan filsafat.6 Kembali ke sumber ini menimbulkan atau mendukung sejumlah aliran pembaruan yang pada akhirnya memainkan peranan penting dalam membentuk kembali wajah Katolisisme pada Konsili Vatikan II. Tambahan pula, dalam masa sesudah Perang Dunia II, dunia sendiri mengalami perubahan. Sesudah kengerian Nazisme, Gereja Kristiani (di Eropa) mengalami kebangkitan iman kembali. Ada rasa optimis dan kebebasan baru. Kita akan melihat secara singkat aliran-aliran pembaruan itu. Gerakan Biblis Modern Gerakan biblis modern telah dimungkinkan oleh perkembangan metode penyelidikan teksteks Kitab Suci (kritik historis, kritik bentuk, kritik redaksi, kritik sumber, dan kritik teks) yang kritis, historis, dan literer di kebanyakan universitas-universitas Jerman. Karena takut kalaukalau dicemari oleh semangat Modernisme, kritisisme biblis yang baru untuk waktu yang lama dilawan oleh Gereja. Komisi Kitab Suci Kepausan, yang mengeluarkan sejumlah keputusan antara tahun 1905 dan 1915 yang menuntut para ahli Kitab Suci Katolik untuk mengambil sikap terhadap keilmuan yang kritis, mulai mempertanyakan, di antaranya kepengarangan Musa atas isi pokok buku Pentateukh, sifat historis bab-bab pertama Kitab Kejadian, pandangan bahwa Kitab Yesaya merupakan karya satu orang pengarang, Injil Matius sebagai Injil pertama yang ditulis, dan lain-lain.7 Titik balik terjadi pada tahun 1943 dengan terbitnya ensiklik Paus Pius XII, Divino Afflante Spiritu, dokumen yang kerap disebut sebagai Magna Charta ilmu Kitab Suci Katolik. Dalam ensiklik itu, Paus memberi kepada ilmuwan Katolik kebebasan untuk menggunakan metode keilmuan historis-kritis yang tidak diperbolehkan sebelumnya. Ilmu Kitab Suci Katolik, yang sebelumnya ketinggalan dari ilmu Kitab Suci Protestan, mulai berkembang setelah ilmuwanilmuwan Katolik yang telah dilatih dalam metode-metode baru itu, mulai mengajar di seminariseminari dan universitas-universitas. Dekrit-dekrit dari Komisi Kitab Suci Kepausan selanjutnya meneguhkan arah baru itu, bahkan membalikkan pengarahan-pengarahan sebelumnya ketika pada tahun 1955 sekretaris komisi memberi kepada para ilmuwan Katolik kebebasan penuh dari pengarahan-pengarahan tahun 1905-1915 kecuali yang berkaitan dengan iman dan moral. Gerakan Liturgis Gerakan liturgis merupakan aliran pembaruan yang kedua yang sudah mulai lama sebelum Vatikan II. Jika dewasa ini kita kadang-kadang menghubungkan gerakan liturgis dengan gitar dan nyanyian-nyanyian rakyat, drama, tarian, dan panji-panji di dalam Gereja, itu semua sesungguhnya menggambarkan usaha untuk menemukan kembali kekayaan simbolis dan komunal ibadat Kristiani tradisional, dengan demikian memberi hidup baru kepada doa dan ibadat resmi Gereja. Akar-akar pembaruan liturgi ditemukan dalam biara-biara Benediktin di Jerman, Swiss, dan Prancis, yang dalam abad ke-19 mulai mempopulerkan penggunaan nyanyian Gregorian dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam liturgi dari pihak awam. Dom Prosper Guéranger (1805-1875) dari Solesmes di Prancis, dengan tulisan-tulisannya tentang tahun liturgi, kerap dianggap sebagai pendiri gerakan liturgis itu. Di Belgia, Dom Lambert Beauduin (1873-1960) menekankan bahwa liturgi merupakan cara untuk memperdalam hidup iman. Liturgi bukan hanya merupakan tindakan imam tetapi tindakan seluruh umat yang berkumpul. Di Amerika Serikat pembaruan liturgi kerap dikaitkan dengan St. John’s Abbey (Biara St. Yohanes) di Collegeville, Minnesota, dan dengan nama Virgil Michel (1890-1938), rahib dari biara itu. Dia mengenal gerakan pembaruan liturgi itu ketika belajar di Eropa. Sekembalinya ke Amerika pada tahun 1925, ia mencurahkan tenaga untuk pembaruan liturgi. Dia mulai menerbitkan majalah bulanan liturgi, Orate Fratres dan mendirikan The Liturgical Press (Penerbitan Liturgi). Pengganti Virgil Michel, Godfrey Dicmann mengubah nama majalah itu dengan nama Worship (Ibadat) pada tahun 1955. Collegeville dengan biara, universitas dan penerbitannya sampai sekarang ini masih menjadi pusat gerakan liturgi di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun sebelum Konsili Vatikan II, orang-orang yang tertarik pada liturgi akan pergi ke biara-biara untuk mengikuti ibadat, mengadakan retret dan mempelajari nyanyian Gregorian. Pada tahun 1951 diadakan Kongres I para ahli liturgi di Maria Lach, Jerman. Kerja gerakan liturgis mendatangkan buah pada Konsili Vatikan II dengan diterbitkannya Konstitusi tentang Liturgi Suci. Teologi Baru Terlalu lama teologi Katolik yang direstui di Roma terbatas pada kategori-kategori filsafat dan teologi Skolastik yang diwarisi dari universitas-universitas besar Eropa pada Abad Pertengahan. Yang paling berpengaruh adalah buku-buku karangan seorang Dominikan bernama Thomas Aquinas. Sesungguhnya, Leo XIII dalam ensikliknya Aeterni Patris (1879) telah berusaha memaksakan Thomisme pada seluruh Gereja, sementara Pius X memerintahkan Summa Theologiae menjadi buku pegangan yang harus digunakan di semua lembaga kepausan.8 Krisis Modernisme pada awal abad ke-20 dipicu oleh usaha untuk lepas dari pendekatan yang sempit ini dan untuk berdialog dengan pemikiran sezaman. Yang disebut nouvelle théologie (”teologi baru”) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya beberapa ilmuwan di Prancis dan Jerman dalam dua dasawarsa sebelum Konsili Vatikan II merupakan tanggapan yang lain. Istilah ”teologi baru” tampaknya digunakan untuk pertama kali oleh Mgr. Pietro Parente dari Kantor Takhta Suci pada bulan Februari 1942 dalam Observatore Romano, surat kabar resmi Vatikan, dan istilah itu digunakan dalam arti buruk. Akan tetapi seperti Modernisme, teologi itu merupakan usaha banyak ilmuwan – Yves Congar, Henri de Lubac, Jean Daniélou, dan MarieDominique Chenu di Prancis; Karl Rahner dan Otto Scmmelroth di Jerman; Hans Urs von Balthasar di Swiss – untuk kembali ke sumber-sumber: Kitab Suci, patristik dan liturgi yang telah sedemikian memperkaya pemahaman-diri Gereja milenium pertama. Eklesiologi merupakan isu utama bagi para teolog itu. Topik-topik lain meliputi perkembangan ajaran, penciptaan, evolusi, dosa asal, rahmat, dan Ekaristi. Karena pendekatan para ilmuwan itu biblis dan historis, mereka diserang oleh para wakil ortodoksi Roma yang menganut pemikiran Skolastik. Para wakil itu melihat karya mereka sebagai Modernisme jenis baru. Ini agaknya menjadi keprihatinan Pius XII dalam ensiklik tahun 1950 Humani Generis. Ensiklik itu menghimbau agar kembali ke pendekatan Thomas, baik dalam filsafat maupun teologi. Ensiklik itu juga menyatakan bahwa tugas sebenarnya para teolog adalah menunjukkan bagaimana hal-hal yang diajarkan oleh Magisterium Gereja ditemukan dalam Kitab Suci dan tradisi (DS 3886). Sejumlah orang yang terlibat dengan teologi baru itu dikenai sanksi disiplin; mereka ”dipecat dari jabatan mereka sebagai profesor, dilarang menyajikan pandangan-pandangan mereka dalam kuliah-kuliah atau tulisan-tulisan, dihukum sehingga terbungkam dan tak aktif lagi”.9 Pada tahun 1954, terjadilah peristiwa yang digambarkan sebagai ”penggerebegan para Dominikan” di mana tiga Provinsial Dominikan Prancis dipecat dari jabatan mereka, dan sejumlah Dominikan, antara lain Chenu dan Congar, dikenai sanksi disiplin atas desakan Takhta Suci, yang takut akan pembaruan-pembaruan yang dianggap berbahaya dalam ajaran mereka. Chenu, teolog tentang abad pertengahan yang hebat, telah membandingkan perubahan-perubahan dalam masyarakat abad ke-13 dan Gereja dengan perubahan masyarakat abad ke-20 dan Gereja. Tulisan-tulisan Congar mengangkat isu-isu seperti sifat organik dari tradisi, pembaruan Gereja, teologi kaum awam, dan ekumenisme. Kedua-duanya dipecat dari jabatan mengajarnya. Namun, kedua-duanya hadir dalam Konsili Vatikan II di mana tugas mereka adalah membantu menyusun sejumlah dokumen Konsili.10 Pius XII Humani Generis bukanlah ensiklik yang progresif. Ensiklik itu kerap digunakan sebagai bukti bahwa Pius XII bukanlah seorang pembaru. Akan tetapi, ilmuwan sezaman menemukan hal-hal yang pantas dihargai sejauh Paus yang hidup keras dan kebapaan itu menyiapkan jalan bagi Vatikan II. Ensikliknya Divino Afflante Spiritu (1943) memasukkan kritik Kitab Suci modern ke dalam Gereja, bahkan jika para pejabat di Kuria Roma terus-menerus ”menembak” dengan sembunyi-sembunyi orang-orang yang menggunakan metode itu. Sampai sekurang-kurangnya tahun 1962, para pejabat itu melancarkan beberapa serangan terhadap Institut Kitab Suci (Institutum Biblicum) di Roma yang dikelola Yesuit dan berusaha agar dua orang profesornya dipecat dari lembaga itu. Ensiklik Paus Pius XII lain yang penting adalah Mystici Corporis (1943), dengan visi sakramentalnya tentang Gereja sebagai tubuh Kristus. Pada tahun 1947 ensiklik itu diikuti ensiklik Mediator Dei, ensiklik besar Paus tentang liturgi. Meskipun memberi peringatan melawan ekses-ekses pembaruan liturgi, namun ensiklik itu mendorong gerakan liturgis dan menganjurkan Misa Dialog. Yohanes XXIII Pada tahun 1958, Pius XII wafat. Wafatnya menandai berakhirnya suatu era. Sedikit saja yang menduga bahwa era baru dalam hidup Gereja akan mulai. Pada waktu para Kardinal berkumpul di Kapel Sistina untuk memilih seorang pengganti, tidak ada harapan lain kecuali perubahan. Kebanyakan Kardinal yang berkumpul menghendaki seseorang yang akan melanjutkan kepemimpinan Pius XII yang kuat dan konservatif. Akan tetapi konklaf (pemilihan Paus) macet. Tak ada calon yang mendapat suara cukup untuk dipilih. Akhirnya terjadilah kompromi. Para Kardinal berpaling pada Kardinal berumur 76 tahun yang bernama Angelo Roncalli (1881-1963). Ia menjadi Paus peralihan. Pendapat umum adalah bahwa ia terlalu tua untuk membuat perubahan. Roncalli, atau Yohanes XXIII, seperti dikenal dalam sejarah, adalah orang Italia yang bulat dan gemuk dengan wajah yang mirip dengan wajah lukisan Michelangelo. Ia berasal dari keluarga petani dari Italia Utara. Di balik penampilannya, Roncalli adalah pejabat Gereja yang cerdik dan berpengalaman. Setelah ditahbiskan pada tahun 1904, pada tahun-tahun awal imamatnya ia menjadi profesor seminari di Bergamo, pastor tentara dalam Perang Dunia I, dan sebagai pembimbing para mahasiswa. Kebanyakan kariernya dijalani di luar Roma dalam diplomasi kepausan. Ia menjadi wakil Vatikan di Belgia dan Turki, yang dalam perjalanan waktu tumbuh penghargaan yang mendalam terhadap Kristianitas Ortodoks dan akrab dengan bahasa-bahasa serta masalah-masalah Eropa Timur. Pada tahun 1941 ia ditunjuk menjadi Nuntius Apostolik untuk Prancis. Pada saat itu, ia dapat menyaksikan pembaruan teologi dan pastoral yang terjadi di negeri itu. Selama bertugas di Prancis, ia menjalin persahabatan dengan sekelompok ekumenis Protestan yang berusaha menghayati hidup monastik di dusun kecil di Burgundy yang disebut Taizé. Di balik segala prestasinya, hatinya yang sebenarnya adalah hati seorang pastor, gembala. Akhirnya pada tahun 1953 ia diangkat menjadi Uskup Agung Venesia. Sebagai uskup, ia dapat mewujudkan perhatian dan minat pastoralnya secara penuh. Segera sesudah terpilih menjadi Paus, Paus yang baru, sambil berbicara dengan sekretaris negara tentang masalah-masalah dunia dan Gereja, memberi tahu kepada sekretaris itu bahwa ia mau mengadakan Konsili. Konsili Paus Yohanes XXIII akan secara radikal mengubah Gereja. 3. Konsili Vatikan II: 1962-1965 Pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII dan tujuh belas Kardinal yang kebanyakan dari Kuria Roma bertemu di Basilika St. Paulus di luar tembok untuk mengadakan ibadat vesper (sore) guna menutup pekan doa untuk kesatuan umat Kristiani. Dalam sambutan singkatnya, Paus mengumumkan bahwa ia bermaksud mengadakan Konsili ekumenis, dengan menambah pada akhir sambutan itu doa untuk ”undangan yang diperbarui kepada umat dari jemaat-jemaat yang terpisah agar mereka juga mengikuti kita sebagai sahabat dalam usaha mencapai kesatuan dan rahmat, yang diharapkan oleh sedemikian banyak orang di segala penjuru dunia.”11 Para Kardinal menyambut pengumuman itu dengan diam karena terkejut. Bagaimana mungkin Paus baru mau berjalan sendiri? Hal terakhir yang dikehendaki para pemimpin tetap Kuria Roma adalah mengumpulkan semua uskup Gereja, terutama beberapa uskup yang lebih progresif dari Prancis, Jerman, Austria, Belgia, dan Belanda. Tahap Persiapan Dalam mengadakan konsili, yang akan disebut Konsili Vatikan II, Paus menegaskan bahwa Konsili itu harus menjadi Konsili ekumenis bagi seluruh Gereja. Dalam bulan-bulan selanjutnya, ia menjelaskan tujuan-tujuan Konsili itu. Pertama, ia menghendaki konsili itu menjadi aggiornamento, pembaruan atau tepatnya ”memperbarui Gereja Katolik hingga menjadi up-todate”. Cerita yang kerap dikisahkan untuk menggambarkan apa yang Paus kehendaki agar dicapai oleh Konsili adalah dengan pergi ke jendela yang terdekat dan membukanya untuk membiarkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Kedua, kesatuan Kristiani merupakan tujuan Konsili yang utama. Sesungguhnya itulah tujuannya sejak semula. Untuk mempromosikan intensi-intensi ekumenisnya, Paus mengambil sejumlah langkah konkret yang masing-masing amat bermakna simbolis. Pertama, ia minta agar pengamat-pengamat resmi dikirim oleh Gereja-Gereja Ortodoks dan Protestan. Kedua, ia mengatur agar mereka disediakan tempat duduk kehormatan di bagian depan Basilika St. Petrus dekat dengan bagian yang dikhususkan bagi para Kardinal. Akhirnya, ia mendirikan kongregasi Vatikan yang baru, Sekretariat untuk Memajukan Kesatuan Kristiani, dengan tugas membawa Gereja Katolik masuk ke dalam gerakan ekumenis, dan menempatkan sumbersumber daya untuk melayani para pengamat. Saat menjadi jelas bahwa Paus tidak dapat diyakinkan untuk tidak mengadakan Konsili, para pemimpin Kuria mengambil strategi agar Konsili itu tetap berada dalam pengendalian mereka. Dibentuk 10 komisi dan 2 sekretariat yang disiapkan untuk Konsili, yang para anggotanya terdiri dari para pejabat dari Kongregasi Kuria yang bersangkutan. Panitia itu menyiapkan 70 bagan atau draft mengenai berbagai masalah dogmatik dan tata tertib yang harus dibahas oleh para uskup ketika mereka berkumpul di Roma. Jelaslah rencana itu adalah untuk membebani Konsili sehingga membuat kerja Kuria mutlak diperlukan. Akan tetapi, dalam dua pidatonya yang penting, Paus menegaskan kepada para uskup yang berkumpul untuk Konsili bahwa pekerjaan Konsili adalah milik mereka sendiri. Dalam pidato radio pada tanggal 11 September 1962, Paus berbicara tentang perlunya bagi Gereja untuk membahas masalah perdamaian, kesamaan dan hak-hak segala bangsa, masalahmasalah negara-negara yang sedang berkembang, dan kesengsaraan-kesengsaraan yang dihadapi oleh sedemikian banyak orang, serta menyarankan agar Gereja ditampilkan sebagai ”Gereja semua orang, dan terutama kaum miskin”.12 Dari topik-topik itu tak ada topik yang berasal dari komisi-komisi persiapan. Kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1962 dalam pidato yang secara resmi membuka Konsili, Paus meminta kepada 2500 uskup yang berkumpul dari seluruh dunia dalam Misa Agung di Basilika St. Petrus agar tidak memandang ke masa lampau tetapi ke masa depan. Dengan memisahkan diri dari ”nabi-nabi kegelapan yang selalu meramalkan malapetaka”, yang berarti kritik terhadap Kuria, ia berkata bahwa Konsili tidak akan membicarakan ajaran fundamental ini atau itu, tetapi ”langkah ke masa depan menuju ke pendalaman ajaran dan pembinaan kesadaran” yang setia pada ajaran autentik Gereja, tetapi yang ”harus dipelajari dan diuraikan melalui metode-metode penelitian dan bentuk-bentuk literer (sastra) pemikiran modern.” Yang paling sering dikutip adalah penegasannya tentang pembaruan bahasa teologis Gereja: ”Inti ajaran lama tentang iman adalah satu hal, dan cara untuk menyampaikannya adalah hal yang lain.”13 Hasil Kerja Konsili Pada sesi kerja pertama, kerja Konsili pada tanggal 13 Oktober 1962 adalah memilih anggota untuk kesepuluh komisi Konsili. Tugas anggota adalah untuk menyampaikan bagan kepada para Bapa Konsili dan mempertimbangkan apakah ada perbaikan-perbaikan yang akan diajukan. Kuria mengharap bahwa anggota-anggota yang telah bertugas dalam komisi-komisi persiapan akan dipilih kembali. Untuk membantu para Bapa Konsili, diedarkan daftar namanama. Akan tetapi Kardinal Liènart, Uskup Agung Lille, Prancis, mengajukan usul yang penting. Ia mengusulkan agar diberi waktu tunda sebelum langkah yang sedemikian penting diambil, supaya para uskup dapat berkonsultasi dalam konferensi nasional atau regional tentang siapa yang akan mereka pilih. Usul itu didukung oleh Kardinal Frings dari Cologne, Jerman, dan kedua intervensi itu disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para Bapa Konsili. Dengan dukungan sedemikian kuat itu, permintaan untuk menunda pemilihan disetujui. Para uskup mulai memegang kendali Konsili. Konsili bertemu dalam tiga sesi. Debat dan voting mengenai berbagai dokumen dilangsungkan di lantai Basilika St. Petrus, di mana para Bapa Konsili, 2500 uskup dan pimpinan religius pria, duduk. Akan tetapi, banyak urusan Konsili yang sebenarnya kurang formal terjadi di ruang-ruang sidang, ruang-ruang makan, tempat-tempat minum kopi Roma, di mana terjadi banyak sekali percakapan di antara berbagai kelompok yang berbeda, yang berkumpul untuk Konsili – para uskup bertemu satu sama lain, dengan para periti (ahli) atau penasihat teologi mereka, dengan para ilmuwan dan para wartawan, serta dengan para pengamat dari Gereja-Gereja Prostestan, Anglikan, dan Ortodoks. Dengan mengundang para pengamat dari Gereja-Gereja Kristiani, Konsili sejak awalnya mendapatkan suasana ekumenis. Ada sekitar 40 pengamat hadir pada waktu Konsili dibuka pada tanggal 11 Oktober 1962; pada waktu Konsili ditutup, jumlah pengamat naik menjadi 80 orang. Meskipun kerahasiaan diusahakan dipertahankan oleh Kuria berkaitan dengan pembicaraan-pembicaraan Konsili, para pengamat sebelumnya menerima salinan draft dari dokumen-dokumen Konsili. Karena diperlakukan sebagai tamu kehormatan, mereka dapat hadir dalam semua sesi di dalam Basilika dan menghadiri pertemuan-pertemuan komisi-komisi. Pelayanan untuk menerjemahkan juga disediakan bagi mereka. Sesudah Kardinal Suenens melihat bahwa tidak ada wanita yang hadir untuk pembicaraanpembicaraan Konsili, beberapa wanita ditambahkan menjadi ”pendengar”. Pada akhir Konsili ada 22 wanita yang hadir, di antaranya Sr. Luke Tobin, pimpinan Suster-Suster Loretto dari Amerika Serikat. Konsili membangkitkan minat yang besar sekali. Dengan kadang-kadang membalikkan pendirian yang dipegang sebelumnya, bahkan pendirian yang diajarkan oleh Paus-Paus, Konsili menggambarkan sifat dinamis Katolisisme. Dua dokumen yang disiapkan oleh Komisi Teologi yang konservatif, skema tentang Gereja dan wahyu Ilahi, dikembalikan oleh para Bapa Konsili kepada Komisi agar ditulis ulang. Enam belas dokumen yang merupakan hasil dari pembahasan-pembahasan menjadi pegangan bagi pembaruan Gereja, yang masih belum selesai, dalam sejumlah bidang. Gereja Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium) merupakan usaha untuk merumuskan pemahaman diri sezaman, Gereja yang berlawanan dengan eklesiologi klerikal dan monarkhial Katolisisme abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang kerap dilambangkan dalam bentuk piramida, di mana segala otoritas turun dari atas ke bawah. Terutama bermaknalah penekanannya pada Gereja sebagai umat Allah, ajarannya tentang kolegialitas episkopal, dan teologi awamnya. Bab 1 merumuskan Gereja sebagai ”Sakramen tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia” (LG 1). Ketika membahas hakikat perutusan Gereja, Konsili menyebut hubungan antara Gereja Katolik dan Gereja-Gereja lain. Ketika membicarakan ”satu-satunya Gereja Kristus” konstitusi menyatakan: ”Gereja itu, yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam Gereja Katolik” (LG 8). Draft sebelumnya, yaitu draft tahun 1963, menyebut: ”Gereja ini .... adalah Gereja Katolik.”14 Penggantian kecil kata ”adalah” (”is”) dengan kata ”berada dalam” (”subsists”) dibuat yang oleh Komisi Teologis sesudah sesi kedua amatlah bermakna secara ekumenis. Itu berarti bahwa Gereja Katolik tidak lagi menyatakan suatu identitas yang eksklusif atau penyamaan total antara Gereja Kristus dan dirinya sendiri. Meski Konsili memahami Gereja Katolik sebagai perwujudan Gereja Kristus dalam kelengkapan dan kepenuhannya yang hakiki (LG 14), namun Konsili menyiratkan bahwa Gereja Kristus dengan berbagai cara juga ada dalam Gereja-Gereja dan jemaat-jemaat gerejawi (LG 8). Bab 2 menggambarkan Gereja sebagai umat Allah, gambaran yang dominan dalam eklesiologi Konsili. Penunjukan pada ”karuniakarunia karismatis” (LG 12), yang di tempat lain digambarkan ”baik hierarkis maupun karismatis” (LG 4), merupakan bukti dari penemuan kembali teologi karismata (karunia-karunia) yang memegang peran sedemikian penting dalam 1Kor 11-14. Perbedaan antara ”imamat jabatan” atau ”hierarki” dan ”imamat umum” (imamat seluruh umat beriman) menggarisbawahi keikutsertaan umat dalam imamat Kristus (LG 10). Bab 3 mengembangkan pemahaman kolegial tentang jabatan uskup. Perdebatan tentang kolegialitas merupakan salah satu perdebatan penting dalam Konsili. Perdebatan itu mengandung arti kembali ke pemahaman yang sudah lama tentang Gereja dan pemerintahannya. Bersama dengan Paus, para uskup memiliki otoritas tertinggi atas Gereja semesta (LG 22) dan ikut ambil bagian dalam tugas mengajarnya yang tidak dapat sesat (LG 25). Dengan demikian, para uskup tidak dimengerti sebagai wakil Paus melainkan Kepala Gereja-Gereja lokal (LG 27). Gereja sendiri merupakan kesatuan Gereja-Gereja, seperti pemahaman Gereja atas dirinya dalam milenium pertama, daripada lembaga satu-satunya dan monolitis. Dengan menegaskan bahwa para uskup ikut mengambil bagian dalam karunia tak dapat sesat, Konsili memberikan suatu konteks penafsiran baru tentang ajaran Konsili Vatikan I (1870) mengenai ketidaksesatan Paus. Bab 4 membahas teologi awam, yang menekankan bahwa melalui baptis dan penguatan, mereka umat awam ikut ambil bagian dalam perutusan Gereja (LG 33) dan dalam tiga jabatan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja (LG 31). Dari tekanan ini, kemudian muncullah berbagai pelayanan kaum awam dalam Gereja sesudah Konsili Vatikan II, pengakuan kewajiban orang awam yang kompeten untuk menyatakan pendapat mereka demi kebaikan Gereja (LG 37), dan keterlibatan baru kaum awam, pria dan wanita, dalam tugas Gereja dalam refleksi teologis (bdk. GS 62). Konstitusi membayangkan bahwa kaum awam pria dan wanita menghayati panggilan mereka justru ”dengan melibatkan diri dalam urusan-urusan dunia,” bekerja ”demi pengudusan dunia dari dalam, bagaikan ragi” (LG 31). Bab 5 berbicara tentang panggilan seluruh Gereja untuk kesucian. Bab 6 berbicara tentang kaum religius. Bab 7 berbicara tentang kesatuan Gereja di dunia dengan Gereja surgawi, para kudus di surga, dan jiwa-jiwa di api pencucian. Gambarannya tentang Gereja sebagai ”Gereja yang berziarah” menjauh dari pengertian tentang Gereja sebagai ”perserikatan sempurna” yang dominan dalam eklesiologi sejak zaman Robertus Bellarminus. Bab terakhir berbicara tentang peran Santa Perawan Maria dalam misteri Kristus dan Gereja. Wahyu Konstitusi Dogmatik Konsili tentang Wahyu Ilahi (Dei Verbum) mengambil pendekatan personal daripada proposisional dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Wahyu bukanlah merupakan sesuatu yang ”tersimpan” dalam sumber-sumber, meski bab pertama dari draft asli Komisi Teologi yang ditolak berjudul ”Dua Sumber Wahyu”. Konsili merumuskan wahyu sebagai pengungkapan-diri Allah dalam sejarah, yang mencapai kepenuhan dalam pribadi Yesus, dan melalui hidup dalam Roh memberi kepada manusia keikutsertaan dalam Kodrat Ilahi Allah sendiri (DV 2). Dengan demikian dalam pengertian Konsili, wahyu lebih bersifat personal, pribadi, daripada proposisional, pernyataan. Wahyu adalah Trinitarian dalam bentuk, Kristologis dalam perwujudan, dan historis dalam perantaraannya. Bab 2 membahas penyampaian wahyu Allah dalam Alkitab dan tradisi. Bab 3 mencerminkan pengaruh gerakan Kitab Suci Modern dalam pembahasannya tentang Alkitab. Dengan menggemakan Ensiklik Pius XII Divino Afflante Spiritu, bab itu menekankan pentingnya pencarian maksud pengarang Kitab Suci dan menemukan bentuk sastra. Bab terakhir menggariskan tindakan-tindakan untuk mengembalikan Sabda Allah ke tempat sentralnya dalam kehidupan Gereja dan terutama dalam liturginya (DV 21). Bab itu meminta terjemahan baru dari teks-teks aslinya, mendorong para ilmuwan Kitab Suci dalam kerja mereka, dan menunjukkan tempat pusat Alkitab dalam teologi. Para imam, diakon, dan katekis didorong untuk berbagi Sabda Allah dengan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka dan umat didorong untuk kerap membaca Kitab Suci serta menggunakan Kitab Suci untuk doa mereka. Dengan demikian, Konstitusi tentang Wahyu Ilahi mengakhiri pengabaian Kitab Suci yang menjadi ciri Gereja Katolik sejak Reformasi, dan menekankan peran sentral Sabda Allah dalam liturgi. Liturgi Konstitusi tentang Liturgi Suci (Sacrosanctum Concilium) mengawali pembaruan yang menyeluruh dalam doa dan ibadat resmi Gereja. Konstitusi itu mendorong partisipasi yang lebih besar dari kaum awam dalam liturgi (SC 14) dan memerintahkan peninjauan kembali teks-teks dan ritus-ritus liturgis untuk membuat liturgi menjadi lebih berbuah dalam hidup Gereja (SC 2). Pembaruannya yang jelas, yang mencerminkan penekanannya pada pentingnya Sabda Allah adalah ketetapannya untuk perayaan liturgi dalam bahasa umat (SC 36). Banyak saran dan langkah-langkah percobaan untuk pembaruan, sejak Konsili itu, menjadi biasa: homili dalam Perayaan Ekaristi, doa umat dan doa semesta Gereja, salam damai, penerimaan komuni dalam dua rupa, konselebrasi, nyanyian umat, dan banyaknya pelayanan liturgis bagi kaum awam pria dan wanita. Ekumenisme Bergerak melampaui kecurigaan Gereja sebelumnya terhadap gerakan ekumenis, Vatikan II dengan tegas melibatkan Gereja Katolik untuk mencari kesatuan Kristiani. Dekrit tentang Ekumenisme (Unitatis Redintegratio) mengakui bahwa orang-orang Kristiani dari berbagai Gereja dan komunitas-komunitas gerejawi sudah bersatu, satu sama lain secara tidak sempurna karena baptis (UR 3). Mereka sampai tahap tertentu sudah ikut mengambil bagian di dalam hidup rahmat. Dekrit itu menekankan bahwa semua ekumenisme mulai dengan pertobatan hati dan atas nama Gereja Katolik secara resmi mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang-orang Kristiani lain karena dosa-dosanya sendiri melawan kesatuan (UR 7). Kemudian Dekrit menguraikan prinsip-prinsip bagi keterlibatan ekumenis Katolik Roma. Dekrit menganjurkan acara-acara doa bersama, meski lebih hati-hati tentang ibadat bersama (UR 8). Dialog ekumenis dianjurkan, dan mereka yang terlibat dalam dialog itu diingatkan bahwa ”ada tata urutan atau hierarki kebenaran.” Dengan perkataan lain, tidak semua ajaran sama pentingnya, karena ”berbeda-bedalah hubungannya dengan dasar iman Kristiani” (UR 11). Kebebasan Agama Perdebatan terbesar dalam Konsili terjadi pada pembahasan deklarasi tentang kebebasan agama. Skema dengan tajam diserang oleh mereka yang menganut pemikiran tradisional bahwa ”kesalahan tidak memiliki hak” dan oleh karena itu menghendaki Gereja untuk terus mempertahankan bahwa di negara-negara yang pada dasarnya Katolik secara prinsip harus mampu melarang praktek dan penyebaran agama-agama yang dipandang salah. Iman-iman lain, termasuk iman Kristiani lain, karena alasan-alasan politis diberi toleransi, tetapi tidak mempunyai hak intrinsik untuk diperlakukan secara sama. Menurut John Courtney Murray, pengarang utama dari dekrit itu, Konsili menjernihkan kekaburan yang sudah berlangsung lama: ”Gereja tidak membahas tatanan sekular dalam kerangka standar ganda kebebasan bagi Gereja bila Katolik merupakan minoritas, hak khusus bagi Gereja dan tak memberi toleransi terhadap orang-orang lain bila Katolik merupakan mayoritas.”15 Perbedaan tentang kebebasan agama sungguh-sungguh panas. Hasil voting atas teks deklarasi yang pro ada 1.114 dan yang kontra ada 1.074. Kemenangan pilihan yang tipis. Namun membalik ajaran Pius IX dan Leo XIII, Dignitatis Humanae menyatakan bahwa manusia mempunyai hak dalam kebebasan agama, untuk beribadat secara merdeka menurut suara hati mereka yang didasarkan pada martabat mereka sebagai pribadi manusia (DH 2). Agama non-Kristiani Melampaui aksioma tradisional ”tak ada keselamatan di luar Gereja,” Konsili mengakui bahwa mereka yang mencari Allah dengan tulus dan membuka diri terhadap rahmat Allah dapat diselamatkan, meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan yang eksplisit tentang Kristus (LG 16). Menurut deklarasi tentang hubungan antara Gereja dan agama-agama non-Kristiani (Nostra Aetate), Gereja Katolik memandang agama-agama besar dunia dengan hormat, dengan mengakui bahwa ajaran-ajaran agama itu kerap mencerminkan sinar kebenaran Ilahi (NA 2). Gereja dan Dunia Modern Mungkin pergeseran yang paling berarti yang ditunjukkan oleh Konsili adalah perhatiannya terhadap dunia dan terutama terhadap kaum miskin. Dari kalimat pembukaannya, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (Gaudium et Spes), dokumen Konsili yang paling panjang, menarik perhatian pada keadaan menyedihkan kaum miskin dan kaum penderita: ”Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga” (GS 1). Sebagai tambahan pada penekanan bahwa harus diadakan usahausaha keras untuk memenuhi keadilan dan kewajaran (GS 66) dan panggilannya kepada orang- orang Kristiani agar meningkatkan perhatian bagi orang miskin (GS 69), Konstitusi menyediakan bab-bab mengenai perkawinan dan keluarga, meliputi konsep menjadi orang tua yang bertanggung jawab, pengembangan keberdayaan, prinsip-prinsip sosioekonomi, hak semua orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, masalah perang dan perlombaan senjata. Gaudium et Spes bermaksud membantu memberi inspirasi kepada sejumlah gerakan religius yang sadar secara sosial, teologi pembebasan Amerika Latin, teologi-teologi asli di Afrika dan Asia, surat-surat pastoral uskup-uskup Amerika tentang pendamaian dan keadilan ekonomis, dan teologi feminis. 4. Kesimpulan Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II mencerminkan hakikat Konsili sendiri yang terpecah. Beberapa dokumen tampak berpendirian terbagi, dengan menempatkan secara berdampingan pandangan-pandangan tradisional dan progresif. Misalnya Konstitusi Dogmatik tentang Gereja menyeimbangkan hampir setiap pernyataan tentang kolegialitas uskup dengan menegaskan kembali hak-hak istimewa kepausan yang tradisional. Akan tetapi, Konsili sangat berhasil dalam melepaskan arus-arus pembaruan dalam Gereja. Dalam waktu beberapa tahun, Katolisisme mengalami pembaruan besar-besaran dalam liturgi dan ibadat, teologi, pemahamannya tentang otoritas dan pelayanan, komunitaskomunitas religius, kehidupan paroki, bahkan dalam budaya populernya. Tidak semua perubahan mendatangkan kebaikan bagi Gereja, dan bagi banyak orang Katolik telah dan masih tetap merupakan kebingungan yang besar. Situasi Gereja pada akhir abad ke-20 tidak dapat dikatakan disebabkan oleh Konsili saja. Pada paro kedua abad ini telah terjadi sejumlah gerakan, di antaranya sekularisme yang semakin menguat, krisis otoritas dan lembaga-lembaga sosial yang makin meluas, revolusi seks, gerakan-gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa, feminisme, dan perhatian yang semakin besar terhadap keadilan sosial. Gerakan-gerakan itu telah mengakibatkan perubahanperubahan besar di dalam Gereja dan dalam hidup Kristiani bahkan tanpa Konsili sekali pun, semua itu telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Akan tetapi, Konsili membawa Gereja ke vitalitas baru, dan dengan memanggil Gereja untuk memperbarui strukturstruktur, teologi dan hidupnya, Konsili telah membuat Gereja mampu memainkan peran secara sadar dalam perubahan dan pembaruannya. Satu konsep yang amat berguna yang muncul dalam Konsili adalah konsep ”ortodoksi nonhistoris” yang dikembangkan oleh Michael Novak dalam bukunya The Open Church (Gereja yang Terbuka). ”Ortodoksi non-historis”16 menggambarkan kepercayaan yang, dengan berjalannya waktu, telah secara salah memegang kepastian suatu ajaran yang dianggap ortodoks, masalah iman, seolah-olah menyajikan secara paling baik pendirian teologis, yang tidak ada dasar biblis atau historisnya. Orang-orang Katolik sebelum Vatikan II tumbuh menjadi dewasa dan menerima begitu saja sekumpulan pendirian ”Katolik” – tentang ketidaksesatan Paus, hakikat Gereja, sumber atau sumber-sumber wahyu, hakikat imamat yang sakral, adanya limbo, dan lain-lain; itu semua dapat dianggap menjadi contoh-contoh ortodoksi non-historis. Benar juga bahwa pendirian-pendirian yang diajarkan oleh magisterium biasa dan – dalam beberapa kasus selama berabad-abad – dianggap sebagai ajaran Katolik pada akhirnya diubah sebagai akibat kritik teologis dan kurangnya penerimaan oleh umat beriman. Contoh-contoh dari sejarah Gereja meliputi ajaran-ajaran tentang kekuasaan duniawi Paus; pengingkaran tentang keselamatan di luar Gereja; ajaran konsiliaris Konsili Konstantinopel; tak terusiknya Gereja oleh praktek perbudakan, yang disetujui oleh 4 Konsili ekumenis; dan pembenaran serta pemberian kuasa untuk menggunakan siksaan guna mendapatkan pengakuan.17 Contoh-contoh ajaran Paus yang dimodifikasikan atau ditolak oleh Konsili Vatikan II meliputi ketidakmampuan Pius IX untuk menemukan kebenaran dan kebaikan dalam agama-agama non-kristiani, penghukumannya atas pernyataan bahwa Gereja dan negara harus dipisahkan, penyangkalannya atas kebebasan agama sebagai hak objektif, dan penyamaan Pius XII atas Gereja Katolik dengan tubuh mistik Kristus.18 Konsili tak hanya memulai pembaruan hidup Gereja; Konsili juga mengubah cara orangorang Katolik memandang diri sendiri dan Gereja mereka. Dalam bab-bab berikut kami akan berusaha untuk menyampaikan pemahaman zaman ini mengenai hidup dan iman Katolik, yang dikembangkan berdasarkan hasil kerja Konsili Vatikan II. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. John O’Malley, Tradition and Transition: Historical Perspectives on Vatican II (Wilmington: Glazier, 1989) hlm. 17. Acta Apostolicae Sedis 20 (1928) 14. ”Allocution to Italian Catholic Action,” Acta Apostolicae Sedis 32 (1940) 362. Lihat Grabriel Daly, Transcendence and Immanence: A Study of Catholic Modernism and Integralism. (Oxford: Clarendon, 1980). Carlo Falconi, The Popes in the Twentieth Century. (London: Weidenfeld & Nicolson, 1967) 54-55. Lihat Stephen Happel dan David Tracy, A Catholic Vision. (Philadelphia: Fortress, 1984) 134-36. Lihat Raymond E. Brown, Biblical Reflection on Crises Facing the Church. (New York: Paulist, 1975) 6-10. Lihat Avery Dulles, The Craft of Theology: From Symbol to System. (New York: Crossroad, 1992) 120. Falconi, The Popes in the Twentieth Century. 283. Thomas O’Meara: ”’Raid on Dominicans’: The Repression of 1954,” America 170 (1994) 8-16. ”Pengumuman Paus Yohanes tentang Konsili Ekumenis,” Council Daybook, Sesi 1-2. (Washington: National Catholic Welfare Conference, 1962) 2. Dikutip oleh Peter Hebblethwaite, ”John XXIII,” dalam Adrian Hastings, ed., Modern Catholicism: Vatican II and After. (New York: Oxford Univ. Press, 1991) 30. Teks sambutan Paus termuat dalam Walter M. Abbott, ed., The Documents of Vatican II. (New York: Herder & Herder, 1966) 710-19; lihat 712, 715. Garis miring ditambahkan. John Courtney Murray, introduction to ”Religious Freedom”, The Documents of Vatican II, ed., Walter M. Abbott, 673. Michael Novak, The Open Church: Vatican II, Act II. (New York: Macmillan, 1964); lihat terutama bab 5, ”The School of Fear.” Lihat Luis M. Bermejo, Infallibility on Trial, Conciliarity, and Communion. (Westminster: Christian Classics, 1992). J. Robert Dionne, The Papacy and the Church: A Study of Praxis and Reception in Ecumenical Perspective. (New York: Philosophical Library, 1987). II Iman dan Jemaat yang Percaya Iman, menurut penulis surat kepada umat Ibrani ”adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibr 11:1). Banyak hal yang kita imani, karena pengalaman memberi kita kepercayaan pada kebenaran atau pada kenyataan akan banyak hal yang tidak dapat kita buktikan bagi diri kita sendiri atau tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkannya. Bahkan ilmuwan yang paling kritis pun menerima begitu saja bahwa dunia ini teratur dan dapat dimengerti. Ilmuwan mempunyai iman yang diatur oleh hukum-hukum alam tertentu yang dapat ditemukan. Iman religius berkaitan dengan kenyataan yang terakhir, dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir yang kita tanyakan pada saat-saat reflektif. Apakah kita sendirian di dunia ini, atau ada kehadiran di atasnya, misteri yang mengatasi pemahaman kita, yang menemui kita untuk memberi kita belas kasih, persahabatan dan cinta? 1. Hakikat Iman Kita semua mengalami saat-saat pewahyuan – ketika di padang memandang rumputrumput yang bergerak lembut tertiup angin, atau mungkin di pantai memandang ombak-ombak laut menerpa pantai, atau pada waktu malam memandang Bima sakti di langit hitam bagai jalan bintang-bintang yang cemerlang – pada waktu kita merasakan hati kita mengembang dan merasa bahwa alam raya jauh lebih banyak daripada awan-awan gas yang panas, benda yang berputar-putar, bentuk-bentuk hidup yang fana, dan bintang-bintang yang meredup. Pada saat-saat seperti itu, alam raya tampak penuh dengan kebaikan; alam raya terasa pribadi, dan kita mengalami kehadiran yang misterius di dalamnya. Orang tua sudah mengalaminya pada waktu bergembira karena kelahiran anak mereka. Suami dan istri yang telah menjadi tua secara bersama sering mengingatnya sepintas dalam hidup mereka. Pada saat-saat keheningan, kegembiraan atau kebersamaan seperti itu, kita tidak mempunyai cukup kata-kata untuk mengungkapkannya. Kita merasakan kehadiran dari yang paling akhir. Akan tetapi, bagaimana kita dapat membayangkan misteri itu? Bagaimana kita dapat mendekati kehadiran yang menarik kita, jika yang lain yang misterius itu, entah bagaimana caranya tidak keluar mendatangi dan menjumpai kita? Seperti apakah yang lain itu? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh Kristianitas! Menurut iman Kristiani, misteri yang ada di dalam inti kenyataan yang biasa disebut Allah, yang telah mengambil inisiatif, prakarsa, dan dinyatakan kepada kita dalam pribadi Yesus dari Nazaret. Perjumpaan dalam iman dengan misteri Allah ini membawa dampak pada pengalaman kita dengan berbagai cara. Dalam membahas perjumpaan dalam iman itu, tradisi Katolik telah lama membedakan antara tindak (act) iman dan isi (content) iman. Kita akan membicarakan dua segi iman itu maupun sumbernya dalam Roh Kudus. Tindak Iman Tindak iman merupakan penerimaan Allah dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus. Tindak iman mencakup perjumpaan pribadi dengan Allah yang membuat orang mempercayakan diri, percaya, menyerah dan mencintai. Tindak iman dapat dibandingkan dengan kisah di dalam Injil; bagaimana seorang wanita yang menderita sakit pendarahan (Mrk 5:28), perwira dengan hamba yang sakit (Mat 8:5-13), dan ayah yang anaknya kerasukan setan (Mrk 9:24) membuka diri mereka kepada Yesus dan mengalami kekuasaan Kerajaan Allah yang hadir dalam diri-Nya. Terutama dalam Injil Sinoptik, iman kepada Yesus selalu menyangkut kepercayaan diri secara pribadi yang mendalam. Dengan demikian, tindak iman merupakan saat Allah menjadi nyata bagi seseorang dan ia mencapai hubungan pribadi dengan Allah dan dengan Yesus. Tindak iman merupakan ”peziarahan iman” pribadi seseorang yang dapat digambarkan sebagai ”penerimaan Allah yang berlangsung secara progresif, yang dapat mencapai ekstasi mistis sebagai puncaknya dalam hidup ini”1 sebagaimana tampak dialami oleh St. Fransiskus Assisi. Tindak iman merupakan tanggapan total seseorang. Kata Injil untuk tanggapan ini adalah metanoia (Mrk 1:15), yang biasanya diterjemahkan menjadi ”penyesalan”, ”pertobatan” atau ”pembalikan”. Akan tetapi, metanoia bukan hanya berarti penyesalan atau kesedihan karena dosa-dosa, melainkan perubahan hati secara total. Metanoia merupakan tindak kreatif yang mengatur kembali prioritas-prioritas seseorang dan memberi kepadanya perasaan diri dicintai dan disayangi oleh Allah, sekalipun berdosa. Tindak iman pada dasarnya merupakan tindakan bebas karena Allah selalu menghormati kebebasan manusia. Allah tidak memaksa kita. Tindak iman merupakan tanggapan terhadap ajakan Allah, rahmat, kehadiran Allah. Akan tetapi sebagai tanggapan pribadi, tindak iman itu dapat berdampingan dengan keraguan, karena objek iman tidak dilihat dengan langsung (bdk. Ibr 11:11). Dalam hidup ini, seperti dikatakan oleh St. Paulus, ”kita melihat suatu gambaran yang samar-samar, seperti dalam cermin” (1Kor 13:12). Jika tindak iman itu sejati, tindak iman itu akan mewujudkan diri dalam perbuatanperbuatan. Tindak iman tidak dapat disempitkan melulu menjadi penerimaan dan kepercayaan. Tradisi Katolik meyakini betul-betul kata-kata St. Yakobus: ”Jika iman itu ..., maka iman itu pada hakikatnya adalah mati” (Yak 2:17). Di kalangan kelompok orang-orang Kristiani tertentu, saat terjadinya iman pribadi kepada Yesus ini digambarkan sebagai ”dilahirkan kembali”, ”membiarkan Yesus masuk ke dalam hidupnya” atau sebagai ”menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat pribadi”. Mereka suka menyebut Yesus ”Tuhanku” atau ”Yesusku”. Sedang orangorang Katolik biasa menggunakan sebutan ”Tuhan” atau ”Kristus” yang lebih bernada formal daripada orang-orang Kristiani yang bernada pribadi dan mungkin agak sarat dengan rasa atau emosi. Sebetulnya orang-orang Katolik dapat belajar sesuatu dari cara menyebut Yesus yang lebih emosional itu. Karena, akibat sebutan formal kepada Yesus itu, tanpa sadar banyak orang Katolik menyempitkan iman menjadi isi teologisnya, yaitu, percaya segala ”pengajaran” dan ”ajaran” Gereja. Mereka kurang memperhatikan dimensi tindak iman yang penting, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus yang dirasakan dengan kuat oleh orang-orang Kristiani di atas. Karena bagaimanapun juga bahasa yang bersifat pribadi itu menggambarkan pengalaman yang amat nyata, saat pertobatan atau keputusan pada waktu orang membuat komitmen yang sangat pribadi kepada Tuhan dalam iman. Namun, banyak orang Katolik telah mendapatkan pengalaman-pengalaman semacam itu pada waktu iman mereka diuji, dan mereka telah menegaskannya serta menjadikannya milik sendiri yang amat pribadi. Orang-orang Katolik lain mengalami iman mereka sebagai sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup mereka, pada waktu kesadaran dan pengetahuan tentang Allah yang tumbuh bersama jalannya waktu dan menjadi mendalam di dalam diri mereka. Sedang orang-orang Katolik yang lain lagi menemukan iman mereka amat nyata, meski adanya kejatuhan-kejatuhan yang mereka alami dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Suatu keraguan dan formalitas tertentu dalam ungkapan tidak berarti bahwa seseorang belum melakukan tindak iman, bahkan jika tindak itu belum diungkapkan secara jelas dalam bahasa injili. Tetapi ada beberapa alasan yang mendalam mengapa orang Katolik mencurigai bahasa yang terlalu personal dan emosional. Bagi orang-orang Katolik, pengetahuan tentang Allah selalu merupakan pengetahuan yang didapat melalui perantaraan tertentu. Allah tidak dialami secara langsung melalui semacam pengalaman rohani atau pewahyuan pribadi. Iman lebih daripada sekadar pengalaman subjektif ”dilahirkan kembali”, dan tak dapat dipersempit menjadi perasaan atau penerangan batin. Meskipun mempunyai tradisi mistik yang kuat dan mengakui adanya kemungkinan visiun, Katolisisme cenderung mencurigai pengalaman iman yang terlalu dipribadikan. Katolisisme selalu menekankan dimensi sosial dan komunal iman, yaitu bahwa iman itu bukan sekadar iman orang-perorangan, melainkan juga iman jemaat yaitu Gereja. Renungkan sejenak perjalanan iman Anda sendiri. Bagaimana Anda sampai pada iman pribadi? Siapakah Allah itu bagi Anda? Bagaimana Anda menggambarkan Allah? Pernahkah Anda mengalami kehadiran Allah secara khusus? Siapakah Yesus? Apakah Anda merasa bahwa Yesus itu seorang pribadi bagi Anda, dan bahwa Anda mempunyai hubungan pribadi dengan-Nya? Dengan cara-cara apa Yesus telah membantu Anda mengenal siapa Allah itu? Atau dikatakan secara lain, apakah Allah yang Anda kenal adalah Allah Yesus seperti terurai dalam Injil? Apakah pengalaman Anda akan Allah Trinitarian; apakah Anda berpikir tentang Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa atau apa yang telah membentuk dan mempengaruhi iman Anda? Apakah orang tua Anda memainkan peran penting? Kakek-nenek? Sanak-saudara? Dapatkah Anda ingat saatsaat, mungkin pada waktu acara keluarga, doa-doa menjelang makan, doa dan renungan di depan gua Natal, atau pada waktu dikaruniai anggota keluarga baru dengan kelahiran anak, pengalaman-pengalaman yang membuat Anda menyadari kehadiran Allah dalam hidup keluarga Anda? Apakah ada guru, imam, bruder, atau suster, pembimbing rohani, atau teman yang telah membantu Anda dalam memperdalam iman Anda? Pernahkah Anda mengadakan diskusi yang serius tentang pergulatan Anda untuk beriman, untuk mengenal Allah dengan sahabat Anda? Biasanya bila kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dengan merenungkan dari mana asalnya iman kita, kita menjadi sadar tentang orang-orang yang telah membantu kita mengenal dan percaya pria dan wanita yang telah berbagi iman mereka kepada kita, yang telah membantu kita mengenal Kitab Suci, yang telah merayakan iman mereka dengan kita dalam doa, ibadat, perayaan keagamaan, yang bagi kita telah menjadi jemaat yang disebut ”Gereja”. Kita akan kembali pada pengertian tentang iman yang sampai kepada kita dengan perantaraan jemaat Kristiani, tetapi sebelum itu bagaimana Sabda men-jadi hidup bagi kita, bagaimana kita mampu mengenal Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kita dibantu menerima Yesus sebagai Allah kita. Roh yang Mewahyukan Jika tindak iman dimengerti sebagai tanggapan pribadi terhadap Allah, tanggapan itu dibuat oleh pribadi Roh yang memungkinkan kita mengenal Allah dan Yesus Kristus, yang telah diutus Allah (bdk. Yoh 17:3). Roh Kudus dengan demikian merupakan sumber iman kita. Meski kerap menjadi yang terakhir dalam perumusan teologis, namun Roh merupakan yang pertama pada tingkat pengalaman. Roh adalah hidup dan napas Allah di dalam dan bagi dunia, kelanjutan misteri penjelmaan sesudah hidup Yesus di dunia. Akan tetapi, sulitlah membicarakan Roh itu. Kita tidak mengalami Roh secara langsung. Roh Kudus harus ditegaskan. Kita merasakan gerak Roh. Kata ”Roh” sendiri menyarankan sesuatu yang lebih terasa daripada dimengerti, sesuatu yang mempercepat dan memperhangat, daya tarik yang memberi hidup dan persatuan. Kata Hibrani ”roh” yaitu, rûah sulit untuk diterjemahkan. Dalam konteks yang berbeda-beda kata itu berarti ”napas,” ”angin”, ”prinsip hidup.” Kata Yunani pneuma sama halnya. Napas merupakan tanda kehidupan. Angin dapat lembut, sejuk, atau panas. Lagu Veni Creator Spiritus, doa Sequentia dalam liturgi Pesta Pentakosta, menyebut kehadiran Roh Kudus yang membawa perubahan: Sembuhkanlah luka kami, perbaruilah kekuatan kami; siramilah jiwa kami yang layu; basuhlah noda-noda kesalahan kami; lenturkanlah hati dan kehendak yang keras; cairkanlah yang beku, hangatkanlah yang dingin. Dalam Kitab Suci Hibrani, terutama sesudah pembuangan, ”roh” kerap dijadikan personifikasi kehadiran dan kegiatan Allah. Roh Allah bersifat kreatif dan memberi hidup (Mzm 104:29-30). Pada awalnya Roh itu melayang di atas air pada waktu Allah mengatur tatanan dan hidup dari kekacauan (Kej 1:2). Roh Allah membuat para nabi mampu mengucapkan Sabda Allah dan dengan demikian kehadiran Allah dalam kehidupan jemaat (Bil 11:17 dst.; 2Sam 23:2; Yeh 3:8). Roh itu juga dikaitkan dengan pengadilan dan perhatian Allah untuk keadilan (Mi 3:8; Yes 11:2-4; 42:7; 61:1-2). Roh Allah hadir dan aktif sepanjang hidup Yesus. Ia dikandung oleh Roh (Mat 1:20; Luk 1:35), menerima Roh pada waktu pembaptisan (Mrk 1:10), melaksanakan pelayanan dengan menyampaikan kabar baik kepada kaum miskin (Luk 4:18-19), dan mengadakan mukjizatmukjizat serta melakukan pengusiran-pengusiran roh-roh jahat dalam Roh (Mat 12:28), dan menghembuskan Roh pada para murid-Nya, Gereja (Luk 24:49). Bagi St. Paulus, Roh merupakan prinsip hidup Gereja. Roh memberi hidup baru kepada umat beriman (Rm 8:11) dan dalam baptis Roh menyatukan mereka menjadi satu tubuh Kristus (1Kor 12:13). Roh merupakan sumber struktur karismatis Gereja dan pelayanannya (1Kor 12). Dalam kisah para Rasul, Roh membimbing pertumbuhan Gereja awal. Rumusan baptis Trinitarian pada akhir Injil Matius (28:19) dan penyebutan Penghibur dalam Injil Yohanes merupakan teks Perjanjian Baru yang paling dekat mempersonifikasikan Roh dalam hubungan Bapa dan Putra. Pengalaman apa yang ada di balik kata ”Roh” dalam Perjanjian Baru ini? Mungkin kuncinya dapat kita temukan dalam surat-surat St. Paulus. Paulus melihat Roh sebagai kurnia Yesus yang telah bangkit; ada ”dalam Kristus” adalah memiliki hidup baru ”dalam Roh” yang membuat kita mampu mengenal kasih Allah (bdk. Rm 5:5), menyebut-Nya sebagai Abba ”Bapa” (Rm 8:15), dan berdoa dari hati (bdk. Rm 8:26-27)2. Dalam 1Kor, St. Paulus menulis, ”Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku ’Yesus adalah Tuhan’ selain oleh Roh Kudus (1Kor 12:3). Kita dapat merumuskan pandangan St. Paulus dengan mengatakan bahwa Rohlah yang membantu kita mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan, yang membuat kita mampu mengenal kasih Allah dan menyeru kepada Allah dalam doa. Selanjutnya, ”buah Roh” dalam hi- dup kita adalah ”kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri” (Gal 5:22-23). Itu semua merupakan kebiasaan-kebiasaan hati atau ”keutamaan-keutamaan” yang menjadi tanda-tanda yang dialami dari kehadiran Roh. St. Paulus menyebut kasih sebagai karunia Roh yang paling besar (1Kor 13:13); kasih merupakan tanda kehadiran Roh dalam hidup kita. Teologi selanjutnya mengembangkan pengertian ini. Bagi St. Agustinus, Roh merupakan kasih timbal balik antara Bapa dan Putra yang menarik kita untuk masuk dalam hubungan kasih itu supaya kita sungguh-sungguh ikut ambil bagian dalam hidup Ilahi. Dalam teologi Trinitarian Gereja, komunikasi-diri Allah terjadi dalam Putra (penjelmaan) dan mengubah hidup kita dalam Roh (rahmat). Pada gilirannya, Roh menarik kita untuk masuk secara lebih mendalam ke dalam hidup Kristus dan dengan demikian kembali kepada Bapa. Sejak awal Gereja, liturgi baptis telah merayakan penyadaran pada iman kepada Allah melalui Kristus dalam Roh ini. Orang yang dibaptis bukan menerima Roh, melainkan mengakui kegiatan Roh yang membawanya kepada Allah dalam Kristus. Sebagai sakramen yang memasukkan orang ke dalam Kristus dan Gereja, baptis justru merupakan tanggapan terhadap rahmat, terhadap kehadiran Allah dalam hidup seseorang. Ini menjadi jelas dalam liturgi pada waktu orang yang akan dibaptis menyangkal perbuatan-perbuatan dan godaan-godaan jahat dan mengungkapkan pernyataan iman Trinitarian. Kita semua merasakan saat-saat kita mengalami kehadiran Roh yang menarik kita untuk percaya, saat-saat iman kita menjadi hidup dengan cara istimewa. Tindakan Roh Kudus yang menarik kita untuk masuk ke dalam hidup yang lebih mendalam di dalam Allah ini, tercermin dalam bahasa tradisional mengenai ”Tujuh Kurnia Roh Kudus”: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keberanian, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Perhatikanlah bagaimana masing-masing ”karunia” itu dengan suatu cara menghubungkan kita dengan Allah. Bagi orang-orang Katolik, pengalaman akan Roh ini selalu merupakan pengalaman yang diperantarai. Pengalaman itu dapat berasal dari pengalaman kasih yang ramah dan menyembuhkan, yang menerima kita sebagai pribadi apa adanya, diperantarai oleh kasih sahabat, pasangan, orang tua, seperti sudah kita bicarakan sebelumnya. Pengalamanpengalaman semacam itu mengembangkan hati kita dan mengisinya dengan ketakjuban; pengalaman itu kerap mendorong kita untuk mencari sumber terakhir dari kasih ini. Kita juga dapat mengalami Roh yang menarik kita kepada Kristus dalam doa dan ibadat jemaat Kristiani. Pengalaman itu dapat muncul dari pewartaan Sabda, mendorong kita untuk mempercayakan diri, untuk membuka diri kita kepada Allah. Hal itu dapat terjadi pada peristiwa sakramental, pada waktu kita menjadi sadar akan kehadiran Kristus dalam roti yang dipecah dan anggur yang dituangkan, atau dalam jemaat, atau dalam menerima pengampunan. Itulah saat-saat kita merasakan kehadiran Roh dalam diri kita. Dalam dua bagian terakhir ini kita telah mengetahui bahwa iman Katolik bersifat iman komunal, eklesial. Meskipun masing-masing orang pada akhirnya harus memberi tanggapan terhadap Roh, terhadap rahmat Allah, dengan membuat tindak iman, orang-orang Katolik menemukan kehadiran Allah yang diperantarai oleh Gereja, dengan jemaat, sejarah, lambanglambangnya yang kudus, sakramen-sakramennya, bahkan struktur-struktur kelembagaannya. Iman Katolik berakar dalam sejarah Israel yang telah diwahyukan secara penuh dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan telah diteruskan selama berabad-abad sejak komunitaskomunitas agama Kristen awal oleh tradisi yang hidup. Isi Iman Jika Injil Sinoptik menekankan iman sebagai mempercayakan diri kepada Yesus, Injil Yohanes menekankan dengan sama kuatnya bahwa iman tidak hanya mempercayakan diri kepada Yesus tetapi juga menerima ajaran-Nya. Percaya kepada Yesus berarti bahwa kita menerima siapa Yesus itu (Yoh 6:69), asal-usul-Nya (Yoh 16:30), dan kata-kata yang telah diucapkan-Nya (Yoh 2:22; 5:47; 8:45). Dengan kata lain, iman juga berkaitan dengan isi, kisah tentang Allah dan umat Allah, yang diungkapkan dalam Kitab Suci, dalam syahadat, dan dalam ajaran-ajaran Gereja. Bagaimana kita dapat meringkas isi iman Kristiani? Untuk itu, kita harus melihat kembali kisah Umat Allah yang termuat dalam Kitab Suci Hibrani, yaitu kumpulan tulisan-tulisan suci Yahudi yang oleh orang Kristiani biasa disebut Perjanjian Lama. Kemudian kita akan membicarakan kisah tentang Yesus, ajaran-ajaran-Nya, hidup, kematian, dan kebangkitan-Nya, dan cara yang digunakan oleh murid-murid-Nya, orang-orang Kristiani pertama untuk menafsirkan dan memahami apa yang terjadi pada-Nya. Pada akhirnya, kita perlu membahas bagaimana Gereja perdana merumuskan imannya kepada Yesus dalam bahasa syahadat-syahadat resminya. 2. Umat Allah Kitab Suci Yahudi dibuka dengan Kitab Kejadian. Sebelas bab pertama dari Kitab Kejadian merupakan pendahuluan untuk kisah biblis mengenai karya Allah yang menyelamatkan. Babbab itu menceritakan kisah penciptaan dunia, asal-usul umat manusia, kejatuhan (manusia pertama ke dalam dosa), penyebaran dosa dan akibat-akibatnya yang membawa malapetaka, dan janji keselamatan, dengan menggunakan mitos-mitos dan kisah-kisah yang sebagian diambil dari bangsa-bangsa tetangga Israel yang belum mengenal Allah. Penciptaan dan Kejatuhan Meski kisah penciptaan ditemukan paling awal dalam Kitab Suci, namun teologi penciptaan dikembangkan baru kemudian dalam tradisi Perjanjian Lama. Orang-orang Israel pada awalnya tidak memikirkan Allah mereka sebagai pencipta kosmis. Pemahaman awal mereka tentang Allah mempunyai ciri dinamis dan personal. Allah bapa-bapa bangsa, dikenal dengan berbagai nama ”Allah Abraham”, ”Yang Perkasa dari Yakub”, ”Allah Mahatinggi”, adalah dewa suku yang menyertai perjalanan suku atau bangsa. Ini merupakan pengalaman tentang Allah orang Israel yang paling mendasar. Kemudian, melalui pengaruh Musa, mereka mulai berbicara mengenai Allah mereka sebagai ”Yahwe”, Allah yang menguasai umat Israel sebagai raja. Selanjutnya, mereka memperluas Kerajaan Allah atas bangsa-bangsa lain juga (Mzm 22:29; 47; 99). Ini merupakan pengembangan teologis yang besar. Pada waktu mereka menemukan kisah-kisah penciptaan bangsa-bangsa tetangga, mereka mulai melihat Allah mereka sebagai pencipta. Mazmur-mazmur menggambarkan Allah yang menjalankan kekuasaan rajawi-Nya, raja atas ciptaan berdasarkan karya-Nya, sebagai pencipta (Mzm 74:12;93;95-99). Mitos merupakan cara pra-ilmiah untuk menjelaskan misteri. Kita dapat mengatakan bahwa dua kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian bercorak mitis, yaitu menyampaikan kebenaran religius dengan cara yang amat imajinatif dan puitis. Kisah penciptaan pertama (Kej 1-2:4a) menyampaikan gambaran yang indah tentang Allah Israel yang membentuk dunia yang teratur, penuh terang, dan hidup, dari kekacauan, hanya melalui Sabda Ilahi-Nya saja. Dari segi sastra, kisah itu merupakan penulisan kembali kisah penciptaan Timur Tengah, yaitu Enuma Elish dalam bentuk Babilonianya, yang dilakukan dengan teliti oleh penulis Kitab Suci.3 Orang-orang Israel meminjamnya dari bangsa-bangsa tetangga mereka, dengan mempertahankan struktur dasarnya tetapi men-”demitologisasi”-kannya dengan meniadakan dari kisah asli penciptaan dunia melalui peperangan hebat antara dewa-dewi yang saling bersaing dan menggubahnya untuk menunjukkan Allah mereka menciptakan dunia tanpa susah payah dan sendirian. Kisah kedua (Kej 2:4b-25) lebih berpusat pada penciptaan Allah atas manusia dari tanah liat. Kisah itu diikuti dengan kisah kejatuhan, yang memasukkan ke dunia kekuatan-kekuatan kekacauan yang amat merusak dan yang telah ditaklukkan serta dikendalikan oleh Allah dalam karya penciptaan. Sesudah manusia, pria dan wanita, jatuh ke dalam godaan ular untuk menjadi ”seperti Allah” (Kej 3:5)—yaitu menempatkan diri sebagai yang utama dengan menolak untuk mengakui Ia yang satu-satunya Allah, dengan demikian mengambil tempat pencipta— dunia yang diberikan Allah kepada mereka mulai rusak. Kedua manusia itu kehilangan kemurniannya dan harus meninggalkan taman; anak-anak mereka mulai saling membunuh; dan pada waktu keadaan tanpa hukum meluas, tak lama kemudian umat manusia sendiri hampir hancur dengan kembalinya air awal dalam banjir besar. Apa yang diajarkan oleh mitos ”pra-sejarah” ini? Ada sejumlah tema penting yang muncul jika teks dibaca dengan teliti. Tema-tema itu tentang kebenaran-kebenaran religius, bukan kebenaran-kebenaran ilmiah. Pertama-tama, pra-sejarah Kejadian mengajarkan bahwa ciptaan sendiri itu baik, karena berasal dari tangan Allah. Kisah penciptaan pertama mengulang-ulang refren yang menyertai karya Ilahi seperti antifon liturgis: ”Allah melihat bahwa semuanya itu baik.” Kedua, Kejadian menegaskan martabat manusia yang tinggi. Dasar Katolik untuk mengatakan bahwa semua kehidupan manusia, mulai dari kehidupan anak yang belum lahir sampai orang tua, orang yang sakit tak tersembuhkan, penjahat yang dihukum, didasarkan dari pernyataan dalam teks bahwa pria dan wanita diciptakan ”menurut gambar Allah”. Dengan cara yang penuh misteri, setiap manusia mencerminkan kemuliaan Allah. Tambahan pula, pria dan wanita merupakan pasangan, diciptakan untuk saling melengkapi secara sejajar, sebagai lakilaki dan perempuan (bdk. Kej 1:27). Kritisisme mutakhir menunjukkan bahwa makhluk ha adam, yang diterjemahkan sebagai ”pria” (Kej 2:7) tidak terbedakan secara seksual sampai Allah menciptakan wanita. Dengan kata lain, tak ada subordinasi satu sama lain. Umat manusia hanya ada sebagai pria dan wanita. Sebelum jatuh dalam dosa, pria dan wanita merupakan pasangan yang sejajar dan menikmati hubungan akrab dengan Allah yang mendatangi mereka untuk bercakap-cakap dengan mereka di taman pada sore hari yang sejuk. Dalam lambang kemurnian yang amat bagus, hidup mereka digambarkan; karena diciptakan yang satu bagi yang lain, pria dan wanita tak terganggu oleh ketelanjangan mereka di hadapan satu sama lain. Ketiga, hubungan mesra antara umat manusia dan Allah rusak akibat dosa. Karena dosa manusia pertama, terjadi tiga macam pengasingan (Kej 3:16-19). Pertama, manusia pertama tidak lagi bersahabat dengan Allah. Kedua, hubungan mereka dengan alam rusak. Wanita harus melahirkan anak dengan susah payah dan kesakitan. Pria harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkahnya berhadapan dengan alam yang sekarang melawannya. Pada akhirnya, hubungan satu sama lain berubah. Seksualitas mereka lalu mendatangkan alienasi dalam hubungan mereka. Mereka menjadi terganggu oleh ketelanjangan mereka dan wanita kehilangan kesamaan dengan suaminya seperti semula dimaksudkan Allah. Masih ada butir yang terakhir. Meski terjadi kekacauan dan alienasi yang diakibatkan oleh tindakan manusia pertama di dalam ciptaan yang baik itu, namun Allah mau menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari akibat-akibat yang datang dari dosa mereka. Kebaikan Allah diungkapkan dalam berbagai campur tangan. Pada waktu Adam dan Hawa malu karena ketelanjangan mereka, Allah membuatkan pakaian bagi mereka. Allah memberi tanda pada Kain untuk melindunginya dari mereka yang mau membalas dendam atas pembunuhannya pada diri Abil. Allah membebaskan Nuh dan keluarganya – dan dengan demikian umat manusia – dari banjir yang menerjang. Akhirnya, kepada Abraham, Allah menjanjikan berkat bahwa segala bangsa di dunia pada suatu hari akan ikut menikmatinya (Kej 12:3). Keluaran dan Perjanjian Karena karya penyelamatan Allah didasarkan atas penciptaan sendiri, kisah Umat Allah yang sebenarnya mulai dengan Abraham, bapa bangsa Israel dan model biblis orang beriman. Allah memanggil Abraham agar meninggalkan keluarga bapak dan sukunya serta pergi ke tanah yang tidak dikenal, Kanaan. Keturunan-keturunannya menetap di sana, tetapi angkatanangkatan sesudahnya terpaksa mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Di Mesir mereka menjadi minoritas yang ditindas, pekerja migran yang dijadikan budak dalam kerajaan yang menindas. Buku Keluaran menceritakan kisah pembebasan Allah atas umat dari belenggu dan penindasan dengan perantaraan kepemimpinan Musa. Keturunan Abraham bukan bangsa yang penting. Secara historis orang-orang yang meninggalkan Mesir bersama Musa, yang kemudian menjadi bangsa Israel, mencakup ”kelompok orang yang bernenek moyang campuran” (Kel 12:38), orang-orang Yahudi dari berbagai suku, budak-budak yang melarikan diri dan sejumlah orang Mesir. Akan tetapi, kisah Keluaran merupakan pusat dari identitas bangsa Yahudi (seperti pengalaman Holokaus zaman Nazi Jerman tidak terpisahkan dari apa arti menjadi Yahudi dewasa ini). Menjadi seorang Yahudi adalah menjadi anggota kelompok malang yang dipilih, dibebaskan, dan dibentuk Allah menjadi suatu bangsa. Yang menjadi butir-butir sejarah bangsa itu adalah bahwa Allah memilih mereka dari antara bangsa-bangsa; mereka dibimbing melalui padang pasir dengan perbuatanperbuatan penuh kuasa; mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh yang penuh dengan Roh seperti Musa dan Miriam; mereka diselamatkan dari pengejaran orang-orang Mesir di Laut Merah dan Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di gunung Sinai. Dekalog, Sepuluh Perintah, yang diberikan kepada Musa di gunung yang kudus merupakan ungkapan paling awal dari Perjanjian itu, dan oleh perjanjian itu terciptalah hubungan antara Yahwe dan Israel, dan Israel dijadikan umat Allah yang kudus: ”Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku” (Kel 20:2-3). Dosa dan Keselamatan Bagi orang-orang Israel, peristiwa Keluaran merupakan penyelamatan Allah. Peristiwa itu merupakan tindakan Allah di masa lampau Israel. Tindakan itu merupakan tindakan Allah dalam sejarah mereka yang diambil Allah untuk membebaskan orang-orang migran yang diperbudak dari penindasan dan membuat mereka menjadi bangsa. Tradisi Israel terus melihat kembali peristiwa besar yang menjadi dasar pembentukan bangsa itu dan merayakannya (Mzm 103:2345; Yes 63:11-14). Penyeberangan Laut Merah yang menakjubkan, awan pada siang hari dan pilar api pada malam hari, penampakan Allah di gunung Sinai, dua loh batu dengan Perintah yang tertulis padanya; semua itu merupakan lambang kehadiran Allah pada bangsa-Nya selama perpindahan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Pesta Paskah merupakan jamuan ritual yang secara simbolis memperagakan kembali peristiwa pembebasan mereka. Akan tetapi, sejarah Israel selanjutnya menyebabkan pergeseran dalam pembayangan religius bangsa, dan keselamatan mulai dilihat sebagai sesuatu yang akan dilakukan Allah di masa mendatang daripada sebagai penyelamatan di masa lampau. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu adalah pengalaman gagal dan bersalah, atau dalam istilah teologis, pengalaman dosa. Sementara dosa dan rahmat selalu ada bersama dalam kehidup-an bangsa Israel, Israel sebagai komunitas mengalami sejumlah krisis antara abad ke-9 dan abad ke-6 SM. Kesatuan yang telah dibentuk oleh Daud antara suku-suku Utara dan Selatan hancur pada tahun 922 SM pada waktu satu kerajaan terpecah menjadi dua, Israel di Utara dan Yudea di Selatan. Kedua kerajaan itu diperlemah oleh serangkaian raja-raja yang lemah dan kerakusan kelas-kelas atasnya. Tambahan lagi, bangsa Yudea, yang secara salah percaya akan pilihan Allah dari keluarga Daud, terutama yang diungkapkan dalam ramalan Nabi Natan (2Sam 7:16), mengubah tradisi religius mereka menjadi ideologi politis. Serangkaian panjang nabi-nabi berusaha mengajak bangsa itu untuk bertobat, dengan menghukumnya karena memuja dewadewa palsu, karena percaya pada senjata dan persekutuannya dengan penguasa-penguasa asing daripada percaya pada Yahwe, dan terutama karena ketidakadilan dan penindasan mereka pada kaum miskin. Nabi-nabi seperti Amos, Yesaya, Mikha, Yeremia, Habakuk, Yehezkiel, dan Maleakhi mencela pemimpin-pemimpin bangsa dan kelas-kelas atas karena kerakusan, korup, tak adanya rasa belas kasihan, dan penggantian mereka atas agama dengan ketaatan lahiriah untuk keadilan dan belas kasihan yang dituntut oleh Hukum (Am 5:7-12,21-24; 8:4-6; Yes 1:1-17; 10:1-4; 58:3-7; Yer 7:3-7). Sulitlah untuk terlalu menekankan pandangan tentang agama biblis dan profetis ini: upacara keagamaan tanpa keadilan dan belas kasih kepada kaum miskin tidak berkenan bagi Tuhan (Yes 1:13-15). Kita perlu mendengar pesan ini dewasa ini seperti zaman Israel kuno. Akan tetapi, nabi-nabi Israel gagal. Kedua kerajaan jatuh, Israel pada tahun 721 SM jatuh ke tangan Asiria, Yudea jatuh ke tangan orang Babilon pada tahun 587 SM. Nabi-nabi melihat peristiwa ini sebagai pengadilan Allah pada bangsa karena ketidaksetiaan, kedosaan mereka. Akan tetapi, khotbah nabi tidak tanpa janji untuk pembebasan di masa datang. Para nabi selalu menyampaikan harapan bahwa Allah akan campur tangan lagi dalam kehidupan bangsa, dengan menunjukkan kebaikan penuh kasih ilahi, menghancurkan kejahatan yang menindas mereka, dan menyatakan keselamatan yang hanya dapat didatangkan oleh Allah. Demikianlah keselamatan menjadi sesuatu yang bakal datang, campur tangan di masa depan. Janji Allah adalah tidak meninggalkan bangsa yang dipilih dan disayangi-Nya ke suatu nasib yang diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Para nabi tidak dapat melukiskan gambaran yang konkret mengenai masa depan. Harapan mereka adalah umum, tidak khusus. Akan tetapi, dalam tulisan-tulisan profetis ditemukan berbagai gambaran dan ungkapan-ungkapan mesianis untuk mengungkapkan kepercayaan mereka akan keselamatan Allah yang bakal datang. Mereka berbicara tentang raja keturunan Daud atau ”mesias” yang akan memulihkan kehidupan religius bangsa dan memerintah dengan bijaksana (Yes 9:16; Mi 5:1-5; Yer 23:5; Yeh 37:24; Za 9:9). Beberapa berbicara mengenai ”Hari Yahwe” pada waktu pengadilan Allah akan dinyatakan, dengan membawa keadilan bagi kaum miskin, hiburan bagi orang yang sedih, dan hukuman bagi mereka yang berbuat jahat (Yes 2:11; Yl 4:14; Zef 1:14-18; 2:4-15). Yesaya (1:12; 5:6), Zefanya (2:7,9; 3:13), dan Zakharia (8:10-12) berbicara tentang ”sisa” Israel yang akan mengenal lagi berkat Yahwe. Yehezkiel berbicara tentang pembaruan perjanjian (Yeh 27:26; 34:27); Yeremia, dengan lebih pesimis, melihat Allah menetapkan perjanjian baru (31:31-34). Dalam Kidung Hamba Yahwe yang indah (Yes 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12) Yesaya kedua menggunakan gambaran Hamba Yahwe yang penuh teka-teki, yang akan membawa sendiri keselamatan Allah. Tradisi apokaliptik pada Yudaisme sesudah pembuangan yang berkembang pada masa krisis yang luar biasa pada waktu orang-orang Yahudi yang taat mati demi hak untuk menjalankan iman mereka, memandang ke akhir sejarah dan tatanan baru yang mencakup kebangkitan orang mati (Dan 12:1-3; 2Mak 12:44); untuk pertama kali gagasan tentang hidup sesudah mati masuk ke dalam tradisi Yahudi. Khotbah nabi-nabi dan harapan akan kebangkitan umum orang mati dalam tradisi apokaliptik menimbulkan harapan pada abad pertama Yudaisme Palestina, yang diungkapkan dengan berbagai cara, bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang baru. Dalam khotbah Yohanes Pembaptis, harapan itu diungkapkan dalam bentuk peringatan akan pengadilan yang akan datang: ”Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepadamu melarikan diri dari murka yang akan datang?” (Luk 3:7). Sebaliknya, khotbah Yesus sejak awal adalah pesan kabar baik, yang secara harfiah merupakan arti dari kata ”injil”. 3. Yesus dan Pemerintahan Allah Sangat mungkinlah bahwa untuk beberapa waktu Yesus menjadi anggota gerakan Yohanes Pembaptis.4 Pastilah pembaptisan Yesus oleh Yohanes merupakan titik balik dalam hidup-Nya. Injil menceritakan penampakan Allah sesudah pembaptisan-Nya, Yesus diurapi dengan Roh dan dinyatakan sebagai Putra Allah. Meskipun tidak mungkinlah menemukan pengalaman batin Yesus di belakang teks-teks, Lukas mencatat bahwa teofani itu terjadi pada waktu Yesus ”sedang berdoa” (Luk 3:21), dan para pengarang Injil Sinoptik sepakat bahwa sesudah itu Yesus mengundurkan diri ke padang gurun dan menggunakan banyak waktu untuk berdoa dan hening. Pada waktu Ia kembali dari padang gurun, Ia mulai berkhotbah dan mengumpulkan sekelompok murid di sekeliling-Nya. Dari murid-murid itu, Ia memilih 12 orang, angka simbolis Israel yang diperbarui. Pewartaan Yesus Dalam tahun-tahun pelayanan-Nya yang tidak panjang, Yesus tidak berbicara banyak tentang diri-Nya sendiri, dan pesan-Nya pun bukan terutama tentang hidup di masa depan. Menurut Lukas, Yesus ”Adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan” (Luk 24:19), yang ”berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis. Sebab Allah menyertai Dia” (Kis 10:38). Bahkan sekarang ini kita dapat merasakan kekuatan perumpamaan-perumpamaan-Nya. Perumpamaan-perumpamaan itu sulit kita terima, karena menantang cara berpikir kita yang sudah biasa. Seperti dikatakan oleh Eamonn Bredin, perumpamaan-perumpamaan itu menyampaikan kepada kita visi, pandangan baru yang mengejutkan, bahkan subversif: ”Orang Samaria-lah yang merupakan sesama; yang terakhir-lah yang menjadi yang pertama; orang yang hilang-lah yang membuat orang gembira; orang asing-lah yang tetap; anak boros-lah yang dipeluk dan dipestakan”.5 Gambaran yang memberi ciri utama pada pewartaan-pewartaan Yesus adalah gambaran tentang Kerajaan Allah, karena Ia menyatakan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat (Mrk 1:15). Meskipun istilah ”Kerajaan Allah” mempunyai akar dalam Perjanjian Lama, terutama dalam konsep merajanya Yahwe, namun sebagian besar merupakan ungkapan Perjanjian Baru. Dalam pewartaan Yesus, istilah ”Kerajaan Allah” itu berfungsi lebih sebagai lambang daripada konsep yang dirumuskan dengan jelas. Yesus tidak menjelaskannya, tetapi menggambarkan maknanya dengan perumpamaan-perumpamaan dan kedatangan-Nya melalui pelayanan-Nya. Istilah ”kerajaan” (basileia) kerap dan lebih tepat diterjemahkan sebagai ”pemerintahan” karena istilah itu menunjuk peristiwa yang dinamis, bukan tempat. Dalam pewartaan Yesus, pemerintahan Allah hadir baik sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Dimensi masa depan pemerintahan Allah amat jelas dalam pewartaan Yesus. Dalam doa Bapa Kami, Ia mengajar murid-murid-Nya berdoa untuk kedatangan pemerintahan Allah (Mat 6:10). Sabda Bahagia menjanjikan hiburan dan kegembiraan kepada orang miskin, orang yang berdukacita, dan yang lapar dalam Kerajaan Allah (Mat 5:3-12; Luk 6:20-23). Sabda-sabda Injil tentang Putra Manusia yang datang untuk mengadili menunjukkan dimensi masa depan Kerajaan Allah (Luk 12:8-9). Seperti dikatakan oleh John P. Meier dalam studinya tentang Yesus historis, ”Kerajaan eskatologis yang diwartakan Yesus ... akan berarti pembalikan dari segala penindasan dan penderitaan yang tidak adil, pemberian ganjaran yang dijanjikan kepada orang-orang Israel yang setia (kebahagiaan), dan keikutsertaan penuh dalam kegembiraan oleh umat beriman (dan bahkan beberapa bangsa lain) dalam pesta surgawi dengan para bapa bangsa Israel (Mat 8:11-12 dsj. dan doa permohonan roti dalam Doa Bapa Kami)”.6 Akan tetapi, Kerajaan dalam arti tertentu sudah hadir dalam pelayanan Yesus, menjadi nyata dalam hidup orang-orang lain melalui pewartaan dan perumpamaan-perumpamaan-Nya, mukjizat-mukjizat dan pengusiran-pengusiran setan, pewartaan tentang pengampunan dosa, dan praktek makan bersama-Nya. Sesudah mengusir setan dari orang yang tidak mampu berbicara, Yesus menjawab orang-orang yang mengecam-Nya: ”Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang padamu” (Luk 11:20). Tentulah inti tradisi mukjizat Injil itu historis, yaitu mukjizat-mukjizat yang berhubungan dengan penyembuhan orang yang menderita dan sakit, meski beberapa mukjizat yang sifatnya lebih hebat, seperti contohnya, mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana, mungkin merupakan ciptaan para pengarang Injil. Tradisi makan bersama, acara makan yang diikuti Yesus bersama teman-teman, para pendosa, dan orang-orang lain yang oleh para penguasa agama dianggap ada di luar hukum (Mrk 2:16-19), menunjukkan bahwa Kerajaan Allah mencakup semua orang; tidak ada orang yang dikecualikan. Yesus terus-menerus dikecam karena bergabung dengan ”para pemungut cukai dan pendosa.” Ekaristi Gereja mempunyai akar dalam tradisi makan bersama ini. Perumpamaan-perumpamaan tentang Kerajaan – petani dan benih, rumput dan gandum, biji sesawi, ragi yang dicampur dalam tepung, jala yang ditebarkan ke laut (Mat 13:1-53) – mengutarakan dimensi Kerajaan Allah, baik kini maupun di masa mendatang. Dengan demikian, Kerajaan Allah ”merupakan istilah Yesus yang menyeluruh untuk berkatberkat keselamatan, sejauh mengandung arti kegiatan Ilahi di dalam hidup manusia”.7 Kerajaan Allah berarti bahwa Allah harus ditemukan di tengah-tengah kita, bahwa kekuasaan penyelamatan Allah harus ditemukan di antara kita, pada waktu kita membuka diri kita kepada Allah dengan iman, dan keluar menghubungi orang-orang lain dengan penuh belas kasih seperti dilakukan Yesus. Namun, kita masih harus menunggu kepenuhan keselamatan kita. Meskipun semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam Kerajaan Allah, Yesus membuat hubungan antara masuk ke dalam Kerajaan dan tanggapan orang secara pribadi. Orang harus menjadi seperti anak kecil untuk masuk ke dalam Kerajaan (Mrk 10:15; Luk 18:17). Ia memanggil mereka yang mendengarkan untuk pertobatan pribadi (Mrk 1:15), untuk menjadi murid demi pelayanan Kerajaan Allah, mengajar mereka untuk mencintai orang lain dengan cinta kepada semua orang dan penuh pengorbanan-diri (Mat 5:38-48), setia kepada pasangan perkawinannya (Mat 5:31-32), dan memperingatkan tentang bahaya-bahaya kekayaan (Mrk 10:24-25; Luk 12:16-21). Sabda Bahagia merupakan inti pewartaan-Nya; Sabda itu menggambarkan mereka yang akan menemukan pemenuhan dalam Kerajaan Allah. Dapat masuk tidaknya ke dalam Kerajaan Allah tergantung dari perilaku orang terhadap sesamanya, terutama orang miskin dan orang yang menderita (Mat 25:34-46). Siapakah Allah yang diwartakan oleh Yesus? Yesus adalah seorang pengkhotbah keliling, tukang cerita, bukan teolog. Ia tidak memberi kuliah-kuliah abstrak tentang hakikat Allah. Gambaran-Nya tentang Allah bersifat pribadi dan konkret. Dalam khotbah-Nya, Allah tampil sebagai seorang Bapa yang penuh kasih, yang begitu melihat anaknya yang hilang kembali segera bergegas untuk menyongsong dan memeluknya (Luk 15:20). Allah adalah gembala yang meninggalkan sembilan puluh sembilan domba untuk pergi mencari satu domba yang tersesat (Mat 18:13). Kegiatan Allah di dunia tidak kelihatan tetapi pasti; Allah adalah wanita yang mencampur ragi ke dalam tepung roti, sampai akhirnya membuatnya khamir seluruhnya (Mat 13:33). Allah adalah tuan yang amat bermurah hati karena perhatiannya kepada mereka yang malang, yang memberi upah pekerja yang nganggur yang dipekerjakan pada akhir hari dengan upah yang sama dengan mereka yang dipekerjakan pada pagi hari (Mat 20:1). Allah adalah Pribadi yang menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang miskin, lapar, dan berduka cita (Luk 6:20-21), yang membalikkan kebiasaan dengan membuat yang terakhir menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir (Mrk 10:31; Luk 1:52-53). Allah adalah pemilik kebun anggur yang membuat diri rentan, yang mengambil risiko dengan mengutus anaknya yang terkasih sesudah para penyewa memperlakukan para buruh dengan kasar dan membunuh orang-orang yang sebelumnya diutus untuk mengambil bagian hasil panenan (Mrk 12:6). Allah adalah pribadi yang oleh Yesus terus-menerus dimohon dalam doa, pribadi yang disebut Yesus ”Abba”, istilah akrab yang digunakan anak untuk bapaknya. Kematian dan Kebangkitan Dalam mewartakan belas kasih Allah, kasih yang merangkum bahkan ”para pemungut cukai dan pendosa,” secara tersirat Yesus menantang para pemimpin religius Yahudi. Perasaan bahwa otoritas mereka terancam telah membuat mereka menjadi semakin melawan Yesus. Pada akhirnya, mereka bersekongkol dengan para pejabat pemerintahan Romawi untuk membunuh-Nya. Dalam arti yang amat nyata kejahatan yang hadir di dunia, kejahatan yang merupakan akibat kedosaan manusia, terungkap secara konkret dalam diri para pemimpin politis dan religius yang menolak untuk mengakui kehadiran Allah dalam pelayanan Yesus. Ia mencurahkan seluruh hidup-Nya bagi orang lain, bahkan sampai mati di salib. Dengan demikian, kematian yang diterima-Nya dengan bebas merupakan pemenuhan hidupNya untuk memberikan diri-Nya kepada orang-orang lain, penyerahan-diri yang merupakan bagian pelayanan-Nya demi Kerajaan Allah. Orang-orang Kristiani awal melihatnya sekaligus sebagai korban. Bahasa korban yang ada dalam kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri atas roti dan piala pada Perjamuan Terakhir ”tubuh-Ku ... yang diserahkan bagi kamu ... perjanjian baru oleh darah-Ku, yang akan ditumpahkan bagimu” (Luk 22:19-20). Yesus menyongsong kematian-Nya sendiri, ditinggalkan oleh teman-teman-Nya dan mungkin merasa ditinggalkan bahkan oleh Allah (bdk. Mrk 15:34). Namun demikian Ia tidak putus asa; sampai akhir Ia terus percaya bahwa Dia yang disebut-Nya ”Bapa” akan membela-Nya;8 dan Allah membangkitkan-Nya ke hidup kekal. Kebangkitan Yesus merupakan inti tradisi Perjanjian Baru. Tanpa kebangkitan itu, kisah orang-orang Kristiani awal tidak masuk akal. Kisah itu tidak padu. Meskipun kadang-kadang kita berkata Yesus ”bangkit” dari mati, bahasa itu kurang tepat. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan merupakan sesuatu yang terjadi pada Yesus. Allah membangkitkan-Nya. Bahkan jika bukan merupakan hal yang dapat dibuktikan dengan metode penelitian historis biasa, kebangkitan bukan hal yang tidak nyata. Kebangkitan tidak dapat disempitkan menjadi pengalaman subjektif dari pihak para murid. Namun, masih tetap merupakan sesuatu yang misterius tentang perjumpaan para murid dengan Yesus yang telah bangkit. Mereka tidak segera mengenal-Nya (Luk 24:31); mereka ketakutan dan berpikiran bahwa mereka melihat hantu (Luk 24:37); beberapa murid terus raguragu bahkan waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka (Mat 28:17); bahkan Maria Magdalena yang begitu dekat dengan Yesus tidak mengenal-Nya (Yoh 20:14). Kisah-kisah penampakan dalam Injil menyarankan bahwa ada sesuatu dalam pengalaman Paskah yang tidak dapat diobjektifikasikan.9 Yesus tidak menampakkan diri kepada musuh-musuh-Nya, tetapi hanya kepada teman-teman-Nya, kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan-Nya. (Di sini St. Paulus merupakan pengecualian, tetapi St. Paulus juga adalah orang yang sungguhsungguh mencari Allah meski secara salah). Itu seolah-olah Yesus telah membuat mereka percaya kepada-Nya. Mungkin pengalaman mereka sampai beriman kepada Yesus itu cukup khas, masih tidak sedemikian berbeda dengan pengalaman kita. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang ada di seberang sisi sejarah. Kebangkitan merupakan pengalaman eskatologis, sangat berbeda dari menghidupkan kembali orang mati. Kebangkitan berarti bahwa Allah telah mempertahankan Yesus; Allah telah membangkitkanNya ke hidup kekal ”di sisi kanan-Nya” (Kis 2:33), bahwa Yesus sekarang hidup di hadirat Allah yang abadi. Kebangkitan juga berarti bahwa kuasa Allah lebih kuat daripada kematian, bahwa seperti Yesus telah ditampilkan; demikian juga kita dapat mengharapkan hidup abadi. Kebangkitan hidup Yesus merupakan janji kemenangan kita yang terakhir atas dosa dan kematian. Terutama kaum miskin melihat kebangkitan sebagai kekuasaan Allah untuk mengalahkan ketidakadilan dan kejahatan. Kristologi dan Soteriologi Kematian dan kebangkitan Yesus mengubah pengertian para murid tentang Yesus. Yesus mewartakan Kerajaan Allah. Orang-orang Kristiani awal, yang menangkap secara intuitif apa yang telah dilakukan Allah dalam kematian dan kebangkitan Yesus, mewartakan Yesus. Mereka melihat hubungan intrinsik antara orang dan pesan-Nya; dengan demikian pewarta menjadi yang diwartakan. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, St. Paulus mengutip rumusan Kristiani awal yang mengatakan bahwa ”Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci” (1Kor 15:3). Dalam surat-suratnya, St. Paulus menggunakan berbagai istilah yang diambil dari tradisi Yahudi untuk mengungkapkan makna penyelamatan tentang apa yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus, Allah telah ”membenarkan” kita, membuat kita benar (Rm 4:25; 5:16-18), ”mendamaikan dunia dengan diri-Nya”, tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita melawan kita (2Kor 5:19). Dengan demikian, Yesus mendatangkan perdamaian kita dengan Allah (Rm 5:10). Ia telah menyelesaikan ”penebusan” kita, menebus seseorang atau sesuatu yang terkena denda, untuk mengungkapkan gagasan bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya (Rm 3:23-25; 1Kor 1:30). Yang paling penting Paulus melihat bahwa kemenangan Yesus atas dosa berarti bahwa kuasa maut telah dihancurkan (Rm 8) dan bahwa mereka yang percaya pada Yesus juga akan ikut dalam kebangkitan-Nya. Yesus sendiri adalah ”buah pertama” kebangkitan dari dunia orang mati (1Kor 15:23). Kebangkitan juga menimbulkan, bagi orang-orang Kristiani awal, pertanyaan Kristologis yang mendasar: Siapakah Yesus ini? Karena mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka menggunakan tradisi religius mereka sendiri, dengan menggunakan gambaran-gambaran dan gelar-gelar penyelamatan dari Kitab Suci, mereka mengungkapkan pengalaman mereka akan Yesus.10 Yesus adalah ”Mesias” atau Kristus, putra Daud yang diurapi, yang dijanjikan oleh para nabi sebagai tokoh yang akan mendatangkan keselamatan Allah, meskipun Yesus historis tidak mengatakan tentang diri-Nya sebagai Mesias dan tampaknya enggan menerima gelar itu dari orang-orang lain (bdk. Mrk 8:30). Yesus juga disamakan dengan ”Putra Manusia”, tokoh yang dalam tradisi apokaliptik akan datang pada hari-hari akhir sebagai penguasa dan hakim. Yesus sendiri berbicara tentang Putra Manusia sebagai Pribadi yang akan menjalankan pengadilan Allah (Luk 12:8-9). Yesus disebut ”Tuhan”, gelar kehormatan seperti ”Tuan”, tetapi juga dalam penggunaannya dalam bahasa Aram digunakan untuk menyebut Allah sebagai ”Tuhan” atau ”Tuhan itu”. Penggunaan yang kabur ini tetap bertahan dewasa ini dalam bahasa Jerman Herr dan dalam bahasa Spanyol Senor. ”Tuhan” dipergunakan untuk menyebut Yesus yang telah bangkit sebagai tokoh yang menampilkan ketuhanan Allah atau pemerintahan Allah di dunia. Akan tetapi, gelar ”Tuhan” merupakan gelar yang amat kuat. Kata Yunani untuk ”Tuhan”, ”Kyrios” telah digunakan dalam Septuaginta, terjemahan Kitab Suci Yahudi, untuk menerjemahkan nama kudus Yahwe. Pada waktu diterapkan pada Yesus, istilah itu mengandung arti bahwa Yesus ikut ambil bagian dalam otoritas Allah dan bahwa kalimat-kalimat dalam Kitab Suci Yahudi yang menunjuk pada Yahwe dapat juga menunjuk pada Yesus. Yesus juga disebut ”Putra Allah”, gelar yang di dalam Injil mempunyai beberapa arti. Markus yang Injilnya tidak terdapat kisah Natal, melihat Yesus sebagai Putra Allah berdasarkan pengangkatan yang dinyatakan atau diangkat sebagai Putra Allah pada waktu pembaptisanNya (Mrk 1:11). Di belakang ini ada gambaran Perjanjian Lama tentang keturunan yang dijanjikan dalam garis Daud, yang menurut ramalan Nabi Natan akan diangkat sebagai Putra Allah (2Sam 7:14). Studi mutakhir telah menekankan pentingnya tradisi kebijaksanaan dalam Yudaisme bagi umat Kristiani awal. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang sungguh benar, disebut Putra Allah dan dapat menyebut Allah Bapa-Nya (Keb 2:13,16-18). Yesus dilihat mempunyai hubungan khusus dengan Bapa (Luk 10:22).11 Dalam Perjanjian Baru, istilah ”Putra Allah” akhir-akhir ini digunakan dalam arti yang lebih metafisis: Yesus dari Kodrat-Nya adalah Putra Allah, seperti dalam Matius dan Lukas, yang menyatakan bahwa Yesus tidak dikandung oleh manusia melainkan oleh Roh Kudus (Mat 1:20; Luk 1:35), atau dalam Yohanes, di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Sabda yang ada sebelum dunia dan Putra Allah yang kekal. Dari Injil Yohanes muncul dasar dogma inkarnasi awal, yang merupakan kepercayaan yang amat mendasar bagi Katolisisme bahwa Sabda Ilahi, Logos, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita (Yoh 1:14), dengan perkataan lain, bahwa Allah telah masuk ke ruang, waktu, dan sejarah manusia dalam pribadi Yesus. Jelaslah bahwa pada akhir masa Perjanjian Baru keilahian Yesus dipahami dengan jelas, dan ada bukti sungguh-sungguh bahwa St. Paulus sadar akan misteri keputraan Ilahi Yesus jauh lebih awal sebelumnya (bdk. Flp 2:6-11). Orang merasa dalam Injil Markus kesadaran tentang misteri hubungan Yesus dengan Allah jauh melampaui apa yang dapat diungkapkannya dalam bahasa tradisional yang tersedia baginya. Apa yang menarik untuk direnungkan sekarang ini, bukan bahwa orang-orang Kristiani membutuhkan waktu yang sedemikian lama untuk mengenal keilahian Yesus, tetapi justru sebaliknya, bahwa umat Kristiani awal, banyak di antaranya adalah orang-orang Yahudi, dengan iman Yahudi kepada satu Allah yang tak tergoyahkan, dalam waktu relatif singkat mengakui bahwa Yesus sendiri adalah bersifat ilahi (bdk. Yoh 20:28). Akan tetapi inilah pengalaman mereka akan Yesus, iman mereka kepada-Nya, yang telah membuat mereka sampai pada pengakuan itu. Seolah-olah iman mereka kepada Yesus terus-menerus melampaui batas-batas imajinasi religius yang telah mereka warisi, dan gambaran-gambaran serta ungkapan-ungkapan biblis yang mereka gunakan untuk mendapatkan makna baru pada waktu mereka bergulat guna menemukan ungkapan yang memadai bagi iman mereka kepada Yesus. Dari Perjanjian Baru ke Kalsedon Setelah Kristianitas bergerak keluar dari tempat kelahirannya di dunia Kristiani Yahudi dan masuk ke dalam Kekaisaran Roma, Gereja menghadapi tantangan baru untuk menemukan bahasa yang mampu mengartikan imannya dalam budaya yang amat berbeda dengan tempat Kristianitas hidup sekarang. Tulisan-tulisan umat Kristiani awal yang segera akan dikenal sebagai Perjanjian Baru telah menggunakan bahasa mito-poetis Kitab Suci Yahudi; untuk sebagian besar, Yesus diuraikan secara fungsional, dalam kerangka hubungan-Nya dengan kita. Yesus adalah Mesias yang membawa keselamatan Allah; Ia adalah Putra Manusia yang melaksanakan pengadilan Ilahi, Putra Allah, Sabda Allah, sebagaimana telah kita lihat. Sekarang, di dunia Yunani-Romawi, pertanyaan ontologis atau metafisis yaitu siapakah Yesus bagi diri-Nya sendiri semakin banyak diajukan serta cara-cara baru untuk mengungkapkan ini dirumuskan dengan menggunakan bahasa filsafat Yunani Helenis yang lebih abstrak. Pemikiran Helenis tidak begitu kesulitan untuk menerima Keallahan Yesus sebagai Sabda (Logos) Allah, karena filsafat Neoplatonis penuh dengan imanensi dan prinsipprinsip kosmis Ilahi, tetapi gagasan bahwa Sabda Ilahi dapat menjadi daging merupakan hal yang berbeda. Itu tak dapat diterima oleh prasangka yang memusuhi persoalan yang khas dalam filsafat Yunani. Bidaah-bidaah awal seperti Docetisme dan Gnosticisme tidak dapat menerima kemanusiaan Yesus. Masalah yang sulit adalah masalah mempertahankan kesatuan biblis tentang Yesus, sementara mengakui kemanusiaan dan keallahan-Nya. Tidak semua usaha untuk memberi ungkapan akan kesatuan dalam diri Yesus itu berhasil. Salah satu krisis terbesar yang dihadapi oleh Gereja awal adalah bidaah Arianisme pada abad ke-3. Arius adalah seorang imam dari Alexandria, Mesir, yang lahir di Libia pada tahun 256. Dalam usaha untuk membela kemanusiaan Yesus yang dirasa diancam oleh ajaran uskupnya, Arius menolak keallahan-Nya. Ia mengajarkan bahwa Logos, atau Putra, adalah makhluk biasa, makhluk yang menerima keberadaan ”sebelum waktu dan zaman”, namun makhluk yang mempunyai awal, atau, seperti slogan teologisnya mengungkapkannya: ”ada waktu ketika Ia tidak ada.” Ajaran Arius tersebar dengan cepat, memecah umat Kristiani dan mengancam kesatuan kekaisaran. Pada akhirnya, dalam usaha untuk memulihkan perdamaian, Kaisar Konstantinus pada tahun 325 mengundang semua uskup untuk berkonsili di Nicea, Asia Kecil. Ini merupakan Konsili umum atau ekumenis yang pertama. Uskup-uskup yang berkumpul menolak pendirian Arian ”ada waktu ketika Ia tidak ada” dan menyiapkan pengakuan iman atau ”credo” untuk mengungkapkan apa yang dipercaya Gereja tentang Yesus: Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Putra Tunggal yang lahir dari Bapa, yaitu dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh-Nya baik yang di surga maupun di dunia. Bahasa Nicea jauh lebih filosofis daripada bahasa Kitab Suci. Bahasa Nicea berbicara tentang Yesus dan hubungan-Nya dengan Allah dalam istilah-istilah ontologis dengan menggunakan istilah Yunani homoousios, ”sehakikat”. Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa, satu dalam keberadaan dengan Bapa. Syahadat Nicea sedikit diubah dan diperluas oleh Konsili lain beberapa tahun kemudian di Konstantinopel (381). Konsili itu meneguhkan keallahan Roh Kudus, ”Yang bersama Bapa dan Putra dipuji dan dimuliakan.” Meski beberapa Gereja pada awalnya melawan syahadat, tahap demi tahap syahadat itu diterima atau ”disetujui” oleh kebanyakan Gereja kuno sebagai ungkapan iman mereka. Sekarang ini syahadat yang dikenal sebagai Syahadat Nicea, masih tetap diucapkan sebagai bagian Ibadat Hari Minggu, pada Gereja Katolik, Ortodoks, dan Gereja-Gereja Protestan Aliran Besar. Dengan Konsili Konstantinopel, Gereja telah maju dari pengalamannya tentang pewahyuan-diri Allah dalam sejarah sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepada dogma Tritunggal yang dirumuskan, yang masih dalam bentuk pokoknya. Konsili Kalsedon tahun 451 menyelesaikan masalah kesatuan Yesus dengan mengambil peristilahan satu pribadi dalam dua kodrat. Konsili-konsili berikutnya mengembangkan dan memperbaiki bahasa Trinitarian Gereja. Allah adalah kesatuan yang mengatasi, tetapi tidak meniadakan perbedaan. Satu Allah ada sebagai satu pengada atau hakikat dalam tiga pribadi yang berbeda tetapi sama. Dalam bahasa yang lebih sesuai dengan zaman ini, hidup batin Allah dibentuk oleh hubungan saling kasih dan kesatuan, kesatuan ke mana kita dipanggil untuk ikut ambil bagian. 4. Kesimpulan Tidak mudahlah untuk menjadi orang beriman dewasa ini. Budaya modern cenderung tidak lagi mengandaikan nilai iman religius dan hanya memberi sedikit dukungan bagi mereka yang berusaha menghayati iman mereka dalam hidup sehari-hari. Dalam budaya seperti itu nilai atau perasaan religius cenderung dipandang sebagai urusan pribadi dan bukan sebagai sesuatu yang dapat memberi sumbangan kepada hidup masyarakat.12 Budaya modern cenderung mendekati kepercayaan religius seperti mendekati kepercayaan atau nilai lain. Budaya itu mengandaikan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk percaya akan apa saja yang dipilihnya, karena tidak ada yang 100% aman. Akibatnya dalam bidang kepercayaan, masalahmasalah kebenaran ditentukan berdasarkan cita rasa pribadi. Pendekatan Katolisisme terhadap iman lebih bersifat pribadi daripada dalil, lebih bersifat bersama daripada perorangan. Tindak iman merupakan perjumpaan pribadi dengan Allah yang diwahyukan dalam Yesus, tetapi perjumpaan itu merupakan karya Roh Kudus melalui perantaraan jemaat yang percaya. Kita dapat mengenal Allah sebagai anggota umat yang telah lebih dulu dipilih Allah dan berhubungan dengannya. Dari zaman Abraham dan Sara, Musa dan Miriam, umat ini adalah umat Allah; dan melalui sejarah mereka dengan perjuangan-perjuangan dan tragedi-tragedinya maupun prestasi roh manusianya, melalui para nabi yang berbicara atas nama Allah, yang menyebut dosa dan meyakinkan umat tentang kesetiaan Allah, pewahyuandiri Allah terjadi. Pewahyuan itu mencapai perwujudannya yang penuh dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dengan demikian, iman jauh lebih banyak daripada pengalaman subjektif pribadi; iman mempunyai isi, isi yang berakar pada pengalaman dan bersamaan dengan itu mengatasinya. Iman diteruskan secara historis, dinyatakan melalui lambang-lambang dan diungkapkan dalam kisah-kisah serta bahasa jemaat yang percaya. Jemaat yang menjadi perantara kita mengenal Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah jemaat para murid Yesus yang kita sebut Gereja. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Avery Dulles, The Assurance of Things Hoped For: A Theology of Christian Faith (New York: Oxford Univ. Press. 1994) 32. Lihat Kilian McDonnell ”A Trinitarian Theology of the Holy Spirit” Theological Studies 46 (1985) 204. Lihat Alexander Heidel, The Babylonian Genesis (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1942). Lihat John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (New York: Doubleday, 1994) 2:123. Eamonn Bredin, Rediscovering Jesus: Challenge of Discipleship (Mystic, Conn: Twenty-Third, 1986) 40. Meier, A Marginal Jew, 2:349. Michael L. Cook, The Jesus of Faith (New York: Paulist, 1981) 56-57. Edward Schillebeeckx, Jesus: An Experiment in Christology (New York: Seabury, 1979) 256-271. Lihat Dermot Lane, The Reality of Jesus (New York: Paulist, 1975) 60. Istilah ”Pengalaman Paskah” berasal dari Schillebeeckx, Jesus, 380. Lihat Bredin, Rediscovering Jesus, 247-259. Marinus de Jonge, Christology in Context: The Earliest Christian Response to Jesus (Philadelphia: Westminster, 1988) 79-82. Lihat Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993). III Gereja yang Kelihatan Ada sebuah lukisan karya pelukis California, bernama John August Swanson, yang diberi nama ”Prosesi.” Pada bagian depan lukisan itu digambarkan sekelompok umat yang keluar dari gereja besar didahului para misdinar yang membawa lilin-lilin dan dupa. Mereka itu mengiringi Ekaristi yang dibawa oleh seorang imam dan dipayungi. Di bagian tengah lukisan tampaklah Gereja, menaranya menjulang ke atas untuk menyangga Yesus dan para murid dalam perahu yang menarik jala besar penuh ikan. Seluruh lukisan penuh dengan manusia – dalam prosesi, pada latar belakang panji-panji yang dibawa umat, dan dalam ruangan-ruangan, dalam ikon-ikon kecil seperti ikon-ikon pada jendela kaca yang berwarna yang melekat pada dinding-dinding gereja. Beberapa tokoh yang dilukis adalah tokoh-tokoh Kitab Suci – Adam dan Hawa yang meninggalkan taman, perahu Nuh, korban Iskak, impian Yakub mengenai tangga ke surga, Musa yang ditemukan oleh putri Firaun di sungai, Daud dan Goliat, Yudit yang memenggal kepala Holofernes, Yunus yang ditelan oleh ikan besar, tiga orang muda di perapian, Maria menerima kabar gembira, kanakkanak Yesus di palungan Betlehem, Tiga Raja, Yesus dibaptis di sungai Yordan, wanita yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya, prosesi Minggu Palma, penyaliban, penampakan Yesus kepada para murid. Beberapa tokoh adalah tokoh-tokoh pria dan wanita kudus dari sejarah Kristiani – St. Heronimus di gua menerjemahkan Kitab Suci, St. Fransiskus dengan serigala-serigala Gubbio, St. Clara, St. Patricius, St. Elisabet dari Hongaria. Beberapa tokoh adalah tokoh-tokoh apokrif – Veronika mengusap wajah Yesus, St. Kristoforus membawa Kanak-kanak Yesus menyeberang sungai, St. Gregorius dan naga. Tokoh-tokoh itu tampak seperti orang Indian atau Hispanik. Warna-warnanya bernuansa Amerika Tengah. Lukisan itu penuh, dipadati manusia – berbagai warna kulit, berbagai kegiatan: bermain musik, merayakan, menjumpai Tuhan. Prosesi hidup itu adalah Gereja – dalam sejarah, dalam keanekaragaman, dan dalam hidup sakramental. 1. Gereja dan Konsili Pada waktu para Bapa Konsili Vatikan II mau mengembangkan dokumen tentang Gereja, yang sungguh-sungguh merupakan pemahaman diri Gereja Katolik Roma, mereka bergulat dengan sejumlah skema atau draft. Draft pertama (1962) disiapkan oleh subkomite dari Komisi Teologis Roma yang konservatif, yang diketuai oleh Kardinal Alfredo Ottaviani, kepala Kantor Takhta Suci. Lencana keuskupan Kardinal bertuliskan semper idem, yang berarti ”selalu sama”. Draft yang dihasilkan oleh komisi itu ditolak oleh para Bapa Konsili. Para Bapa Konsili berpendapat bahwa penguraiannya tidak cukup biblis, bahwa dokumen itu merumuskan Gereja hampir sepenuhnya – dalam kerangka hierarki, dan bahwa dokumen itu tidak memenuhi keprihatinan ekumenis Paus Yohanes XXIII, yang telah menjadikan kesatuan Kristiani salah satu tujuan utama Konsili. Menurut Uskup de Smedt dari Bruges, dokumen itu terlalu triumpal, klerikal, dan yuridis.1 Draft kedua, yang disampaikan kepada para uskup pada musim semi tahun 1963, menunjukkan perbaikan yang berarti. Sesudah beberapa revisi lebih lanjut, dokumen itu disetujui oleh para uskup pada tanggal 21 November 1964, dengan 2.151 suara setuju dan 5 melawannya. Dokumen, yang disebut Konstitusi Dogmatik tentang Gereja (Lumen Gentium) dibuka dengan bab yang berjudul ”Misteri Gereja”. Bab 2 membahas seluruh Gereja sebagai ”Umat Allah.” Bab 3, ”Susunan Hierarkis Gereja, khususnya keuskupan” difokuskan pada pelayanan resmi Gereja, terutama jabatan uskup. Gereja adalah jemaat para murid Yesus. Gereja harus tetap demikian pada masa sekarang. Akan tetapi, apa hubungan antara Gereja sebagai jemaat dan Gereja sebagai lembaga? Bagaimana orang-orang Kristiani Katolik mengerti Gereja? Dalam bab ini, kita akan menyelidiki dialektika antara Gereja sebagai jemaat serta ungkapannya yang institusional dan kelihatan. Kita akan membahas Gereja sebagai jemaat para murid, pelayanan resminya, dan hakikatnya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 2. Jemaat Para Murid Gereja telah ada sejak sahabat-sahabat dan murid-murid Yesus, yang terpencar-pencar karena penangkapan dan penyaliban-Nya, berkumpul kembali karena kehadiran Yesus, dalam wujud yang baru sebagai Dia yang telah bangkit, di antara mereka. Pada hakikatnya Gereja adalah jemaat para murid Yesus. Dalam arti apa kita dapat mengatakan bahwa Yesus ”mendirikan” Gereja? Di satu pihak, Yesus historis tidak merancang dan merencanakan Gereja sebagai organisasi, dengan serangkaian pejabat, tujuh sakramen dan sebuah konstitusi. Di pihak lain, Yesus memang mengumpulkan pria dan wanita, yang adalah murid-murid-Nya, menjadi suatu jemaat, mengikutsertakan mereka dalam pelayanan-Nya sendiri dalam mewartakan kabar baik tentang pemerintahan Allah, menunjuk dua belas orang menjadi Rasul, memberitahu mereka untuk meneruskan tradisi mohon bersama dengan memecah roti dan minum dari cawan untuk mengenang-Nya, dan memberi kuasa kepada mereka dengan Roh Kudus. Orang dapat melacak ”penerusan iman, petugas dan praktek antara kelompok yang berkumpul di sekeliling Yesus dalam pelayanan-Nya di dunia (para murid) dan kelompok yang berkumpul di sekeliling Tuhan yang sudah bangkit (Gereja).”2 Pada waktu jemaat itu menyebar dan berkembang, jemaat itu tahap demi tahap mengembangkan struktur kelembagaan dan pelayanan yang akan menjamin kesetiaannya kepada asal-usul dan perutusannya. Semua ini terjadi di bawah bimbingan Roh, yang dicurahkan oleh Yesus yang sudah bangkit. Dengan demikian, Gereja Katolik dapat menyatakan lembaga Ilahi bagi struktur-struktur historisnya. Gereja Kata Perjanjian Baru untuk ”Gereja,” ekklesia, yang berasal dari kata Yunani ex (keluar) dan kaleo (memanggil), secara harfiah berarti ”mereka yang telah dipanggil keluar,” yaitu ”kumpulan” atau ”jemaat”. Kata itu merupakan kata Pentakosta, bukan kata Injil, yang hanya muncul tiga kali dalam Injil terutama dalam Injil Matius 16:18 dan 18:17. St. Paulus menggunakan kata ekklesia dengan tiga cara dalam surat-suratnya. Kadangkadang ia menggunakan ungkapan ”jemaat di rumah mereka” atau jemaat keluarga, untuk kumpulan orang-orang Kristiani setempat dalam rumah perorangan (1Kor 16:19; Rm 16:5; Kol 4:15). Jemaat-jemaat keluarga itu merupakan ungkapan paling awal dari Gereja; di sini orangorang Kristiani berkumpul untuk pengajaran (didache), persekutuan (koinonia), dan ibadat (leiturgia) dan dari jemaat-jemaat itu muncul banyak kepemimpinan Gereja awal. Secara teologis, tatanan jemaat keluarga menunjukkan bahwa tempat kehadiran Allah bagi jemaat Kristiani awal bukan tempat khusus, atau tempat kudus tetapi jemaat itu sendiri. Realitas Gereja ada dalam jemaat umat beriman sendiri.3 Kerap kali St. Paulus menggunakan kata ekklesia untuk menyebut jemaat setempat seperti ”jemaat Allah di Korintus” (1Kor 1:2) atau menyebut semua jemaat (1Kor 11:16). Kadangkadang ia menggunakan kata ”jemaat” secara umum, penggunaan yang menjadi lebih umum pada Perjanjian Baru yang kemudian (bdk. Kol 1:24; Ef 5:29). Dewasa ini kita berbicara tentang Gereja yang ”menyeluruh”, ”universal” atau ”Katolik” maupun Gereja ”lokal” atau ”khusus” yang dipimpin oleh uskup. 4 Tubuh Kristus Istilah lain dari St. Paulus untuk Gereja adalah ”Tubuh Kristus”. Sebagai jemaat dengan anggota-anggota yang berbeda dan karunia-karunia serta pelayanan-pelayanan yang berbedabeda (1Kor 12:4-7) yang dijadikan satu tubuh dalam Roh oleh pembaptisan (1Kor 12:13) dan Ekaristi (1Kor 10:17), jemaat, atau Gereja, membentuk tubuh Kristus (1Kor 12:27). Dasar pemahaman St. Paulus tentang Gereja sebagai tubuh Kristus adalah pendamaian orang-orang yang merupakan buah baptis dan Ekaristi. Ia memberitahu umat Kristiani di Korintus bahwa mereka berdosa melawan tubuh dan darah Tuhan karena jemaat mereka terpecah dalam perjamuan Ekaristinya (1Kor 11:17-34). Ia memperingatkan mereka bahwa ”Dalam satu Roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh” (1Kor 12:113). Ia menggunakan bahasa yang serupa kepada umat Galatia: ”Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua ada-lah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal 3:27-28). Dengan kata lain, segala perpecahan buatan berdasarkan ras, status sosial, atau jenis kelamin tidak ada lagi bagi mereka yang dipersatukan ke dalam Kristus melalui baptis. Tidak terbantahkan lagi bahwa ada sifat yang inklusif pada Gereja. Hidup dalam Roh St. Paulus biasanya menyebut kehidupan Kristiani sebagai hidup dalam Roh. Ia melihat bahwa jemaat Kristiani kaya dalam karisma dan pelayanan. Karisma dan pelayanan itu meliputi karunia-karunia (charismata) seperti kebijaksanaan, iman, penyembuhan, penegasan, pelayanan, pemberian derma, kerja amal maupun peran-peran atau pelayanan-pelayanan yang lebih tetap (diakonia) seperti rasul, nabi, guru, dan pemimpin. Semua diberikan untuk pembangunan Gereja (1Kor 12:4-7; Rm 12:4-8). Ia juga menyebut perkawinan dan selibat demi kerajaan sebagai karunia (1Kor 7:7). Gereja, menurut pandangan Paulus, merupakan paguyuban yang dipenuhi oleh Roh. Masing-masing anggota paguyuban dapat menyumbangkan sesuatu: ”Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama” (1Kor 12:7). Konsili Vatikan II dengan berbagai cara menekankan bahwa umat awam ikut ambil bagian di dalam perutusan dan pelayanan Gereja. Meski Konsili tidak sampai berbicara secara khusus tentang pelayanan kaum awam, namun jelas bahwa Konsili menggerakkan Gereja ke arah itu. Konstitusi Dogmatik tentang Gereja mengambil kembali, bagi orang-orang Katolik, pandangan St. Paulus tentang Gereja yang dilengkapi dengan berbagai karunia karismatis. Beberapa kali Konsili berbicara tentang keanekaragaman karunia (LG 12), ”baik hierarkis maupun karismatis” (LG 4). Konsili juga menekankan bahwa baik imamat hierarkis maupun imamat umum dari semua orang yang dibaptis ikut ambil bagian di dalam imamat Kristus (LG 20), dan bah-wa kaum awam ikut ambil bagian baik dalam fungsi Kristus sebagai imam, nabi dan raja (LG 31) maupun dalam perutusan Gereja sendiri (LG 33). Tidaklah pernah mudah bagi Gereja untuk menjadi apa yang seharusnya, yaitu jemaat para murid. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi oleh Gereja Perjanjian Baru adalah menciptakan kesatuan baru antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi hasil pendamaian Allah dalam Kristus. Tidak segera jelas bagi orang-orang Kristiani awal, karena mereka orang Yahudi, tentang apa tepatnya arti pendamaian itu. Bagi banyak orang di antara mereka, amat sulit dimengerti bagaimana orang dapat menjadi murid Yesus dan anggota jemaat Kristiani tanpa terlebih dulu menjadi orang Yahudi, yang artinya menaati hukum Yahudi dengan segala peraturan makan dan bagi orang laki-laki sunat, (bdk. Kis 15; Gal). Paulus sendiri melihat dengan jelas bahwa menjadi Yahudi atau non-Yahudi tak ada bedanya. Pesan pentingnya yang tertulis dalam surat kepada umat Roma adalah bahwa semua dibenarkan oleh iman akan Yesus Kristus. Gereja membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menentang perbudakan sebagai lembaga. Sementara mengajarkan bahwa hubungan antara budak dan tuan harus berbeda berdasarkan kebersamaan baru dalam Yesus Kristus (Flm; Ef 6:5-9), St. Paulus tidak menantang lembaga perbudakan, yang diterima begitu saja di dunia kuno. Gereja menerima perbudakan selama berabad-abad. Sejumlah Paus mulai berbicara melawan perdagangan budak pada abad ke-16, meski baru pada zaman Paus Leo XIII (1873-1903), Gereja secara resmi mulai memperbaiki ajarannya tentang perbudakan.5 Dapat diperdebatkan, sebagaimana banyak dilakukan sekarang ini, bahwa Gereja belum mengalami persamaan penuh antara pria dan wanita, bukan hanya dalam prinsip melainkan dalam Gereja sendiri. Bagaimana Gereja berkembang dari jemaat para murid Yesus menjadi Gereja dengan pelayanan uskup, imam, dan diakon yang hierarkis dan disusun, serta dikepalai oleh Uskup Roma, Paus? 3. Pelayanan Resmi Sejak awal keberadaannya, jemaat para murid Yesus mempunyai sekelompok kepemimpinan pada dua belas Rasul, kelompok inti yang dipilih oleh Yesus selama pelayanan historisnya. Perjanjian Baru mengakui lingkungan rasul-rasul yang lebih luas sejak awal maupun tempat khusus dua belas Rasul. Rasul-rasul adalah saksi mata atas kebangkitan Yesus, mereka yang mempunyai ”Pengalaman Paskah” dari Yesus yang sudah bangkit. Meski Yesus yang telah bangkit menampakkan diri baik kepada pria maupun wanita, wanita tidak diberi sebutan ”rasul” oleh para penulis Perjanjian Baru,6 mungkin sekali karena alasan budaya bahwa dalam masyarakat Yahudi suara wanita tidak dianggap sebagai kesaksian yang mengikat secara legal. Kebanyakan rasul bekerja sebagai penginjil yang berkeliling daripada pastor yang menetap. Sebagaimana St. Paulus sendiri, mereka terus-menerus bergerak untuk membangun komunitas-komunitas atau jemaat-jemaat. Sejak awal, dua belas Rasul memilih untuk berbagi pelayanan kerasulan dengan orang lain (Kis 6:1-6). Tambahan pula, rasul-rasul bukan satu-satunya pelayan atau penginjil pada zaman Gereja awal itu. Semua murid dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam perutusan Yesus. St. Paulus berbicara tentang berbagai karunia dan pelayanan (1Kor 12:4), dan daftar nama dari ”rekan-kerjanya” pada akhir banyak suratnya merupakan bukti bahwa ia tergantung pada orang- orang lain, beberapa orang diantaranya adalah suami-istri (bdk. Rm 16). Pada hari-hari awal itu bahasanya cukup encer, meski di sana-sini sudah ada aturan tertentu. Dalam 1Kor, Paulus berbicara tentang ”pertama, rasul-rasul; kedua, nabi-nabi; ketiga, pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengajarkan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh” (1Kor 12:28). Dalam surat kepada umat di Roma, Paulus menyebut karunia bernubuat, mengajar, menasihati, memberi dana, memimpin, dan berbuat amal. Pelayanan dan Kepemimpinan Kiranya baik untuk merenungkan sifat bahasa yang digunakan oleh jemaat-jemaat awal bagi para pelayan dan pemimpin mereka.7 Pertama, bahasa itu fungsional. Para pelayan dan pemimpin biasanya disebut dalam kerangka peran yang mereka mainkan: mengajar, memimpin, mengawasi, menggembalakan. Perjanjian Baru tidak menggunakan kata ”imam” (hiereus) bagi para pelayan Kristiani. Kedua, bahasa yang digunakan menyarankan sesuatu berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan cara menjalankan otoritas dalam jemaat Kristiani. Kata-kata kekuasaan dihindari. Ajaran Yesus tentang kepemimpinan sebagai pelayanan dalam jemaat para murid diingat dan diwariskan. ”Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya.” (Mrk 10:42-44; bdk. Luk 22:25-26). Kata ”gembala” (pastor dalam bahasa Latin) dihubungkan dengan guru (Ef 4:11) dan penilik (Kis 20:28; 1Ptr 5:2-4). Petrus dijadikan gembala dalam arti amat khusus (Yoh 21:15-17). Pikirkanlah sejenak tentang bagaimana gembala berfungsi terhadap kawanannya. Pada umumnya gembala mengikuti daripada memimpin kawanan, karena domba-domba tahu ke mana mereka mau pergi. Gembala hanya campur tangan bila seekor domba menyeleweng atau ada bahaya yang mengancam. Perannya adalah membimbing dan melindungi, bukan menguasai. Kita masih berbicara tentang kepemimpinan atau pelayanan ”pastoral” dan berkeberatan bila kepemimpinan itu dijalankan secara otoriter. Kata Perjanjian Baru yang pokok untuk ”pelayanan” adalah kata Yunani diakonia yang diturunkan dari kata diakonos, ”hamba”, ”pelayan”. Kata diakonia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi ministerium. Dari kata itu kita mendapatkan kata Inggris ”ministry”. Pelayanan adalah tugas demi komunitas Kristiani; seperti setiap karunia spiritual atau karisma, maksud pelayanan adalah untuk pembangunan Gereja (1Kor 14). St. Paulus menggambarkan diri sebagai pelayan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi (Rm 15:16), dan ia menyebut Febe ”saudari kita” sebagai ”pelayan” (bukan diakonos) Gereja di Kengkrea (Rm 16:1). Para pemimpin Gereja setempat digambarkan dengan berbagai istilah, antara lain: ”pemimpin” atau ”ketua” (bdk. 1Tes 5:12; Rm 12:8), ”nabi” dan ”guru” (1Kor 12:28, bdk. Kis 13:1), ”gembala dan guru” (Ef 4:11), ”pemimpin” (Ibr 14:7,17, 24), ”penatua” (Kis 14:23; 20:17; 1Tim 5:17-22; Tit 1:5), atau ”penilik”, karena dua istilah itu tidak selalu jelas dibedakan (bdk. Kis 20:17-35; 1Ptr 5:1-4). Sedikit demi sedikit penilik mengambil alih peran-peran yang sebelumnya dilaksanakan oleh nabi, guru, dan pemimpin. Tanggung jawab mereka meliputi baik kepemimpinan jemaat maupun, sedikit demi sedikit, fungsi mengajar dan liturgis yang dilakukan oleh nabi dan guru (Kis 13:2). Dari satu pelayanan, yang disebut dengan berbagai sebutan ini, muncul dua jabatan yang berbeda, penatua atau ”imam” sebagai istilah yang kemudian menjadi lebih populer dikenal, dan uskup. Perjanjian Baru yang kemudian juga mengenal kelompok yang disebut ”diakon”. Tahbisan Pada akhir masa Perjanjian Baru penatua diangkat menduduki jabatan, mungkin dengan penumpangan tangan (1Tim 4:14; 5:22). Penunjukan pada jabatan dengan ritual dan doa menjadi dikenal sebagai ”tahbisan”, istilah yang ditemukan dari kata Latin ordo yang berarti ”lembaga yang mantap”. Dengan tahbisan, seseorang dimasukkan ke dalam ordo episcoporum (jajaran uskup), ordo presbyterorum (jajaran penatua), atau ordo diaconorum (jajaran diakon), dengan demikian ke dalam jabatan pastoral resmi Gereja. Ada juga ”jajaran” perawan, janda, katekumen, dan peniten pada Gereja awal. Dalam tradisi penunjukan ke jabatan pastoral melalui doa dan penumpangan tangan menjadi dikenal sebagai sakramen ”tahbisan suci”. Uskup Kata ”uskup” dari bahasa Yunani episkopos, berarti ”penilik”. Peranan episkopos adalah mengawasi jemaat dengan menjalankan reksa gembala untuk kebaikannya. Dalam 1 Clement, surat yang ditulis dari Gereja di Roma sekitar tahun 96, istilah ”penatua” dan ”penilik” masih dipakai secara bergantian. Akan tetapi dalam 1Tim, dua jabatan penatua-penilik dan diakon tampaknya dalam proses berkembang menjadi tiga jabatan: uskup dibantu oleh penatua dan diakon. Surat itu menguraikan beberapa penatua dengan memberi tambahan pada peran mereka untuk mengawasi jemaat tugas-tugas untuk berkotbah dan mengajar (1Tim 5:17). Dengan kata lain, kelompok penatua-penilik agaknya dalam proses untuk berkembang lebih lanjut menjadi penatua dan beberapa penatua dengan tambahan tanggung jawab kepemimpinan, yang mungkin sekali telah mendapat sebutan episkopos di Efesus (bdk. 1Tim 3:1-7). Di Antiokhia tiga pelayanan itu sudah menjadi mantap pada tahun 115. Pada tahun 150, tiga pelayanan itu sudah tersebar di sebagian besar Gereja dan dalam langkah menjadi universal. Sejak zaman Ignasius dari Antiokhia (± 115) peranan uskup sudah menjadi kepala Gereja setempat dan menjaga kesatuan (koinonia) antara Gereja itu dengan Gereja-Gereja lain dalam kesatuan dengan uskup-uskup mereka. Dengan demikian, ada dimensi simbolis penting pada jabatan uskup. Uskup-uskup melambangkan dan menjaga kesatuan antara Gereja-Gereja setempat mereka dan Gereja Apostolik maupun dengan kesatuan Gereja seluruh dunia. Ajaran Katolik menyatakan bahwa para uskup mengganti fungsi kepemimpinan yang pernah dijalankan oleh para rasul (LG 20). Mereka merupakan suatu dewan yang bersama kepalanya, uskup Roma, memiliki otoritas tertinggi dan penuh atas Gereja universal (LG 22). Bersatu dengan Paus, para Uskup ikut memiliki karisma Gereja akan ketidak-dapat-sesatan (LG 25). Imam Kata Yunani Presbyteros, yang secara etimologis merupakan asal kata Inggris ”priest”, aslinya berarti ”penatua”. Para penatua pertama kali ada di Gereja-Gereja Kristiani Yahudi, yang diambil dari sinagoga di mana tanggung jawab para penatua adalah menjadi penyuluh dan pembimbing jemaat. Kebanyakan penatua, atau ”imam” membantu uskup dengan mengepalai jemaat umat setempat, mewartakan sabda, merayakan sakramen-sakramen, dan menjalankan kepemimpinan dan reksa pastoral (LG 28). Karena mereka menjadi milik Gereja setempat atau diosis, mereka dikenal sebagai imam diosesan atau ”sekulir”. Para imam yang menjadi anggota ordo atau kongregasi religius kerap menjalankan imamat yang lebih kerigmatis atau profetis, dengan menggabungkan pelayanan liturgis dan sakramental dengan pelayanan sabda yang lebih luas yang meliputi pewartaan, pengajaran, dan keilmuan, bimbingan rohani, dan berbagai pelayanan keadilan sosial. Diakon Dalam Perjanjian Baru, diakonos agaknya banyak dipergunakan sebagai sebutan bagi mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kepemimpinan. Baru dalam masa Perjanjian Baru yang kemudian, diakonos mulai digunakan untuk jabatan khusus, jabatan diakon (1Tim 3:8-13). Pada masa pasca Perjanjian Baru, diakon berfungsi sebagai pembantu uskup, kerap mengurus urusan harta benda dan kekayaan Gereja, peran yang membuat beberapa diakon menjadi amat berkuasa. Mereka diserahi berbagai tugas amal dan liturgis, dan tugas yang paling penting adalah memberi derma kepada orang-orang miskin dalam jemaat dan membantu dalam upacara inisiasi Kristiani.8 Mereka kerap diserahi tugas mengajar orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima baptis. Diakon ditunjuk menduduki jabatan melalui tahbisan dengan penumpangan tangan atau kadang-kadang hanya diangkat begitu saja dan diberi peran dalam liturgi. Wanita berperan menjadi diakones, baik di Gereja Barat maupun di Gereja Timur. Fungsi mereka agaknya adalah mengurapi wanita-wanita di antara orang-orang yang dibaptis dan mengunjungi orang sakit. Beberapa diakones ditahbiskan, tetapi pelayanan mereka pada umumnya ada di bawah diakon dan tidak berlangsung lama. Menurut normanya, jangka waktunya adalah baptis orang dewasa. Pada abad ke-10 dan ke-11 diakones tidak ditemukan lagi, bahkan di Gereja-Gereja Timur.9 Di Gereja Barat, pelayanan diakon secara bertahap dijadikan tahap atau langkah sebelum tahbisan imamat. Diakonat tetap sebagai ungkapan dari 3 pelayanan tradisional Gereja tidak diadakan lagi sampai Konsili Vatikan II. Diakon diberi wewenang untuk mewartakan Injil dan mengepalai baptis, pernikahan, dan pemakaman (bdk. LG 29). Karena ditahbiskan, diakon permanen secara teknis masuk kedalam jajaran ”klerus” dan diwajibkan selibat, meski Gereja juga menahbiskan pria-pria yang sudah nikah menjadi diakon. Sementara peran uskup, imam dan diakon telah dibentuk dan dikondisikan oleh berbagai periode dalam sejarah Gereja, ada beberapa hal yang tetap. Mereka terutama adalah pelayan. Seperti semua pelayan, jabatan mereka ada demi pelayanan dan pembangunan Gereja. Imamat Meskipun Perjanjian Baru mengatakan seluruh jemaat sebagai ”imamat rajawi” (1Ptr 2:9), baru pada awal abad ke-3 istilah ”imam agung” dan ”imam” kultis mulai digunakan untuk pelayan Kristiani. Istilah pertama, untuk uskup dan istilah kedua, untuk para pembantu uskup, imam. Kata Inggris ”priest” mengandung arti pelayan kultis (hiereus) dan pemimpin jemaat (presbyteros). Kaum Reformasi Protestan pada abad ke-16, dengan mengikuti prinsip ketat ”hanya Kitab Suci” menyebut pelayan yang ditahbiskan sebagai ”minister” atau ”pastor”. Kaum Lutheran menyatakan bahwa Allah telah menetapkan ”jabatan pewarta” bagi Gereja. Akan tetapi, istilah imamat bagi uskup dan imam sebaiknya tidak ditolak karena merupakan suatu yang baru atau berlawanan dengan hakikat pelayanan yang ditahbiskan. Istilah itu muncul pada awalnya dalam tradisi Gereja pada waktu dimensi korban Ekaristi menjadi lebih jelas dipahami. Konsili Vatikan II kembali ke pemahaman kuno mengenai jabatan uskup, yang melihat uskup memiliki kepenuhan imamat. Konsili juga mengajarkan bahwa baik imamat pelayanan atau hierarkis dan imamat umum semua umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus (LG 10). Pelayanan Paus Rasa universalitas dan katolisitas Gereja, yang berpusat pada Uskup Roma, Paus, merupakan hal yang mendasar bagi pemahaman Katolik Roma tentang Gereja. Paus adalah lambang Katolisisme yang paling jelas. Ada dua dasar untuk jabatan Paus itu. Dua dasar yang terpisah tetapi berhubungan. Dasar pertama adalah tradisi kepemimpinan Petrus di antara para murid pertama Yesus. Dasar kedua adalah supremasi atau kedudukan tertinggi Gereja Roma. Simon, anak Yonas, yang oleh Yesus kemudian diubah menjadi Kefas, atau Petrus (”batu karang”), adalah murid Yesus yang terkemuka. Namanya selalu tertulis pertama dalam daftar para Rasul dan disebut lebih banyak daripada rasul-rasul lain mana pun. Petrus menonjol dalam Gereja awal sebagian karena kedudukannya yang istimewa di antara Kedua Belas Rasul dan sebagian karena ia adalah orang pertama yang mengalami penampakan Diri Yesus sesudah bangkit (meski tradisi lain, yang sama-sama kuno, melaporkan bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lain). Gereja Roma mempunyai kedudukan yang menonjol sejak awal. Selain merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi, kota itu memiliki warisan apostolis yang khas, yaitu bahwa baik Petrus maupun Paulus telah bekerja dan meninggal di kota itu. Sudah pada zaman Perjanjian Baru, Gereja Roma sudah mengajar jemaat-jemaat Kristiani lain. Surat I Petrus mungkin sekali ditulis dari Roma atas nama Petrus untuk sekelompok orang Kristiani di Asia Kecil pada pertengahan tahun 80-an. Surat yang dikenal sebagai I Clement ditulis dari Roma sekitar tahun 96 untuk menasihati orang-orang Kristiani di Korintus. Seperti dicatat oleh Raymond Brown, amat mungkinlah bahwa alasan Gereja Romawi tidak ragu-ragu untuk mengajar Gereja-Gereja lain adalah karena merasa telah mewarisi tanggung jawab pastoral Petrus dan Paulus terhadap Gereja-Gereja yang mereka dirikan.10 Beberapa tahun sesudah Clement, Ignasius dari Antiokhia menyebut Roma sebagai ”keunggulan cinta” karena telah mengajar Gereja-Gereja lain. Ireneus mengatakan ”asal-usul Roma yang lebih kuat” berdasarkan dua rasul yang mendirikannya. Ciprianus (meninggal tahun 258) menyebut Roma sebagai ”Gereja utama”. Karena Gereja Roma terus berlanjut memberi saran-saran kepada Gereja-Gereja lain dan Gereja-Gereja lain naik banding ke Roma sebagai semacam pengadilan banding, otoritasnya tumbuh menjadi besar. Pada abad ke-4, sejumlah uskup di Roma mengacu pada otoritas yang diberikan kepada Petrus dalam Matius 16:18 sebagai sumber otoritas mereka sendiri. Paus Leo Agung (440-461) menyebut diri sebagai”wakil Petrus”, sebuah gelar yang digunakan sekurang-kurangnya pada abad ke-11 dan ke-12. Gregorius Agung (590-604) menolak gelar”Paus Universal” karena gelar itu mengambil kehormatan rekan-rekan uskupnya, dengan memilih gelar servus servorum Dei, ”hamba para hamba Allah”, sebagai gantinya. Gelar ”Wakil Kristus” dipopulerkan oleh Paus Inosensius III (meninggal tahun 1216). Satu gelar Paus yang lain Pontifex Maximus atau ”Imam Tertinggi” mempunyai sejarah yang menarik. Pada awalnya gelar itu adalah gelar kafir yang digunakan untuk Ketua Dewan Imam Romawi Kuno. Gelar itu baru dipakai untuk menyebut Paus sesudah abad ke-15. Dewasa ini penggunaan sebutan ”Imam Tertinggi” bernada amat imamat dan hierarkis. Akan tetapi, etimologi populer yang telah menerjemahkan gelar itu sebagai ”pembangun jembatan yang utama”, pastilah merupakan gelar yang tepat untuk Paus. Konsili Vatikan I (1869-1870) secara meriah menyatakan bahwa Paus Roma mempunyai kekuasaan penuh dan tertinggi atas Gereja universal, tidak hanya dalam hal iman dan moral, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan pemerintahan Gereja di seluruh dunia. Sehubungan dengan otoritas mengajar, Konsili berkata bahwa bila Paus berbicara ex cathedra, ia ”memiliki infalibilitas (ketidak-dapat-sesatan) yang dikehendaki oleh Penebus Ilahi untuk dimiliki Gereja guna meneruskan ajaran yang berkaitan dengan iman dan moral”(DS 3074). Perlu dicatat bahwa Konsili memandang karisma infalibilitas terutama menjadi milik Gereja, bukan kepada Paus saja. Pertanyaan pokok adalah bagaimana infalibilitas Gereja diungkapkan? Konsili Vatikan II, dengan teologi kolegialitas tentang jabatan uskup menempatkan ajaran Vatikan I tentang kedudukan utama dan infalibilitas Paus dalam konteks yang baru. Sebagai kepala Dewan para uskup, Uskup Roma mengepalai kesatuan Gereja dan menjaga kesatuannya. Uskup-uskup dalam kesatuan dengan Paus mempunyai otoritas atas Gereja universal dan ikut memiliki infalibilitas (LG 25). Bersamaan dengan itu, otoritas Paus tidak dapat hanya bersifat simbolis, karena sebagai gembala universal dan kepala Dewan para uskup, Paus harus mempunyai kekuasaan untuk bertindak. Magisterium Tugas mengajar Paus dan uskup-uskup disebut ”magisterium”. Kata itu berasal dari kata Latin magister, yang berarti ”tuan” atau ”guru”. Para Bapa Konsili dengan hati-hati membedakan antara pelaksanaan magisterium yang tak dapat sesat dan apa yang biasanya disebut ajaran magisterium biasa (atau tidak-tidak dapat sesat). Kedua hal itu penuh wibawa. Tetapi macam kesetujuan terhadapnya berbeda. Umat beriman menyampaikan ”ketaatan iman” terhadap ajaran-ajaran yang dinyatakan tidak dapat sesat (LG 25). Ajaran-ajaran yang tidak dapat sesat, yang dinyatakan dengan otoritas Gereja yang paling tinggi, disebut ”dogma”. Ajaran-ajaran itu meliputi butir-butir syahadat, ajaran resmi Konsili-Konsili Ekumenis dan ajaran-ajaran ex cathedra dari magisterium Paus. Dogma merupakan peraturan-peraturan iman Gereja. Menolak dogma akan membuat orang berada di luar jemaat yang percaya. Dogma tak dapat diubah dalam arti bahwa keputusan yang terkandung dalam dogma tidak dapat diubah, meski seperti setiap ungkapan iman yang muncul secara historis, dogma itu dikondisikan secara historis dan dengan demikian dapat ditafsirkan kembali. Doktrin-doktrin punya wibawa tetapi doktrin-doktrin itu merupakan ajaran-ajaran Gereja yang dinyatakan tidak-tidak dapat sesat. Apakah tentang Kitab Suci, Konsili, atau Magisterium Paus yang biasa, ajaran-ajaran itu menuntut ”ketaatan religius” obsequium religiosum kehendak dan budi (LG 25). Diandaikan bahwa orang beriman selalu menyetujui ajaran-ajaran karena berasal dari kewibawaan Gereja. Akan tetapi, karena ajaran-ajaran tidak dinyatakan tidak dapat sesat, kemungkinan salah dapat terjadi, tidak seperti dogma, doktrin-doktrin itu tidak hanya dapat ditafsirkan kembali tetapi kadang-kadang dapat diubah sebagaimana tampak pada studi sejarah tradisi doktrin Gereja. Teologi melayani Gereja dengan meneliti tradisi dan mencari cara-cara yang lebih memadai untuk mengungkapkan iman Kristiani. Beberapa orang Katolik salah mengerti tentang magisterium. Mereka lebih memahami magisterium sebagai otoritas mengajar yang ada di atas Gereja dan disertai dengan bantuan khusus Roh Kudus untuk merumuskan iman dan ajaran daripada jabatan untuk mengungkapkan iman yang dipercayakan kepada seluruh Gereja. Dari sudut pandangan ini, magisterium disebut sebagai ecclesia docens, ”Gereja yang mengajar,” yang ditempatkan dan terpisah dari ecclesia discens, ”Gereja yang belajar”. Demikian juga, sementara orang Katolik masih saja membayangkan Paus sebagai sumber, sesudah Allah, dan dari sumber itu mengalir segala kuasa dan otoritas serta sebagai pengambil keputusan utama untuk masalah-masalah sezaman. Orang-orang seperti itu masih memahami Gereja secara monarkis. Masalah-masalah yang diperdebatkan dapat dijawab hanya dengan mengutip kata-kata Paus. Dengan demikian, masalah-masalah yang rumit dipecahkan hanya atas dasar otoritas saja, dan seluruh proses pengembangan ajaran yang banyak seginya diabaikan. Pendekatan ini merupakan sikap fundamentalisme bentuk Katolik, meski fundamentalisme kepausan dan magisterial dan bukan fundamentalisme biblis. Dalam tatanan yang nyata, magisterium berfungsi amat berbeda. Gereja pada dasarnya bukanlah lembaga yang menjalankan otoritas mengajarnya dari atas ke bawah. Roh Kudus aktif dalam seluruh Gereja, bukan hanya dalam hierarki. Ajaran tentang sensus fidelium (”keyakinan umat beriman”) menunjukkan bahwa doktrin-doktrin dan dogma-dogma Gereja muncul dari iman seluruh Gereja. Rumusan ajaran tidak didasarkan ajaran mayoritas pendapat, tetapi keluar dari kesepakatan, yang di bawah bimbingan Roh Kudus mencakup para imam dan awam (LG 12). Praktek Gereja dalam ”menerima ajaran” merupakan bukti lebih lanjut tentang mentalitas atau saling ketergantungan antara otoritas hierarkis dan keseluruhan umat dalam merumuskan ajaran yang kadang-kadang menghasilkan modifikasi dan peninjauan kembali ajaran-ajaran magisterium Paus yang biasa. Misalnya ajaran Pius XII yang bulat-bulat menyamakan Gereja Katolik dengan tubuh mistik Kristus dalam ensikliknya Mystici Corporis diubah oleh Konsili Vatikan II. Konsili mengatakan bahwa Gereja Kristus ”berada dalam” bukan ”sama dengan” Gereja Roma Katolik, sebagaimana dinyatakan dalam draft pertama (LG 8). 11 Perkembangan dan perumusan ajaran selalu merupakan proses yang rumit yang melibatkan kerja para teolog, perasaan umat beriman, proses penerimaan, dan ajaran otoritatif uskup-uskup Gereja. Percaya bahwa kebenaran Kristiani hanya ditegaskan oleh ucapan magisterial tanpa memperhitungkan proses yang rumit ini, merupakan semacam fundamentalisme kepausan yang disebut di atas. Bahkan dalam menjalankan magisterium yang luar biasa atau tak dapat sesat, Paus merumuskan apa yang dipercayai oleh Gereja. Ini jelas dalam dua kasus perumusan tak dapat sesat dari magisterium Paus yang luar biasa, Maria dikandung tanpa dosa asal (1854) dan Maria diangkat ke surga (1950). Kedua dogma itu dibuat hanya sesudah proses berkonsultasi dengan Gereja melalui pengumpulan pendapat para uskup. Dengan demikian, Gereja berfungsi sebagai kesatuan semua anggota umat beriman dan hierarki, saling tergantung secara timbal balik. Tak ada fungsi yang terlepas dari fungsi lain. Pemahaman yang jelas mengenai saling ketergantungan ini akan sangat banyak membantu untuk meyakinkan umat Kristiani dari Gereja-Gereja lain yang masih curiga terhadap magisterium Paus. 4. Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik Sejak zaman Konsili Konstantinopel pada tahun 381, orangorang Kristiani telah menyatakan bahwa mereka percaya akan ”Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik”. Empat sifat itu menjadi ciri Gereja Kristus. Dalam Gereja kuno, sifat-sifat itu berguna untuk membedakan Gereja yang benar dari kumpulan-kumpulan atau Gereja-Gereja yang palsu. Sejak Reformasi, ciri-ciri itu kerap dijadikan bahan perdebatan, untuk membenarkan pernyataan satu Gereja melawan Gereja yang lain. Di situlah masalahnya. Dewasa ini bagi banyak orang, sifat-sifat itu lebih tampak sebagai uraian tentang apa hakikat Gereja itu sesungguhnya daripada apa Gereja itu sebagaimana adanya sekarang ini. Jelas bahwa Gereja dewasa ini bukan satu tetapi banyak. Bagi cukup banyak orang, kekudusan Gereja tidak segera kelihatan. Agaknya lebih jelas bahwa Gereja itu adalah Gereja yang berdosa. Jika beberapa Gereja masih menyebut diri sebagai Katolik, Gereja-Gereja itu masih harus menetapkan diri lebih lanjut sebagai Anglo-Katolik, Katolik Lama atau Katolik Roma. Kebanyakan Gereja menyatakan diri sebagai apostolik dalam arti menjadi ganti Gereja para Rasul. Bagaimana harus memahami sifat-sifat itu? Akan salahlah menyempitkan ciri-ciri Gereja melulu pada sifat-sifat eskatologis, sifat-sifat yang diterima Gereja dari Tuhan hanya dalam pemenuhan waktu. Sifat-sifat itu merupakan atribut-atribut Gereja Kristus yang ada dalam waktu dan ruang. Orang terjebak dalam eskatologi kalau berkata bahwa tidak ada cara untuk mengenal Gereja yang tampak dan historis. Keterjebakan itu merupakan semacam relativisme eklesial – mirip dengan kecenderungan modern untuk mengabaikan masalah-masalah pernyataan historis, kesetiaan terhadap tradisi para Rasul, perhatian untuk pewartaan yang benar dan pelaksanaan Sakramen yang sesuai dan menekankan sifat jemaat yang menyenangkan, musik yang bagus, dan kecocokan pribadi. Ini merupakan satu ekstrem, yang dengan membuat satu Gereja adalah sebaik Gereja yang lain, mengambil setiap dorongan untuk berusaha menjadi Gereja Kristus secara lebih penuh dari semua Gereja. Pada ekstrem yang lain, pendekatan ”satu Gereja yang benar” yang menyatakan identitas eksklusif antara jemaat khusus dan Gereja Kristus. Dewasa ini pendekatan itu merupakan ciri yang lebih umum pada kaum sektarian. Pendekatan itu mengabaikan kompleksitas Gereja. Gereja adalah kelihatan maupun tak kelihatan, satu dan banyak, tubuh mistik dan jemaat yang kelihatan, yang dipersatukan oleh Roh dan diungkapkan dalam struktur sakramen, pemerintahan gerejawi, dan kesatuan (bdk. LG 8). Gereja yang Satu Sejak awal Gereja adalah satu, karena Gereja Perjanjian Baru merupakan kesatuan Gereja-Gereja. Kata koinonia yang biasanya diterjemahkan sebagai ”persatuan” atau ”persekutuan” untuk pertama kali digunakan oleh St. Paulus. Kata itu berarti hubungan kesatuan antara orang-orang beriman berdasarkan pemilikan bersama atas hal-hal tertentu (koinon). Dasar kesatuan itu pertama-tama bersifat spiritual; kesatuan itu muncul dari keikutsertaan dalam ambil bagian didalam hidup bersama dalam Roh yang diberikan dalam baptis (1Kor 12:13) dan terutama karena keikutsertaan ambil bagian dalam Ekaristi. Para anggota Gereja merupakan ”satu tubuh” karena mereka berpartisipasi dan bersatu (koinonia) dalam Tubuh dan Darah Kristus (1Kor 10:16-17). Koinonia diungkapkan dalam tanda-tanda yang kelihatan. St. Paulus memberi tahu kita bahwa sesudah pergi ke Yerusalem untuk menyampaikan kepada para pimpinan Gereja, Injil yang diwartakannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dia menerima jabat tangan persekutuan (koinonia) dari Yakobus, Kefas, dan Yohanes (bdk. Gal 2:9). Usaha St. Paulus untuk memerintahkan Gereja-Gerejanya menyumbang secara finansial untuk membantu orang miskin di Gereja Induk Yerusalem (Rm 15:25-26; 1Kor 16:1-4; 2Kor 8:1-5) merupakan tanda lain dari keinginannya untuk menjaga koinonia. Selama milenium pertama ciri autentik dari GerejaGereja yang bersangkutan ditunjukkan melalui tanda-tanda koinonia yang kelihatan, yang menghubungkan mereka satu sama lain menjadi ecclesia catholica, perjamuan Ekaristi, suratsurat kontak, kesatuan antar uskup-uskup sendiri, dan paling sedikit sejak abad ke-3 dengan Roma. Akan tetapi, Gereja tidak mampu mempertahankan kesatuan dan persatuan dengan semua yang mengakui iman Kristiani. Beberapa Gereja kuno kehilangan kesatuan dengan Gereja universal karena ketidakmampuan mereka untuk menerima ajaran Kristologi Gereja yang berkembang: Gereja Nestorian atau Timur sesudah Konsili Efesus (431) Koptik di Mesir dan Armenia sesudah Kalsedon (451). Perpecahan besar pertama terjadi pada tahun 1054 karena ketegangan dan salah paham antara Roma dan Konstantinopel. Sesudah utusan Paus Leo IX mengekskomunikasikan patriach Michael Cerularius, dan kemudian diekskomunikasi oleh sinode lokal, kesatuan antara Gereja Timur dan Barat pecah. Gereja-Gereja Timur menjadi dikenal sebagai ”Ortodoks”. Kata ini digunakan terutama di Timur untuk menggambarkan Gereja-Gereja yang tetap setia pada ajaran-ajaran Konsili Efesus dan Kalsedon. Gereja-Gereja Barat yang hidup dalam persatuan dan yang semakin di bawah uskup Roma selanjutnya dikenal sebagai Gereja Katolik, meski kesatuannya rusak selama Reformasi pada abad ke-16 dan ke-17. Di Eropa Barat muncul tiga tradisi Gereja, Gereja Lutheran di Jerman dan Skandinavia, Gereja Kalvinis atau Reformasi di Swiss dan Prancis, dan Gereja Anglikan di Inggris. Tambahan pula yang disebut Reformasi sayap kiri atau radikal menciptakan sejumlah jemaat yang secara kolektif disebut Anabaptis: Persaudaraan Swiss, Kaum Huterit di Moravia, dan Mennonit Belanda. Jemaat-jemaat itu tidak hanya berusaha mengubah Gereja, tetapi memulihkan hidup Kristiani menurut model Gereja Perjanjian Baru. Bagian tragedi Reformasi adalah ketidakmampuannya mempertahankan kesatuan di dalam dirinya sendiri. Gereja-Gereja baru terus saja bermunculan. Karena pemikiran Kalvin tersebar, Gereja-Gereja dalam tradisi Reformasi berdiri di Eropa Timur, Belanda, Skotlandia, Inggris, Irlandia, dan akhirnya Amerika Serikat. Pada abad ke-17 dari gerakan Puritan di Inggris muncul Gereja Baptis. Kaum Metodis yang berawal sebagai gerakan pembaruan di Gereja Inggris abad 18 dipimpin oleh John dan Charles Wesley. Dewasa ini ada 1,8 milyar orang Kristiani di dunia dan itu merupakan 33,5% dari penduduk dunia. Orang-orang Kristiani itu terbagi-bagi dalam berbagai Gereja. Jumlah orang Katolik lebih dari satu milyar. Orang Kristiani Ortodoks 173 juta, orang Protestan 382 juta, dan orang Anglikan 75 juta.12 Ada lebih dari 300 Gereja dalam keanggotaan Dewan Gereja Dunia. Dewan ini merupakan persekutuan Gereja-Gereja Protestan dan Ortodoks yang didirikan pada tahun 1948. Bagaimana kita dapat dengan paling baik memahami hubungan antara satu Gereja dan banyak Gereja dan bersamaan dengan itu, mengerti pernyataan Konsili Vatikan II bahwa agar dapat ”masuk sepenuhnya” ke dalam Gereja, orang harus ada dalam kesatuan penuh yang kelihatan dengan Gereja Katolik. Gereja tidak dapat dipersempit menjadi sekadar umat setempat atau kumpulan semua Gereja khusus, seperti cenderung dilakukan oleh banyak orang Protestan. Konsep tentang Gereja yang atomistik itu berlawanan dengan cara Gereja milenium pertama mempertahankan kesatuan dan keanekaragaman bersama-sama secara seimbang. Jika Gereja merupakan kesatuan Gereja-Gereja, maka untuk menjadi Gereja yang penuh, setiap Gereja lokal atau khusus harus menjadi bagian kesatuan itu. Bersamaan dengan itu, Gereja tidak dapat dimengerti sebagai satu lembaga yang monolitik, dan tersebar di seluruh dunia. Terlalu banyak orang Katolik berpikir seperti itu. Menurut Vatikan II, Gereja-Gereja khusus ”dibentuk menurut citra Gereja semesta”, sementara ”Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam GerejaGereja khusus dan terhimpun daripadanya” (LG 23). Sebagai kesatuan Gereja-Gereja seluruh dunia, Gereja Katolik adalah sekaligus satu dan banyak. Gereja lokal atau khusus dihubungkan satu sama lain dengan Uskup Roma melalui ikatan-ikatan kesatuan antara uskup-uskup mereka. Termasuk di dalam kesatuan ini adalah Gereja-Gereja Katolik Timur, yang kadang-kadang disebut secara salah sebagai Gereja-Gereja yang ”Terpisah”. Gereja-Gereja itu adalah jemaat-jemaat yang dulu disebut Ortodoks tetapi yang pada berbagai saat dalam sejarah telah membangun kembali kesatuan dengan Uskup Roma. Gereja-Gereja itu mempertahankan tradisi-tradisi teologis, liturgis dan kanonis, mereka termasuk klerus yang menikah. Dekrit Konsili tentang Gereja-Gereja Timur Katolik mengakui ritus Latin (OE 3). Kesatuan yang menghubungkan Gereja-Gereja bukan hanya kesatuan teologis melainkan juga institusional. Ini berarti bahwa kesatuan Gereja-Gereja dapat bertindak sebagai satu Gereja, seperti terjadi pada Konsili Vatikan II. Menurut Konsili, kesatuan atau sifat satu yang diberikan oleh Kristus kepada Gereja-Nya sudah ada dalam Gereja Katolik sebagai sesuatu yang tidak dapat hilang. Namun, kesatuan itu belum sempurna, karena Konsili mengungkapkan harapan agar ”kesatuan itu dari hari ke hari bertambah erat sampai kepenuhan zaman” (UR 4). Gereja Katolik selalu mengakui Gereja-Gereja Ortodoks sebagai Gereja, dan Konsili berbicara tentang ”Gereja-Gereja dan Jemaat-jemaat gerejawi” yang terpisah (UR 19) untuk menyebut perpecahan-perpecahan di Barat. Ungkapan ”Gereja dan Jemaat gerejawi” digunakan untuk membedakan antara Gereja-Gereja yang memiliki tata tertib yang sah dan GerejaGereja yang tidak mempunyainya, dan dengan demikian ”sudah kehilangan hakikat misteri Ekaristi yang autentik dan sepenuhnya” (UR 22). Gereja-Gereja yang tidak memiliki tata tertib itu tidak diakui sebagai Gereja dalam arti teologis yang penuh. Bersamaan dengan itu, disebut jemaat gerejawi karena Gereja Kristus dengan sesuatu cara hadir dalam jemaat-jemaat itu, meski tidak sempurna. Gereja-Gereja itu analog dengan Gereja-Gereja khusus dari Gereja Katolik.13 Gereja yang Kudus Satu segi yang paling menarik dari pengalaman akan Allah yang muncul dari Kitab Suci Yahudi adalah gagasan bahwa Allah adalah ”kudus” dan umat Allah adalah juga kudus. ”Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, kudus.” Gagasan tentang ”kekudusan” (yang akar kata Hibraninya qds, berarti ”terpisah”) menggambarkan sifat hakiki Allah – lain, berbeda, terpisah dari segala hal yang diciptakan, yang terbatas, dan tidak sempurna. Kekudusan Allah meliputi baik kekuasaan Ilahi maupun kebenaran moral. Kekudusan Allah ditunjukkan dalam pembebasan oleh Allah atas bangsa terpilih, dalam keadilan, dan rasa jijik akan dosa. Dalam arti kedua, orang, tempat, dan benda disebut kudus karena hubungannya dengan Allah. Tanah di sekitar semak yang menyala adalah kudus karena Allah ada di sana (Kel 3:4-5). Israel adalah kudus karena hubungan perjanjian – yang dirumuskan dalam Sepuluh Perintah – antara umat dan Yahwe (Kel 19:5-6). Benda-benda yang digunakan dalam ibadat atau liturgi dipandang kudus, tenda pertemuan, tempat ibadat, altar, pakaian ibadat, imam, hari Sabat, korban. Segala itu kudus bukan dalam arti gaib tetapi karena kedekatan dan hubungannya dengan yang Ilahi. Gereja disebut ”kudus” dalam arti derivatif (dikembangkan lebih lanjut). Gereja adalah kudus karena menjadi tempat kehadiran Allah yang tetap. Dalam Kristus, Allah telah menguduskan para murid; mereka telah menjadi satu sebagai ”Tubuh Kristus”(1Kor 12:27); jemaat adalah ”bangunan Allah”( 1Kor 3:9), dan melalui Kristus jemaat menjadi ”bait Allah yang kudus di dalam Tuhan” dan ”tempat kediaman Allah di dalam Roh” (Ef 2:21-22). Jemaat adalah ”imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri” (1Ptr 2:9). Dokumendokumen Perjanjian Baru yang paling awal menyebut para anggota Gereja sebagai ”orangorang kudus” (hagioi) atau ”orang-orang suci”(Rm 1:7; 12:13; 15:25; 1Kor 14:33; 16:1; Fil 4:22; Kis 9:13,32), yang ”dikuduskan” dalam Kristus Yesus (1Kor 1:2) atau oleh Roh Kudus (Rm 15:16). Konsili Vatikan II menggemakan teologi ini, dengan mendasarinya dalam baptis: ”mereka yang dibaptis karena kelahiran kembali dan pengurapan Roh Kudus disucikan menjadi kediaman rohani dan imamat suci”(LG 10). Akan tetapi, jika Allah telah membuat Gereja kudus sebagai umat yang dikuduskan ”Umat Kudus Allah” (LG 12), maka jelaslah bahwa sebagai perorangan mereka harus menjadi kudus (1Kor 1:27; Rm 1:7). Mereka harus menanggapi dalam ketaatan (1Ptr 1:14-16). Gereja juga kudus karena Allah telah memberi kepadanya karunia-karunia kudus: Sabda Allah (Yoh 1:21; 1Ptr 1:23), pelayanan Gereja (2Kor 5:18; Ef 4:11-12), sakramen-sakramen (Yoh 3:5; 20:3; 1Kor 6:11; 11:27; Yoh 5:14-15), untuk melestarikan dan menguduskan umat. Anugerah-anugerah atau struktur Gereja itu kudus pada dirinya sendiri karena merupakan karunia-karunia Ilahi. Anugerah-anugerah itu membuat Gereja mampu menjadi tanda kekudusan yang efektif dan sakramen di dunia selain ketidaklayakan umat atau pelayan Gereja. Dalam liturgi Gereja-Gereja Timur, dua dimensi kekudusan Gereja bergabung pada waktu diakon mengundang umat untuk maju dan menerima Ekaristi dengan kata-kata ”hal-hal kudus bagi orang kudus”. Dapatkah Gereja kudus sekaligus berdosa? Tradisi resmi enggan untuk berbicara tentang Gereja sebagai berdosa, tetapi Konsili mengakui bahwa kesucian Gereja tidaklah sempurna: ”Gereja harus selalu dibersihkan” (LG 8). Wajah Gereja ”kurang terang bersinar” karena dosadosa para anggotanya (UR 4); dan sebagai Gereja yang berziarah perlu ”terus-menerus memperbaiki diri”(UR 6), menggemakan penekanan Protestan pada Gereja yang selalu memerlukan perombakan (ecclesia semper reformanda). Gereja-Gereja lain kurang yakin untuk mengakui bahwa Gereja Kudus, karena terdiri dari orang-orang kudus dan pendosa, juga berdosa. Konsili mengingatkan tanggung jawab Gereja karena ikut berdosa melawan kesatuan pada abad ke-16 (UR 7) dan Sullivan dalam bukunya The Church We Believe In menambahkan contoh dosa-dosa historis yang secara kolektif, Gereja ikut bertanggung jawab: ”... perlakuan buruk terhadap orang-orang Yahudi, dan menerima perbudakan.”14 Dengan demikian, seperti Gereja dapat menjadi lebih satu secara penuh, demikian Gereja juga dapat menjadi lebih kudus secara lebih sempurna. Gereja yang Katolik Kata sifat Yunani katholikos, yang berarti ”umum”, ”menyeluruh” atau ”universal” pertama kali digunakan Gereja dalam arti Gereja keseluruhan atau universal oleh Ignasius dari Antiokhia sekitar tahun 115. Ignasius menulis: ”Di mana uskup berada, di sana umat harus berada, seperti, di mana Yesus Kristus berada, di sana Gereja Katolik berada” (Smyrn.8.2). Ignasius menyatakan bahwa seperti Kristus menjadi kepala dan pusat seluruh Gereja, demikian pula uskup adalah kepala dan pusat jemaat setempat. Tetapi sekurang-kurangnya pada abad ke-3 dan ke-4 kata ”katolik” digunakan secara polemis untuk membedakan Gereja yang besar atau benar dari kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan heretik yang terpisah daripadanya. Ignasius (meninggal tahun 430), pada waktu mendaftar ciri-ciri Gereja yang benar – kesepakatan universal, otoritas, penggantian dalam imamat dari takhta St. Petrus – pada akhirnya menyebut ”nama ’katolik’ sendiri, yang tidak tanpa alasan di tengah sedemikian banyak bidaah, hanya satu Gereja telah bertahan sehingga semua heretik mau disebut ’katolik’, tidak seorang pun dari mereka akan berani menjawab pertanyaan orang asing tentang di mana Gereja Katolik bertemu dengan menunjukkan basilika atau rumahnya sendiri”.15 Agustinus juga ikut berjasa dalam memberi arti ketiga pada kata ”katolik”: dalam perdebatan dengan kaum Donatis ecclesia catholica dimengerti secara geografis untuk menyebut Gereja tersebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, kata ”katolik” berarti: Gereja dalam kepenuhan atau keseluruhannya; telah digunakan secara polemik untuk Gereja yang benar; dan mempunyai arti geografis atau universal bagi Gereja yang hadir di mana-mana. Cyrilus dari Yerusalem (meninggal tahun 387) menggunakan kata ”katolik” dalam beberapa arti, pada waktu ia menggambarkan Gereja sebagai katolik karena terbentang sampai ke ujung dunia, mengajarkan segala ajaran yang diperlukan untuk keselamatan, mengajar segala bangsa, menyembuhkan segala macam dosa, dan memiliki segala keutamaan (Catechesis 18). Kekatolikan Gereja mencakup sifat menyeluruh terhadap keanggotaan Gereja. Sebagai tanda perdamaian dalam Kristus dan kesatuan dalam Roh, Gereja harus merangkum segala bangsa, mendamaikan ras-ras, kelas, dan budaya yang berbeda-beda, sebagaimana disarankan saat kelahirannya pada pesta Pentakosta (Kis 2:5-11). Perutusan Gereja untuk memberi wujud pada penebusan Kristus menuntut kekatolikan itu; kekatolikan merupakan tanda kesatuan seluruh umat manusia (Bdk. LG 1). Sebuah Gereja yang tidak menerima orang-orang lain karena ras, etnik, atau status sosial tidak dapat bersifat katolik. Kesatuan dan kekatolikan ecclesia catholica berkurang karena perpecahan antara Gereja Timur dan Barat pada tahun 1054, maupun oleh perpecahan-perpecahan baru yang diakibatkan oleh Reformasi. Dengan Kristianitas yang terpecah-pecah, katolisitas tak hanya menjadi milik Gereja Katolik, yang sejak abad ke-16 disebut sebagai ”Gereja Katolik Roma”, meski dalam dokumen-dokumen resmi Gereja terus-menerus menyebut dirinya hanya sebagai ”Gereja Katolik”. Dalam keanggotaan keseluruhannya, Gereja Katolik sedikit lebih dari separo jumlah seluruh orang Kristiani. Sebuah Gereja setempat adalah Katolik jika Gereja itu ada dalam kesatuan dengan Gereja-Gereja yang membentuk Gereja universal. Vatikan II mengajarkan bahwa ada kepenuhan katolisitas yang menjadi milik Gereja Katolik, meski Konsili juga mengakui bahwa karena perpecahan-perpecahan historis, Gereja ”menjadi lebih sukar untuk mengungkapkan dalam kenyataan hidupnya kepenuhan sifat katoliknya dalam segala seginya (UR 4). Tentu saja ada unsur-unsur kekatolikan dalam tradisi-tradisi lain. Tradisi-tradisi teologis, liturgis, dan spiritual yang kaya dari Gereja-Gereja Timur yang terpisah merupakan bagian kekatolikan Gereja yang tak terpecah-pecah. Sejumlah tradisi menunjukkan kekatolikan melalui anggota-anggota mereka dalam kelompok-kelompok konfesional dunia seperti Persatuan Anglikan, Federasi Dunia Lutheran, dan Perserikatan Dunia Gereja-Gereja Reformasi, meski masing-masing anggota Gereja secara yuridis mandiri. Dewan Gereja Dunia merupakan keinginan untuk mewujudkan katolisitas dari pihak Gereja-Gereja, meski Dewan itu sendiri bukanlah Gereja tetapi dewan dari Gereja-Gereja yang mandiri yang tetap bebas untuk memisahkan diri dalam setiap pendirian atau pernyataan dewan. Jika Gereja Katolik merasa berhak menyatakan kepenuhan katolisitas, mungkin Gereja Katolik mempunyai tanggung jawab khusus dalam menemukan jalan untuk memasukkan Gereja-Gereja lain dalam kepenuhan itu. Gereja yang Apostolik Dalam uraian singkat Lukas tentang Gereja Kristiani awal, ia mengatakan bahwa semua ”bertekun dalam pengajaran Rasul-rasul” (Kis 2:42). Dewasa ini semua orang Kristiani sepakat mengenai peranan para Rasul yang khas dan tak tergantikan dalam pendirian Gereja. Semua sepakat bahwa Gereja dewasa ini harus apostolik dalam arti mengganti Gereja para Rasul. Tetapi sejak Reformasi pada abad ke-16, penggantian apostolik dimengerti secara lain. Gereja-Gereja Anglikan, Katolik dan Ortodoks secara tradisional telah menekankan penggantian melalui jabatan uskup historis. Gereja Katolik berpendapat bahwa ”atas penetapan Ilahi, para uskup menggantikan para Rasul sebagai gembala Gereja” (LG 20). Gereja-Gereja Protestan memisahkan diri dari Gereja yang diatur secara episkopal pada abad ke-16. Dalam hal kaum Lutheran, uskup-uskup tidak bersedia menahbiskan pastor-pastor mereka. Yohanes Calvin berpendapat bahwa apostolisitas harus ditemukan dalam kesesuaian dengan ajaran para Rasul (Institute 4.2.6). Ini menjadi pendirian tradisional Gereja-Gereja Protestan. Penggantian apostolik dimengerti dalam kerangka penggantian dalam iman para Rasul. Prinsip penggantian para Rasul ditetapkan sekurang-kurangnya pada tahun 96 oleh penulis surat Clement. Dalam menasihati Gereja di Korintus karena memecat episkopoi mereka dari jabatan mereka, Clement menyatakan bahwa para Rasul sendiri, untuk mencegah kasak-kusuk minat atas jabatan uskup, telah ”menunjuk orang-orang pentobatan pertama ... menjadi uskup dan diakon dan orang-orang beriman masa yang akan datang” (42.4) asalkan bila orang-orang ini meninggal ”orang-orang lain yang disetujui harus mengganti pelayanan mereka” (44.2). Kebanyakan sarjana dewasa ini menganggap prinsip Clement lebih bercorak teologis daripada historis, tetapi gagasan tentang penggantian pelayanan para Rasul sudah ada dalam Perjanjian Baru. Para pemimpin Gereja lokal kerap digambarkan sebagai mengganti tanggung jawab pastoral para Rasul, kedua-duanya dalam kerangka menjaga tradisi apostolik (Kis 20:2930; 1Tim 1:14; 2:2) dan dengan berbagai usaha menghubungkan pelayanan mereka dengan pelayanan para Rasul sendiri (1Ptr 5:1; Kis 14:23; 1Tim 3:22; Tit 1:5). Di satu sisi, terdapat cukup bukti yang menyarankan bahwa gambar para Rasul yang menunjuk pemimpin-pemimpin yang kemudian dikenal sebagai penatua-penilik (uskup-presbyter) mungkin mempunyai dasar historis. Di lain sisi, itu mungkin bukan satu-satunya praktek. Misalnya jemaat-jemaat yang disebut oleh Didache diperintahkan untuk ”menunjuk sendiri uskup-uskup dan diakon-diakon kalian yang layak bagi Tuhan” (15:1). Dalam Gereja pasca Perjanjian Baru, yang terganggu munculnya jemaat-jemaat heretik dan pernyataan kaum Gnostik tentang tradisi tak tertulis dan rahasia yang berasal dari Yesus, para penulis seperti Hegesippus (± 180), Ireneus (meninggal ± 100), dan Tertulianus (± 200) mengacu pada tradisi apostolik yang benar yang diwariskan melalui Gereja-Gereja dengan dasar apostolik, dengan menggunakan daftar para uskup dari Gereja-Gereja itu untuk menunjukkan kelanjutan yang kelihatan dengan Gereja Apostolik. Tertulianus menantang Marcion untuk membentuk satu Gereja Marcionit yang dapat menemukan keturunannya dari seorang Rasul (Marc 1.21.5). Dengan demikian, uskup-uskup diakui sebagai pengganti para Rasul dan penjaga tradisi apostolik sekurang-kurangnya sejak abad ke-2. Ada bukti liturgis untuk hakikat kolegial jabatan uskup dalam Tradisi Apostolik (Traditio Apostolica) dari Hyppolytus, yang berasal dari akhir abad ke-2 atau awal abad ke-3. Dalam upacara pemberkatan uskup, uskup baru menerima penumpangan tangan dari uskup-uskup lain yang hadir (2.3). Keikutsertaan mereka merupakan tanda bahwa uskup baru dan Gerejanya ada dalam kesatuan dengan Gereja-Gereja lain dan mengganti Gereja para Rasul. 5. Kesimpulan Gereja sebagai jemaat murid-murid Yesus merupakan kenyataan historis yang kelihatan. Katolisisme memahami bahwa jemaat itu diperantarai dan dipertahankan oleh lambang-lambang sakramental dan struktur-struktur kelembagaan, ungkapan-ungkapan tradisi yang hidup yang berawal dari zaman para Rasul. Ada jabatan pelayanan di dalam Gereja, yang berhubungan dengan pelayanan para Rasul, tetapi itu bukan merupakan satu-satunya sumber otoritas. Otoritas Gereja ditemukan dalam Kitab Suci, tradisi, kesaksian dan hidup para kudus, sensus fidelium (keyakinan umat beriman) maupun di dalam keputusan-keputusan magisterium. Orang-orang Kristiani Prostestan, yang hidup dalam tradisi yang menekankan kemerdekaan mutlak dan transendensi Allah, satu perantara Yesus Kristus, dan keunggulan Sabda, kerap curiga terhadap penekanan Katolik atas tradisi, lambang-lambang dan strukturstruktur. Bagi banyak orang Protestan, dengan mengikuti Calvin, Gereja yang benar adalah kumpulan orang yang terpilih yang tidak kelihatan. Yang penting adalah jemaat umat beriman yang berkumpul yang menanggapi sabda yang diwartakan, bukan denominasi atau institusi. Iman dan hidup lebih penting dari sumber-sumber kepercayaan historis. Bagi umat Protestan, Gereja Kristus ada dalam banyak Gereja. Orang-orang Katolik juga memahami Gereja Kristus sebagai ada dalam banyak Gereja yang berbeda-beda, tetapi mendekati permasalahan secara berbeda. Sejak awal, kata ”jemaat” berarti baik Gereja setempat maupun seluruh Gereja, yang disebut ”Katolik” sejak awal abad ke-2. Kepausan merupakan kepenuhan Gereja. Orang-orang Katolik melihat Gereja Kristus sebagai ada dalam Gereja Katolik dalam kepenuhan hakikinya karena struktur-struktur historis Gereja itu dan pernyataan khasnya atas kesatuan, kekudusan, katolisitas, dan apostolitas. Mereka tidak menyangkal bahwa Gereja Kristus dapat juga ada dengan berbagai cara dalam Gereja-Gereja lain dan jemaat-jemaat gerejawi. Gereja Katolik adalah Gereja dunia. Gereja itu ada di setiap negeri. Mayoritas orang Katolik bergeser dari Hemisfer Utara ke Hemisfer Selatan. Pada Sinode Istimewa Para Uskup yang berkumpul di Roma pada tahun 1985, 74% uskup datang dari benua bukan Eropa dan Amerika Utara. Diperkirakan bahwa pada tahun 2000, mungkin 70% umat Katolik akan ada di negerinegeri Dunia Ketiga.17 Vatikan II mengakui bahwa berkat baptis sudah ada kesatuan yang nyata tetapi belum sempurna antara orang-orang Kristiani lain dengan Gereja Katolik (UR 3; LG 25). Buku Petunjuk Ekumene (Ecumenical Directory) Katolik Roma, yang direvisi pada tahun 1993, berpikir lanjut. Direktori itu berbicara jauh lebih jelas tentang kesatuan yang nyata tetapi belum sempurna itu tidak hanya ada di antara orang-orang Kristiani tetapi juga di antara Gereja Katolik dan Gereja-Gereja lain dan jemaat-jemaat gerejawi (no. 28).18 Jika satu Gereja itu merupakan kesatuan Gereja-Gereja, tugas ekumenis adalah menemukan jalan untuk menciptakan kembali kesatuan penuh antara Gereja-Gereja yang berbeda dan jemaat-jemaat gerejawi. Dengan cara ini, kesatuan yang sudah ada dalam Gereja Katolik dapat merangkum semua Gereja dan dengan demikian menjadi kesatuan yang sempurna yang oleh Yesus didoakan (Yoh 17:22). Catatan: 1. 2. 3. Untuk melihat kembali debat dalam Konsili, lihat Xavier Rynne, Vatican Council II (New York: Farmar, Straus and Giroux, 1968). Daniel J. Harrington, God’s People in Christ, (Philadelphia: Fortress, 1980) 29. Lihat Thomas. O’Meara, Theology of Ministry, (New York: Paulist, 1983) 102-104. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Lihat Joseph A. Kamonchak, ”The Local Church and the Church Catholic”: The Contemporary Theological Problematic,” The Jurist 52 (1992) 416-447. Lihat John Francis Maxwell, Slavery and the Catholic Church, (London: Barry Rose, 1975) 115-120. St. Paulus menyebut Andronicus dan Yunia sebagai ”menonjol di antara rasul-rasul” (Rm 16:7). Yunia adalah nama wanita, meskipun kerap ditafsirkan sebagai nama pria. Lihat Kenan Osborne, Priesthood: A History of Ordained Ministry in the Roman Catholic Church, (New York: Paulist, 1988) 4085; Paul Bernier, Ministry in the Church: A Historical and Pastoral Approach, (Mystic, Conn.: Twenty Third, 1992) 15-49. Lihat James M. Barnett, The Diaconate: A Full and Equal Order, (New York: Seabury, 1981) 57-93. Lihat Aimé Georges Martimort, Deaconesses: An Historical Study, (San Francisco: Ignatius, 1986) 182-183. Raymond E. Brown dan John P. Meier, Antioch and Rome: New Testament Cradles of Catholic Christianity (New York: Paulist, 1983) 165-166. Lihat Francis A. Sullivan, The Church We Believe In: One Holy, Catholic and Apostolic, (New York: Paulist, 1988) 23-33. Berdasarkan Statistik pada tahun 1994, Britannica Book of the Year, 271. Sullivan, The Church We Believe In, 54. Sullivan, The Church We Believe In, 82-83. Contra ep. Manichaei 4.5; PL 42,175. World Council of Churches, Baptism, Eucharist and Ministry, (Geneva: WCC, 1982). Lihat Walter Bühlmann, The Church of the Future, (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1988) 3-11. Lihat ”Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism” Origins, 23 (1993). IV Tradisi yang Hidup Sementara orang menolak pengertian tradisi. Bagi mereka, kata tradisi sendiri menyarankan sesuatu yang beku, otoritarian, yang mengunci orang di masa lampau. Mereka melihat tradisi sebagai tantangan terhadap otonomi pribadi. Kata tradisi (dalam bahasa Yunani: paradosis, Latin: traditio) secara harfiah berarti sesuatu yang telah ”diserahkan”, ”diteruskan”, ”diwariskan.” Banyak sekali istilah ”tradisi” disamakan dengan arti kedua yaitu segala kebiasaan, praktek, kepercayaan, dan ajaran populer tetapi merupakan kepercayaan jemaat yang tidak resmi. Orang-orang Katolik pernah mempunyai tradisi-tradisi semacam itu, puasa selama masa Puasa, puasa sebelum menerima Komuni, pantang daging pada hari Jumat, mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja (karena Sakramen Mahakudus ada di dalamnya), wanita menutup kepala di gereja, dan lain-lain. Tradisi-tradisi itu pernah menjadi bagian budaya Katolik populer dan membantu memperkuat identitas Katolik. Akan tetapi, tradisi-tradisi itu telah dikondisikan oleh zaman dan pada akhirnya tidak penting. Dalam arti yang paling dasar, ”tradisi” merupakan pengalaman iman bersama jemaat Kristiani, hidupnya dalam Kristus, dan persatuannya di dalam Roh. Bagi para Bapa Gereja, tradisi itu, sebagai hal yang diwariskan dari zaman para Rasul, mempunyai tiga ciri: ”antikuitas, universalitas, dan konsensus”. Pengertian mengenai prinsip tradisi itu membuat Gereja awal mampu mengumpulkan tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai apostolik oleh semua Gereja ke dalam kanon Kitab Suci, untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli dan mengembangkan syahadat dan pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Tradisi jauh lebih banyak daripada hormat terhadap hal-hal yang kuno. Tradisi merupakan kenyataan yang hidup yang menyimpan pengalaman iman jemaat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Vatikan II membicarakan peran aktif tradisi ini dalam konstitusi tentang Wahyu Ilahi: ”Demikianlah Gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan, dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya”. Tradisi ”berkat bantuan Roh Kudus” berkembang dalam Gereja, ”sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan,” dan ”Gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran Ilahi” (D8). Dalam arti ini tradisi mempunyai orientasi ke masa depan. Menurut Jaroslav Pelikan, ”Tradisi adalah iman hidup orang yang sudah mati. Sedang tradisionalisme adalah iman mati orang yang masih hidup.”1 Dalam bab ini kita akan membahas hubungan antara hidup atau tradisi jemaat dan wahyu, dialog atau pewahyuan dari Allah yang telah diadakan-Nya dengan umat manusia. Kemudian, kita akan membicarakan berbagai ungkapan resmi dari tradisi Gereja. Akhirnya, kita akan menguraikan ciri-ciri khusus tradisi Katolik. 1. Wahyu dan Tradisi Banyak orang Kristiani, yang akrab dengan cara Allah berhubungan dengan umat manusia yang tampaknya terjadi secara langsung, rindu akan kejelasan zaman biblis dengan nostalgia. Segalanya sedemikian sederhana. Allah berbicara melalui semak yang menyala kepada Musa, dari asap dan api Gunung Sinai kepada umat. Allah memberi 10 perintah yang jelas tertulis di loh batu. Umat dibimbing melewati padang pasir dengan awan pada siang hari dan pijar api pada malam hari. Terjadi banyak mukjizat, seperti wabah penyakit di Mesir, terbelahnya laut Merah selama masa pengungsian dari Mesir, matahari terhenti di langit di Gibeon, dan ramalanramalan eksplisit para nabi. Kegamblangan yang sama rupanya juga terjadi dalam Perjanjian Baru. Yesus memiliki perasaan yang jelas tentang identitas-Nya, dengan berkata kepada orang Yahudi dalam Injil Yohanes, bahwa diri-Nya dan Bapa adalah satu (Yoh 10: 30), bahwa Ia ada sebelum Abraham (Yoh 8: 58). Dalam Injil Matius, Ia memberikan instruksi-instruksi yang eksplisit kepada para Rasul sesudah kebangkitan-Nya: mereka diutus untuk mengajar segala bangsa menjadi muridmurid-Nya (Mat 28: 19). Khotbah-khotbah para Rasul sesudah Pentakosta disertai dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan, termasuk membangkitkan orang mati (Kis 9: 40), dan pada waktu ada masalah yang harus dipecahkan, Petrus dan Paulus mendapatkan mimpi atau visiun pewahyuan, sehingga kehendak Allah dengan mudah ditegaskan (Kis 10: 10-16, 23:11). Bagaimana kita dapat menjelaskan bantuan Ilahi yang menakjubkan pada zaman kitab suci dan menerangkan Allah yang diam dan tersembunyi pada zaman kita ini? Mengapa Allah sedemikian membantu nenek moyang kita dan membiarkan kita pada sumber-sumber daya kita sendiri? Barangkali situasi pada zaman Kitab Suci tidak sesederhana seperti tampak sekilas. Sesungguhnya dengan membaca Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa situasi Gereja awal tidak sedemikian berbeda dengan zaman kita. Keadaan-keadaan Perjanjian Baru menimbulkan masalah-masalah baru dan jawaban atas masalah-masalah itu tidak segera ditemukan. Krisis terbesar pertama yang dihadapi oleh Gereja Perdana adalah masalah orang-orang non-Yahudi, pria dan wanita, yang percaya kepada Yesus dan menghendaki dibaptis ke dalam jemaat Kristiani. Ini menjadi masalah besar bagi Gereja: apakah para calon Kristiani itu terlebih dulu harus menjadi Yahudi, menaati kewajiban-kewajiban hukum Yahudi, bagi pria non-Yahudi itu juga berarti harus disunat? Masalah itu bukan masalah mudah bagi Gereja Perdana. Meskipun tampak jelas teks-teks Injil seperti Matius 28:19, yang menginstruksikan para Rasul untuk membaptis segala bangsa, masalah orang non-Yahudi itu membutuhkan waktu lama bagi Gereja untuk memecahkannya. Model-Model Wahyu Dengan demikian, bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita? Berbagai jawaban sudah diberikan.2 Beberapa orang mengerti wahyu sebagai penyampaian ”kebenaran-kebenaran” tertentu oleh Allah, yang kemudian dapat dirumuskan ke dalam pernyataan-pernyataan yang jelas. Wahyu semacam ini membuat Allah tampak seperti teolog yang berbicara dengan konsep-konsep yang jelas, atau Yesus seperti guru yang menyampaikan kumpulan ajaran khusus kepada para Rasul-Nya. Orang-orang Katolik kerap berbicara tentang ”harta perbendaharaan iman” dalam arti ini. Wahyu dimengerti secara statis, seolah-olah Yesus mempercayakan iman kepada para Rasul sebagai kumpulan kebenaran yang lengkap. Konsili Trente (1546-1563) mengerti wahyu seperti itu pada waktu berkata tentang Injil sebagai ”Kebenaran-kebenaran dan peraturan-peraturan ... yang termuat dalam kitab tertulis dan tradisi-tradisi tak tertulis yang telah sampai pada kita, sesudah diterima oleh para Rasul dari Yesus sendiri” (DS 1501). Sumpah melawan modernisme menguraikan iman sebagai ”penerimaan secara intelektual yang sungguh-sungguh atas kebenaran yang diterima dari luar dengan mendengar” (DS 2145). Bagi banyak orang Protestan, ajaran tentang inspirasi Kitab Suci mencerminkan permohonan tentang wahyu seperti di atas. Kata-kata Kitab Suci dimengerti sebagai benar dalam arti harfiah, yang didiktekan kepada pengarang suci oleh Roh Kudus. Misalnya, banyak orang fundamentalis yang melihat dalam Kitab Wahyu, buku Kristiani awal yang hampir tidak masuk ke dalam Perjanjian Baru, isyarat yang diwahyukan secara Ilahi untuk segala peristiwa historis yang akan memaklumkan akhir dunia dan kedatangan Kristus yang kedua. Pendekatan yang proposisional terhadap wahyu dengan benar memahami bahwa ada bagian dalam pewahyuan diri Allah yang dapat dirumuskan dalam pernyataan-pernyataan teologis. Akan tetapi, pendekatan itu tidak berhasil memahami bahwa dalil-dalil atau doktrindoktrin itu secara historis adalah susunan manusia yang dapat ditafsirkan kembali. Lagi pula, dengan mereduksikan pewahyuan pada kebenaran-kebenaran yang berasal dari luar, pendekatan semacam itu tidak memberi tempat bagi perkembangan pemahaman peristiwa Kristus dan bagi perkembangan doktrin. Orang-orang lain melihat wahyu dalam karya-karya kuasa Allah dalam sejarah, peristiwaperistiwa ajaib atau peristiwa-peristiwa historis yang dengan sendirinya jelas seperti keluaran, terbelahnya Laut Merah, atau terbelahnya tirai Bait Allah pada saat Yesus wafat. Sementara benar bahwa wahyu terjadi di dalam sejarah Israel. Pendekatan ini menyarankan model wahyu yang interventionis (campur tangan). Wahyu itu menggambarkan Allah campur tangan langsung dalam tata alam-dunia. Sayangnya, peristiwa-peristiwa yang dinyatakan sebagai intervensi Ilahi sama sekali tidak jelas dengan sendirinya. Apa yang dilihat oleh orang beriman ketika Allah membebaskan anak-anak Israel dari perbudakan di Mesir, oleh ahli sejarah atau antropologi dilihat sebagai migrasi penduduk sebagai akibat kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Tambahan pula, pendekatan interventionis menciptakan masalah lebih lanjut dengan menyarankan bahwa Allah bertindak dengan meniadakan atau mengatasi hukum-hukum alam. Dewasa ini banyak orang berpikir jauh lebih masuk akal dalam melihat wahyu Allah, atau lebih tepat, pewahyuan-diri Allah, sebagai sesuatu yang tidak berasal dari luar melainkan dari dalam dunia, di mana Allah yang transenden ada dalam hubungan imanen dengan ciptaan. Pendekatan ini berpendapat bahwa kita tidak berjumpa dengan Allah secara langsung. Pewahyuan selalu diperantarai oleh pengalaman di dunia, orang, peristiwa, kisah, atau gejala alam yang menjadi lambang yang mengungkapkan makna yang lebih dalam. Pengalaman kita merupakan kenyataan yang dalam dan kompleks. Pengalaman itu meliputi hal-hal yang terjadi pada kita secara pribadi, peristiwa-peristiwa historis dalam hidup jemaat kita, masalah yang mengganggu kita, keinginan kita akan makna, kebahagiaan, pemenuhan, dan kelaparan akan Allah. Dari sudut pandang ini, pengalaman manusia sendiri dan terutama pengalaman jemaat yang percaya menjadi medan komunikasi diri Allah. Dengan cara itu, apa yang kita sebut ”wahyu” merupakan pemahaman atau visi religius yang muncul dari jemaat beriman. Jemaat melihat kehadiran dan tindakan Allah melalui manusia, peristiwa, dan benda. Jemaat mengungkapkannya dalam bahasa atau kisah, dan akhirnya merumuskannya sebagai ajaran religius. Ini tidak menyangkal karya Roh Kudus yang penuh misteri. Justru Roh Kuduslah yang membuat umat beriman dan penafsir-penafsir profetis sampai pada kesadaran baru akan kehadiran dan tindakan Allah melalui berbagai lambang alamiah dan religius, dan terutama dalam pribadi Yesus. Kisah-kisah suci atau mitos dapat juga menjadi sarana pewahyuan diri Allah, seperti peristiwa historis dan khotbah profetis. Kisah biblis tentang kejatuhan manusia pertama adalah mitos yang digunakan oleh pengarang-pengarang Kitab Suci untuk menerangkan pengalaman umat mereka akan kejahatan dan dosa. Kisah ular yang membuat pria dan wanita pertama jatuh ke dalam dosa di taman, mengajarkan kebenaran religius yang mendalam dengan menyarankan bahwa akar seluruh dosa adalah kegagalan umat manusia untuk mengakui keterbatasan manusia dan mengakui Allah sebagai Allah. Dari kisah itu, St. Paulus mengembangkan teologi dosa yang ditulis dalam surat kepada umat di Roma dan Agustinus merumuskan apa yang kemudian menjadi ajaran tentang dosa asal. Demikian juga kepercayaan akan hidup sesudah mati, pada awalnya merupakan bagian tradisi Israel. Akan tetapi, harapan bahwa Allah akan membangkitkan orang mati menjadi hidup mulai tampak dalam Kitab Suci Yahudi dalam tulisan-tulisan apokaliptik seperti Kitab Daniel, yang ditulis sekitar zaman Antiochus IV (150 SM), pada waktu orang-orang Yahudi yang saleh disiksa dan dibunuh karena iman mereka. Kebangkitan Kristus merupakan bukti kuasa Allah atas maut itu sendiri dan menjadi dasar ajaran kebangkitan badan, yang amat sentral dalam iman Kristiani. Bagan pada halaman 121 memberi beberapa contoh bagaimana jemaat beriman bergerak dari pengalaman melalui lambang-lambang interpretatif ke apa yang pada akhirnya menjadi kepercayaan-kepercayaan atau ajaran-ajaran resmi. Dengan demikian wahyu terjadi dalam sejarah umat Allah yang tercermin dalam Kitab Suci Yahudi dan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan mencapai kepenuhan dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dengan kata lain, pewahyuan-diri Allah dalam Yesus hanya dapat dimengerti sepenuhnya dalam konteks bangsa yang menjadi asal Yesus dan jemaat-jemaat para murid awal yang merayakan kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka. Tradisi mereka diungkapkan dan disimpan bagi kita di dalam Kitab Suci. Ungkapan ”wahyu selesai dengan kematian Rasul yang terakhir” menunjuk pada Yesus sebagai pewahyuan-diri Allah yang definitif dan mutu normatif Kitab Suci Gereja Apostolik. Tidak lagi ada wahyu karena Sabda Allah yang definitif sudah diucapkan dan menjadi daging dalam Yesus. 2. Ungkapan-Ungkapan Tradisi Pengalaman iman jemaat diungkapkan baik secara resmi maupun tidak resmi. Secara tidak resmi pengalaman iman diungkapkan dalam seni, musik, dan sastra Kristiani, dalam kepercayaan populer dan ajaran para teolog, dalam berbagai spiritualitas dan tradisi-tradisi devosional, dalam ceritera-ceritera para kudus, dan hidup orang Kristiani, dan seterusnya. Secara resmi tradisi Gereja yang hidup diungkapkan dalam Kitab Suci kanonis, dalam syahadat, dalam liturgi, dan dalam sakramen-sakramen Gereja, serta dalam rumusan doktrinal jabatan mengajar Gereja atau magisterium. Kitab Suci Alkitab dipandang sebagai tulisan-tulisan suci, atau Kitab Suci, karena dalam kitab-kitab itu Gereja mengenal suara Tuhannya. Menurut Konstitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus; Allah adalah pengarang yang benar dan ”harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran, yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam Kitab-Kitab Suci demi keselamatan kita” (DV 11). Dengan demikian, Alkitab itu menjadi norma bagi iman, pewartaan, dan ajaran Kristiani, serta sebagai sabda Allah merupakan sumber yang kaya untuk doa pribadi. Bersamaan dengan itu, Alkitab sendiri merupakan produk tradisi; Alkitab merupakan ungkapan tertulis iman Israel dan jemaat-jemaat Kristiani awal. Sebagai saksi utama untuk pewahyuan Allah kepada Israel dan dalam Yesus, Alkitab adalah normatif bagi iman jemaat Kristiani dewasa ini dan harus terus ditafsirkan dalam tradisi hidup Gereja. Kitab Suci Yahudi merupakan koleksi atau kanon yang beranekaragam dari kitab-kitab suci yang ditulis selama lebih dari 1000 tahun. Kumpulan buku itu dibagi menjadi tiga bagian: Hukum, Nabi-nabi, dan Tulisan-Tulisan. Kitab Hukum, yang secara tradisional dianggap ditulis oleh Musa, berisi lima buku dari Alkitab Yahudi: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima buku itu juga disebut Pentateukh. Kitab Nabi-Nabi yang memuat lebih daripada kitab-kitab profetis tradisional, mencakup semua nabi, dari Yosua dan Hakim-Hakim sampai Maleakhi. Kitab-kitab biblis sisanya – kitab-kitab sejarah, mazmur, sastra kebijaksanaan – dikelompokkan bersama menjadi Tulisan-Tulisan. Kanon Perjanjian Lama Katolik memuat semua tulisan itu ditambah enam kitab dan bagianbagian tambahan kitab yang hanya tersimpan dalam bahasa Yunani (1 dan 2 Makabe, Tobit, Yudit, Sirakh, Kebijaksanaan Salomo, Barukh, dan bagian-bagian tambahan Kitab Daniel dan Ester). Kitab-kitab itu merupakan bagian ”Septuaginta”, terjemahan Kitab Suci Yahudi ke dalam bahasa Yunani, yang dibuat sekitar tahun 250 SM di Aleksandria, Mesir. Kitab-kitab itu digunakan oleh banyak jemaat Kristiani awal, yang sebagian besar adalah pertobatan orangorang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orangorang non-Yahudi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon Yahudi, yang disusun oleh kaum Farisi di Yamnia sekitar tahun 90 SM. dengan menggunakan norma bahwa untuk dapat dimasukkan ke dalam kanon kitab itu harus berbahasa Ibrani. Pada abad ke-16, kaum Reformasi Protestan kembali ke kanon Yahudi. Dengan menolak kitab-kitab Deuterokanonika, yang mereka sebut ”apokrif”, kaum reformasi menetapkan kanon Perjanjian Lama Protestan agak berbeda dari kanon yang secara tradisional diikuti oleh Gereja-Gereja Katolik dan Ortodoks. Kanon Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang ditulis selama jangka waktu 60 tahun. Dokumen-dokumen Perjanjian Baru awal adalah surat-surat St. Paulus yang asli, I Tesalonika, I dan II Korintus, Galatia, Filipi, Roma, dan Filemon yang singkat yang ditulis sendiri oleh St. Paulus pada awal tahun 50-an. Surat-surat lain yang dianggap ditulis oleh St. Paulus mungkin ditulis oleh salah satu muridnya satu – tiga dasawarsa sesudah St. Paulus meninggal (63). Injil Pertama, yaitu Injil Markus, muncul pada kira-kira tahun 68, tidak lama sebelum kehancuran Yerusalem, yang menandai berakhirnya zaman para Rasul. Injil Matius dan Lukas, yang sebagian besar didasarkan pada Injil Markus, tetapi juga menggunakan sumber lain tentang ucapan-ucapan Yesus yang hanya disebut ”Q” (dari kata Jerman Quelle, yang berarti ”sumber”), ditulis antara tahun 85 dan 90, bersama Kisah Para Rasul oleh Lukas, Injil Yohanes muncul sekitar tahun 100; 3 surat Yohanes muncul tidak lama kemudian. Kitab Perjanjian Baru yang terakhir, 2 Petrus ditulis sekitar atau sesudah tahun 110. Kitab-kitab itu diterima dalam kanon biblis dan diakui sebagai diilhami secara ilahi. GerejaGereja awal melihat kitab-kitab itu sebagai ungkapan iman mereka dan dengan demikian memiliki otoritas Ilahi. Kita dapat menyatakan kitab-kitab itu merupakan tradisi hidup jemaat atau Gereja sampai menjadi ungkapan tertulis. Memang masih ada kitab-kitab lain, baik Yahudi maupun Kristiani, yang oleh orangorang atau jemaat-jemaat tertentu, kerap Gnostik, dinyatakan berotoritas Ilahi. Kitab-kitab pseudoprofetis, surat-surat, injil-injil, dan kisah berbagai rasul yang secara kolektif dikenal sebagai tulisan-tulisan ”apokrif”. Pada akhirnya, kitab-kitab itu tidak dapat diakui dan diterima; yang menjadi dasar kanon biblis. Alkitab dengan demikian muncul dari Gereja dan bukan sebaliknya. Pada abad ke-16 orang-orang Katolik dan kaum Reformasi berdebat tentang hubungan antara Kitab Suci dan tradisi.3 Kaum reformasi berpegang pada sola scriptura (Kitab Suci saja) sebagai patokannya. Gereja Katolik terus melihat Kitab Suci sebagai kitab Gereja, yang ditafsirkan dalam tradisinya yang hidup. Dewasa ini kedua pihak itu jauh lebih dekat. Para ahli Katolik dan Protestan kerap belajar di Universitas atau sekolah teologi yang sama. Mereka mengambil kuliah dari profesor-profesor yang sama dan membaca buku-buku oleh pengarang yang sama. Kebanyakan orang Protestan mengakui bahwa Alkitab sendiri merupakan ungkapan tradisi dan selalu ditafsirkan dalam jemaat beriman tertentu yang memberinya hidup. Orang Katolik mengakui bahwa Kitab Suci tetap merupakan patokan utama bagi iman dan ajaran Kristiani. Konstitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi Vatikan II berkata tentang magisterium: ”wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja, dengan bantuan Roh Kudus” (DV 10). Syahadat Iman Gereja juga diungkapkan dalam syahadat. Syahadat dalam bahasa Latin, credo (berarti ”aku percaya”) merupakan pengakuan iman yang resmi. Salah satu pengakuan Kristiani yang paling awal adalah ungkapan ”Yesus adalah Tuhan” (1Kor 12: 3). Demikian juga rumusan, ”Jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan” (Rm 10:9) mungkin merupakan bagian dari pengakuan kuno pada waktu pembaptisan. Rumusan-rumusan kepercayaan seperti itu sejak awal dituntut dari para calon baptis. Dari konteks baptis inilah, terutama dari pembinaan katekese sebelum pembaptisan, syahadat historis Gereja berkembang.4 Rumusan dalam Injil Matius, ”Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus” (Mat 28:19), mungkin telah menjadi model Trinitarian untuk syahadat-syahadat sebelumnya. Pada abad ke-2 dan ke-3 kepada para calon baptis diajukan ketiga pertanyaan yang memungkinkan mereka mengakui kepercayaan mereka kepada Allah sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebuah contoh dari Gereja Roma abad ke-3 dapat ditemukan dalam Traditio Apostolica (Tradisi Apostolik) Hippolytus (21:12 – 18). Syahadat yang bersifat pertanyaan itu hilang pada waktu muncul syahadat yang bersifat pernyataan. Syahadat para Rasul agaknya berasal dari syahadat pembaptisan Gereja Roma, meski teks sesungguhnya diperkirakan berasal dari St. Paulus. Syahadat itu masih dihubungkan dengan baptis. Yang disebut syahadat Nicea sesungguhnya merupakan peninjauan kembali syahadat Nicea (325) oleh konsili Konstantinopel I (381). Syahadat itu kadang-kadang disebut sebagai ”syahadat Ekumenis”. Syahadat Athanasia mungkin sudah ditulis pada abad ke-5 oleh Caesarius Arles, murid Agustinus. Dan masih ada syahadatsyahadat lain. Syahadat Nicea masih dipertahankan di kalangan Gereja-Gereja Katolik, dan aliran utama Protestan (meskipun Gereja Ortodoks menghapuskan kata filioque yang menyatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, yang ditambahkan pada syahadat di Barat pada abad ke-11). Sayangnya, banyak dari antara kita dewasa ini, biasa mendaraskan syahadat tanpa banyak berpikir. Akan tetapi, perenungan sejenak mengungkapkan harta kekayaan ajaran Kristiani karena syahadat menyampaikan peraturan Gereja dalam hal iman, yang dipadatkan menjadi ”butir-butir rumusan” yang relatif tidak banyak. Kepercayaan kepada Allah sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, keperawanan Maria, Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal – ini semua diakui secara publik dalam pengalaman historis iman Kristiani. Jika kita mau tahu apa yang dipercaya oleh Gereja, telitilah syahadat, lalu lihatlah hidup ibadatnya. Liturgi Kata liturgi (leitourgia) berasal dari kata Yunani laos, ”rakyat”. ”Umat” dan ergon ”kerja”. Maka, leitourgia berarti ”kerja rakyat”, ”kerja umat”. Kata itu dipergunakan untuk menyebut doa publik resmi Gereja, Ekaristi, Sakramen-sakramen, serta upacara-upacara resmi lain, Doa Ofisi, yang sekarang disebut ”Liturgi Ibadat Harian”. Liturgi menampilkan Gereja dalam doa, bukan sebagai perorangan atau bahkan para petugas resmi Gereja, tetapi seluruh umat atau ”jemaat”. Ketika Gereja menghantarkan orang masuk ke dalam jemaatnya dan dengan demikian ke dalam Kristus dalam sakramen Baptis, ketika Gereja berkumpul untuk memecah roti dan berbagi piala bersama untuk mengenang Yesus, ketika Gereja memaklumkan pengampunan dosa atas nama-Nya, Gereja sendiri menjadikan secara lebih penuh kehadiran Kristus yang sudah bangkit di tengah umat-Nya. Dengan cara itu, tradisi hidup Gereja diungkapkan lagi. Sakramen-sakramen merupakan lambang-lambang yang terdiri dari tindakan dan kata-kata ritual. Sakramen-sakramen ”dapat digambarkan sebagai lambang kehadiran Allah di dunia, hidup, sejarah, dan Gereja”.5 Perhatikanlah berapa banyak iman Kristiani dipadatkan dalam masing-masing sakramen itu. Baptis menghantarkan orang masuk ke dalam jemaat Kristiani. Rumusan baptis merupakan pengakuan iman akan Allah Tritunggal; baptis menuntut pengakuan iman dari pihak orang yang dibaptis atau dalam kasus baptis bayi, dari pihak orang tua dan bapak/ibu baptis, yang akan menjadi Gereja utama, yang akan dialami oleh anak selama bertahun-tahun. Dibaptis merupakan tanda dibersihkan dari dosa dan bangkit ke hidup baru yang menjadi milik seseorang yang dibaptis melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian juga, perhatikan berapa banyak yang hadir ketika kita membuka sakramen Ekaristi. Pada waktu berkumpul untuk Ekaristi, Gereja mengucap syukur kepada Allah dalam doa syukur Agung karena hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus dan mohon kepada Allah agar berkenan mencurahkan karunia Roh Kudus. Pada waktu berbagi roti dan piala untuk mengenang Yesus, jemaat mengakui kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam roti dan anggur yang menjadi sakramen Tubuh-Nya yang dipecah-pecah dan Darah-Nya yang dicurahkan, korban agung Yesus, yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena kita sudah didamaikan dengan Allah dan satu sama lain, jemaat Ekaristis merupakan tanda kesatuan seluruh umat manusia; apa pun yang merusak kesatuan itu, seperti kata St. Paulus, adalah dosa melawan Tubuh dan Darah Tuhan (1Kor 11: 27). Ekaristi memanggil kita untuk berdamai dengan saudara-saudari kita dan mengakui kesatuan kita dengan mereka yang telah ditebus oleh Kristus. Bersamaan dengan itu, pesta Ekaristi merupakan lambang pesta eskatologis besar di dalam Kerajaan Allah. Praktek orang Yahudi berdoa tiga kali sehari, pagi, siang dan malam, mungkin sekali menjadi asal-usul Doa Ofisi Harian sekarang ini. Pada abad ke-3 dan ke-4, para Bapa padang pasir menyanyikan mazmur di sel-sel mereka atau pada pertemuan-pertemuan mingguan mereka, ”doa ofisi” pagi serta sore dirayakan di Gereja-Gereja besar, baik di Timur maupun di Barat sudah pada abad ke-4. Setiap doa ofisi meliputi beberapa mazmur dan nyanyian- nyanyian, beberapa doa permohonan, dan berkat terakhir serta pembubaran. Komunitaskomunitas monastik membangun hidup religius mereka di seputar doa ofisi: bangun sebelum fajar untuk doa vigili, dan kembali ke Gereja lima kali lagi untuk mendoakan doa-doa ofisi lain sampai ibadat akhir completorium untuk menutup hari. Dewasa ini komunitas-komunitas monastik masih mendoakan doa ofisi dengan dinyanyikan dalam koor. Imam diosesan dan religius pria serta wanita dari komunitas-komunitas religius apostolik biasanya mendoakan doa ofisi sendirian, sebagaimana dilakukan banyak orang awam. Namun idealnya, doa ofisi sebaiknya didoakan bersama. Ajaran Akhirnya tradisi Gereja diungkapkan secara resmi dalam doktrin atau ajarannya. ”Doktrin”, ”Ajaran” (berasal dari kata latin doctrina yang berarti ”pengajaran”) berarti lebih daripada kepercayaan atau pendapat teologis. Doktrin adalah kepercayaan yang telah menjadi ajaran resmi Gereja, biasanya sebagai hasil dari pengajaran secara otoritatif oleh magisterium Gereja. ”Dogma” adalah ajaran atau doktrin yang dianggap telah diwahyukan secara ilahi dan diajarkan dengan otoritas Gereja yang paling tinggi. Seperti sudah kita lihat sebelumnya, doktrin meliputi butir-butir syahadat, ajaran-ajaran konsili-konsili ekumenis, dan ajaran ex-cathedra (tak dapat sesat) magisterium Paus yang luar biasa. Tradisi doktrinal Gereja merupakan sumber daya yang kaya. Akan tetapi, ada kerawanan pada doktrin kita. Pernyataan doktrinal merupakan usaha dari pihak Gereja untuk menemukan bahasa dan konsep guna mengungkapkan apa yang secara intuitif ditangkap tentang imannya. Jika kita tidak memilih tinggal diam, mau tak mau kita merasa butuh untuk mengungkapkan iman kita dalam kata-kata. Sesungguhnya itulah yang menjadi hakikat teologi, yaitu menemukan bahasa untuk mengungkapkan apa yang kita percayai agar kita dapat mengerti iman kita dengan lebih baik dan berbagi dengan orang lain. Menurut St. Anselmus (meninggal 1109), teologi adalah iman yang mencari pemahaman (fides querens intellectum). Akan tetapi betapapun perlunya bahasa teologis, bahasa itu tetap tidak memadai. Pernyataan-pernyataan teologis kita selalu merupakan beberapa tingkat abstraksi yang dijauhkan dari kenyataan, baik manusiawi atau Ilahi, yang mau diuraikan. Betapapun besarnya prestasi seperti ajaran tentang dosa asal, ajaran itu tetap merupakan ungkapan yang tidak memadai bentuk misteri kejahatan, yang telah mengenai diri kita masing-masing, dengan caracara yang tragis dan kuat sejak saat-saat pertama keberadaan kita. Demikian juga bahasa rahmat masih jauh dari pengalaman akan hidup dalam Roh. Bahasa kita tentang Allah palingpaling hanyalah analogis. Bahasa itu sekaligus mengandung penegasan maupun penyangkalan karena Allah yang transenden melampaui kemampuan kita untuk memahami dan menguraikan. Doktrin dapat benar dan meski demikian masih belum memadai seperti Kongregasi Vatikan untuk Ajaran Iman mengakui dalam instruksi Mysterium ecclesiae (24 Juni 1973), setiap ”ungkapan wahyu” (yang meliputi bahasa syahadat, doktrin, dogma dan ajaran magisterium, bahkan Kitab Suci) secara historis dikondisikan dan oleh karena itu terbatas.6 Instruksi Kongregasi untuk Ajaran Iman melihat bahwa ungkapan-ungkapan wahyu dapat dibatasi oleh kemampuan ekspresif bahasa yang digunakan, oleh pengetahuan yang terbatas atau konsep zaman yang berubah dan oleh perhatian khusus yang mendorong munculnya ajaran tertentu. Salah satu tugas teologi adalah menafsirkan kembali bahasa Gereja, bahkan bahasa dari doktrinnya, supaya bahasa itu secara lebih memadai mencerminkan iman yang mau diungkapkannya. Bahkan, dogma-dogma Gereja adalah ungkapan-ungkapan wahyu yang dapat ditafsirkan kembali. Misalnya Konsili Vatikan II (1962 – 1965) menafsirkan kembali ajaran dogmatik Konsili Vatikan I (1870) tentang infalibilitas Paus, dengan menempatkannya dalam konteks baru dengan melibatkan uskup-uskup dalam melaksanakan karisma Gereja dalam infalibilitas. 3. Tradisi Katolik Kata Yunani katholikos aslinya berarti ”keseluruhan” atau ”umum” sebagai lawan dari ”sebagian”, ”parsial” atau ”khusus”, ”partikular”. Pemahaman Katolisisme tentang iman Kristiani adalah ”Katolik”, justru dalam kerangka pendekatan yang menyeluruh terhadap iman. ”Katolisisme, dengan demikian, dicirikan dengan pendekatan keduanya (dan) daripada pendekatan baik keduanya (atau).”7 Katolisisme bukanlah produk dari satu perubahan atau gerakan historis dalam sejarah Kristiani Pasca-Perjanjian Baru. Katolisisme tidak menemukan identitas atau jati dirinya dalam satu doktrin, aliran, teks liturgis atau teori penafsiran biblis, Dengan demikian, dapat merangkum dalam dirinya beraneka ragam teologi, spiritualitas, ritus liturgis, dan ungkapan hidup Kristiani. Menjadi ”katolik” berarti terbuka terhadap segala kebenaran, terhadap apa pun yang betulbetul manusiawi dan dari kodratnya baik. Ada kesan bahwa dalam seluruh sejarah Gereja, ada ”kecenderungan menuju ke rasionalitas”, tetapi di pihak lain Katolisisme dinilai lamban untuk menerima penalaran kritis, terutama yang muncul pada zaman pencerahan dan empirisisme modern.8 Gereja resmi kadang-kadang menghambat kegiatan pemikir-pemikir dan ilmuwanilmuwan yang menentang hal yang oleh Gereja dimengerti sebagai doktrin. Kasus Galileo masih tetap memalukan sampai hari ini, dan kasus itu bukan satu-satunya. Seperti dikatakan oleh Hans Küng, ”pada abad ke-19 karya-karya para ilmuwan modern tetap ditempatkan dalam buku-buku Index yang dilarang untuk dibaca oleh orang-orang Katolik, sejajar dengan kaum Reformasi dan filsafat modern (dari Descartes sampai Kant)”. 9 Akan tetapi, saat-saat atau zaman-zaman penekanan, yang ditandai oleh rasa takut terhadap apa yang baru akan berbeda, tidaklah khas. Bagaimanapun juga tradisi telah mengakui bahwa kebenaran itu satu dan ilmu serta seni dapat juga membimbing kepada Allah. Dari para teolog skolastik universitasuniversitas Abad Pertengahan sampai para teolog sistematik dewasa ini, para pemikir Katolik telah berusaha mengintegrasikan iman dan pengetahuan yang datang dari filsafat dan ilmu. Iman dan Pikiran Katolisisme tidak melihat ketidaksesuaian antara iman dan pikiran. Diterangi oleh iman, pikiran dapat memberi dasar tindak iman dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang misteri-misteri iman. Tradisi hukum kodrat dalam etika filosofis Katolik dan teologi moral mencerminkan kepercayaan terhadap saling melengkapinya iman dan pikiran ini. Reformasi pada abad ke-16 cenderung mengikuti pendekatan ”atau/atau” terhadap iman Kristiani. Pandangan Luther yang fundamental yang muncul dari pergulatannya sendiri untuk membuat dirinya benar di hadapan Allah dengan menaati peraturan biara adalah bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh pelaksanaan kesalehan atau hukum.10 Penemuan Luther yang besar dari studinya atas Surat Paulus kepada umat Roma (lih. 1:17) ini dirumuskan oleh Reformasi sebagai prinsip sola fide, hanya iman saja. Sebagai profesor Kitab Suci yang cemas karena Gereja telah menggantikan Injil dengan teologi filosofis skolastik, Luther menjadikan Kitab Suci sebagai dasar semua teologinya. Dari sinilah muncul semboyan sola scriptura, Kitab Suci saja. Seperti Agustinus, Luther pesimis tentang apa yang dapat dicapai oleh manusia yang sudah jatuh dengan kekuatannya sendiri. Ia menekankan orang dapat mendekati Allah hanya lewat rahmat saja, sola gratia. Akhirnya ia menolak apa yang disebutnya sebagai ajaran Gereja Abad Pertengahan tentang perantaraan rahmat melalui para Kudus, sakramen, imam, devosi, dan mengajarkan bahwa kita hanya diselamatkan oleh Kristus saja, Solus Christus. Luther menekankan apa yang telah dicapai Allah melalui kematian Kristus. Dengan demikian, ia menganut ”teologi salib” (theologia crucis). Namun, penolakan Luther atas segala macam teologi filosofis sebagai jenis ”teologi kemuliaan” (theoligia gloriae) yang dilarang, bersamaan dengan prinsip Kitab Sucinya, kemudian menimbulkan masalah dalam tradisi Protestan. Karena Reformasi mengandaikan kejelasan Kitab Suci pada waktu Kitab Suci ditafsirkan menurut prinsip-prinsip yang sehat. Akan tetapi, tanpa merasa bahwa iman dan akal saling melengkapi, prinsip Kitab Suci pada akhirnya berantakan karena dirongrong oleh rasionalisme pencerahan abad ke-18 dan kemenangan metode historis-kritis abad ke-19. Sejak itu, teologi Protestan tidak jarang mengarah ke kedua kecenderungan rasionalisme filosofis atau fundamentalisme biblis. Tradisi Katolik lebih suka berkata ”baik/maupun”. Pendekatannya inklusif (mencakup semua) dan komprehensif (menyeluruh) bukan hanya Kitab Suci saja tetapi Kitab dan tradisi; bukan hanya rahmat, tetapi rahmat dan kodrat, bukan iman saja tetapi iman dan perbuatan maupun iman dan akal. Konsili Trente (1546 – 1543) merupakan tanggapan Gereja terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh kaum Reformasi. Melawan prinsip ”hanya Kitab Suci saja”, Konsili Trente mengajarkan ”kebenaran-kebenaran dan peraturan-peraturan” yang berasal dari Injil ”terkandung dalam buku-buku yang ditulis dan tradisi-tradisi yang tak tertulis” (DS 1501). Dengan kata lain, baik Kitab Suci maupun tradisi merupakan saksi bagi wahyu. Dekrit Konsili Trente tentang kebenaran berusaha menjawab masalah-masalah yang diangkat oleh Luther tanpa mengkanonisasikan salah satu aliran pemikiran dalam Gereja. Dekrit itu meneguhkan bahwa iman merupakan ”dasar dan akar segala pembenaran”, bahwa rahmat pembenaran tidak dapat diperoleh lewat jasa manusia (DS 1532), dan bahwa pembenaran merupakan karya Allah dalam Kristus sejak awal karena manusia tanpa rahmat Allah tidak mampu membuat ini benar di hadapan Allah (DS 1525). Konsili Trente juga menekankan bahwa iman tidak dapat menyatukan orang secara sempurna pada Kristus tanpa harapan dan cinta kasih, karena ”iman tanpa perbuatan adalah mati” (DS 1531). Salah satu perhatiannya yang utama adalah melindungi peran kebebasan manusia dalam proses pembenaran. Dengan demikian, Konsili menegaskan bahwa manusia tidak hanya pasif; manusia harus bekerja sama dengan rahmat Allah (DS 1554). Antropologi Teologis Antropologi teologis tradisi Katolik, yang mencerminkan sudut pandang inkarnasi teologi patristik, bersikap serius terhadap kodrat dan rahmat. Penekanan Konsili Trente bahwa kita harus dengan bebas bekerja sama dengan rahmat pembenaran mencerminkan tradisi itu. Antropologi Protestan, karena amat dipengaruhi teologi Agustinus dan minat soteriologis Luther, cenderung menjadi pesimis. Protestantisme memandang kodrat manusia sesudah jatuh sebagai sama sekali rusak. Citra Allah telah lenyap. Karena kehendak dilihat ada dalam keadaan terbelenggu, tak mampu memilih atau berbuat baik, kerja sama manusia dengan rahmat tidak mungkin. Pembenaran melalui iman merupakan tindakan Allah. Jasa Kristus dikenakan pada kita, dosa ditutupi, bukan dihapuskan. Ajaran Kalvin tentang predestinasi (takdir) merupakan bentuk ekstrem dari pesimisme itu. Demikian juga, bagi kaum Reformasi, budi dibutakan oleh dosa, tak mampu mengetahui sesuatu pun tentang Allah, terlepas dari Kitab Suci. Sementara teologi Katolik tidak sepenuhnya bebas dari sikap pesimisme semacam itu terhadap kodrat sesudah jatuh, terutama sesudah dipengaruhi oleh Jansenisme, teologinya sendiri lebih optimistis. Tradisi terus mengulangi bahwa rahmat berdasar atas kodrat, berbicara tentang kodrat yang sudah jatuh dan kodrat yang telah ditebus. Akan tetapi, kodrat saja tanpa rahmat tidak ada, maka kodrat selalu merupakan kodrat yang sudah dirahmati, dirusak tetapi tidak secara radikal hancur oleh dosa asal. Karena umat manusia diciptakan untuk bersatu dengan Allah, kemampuan budi dan kehendak manusia terarah pada Yang Ilahi. Kata-kata Agustinus yang terkenal, ”Hati kami diciptakan bagi-Mu ya Allah, dan tidak akan damai sampai beristirahat pada-Mu,”11 menyarankan bahwa dengan suatu cara, jiwa manusia dapat mencapai melebihi kemampuannya, atau lebih cepat, jiwa manusia menangkap lebih dari apa yang dapat diketahui dengan sadar. Thomas Aquinas melihat hubungan antara budi manusiawi dan budi ilahi. Ia berpendapat bahwa ”terang intelek” dari budi manusia ”tidak lebih dari kesamaan yang mengambil bagian dari terang yang tak terciptakan yang mengandung gagasan-gagasan Ilahi”.12 Dengan perkataan lain, budi merupakan dinamisme yang dengan suatu cara menangkap inteligibilitas (dapat dimengertinya) pengada yang absolut, karena ikut mengambil bagian dalam terang yang tak terciptakan, di mana pengada yang tak terbatas dan inteligibilitas tak terbatas yang sama. Kaum Thomis transendental mengembangkan segi pemikiran Aquinas ini. Bagi Karl Rahner, Allah telah ditangkap dengan cara yang tidak eksplisit sebagai dasar dari kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan tentang pengada dan menginginkan kebaikan.13 Menurut tradisi, keberadaan Allah dapat diketahui dengan merenungkan Yang Ilahi dalam karya ciptaan, meski kita tergantung pada wahyu untuk mengetahui siapa Allah itu. Pembenaran merupakan karya Allah, tetapi kebebasan manusia selalu terlibat karena manusia harus bekerja sama dengan rahmat Allah. Pembenaran bukan hanya merupakan tindakan yuridis. Kodrat sungguh-sungguh diubah oleh rahmat. Tubuh sendiri dianggap suci; daripada dipandang berlawanan dengan roh, tubuh merupakan medium yang dipergunakan oleh roh untuk mengungkapkan diri. Tradisi secara serius memperhatikan teologi Yohanes tentang Allah yang tinggal di antara manusia dan di dunia. Allah tidak hanya ”menutupi” dosa, tetapi menebus kita, dengan mengikutsertakan dalam hidup batin Trinitas (Yoh 14:16–23). Tradisi GerejaGereja Timur menyebut keikutsertaan kita dalam hidup Ilahi sebagai pengilahian yang progresif (apotheosis). Tekanan pada Inkarnasi Doktrin inkarnasi, penjelmaan, dalam arti imanensi, keberadaan Ilahi dalam ciptaan, merupakan dasar dari penghargaan Katolisisme terhadap kenyataan yang diciptakan, penghormatannya terhadap tradisi, teologi antropologis dan imajinasi sakramentalnya. Teologi Protestan cenderung menekankan transendensi Allah yang Mahatinggi, tetapi mengurbankan penghargaan terhadap tata ciptaan. Sementara berguna menggunakan bahasa transendensi dan imanensi dalam membicarakan Allah, pandangan inkarnasi menekankan bahwa dalam diri Yesus, Allah secara definitif telah masuk ke dalam ruang, waktu, dan sejarah manusia. Karena inkarnasi, kenyataan-kenyataan ciptaan dirahmati. Kodrat dan rahmat dapat dipisah secara konseptual seperti sudah kita lihat, namun ciptaan sendiri ditata oleh inkarnasi. Kristus adalah ”yang sulung dari segala yang diciptakan” (Kol 1:15), ”Segala sesuatu dijadikan oleh Dia” (Yoh 1:3). Dalam tradisi patristik, yang mengembangkan pengertian creatio ex nihilo (penciptaan dari ketiadaan), karya kreatif Allah merupakan hal yang dinamis dan terus-menerus berlangsung. Penciptaan bukan peristiwa satu-waktu di masa lampau, karena Allah terus mempertahankan dan mendukung segalanya dalam keberadaan. Tradisi Skotlandia, berdasarkan ajaran seorang Fransiskan, bernama John Duns Scotus (meninggal tahun 1308) berpendapat bahwa Sang Sabda telah menjadi manusia bahkan jika Adam tidak melakukan dosa, untuk membawa ciptaan menuju ke kesempurnaan. Roh Allah aktif dalam segala ciptaan, yang mencerminkan kemuliaan pencipta. St. Ignasius dengan jelas melihat hal ini pada abad ke-16. Dalam ”Kontemplasi untuk Mendapatkan Cinta”, renungan pada akhir Latihan Rohani, Ignasius mengajak para retretan untuk membayangkan bagaimana Allah memberikan kepada kita segala benda ciptaan, tinggal di segala benda ciptaan, bekerja dalam benda-benda itu, dan bagaimana segala anugerah dan berkat yang diciptakan datang dari atas. Pada abad ke-20, teologi Katolik semakin kembali ke pengertian patristik bahwa kodrat manusia secara intrinsik diarahkan menuju kepada yang Ilahi dan penggunaan unsur-unsur kebenaran Ilahi di dalam agama dunia lain, tanpa menyangkal bahwa kepenuhan kebenaran diwahyukan di dalam Kristus. 4. Kesimpulan Katolisisme amat menghormati apa yang biasa disebut ”tradisi” (yang bertolak belakang dari ”tradisi-tradisi”). Penghormatan ini lebih dari sekadar menghormati apa yang kuno. Tradisi merupakan pengalaman iman Gereja, yang diterima, dihayati, dirayakan, dan diteruskan. Tradisi itu diungkapkan secara resmi dalam Kitab Suci yang dikanonkan, syahadat, sakramensakramen, dan liturgi Gereja, dan dalam ajaran magisterium. Dengan demikian, tradisi menyimpan bagi kita dan angkatan-angkatan yang akan datang wahyu Allah dalam Kristus melalui jemaat Gereja. Wahyu merupakan pengungkapan diri pribadi Allah. Melalui manusia, peristiwa, dan benda; wahyu terjadi dalam sejarah umat Allah, yang dicerminkan dalam Kitab Suci Yahudi dan Perjanjian Baru, dan mencapai kepenuhan dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kitab Suci sendiri merupakan produk tradisi. Kitab Suci merupakan ungkapan normatif yang dihayati dari iman Israel kuno dan jemaat-jemaat Kristiani kuno, dan dewasa ini tetap merupakan norma bagi iman, pewartaan, dan ajaran Kristiani. Pada waktu yang sama, Kitab Suci terus ditafsirkan dalam tradisi hidup Gereja dengan bantuan magisterium. Tradisi Katolik menyeluruh dalam pendekatannya pada kebenaran. Tradisi Katolik mencakup keanekaragaman teologi, spiritualitas, dan ungkapan hidup Kristiani. Percaya bahwa rahmat berdasar atas kodrat, tradisi Katolik berusaha mengintegrasikan budi dan iman. Pandangan inkarnasinya membuatnya menghargai segala yang manusiawi dan penghormatan pada ciptaan, karena yang manusiawi diangkat oleh Allah dalam inkarnasi, dan ciptaan mencerminkan kehadiran serta kegiatan sang pencipta. Tradisi Gereja bukanlah huruf-huruf yang mati. Tradisi merupakan penerusan atau pewarisan iman jemaat yang terus hidup di dalam Roh Yesus. Seperti sudah kita lihat, tradisi itu mengambil ungkapan yang konkret, baik secara resmi maupun tidak resmi. Ungkapan tradisi dalam Kitab Suci, syahadat, liturgi, dan doktrin penting karena menghubungkan dan mengantarkan jemaat sekarang dengan wahyu Allah di dalam sejarah terutama di dalam Yesus. Dengan demikian, ada dimensi yang secara intrinsik konservatif dalam tradisi. Akan tetapi, justru karena merupakan kenyataan yang hidup, tradisi terus tumbuh, berkembang, menjumpai tantangan-tantangan baru sebagaimana diperlihatkan oleh studi historis mengenai tradisi itu. Banyak tantangan yang dihadapi Gereja dewasa ini dan di masa depan. Gereja harus terus melanjutkan pembaruan yang sudah dimulai oleh Konsili Vatikan II. Tetap ada ketegangan antara Roma dan ahli teologi Katolik. Umat awam minta bagian yang lebih besar di dalam hidup liturgi Gereja dan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan doktrinal. Kaum wanita menghendaki agar kehadiran mereka lebih memadai diakui dalam bahasa dan pelayanan Gereja. Kaum minoritas minta agar diperhitungkan dan diberi tempat. Gereja di masa depan haruslah menjadi Gereja yang terekonsiliasikan, terdamaikan; Gereja di mana Gereja-Gereja yang berbeda-beda dapat menambahkan tradisi-tradisi khasnya sendiri pada katolisitas Gereja. Gereja harus dapat mempertahankan universalitas dan partikularitas, termasuk ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan budaya masing-masing, bersamasama di dalam satu kesatuan. Gereja harus mengadakan dialog dengan agama-agama besar dunia. Gereja harus menemukan bahasa baru untuk imannya, Gereja yang membawa pesan Injil yang membebaskan kepada jutaan kaum miskin dan menderita yang merupakan mayoritas bangsa di dunia. Isu-isu seperti itu akan membentuk kembali tradisi Gereja. Kita akan membahasnya pada bab terakhir buku ini. Tradisi tidak pernah statis. Tradisi sekaligus merupakan kenyataan normatif dan dinamis yang merangkum keyakinan umat beriman, karya ilmiah para teolog, kesaksian berbagai suara kenabian, kepemimpinan pastoral, uskup-uskup, dan otoritas mengajar tertinggi Gereja. Sulit mengatakan kata akhir tentang apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan di masa depan justru karena tradisinya merupakan tradisi yang hidup. Pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah dilakukan Gereja di masa lampau, tetapi untuk apa Gereja dipanggil oleh Roh pada zaman sekarang ini, pada waktu Gereja menghadapi tantangan-tantangan baru, sehingga dapat melanjutkan memberi hidup baru dalam Kristus Yesus dan kesatuan di dalam Roh. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jaroslav Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition (100-600) (Chicago: Univ of Chicago Press, 1971) 9. Lihat buku Avery Dulles, Models of Revelation (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1983). Lihat George H. Tavard, Holy Writ or Holy Church: The Crisis of the Protestant Reformation (London: Burns & Oats, 1959). Lihat J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds (London: Longman, 1972) 50. Michael Downey, Clothed in Christ: The Sacraments and Christian Living (New York: Crossroad, 1987) 23. ”Declaration in Defense of the Catholic Doctrine on the Church Against Certain Errors of the Present Day”, Origins 3 (1973) 97-100. Richard P. McBrien, Catholicism: New Edition (San Francisco: Harper, 1994) 16. Catholicism Confronts Modernity (New York: Seabury, 1975) 23. Hans Küng, Great Christian Thinkers (New York: Continuum, 1994) 161. H. George Anderson, F, Austin Murphy dan Joseph A. Burges, eds., Justification by Faith: Lutherans and Catholics in Dialogue VIII (Minneapolis: Augsburg, 1985). Confessiones 1.1. Summa Theologiae I.84.5 Karl Rahner, Foundations of Christian Faith (New York: Seabury, 1978) 33-35. V Sakramen-Sakramen dan Inisiasi Kristiani Setiap tahun saya menanti-nantikan Perayaan malam Paskah. Umat berkumpul dalam kegelapan malam di luar Gereja untuk menyalakan api baru, yang digunakan untuk menyalakan lilin Paskah, yang melambangkan kehadiran Tuhan yang telah bangkit di tengah-tengah umatNya. Sewaktu diakon mulai membawa lilin ke altar, lilin umat yang hadir dinyalakan dengan api lilin Paskah itu, dan seluruh sinar lilin menyebar dan memenuhi ruang gereja yang gelap. Tiga kali selebran menyerukan kata, ”Kristus cahaya dunia” dan umat menanggapi dengan kata ”Syukur kepada Allah”. Pada waktu arak-arakan sampai panti imam, diakon mendupai lilin dan kemudian mengidungkan lagu Exsultet, kidung pujian yang mengajak segala ciptaan menjadi saksi dan merayakan Kristus yang bangkit dari mati; ”Bergembiralah, hai bumi, dalam kemegahan yang bersinar, berseri-seri dalam penerangan rajamu. Kristus telah menang. Kemuliaan memenuhimu. Kegelapan lenyap untuk selama-lamanya”. Lalu serangkaian bacaan mulai dari kitab Kejadian tentang kisah penciptaan guna melihat kembali sejarah keselamatan. Pada waktu koor menyanyikan Kemuliaan, semua lampu gereja dinyalakan dan lilin serta bunga-bunga dibawa ke altar. Sesudah itu para calon baptis dibawa maju ke depan altar, doa litani para Kudus untuk mohon perantaraan para Kudus dinyanyikan. Para calon baptis menyatakan iman mereka, dibaptis dan dikuatkan dalam Roh Kudus dan diterima dalam jemaat. Pada akhirnya, seluruh jemaat dengan para anggotanya yang baru merayakan Perayaan Ekaristi Paskah meriah. Ibadat – dengan gelap dan terang, api dan air, roti dan anggur serta minyak, bau harum dupa, lilin dan saat-saat hening, musik dan nyanyian – mengambil unsur-unsur pengalaman kita sehari-hari dan membuatnya menjadi lambang-lambang hidup Kristus yang baru dan kehadiranNya penuh misteri di tengah-tengah kita. Semua itu mengubah cara kita melihat. Melihat lilin besar kita berpikir tentang Paskah. Semua ini menggambarkan apa yang kerap disebut sebagai imajinasi sakramental. 1. Prinsip Sakramental Imajinasi sakramental ini merupakan inti tradisi Katolik. Imajinasi sakramental mencerminkan apa yang disebut ”prinsip sakramental”, perasaan mendalam bahwa kehadiran Ilahi yang tak kelihatan dinyatakan melalui benda-benda ciptaan yang berfungsi sebagai lambang. Seperti dikatakan Langdon Gilkey, bagi orang-orang Katolik, misteri Ilahi disampaikan ”tidak hanya melalui kesadaran rasional atau ekstasi saja, tetapi melalui berbagai lambang yang berkaitan dengan segala segi kehidupan”.1 Setiap lambang yang menyarankan atau memungkinkan kita untuk melihat secara intuitif sesuatu yang secara misteri kedalaman kebaikan, kasih, belas kasih, dan kehadiran yang kita sebut Allah dapat menjadi tanda sakramental. Lambang-lambang seperti itu terutama tidak bersifat intelektual; lambang-lambang itu tidak hanya berbicara kepada otak, tetapi juga kepada perasaan, intuisi, hal-hal yang afektif. Beberapa lambang itu alamiah sifatnya yang dapat menjadi religius melalui kekuatan evokatif. Matahari yang sedang terbenam kelihatan indah seakan menyampaikan rasa keselarasan dan kedamaian akan kehadiran Allah yang penuh misteri. Lambang-lambang lain merupakan lambang religius. Tokoh-tokoh profetis seperti Musa, Yesaya dan Yesus sendiri, menyatakan kehadiran dan tindakan Allah melalui kata dan perbuatan-perbuatan mereka. Sebuah kisah dapat membantu kita mengenal makna religius yang mendalam dari beberapa segi hidup kita sehari-hari. Lambang-lambang religius seperti upacara-upacara sakramental, patung, salib, ikon, dan gereja menyangkut budi dan hati kita kepada Allah. Orang-orang Katolik memiliki penghargaan yang mendalam terhadap lambang-lambang religius seperti itu. Mereka menghias rumah dan lembaga mereka dengan seni religius, dan gereja-gereja mereka penuh dengan gambar, patung, salib, dan kaca-kaca bergambar berwarna-warni. Tempat air suci ada di samping pintu masuk gereja, dan lampu merah menyala di sekitar tabernakel. Liturgi Katolik, dengan perarakan, lilin yang menyala, dupa, musik suci, dan pelayan yang berpakaian warna-warni, sangat menarik indra dan hati. Uskup dan Paus mengenakan pakaian dan hiasan-hiasan yang sudah berabad-abad umurnya. Pesta-pesta dan upacara-upacara religius merayakan misteri-miseri hidup Maria dan teladan-teladan orangorang Kudus. Hidup devosional Katolik kerap kali mengambil alih lambang, kebiasaan, pesta, dan upacara dari budaya di mana hidup Gereja sudah diinkulturasikan.2 Merayakan kelahiran pada tanggal 25 Desember mungkin sekali merupakan pengkristenan pesta orang Roma akan kelahiran dewa matahari (Sol Invictus, ”Matahari yang tak tertaklukkan”), pesta itu dijadikan ”Kersmis”, ”Christmas” (Misa Kristus) untuk memperingati kelahiran Putra Allah yang diakui sebagai Terang Dunia. Salib Celtik pada awalnya merupakan lambang kesuburan Eropa. 3 Orang-orang Katolik Italia mengadakan perarakan dengan patung santo/santa pelindung komunitas mereka pada hari raya santo/santa itu. Orang-orang Katolik Meksiko menghormati Santa perawan Maria di Guadalupe; beberapa orang Katolik mengungkapkan devosi mereka dengan berjalan berlutut menuju patung Maria. Orang-orang Katolik Filipina kerap memperagakan kisah penyaliban sebagai bagian dari pelaksanaan puasa mereka pada masa puasa. Sakramen-Sakramen Gereja Konsep sakramentalitas diungkapkan di dalam Perjanjian Baru dan Gereja perdana dengan kata Yunani mysterion, ”misteri”, yang dalam penggunaan sekular berarti ”rahasia” atau ”tersembunyi”. St. Paulus menggunakan kata mysterion untuk melukiskan kebijaksanaan Allah yang penuh misteri yang diwahyukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus (1Kor 2: 7). Dalam Gereja pasca-Perjanjian Baru, kata mysterion digunakan untuk upacara-upacara, lambang-lambang, benda-benda liturgis, berkat-berkat, dan perayaan-perayaan Kristiani. Kata latin untuk kata mysterion adalah sacramentum. Baru pada Abad Pertengahan kata ”sakramen” dibatasi penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan resmi Gereja tertentu. Petrus Lombardus (meninggal pada tahun 1160) dalam bukunya De Sententiis (Buku tentang pendapat-pendapat) membedakan antara ”tujuh sakramen” sebagai penyebab-penyebab rahmat dan ”sakramentalsakramental” lain, yang disebutnya sebagai tanda-tanda rahmat. Jumlah sakramen yang ada tidak amat penting. Orang-orang Kristiani Protestan pada umumnya hanya mengakui dua sakramen saja, Baptis dan Ekaristi, dengan menggunakan norma biblis ketat tentang pendiriannya oleh Yesus historis, yang dewasa ini baik orang Katolik maupun Protestan tidak akan menekankan. Namun sakramentalitas itu sendiri sangat penting. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan yang adalah Roh, dapat kelihatan dan dapat dirasakan di dunia ruang dan waktu kita? Inilah masalah yang diperhatikan oleh teologi sakramental. Teologi sakramental dewasa ini, yang sebagian besar bertumpu pada karya Karl Rahner dan Edward Schillebeeckx, melihat Yesus di dalam pelayanan historis sebagai sakramen Allah yang fundamental.4 Seperti diakui oleh Perjanjian Baru dan tradisi Kristiani selanjutnya, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus dalam penyembuhan orang sakit dan pengusiran setan dari para penderita, penghiburan-Nya terhadap orang-orang yang sedih, penerimaan-Nya atas orang-orang yang tersingkir, dan pemberian pengampunanNya kepada kaum pendosa, dalam perjamuan-Nya bersama para murid, dan cinta kasih istimewa-Nya kepada kaum miskin, dalam kemenangan-Nya atas dosa dan maut, dalam kebangkitan-Nya di sisi kanan Bapa, kasih dan perhatian Allah yang tak terbatas terhadap umat manusia, menjadi kelihatan dan masuk ke dalam sejarah umat manusia. Gereja yang ”dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah” (LG 1) terus membuat kasih dan perhatian itu menjadi tampak di dunia. Sebagai jemaat para murid Yesus, Gereja hidup dari Roh Yesus dan melaksanakan pelayanan-Nya. Dalam mewartakan kedekatan Allah, dalam menyembuhkan, membebaskan, menghibur, mengumpulkan dan mendamaikan, mengurapi dan memberkati serta berbagi roti dan anggur hidup abadi – dalam semua itu pelayanan Yesus terus dibuat tampak di dalam ruang dan waktu. Seperti halnya Yesus adalah sakramen Allah, Gereja adalah sakramen Yesus. Gereja membuat kasih Allah yang diwahyukan dalam Yesus menjadi kelihatan dalam berbagai saat sakramental dan terutama dalam tanda-tanda resmi rahmat yang disebut sakramen. Bagaimana ”kerja” sakramen-sakramen? Sakramen-sakramen menyampaikan rahmat dengan melambangkan, menggabungkan kisah dan tindakan: membasuh dengan air, berbagi roti dan anggur, mengurapi dengan minyak, menumpangkan tangan, mewartakan pengampunan. Sebagai lambang, sakramen-sakramen mengandung banyak nilai dan dapat menyampaikan beberapa arti. Sean McDonagh mengamati bahwa sakramen-sakramen ”mengambil dari unsur-unsur alam – air, makanan, minyak, terang, kegelapan, dan angin”; sakramen-sakramen harus dapat menarik kita keluar dari kepompong yang salah dengan menghubungkan kita kembali dengan Allah dan ciptaan.”5 Sakramen-sakramen harus menjadi lambang yang tulus. Air baptis harus menjadi pembasuhan yang nyata dengan air hidup, bukan hanya beberapa tetes simbolis. Roti Ekaristi harus tampak seperti roti betulan. Ekaristi sendiri merupakan lambang kesatuan, tetapi bagi banyak wanita dewasa ini dialami sebagai lambang penyingkiran diri mereka. Sebagai tanda, sakramen-sakramen kehilangan banyak kekuatannya jika dilaksanakan secara asal-asalan, tanpa rasa hormat dan iman yang penuh harapan. Sebagai tindakan Gereja, sakramen-sakramen mengungkapkan hakikat Gereja sendiri sebagai tubuh Kristus yang hadir di dunia, yang membagikan hidup baru dalam Roh Yesus (baptis), yang mewartakan pengampunan dosa atas nama-Nya (rekonsiliasi), melayani orang sakit (sakramen orang sakit), merayakan cinta pasangan manusia (perkawinan), mewujudkan kepemimpinan dalam jemaat Gereja (tahbisan) dan mengakui kehadiran-Nya kepada umat-Nya sendiri dalam perjamuan Ekaristi (Ekaristi). Sakramentalia Kecuali tujuh sakramen, ada banyak lambang, benda, upacara, dan doa religius yang menjadi ungkapan misteri-misteri Kristiani. Itu disebut ”sakramentalia” yang pada dasarnya merupakan tanda dari yang suci (SC 60). Banyak tindakan merupakan tindakan ritual, yang bila dilakukan memberi kepada iman kita ungkapan tubuh. Pada tindakan-tindakan sakramental itu ada dimensi sosialnya. Karena dilakukan secara publik, sakramentalia menjadi saksi untuk dan mengingatkan orang lain akan kehadiran Allah di tengah manusia. Katolisisme kaya dalam tindakan-tindakan ritual seperti itu. Tanda salib, dengan memberi tanda salib pada diri sendiri dengan mengucap ”demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merupakan pengakuan iman Trinitarian kita. Tanda salib dapat digunakan untuk menandai secara ritual saat awal dan saat akhir doa. Membuat tanda salib dengan air suci mengingatkan rahmat baptis Kristiani, orang tua memberi tanda salib pada dahi bayi ketika bayi itu dibaptis. Menerima abu di dahi pada hari Rabu Abu melambangkan awal masa Puasa. Abu yang melambangkan penyesalan pada zaman Perjanjian Lama (Yun 3:6, Dan 9:3) maupun abu yang menjadi asal-usul kita yang pada suatu saat nanti kita akan kembali, mengingatkan kita akan kematian kita dan membuka diri kita lagi terhadap rahmat Injil. Demikian juga perarakan dengan daun palma pada hari Minggu Palma mengajak kita untuk ikut serta secara lebih pribadi dalam misteri-misteri Minggu Suci. Banyak orang Katolik menyimpan daun palma sampai tahun berikutnya, dengan memasangkannya di bawah salib atau di belakang gambar religius sebagai kenangan mereka menyertai Yesus melalui misteri-misteri kesengsaraan-Nya. Tindakan-tindakan sakramental lain berlutut di depan sakramen Mahakudus, menundukkan kepala pada waktu nama Yesus disebut, berbagi salam damai dalam perayaan liturgi, memberi berkat, menumpangkan tangan dalam doa penyembuhan, dan menyalakan lilin untuk melambangkan kesucian tempat di mana orang berdoa. Dalam budaya Latin, banyak orang Katolik melengkapi tanda salib dengan membuat dan mencium salib kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Salib, lengkap dengan patung tubuh Yesus (corpus), sangat berharga bagi orang-orang Katolik sebagai tanda kasih dan korban penebusan Kristus. Patung-patung religius mengingatkan kita akan Gereja yang telah jaya, persekutuan para Kudus, yang bagi kita menjadi teladan dan pengantara. Sulit untuk membayangkan gereja atau kapel Katolik tanpa patung atau gambar Maria. Ikon, warisan yang sedemikian kaya dalam Gereja Timur, merupakan gambar Kristus, Santa perawan Maria dan para Kudus, yang digayakan, yang mengajak kita untuk merenungkan misteri-misteri yang ditampilkan.6 Masa-masa liturgi seperti Adven, Natal, Puasa, dan Paskah merayakan misteri-misteri keselamatan, yang membuat masa itu menjadi suci. Lilin Paskah, yang dinyalakan pada upacara Malam Paskah, menjadi lambang Kristus yang amat kuat dan lambang terang yang dibawa-Nya dalam hidup kita. Cincin perkawinan mengingatkan pasangan akan janji saling mencintai dan setia. Pakaian-pakaian liturgi, pakaian biara, medali, salib, lilin, air suci, – semua itu merupakan tanda dari Yang Suci, yang hadir dalam waktu dan ruang serta sejarah pribadi. Semua itu mengundang dan memungkinkan kita mengambil bagian dalam dunia roh yang tidak kelihatan. Sakramentalia dapat disalahgunakan. Sakramentalia dapat menjadi sasaran takhyul, seperti membuat tanda salib sebelum menendang bola pinalti di muka gawang lawan. Sakramentalia bukan seperti jimat-jimat, daya sihir yang melindungi pemiliknya. Sakramentalia mengundang kita untuk ikut serta dalam misteri-misteri Kristiani. Jika melibatkan iman kita, sakramentalia dapat membantu kita melihat melampaui permukaan perkara dan mengangkat budi serta hati kita kepada Allah. 2. Sakramen Inisiasi Sakramen inisiasi – Baptis, Penguatan, Ekaristi – melambangkan dan merayakan masuknya orang secara bertahap ke dalam Kristus dan Gereja. Pada Gereja perdana, Baptis dan Penguatan merupakan saat-saat terpisah dalam satu upacara inisiasi Kristiani, yang selesai pada waktu orang-orang Kristiani baru – dibaptis, diurapi dengan minyak, dan diberi pakaian putih – dibawa kepada jemaat, biasanya dilaksanakan pada upacara malam Paskah pada hari Sabtu malam, untuk ikut berbagi dalam Ekaristi untuk pertama kali. Tiga sakramen inisiasi merayakan kenyataan-kenyataan yang paling mendalam dalam hidup orang Kristiani: diperintahkan dengan Kristus, hidup dalam Roh, persatuan dalam tubuh-Nya, Gereja. Baptis Kata ”baptis” berasal dari kata Yunani baptizo, yang digunakan dalam upacara pencucian atau pembasuhan. Dalam Kristianitas zaman sekarang ini, baptis kerap kali dimengerti sebagai sakramen untuk bayi yang membersihkannya dari noda dosa asal. Akan tetapi, pengertian itu menyempitkan simbolisme sakramen baptis yang kaya menjadi satu dimensi saja. Baptis terutama merupakan sakramen bagi orang dewasa. Baptis merupakan tanggapan iman pribadi terhadap sabda yang telah dikhotbahkan (Kis 8:26–40). Gereja-Gereja yang terus membatasi baptis pada orang dewasa (baptis orang beriman) merupakan peringatan terhadap Gereja lain mengenai fakta itu. Dengan baptis, kita dimasukkan ke dalam Kristus. St. Paulus berkata bahwa kita dibaptis dalam kematian Kristus (Rm 6:3), secara mistik dipersatukan ke dalam kesengsaraan-Nya supaya kita dapat bangkit bersama-Nya. ”Baptis dalam kematian Kristus” berarti pengampunan dosa. Mereka yang dibaptis telah dicuci, disucikan, dan dibenarkan dalam nama Yesus dan dalam Roh (1Kor 6:11). Pada waktu yang sama, dipersatukan dengan Kristus berarti dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, Gereja (1Kor 12:13) dan menerima hidup baru dalam Roh (Yoh 3:5). Dalam teks yang amat awal dengan implikasi eklesial yang penting, St. Paulus menyatakan bahwa dengan baptis kita ”mengenakan” Kristus (yang dalam Gereja perdana dilambangkan dengan memberi kepada mereka yang dibaptis pakaian putih) sejauh kita menjadi bagian dari umat baru yang mengatasi perbedaan ras, status sosial, dan jenis kelamin. ”Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal 3:28). Bagaimana kita dapat lebih memaknakan baptis di dalam pengalaman hidup kita? Bagaimana baptis ”melaksanakan” perubahannya? Baptis menyatukan kita dengan Kristus justru karena baptis memasukkan kita ke dalam Gereja. Meski Roh tidak dibatasi oleh struktur Gereja, namun Gerejalah yang mengantarai Yesus yang telah bangkit dengan kita. Hanya melalui Gerejalah – jemaat melanjutkan pewartaan Injil, merayakan sabda dan upacara misterimisteri hidup-Nya, melanjutkan pelayanan-Nya yang penuh belas kasih – kita dapat mengenal siapa Yesus itu dan mengenal kehadiran-Nya. Terlepas dari jemaat yang beriman, Kitab Suci paling-paling hanya menjadi kisah-kisah saleh. Baptis memungkinkan hidup baru, hidup di dalam ”Roh” atau hidup ”rahmat” justru dengan membawa orang ke dalam jemaat baru di mana para anggotanya berusaha menghayati dalam hidup mereka misteri Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Orang-orang yang sudah dibaptis telah mati terhadap dosa dan berusaha mencontoh cinta Yesus yang penuh kasih dan pengorbanan diri dalam hidup mereka. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak pernah gagal atau bahwa cita-cita hidup dalam Yesus kadang-kadang tak pernah menjadi kendor. Akan tetapi, keterlibatan mereka pada Gereja merupakan lambang dari keinginan mereka untuk hidup dalam Roh Yesus. Secara teologis, Roh itu adalah Roh Ilahi yang dicurahkan pada para murid Yesus melalui kematian dan kebangkitan, Roh kebenaran, yang memberi kesaksian tentang Yesus di dalam hati kita (Yoh 15:26). Berdasarkan pengalaman, kita dapat mengenal kehadiran Roh melalui dampak-dampak atau buah-buah kehidupan para anggota jemaat. St. Paulus menyebut buah-buah Roh seperti ”kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri (Gal 5:22–23). Kita tidak selalu menangkap pentingnya hidup dalam jemaat beriman, karena, meski dewasa ini banyak dibicarakan tentang ”hubungan”, kita tidak secara sunguh-sungguh memperhatikan jaringan hubungan-hubungan yang membentuk hidup kita. Namun, siapa saja yang pernah mengalami jatuh cinta tahu dari pengalaman betapa kreatif dan menggairahkan hidup sebuah hubungan itu berlangsung. Hubungan-hubungan yang baik memberdayakan kita. Bila kita dicintai, seluruh dunia tampak berbeda; kita menemukan kebebasan baru untuk menjadi diri sendiri maupun rasa sejahtera dan aman yang membuat kita mampu berusaha menyelesaikan hal-hal yang tanpa rasa dicintai tak pernah berpikir mampu kita lakukan. Demikian juga, hubungan-hubungan yang negatif dapat membuat orang melawan kita, dengan membuat mereka marah dan pahit. Kerap kali mereka melakukan hal yang mengakibatkan kerugian seumur hidup. Kita tahu betapa pentingnya anak tumbuh dalam keluarga di mana ia dikasihi dan disayangi, dan betapa berbeda perkembangan anak yang lingkungannya merusak. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, keamanan, dan hubungan dengan orang-orang lain yang diperlukannya, tumbuh lemah seperti bunga tanpa tanah dan air yang baik. Mungkin seumur hidup ia akan berusaha mencari kompensasi, dengan susah payah mencari afeksi dan persetujuan, kerap dengan cara yang tidak tepat. Kerap kali pengalaman tidak mendapatkan cinta kasih dan keamanan yang dibutuhkan atau luka batin yang dialami beberapa tahun kemudian meledak dalam bentuk permusuhan dan amarah, dan anak yang diperlakukan buruk tidak jarang menjadi orang dewasa yang suka memperlakukan sesamanya dengan buruk pula. Orang dewasa pun membutuhkan komunitas yang mendukung, jika saja mereka hendak dibantu untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kita juga tahu betapa sulitnya menjalani hidup bergaya sederhana dalam budaya konsumeristik yang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan oleh iklan, menghargai kemurnian dalam masyarakat yang meremehkannya, dan mempertahankan integritas dalam lingkungan bisnis di mana ”setiap orang melakukannya”. Betapa lebih memberdayakanlah hidup dengan pria dan wanita yang berusaha hidup sebagai murid Yesus, membentuk hidup mereka berdasarkan Injil. Hidup seperti itu membantu kita melihat kemungkinan-kemungkinan baru, untuk mendapatkan dukungan guna usaha-usaha baru, dan mampu menjalani macam hidup yang lain. Secara teologis, jemaat yang disebut Gereja berbagi dengan kita, Roh yang menghidupinya, Roh Yesus atau ”Rahmat”. Roh itu mengatasi kekuatan-kekuatan negatif dan kepentingan diri yang kita sebut dosa asal, dengan membuat kita mampu untuk menjalani hidup baru, untuk bangkit kembali manakala kita jatuh, dan untuk menerima dan memberi maaf satu sama lain. Hidup dalam Roh ini berarti bahwa dalam arti yang sebenarnya, kita ikut ambil bagian dalam hidup Tritunggal, atau bahwa Allah tinggal di dalam diri kita dengan berbagi hidup dan kasih melalui Roh. Jika rahmat baptis diharapkan menjadi efektif dalam hidup orang yang dimasukkan ke dalam jemaat Gereja, maka makin menjadi jelaslah mengapa tidak banyak maknanya merayakan sakramen baptis bagi anak yang orang tuanya tidak menjalankan dan tidak mau menjalankan imannya. Dalam baptis, yang asal-asalan seperti itu, betapapun baiknya orang tua, bila tidak ada komunitas kaum beriman yang menerima anak itu di lingkungannya, tidak ada ”Gereja keluarga” guna mengungkapkan dan memupuk iman anak selama masa pertumbuhannya. Sakramen-sakramen bukanlah upacara magis. Sakramen-sakramen tidak bekerja ”secara otomatis”, lepas dari kerja sama kita. Sebagaimana pepatah teologi menyatakan, rahmat mengembangkan kodrat. Sayangnya, baptis asal-asalan banyak dipraktekkan dewasa ini, dengan akibat, baptis menjadi upacara inisiasi kultural daripada perayaan sakramental masuknya orang ke dalam kehidupan baru dalam Kristus. Penguatan Kadang-kadang dikatakan bahwa penguatan adalah sakramen yang masih mencari teologi. Pada awalnya tanda penguatan, pengurapan dengan minyak yang disertai dengan penumpangan tangan, merupakan bagian perayaan baptis. Masih dipraktekkan di Gereja Timur, di mana urutan inisiasi Kristiani – Baptis, Penguatan, Ekaristi – masih dipertahankan. Bahkan anak-anak dibaptis, diurapi dengan minyak, yang oleh umat Ortodoks disebut: ”Chrismatio” dan diberi Ekaristi, biasanya dengan sendok yang dicelupkan dalam anggur yang telah dikonsekrasikan. Pelayan biasa yang menerimakan penguatan di Timur masih imam biasa. Akan tetapi, di Gereja Barat, pengurapan sesudah baptis biasanya dilakukan oleh uskup. Ketika Gereja tumbuh dan tersebar di daerah-daerah pedesaan dan jumlah calon baptis bertambah, uskup tidak selalu hadir pada pembaptisan. Lama-kelamaan penguatan menjadi upacara yang terpisah. Meskipun uskup tetap menjadi pelayan penguatan yang asli dan biasa, imam diberi kuasa untuk memberikan penguatan pada waktu membaptis atau menerima orang dewasa dalam Gereja. Apa arti penguatan? Penguatan hendaknya jangan dimengerti terutama sebagai pemberian Roh, karena Roh diberikan bersama baptis dan sesungguhnya sudah aktif menarik orang kepada Kristus sebelum baptis. Sakramen penguatan juga jangan dimengerti sebagai sakramen kedewasaan Kristiani. Meskipun demikian, St. Thomas Aquinas mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa penguatan adalah sakramen kedewasaan spiritual yang mempersiapkan orang untuk berperang melawan musuh-musuh iman. ”Penamparan ringan pada pipi” zaman pra-Vatikan II mencerminkan teologi itu. Sementara itu, teolog dewasa ini melihat penguatan sebagai sakramen yang mengungkapkan keterbukaan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Pastilah penguatan merupakan perayaan hidup dalam Roh Yesus, dan masih benar bagi banyak orang Kristiani Barat yang dibaptis pada masa bayi, penguatan dialami sebagai saat sakramental di mana keterlibatan yang dulu dibuat oleh orang tua mereka pada waktu mereka masih bayi, mereka teguhkan sebagai keterlibatan mereka sendiri. Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 menyatakan agar penguatan diberikan pada waktu anakanak ”mencapai umur nalar” (Kan. 891), meski kodeks memberi keleluasan besar kepada para uskup dalam hal penetapan waktu penerimaan sakramen penguatan. Dewasa ini di negeri kita, sakramen penguatan diberikan kepada anak-anak umur 10-an tahun atau kelas IV – VI SD. Karena sakramen penguatan berarti kesanggupan sebagai orang yang mengikuti Yesus, sebagai orang Kristiani, bagi anak-anak yang dibaptis pada masa bayi, tepatlah bahwa sakramen penguatan itu diberikan pada waktu anak-anak sudah sadar akan arti hidup dan arti hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, anggota Gereja. Ekaristi Ekaristi merupakan ”kegiatan ibadat Gereja yang sentral” dan perayaan kesatuannya dalam Yesus yang sudah bangkit yang menjadi sumber hidupnya.7 Dalam tradisi Kristiani, Ekaristi disebut dengan beberapa nama: korban Misa, Perjamuan Tuhan, Ibadat Ilahi, Komuni Kudus. Menurut Konsili Vatikan II, korban Ekaristi ”merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani” (LG 11). Asal-usul Ekaristi amat kompleks. Dalam Kitab Suci Yahudi, gambaran tentang perjamuan eskatologis tampak sebagai tanda kesatuan dengan Allah pada zaman keselamatan mesianis (Yes 25:6). Yesus menggunakan gambaran ini dalam perumpamaan-Nya tentang Kerajaan Surga (Mat 8:11; Luk 14:15–24). Pastilah tradisi makan bersama dalam pelayanan Yesus, makan yang Ia bagi bersama murid-murid-Nya dan orang-orang lain, termasuk ”pemungut cukai dan pendosa”, merupakan bagian dari sejarah Ekaristi, sebagai perjamuan terakhir yang Yesus adakan bersama murid-murid-Nya pada malam sebelum wafat. Sesudah wafat-Nya, muridmurid-Nya melanjutkan berkumpul untuk memecah roti dan berbagi piala untuk mengenang Dia. Dalam pemecahan roti dan berbagi piala itu, mereka mengenal-Nya hadir bersama mereka dengan cara baru. Inilah inti cerita dua murid di jalan ke Emaus yang mengenal Yesus yang telah bangkit ”pada waktu Dia memecah-mecah roti” (Luk 24:35; bdk. Kis 10:41; Yoh 21:12). Ada kesinambungan dalam makan bersama Yesus selama pelayanan-Nya, pada waktu perjamuan terakhir, dalam makan bersama para murid sesudah Paskah, dan dalam Ekaristi Gereja. Susunan liturgi Ekaristi terdiri dari Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi. Liturgi Sabda diambil dari ibadat sinagoga Yahudi, yang terdiri dari Doa Pembukaan, 2 Bacaan Kitab Suci (satu dari kitab hukum, dan satu lagi dari kitab Nabi-Nabi), yang diikuti dengan homili atau perenungan dan beberapa doa (bdk. Luk 4:16–21). Liturgi Ekaristi atau perjamuan Tuhan dirayakan dalam konteks makan bersama dalam jemaat-jemaat paling awal, meskipun pemisahan antar kedua hal itu sudah terjadi pada zaman St. Paulus. St. Paulus menegur umat Korintus karena perjamuan Ekaristi mereka yang tidak pantas dengan mengatakan kepada para anggota jemaat agar mereka makan saja di rumah (1Kor 11:12,34). Seperti berlian, Ekaristi merupakan realitas yang mempunyai banyak segi. Ekaristi memancarkan misteri penyelamatan Allah dalam Yesus dengan berbagai cara. Ekaristi adalah perjamuan sakramental, kesatuan dalam tubuh dan darah Kristus, kenangan akan kematian dan kebangkitan-Nya, doa syukur, korban dan tanda kerajaan. Perjamuan Sakramental Pertama-tama Ekaristi adalah perjamuan sakramental. Tanda atau lambang Ekaristi adalah tindak sakramental berbagi roti yang sudah dipecah-pecah dan piala yang sudah diberkati untuk mengenangkan Yesus. Paulus mendasarkan kesatuan jemaat sebagai satu tubuh Kristus dalam berbagi atau ikut serta dalam tubuh dan darah Ekaristis Kristus: ”Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu” (1Kor 10:16–17). Dalam berbagi roti dan anggur Ekaristi itulah, jati diri Gereja menjadi lebih penuh yaitu tubuh Kristus di dunia. Tanda Kerajaan Dengan didamaikan satu sama lain dalam Yesus Kristus, disatukan dalam tubuh-Nya, orang-orang Kristiani menjadi tanda yang mengantisipasi dan menunjukkan kesatuan semua umat manusia. Dengan cara itu, Ekaristi merupakan tanda kerajaan. Doa indah dari Didache atau ”ajaran 12 Rasul”, kumpulan pengajaran mengenai moralitas dan tata tertib Gereja yang ditulis sekitar tahun 100 SM mengungkapkannya secara puitis ”Sebagaimana roti yang dipecah- pecah ini dulu tersebar di puncak-puncak gunung dan sesudah dipanen dijadikan satu, demikian juga biarkanlah Gereja-Mu dikumpulkan dari ujung-ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu” (9.4). Dengan demikian Ekaristi merupakan sakramen perdamaian yang paling mendasar dan memanggil masing-masing di antara kita untuk menjadi tanda perdamaian di dunia yang terpecah-pecah. Perpecahan di dalam Gereja, entah didasarkan atas status ekonomi, ras, jenis kelamin, atau kedudukan sosial, merusak kenyataan sakramental jemaat Ekaristis; seperti dikatakan oleh St. Paulus, membiarkan atau mendatangkan perpecahan dalam jemaat adalah berdosa melawan Tubuh dan Darah Tuhan (1Kor 11:17–30). Sebagai kenangan (anamnesis) kematian dan kebangkitan Yesus, Ekaristi merupakan jaminan kebangkitan kita sendiri. Banyak orang Kristiani mengalaminya di dalam perayaan Ekaristi, terutama dalam perayaan Misa Pemakaman sebagai bagian liturgi penguburan. Di sini terutama kesatuan kita dengan Kristus yang sudah bangkit merupakan lambang yang amat kuat dari harapan kita akan hidup abadi. Doa Syukur Ekaristi juga merupakan doa Syukur Agung Gereja (dalam bahasa Yunani eucharistia berarti ”ucapan syukur”). Pimpinan Ekaristi mengajak umat untuk mengucap syukur bersamanya dalam dialog pembukaan dalam prefasi dan kemudian berdoa atas nama mereka, dengan bersyukur kepada Allah karena karya-karya agung penciptaan, penebusan dan mengenang terutama penyerahan diri Yesus sebelum Dia wafat, kematian dan kebangkitanNya dan pemberian Roh Kudus. Pemimpin ibadat menyeru Roh Kudus atas persembahan roti dan anggur Ekaristi dan atas umat (epiclesis) dan mendoakan doksologi penutupan, yang dijawab oleh umat ”Amin” yang menjadikan doa itu menjadi doa mereka sendiri. Pengenangan atas korban Kristus Orang-orang Katolik secara tradisional menyebut Ekaristi sebagai ”korban Misa”. Dimensi korban Ekaristi dikenal awal abad ke-2, karena Didache berbicara tentang Ekaristi sebagai korban (14.1–3). Melalui pengkisahan dan upacara, Doa Ekaristi menghadirkan atau mengenang korban Kristus di salib, sehingga dalam arti yang sesungguhnya ibadat Ekaristi Gereja menghadirkan penyerahan diri Kristus kepada Allah. Konsep anamnesis atau pengenangan merupakan hal yang sangat penting di sini. Dalam bahasa yang lebih tradisional, orang-orang Katolik telah menggambarkan Ekaristi sebagai pengulangan korban salib ”dengan cara yang tidak berdarah”. Teologi zaman ini kadang-kadang membicarakan Ekaristi sebagai sakramen korban Kristus, dengan membuat korban Kristus secara sakramental,dan oleh karena itu nyata, hadir dalam ibadat Gereja. Kehadiran Nyata Apa yang disebut oleh orang-orang Katolik sebagai ”kehadiran nyata” Kristus dalam roti dan anggur Ekaristi telah dikenal sejak zaman Perjanjian Baru (bdk. Yoh 6:52–60). Akan tetapi, cara mengungkapkan ajaran ini dalam bahasa teologi merupakan masalah yang sulit. Sejak abad ke-2, teologi Kristiani telah berbicara tentang ”perubahan roti dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Bahasa ”transubstansi” digunakan pada Abad Pertengahan untuk menyatakan bahwa sementara rupa roti dan anggur (”spesies”) tetap sama, substansi dari keduanya sungguh-sungguh berubah. Melalui tindakan Roh Kudus dalam liturgi, roti dan anggur menjadi tanda sakramental kehadiran Kristus. Kedua benda itu bukan lagi roti dan anggur melainkan Tubuh dan Darah Kristus. Akan tetapi, bahasa yang tampaknya amat harfiah ini masih mengakui bahwa kehadiran Kristus bukanlah bersifat fisik. Kehadiran itu bersifat sakramental. Maksudnya, Kristus yang telah bangkit hadir dalam tindak sakramental, bukan dalam tubuh dan darah tersendiri yang dimengerti dalam arti fisik tetapi dalam arti pribadi, dalam kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Jika bahasa Katolik tradisional kadang-kadang berbicara tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi dengan cara yang amat harfiah, orang-orang Katolik sudah lama diajar bahwa menerima ”satu rupa” bukanlah menerima hanya Tubuh atau hanya Darah Kristus tetapi keduaduanya, Tubuh dan Darah Kristus. Menerima roti atau anggur adalah berjumpa dan menerima Yesus yang sudah bangkit. ”Tubuh Kristus yang diberikan kepada orang-orang Kristiani dalam roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan bukanlah sesuatu melainkan seseorang. Dalam Ekaristi, Kristus hadir bukan sebagai ’objek’ yang dikagumi, tetapi sebagai ’subjek’ yang harus dijumpai”.8 Devosi Ekaristi Sejak abad-abad awal, roti Ekaristi yang dikonsekrasikan disimpan di sakristi untuk komuni orang sakit, tetapi tidak ditampilkan secara jelas dalam Gereja sampai Abad Pertengahan. Mulai abad ke-11 ”ibadat kehadiran Ekaristis Kristus menjadi populer. Astuti, Pentahtaan Sakramen Mahakudus atau Benedictio merupakan salah satu ungkapannya. Konsili Trente pada abad ke-16 memerintahkan agar ditempatkan tabernakel di altar pusat setiap gereja. Sesudah pembaruan liturgi Konsili Vatikan II, sudah menjadi biasa untuk menyimpan Ekaristi untuk doa pribadi di tempat khusus terpisah dari altar atau malah di ruang tersendiri. Ungkapan devosi Ekaristis Katolik meliputi perayaan Ekaristi setiap hari, ”kolosanto”, ”tuguran”, prosesi ”Corpus Christi” dan kunjungan ke Sakramen Mahakudus. Konsili dan pembaruan liturgi yang mendahuluinya telah menekankan sentralitas liturgi Ekaristi dalam hidup Gereja dan pentingnya keikutsertaan penuh dalam liturgi itu dengan menerima Komuni Kudus. Ini telah mengakibatkan pergeseran dari devosi kepada Sakramen Mahakudus terlepas dari misa ke keikutsertaan secara penuh di dalam liturgi. Demikian juga, ajaran sesudah Konsili menekankan bahwa ibadat Ekaristi di luar Misa harus selalu dikaitkan pada perayaan Misa yang menjadi pusatnya. Di banyak tempat, penekanan ini telah mengurangi praktek Astuti atau pentahtaan Sakramen Mahakudus. Pada waktu yang bersamaan, menarik untuk dicatat bahwa sejumlah komunitas Kristiani dewasa ini seperti Arche, suster-suster Misionaris Caritas, Bruder dan Suster Kecil Yesus mengadakan doa kontemplasi di hadapan Sakramen Mahakudus sebagai bagian biasa dari spiritualitas mereka.9 Kunjungan ke Sakramen Mahakudus pun tetap merupakan ungkapan devosi Ekaristis Katolik yang penting. Interkomuni Hal yang amat menyedihkan dewasa ini adalah ketidakmampuan untuk ikut serta dalam Ekaristi karena perpecahan di dalam Gereja. Masalah hospitalitas Ekaristi, atau interkomuni sendiri sudah bersifat memecah belah. Bagi banyak orang Protestan, interkomuni sendiri merupakan tanda kesatuan yang berkembang dan sarana untuk pemenuhannya. Mereka menekankan bahwa Tuhanlah yang memanggil orang-orang beriman yang sudah dibaptis ke satu meja makan dan tak ada Gereja yang membatasinya. Gereja Roma dan Ortodoks mengambil pandangan yang berbeda dengan berpendapat bahwa komuni Ekaristi merupakan tanda kesatuan yang sudah ada dalam iman, tradisi apostolik, dan hidup Gereja. Menurut buku Petunjuk Ekumene (Ecumenical Directory) Katolik Roma yang baru (1993), interkomuni diperbolehkan hanya dengan syarat-syarat tertentu yang terbatas. Berteman dengan Gereja-Gereja Timur, pada prinsipnya ikut serta dalam Ekaristi dimungkinkan, meski memberi peringatan kepada orang-orang Katolik bahwa Gereja-Gereja itu kerap mempunyai disiplin yang lebih membatasi dan harus dihormati. Karena alasan-alasan keperluan atau manfaat spiritual yang sejati, orang-orang Katolik dapat mendatangi pelayan suatu Gereja Timur untuk mendapatkan sakramen Ekaristi, pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit. Pelayan Katolik pun dapat memberi sakramen-sakramen itu kepada anggota suatu Gereja Timur yang memintanya. Hal itu harus diatur dengan baik, dan menghindari kesan pemertobatan. Peraturan-peraturan untuk menerima orang-orang dari Gereja-Gereja dan jemaat-jemaat lain jauh lebih keras. Pelayan Katolik dapat memberikan sakramen-sakramen itu kepada orangorang non-Katolik bila ada bahaya maut atau kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan syaratsyarat berikut: orang yang bersangkutan tidak mampu mendapatkan pelayan sakramen dari Gereja atau jemaatnya dan bahwa ia minta pelayanan sakramen dan menampakkan iman Katolik dan sikap yang sesuai untuk menerima sakramen itu. Orang Katolik yang ada dalam keadaan yang sama, hanya boleh meminta Gereja lain kepada pelayan sakramen-sakramen yang sah atau dari pelayan yang diketahui ditahbiskan secara sah menurut ajaran Gereja tentang pentahbisan ” (No. 132). Waktu untuk memulihkan kesatuan Ekaristis yang penuh tampaknya belum ada. Sementara kemajuan besar pada tingkat teologis dalam dialog-dialog ekumenis, pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati bersama yang dihasilkan belum diterima oleh Gereja-Gereja yang bersangkutan. Juga jika Gereja-Gereja diharapkan berbagi dalam misi bersama, Gereja-Gereja itu harus menemukan jalan untuk bekerja sama secara efektif dalam bidang-bidang otoritas mengajar dan kegiatan sosial, hal yang belum mampu dikerjakan. Pada waktu yang bersamaan, dapat dipertanyakan apakah Gereja Katolik tidak perlu menemukan jalan agar menjadi lebih fleksibel, luwes. ”Berbagi dalam komuni tidak pada tempatnya bila tidak ada pemahaman bersama tentang sakramen dan tidak ada keikutsertaan bersama yang nyata dalam kehidupan Gereja. Akan tetapi pemahaman tentang sakramen dan keikutsertaan dalam kehidupan Gereja itu sekarang ini merupakan kenyataan yanag semakin besar melintasi batas-batas Gereja/denominasi formal”.10 Gerakan liturgi sudah mengakibatkan penghargaan yang diperbarui terhadap Ekaristi di banyak Gereja, dan sedikit orang Katolik dewasa ini akan mengajukan pertanyaan tradisional ”sahnya” perayaan Ekaristi di GerejaGereja lain bila perayaan-perayaan itu mencerminkan iman Ekaristi mereka. Disiplin Gereja Katolik yang ada pada saat ini tampaknya tidak sejalan dengan teologinya sendiri. Dekrit Konsili Vatikan II tentang ekumenisme mengajarkan bahwa ”Kebersamaan merayakan sakramensakramen janganlah dianggap sebagai upaya yang boleh digunakan secara acak-acakan untuk memulihkan kesatuan umat Kristen. Namun rahmat yang dapat diperoleh kadang-kadang menganjurkannya” (UR 8). Beberapa ekumenis Katolik dewasa ini menyatakan bahwa interkomuni tertentu sebaiknya diperbolehkan, misalnya, dalam nikah campuran dalam komunitas ekumenis yang tetap di mana iman Ekaristi dimiliki bersama. Hospitalitas Ekaristi dalam situasi-situasi seperti itu dapat menjadi sarana untuk kesatuan dan merupakan tanda harapan untuk masa depan. 3. Upacara Inisiasi Kristiani Bagaimana orang menjadi anggota Gereja? Dalam Gereja awal, orang dewasa secara sakramental menjadi anggota Gereja hanya sesudah menyelesaikan proses persiapan dan pengajaran yang dikenal dengan nama ”katekumenat” (dari kata Yunani catechesis, yang berarti ”pengajaran”), yang dapat berlangsung selama 3 tahun. Hal yang pokok dalam proses itu adalah keputusan pribadi, bebas untuk baptis. Keputusan ini mengandaikan pertobatan kepada Kristus, yang diuji oleh orang itu dan ditegaskan oleh jemaat selama proses katekumenat. Setiap calon, atau ”katekumen”, mempunyai seorang wali/pendamping, (sponsor) seorang anggota jemaat yang membantu membimbingnya dengan doa, berbagi iman secara pribadi, dan pengajaran. Pada awal proses, calon-calon diperkenalkan pada uskup dan jemaat, dan nama mereka dicatat dalam buku baptis. Pada hari-hari Minggu mereka hadir dalam ibadat liturgis, terutama untuk pengajaran yang terjadi dalam homili, meski mereka secara formal dipersilakan meninggalkan upacara liturgi sebelum liturgi Ekaristi. Selama minggu-minggu terakhir sebelum Paskah diadakan persiapan intensif untuk inisiasi sakramental calon. Mereka diuji dengan berbagai pertanyaan atau ”penyelidikan”, dan mereka menyiapkan diri dengan doa dan puasa. Persiapan akhir untuk pesta Besar Paskah ini dalam perjalanan waktu menjadi masa liturgi Puasa. Akhirnya, pada waktu jemaat berkumpul untuk merayakan Malam Paskah, sesudah menyatakan menolak setan, calon-calon dibaptis, diurapi dengan minyak, diberi pakaian jubah, dan dibawa kepada jemaat untuk ikut serta dalam Ekaristi untuk pertama kalinya. Upacara inisiasi Kristiani kuno merupakan peziarahan rohani yang nyata, yang ditandai dengan tahap-tahap simbolis seperti pencatatan nama calon-calon di dalam buku baptis, pengusiran setan, pemeriksaan oleh uskup dan akhirnya pemasukan secara sakramental ke dalam Gereja. Sayangnya, upacara mulai berkurang maknanya sesudah Dekrit Milan oleh Konstantinus pada abad ke-4 mengakhiri pengejaran orang-orang Kristiani di Barat dan memberi toleransi kepada Gereja. Sesudah tonggak dalam sejarah Gereja ini, jumlah orang yang minta baptis bertambah luar biasa, dan pembaptisan bayi semakin menjadi kebiasaan. Lambat laun, proses katekumenat yang kaya disempitkan menjadi satu unsur saja, yaitu pengajaran. Sebelum Konsili Vatikan II, orang yang ingin menjadi anggota Gereja dapat diajar secara privat oleh imam atau mengikuti kelas ”penyelidikan”. Teks dasarnya biasanya adalah katekismus. Akan tetapi, tekanan pada doa pribadi, pertumbuhan rohani, penegasan bersama, dan perayaan ritual dari proses upacara inisiasi kebanyakan menghilang. Mungkin salah satu pembaruan liturgi Konsili Vatikan II yang paling berarti adalah pengembalian katekumenat ke upacara Inisiasi Kristiani bagi Orang Dewasa (IKOD) tahun 1972. Dengan upacara baru itu, inisiasi Kristiani sekarang dimengerti sebagai suatu proses dari lima tahap yang pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu satu tahun atau lebih. Prakatekumenat Tahap pertama adalah masa orang mulai mencari kemungkinan untuk bergabung ke dalam Gereja. Tahap pertama adalah saat pertobatan sejati terjadi dalam hidup orang itu. Pada tahap pertama dapat terjadi dialog dengan Gereja, kerap melalui teman-teman yang imannya telah membangkitkan minat orang itu dalam hidup Kristiani. Teman-teman itu dapat memperkenalkannya pada hidup dan ajaran Gereja. Katekumenat Tahap kedua adalah untuk pengajaran resmi atau katekese, doa, dan penegasan. Katekumenat dimulai dengan upacara penerimaan yang dirayakan dengan pertemuan liturgi seluruh jemaat, biasanya pada hari Minggu pertama Masa Adven. Setiap calon diperkenalkan kepada jemaat oleh walinya/pendamping, dan jemaat berjanji untuk membantu keinginan calon untuk mengenal Yesus. Kitab Suci yang diwartakan dalam liturgi seharusnya memainkan peranan penting dalam proses katekumenat, demikian juga walinya, ia menjadi sahabat rohani dan ikut serta dalam peziarahan para calon. Masa Pembersihan dan Penerangan Bagian terakhir dari masa katekumenat sendiri dimulai dengan upacara pemilihan yang biasanya dirayakan pada hari Minggu pertama dalam Masa Puasa. Para calon dipersilakan maju ke depan sesudah homili, ditanyai maksud mereka, dan secara resmi diterima dalam kelompok ”orang terpilih”. Para calon memperdalam persiapan mereka selama masa itu. Menurut tradisi kuno Gereja, bacaan Injil untuk Minggu ke-3, 4, 5 dalam masa Puasa adalah kisah wanita Samaria (Yoh 4), penyembuhan orang buta sejak lahir (Yoh 9), dan pembangkitan Lazarus (Yoh 11), dengan tema air, terang, dan hidup. Inisiasi Sakramental Masa pembersihan dan penerangan memuncak dengan sakramen inisiasi sendiri, baptis, penguatan dan Ekaristi, yang biasanya dirayakan sebagai bagian upacara Malam Paskah. Katekese sesudah Baptis (Mystagogy) Tahap akhir inisiasi Kristiani dimaksudkan untuk melanjutkan penyatuan orang-orang yang baru dibaptis ke dalam kehidupan Gereja. Mereka yang secara sakramental telah dimasukkan ke dalam misteri-misteri Kristiani, perlu memperdalam pemahaman mereka atas misteri-misteri itu untuk hidup mereka sendiri. Katekese sesudah baptis dapat dilaksanakan selama masa Paskah dan selanjutnya. Upacara inisiasi Kristiani bagi orang dewasa (IKOD) berusaha menjadi cara yang lebih holistik untuk menginisiasikan orang ke dalam Gereja. Inisiasi bukan hanya pengajaran katekese tetapi harus meliputi doa, renungan bersama, dan penegasan. Inisiasi tidak dimaksudkan menjadi proses yang kaku melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhankebutuhan masing-masing calon. Dewasa ini IKOD yang baik dapat merangkum orang yang belum dibaptis dan orang-orang Kristiani yang telah dibaptis yang sudah minta menjadi anggota Gereja Katolik. Daripada menyebut orang Kristiani itu sebagai ”orang yang bertobat” lebih baik menyebut mereka sebagai orang yang minta masuk ke dalam jemaat secara penuh dengan Gereja Katolik, karena mereka telah bersatu dengan Gereja melalui baptis mereka (bdk. UR 3). Dewasa ini dapat terjadi bahwa orang-orang Katolik dibaptis bayi tetapi belum pernah menerima komuni pertama, biasanya karena orang tua mereka tidak menjalani iman mereka. Dengan demikian inisiasi Kristiani mereka tidak pernah lengkap. Perayaan IKOD harus membedakan antara mereka yang minta baptis dan mereka yang telah dibaptis. Mereka yang minta baptis akan menerima tiga sakramen inisiasi. Mereka yang minta diterima penuh ke dalam kesatuan dengan Gereja Katolik mengucapkan syahadat iman, karena baptis dalam Gereja-Gereja lain diakui sah dan tidak perlu diulang (kecuali ada alasan untuk mempertanyakan bentuk atau maksud baptis aslinya). Jika mereka berasal dari jemaatjemaat Gereja Reformasi abad 16, pembaptisan mereka harus diberi penguatan karena belum ada kesepakatan dengan jemaat-jemaat itu tentang makna dan hakikat sakramen penguatan. Mereka yang inisiasi Kristianinya terputus menerima penguatan bersama calon-calon lain, dan menerima komuni untuk pertama kalinya. Meski uskup adalah pelayan biasa untuk penguatan, pastor atau imam yang memimpin Misa Malam Paskah memberi penguatan sebagai bagian dari proses inisiasi. 4. Kesimpulan Kristianitas bukanlah agama dunia seberang sana. Kristianitas tidak meremehkan dunia material tetapi melihatnya sebagai jejak-jejak Yang Ilahi. Allah ditemukan di dalam kedalaman umat manusia, dalam hubungan-hubungan pribadi dan keluarga, pada saat-saat keharuan dan kerinduan untuk kesatuan, dalam menghadapi misteri kejahatan dan penderitaan, dalam pengalaman kegembiraan cinta dan persahabatan, berkurangnya umur, dan maut yang tak mungkin dihindari. Justru dalam dan melalui kenyataan-kenyataan yang amat manusiawi itu hidup Kristiani harus dijalani. Orang-orang Katolik memandang dunia ini dengan cara yang secara mendalam dipengaruhi oleh imajinasi atau penggambaran sakramental. ”Dunia dipenuhi oleh keagungan Allah”, kata Gerard Manley Hopkins.11 Imajinasi sakramental mengenal kehadiran Allah yang penuh misteri yang tercermin dalam keajaiban-keajaiban alam dan dalam upacara-upacara serta seni religius yang mengungkapkan iman. Imajinasi sakramental melihat dalam sakramensakramen, rahmat dan kehadiran Allah yang menjadi tampak dalam jemaat Kristiani ketika membagikan hidup baru dalam Roh Yesus, menyatakan pengampunan dosa, berdoa bagi orang sakit, merayakan cinta yang setia dalam perkawinan dan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Orang-orang yang minta baptis dan diterima masuk ke dalam Gereja kerap tertarik ke Gereja karena telah merasakan kehadiran Ilahi dalam hidup jemaat itu dan iman para anggotanya. Upacara inisiasi Kristiani berarti ikut ambil bagian dalam iman itu melalui doa dan penegasan, melalui renungan atas Kitab Suci yang dimaklumkan dan didengarkan dalam umat, melalui berbagi tentang peziarahan iman dengan orang-orang lain, dan akhirnya merayakannya dalam Baptis, Penguatan, dan Ekaristi. Ekaristi ada di pusat dalam pemahaman orang Katolik tentang Gereja. Kebanyakan orang Katolik merasakannya, bahkan jika mereka tidak selalu dapat menjelaskan mengapa demikian atau apa persis artinya. Mereka telah dibentuk secara mendalam oleh pengalaman kesatuan dengan Yesus yang sudah bangkit dan satu sama lain dalam pemecahan roti dan berbagi piala untuk mengenang kematian dan kebangkitan-Nya. Sebagai medan tindak-tindak sakramental, Gereja sendiri merupakan ungkapan sakramental dari kehadiran Kristus di tengah-tengah umat yang berkumpul atas nama-Nya. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Langdon Gilkey, Catholicism Confronts Modernity (New York: Seabury, 1975) 47. Lihat Greg Dues, Catholic Customs and Traditions: A Popular Guide (Mystic, Conn: Twenty Third, 1989). Lihat Andrew Greeley, ”Sacramental Experience” dalam Andrew M. Greeley dan Mary Greeley Durkin, How to Save the Catholic Church (New York: Viking, 1984) 44-45. Edward Schillebeeckx, Christ the Sacrament of the Encounter with God (New York: Sheed & Ward, 1963); Karl Rahner, The Church and the Sacraments (New York: Herder & Herder, 1963). Scan McDonagh, Passion for the Earth (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1994) 148. Lihat Henri J.M. Nouwen, Behold the Beauty of the Lord: Praying with Icons (Notre Dame: Ave Maria, 1987). Lihat Baptism, Eucharist and Ministry (Geneva: WCC, 1982) 10. Nathan Mitchell, ”Who Is at the Table: Reclaining the Real Presence,” Commonweal 122 (January 27, 1995) 12. Lihat Thomas P. Rausch, Radical Christian Communities (Collegiville: The Liturgical Press 1990). Adrian Heastings, ”How to Be Ecumenical in 1995,” Priests & People 9 (January 1995), 6. 11. ”God”, Grandeur,” Poems of Gerard Manley Hopkins, 4th ed., ed. W.H. Gardner and N.H. Mackenzie (London) New York: Oxford Univ. Press, 1967). VI Hidup Kristiani dan Panggilan Menjadi Murid Abad kita, yang akan segera berakhir ini, telah menyaksikan kekejaman dan penderitaan manusia pada taraf yang jarang terbayangkan sebelumnya. Akan tetapi, abad yang sama juga telah menyaksikan contoh-contoh luar biasa bagaimana menjadi murid Kristus itu. Pada tahun 1930-an di Amerika, Dorothy Day, seorang Katolik pertobatan, mendirikan gerakan Pekerja Katolik untuk membela para pekerja miskin di New York. Dalam Perang Dunia II, seorang petani Austria bernama Franz Jäggerstätter dihukum mati karena menolak dinas militer di Jerman. Ia berpendapat bahwa perang Hittler tidak bermoral. Pada zaman itu juga Dietrich Bonhoeffer, Pastor Lutheran, dihukum mati karena melawan perang yang sama. Pada tahun 1980, Oscar Romero, uskup San Salvador, pejuang kaum miskin dibunuh oleh partai sayap kanan. Masih ada banyak kisah lain tentang orangorang, pria dan wanita, yang konsekuen mengikuti panggilan menjadi murid Yesus dan menderita, bahkan korban nyawa karenanya. Bila kita mendengar kisah-kisah itu, kita terkagum-kagum akan keberanian dan iman mereka. Dalam bab ini, kita akan membahas panggilan dasar menjadi murid yang ditujukan kepada semua pengikut Yesus dan kemudian melihat ungkapan-ungkapan menjadi murid yang berbeda-beda dalam hidup Kristiani. 1. Panggilan Menjadi Murid Yesus tidak datang untuk mendirikan agama baru. Dalam pelayanan singkat-Nya yang hanya berlangsung selama tiga tahun itu, Ia memaklumkan kedatangan Kerajaan Allah dan memanggil semua orang yang mau mendengarkan dan menjadi murid-Nya untuk mengikuti Dia dalam pelayanan. Murid dalam Perjanjian Baru Kata ”murid”, yang dalam bahasa Yunani adalah mathetes, disebut 250 kali dalam Perjanjian Baru, kebanyakan dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Kata ”mengikuti” atau akolouthe dalam bahasa Yunani terdapat 70 kali. Menjadi murid berarti mengikuti Yesus. Konsep murid bukanlah sesuatu yang baru. Baik orang-orang Farisi maupun Yohanes Pembaptis mempunyai murid. Akan tetapi, menjadi murid Yesus unik sifatnya karena beberapa alasan. Pertama, tidak seperti menjadi murid dalam Yudaisme Rabbinik, murid-murid Yesus tidak memilih guru. Akan tetapi, guru yang memilih dan memanggil murid-murid. Prakarsanya selalu datang dari Yesus (Mrk 1:17; 2:14). Kedua, ada unsur keterbukaan dalam panggilan Yesus. Ia tidak membatasi panggilan pada orang-orang yang secara ritual bersih dan secara religius taat. Di antara mereka yang dipanggil mengikuti-Nya adalah ”para pemungut cukai dan pendosa.” Ia kerap dikecam karena bergaul dengan mereka (Mrk 2:16). Wanita juga menyertai-Nya sebagai murid (Luk 8:2). Ketiga, panggilan Yesus untuk menjadi murid menuntut perubahan hati secara mendasar (metanoia), pertobatan religius yang kerap dilambangkan dengan meninggalkan segala milik. Kisah orang muda yang kaya dalam Injil Sinoptik menggambarkan tema pertobatan itu. Kepada orang muda, yang telah menaati segala perintah Allah sejak muda, Yesus berkata: ”Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku” (Mrk 10:21). Dengan demikian menjadi murid adalah putus total dengan masa lampau seseorang. Dalam Injil mereka yang mengikuti Yesus ”meninggalkan segala sesuatu” (Luk 5:11). Mereka meninggalkan pekerjaan mereka (Mrk 2:14), orang tua, keluarga, anak (Luk 14:26). Bagi beberapa orang, menjadi murid juga berarti selibat, tidak nikah, yang dihayati demi Kerajaan (Mat 19:11-12). Keempat, menjadi murid Yesus adalah ikut serta dalam pelayanan-Nya. Tidak seperti murid-murid Rabbi yang harus menghafalkan ajaran-ajaran guru mereka, murid-murid Yesus dipanggil untuk melayani seperti yang dilakukan Yesus. Yesus mengutus mereka untuk mengajar dan bertindak atas nama-Nya, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memaklumkan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat (Mrk 6:7-12; Luk 10:2-12). Menjadi murid tidak hanya ikut melayani tetapi juga ambil bagian dalam kemiskinan dan menyertai pengembaraan-Nya (Mat 8:20). Mereka bersikap hormat terhadap penguasa, tetapi bukan tidak kritis (Mrk 12:17; Mat 23:2-3). Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka akan ditolak, dikejar-kejar oleh penguasa religius dan sipil, bahkan terasing dari keluarga mereka (Mat 10). Akhirnya, menjadi murid Yesus berarti bersedia mencintai orang-orang lain dengan cinta penuh pengorbanan, dan tanpa syarat dan batas. Murid-murid harus bersedia berbagi apa pun dengan orang-orang lain (Luk 6:30). Mereka harus mencari tempat yang terakhir dan melayani orang lain (Mrk 9:35). Cita-cita menjadi murid sebagai cinta yang penuh pengorbanan diungkapkan paling jelas dalam Injil Yohanes, di mana Yesus berkata: ”Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh 15:12-13). Menjadi Murid Sesudah Paskah Sesudah Paskah para murid memahami bahwa mengikuti Yesus meliputi mengikuti Dia dalam peralihan Paskah dari kematian ke kehidupan. Dalam bagian ”perjalanan” (Mrk 8:27– 10:52) Markus membeberkan pengajaran tentang menjadi murid. Jalan Yesus berarti memanggul salib dan mengikuti-Nya, mengambil tempat terakhir, bahkan bersedia menyerahkan hidup (Mrk 8:34-35). Markus menggabungkan gagasan tentang mengikuti Yesus dengan kemartiran, pengertian yang populer dalam Gereja awal yang memandang kemartiran sebagai ungkapan yang tertinggi dari menjadi murid. Kisah Para Rasul menggunakan kata ”murid” untuk menyebut orang-orang Kristiani awal, meski penggunaan itu tak bertahan lama. Akan tetapi, gagasan menjadi murid, yang diungkapkan dengan cara-cara yang berbeda, merupakan hal penting dalam Gereja Awal. Dengan demikian, menjadi murid dalam Injil berarti mengikuti Yesus secara pribadi dan kerap kali mahal yang mempengaruhi setiap dimensi hidup manusia. Menjadi murid membentuk sikap seseorang terhadap milik dan kekayaan, mengubah cara memandang keberhasilan dan pemenuhan pribadi, dan akhirnya memanggilnya untuk masuk secara lebih mendalam ke dalam misteri Paskah Yesus, peralihan-Nya dari kematian ke kehidupan. Intinya adalah apa yang oleh tradisi Kristiani disebut Imitatio Christi, menyerupai Kristus. St. Paulus tidak menggunakan kata ”murid” untuk menggambarkan para anggota Gereja, meski gagasan tentang murid itu ada. Bagi St. Paulus, segala hidup Kristiani adalah menyerupai Kristus; kita dimasukkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus melalui pembaptisan kita (Rm 6:3-5) dan dipanggil untuk membentuk hidup kita berdasar misteri PaskahNya (Fil 3:8-11). Jika setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi murid Yesus, untuk menjalani hidup pelayanan dengan menggunakan karunia-karunia yang telah mereka terima dari Roh Kudus, maka baptis, yang memasukkan seseorang ke dalam Gereja, menjadi sakramen dasar untuk pelayanan Kristiani. Jemaat atau paroki lokal merupakan wadah di mana sumbangan masingmasing anggota jemaat dapat diberikan. Kerap kali paroki-paroki terlalu terfokus pada keluargakeluarga sehingga mereka yang tidak masuk ke dalam pola keluarga tradisional – apakah mereka itu satu orang dewasa, satu pasang orang tua, orang homo, mereka yang menikah antar Gereja, mereka yang cerai dan nikah lagi, janda – dapat merasa terabaikan. Semua orang Kristiani dipanggil untuk menjadi murid dan memberi pelayanan. Beberapa orang menjalani panggilan mereka melalui pernikahan Katolik; yang lain mengungkapkannya sebagai pelayan yang ditahbiskan. Beberapa orang berusaha mengikuti Kristus dengan menjadi anggota jemaat Kristiani dan yang lain memilih panggilan hidup sendiri, single. 2. Perkawinan dalam Kristus Bagi banyak orang, perkawinan merupakan tempat pendidikan atau sekolah cinta yang besar. Hidup dalam hubungan erat dengan orang lain, harus menyusun kembali prioritasprioritas untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pasangan, mengolah konflik dalam lingkup-lingkup hidup yang sempit, belajar untuk mengampuni dan minta maaf karena kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat, menerima pengampunan, dan memulai yang baru lagi tanpa dendam karena perasaan yang terluka, atau cedera-cedera di masa lampau, terbagi atas ruang pribadi, tugas-tugas rumah tangga, kepekaan, dan iman, semua itu merupakan pengajaran hidup perkawinan, yang membuat janji perkawinan bukan hanya menjadi kata-kata kosong melainkan perjanjian untuk penyerahan diri. Sakramen Perkawinan Dimensi sakramental cinta perkawinan telah dikenal sejak awal sejarah Kristianitas. St. Paulus memasukkan perkawinan di antara karisma-karisma, sebagai penampakan kehadiran Roh dalam hidup dua orang demi pembangunan Gereja (1Kor 7:7). Harapan St. Paulus akan kedatangan kembali Yesus yang sudah bangkit yang akan segera terjadi membuatnya membuat ucapan-ucapan yang bernada agak negatif tentang perkawinan (1Kor 7:27-29). Akan tetapi, ia juga melihat kekuatan perkawinan yang dihayati dalam iman yang menyempurnakan. Ia menyatakan bahwa hidup dengan pasangan Kristiani dapat menguduskan pasangan yang belum beriman dan anak-anak buah kesatuan mereka (1Kor 7:14). Selanjutnya ia menyebut saling cinta kasih suami-istri sebagai mysterion (misteri) besar, atau lambang, kesatuan mesra antara Kristus dan Gereja-Nya. St. Agustinus kemudian menggunakan teks itu untuk membahas hakikat sakramen perkawinan. Pada abad ke-12, Petrus Lombardus memasukkan perkawinan dalam daftarnya tentang ”tujuh sakramen” dalam bukunya De Sententiis. Perkawinan bukanlah sakramen yang diterima oleh pasangan tetapi lebih sakramen yang membuat mereka menjadi suami-istri. Pasangan yang saling mencintai dengan cinta tanpa syarat, pengampunan, dan penyerahan diri menjadi perwujudan sakramental, cinta Allah yang tak bersyarat, mengampuni, yang memberi hidup – bagi satu sama lain, bagi anak-anak mereka, dan bagi jemaat Kristiani. Menjalani sakramen semacam itu tidaklah mudah. Banyak orang yang tidak menikah, termasuk imam dan biarawan/biarawati, sulit memahami betapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk menjadi pasangan dan orang tua yang baik. Perkawinan merupakan komitmen untuk seumur hidup. Sebagaimana orang-orang dalam ME (Marriage Encounter) menyatakan bahwa cinta bukanlah perasaan, melainkan keputusan, sesuatu yang harus dijalani setiap hari. Menjanjikan cinta semacam itu kepada pasangan menjadi panggilan sakramental justru karena mengantarai cinta dan kesetiaan Allah kepada orang lain. Berapa banyak di antara kita dapat menghargai sesuatu dari misteri cinta Allah bagi kita melalui cinta yang telah kita alami dari orang tua! Seperti karisma lain, keinginan untuk menikah perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh untuk melihat apakah keinginan itu betul-betul merupakan penampakan Roh. Tanggung jawab utama ada pada pasangan sendiri. Mereka perlu menguji hubungan mereka, untuk melihat apakah cocok dan sungguh-sungguh memiliki kesatuan minat, untuk menemukan apakah cinta mereka sejati, apakah cukup kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan dan tantangantantangan yang dapat timbul dalam hidup mereka bersama. Seluruh waktu pacaran dan pertunangan merupakan bagian yang penting untuk pertimbangan itu. Jemaat Kristiani telah berbuat banyak dalam perkawinan anggota-anggotanya. Dengan demikian, Gereja berusaha membantu pasangan-pasangan dalam pertimbangan-pertimbangan mereka, meski usaha-usahanya untuk melembagakan proses pertimbangan melalui hukum kanonik tentang perkawinan dan kuesionernya sebelum perkawinan masih belum sempurna. Sejak Konsili Trente berusaha memperbarui praktek Kristiani pada abad ke-16, orang-orang Katolik telah dituntut untuk menaati ”bentuk kanonik” untuk sahnya perkawinan mereka. Mereka dituntut untuk merayakan perkawinan mereka di dalam Gereja di hadapan imam atau diakon beserta dua orang saksi. Perkawinan Beda Gereja Dewasa ini jumlah perkawinan orang Katolik dan orang Kristiani yang dibaptis dari Gereja lain bertambah dan mengakibatkan pertambahan jumlah keluarga antargereja. Direktori Ekumenis telah mengambil beberapa langkah untuk menanggapi keprihatinan-keprihatinan khusus orang-orang Kristiani dalam masalah perkawinan campur atau antargereja.1 Direktori menekankan perlunya menghormati hati nurani baik pasangan Katolik maupun non-Katolik. Pasangan Katolik diharapkan ”berjanji secara jujur untuk berbuat sekuat tenaga menjaga agar anak-anak, buah perkawinan, dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.” Akan tetapi, pasangan Katolik juga mengakui bahwa pasangan non-Katolik mungkin merasakan kewajiban yang sama terhadap Gerejanya dan oleh karena itu, mereka tidak lagi dituntut untuk mengucapkan janji formal, entah secara lisan maupun tertulis, untuk mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik (no. 50), sebagaimana terjadi di masa lampau. Jika meski usaha betul-betul dari pihak pasangan Katolik, anak-anak tidak dibaptis dan dididik di dalam Gereja, pasangan Katolik tidak terkena sanksi hukum kanonik (no. 151). Perkawinan campur biasanya dilangsungkan di luar Perayaan Ekaristi, karena pasangan Gereja-Gereja itu belum bersatu. Namun uskup dalam kasus-kasus tertentu dapat memberi pengecualian pada peraturan itu (no. 159). Orang-orang Katolik, dengan alasan-alasan yang baik, menerima dispensasi dari peraturan kawin sehingga perkawinan dapat dirayakan di dalam Gereja (atau sinagoga) pasangan non-Katolik. Ibadat perkawinan antargereja dengan persetujuan kedua pelayan dapat dirayakan secara ekumenis. Dalam ibadat-ibadat semacam itu, satu pelayan mengetuai dan menerima kaul, sedang pelayan dari pihak lain dapat membantu dengan memanjatkan doa, membaca Kitab Suci, memberi khotbah pendek, atau memberkati pasangan. Yang dilarang adalah pasangan mengadakan dua ibadat dengan kesepakatan bersama. Kapan Perkawinan Putus? Salah satu masalah yang dihadapi oleh Gereja pada saat ini adalah bagaimana menangani secara pastoral perkawinan-perkawinan yang karena satu dan lain hal tidak jalan lagi. Tentu saja banyak orang Katolik juga mengalami situasi yang sulit itu. Ada banyak orang Katolik yang cerai. Dalam hal ini, Gereja menghadapi dilema dari dua nilai yang bertentangan. Dari satu sudut, Gereja bermaksud mempertahankan dan mengajarkan nilai indissolubilitas, ketidakdapat-diceraikannya, perkawinan pada zaman dan budaya di mana orang kawin dan cerai tanpa pikir panjang. Ajaran Gereja tentang ketetapan perkawinan berasal dari Yesus sendiri, yang melarang perceraian dan perkawinan kembali (Mrk 10:2-12). Meski menarik untuk dicatat bahwa St. Paulus (1Kor 7:10-16) maupun Matius (5:32;19,1-2) mengakui adanya pengecualian untuk larangan itu. Di pihak lain, Gereja merasakan kebutuhan untuk melayani secara pastoral orang-orang yang mau menikah lagi sesudah perkawinan mereka gagal atau yang kecewa perkawinannya, mereka tak diperbolehkan untuk ikut serta dalam Ekaristi. Sebelum Konsili Vatikan II, syarat-syarat untuk pembatalan dimengerti lebih keras. Perkawinan diakui tidak sah jika dilangsungkan dengan tidak bebas, atau jika satu pihak menarik persetujuan untuk salah satu ”keutamaan” perkawinan seperti ketetapan atau anakanak, atau jika beberapa ”halangan” seperti ada ikatan nikah sebelumnya. Sejak Konsili Vatikan II syarat-syarat itu dimengerti secara lebih luas. Gereja telah mengetahui dengan lebih jelas bahwa membuat komitmen perkawinan dalam Kristus menuntut kedewasaan dan keputusan yang hati-hati dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pasangan dapat diberi pembatalan perkawinan berdasarkan ”tidak adanya pertimbangan yang seharusnya ada”. Dewasa ini jauh lebih mudah mendapatkan pembatalan daripada di masa lampau. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan ke Roma, pembatalan perkawinan dapat diberikan oleh uskup setempat. Dan jumlah pembatalan amat meningkat. Namun proses pembatalan perkawinan tidak mudah. Satu pemecahan yang dianjurkan oleh sejumlah ahli hukum dan teologi moral adalah mengizinkan pasangan yang perkawinan keduanya menunjukkan bukti cinta yang amat mendalam, untuk menerima Ekaristi tanpa secara resmi merayakan pernikahan kedua mereka secara sakramental. Gereja-Gereja Ortodoks, untuk melunakkan kekerasan hukum yang tidak dimaksudkan, mengizinkan perkawinan sesudah cerai dengan prinsip ”ekonomi” (mirip dengan ”dispensasi” di Gereja Roma). Gereja Katolik berusaha menanggapi secara lebih pastoral mereka yang menikah lagi tanpa mendapatkan pembatalan. Pasangan yang melangsungkan perkawinan semacam itu tidak perlu mendapatkan ekskomunikasi. Gereja juga tidak menyebut perkawinan-perkawinan seperti itu sebagai ”perkawinan zina”, karena kebanyakan orang Katolik mengakui bahwa perkawinan kedua mungkin pada suatu saat dapat menunjukkan segala tanda cinta dan komitmen yang diharapkan dalam sakramen perkawinan, bahkan jika Gereja tidak dapat secara resmi mengakuinya demikian. 3. Imamat Peran imam dalam jemaat Kristiani telah amat berubah sejak Konsili Vatikan II. Sebelum Konsili, imam menduduki tempat istimewa di dalam budaya Katolik. Pemahaman yang sakral tentang imamat yang muncul pada Abad Pertengahan merumuskan imamat selalu eksklusif dalam kerangka peran imam dalam Perayaan Ekaristi. Secara populer, imam dipandang sebagai orang kudus, memiliki kekuasaan sakramental sehingga dapat mempersembahkan korban Misa Kudus dan ”mengkonsekrasikan” Ekaristi. Imam adalah ”Kristus yang lain”. Perannya dengan jelas dirumuskan dan dilindungi oleh budaya klerikal. Imam adalah manusia yang dikhususkan, dipisahkan dari awam oleh pakaian dan hak istimewa klerikal, gelar kehormatan, sistem pendidikan terpisah yang diikuti oleh anak laki-laki saja, hidup di pastoran, bahkan bahasa yang digunakan dalam liturgi, yaitu bahasa Latin. Dalam tahun-tahun sesudah Konsili Vatikan II, dengan tekanannya pada Gereja sebagai Umat Allah, dan penemuannya atas konsep pelayanan yang lebih luas, konsep sakral imamat secara luas tidak diterima. Bahkan ada yang berkata bahwa kata ”imam” pun harus dibuang karena sejak Perjanjian Baru pelayan-pelayan jemaat tidak disebut imam-imam.2 Imamat dimengerti dalam kerangka pelayanan dan pengabdian, bukan kekuasaan dan otoritas. Dalam banyak hal penekanan ini penting, karena pendekatan sakral pada imamat yang berat sebelah sebelum Konsili Vatikan II. Imam adalah pemimpin pelayan, yang dipanggil untuk pelayanan yang rendah hati menurut teladan pelayanan Yesus. Akan tetapi, karena teologi populer cenderung menggambarkan semua orang Kristiani itu pelayan, lalu pertanyaan di mana khasnya pelayanan imam menjadi semakin meningkat. Pada awal tahun 1990-an, berdasarkan peran imam dalam perayaan sakramen-sakramen, disarankan model ”perwakilan” bagi imamat. Gereja sebagai tubuh Kristus mewakili dan membuat Kristus hadir bagi dunia, tetapi untuk itu, ”juga perlu bagi Kristus diwakili oleh tindakan-tindakan resmi Gereja sebagai Gereja”.3 Peran mewakili ini dilaksanakan oleh uskup-uskup dan imam-imam, yang mendapat otoritas sebagai pelayan resmi Gereja oleh tahbisan mereka dan dengan demikian dapat mewakili Kristus dalam tindakan-tindakan resmi Gereja, sakramensakramennya. Dalam bahasa yang telah menjadi tradisi sejak abad-abad awal, uskup dan imam bertindak ”atas nama Kristus” (in persona Christi). Atas Nama Kristus Konsep itu didasarkan pada peran uskup sebagai pemimpin Gereja setempat. Sebagai orang yang mengepalai jemaat, atau Gereja, dan sudah ditahbiskan, uskup atau imam bertindak atas nama Kristus dalam sakramen-sakramen Gereja dan terutama dalam Ekaristi. Bersamaan itu, uskup atau imam bertindak ”atas nama Gereja” (in persona ecclesiae) berdasarkan perannya sebagai pimpinan umat yang beribadat. Imam dapat bertindak atas nama Kristus karena ia bertindak atas nama Gereja, Tubuh Kristus. Di luar Gereja, imamat tidak mempunyai makna. Kebanyakan imam diosesan atau sekular melaksanakan pelayanan sabda, sakramen, dan kepemimpinan pastoral dalam Gereja, biasanya dengan mengepalai jemaat beriman lokal, paroki. Kebanyakan imam monastik melaksanakan imamat yang terutama bersifat kultis, ibadat, berpusat pada puji-pujian kepada Allah melalui liturgi. Imam-imam yang menjadi anggota komunitas religius apostolik pada umumnya melaksanakan pelayanan yang jangkauannya melampaui batas-batas Gereja lokal. Pelayanan mereka kerap lebih profetis atau kerigmatis, karena meliputi bidang pelayanan sabda yang jauh lebih luas, memberi retret, dan memberi bimbingan rohani, mengajar dan menulis, membaktikan diri untuk pelayananpelayanan penginjilan dan keadilan sosial. Selibat Kita akan membicarakan selibat, tidak nikah, demi Injil bila kita membicarakan panggilan untuk hidup sendiri. Cukuplah di sini jika dikatakan bahwa meski selibat telah menjadi nilai dalam hidup Kristiani sejak awal, namun selibat tidak selalu dikaitkan dengan imamat. Pada abad-abad awal banyak imam menikah, meski cukup banyak yang memilih selibat. Di Gereja Timur berkembang tradisi bahwa uskup harus selibat, sebagian besar karena praktek pemilihan uskup diadakan di antara para rahib. Tradisi itu masih berlangsung sampai sekarang. Uskup harus selibat. Akan tetapi, baik Gereja Ortodoks Timur maupun Gereja Katolik Timur menahbiskan pria yang sudah menikah. Di Barat, tradisi wajib selibat berkembang lambat. Pada abad ke-4 dan ke-5 berbagai konsili lokal – di Spanyol (Elvira, 306), Afrika (Cartago, 390, 419), Italia (Turino, 398), dan Prancis (Orange, 441) – berusaha menuntut pantang seks pada imam-imam yang menikah. Caloncalon untuk tahbisan harus mengucapkan kaul kemurnian. Akan tetapi, banyak imam terus menikah dan mempunyai anak meski diprotes Paus-Paus dan perundang-undangan sinoda dan Konsili. Nikolas II (1059) berusaha mencegah umat menghadiri Misa yang dirayakan oleh imam-imam yang menikah. Konsili Lateran I (1123) menetapkan selibat menjadi wajib bagi mereka yang mendapat tahbisan besar. Konsili Lateran II (1139) menyatakan bahwa perkawinan klerus tidak berlaku. Sejak itu selibat merupakan kewajiban dan berlaku umum di Gereja Barat. Perlu dicatat bahwa selibat merupakan perkara disiplin Gereja, bukan ajaran, sebagaimana diakui oleh Konsili Trente (DS 1809). Meski, jika dilakukan secara bebas, selibat dapat merupakan tanda kerajaan, namun tidak intrinsik untuk panggilan menjadi imam diosesan. Dengan demikian menurut pikiran dapat diubah. Namun bagi imam-imam religius (biarawan) yang hidup di dalam komunitas dan mengucapkan kaul nasihat Injili kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, selibat merupakan hal yang intrinsik bagi panggilan mereka. Baik Paus Paulus VI maupun Yohanes Paulus II telah dengan tegas meneguhkan tradisi selibat bagi klerus,3 meskipun banyak orang Katolik dewasa ini menyatakan bahwa apa yang merupakan karisma bebas, jangan dijadikan masalah hukum Gereja terutama berdasarkan kenyataan bahwa jumlah calon untuk tahbisan yang tidak menikah terus berkurang. Di masa lampau imamat telah mengambil sejumlah bentuk yang berbeda-beda. Bentuk dan ungkapan apa yang akan terjadi di masa depan masih perlu dilihat. Imamat Dewasa Ini Memaklumkan Injil berhadapan dengan sekularisasi yang semakin meluas dan ketidakacuhan keagamaan, bersaksi tentang dimensi sosialnya berhadapan dengan kemiskinan yang menghancurkan, yang menimpa sedemikian banyak manusia dewasa ini, dapat berbagi pengalaman iman pribadi dengan orang-orang lain yang bergulat dengan iman mereka sendiri merupakan bagian tantangan menjadi imam dewasa ini. Bagaimana imam berbicara dengan orang tua yang telah kehilangan anak atau ada dalam bahaya kehilangan anak karena mereka tidak dapat lagi berkomunikasi dengannya? Bagaimana ia membantu orang tua yang bingung untuk menerima dan mencintai anak yang homo atau memberitahukan bahwa ia positif terkena virus HIV? Bagaimana ia dapat menjangkau wanita yang terluka dan terasing karena merasa didiskriminasi oleh Gereja dan menemukan peran yang bermakna di dalam Gereja? Bagaimana ia dapat menolong anggotaanggota masyarakat yang telah berumur agar menjadi damai dengan kekuatan mereka yang menurun atau malah tak mempunyai kemampuan lagi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu lebih mudah diajukan daripada dijawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang dihadapi imam-imam dewasa ini. Imam hanya dapat membantu jika mudah dihubungi. Ia tidak dapat menyembunyikan diri di belakang status atau perannya. Zaman pada waktu imam menjadi orang di Paroki yang paling terdidik sudah berlalu. Gambaran tentang imam sebagai ”manusia yang terpisah” tidak amat membantu pada zaman sekarang ini. Juga budaya klerikal yang mendirikan penghalangpenghalang di antara imam dan umat tidak lagi pada tempatnya. Imam hanya dapat menjalankan peran kepemimpinan di antara umat jika ia menjadi bagiannya, terlibat dengan para anggotanya. Ini nyata sekali pada waktu ia memimpin Ekaristi. Ekaristi menjadi pusat pelayanan imam, karena umat yang dilayani imam, diciptakan dan dilestarikan oleh Ekaristi. Melalui perayaan Ekaristi umat menjadi Gereja, sedang imam berdasarkan kesatuannya dengan uskup melambangkan dan melestarikan umat lokal dan kesatuan Gereja di seluruh dunia. Pada waktu imam memimpin Ekaristi, hakikat Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik diungkapkan. Pada akhirnya, imamat merupakan panggilan, bukan karier. Mereka yang menjadi imam dengan pemikiran bahwa imamat itu memberi mereka keamanan, status, atau kemajuan diri akan kecewa. Doa merupakan hal yang amat penting dalam hidup imam. Orang-orang Katolik mengharapkan agar imam mereka menjadi manusia pendoa agar mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan tulus dan kedalaman rohani yang cukup. Jika dihayati dengan benar, imamat merupakan ungkapan dari kemuridan Kristiani – bukan satu-satunya, tetapi pasti dekat sekali dengan imamat Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dan murid-murid lain yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi sahabat Yesus dan ikut serta dalam pelayanan-Nya. 4. Komunitas Kristiani dan Hidup Religius Sejak abad-abad awal Gereja, sejumlah pria dan wanita telah berusaha menanggapi panggilan Injil untuk menjadi murid Yesus dengan hidup bersama orang-orang Kristiani lain dalam komunitas yang dibentuk untuk doa, pelayanan Injil, dan pelayanan Kristiani. Lambat laun, beberapa komunitas itu menjadi ordo atau kongregasi religius, komunitas rahib atau rubiah, imam, bruder, atau suster yang hidup bersama dan mengikat diri mereka dengan nasihat Injil ”kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan.” Ada juga komunitas orang awam yang para anggotanya hidup dan melaksanakan pelayanan bersama. Ada juga lembaga-lembaga sekular yang diakui secara kanonik, perkumpulan pria atau wanita yang mengucapkan kaul religius tradisional secara pribadi dan ”terus” melanjutkan hidup di dunia dan tidak di dalam komunitas religius. Monastisisme Gereja telah selalu mengakui berbagai kelompok, atau ordo, orang-orang Kristiani yang menghayati nilai-nilai Injil dengan cara khusus. Gereja awal menghormati wanita-wanita yang mempersembahkan keperawanan mereka dan martir-martir yang mengorbankan hidup mereka demi iman sebagai ungkapan kemurnian mereka. Pada abad ke-3 dan ke-4, pada waktu hidup Kristiani tidak hanya menjadi legal tetapi juga dihormati dan tidak jarang hidup makmur, banyak pria dan wanita pergi meninggalkan kota untuk mencari Allah dalam keheningan padang pasir. Mereka kemudian dipanggil ”rahib”, karena mereka hidup sendiri (monos). St. Antonius dari Mesir, seorang pertapa (heremios berarti ”mendatangi padang pasir” atau ”sendirian”) abad ke-3, dianggap sebagai bapa monastisisme. Bahkan jika ia bukan rahib yang pertama, kisahnya, Hidup Antonius, yang ditulis oleh St. Athanasius (meninggal tahun 373) memberi inspirasi ribuan orang untuk mengikuti teladannya. Pria dan wanita itu, yang mengikuti nasihat Injil, melepaskan segala harta bendanya, menjalani hidup selibat, dan kerap menjanjikan ketaatan terhadap guru, bapa rohani (abbas) atau ibu rohani (amma). Meski ada ribuan rahib yang hidup di padang pasir sebagai pertapa, pada waktu Antonius meninggal (± 356), banyak dari mereka hidup dalam tempat-tempat tinggal yang dibangun di seputar bangunan untuk keperluan bersama. Pachomius (± 292-346) menyatukan sejumlah pertapa dari tempat-tempat tinggal kecil itu menjadi komunitas atau biara monastik, yang anggota-anggotanya hidup dalam komunitas dan mengadakan doa bersama, bekerja tangan, dan kemudian belajar bersama di bawah bimbingan seorang pemimpin. Basilius dari Kaisarea (± 330-379) membuat gambaran singkat tentang cara hidup yang memperlunak askese pribadi dengan penekanan pada kasih dan karya amal. Regulae-nya (peraturan-peraturan) membantu pemantapan gerakan monastik dalam Gereja. Evagrius dari Pontus (349-399) ikut mengembangkan spiritualitas monastik dengan membagi hidup rohani menjadi dua tahap: hidup ”aktif” yang berkaitan dengan pembersihan indra dan perolehan keutamaan, dan hidup ”kontemplatif”, semacam doa yang diatur untuk mendapatkan ketenangan budi dan mengasingkannya dari gangguan-gangguan supaya rahib dapat bersatu dengan Allah. Monastisisme juga berkembang di Gereja Barat. Di Roma, ada pria dan wanita yang hidup di semacam monastisisme kota pada awal abad ke-4. Orang-orang yang askese (dari kata Yunani askeis, yang digunakan untuk latihan olah raga) menjalani hidup selibat dan membaktikan diri untuk mempelajari Kitab Suci dan berdoa. Terutama bagi wanita, hidup monastik memberi kemungkinan bentuk hidup lain daripada pernikahan dan memberi pembebasan dari peran yang didiktekan oleh budaya mereka. Martinus dari Tours (317-397) dan Yohanes Casianus (± 360-435) membawa hidup monastik ke Prancis. Dari sana, rahib misionaris membawanya ke kepulauan Inggris, terutama Irlandia, di mana tumbuh monastisisme Celtik yang unik dan membentuk Gereja Irlandia selama berabad-abad. Nama tokoh yang paling terkenal dalam monastisisme Barat adalah Benediktus Nursia (480-550). Berturut-turut, Benediktus adalah pelajar di Roma, pertapa di Subiaco, dan pendiri komunitas rahib di Monte Casino. Ia menulis Regulae-nya yang terkenal, yang menetapkan pola monastisisme Barat. Regulae itu seimbang dengan berusaha mengintegrasikan hidup doa dan bekerja, kesendirian dan kebersamaan, tanggung jawab pribadi dan otoritas. Para rahib hidup dalam komunitas yang praktis mandiri di bawah bimbingan Abbas. Bangunan-bangunan, gereja, tempat tidur, rapat komunitas, dan kamar makan dibangun mengelilingi kebun terbuka, atau kloster. Rahib-rahib bekerja, belajar, berjalan-jalan di jalanjalan tertutup, yang membentuk sisi kloster. Hari mereka dibagi menjadi tiga bagian. Tujuh kali sehari mereka berkumpul di gereja untuk ibadat monastik, yang dikenal dengan nama opus Dei (ofisi Ilahi) dengan menyanyikan mazmur untuk memuji Allah. Beberapa jam sehari digunakan untuk membaca sambil merenungkan Kitab Suci (lectio divina) yang menghidupi doa mereka. Akhirnya, enam atau tujuh jam digunakan untuk kerja tangan (labora) guna mendukung hidup mereka. Pada awal Abad Pertengahan, biara-biara menyediakan jaringan pelayanan kemasyarakatan yang penting. Mereka menyediakan penginapan bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan, dan makanan serta pakaian dan perlindungan bagi orang-orang miskin. Biara menjadi pusat belajar dan seni. Banyak keluarga mengirimkan anak mereka untuk hidup di biara-biara untuk mendapat pendidikan. Bersamaan dengan itu, tidak selalu mudah mempertahankan idealisme yang menjadi pangkal yang menarik orang-orang untuk hidup monastik. Bila kita mempelajari sejarah monastik, pola-pola yang sama terjadi. Cara hidup yang mulai sebagai komunitas yang mencari Allah dalam keheningan, kemiskinan, dan penyangkalan diri secara bertahap menjadi mapan, terjamin dan makmur. Selibat menjadi faktor di sini. Karena rahib-rahib tidak mempunyai anak-anak untuk mewarisi kekayaan yang dihasilkan oleh usaha mereka, komunitas monastik sendiri sedikit demi sedikit mempunyai harta bersama. Banyak biara Benediktin menjadi cukup kaya. Akan tetapi, kelompok-kelompok baru muncul untuk mulai lagi dengan mencari melalui keheningan dan doa, Allah yang tersembunyi yang dirindukan hati manusia. Romualdus dari Ravenna (± 950-1027) dan Bruno dari Koeln (1032-1101) membantu mendirikan komunitaskomunitas pertapa yang baru. Romualdus mendirikan Camaldolese, yang namanya diambil dari pertapaan di Camaldoli di pegunungan Tuscan. Bruno membantu mendirikan Kelompok Kartusia yang menyebut biara mereka di Prancis Alp La Grande Chartreuse. Di Prancis, sekelompok rahib meninggalkan biara mereka di Solesmes pada tahun 1098 dengan harapan untuk memulihkan hidup doa dan kerja yang sederhana yang menjadi ciri regulae St. Benediktus. Mereka memilih daerah yang terpencil untuk biara-biara mereka, mengembalikan liturgi Benediktin yang sudah dikembangkan ke bentuk dasarnya, dan berusaha membuang dari gereja-gereja mereka yang penuh seni, patung, kaca-kaca dan menara-menara Benediktin yang besar-besar. Dikenal dengan nama kelompok Cisterciensis, dari biara baru mereka di Citeaux (Cistercium), ”Rahib-rahib Putih” menjadi ordo monastik yang paling berpengaruh pada abad ke-12. Kelompok Cisterciensis juga ada di Indonesia, yaitu di Rowoseneng, Temanggung, Jawa Tengah. Komunitas Injili dan Ordo Apostolik Dalam huru-hara dan pergolakan yang mengubah hidup dan peta Eropa pada abad ke-12 dan ke-13, komunitas-komunitas baru yang dipengaruhi oleh kebangkitan injili yang melanda Eropa muncul. Komunitas-komunitas itu berusaha menjalani kemiskinan injili dan pewartaan apostolik menurut model Injil dalam budaya kota yang makin berkembang. Banyak dari komunitas-komunitas itu merupakan gerakan awam. Beberapa di antaranya seperti Humiliati, Kaum Waldenses, dan orang-orang Katolik miskin merupakan komunitas campur pria dan wanita. Yang lain, komunitas-komunitas wanita seperti Beguines dapat dipandang sebagai mewakili untuk pertama kali gerakan wanita sejati dalam Gereja. Usahausaha komunitas-komunitas untuk mengembangkan dan menjalani spiritualitas awam berdasarkan Injil menimbulkan ketegangan antara mereka dan Gereja resmi, terutama tentang masalah khotbah oleh kaum awam. Beberapa, seperti kaum Waldenses, pada akhirnya menyeleweng dan memisahkan diri dari Gereja. Komunitas-komunitas lain menjadi ordo religius baru, yang paling terkenal adalah Fransiskan dan Dominikan. Dominikus Guzman (1172-1221) seorang kanon katedral Diosis Osma di Spanyol. Ordonya berkembang dari sekelompok misionaris yang bergabung dengannya dalam pelayanan khotbah melawan kaum Albigens di Prancis selatan. Fransiskus Assisi (1182-1226) adalah seorang anak pedagang kain Italia yang kaya. Sesudah pengalaman pertobatan yang terjadi selama beberapa tahun, Fransiskus mengumpulkan sekelompok teman dan bersama kelompoknya mulai berkeliling daerah Umbria, berkhotbah di alun-alun kota, bekerja bersama petani-petani di ladang, dan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baik Dominikus maupun Fransiskus tergerak oleh semangat Injil baru yang mempengaruhi sekian banyak orang sezamannya. Pengertian komunitas apostolik, bebas pergi ke manapun dibutuhkan, mewartakan Injil di kota-kota kecil dan di kota-kota besar, hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan, tidak berasal dari kedua orang itu. Sesungguhnya, pada awalnya komunitas mereka kadang-kadang tak terbedakan dari komunitas-komunitas yang lebih radikal dan menyimpang ajarannya. Dominikus dan beberapa teman awalnya berjalan dengan telanjang kaki sampai Konsili Konstanz memerintahkan agar mereka mengenakan sepatu untuk membedakan pengkhotbah-pengkhotbah yang sejati dan bidaah yang menyamakan hak untuk berkhotbah dengan berjalan dengan kaki telanjang. Orang-orang Fransiskan awal kerap kali secara keliru dianggap sebagai anggota-anggota persaudaraan penginjil lain yang dicurigai, terutama kaum Waldenses yang telah dihukum, dan karena kurangnya mereka akan pendidikan, menjadi peluang bagi beberapa untuk menerima pandangan-pandangan bidaah bagi mereka sendiri. Akan tetapi, baik Dominikus dan Fransiskus berhasil menemukan jalan untuk memasukkan visi tentang hidup apostolik mereka ke dalam struktur hidup Gereja. Teman-teman Dominikus membentuk komunitas klerikal sejak awal, yang dibantu oleh para Bruder dan ”ordo kedua”, sekelompok wanita yang beberapa di antaranya bertobat dari kaum Albigens. Paus Honorius III mengakui komunitas Dominikus sebagai Ordo Praedicatorum (Ordo Para Pengkhotbah) pada tahun 1217. Fratres minores (saudara-saudara dina) Fransiskus pada awalnya komunitas awam, menjadi semakin klerikal untuk menyesuaikan penekanan mereka pada khotbah. Fransiskus menulis beberapa Regulae sebelum Regula Bullata (Regula Kedua) disetujui oleh Paus Honorius III pada tahun 1223. Tampaknya, Fransiskus sendiri ditahbiskan menjadi diakon. Fransiskan wanita, yang dipimpin oleh teman Fransiskus, Clara, berusaha menjalani hidup yang sama yang dijalani oleh saudara-saudara dina, terutama dalam melayani orang miskin, tetapi tahap demi tahap mereka diharuskan menerima kewajiban hidup membiara yang menghilangkan gaya apostolik mereka. Gereja tidak cukup siap untuk menerima komunitas apostolik wanita. ”Clara-Clara yang miskin” menjadi komunitas monastik kontemplatif. Komunitas-Komunitas Sesudah Reformasi Meskipun Reformasi pada abad ke-16 merupakan pukulan berat bagi hidup religius di Eropa, semangat perubahan yang dibangkitkan dalam Gereja Katolik melahirkan sejumlah komunitas religius baru. Di Spanyol, Teresia Avila dibantu oleh Yohanes dari Salib, melaksanakan pembaruan di kalangan Karmelit untuk menghidupkan lagi hidup kontemplatif. Pada tahun 1526, pembaruan di kalangan Fransiskan menghasilkan kelompok Kapusin. Abad ke-16 juga menyaksikan pendirian sejumlah komunitas imam, ”clerus regularis” seperti Theatin (1524), Somaschi (1528), Barnabit (1533) dan Piaris (1597). Mungkin yang paling berhasil di antara komunitas-komunitas baru religius pria itu adalah Serikat Yesus, atau Yesuit, sekelompok mantan mahasiswa Universitas Paris yang dipimpin oleh Ignasius Loyola. Cara hidup mereka berbeda dari cara ordo-ordo religius zaman itu. Mereka tidak mempunyai pakaian khusus, tak ada puasa dan mati raga yang diwajibkan, tidak ada doa koor – lepas dari tradisi secara radikal. Hidup religius ”teman-teman dalam Tuhan” itu tidak didasarkan atas peraturan melainkan pada pengalaman bersama dari Exercitia Spiritualia (Latihan Rohani), serangkaian pertimbangan dan renungan atas Injil yang dimaksudkan untuk membimbing orang ke dalam hubungan baru dengan Allah, yang telah berkembang dari doa Ignasius selama berbulan-bulan di Manresa pada tahun 1522. Cara hidup mereka disetujui pada tahun 1540 pada waktu Paus Paulus II menyetujui Formula Instituti yang ditulis oleh Ignasius. Pada waktu Ignasius meninggal pada tahun 1556, Yesuit-Yesuit bekerja sebagai misionaris di India, Jepang, dan Afrika, serta membimbing 46 kolese. Pada abad-abad sesudah Reformasi, berturut-turut muncul komunitas-komunitas religius pria dan wanita. Vincensius Paulo mendirikan kelompok Lazaris pada tahun 1663 dan bersama Louise de Marillac membentuk Suster-suster Kasih untuk melayani orang-orang sakit dan miskin. Yohanes Baptista dari sales membentuk Bruder-Bruder Kristiani pada tahun 1681 untuk mendidik anak-anak buruh. Abad ke-18 menyaksikan berdirinya kelompok Pasionis (1725) dan Redemptoris (1735). Sekitar 65 kongregasi dan serikat imam didirikan pada abad ke-19. Meski wanita beriman telah berusaha membaktikan diri untuk karya amal dan kerasulan bahkan sebelum zaman St. Clara, mereka harus berjuang melawan Gereja yang tidak dapat membayangkan religius wanita hidup di dalam komunitas, tanpa perlindungan praktek hidup monastik seperti pakaian khusus, tempat tersendiri, biara dan koor. Suster-Suster Ursulin yang didirikan oleh Angela Merici pada tahun 1535 mulai sebagai komunitas religius wanita yang tidak tinggal di biara. Pada awalnya, wanita-wanita itu hidup di keluarga bersama keluarga mereka, tetapi tahap demi tahap mereka dituntut untuk hidup dalam komunitas yang semakin menjadi monastik. Sama halnya dengan Suster-Suster Visitasi, yang didirikan oleh St. Fransiskus dari Sales dan Jean Frances de Chantal di Prancis pada tahun 1610. Mereka mulai sebagai komunitas yang membaktikan diri untuk merawat orang sakit, tetapi tak lama kemudian diubah menjadi Ordo Suster-suster berklausura tertutup yang ketat. Lebih dari 400 kongregasi religius apostolik wanita didirikan di Prancis antara tahun 1800 dan 1880. Dari komunitas-komunitas wanita yang membaktikan diri itu – komunitas-komunitas seperti SusterSuster Belas Kasih, Suster-Suster St. Yosef, Suster-Suster Hati Maria Tak Bercela, – muncul Suster-Suster yang membuat pelayanan sosial dan pendidikan Gereja menjadi konkret bagi jutaan manusia di dunia. Mereka melaksanakan karya misioner, berkarya di rumah sakit dan sekolah, merawat orang sakit, anak yatim piatu, orang tua dan orang yang tak beruntung. Komunitas-Komunitas Religius Baru Dorongan untuk hidup komunitas Kristiani masih tetap kuat pada abad ke-20. Komunitaskomunitas baru muncul, baik awam maupun religius, yang berusaha membuat cara hidup para anggotanya berakar dalam Injil. Suster-Suster dan Bruder-Bruder kecil mendapatkan inspirasinya dari Charles de Foucauld, rahib-pertapa Prancis yang hidup di antara orang Berber di Tamanrasset di Sahara yang berusaha membentuk hidup mereka menurut teladan hidup sembunyi Yesus di Nazaret. Foucauld dibunuh pada tahun 1916 oleh anak suku berumur 16 tahun. Teladan kesetiakawanannya dengan orang miskin mempengaruhi sejumlah komunitas religius sezaman. Suster-Suster dan Bruder-Bruder berusaha menghayati hidup bersama orang miskin, bekerja seperti orang-orang biasa di pabrik-pabrik, ladang-ladang pertanian, dan toko-toko, dan kembali pada sore harinya ke komunitas mereka untuk berdoa selama satu jam di hadapan Sakramen Mahakudus. Mereka adalah kontemplatif yang biaranya adalah dunia sehari-hari orang miskin. Jauh lebih dikenal adalah komunitas-komunitas Ibu Teresa, Misionaris Kasih (The Missionaries of Charity). Para Suster Misionaris Kasih menjalani kemiskinan yang keras dan mengucapkan kaul keempat: kasih. Aktivitas harian mereka dimulai kira-kira pukul 04.30 pagi dengan renungan dan Misa Kudus dan seluruh hari diisi dengan merawat ”orang-orang yang paling miskin dari antara orang miskin.” Bruder-Bruder Kasih, meski jumlahnya lebih kecil, mengikuti hidup religius yang sama. Sesudah meditasi dan Misa, mereka pergi melaksanakan karya kasih dan kembali pada sore harinya untuk Doa Sore dan meditasi di hadapan Sakramen Mahakudus. Misionaris Kasih bukan satu-satunya komunitas modern yang melayani orang miskin. Banyak komunitas religius pria dan wanita terlibat dalam pelayanan yang serupa. Mereka menjadi anggota staf paroki-paroki di tengah kota, menjalankan tempat-tempat perlindungan dan rumah-rumah penginapan dan menyediakan jaringan-jaringan pelayanan bagi orang-orang yang tidak beruntung. Hidup Religius Sesudah Konsili Vatikan II Konsili Vatikan II menyerukan dua pembaruan hidup religius: ”(1) pengacuan terus-menerus kepada sumber-sumber seluruh hidup Kristiani serta inspirasi tarekat yang mulamula dan (2) penyesuaiannya dengan kenyataan zaman yang sudah berubah” (PC 2). Dalam tahun-tahun selanjutnya, hidup religius sangat berubah, baik dalam penampilan maupun dalam pemahamannya. Perubahan-perubahan itu kebanyakan menyangkut hal-hal luar, lahiriah. Bagi cukup banyak komunitas religius aktif pria dan wanita, pakaian biara, hidup harian, devosi-devosi yang dituntut, mati raga lahir, peraturan-peraturan yang membatasi, biara dan lambang-lambang luar lain yang dulu menjadi ciri-ciri hidup religius lenyap. Komunitas-komunitas religius memangkas banyak praktek yang sudah dijalani selama berabad-abad. Perubahan-perubahan lain lebih menyangkut hakikatnya. Tantangan untuk kembali ke sumber ternyata berbuah banyak. Komunitas-komunitas monastik mulai menemukan dimensi kontemplatif panggilan mereka. Banyak komunitas berpikir kembali tentang pemisahan antara anggota-anggota komunitas yang ditahbiskan dan yang tidak ditahbiskan, dan pengandaian umum bahwa rahib haruslah imam. Komunitas-komunitas apostolik berusaha menemukan karisma para pendiri mereka. Para Fransiskan memusatkan perhatian pada kesederhanaan hidup St. Fransiskus dan kesetiaan kawanannya dengan orang miskin. Para Yesuit menemukan kembali retret yang dibimbing secara pribadi, yaitu cara para Yesuit awal untuk memberi Latihan Rohani. Bagi kebanyakan komunitas religius wanita, kembali ke sumber berarti menemukan kembali fleksibilitas asli yang telah lenyap karena hidup mereka telah dimonastikkan oleh Gereja. Mereka meninjau kembali konstitusi dan pelayanan-pelayanan mereka. Banyak komunitas, diilhami Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini yang dikeluarkan Konsili untuk membaca ”tanda-tanda zaman” (GS 4), mulai lebih mengarahkan energi mereka demi keadilan sosial dan pelayanan kaum miskin. Bagi kebanyakan komunitas religius, proses pembaruan memakan banyak biaya. Pada waktu komunitas-komunitas meninjau kembali arti hidup religius, beberapa ”mitos” dan dasar pemikirannya ditafsirkan kembali. Selama berabad-abad, hidup religius dikatakan lebih tinggi dari panggilan awam. Hidup religius digambarkan sebagai ”status kesempurnaan” dan dipandang ”secara objektif lebih tinggi”. Terlalu kerap pengudusan diri dijadikan tujuan utamanya, sedang pelayanan atau pengabdian dipandang nomor dua. Bagi beberapa religius, penekanan Konsili bahwa semua orang Kristiani dipanggil ke kesucian, dianggap meniadakan salah satu alasan utama untuk menjalani hidup religius. Dalam dasawarsa sesudah Konsili, ribuan religius meninggalkan komunitas mereka. Selama 30 tahun ”jumlah kaum religius merosot 45% bagi Bruder dan Suster dan 27% bagi imam religius.”5 Beberapa komunitas mungkin akan lenyap dan bergabung dengan komunitas lain. Jika proses pembaruan menyakitkan, proses itu juga merupakan pembaruan dan pembersihan yang sejati. Hidup religius akan tetap hidup sebagaimana pada zaman-zaman kacau dan perubahan dalam Gereja, tetapi komunitas religius mungkin pada pertengahan abad 20 tidak akan besar jumlahnya. Dewasa ini ada banyak sekali ungkapan menjadi murid Kristus dan pelayanan, terutama bagi wanita. Komunitas-komunitas religius dewasa ini menghadapi sejumlah tantangan. Komunitaskomunitas akan terus bergulat menemukan keseimbangan antara individu dan komunitas, spontanitas dan struktur, kesetiaan kepada tradisi dan penyesuaian. Mereka harus menemukan cara untuk bersaksi tentang hidup yang sederhana di tengah zaman kemewahan. Mereka perlu menarik anggota-anggota baru. Akan tetapi, mereka juga diteguhkan oleh penekanan baru pada komunitas, penghargaan baru pada doa dan kontemplasi, dan kerelaan baru untuk keadilan sosial dan kesetiakawanan pada kaum miskin dalam sejarahnya. Gereja diperkaya oleh adanya komunitas-komunitas religius bukan karena cara hidup mereka lebih tinggi atau lebih sempurna dari cara hidup orang Kristiani lain, tetapi keberadaan komunitas-komunitas itu melambangkan keunggulan Injil dan menjadi murid Yesus yang menjadi panggilan semua orang Kristiani. Komunitas-Komunitas Awam Abad ke-20 juga menyaksikan munculnya berbagai komunitas awam di mana pria dan wanita, baik hidup sendiri maupun berkeluarga, berjuang untuk menjalani hidup menjadi murid. Komunitas Pekerja Katolik telah memberi makan dan memberi pakaian orang-orang miskin dan para gelandangan di kota-kota dan bekerja demi keadilan sosial sejak tahun 1933. Waktu itu Dorothy Day dan Peter Maurin mulai menerbitkan Catholic Worker (Pekerja Katolik), surat kabar radikal Katolik di kota New York. Sejak itu, dapur umum dan rumah-rumah penampungan telah menjadi ciri banyak kota besar di Amerika Serikat. Sekarang ini di Amerika Serikat ada 80 komunitas Pekerja Katolik. L’Arche (yang berarti bahtera), gerakan yang didirikan oleh Jean Vanier di Trosly-Breuil, Prancis tahun 1964, menyediakan rumah-rumah bagi orang-orang yang terlambat perkembangannya. Di rumah-rumah itu, mereka dapat hidup di dalam komunitas bersama dengan pria dan wanita normal, yang disebut ”assistant” (”pembantu”) yang membaktikan hidup mereka untuk merawat orang-orang malang itu. Komunitas-komunitas alternatif itu menjalani cara hidup yang terpusat pada doa dan Ekaristi. Spiritualitas mereka berdasar Sabda Bahagia Yesus, yang menyamakan diri dengan orang miskin dan orang yang menderita. Mereka yang bergabung dengan l’Arche mengetahui bahwa jika kita membuka diri terhadap orang miskin dan malang, kita mengetahui kehadiran Kristus dan mengalami kedamaian-Nya. Dewasa ini ada lebih dari 100 komunitas l’Arche di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah ekumenis dan antar penganut agama. Di banyak negara Dunia Ketiga dewasa ini, kelompok-kelompok kecil orang Kristiani, kerap kali tetangga dan kebanyakan miskin, membentuk Komunitas basis Kristiani. Para anggota berkumpul setiap minggu untuk berbagi keprihatinan dan iman. Kitab Suci mendapat perhatian utama dalam Komunitas Kristiani Basis. Para anggota merenungkan teks Kitab Suci untuk menyoroti pengalaman hidup mereka dengan Sabda Allah yang hidup. Komunitas-komunitas Kristiani Basis membantu memberdayakan orang-orang miskin dan mengembangkan kelompok baru pemimpin pastoral yang efektif dari masyarakat bawah (di Amerika Latin banyak pemimpin pastoral itu adalah wanita). Mereka telah berbuat banyak untuk memperbarui Gereja. Komunitas-komunitas Perjanjian mengambil asalnya dari gerakan pembaruan karismatik, yang mulai di dalam Gereja Katolik tak lama sesudah Konsili Vatikan II. Gerakan itu terdiri dari kelompok-kelompok orang Kristiani yang terlibat satu sama lain dalam berbagi hidup beriman. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:42-47, para anggota sepakat untuk berbagi hidup, iman, dan biasanya sumber keuangan mereka. Mereka biasanya berkumpul setiap hari untuk sejenak berdoa bersama. Komunitas Perjanjian kuat di Amerika Serikat dan di Prancis. Di Prancis pembaruan karismatik mungkin telah menjadi kekuatan utama untuk pembaruan Gereja. Mereka telah menolong banyak orang Kristiani, Katolik dan non-Katolik, untuk mengembangkan gambaran Allah yang lebih penuh kasih dan merasa nyaman dengan gaya doa yang lebih spontan dan efektif. 5. Hidup Sendiri, Tidak Menikah Hidup sendiri, tidak nikah, juga dapat merupakan panggilan, yaitu, panggilan dari Allah untuk menjadi murid dan melayani. Banyak pria dan wanita di dalam Gereja yang hidup sendiri, entah karena pilihan atau keadaan. Meski selibat pada umumnya tidak dihargai dalam Perjanjian Lama, gagasan untuk melepaskan hidup perkawinan demi Kerajaan Allah jelas merupakan nilai Injil. Yesus sendiri menjadi contoh utama untuk hidup sendiri yang dibaktikan itu, dan Ia mengajarkan bahwa orang-orang lain dipanggil untuk melepaskan perkawinan ”demi Kerajaan Surga” (Mat 19:12). Ungkapan ”demi Kerajaan Surga” merupakan kunci. Hidup sendiri dapat dipilih berdasarkan berbagai alasan demi keenakan diri. Orang dapat memilih hidup sendiri karena ia tidak mau bertanggung jawab atas hidup perkawinan, atau takut keintiman dan keterlibatan, atau memungkinkan gaya hidup yang terpusat pada diri dan kebutuhan-kebutuhan sendiri. Memilih selibat demi Kerajaan Surga berarti bahwa hidup sendiri tanpa nikah menjadi ungkapan hidup yang diserahkan demi cinta kepada Allah dan secara khusus membagi kasih itu kepada orang lain. Paulus mencerminkan pemahaman itu pada waktu ia membicarakan perkawinan dan hidup sendiri tanpa nikah sebagai karisma, kurnia Roh demi pembangunan Gereja (1Kor 7:7). Bagi sementara orang, hidup sendiri berarti hidup sebagai pertapa, dibaktikan untuk kontemplasi, doa, dan keheningan. Bagi yang lain, hidup sendiri dapat diungkapkan melalui pelayanan dan pengabdian di dalam Gereja. Hidup sendiri mungkin juga mencerminkan keterlibatan yang mendalam pada kurnia yang telah diterima dan dapat digunakan untuk memuliakan Allah dan membantu umat-Nya. Di luar orang-orang yang dipanggil untuk hidup religius, dalam sejarah Kristiani ada banyak contoh pria dan wanita yang telah memilih hidup sendiri untuk membaktikan diri pada seni, musik, studi, teologi, kedokteran, perawatan, pendidikan atau keadilan sosial – bukan hanya sebagai minat atau karier melainkan sebagai ungkapan iman dan menjadi murid. Bagaimana dengan mereka yang hidup sendiri tidak nikah bukan karena pilihan melainkan karena keadaan? Ada banyak orang yang ingin menikah tetapi tidak dapat menemukan pasangan. Yang lain kehilangan pasangan karena mati, pisah atau cerai. Bagi sementara orang, perkawinan tidak dapat mereka jadikan pilihan karena tidak mampu, orientasi seks atau keadaan fisik. Ini tidak menyarankan bahwa perkawinan adalah normal dan hidup sendiri merupakan gaya hidup kelas dua, tetapi untuk mengakui bahwa kadang-kadang impian-impian kita tidak dapat diwujudkan. Di antara kita tak ada orang yang bebas sebebas-bebasnya dan pilihan-pilihan kita kerap terbatas. Dengan demikian, panggilan dapat dipeluk maupun dipilih. Yang paling penting adalah bahwa orang menanggapi kehadiran Allah yang penuh rahmat dan panggilan-Nya untuk hidup bersatu mesra dalam keadaan hidupnya yang konkret dan khusus. Di sinilah terutama bidang-bidang pilihan terbuka. Kita dapat tetap tertutup pada diri sendiri dan merasa sakit hati karena peristiwa-peristiwa hidup dan keadaan dalam hidup kita tidak dapat kita kendalikan. Kita dapat berusaha mengisi kekosongan kita dan kesendirian yang merupakan bagian hidup setiap orang dengan harta milik atau kekuasaan atas orang-orang lain dan mengumbar berbagai macam kesenangan. Kita dapat membuka diri terhadap Allah yang selalu bersama kita untuk menarik harapan dari kekecewaan, kebaikan dari keburukan, hidup dari kematian. Justru di sinilah masing-masing di antara kita harus menjumpai salib dan memasuki misteri Paskah dari kematian dan kebangkitan Yesus ke hidup yang baru, yang tetap merupakan pola bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Yesus (Mrk 8:34-35; Fil 3:10; Yoh 12:24-25). Hidup sendiri, bahkan jika terpaksa oleh keadaan, dapat menjadi panggilan, pilihan Allah dalam misteri hidup kita sendiri dan perayaan iman yang menggembirakan. Menjalaninya sebagai panggilan adalah membiarkan diri kita diubah oleh rahmat. Panggilan untuk hidup sendiri, seperti panggilan lain, perlu dipupuk dengan doa dan ibadat dan diungkapkan dalam suatu kepedulian bagi komunitas yang lebih luas.6 Jika merupakan perayaan yang autentik atas kehadiran hidup Allah dalam hidupnya, hidup sendiri itu harus terbuka bagi orang-orang lain. Orang-orang yang hidup sendiri bebas untuk mencintai dengan cinta yang tidak eksklusif yang menyambut dan menghargai semua orang yang mereka jumpai. Mereka lebih bebas untuk melayani. Ini seharusnya juga berlaku bahkan bagi para pertapa. Para pertapa berbeda dengan orang yang hidup menyendiri. ”Keutamaan-keutamaan yang menjadi ciri pertapa yang sejati adalah belarasa dan keramahtamahan.”7 6. Kesimpulan Dalam bab 3, kita melihat bahwa Gereja diakui kudus sebagian karena Gereja merupakan kumpulan umat Allah yang kudus, yaitu orang-orang yang sudah dibaptis, yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus. Sayangnya banyak orang Kristiani masih terus mengira bahwa kesucian hidup hanya menjadi milik orang-orang kudus saja atau hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjalani hidup ”religius” dalam Gereja, seperti imam, bruder atau suster. Ini sama sekali salah. Dalam salah satu bab penting dari Konstitusi Dogmatik tentang Gereja yang berjudul ”Panggilan Umum Untuk Kesucian”, para uskup pada Konsili Vatikan II menekankan bahwa semua orang Kristiani dipanggil untuk kesucian, bukan berdasarkan status atau kedudukan mereka dalam Gereja tetapi justru dengan bekerja sama dengan rahmat Allah dalam keadaan konkret dari hidup mereka sehari-hari (LG 41). Bukan hanya religius tetapi semua orang Kristiani – uskup, imam, diakon, pasangan yang menikah, dan orang tua, orang yang hidup sendirian, dan mereka yang telah kehilangan pasangan mereka, para buruh, orang sakit dan orang lemah, orang miskin – dipanggil untuk kekudusan dan kesucian hidup, bukan dengan menjalani suatu religiositas buatan tetapi dengan menghayati hidup yang bercirikan ”doa, penyangkalan diri, pelayanan yang aktif terhadap sesama, dan latihan dalam segala keutamaan” – singkatnya, dengan menghayati cinta yang dicurahkan Roh Allah ke dalam hati kita (LG 42). Dalam bab ini, kita telah membahas panggilan semua orang Kristiani untuk menjadi kudus dalam kerangka panggilan Yesus untuk menjadi murid; mengikuti Yesus, yang merupakan inti hidup Kristiani; dan beberapa perbedaan ungkapan dari kemuridan dalam kehidupan Gereja. ”Menjadi murid” dalam Injil bukan merupakan sesuatu yang mengambil kita dari dunia. ”Menjadi murid” lebih merupakan undangan untuk mengubah cara kita memandang dunia, untuk bergabung dengan Yesus dalam pelayanan-Nya demi Kerajaan Allah, mencintai dengan cinta tanpa syarat, dan cinta yang penuh pengorbanan. Sesudah Paskah, menjadi murid mendapat makna tambahan, yaitu mengikuti Yesus dalam misteri Paskah-Nya. Semua orang dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan ada banyak ungkapan untuk menjadi murid dan pelayanan Kristiani di dalam Gereja. Banyak orang Kristiani menghayati panggilan menjadi murid melalui sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan bukanlah sakramen untuk diterima tetapi untuk dihayati, karena panggilan pasangan yang menikah dalam Kristus adalah untuk menggambarkan cinta Allah yang tidak bersyarat dalam cinta mereka satu sama lain dan kepada anak-anak mereka. Imam-imam mengungkapkan panggilan mereka menjadi murid melalui pelayanan sabda, sakramen, dan reksa pastoral umat Allah. Terutama dalam merayakan sakramen-sakramen bagi umat beriman, imam bertindak atas nama Kristus, dengan menunjukkan kehadiran Kristus dan kesetiaan-Nya terhadap umat-Nya dalam tindakan-tindakan sakramental Gereja. Sepanjang sejarah Kristiani, banyak pria dan wanita telah berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus melalui hidup religius. Dalam tradisi, hidup religius baik monastik maupun apostolik telah digambarkan sebagai tanda Kerajaan. Konsili Vatikan II meneguhkan pemahaman ini (PC 1). Akan tetapi, fungsi ini tidak dapat dibatasi pada komunitas-komunitas religius kanonis. Setiap komunitas Kristiani, entah awam atau religius, Katolik, Protestan atau ekumenis, yang anggota-anggotanya berusaha menghayati menjadi murid Kristiani secara publik berperan sebagai tanda Keraja-an Allah. Sebagai komunitas-komunitas yang hidup anggota-anggotanya berakar pada Injil, komunitas-komunitas itu merupakan tanda pelayanan penuh kasih bagi orang miskin, pendamaian antarmanusia, kesucian hidup, dan kesatuan dalam Kristus, yang semua itu merupakan tanda kerajaan. Akhirnya, banyak pria dan wanita yang menghayati panggilan mengikuti Yesus sebagai orang yang hidup sendiri, tidak nikah. Cara hidup mereka juga merupakan panggilan, karena dihayati tanpa pasangan atau komunitas karena mereka bebas untuk persahabatan yang tidak eksklusif dan kerap kali ikut ambil bagian dalam beberapa komunitas yang berbeda-beda. Panggilan itu juga tidak tanpa ungkapan sakramental, karena rahmat baptis menumbuhkan panggilan ini dan panggilan-panggilan lain. Keterlibatan terhadap Kristus sebagai orang yang hidup sendiri juga diteguhkan dalam perayaan Sakramen Ekaristi yang biasa. Panggilan-panggilan umum yang telah kita bahas hanyalah merupakan ungkapanungkapan panggilan untuk menjadi murid, yang ditujukan kepada semua orang yang menyatakan untuk mengikuti Yesus. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ”Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism,” Origins 23 (July 29, 1993). Hans Küng, Why Priest?: A Proposal For a New Church Ministry (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974) 42. Lih. Avery Dulles, ”Models for ministerial Priesthood,” Origins 20 (1990) 288. Paulus VI, Sacerdotalis coelibatus, 1967; Yohanes Paulus II, Résurrection, marriage et célibat: L’Evangile de la rédemption du corps (Paris: Cerf, 1985). David Nygren dan Miriam Ukeritis, ”Future of Religious Orders in the United States,” Origins 22 (1922) 257. Lihat Susan A. Muto, Celebrating the Single Life: A Spirituality for Single Persons (New York: Crossroad, 1989). Karen Karper, ”’By No Worldly Logic’: To Be a Hermit in the 1990s,” America 171 (September 10, 1994) 28. VII Dosa, Pengampunan, dan Penyembuhan Baru-baru ini seorang rekan di universitas menceritakan kepada saya tentang anaknya yang mempersiapkan pengakuan dan penerimaan komuni pertama. Ia sungguh terkesan terhadap katekese yang diterima anaknya dan pemahaman anak laki-lakinya tentang Ekaristi. Lalu ia berkata, sedikit terkejut, ”Anda tahu mereka tidak bicara lagi tentang dosa. Mereka berbicara tentang membuat pilihan-pilihan yang buruk.” Bagaimana mungkin di dunia yang banyak kejahatan yang sungguh nyata, kita sedemikian enggan berbicara tentang dosa? Karl Menninger, seorang Psikiatris, mengangkat masalah itu lebih dari 20 tahun yang lalu dalam bukunya Whatever Became of Sin?1 ”Jika aku OK dan kamu OK, dan teman-teman kita (orang-orang baik, dan seperti kita, jelas dari kelas menengah) OK, mengapa dunia jelas tak OK.”2 Agaknya lebih mudah merumuskan kejahatan daripada dosa. Adanya kejahatan di dunia kita jelas dengan sendirinya. Kita mengetahui contoh-contoh kejahatan yang menggemparkan pada zaman kita. Kita membaca tentang kejahatan dalam surat-surat kabar dan melihat contohcontoh setiap sore pada waktu kita menyaksikan berita di TV. Kita kerap tertimpa kejahatan dalam hidup kita sendiri atau dalam hidup orang-orang yang kita sayangi. Akan tetapi, kejahatan tetap merupakan sesuatu yang ada di luar diri kita. Dosa lebih rumit lagi. Dosa adalah segi pribadi dari kejahatan. Dosa berkaitan dengan pilihan-pilihan kita, dengan keterlibatan kita dalam misteri kejahatan. Kita kerap kali enggan mengakui keterlibatan kita. Rasa salah kerap merupakan tanda adanya dosa dalam hidup kita. Sayangnya dalam budaya terapeutik (pengobatan) kita, rasa salah kerap dianggap begitu saja sebagai masalah neurotik. Rasa salah tidak diakui sebagai tanggapan yang sehat terhadap kejahatan yang telah kita lakukan. Meski ada hal yang disebut rasa salah yang neurotik (misalnya dalam kasus skrupel atau kebingungan), pengalaman rasa salah juga dapat menjadi tanda suara hati yang sehat. ”Apa yang Anda dapat di dunia tanpa rasa salah adalah kamp Auschwitz, pemerkosaan kelompok, orang yang ambisius, pemboman membabi buta, pembuangan sampah beracun, penembak kendaraan, terorisme. Masyarakat kita – dan pendidikan religius – amat perlu menghentikan rasa salah yang sah”.3 Kita tahu bahwa kita melakukan hal-hal yang jahat, bahwa kita bertindak karena mau mengejar kepentingan diri sehingga merugikan orang lain, bahwa kita berdosa. Akan tetapi, kadang-kadang kita juga mempunyai perasaan bahwa dosa merupakan sesuatu yang lebih besar dari ”dosa-dosa” kita lakukan, bahwa dosa merupakan rakitan yang jauh lebih menyeluruh, bahwa dosa melebihi pilihan-pilihan buruk atau tindakan-tindakan salah. Dalam surat kepada umat di Roma, St. Paulus menangkap makna eksistensial dosa ini sebagai kekuatan yang menumbangkan intensi-intensi kita dan membatasi kemerdekaan kita: ”Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci .... Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kukehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku” (Rm 7:15,17-20). Kadang-kadang kita mendapatkan pandangan sekilas tentang kekuatan dosa yang destruktif ini, kekuatan yang dapat menangkap dan menguasai orang lain, yang mengakibatkan tragedi dan kehancuran hati di belakangnya. Betapa kerap kita telah membaca laporan tentang kejahatan yang mengerikan; korban yang tidak bersalah telah dibunuh secara brutal. Kita menjadi muak karenanya. Kita mau agar pelaku kejahatan itu dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi kerap kali, pada waktu kita mendengar lebih banyak tentang kasus itu, membaca laporan selengkapnya, kita menemukan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu telah menjadi korban, akibat keluarga yang bobrok, tidak pernah mengalami kasih orang tua atau masa kanak-kanak yang normal. Tiba-tiba kita mengerti cerita itu dengan terang baru. Kejahatan orang itu tidak dapat dimaafkan, tetapi amarah yang telah meledak menjadi tragedi bukan lagi misteri seluruhnya. Kejahatan itu mempunyai latar belakang dan mungkin sudah menyampaikan tanda-tanda peringatan selama bertahun-tahun. 1. Dosa dalam Tradisi Kitab Suci Dalam tradisi Kitab Suci, dosa dan hal yang dihasilkan, kejahatan, masuk ke dalam sejarah umat manusia pada bab-bab awalnya. Kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian bab 1 (Kej 1:1– 2:4a) berkali-kali menekankan bahwa ciptaan Allah itu baik adanya. Sesungguhnya, karya penciptaan Allah justru menghasilkan dunia yang teratur, hidup dari kekacauan yang gelap dan tak berbentuk. Dalam istilah-istilah yang lebih filosofis, mitos Taman Firdaus mengatakan bahwa di dunia tempat pria dan wanita ditempatkan oleh Allah tidak ada kejahatan. Mereka menikmati kekuasaan atas alam, kesamaan satu sama lain, dan berhubungan akrab dengan Penciptanya. Akan tetapi, kisah kejatuhan (Kej 3) memberi kesan bahwa nenek moyang kita yang pertama tidak puas dengan status mereka sebagai ciptaan. Dengan mudah mereka jatuh pada godaan ular agar makan buah terlarang, yang membuat mereka menjadi seperti Allah sendiri. Akibatnya, kemurnian mereka lenyap untuk selama-lamanya. Dosa mereka menghancurkan ciptaan, dan mereka mengalami tiga bentuk pengasingan. Mereka menjadi terasing satu sama lain, dari dunia tempat mereka hidup, dan dari Allah (Kej 3:7-19). Ada pemahaman mendalam dalam kisah itu. Dalam keinginan mereka menjadi Allah, penolakan Adam dan Hawa untuk mengakui bahwa hanya Allah saja yang menjadi Allah merupakan bencana besar. Jika kita membaca bab-bab selanjutnya dengan baik, jelaslah bahwa ada sesuatu yang baru di dunia, yaitu kejahatan yang merupakan akibat langsung dari egoisme manusia. Teks itu berkisah tentang pembunuhan atas saudara dan tak lama kemudian kejahatan manusia yang meningkat, mendatangkan Banjir Besar. Hanya karena campur tangan Allah yang langsung sajalah sejarah umat manusia dapat terus berjalan. Sepuluh Perintah Kisah kejadian yang termuat dalam Kitab Kejadian menunjukkan bagaimana dosa dan akibat-akibatnya yang menghancurkan masuk ke dunia. Karena dosa, hubungan akrab dengan Allah yang dinikmati nenek moyang kita yang pertama lenyap. Akan tetapi, Kitab Kejadian dan buku-buku Pentateukh yang lain juga merupakan pengantar untuk karya penyelamatan Allah. Tema-tema besar tentang pilihan dan perjanjian menunjukkan Allah yang memilih dan menjalin hubungan dengan umat-Nya. Sepuluh Perintah, ungkapan perjanjian yang pertama dan dasar dari Hukum Yahudi, merumuskan apa arti hidup dalam hubungan perjanjian dengan Yahwe (Ul 5:6-21; bdk. Kel 20:2-17). Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Janganlah membunuh. Janganlah berzinah. Janganlah mencuri. Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Janganlah mengingini istri sesamamu. Janganlah mengingini rumahnya atau ladangnya, ... ataupun segala sesuatu yang dipunyai sesamamu. Perintah-perintah itu tidak hanya dimengerti sebagai norma-norma etis. Perintah-perintah itu merupakan syarat-syarat perjanjian dengan Allah. Dengan demikian, ada dimensi yang amat pribadi pada pemahaman dosa Yahudi itu. Dosa berarti pemutusan hubungan. Dua pesan yang memuat sepuluh Perintah menguraikan dosa sebagai kebencian terhadap Allah (Kel 20:5; Ul 5:9). Akan tetapi karena sepuluh Perintah menuntut hormat terhadap orang lain sebagai syarat untuk ada dalam hubungan dengan Allah, maka jelaslah bahwa kebencian terhadap Allah dan menyalahgunakan orang-orang lain menjadi syarat yang sama. Dalam Kitab Suci Yahudi disebut beberapa dosa yang amat berat, dosa-dosa yang ”menyeru ke surga” di antaranya adalah pembunuhan saudara (Kej 4:10), menindas orang asing, janda atau anak yatim (Kel 2:20-22), atau mengambil keuntungan dengan tidak membayar upah pekerja pada waktunya (Bil 24:15). Yesus Yesus menerima adanya dosa. Ia mengajarkan kepada murid-murid-Nya bahwa dosa berasal dari hati manusia: ”Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat” (Mat 15:19). Secara tersirat Ia menunjukkan dalam kisah wanita yang tertangkap berzinah bahwa semua orang adalah pendosa, dengan menantang mereka yang sedemikian cepat menghukum wanita itu agar siapa pun di antara mereka yang tidak berdosa hendaknya paling dulu melemparkan batu (Yoh 8:7). St. Paulus Uraian Perjanjian Baru yang paling sistematis tentang dosa adalah surat St. Paulus kepada jemaat di Roma. Pada bagian pertama surat itu, Paulus mementaskan sebuah drama yang panggungnya adalah seluruh sejarah keselamatan. Para aktor dalam drama itu adalah Adam, Dosa, Maut, Hukum, dan Kristus. Adam memasukkan Dosa ke dunia, dan bersama Dosa muncul Maut. Maut merupakan buah Dosa, dan memang merupakan bagian rusaknya tatanan ciptaan yang benar yang sedemikian jelas dalam kisah kejatuhan dalam Kitab Kejadian. Dalam teologi Paulus, Dosa mendatangkan tiga macam kematian; pertama, kehancuran di dunia atau kematian yang diakibatkan dalam hubungan-hubungan kita. Dosa mengasingkan kita satu sama lain. Dosa mengakibatkan perpecahan-perpecahan ke dalam masyarakat (Rm 3:13-17; bdk. Gal 5:20). Kedua, Paulus menyebut dosa sebagai penyebab kematian fisik. Ia menulis bahwa maut menimpa semua orang ”karena semua orang telah berbuat dosa” (Rm 5:12). Dengan kata lain, maut menimpa semua orang bukan hanya karena Adam dulu berdosa, tetapi lebih tepat, karena semua orang hidup di dunia di mana dosa sudah masuk dan mereka sendiri secara pribadi telah berdosa dan dengan demikian mereka telah memenuhi syaratsyarat untuk mati. Dosa telah menjadi bagian dari kondisi manusia. Akhirnya, karena dosa mengasingkan kita dari Allah, dosa mendatangkan kematian kekal. Aktor besar keempat dalam drama Paulus adalah Hukum Musa, yang tampil di pentas bersama Musa. Apa fungsi Hukum? Orangorang Yahudi mempunyai keuntungan yang tidak dinikmati oleh orang-orang non-Yahudi; karena Hukum berperan untuk menyatakan keadaan dosa mereka. Tema ini untuk pertama kali diolah dalam surat kepada umat Galatia di mana Paulus menyebut Hukum sebagai ”penuntun” atau ”pendisiplin” (Gal 3:24) sebelum kedatangan Kristus. Dengan jelas Paulus berkata bahwa ”justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa (Gal 3:20) dan ”aku tidak mengenal dosa kecuali melalui hukum” (Rm 7:7). Orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum dibuat sadar akan dosa-dosa mereka, karena dosa membuat terbuka pelanggaran mereka atas hukum batin yang ditulis oleh kodrat di dalam hati semua orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi (Rm 2:1415). Akan tetapi, Paulus menekankan bahwa baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi telah berdosa. Hukum mengungkapkan hakikat dosa, tetapi tidak mampu membebaskan orang-orang Yahudi dari dosa karena hukum tidak mampu menghancurkan kekuatan dosa. Menghancurkan kekuatan dosa adalah karya Kristus, manusia yang menjadi gambaran Adam, manusia pertama (Rm 5:14) dalam teologi Paulus. Jika dosa dan maut masuk ke dunia karena ketidaktaatan satu orang maka karena ketaatan Kristuslah banyak orang akan dibenarkan dan rahmat akan berkuasa (Rm 5:19-20). Dalam surat kepada umat Roma bab 8, drama bergeser. Temanya bukan lagi dosa dan maut, tetapi rahmat dan hidup dalam Roh, bukan perbudakan dan belenggu tetapi kemerdekaan, ”buah-buah pertama” kematian dan kebangkitan Kristus (Rm 8:23). Meskipun dunia belum kembali ke tatanan ideal awal mula, namun pembenaran, rahmat, dan keselamatan sekarang tersedia bagi semua melalui Kristus dalam Roh. Sebelum Surat kepada umat Roma bab 8, Roh hanya disebut 5 kali; dalam bab 8 disebut 29 kali. Dalam Surat Pertama kepada umat Korintus, Paulus membicarakan Kristus sebagai ”Adam terakhir” dan ”manusia kedua” (1Kor 15:45,47). Dalam arti sebenarnya, karena Kristus umat manusia sudah diciptakan kembali. Dengan demikian, Kristus adalah Adam yang baru. Rahmat adalah istilah Paulus untuk tindakan penyelamatan Allah demi kita dan, sekaligus, untuk hidup baru yang datang pada kita sebagai akibat tindakan penyelamatan Allah. Dalam kenyataannya yang pokok, rahmat adalah keikutsertaan kita dalam hidup Allah sendiri melalui Kristus dan di dalam Roh. Paulus cukup realistis dan mengakui bahwa bahkan bagi orang yang sudah dibaptis ada pergulatan yang terus-menerus antara usaha untuk hidup dalam Roh dan keinginan-keinginan daging. Dalam suratnya kepada umat Galatia, perbedaan yang dibuatnya tentang ”perbuatanperbuatan daging” dan ”buah-buah Roh” memberi prinsip penegasan mengenai mutu hidup kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu – seperti telah kubuat dahulu – bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Tetapi buah-buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri (Gal 5:19-23). Singkatnya, bagi Paulus dalam arti yang paling mendalam, dosa lebih daripada masalah tindakan yang salah, ”pelanggaran hukum”. Dosa adalah keadaan eksistensial, kondisi-beradadi-dunia ontologis yang mengenai semua orang karena semua orang telah berdosa. ”Dua macam dosa dapat dibedakan. Pertama, seluruh umat manusia dirusak oleh dosa dan tunduk kepada kematian kekal. Kedua, dosa yang diketahui oleh orang yang mempunyai Hukum ketika tindakan-tindakan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan dilakukan. Bahkan hukum sipil berbicara tentang jenis dosa yang kedua itu, meski tidak amat tepat.”4 Ungkapan ”seluruh umat manusia” mungkin agak ekstrem. Akan tetapi, pemahaman pokoknya benar. Bagi Paulus kejahatan dosa yang sesungguhnya adalah akibat eksistensialnya, kacaunya arah dasar umat manusia kepada Allah. Dosa sebagai keadaan atau kondisi berarti bahwa struktur dinamis pribadi manusia menjadi semakin terarah kepada dirinya sendiri, dan dengan demikian lebih terarah kepada kematian daripada kepada Allah dan hidup. Kata yang digunakan Paulus untuk dosa adalah harmartia (bahasa Yunani) yang berarti ”tidak mengenai sasaran” atau secara lebih umum ”menyeleweng”, ”berjalan salah”. Kata itu menegaskan pandangannya atas dosa sebagai kekacauan radikal hubungan orang dengan Allah yang diberikan dalam ciptaan. 2. Ajaran tentang Dosa Dalam arti yang paling dalam, dosa jauh melebihi pelanggaran peraturan atau hukum. Personifikasi Paulus akan dosa sebagai kekuatan jahat yang merajalela di dunia amatlah tepat. Personifikasi itu amat sejalan dengan tradisi Kitab Suci, yang menguraikan makna sesungguhnya kesatuan komunitas manusia dan apa artinya menjadi bagian orang yang berdosa. Kedosaan kita sendiri untuk sebagian dijelaskan oleh komunitas manusia yang berdosa dimana kita menjadi anggota-anggotanya. Ada semacam kesetiakawanan dalam dosa, seperti juga ada kesetiakawanan dalam keselamatan. Dengan mudah kita melihat kekuatan kebiasaan jahat yang merusak dan bahwa ”kekerasan melahirkan kekerasan.” Dengan demikian, dosa melahirkan dosa, mengenai masyarakat tempat kita hidup. Akibat-akibat dosa bersifat dinamis. Seperti riak-riak air yang dibuat kerikil yang dilemparkan ke kolam, akibat-akibat dosa memencar dari sumbernya, mengenai orangorang yang ada di sekitar pendosa. Dosa Asal Jika Paulus memahami benar-benar bahwa dosa yang masuk ke dunia bersama-sama Adam merupakan kekuatan yang mengacau maksud-maksud baik kita dan membatasi kemerdekaan kita, St. Agustinuslah (meninggal tahun 430) yang merumuskan ”ajaran tentang dosa asal”. Untuk sebagian besar Agustinus memberi tanggapan terhadap Pelagius (meninggal ± 418), seorang guru asketis dari Inggris, yang berpendapat bahwa orang Kristiani dipanggil kepada hidup sempurna (lihat Mat 5:48) dan sesudah dibaptis mampu menghayati secara penuh hidup sempurna itu berkat kurnia kehendak bebas. Penekanan Pelagius pada kehendak bebas sepertinya membuat kodrat manusia sendiri merupakan ungkapan rahmat. Ia menyangkal bahwa dosa Adam mempunyai akibat nyata pada orang-orang yang lahir sesudahnya, melampaui kenyataan bahwa banyak orang berdosa karena ”peniruan.” Satu akibat dari penyangkalan ini bagi Pelagius adalah penolakan tradisi pembaptisan bayi yang sudah secara luas dilaksanakan. Mungkin kita dapat memahami Pelagius sebagai seorang humanis yang mengandaikan kebaikan fundamental kodrat manusia atau sebagai pembimbing rohani yang mau mendorong orang-orang lain untuk berusaha mencapai hidup sempurna. Agustinus yang bertobat menjadi Kristiani sesudah dewasa dan hanya sesudah pergulatan hebat (doanya yang terkenal, ”Tuhan, berilah aku kemurnian, tetapi jangan sekarang”)5 mempunyai pengertian tentang misteri dosa yang jauh lebih baik. Pengalamannya yang paling mendasar adalah tentang kekuatan rahmat Allah yang kuasa, yang pada akhirnya membebaskan dirinya dari hidup yang kacau balau. Dengan demikian, pengalaman pribadinya amat mempengaruhi teologinya. Ia berpendapat bahwa dosa Adam tidak hanya merusak kodrat manusia tetapi secara radikal menghancurkannya, yang membuat kehendak tidak mampu memilih kebaikan tanpa rahmat yang diperlukannya. Agustinus jauh melampaui konsep Paulus tentang kesetiakawanan umat manusia dalam dosa. Menurut Agustinus, dosa Adam diteruskan ke setiap orang melalui hubungan seks pada waktu pembuahan, oleh ”penurunan”. Bahkan dengan demikian, anak pun tercemar oleh dosa pertama atau ”asal” ini dan perlu dibaptis untuk membersihkannya dari keadaan berdosa. Teologi Agustinus membantu menjelaskan praktek pembaptisan bayi. Pembaptisan bayi dijadikan ajaran resmi Gereja oleh Sinode Daerah di Cartago (418) dan Konsili Orange II (529). Pada abad ke-16, baik teolog Reformasi maupun Katolik amat dipengaruhi oleh teologi Agustinus tentang dosa asal, tetapi mereka menafsirkan dengan cara yang berbeda. Dengan menggunakan kata-kata Agustinus, kaum Reformasi mengajarkan bahwa kodrat manusia secara radikal dihancurkan oleh dosa Adam dan imago Dei, citra Allah, yang tercermin pada budi dan kehendak manusia telah hilang. Budi, karena dibutakan oleh dosa, tak mampu mengetahui apa pun tentang Allah tanpa Kitab Suci. Tanpa adanya pengetahuan kodrati tentang Allah melalui refleksi filosofis, sejak itu terjadilah pemisahan antara akal dan iman yang sampai waktu itu tidak dikenal. Kehendak ada dalam keadaan terbelenggu, tak mampu memilih kebaikan berdasarkan kemampuannya sendiri. Kehendak tidak dapat bekerja sama dengan rahmat Allah; pembenaran seluruhnya merupakan karya Allah. Calvin mengikuti jalan pemikiran itu sampai pada kesimpulan logisnya dan, seperti Agustinus, berakhir dengan ajaran predestinasi. Pada tahun 1546 Konsili Trente menegaskan kembali ajaran Agustinus bahwa dosa Adam ”diteruskan oleh kelahiran bukan oleh peniruan” (DS 223), tanpa perlu mengambil pandangannya yang negatif terhadap hubungan seksual. Konsili mengajarkan, melawan kaum reformasi, bahwa baptis meniadakan kesalahan dosa asal, bahkan jika ”keinginannya pun”, kecenderungan terhadap dosa tetap ada pada kemampuan-kemampuan yang lebih rendah. Menurut pandangan Katolik, kodrat manusia dirusak oleh dosa tetapi tidak secara radikal dihancurkan. Jika kita kehilangan citra Allah, kita masih diciptakan menurut ”citra” Allah. Pendekatan Dewasa Ini Bagaimana sebaiknya kita memahami ajaran tradisional Gereja tentang dosa Adam dewasa ini? Ajaran tentang dosa asal berakar dalam sifat sosial dasar dari pribadi manusia. Sifat sosial manusia itu menyatakan bahwa masing-masing dari antara kita dilahirkan di dunia atau lebih konkret, jaringan hubungan antarmanusia telah dirusak oleh dosa. Kita dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial kita. Bahkan sebelum kita lahir, masing-masing di antara kita mempunyai kebutuhan akan perkembangan yang harus dipenuhi jika kita pada suatu saat diharap dapat secara penuh mewujudkan potensi kemanusiaan kita. Kita butuh diterima dan dicintai sebagai anak, jika kita diharap bahagia dan aman. Kita perlu dibelai, dipeluk waktu tidur dan dicintai, jika pada suatu saat nanti kita diharap mampu mencintai dan mengungkapkan pe- rasaan kita sendiri. Tanpa masyarakat manusia, dengan bahasa, budaya, dan hubunganhubungan pribadi, tak seorang pun di antara kita akan mengembangkan kemampuan untuk berbicara, berpikir abstrak, bahkan menyadari diri-sendiri. Kita belajar hidup dan berfungsi sebagai manusia dari masyarakat manusia di mana kita menjadi bagiannya, dan untuk sebagian besar kita dibentuk dan dididik oleh hubungan kita dengan orang tua, saudara-saudari sekandung, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena hubungan-hubungan itu sudah dirusak oleh egoisme, rasa-rasa yang tak pada tempatnya, pengasingan yang dimasukkan oleh dosa ke dunia, setiap orang tidak mendapatkan yang diperlukan, dirusak dan diperlemah oleh dunia yang berdosa tempat ia dilahirkan. Sejarah kita berisi luka-luka kekerasan, perang, ketidakadilan yang membuat anggota-anggota masyarakat sakit hati satu terhadap yang lain. Budaya kita kerap berprasangka terhadap mereka yang berbeda dari kita. Budaya-budaya itu mengajarkan peran sosial berdasar pada jenis kelamin yang fungsional tetapi juga membatasi. Bahasa kita mengkondisikan cara kita melihat kenyataan. Masing-masing dari kita telah dibentuk, dipengaruhi dan dengan berbagai cara dibatasi oleh keadaan historis dan sosial kita yang konkret, oleh keluarga, ras, budaya, seksualitas, lingkungan pribadi, dan hubungan antarmanusia. Karena semua itu tersentuh oleh dosa, maka kita pun juga tersentuh dosa dengan cara-cara yang jarang kita curigai. Kita kerap mengalami diri kita berantakan. Kita merasa bahwa hubungan kita kacau. Kita menyesali ketidakmampuan kita untuk mencinta. Sifat sosial dosa asal, yang membatasi kebebasan bahkan sebelum dilaksanakan, dapat dilihat dalam kisah-kisah anak-anak yang tak terbilang jumlahnya, yang tumbuh dalam keluarga yang tak berfungsi, mengalami kekerasan fisik dan seksual, anak-anak yang orang tuanya peminum, anak-anak di daerah kumuh di kota, atau dipaksa oleh teman-teman sebaya dan oleh ketidakamanan lingkungan hingga terseret masuk menjadi anggota ”gang”. Dosa asal berarti bahwa kita merasa sulit menjadi diri sendiri. Kita semua mengenal kisah orang-orang yang hancur dan hidup rusak, kerap tak mungkin diperbaiki lagi. Bahkan beberapa berhasil mengatasi sejarah pribadi mereka karena nasib baik, watak atau rahmat, banyak dari mereka yang telah menjadi korban dosa terus melakukan dosa melawan orang-orang lain. Demikian polanya diteruskan. Kita mengerti dinamika ini secara tersirat bahkan bila kita gagal melihat pola yang sama terjadi dalam hidup kita. Meski tidak selalu dimengerti dengan baik, ajaran tentang dosa asal tetap merupakan salah satu prestasi yang terbesar yang diperoleh Kristianitas, salah satu dari beberapa ajaran, sebagaimana kerap dikatakan, yang mempunyai bukti-bukti empirik. Ajaran itu mengungkapkan dalam bahasa yang tidak selalu memadai, hal-hal yang dewasa ini kita andaikan saja; konstitusi pribadi manusia yang paling mendasar, kekuasaan jahat yang menular, kehadiran di dalam hidup kita kekuatan-kekuatan negatif yang ada sebelum pilihan-pilihan sengaja kita, kebutuhan mendasar kita akan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya bila kita mengenal diri kita sebagai pendosalah kita dapat membuka diri kita terhadap sentuhan Allah yang menyembuhkan dan menerima pengampunan Allah. Dosa yang Kita Lakukan Perjanjian Baru mengakui bahwa dosa membawa kematian (Rm 6:16; 1Kor 6:9-10), tetapi juga menyadari bahwa tidak semua dosa ”mematikan” (1Yoh 5:16-17). Tradisi sudah menemukan tujuh dosa yang mematikan atau ”berat”: kesombongan, kerakusan, iri, amarah, keinginan nafsu jahat, gelojoh atau tak mampu mengendalikan nafsu makan, dan kemalasan. Perlu dibedakan antara dosa ”berat” (yang membawa maut) dan dosa ”ringan”. Dosa berat adalah pelanggaran yang menghancurkan hubungan dengan Allah. Dosa ringan adalah dosa yang merusak hubungan itu tanpa sepenuhnya memutuskannya. Perbedaan itu membantu. Tentu saja ada dosa-dosa yang kurang serius atau dosa-dosa serius menjadi kurang serius karena tidak tahu atau kurang bebas, apa yang oleh tradisi disebut ”kurang persetujuan penuh”. Dalam satu hari banyak kali kita gagal dalam hubungan kita dengan sesama, baik karena perbuatan maupun karena kelaliman. Namun kita belum memisahkan diri kita dari rahmat Allah dan dapat membuka diri kita terhadap hidup Allah dengan cara baru. Bersamaan dengan itu, ada dosa yang sedemikian berat sehingga memutuskan hubungan kita dengan Allah atau mungkin lebih tepat, sedemikian memenuhi diri kita dan memusatkan perhatian kita pada diri sendiri dan keinginan kita sendiri sampai Allah sungguh-sungguh dilepaskan dari hidup kita. Untuk melakukan dosa semacam itu, perkaranya harus serius dan kebebasan kita harus terlibat secara penuh. Dalam bahasa yang masih dipakai di dalam Gereja, Thomas Aquinas berpendapat bahwa dosa berat adalah dosa yang menyangkut perkara berat, cukup pemikiran, dan kesetujuan kehendak yang penuh.6 Pembedaan antara dosa berat dan dosa ringan itu berguna. Akan tetapi, pembedaan itu juga cenderung memperkecil dosa-dosa kecil dengan membuatnya menjadi tidak penting, dan terhadap dosa kecil itu orang dengan gampang dapat mengatakan, ”Hanya dosa kecil.” Teologi tradisional mengajarkan bahwa tidak ada dosa-dosa kecil yang jika dikumpulkan menjadi satu menciptakan dosa besar. Akan tetapi, yang diabaikan oleh cara pendekatan itu adalah dosadosa yang terus-menerus dilakukan cenderung melemahkan kehendak dan memperkuat kebiasaan-kebiasaan yang merusak dalam diri kita. Lama kelamaan situasi itu mengubah orientasi utama kita terhadap Allah ke diri kita sendiri. Bila kita terlalu terfokus pada diri sendiri, secara rohani kita sudah mati. Beberapa teolog dewasa ini telah menggunakan istilah ”opsi fundamental” (fundamental option) untuk menggambarkan proses pembentukan sikap atau pendirian moral dasar seseorang atas segala keputusan yang telah dibuat sepanjang hidupnya. Dari sudut pandang ini sulit untuk mengatakan pada saat mana dan oleh keputusan khusus mana pendirian dasar orang terhadap Allah dan sesama sudah ditentukan, meski seluruh pola dan arah hidup orang itu amat jelas. Setiap pilihan baik atau jahat adalah berarti, bahkan jika beberapa dosa lebih berat daripada yang lain. Misalnya, sulit untuk mengatakan bahwa dengan sengaja tidak menghadiri Misa pada suatu hari Minggu sama dengan memutuskan hubungannya dengan Allah. Akan tetapi, kebiasaan untuk tidak menghadiri Misa atau sikap yang tidak menganggap penting untuk memuji Allah secara teratur dan menjadi anggota umat yang berkumpul bersama untuk berdoa, dapat menggerogoti hubungan dengan Allah sampai pada suatu saat lenyap. Kita mengetahui betul-betul betapa mudahnya hubungan kita dengan seseorang yang kita cintai putus karena kurang perhatian. Baik konsep opsi fundamental maupun perbedaan antara dosa berat dan ringan memberi penjelasan yang memuaskan atas keterlibatan kita dalam misteri kejahatan. Pembedaan itu sudah lama ada dalam sejarah tradisi Katolik. Pembedaan itu mengakui bahwa beberapa perbuatan secara objektif jahat dan beberapa dosa sedemikian berat sampai menolak kasih Allah. Penekanannya pada perlunya pengertian yang mencukupi dan persetujuan yang penuh menghargai hakikat rumit dari motivasi dan kemampuan atas kebebasan yang kerap telah berkurang. Pada waktu yang sama, pembedaan itu dapat dengan mudah membentuk sikap legalistik (seberapa banyak? seberapa jauh?), memperkecil dosa-dosa ringan, dan untuk kesopanan. Istilah opsi fundamental kurang objektif dan yuridis, lebih psikologis. Istilah itu mengakui sifat kompleks dari kesadaran moral dan pentingnya pilihan dan perilaku dalam perkembangan pribadi. Istilah itu menyajikan pengertian yang lebih personal, biblis, yang melihat dosa tidak terutama dalam kerangka peraturan atau hukum melainkan dalam kerangka hubungan. Dosa mengasingkan kita dari Allah dan dari sesama. Kedua pendekatan itu telah memberi sumbangan besar dalam usaha kita untuk memahami kelemahan dan kemampuan kita untuk berbuat jahat, untuk berdosa. Dosa Sosial Pada tahun-tahun akhir ini, istilah-istilah seperti ”struktur dosa,” ”kekerasan yang dilembagakan,” dan ”dosa sosial” telah menjadi bagian kosa kata teologi moral.7 Khususnya Teologi Pembebasan telah memberi sumbangan besar pada peristilahan itu. Akan tetapi, gagasan bahwa struktur sosial dapat dipengaruhi oleh dosa yang hadir di dunia dan pada gilirannya ikut menciptakan perilaku yang merusak atau berdosa terhadap orang-orang lain, sudah ada dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang Gereja dalam dunia modern (GS 25). Para uskup Amerika Latin di Medelin (1968) berbicara tentang ”keadaan ketidakadilan yang dapat disebut kekerasan dilembagakan.”8 Kita dapat menambah contoh-contoh dosa sosial lain seperti rasisme, seksisme, militarisme, dan pencemaran lingkungan. Paus Yohanes Paulus II mengartikan dosa sosial dalam arti khusus. Dalam nasihat apostoliknya, Reconciliatio et Paenitentia, Paus menyatakan bahwa dosa sosial harus dimengerti secara ”analogis” (no. 16). Dalam ensikliknya, Sollicitudo Rei Socialis, Paus menggunakan istilah ”struktur dosa”, tetapi ia menekankan bahwa struktur-struktur itu selalu berakar pada dosa-dosa pribadi perorangan. Jaringan struktur-struktur itu tumbuh dan menyebar, lalu menjadi sumber dosa-dosa baru pada pihak orang-orang lain (no. 36). Dalam arti apa kita dapat berbicara tentang dosa sosial. Pada dasarnya, lembaga atau struktur tidak dapat menjadi subjek perbuatan moral, karena hanya orang-orang yang mampu membuat keputusan-keputusan moral. Akan tetapi, sejauh struktur memasukkan keputusankeputusan dan mencerminkan kepentingan-kepentingan manusia yang berdosa, struktur dapat menjadi moral atau imoral, dan kekuasaan untuk kejahatan yang dapat dilaksanakan oleh struktur itu amatlah besar. Gereja tidak ragu-ragu untuk mengajarkan ajaran-ajaran sosialnya, tidak hanya terhadap orang perorangan tetapi juga terhadap kelompok atau sistem sosial. 9 Hukum, struktur sosial, sistem ekonomis dan negara dapat memasukkan ke dalam dirinya kepentingan-diri yang sempit dari orang perorangan dan kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat. Jika melanggar hak-hak azasi manusia, membuat orang-orang lemah menjadi korban, atau melembagakan pembagian kekayaan yang tidak adil, struktur itu dapat dikatakan berdosa atau tidak adil. Apa yang mungkin paling merusak tentang struktur-struktur kejahatan adalah karena sifat sosial kita sehingga kita pasti terkena olehnya. Kita dapat menerima keadaan begitu saja karena kita diuntungkan, atau dengan susah payah melawannya. Dari sudut pandang ketidakpedulian atau keterlibatan menghadapi kejahatan, atau menjadi ikut dalam melawan kejahatan itu, kekuatan struktur dosa yang destruktif menjadi makin jelas. Di sinilah dosa sosial masuk. Dosa sosial berkaitan dengan kejahatan struktural yang secara moral patut dicela, kejahatan yang seharusnya perlu dilawan”10. Kita kerap merasakan keterlibatan kita dalam kejahatan sosial dan kebutuhan kita untuk dibersihkan dari rasa salah yang menyertainya. Kita merasa tercemar oleh kekerasan dan diskriminasi dalam masyarakat kita, tetapi tidak seperti orang Israel yang mempunyai upacara-upacara dan hari-hari pemberian silih (Im 4:13-29; Bil 29:7-11; Mzm 106), kita tidak mempunyai upacara-upacara sakramental untuk membersihkan diri kita dari keterlibatan kita dalam dosa semacam itu. Mungkin pada suatu hari Gereja merayakan ibadat tobat bersama dengan pengampunan umum untuk dosadosa sosial yang dengan jelas kita merasa bersalah. 3. Pengampunan dan Pendamaian Yesus Kristus berbicara lebih banyak tentang pengampunan daripada tentang dosa. Ia memaklumkan pengampunan dosa dalam pewartaan-Nya, menguraikannya dalam perumpamaan-perumpamaan, dan membuat orang mampu mengalaminya dalam perjamuan makan bersama-Nya (lihat Mrk 2:15). Perintah Yesus untuk memaklumkan pengampunan dosa merupakan bagian dari pesan Paskah (Yoh 20:23). Pertobatan dan Rekonsiliasi Gereja perdana lambat mengembangkan perayaan ritual pengampunan sesudah sakramen baptis. Mungkin umat Kristiani mengandaikan secara naif bahwa mereka yang telah menemukan hidup baru di dalam Kristus dan sudah dibaptis akan mampu menjalani hidup yang bebas dari dosa. Namun, sejak awal jemaat Kristiani sadar akan akibat-akibat dosa atas anggota-anggotanya dan menyediakan cara-cara untuk menangani para pelaku dosa berat. Dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama, St. Paulus memerintahkan agar orang yang hidup dengan istri ayahnya diusir dari jemaat (2Kor 5:1-13). Dalam kasus lain, Paulus mendorong jemaat agar mengampuni dan menyambut kembali orang yang telah ditertibkan karena pelanggaran (2Kor 5:5-11). Injil Matius melihat para pimpinan jemaat mempunyai kekuasaan akhir untuk ”mengikat dan melepaskan”, yaitu mengeluarkan dan menerima kembali mereka yang telah menyesal, seperti dalam tradisi sinagoga (Mat 18:15-18). Beberapa jemaat dalam beberapa kasus menolak untuk menyambut kembali pendosa-pendosa yang menyesal (Ibr 6:4-6). Beberapa dokumen sesudah Perjanjian Baru yang lebih awal (1Clement; Didache) berbicara tentang pengampunan dan pendamaian sesudah baptis, meski Pastor dari Hermas (Gembala dari Hermas) menyebutnya sebagai ”kesempatan kedua,” yang ditafsirkan berarti hanya satu kali. Pada akhir abad ke-2 dan awal abad ke-3, disiplin pertobatan seperti disiplin para katekumen mulai dilaksanakan. Mereka yang bersalah karena dosa-dosa berat – murtad, pembunuhan, perzinahan, masuk ke dalam kelompok peniten; mereka dipisahkan dari umat sesudah Liturgi Sabda dan hanya dapat diterima kembali ke dalam liturgi secara penuh oleh uskup sesudah masa doa dan puasa. Dalam beberapa Gereja, mereka yang masuk ke dalam kelompok peniten menerima abu pada dahi mereka sebagai tanda penyesalan. Praktek ini berkembang menjadi upacara Rabu Abu yang menandai Masa Puasa. Proses ”pertobatan kanonik” ini, yang kadang disebut sebagai ”baptis yang kedua dan yang lebih berat,” merupakan proses yang keras, terutama di dunia Barat. Pertama, karena yang masuk ke dalam kelompok peniten dipisahkan dari umat, ibadat itu bersifat publik. Kedua, orang hanya mendapatkan pendamaian ini sekali saja. Pada abad ke-6 praktek itu disalahgunakan. Kebanyakan orang menunggu pendamaian sakramental itu sampai menjelang ajal, meski ada berbagai usaha dari pihak Paus-Paus dan uskup-uskup untuk menghidupkan praktek ibadat itu. Sejak abad ke-6 perayaan pengampunan baru, yang diperkenalkan ke Eropa oleh rahib Irlandia, mulai menjadi populer. Praktek itu mempunyai akar dalam tradisi monastik, di mana rahib yang mencari pengarahan dan bimbingan mengakukan dosa-dosanya kepada anggota komunitas yang lain – dan tidak selalu imam – dan akan menerima penegasan pengampunan dosa. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan praktek ini adalah pengakuan dosa pribadi dan orang dapat melakukannya berulang-ulang. Sebagai ganti waktu pertobatan umum yang panjang, ”orang yang menerima pengakuan” (confessor) akan memberi tugas pertobatan khusus seperti pantang makan makanan-makanan tertentu untuk dosa-dosa ringan, atau hubungan seks atau penggunaan senjata untuk dosa-dosa berat seperti perzinahan atau penumpahan darah. Rahib-rahib Irlandia mengumpulkan denda-denda dosa itu dalam buku yang disebut buku Paenitentiales sebagai bantuan bagi para penerima pengakuan dosa. Gereja di benua Eropa menanggapi praktek ini sebagai penyalahgunaan. Berbagai Konsili dan Sinode berusaha untuk melarangnya. Akan tetapi, praktek itu jelas memenuhi kebutuhan pastoral, dan pada abad ke-10 pengakuan pribadi sudah menjadi praktek yang hampir umum. Untuk mengakuinya, Konsili Lateran IV mengeluarkan dekrit pada tahun 1215 bahwa setiap orang Kristiani yang telah melakukan dosa berat harus mengakukannya dalam waktu 1 tahun. Perhatikanlah bahwa hukum itu, yang masih tetap berlaku, menuntut agar orang mengakukan dosa-dosanya setiap tahun hanya jika ia mempuyai dosa berat untuk diakukan. Banyak orang masih berpendapat salah bahwa orang harus mengaku sebelum menerima Ekaristi. Dengan demikiran pengakuan dosa secara pribadi tidak lagi dipandang sebagai penyalahgunaan, tetapi peraturan. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, bagi orang Kristiani yang menjadi dewasa sebelum Konsili Vatikan II, pengakuan yang kerap itu menjadi norma. Di belakang praktek ini ada tekanan yang terlalu berlebihan pada dosa yang merupakan bagian pandangan zaman pra Konsili Vatikan II, dengan ciri-ciri: ”otoritas, dosa, ibadat, dan mukjizat”.11 Devosi Katolik yang amat dipengaruhi oleh pesimisme Agustinus ini melihat ancaman dosa di mana-mana. Bukubuku doa dan pegangan-pegangan devosi, pemeriksaan batin yang berkepanjangan, devosi kepada Hati Kudus dengan tekanan pada pemulihan dosa, retret umat dengan khotbah-khotbah tentang neraka dan uraian tentang siksaan bagi para pendosa yang dihukum, curiga terhadap dunia sekular, dan terutama pengakuan berkali-kali merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai ”budaya dosa.”12 Satu akibat dari budaya dosa ini adalah bahwa banyak orang Katolik membayangkan Allah sebagai hakim yang keras, yang membuat catatan-catatan yang rapi dan menunggu orang membuat kesalahan-kesalahan. Banyak orang Katolik yang saleh pergi mengaku beberapa kali setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Di sekolah-sekolah Katolik anak-anak diperbolehkan meninggalkan kelas untuk pergi ke pengakuan sebelum ”Jumat Pertama” setiap bulan bila memang mereka diharapkan menghadiri Misa. Dewasa ini, praktek menerima sakramen pengakuan disebut sebagai ”pengakuan devosi” (sebagai lawan dari pengakuan wajib) karena kebanyakan orang datang mengakukan dosa meskipun mereka tidak mempunyai dosa berat untuk diakukan. Seperti banyak devosi Katolik, praktek menerima sakramen pengakuan berkalikali ini menghilang sesudah Konsili Vatikan II. Rekonsiliasi Dewasa Ini Banyak orang Katolik dewasa ini merasa bahwa pendamaian atau rekonsiliasi sakramental itu sulit. Beberapa orang yang ter-biasa dengan praktek pengakuan yang rutin masih tetap merasa perlu mendaftar segala kegagalan mereka, betapapun tak berartinya. Beberapa orang tidak mengaku dosa lagi karena mereka tidak merasa bahwa ”daftar” dosa mereka, entah nyata atau hanya bayangan, amat bermakna. Orang-orang lain lagi merasa tidak nyaman karena mereka tidak tahu lagi bagaimana ”mengaku dosa” dewasa ini. Saya kerap mendapatkan pengalaman tentang siswa yang mengenal saya ter-utama ketika seorang guru bertanya, ”Apakah kamu mengakukan dosa?” Fakta bahwa selama berabad-abad dalam hidup Gereja orang hanya dapat menerima pendamaian sakramental ritual hanya satu kali dan kemudian hanya untuk dosa-dosa berat merupakan bukti yang jelas bahwa komunitas Kristiani saat itu, seperti juga sekarang, mengenal berbagai cara untuk mengalami rahmat pengampunan. Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita bahwa dosa-dosa kita diampuni jika kita mengakuinya dengan tulus (Luk 18:9-14; 1Yoh 1:9), atau saling mengakukan (Yak 5:16). Kita dapat mohon pengampunan dosa dengan berdoa kepada Allah dengan rendah hati. Ibadat tobat pada awal liturgi dapat menjadi pengalaman pengampunan yang kaya bila kita melakukannya dengan menyesal atas sesuatu yang sungguh kita sesali. Sakramen pendamaian atau rekonsiliasi dapat merupakan rahmat yang amat menyembuhkan karena membuat kita mampu mendengar kepastian pengampunan dari Allah dari orang yang diberi kuasa oleh Gereja untuk bertindak atas namanya sebagai wakil Kristus. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa kita adalah pendosa. Kita dapat mengatakan hal ini tanpa perlu mengakukan dan dengan demikian tidak perlu banyak usaha. Akan tetapi, mengakui bahwa kita telah tidak jujur, merugikan nama baik orang, memanfaatkan sesama, jauh lebih sulit. Pengakuan itu menuntut agar kita memeriksa perilaku kita secara jujur, agar kita mengakui di hadapan bapa pengakuan kita bahwa kita telah gagal di jalan menuju hidup suci yang menjadi panggilan kita. Pada hakikatnya sakramen pendamaian atau rekonsiliasi adalah dialog antara dua orang; orang yang mengaku, yang dosa-dosanya telah mengurangi jemaat dan mendatangkan halangan dalam hubungan orang itu dengan Allah, dan imam yang mewakili Kristus dan Gereja. Orang yang mengaku mengakui bahwa dirinya adalah orang pendosa, mengakukan dosadosanya yang menurutnya penting, dan mohon pengampunan. Bapa pengakuan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberi denda, kerap berdoa bersama orang yang mengaku itu, dan menyatakan pengampunan Allah dengan rumusan absolusi (pengampunan) sakramental Gereja. Dialog antara imam dan orang yang mengaku dan kesedihan serta kehendak untuk memperbaiki diri yang diungkapkan jauh lebih penting daripada rumusan atau ”kata-kata yang tepat”. Orang yang belum biasa dengan ibadat pengakuan dan kacau karena kebingungan atau kesedihan hanya perlu dibantu. Upacara Pertobatan Baru Ibadat Pertobatan Baru, yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ibadat Ilahi pada tahun 1973, menyediakan tiga bentuk ibadat. Pertama, pengakuan perorangan dan pengampunan/absolusi. Kedua, merupakan ibadat tobat bersama yang diikuti dengan pengakuan dan pengampunan/absolusi. Ketiga, memberi kemungkinan pengampunan umum, tetapi hanya dalam situasi-situasi tertentu; jumlah orang yang hadir harus tidak terlalu besar untuk dapat mengaku secara perorangan dan mereka yang menerima sakramen pengakuan ”harus memutuskan untuk mengakukan pada waktunya dosa-dosa beratnya yang tidak dapat diakukan dalam ibadat itu (no. 33). Dalam ibadat baru itu, penekanan jauh lebih pada penyembuhan dan rekonsiliasi daripada pengampunan dosa secara yuridis. Dengan demikian ibadat itu lalu disebut sebagai ”sakramen rekonsiliasi”. Untuk ibadat rekonsiliasi perorangan seluruh suasana berbeda. Kebanyakan Gereja sekarang ini menyediakan ruang pengakuan, ruang yang diatur bagus dengan meja yang ada Kitab Suci dan kerap kali lilin, untuk merayakan sakramen itu. Meskipun orang yang mengaku dapat memilih mengaku secara terpisah, sekarang ini mulai banyak yang mengaku dengan duduk berhadapan dengan bapa pengakuan. Imam menyambut orang yang mengaku dengan kata-kata sambutan yang membesarkan hati, biasanya dengan kata-kata dari Kitab Suci. Imam dapat membaca – jika waktu mengizinkan – kutipan dari Kitab Suci, sesudah itu orang yang mengaku mengakukan dosadosanya, mulai dengan mengatakan sesuatu seperti ”Berkatilah saya Pater/Romo, karena saya telah berdosa” atau ”Saya mengakukan dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya adalah .... Untuk dosa-dosa itu saya mohon pengampunan dan absolusi....” Imam lalu menyarankan denda, doa, kerja amal, atau tindakan simbolis yang harus dilakukan sebagai tanda kesedihan dan silih. Kemudian imam meminta orang yang mengaku dosa berdoa untuk pengampunan dan penyembuhan. Banyak orang Katolik pada waktu mengaku itu mendoakan doa penyesalan, tetapi berdoa mohon bantuan dan pengampunan Allah, entah didoakan keras atau dalam hati, akan cukup. Akhirnya, imam mengulurkan tangan dan mendoakan doa absolusi, dan orang yang mengaku menjawab ”Amin”. Ibadat tobat model baru memungkinkan lebih banyak dialog antara imam dan orang yang mengaku daripada ibadat lama. Banyak orang yang memanfaatkan sakramen pengakuan untuk mendapatkan kesempatan mengadakan percakapan rohani pendek. Mereka jarang menerima sakramen pengakuan, tetapi mereka menerimanya dengan persiapan dan renungan yang lebih sungguh-sungguh. 4. Penyembuhan dan Pengurapan Orang Sakit Sakramen rekonsiliasi merupakan sakramen penyembuhan. Ketika kita mengakui dosadosa dan kegagalan-kegagalan kita, kita membuka diri terhadap rahmat Allah yang mengubah. Rahmat mendamaikan kembali kita dengan Allah dan memulai proses penyembuhan akibatakibat negatif dosa dan kejahatan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang lain, yang membuat kita mampu menjadi terlibat dalam penyembuhan luka yang telah diakibatkan oleh dosa antara kita dan orang-orang lain. Ekaristi juga merupakan sakramen penyembuhan yang membarui perjanjian kita dengan Allah (SC 10). Namun, rahmat penyembuhan tidak terbatas pada sakramen rekonsiliasi dan Ekaristi. Sejak zaman Perjanjian Baru, Gereja telah memohonkan rahmat penyembuhan Allah bagi orang sakit dengan doa dan upacara. Penulis surat St. Yakobus menulis, ”Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni” (Yak 5:14-15). Gereja berdoa agar rahmat penyembuhan Kristus menyentuh seluruh pribadi tidak hanya penyembuhan fisik, tetapi agar orang yang sakit mendapatkan pengampunan dan harapan. Sakramen Orang Sakit Bukti adanya sakramen ini amat sedikit pada abad-abad awal. Hippolytus membicarakan uskup yang memberkati minyak dengan doa, agar minyak itu ”memberi kekuatan kepada semua yang merasakannya dan kesehatan kepada semua yang menggunakannya” (Traditio Apostolica 5). Pada abad-abad awal, minyak yang diberkati oleh uskup digunakan dengan berbagai cara untuk penyembuhan. Kadang-kadang orang sakit meminumnya atau mengoleskannya pada diri mereka, atau para anggota keluarga mengolesi mereka dengan minyak dan menyertai pengolesan itu dengan ”doa iman”. Pada zaman pembaruan Karl Agung (740-840) muncul buku-buku upacara yang memuat ibadat pengurapan orang sakit dan Viaticum, Komuni suci sebagai ”makanan untuk perjalanan.” Buku-buku itu harus digunakan oleh imam-imam dalam memberikan sakramen tobat bagi orang yang akan meninggal. Sejak zaman itu, pengurapan orang sakit hanya boleh dilakukan oleh imam-imam, dan ibadat semakin dikaitkan dengan persiapan untuk meninggal dan pengampunan dosa.13 Pada abad ke-12, Petrus Lombardus memasukkan ”pengurapan terakhir” ini ke dalam daftar tujuh sakramennya. Akibatnya, muncul nama yang tak mengenakkan ”pengurapan terakhir” sampai Konsili Vatikan II. Dalam pembaruan sakramennya, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa pengurapan terakhir dapat juga dan lebih cocok disebut dengan nama ”Pengurapan Orang Sakit”, dengan menekankan bahwa ”sakramen itu bukanlah sakramen bagi mereka yang berada di ambang kematian saja” (SC 73). Dewasa ini sakramen itu dimengerti sebagai sakramen bagi kesehatan dan penyembuhan. Sakramen itu dirayakan bagi orang yang sakit keras, orang yang sudah berumur, mereka yang akan menjalani operasi besar, dan kadang-kadang bagi mereka yang menderita trauma psikologis. Sakramen itu dapat merupakan pengalaman yang hebat bagi semua orang itu, membantu mereka untuk menemukan rahmat Allah justru pada saat sakit, tak mampu, atau menjelang kematian. Ibadat yang sudah diperbarui menempatkan sakramen pengurapan dalam konteks reksa pastoral bagi orang sakit.14 Unsur-unsur paling penting dalam ibadat itu adalah pewartaan Sabda, doa iman, penumpangan tangan, dan pengurapan dahi serta tangan dengan minyak. Yang amat penting adalah sentuhan manusia. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan menyentuh mereka (Mrk 1:41; 8:23; Luk 4:40). Sentuhan manusia dengan penumpangan tangan membantu menjembatani pemisahan yang kerap dialami oleh orang sakit, terutama menjelang ajalnya. Orang sakit perlu mengetahui bahwa ia tidak sendirian, bahwa sahabatsahabat, mereka yang dicintai dan Gereja ada bersamanya. Karena alasan yang sama, sakramen itu sebaiknya dirayakan bersama. Sakramen dapat dirayakan pada ibadat Ekaristi, atau jika orang yang sakit tidak lagi mampu beranjak dari tempat tidur, di hadapan para anggota keluarga yang menggabungkan doa mereka dengan doa imam. Reksa pastoral orang sakit menyangkut lebih banyak orang daripada imam. Pengolesan dengan minyak atas orang sakit mengingatkan orang akan pengurapan baptis mereka dan penyatuan dirinya dengan Kristus dan dalam misteri Paskah. 5. Kesimpulan Banyak pemikir pada masa kini kerap menggunakan adanya sedemikian banyak penderitaan dan kejahatan di dunia sebagai argumen untuk melawan adanya Allah. Sedemikian banyak penderitaan, terutama yang menimpa mereka yang tidak bersalah, merupakan halangan untuk percaya. Bagaimana Allah yang sedemikian baik menciptakan dunia semacam itu, bagaimana Allah Yang Mahakuasa membiarkan terjadi sedemikian banyak penderitaan? Misteri kejahatan tidak begitu mudah untuk dimengerti. Sudah sejak awalnya tradisi Kitab Suci menekankan bahwa ciptaan itu baik. Kisah penciptaan pertama merayakan kemenangan Allah atas kekuatan-kekuatan kekacauan untuk menciptakan dunia yang indah dan teratur (Kej 1:1–2:4a). Masalahnya bukan pada dunia ciptaan melainkan dalam hati makhluk yang ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ciptaan, pria dan wanita, yang diciptakan menurut citra Allah, yang mampu menerima dan menanggapi cinta tetapi juga mampu menolak karunia itu. Karena kita diciptakan sebagai makhluk bebas, Allah tak dapat memaksa cinta kita. Allah hanya dapat mengundang kita untuk menjawab dengan bebas. Bersama kebebasan muncul kemungkinan dosa, yang masuk ke dunia karena pilihan bebas manusia. Tradisi Kitab Suci menekankan kenyataan dosa yang tersebar di mana-mana. Dosa adalah kekuatan yang merajalela di dunia, yang mendatangkan penderitaan, kematian, dan kehancuran. Akan tetapi, daripada mengakui kekuatan dosa yang destruktif, kita cenderung mempersalahkan Allah atas adanya penderitaan dan kejahatan itu. Bagian dari masalah adalah kecenderungan alamiah untuk terlalu menekankan kekuasaan Allah. Kita kerap berpikir tentang Allah dalam kerangka filosofis, dengan menyebut Allah sebagai ”Mahakuasa”. Pada kenyataannya, sebagaimana dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, justru penciptaan kebebasan oleh Allah merupakan pembatasan-diri kekuasaan Ilahi: ”Dalam arti tertentu, orang dapat menyatakan bahwa berhadapan dengan kebebasan manusia, Allah memutuskan untuk membuat Diri-Nya tak berdaya.”15 Allah tidak dapat tidak menghormati kebebasan kita. Oleh karena itu, daripada melihat Allah sebagai penyebab langsung setiap peristiwa, lebih masuk akallah membayangkan lamanya penderitaan dan belas kasih Allah yang secara misterius pada karya yang membawa kebaikan dari kejahatan, kemenangan dari kekalahan, kehidupan dari kematian. Hal ini tak ditunjukkan secara lebih jelas di mana pun kecuali dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Pandangan tentang dosa yang muncul dalam Alkitab dengan demikian bersifat pribadi. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah dan mengasingkan kita satu sama lain. Kejahatan terakhir dosa ditunjukkan dalam keperkasaannya atas Yesus, ”Orang yang benar” (Kis 3:13; 7:52) dengan mendatangkan kematian-Nya. Namun demikian, kematian dan kebangkitan-Nya menyatakan kemenangan besar Allah atas dosa, mematahkan kekuasaannya sekali untuk selamanya dan mengadakan perjanjian baru dalam darah Kristus (Luk 22:20). Sewaktu menulis kepada umat di Korintus, Paulus membicarakan misteri salib sebagai ”kelemahan Allah” yang ternyata lebih kuat daripada kekuatan manusia (1Kor 1:25). Baru pada abad ke-5 Agustinus merumuskan apa yang kemudian menjadi ajaran tentang dosa asal, tetapi akarnya sudah ditemukan dalam surat St. Paulus dan kita dapat merasakan akibat-akibatnya dalam hidup kita sendiri. Masing-masing dari kita dipengaruhi oleh kelahiran kita ke dunia yang berdosa dan membutuhkan belas kasihan Allah. Kita menyadari kedosaan kita, bahwa kita hancur, bahwa kita butuh disembuhkan dan dibebaskan. Kita dapat berdosa karena perbuatan dan kelalaian, seperti diajarkan Yesus dalam perumpamaan tentang hari penghakiman; ”Ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum” (Mat 25:31-46). Tobat dan pengurapan orang sakit merupakan sakramen-sakramen penyembuhan. Mewartakan pengampunan dosa merupakan tema sentral dalam pewartaan Yesus, dan Gereja terus memaklumkan pengampunan atas nama-Nya (Yoh 20:23). Dalam sejarah Gereja, sakramen pengampunan telah mengambil beberapa bentuk. Jika orang-orang Katolik dewasa ini ikut serta dalam ibadat tobat yang baru, mereka akan mendapatkan buah yang banyak dalam sakramen yang memberi tekanan pada doa, penyembuhan dan rekonsiliasi itu. Dewasa ini banyak Paroki menyelenggarakan ibadat tobat dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk pengakuan pribadi sebagai bagian dari pengisian masa Adven dan Puasa. Pelayanan penyembuhan Yesus terus ditampakkan dalam sakramen pengurapan orang sakit. Dalam sejarah, sakramen itu juga telah mengambil beberapa bentuk dan memberi beberapa tekanan. Ibadat yang baru menekankan penyembuhan orang sakit dari akibat-akibat kejahatan dan dosa, yaitu dari penyakit, penderitaan dan ketakutan akan kematian. Sakramen itu membawa rahmat penyembuhan Kristus dan memperkuat mereka yang mendekati kematian dengan janji dibangkitkan kembali. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Karl Menninger, Whatever Become of Sin? (New York: Hawthorn, 1973). Kathleen Norris, Dakota: A Spiritual Geography (Boston: Houghton Mifflin, 1993) 97-98. Wiliam J. O’Malley, ”A Sane Sense of Sin,” America 172 (April 8, 1995) 11. Martin Luther, ”The Psalm Miserere,” Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan (St. Louis: Concordia, 1955) 12:307-308. Augustinus, Confessiones 8.7. Thomas Aquinas, Summa Theologiae I-II. 88.2.6. Lih. Mark O’Keefe, What Are They Saying About Social Sin? (New York: Paulist, 1990) 13-17. CELAM II, ”Peace,” no. 17. Lihat Peter J. Henriot, Edward P. DeBerri dan Michael J. Schultheis, eds., Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret (Mayknoll, N.Y.: Orbis, 1988). Joseph Mckenna, ”The Possibility of Social Sin,” The Irish Theological Quarterly 60 (1994) 130. Jay Dolan, The American Catholic Experience (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1985) 221. Ibidem, 226-227. Lihat John J. Ziegler, Let Them Anoint the Sick (Collegeville: The Liturgical Press, 1987) 68-70. Ibadat itu pada awalnya disebut Ibadat Pengurapan dan Reksa Pastoral Orang Sakit. Setelah ditinjau lagi ibadat itu disebut Reksa Pastoral Orang Sakit: Ibadat Pengurapan dan Viaticum (Washington: ICEL, 1982). Yohanes Paulus II, Crossing the Threshold of Hope, ed. Vittorio Messori (New York: Random House, 1994) 61. VIII Moralitas Seksual dan Keadilan Sosial Menjadi murid Kristus harus membentuk hidup interpersonal dan sosial kita. Moralitas seksual berkaitan dengan ungkapan yang tepat dari dorongan, keintiman, cinta dan penerusan keturunan, yang memegang peran sedemikian penting dalam hubungan antarpribadi kita. Keadilan sosial menggambarkan apa yang terjadi bila masyarakat kita ditata sedemikian rupa sehingga setiap orang dihormati dan dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Masalah-masalah yang diangkat oleh kedua bidang itu menyentuh diri kita secara pribadi. Kedua bidang itu telah ditanggapi secara luas oleh otoritas mengajar Gereja dan kedua bidang itu merupakan bidang perselisihan pendapat yang menimbulkan banyak emosi, perhatian, dan tanggapan yang berbeda terhadap otoritas Gereja. Beberapa orang Katolik dewasa ini tidak menyetujui ajaran Gereja tentang masalahmasalah pengaturan kelahiran, perceraian, dan pernikahan kembali, hubungan seksual di luar nikah, dan perkawinan antara orang homo, dan (pada tingkat yang kurang luas) pengguguran. Orang-orang Katolik lain, yang menerima ajaran Gereja tentang masalah-masalah itu mendapatkan kesulitan besar untuk menerima ajaran Gereja di bidang keadilan sosial, misalnya, tentang hak orang untuk berimigrasi, penggunaan senjata-senjata nuklir untuk menakut-nakuti, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif, yang menegaskan hak semua warga negara untuk ikut ambil bagian secara sama dalam kehidupan ekonomi. Demikian juga, di masa lalu beberapa orang Katolik tidak menyetujui ajaran Gereja tentang hak kaum pekerja untuk bergabung dalam serikat buruh atau penghukumannya atas kejahatan rasisme dan pemisahan orang menurut warna kulit. Dalam bab ini akan kita bahas moralitas seksual dan keadilan sosial. 1. Moralitas Seksual Secara jujur harus diakui bahwa Gereja Katolik telah amat mendua dalam sikapnya terhadap seks. Dari satu pihak, Gereja mengakui bahwa seksualitas merupakan anugerah Allah yang baik yang diberikan kepada nenek moyang kita pertama untuk cinta timbal balik mereka dan untuk mendatangkan kehidupan baru di dunia. Ini telah selalu menjadi keyakinan mendalam tradisi Katolik. Di pihak lain, Gereja tampaknya takut-takut terhadap kekuatan misterius seksualitas. Menggunakan pesimisme St. Agustinus, Gereja kerap kali menyempitkan makna hubungan seksual pada prokreasi (penciptaan anak), hampir tidak menenggang kesenangan pasangan yang menyertai hubungan seks itu. Berdasarkan pandangan itu, berkembanglah teologi moral yang cenderung memandang seksualitas dalam kerangka tindakan abstrak daripada hubungan manusia yang kompleks. Pandangan Katolik bahwa seksualitas merupakan kurnia ilahi yang mendapatkan pemenuhannya yang tepat dalam hubungan kasih dan khusus, terbuka untuk terciptanya hidup baru, berakar dalam Kitab Suci. Kitab Kejadian mengajarkan bahwa seks adalah untuk prokreasi (ikut penciptaan manusia) (1:28) dan cinta kasih timbal balik (2:18-24). Kidung Agung, puisi yang jelas-jelas erotik, merayakan cinta fisik antara pria dan wanita. Yesus mengandaikan lembaga perkawinan bersifat ilahi dan meneguhkan kembali ketidakdapatputusnya hubungan perkawinan. Dengan menolak kelonggaran hukum Musa yang memperbolehkan pria menceraikan istri tetapi bukan sebaliknya, Yesus mengajarkan prinsip timbal-balik dalam hubungan seksual yang tidak dihormati dalam tradisi. St. Paulus mengakui perkawinan sebagai karisma, kurnia rahmat untuk pembangunan Gereja (1Kor 7:7). Surat kepada umat Efesus melihat hubungan intim antara suami dan istri sebagai misteri besar (mysterion) yang menggambarkan kesatuan Kristus dan Gereja (Ef 5:31-32), pemahaman intuitif tentang perkawinan yang sakramentalitasnya kemudian diakui oleh Gereja. Kitab Suci menekankan bahwa Alkitab memandang seksualitas tidak secara terpisah melainkan selalu dalam hubungan dengan jemaat. Masih ada teks Kitab Suci yang menghukum beberapa perilaku seksual yang dianggap menyeleweng dari norma umum perkawinan heteroseksual, monogam dan tetap. Perilaku-perilaku itu meliputi: Perzinahan (Im 20:10; Kej 39:9 Ams 2:17; Sir 23:16-21; Kel 20:14; Bil 5:18; Mrk 7:22; Mat 5:28; 15:19; 1Kor 6:9); perbuatan seks di luar nikah (Sir 42:10; Bil 22:13-21; Im 19:29; porneia atau imoralitas seksual yang mencakup perbuat-an seks di luar nikah (Mrk 7:21; Mat 15:19; 1Kor 5:9-11; 7:2; 2Kor 12:21; Gal 5:19; Ef 5:3,5), dan perbuatan homoseksual (Im 18:22; 20:13; Rm 1:27; 1Kor 6:9). Semua perbuatan itu tidak sesuai dengan hidup iman dalam jemaat religius. Yang jauh lebih penting adalah hakikat jemaat dan ciri-ciri hidup para anggotanya.1 Tentu saja harapan sudah ada sejak permulaan agar mereka, yang sudah dibaptis dalam Kristus dan jemaat murid-murid-Nya, harus hidup dengan cara yang mencerminkan kedua kenyataan Kristiani yang fundamental itu. St. Paulus mengajarkan kepada umat di Korintus untuk mengeluarkan seorang anggota yang hidup dalam hubungan sumbang dengan ibu tirinya. Perkataan St. Paulus tidak hanya tertuju kepada orang perorangan melainkan demi kesejahteraan jemaat (1Kor 5:1-13). Demikian juga, dalam hal orang-orang Kristiani yang berhubungan seks dengan pelacur-pelacur, St. Paulus menyatakan bahwa kesatuan yang sudah ada antara mereka dan Kristus, dengan demikian, setiap hubungan seksual harus mencerminkan kesucian hubungan ini (1Kor 6:15-20). Di sini St. Paulus menyarankan sebuah teologi tentang hubungan seksual. Perkembangan Teologi Moral Orang-orang Kristiani awal, yang dibina dalam konflik besar tentang sunat dan hukum Musa, pada zaman St. Paulus tidak memahami hidup mereka dalam Kristus dalam kerangka hukum moral baru. Mereka mengetahui ajaran Kristus bahwa cinta kepada Allah, yang tak terpisahkan dari cinta kepada sesama, meringkas segala perintah (Mrk 12:29-31). Mereka berusaha meresapkan panggilan Injil untuk bertobat. Mereka sadar untuk membedakan kehadiran Roh dalam jemaat dan hidup mereka. Dengan demikian seorang penulis Kristiani pasca Perjanjian Baru, yang menulis bagaimana orang-orang Kristiani hidup di antara sesama mereka tetapi berbeda dari mereka, menunjukkan bahwa orang-orang Kristiani tidak memamerkan anak-anak mereka atau saling berbagi ranjang istri-istri mereka dengan orangorang lain (Ad Diognetus 5). Lalu, bagaimana ajaran Katolik tentang seksualitas menjadi sedemikian legalistik ungkapannya, sedemikian menaruh perhatian pada dosa? Ajaran itu untuk sebagian besar ternyata dipengaruhi oleh ajaran St. Agustinus, perhatian yang terlalu banyak terhadap dosa yang berkembang bersamaan dengan praktek pengakuan dosa.2 St. Agustinus, Uskup Hippo (354- 430), merupakan salah seorang tokoh yang berpengaruh besar pada teologi Kristiani di Barat. Ajaran-ajaran tentang Allah, Tritunggal, rahmat, dosa asal, Gereja, sakramen, kedudukan Roma mendapatkan pengaruh daripadanya hingga hari ini. Akan tetapi seperti sudah kita lihat, ada unsur gelap dalam pemikiran St. Agustinus, pesimisme yang mendalam tampak pada pandangannya tentang kerusakan yang diakibatkan dosa asal pada kodrat manusia dan kesibukan pikirannya tentang masalah dosa dan kejahatan. Segi gelap ini menandai teologi Katolik sekurang-kurangnya dengan dua cara. Pertama, prinsipnya bahwa Allah tidak memerintahkan hal yang mustahil yang dirumuskannya untuk menekankan keunggulan rahmat melawan tekanan Pelagius tentang apa yang dapat dicapai oleh kebebasan manusia dengan kekuatannya sendiri, mempengaruhi tumbuhnya dimensi yang halus pada ajaran moral Katolik yang berlangsung selama berabad-abad. Pius XI mengacu pada prinsip itu sewaktu menghukum kontrasepsi dalam ensikliknya Casti Connubii (1930)3 dan Paus Johanes Paulus II mengutipnya dalam ensiklik Veritatis Splendor (no. 103)4 tentang prinsip-prinsip teologi moral. Dewasa ini beberapa orang akan melihat penalaran yang keras dalam ajaran Gereja bahwa satu-satunya pilihan moral bagi orang yang mempunyai kecenderungan homoseksual adalah hidup selibat. Kedua karena dipengaruhi oleh pergulatannya yang panjang dan sulit untuk kemurnian, Agustinus melihat seks sesudah kejatuhan manusia pertama sedemikian dikuasai oleh nafsu sehingga tujuan moral satu-satunya untuk hubungan seksual adalah prokreasi. Ajaran St. Agustinus ini juga mempunyai sejarah panjang dalam teologi Katolik. Pada Abad Pertengahan dengan mengikuti St. Agustinus, para teolog terus mengajarkan bahwa hubungan suami-istri yang lebih untuk mendapatkan kesenangan daripada untuk prosesi adalah dosa – berat bagi teolog moral yang berpendirian keras atau sekurang-kurangnya ringan menurut pandangan kebanyakan teolog moral.5 Faktor lain yang membuat teologi moral menjadi terlalu menaruh perhatian terlalu banyak pada dosa adalah praktek pengakuan dosa yang mulai abad ke-6. Sebelum abad itu, sakramen rekonsiliasi hanya diperuntukkan bagi orang murtad, berzinah, dan membunuh. Seperti sudah kita lihat, sakramen rekonsiliasi merupakan ibadat publik dan hanya diterima satu kali seumur hidup. Akan tetapi, praktek pengakuan pribadi, praktek yang dipinjam dari tradisi monastik, mengembangkan buku-buku penitensi, yang disusun untuk membantu para penerima pengakuan dalam menemukan dan menggolongkan dosa-dosa dan menetapkan silih. Buku-buku penitensi awal, secara teologis sederhana dan tidak muluk-muluk, kemudian dikembangkan menjadi summa (kumpulan pokok-pokok) yang sistematis bagi para bapa penerima pengakuan, terutama sesudah Konsili Lateran IV (1215) yang menetapkan pengakuan dosa dan komuni sekali dalam satu tahun selama Masa Paskah. Kumpulan-kumpulan itu terus menjadi berlipat ganda – kumpulan untuk para bapa pengakuan, kumpulan kasus-kasus moral (yang disukai oleh yesuit), kumpulan teologi moral – sampai pertengahan abad ke-20. Dari tradisi ini berkembanglah teologi moral yang khusus disusun bagi para bapa pengakuan. Sayangnya, teologi moral itu menjadi teologi moral yang terputus dari teologi dogmatik dan teologi spiritual. Penekanan Konsili Trente pada peran imam sebagai hakim dalam pengakuan, menambah sifat legalistik pada sakramen pengakuan. Perhatian yang keterlaluan terhadap dosa seksual diperkuat oleh deklarasi Takhta Suci Vatikan pada abad ke-17 yang ”mengelompokkan setiap pelanggaran dalam masalah seksualitas yang secara objektif merupakan perkara berat yang merupakan dosa berat”.6 Ajaran tradisional tentang seksualitas yang berasal dari teologi moral ini diterima begitu saja oleh orang-orang Katolik – jika tidak selalu dihormati – sampai Konsili Vatikan II. Akan tetapi sesudah Konsili itu, kredibilitas ajaran itu mulai melemah. Dalam proses ini, ajaran Gereja tentang kontrasepsi artifisial memegang peranan kunci. Banyak orang telah berharap agar pembaruan-pembaruan Konsili melunakkan pendekatan Gereja yang keras terhadap masalahmasalah yang berkaitan dengan seksualitas. Ada tanda-tanda yang membesarkan hati. Konsili, untuk menghindari bahasa tradisional tentang ”tujuan primer dan sekunder perkawinan”, pada akhirnya meninggalkan penomorduaan cinta timbal balik suami-istri pada prokreasi yang telah menjadi pendirian Gereja sejak zaman St. Agustinus (GS 48- 50). Pada tahun 1963, Paus Yohanes XXIII menetapkan panitia untuk menyelidiki larangan tradisional Gereja atas kontrasepsi, terutama menanggapi ”pil pengaturan kelahiran” yang anovulant yang dikembangkan oleh Dr. John Rock dan lain-lain pada tahun 1950-an. Akan tetapi pada tahun 1967, Paus Paulus VI menolak metode-metode kontrasepsi dalam ensikliknya Humanae Vitae. Para komentator teologi Katolik menyatakan bahwa Humanae Vitae memberi pukulan pada otoritas mengajar magisterium yang masih harus dipulihkan kembali.7 Akan tetapi, ada juga faktor-faktor lain yang membuat orang kehilangan kepercayaan pada ajaran Gereja tentang seksual, di antaranya adalah yang disebut revolusi seksual pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, yang dibantu oleh tersedianya secara luas pil-pil kontraseptif, gerakan wanita, dan bertambahnya jumlah pembangkang terhadap doktrin magisterium tentang seksualitas (terutama sesudah Humanae Vitae) dari pihak teolog-teolog Katolik. Pada tahun 1976 karena prihatin bahwa orang-orang Kristiani yang setia pun merasa ”tidak tenang”, Kongregasi untuk Ajaran Iman menerbitkan ”Deklarasi tentang Masalah-Masalah Tertentu Berhubungan dengan Etika Seksual”.8 Deklarasi itu meneguhkan kembali ajaranajaran tradisional Gereja dengan ungkapan yang tegas. Ajaran-ajaran itu, argumentasinya didasarkan atas beberapa segi dari hukum kodrat yang ”memiliki nilai mutlak dan tak dapat diubah” (no. 4). Menurut ajaran itu, ”setiap hubungan seksual haruslah dalam kerangka perkawinan” (no. 7); dengan demikian setiap perbuatan seksual di luar konteks itu dilarang. Secara khusus deklarasi menyebutkan marturbasi, seks sebelum nikah, perbuatan homoseksual untuk diperhatikan secara khusus dan tradisi menegaskan kembali bahwa tidak ada ”masalah kecil” jika menyangkut seks: ”Tatanan moral seksualitas menyangkut nilai hidup manusia yang tinggi sehingga setiap pelanggaran langsung terhadap tatanan itu secara objektif berdosa” (no. 9).9 Tidak pada tempatnya jika dalam buku ini kita masuk ke dalam diskusi-diskusi tentang masalah-masalah hubungan Gereja Katolik dan seksualitas yang muncul dewasa ini. Cukuplah bila disampaikan ajaran resmi Gereja dan bersamaan dengan itu, ditunjukkan beberapa masalah yang dewasa ini diangkat oleh teolog-teolog moral Katolik. Kita akan membahas pengaturan kelahiran, pengguguran, masturbasi, seks sebelum nikah, dan hubungan homoseksual. Pengaturan Kelahiran Meskipun kontrasepsi (anti kehamilan dengan segala cara) sudah dihukum oleh para teolog sekurang-kurangnya sejak abad ke-4, namun tidak menjadi masalah gawat sampai akhir abad ke-19, pada waktu praktek pengaturan kelahiran mulai menjadi lebih umum di Eropa. Sesudah sejumlah pernyataan melawan kontrasepsi oleh hierarki-hierarki nasional dan persetujuan bersyarat atas metode-metode kontrasepsi oleh Konferensi Lambeth para Uskup Anglikan (Lambeth Conference of Anglican Bishops) tahun 1930, Paus Pius XI menghukum segala bentuk kontrasepsi dalam ensikliknya tentang perkawinan, Casti Connubii (1930). Pius XII memajukan ajaran Katolik satu langkah lagi pada tahun 1951, ketika dalam sambutannya kepada Ikatan Bidan Katolik Italia, ia menyetujui pantang berkala selama masa subur wanita untuk menghindari kehamilan, asal ada alasan cukup. Metode itu disebut metode ritma (rhytm method). Dengan beredarnya pil kontraseptif pada tahun 1950-an, masalah kontrasepsi artifisial (buatan) menjadi pembicaraan hangat. Paulus VI tidak menghendaki Konsili Vatikan II membahas masalah kontrasepsi artifisial itu. Paus Paulus VI malah memperluas menjadi 69 anggota Komisi Internasional yang dibentuk oleh Paus Yohanes XXIII untuk mempelajari ajaran Gereja tentang kontrasepsi. Pada tahun 1967, 64 anggota Komisi mendukung dan 4 anggota tak mendukung (Uskup Agung Karol Wojtyla – yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II – tidak menghadiri pertemuan) untuk mengubah ajaran tradisional yang menyatakan bahwa penggunaan segala alat kontraseptif adalah imoral. Namun, sesudah pembahasan susah payah mengenai masalah itu, Paus Paulus VI menegaskan lagi larangan tradisional dalam ensikliknya, Humanae Vitae, yang terbit pada tahun 1968. Humanae Vitae menyatakan bahwa ”masing-masing dan setiap hubungan suami-istri dalam perkawinan harus terbuka untuk penerusan kehidupan” (no. 11) karena hubungan yang tak terpisahkan antara makna perbuatan seksual yang sifatnya unitif dan prokreatif (no. 12). Ada sedikit masalah yang telah bersifat memecah belah bagi agama Katolik pada zaman ini seperti ajaran Paus melawan kontrasepsi. Ensiklik itu merupakan tindak magisterium yang otoritatif meski tidak dapat tidak sesat, sebagaimana dinyatakan oleh Vatikan pada waktu ensiklik dikeluarkan. Konferensi para uskup sebanyak 13 negara menunjukkan kecenderungan untuk memperlunak pendirian Paus dalam tanggapan mereka.10 Charles Curran, teolog moral di The Catholic University of America, AS, pada waktu itu, menulis pernyataan yang tak menyetujui pendirian Paus. Curran menyatakan bahwa pasangan dapat secara bertanggung jawab memutuskan menurut hati nurani mereka bahwa kontrasepsi artifisial dalam keadaankeadaan tertentu diperbolehkan dan memang diperlukan untuk menjaga dan memupuk nilai dan kesucian perkawinan. Lebih dari 600 teolog, imam, dan akademisi menandatangani pernyataan itu. Dewasa ini banyak teolog mengambil pendirian bahwa makna unitif dan prokreatif seksualitas perlu disatukan prinsip, tetapi tidak harus dalam segala hubungan seksual. Perdebatan yang disulut oleh Humanae Vitae berlangsung selama bertahun-tahun.11 Pada Sinode Para Uskup tentang Keluarga di Roma tahun 1980, Uskup Agung John R. Quinn dari San Francisco berbicara atas nama banyak orang – awam, klerus, dan tentu saja sejumlah uskup – pada waktu melihat bahwa ada perlawanan luas di kalangan orang-orang Katolik terhadap ajaran ensiklik tentang kejahatan intrinsik dari masing-masing dan tiap-tiap penggunaan kontraseptif. Ia mengutip sebuah studi yang menunjukkan bahwa 76,5% wanita Katolik Amerika menggunakan beberapa bentuk pengaturan kelahiran, dan 94% dari jumlah itu menggunakan metode-metode yang dihukum oleh ensiklik. Quinn menyarankan agar Gereja berusaha menciptakan konteks baru bagi ajarannya mengenai kontrasepsi dengan menekankan apa yang telah dikatakan Gereja tentang orang tua yang bertanggung jawab; agar Gereja mulai dialog dengan para teolog tentang masalah-masalah yang diangkat oleh mereka yang tidak menyetujui ajara-ajaran Humanae Vitae; dan bahwa perhatian yang sungguh-sungguh diberikan pada cara ensiklik-ensiklik ditulis dan dikomunikasikan.12 Pengguguran Jika ajaran tradisi Gereja melawan kontrasepsi belum diterima secara luas oleh umat Katolik, situasi terhadap pengguguran berbeda. Kebanyakan orang Katolik dewasa ini percaya bahwa secara langsung mengakhiri hidup dalam rahim merupakan kejahatan moral yang berat, bahkan jika tidak semua dari mereka sepakat tentang cara terbaik menyelesaikan masalah itu. Sejak awal, tradisi Katolik sudah melawan pengguguran.13 Didache yang berasal dari awal abad ke-2, mengajarkan bahwa ”kamu jangan membunuh anak dengan pengguguran atau membunuhnya pada saat kelahiran” (2.2). Baru pada pertengahan abad ke-2, tradisi ini mulai ditantang oleh dunia yang semakin sekular, dan menyebabkan munculnya sejumlah pernyataan Paus dan uskup yang untuk sebagian berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moralitas.14 Kongregasi untuk Ajaran Iman mengeluarkan Deklarasi tentang Pengguguran yang Diusahakan (Declaration on Procured Abortion) pada bulan November 1974. Kitab Hukum Kanonik yang direvisi tahun 1983, menyatakan bahwa ”orang yang mengusahakan pengguguran dan berhasil dengan sendirinya terkena ekskomunikasi” (Kan. 1398). Ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae, meneguhkan kembali dengan kata-kata tegas ajaran Gereja tentang pengguguran, dengan menekankan bahwa semua orang dipanggil untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi hidup manusia yang tak berdosa. Meskipun Gereja belum menetapkan kapan hidup manusia sesungguhnya mulai, Gereja telah mengambil tindakan untuk mempertahankan bahwa hidup manusia sudah ada dari saat pembuahan atau fertilisasi. Ini berarti bahwa Gereja memandang campur tangan seperti I.U.D (intra uterine device) atau pil morning after (digunakan sesudah hubungan seksual) yang mencegah ovum yang sudah dibuahi tidak menempel pada dinding rahim, sebagai yang bersifat abortif. Sejumlah teolog Katolik seperti Richard McCormick, Charles Curran, Bernard Häring, dan Karl Rahner menyarankan bahwa penemuan-penemuan dalam biologi reproduktif memungkinkan bahwa hidup manusia perorangan dapat sudah ada sampai dua atau tiga minggu sesudah fertilisasi. ”Hominisasi” menuntut dua perubahan yang harus terjadi pada embrio awal. Pertama, hominisasi harus melewati tahap twinning, tahap selama embrio dapat terbagi menjadi dua atau lebih, dan sesudah itu ada kepastian bahwa individualitas satu atau dua embrio telah mantap. Kedua, hominisasi harus berubah dari ”hidup manusia berbentuk sel ke bentuk yang mulai menunjukkan diferensiasi yang khas dari organisme manusia”15 Pendapat ini menyediakan periode 14 sampai 21 hari yang terbatas, suatu bidang kelabu, yang karena alasan-alasan serius seperti perkosaan atau inses, embrio awal dapat gugur. Namun, yang lain menyatakan bahwa hidup manusia sedemikian suci sehingga bahkan hidup manusia yang potensial pun harus dilindungi. Sungguh penting dicatat bahwa dokumen-dokumen Gereja ”pada umumnya menyatakan perang melawan pengguguran dalam konteks penghormatan terhadap hidup yang lebih luas pada setiap tahap dan dalam segala bidang”.16 Aborsi terapeutik, karena alasan-alasan medis membuang fetus seperti embrio yang sudah bersarang pada tuba falopi dan dengan demikian tidak dapat berkembang untuk kehamilan (kehamilan ektopik) atau dalam proses membuang rahim yang terserang kanker, merupakan persoalan yang lain. Prosedur-prosedur semacam itu merupakan pengguguran yang tidak langsung. Prosedur-prosedur itu diperbolehkan dan diperlukan untuk menyelamatkan hidup ibu. Bagaimana Gereja dapat membuat posisinya tentang kesucian hidup lebih didengarkan? Ada pendapat yang diajukan yang menyatakan bahwa posisi Gereja dalam masalah aborsi itu dapat menjadi lebih kokoh, jika Gereja memasukkan istilah ”hak untuk hidup” dalam kerangka pemahaman tradisional ”kebaikan bersama” (bonum commune), dan jika menempatkan pengguguran dalam konteks masalah peran gender dalam masyarakat. Gereja sebaiknya lebih mengakui hak-hak wanita untuk ikut ambil bagian dalam sektor publik agar ”kebebasan reproduktif” tidak dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin hak untuk hidup. Gereja masih mempertahankan peran-peran sosial yang berpedoman pada gender dengan memberikan peran wanita dalam rumah dan keluarga tanpa mengakui secara memadai hak mereka untuk ikut ambil bagian secara sejajar dalam bidang publik. Salah satu cara untuk itu adalah mengajar pria untuk juga ikut bertanggung jawab dalam rumah tangga supaya masalah pengasuhan anak menjadi urusan bersama dalam keluarga dan bukan hanya urusan wanita saja.17 Masturbasi Pernyataan-pernyataan magisterium yang melawan masturbasi sudah muncul pada abad ke-11.18 Ajaran bahwa dalam masalah seks tidak ada ”perkara kecil” membuat masturbasi menjadi perkara penting dalam Teologi Moral dan mungkin juga dalam sebagian besar hidup banyak orang Katolik. Dewasa ini pendapat mengenai masalah itu amatlah beragam. Banyak orang berpendapat bahwa masturbasi merupakan bagian dari kesadaran dan kematangan seksual remaja. Oleh karena itu, masturbasi di kalangan remaja kerap mengurangi kebebasan mereka dan dengan demikian juga tanggung jawab mereka. Kebiasaan masturbasi yang sudah kuat merupakan gejala bahwa seksualitas orang yang bersangkutan belum terintegrasi dalam dirinya. Dengan demikian masturbasi mempunyai makna yang berbeda-beda bagi anak remaja, dan orang dewasa, orang yang telah menikah atau hidup sendirian tidak kawin. Kebanyakan ahli moral Katolik enggan untuk berpandangan bahwa masturbasi hanya merupakan bentuk pelampiasan seksual yang normal. Mereka menyatakan bahwa secara fenomenologis, masturbasi merupakan ungkapan seksualitas yang lebih berpusat pada diri sendiri, sendirian, dan hedonistis daripada relasional, timbal-balik, dan memberi. Dengan demikian, tindakan itu mengungkapkan kegagalan mencapai dimensi integratif dari hakikat seksual. Melakukan masturbasi dengan tahu dan sengaja menghambat pengintegrasian dan perubahan pribadi yang merupakan buah Roh. Orang-orang yang mengalami masa-masa masturbasi yang teratur, yang bergantian dengan masa-masa pengendalian diri, menyarankan untuk tidak menerima masturbasi sebagai hal yang baik. Mereka melihatnya sebagai tanda kelemahan, yang menimbulkan perasaan malu terhadap diri sendiri. ”Tetapi ketidakmauan dan ketidaksediaan untuk menuruti dorongan masturbasi dan menguasai dirinya merupakan fakta bahwa bagi orang itu, masturbasi merupakan dorongan untuk merendahkan diri daripada ungkapan kedosaan dasar dan berat”.19 Seks Pranikah Salah satu masalah pelik yang merupakan bahan pembicaraan dengan anak-anak remaja adalah tentang seks pranikah. Para teolog Katolik ”selalu dan di mana-mana” berpendapat bahwa hubungan seksual pranikah merupakan dosa berat.20 Visi Gereja yang paling mendalam tentang seksualitas adalah bahwa makna unitif dan prokreatif hubungan seksual secara intrinsik berhubungan. Dengan demikian, Gereja melihat bahwa hubungan antara kesetiaan perkawinan dan ungkapan seksual tak terpisahkan. Hubungan seksual merupakan saling penyerahan total antara suami-istri. Jika hubungan itu penuh cinta, maka menyangkut komitmen. Akan tetapi, jika ungkapan lahir, fisik, bukan merupakan pernyataan kenyataan batin, spiritual yang menyangkut cinta tanpa syarat dan penyerahan diri, maka kesatuan tubuh pasangan bukan merupakan lambang kesatuan roh mereka, seks mereka dengan mudah menjadi eksploitatif. Tanpa penyerahan-diri dan keterlibatan yang setia satu sama lain, maka tidak ada kesatuan cinta yang dapat menyambut dan mengasuh hidup yang baru. Tragedi pengguguran seringkali terjadi karena pasangan melakukan hubungan seksual sebelum mereka siap untuk menyambut anak yang merupakan buah dari hubungan seksual itu. Sekarang ini banyak anak muda menggunakan istilah ”hubungan” untuk menyatakan hubungan seksual yang eksklusif tetapi tidak mengikat. Karena hubungan semacam itu merupakan hubungan yang bersifat sementara, hubungan itu tidak mencapai makna seksualitas baik yang unitif maupun yang prokreatif. Sedang pandangan Katolik justru sebaliknya. ”Keyakinan Kristiani menyatakan bahwa hubungan yang dihayati dalam janji untuk membangun hubungan yang tetaplah yang mencegah hubungan seksual menjadi kegiatan tak berarti yang memecah-belah, mengasingkan, dan menghancurkan.”21 ”Seks tanpa komitmen bersama penuh dengan bahaya penipuan, dan eksploitasi diri, khususnya pada wanita oleh pria.”22 Beberapa moralis dewasa ini membedakan seks pra-upacara (praseremonial) dan seks pranikah. Pembedaan itu mengandung arti bahwa jika sudah ada komitmen, ungkapan seksual dalam beberapa kasus tertentu dapat tepat. Akan tetapi, pantas ditanyakan apakah komitmen itu sungguh-sungguh ada sebelum dinyatakan secara publik. Mewujudkan hubungan perkawinan sebelum komitmen publik apakah bukan merupakan jalan pintas dalam proses pemantapan – tujuan utama pertunangan – di mana akan dilihat apa masing-masing pasangan memang akan mampu membuat komitmen itu? Salah satu alasan mengapa banyak perkawinan gagal dewasa ini adalah terlalu banyak pasangan menempuh jalan pintas pada proses pemantapan. Daripada membiarkan kesatuan seksual menjadi meterai dan ungkapan cinta yang telah tumbuh sampai pasangan sungguhsungguh terlibat satu sama lain, mereka mulai hidup bersama sebelum mereka tahu bagaimana saling berbicara, berbagi perasaan mereka yang paling dalam, menjadi nyaman dalam kehadiran bersama, erat dan akrab satu sama lain dengan saling mengungkapkan rasa cinta dengan cara-cara yang wajar dan saling dapat diterima. Mudahlah untuk mengacaukan ”seks yang nikmat” dengan cinta yang sejati, dan pada waktu seks tidak lagi baru dan menggairahkan, mereka mendapatkan bahwa cinta yang mau diungkapkan ternyata tidak ada. Sayangnya, penemuan ini kerap kali terlalu terlambat datangnya. Hubungan Homoseksual Salah satu masalah sulit yang dihadapi oleh jemaat Kristiani dewasa ini adalah hubungan homoseksual. Ada sejumlah penghukuman eksplisit terhadap hubungan homoseksual baik di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, tetapi banyak penafsir dan ahli Kitab Suci dewasa ini, tidak melihat dalam teks-teks Kitab Suci itu penghukuman terhadap hubungan homoseksual, karena konsep homoseksual baru dikenal pada zaman modern ini. Menurut pendapat para penafsir dan ahli Kitab Suci, teks-teks Kitab Suci itu berkenaan dengan tindakan ikut serta dalam ibadat tahayul dengan ikut bergabung bersama pelacur-pelacur kuil laki-laki dan perempuan (Im 18:22; 20:13; Bil 23:18; bdk. 1Raj 14:24; 15:12), praktek umum di Timur Tengah kuno, atau berkenaan dengan pelanggaran kewajiban kesediaan menerima tamu (Kej 19:4-8), atau berkenaan dengan pemburit (1Kor 6:9-10; 1Tim 1:10). Teks yang lebih sulit adalah Rm 1:24-31. St. Paulus dengan jelas berbicara tentang hubungan homoseksual. Akan tetapi, fakta bahwa St. Paulus melihat orang yang dihukumnya, pria dan wanita, karena meninggalkan hubungan yang normal dan lebih menyukai hubungan homoseksual, membuktikan bahwa St. Paulus tidak mengerti homoseksual sebagai keadaan.23 Ahli-ahli lain tentu saja tidak setuju dengan penafsiran itu atau berpendapat penafsiran itu tidak ada kaitan dengan penghukuman biblis. Jelaslah dewasa ini bahwa orang tidak memilih menjadi homoseksual, bahkan bila kita belum yakin apa yang menjadi penyebab kecenderungan homoseksual itu. Katekismus Gereja Katolik mengakui bahwa kecenderungan homoseksual bukanlah pilihan (2358). Dengan demikian, istilah ”memilih secara seksual” tidaklah tepat. Gereja membedakan kecenderungan homoseksual dan perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual inilah yang dipandang amoral. Perbuatan-perbuatan homoseksual yang tidak bertanggung jawab, bebas memilih pasangan dan kasar merupakan kejahatan moral seperti halnya heteroseksual yang berciri sama. Dilema yang dihadapi Gereja dewasa ini adalah apa yang harus dikatakannya kepada orang homo dan lesbi yang hubungannya tetap, eksklusif dan setia, dan yang mau mengungkapkan cinta mereka secara seksual. Ini merupakan masalah pelik yang akan selalu menjadi masalah sulit bagi jemaat Kristiani. Veritatis Splendor Baru-baru ini Paus Yohanes Paulus II, seorang filsuf moral dan mantan profesor etika di Universitas Katolik Lublin di Polandia, ikut terlibat ke dalam wacana tentang teologi moral fundamental dan penerapan-penerapannya. Dalam ensikliknya Veritatis Splendor (1993), perhatiannya ditujukan untuk menegaskan kembali ajaran tradisional teologi moral Katolik bahwa perintah-perintah larangan hukum kodrat secara universal valid, berlaku (no. 52). Dengan menunjukkan keakraban yang mengesankan dengan perdebatan zaman ini, secara khusus ia menolak teori-teori etika teologis, proporsionalis, dan konsekuensialis yang berpendirian bahwa ”tidak pernah mungkin merumuskan larangan mutlak tentang jenis perilaku tertentu yang dalam segala hal bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ditunjukkan oleh akal dan wahyu (no. 75). Dengan demikian, ia meneguhkan kembali adanya ”perbuatan yang secara intrinsik jahat”, tindakan yang pada dirinya jahat terlepas dari keadaan dan intensi pelakunya (no. 80). Ia juga menegaskan lagi konsep tradisional tentang dosa berat, dengan mengemukakan bahwa pilihan fundamental atau orientasi orang terhadap Allah dapat berubah secara radikal oleh perbuatan-perbuatan tertentu (no. 70). Veritatis Splendor merupakan pernyataan kembali yang kuat tentang tradisi. Ensiklik itu perlu diperhatikan, dihormati, dan ditaati berdasarkan ajaran otoritatif magisterium Paus yang sederhana (LG 25). Akan tetapi, orang-orang Katolik dan Kristiani lainnya akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai tradisi dan ajaran Gereja, pada waktu mereka berusaha mempersatukan hidup pribadi dan seksual mereka dengan panggilan Injil untuk menjadi murid. 2. Keadilan Sosial Mungkin salah satu dokumen Konsili Vatikan II yang paling berarti adalah Konstitusi Pastoral tentang Gereja Dewasa Ini, Gaudium et Spes. Dokumen ini, dengan visinya tentang Gereja untuk pelayanan dunia (GS 3) dan ajakannya terhadap orang-orang Kristiani untuk meringankan hidup orang miskin (GS 69), memberi inspirasi kepada banyak orang Katolik untuk berperan aktif dalam berbagai gerakan pemerdekaan yang menandai bagian kedua abad ke-20 ini. Akan tetapi, Gaudium et Spes bagaimanapun juga bukan satu-satunya contoh ajaran magisterial Gereja mutakhir tentang keadilan sosial dan hak-hak azasi manusia. Akar-akar ajaran sosial Gereja harus ditemukan dalam tulisan-tulisan profetik Kitab Suci Yahudi dan dalam tradisi kaya pemikiran sosial Katolik yang mencakup para pemikir selama berabad-abad seperti Agustinus, Aquinas, Suarez, von Ketteler, Maritain, dan John Courtney Murray maupun tradisi ensiklik sosial para Paus selama 100 tahun terakhir ini. Ensiklik-Ensiklik Sosial Ensiklik-ensiklik sosial para Paus merupakan pernyataan gerejawi yang paling mutakhir dari ajaran sosial Gereja. Dari Rerum Novarum (Leo XIII) (1891) tentang hak-hak pekerja, ensiklikensiklik sosial telah meluaskan pusat perhatiannya sampai meliputi masalah-masalah perkembangan dan keadilan ekonomis antarbangsa, teknologi dan perlombaan senjata, makin melebarnya jurang antara kaum kaya dan miskin dan kritik baik terhadap komunisme maupun kapitalisme. Inti ajaran sosial dan pendasaran sikap pro-hidup adalah keyakinan Katolisisme yang mendalam tentang nilai luhur setiap pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah (GS 12). Sayangnya, tradisi tentang ajaran sosial Gereja ini merupakan tradisi yang paling sedikit diketahui oleh orang-orang Katolik zaman sekarang ini.24 Richard P. McBrien membedakan 3 periode dalam tradisi itu.25 Tahap I: 1891 – 1930. Rerum Novarum dari Paus Leo XIII dikeluarkan pada zaman Revolusi Industri. Pada masa itu, di Eropa dan Amerika Serikat hukum pasar dibiarkan mendominasi sepenuhnya hak-hak pekerja. Upah memprihatinkan, buruh anak-anak diterima begitu saja, dan setiap usaha untuk membentuk serikat buruh guna melindungi kaum buruh ditentang, kerap dengan kekerasan. Rerum Novarum memusatkan perhatian pada hak-hak itu, terutama hak untuk mendapatkan upah yang adil yang mendukung keluarga pekerja dan hak untuk bergabung pada serikat pekerja. Ensiklik menegaskan hak atas milik pribadi, tetapi menekankan fungsinya untuk melayani kepentingan bersama. Dengan kata lain, hak atas milik pribadi tidaklah mutlak. Ensiklik menekankan agar pemerintah campur tangan untuk mencegah kerugian bagi orang-perorangan maupun kesejahteraan bersama. Dengan membela hak-hak kaum buruh untuk masuk ke dalam perhimpunan-perhimpunan, termasuk ”perserikatan-perserikatan buruh” (no. 36), Leo mendesak para penindas untuk bertobat guna menghadapi masalah yang sekarang disebut ketidakadilan tingkat struktural. Namun, pendekatan Paus masih cukup konservatif. Curiga terhadap munculnya gerakan serikat buruh karena sifatnya yang sekular dan kadang-kadang anti-Katolik, Leo mendorong para pekerja Katolik untuk membentuk perhimpunan mereka sendiri, dengan akibat Gereja tak dapat mempengaruhi atau mendukung gerakan buruh sebagaimana seharusnya.26 Namun dengan meminta perhatian pada masalah keadilan dalam tatanan sosial, Leo mengangkat suara Gereja demi kaum miskin, Ensikliknya memberi dasar yang kuat bagi ajaran sosial Gereja, dasar yang terus berfungsi sebagai patokan dan titik acuan bagi Paus-Paus selanjutnya. Empat puluh tahun kemudian, Paus Pius XI mengembangkan ajaran sosial Paus Leo XIII dalam ensikliknya Quadragesimo Anno (1931). Paus merumuskan untuk pertama kalinya prinsip subsidiaritas (no. 79-80). Gagasan dasarnya adalah prioritas dan hak-hak masingmasing orang dan keluarga. Intinya, lembaga-lembaga masyarakat yang lebih besar jangan mengambil tanggung jawab kelompok-kelompok atau perhimpunan-perhimpunan yang lebih kecil. Pius XI juga memperkenalkan konsep keadilan sosial (justitia socialis) sebagai ”prinsip yang membimbing” atau norma bagi lembaga-lembaga publik dan tatanan ekonomis (no. 8890). Pada tahun 1937, Pius XI mengeluarkan Mit Brennender Sorge, ensiklik yang amat tajam mengecam pemerintahan Nazi karena melanggar hak-hak Gereja Katolik. Ensiklik itu dibacakan di semua mimbar Katolik di Jerman. Pada tahun terakhir hidupnya, Pius XI sedang menyiapkan suatu ensiklik tentang kesatuan umat manusia. Sebagian besar dari ensiklik itu, yang berulangulang menganalisis dan menghukum anti-semitisme di Jerman dan rasisme di Amerika Serikat, disiapkan atas permintaan Paus oleh John Lafarge, seorang Yesuit Amerika. Sayangnya, seseorang di Roma berpendapat bahwa dokumen, yang secara khusus menghukum antisemitisme itu, tidak menguntungkan, berdasarkan situasi politik di Eropa yang memanas, dan draft yang sudah selesai dicegah agar tidak sampai di meja Paus. Pius XI wafat tahun 1939, tanpa mengeluarkan dokumen yang dapat merupakan ensikliknya tentang rasisme. Tahap II: Pasca Perang Dunia II. Masa sesudah Perang Dunia II merupakan masa penginternasionalisasian ajaran sosial Gereja. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan pada masa itu membahas organisasi masyarakat internasional, tuntutan-tuntutan keadilan sosial pada tingkat internasional, dan masalah-masalah moral yang dimunculkan oleh perang pada zaman nuklir. Ensiklik Paus Yohanes XXIII yang pertama, Mater et Magistra, memusatkan perhatian pada masalah melebarnya jurang antara kaum kaya dan kaum miskin. Ensiklik itu menekankan fungsi sosial hak milik pribadi dan mengajak untuk diadakan rekonstruksi hubungan-hubungan sosial. Pacem in terris (1963), ensikliknya tentang perdamaian, merupakan himbauan kepada orang-orang yang berkehendak baik. Paus menyerukan larangan atas senjata-senjata nuklir dan menekankan tanggung jawab tiap-tiap orang untuk melindungi hidup ”jika otoritas sipil mengundang-undangkan atau memperbolehkan apa pun yang berlawanan dengan kehendak Allah, baik hukum yang dibuat maupun otorisasi yang diberikan, tidak dapat mengikat hati nurani warga negara karena ’kita harus menaati Allah daripada manusia’” (no. 51). Ajaran sosial Konsili Vatikan II termuat dalam dua dokumen yang terbit tahun 1965. Gaudium et Spes (Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini) membahas praktek keadilan sosial sebagai bagian misi Gereja.27 Dignitatis Humanae, Deklarasi tentang Kebebasan Beragama, merupakan salah satu dokumen konsili yang paling kontroversial. Populorum Progressio, ensiklik Paus Paulus VI, terbit pada tahun 1967. Kecuali mengulang ajaran tradisional bahwa hak atas milik pribadi tidaklah mutlak, Paus mengutarakan masalah land reform: ”Jika pertanahan luas menghambat kesejahteraan umum karena terlalu luas, tidak didayagunakan atau didayagunakan secara buruk, atau mendatangkan kesusahan bagi rakyat atau merugikan kepentingan negara, kesejahteraan umum kadang-kadang menuntut pengambilalihan” (no. 24). Paus Paulus VI juga menolak kapitalisme liberal sebagai ”sistem ... yang memandang keuntungan sebagai motif utama untuk kemajuan ekonomis, persaingan sebagai hukum tertinggi ekonomi, dan pemilikan pribadi atas sarana produksi sebagai hak mutlak yang tidak mempunyai batas dan tidak mempunyai kewajiban sosial yang sesuai” (no. 26). Justitia in Mundo (1971) atau Keadilan di Dunia merupakan dokumen Sinode Para Uskup III, menghubungkan evangelisasi dengan keterlibatan untuk perubahan dunia: ”Tindakan demi keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia bagi kami jelas merupakan dimensi konstitutif dari pewartaan Injil, atau dengan kata lain, dari misi Gereja untuk penebusan umat manusia dan pemerdekaannya dari segala macam keadaan yang menindas” (no. 6). Tahap III: 1971 – . Tahap mutakhir ajaran sosial Gereja mengangkat masalah makin melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin, masalah-masalah yang disebabkan oleh teknologi perlombaan senjata, siksaan dan penindasan, dan memuat kritik baik terhadap komunisme dan kapitalisme. Octogesima Adveniens, surat yang dikirimkan oleh Paus Paulus VI kepada Kardinal Maurice Roy, presiden Dewan Pontifikal tentang Keadilan dan Perdamaian, membahas masalah-masalah yang diakibatkan oleh urbanisasi, mencakup keadaan kaum wanita, kaum muda, dan kaum miskin baru. Ada tiga butir penting dalam surat itu. Pertama, surat itu mengakui bahwa sosialisme merupakan pilihan bagi orang-orang Katolik. Kedua, surat itu mengambil pendekatan yang sedikit berbeda terhadap Marxisme, dengan menolaknya sebagai sistem filsafat yang lengkap dan sebagai bentuk politik pemerintahan yang terkait dengan kediktatoran, namun mengakui kegunaannya sebagai bentuk analisa sosial, meski harus digunakan dengan amat hati-hati. Akhirnya, surat itu menunjukkan penghargaan atas fungsi kritis ”utopia”, suatu pengertian yang dipinjam dari filsuf Marxis revisionis Ernst Bloch, yang dapat merangsang visi tentang masyarakat alternatif.28 Amanat Apostolik Paus Paulus VI tentang Evangelisasi, Evangelii Nuntiandi, menekankan bahwa evangelisasi mempunyai dimensi baik sosial maupun personal. Dimensi sosial menyangkut hak-hak asasi manusia, hidup keluarga, perdamaian, keadilan, perkembangan dan pemerdekaan (no. 29). Paus melihat hubungan mendalam antara evangelisasi dan pemerdekaan karena pribadi ”yang akan menerima evangelisasi bukanlah makhluk abstrak tetapi tunduk pada masalah-masalah sosial dan ekonomi” (no. 31). Ia mencatat bahwa meski beberapa komunitas basis penuh kritik pedas terhadap Gereja dan hierarki, komunitaskomunitas basis lainnya membuat Gereja tumbuh dan dapat menjadi tempat evangelisasi (no. 58). Evangelisasi merupakan inti perutusan Gereja; evangelisasi menjadi tanggung jawab Gereja lokal maupun Gereja universal. Semua orang Kristiani, baik klerus maupun awam, mempunyai peranan penting yang harus dimainkan dalam evangelisasi. Ensiklik sosial pertama Paus Yohanes Paulus II, Laborem Exercens, terbit pada tahun 1981. Ensiklik itu telah dipuji sebagai dokumen pengajaran yang sejati, ensiklik yang tidak hanya mengajar, tetapi menerangkan dan menjelaskan. Dengan menekankan prioritas kerja di atas modal dan prioritas manusia di atas benda, ensiklik itu menyampaikan kritik yang seimbang terhadap kapitalisme liberal dan Marxisme. Dengan mengembangkan spiritualitas kerja, Paus Yohanes Paulus II melihat kerja diperlukan bagi martabat manusia dan bagi perkembangan kerajaan. Konsep kunci ensiklik itu adalah solidaritas (kesetiakawanan) (no. 8). Kerap digunakannya istilah solidaritas dalam ensiklik pada waktu bersamaan ketika gerakan solidaritas Polandia sedang berjuang melawan pemerintah Komunis di negara itu ”pastilah mendatangkan dampak memberi aura tersamar tertentu atas persetujuan Vatikan terhadap Gerakan Buruh Polandia”.29 Sollicitudo Rei Socialis (1987), ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang keprihatinankeprihatinan sosial Gereja, dirancang untuk merayakan dan mengembangkan lebih lanjut Populorum Progressio dari Paus Paulus VI. Ensiklik itu menekankan jurang yang makin menganga antara negara-negara maju di belahan bumi Utara dan negara-negara yang sedang berkembang di belahan bumi Selatan, dengan menimpakan banyak kesalahan atas keadaan ini karena adanya dua blok yang berlawanan, kapitalisme liberal di Barat dan kolektivisme Marxis di Timur. Ajaran sosial Gereja bersikap kritis terhadap kedua sistem itu. Paus Yohanes Paulus menegaskan bahwa Gereja tidak mempunyai pemecahan untuk masalah keterbelakangan, ”jalan ketiga” antara dua sistem yang bersaing. Menggunakan teologi pembebasan, Paus menyerukan ”opsi atau pilihan keberpihakan pada kaum miskin,” keprihatinan bagi kaum miskin yang harus mengkondisikan ”hidup kita sehari-hari maupun keputusan-keputusan di dalam bidang politik dan ekonomi” (no. 42). Ensiklik itu merupakan tantangan Paus yang paling kuat terhadap negara-negara makmur dan pantas dicatat karena minta perhatian pada soal-soal ekologi (no. 39). Centesimus Annus (1991), menandai satu abad Rerum Novarum, diterbitkan sesudah runtuhnya Komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet. Ensiklik itu bersikap lebih positif terhadap kapitalisme, dengan pengakuannya terhadap peranan bisnis yang positif dan penghargaannya terhadap kreativitas manusia dalam ekonomi. Namun, kapitalisme mempunyai kelemahankelemahannya sendiri. Kapitalisme tidak dapat begitu saja dijadikan sasaran Dunia Ketiga dan negara-negara yang sedang berkembang, di mana ada kebutuhan untuk membatasi kebebasan dalam sektor ekonomi dalam kerangka yuridis yang menghormati pengertian yang lebih komprehensif tentang kebebasan yang berakar pada nilai-nilai etika dan religius (no. 42). Evangelium Vitae, ensiklik panjang tentang hidup manusia dari Paus Yohanes Paulus II, terbit pada tahun 1995. Dengan mengambil titik tolak ”nilai kudus hidup manusia dari sejak awal sampai akhirnya” (no. 2), Paus mengajak semua orang yang berkehendak baik untuk menegaskan ”budaya baru hidup manusia” (no. 6). Contoh-contoh kekuranghormatan terhadap hidup dewasa ini mencakup pembagian sumber-sumber daya yang tidak adil yang mendatangkan kemiskinan, kekurangan gizi, dan kelaparan bagi jutaan manusia, kekerasan peperangan dan perdagangan senjata yang memalukan, perusakan yang tidak bertanggung jawab atas keseimbangan ekologi dunia, penyebarluasan obat bius, dan promosi jenis kegiatan seksual tertentu yang mendatangkan risiko yang besar kepada hidup (no. 10). Khususnya ensiklik itu berpusat pada ”serangan-serangan yang mengenai hidup pada tahap paling awal dan pada tahap paling akhir” (no. 11). Ensiklik itu menyampaikan dasar baru pada waktu berbicara amat keras melawan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa dewasa ini ”sebagai akibat pengembangan yang terus menerus dalam organisasi sistem hukuman,” kasus-kasus di mana hukuman mati dibenarkan untuk melindungi masyarakat ”amatlah jarang jika tidak secara praktis tidak ada” (no. 56).30 Ensiklik itu meneguhkan kembali pendirian Gereja bahwa ”pengguguran yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana selalu merupakan kekacauan moral yang berat” (no. 62) dan menghukum ”penggunaan embrio atau janin manusia sebagai objek percobaan” (no. 63). Meski ensiklik itu menolak eutanasia, bunuh diri, dan ”bunuh diri yang dibantu” karena berlawanan dengan hukum Allah, namun menghormati keputusan penderita untuk tidak menjalani ”perawatan medis yang agresif” yang ”hanya akan melindungi perpanjangan hidup yang rentan dan memberatkan, selama perawatan yang biasa yang harus diberikan kepada orang sakit dalam kasus yang sama tidak diputus’ (no. 65). Dalam bab terakhir, Paus menghimbau penciptaan budaya baru yang menghormati dan melindungi setiap hidup manusia. Orang-orang Kristiani harus menunjukkan perhatian khusus bagi kaum miskin dan tak beruntung; jemaat-jemaat mereka harus mendukung ibu-ibu yang tidak menikah, badan-badan konseling perkawinan dan keluarga, program pengobatan dan perawatan untuk mereka yang kecanduan obat bius, orang yang belum dewasa, orang yang sakit mental, orang-orang yang terkena AIDS, dan orang-orang cacad (no. 87-88). Gereja dan Lingkungan Meskipun Evangelium Vitae memasukkan penyalahgunaan lingkungan di dalam ancamanancaman modern terhadap kehidupan, Gereja Katolik telah lambat memasukkan perhatian terhadap lingkungan ke dalam ajaran resminya.31 Para uskup dalam Konsili Vatikan II tidak mengangkat masalah itu dan dokumen-dokumen konsili mencerminkan apa yang sekarang disebut ”teologi dominasi”, teologi yang melihat dunia alam ada hanya untuk umat manusia (bdk. GS 34). Teologi ini dapat ditemukan dalam ensiklik Paus Paulus VI yang terbit tahun 1967, yang mengutip perintah dalam Kitab Kejadian 1:28 ”untuk mengisi bumi dan menaklukkannya” (no. 22). Kisah penciptaan kedua dalam Kitab Kejadian menyarankan tanggung jawab yang lebih besar terhadap dunia alam; menurut kisah itu Tuhan Allah ”mengambil wanita itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu” (Kej 2:15). Gambaran di sini bukan dominasi melainkan penjagaan. Octogesima Adveniens, surat Paus Paulus VI, yang dikeluarkan tahun 1971 mengungkapkan keprihatinan pada lingkungan (no. 21), dan Paus Yohanes Paulus II menyebut beberapa kali masalah perusakan bumi dalam ensiklik pertamanya, Redemptor Hominis (no. 8, 15, 16). Akan tetapi, laporannya pada Sinode Para Uskup tahun 1984 tentang rekonsiliasi, Reconciliatio et Poenitentia, sayang tidak memuat pengasingan yang makin besar umat manusia dari lingkungannya yang mendukung hidup mereka sebagai salah satu hubungan yang memerlukan rekonsiliasi. Ensikliknya tahun 1988 Sollicitudo Rei Socialis merupakan ensikliknya yang pertama yang menyampaikan penekanan pada keprihatinan-keprihatinan terhadap lingkungan. Dalam pesannya untuk hari Perdamaian Dunia, 1 Januari 1991, ”Damai dengan Allah Pencipta, Damai dengan segala ciptaan” (Peace with God the Creator, Peace with All Cretion) seluruhnya membahas masalah lingkungan. Dewan Gereja-Gereja Dunia (The World Council of Churches) telah menaruh perhatian pada masalah lingkungan dalam agendanya sekurang-kurangnya sejak tahun 1975. Pada sidangnya di Vancouver, Kanada, tahun 1983, Dewan itu memperluas perhatiannya pada pelestarian masyarakat dengan menyebut perhatiannya untuk ”keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.” Disesalkan, bahwa Gereja Katolik tidak memenuhi undangan Dewan GerejaGereja Dunia untuk bersama-sama mensponsori Konferensi Dunia tentang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di Korea tahun 1990. Prinsip-Prinsip Sosial Katolik Sementara ajaran sosial Gereja dibangun berdasarkan prinsip martabat pribadi manusia, pendekatannya lebih bersifat komunitarian daripada perorangan. Dengan cara itu, ajaran sosial Gereja sangat berbeda dengan etos individualistis Barat. Peninjauan sistematis terhadap ajaran sosial Gereja mengungkapkan prinsip-prinsip dasar berikut. 1. Martabat pribadi manusia. Setiap manusia diciptakan menurut citra Allah, maka setiap hidup manusia adalah suci dan tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana. Akibatnya, segala sesuatu dalam bidang ekonomi dan politik harus dinilai berdasarkan kriteria, apakah bidang itu melindungi atau merongrong martabat manusia. Prinsip ini merupakan prinsip dasar pemikiran sosial Gereja. 2. Prioritas masyarakat dan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya, manusia itu bersifat sosial dan harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat, yang diperlukan oleh manusia untuk perkembangannya secara penuh. Hak-hak azasi manusia harus dilindungi agar setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam hidup masyarakat. Hak-hak individual 3. 4. 5. 6. 7. 8. mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dan harus dilaksanakan dengan pandangan untuk kesejahteraan umum. Keluarga merupakan unit dasar masyarakat. Keadilan distributif. Hal pokok untuk kesejahteraan bersama adalah distribusi yang adil. Tanpa itu hak masing-masing orang untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap mutlak untuk standar hidup yang layak, tidak dapat terwujud. Tujuan ekonomi adalah melayani kesejahteraan bersama (daripada memperbesar untung). Prioritas tenaga kerja atas modal. Orang-orang lebih penting daripada barang-barang. Benda-benda material bukan satu-satunya alasan untuk komunitas ekonomi, karena martabat manusia adalah yang utama dan kerja harus mengabdi martabat itu. Kerja juga mempunyai martabat, dan martabat manusia tak terpisahkan dari kerjanya. Melalui kerja, manusia menjadi lebih manusiawi. Hak untuk mengambil bagian. Semua orang mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hak untuk ikut mengambil bagian itu meliputi hak untuk bekerja, karena kerja hakiki bagi martabat manusia. Kerja penuh merupakan tujuan utama. Pengangguran tidak dapat dibiarkan menjadi sarana untuk tujuan lain, karena dengan demikian modal lebih diutamakan dari tenaga kerja. Kerja merupakan sarana untuk ikut ambil bagian dalam tatanan ekonomi, dan para pekerja tidak boleh dibiarkan tidak mendapatkannya. Para pekerja harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam keputusankeputusan organisasi sehari-hari. Kerja tidak hanya merupakan fungsi ekonomi tetapi juga kegiatan yang mempengaruhi sifat psikologis dan spiritual manusia. Prinsip subsidiaritas. Bilamana mungkin keputusan-keputusan harus dibuat pada tingkattingkat lokal daripada oleh badan-badan yang lebih tinggi, dengan demikian memberi prioritas pada inisiatif pribadi. Ikatan-ikatan pengantara (keluarga, masyarakat lokal, perserikatan, perkumpulan) harus bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ikatan-ikatan itu tanpa campur tangan negara. Hak milik pribadi yang dibatasi. Hak untuk milik pribadi tidaklah mutlak. Hak itu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang terhadap kesejahteraan bersama. Kewajiban terhadap kaum miskin. Baik orang perorangan maupun masyarakat sipil mempunyai kewajiban terhadap mereka yang rentan. Tidak setiap orang mempunyai titik tolak yang sama dalam kehidupan ekonomi, karena itu kemiskinan tidak dapat dipersalahkan kepada perorangan. Apa pun penyebab kemiskinan, kaum miskin mempunyai martabat yang sama dengan orangorang lain. 3. Hati Nurani dan Otoritas Dalam bab ini, kita telah melihat ajaran Gereja di bidang seksualitas dan keadilan sosial. Sekarang kita akan membahas peran hati nurani. Dalam tradisi Katolik, baik hati nurani maupun otoritas mempunyai peran penting untuk membantu orang mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi khusus. Akan tetapi, baik hati nurani maupun otoritas dengan mudah dapat disalah mengerti. Hati Nurani Katolisisme menghargai hati nurani sebagai bimbingan manusia yang terakhir. Konsili Vatikan II menggambarkan hati nurani sebagai ”inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci” manusia, di mana ia seorang diri bersama Allah (GS 16). Di sini Konsili menggemakan Thomas Aquinas yang mengajarkan bahwa hati nurani dalam arti yang paling umum adalah kebiasaan (synderesis), rasa intuitif yang ada dalam masing-masing orang untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Aquinas memahami hati nurani dalam arti tegas sebagai proses mencari apa arti rasa kewajiban untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat dalam situasi khusus.32 Karena menyangkut proses penegasan di mana kebaikan tertentu tidak segera menjadi jelas, proses mencari itu dapat meliputi penggunaan akal atau bersandar pada wahyu yang dipercayakan kepada Gereja. Dewasa ini banyak teolog moral Katolik mengikuti analisis Timothy O’Connell tentang tradisi: Hati nurani merupakan kesadaran moral manusia yang meliputi: 1) pemahaman dasar kita tentang bentuk perintah moral, melakukan yang baik dan menghindari yang jahat; 2) proses atau ”pengetahuan moral” untuk menemukan kebaikan khusus yang harus dilakukan dan kejahatan yang harus dihindari; dan 3) penilaian khusus yang dibuat pada kasus tertentu.33 Karena hati nurani pada akhirnya harus berakhir pada keputusan praktis yang dicapai sesudah pertimbangan teliti atas situasi, pentinglah untuk tidak membuatnya menjadi rasa atau suara batin subjektif. Hati nurani jangan disamakan dengan apa yang disebut oleh Freud sebagai ”superego”, sensor yang dikenakan yang merupakan ”keharusan-keharusan” dari berbagai tokoh yang berwibawa dalam hidup kita dan bersandar pada rasa salah untuk pelaksanaannya. Hati nurani mencakup seluruh pribadi: budi, intuisi, kepekaan moral, dan keputusan praktis. Meski orang harus selalu mengikuti hati nuraninya, hati nurani itu dapat keliru, entah karena ia belum dewasa sehingga belum mampu mengatasi kepentingan pribadi dan mengikuti saja pendapat masyarakat dalam membuat keputusan moral, atau ketidaktahuan, atau karena orang itu tidak berusaha menemukan kebenaran. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kewajiban untuk membentuk hati nurani yang benar. Otoritas Gereja, yang oleh umat Katolik dipandang sebagai ibu dan guru, membantu dalam proses ini. Inilah titik di mana otoritas masuk. Sebagai jemaat murid-murid Yesus, otoritas Gereja diungkapkan dalam Kitab Suci, tradisi, dan magisteriumnya, atau jabatan mengajar resminya. Kitab Suci menyampaikan kepada kita kisah Allah dan umat Allah yang kudus. Kitab Suci memberikan kita dekalog, sepuluh perintah (Kel 20:2-17), yang menetapkan parameter untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Hubungan perjanjian itu dilanggar jika kita menyembah dewa lain, tidak menghormati orang tua, melakukan pembunuhan atau perzinahan, mencuri, merusak nama baik sesama, atau mengingini apa yang menjadi milik orang lain Para nabi mengingatkan kita akan cinta Allah terhadap keadilan dan perintah terusmenerus untuk mengingat orang miskin dan orang lemah, ”tidak menindas orang asing, yatim dan janda” (Yer 7:6; bdk. Ul 24:21). Melalui Injil kita mengenal Yesus; seperti dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Veritatis Splendor, mengikuti Yesus merupakan dasar hakiki dan terutama dari moralitas Kristiani (no. 19). Injil membuat kita menjadi akrab dengan sabda dan ajaran Yesus, memberi kita kebijaksanaan yang termuat dalam perumpamaan-perumpamaannya, dan menantang kita untuk mencontoh teladan pelayanan setia-Nya. Tradisi menyimpan kumpulan kebijaksanaan Gereja, kebijaksanaan yang datang dari pewartaan, perayaan dan penyebaran iman jemaat Kristiani melalui banyak generasi. Tradisi itu ditunjukkan dalam hidup para martir dan para kudus. Tradisi meliputi keyakinan Gereja bahwa Allah telah memasukkan ke dalam setiap hati manusia ”hukum kodrat” untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, maupun pemahaman Gereja tentang apa yang disebut kebaikan manusiawi dalam situasi-situasi khusus, didasarkan atas wahyu Kitab Suci dan renungannya atas tatanan moral yang diwahyukan dalam ciptaan dan dalam martabat pribadi manusia. Magisterium mengajar atas nama Gereja dan juga atas nama Kristus; melalui magisterium, otoritas yang dipercayakan oleh Kristus kepada para Rasul dan para pengganti mereka, para uskup, diungkapkan. Dengan demikian tidak hanya mengingatkan umat Katolik tentang apa yang telah diajarkan oleh Gereja secara resmi di masa lampau, magisterium juga berfungsi sebagai jabatan mengajar yang hidup, yang memaklumkan prinsip-prinsip moral dan menerapkan prinsip-prinsip itu baik untuk hidup pribadi maupun tatanan moral. Katolisisme memiliki keyakinan mendalam bahwa setiap segi hidup manusia – pribadi, seksual, ekonomi, sosial – harus diubah berdasarkan janji Kerajaan Allah dalam Yesus. Banyak ajaran resmi Gereja di bidang seksualitas dan perkawinan berlawanan dengan nilai-nilai budaya modern. Orang Katolik menerima perutusan mengajar ini secara sungguh-sungguh dan menghormatinya. Mungkin karena ini orang berpikir bahwa orang-orang Katolik selalu berbicara tentang moralitas dan seksualitas. Gereja terus menekankan kesucian hidup, tak terceraikannya perkawinan, dan hubungan yang erat antara kesetiaan perkawinan dan ungkapan seksual. Bersamaan dengan itu, dalam bidang penerapan prinsip-prinsip moralitas Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, hati nurani dan otoritas kadang-kadang dapat konflik. Hati Nurani yang Terbentuk Baik Bagaimana konflik-konflik antara hati nurani dan otoritas itu diatasi? Prinsipnya tetap sama yaitu pada akhirnya orang harus mengikuti hati nuraninya. Akan tetapi, hati nurani itu tidak berdiri sendiri. Karena hati nurani orang dapat salah dan keliru, pengutamaan hati nurani tidak pernah dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab untuk membentuk hati nurani, yang bagi orang Katolik meliputi usaha yang sungguh-sungguh dan penuh doa untuk merasukkan pandangan moral yang muncul dari tradisi Katolik, yang dimengerti dalam arti penuh menurut Kitab Suci, Tradisi Gereja, keyakinan umat, pengajaran magisterium yang dilakukan oleh Paus dan para uskup. Dalam membentuk hati nurani, magisterium memainkan peran penting. Misalnya, orang Katolik yang berkata bahwa ”Gereja tak mempunyai hak untuk memberitakan tentang apa yang saya lakukan di tempat tidur” atau yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran sosial Gereja merupakan campur tangan yang tak berdasar ke dalam bidang politik dapat berbuat demikian lebih karena kepentingan pribadi atau kesadaran kelas daripada keinginan murni untuk menemukan kebenaran. Dalam masyarakat yang narsisistik dan tersekularisasi, seperti masyarakat modern ini, kita membutuhkan pandangan moral sebagai pedoman hidup. Pentinglah bahwa magisterium terus melaksanakan fungsi profetisnya untuk membantu umat Katolik dalam pembentukan moral mereka. Akan tetapi, pada akhirnya, tetap benarlah bahwa otoritas tidak pernah dapat menjadi pengganti keputusan-keputusan yang bertanggung jawab yang dibuat menurut hati nurani yang terbentuk baik.34 4. Kesimpulan Masalah-masalah seksualitas dan keadilan yang telah kita bahas adalah masalah-masalah penting karena berusaha mengungkapkan implikasi-implikasi menjadi murid dan pandangan Kristiani tentang kerajaan untuk hidup pribadi dan sosial. Masalah-masalah seksualitas dan keadilan menjadi kontroversial karena masalah-masalah itu menyangkut kita masing-masing secara pribadi. Ajaran Kristiani tentang seksualitas telah bertahan lama. Bahwa ajaran tentang seksualitas dalam perjalanan waktu hanya berubah sedikit tidaklah harus menjadi argumen untuk melawannya. Hidup Kristiani harus dibina oleh Injil, bukan oleh nilai-nilai kebudayaan tertentu. Namun demikian, pandangan etis tidak boleh membuat orang menjadi buta sehingga tidak dapat berbelaskasihan dan mengakui kekhasan orang-perorangan. Gereja bersikap keras dalam perannya sebagai guru, namun pada umumnya dalam praktek pastoralnya Gereja bersikap penuh belas kasihan. Ada juga suara-suara lain dalam Gereja yang pantas didengarkan. Ajaran sosial Gereja dilihat dari penyampaiannya masih baru, tetapi mempunyai akar yang kuat di dalam tradisi. Kisah Para Rasul menggambarkan jemaat Kristiani sebagai jemaat yang ”tak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama” (Kis 4:32). Gambaran itu mungkin merupakan pandangan tentang yang ideal, tetapi zaman kita mungkin membutuhkan visi seperti itu. Kita hidup dalam dunia di mana jurang antara kaum kaya dan miskin semakin melebar, tidak hanya dalam bangsa-bangsa melainkan juga secara global. Pada saat ini beberapa negara hancur menjadi anarki; ekonomi mereka tidak jalan, dan sistem pengekangan budaya, religius dan sipil mereka mulai runtuh. Di samping itu, lingkungan alam pun ada dalam situasi krisis. Habisnya sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbarui kembali, pengikisan hutanhutan hujan tropis, hilangnya humus tanah, pencemaran sungai, danau, dan udara, menipisnya lapisan ozon, pengumpulan berton-ton sampah beracun – semua ini membahayakan kemampuan planet bumi untuk mendukung hidup manusia sendiri. Dalam dunia yang begitu terancam, tradisi komunitarian yang berbicara tentang kesejahteraan bersama, keadilan distributif hak semua untuk ikut ambil bagian di dalam harta kekayaan masyarakat, dan hak atas milik pribadi yang dibatasi, dapat menjadi sumber daya yang kaya. Tetapi sungguh mengancam karena mengajak mereka yang hidup di Dunia Pertama yang makmur untuk meninjau kembali dan mungkin mengubah cara hidup mereka. Bagi orang Katolik, merupakan hal yang diterima bahwa Allah berbicara melalui Gereja meski tidak hanya melalui Gereja saja. Jika ada saat-saat atau situasi-situasi di mana orang menurut suara hatinya tidak dapat menerima apa yang diajarkan oleh Gereja, maka sesudah cukup doa dan studi, orang itu harus mengikuti suara hatinya. Akan tetapi, sama-sama penting bahwa dewasa ini menegaskan hak Gereja untuk mengajar, dan kewajiban orang Katolik untuk mengakui ajaran itu (bdk. LG 25). Jika ajaran magisterium harus diterima oleh umat beriman agar efektif di dalam hidup Gereja, juga benar bahwa para uskup, yang merupakan magisterium, mempunyai peran profetis penting untuk dimainkan guna membawa terang Injil untuk menerangi masalah-masalah yang dihadapi oleh Gereja di dunia dewasa ini. Catatan: 1. 2. 3. 4. Lisa Sowle Cahill, ”Humanity as Female and Male: The Ethics of Sexuality”, Called to love: Towards a Contemporary Christian Ethic, ed., Francis A. Eigo (Villanova, Pa.: Villanova Univ. Press, 1985) 87. John Mahoney, The Making of Moral Theology: A Study of the Roman Catholic Tradition (Oxford: Clarendon, 1987). Ibid., 53-54. Origins 23 (Oktober 14, 1993). 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. John T. Noonan, Contraception, (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1965) 251-252. Mahoney, The Making of Moral Theology, 33. Lihat, misalnya, George Gallup Jr. dan Jim Castelli, The American Catholic People: Their Beliefs, Practices, and Values, (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1987) 51. Origins 5 (1976) 485-494. Survey tentang tanggapan terhadap deklarasi itu, lihat Richard A. McCormick, ”Notes on Moral Theology,” Theological Studies. 38 (1977) 100-114. Lihat Vincent J. Genovesi, In Pursuit of Love: Catholic Morality and Human Sexuality (Wilmington: Glazier, 1987) 237-238. Lihat Richard A. McCormick, ”Notes on Moral Theology,” Theological Studies 30 (1969) 635-644; 40 (1979) 80-97. ”New Context for Contraception Teaching,” Origins 10(1980) 263-267. Lihat John Connery, Abortion: The Development of the Roman Catholic Perspective (Chicago: Loyola Univ. Press, 1977). Richard A. McCormick, ”Notes on Moral Theology,” Theological Studies 35 (1974) 325. Lihat Carol A. Tauer, ”The Tradition of Probabilism and Moral Status of the Early Embrio,” Theological Studies 45 (1984) 5-6. McCormick ”Notes on Moral Theology” Theological Studies 35(1974) 490-491. Todd David Whitmore, ”Notes for a ’New Fresh Compelling’ Statement,” America, 171 (October 8, 1994) 14-18. Lihat John P. Dedek, Contemporary Sexual Morality (New York: Sheed & Ward, 1971) 51-55. Genovesi, In Pursuit of Love, 318. Dedek, Contemporary Sexual Morality, 36. McCormick, ”Notes on Moral Theology”, Theological Studies, 35(1974) 461. Andrew Greeley, ”Sex and Single Catholic,” America 167(1992) 345. Lihat Genovesi, In Pursuit of Love, 262-273; Jeffrey S. Siker, Homoseksuality in the Church: Both Sides of the Debate, (Louisville: Westminster/John Knox, 1994). Lihat Michael J. Schultheis, Edward P. De Berri, dan Peter J. Henriot, Our Best Kept Secret: The Rich Heritage of Catholic Social Teaching (Washington: Center of Concern, 1987). Richard P. McBrien, Catholicism, rev. ed. (San Francisco: Harper, 1994) 913-914. Donal Dorr, Option for the Poor: A Hundred Years of Vatican Social Teaching (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1983) 26-27. Lihat Timothy G. McCarthy, The Catholic Tradition: Before and After Vatican II (Chicago: Loyola Univ. Press, 1994) 251. Gregory Baum, ”Faith and Liberation: Development since Vatican II,” Gerald M. Fagin, ed., Vatican II: Open Questions and New Horizons (Wilmington: Glazier, 1984) 90-93. Donal Dorr, Option for the Poor: A Hundred Years of Vatican Social Teaching, (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1983) 248; Paus Johanes Paulus II untuk pertama kali menganalisis solidaritas sebagai konsep pada tahun 1969 pada waktu menjadi Uskup Cracow; lihat hlm. 245. Dengan terbitnya ensiklik itu, uraian dalam Katekismus Gereja Katolik perlu dirumuskan kembali berdasarkan ajaran Paus yang termuat dalam ensiklik itu. Sean McDonagh, The Greening of the Church (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1990) 175; lihat ”The Environment in the Modern Catholic Church,” 175-203. Summa Theologiae I. 79. 12-13. Timothy O’Connell, Principles for a Catholic Morality (San Francisco: Harper & Row, 1990) 109 dst. Philip S. Kaufman, Why You Can Disagree and Remain a Faithful Catholic (Bloomington, Ind.: Meyer-stone Books, 1989). IX Doa dan Spiritualitas Thomas Merton menceritakan cerita yang bagus tentang pengalamannya mengikuti Misa untuk pertama kali di sebuah Gereja Katolik, tidak lama sebelum pertobatannya. Pada waktu ia masuk dan duduk di deretan bangku doa, tidak yakin tentang apa yang diharapkan daripadanya, ia melihat di dekatnya seorang gadis muda sekitar umur 16 tahun yang berlutut dengan tenang dalam doa. Kemudian ia menulis dalam autobiografinya yang terkenal, ”Saya amat terkesan ketika melihat bahwa seorang gadis yang masih sedemikian muda dan cantik dengan sedemikian sederhana dapat membuat doa menjadi alasan utama, sungguh-sungguh dan nyata untuk pergi ke Gereja.”1 Kristianitas bukanlah pesan atau wahyu tentang Allah yang tetap jauh. Menurut St. Agustinus, Allah jauh lebih dekat dengan saya daripada saya dengan diri saya sendiri. Pewahyuan-diri Allah dalam pribadi Yesus Kristus berarti bahwa Allah adalah Pemberi dan DiriNyalah yang diberikan. Dalam Yesus, yang membuat kita saudara dan saudari dan mencurahkan Roh-Nya kepada kita, kita telah diikutsertakan dalam hidup batin Tritunggal. Doa Kristiani selalu merupakan doa Trinitarian. Kita berdoa kepada Bapa dalam Putra melalui Roh Kudus. Sebagian besar misteri Tritunggal justru misteri keikutsertaan kita dalam hidup Ilahi. ”Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia” (Yoh 14:23). Akan tetapi, kita tidak selalu mengenal kedalaman Ilahi ini. Bukan jarak Allah tetapi justru kedekatan Allah itulah yang membuat kita sulit untuk menyadari kehadiran-Nya itu. Allah melingkupi kita, lebih dekat daripada udara yang kita hirup. Kadang-kadang kita tidak menyadari kehadiran Allah yang terus berlangsung seperti ikan tidak sadar akan air laut yang terus ada. Doa merupakan sarana bagi kita untuk mengalami hidup Ilahi itu. Doa mengembangkan hidup kita dalam Allah seperti gerimis yang jatuh di tanah membuat tanah itu menjadi gembur dan menjadikannya subur. Ada banyak bentuk doa, tetapi pada dasarnya semua doa berarti membuka diri kepada Allah. Doa mengangkat budi dan hati kita pada Allah. Berdoa adalah bersantai, membiarkan, mengulurkan tangan dan membuka telapak tangan sebagai tanda mau menerima.2 Kita berdoa dalam harapan karena Allah itu dekat dan mau mengisi kita. Kita merasa perlu berdoa karena tanpa Allah kita tak berakar dan sendirian, dan hidup kita menjadi dangkal. Kita berdoa penuh ketakjuban karena Allah adalah Pencipta dan kita adalah ciptaan, buah karya tangan-Nya. Doa tak terpisahkan dari hidup umat Allah dalam Kitab Suci. Orang tidak dapat membaca Mazmur tanpa rasa yang hidup betapa nyata kehadiran Allah bagi bangsa Yahudi. Mereka menyanyikan kenyataan Allah, untuk memuji dan mengucap syukur pada waktu kehadiran Allah dialami: ”Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya” (Mzm 89:2); ”Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada-Nyalah keselamatanku” (Mzm 62:2). Atau dengan cucuran air mata dan ratapan pada waktu Allah terasa jauh atau tidak hadir: ”Aku mau berseruseru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku (Mzm 77:2); ”Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?” (Mzm 22:2). Hal yang paling mengesankan adalah bahwa mazmur-mazmur menyampaikan rasa yang mendalam mengenai apa arti hidup dalam hubungan perjanjian dengan Allah Yahwe tanpa gagasan tentang hidup sesudah mati. Dalam tradisi Perjanjian Lama, gagasan itu baru muncul kemudian. Kurang lebih 200 tahun sebelum zaman Yesuslah harapan bahwa Allah orang yang hidup juga memberi hidup kepada orang yang mati muncul dalam tulisan religius Yahudi. Injil menampilkan Yesus sebagai manusia pendoa. Ia mengikuti tradisi-tradisi religius bangsa-Nya, dengan teratur mengikuti ibadat Sabat resmi ”menurut kebiasaan-Nya” (Luk 4:16) dan amat mungkin mendaraskan tiga kali sehari Shema, doa syahadat yang mulai ”Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa!” (bdk. Ul 6:4-5). Lukas terutama menekankan Yesus yang sedang berdoa. Pengalaman-Nya di sungai Yordan sesudah baptisNya terjadi sementara Ia sedang berdoa (3:21). Lukas menunjukkan Yesus yang berdoa sebelum saat-saat penting lain dalam hidup-Nya (5:16; 6:12; 9:18,28; 11:1; 22:42; 23:46) dan menasihati orang-orang lain agar berdoa (11:5-13; 18:1,9-14; 21:36; 22:40). Satu ucapan Yesus yang indah mendorong murid-murid-Nya agar bertekun dalam doa; dorongan itu juga merupakan pelajaran bagi kita juga: ”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu” (Luk 11:9). Mungkin hal yang paling menyentuh dari hubungan Yesus dengan Allah adalah istilah yang biasa digunakan-Nya dalam doa-Nya sendiri, yang menyapa Allah sebagai ”Abba”, ”Bapa”: ungkapan dalam keluarga yang artinya bukan hanya sebutan formal ”Bapak” tetapi seperti ”Bapa yang penuh kasih”, istilah yang digunakan oleh anak-anak dalam hubungan akrab keluarga. Tidak ada orang Yahudi pada zaman itu akan berani menyebut Allah dengan istilah akrab itu. Sungguh, orang-orang Yahudi yang saleh bahkan tidak menyebut nama Allah yang kudus. Mereka lebih suka menggunakan kata-kata, seperti ”Yang Terpuji” (Mrk 14:61) daripada mengucapkan nama kudus. Akan tetapi, kenyataan bahwa Yesus secara teratur berbicara dengan Allah dengan cara yang akrab itu menyarankan kepada kita banyak hal bukan hanya tentang pengalaman-Nya akan Allah tetapi juga tentang hakikat doa. Doa adalah berbicara secara pribadi dengan Allah yang mencintai dan memelihara kita. Pada akhir hidup-Nya, dengan pelayanannya yang tampaknya gagal, Yesus menghadapi kematian sendirian, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat-Nya. Bahkan Allah-Nya terasa tidak hadir. Namun Ia tidak putus asa, tidak berhenti mempercayakan Diri kepada Pribadi yang disebut-Nya ”Abba”, dengan harapan bahwa Allah akan membela-Nya. Allah ternyata tidak meninggalkan-Nya. Allah membangkitkan-Nya ke hidup abadi. 1. Jenis-Jenis Doa Doa Kristiani selalu merupakan usaha memalingkan diri kita kepada Allah melalui Kristus dalam Roh. Uraian tentang doa ada banyak, beraneka ragam, dan agak artifisial. Doa dapat berupa doa liturgi yang dilakukan bersama-sama atau pribadi. Tradisi Katolik juga mempunyai tradisi doa devosional seperti devosi kepada Hati Kudus Yesus, berbagai devosi kepada Maria, mengenang para Kudus dan mohon perantaraan mereka, berdoa di depan Sakramen Mahakudus, menyalakan lilin untuk melambangkan hakikat doa yang tidak kunjung putus, mengadakan peziarahan, atau novena (doa 9 hari berturut-turut) dan seterusnya. Devosi-devosi itu merupakan pelaksanaan kesalehan yang dimaksudkan untuk mendorong dan memperdalam hidup doa. Penulis-penulis rohani berbicara tentang beberapa jenis doa pribadi: doa lisan dan mental, doa afektif dan doa diskursif, doa spontan dan doa formal, doa meditasi, doa kontemplasi dan doa mistik. Akan tetapi, pembedaan yang rapi itu kerap luluh menjadi satu jenis doa yang berkembang menjadi doa lain. Doa lisan dengan Rosario dapat dengan mudah membawa orang berkontemplasi atau meditasi imaginatif tentang misteri-misteri hidup Yesus. Meditasi diskursif dapat menjadi doa kontemplatif, termasuk doa kontemplasi yang dalam yang memusat menjadi doa ”mistik”. Untuk membuat jelas, kita akan mengikuti pembedaan doa tradisional menjadi doa lisan atau diucapkan (oratio), doa mental (meditatio), dan doa kontemplasi (contemplatio) dengan mengakui keterbatasan pengelompokan itu sendiri. Doa Lisan Doa lisan merupakan cara untuk menyapa Allah dengan menggunakan baik doa-doa formal seperti Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan Kepada Allah maupun mengungkapkan pemikiran dan keprihatinan hati kita kepada Allah dengan kata-kata kita sendiri. Kita tidak pernah boleh berpikiran bahwa doa formal atau percakapan merupakan doa kelas dua. Doa-doa formal dapat amat membantu pada saat kita mau berdoa tetapi tidak mempunyai kata-kata untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita, terutama pada waktu mengalami kekosongan yang kadang-kadang kita alami. Mereka yang lemah karena sakit yang lama seringkali merasa sulit untuk mengumpulkan pemikiran dan berkonsentrasi. Mereka dengan senang menerima kehadiran orang yang dapat membantu mereka berdoa dengan mengulang bersama mereka doa-doa yang sederhana. Berdoa kepada Allah dengan ucapan dapat menjadi pengalaman yang mendalam pada waktu kita merasakan kegembiraan atau kesedihan, atau pergulatan batin. Kita harus dapat mengungkapkan diri kita secara leluasa kepada Allah pada waktu amat tergerak. Kedua macam doa lisan itu harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, seperti kadang-kadang kita perlu menantikan Tuhan dengan diam dan berharap. Yang penting adalah bahwa kita secara jujur berdoa dari hati daripada berusaha memaksakan sesuatu yang sebetulnya tidak mengungkapkan perasaan-perasaan terdalam kita. Beberapa macam doa lisan melibatkan tidak hanya pikiran dan perasaan kita, tetapi tubuh dan imajinasi kita. Hal yang mengherankan adalah bahwa banyak orang Katolik sekarang ini malah pergi ke pusat-pusat doa non-Katolik untuk berdoa dengan tubuh, padahal tradisi Katolik mempunyai cara doa dengan tubuh itu. Rosario merupakan metode doa kuno yang menggabungkan doa-doa sederhana yang dikeramatkan oleh tradisi dengan renungan pendek tentang peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus dan Santa Perawan Maria. Doa Rosario merupakan doa mantra, menenangkan pikiran dan imaginasi dengan memegang tasbih dengan jari kita satu per satu dan mengulang-ulang kata-kata sederhana dari Salam Maria sambil memusatkan perhatian pada misteri penyampaian kabar gembira, kelahiran Yesus, penyaliban, turunnya Roh Kudus, dan seterusnya. Jalan salib merupakan bentuk doa lain yang menggabungkan doa lisan dan meditasi tentang misteri-misteri kesengsaraan Kristus dengan gerakan tubuh, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berlutut, berjalan bersama Yesus dari satu pemberhentian ke pemberhentian yang lain. Bentuk doa lisan lain adalah ”glossolalia”, atau kurnia bahasa yang timbul dari pengalaman gerakan pembaruan karismatik. Disebut dalam Surat pertama St. Paulus kepada umat Korintus (bab 12, 14), bahasa adalah doa pujian yang meluap dari dalam diri orang sedemikian rupa sehingga perasaan mengatasi batasan-batasan bahasa dan menghasilkan ucapan atau nyanyian dalam lafal-lafal yang tidak dimengerti. St. Paulus mengakui bahwa bahasa merupakan anugerah Roh yang sejati, tetapi jelas merupakan rahmat kecil yang perlu diatur (1Kor 14). Meski jarang terlihat di luar lingkungan karismatik, karunia bahasa tidak perlu dianggap luar biasa atau mukjizat. Doa Mental Bila kita berdoa secara diskursif, dengan menggunakan budi, pikiran, dan imaginasi kita untuk menyatukan diri kita dengan Allah atau merenungkan misteri ilahi, kita melakukan doa mental. Meditasi atau renungan merupakan bentuk yang paling umum dari doa mental. Alkitab terutama merupakan sumber meditasi yang kaya. Kita dapat merenungkan kutipan Kitab Suci, dengan membacanya, menikmati bahasa dan penggambarannya, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui teks. Kita dapat merenungkan salah satu peristiwa dalam hidup Yesus dengan membayangkan penyembuhan orang buta misalnya, memasukkan diri kita dalam peristiwa itu, mengambil salah satu peran dalam kisah, membayangkan diri sebagai orang buta, menyeru kepada Yesus (atau merasa enggan untuk mendekati-Nya), merasakan sentuhan-Nya, membuka mata untuk pertama kalinya. Bila kita merenungkan hidup Yesus dalam Injil kita membiarkan penggambaran dan bahasanya tahap-demi-tahap menjadi milik kita. Lebih penting, dengan mengadakan semacam hubungan imaginatif dengan pribadi Yesus yang disajikan kepada kita dalam misteri-misteri Injil, kita menemukan kesejajaran antara kemanusiaan-Nya dan kemanusiaan kita. Yesus menjadi lebih nyata bagi kita. Dengan demikian, kita tumbuh dalam cinta dan penghargaan terhadap Tuhan yang tidak kita lihat. Satu cara yang amat bagus untuk berkembang dalam doa adalah setiap hari mengambil kutipan pendek dari Injil tertentu, bukan seluruh bab tetapi satu kisah sederhana – kisah mukjizat, ajaran atau sabda, – dan menggunakannya untuk doa. Beberapa orang merasa terbantu dengan menggunakan bacaan-bacaan liturgi harian yang bersangkutan yang termuat dalam kalender liturgi, sebagai bahan doa harian. Manfaatnya adalah menyatukan bacaanbacaan untuk doa mereka dengan liturgi atau mempersiapkan bacaan-bacaan untuk liturgi hari berikutnya jika mereka dapat mengikuti Misa harian. Orang lain merasa terbantu dengan menggunakan buku renungan-renungan pendek seperti Mengikuti Jejak Kristus (Imitatio Christi) oleh Thomas à Kempis. Bentuk-bentuk doa mental atau diskursif lain dapat meliputi bacaan meditatif Kitab Suci, bacaan rohani, mengadakan pemeriksaan batin atau ”pemeriksaan kesadaran” – atau membuat jurnal di mana kita merenungkan pengalaman doa dan perjalanan rohani kita. Mereka yang berdoa secara teratur seringkali menemukan bahwa doa mereka secara bertahap dapat bergeser dari doa diskursif ke cara doa yang lebih sederhana, lebih kontemplatif. Kontemplasi Doa kontemplatif adalah doa perhatian yang penuh cinta atas kehadiran Allah yang penuh misteri, meski kehadiran itu tidak langsung dialami tetapi hanya diketahui berdasarkan iman. Doa Samuel muda yang dipelajarinya dari imam Eli ”Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar” (1Sam 3:9). Bila doa mental menggunakan daya-daya imajinasi dan intelek, doa kontemplatif lebih tenang, reseptif dan afektif. Doa kontemplatif adalah doa dari hati, berfokus, dan menyadari dengan tenang kehadiran Allah yang dirasa dalam di dalam diri kita atau terkesan oleh kedamaian atau keheningan pandangan alam – padang rumput hijau di bawah langit biru yang luas membentang atau langit malam yang penuh bertaburan bintang-bintang. Kadang-kadang kehadiran Allah itu mendorong kita untuk berdoa secara afektif, dengan memuji, mengasihi dan memohon ampun. Dengan demikian, kontemplasi tidak sedemikian banyak melibatkan imajinasi atau penalaran diskursif tetapi melibatkan hati dan perasaan. Thomas Merton, biarawan Trapis yang mungkin menjadi orang yang paling berjasa memperkenalkan kontemplasi pada orang-orang zaman modern ini, menggambarkan kontemplasi sebagai pendalaman iman sampai ke titik di mana kesatuan dengan Allah yang sudah diberikan dalam hakikat diri kita diwujudkan dan dialami. Kontemplasi bukanlah buah akal-akalan psikologis tetapi rahmat sejati yang timbul sebagai kurnia dan bukan hasil penggunaan teknik-teknik khusus kita sendiri. Dalam bahasa yang puitis, Merton menggambarkan kontemplasi sebagai pintu yang terbuka di pusat diri kita dan melalui pintu itu, kita seolah-olah jatuh ke dalam kedalaman yang luar biasa dari keheningan dan kehadiran sementara daya-daya pikiran dan imaginasi kita terhenti.3 Pada titik ini pada waktu daya-daya alamiah kita tenang dan dalam kegelapan dan doa menjadi kesadaran yang sederhana, kontemplasi mulai berubah menjadi kontemplasi ”yang dicurahkan”, yang merupakan tahaptahap awal doa mistik. Doa mistik ini jangan disamakan dengan fenomena luar biasa seperti suara, visiun, atau pengangkatan. Kontemplasi lebih baik dimengerti sebagai doa kontemplatif yang meningkat, yang merupakan jalan bagi orang untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih mendalam tentang kehadiran Allah yang penuh misteri. Gereja telah amat diperkaya oleh guru-guru spiritual dan mistik-mistiknya, pria dan wanita, seperti Bernardus dari Clairvaux, Katarina dari Siena, Fransiskus dari Assisi, Julianus dari Norwich, Jean Gerson, Teresia dari Avila, Ignasius dari Loyola, Fransiskus dari Sales, Dorothy Day, dan Thomas Merton. Mistisisme merupakan bagian besar dari tradisi Katolik. Akan tetapi, doa kontemplatif bukan merupakan hal yang terbatas pada orang-orang mistik atau mereka yang hidup dalam hidup monastik atau religius. Doa kontemplatif dapat dilakukan oleh semua orang Kristiani. Dewasa ini banyak orang merasa bahwa apa yang disebut doa ”yang memusat” (centering prayer) merupakan persiapan yang membantu untuk doa kontemplatif.4 Doa yang memusat dapat menenangkan budi dan imaginasi dan berpusat pada kesadaran diri. Pendekatannya sederhana. Orang duduk dengan tenang dan mata tertutup menghadap Allah dalam iman, dengan mengabaikan pikiran-pikiran dan gambaran-gambaran yang terus keluar dari imaginasi. Banyak orang merasakan kegunaan ”kata suci” seperti ”Abba” atau ”Yesus Tuhan” untuk memusatkan perhatian mereka. Bila pikiran melayang, orang kembali lagi ke kata suci itu. Doa yang memusat berkaitan dengan tradisi Timur kuno yang dikenal sebagai Hesychasme (dari kata Yunani hesychia yang berarti ”tenang” atau ”diam”) atau Doa Yesus, suatu cara untuk memusatkan diri dengan mengulang-ulang kata-kata ”Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku.” Doa Liturgis Doa liturgis adalah doa Gereja atau umat yang berkumpul untuk beribadat dan memuji Allah. Pertama adalah Ekaristi itu sendiri, ”sumber dari puncak seluruh hidup Kristiani” (LG 11). Ibadat harian atau Doa Ofisi Harian merupakan doa pujian liturgis yang didasarkan pada doa biblis sinagoga-sinagoga Yahudi. Pada Gereja awal, Ibadat Harian dirayakan di dalam gerejagereja besar dan di biara-biara. Struktur pokok dari Doa Ofisi katedral awal meliputi beberapa mazmur dan kidung, Gloria in excelsis, beberapa doa umat, dan berkat penutup serta pembubaran. Vatikan II berusaha mengembalikan irama asli Doa Ofisi supaya Doa Ofisi tidak hanya merupakan doa imam-imam dan kaum religius melainkan seluruh Gereja (SC 100). Konsili Vatikan II menyebut secara khusus Ibadat Pagi dan Ibadat Malam sebagai ”poros rangkap Ibadat Harian, sebagai dua Ibadat yang utama” (SC 89). Dewasa ini Ibadat Harian semakin banyak didoakan oleh orang awam Kristiani. Banyak komunitas religius mendoakan Ibadat Harian pada pagi, siang dan sore hari untuk menetapkan irama doa pada hari yang bersangkutan. 2. Spiritualitas Hidup Kristiani adalah hidup di dalam Kristus. Seperti doa Kristiani, hidup Kristiani merupakan gerakan menuju kepada Allah melalui Kristus dalam Roh. Kata ”spiritualitas” berasal dari St. Paulus yang menggunakan kata pneumatikos, ”spiritual” dalam arti apa pun yang mendapat ciri atau dipengaruhi oleh Roh Allah. Di masa lampau spiritualitas terlalu kerap dipandang sebagai hal yang berhubungan dengan hidup rohani para rahib dan biarawati, kerap digambarkan sebagai ”hidup batin”. Dewasa ini, istilah spiritualitas dimengerti jauh lebih menyeluruh. Spiritualitas digunakan untuk melukiskan banyak cara yang berbeda yang menjadi sarana orang mengalami yang Transenden dan secara populer kerap digunakan untuk berbagai macam program peningkatan diri yang bertitik tolak pada sumber-sumber daya batin manusia. Dalam tradisi Kristiani, spiritualitas telah digunakan untuk menggambarkan cara-cara khusus untuk mengalami dan memupuk hidup dalam Kristus. Spiritualitas ”berkaitan dengan pengembangan, hari demi hari, keputusan mendasar untuk menjadi atau tetap menjadi orang Kristiani yang dibuat pada waktu baptis, diulangi pada waktu penguatan, dan diperbarui ketika kita menerima Ekaristi.”5 Karena banyaknya pandangan mengenai apa makna sebenarnya hidup dalam Kristus, maka terdapat banyak spritualitas yang berbeda.6 Beberapa spiritualitas ditemukan oleh gerakan atau cara hidup di dalam Gereja seperti monastisisme, hidup religius apostolik, dan berbagai gerakan awam seperti Marriage Encounter, Cursillo, dan pembaruan karismatik. Spiritualitas lain dikenal karena berhubungan dengan orang dalam sejarah Gereja seperti Fransiskus Assisi, Ignatius Loyola, atau Dorothy Day. Spiritualitas monastik, yang selalu memusatkan perhatian pada usaha mencari Allah saja, bersifat kontemplatif. Rahib dan rubiah kontemplatif berusaha untuk memusatkan hidup mereka pada Allah melalui selibat, diam, dan bagi banyak spiritualitas, kaul stabilitas. Hidup yang berpusat pada opus Dei atau doa liturgis, memberi dimensi liturgis yang kuat pada spiritualitas monastik; sedang hidup yang menekankan lectio divina, bacaan kontemplatif Kitab Suci membuat spiritualitas monastik menjadi amat bersifat biblis. Spiritualitas Benediktin khususnya menempatkan nilai besar pada hospitalitas atau keramahtamahan. Menurut Regulae St. Benedicti (Peraturan St. Benediktus) tamu harus diterima seperti Yesus sendiri. Para Fransiskan membaktikan diri pada Yesus yang miskin dan menderita dan berusaha melayani Yesus dalam orang miskin. Dengan demikian, spiritualitas Fransiskan mempunyai ciri khas cinta pada kemiskinan Injil dan kesetiakawanan dengan mereka yang kurang beruntung. Segi-segi lain meliputi usaha untuk menemukan pedoman hidup dalam Injil, rasa persaudaraan yang kuat, dan hormat terhadap ciptaan, yang meliputi rasa sayang besar terhadap binatang. Spiritualitas Ignasian, tumbuh dari pengalaman mistik Kristus, berciri Trinitarian. Cirinya yang kuat untuk kerasulan mencerminkan latar belakang Ignasius sebagai tentara. Beberapa segi spiritualitas Ignasian dapat dilihat pada Exercitia Spiritualia (Latihan Rohani); meditasi tentang Kristus Raja dan Dua panji-panji menekankan mengikuti Kristus dalam pelayanan-Nya dan penyamaan diri dengan-Nya dalam pengalaman direndahkan dan ditolak. Dari pandangan tentang Allah yang hadir dan aktif dalam segala ciptaan pada akhir Latihan Rohani, dikenal sebagai ”Kontemplasi untuk Mendapatkan Cinta” tampaklah cita-cita Ignatius untuk menemukan Allah di dalam segala hal. Peraturan tentang penegasan rohani merupakan perwujudan pemahaman Ignatius bahwa kita dapat mengenal kehendak Allah dalam gerakan-gerakan rasaperasaan kita. Spiritualitas Ignatian menekankan penegasan rohani. Dalam segala ungkapannya, spiritualitas Kristiani mau membimbing orang-orang lain ke hidup yang lebih mendalam dalam Kristus dan tumbuh dalam Roh. Dengan demikian, hidup cinta kasih harus menjadi inti setiap spriritualitas. Jika tidak ada cinta kasih, spiritualitas itu bukan spiritualitas Kristiani yang otentik. Tanpa cinta kasih, spiritualitas dapat dengan mudah terarah ke dalam, dengan menjadi semacam narsisisme rohani yang hanya sibuk dengan diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhannya atau asketisme yang mengingkari dunia yang mengasingkan yang satu dari yang lain dan mematikan roh. Hidup dalam Kristus berarti hidup untuk menjadi murid, dan menjadi murid diringkas dalam Injil Yohanes oleh perintah Yesus ”supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh 15:12). Dalam khotbah eskatologis yang terkenal dalam Injil Matius, Yesus menegaskan bahwa pada suatu hari kita akan diadili berdasarkan bagaimana kita menaruh perhatian terhadap kaum miskin dan kekurangan, terutama mereka yang menderita kelaparan, kehausan, orang asing, yang telanjang, yang sakit atau dalam penjara (Mat 25:31-46). Khotbah itu menjadi titik tolak untuk melakukan apa yang oleh katekismus tradisional disebut ”karya amal”, baik jasmani seperti memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi perlindungan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, mengunjungi orang sakit, membebaskan tawanan, dan mengubur orang mati, maupun rohani seperti mengajar orang yang tidak tahu, menasihati orang yang bingung, menasihati orang yang salah, menanggung kejahatan dengan sabar, mengampuni penghinaan, menghibur orang yang sedih, berdoa bagi orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Karya amal itu dianjurkan kepada semua orang Kristiani. Untuk mendorong pertumbuhan dalam iman, harapan, dan terutama cinta kasih, kebanyakan spiritualitas menekankan doa. Doa merupakan hal yang hakiki. Tanpa doa tidak ada hidup batin, tidak ada pengalaman kehadiran Allah yang mengubah. Di samping doa, spiritualitas-spiritualitas Kristiani mengajarkan disiplin rohani. Kita tahu bahwa sejumlah disiplin diperlukan bagi kesehatan fisik kita. Kita memerlukan olah raga, diet yang hati-hati, ugahari dalam penggunaan alkohol dan obat perangsang, dan lama waktu tidur yang tepat. Demikian juga, kita membutuhkan disiplin dalam hidup rohani kita. Istilah tradisional untuk disiplin semacam itu adalah ”asketisme”, istilah yang dewasa ini menimbulkan rasa tidak enak, meski istilah itu masuk dalam perbendaharaan kata Kristiani dari kata Yunani yang berarti cinta atletik (kata Yunani askesis berarti ”latihan atletik” atau ”praktek”). St. Paulus sendiri membandingkan usahanya untuk menguasai tubuhnya demi kerja kerasulan dengan latihan atletik yang diperlukan untuk dapat ikut bertanding (1Kor 9:25-27). ”Asketisme” berarti praktek disiplin rohani untuk mengatur dorongan-dorongan alamiah, membuat orang menjadi berpusat, dan membuka roh bagi kehadiran Allah. Ada sejumlah praktek asketis tradisional yang masih dapat amat membantu. Kebanyakan tradisi religius telah mengakui nilai rohani dalam berpuasa. Dalam Perjanjian Lama, puasa merupakan tanda silih dosa. Dalam sejarah Kristianitas, puasa telah dipraktekkan sebagai cara untuk menyatukan diri dengan Yesus yang menderita sengsara dan persiapan untuk doa (bdk. Kis 13:2-3). Menurut Didache abad ke-2, orang yang akan dibaptis dan orang yang akan membaptis harus berpuasa sebelum merayakan sakramen (Didache 7). Dalam literatur patristik, puasa kerap kali dikaitkan dengan pemberian derma. Paling sedikit mulai abad ke-3 orang-orang Kristiani berpuasa dalam persiapan Paskah, praktek yang kemudian berkembang menjadi masa liturgi puasa. Peraturan puasa, yang telah selama berabad-abad menjadi bagian dari praktek keagamaan orang Katolik telah amat diringankan di sekitar waktu Konsili Vatikan II. Pada tahun 1964, Paus Paulus VI mengurangi waktu puasa sebelum menerima Komuni dari pukul 12 malam menjadi 1 jam sebelum menerima Komuni. Sesudah Konsili, puasa Masa Puasa yang diwajibkan amat diperlunak, meskipun orangorang Katolik masih dituntut menaati puasa kecil pada hari Rabu Abu dan Jumat Suci. (Aturannya adalah dalam satu hari hanya makan kenyang satu kali). Dewasa ini banyak orang Kristiani menemukan kembali puasa sebagai disiplin untuk doa dan cara untuk mengalami kesetiakawanan dengan orang kelaparan dan kaum miskin. Pantang, tidak makan daging, merupakan praktek asketis lain yang mempunyai sejarah panjang di dalam Gereja. Banyak komunitas monastik sama sekali tidak makan daging baik sebagai disiplin maupun sebagai tanda silih dosa, praktek yang masih dipertahankan oleh biarawan trapis dan komunitas-komunitas kontemplatif lain. Menemukan waktu dan tempat untuk sendiri di hadapan Allah, untuk keheningan, merupakan disiplin spiritual yang lain. Dalam sejarah spiritualitas, padang gurun telah berfungsi sebagai lambang keheningan yang memupuk doa dan membantu untuk bertemu dengan Allah. Sejumlah komunitas kontemplatif modern menyediakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman ”padang gurun” itu satu hari seminggu, hari yang dikhususkan untuk keheningan dan kontemplatif tenang, terbebas dari acara harian komunitas yang biasa. Dalam kehidupan kita yang sibuk dan gaduh, kita perlu menemukan tempat untuk hening. Kadang-kadang kita perlu dapat mencium bau tanah, merasakan rumput dengan telapak kaki kita yang telanjang dan terpaan angin pada wajah kita. Keheningan membantu kita membuka diri kepada Allah yang berbicara kepada kita dalam keheningan dan dalam keindahan alam. Kita juga harus menemukan tempat tenang dan keheningan dalam hidup kita sehari-hari, tempat tertutup untuk berjalan-jalan sambil refleksi atau sudut di dalam kamar di mana kita dapat menyalakan lilin di depan ikon atau salib dan duduk dalam doa dan keheningan. Retret merupakan waktu hening yang panjang, waktu untuk masuk secara lebih intensif ke dalam doa dan meditasi. Ada rumahrumah retret yang memberi kesempatan untuk mengadakan Latihan Rohani, bahkan ada rumah retret yang menyediakan tempat bagi orang yang mau berakhir pekan untuk berdoa dan merenung. Bimbingan rohani dapat amat membantu dalam usaha kita untuk menghayati hidup rohani secara lebih sadar. Pembimbing rohani lebih sebagai sahabat yang dipercaya daripada orang yang ”mengarahkan” atau memberi tahu kita tentang apa yang harus kita lakukan. Pembimbing rohani adalah orang yang dapat kita curahi kisah tentang peziarahan batin kita, dengan mengutarakan doa dan usaha kita untuk menegaskan di mana kita berdiri di hadapan Allah dan ke mana kita sebaiknya mengarah. Disiplin untuk bertemu secara teratur dengan pembimbing rohani, seperti menulis jurnal, membantu mengobjektifikasikan pengalaman kita dan dapat melindungi diri terhadap penipuan-diri. Pembimbing rohani yang baik adalah orang yang mendengarkan dengan baik dan dirinya sendiri berpengalaman dalam doa. Dewasa ini semakin banyak orang awam pria dan wanita yang memberi pelayanan sebagai pembimbing rohani. Tanpa Kekerasan Meksipun pada umumnya tidak termaktub dalam tulisan-tulisan tradisional tentang spiritualitas, tanpa kekerasan (nonviolence) juga merupakan disiplin rohani yang menuntut banyak. Dalam esainya yang berjudul ”Berbahagialah mereka yang lemah lembut,” Thomas Merton menyebut tujuh prinsip.7 Tanpa kekerasan Kristiani secara teologis didasarkan pada Sabda Bahagia. Mereka yang mempraktekkannya harus bersedia menolak penggunaan kekuasaan yang tidak adil dan salah. Merton yakin bahwa mereka yang melawan kekerasan dengan menggunakan kekerasan akan tertular oleh kejahatan yang justru mereka lawan, dan jika berhasil, mereka sendiri akan menjadi sama kejam dan tidak adil. Akan tetapi, tanpa kekerasan bukanlah kepasifan. Tanpa kekerasan berarti menjadi bagi orang lain terutama kaum miskin dan kaum yang tak beruntung. Mereka yang mempraktekkan tanpa kekerasan harus menghindari sikap benar-diri yang dengan mudah dapat membuat mereka yang terlibat terpuruk ke dalam pergulatan moral. Mereka harus bersedia melepaskan fetisisme untuk mencari hasil-hasil yang segera tampak, cara struktur kekuasaan yang mereka lawan. Terutama, harus ada sikap menolak secara mutlak terhadap kejahatan, termasuk ketidakjujuran, dan mereka harus bersedia mengakui dan menerima kebenaran pendirianpendirian lawan-lawan mereka. Merton menyatakan bahwa tanpa kekerasan tidak dapat dipandang sebagai taktik yang akan digunakan untuk memperoleh perdamaian sebagai tujuan politik, betapapun pantas dipujinya. Tanpa kekerasan akan berhasil hanya jika merupakan usaha untuk mengejar kebenaran. Merton telah mempelajarinya dari Gandhi dan mengutip kata-kata Gandhi yang merupakan ringkasan Gandhi tentang seluruh ajaran tanpa kekerasan: ”Jalan perdamaian adalah jalan kebenaran ... Kebenaran bahkan lebih penting daripada perdamaian.”8 Merton menekankan bahwa mereka yang melawan tanpa kekerasan tidak berjuang demi kebenaran-”nya” atau hati nurani-”nya”, tetapi demi kebenaran, kebenaran umum baik bagi mereka yang melawan kekuasaan maupun lawan, dan dengan demikian mereka yang melawan tanpa kekerasan sesungguhnya berjuang bagi semua orang. Pandangan Merton tentang tanpa kekerasan mengalir dari kontemplasi dan rasa keterkaitan segala hal yang merupakan buah kontemplasi itu. Tanpa kekerasan harus melepaskan segala kebenaran khusus, betapapun berharga, demi kebenaran sendiri, kebenaran yang adalah Allah sendiri. 3. Spiritualitas-Spiritualitas Dewasa Ini Spiritualitas Awam Hidup religius dengan kaul dalam Gereja kerap disebut sebagai ”status perfectionis,” status hidup sempurna, dan terlalu kerap tradisi Katolik cenderung mengatakan seolah-olah spiritualitas hanya berkaitan dengan hidup yang dijalani oleh kaum religius. ”Identitas orang Kristiani awam telah menjadi amat kabur selama berabad-abad karena hidup religius menjadi kerangka normatif bagi hidup Kristiani.”9 Kita cenderung melupakan bahwa banyak tradisi spiritual yang kaya dalam Gereja diciptakan oleh pria dan wanita awam. Bapa-bapa dan ibu-ibu padang gurun awal adalah orang awam, bukan klerus atau religius. Beguine dan Beghard dari abad ke-12 dan ke-13 merupakan gerakan awam seperti halnya spiritualitas St. Fransiskus Assisi. Semua orang Kristiani, awam pria dan wanita maupun religius, dipanggil ke hidup rohani. Dengan demikian, pentinglah memperluas konsep spiritualitas untuk mencerminkan lingkungan dan kebutuhan orang awam yang berbeda-beda, apakah hidup sendiri atau nikah. St. Fransiskus dari Sales (meninggal tahun 1622) mengenal keanekaragaman spiritualitas. Dalam bukunya Introduction to the Devout Life, Fransiskus dari Sales menekankan bahwa praktek devosi harus disesuaikan untuk setiap orang menurut tugas dan pekerjaan masing-masing: Saya minta kepadamu, Philothea, apakah baik bahwa uskup menjalani hidup bertapa seperti seorang cartusian? Atau orang yang menikah tidak mengumpulkan lebih banyak kebaikan daripada seorang Kapusin? Jika pedagang harus tetap berada di dalam Gereja, seperti anggota Ordo Religius, atau religius terus-menerus bersusah payah melayani sesama, seperti seorang uskup, bukankah itu devosi yang lucu, kacau, dan tak dapat dijalani?10 Konsili Vatikan II, dengan penekanannya pada panggilan umum untuk kesucian (LG 42) memberikan dasar untuk berbagai spiritualitas awam. Dasar semua spiritualitas adalah baptis yang memasukkan orang ke dalam Kristus dan Gereja, dan memberi bagian kepada masing-masing, baik awam, religius, atau ditahbiskan dalam fungsi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja (LG 31). Spiritualitas awam mengembangkan panggilan baptis ini baik di dalam Gereja maupun di dunia. Sebagai panggilan di dalam Gereja, spiritualitas awam dipupuk oleh Sabda Allah dan Sakramen-sakramen. Sebagai panggilan di dunia, spiritualitas awam harus inkarnasional. Spiritualitas awam harus dapat menemukan kehadiran Allah di tengah-tengah hal yang biasa dan sehari-hari, dan mengetahui bahwa kerja dapat menjadi ungkapan keterlibatan Kristiani seseorang. Spiritualitas awam dapat dihayati dalam perkawinan atau dalam hidup sendiri tanpa nikah. Pasangan suami-istri dipanggil untuk spiritualitas yang pada dasarnya relasional, saling berhubungan satu sama lain. Panggilan utama mereka adalah perkawinan dan keluarga. Mereka dipanggil untuk hidup bersama yang menghormati dan mengatasi perbedaan-perbedaan. Cinta seksual mereka merupakan ungkapan spiritualitas mereka. Cinta seksual merupakan tanda yang penting dari cinta Allah yang lembut dan penyerahan diri. Kesenangan seksual mengikat suami dan istri satu sama lain dan menyembuhkan friksi dan konflik yang kerap muncul dari hidup bersama.11 Dalam arti sebenarnya, suami dan istri menggambarkan Allah bagi pasangannya dan bagi anak-anak mereka. Keluarga dan rumah tangga mereka menjadi tempat di mana orang-orang lain dapat mengalami kegembiraan dan jaminan kasih Allah. Baik hidup perkawinan maupun hidup sendiri dapat membawa orang dekat pada Allah. Gerakan Marriage Encounter telah amat berjasa dalam meningkatkan spiritualitas perkawinan. Marriage Encounter telah membantu pasangan menemukan apa makna menjalani perkawinan Kristiani sebagai sakramen. Beberapa pria dan wanita memilih hidup sendiri tanpa nikah sebagai cara untuk mengembangkan keakraban dengan Allah dan untuk menyerahkan diri secara lebih lengkap bagi pelayanan khusus di dalam Gereja. Hidup sendiri mereka dapat merupakan ungkapan selibat demi Kerajaan (bdk. Mat 19:12). Pembaruan karismatik telah menolong banyak orang awam untuk mengalami hidup yang mendalam dalam roh. Gerakan Cursillo, yang didasarkan pada pembaruan rohani pada akhir minggu, meningkatkan spiritualitas yang menemukan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, dan terutama di dalam Gereja lokal. Penemuan kembali pelayanan awam menuntut spiritualitas pelayanan. Keadilan dan Solidaritas dengan Kaum Miskin Salah satu aliran yang paling kuat mempengaruhi spiritualitas dalam abad ke-20 adalah gabungan spiritualitas kontemplatif dengan keterlibatan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan solidaritas (kesetiakawanan) dengan kaum miskin. Spiritualitas pembebasan, yang berkembang dari teologi pembebasan di Amerika Latin, merupakan ungkapan dari aliran spiritualitas itu. Gagasan tentang solidaritas dengan kaum miskin bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah Gereja. Meskipun retorikanya berbeda, panggilan untuk mengikuti Yesus yang miskin, yang didengar oleh Fransiskus Assisi dan Saudara-Saudara Dinanya, dan praktek kemiskinan mereka dengan mengemis pasti merupakan ungkapan dari apa yang dewasa ini disebut ”pilihan mengutamakan kaum miskin.” Charles de Foucauld, dalam usahanya mewartakan Injil dengan meneladan hidup Yesus yang tersembunyi di Nazaret, dengan hidupnya sendiri di tengah suku-suku Sahara merupakan contoh modern dari tradisi ini. Ia mempunyai pengaruh yang amat besar pada komunitaskomunitas religius tertentu dewasa ini. Ada beberapa komunitas yang didirikan oleh pria dan wanita awam seperti komunitas Pekerja Katoliknya Dorothy Day dan l’Archenya Jean Vanier, yang anggota-anggotanya berusaha menggabungkan kontemplasi, kesederhanaan hidup, dan pelayanan langsung kepada orang miskin dalam hidup mereka. Spiritualitas gerakan Pekerja Katolik didasarkan pada Injil. Dalam sebuah pahatan yang dibuat oleh seniman Quacker, Fritz Eichenberg, yang menjadi semacam ikon tidak resmi dari gerakan itu, Yesus berdiri kedinginan dan tak dikenal dalam deretan orang-orang miskin yang dengan sabar menunggu. Para Pekerja Katolik melihat hubungan yang jelas antara praktek perayaan Ekaristi dan makanan yang mereka sajikan kepada orang-orang lapar di dapur mereka. Mereka mengulang kata-kata Dorothy Day: ”Kita mengenal Kristus dalam pemecahan roti. Kita mengenal satu sama lain dalam pemecahan roti.” Mereka yang tertarik pada l’Arche merasakan dalam orangorang yang cacat mental kerentanan yang membuat mereka terbuka terhadap Allah dengan cara khusus. Spiritualitas mereka didasarkan pada kebenaran dasar Injil: Yesus menyamakan diri dengan orang miskin dan menderita, dan bila kita membuka hati kita bagi orang miskin, kita dapat mengenal kedamaian dan kehadiran-Nya. Mereka tak dapat meneruskan hidup sehari-hari mereka untuk merawat orang-orang cacad jika mereka tidak yakin akan kebenaran itu. Sabda Bahagia (Mat 5:3-12; Luk 6:20-26) menjadi pusat spiritualitas mereka. Mereka yang disebut bahagia oleh Yesus adalah mereka yang miskin, menderita, dan berbelaskasihan, dan bukan mereka yang enak dan berkuasa. Sabda Bahagia merupakan tantangan yang terus-menerus bagi kita, karena Sabda itu menjungkirbalikkan nilai-nilai konvensional kita dan membuka pandangan dunia yang sama sekali baru. Dewasa ini krisis AIDS telah menantang orang-orang Kristiani untuk menanggapi mereka yang hidup dan menghadapi ajal karena penyakit yang mengerikan itu. Dewasa ini ada kira-kira 13 juta orang terinfeksi virus HIV. Diperkirakan jumlah itu akan membengkak menjadi 110 juta pada tahun 2000.12 Di antara para penderita AIDS itu, banyak yang menanggung penderitaan tambahan karena penyakit itu dicap negatif oleh masyarakat, ditinggalkan oleh keluarga mereka, dan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Banyak orang yang merawat orang yang terkena AIDS dan mereka yang menderita penyakit itu menemukan spiritualitas belas kasihan, doa dan harapan, dalam usaha untuk menghadapi AIDS sebagai fakta dalam hidup mereka. Usaha orang-orang Kristiani dan Gereja-Gereja Amerika Latin untuk menghayati pengutamaan kaum miskin di tengah-tengah masyarakat yang keras dan menindas telah menciptakan spiritualitas menjadi murid bahkan menjadi martir. Harganya amat mahal. Jumlah imam, suster, bruder dan pendeta-pendeta Prostestan yang terbunuh di Amerika Tengah dan Latin sejak akhir Konsili Vatikan II sudah ratusan orang. Pada tahun 1980-an lebih dari dua belas imam dan sekurang-kurangnya tiga pendeta dibunuh atau hilang di Guatemala. Dalam jangka waktu yang sama di El Salvador, Uskup Agung Romero, 4 wanita Gereja dan sekurangkurangnya 17 imam dibunuh. Pada tahun 1989, enam Yesuit bersama dengan juru masak dan anak perempuannya dibunuh pada waktu pasukan Salvador masuk ke dalam tempat tinggal mereka dan membunuh mereka dengan kepala dingin. Jika tokoh-tokoh awam dihitung, jumlah orang yang dibunuh di Amerika Tengah dan Latin mencapai ribuan orang. Jon Sobrino, salah seorang Yesuit Salvador yang kebetulan tidak ada di rumah pada waktu enam rekannya dibunuh di tempat tinggal mereka, telah banyak menyumbangkan apa yang disebutnya spiritualitas pemerdekaan, spiritualitas keadilan, dan solidaritas dengan kaum miskin.13 Ia menceritakan malam yang tragis yang dialami rekan-rekannya pada malam itu, yang melambangkan secara lebih kuat dari segala tulisannya solidaritas Allah dengan kaum miskin dan kaum tak berdaya.14 Di kamarnya di antara buku-bukunya ada buku yang ditulis oleh teolog Jerman Jürgen Moltmann yang berjudul The Crucified God. Sesudah pembunuhan, tentaratentara menyeret satu mayat Yesuit yang sudah meninggal ke kamar Sabrino. Tentara-tentara itu menabrak rak buku sampai buku Moltmann jatuh. Buku itu jatuh dekat tubuh Yesuit yang meninggal, dan ditemukan keesokan harinya; buku penuh berlumuran darah Yesuit yang meninggal itu. Jauh lebih bagus daripada semua uraian teologis, buku yang penuh darah itu dengan judulnya yang kuat berbicara tentang rasa-perasaan Allah sendiri, solidaritas Allah melalui Yesus yang disalib dengan korban-korban kekuasaan dan ketidakadilan sepanjang sejarah umat manusia. Apa ciri-ciri spiritualitas keadilan dan solidaritas dengan kaum miskin itu? Pertama, spiritualitas itu harus berakar pada doa dan kontemplasi, yang selalu merupakan pergulatan untuk mencapai kenyataan, untuk melihat segala sesuatunya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Membaca Kitab Suci sehingga hidupnya sehari-hari dimengerti menurut penerangannya memegang peranan vital di sini. Kedua, kesederhanaan hidup. Sulit malah mustahil untuk solider dengan kaum miskin sementara ia menjalani gaya hidup enak – makmur melimpah. Pada kenyataannya, budaya kelimpahan, yang dapat membunuh roh merupakan produk jaringan ekonomi dan strukturstruktur sosial yang memungkinkan sejumlah kecil orang hidup melimpah dengan mengorbankan mayoritas orang. ”Pengalaman terlibat”, yang diperoleh dengan hidup dan bekerja selama beberapa waktu dengan kaum miskin dan juga pelayanan langsung kepada mereka yang tidak beruntung dapat amat membantu mengembangkan spiritualitas itu. Demikian analisis sosial yang terus-menerus dapat memperdalam kesediaan terlibat untuk hidup sederhana dan solider dengan kaum miskin. Ketiga, keinginan untuk membangun masyarakat yang mencakup semua orang yang mengatasi segala batas dan halangan. Gereja sendiri merupakan tanda kesatuan semua orang untuk kedatangan Kerajaan Allah. Perpecahan antara mereka yang telah dibaptis entah didasarkan ras, jenis kelamin, kekayaan, atau status sosial, memecah kesatuan tubuh Kristus. Itu semua, menurut St. Paulus, merupakan pelanggaran melawan Tubuh dan Darah Tuhan (1Kor 11:17-31). Pada akhirnya bertindak demi keadilan. Doa yang autentik membawa ke perhatian bahkan keprihatinan terhadap keadilan. Terlibat aktif dalam perjuangan demi keadilan merupakan bagian tanggung jawab semua orang Kristiani. Keterlibatan itu merupakan ungkapan keikutsertaan mereka dalam perutusan Gereja. Sinode para uskup tahun 1971 menegaskannya dalam pengantar dokumen Justitia in Mundo (Keadilan di Dunia): ”Tindakan demi keadilan dan keikutsertaan dalam perubahan dunia bagi kami tampak secara penuh sebagai dimensi konstitutif pewartaan Injil, atau dengan kata lain, dari perutusan Gereja untuk penebusan umat manusia dan pembebasannya dari segala situasi yang opresif.” Spiritualitas keadilan dan solidaritas dengan kaum miskin harus selalu memberi perhatian pada pergeseran dari mewartakan kebenaran ke melaksanakan kebenaran. Anak-anak muda Kristiani dapat mempelajari nilai-nilai spiritualitas keadilan sosial itu dengan melaksanakan pelayanan kepada orang miskin dengan hidup selama satu atau dua tahun melalui kelompok-kelompok pelayanan yang sudah atau dibentuk secara khusus untuk pelayanan itu. Spiritualitas Feminis Spiritualitas feminis merupakan spiritualitas yang relatif baru. Spiritualitas ini tumbuh dari perjuangan wanita demi kesamaan, baik di dalam masyarakat maupun di dalam Gereja. Spiritualitas itu juga merupakan ungkapan teologi pembebasan. Seperti teologi feminis (karena kerap sulit dibedakan antara teologi dan spiritualitas), spiritualitas feminis memuat berbagai pandangan dan mencakup berbagai tokoh di dalam Gereja Katolik dewasa ini. Beberapa teolog feminis secara terang-terangan sudah bergerak lebih jauh dari tradisi Kristiani. Minat teologis mereka terpusat pada pemujaan dewi Eropa pra-Kristiani, agama asli yang dikenal dengan nama Wicca. Mary Daly adalah salah seorang dari kaum feminis yang menyebut diri sebagai pasca-Kristiani. Feminis-feminis lain, seperti Rosemary Radford Ruether dan Elisabeth Schüssler Fiorenza, telah menantang tradisi secara radikal dari dalam. Apa yang umum bagi kebanyakan teolog feminis adalah usaha untuk memasukkan ke dalam permenungan teologis pengalaman kaum wanita yang kerap dilupakan. Spiritualitas feminis berusaha untuk merumuskan pandangan tentang hidup rohani yang dapat menampung pengalaman kaum wanita, terutama pengalaman penindasan; teologi itu mengolah kebutuhan-kebutuhan khusus kaum wanita dan membantu mereka untuk mendapatkan kembali kekuasaan rohani mereka. Timbulnya kesadaran merupakan langkah pertama terhadap visi spiritual feminis yang sejati. Wanita, yang kerap kali telah didefinisikan dalam kerangka fungsi seksual dan reproduktif mereka, menekankan bahwa nilai dan kemungkinan-kemungkinan pribadi mereka tidak dapat ditentukan oleh biologi. Dengan demikian, teologi feminis memberi kepada kaum wanita pandangan alternatif yang mengandung kritik terhadap kekuatan-kekuatan dan gerakan-gerakan yang menindas kaum wanita dan mengasingkan mereka dari diri mereka sendiri. Patriarki (penyusunan) masyarakat dan budaya dalam kerangka minat dan kekuasaan pria dan hierarki (pengorganisasian masyarakat dan Gereja dalam kerangka status yang lebih tinggi dan lebih rendah), ditolak. Teologi feminis menekankan kesamaan, perangkuman dan ketimbalbalikan. Teologi itu lebih merupakan diskusi daripada kuliah, lingkaran daripada segi empat. Spiritualitas feminis amat berbeda dari spiritualitas tradisional dalam pendekatannya yang non dualitis terhadap segala kenyataan. Teologi itu berusaha mengatasi keterpisahan antara badan dan jiwa, antara spiritualitas dan seksualitas, antara yang transenden dan yang imanen, pikiran dan perasaan, yang suci dan yang sekular, antara dunia ini dan dunia yang akan datang. Teologi itu berusaha membaca Injil sedemikian rupa, sehingga wanita diberdayakan. Dengan demikian, teologi feminis merasa tidak nyaman dengan penekanan dalam teologi klasik tentang mengalahkan diri sendiri dengan mengutamakan orang lain, karena melihat di sini penguatan kembali pada kepasifan dan penundukan yang dialami oleh sedemikian banyak wanita karena kebudayaan patriarkal dan Gereja. Menggantikan egonya sendiri adalah bagus jika godaannya adalah kesombongan, tetapi bagi banyak wanita tugas pertobatan sejati yang nyata adalah menjadi lebih tegas, menegaskan nilai mereka sendiri, dan sungguh-sungguh mencintai diri sendiri.15 Ada sejumlah ciri khas spiritualitas feminis: pertama, spiritualitas itu berakar pada pengalaman kaum wanita. Dengan demikian pada umumnya ada tekanan pada penyampaian (sharing) pribadi tentang kisah-kisah sebagai cara untuk mendapat kembali apa yang tertekan dan peningkatan kesadaran. Kedua, spiritualitas itu mengungkapkan segi-segi yang berkaitan dengan tubuh, terutama yang berhubungan dengan pengalaman wanita seperti melahirkan dan menstruasi, yang sama sekali tidak diperhatikan oleh agama. Segi-segi tubuh itu memberi hidup, bukan memalukan. Ketiga, spiritualitas itu berkaitan dengan alam non-manusia, dengan makna hubungan organis kita dengan alam raya; secara ekologis, visinya peka. Keempat, spiritualitas itu menekankan upacara-upacara yang lebih inklusif daripada hierarkis, gembira dan partisipatif daripada non-emosional dan dominatif. Spiritualitas feminis menaruh perhatian besar pada pembaruan pelayanan, liturgi, organisasi, dan jemaat Gereja. Pada akhirnya, spiritualitas feminis melihat hubungan yang intrinsik antara pertumbuhan pribadi dan keadilan sosial. Dari sudut pandang spiritualitas feminis, yang pribadi itu selalu bersifat politis.16 4. Mariologi Devosi atau kebaktian kepada Maria Bunda Yesus merupakan bagian penting dari spiritualitas Katolik sejak abad-abad awal. Sulitlah untuk membayangkan Gereja Katolik tanpa patung atau gambar Maria yang dipasang di tempat yang menyolok. Perkembangan ajaran Gereja tentang Maria merupakan masalah yang rumit, tetapi tidak ada masalah tentang tempat yang dipegang Maria dalam hati orang-orang Katolik. Maria telah lama menarik bagi orangorang Kristiani sebagai lambang keterbukaan manusia terhadap Yang Ilahi dan kekuatan Roh yang mengubah dalam hidup manusia. Oleh karena itu, Maria kerap dipandang sebagai contoh Gereja. Maria dalam Kitab Suci Simbolisme mungkin merupakan pendekatan yang paling tepat terhadap Maria dalam Kitab Suci. Dengan menggunakan penafsiran topologis (sebagai lawan dari literal) yang sedemikian populer pada Gereja awal, tradisi Kristiani telah melihat Maria digambarkan dalam kutipan seperti Kejadian 15:3, yang menyatakan permusuhan antara keturunan wanita, Hawa, dan ular, dan Yesaya 7:14 di mana almah, kata Hibrani yang berarti ”wanita muda” diterjemahkan ”anak dara” atau ”perawan” oleh Hieronimus dalam Vulgata: ”Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel” (Mat 1:23). Tidak banyak dikatakan tentang Maria dalam dokumen-dokumen Perjanjian Baru awal; Markus agaknya memasukkan Maria di antara para anggota keluarga Yesus yang menganggap-Nya tidak waras (Mrk 3:21). Akan tetapi, Maria memainkan peranan yang lebih penting dalam buku-buku yang kemudian, dan kisah kanak-kanak Matius dan Lukas dengan laporan mereka tentang Yesus yang dikandung oleh perawan, dan dalam Injil Yohanes. Banyak dari bahan ini melihat Maria sebagai lambang: sebagai murid yang sejati (Luk 8:21), sebagai pengantara (Yoh 3:2), dan ibu murid (Yoh 19:26-27). Maria dalam Tradisi Bapa-Bapa Gereja melanjutkan mengembangkan simbolisme kaya yang disarankan oleh gambaran ibu Yesus. Semua Bapa Gereja mengajarkan keperawanan Maria. Yustinus martir (meninggal tahun 165), Ireneus (meninggal tahun 202), dan Tertulianus (meninggal tahun 221) berpangkal pada pengertian St. Paulus tentang Yesus sebagai Adam Baru, mengembangkan gagasan Maria sebagai Hawa baru. Ireneus, yang menekankan peran aktif Maria dalam karya penebusan melalui ketaatannya, mengaitkan Maria dengan Gereja, seperti dilakukan oleh Tertulianus, Hipolitus, Ambrosius, dan Agustinus. Gambaran Ambrosius tentang Maria sebagai contoh Gereja diteguhkan oleh Konsili Vatikan II. Salah satu gelar Maria yang paling penting adalah Theotokos, ”Bunda Allah” yang secara harafiah berarti ”yang melahirkan Allah”, yang sedemikian dihormati di Gereja Timur. Gelar itu agaknya digunakan mulai tahun 220 oleh Hipolitus dari Roma dan kemudian menjadi populer dalam perlawanan melawan kaum Arian pada abad IV karena makna kristologis yang sedemikian jelas. Meski gelar itu ditolak oleh kaum Nestorian, namun diterima oleh Gereja universal sesudah rumusan Efesus (431) dan Kalsedon (451). Bersamaan dengan pengembangan teologi Maria adalah tempat penting yang diperolehnya dalam kesalehan dan devosi orang-orang Kristiani awal. Salah satu tandanya adalah kerapnya Maria ditampakkan dalam tulisan-tulisan apokrif. Meski bahan-bahan ini kebanyakan merupakan imaginasi saleh yang berusaha mengisi lubang-lubang dalam kisah Yesus dan Maria, namun merupakan bukti bahwa Maria disebut-sebut. Jauh lebih bermakna adalah fakta bahwa orang-orang Kristiani berdoa kepada Maria sebagai pengantara mulai abad ke-3. Tulisan tangan dari waktu itu memuat doa ini: ”Kami mengungsi di bawah naunganmu (sub tuum praesidium), hai Bunda Allah (theotokos) yang suci; janganlah memandang hina doa permohonan kami, tetapi bebaskanlah kami selalu dari segala bahaya, hai perawan yang mulia dan terpuji.” Bentuk doa yang lain yang tampak masih populer dewasa ini adalah doa Memorare (Ingatlah), doa yang berasal dari Abad Pertengahan: ”Ingatlah ya Perawan Maria yang penuh kasih karena tak pernah ada orang yang lari pada perlindunganmu ...”. Dari abad ke-5 dan seterusnya, gereja-gereja mulai diberi nama untuk menghormati Maria. Bagi orang-orang Katolik, Maria merupakan yang paling utama dalam kesatuan para kudus. Maria juga dirayakan dalam liturgi. Pesta Maria yang berdiri sendiri yang pertama berasal dari luar Yerusalem pada tahun 430. Pesta itu dirayakan pada tanggal 15 Agustus untuk menghormati Maria, Bunda Allah, tetapi dalam beberapa dasa warsa dibuat menjadi peringatan ”meninggalnya” Maria. Nama Maria disebut dalam Doa Ekaristi Romawi sejak abad ke-5. Pada abad ke-7 Pesta Penyampaian Kabar Gembira (25 Maret), wafat atau kenaikan ke surga (15 Agustus), kelahiran (8 September) dan Penyucian (2 Februari yang sekarang dikenal dengan pesta Persembahan Tuhan) ditaati, baik di Gereja Barat maupun Gereja Timur. Gereja pada umumnya mendorong devosi populer Maria, tetapi juga hati-hati membedakan dengan teliti apa yang merupakan kesalehan populer dan pengakuan iman, seperti dalam dogma Maria. Bahkan penampakan dan visiun seperti di Tepeyac, Lourdes, dan Fatima, meski dapat disetujui Gereja, namun pada dasarnya merupakan devosi pribadi. Devosi-devosi itu bukan ajaran resmi Gereja. Beberapa penampakan itu telah memainkan peranan penting dalam pengembangan Katolisisme populer. Kisah tentang penampakan Perawan Maria di Guadalupe pada tahun 1531 kepada petani Aztec Juan Diego di Tepeyac, dekat Kota Meksiko, amat berpengaruh dalam membuat rakyat Indian Meksiko mampu mengenal diri mereka dalam agama para penakluk mereka. Dalam gambar yang terkenal, masih dihormati oleh orang Meksiko dan Amerika Meksiko, Maria tampak sebagai mestiza, wanita berdarah campuran Spanyol dan Indian, dan tampaknya ia hamil. Penampakan kepada Bernadette Soebirous, gadis muda Prancis, pada tahun 1855 di Lourdes mendorong pendirian gereja dan pembangunan tempat ziarah yang telah menjadi tempat rahmat dan penyembuhan bagi jutaan orang. Ajaran tentang Maria Devosi Katolik terhadap Maria timbul karena saling mempengaruhinya antara kepentingan dan imajinasi doa dan perayaan liturgis, kesalehan populer dan refleksi teologis. Proses yang panjang menggambarkan prinsip bahwa doa dan liturgi membantu dalam pembentukan iman (lex orandi, lex credendi). Gereja telah mengajarkan keperawanan kekal Maria sejak abad ke-4. Konsili Trente meneguhkan ketidakberdosaan Maria (DS 91). Dua ajaran yang paling baru adalah dogma Maria dikandung tanpa dosa asal, yang dengan meriah dirumuskan oleh Paus Pius IX pada tahun 1854, dan rumusan agung Paus Pius XII tentang pengangkatan ke surga pada tahun 1951. Meski kedua dogma itu tidak dapat ”dibuktikan” dari Kitab Suci, masingmasing dogma itu mempunyai sejarah panjang dalam tradisi dan masing-masing dinyatakan hanya sesudah proses pertimbangan atas iman Gereja melalui polling (jajak pendapat) pada para uskup. Dalam menyatakan bahwa Maria dikandung ”bersih dari segala noda dosa asal”, dekrit Paus Pius IX Ineffabilis Deus mengutip teks-teks seperti salam malaikat Gabriel kepada Maria ”penuh rahmat” (Luk 1:28) dan seru Elisabet ”Terpujilah engkau di antara wanita” (Luk 1:42). Agaknya ajaran itu berasal dari tradisi liturgi Kristianitas Timur, yang mulai merayakan terkandungnya Maria sekitar akhir abad ke-7. Pesta itu sampai di Eropa pada abad ke-9 dan ke10, yang sempat menimbulkan kontroversi besar atas ajaran itu. Menarik untuk dicatat bahwa teolog-teolog seperti Anselmus, Bernardus, Albertus, Aquinas, dan Bonaventura – semua itu adalah orang kudus Gereja – melawan ajaran itu karena tidak dapat memadukanya dengan gagasan bahwa semua manusia diselamatkan melalui Kristus. Dilema itu dipecahkan oleh Duns Scotus yang menyatakan bahwa Kristus dapat menyelamatkan umat manusia dengan mempertahankan mereka dari dosa maupun dengan mengambil dosa dari mereka yang telah terkena. Dogma terkandung tanpa dosa asal tidak menyangkal bahwa Maria diselamatkan oleh Kristus; apa yang diteguhkan adalah bahwa karena Maria ditakdirkan menjadi ibu penebus, ia dipersatukan dengan Allah dengan cara yang amat mesra sejak awal hidupnya. Tradisi tentang pengangkatan Maria ke surga sudah lebih tua. Pengangkatan Maria ke surga sudah dirayakan oleh Gereja sekurang-kurangnya pada akhir abad ke-6. Dogma itu menyatakan bahwa dari saat kematiannya, Maria secara penuh ikut dalam kebangkitan Kristus – yaitu bahwa Maria masuk ke surga dengan kemanusiaannya secara penuh, ”jiwa dan badan”. Dogma itu merupakan peneguhan yang penting atas keikutsertaan kita dalam kebangkitan Kristus, bahkan jika Gereja belum secara definitif menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan kapan kebangkitan dari mati terjadi pada kita. Beberapa teolog dewasa ini menyatakan bahwa apa yang ditegaskan Gereja tentang masuknya Maria ke dalam kemuliaan terjadi dengan cara yang sama bagi semua orang benar pada saat kematian mereka.17 Beberapa orang mempunyai harapan bahwa Konsili Vatikan II akan mengeluarkan dokumen yang terpisah tentang Maria, dengan menyatakannya menjadi Mediatrix (Perantara) segala rahmat. Yang lain menyatakan bahwa tidak perlulah mengeluarkan dokumen terpisah karena hanya akan merusak gerakan ekumenis. Sesudah perdebatan yang cukup, para Bapa Konsili memilih untuk mengeluarkan ajaran Konsili tentang Maria dimasukkan sebagai bab terpisah dalam Konstitusi Dogmatik tentang Gereja. Meski bab itu hanya menyinggung secara singkat tentang hubungan Maria dengan misteri Kristus, namun memberi tekanan lebih besar pada Maria sebagai model Gereja dengan menekankan iman, kasih dan kesatuannya dengan Kristus (LG 63). Maria dan Ekumenisme Meski agama Kristen Ortodoks mempunyai devosi besar terhadap Bunda Allah, devosi Katolik terhadap Maria kerap disalahmengerti oleh orang-orang Kristen Protestan. Mereka kadang-kadang menuduh orang-orang Katolik menyembah Maria. Maria mempunyai tempat terhormat dalam tradisi Katolik, baik dalam hidup devosional maupun dalam warisan ajaran. Akan tetapi, tradisi telah selalu dengan teliti membedakan antara pemujaan (latria), yang hanya ditujukan kepada Allah dan penghormatan (dulia bagi orang-orang kudus dan hyperdulia bagi Maria). Gereja juga telah dengan teliti mempertahankan pembedaan antara kesalehan populer dan pengakuan iman secara publik, sebagaimana kita lihat di atas. Orang Katolik amat menghargai penghormatan mereka kepada Maria, tetapi tidak berusaha memaksakannya pada orang Protestan. Bersamaan dengan itu, orang Kristen Protestan hendaknya tidak melihat penghormatan orang Katolik terhadap Maria sebagai hal yang berlawanan dengan Injil atau hambatan untuk kesatuan umat Kristiani. Dogma-dogma tentang Maria hendaknya dimengerti sebagai contoh yang sah tentang perkembangan ajaran dalam tradisi Katolik. Dewasa ini baik orang Protestan maupun orang Katolik sampai pada penghargaan baru atas kekuatan Maria sebagai lambang. Dulu devosi Katolik terhadap Maria merupakan halangan besar bagi orang Protestan yang sekarang menemukan Maria yang mengucapkan Magnificat (Jiwaku Mengagungkan).18 Meski gambaran Maria dapat ditafsirkan secara stereotipe dengan menempatkan wanita dalam peran tersubordinasi, namun tradisi Maria (dan wanita pada umumnya) dapat menjadi sumber yang kaya tentang penggambaran Ilahi.19 5. Kesimpulan Godaan untuk mengecilkan Kristianitas menjadi sistem etika atau hanya sebagai pelaksanaan peraturan emas, merupakan pemiskinan yang besar. Yesus berkata bahwa Ia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan (Yoh 10:10). Hidup yang diberikan kepada kita bukan hanya hidup kekal tetapi ikut ambil bagian dalam hidup Allah sekarang ini. ”Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satusatunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kauutus” (Yoh 17:3). Doa, entah lisan, mental atau kontemplatif, menyatukan kita dengan Allah sehingga kita dapat mengalami sesuatu dari kelimpahan hidup yang diberikan Kristus kepada kita. Doa liturgis merupakan doa resmi Gereja. Disiplin rohani membantu kita untuk menyiapkan tanah hati kita, untuk menyiangi dan menyiraminya dengan air, supaya hidup Ilahi dalam Kristus dapat berakar kuat di dalam diri kita. Spiritualitas mengembangkan hidup itu dan memberinya ungkapan dalam hidup kita sendiri. Spiritualitas yang sejati merupakan hal yang mengembangkan kedewasaan psikologis dan spiritual dan membuka diri kita terhadap orang lain. Gereja telah diperkaya oleh jumlah besar orang-orang mistik dan guru-guru rohani. Keanekaragaman yang kaya dari spiritualitas dalam tradisi Katolik – monastik, apostolik, keadilan sosial, karismatik, matrimonial (perkawinan), awam, feminis – menampakkan keseluruhan Katolik yang sejati. Pada waktu yang sama, pada umumnya ada satu segi eklesial pada spiritualitas Katolik. Spiritualitas Katolik bersifat komunal (melibatkan banyak orang) dan liturgis. Spiritualitas Katolik meliputi tradisi kuno untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Sebagai lambang, Maria menunjukkan kekuasaan Allah maupun kemungkinan manusia. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Thomas Merton, The Seven Storey Mountain (New York: Harcourt, Brace, 1948) 204. Henri Nouwen, With Open Hands (Notre Dame: Ave Maria, 1972) 2. Thomas Merton, New Seeds of Contemplation (New York: New Directions, 1962) 227. Lihat M. Basil Pennington, Centering Prayer: Renewing an Ancient Christian Prayer Form (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1980); Thomas Keating, Open Mind, Open Heart: The Contemplative dimension of the Gospel (Rockport, Mass: Element, 1992). William Reiser, Looking for a God to Pray To: Christian Spirituality in Transition (New York: Paulist, 1994) 2. Lihat Michael Downey, ed., The New Dictionary of Catholic Spirituality (Collegeville: The Liturgical Press, 1993). Thomas Merton, Faith and Violence: Christian Teaching and Christian Practice (Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1968) 14-29. Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968) 84. Philip Sheldrake, Spirituality and History (New York: Crossroad, 1992) 107. St. Francis de Sales, The Introduction to the Devout Life, trans. and ed. John K. Ryan (New York: Harper & Brothers, 1950) 6. Andrew M. Greeley, Sex: The Catholic Experience (Chicago: Thomas More, 1994). Lihat Keneth R. Overberg, Aids, Ethics, and Religion (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1994) 3. Jon Sobrino, Spirituality of Liberation: Toward Political Holiness (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1988). Jon Sobrino, A Question of Conscience: The Murder of The Jesuit Priests in El Salvador, dir. Ilan Ziv, First Run Features, 1990, videocassette. Rosemary Chinnici, Can Women Re-Image The Church? (New York: Paulist, 1992) 11-36. Sandra M. Schneiders, ”Feminist Spirituality,” The New Dictionary of Catholic Spirituality, ed. Michael Downey (Collegeville: The Liturgical Press, 1993) 400. Misalnya, Karl Rahner, Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity (New York: Seabury, 1978) 388. Robert McAfee Brown, ”Protestants and the Marian Year,” Christian Century 104 (June 3, 1987) 520-521. Elizabeth Johnson, ”Mary and Female Face of God,” Theological Studies 50 (1989) 525-526. X Kepenuhan Harapan Kristiani Tujuan akhir kita, adalah hidup abadi kepenuhan hidup bersama Allah, yang diwahyukan dan dijanjikan oleh Yesus dalam kemenangan atas dosa dan maut. Inilah arti terakhir keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Menurut Yohanes Paulus II, ”Menyelamatkan berarti membebaskan dari kejahatan yang mendasar”.1 Tradisi Kristiani menggunakan sejumlah lambang, gambaran, dan konsep untuk mengungkapkan kepenuhan harapan Kristiani, yang sebetulnya melampaui kemampuan kita untuk membayangkan. Kebangkitan badan, kedatangan Kristus yang kedua, pengadilan pribadi pada saat ajal, pengadilan umum pada akhir zaman, imortalitas (tidak dapat matinya) jiwa, surga, visiun yang membahagiakan, hidup abadi – itu semua merupakan konsep-konsep eskatologis (eschatos, bahasa Yunani, berarti ”terakhir” atau ”akhir”) yang merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran teologis dari tujuan akhir kita, tujuan yang berakar pada kebangkitan Kristus. Itu semua merupakan istilah-istilah keselamatan yang menyatakan tentang masa depan yang disediakan Allah bagi kita. Akan tetapi, keselamatan tidak selalu merupakan konsep eskatologis. 1. Keselamatan dan Eskatologi Keselamatan dalam Kitab Suci Yahudi Kata Hibrani untuk ”keselamatan” dan kata-kata bentukannya berasal dari akar kata YS, yang mengandung arti ruang, keamanan, dan kebebasan dari pembatasan. Dalam tradisi Israel kuno, pengertian keselamatan berkaitan dengan campur tangan Allah demi umat Israel. Meskipun Allah ”menyelamatkan” umat-Nya dengan banyak cara, namun paradigma keselamatan bagi Israel kuno adalah senantiasa peristiwa besar Keluaran (Exodus), pembebasan Allah atas umat dari perbudakan Mesir (Kel 15:2; Mzm 78:22; Yes 63:9). Selama jangka waktu yang panjang yang tercermin dalam Alkitab tidak terdapat kepercayaan terhadap kehidupan di balik kubur, atau kebangkitan kembali orang mati memainkan peran amat besar dalam Kitab Suci Yahudi. Kita dapat tahu banyak tentang bagaimana kuatnya pengalaman orang Yahudi tentang Allah dengan membaca mazmur; mereka hidup dengan kegembiraan karena hidup dalam hubungan perjanjian dengan Allah, karena merasakan kehadiran Allah, karena memuji nama Allah dalam jemaat – dan semua ini tanpa gagasan apa pun tentang hidup sesudah kematian. Hal ini mungkin sulit bagi banyak orang di antara kita untuk mengerti, karena kita merupakan produk hampir 2000 tahun sejarah Kristianitas; karena kebangkitan Yesus, kita menerima begitu saja kebangkitan orang mati. Cara berpikir kita juga telah amat dipengaruhi oleh antropologi dualistik yang diwarisi dari filsafat Yunani. Orang Yunani berpikir tentang pribadi sebagai gabungan jiwa dan badan atau seperti dikatakan oleh para penganut Plato, jiwa ”terpenjara” dalam tubuh. Dalam tradisi Yahudi, pribadi tidak dipahami secara dualistik. Manusia selalu merupakan tubuh yang hidup. Bila orang meninggal, ”roh” atau prinsip hidup dan kegiatan hilang (ruah) dan diri (nepes) turun ke Sheol, dunia bawah atau tempat tinggalnya orang mati. Akan tetapi, Sheol bukan merupakan tempat untuk jenis hidup yang lain. Sheol adalah tempat kegelapan, ulat, debu, lubang (Ayb 17:13-16). Kadang-kadang kata ”sheol” digunakan begitu saja sebagai sinonim dengan kematian atau kubur. Keadaan orang mati di Sheol sama sekali berlawanan dengan keadaan dalam kehidupan. Keadaan itu adalah keadaan pasivitas penuh; di Sheol tidak ada pekerjaan, pemikiran, pengetahuan dan kebijaksanaan (Pkh 9:10). Yang paling buruk, di Sheol tidak ada lagi hubungan apa pun dengan Yahwe karena orang mati tidak dapat mengingat atau memuji Yahwe (Mzm 6:6; 88:12). Baru pada sastra antar perjanjian, yang ditulis pada zaman yang dekat dengan zaman Yesuslah Sheol tampak sebagai tempat khusus bagi orang jahat. Kebangkitan Orang Mati Selama dan sesudah pembuangan di Babilon pada abad ke-6, Yudaisme mulai bergulat secara serius dengan masalah-masalah kesetiaan Yahwe dan keselamatan dalam konteks harapan-harapan yang hancur, kejahatan dan kematian. Visiun Yehezkiel dalam bab 37:1-14 menunjukkan bahwa Yahwe menghidupkan kembali tulang-tulang kering bangsa dan membawa padanya kehidupan baru. Kisah Ayub, orang benar yang menderita, mengangkat masalah misteri kejahatan. Bukti jelas pertama tentang harapan orang Yahudi untuk kebangkitan orang mati tampak dalam buku Daniel yang ditulis pada zaman pengejaran Antiokhus IV Epifanes (167-164 SM), 150 tahun lebih sedikit sebelum zaman Yesus. Antiokhus telah melarang orang Yahudi untuk menjalani agama mereka. Mereka yang tidak mentaati dibunuh. Kesetiaan mereka pada Hukum tidak menyelamatkan mereka dari siksaan dan pembunuhan (bdk. 2Mak 6-7). Dengan demikian, kemartiran mereka menimbulkan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan Yahwe dengan cara baru. Di mana Allah mereka? Pengarang buku Daniel meyakinkan rakyat bahwa campur tangan Allah sudah dekat. Bagi mereka yang mati demi iman, pengarang mengungkapkan harapan bahwa pengadilan apokaliptik yang akan datang akan melihat orang mati dibangkitkan ke dalam hidup abadi (Dan 12:1-3). Dalam 2 Makabe (2:7; 14:46), buku lain dari zaman yang sama, kepercayaan akan kebangkitan orang mati jelas ada. Gagasan yang sama ada pada buku-buku apokaliptik non-kanonis (Enoch 51; Barukh 50; 4 Ezra 7.29). Ini berarti bahwa dalam beberapa ungkapan tradisi Yahudi dalam abad sebelum Yesus, keselamatan telah menjadi konsep eskatologis. Pada zaman Yesus, orang-orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati, sedang orang Saduki tidak (Luk 20:27-28). Dengan demikian, gagasan tentang kebangkitan orang mati merupakan perkembangan yang kemudian dalam tradisi Yahudi. Akan tetapi, konsep Yahudi tentang kebangkitan orang mati merupakan pengertian apokaliptik. Kepercayaan itu berkaitan dengan kebangkitan semua orang mati, yang akan terjadi pada akhir zaman. Karena dipengaruhi oleh pemikiran apokaliptik Yahudi itu, banyak orang Kristiani awal percaya bahwa kebangkitan Yesus dan orang mati berarti bahwa akhir dunia sudah dekat (1Kor 7:29). Kebangkitan Yesus Kematian Yesus merupakan pengalaman yang menghancurkan bagi murid-murid-Nya. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan arah, kacau, dan takut akan keselamatan mereka. Salah satu unsur pengalaman mereka ditangkap oleh Lukas dalam kisahnya tentang dua murid dalam perjalanan ke Emaus. Sementara kedua murid itu sedang berjalan, mereka memberitahukan kepada seorang asing yang bergabung dengan mereka tentang kesedihan mereka karena kematian Yesus: ”Padahal dahulu kami mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel” (Luk 24:21). Kedua murid itu lamban untuk mengenal kembali bahwa orang asing itu adalah Yesus yang telah bangkit dari mati, tema yang jika dibaca dengan teliti ditemukan juga dalam kisah-kisah penampakan Paskah yang lain. Namun dua murid itu seperti halnya Petrus, Maria Magdalena dan orang-orang lain yang telah mengikuti Yesus, yakin oleh pengalaman Paskah mereka tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah telah membebaskan Yesus dari dunia orang mati dan memberi kepada-Nya hidup baru. Pengalaman Paskah kedua murid atas kehadiran Dia yang sudah disalibkan di antara mereka dengan cara baru menantang kemampuan pengungkapan mereka. Hidup baru Yesus merupakan misteri yang tidak mudah ditangkap dalam bahasa. Kebangkitan itu sama sekali berbeda dari pembangkitan Lazarus. Yesus yang sudah bangkit sekarang hidup dalam sisi lain dari waktu dan ruang, dalam kehadiran Allah. Menurut St. Paulus: ”Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah” (Rm 6:10). Bahasa kebangkitan menonjol dalam Perjanjian Baru, meski mempunyai cara-cara lain untuk mengungkapkan apa yang masih misteri dari hidup baru Yesus dengan Allah. Tradisi awal berbicara tentang Allah ”yang melepaskan Dia dari sengsara maut karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu” (Kis 2:24). Beberapa tradisi menggunakan kata ”peninggian” daripada ”kebangkitan” (Fil 2:9; Luk 24:26; Ef 4:8; Kis 5:6). Berlawanan dengan kisah-kisah yang amat kemudian tentang pertobatannya yang tampak dalam Kisah Para Rasul, St. Paulus sendiri tidak banyak memberi rincian atas pengalaman Paskahnya. Ia hanya menyatakan dalam suratnya kepada umat Galatia bahwa Allah ”berkenan menyatakan AnakNya di dalam aku” (Gal 1:16). Ada cara-cara lain untuk mengungkapkan kepercayaan bahwa Yesus telah dipertahankan dan hidup bersama Allah. Akan tetapi, tidak mengherankan bahwa bahasa kebangkitan menonjol karena gagasan tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman sudah merupakan bagian harapan eskatologis Yahudi. 2. Eskatologi Kristiani Kebangkitan Tubuh Kebangkitan tubuh merupakan konsep yang mendasari eskatologi Kristiani daripada imortalitas jiwa. St. Paulus mengandaikan kebangkitan orang mati dalam surat pertamanya kepada umat Korintus; sesungguhnya dua kali ia berani menyatakan dari kebangkitan orang mati ke kebangkitan Yesus (1Kor 15:13; 16) untuk meyakinkan orangorang Korintus akan harapan mereka untuk ikut serta dalam kebangkitan. Dengan kata lain, kebangkitan kita dan kebangkitan Yesus tidak terpisahkan. St. Paulus menggambarkan Yesus yang telah bangkit sebagai ”yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal” (1Kor 15:20) dan sebagai ”Adam yang terakhir” (1Kor 15:45). Akan tetapi ketika sampai pada titik usaha untuk menerangkan kepada mereka apa tubuh yang bangkit itu, bahasa St. Paulus mulai macet. Ia berbicara tentang apa yang dibangunkan sebagai ”yang tidak dapat binasa” (1Kor 15:42), tentang ”tubuh rohani” (soma pneumatikon) sebagai lawan dari tubuh alamiah (1Kor 15:14), tentang tubuh yang mengenakan ”yang tidak dapat binasa” (1Kor 15:53). Tetapi apa tubuh rohani itu? Ungkapan itu sendiri kedengarannya bertentangan. Apa yang ditegaskan oleh St. Paulus pada dasarnya adalah pengalaman pribadi, karena kebangkitan badan berarti bahwa kita masuk ke dalam hidup bersama Allah dalam kepenuhan kemanusiaan pribadi, yang bagi cara berpikir Yahudi yang tidak dualistik tidak terpisahkan dari keberadaan badani. Dengan demikian, kebangkitan tubuh berarti satu jenis keberadaan yang melampaui batas-batas waktu dan ruang tetapi bersamaan dengan itu jauh lebih banyak daripada tetap hidupnya jiwa kita. St. Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus ”yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia” (Fil 3:21). Sesungguhnya, bagi St. Paulus ”makhluk sendiri” ditujukan untuk ikut mengambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus; makhluk itu ”sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah” (Rm 8:21). Rahmat Allah yang mengubah, bekerja tidak hanya dalam manusia tetapi juga dalam alam semesta. Beberapa teolog zaman sekarang membuat spekulasi bahwa kebangkitan orang benar terjadi pada saat meninggalnya.2 Pendapat ini mempunyai keuntungan untuk memecahkan salah satu pertanyaan yang belum terjawab dari pengertian yang lebih tradisional mengenai eskatologi Kristiani yang melihat jiwa ”memasuki surga” sesudah pengadilan pribadi tetapi harus menanti sampai kebangkitan orang mati pada akhir zaman untuk dipersatukan dengan badannya. Pengertian harfiah tentang teks-teks Kitab Suci seperti Yoh 6:54 dan Why 20:12-13, merupakan cara sementara untuk merumuskan eskaton, yang dari definisinya mengatasi ruang dan waktu. Tambahan pula, pengertian itu membiarkan tidak dijelaskan bagaimana identitas dan kesadaran pribadi dapat dipertahankan dalam jiwa yang dipisahkan dari tubuh yang merupakan sarana untuk mengetahui dan sadar diri. Seperti dikatakan oleh Rahner: ”Keabadian bukanlah cara waktu murni yang memuat perhitungannya amat lama, tetapi cara roh dan kebebasan yang telah diaktualisasikan pada waktu, dan oleh karena itu hanya dapat ditangkap dari pengertian tentang roh dan kebebasan yang benar.”3 Kebangkitan badan tetap merupakan pernyataan teologis yang paling mendasar tentang harapan Kristiani. Kebangkitan badan merupakan rumusan iman yang diakui dalam syahadat para Rasul, Nicea-Konstantinopel, dan Athanasian. Kebangkitan badan merupakan lambang yang amat kuat. Akan tetapi, ada lambang-lambang lain yang mengungkapkan harapan eskatologis Kristiani, dan beberapa di antaranya telah ditafsir secara terlalu harfiah. Surga Lambang surga merupakan ungkapan eskatologi Kristiani yang paling populer. Dalam Perjanjian Lama, surga berarti daerah di atas bumi dan tempat Allah bersemayam. Dalam Perjanjian Baru surga menjadi tempat tinggal maupun ganjaran orang Kristiani (Mat 5:12; 1Tes 4:16-17). Sesungguhnya, surga bukanlah tempat. Berada di surga berarti sepenuhnya berada di hadirat Allah. Surga tidak hanya ada tetapi menjadi ada ”bila makhluk ciptaan yang pertama ada secara eskatologis dan akhirnya diambil oleh Allah. Surga dibentuk dalam kebangkitan dan peninggian Kristus.”4 Cara-cara Alkitab lain yang mengungkapkan tujuan akhir orang yang benar meliputi istilah ”hidup kekal” (Rm 2:7; 6:23; 1Tim 1:16; Yoh 3:15,36; 6:68; 12:50; 20:31); ungkapan St. Paulus ”mewarisi Kerajaan Allah” (1Kor 6:9; 15:50; Gal 5:21; Ef 5:5); dan gagasannya yang indah bahwa kita telah melihat kemuliaan Allah yang dicerminkan pada wajah Kristus (2Kor 4:6) dan pada suatu hari akan melihat wajah Allah secara langsung (1Kor 13:12). Gereja yang kemudian mengungkapkan gagasan melihat wajah Allah berhadap-hadapan ini dengan istilah ”visio beatifica”, penglihatan yang membahagiakan. Kedatangan yang Kedua Kedatangan Kristus yang kedua, kadang-kadang disebut parousia (kata Yunani yang berarti ”kehadiran” atau ”kedatangan”) merupakan konsep yang telah kerap ditafsirkan secara terlalu harfiah. Konsep itu mempunyai sejarah yang panjang dan merupakan campuran beberapa gambaran alkitabiah yang berbeda-beda. Akarnya ada dalam gambaran Anak Manusia dalam Daniel 7:13 yang digambarkan sebagai ”datang dengan awan-awan dari langit”. Dalam kutipan ini, Anak Manusia berperan sebagai lambang bagi umat Israel. Akan tetapi, dalam sastra apokaliptik yang kemudian, Anak Manusia tampil sebagai pelaku pengadilan Allah, yang datang dengan awan-awan dari langit pada akhir dunia. Yesus kerap kali berbicara tentang Anak Manusia dalam konteks pengadilan terakhir (Mat 24:30; 25:31; Mrk 8:38; Luk 12:8). Akan tetapi, jemaat Kristiani awallah yang mulai mewartakan kedatangan dengan segera Kristus yang sudah bangkit dalam pengadilan. Dari sinilah gambaran tentang kedatangan yang kedua berkembang. Dalam perkembangan Kristologis yang amat awal, terbentuk dua gabungan gagasan. Pertama, kebangkitan Kristus ditafsirkan berdasarkan latar belakang harapan apokaliptik atas kebangkitan umum orang yang sudah meninggal pada akhir dunia, yang waktu itu populer di kalangan masyarakat Yahudi Palestina. Jika Yesus sudah dibangkitkan dari mati, maka akhir dunia pastilah sudah dekat. Ini membawa ke harapan apokaliptik sedemikian jelas pada tahap-tahap awal tradisi (bdk. Luk 12:8), termasuk St. Paulus (1Kor 1:8; 7:29). Paulus menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang turun dari surga dengan seru penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah (1Tes 4:16). Kedua, Yesus yang sudah bangkit disamakan dengan Anak Manusia surgawi, pelaku pengadilan Allah dan pembawa keselamatan Allah. Para penginjil Sinoptik kerap kali menampilkan Kristus yang menyebut diri sebagai Anak Allah. Orang-orang Kristiani fundamentalis telah menggunakan teks seperti 1Tes 4:17 dan Why 3:10 untuk mengajarkan kedatangan Yesus untuk mengadili secara amat harfiah seperti lukisan Michelangelo, Pengadilan Terakhir, yang terkenal di Kapel Sistin. Beberapa orang berbicara tentang ”pengambilan”, pada waktu orang-orang Kristiani yang setia yang masih hidup di dunia diambil untuk menjumpai Tuhan dengan semua orang kudus, meski ada ketidaksepakatan tentang apakah peristiwa itu akan terjadi sebelum atau sesudah ”huru-hara besar” yang akan membawa pengadilan Allah atas orang-orang jahat. Akan tetapi, itu bukan satu-satunya penafsiran yang mungkin. Iman Katolik tidak mewajibkan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan datang secara harfiah pada suatu pagi atau pada suatu siang dengan awan-awan dari langit. Ada banyak cara untuk membayangkan akhir dunia, beberapa di antaranya, sayangnya, seluruhnya kita buat sendiri. Apa yang jelas adalah bahwa masing-masing di antara kita pada suatu hari harus menghadapi pengadilan Allah tetapi bagaimana atau kapan atau dalam keadaan apa, kita tidak tahu. Sekurang-kurangnya kita dapat mengatakan bahwa bagi orang yang sudah meninggal, parousia sudah terjadi. Pengadilan Terakhir Bagaimana nasib orang-orang jahat? Gagasan bahwa pada suatu hari orang-orang jahat harus menghadapi pengadilan Allah dan menanggung akibat atas dosa-dosa mereka ditemukan dalam Kitab Suci Yahudi maupun Kristiani. Eskatologi Kristiani populer menggunakan gambaran neraka (”tempat orang mati”) untuk menggambarkan dalam istilahistilah yang amat imajinatif nasib akhir orang-orang jahat. Di belakang gambaran ini dapat ditemukan pengertian Alkitab tentang pengadilan dan gambaran Gehenna. Pengertian Perjanjian Lama tentang pengadilan Allah (mispat) mungkin berasal dari pengadilan di dunia yang dilakukan oleh kepala suku dan raja-raja. Pengadilan Allah ditunggutunggu dengan penuh keinginan besar atau ditakuti, tergantung pada keadaan moral orang. Bagi orang benar, pengadilan Allah berarti pembelaan (Ul 10:18; Mzm 7:7; 9:5; 76:10; Yes 11:4), tetapi bagi orang-orang jahat pengadilan Allah mendatangkan hukuman dan siksaan (Yeh 5:7; 7:3). Gagasan tentang hari pengadilan, Hari Yahwe, muncul pertama kali pada nabi Amos, tetapi pasti berasal dari periode yang lebih dulu, karena Amos tidak menjelaskannya. Amos yang pesimis mengaitkan Hari Yahwe dengan pengadilan Allah atas Israel. Hari Yahwe akan menjadi hari kegelapan dan kekelaman (Am 5:18-20; 8:9). Pada nabi-nabi selanjutnya, Hari Yahwe berarti hari di masa depan pada waktu Allah menampakkan keadilan Ilahi, kerap dengan memperagakan kekuasaan kosmis. Yesaya memperluas konsep itu menjadi berlaku bagi bangsa-bangsa lain tanpa mengesampingkan Israel. Hari Yahwe adalah hari pada waktu Yahwe menurunkan orang-orang congkak dan angkuh (Yes 2:12), hari kebengisan dan murka pada waktu matahari dan bintang-bintang menjadi gelap, bulan tidak memancarkan sinarnya, bumi menjadi sunyi sepi, dan orang-orang berdosa dimusnahkan (Yes 13:9-11). Pada beberapa nabi yang kemudian, Hari Yahwe dimengerti secara eskatologis. Yoel (3:12-14) melihatnya sebagai hari yang membawa pengadilan Allah kepada segala bangsa. Zefanya (1:15) menggambarkannya dalam istilah-istilah kegemasan, kesusahan, dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan kegelapan dan kesuraman yang bergema dalam kidung Abad Pertengahan, Dies Irae, Gambaran tentang neraka berasal dari kata Aram Gehenna, bentuk singkatan dari ”lembah anak Hinnon”. Terletak di daerah pinggiran Yerusalem, lembah itu telah mendapat nama buruk karena pernah menjadi tempat keramat, tempat dipersembahkan korban manusia (2Raj 23:10). Yeremia mengutuknya (Yer 7:31-33). Meski Yesaya tidak menyebutnya, ia menyindirnya sebagai tempat mereka yang memberontak kepada Yahwe akan dijebloskan dan ia memberikan gambaran-gambaran api dan siksaan ”di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam” (Yes 66:24). Dalam tulisan-tulisan di luar Kitab Suci Yahudi, penggambaran itu digunakan lagi untuk melukiskan Gehenna sebagai tempat orang-orang jahat yang dihukum sesudah meninggal. Dalam Perjanjian Baru Gehenna digambarkan sebagai tempat api (Mat 5:22; 18:9) yang tak terpadamkan (Mrk 9:43), sebagai lubang ke mana orang-orang jahat dilemparkan (Mat 5:29; Mrk 9:45), ”di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam” (Mrk 9:48). Dari sinilah gambaran populer tentang neraka muncul. Bagaimana tentang setan? Meski kepercayaan pada roh-roh jahat tersebar luas di dunia kuno dan masuk ke dalam tradisi Yahudi melalui Mesopotamia, namun kepercayaan itu tidak memegang peran penting dalam Kitab Suci Yahudi awal. Tokoh setan, yang arti namanya adalah ”penuduh”, berperan sebagai lawan atau tokoh yang menguji keutamaan manusia pada sastra yang lebih awal (bdk. Ayb 1:6; 2:1). Dalam Septuaginta yang merupakan terjemahan Kitab Suci Yahudi, kata ”Setan” diterjemahkan menjadi diabolos (dari kata itu terbentuk kata ”devil” dalam bahasa Inggris), yang juga berarti ”penuduh”. Hanya baru kelak kemudian hari, dalam sastra intertestamental, demonologi menjadi jauh lebih penting dan setan dipandang sebagai roh jahat yang berkuasa untuk menghancurkan umat manusia. Dalam tulisan-tulisan Yahudi apokrif, setan digambarkan sebagai malaikat yang jatuh dan setan diusir dari surga karena menolak menghormati manusia sebagai gambar Allah. Perjanjian Baru menerima begitu saja kekuasaan dan sikap bermusuhan setan terhadap Kerajaan Allah (Mat 13:19; Luk 22:3; Yoh 13:2). Pengusiran setan yang dilakukan Yesus digambarkan sebagai ”pengusiran” (ekballein) roh-roh jahat (Mat 8:16; Luk 11:14) atau ”penyembuhan” (therapeuein) orang-orang dari setan-setan (Mrk 1:34; Luk 6:18; 8:2). Keberadaan setan dan roh-roh jahat diandaikan dalam kepercayaan Katolik tradisional, tetapi tidak jelas bahwa keberadaannya telah ditetapkan secara formal. Keberadaan setan telah ditunjukkan oleh magisterium, yaitu dalam konteks teologi penciptaan, dengan menegaskan bahwa setan dan roh-roh jahat diciptakan baik tetapi menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri (DS 800). Tidak semua penulis Perjanjian Baru menggambarkan nasib akhir orang-orang jahat berkaitan dengan neraka, dengan api dan setan-setan. Akan tetapi, gagasan bahwa pada suatu hari mereka harus menghadapi pengadilan Allah ditemukan di mana-mana. St. Paulus mengajarkan bahwa orang-orang berdosa tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Allah (1Kor 6:10; Gal 5:19-21) dan akan dihukum dengan kebinasaan kekal (Fil 3:19). Bagi Yohanes orang-orang berdosa sudah ada di bawah pengadilan Yesus (Yoh 3:18; 5:22-24; 12:31) dan akan dikeluarkan dari hidup abadi (Yoh 5:29; 8:24; 10:28). Apakah Allah mengenakan hukuman kekal atas pendosa-pendosa? Memang Perjanjian Baru berbicara tentang hukuman kekal sebagai hasil akhir orang-orang jahat (Mat 25:41; Luk 16:23; Why 20:10). Beberapa orang Kristiani dewasa ini menyatakan bahwa adanya sedemikian banyak kejahatan di dunia menuntut adanya neraka bagi mereka yang telah memilih hidup tanpa Allah, atau dalam istilah-istilah yang lebih alkitabiah, mereka yang berusaha menjadi allah mereka sendiri (Kej 3:5). Yang lain-lain mengungkapkan harapan bahwa pada akhirnya semua akan diselamatkan. Pentinglah kita berpikir lebih lanjut tentang masalah hukuman kekal ini. Secara teologis tidak banyak artinya berpikir tentang Allah yang menghukum orang jahat dengan siksaan kekal. Allah tidak menghukum, entah dalam hidup sekarang ini atau hidup di masa yang akan datang. Penderitaan dan pengasingan yang diakibatkan oleh dosa kita di dunia merupakan hukumannya sendiri. Allah adalah sekaligus Pencipta hidup kita dan Tujuan akhir kita, yang mengundang kita untuk bersatu, dalam hidup Ilahi. Akan tetapi, Allah selalu menghormati kebebasan kita. Tanggapan kita harus diberikan dengan bebas-merdeka. Jika kita menolak untuk menanggapi, itu merupakan pilihan kita. Allah tidak dapat memaksakan cinta dan kesatuan pada kita seperti halnya kita tidak dapat memaksa cinta dan kesatuan kita satu sama lain. Cinta yang tidak secara bebas diberikan bukanlah cinta. Menyingkirkan Allah dari hidup kita adalah dosa. Meninggal dalam keadaan dosa adalah telah menolak pemberian Allah untuk bersatu dalam hidup Ilahi. Inilah arti sebenarnya neraka, terlepas dari segala penggambaran yang seram-seram. Neraka merupakan pengasingan yang terakhir yang diakibatkan dosa. Neraka ada untuk selama-lamanya tanpa Allah yang menjadi Pencipta kita dan menjadi kerinduan hati kita. Neraka ada untuk selamanya menjadi seperti yang telah kita buat bagi diri sendiri. Pandangan yang melihat bahwa semua orang akan diselamatkan terlalu dangkal. Pandangan itu meremehkan peperangan nyata antara yang baik dan yang buruk, yang sedemikian jelas dalam sejarah umat manusia. Akan tetapi, surga dan neraka tidak dapat dipikirkan pada tingkat yang sama. Surga dan neraka merupakan penegasan iman yang berlawanan total. Tidak masuk akal untuk membayangkan orang benar hidup dalam kemuliaan, sedang orang jahat ”hidup bersebelahan dengan mereka” menderita siksaan neraka. Di sinilah letak sifat berlawanannya. Allah memang memberi kesatuan atau hidup abadi kepada orang-orang yang telah bersatu dengan misteri Ilahi dan solider dengan orang-orang lain selama hidup mereka di dunia. Ini merupakan ikatan yang tidak dapat dihancurkan oleh kematian. Akan tetapi, daripada melihat Allah yang menghukum orang jahat dengan hukuman kekal, lebih tepat melihat orang-orang yang telah menolak untuk solider dengan sesama mereka dan dengan demikian menolak kesatuan dengan Allah, tidak akan selamat sesudah kematian mereka. ”Maka tidak ada masa depan untuk kejahatan dan penindasan, sementara kebaikan masih mengenal masa depan melampaui batas-batas kematian, berkat Tangan Allah yang terbuka yang menerima kita. Allah tidak dapat mengambil tindakan balasan. Allah menyerahkan kejahatan pada logikanya sendiri yang terbatas”.5 Cara berpikir di atas menarik justru karena memperhatikan keadilan Allah dan kebebasan manusia secara sungguh-sungguh. Cara berpikir itu menghormati Allah dan manusia tanpa mengubah Allah yang berbelaskasihan dan hidup menjadi hakim yang suka menghukum yang membiarkan orang-orang jahat ada dalam hukuman selama-lamanya. Api Pencucian Ajaran tentang Api Pencucian merupakan dasar bagi orang Katolik untuk berdoa bagi orang yang sudah meninggal (bdk. 2Mak 12:43-46). Ajaran itu berkaitan dengan pembersihan yang harus dijalani untuk ”hukuman sementara” karena dosa yang sudah diampuni, atau dengan kata lain, untuk meniadakan akibat-akibat dosa. Gagasan dasarnya adalah pembersihan sebelum menghadap hadirat Allah. Ada banyak bukti bahwa orang-orang Kristiani berdoa bagi orangorang beriman yang sudah meninggal sejak abad-abad awal. Pada Abad Pertengahan, gagasan Barat tentang api pencucian menjadi lebih yuridis, dengan menekankan kebutuhan untuk pemulihan dosa. Gereja Timur terus melanjutkan penekanan pada pembersihan dan pertumbuhan rohani. Pengertian tentang api pencucian sebagai tempat agaknya berawal pada abad ke-12. Ajaran tentang api pencucian diteguhkan oleh Konsili Lyon II (1274) dan oleh Konsili Florence (1439). Ajaran itu diteguhkan kembali oleh Konsili Trente melawan kaum Reformasi. Sebagai konsep eskatologis, api pencucian janganlah dibayangkan dalam kerangka waktu atau ruang. Teologi zaman sekarang ini cenderung memahami api pencucian dalam kaitan dengan perjumpaan dengan Allah pada saat kematian atau mungkin malah sebelumnya. Suatu perjumpaan yang menghanguskan perlawanan kita terhadap kecemerlangan kehadiran Ilahi dan membersihkan kita dari egoisme macam apa pun yang masih ada yang menghalangi persatuan kita dengan Allah. Orang-orang Katolik menyerahkan anggota jemaat yang meninggal kepada Allah dengan merayakan Misa Penguburan Katolik. Orang-orang Katolik mengenangkan mereka yang ada dalam Api Pencucian pada Hari Arwah, tanggal 2 November. Limbo Bagaimana tentang limbo? Banyak orang Katolik menjadi percaya bahwa anak-anak yang meninggal tanpa baptis, jadi masih ada dalam dosa asal, pergi ke limbo, keadaan bahagia secara alamiah, karena mereka belum melakukan dosa apa pun, tetapi tanpa kegembiraan visio beatifica, penglihatan yang membahagiakan. Akan tetapi, magisterium belum menyatakan sikap resmi tentang masalah limbo ini. Kepercayaan pada limbo berkembang di dalam Gereja untuk melawan ajaran St. Agustinus tentang nasib anak-anak yang belum dibaptis. Dalam menanggapi ajaran Pelagius bahwa anakanak seperti itu diberi kemungkinan memasuki tempat kebahagiaan, Agustinus mengajarkan bahwa anak-anak itu dibuang ke hukuman kekal, meski jenisnya paling lunak (Enchiridion 93). Pendapat St. Agustinus ini diperlunak oleh Petrus Lombardus dan teolog Abad Pertengahan yang lain pada abad ke-12 dengan menyampaikan pendapat bahwa anak-anak yang belum dibaptis tidak dihukum, tetapi tidak dapat menerima visio beatifica. Keadaan tengah-tengah ini dikenal sebagai limbo (dari bahasa Latin limbus, yang berarti ”perbatasan”). Meski kepercayaan pada limbo menjadi bagian katolisisme populer dan diterima luas, Gereja tidak mempunyai ajaran formal tentang nasib anak-anak yang belum dibaptis. Dengan demikian, limbo tetap merupakan pendapat teologis. Dewasa ini teologi Katolik mengandaikan bahwa anak-anak yang meninggal tanpa baptis masuk ke dalam hidup abadi, karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolak keselamatan yang diperuntukkan bagi umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus sendiri memeluk anak-anak kecil Yahudi sebagai contoh keterbukaan terhadap Kerajaan Allah (Mrk 10:14). Katekismus Gereja Katolik tidak menyebut limbo dan mengungkapkan harapan bahwa ada jalan keselamatan bagi anak-anak yang telah meninggal tanpa baptis. Fakta bahwa anak belum dibaptis tidak menyingkirkan anak dari rahmat Allah. Memang praktek membaptis begitu saja anak-anak yang orang tuanya tidak menjalankan iman mereka sekurang-kurangnya perlu dipertanyakan, karena mengandung bahaya menjadikan baptis sebagai upacara inisiasi atau peralihan secara kultural daripada perayaan iman secara sakramental. Namun demikian, Gereja meneruskan tradisinya membaptis anak-anak dalam bahaya maut agar mereka dapat disatukan dalam kematian dan kebangkitan dengan hidup baru Yesus dan menjadi anggota tubuh-Nya, Gereja. 3. Persekutuan Orang Kudus Salah satu ciri Katolisisme adalah kesadarannya akan hubungan antara orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Hubungan itu diungkapkan dalam ajaran persekutuan orang kudus, kepercayaan bahwa mereka yang ada dalam Gereja di dunia berada dalam persekutuan dengan mereka yang sudah meninggal dalam Allah, ”para kudus” entah dikanonisasi atau tidak, orang kudus dari Perjanjian Lama dan jiwa-jiwa di api pencucian. Istilah asli persekutuan para kudus (communio sanctorum) mendua artinya. Istilah itu dapat berarti kesatuan benda-benda kudus maupun orang-orang kudus. Istilah itu berasal dari Gereja Timur, yang diartikan sebagai kesatuan ”benda-benda kudus” (ta hagia), mungkin dalam kaitan dengan kesatuan Ekaristis. Di Barat communio sanctorum termuat dalam syahadat, mungkin berasal dari Gaul Selatan pada abad ke-5. Dalam penggunaan Barat aslinya istilah itu berarti ”persekutuan terakhir dengan orang-orang kudus dari segala zaman maupun dengan seluruh rombongan surga”.6 Meskipun istilah itu di Barat juga digunakan dalam kaitan dengan sakramen-sakramen, namun sejak sekurang-kurangnya abad ke-6 istilah itu telah dimengerti dalam arti persekutuan orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kita berhubungan dengan Gereja yang sudah jaya dan Gereja yang masih berjuang melalui kesatuan kita dengan Yesus yang telah bangkit dan dalam Roh Kudus. Konsili Vatikan II ”penuh khidmat menerima iman yang layak kita hormati, pusaka leluhur kita: iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulia di surga, atau sudah meninggal masih mengalami pentahiran” (LG 51). Refleksi teologis dewasa ini menyatakan bahwa persekutuan orang kudus tidak terbatas pada mereka yang sudah meninggal atau masih hidup yang menjadi anggota Gereja namun meliputi semua yang telah mendapatkan jasa dari karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Dengan demikian, istilah persekutuan orang kudus sejajar artinya dengan Kerajaan Allah daripada dengan Gereja. Pengantaraan Para Kudus Orang kudus adalah pria dan wanita yang rahmat dan kehadiran Allah amat jelas tampak pada diri mereka – dalam kesaksian heroik mereka atas iman dalam kemartiran (”martyr” bahasa Yunani berarti ”saksi”), dalam kasih dan belas kasihan pada orang lain, dalam karya mereka bagi Gereja, atau kesetiaan mereka dalam menghayati panggilan mereka. Para ahli sejarah Gereja telah menemukan sepuluh ribu orang kudus yang pemujaannya telah dirayakan oleh umat beriman, yang kebanyakan tidak pernah secara resmi dikanonisasi.7 Orang kudus adalah orang yang dikenang, dipuja, dan diseru namanya oleh orang beriman. Proses kanonisasi belum sungguh-sungguh berkembang sampai sesudah tahun 1000 dan menjadi hak Paus sampai tahun 1234, pada waktu Paus Gregorius IX dalam Dekritnya menyatakan hak mutlak Paus dalam segala urusan orang kudus.8 Bahkan sekarang ini, beberapa orang secara resmi dinyatakan sebagai orang kudus oleh orang-orang – Uskup Agung Romero dari El Salvador, Ibu Teresa dari Kalkuta, dan Paus Yohanes XXIII – karena kedekatan mereka dengan Allah jelas nyata dalam hidup mereka. Karena sadar akan persekutuan atau kesatuan mereka dengan orang-orang kudus, orangorang Kristiani telah memohon perantaraan orang kudus mungkin sejak pertengahan abad ke2. Pada awal abad ke-3, Origenes menulis bahwa doa-doa pengantara yang ditujukan kepada orang kudus sah dan kuat (De Oratione 11.2) (Tentang Doa). St. Agustinus mengagungagungkan kekuatan orang-orang kudus dan mendorong untuk mengajukan doa perantaraan kepada mereka (Urbs Dei 22.8 dst.) (Kota Allah). Mohon perantaraan orang kudus merupakan bagian pokok kesalehan Katolik dan tradisi liturgi Katolik. Litani Para Kudus, yang didoakan pada kesempatan-kesempatan besar seperti tahbisan atau pembaptisan para calon baptis pada upacara Malam Paskah, dapat menjadi ungkapan yang kuat dari kesatuan Gereja dengan pria dan wanita kudus dari masa lampau. Hari-hari pesta orang kudus banyak diperingati dalam kalender liturgi. Pesta Semua Orang Kudus, yang dirayakan pada tanggal 1 November, menghormati semua orang kudus yang telah meninggal dalam persatuan dengan Kristus bahkan jika mereka belum secara resmi diakui sebagai orang kudus oleh Gereja. Orang-orang Kristen Protestan merasa kesulitan untuk memohon perantaraan orang-orang kudus maupun berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Menurut mereka, kedua praktek itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Apalagi, mereka takut kalau-kalau memohon perantaraan orang kudus dapat membahayakan kepengantaraan Kristus. Kedua, praktek itu berasal dalam pengalaman iman orang-orang Kristiani selama berabad-abad dan sudah diakui oleh Gereja. Permohonan perantaraan para kudus pada saat ini masih berlaku, terutama dalam budayabudaya tertentu, dan menjadi bagian pokok agama populer, yang dengan senang telah diterima oleh Gereja sebagai bagian inkulturasi iman. Bersamaan dengan itu, Gereja telah berusaha untuk menjaga, meski tidak selalu berhasil, agar tidak terjadi penyelewengan yang terjadi di dalam agama populer. Indulgensi Pengertian indulgensi berkaitan dengan ajaran tentang persekutuan para kudus. Dalam sejarah Gereja, indulgensi merupakan bab yang ruwet dan kadang-kadang pantas disayangkan. Indulgensi tidak berkaitan dengan peniadaan dosa sendiri, yang diampuni melalui rahmat Allah, tetapi dengan peniadaan sepenuhnya (indulgensi penuh) atau mengurangi ”hukuman sementara” yang merupakan akibat dari dosa yang dilakukan sesudah baptis. Pada awal-awal sejarah Gereja, orang yang melakukan dosa yang berat akan dimasukkan ke dalam kelompok peniten, orang-orang yang menyesal, untuk menjalani masa penebusan dosa publik. Kelak kemudian, pada waktu pengakuan pribadi mulai dipraktekkan, orang yang mengaku dosa kerap diberi ”keringanan” atau pengurangan hukuman dosa kanonis tetapi akan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini mirip dengan ”hukuman” atau denda dosa yang masih kita terima dalam pengakuan dosa sekarang ini. Indulgensi-indulgensi pertama muncul pada abad ke-11 pada waktu Gereja berdoa untuk penghapusan hukuman sementara karena dosa-dosa mereka dan bersamaan dengan itu memberi pengurangan atas sebagian atau seluruh hukuman kanonis mereka. Akan tetapi, tahap demi tahap dua unsur, doa dan pengurangan hukuman, bergabung menjadi satu tindakan menghapuskan hukuman sementara yang diakibatkan dosa. Hugo dari St. Cher (1230) membenarkan praktek itu atas dasar ”perbendaharaan Gereja”, ”jasa” atau lebih tepatnya, rahmat Kristus yang amat melimpah dan para kudus yang diterapkan oleh Gereja, semakin bertambah karena otoritas Paus, demi orang berdosa. Gagasan untuk melakukan pekerjaan baik, warisan perubahan hukuman kanonik, masih dituntut. Akan tetapi tidak lagi masuk akal, pada waktu Gereja mulai memberikan pengurangan atas hukuman sementara yang sekarang ada di luar forum pengakuan. Dari abad ke-15, indulgensi mulai diterapkan pada orang yang sudah meninggal. Praktek memberi pengurangan hukuman dosa, yang disertai dengan pemberian dana, yang pada awalnya merupakan karya amal baik, jelas terbuka untuk penyalahgunaan. ”Penjualan” indulgensi-indulgensi oleh Yohanes Tetzel di Jerman pada abad ke-16 menjadi pemicu protes Luther di Wittenburg. Itu merupakan rumput kering yang mematahkan punggung unta. Pada waktu Trente menghukum penyalahgunaan yang berkaitan dengan indulgensi, kerugian sudah terjadi. Paus Paulus VI secara khusus mengaitkan ajaran tentang indulgensi dengan ajaran tentang persekutuan orang kudus dalam konstitusi apostoliknya, Indulgentiarum doctrina, yang terbit pada tahun 1967. Dalam konteks ini masuk akallah, karena praktek berdoa bagi orang yang sudah meninggal merupakan ajaran kuno. Persekutuan para kudus merupakan persekutuan yang nyata. Namun demikian, pendekatan yang egosentris dan penuh perhitungan terhadap nasib akhir orang Kristiani di mana orang terutama menaruh perhatian pada pengumpulan ”kredit” spiritual, sama sekali berlawanan dengan prinsip-prinsip teologi dan ajaran bahwa hilangnya praktek-praktek indulgensi semacam itu hanya harus diterima dengan baik”.10 Paus Paulus kemudian mengubah disiplin yang berkaitan dengan indulgensi dengan meniadakan waktu khusus (30 hari, 7 tahun, dst.) dan membatasinya. 4. Keselamatan di Luar Gereja Penekanan tradisional Gereja atas perlunya baptis untuk keselamatan mendatangkan keganjilan-keganjilan teologis lain selain kepercayaan akan limbo. Yang juga menjadi persoalan adalah aksioma yang berbunyi ”tidak ada keselamatan di luar Gereja” (extra ecclesiam nulla salus). Aksioma itu tidak hanya bernada sombong dan tidak tenggang rasa pada sebagian orang-orang Katolik dan orang-orang Kristiani lain, tetapi yang lebih buruk lagi, aksioma itu menyiratkan konsep tentang Allah yang sangat sempit dan dipermiskin. Ajaran Tradisional Aksioma itu mempunyai sejarah yang panjang dalam tradisi.11 Kebanyakan Bapa Gereja sebelum St. Agustinus menerapkan aksioma itu pada orang-orang Kristiani yang memisahkan diri dari Gereja entah karena ajaran sesat atau pemisahan. Dengan kata lain, aksioma itu dipergunakan dalam kaitan dengan orang-orang Kristiani yang tersesat. Akan tetapi menjelang abad ke-4, pada waktu sebagian besar Kekaisaran Romawi telah menjadi Kristiani, aksioma itu mulai digunakan sebagai peringatan melawan orang kafir dan orang Yahudi. Yohanes Chrysostomus, misalnya, menggunakan aksioma itu terutama melawan orang Yahudi, dan disesalkan, dengan menyebut mereka dengan ”bahasa yang paling menyakitkan tentang orang Yahudi yang ditemukan dalam sastra Kristiani.”12 Penekanan St. Agustinus pada perlunya baptis dan Gereja memperkuat pendirian itu; St. Agustinus secara khusus menolak kemungkinan keselamatan bagi orang kafir dan Yahudi, apakah mereka telah mendengar Injil atau tidak. Bahkan anak yang belum dibaptis dihukum, seperti kita lihat di atas. Pengaruh Agustinus sedemikian membentuk tradisi selanjutnya sehingga Paus-Paus dan konsili-konsili sepanjang sejarah Kristiani mengulang apa yang sudah menjadi ajaran tradisional. Bahkan sampai tahun 1863, Paus Pius IX dapat menyatakan, ”Merupakan dogma Katolik yang dikenal umum bahwa tak ada orang yang dapat diselamatkan di luar Gereja Katolik” (DS 2867). Yang menjadi keprihatinan Paus adalah sikap indiferentisme religius, tetapi pada waktu bersamaan, ia tampaknya tidak dapat mengakui kebenaran atau kebaikan apa pun dalam agama-agama non-Kristiani.13 Namun demikian, ada tradisi lain yang mengakui kemungkinan keselamatan bagi mereka yang bukan karena salah mereka sendiri tetap berada di luar Gereja. Akar-akarnya dapat dilacak sampai ke Thomas Aquinas abad ke-13. Meskipun Thomas percaya bahwa tak seorang pun dapat diselamatkan tanpa iman yang eksplisit pada Kristus, ia juga percaya dengan teguh pada universalitas kehendak Allah untuk menyelamatkan dan tampaknya mengakui kemungkinan atas ketidaktahuan akan Kristus yang tak dapat disalahkan. Ia juga berbicara tentang keinginan yang implisit untuk baptis. Sesudah penemuan Dunia Baru, dengan benuabenua yang besar dan jutaan orang yang belum pernah mendengar Kristus, teolog-teolog mulai mengangkat masalah keselamatan di luar Gereja dengan cara baru. Para Dominikan di Salamanca, Spanyol, mengembangkan gagasan St. Thomas, menggali konsep ketidaktahuan yang tak dapat diperbaiki atau dapat disalahkan maupun kemungkinan bahwa orang-orang Indian di Dunia Baru tidak dapat menerima iman karena perilaku yang jahat para penjajah Kristiani. Mereka dan para Yesuit di Roma sampai pada kesimpulan bahwa ”keselamatan harus mungkin, bahkan pada zaman Kristiani, melalui iman kepada Allah tanpa iman eksplisit pada Kristus.”14 Arah Baru Baru pada pertengahan abad ke-19, Paus Pius IX mengakui bahwa orang yang tetap di luar Gereja karena ketidaktahuan yang tak dapat disalahkan dapat diselamatkan bila mereka bekerja sama dengan rahmat Ilahi. Konsili Vatikan II secara resmi mengubah sikap Gereja Katolik terhadap agama-agama lain. Konstitusi Dogmatik tentang Gereja mengakui bangsa Yahudi yang ”sangat dicintai oleh Allah, sebab Allah tidak menyesalkan kurnia-kurnia serta panggilan-Nya”. Rencana penyelamatan Allah juga mencakup orang-orang Muslim, yang ”bersama kami menyembah Allah satu-satunya dan penuh belas kasihan”. Konsili dengan jelas mengakui bahwa orangorang lain dapat diselamatkan: ”Mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta Gereja-Nya tetapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendak-Nya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Penyelenggaraan Ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka, yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah, namun berkat rahmat Ilahi berusaha menempuh hidup yang benar” (LG 16). Kebanyakan orang Katolik dewasa ini mengakui bahwa keselamatan ada di luar Gereja bagi mereka yang tidak menyadari pewahyuan Allah dalam Yesus. Rahmat Allah tidak terbatas pada struktur-struktur Gereja; Roh bergerak ke mana Ia kehendaki. Seperti Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini menyatakan, Roh Kudus memberikan kemungkinan kepada semua orang ”dengan cara yang diketahui oleh Allah” disatukan dengan misteri Paskah itu (GS 22). Namun pada waktu yang bersamaan orang-orang Kristiani menekankan bahwa Gereja mengandung kepenuhan kebenaran. Gereja merupakan sakramen universal keselamatan (LG 48). Melalui Gereja diwartakan hakikat Tritunggal Allah, keselamatan semua orang dalam Yesus, dan hidup dalam Roh. Mereka yang menjadi anggota Gereja secara sadar hidup, mewartakan, dan merayakan misteri iman ini. Gereja harus melanjutkan mewartakannya kepada segala bangsa. Akan tetapi Gereja, harus melakukannya dengan cara-cara yang amat penuh hormat terhadap mereka yang menganut agama-agama lain, karena Roh Allah hadir dalam hidup mereka. 5. Kesimpulan Di masa lampau penekanan yang terlalu banyak pada dimensi masa depan eskatologi Kristiani membuat Gereja lupa akan makna penyelamatan dan pemerdekaan Injil bagi hidup di dunia. Iman yang hanya memandang ke masa depan mudah menjadi ideologi, yang mengajar kaum miskin dan tertindas untuk menerima kondisi mereka tanpa mengeluh dan membenarkan struktur-struktur sosial yang menindas. Ungkapan agama menjadi ”candu bagi masyarakat” merupakan reaksi terhadap iman yang berat sebelah itu. Mengideologisasikan Injil juga mempersempit Injil menjadi pesan untuk mengubah masyarakat tanpa menyebut tujuan akhir kita untuk hidup abadi bersama Allah. Agama Kristen mulai dengan kebangkitan Yesus dari mati. Kebangkitan merupakan misteri yang ada pada inti pewartaan para murid pertama. Misteri itu ditafsirkan dengan kekayaan lambang-lambang dan gambaran-gambaran yang meliputi eskatologi Kristiani yang tidak selalu dapat ditafsirkan secara harfiah. Akan tetapi, kebangkitan Yesus dari mati bukan hanya merupakan lambang. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa eskatologi, merasuknya Allah ke dalam sejarah manusia di masa depan, yang menyatakan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian serta janji untuk kebangkitan kita sendiri. Ajaran tentang persekutuan para kudus, dalam mengumpulkan ke dalam Gereja tak hanya orang-orang yang dibaptis di dunia, tetapi juga umat beriman yang sudah meninggal, merupakan ungkapan hakikat eskatologis Gereja. Orang-orang Kristiani mempunyai persekutuan dengan para kudus di surga dan jiwa-jiwa di api pencucian, yang akan diwujudkan secara penuh dalam eskaton pada waktu segala-galanya akan dipulihkan dalam Kristus (Ef 1:10; Kol 1:20). Orang-orang Kristiani telah memohon perantaraan para kudus dan berdoa bagi orangorang yang sudah meninggal sejak abad-abad awal. Kedua praktek itu berakar dalam kesalehan populer dan telah diakui oleh Gereja. Orang-orang Katolik percaya bahwa rahmat dan keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan demikian, orang-orang Kristiani melihat jemaat Gereja sebagai lambang semua keselamatan yang paling lengkap. Akan tetapi, rahmat tidak pernah terkungkung dalam batas-batas Gereja atau sakramensakramen. Meskipun orang-orang Katolik telah diajar dan percaya untuk beberapa waktu bahwa mereka yang bekerja sama dengan rahmat Allah dapat diselamatkan meskipun mereka belum mendengar Injil, Konsili Vatikan II menyatakan hal itu secara tegas. Dengan demikian sesungguhnya ajaran itu menafsirkan kembali aksioma ”tak ada keselamatan di luar Gereja” menjadi lebih memadai dengan memperhitungkan universalitas keselamatan yang tersedia melalui Yesus Kristus. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Johanes Paulus II, Crossing the Threshold of Hope, ed. Vittorio Messori (New York: Random House, 1994) 67. Lihat Karl Rahner, Foundations of Christian Faith (New York: Seabury, 1978) 270-274. Ibid., 271. Walter Kasper, Jesus the Christ (New York: Paulist, 1976) 152. Edward Schillebeeckx, Church: The Human Story of God (New York: Crossroad, 1990) 138. J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds (London: Longman, 1972) 391. Kenneth L. Woodward, Making Saints (New York: Simon & Schuster, 1990) 17. Ibid., 66-67. H. George Anderson, Y. Francis Stafford, and Yoseph A. Burgess, eds., The One Mediator, The Saints and Mary (Minneapolis: Augsburg, 1992) 62. Richard McBrien, Catholicism (San Francisco: Harper, 1994) 1171. Lihat Francis A. Sullivan, Salvation Outside the Church? Tracing the History of the Catholic Response (New York: Paulist, 1992). Ibid., 26. J. Robert Dionne, The Papacy and The Church: A Study of Praxis and Reception in Ecumenical Perspective (New York: Philosophical Library, 1987) 92. Sullivan, Salvation Outside the Church? 98. XI Agenda yang Belum Selesai Apakah penerbitan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II menandai selesainya pembaruan Gereja yang dikemukakan oleh Konsili, atau apakah dokumen-dokumen itu hanya merupakan awal dari proses pembaruan yang belum selesai? Masalah ini masih menjadi bahan perdebatan. Sementara orang Katolik merasa bahwa Gereja telah menapak terlalu jauh, dengan menyesuaikan diri dengan semangat zaman daripada menantang zaman dengan kebenarannya yang abadi. Sejumlah orang bergabung dengan Serikat Orang-Orang Katolik Konservatif, Catholic United for the Faith (CUF) (Persatuan Orang Katolik demi Iman), Opus Dei, atau The Fellowship of Catholic Scholars (Ikatan Sarjana Katolik). Beberapa orang menulis surat kepada para pejabat resmi di Roma dengan mencela kelunakan uskup-uskup yang ”tidak tegas” dan kesalahan-kesalahan teolog-teolog ”modernis”. Orang-orang Katolik itu kerap disebut sebagai kaum ”integralis”. Istilah itu yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang memandang ajaran-ajaran Katolik adalah sama pentingnya dan sedemikian saling berkaitan erat, sehingga menentang salah satu ajaran berarti merongrong seluruh struktur yang diwahyukan secara Ilahi.1 Integralisme merupakan suatu jenis fundamentalisme Katolik. Orangorang Katolik bahkan lebih kecewa; beberapa orang menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk ikut serta dalam Perayaan Misa dalam bahasa Latin; yang lain, sesudah menolak Konsili Vatikan II, bergabung dengan jemaat-jemaat skisma Konsili Trente, Serikat St. Pius X Uskup Agung Lefebvre, dan dengan demikian memisahkan diri dari Gereja.2 Orang-orang Katolik lain pada zaman sekarang ini juga tak bahagia, tetapi dengan alasan yang berlawanan. Mereka merasa bahwa Gereja telah bergerak lambat, sehingga gagal untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen Konsili, bahwa timbul reaksi yang berusaha mengembalikan Katolisisme zaman sebelumnya yang tertutup dan tersentralisasikan. Banyak orang bekerja demi perubahan melalui lembaga, bekerja di pengadilan, melayani di Paroki, mengajar di kursus katekese, sekolah-sekolah, dan universitasuniversitas. Beberapa bergabung dalam perhimpunan-perhimpunan seperti The Call for Action, (Panggilan untuk bertindak), Women’s Ordination Conference (Konferensi Penahbisan Wanita), atau CORPUS, yaitu organisasi imam-imam yang telah menjadi awam dan istri-istri mereka yang berjuang untuk mengungkapkan pelayanan imamat yang lebih luas. Beberapa berusaha mencari Gereja yang lebih sesuai dengan bergabung ke dalam komunitas-komunitas kecil tanpa pimpinan yang ditahbiskan. Beberapa menyerah begitu saja dan meninggalkan Gereja. Jika ada kekecewaan pada dua sayap Gereja, ada juga banyak kecemasan di Roma. Baik orang Katolik maupun orang Protestan menaruh perhatian tentang apa yang mereka lihat sebagai usaha dari pihak Roma pada tahun-tahun akhir kepausan Paus Yohanes Paulus II untuk membuat pembaruan atau ”pemulihan”, istilah yang digunakan oleh Kardinal Yoseph Ratzinger, Prefek Congregatio de Doctrina Fidei, dalam wawancara yang diberikan kepada majalah Italia tak lama sebelum Sinode Uskup Luar Biasa pada tahun 1985. Bagi banyak orang, Paus Yohanes Paulus tampak menaruh perhatian terutama menyatukan umat yang terpecah dan memulihkan disiplin. Sementara progresif dalam masalah-masalah sosial, Paus Yohanes Paulus konservatif dalam hal ajaran dan moral, dan ia telah menunjuk uskup-uskup – sekarang jumlahnya lebih dari separoh seluruh jumlah uskup dalam Gereja – yang mencerminkan pandangannya.3 Akan tetapi, bagi mayoritas orang-orang Katolik di seluruh dunia, Konsili Vatikan II telah menjadi bagian sejarah dan perubahan-perubahan yang dimasukkan ke dalam kehidupan Katolik diterima begitu saja. Mereka yang sekarang berumur di bawah 30, belum pernah mengenal Gereja lain. Dokumen-dokumen Konsili menetapkan ukuran untuk pembaruan, dan dokumen-dokumen itu merupakan ungkapan normatif dari pemahaman-diri Gereja Katolik menjelang abad 21 atau milenium ketiga ini. Akan tetapi, aliran-aliran pembaruan yang mendahului Konsili dan pembaruan-pembaruan baru yang dilepas kendalinya oleh Konsili terus membentuk Katolisisme dewasa ini. Dalam arti yang sebenarnya, masalah-masalah yang diangkat oleh aliran-aliran itu merupakan agenda Konsili yang belum selesai, kami menyebut beberapa agenda pada akhir bab 4. Dalam bab terakhir ini, kita perlu membahas beberapa masalah itu, antara lain pembaruan liturgi, persoalan otoritas, wanita dalam Gereja, gerakan ekumenis, dan dialog antaragama. Masalah-masalah itu akan terus mengubah cara orang Katolik mengalami diri sendiri dan Gereja mereka dalam memasuki abad ke-21. 1. Pembaruan Liturgi Salah satu tujuan utama gerakan liturgi sejak awal adalah mendorong ”partisipasi atau keikutsertaan secara penuh, sadar, dan aktif dalam perayaan liturgi” oleh umat beriman (SC 14). Konsili Vatikan II bergerak cukup jauh menuju ke tujuan itu dengan memungkinkan penggunaan bahasa daerah dalam liturgi dan memberi peran kepada pria dan wanita sejumlah peranan liturgis yang sebelumnya merupakan peran khas para klerus. Perubahan Liturgi Dalam tahun-tahun sesudah Konsili, orang-orang Katolik mengalami deretan perubahan yang dirancang untuk mengurangi jarak fisik dan psikis antara imam dan umat. Pusat perhatian tidak lagi ditekankan pada konsekrasi tetapi dipusatkan pada perayaan umat yang berkumpul. Mulai tahun 1966, altar-altar di banyak gereja dibuat menghadap umat sehingga imam dapat memimpin Misa berhadapan dengan umat. Sebelumnya imam berada jauh di depan umat dan membelakangi mereka. Bangku-bangku komuni mulai disingkirkan. Hal ini meniadakan halangan fisik yang pernah memisahkan umat dari tempat kudus. Pemisahan itu secara tersirat memberi tahu kepada umat pengertian yang salah bahwa hanya orang yang ditahbiskan dapat memasuki tempat kudus. Dengan keikutsertaan umat, Misa menjadi dialog antara imam dan umat, dan bukan lagi percakapan berbisik-bisik antara imam dan putra-putra altar, yang selama berabad-abad telah menjawab imam menggantikan umat. Pada waktu umat mulai bereksperimen dengan berbagai macam musik, gitar dipergunakan, dan ”Misa Rakyat” menjadi populer. Salam damai yang dulu hanya dilakukan oleh tiga pelayan klerikal yang mempersembahkan Misa Agung, dilakukan oleh seluruh umat. Tiga Doa Syukur Agung baru, dikeluarkan pada tahun 1968 dan tata laksana Misa disetujui pada tahun 1969. Doa-doa Syukur Agung lain menyusul disetujui sehingga sekarang ini ada sembilan Doa Syukur Agung. Kebanyakan perubahan dalam liturgi, yang pada dasarnya tak pernah berubah sejak abad ke-16, diterima dengan gabungan rasa acuh-tak-acuh dan humor yang baik. Kerapkali penjelasan-penjelasan yang diperlukan amatlah buruk jika ada. Beberapa orang menjadi bingung mengapa memotong doa mereka ”untuk bertukar salam damai dengan umat lain yang hadir atau merasa tidak enak” menerima Komuni dari ”pelayan awam” daripada dari imam. Pada waktu menerima komuni dengan tangan disetujui, beberapa orang merasa bahwa Sakramen Mahakudus tidak diterima dengan hormat sebagaimana layaknya, sementara yang lain menyatakan tangan orang yang dibaptis dan diurapi dalam Roh merupakan penerimaan yang layak seperti jambangan emas yang diberkati oleh imam. Umat yang Beribadat Di luar perubahan-perubahan yang relatif kecil, studi tentang liturgi telah mengakibatkan pergeseran dalam pemahaman tentang liturgi. Khususnya yang penting adalah penekanan dalam teologi liturgi akhir-akhir ini bahwa umat yang mengambil bagian dalam liturgilah yang merayakan liturgi. Bahasa liturgi pada milenium pertama menunjukkan bahwa seluruh umatlah yang merayakan Ekaristi. Instruksi umum untuk Missal (Buku Misa) Roma (1970) telah kembali pada pandangan ini. Dari sudut pandang ini imam lebih tepat disebut pemimpin daripada selebran. Akan tetapi, mempraktekkan tidaklah selalu mudah. Tantangannya adalah menemukan cara-cara yang tepat untuk bergeser dari ”liturgi yang berpusat pada imam dengan umat” ke ”liturgi yang berpusat pada umat dengan pemimpin”, sehingga peranan umat dalam perayaan dapat diungkapkan secara lebih jelas.4 Pengaturan orang untuk liturgi harus mencerminkan pentingnya umat. Dalam Gereja perdana, tempat kehadiran Allah bukan pada tempat tetapi pada umat yang berkumpul sendiri. St. Paulus memberi tahu kepada umat Korintus ”Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?” (1Kor 3:16; bdk. Ef 2:19-2). Jemaat-jemaat perdana berkumpul untuk Ekaristi di rumah-rumah perorangan. Ketika Gereja berkembang, bangunan-bangunan besar menjadi perlu, tetapi gereja seharusnya tidak seperti gedung teater di mana fokusnya adalah seorang pemimpin yang berada jauh dan yang dilihat adalah belakang kepala para anggota umat lain. Gereja seharusnya dibangun sedemikian rupa sehingga umat Allah harus dapat melihat satu sama lain dan berkumpul di seputar meja Ekaristi. Seluruh tempat adalah suci, bukan hanya ”panti imam”. Dengan demikian, arsitektur gereja modern cenderung menggeser altar maju ke depan mendekati umat. Ada dimensi ”stasional” pada liturgi. Pusat perhatian perbuatan liturgis bergerak ke tempat duduk pemimpin pada upacara pendahuluan, ke mimbar bacaan pada liturgi Sabda, ke altar pada liturgi Ekaristi, dan akhirnya kembali ke tempat duduk. Dari tempat duduk itu, imam membubarkan umat dengan berkat dan penugasan untuk membawa misteri kasih Allah yang sudah mereka rayakan kepada orang-orang lain. Penemuan kembali konsep umat yang beribadat juga berarti deklerikalisasi liturgi. Ini tidak hanya menciptakan peran-peran liturgi baru bagi awam pria dan wanita tetapi juga harapanharapan baru. Orang- orang Katolik dewasa ini, terutama kaum mudanya, berharap untuk dapat berperan aktif dalam liturgi. Mereka bersemangat untuk melayani – sebagai pembaca atau pelayan Ekaristi, sebagai perencana, pelayan di bidang musik, dan dalam kesempatankesempatan tertentu sebagai pengkhotbah pada upacara-upacara non-liturgis dan pemimpin dalam Ibadat Komuni bila imam berhalangan hadir. Dewasa ini, awam pria dan wanita merasa tersinggung dikatakan oleh Gereja resmi bahwa mereka itu hanyalah pelayan Ekaristi ”luar biasa” dan oleh karena itu mereka tidak dapat melayani roti atau piala dalam liturgi besar bila ada cukup jumlah imam yang merayakan. Mereka bertanya-tanya mengapa pria yang tak ditahbiskan dapat diangkat menjadi akolit dan lektor tetapi wanita tidak? Beberapa orang bertanya mengapa awam pria dan wanita yang memenuhi syarat tidak dapat kadang-kadang memberi homili pada Perayaan Ekaristi, peran yang oleh hukum kanonik (Kan. 767.1) hanya diberikan kepada orang-orang yang ditahbiskan. Sementara khotbah tidak dapat dipisahkan dari peran pelayan yang ditahbiskan untuk memimpin jemaat lokal, beberapa orang menyatakan bahwa tanggung jawab pastoral imam dapat secara sah dilakukan dengan kadang-kadang mengakui anggota-anggota umat yang memiliki kharisma untuk berkhotbah dengan baik. Tentu saja ketika semakin banyak awam pria dan wanita mengambil peran pelayanan purna waktu di dalam Gereja atau mendapatkan reputasi sebagai teolog dan pembimbing rohani, akan terus ada ketegangan dalam hal pembatasan peran pelayan awam yang dapat mereka lakukan dalam Ekaristi. Pembaruan Teologi Imamat Ada juga kebutuhan untuk memikirkan kembali pertanyaan siapa yang dapat ditahbiskan. Meskipun Konsili Vatikan II membuat langkah yang berarti dalam mengembangkan teologi jabatan uskup dan teologi awam, Konsili berbicara sedikit tentang imamat kecuali menggambarkan imam ”sebagai pembantu yang arif badan para uskup” (LG 28). Tanpa pembaruan teologi imamat dan dengan harapan-harapan baru terhadap imam dari pihak orang awam, apa yang sudah amat jelas tentang panggilan imam tampak hilang sesudah Konsili.5 Sejak itu, lima puluh ribu imam telah melepaskan jabatan mereka. Dan dengan bertambah sedikitnya calon untuk tahbisan, Gereja dewasa ini mengalami kekurangan imam yang berat. Diperkirakan 50% paroki dan stasi di Dunia Ketiga tidak mempunyai imam yang menetap. Kekurangan jumlah imam itu merupakan masalah besar di dalam Gereja. Ini menantang Gereja untuk memikirkan kembali hakikat imamat dan menetapkan siapa yang dapat ditahbiskan menjadi imam termasuk syarat-syaratnya. Yang menjadi titik tolak pemikiran tentang imamat adalah terlantarnya pelayanan umat karena kekurangan imam itu. Bagaimana kebutuhan akan imam itu dapat dipenuhi? Memikirkan Kembali Diakonat Masalah lain adalah diakonat tetap, yang dipulihkan oleh Konsili. Sekarang ini sudah banyak orang awam yang diangkat menjadi diakon tetap. Akan tetapi, masih ada kebingungan tentang perannya. Meski diakon berfungsi dalam Gereja awal sebagai pelayan dengan tugas melayani orang miskin, dalam masyarakat sekarang ini pelayanan diakon terlalu kerap dilihat hampir secara eksklusif dalam kerangka pelayanan liturgi. Walaupun peran liturgis mereka itu penting, masuk akallah, jika saat ini Gereja memusatkan pelayanan diakon pada tugas karitatif, karena pelayanan kepada orang yang tidak beruntung merupakan dimensi pokok dari perutusan Gereja. 2. Masalah Otoritas Sejumlah perkembangan dalam sejarah akhir-akhir ini telah memainkan peranan yang amat besar dalam mengubah cara orangorang Katolik memahami otoritas Gereja. Pertama, teologi Katolik sejak akhir Konsili Vatikan II telah mengalami revolusi yang sebenarnya dalam metodologi. Kedua, sejak waktu yang sama telah terjadi laisisasi (pengawaman) teologi. Akhirnya, berkembangnya pelayanan awam pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang ketiga. Secara metodologis, teologi Katolik sebelum Konsili Vatikan II terutama bersifat spekulatif dan deduktif. Teologi Katolik berperan dalam menganalisis dan menjelaskan kebenaran Ilahi yang diajarkan oleh magisterium. Akan tetapi, penerimaan Gereja atas kritik alkitabiah modern dan pergeseran dari cara pemahaman yang abstrak, dogmatik, ”klasik” ke pemahaman yang didasarkan kesadaran historis membawa perubahan besar dalam pendekatan. Ketika kerangka Skolastik lama banyak ditinggalkan, teologi menjadi disiplin yang jauh lebih kritis – menguji dasar-dasar, menyelidiki perkembangan-perkembangan historis, menafsirkan kembali formulaformula (rumusan-rumusan) tradisional, dan semakin berpaling pada pengalaman. Dalam istilah-istilah mereka yang berteologi, kebanyakan teologi sampai zaman itu adalah teologi yang dilakukan di seminari-seminari oleh imam-imam. Belum ada teologi bagi awam pria apalagi awam wanita termasuk para suster atau para biarawati. Perkembangan-perkembangan dan pergeseran-pergeseran dalam teologi Katolik itu telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang berarti. Pertama, teologi Katolik jauh lebih mandiri daripada pada zaman ketika teologi dilakukan hampir sepenuhnya oleh para imam dan religius. Karena kemandirian itu, para teolog Katolik ditempatkan dalam pengawasan uskup setempat, terutama melalui peraturan bahwa untuk dapat mengajar, para teolog harus mendapat mandat kanonik (bdk. kan. 812). Kedua, banyak orang Katolik dewasa ini jauh lebih terdidik daripada masa lampau, ketika hanya imam-imam dan religius yang mendapat pendidikan teologi. Banyak orang awam menjadi sadar akan berbagai sifat sumber-sumber alkitabiah dan konteks historis yang berbeda yang menjadi latar belakang timbul dan berkembangnya ajaran-ajaran Katolik dan jauh lebih siap untuk menerima perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, banyak orang awam yang mengetahui bahwa wahyu tidak disampaikan dalam ajaran-ajaran yang dirumuskan atau pernyataan-pernyataan abadi tetapi diperantarai oleh lambang-lambang yang muncul dari pengalaman jemaat religius. Hanya baru kemudianlah pengalaman religius itu dirumuskan dalam pernyataan-pernyataan doktrinal yang tetap terbatas dan dikondisikan secara historis. Mereka menjadi menghargai Yesus historis, menjadi lebih dekat dengan Yesus dari Injil Sinoptik daripada Yesus dari Injil Yohanes, yang berbicara sedemikian terbuka dan sadar tentang keallahan-Nya. Mereka memahami Gereja bukan sebagai lembaga yang secara rinci didirikan oleh Yesus, tetapi jemaat para murid, yang di bawah bimbingan Roh Kudus berkembang dari jemaat Kristiani awal menjadi kesatuan GerejaGereja di seluruh dunia. Mereka menghargai pentingnya ajaran magisterium yang kuat, tetapi bersamaan dengan itu mereka juga menjadi sadar bahwa magisterium adalah jabatan dalam Gereja, bukan otoritas lepas yang ditempatkan di atasnya. Perkembangan ketiga adalah bahwa dalam tahun-tahun sesudah Konsili jumlah awam pria dan wanita yang menyiapkan diri untuk pelayanan bertambah banyak, sementara jumlah imam dan religius cenderung terus menurun. Pelaksanaan Otoritas Perkembangan-perkembangan yang telah kita bahas telah mempertajam masalah bagaimana otoritas dilaksanakan dalam Gereja. Masalah ini akan terus menjadi masalah kontroversi di masa datang. Ada banyak masalah – antara lain, kekurangan imam, tempat wanita di dalam Gereja, dan moralitas seksual Gereja – yang harus dihadapi dengan jujur oleh Gereja dewasa ini. Masalah-masalah itu harus dibahas secara terbuka. Orang-orang Katolik awam belum mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan Gereja atau mempengaruhi proses pembuatan keputusannya. Bagi banyak orang Katolik, Gereja masih tampak berstruktur dan berpola hidup ala monarki yang badan-badan mengajar dan pemerintahannya di luar pengaruh atau jangkauan umat yang diajar dan diperintah. Kepada siapa otoritas Gereja bertanggung jawab? Orang awam Katolik belum banyak ikut dalam pengarahan hidup dan pelayanan Gereja. Mereka belum dapat ikut dalam proses pengambilan keputusan Gereja, dalam perumusan ajarannya dan dalam pemilihan para gembalanya. Namun, sementara itu perlu diingat bahwa Gereja jauh lebih fleksibel daripada yang kelihatan. Gereja bukanlah sebuah demokrasi, dan juga bukan sebuah monarki absolut. Gereja bukanlah struktur kelembagaan tetapi organisme yang hidup, komunitas awam sejati dan anggota-anggota yang ditahbiskan. Bagaimana Gereja dapat mengungkapkan tanggung jawab bersama untuk hidup dan pelayanannya berdasarkan hakikat saling ketergantungannya itu? Ada beberapa langkah yang dapat diambil, dengan tetap mengakui hubungan dialektika yang harus ada antara jabatan dan karisma tanpa mengubah struktur fundamental Gereja. Membuat Keputusan Bersama Wakil-wakil klerus dan awam dapat ikut ambil bagian dalam struktur pembuatan keputusan Gereja tanpa meniadakan peran Paus atau kolegialitas uskup. Keikutsertaan dalam pembentukan jemaat merupakan masalah keadilan. Menurut Konsili Vatikan II, orang-orang merupakan faktor yang menentukan struktur-struktur sosial dan ”menyadari bahwa merekalah ahli-ahli serta pencipta-pencipta kebudayaan masyarakat mereka” (GS 55). Ini bahkan lebih berlaku bagi jemaat Gereja.6 Fakta bahwa doktor-doktor teologi universitas dan wakil-wakil ordo-ordo religius ikut serta dalam Konsili-konsili Gereja pada Abad Pertengahan merupakan contoh peristiwa yang dapat dijadikan awal, untuk memperluas cara magisterium mengajar Gereja dapat dilak-sanakan dalam Gereja di masa depan. Kehadiran para ahli teologi dan pendengar awam pada Sinode para Uskup tentang kaum awam pada tahun 1987, dapat ikut serta dalam diskusi-diskusi dalam kelompok kecil tetapi tidak memilih merupakan satu model untuk gaya pembuatan keputusan yang lebih partisipatif. Dan masih banyak hal lain. Pemilihan Uskup Bagaimana uskup dipilih merupakan masalah yang rumit dewasa ini. Selama 1000 tahun pertama sejarah Gereja, hak Gereja-Gereja lokal untuk memilih uskup-uskup mereka jelas diakui. Paus Celestinus I menyatakan: ”Janganlah uskup dipaksakan pada umat yang tidak menghendakinya.”7 Paus Leo I menyatakan: ”Orang yang memimpin semua harus dipilih oleh semua.”8 Pada tahun 1305, Paus Clemens V berusaha membuat hak untuk menunjuk uskupuskup menjadi haknya sendiri dengan tujuan menaikkan penghasilan, tetapi uskupuskup tetap terus dipilih oleh para penguasa setempat, kadang-kadang raja-raja, kadangkadang klerus katedral. Namun, uskup baru harus diakui oleh Paus dan membayar untuk persetujuannya. Ini tentu saja menambah kas Paus, tetapi juga berguna untuk mengungkapkan dan mempertahankan kesatuan antara Gereja lokal dan Uskup Roma. Pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18, uskup-uskup kerap kali diangkat oleh para penguasa negara-negara Eropa yang semakin disekularisasikan. Baru pada tahun 1884, Paus menyatakan sebagai haknya untuk mengangkat uskup-uskup di seluruh dunia. Praktek pemilihan uskup oleh Roma pada akhir abad ke-19 menjadi pola untuk seluruh Gereja Barat.9 Jika ada sejarah panjang bahwa uskup-uskup dipilih pada tingkat lokal, maka GerejaGereja setempat mempunyai hak untuk memilih uskup-uskup mereka, atau mengajukan tiga calon ke Roma. Kitab hukum Kanonik baru sebenarnya mengakui kemungkinan ini dengan menyatakan bahwa Paus ”dengan bebas menunjuk uskup-uskup atau meneguhkan uskupuskup yang dipilih secara legal (Kan. 375). Agar tetap ada dalam kesatuan dengan Gereja universal, uskup-uskup yang dipilih secara lokal perlu diakui oleh Takhta Suci di Roma. Dengan demikian, sebagai ganti praktek pengangkatan uskup oleh Roma yang berlaku sekarang tidak perlu berupa pemilihan calon-calon yang mengajukan diri sebagai uskup, karena dapat mempolitisasikan jabatan uskup. Akan tetapi, ada peristiwa-peristiwa historis yang mendahului dan hukum kanonik yang memungkinkannya. Berdasarkan peristiwa-peristiwa historis dan hukum kanonik itu, awam dan klerus Gereja-Gereja setempat dapat diberi kesempatan lebih untuk menyampaikan pendapat dalam proses pemilihan uskup-uskup mereka. Cara itu juga akan mengakui secara lebih efektif dalam hidup Gereja prinsip subsidiaritas yang sedemikian penting dalam ajaran-ajaran sosial Gereja. 3. Wanita dalam Gereja Tantangan yang paling radikal terhadap status quo dalam Gereja mungkin muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh banyak wanita dewasa ini. Meski banyak kemajuan telah dicapai oleh wanita dalam masyarakat sekular pada tahun-tahun terakhir ini, banyak wanita Katolik merasa sebagai warga kelas dua dalam Gereja. Mereka melihat bahwa Gereja tidak dapat menerima wanita ke dalam jabatan pelayanan yang ditahbiskan. Dengan demikian, Gereja tidak dapat menerima mereka ke dalam jabatan pemimpin dan pengambil keputusan resmi. Gereja menyatakan bahwa baptis mengatasi perpecahan atas dasar ras, status sosial, dan jenis kelamin (Gal 3:28). Berdasarkan makna baptis itu, kaum wanita merasa bahwa baptis mereka tidak dianggap serius karena ajaran tentang baptis itu belum diakui oleh Gereja resmi. Dengan demikian, banyak wanita diasingkan dari Gereja. Jika gerakan wanita dalam Gereja berkembang dari gerakan feminis yang lebih luas dewasa ini, dasarnya dapat ditemukan jauh lebih awal pada wanita-wanita yang menantang apa yang dianggap merupakan pandangan alkitabiah tentang tempat wanita dalam Gereja dan masyarakat. Sarah Grimke (1792-1873) merupakan salah seorang wanita yang menyarankan bahwa masalahnya bukan pada teks Kitab Suci, melainkan dalam cara menafsirkannya. Perbedaan penafsiran Kitab Suci ini menjadi dasar munculnya cabang-cabang gerakan feminis dari yang paling kanan seperti menafsirkan kembali tradisi Kristiani secara lebih inklusif sampai yang paling kiri seperti yang menolak Yesus dan karya penyelamatan-Nya berdasarkan argumen bahwa wanita tidak dapat diselamatkan oleh Allah yang laki-laki. Akan tetapi, gerakan wanita dalam Gereja dewasa ini juga merupakan bagian dari gerakan pemerdekaan yang berasal dari sikap berpalingnya perhatian Gereja ke dunia, kaum miskin, dan kaum tertindas sesudah Konsili Vatikan II. Paus Yohanes XXIII menarik perhatian pada tumbuhnya kesadaran wanita akan martabat mereka dalam ensikliknya Pacem in Terris (no. 41) tahun 1963. Ada kesamaan yang jelas antara teologi pembebasan Amerika dan teologi feminis. Dalam konteks Gereja, feminisme merupakan kesadaran yang seluruhnya baru dari pihak wanita yang meminta kesamaan mereka secara penuh baik di dalam Gereja maupun di dalam masyarakat. Apa yang diminta oleh gerakan wanita dewasa ini? Agar Gereja memperhatikan pengalaman wanita secara serius; agar Gereja mengakui bahwa teks-teks Kitab Suci dikondisikan oleh budaya androsentris (yang berpusat pada kaum laki-laki) atau patriarkal, agar Gereja berbicara lebih secara inklusif dengan memasukkan wanita ke dalamnya, dan agar Gereja menyediakan pelayanan yang lebih melibatkan wanita. Memperhatikan Pengalaman Wanita Secara Serius Wanita dewasa ini menekankan bahwa kebenaran datang dari pengalaman dan tidak harus dari otoritas. Mereka menghendaki agar pengalaman mereka diperhatikan secara serius. Baik teologi feminis maupun teori psikologi berpendapat bahwa ”1) pengalaman pribadi ada pada inti kebenaran; 2) pengalaman wanita itu sah; dan 3) wanita mempunyai kekuasaan untuk menyebutkan pengalaman-pengalaman yang diambil dari mereka.”10 Memperhatikan pengalaman wanita sekurang-kurangnya berarti mengakui dua hal. Pertama, Apa yang dialami wanita amat kerap berbeda dari apa yang dialami pria. Apa yang dialami oleh wanita adalah penindasan dan pengingkaran. Mereka amat menyadari bahwa banyak wanita di seluruh dunia diingkari hak penuh mereka, bahwa wanita bekerja selama 2/3 dari jam kerja dunia, bahwa mereka merupakan 2/3 dari manusia buta aksara di dunia, dan bahwa mereka kerap disalahmanfaatkan secara fisik dan secara seksual dieksploitasi. Hal-hal itu telah mereka alami sendiri secara pribadi. Mereka mengetahui ada hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan, bukan karena dibatasi oleh bakat atau oleh biologi, tetapi karena peran sosial yang ditentukan hanya berdasarkan jenis kelamin. Penyingkiran berdasarkan jenis kelamin seperti itu kerap mengakibatkan berkurangnya rasa harga diri. Bila suatu pengalaman khusus membuat wanita tiba-tiba menyadarinya untuk pertama kali, ia kerap mengalami luka yang dalam dan marah yang berat. Akan tetapi, bahkan dalam kasus-kasus seperti itu ada peraturan-peraturan yang memberi tahu kepadanya bagaimana harus menanggapi. Jika ia mengungkapkan kemarahan karena distereotipkan dan disingkirkan, ia dibuat merasa bersalah, dikatakan bahwa itu tidak selayaknya, atau bahwa ia harus mempertimbangkan orang lain dan bukan diri sendiri. Tidak mengherankan bahwa banyak wanita memandang masyarakat dan Gereja itu sangat patriarkal dan menindas. Kedua, seperti teologi feminis menyatakan, cara wanita mengalami diri sendiri dan dunia berbeda dengan cara laki-laki mengalaminya. Perbedaan itu berakar pada cara-cara berbeda yang digunakan anak-anak laki-laki dan perempuan mengembangkan rasa identitas pada tahun-tahun awal hidup mereka.11 Sejak awal, anak-anak perempuan mengalami bahwa mereka ”menyerupai” ibu mereka. Ketika rasa keterikatan dan relasi ini dipindahkan pada orang lain, berkembanglah rasa diri-dalam-hubungan (self-in-relation). Sebaliknya anak-anak laki-laki mengalami bahwa mereka bukan seperti ibu mereka dan dengan demikian mereka dapat mengalami diri-sebagai-terpisah (self-as-separate) berdiri sendiri. Dengan demikian, bagi orang dewasa, pria cenderung mengalami diri sebagai terpisah dan berbeda dari orang lain dan benda-benda di dunia, sementara wanita mengalami diri dan dunia dalam kerangka hubungan. Ini berarti bahwa pria dan wanita mempunyai tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Menurut Chinnici, kedewasaan bagi pria dan wanita terletak pada kemampuan mereka untuk sekaligus berhubungan dan terpisah pada waktu yang bersamaan.... Wanita memandang diri mereka sebagai manusiadalam-hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai diri yang sehat mereka harus didorong untuk mengembangkan kemandirian dan ketegasan-diri. Pria memandang diri sendiri sebagai manusia/sebagai/terpisah dan harus belajar mengembangkan segi kepribadian mereka yang mendorong hubungan.... Perbedaan dalam perkembangan itu penting bagi pemahaman kita, karena, jika pengalaman pria dianggap sebagai normatif, komunikasi masyarakat yang didengar wanita akan berupa pesan yang diperlukan oleh kaum laki-laki, komunikasi yang akan mendorong perkembangan hubungan tetapi yang akan merugikan perkembangan wanita.12 Hermeneutik Feminis Mungkin tantangan yang paling radikal terhadap Kristianitas zaman ini datang dari teologteolog feminis yang menggunakan hermeneutik feminis, yaitu teori penafsiran untuk mendekonstruksikan Perjanjian Baru dan menafsirkan kembali pesan Yesus dalam kerangka keprihatinan feminis. Tidak semua usaha mereka dapat diterima oleh mayoritas orang Katolik. Beberapa teolog bergerak melampaui batas-batas ortodoksi atau sedemikian radikal menafsirkan kembali Kitab Suci sehingga arti rekonstruksinya hanya dapat dimengerti oleh orang yang ahli. Akan tetapi, keekstreman gerakan itu jangan membuat kita buta terhadap pengertian sejati dari studi feminis. Para sarjana Kitab Suci feminis minta agar kita mendekati teks Kitab Suci dengan kesadaran bahwa teks itu dikondisikan bukan hanya secara historis melainkan juga oleh budaya androsentris (yang berpusat pada kaum laki-laki) yang menjadi asalnya.13 Artinya, teksteks Kitab Suci cenderung mencerminkan kepentingan laki-laki, karena ditulis oleh orang-orang laki-laki, diterjemahkan oleh orang-orang laki-laki, dan dalam tradisi selanjutnya ditafsirkan dan dijelaskan oleh orang-orang laki-laki. Misalnya, ada sejumlah pemimpin Kristiani awal yang nama dalam teks-teks awal adalah perempuan, namun dalam teks-teks kemudian nama-nama itu berubah menjadi laki-laki (Junias dalam Surat Kepada Umat Roma 16:7; Nympha/Nymphas dalam Surat kepada Umat Kolese 4:15). Bahkan dewasa ini kita mengira dua murid dalam perjalanan ke Emaus (Luk 24) adalah laki-laki, meski hanya satu orang diketahui laki-laki atau Maria Magdalena adalah seorang pelacur, bahkan jika Kitab Suci tidak pernah menyebutnya demikian. Oleh karena itu, kritik feminis minta agar kita mendekati Kitab Suci dengan ”kecurigaan hermeneutik”, pendekatan kritis terhadap teks yang mengakui bias patriarkal dan berusaha menemukan kembali kisah-kisah wanita yang kerap ditiadakan dalam sejarah Kristiani awal. Mengapa, misalnya, kata diakonos bila diterapkan pada Febe dalam Surat kepada umat Roma 16:1 sedemikian kerap diterjemahkan ”diakones” ketika para ahli sadar bahwa tidak ada diakonos atau diakones dalam Gereja-Gereja tahun 50-an, bahwa diakonos di sini adalah lakilaki, bukan perempuan, dan kata yang sama bila diterapkan pada Paulus selalu diterjemahkan ”pelayan”. Terjemahan yang lebih tepat adalah ”Febe saudari kami yang adalah pelayan Gereja di Kengkrea.” Atau haruslah ”tata tertib rumah tangga” yang tampak pada tulisan-tulisan Perjanjian Baru kemudian (Kol 3:18–4.1; Ef 5:22–6:9; 1Ptr 2:13–3:7; Tit 2:5-9) tidak dimengerti sebagaimana adanya, sebagai peraturan tata tertib rumah tangga yang berasal dari masyarakat RomawiYunani yang ke dalam masyarakat itu Gereja awal berjuang untuk masuk daripada pernyataan wahyu Ilahi yang berlaku selama-lamanya? Peraturan-peraturan itu, yang menekankan bahwa istri tunduk kepada suami mereka, anak-anak menurut kepada orang tua mereka, dan budak taat kepada tuan mereka, merupakan hasil kebudayaan. Para penulis Perjanjian Baru meminjamnya dari lingkungan mereka dengan memberi alasan baru dalam kerangka iman Kristiani. Penulis Surat kepada umat Efesus melihat cinta Kristus kepada Gereja sebagai model bagaimana suami harus mencintai istri (Ef 5:25) dan menyatakan bahwa hubungan antara tuan dan budak harus berbeda bagi orang Kristiani (Ef 6:5-9). Baru berabad-abad kemudian, Gereja menantang perbudakan sebagai lembaga. Pemasukan tata tertib keluarga kafir ke dalam tulisan-tulisan Kristiani itu merupakan contoh-contoh yang baik dan inkulturasi awal, bahkan jika hasilnya adalah menempatkan wanita di tempat bawah, mengurangi kesamaan jenis kelamin yang lebih khas dari jemaat Kristiani awal. Orang harus hati-hati agar tidak memaksa bukti Perjanjian Baru ke arah ini atau itu. Dari satu pihak, Perjanjian Baru tidak mengangkat wanita sebagai Rasul atau menunjukkan wanita memimpin Ekaristi. Perjanjian Baru tidak memberi banyak informasi tentang siapa yang memimpin Ekaristi. Di pihak lain, orang tidak dapat menyatakan secara dogmatik bahwa wanita tidak memegang peran kepemimpinan dalam jemaat Kristiani awal. Fakta bahwa beberapa wanita diketahui sebagai pelayan (Rm 16:1), sebagai tuan rumah untuk berkumpulnya umat lokal (Kol 4:15), sebagai suami yang berkeliling dan istri menjadi rekan sekerja atau penginjil (Rm 16:3-5,7; 1Kor 16:19), menjalankan peran profetis dalam kumpulan umat (1Kor 11:5) atau ”menonjol di kalangan para Rasul” (Rm 16:7) seharusnya membuat orang hati-hati. Juga tidak dapat disangkal bahwa ketika jemaat Kristiani menjadi lebih terstruktur dan terinkulturasi menjelang akhir masa Perjanjian Baru, jemaat juga semakin menjadi membatasi dalam hal apa yang dapat dilakukan wanita. Pemasukan tata tertib rumah tangga seperti disebut di atas, pembatasan istilah ”karisma” pada para pemimpin Gereja, dan perintah yang melarang wanita untuk mengajar (1Tim 2:12) membuktikan hilangnya keterbukaan terhadap pelayanan wanita yang dapat sedikit dilihat pada jemaat-jemaat paling awal. Bahasa yang Inklusif Masalah bahasa yang inklusif, memasukkan jenis kelamin, merupakan masalah yang sulit. (Masalah ini sebetulnya masalah Gereja Barat, khususnya yang berbahasa Inggris, namun baik juga jika kita mengetahui duduk perkaranya.) Bagaimana kita berbicara tentang diri sendiri sebagai jemaat pada waktu berdoa, bagaimana kita menyebut Allah. Banyak orang Kristiani dewasa ini, baik pria maupun wanita, peka terhadap fakta bahwa cara kita menggunakan bahasa agaknya tidak secara khusus mencakup wanita. Bahasa kita menggunakan kata benda umum ”orang” untuk menyebut pria dan wanita. Allah digambarkan dalam istilah-istilah maskulin dan disapa sebagai Bapa, meski kita tahu Allah itu bukan maskulin, laki-laki, maupun feminin, perempuan. Bila bahasa liturgi kita terus berbicara seolah-olah Allah itu laki-laki dan tidak ada usaha memasukkan wanita, banyak objek yang berdasarkan jenis kelamin atau tidak inklusif. Bahasa yang non-inklusif tidak hanya tidak mengenakkan bagi banyak orang, tetapi juga merugikan, karena melestarikan gagasan bahwa jenis kelamin perempuan adalah sekunder dan turunan. Kepekaan akan gender yang rendah ini, digabung dengan fakta bahwa kita seringkali berbicara tentang Allah sebagai maskulin, kita mulai mengalami Allah sungguh sebagai laki-laki, dan mengakibatkan pengalaman kita tentang Allah dan pandangan tentang wanita menjadi terbatas. Bagaimana kita dapat membuat bahasa kita menjadi lebih inklusif?14 Banyak hal yang dapat dilakukan, tanpa mengganti kata Allah menjadi Dewi atau mengganti tanda salib ke dalam istilah-istilah yang bebas jenis kelamin. Langkah pertama adalah berusaha untuk menjadi inklusif, dengan mengatakan”saudara dan saudari” atau ”pria dan wanita”. Kita dapat berusaha untuk menyebut Allah sebagai ”laki-laki”. Kedua, kita perlu mengakui bahwa bahasa kita tentang Allah bersifat metaforis atau analogis. Metafora Allah sebagai Bapa adalah tepat. Istilah itu berakar dalam tradisi Kristiani, berasal dari istilah ”Abba” yang digunakan Yesus dalam doaNya. Akan tetapi, sebutan itu bukan satu-satunya. Ada juga metafora feminin bagi Allah dalam tradisi Kristiani. Allah dikatakan telah melahirkan Israel (Ul 32:18), dan cinta Allah bagi Israel dibandingkan dengan cinta ibu bagi anaknya (Yes 49:15), yang menyarankan bahwa keibuan dapat menggambarkan yang Ilahi seperti juga kebapaan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus membandingkan Allah yang berkarya penuh rahasia di dunia dengan wanita yang menjatuhkan ragi dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya (Mat 13:33). Gereja (Gereja Barat yang berbahasa Inggris) akan terus bergulat dengan masalah bagaimana kita berbicara tentang Allah. Masalah ini bukan tidak berarti. Perlulah menemukan jalan dan cara-cara untuk membuat bahasa, terutama bahasa liturgi, menjadi inklusif dan menemukan kembali dan memasukkan gambaran Allah, yang feminin yang juga merupakan bagian tradisi. Bersamaan dengan itu, kita perlu ingat bahwa sementara kita menggunakan bahasa untuk berbicara tentang Allah, bahasa tentang Allah selalu bersifat metaforis dan tetap melampaui bayangan dan konsep kita. Beberapa teolog wanita berusaha membangun jembatan antara teologi klasik dan feminis;15 bagaimana bahasa berdampak pada imajinasi religius dan membentuk imajinasi religius. Wanita dan Pelayanan Dewasa ini wanita menjalankan banyak peran dan melaksanakan banyak pelayanan yang di masa lampau tertutup bagi mereka. Mereka menjalankan program katekese di paroki-paroki, mengajar teologi di universitas-universitas, sekolah tinggi, seminari-seminari dan memberi bimbingan rohani. Pada tahun 1994, sesudah perdebatan bertahun-tahun, Congregatio de Divinis Officiis (Kongregasi untuk Ibadat) pada akhirnya memutuskan bahwa wanita (termasuk anak-anak perempuan) dapat membantu Misa sebagai putri altar.16 Lebih penting lagi, banyak wanita dewasa ini bertindak sebagai administrator di paroki-paroki yang tidak mempunyai imam yang menetap. Peran mereka juga meliputi tugas pastoral. Tidak mungkinnya wanita ditahbiskan masih merupakan masalah yang sulit dan berat. Gereja resmi tidak melihat bagaimana dapat mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi pelayan Gereja, dengan menyatakan bahwa tradisi Gereja yang tetap melawan, bahwa Yesus tidak memanggil wanita di antara 12 Rasul-Nya, dan bahwa imam, untuk bertindak secara sakramental In persona Christi (menggantikan Kristus), haruslah laki-laki seperti Kristus sendiri.17 Akan tetapi, argumen melawan tahbisan wanita tidak meyakinkan bagi banyak orang Katolik, termasuk banyak teolog Katolik. Bersamaan dengan itu, gelombang pendapat umum menunjukkan kesediaan yang semakin meningkat untuk menerima pelayanan wanita yang ditahbiskan. Paus Yohanes Paulus II berusaha menghentikan pembicaraan mengenai masalah itu dalam Ordinatio Sacerdotalis, deklarasi yang diterbitkan tahun 1994, dengan menyatakan bahwa ”Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman” (no. 4).18 Apakah akan ada perkembangan dalam masalah ini? Jika masa depan sulit diramalkan, sulit juga mengatakan dengan pasti bahwa Gereja pada akhirnya akan berbuat sesuatu atas masalah itu. Mereka yang berusaha berbuat demikian di masa lampau kerap kali terbukti salah. Banyak Gereja Kristiani dewasa ini menerima begitu saja tahbisan wanita. Jika Gereja Katolik berharap untuk suatu saat hidup dalam kesatuan dengan Gereja-Gereja itu, pada akhirnya dapat memikirkan kembali ketidakmampuannya menemukan tempat bagi wanita dalam pelayanan Gereja yang ditahbiskan. Pengasingan yang dialami oleh banyak wanita Katolik dewasa ini amatlah nyata; Menyedihkan bukan hanya bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi banyak pria. Mereka yang mencintai Gereja dan menyadari kemungkinan-kemungkinan serta kebutuhan-kebutuhannya, risau pada waktu melihat wanita yang berbakat dan berdedikasi melepaskan usaha mereka untuk melayani dalam Gereja atau bergabung dengan Gereja-Gereja lain. Mereka merasa sedih atas wanita-wanita itu dan susah karena Gereja dan kesaksiannya berkurang karena pengasingan, amarah, luka hati, dan kehilangan. Pentinglah menanggapi keprihatinan wanita dan pria itu. Satu hal pasti, gerakan wanita sudah mengubah Gereja dan terus akan mendatangkan pembaruan dalam tahun-tahun yang akan datang. 4. Ekumenisme Gereja Katolik yang terlambat bergabung dengan gerakan ekumenis, sesudah Konsili Vatikan II, giat terlibat dalam gerakan itu. Di bawah pengarahan Sekretariat untuk memajukan kesatuan Kristiani, sekarang diganti namanya menjadi Dewan Kepausan untuk Meningkatkan Kesatuan Kristiani, Gereja Katolik melakukan dialog bilateral secara resmi dengan kebanyakan Gereja dunia. Dialog-dialog itu meliputi dialog dengan Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma, Komisi Gabungan Internasional Katolik Roma-Lutheran, maupun dengan Gereja-Gereja Ortodoks, Dewan Metodis Dunia, Perserikatan Gereja-Gereja Reformasi Dunia, Perserikatan Gereja Baptis, Gereja-Gereja Pentekosta, Para Murid Yesus, sedang dengan Gereja-Gereja Evangelis masih pada tahap-tahap awal. Kelompok Kerja Gabungan didirikan di antara Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang berkantor pusat di Jenewa dan di Roma; dan teolog-teolog Katolik menjadi anggota Komisi Iman dan Tatanan Dewan Gereja-Gereja Dunia. Selama tiga puluh tahun sejak Konsili Vatikan II berakhir telah tercapai banyak perkembangan dalam pernyataan-pernyataan yang disetujui bersama. Bagaimana keadaan gerakan ekumenisme menjelang abad ke-21 ini? Milenium (sepuluh abad) pertama merupakan abad-abad di mana Gereja bersatu tak terbagi. Gereja Katolik dan universal memahami diri dan berfungsi sebagai kesatuan Gereja-Gereja. Pada Milenium kedua persatuan Gereja pecah, pertama perpecahan Gereja Timur dan Barat, secara tradisional mulai tahun 1054 ketika Michael Cerularius dan utusan Paus Leo IX saling mengekskomunikasikan. Kedua, pada abad 16, protes Luther di Jerman mengakibatkan Reformasi Protestan dan perpecahan baru kesatuan Gereja di Barat. Apakah milenium ketiga akan menyaksikan pemulihan kesatuan antar Gereja-Gereja yang terpecah itu? Pada saat ini tanda-tandanya tidak amat bagus. Dewasa ini ada perasaan yang kuat bahwa gerakan ekumenis telah kehilangan momentumnya. Sejumlah pengamat telah mengamati bahwa kegairahan yang ditimbulkan oleh Konsili Vatikan II telah pudar menjadi rasa kecil hati karena sedemikian banyak harapan yang tak terpenuhi. Paus Yohanes Paulus telah membuat beberapa isyarat yang dramatis, dengan mengunjungi Uskup Agung Canterbury di katedralnya, Markas Besar Dewan Gereja-Gereja Dunia di Jenewa, dan sinagoga Yahudi di Roma, kunjungan pertama yang pernah dilakukan oleh Paus. Akan tetapi, isyarat-isyarat itu kebanyakan masih tetap bersifat simbolis dan ada kesan bahwa Yohanes Paulus lebih tertarik dalam menegaskan kembali disiplin dan keutuhan doktrinal dalam Gereja Katolik. Lalu, ke mana kegiatan-kegiatan dan dialog ekumenis yang telah dilakukan bertahun-tahun itu mengarah? Perbedaan-Perbedaan di Masa Lampau Salah satu prestasi yang paling berarti dari gerakan ekumenis adalah kesepakatan yang luas yang telah dicapai tentang masalah-masalah yang memecah Gereja-Gereja sejak abad ke16: ajaran tentang pembenaran, hakikat Ekaristi, teologi, dan struktur pelayanan yang ditahbis- kan, pelaksanaan otoritas, lembaga keuskupan bahkan tentang masalah kedudukan utama Paus.19 Lebih tepat dikatakan bahwa telah terjadi banyak kemajuan selama bertahun-tahun atau kesepakatan yang dicapai para wakil Gereja dan teolog, tetapi kesepakatan itu belum diterima secara resmi oleh Gereja-Gereja yang mensponsori mereka. Sesudah 16 tahun bekerja, Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma menemukan ”kesepakatan substansial” tentang Ekaristi, dan pelayanan dan kesatuan pandangan tentang otoritas. Para Anggota Komisi telah menyatakan bahwa dalam setiap kesatuan seluruh jemaat Kristiani kedudukan utama universal yang melayani kesatuan Gereja-Gereja harus dilakukan oleh Takhta Suci Roma, satu-satunya takhta yang sudah dan masih melaksanakan 20 pelayanan itu. Dialog Lutheran-Katolik Roma (di Amerika Serikat) telah menerbitkan seri pernyataanpernyataan yang sudah disetujui tentang Syahadat, Ekaristi sebagai korban, pelayanan, pelayanan Petrus, infalibilitas, pembenaran, maupun Maria dan para kudus. Orang Lutheran telah berbicara tentang ”fungsi Petrus”, pelayanan kesatuan demi Gereja keseluruhan. Dialog Lutheran-Roma Katolik itu telah mengungkapkan minat dalam hal kedudukan utama Paus yang diperbarui berdasarkan Injil demi Gereja masa depan.21 Berkenaan dengan masalah sulit tentang pembenaran oleh iman, dialog menemukan ”kesepakatan fundamental tentang Injil” (no. 163), meski dialog itu mengakui masih ada perbedaan-perbedaan dalam rumusan-rumusan teologis dan pendekatan-pendekatan pastoral (no. 157).22 Laporan lain, yang diterbitkan di Jerman pada tahun 1988 oleh Kelompok Studi Ekumenis, yang diketuai oleh seorang Kardinal Roma Katolik dan seorang Uskup Lutheran, menyatakan bahwa penghukuman orang Protestan dan orang Katolik Roma yang dijauhkan satu sama lain pada abad ke-16 kerap terjadi karena salah pengertian dan jangan dianggap memecah Gereja.23 Berdasarkan konsultasi internasional uskup-uskup dan teolog-teolog Katolik dan Lutheran yang bertemu di Florida pada tahun 1993, dua tradisi bekerja untuk menyusun deklarasi bahwa penghukuman sudah tak dapat diterapkan lagi. Mungkin dokumen ekumenis yang paling berarti sejak Konsili Vatikan II menerbitkan Dekrit tentang Ekumenisme adalah teks Dewan Gereja-Gereja Dunia Baptism, Eucharist, and Ministry (Baptis, Ekaristi, dan Pelayanan) yang dikeluarkan tahun 1982, disetujui oleh Komisi Iman dan Tatanan pada pertemuan pertamanya di Lima, Peru. Dokumen itu, hasil kerja selama lebih dari 50 tahun, memuat pengertian bersama mengenai baptis, Ekaristi, dan pelayanan yang sampai tingkat yang mengesankan, memasukkan pendirian-pendirian doktrinal dan pokok perhatian Gereja-Gereja yang berbeda. Dokumen itu juga memberi bukti tumbuhnya kesepakatan tentang masalah otoritas. Dokumen itu melihat pergantian uskup secara historis ”sebagai tanda, meskipun bukan jaminan, dari kelangsungan dan kesatuan Gereja” (M. no. 38) dan menyarankan agar Gereja-Gereja yang tidak mempunyainya ”mungkin perlu menemukan kembali jejak penggantian uskup” (M. no. 536). Apa yang tidak dapat diterima oleh dokumen itu adalah setiap saran bahwa pelayanan dianggap tidak berlaku sampai masuk ke garis penggantian uskup (M. no. 38). Tanda kemajuan lain yang membesarkan hati adalah minat baru pada ekumenisme oleh Gereja-Gereja Evangelis dan Pentekosta, sekurang-kurangnya pada belahan bumi utara. Dialog internasional Katolik Roma dan Pentekosta yang diawali pada tahun 1972 telah menghasilkan saling pengertian yang makin besar pada kedua belah pihak. ”Umat Pentekosta telah ditanya oleh pasangan dialog mereka, Katolik Roma, yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya dan telah menantang mereka untuk menjadi lebih jelas dalam ungkapan teologis dan penafsiran Kitab Suci mereka. Orang Pentekosta dalam dialog itu menemukan bahwa orang Katolik Roma adalah orang Kristiani,” kesan salah seorang teolog Pentekosta.24 Berbagai Masalah Baru Jika banyak kesepakatan telah dicapai atas banyak masalah yang telah memecah GerejaGereja, paruh kedua abad ke-20 telah menyaksikan perpecahan-perpecahan baru muncul yang membuat Gereja-Gereja menjadi terpisah seperti sebelumnya. Di antara perpecahanperpecahan itu yang paling menonjol adalah masalah-masalah etika dan tempat wanita di dalam Gereja. Fakta bahwa Gereja-Gereja pada umumnya telah menggali perbedaan-perbedaan mereka tentang masalah-masalah etika dapat menjadi petunjuk bahwa Gereja-Gereja itu secara tersirat menyadari adanya jarak yang besar satu sama lain dalam bidang itu. Tambahan pula, GerejaGereja itu kerap berbeda pendapat tentang bagaimana masalah-masalah khusus harus ditentukan. Misalnya, apakah masalah pengguguran merupakan masalah hidup manusia atau hak wanita? Ada perbedaan-perbedaan besar terhadap masalah-masalah seperti perceraian dan pernikahan kembali, pengguguran, pengaturan kelahiran, seks di luar nikah, hubungan homoseksual, teknologi reproduksi baru, orang tua pengganti, dan sterilisasi (pemandulan). Masalah tahbisan wanita, yang diterima begitu saja dalam banyak Gereja dewasa ini, mungkin merupakan halangan yang paling besar bagi rekonsiliasi Gereja-Gereja dan ikut ambil bagian dalam sakramen-sakramen sebagai kelanjutannya. Gereja-Gereja yang telah menahbiskan wanita tidak akan mengubah kembali keputusan-keputusan yang sudah dibuat berdasarkan refleksi, doa dan penegasan teologis yang lama. Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Ortodoks berbeda pendapat dalam hal tahbisan wanita atas dasar apa yang dianggap merupakan tradisi kuno Gereja. Bahkan jika Gereja-Gereja secara resmi menerima kesepakatan yang muncul dari dialog-dialog, masalahnya tetap bagaimana Gereja-Gereja yang tidak dapat menerima tahbisan wanita dapat bersama-sama merayakan Perjamuan Ekaristi dengan Gereja-Gereja yang menerimanya? Situasinya ada dalam keadaan macet. Masalah-masalah etika dan gerejawi itu dapat menjadi tumit Achilles gerakan ekumenis. Ada bahaya nyata dewasa ini bahwa perasaan-perasaan umat yang dibangkitkan oleh masalah-masalah itu dapat mengakibatkan mentalitas satu – masalah, misalnya, tentang tahbisan wanita atau hak hidup anak yang belum lahir. Mentalitas semacam itu dapat menjadi semacam lakmus tes untuk keterlibatan ekumenis, yang membuat dialog mustahil dan mengandung bahaya perpecahan-perpecahan baru yang lebih parah. Bersamaan dengan itu, keseriusan masalah-masalah itu janganlah membuat kita buta akan perlunya dapat hidup dengan perbedaan-perbedaan kuat terhadap masalah-masalah itu. Pertemuan ekumenis tidak berarti bahwa setiap orang harus percaya, berpikir, dan berbuat yang sama. Perlunya pertemuan itu adalah untuk menemukan apa yang dimiliki bersama meskipun ada perbedaan-perbedaan dan bekerja untuk mencapai rekonsiliasi. Harus juga diakui bahwa ada perbedaan-perbedaan besar tentang masalah-masalah itu dewasa ini, bukan hanya di antara berbagai tradisi tetapi juga dalam suatu Gereja tertentu. Arah Masa Depan Jika dewasa ini ada tantangan-tantangan baru untuk rekonsiliasi Gereja-Gereja, juga jelas bahwa sejumlah arah ke masa depan muncul dari pertemuan dan dialog selama lebih dari 30 tahun ini. Gerakan ekumenis telah menunjukkan bahwa prinsip Ecclesia semper reformanda (Gereja selalu harus diperbarui) berlaku bagi semua Gereja, Protestan, maupun Katolik serta Ortodoks. Mungkin sekali kekurangan gerakan yang tampak jelas dewasa ini menunjukkan bahwa kegairahan semula yang mengikuti Konsili telah berubah menjadi pengakuan yang lebih tenang dan realistis bahwa Gereja-Gereja membutuhkan waktu untuk menilai dan menyaturagakan kemajuan yang telah dibuat maupun langkah-langkah positif menuju ke pembaruan dan penemuan kembali tradisi. Setiap Gereja akan dipanggil untuk mencapainya. Gereja-Gereja Protestan aliran utama sedang ditantang oleh dialog ekumenis untuk memperbarui struktur pelayanan dan otoritas mereka. Teks Baptism, Eucharist and Ministry terbitan Dewan Gereja-Gereja Dunia menyarankan bahwa pengambilan kembali tanda kesatuan dengan Gereja kuno melalui tahbisan dalam penggantian uskup historis mungkin diperlukan. Yang lain, kesepakatan-kesepakatan bilateral seperti, Facing Unity, laporan KatolikLutheran, dan Niagara Report antara Anglikan-Lutheran, mengajak pelaksanaan bersama jabatan uskup, termasuk tahbisan bersama, yang akan menghasilkan terciptanya pelayanan yang diakui bersama.25 Gereja-Gereja Evangelis dan Pentekosta dipanggil untuk memperoleh kembali tradisi liturgis dan sakramental Gereja kuno, terutama sentralitas Ekaristi. Gereja-Gereja itu perlu menemukan suatu cara untuk memberi ungkapan institusional bagi universalitas dan katolisitas Gereja. Gereja-Gereja Katolik dan Ortodoks dipanggil untuk mengubah cara otoritas dilaksanakan, sehingga keputusan-keputusan dibuat dengan cara yang sungguh-sungguh kolegial dan entah bagaimana caranya mengikutkan awam. Gereja-Gereja itu sebaiknya mengakui autentisitas pelayanan yang ditahbiskan dalam Gereja-Gereja lain, meski pelayanan itu tidak mempunyai tanda kelanjutan dengan Gereja kuno melalui tahbisan dalam penggantian uskup. GerejaGereja itu sebaiknya menerima keanekaragaman yang lebih besar dalam teologi, spiritualitas, dan hidup Gereja dan mengakui bahwa warisan ajaran dari satu Gereja tidak dipaksakan pada yang lain. Gereja-Gereja itu pada akhirnya sebaiknya dapat menerima tahbisan wanita, meskipun ini merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh Gereja, bukan hanya oleh satu Gereja. Akhirnya Gereja-Gereja ditantang untuk melaksanakan ekumenisme secara lebih serius pada tingkat lokal. Ekumenisme resmi dari para pemimpin Gereja tidak berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan ekumenisme di tingkat bawah, karena rekonsiliasi tidak akan terjadi sampai orang-orang Kristiani dari Gereja-Gereja yang berbeda dapat saling mengakui bahwa mereka mempunyai iman yang sama. Perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan antargereja, antara umat lokal dan Gereja-Gereja dari tradisi-tradisi yang berbeda yang menjanjikan saling kerja sama, doa bersama, dan bila mungkin, pelayanan bersama, dapat mengungkapkan kebersamaan iman dan menjadi langkah yang berarti menuju ke rekonsiliasi dan kesatuan penuh. Gereja-Gereja juga harus bekerja sama untuk menemukan cara guna mengungkapkan kembali pesan Injil dalam bahasa yang dapat menyapa harapan-harapan dan keinginankeinginan terdalam manusia zaman ini. Orang-orang Kristen evangelis biasanya menggunakan bahasa yang amat individualistis, dengan membicarakan keselamatan pribadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Orang-orang Katolik kelas menengah dan orang-orang Protestan dari aliran utama kerap memahami hidup baru dalam Kristus secara terapetis, dalam kerangka penyembuhan luka-luka psikologis, perilaku adiktif, dan keluarga atau masyarakat yang disfungsional. Orangorang Kristiani lain menafsirkan Injil dalam kerangka pembebasan dari ketidakadilan dan struktur-struktur sosial yang menindas dan dari diskriminasi melawan kelompok-kelompok tertentu – wanita, kaum homo, dan lesbian, etnik minoritas. Gereja masa depan membutuhkan bahasa Injil yang mengakui dosa pribadi dan sosial, yang mengintegrasikan moralitas pribadi dan keadilan sosial, rahmat dan inisiatif manusia, evangelisasi dan pembangunan kembali masyarakat. Gereja Masa Depan Bagaimana Gereja masa depan dapat dibayangkan? Gereja Katolik dewasa ini harus kembali ke konsep Gereja sebagai koinonia, kesatuan, atau persekutuan yang merupakan pemahaman dirinya selama milenium pertama. Sebagai kesatuan, Gereja memiliki unsur yang kelihatan dan tidak kelihatan. Secara tidak kelihatan, kesatuan Gereja didasarkan atas penghayatan hidup bersama dengan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Secara kelihatan, hidup bersama itu diwujudkan melalui struktur-struktur sakramental dan institusional – terutama baptis, Ekaristi, dan ikatan persekutuan dari Gereja-Gereja partikular yang kelihatan. Setiap Gereja lokal atau partikular, agar menjadi Gereja yang penuh, harus menjadi bagian kesatuan. Ciri autentik dari Gereja-Gereja yang bersangkutan dalam milenium pertama ditunjukkan justru oleh tanda-tanda communio kesatuan yang kelihatan yang menyatukan Gereja-Gereja menjadi Ecclesia Catholica. Dalam eklesiologi komunal ini, Paus telah memiliki dan terus akan memiliki peran penting untuk dimainkan. Justru melalui kesatuan dengan Uskup Roma, uskup dan Gereja partikular tampak secara kelihatan dalam kesatuan dengan Gereja Katolik, kesatuan Gereja-Gereja. Dewasa ini semakin bertambah jumlah orang-orang Kristen Protestan yang mengakui pentingnya peran yang harus dimainkan oleh Uskup Roma dalam Gereja masa depan. Orangorang Anglikan dan Lutheran bersedia mempertimbangkan pelayanan Paus atau Petrus, yang diperbarui menurut Injil, seperti sudah kita lihat. Pada suatu saat, Uskup Roma dapat dipilih oleh para wakil Gereja Roma (yang pada awalnya adalah Kardinal) maupun oleh ”beberapa wakil Gereja Waldesian, Anglikan, Baptis, Lutheran, dan Ortodoks yang melayani jemaat di Roma – bagaimanapun bukan para administrator Gereja yang tidak mempunyai tanggung jawab atas umat lokal”.26 ”Hanya Roma memiliki otoritas tradisional, eklesiologis, dan moral untuk bekerja menyatukan Gereja.” Akan tetapi, yang mengecewakan sesudah selama sekian tahun dialog dan sedemikian banyak kemajuan adalah bahwa ”Roma belum berhasil menemukan cara untuk membuka kembali bendungan kuno sehingga air kesatuan yang mengalir dari sumbernya dapat mengalir lagi kepada saudari-saudarinya yang terdampar dan terasing.”27 Rekonsiliasi GerejaGereja agaknya menunggu tindakan dari pihak Roma. Paus Yohanes Paulus II mengambil langkah penting ke arah itu dan ensikliknya tentang ekumenisme, Ut Unum Sint,28 yang diterbitkan pada tahun 1995. Tanpa memperkecil masalah-masalah yang ada, Paus Yohanes Paulus mencatat bahwa dialog telah dan terus berbuah dan penuh janji? (no. 69), dan ia mengajak para wakil Gereja-Gereja lain untuk bergabung dengannya dalam mencari ”cara untuk menjalankan primasi, kedudukan utama yang, tanpa meniadakan apa yang hakiki bagi perutusannya, namun terbuka terhadap situasi baru? (no. 95). 5. Dialog Antaragama Dokumen Konsili yang paling pendek, Deklarasi tentang Hubungan Gereja dengan AgamaAgama non-Kristiani (Nostra Aetate) dapat menjadi salah satu dari dokumen Konsili yang paling penting. Sejarahnya rumit. Keinginan Paus Yohanes XXIII agar Konsili memuat pernyataan tentang hubungan Yahudi-Katolik pada awalnya merupakan bagian dari Dekrit Konsili tentang Ekumenisme. Kemudian uskup-uskup memutuskan agar disiapkan pernyataan terpisah tentang hubungan Yahudi-Kristiani. Pada akhirnya, pernyataan Yahudi-Kristiani diperluas dan meliputi hubungan dengan agama-agama dunia.29 Untuk pertama kalinya Gereja Katolik menerima adanya kebenaran dalam agama-agama besar dunia, dengan secara khusus menyebut Hinduisme, Budhisme, dan Islam. ”Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu apa yang benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar Kebenaran, yang menerangi semua orang.” (NA 2) Dalam dokumen itu, ada bagian khusus yang diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Sambil mengingat ”hubungan rohani” yang mengikat orang-orang Kristiani dan orang-orang Yahudi, deklarasi mengajak untuk saling memahami, menghormati, dan berdialog, dan ”sangat menyesalkan kebencian antisemitisme terhadap bangsa Yahudi kapan pun dan oleh siapa pun itu dijalankan” (NA 4). Dengan menerbitkan Nostra Aetate, Gereja telah amat maju bergerak dari ajaran tradisionalnya bahwa tak ada orang di luar Gereja dapat diselamatkan ke pengakuan bahwa kebenaran juga tercermin dalam agama-agama besar dunia, dan mereka yang bekerja sama dengan rahmat Allah dapat diselamatkan. Ini merupakan pendirian yang ”inklusif”, lebih toleran daripada pendekatan ”tak ada keselamatan di luar Gereja” tetapi masih mengakui pernyataan Kristianitas sebagai pewahyuan definitif keselamatan Allah. Apakah Agama-agama Lain Menyelamatkan? Para Bapa Konsili tidak secara eksplisit menyangkut masalah nilai penyelamatan agamaagama besar lain. Akan tetapi, masalah itu telah semakin dibicarakan sesudah Konsili. Pasti sulitlah untuk mempertahankan bahwa Kristianitas merupakan satu-satunya jalan keselamatan bila agama itu hanya dianut oleh 1/3 penduduk dunia. Namun, banyak orang Kristiani mendapatkan bahwa penilaian kembali atas kebenaran dan nilai penyelamatan agama-agama non-Kristiani sulit diterima. Teologi Katolik masih mempertahankan bahwa keselamatan dunia telah dicapai satu kali untuk selama-lamanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Konsili mengajak Gereja memasuki dialog yang sejati dengan para wakil tradisi-tradisi agama lain. Dialog dan Magisterium Dalam dokumennya tentang evangelisasi, Evangelium Nuntiandi, yang terbit pada tahun 1975, Paus Paulus VI mengatakan tentang agama-agama non-Kristiani sebagai mengandung ”gema pencarian Allah yang sudah berlangsung selama ribuan tahun.” Ia memuji nilai-nilai spiritual, dengan menyebut agama-agama itu sebagai ”benih-benih sabda” dan ”persiapan untuk Injil.” Tetapi ia juga menekankan hakikat pernyataan khusus Kristianitas atas kebenaran dengan menyatakan bahwa ”agama kami secara efektif menciptakan hubungan yang autentik dan hidup dengan Allah yang agama-agama lain belum berhasil menciptakan, meski agamaagama itu seolah-olah telah merentangkan lengan ke surga” (no. 53). Paus tidak hanya menaruh perhatian agar penghargaan baru terhadap agama-agama lain tidak sedikitpun mengurangi karya evangelisasi Gereja. Dalam menegaskan kembali bahwa Yesus datang untuk mewahyukan ”jalan-jalan keselamatan yang biasa” (no. 80), Paus agaknya menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa agama-agama dunia merupakan jalan-jalan keselamatan yang biasa bagi para pemeluknya. Paus Yohanes Paulus II menghargai agama-agama non-Kristiani namun tidak terlalu jauh sampai mengakui bahwa agama-agama itu menyelamatkan. Ia berpegang secara teguh pada sentralitas mutlak Kristus pada ensikliknya tentang misiologi, Redemptoris Missio, yang dikeluarkan pada tahun 1990. Dalam ensiklik itu, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa: ”Kristus adalah satu-satunya penyelamat bagi semua, satu-satunya yang dapat mewahyukan Allah dan membawa kepada-Nya” (no. 5). Seperti Paus Paulus VI, ia menekankan ”bahwa Gereja merupakan sarana keselamatan yang biasa” (no. 55). Akan tetapi, Paus Yohanes Paulus II juga melihat tanda-tanda karya Roh di dalam agama-agama lain. Ia telah pergi untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agama lain dan menegaskan bahwa dialog antaragama merupakan bagian dari pengutusan penginjilan Gereja (no. 55). Jika ajaran-ajaran Paus Yohanes Paulus II tentang evangelisasi dipelajari sungguhsungguh, kita menemukan bahwa meskipun tidak secara eksplisit mengakui agama-agama lain sebagai perantara keselamatan bagi para penganutnya, Paus Yohanes Paulus dapat mengakui agama-agama itu sebagai ”bentuk-bentuk perantaraan yang dipartisipasikan”, tergantung pada perantaraan Kristus sendiri. Namun demikian, ia merasa bahwa hal ini merupakan masalah yang perlu dipelajari dan direnungkan lebih lanjut sebelum magisterium mengambil pendirian tertentu. Dialog antaragama akan terus menantang Gereja, meski pentingnya tidak selalu diakui oleh orang-orang Kristiani di Eropa dan Amerika Utara dan Selatan. Akan tetapi di Asia, India, bagian-bagian tertentu Afrika, di mana jumlah orang-orang Kristiani bukan hanya minoritas, tetapi minoritas yang terancam, dialog antaragama merupakan kebutuhan yang mendesak dan nyata-nyata terasa. Dialog antaragama dapat menjadi salah satu masalah penting dalam agenda Gereja pada abad ke-21. 6. Kesimpulan Gereja Katolik menjelang milenium ke-3 amatlah berbeda dari Gereja pada awal abad ke20. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, Gereja telah mengalami kekacauan dan perubahan jauh lebih banyak daripada umat-umat agama lain, berkat kebijaksanaan Paus Yohanes XXIII yang mengundang Gereja untuk meluangkan waktu guna melakukan pemeriksaan diri secara intensif dan pembaruan. Konsili Vatikan II jelas merupakan Konsili tentang Gereja itu sendiri. Konsili itu dimaksudkan agar Gereja dapat mendayagunakan tradisi, studi, dan tenaga para anggotanya untuk secara sadar mengadakan pembaruan daripada sekadar membiarkan diri ikut terseret angin perubahan. Akan tetapi, arus-arus pembaruan yang didatangkan oleh Konsili belum mendapatkan jalannya. Sesungguhnya, aliran-aliran pembaruan itu tampaknya melampaui kemampuan para pemimpin Gereja untuk mengendalikan atau menyalurkannya. Gereja dewasa ini menghadapi tantangan-tantangan yang tak kalah besarnya seperti tantangan-tantangan pada zaman-zaman lain. Beberapa tantangan itu menyangkut kehidupan Gereja ke dalam, masalah-masalah seperti keikutsertaan dalam liturgi, kekurangan imam, hak umat untuk merayakan Ekaristi, gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, kemungkinan awam ikut terlibat dalam pembuatan keputusan Gereja dan dalam perumusan ajarannya, meninjau kembali cara kita menyebut Allah, mengizinkan wanita untuk ikut ambil bagian dalam hidup dan pelayanan Gereja. Pada waktu mayoritas penduduk Katolik dunia bergeser dari Eropa dan Amerika Utara ke Afrika dan Asia dan belahan bumi bagian Selatan, semakin pentinglah memungkinkan Gereja-Gereja baru itu mengungkapkan hidup gerejawi dan iman mereka dalam kerangka budaya mereka sendiri, untuk mengimbangi secara lebih memadai universalitas dan partikularitasnya. Tantangan-tantangan lain berkaitan dengan hubungan Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Kristen, iman religius lain, dan dunia. Gereja perlu mempertimbangkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menciptakan rekonsiliasi Kristiani agar Gereja-Gereja lain dapat ikut serta menikmati tradisi Katolik secara penuh tanpa menolak warisan-warisan mereka yang khusus. Gereja perlu terlibat ke dalam dialog yang konstruktif dan sungguh-sungguh timbalbalik dengan agama-agama lain, dan mengembangkan bahasa evangelisasi yang dapat dipercaya dalam dunia yang terpecah-pecah dan tersekularisasikan. Apakah Gereja akan mampu membawa pesan Yesus yang menebus dan memerdekakan dunia di mana ditemukan sedemikian banyak ketidakadilan dan penderitaan sehingga jutaan orang miskin mendapat bagian yang lebih memadai dalam menikmati kekayaan bumi? Apakah Gereja akan dapat menemukan di dalam visi sakramentalnya tentang ciptaan, sumber daya bagi hidup biologi planet yang terancam? Apakah Gereja akan mampu membawa visi Katolik tentang universalitas, komprehensivitas dan inklusivitasnya pada masyarakat dan bangsa-bangsa abad ke-21 yang saling bersaing? Atau apakah Gereja akan menjadi gerakan sektarian, yang hanya menaruh perhatian pada kelangsungan lembaganya sendiri saja? Cara Gereja menanggapi masalah-masalah itu akan menentukan kelangsungan hidupnya pada milenium ketiga. Gereja akan terus memaklumkan kabar gembira tentang keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, karena kehidupan yang sebenarnya bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari kehadiran Kristus yang telah bangkit di tengah-tengah jemaat yang berkumpul atas nama-Nya. Apa yang dikatakan St. Paulus tentang pelayanan Gereja dapat dikatakan juga tentang hidup Gereja: ”Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami” (2Kor 4:7). Gereja sendiri adalah bejana yang mudah pecah. Jika ingin secara efektif menjadi sakramen kesatuan umat manusia (LG 1) dalam abad ke-21 seperti dibayangkan oleh Konsili, Gereja harus terus memperbarui hidup dan struktur-strukturnya. Hal itu tidak pernah mudah. Itu berarti mau mati terhadap yang sudah ada supaya hidup baru dilahirkan. Ini merupakan misteri Paskah. Tentu saja pembaruan struktur-struktur otoritasnya akan terus menjadi masalah sentral bagi Gereja dalam abad ke-21. Akan tetapi, kata-kata St. Paulus juga mengingatkan akan janji atas kehadiran Allah. Itulah kekuatan Gereja dan harapannya. Catatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Lihat Gabriel Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism. (Oxford: Clarendon, 1980) 187. Lihat Michael J. Walsh ”The Conservative Reaction,” Modern Catholicism: Vatican II and After, ed. Adrian Hastings (New York: Oxford Univ. Press, 1991) 283-288. Heinrich Fries, Suffering from the Church: Renewal or Restoration? (Collegeville: The Liturgical Press, 1995). Bdk. Bob Hurd, ”Liturgy and Empowerment: The Restoration of the Liturgical Assembly” That They Might Live: Power, Empowerment, and Leadership in the Church, ed. Michael Downey (New York: Crossroad, 1991) 132. Lihat Thomas P. Rausch, Priesthood Today: An Appraisal (New York: Paulist, 1992). John Coleman ”Not Democracy but Democratization,” A Democratic Catholic Church, ed. Eugene C. Bianchi, and Rosemary Radford Ruether (New York: Corrsroad, 1992) 233. J. Migne, PL 50, 434. Ibid., 54, 634. James Hennesey, ”Rome and the Origins of United States Hierarchy,” The Papacy and the Church in the United States, ed. Bernard Cooke (New York: Paulist, 1989) 90-92. Rosemary Chinnici, Can Women Re-Image the Church? (New York: Paulist, 1992) 11. Lihat misalnya, Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1982). 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Rosemary Chinnici, Can Women Re-Image the Church? 14. Lihat Elisabeth Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Reconstruction of Christian Origins (New York: Crossroad, 1983). Buku yang membantu adalah Thomas H. Groome Language for a ”Catholic” Church (Kansas City: Sheed & Ward, 1955). Lihat Elizabeth A. Johnson, She Who is (New York: Crossroad, 1992); Sandra M. Schneiders, Women and The Word (New York: Paulist 1986). Lihat ”Use of Female Altar Servers” Origins 23 (1994) 779. Lihat Congregatio de Doctrina Fidei, Congregation for the Doctrine of Faith, Declaration on the Question of the Admission of Women to the Ministerial Priesthood (Washington: USCC, 1977). Origins 24 (1994) 49-52. Lihat George Weigel, ”Re-viewing Vitican II: An Interview with George A. Lindbeck,” First Things 48 (December 1994) 48. ”Authority in the Church I” (no. 23); teks dalam Komisi Internasional Anglikan – Katolik Roma, The Final Report (Washington: USCC, 1982) 64. Paul C. Empie dan T. Austin Murphy, eds., Lutheran and Catholics in Dialogue V: Papal Primacy and the Universal Church (Minneapolis: Augsburg, 1974) no. 32. H. George Anderson, T. Austin Murphy, and Joseph A. Burgess, eds., Justification by Faith: Lutherans and Catholics in Dialogue VII (Minneapolis: Augsburg, 1985). Karl Lehmann and Wolfhart Pannenberg, eds., The Condemnations of the Reformation Era: Do They Still Divide? (Minneapolis: Fortress, 1990). Jerry Sandidge, ”The Pentecostal Movement and Ecumenism: An Update, Ecumenical Trends 18 (1989) 103 (huruf miring adalah asli). Roman Catholic – Lutheran Joint Commission, Facing Unity: Models, Forms, and Phases of Catholic-Lutheran Fellowship (Geneva: Lutheran World Federation, 1985); Anglican – Lutheran Consultation, Niagara Report (London: Church Publishing House, 1988). Gordon Lathrop, Holy Things: A Liturgical Theology (Minneapolis: Fortress, 1993) 200-201. Mark Chapman, ”Rome and the Future of Ecumenism: Rome as the Future of Ecumenism,” Ecumenical Trends 23 (1994) 8/40. Origins 25 (1995) 49-72. Lihat John M. Oesterreicher, ”Declaration on the Relationship of the Church to Non-Christian Religions,” Commentary on the Documents of Vatican II, ed. Herbert Vorgrimmler (New York: Herder & Herder, 1969) 1-36. Paul Knitter, ”Christian Salvation: Its Nature and Practice An Interreligious Proposal,” New Theology Review 7/4 (1994) 43. Daftar Pustaka Abbott, Walter M., ed. The Documents of Vatikan II. New York: The America Press, 1966. Bokenkotter, Thomas, Essential Catholicism: Dynamics of Faith and Belief. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1985. Brown, Raymond E., Joseph A. Fitzmyer, dan Roland E. Morphy, ed. The New Jerome Biblical Commentary. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1990. –––––,Catechism of the Catholic Church. Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1994. Cunningham, Lawrence. The Catholic Faith: An Introduction. New York: Paulist, 1987. Downey, Michael, ed. The New Dictionary of Catholic Spirituality. Collegeville: The Liturgical Press, 1993. Dulles, Avery. The Chatolicity of the Church. Oxford: Clarendon, 1985. –––––,Models of the Church. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974. Dwyer, Judith A., ed. The New Dictionary of Catholic Social Thought. Collegeville: The Liturgical Press, 1994. Eagan, Joseph F. Restoration and Renewal? The Church in the Third Millennium. Kansas city: sheed and Ward, 1995. Fink, Peter, ed. The New Dictionary of Sacramental Worship. Collegeville: The Liturgical Press, 1990. Flannery, Austin, ed. Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents. 2 volume. Northport, N.Y. Costello, 1975-1982. Fiorenza, Francis Schüssler, dan John P. Galvin, ed. Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives. 2 volume. Minneapolis: Forress, 1991. Glazier, Michael, dan Monika K. Hellwig, ed. The Modern Catholic Encyclopedia. Collegeville: The Liturgical Press, 1994. Hastings, Adrian, ed. Modern Catholicism: Vatikan II and After. New York: Oxford Univ. Press, 1991. Hennesey, James. American Catholics. Oxford: Oxford Univ. Press, 1981. Komonchak, Joseph A., Mary Collins, dan Dermot A. Lane, ed. The New Dictionary of Theology. Collegeville: The Liturgical Press, 1991. McBrien, Richard P. Catholicism. San Francisco: Harper, 1994. –––––,The Harper Collins Encyclopedia of Chatolicism. San Francisco: Harper San Francisco, 1995. McCharthy, Timothy G. The Catholic Tradition: Before and After Vatican II: 1878-1993. Chicago: Loyola Univ. Press, 1994. McKenzie, John L. Dictionary of the Bible. Milwaukee: Bruce, 1965. Rahner, Karl, ed. The Teaching of the Catholic Church. Aslinya dipersiapkan oleh Joseph Neuner dan Heinrich Roos. Staten Island, N.Y.: Alba, 1967. Rausch, Thomas P. The Roots of the Catholic Tradition. Wilmington: Glazier, 1986. Sanks, T. Howland. Salt, Leaven, and Light: The Community Called Church. New York: Crossroad, 1992. Sullivan, Francis A. Magisterium: Teaching Authority in the Catholic Church. Mahwah, N.J.: Paulist, 1983. Vorgrimler, Herbert, ed. Commentary on the Documents of Vatican II. 5 volumes. New York: Herder & Herder, 1967-1969. Wilhelm, Anthony. Christ Among Us: A Modern Presentation of the Catholic Faith for Adults. San Francisco: Harper, 1990. Daftar Sumber Gambar/Foto Singkatan sumber foto/gambar: Der Rosenkranz (DR) Ensiklopedi Gereja III (EG) Encyclopedia of Catholicism (EC) Hell (Hell) Modern Catholic Encyclopedia (MCE) Roots of Faith (RF) The Grand Louvre (TGL) I. GEREJA DAN KONSILI Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. 18 – Suasana Konsili – EC, hlm. 1299 21– Yesus Kristus Sang Penyelamat – MCE, plate 27 30 – Yohanes XXIII – MCE, hlm. 455 32 – Suasana Konsili Vatikan II – EC, hlm. 1300 36 – Perjumpaan dengan yang lain (dok. Kanisius) II. IMAN DAN JEMAAT YANG PERCAYA Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. 47 – Roh Kudus dan Jemaat – poscard 53 – Manusia pertama, DR, hlm. 17. 59 – Penyembuhan di Kapernaum, MCE, plate 10 62 – Yesus disalib – postcard 64 – Kebangkitan Yesus – MCE, hlm. 742 III. GEREJA YANG KELIHATAN Hlm. 75 – ”Umat Allah” berziarah (dok. Basis/Kanisius) Hlm. 78 – Basilika St. Petrus – MCE, hlm. 627 Hlm. 81 – Upacara tahbisan imam baru – (terlampir 2 buah) Basis/Kanisius) Hlm. 85 – Paus Yohanes Paulus II – MCE, hlm. 462 Hlm. 88 – Suasana pertemuan magisterium Gereja – EC, hlm. 806 Hlm. 95 – Gereja Perdana – MCE, plate 26 Hlm. 99 – St. Petrus dan St. Yohanes – EC, hlm. 990 (dok. IV. TRADISI YANG HIDUP Hlm. 104 – St. Agustinus (354-430) – MCE, hlm. 59 Hlm. 108 – St. Paulus yang sudah tua di dalam penjara di Roma – Hlm. 115 – Sakramen Baptis mengantar orang ke dalam Jemaat Kanisius) EG, hlm. 286 Kristiani (dok. Hlm. 119 – Martin Luther – MCE, hlm. 530 V. SAKRAMEN-SAKRAMEN DAN INISIASI KRISTIANI Hlm. 128 – Pemberkatan air baptis dalam ibadat meriah upacara Paskah – EG, hlm. 278 Hlm. 131 – Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembatis – RF, hlm. 31 Hlm. 137 – Penerimaan sakramen Krisma (dok. Basis/Kanisius) Hlm. 140 – Perjamuan Malam dan Ekaristi – dari buku DR, hlm. 25 Hlm. 146 – Ekaristi bersama anak-anak (dok. Basis/Kanisius) Hlm. 148 – Pendampingan Iman Anak (dok. Kanisius) VI. HIDUP KRISTIANI DAN PANGGILAN MENJADI MURID Hlm. 154 – Oscar Romero, ’Martir’ pembela kaum tertindas –MCE, hlm. 755 Hlm. 156 – Upacara penerimaan Sakramen Perkawinan (dok. Kanisius) Hlm. 163 – Komunitas Biarawati (dok. Kanisius) Hlm. 171 – Ibu Teresa, ibu kaum papa - EC, hlm. 1246 Hlm. 174 – St. Ignatius Loyola – MCE, hlm. 415 VII. DOSA, PENGAMPUNAN, DAN PENYEMBUHAN Hlm. 186 – Musa menerima 10 perintah Allah – DR, hlm. 32 Hlm. 194 – St. Polikarpus dibakar hidup-hidup – RF, hlm. 59 Hlm. 198 – Berdamai dengan sesama dan Tuhan (dok. Kanisius) Hlm. 202 – Sakramen Pengakuan Dosa masih perlu! (dok. Kanisius) Hlm. 206 – Mendampingi orang sakit (dok. Basis/Kanisius) VIII. MORALITAS SEKSUAL DAN KEADILAN SOSIAL 213 – Sepasang muda-mudi (dok. Kanisius) 219 – Yesus mencintai anak-anak – MCE, plate 11 229 – Paus Paulus VI – EC, hlm. 976 231 – YB. Mangunwijaya, pejuang kemanusiaan (dok. Kanisius) Hlm. 236 – Para guru mencari keadilan (dok. Kanisius) Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. IX. DOA DAN SPIRITUALITAS Hlm. 245 – Pasrah di dalam doa (dok. Basis/Kanisius) Hlm. 250 – Membiasakan berdoa bersama dalam keluarga (dok. Kanisius) Hlm. 252 – Perayaan Ekaristi (dok. Kanisius) Hlm. 258 – Yesus menjadi korban kekerasan – TGL, hlm. 68. Hlm. 262 – Fransiskus Assisi Hlm. 267 – Ibu Maria dan putranya – DR, hlm. 5 Hlm. 271 – Ibu Maria mengajak kita untuk berdoa Rosario – DR, hlm. 5 malam X. KEPENUHAN HARAPAN KRISTIANI Hlm. 278 – Kristus menampakkan diri kepada ibu-Nya, MCE, plate 24 Hlm. 282 –Yesus duduk di sisi kanan Bapa - DR, hlm. 71 Hlm. 285 – Balatentara setan – Hell, hlm. 39 Hlm. 287 – Gambaran neraka – RF, hlm. 41 Hlm. 290 – Gambaran persekutuan orang kudus di surga – DR, hlm. 43 Hlm. 295 – Ibu Maria dan Kanak-kanak Yesus, (Koleksi Museum Benaki, Athena, Yunani) XI. AGENDA YANG BELUM SELESAI Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. Hlm. 302 – Inkulturasi dalam Ekaristi (I) (dok. Kanisius) 304 – Inkulturasi dalam Ekaristi (II) (dok. Kanisius) 307 – Bagaimana dengan perempuan awam? (dok. Kanisius) 310 – Wanita dalam Gereja – EC, hlm. 1334 314 – Cerah menatap masa depan? (dok. Basis/Kanisius) 325 – Imam dan umat bersama-sama (dok. Kanisius) 327 – Membangun persaudaraan sejati (dok. Kanisius)