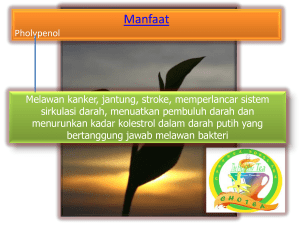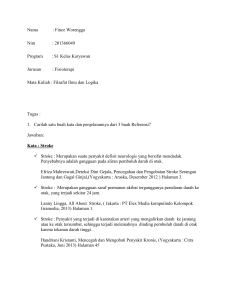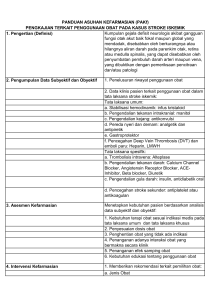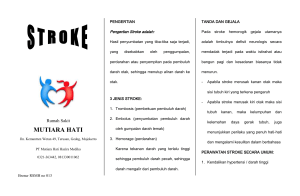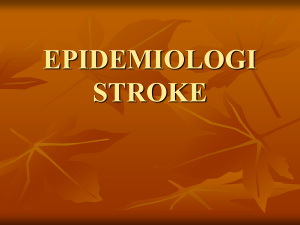Uploaded by
desys4452
PNNLS: Manual Pelatihan Neuroemergency & Neurosurgical Life Support
advertisement
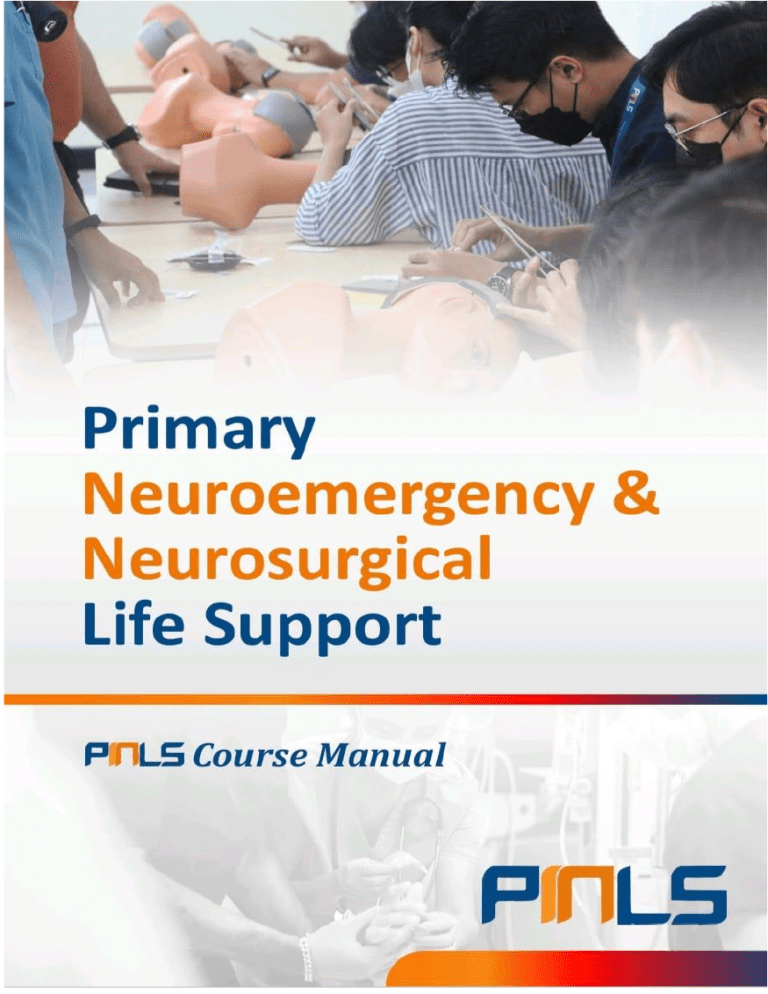
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Kematian dan kecacatan akibat kelainan dan penyakit sistim syaraf masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Kematian akibat stroke merupakan 5 besar di negara kita. Trauma kepala serta trauma otak menduduki peringkat pertama kecacatan pada sistim syaraf. Penyakit-penyakit sistim syaraf memerlukan tatalaksana yang cepat, tepat dan komprehensif serta biasanya berbiaya mahal. Kecacatan dan kematian lebih dari lima puluh persen sebenarnya dapat di cegah bila tatalaksana pada fase kegawatan yang sering ditangani oleh sejawat dr umum yang bertugas di lini terdepan yaitu di IGD dan poliklinik dilakukan dengan cepat dan tepat. Perspebsi sebagai organisasi profesi yang kompeten dalam menangani kelainan penyakit syaraf, tergugah untuk turut serta memberikan kontribusi dalam menurunkan kecacatan dan kematian akibat penyakit sistim syaraf, yaitu dengan menyusun PNNLS. Mempertimbangkan kompleksitas penyakit syaraf maka Perspebsi bersama organisasi profesi lain yaitu Ilmu penyakit syaraf, radiologi, anestesi bekerjasama dan sama sama menyusun program yang bertujuan untuk meningkatkan tatalaksana kegawat daruratan penyakit susunan syaraf guna menurunkan kecacatan dan kematian yang masih merupakan tugas berat kita semua. Pelaksanaan program berupa paket paket yang secara bergantian akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. PNNLS adalah program Perspepsi dengan kerjasama dengan Organisasi Profesi dengan sasaran para dokter umum yang merupakan lini terdepan dalam penanganan kegawatan bidang penyakit syaraf. Para intruktur adalah ahli ahli dalam bidangnya. Pelaksanaan melibatkan Perspebsi pusat, cabang dan wilayah serta teman sejawat profesi lain. Modul secara konprehensif telah tersusun praktis berisi proses diagnosa, patofisiologi ringkas dan tatalaksana i KATA PENGANTAR praktis kegawatan penyakit syaraf. Peningkatan ketrampilan tindakan minor pada kegawatan penyakit syaraf dan soft skill dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan kompetitip juga merupakan materi modul yang diajarkan. Evaluasi pre dan post course juga dilakukan guna jaga mutu dan peningkatan program. Tiada gading yang tidak retak, sebaik apapun program telah kita susun dan laksanakan selalu memerlukan kritik dan saran dalam perbaikannya. PNNLS adalah salah satu program perspebsi dalam kepeduliannya pada pembangunan kesehatan di negara kita. Selamat Berjuang. Ketua PERSPEBSI Joni Wahyuhadi ii PRAKATA PRAKATA Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi dan dihuni oleh sekitar 267,1 juta jiwa, masih dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan yang kompleks. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah angka kejadian trauma kepala, tulang belakang, dan stroke yang masih tinggi. Prevalensi trauma kepala akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 7,5% dari total populasi penduduk Indonesia, sedangkan angka kejadian stroke mencapai 10,9 per 1000 penduduk atau sekitar 2,91 juta penduduk per tahun. Dalam menghadapi banyaknya kasus neuroemergency di Indonesia, dokter umum sebagai garda terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun, masih banyak dokter yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, belum ada pelatihan yang standar untuk menangani kasus neuroemergency di Indonesia. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk menyelenggarakan pelatihan penatalaksanaan neuroemergency yang kami sebut Primary Neuroemergency dan Neurosurgical Life Support (PNNLS). Pelatihan ini dirancang secara komprehensif, terstandar, dan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang. Terdapat lima spesialis yang terlibat dalam pelatihan PNNLS, yaitu spesialis bedah saraf, spesialis syaraf, spesialis radiologi, spesialis anestesi, dan spesialis neurologi anak. Pelatihan PNNLS akan memberikan pengetahuan dan keterampilan neuroemergency kepada dokter umum melalui seminar lanjutan dan workshop intensif selama dua hari. Terdapat 12 modul dan skill station yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Dengan fasilitas yang memadai, instruktur yang ahli dalam bidangnya, modul yang terstandarisasi, serta mendapatkan sertifikasi dari Perhimpunan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PNNLS hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan terutama dalam penanganan iii kasus neuroemergency. Pelatihan ini akan diadakan di seluruh kota di Indonesia. Kami berharap bahwa melalui pelatihan PNNLS, dokter umum akan memiliki wadah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kasus neuroemergency, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Mei 2023 Tim Penyusun iv PRIMARY NEURO EMERGENCY & NEURO SURGICAL LIFE SUPPORT EDITOR Prof. dr. Ahmad Faried, Sp.BS(K), PhD., FICS dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS(K) Dr. dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS(K), SE, MM, FICS, FACS, IFAANS Dr. dr. Farhad Bal’afif. Sp.BS(K), FICS Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D., PA., Sp.BS(K) Dr. dr. Rahadian Indarto Susilo, Sp.BS(K) PENULIS DAN KONTRIBUTOR Prof. dr. Ahmad Faried, Sp.BS(K), PhD., FICS dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS(K) dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K), FINPS Dr. dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS(K), SE, MM, FICS, FACS, IFAANS dr. Heri Subianto, Sp.BS(K), FINPS Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS(K)., MARS Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D., PA., Sp.BS(K) Dr. dr. Muhammad Faris, Sp.BS(K), FINSS Dr. dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K), IFAANS. Dr. dr. Rahadian Indarto Susilo, Sp.BS(K) Dr. dr. Tedy Apriawan, Sp.BS(K), FICS Dr. dr. Abdulloh Machin, Sp.S(K) dr. Badrul Munir, Sp.S(K) dr. Bimo Dwi Lukito, Sp.S v PENULIS DAN KONTRIBUTOR Dr. dr. Prastiya Indra Gunawan, Sp.A(K) dr. Prihatma Kriswidyatomo, Sp.An dr. Ristiawan Muji Laksono, Sp.An., KMN, FIPP Dr. dr. Sri Andreani Utomo, Sp.Rad(K)N-KL Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad(K) TATA LETAK DAN DESAIN SAMPUL dr. Kahexa Firman Ramadhan dr. Naufal Najmuddin dr. Vira Dwi Nisrina Devi Fabiola S., S.Kom. ISBN: Hak Cipta © 2023 pada penulis Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip, menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Cetakan pertama, tahun 2023 Diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Jalan Prof. Eyckman No. 38 Sukajadi, Bandung, Jawa Barat Surel: [email protected] vi DAFTAR ISI DAFTAR ISI PENGANTAR ...................................................................................................i DAFTAR ISI ................................................................................................... vii BAB I ............................................................................................................. 1 CEDERA OTAK TRAUMATIK ......................................................................... 1 1.1 PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1.2 CEDERA OTAK TRAUMATIK ....................................................... 1 1.3 PRINSIP TATALAKSANA CEDERA OTAK ..................................... 3 1.4 IMAGING PADA CEDERA OTAK ............................................... 10 1.5 FRAKTUR BASIS CRANII ........................................................... 18 1.6 FRAKTUR CRANII ...................................................................... 20 1.7 KESADARAN ............................................................................. 21 1.8 PATOFISIOLOGI CEDERA OTAK ............................................... 24 1.9 KOMPLIKASI NEUROTRAUMA ................................................. 26 BAB II .......................................................................................................... 40 CEDERA SPINAL .......................................................................................... 40 2.1 PENDAHULUAN ....................................................................... 40 2.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI SPINAL .......................................... 40 2.3 PENEGAKAN DIAGNOSIS CEDERA SPINAL .............................. 41 2.4 SINDROMA KLINIK CEDERA SPINAL ........................................ 44 2.5 NEUROGENIC SHOCK DAN SPINAL SHOCK ............................. 46 2.6 EKSKLUSI CEDERA SPINAL ....................................................... 47 2.7 PENGGOLONGAN CEDERA SPINAL ......................................... 49 2.8 TATALAKSANA CEDERA SPINAL .............................................. 51 2.9 RUJUKAN KASUS CEDERA SPINAL ........................................... 53 vii DAFTAR ISI BAB III ......................................................................................................... 56 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL ..................................... 56 3.1 PENDAHULUAN ....................................................................... 56 3.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI ....................................................... 56 3.3 PATOLOGI DARI TEKANAN TIK ................................................ 61 3.4 GAMBARAN KLINIS .................................................................. 70 3.5 PENANGANAN ......................................................................... 71 BAB IV ......................................................................................................... 80 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS .................................................................................................................... 80 4.1 PENDAHULUAN ....................................................................... 80 4.2 KLASIFIKASI .............................................................................. 80 4.3 EPIDEMIOLOGI......................................................................... 81 4.4 ATOFISIOLOGI .......................................................................... 81 4.5 PENGOBATAN FARMAKOLOGIS .............................................. 84 4.6 STATUS EPILEPTIKUS REFRAKTER (SER).................................. 88 4.7 PENGOBATAN STATUS EPILEPTIKUS ...................................... 89 4.8 MANAJEMEN KEJANG NEONATAL .......................................... 93 4.9 KESIMPULAN............................................................................ 99 BAB V ........................................................................................................ 103 MANAJEMEN HIDROSEFALUS ................................................................. 103 5.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 103 5.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM VENTRIKEL DAN ALIRAN CSS.......................................................................................... 103 5.3 DEFINISI.................................................................................. 105 5.4 TANDA DAN GEJALA HIDROSEFALUS ................................... 106 5.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS HIDROSEFALUS ............................. 108 viii DAFTAR ISI 5.6 EVALUASI PASCA BEDAH ....................................................... 111 5.7 TATALAKSANA ....................................................................... 112 BAB VI ....................................................................................................... 114 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK ............................................................... 114 6.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 114 6.2 EPIDEMIOLOGI....................................................................... 115 6.3 ETIOLOGI ................................................................................ 116 6.4 KLASIFIKASI ............................................................................ 117 6.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS STROKE ISKEMIK........................... 121 6.6 TATALAKSANA STROKE ISKEMIK ........................................... 128 BAB VII ...................................................................................................... 132 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN ..................................................... 132 7.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 132 7.2 STROKE PERDARAHAN .......................................................... 132 7.3 EPIDEMIOLOGI....................................................................... 133 7.4 KLASIFIKASI ............................................................................ 134 7.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS STROKE PERDARAHAN ................. 137 7.6 GRADING/STAGING/SCORING .............................................. 139 7.7 TATALAKSANA STROKE PERDARAHAN ................................. 144 BAB VIII ..................................................................................................... 155 MANAJEMEN KOMA ................................................................................ 155 8.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 155 8.2 KONDISI BANGUN DAN KONDISI AWAS ............................... 155 8.3 NEUROBIOLOGI KESADARAN ................................................ 156 8.4 ARAS ....................................................................................... 157 8.5 ETIOLOGI ................................................................................ 158 8.6 PEMERIKSAAN KESADARAN .................................................. 158 ix DAFTAR ISI 8.7 GANGGUAN POLA NAPAS ..................................................... 161 8.8 KONDISI MIRIP KOMA ........................................................... 167 BAB IX ....................................................................................................... 174 SKILL STATION I ........................................................................................ 174 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY ............................ 174 9.1 ANATOMI IMAGING .............................................................. 174 9.2 FOTO POLOS .......................................................................... 177 9.3 CT-SCAN ................................................................................. 179 9.4 MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)............................. 181 9.5 TRAUMA SPINAL .................................................................... 183 9.6 STROKE PERDARAHAN .......................................................... 186 9.7 STROKE ISKEMIK .................................................................... 188 9.8 ASPECTS SCORE ..................................................................... 190 BAB X ........................................................................................................ 194 SKILL STATION II ....................................................................................... 194 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT ............................................ 194 10.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 194 10.2 PERSIAPAN TIM DALAM TRANSPORTASI PASIEN ................. 194 10.3 TINDAKAN YANG DILAKUKAN ............................................... 195 10.4 PEMERIKSAAN KESADARAN .................................................. 196 10.5 TINDAKAN SAAT DI FASKES TERDEKAT ................................. 196 10.6 PEMERIKSAAN FISIK LANJUTAN ............................................ 197 BAB XI ....................................................................................................... 200 SKILL STATION III ...................................................................................... 200 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE ......................................................... 200 11.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 200 x DAFTAR ISI 11.2 CARA MENENTUKAN GEJALA PASIEN STROKE DI LAYANAN PRIMER .................................................................................. 200 11.3 ALGORITMA PENANGANAN STROKE .................................... 207 11.4 KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI PADA STROKE TROMBOLISIS ................................................................................................ 208 11.5 PILIHAN TINDAKAN UNTUK ACUTE ISCHEMIC STROKE ....... 209 11.6 ALGORITMA UNTUK COMPLETE MCAO ............................... 210 11.7 STROKE MIMIC ...................................................................... 210 BAB XII ...................................................................................................... 213 SKILL STATION IV ...................................................................................... 213 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY ............................................................................................. 213 12.1 PENDAHULUAN ..................................................................... 213 12.2 ANATOMI SCALP DAN STRUKTUR PENTING DIBAWAHNYA ....... ................................................................................................ 213 12.3 JENIS LUKA PADA KEPALA ..................................................... 215 12.4 PRINSIP PENANGANAN LUKA ............................................... 217 12.5 JENIS DAN TEKNIK PENJAHITAN LUKA.................................. 217 BAB XIII ..................................................................................................... 226 SOFT SKILL ................................................................................................ 226 xi BAB I BAB I CEDERA OTAK TRAUMATIK 1.1 PENDAHULUAN Insiden TBI yang dilaporkan sangatlah bervariasi. Di Eropa sendiri, diperkirakan terdapat 47 - 694 kasus baru per 100.000 orang dalam satu tahun. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab paling sering dari trauma kepala. Polrestabes Surabaya (2011): dari 872 keselakaan lalu lintas, cedera kepala terjadi pada kelompok usia 30 tahun VS POLRI (2011). Usia rata-rata kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah 15-44 tahun dan didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 58%. Traumatic Brain Injury adalah beban penyakit yang besar di seluruh dunia. Tatalaksana cedera otak traumatis (TBI) dilakukan tidak hanya saat pasien sudah mencapai RS namun yang paling penting adalah penanganan sebelum pasien mencapai RS (pra rumah sakit) dimana stabilisasi sangat diperlukan saat transportasi. Beberapa hal dapat menjadi sebab terjadinya secondary brain injury apabila saat penanganan awal (pra rumah sakit) tidak dilakukan dengan baik. Penilaian awal saat pre hospital juga sangat penting untuk menjadi dasar evaluasi terapi yang diberikan setelahnya. 1.2 CEDERA OTAK TRAUMATIK Cedera Otak didefinisikan sebagai perubahan atau gangguan fungsi neurologis atau struktur pada otak akibat gaya dari luar (benturan, tusukan, tembakan). Pembagian derajat cedera otak dapat dibagi menjadi cedera otak ringan (COR) ketika GCS 14-15, cedera otak sedang (COS) ketika GCS 9-13 dan cedera otak berat (COB) ketika GCS kurang dari 8. 1 CEDERA OTAK TRAUMATIK Cedera Otak berbeda dengan Trauma Kapitis, dimana pada Trauma Kapitis tidak menyebabkan gangguan fungsi neurologis dan kerusakan pada jaringan otak. Traumatic Brain Injury (TBI) atau cedera otak traumatik merupakan gangguan fungsi atau adanya kerusakan patologi pada otak yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Cedera otak di klasifikasikan menjadi cedera otak primer dan sekunder. Cedera otak primer merupakan kejadian traumatis itu sendiri, sedangkan cedera otak sekunder dapat terjadi beberapa menit, jam, hari atau bahkan minggu setelah cedera primer. Klasifikasi cedera otak primer dibagi menjadi ekstra-parenkim dan intra-parenkim. Cedera otak primer ekstra-parenkim antara lain suatu epidural hematoma (EDH), subdural hematoma (SDH) dan subarachnoid hematoma traumatik. Sedangkan cedera otak primer intra-parenkim dapat berupa contusio, intracerebral hematoma (ICH), diffuse axonal injury hingga diffuse vascular injury. Sementara itu, penyebab paling sering pada cedera otak sekunder selanjutnya dapat dibagi menjadi penyebab sistemik dan intrakranial. Penyebab sistemik antara lain karena hipoksia, hipotensi, hipo/hiperglikemia, hipertermia, gangguan elektrolit, gangguan koagulasi dan infeksi. Penyebab intrakranial dapat berupa peningkatan tekanan intrakranial (TIK), edema otak, kejang hingga suatu kejang. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya secondary brain injury pada pasien cedera otak traumatik dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1). Beberapa kondisi ekstrakranial ini dapat menyebabkan kondisi yang lebih buruk dari klinis pasien dan memerlukan tatalaksana yang optimal. 2 CEDERA OTAK TRAUMATIK COAGULOPAT HY HYPONATRE MIA HYPERTENSION HYPERNATRE MIA SECONDARY BRAIN INJURY HYPERGLICEMI A HYPOGLICEM IA HYPOXIA HYPERCAPNE A Gambar 1 Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya secondary brain injury pada pasien cedera otak traumatik 1.3 PRINSIP TATALAKSANA CEDERA OTAK Prinsip tatalaksana pada cedera otak atau trauma otak adalah sebagai berikut: 1. Penanganan cedera otak primer 2. Mencegah dan menangani cedera otak sekunder 3. Optimalisasi metabolisme otak 4. Rehabilitasi Tatalaksana Pra Rumah Sakit Tatalaksana pra rumah sakit memegang peranan penting pada beberapa jam pertama setelah kejadian. Hal yang paling utama adalah mempertahankan patensi jalan nafas, memastikan oksigenasi yang adekuat, kontrol cervical spine dan memastikan kondisi hemodinamik yang memadai. Kita mengenal dengan A, B, C → D, E. 3 CEDERA OTAK TRAUMATIK • Airway + C Spine Control 1. Menjamin saturasi oksigen >90%. 2. Pemantauan jalan nafas dengan stabilisasi servikal tetap dilakukan walaupun pasien sadar. 3. Oksigen dapat diberikan menggunakan masker. 4. Pada pasien tidak sadar atau cidera otak berat, mengingat risiko lidah jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas, pemasangan orofaringeal tube dapat dilakukan. 5. Bila jarak RS tujuan cukup dekat, intubasi di tempat tidak disarankan. Pada perjalanan yang jauh dan medan yang sulit, intubasi diperbolehkan dan hanya dilakukan oleh personil yang ahli. 6. Apabila intubasi tidak dapat dilakukan, penggunaan Laryngeal Mask Airway (LMA) dapat dilakukan sebelum tindakan definitif dilakukan. • Breathing 1. Melihat Gerakan dada (Normal: Simetris) 2. Suara nafas Vesikuler/Vesikuler 3. Pernafasan normal harus dipertahankan dengan target pCO2 35-45 mmHg. 4. Pada kondisi dengan klinis menuju herniasi otak, dapat dilakukan hiperventilasi dengan pCO2 28-35 mmHg. • Circulation 1. Pada orang dewasa, tekanan darah dijaga pada sistolik >100 mmHg. 2. Pada anak, tekanan darah sistolik dijaga pada >5th percentile usianya (70 mmHg + usia x 2). 4 CEDERA OTAK TRAUMATIK 3. Bila tekanan darah turun, infus cepat cairan isotonic (20-40 ml/kg BB normal salin) diberikan. 4. Cairan hipotonik seperti D5 1/2NS atau D5 dihindari karena dapat memperberat edema cerebri. • Parameter Tambahan Kadar glukosa darah harus selalu diperiksa selama transport. ▪ Hipoglikemia pada orang dewasa (GDA <60 mg/dl) → Tx: 25 gram Dextrose baik menggunakan D10% atau D40% i.v bolus. ▪ Pada anak, hipoglikemi diterapi dengan 0,5 gram/kgBB D10). GCS selalu dimonitor secara berkala. Pupil juga dimonitor secara berkala untuk melihat apakah terjadi perubahan patologi intracranial. Pupil dianggap asimetri apabila terdapat perbedaan diameter >1 mm. Indikasi Masuk Rumah Sakit Pada Cedera Otak Beberapa kondisi yang merupakan indikasi seseorang dengan cedera otak memerlukan perawatan di Rumah Sakit adalah adanya kebingungan atau riwayat pingsan/penurunan kesadaran, keluhan dan gejala neurologik (termasuk nyeri kepala menetap dan muntah), kesulitan dalam penilaian klinis (misalnya pada alkohol dan epilepsi), kondisi medik lain (gangguan koagulasi, diabetes mellitus), fraktur tengkorak, CT scan abnormal, tidak ada yang dapat bertanggung jawab untuk observasi di luar rumah sakit, pasien anak ataupun >50 tahun hingga indikasi sosial. Indikasi Memulangkan Pasien Pada Cedera Otak Beberapa kondisi yang harus dicapai saat akan memulangkan pasien yaitu pasien sadar dengan orientasi baik, tidak pernah pingsan, tidak ada gejala neurologis, keluhan berkurang (muntah atau nyeri kepala 5 CEDERA OTAK TRAUMATIK hilang), tidak ada fraktur kepala atau basis kranii, ada yang mengawasi di rumah dan tempat tinggal dalam kota. Multi trauma + cedera otak Pada trauma berat, TBI dan pendarahan adalah penyebab kematian utama. Laju kematian 3x lipat lebih tinggi pada pasien multi trauma + TBI. Faktor yang mempengaruhi perburukan pada kondisi ini adalah hipotensi, hiperkapnia, hipksia, asidosis, koagulopati, dan hipotermia. Tatalaksana utama pada multi trauma+TBI adalah cerebral perfusion pressure guided cardiovascular management. Intervensi pembedahan harus memperhatikan patologi TBI. Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara intensivis, ahli bedah terkait, serta ahli bedah saraf untuk penanganan pasien yang spesifik. Transfer antar rumah sakit Hal yang perlu dilaporkan pada saat komunikasi dalam proses transfer antar rumah sakit adalah usia pasien dan mekanisme cedera, kondisi sebelum cedera atau pengobatan sebelumnya, hasil CT scan, GCS pasca resusitasi dan detail pemeriksaan neurologi, tindakan yang telah dilakukan, hasil laboratorium (terutama faal koagulasi), cedera lain yang menyertai, status cervical spine dan tanda vital terakhir pasien. GOAL penanganan cedera otak Target Fisiologi pada Cidera Otak antara lain: 1. Pulse oximetry >90% 2. PaCO2 35–40 mmHg 3. Tekanan darah sistolik > 100 mmHg 4. ICP < 20 mmHg 5. CPP 60–70 mmHg (45–60 mmHg pada anak) 6. Brain tissue oxygen pressure (PbtO2) > 15 mmHg 7. Temperatur 36.0–38.3 °C 6 CEDERA OTAK TRAUMATIK 8. Glucose 140–180 mg/dL 9. Physiologic Na + 135–145, if using hypertonic saline (HTS) 145–160 10. Platelets > 100 x 103/mm3 11. Hb > 11 g/dL Tatalaksana Cedera Otak di IGD Berikut langkah-langkah tatalaksana pasien cedera otak saat di IGD: 1. General precaution 2. Stabilisasi Sistem Kardiorespirasi (Airway, Breathing, Circulation) 3. Survey sekunder (pemeriksaan status general terdiri dari anamnesa dan 4. pemeriksaan fisik seluruh organ) 5. Pemeriksaan neurologis (Meningeal Sign, GCS, CN II-III, CN III-IV-VI, CN VII, CN VIII, CN IX, CN X, CN XI, CN XII, Motorik, Sensorik, Refleks Fisiologis, Refleks Patologis, Autonom) 6. Menentukan diagnosis klinis dan pemeriksaan tambahan 7. Menentukan diagnosis pasti 8. Menentukan tatalaksana Pemeriksa dapat menentukan derajat cedera otak pasien berdasarkan GCS, yaitu COR, COS ataupun COB. Di bawah ini adalah algoritma penangan pasien cedera otak traumatik di IGD berdasarkan nilai GCS pasien (Gambar 2-4). 7 CEDERA OTAK TRAUMATIK Algoritma pasien Cedera Otak Ringan (COR) Gambar 2 Algoritma tatalaksana pasien cedera otak ringan (COR) (Wahyuhadi, J., 2019). 8 CEDERA OTAK TRAUMATIK Algoritma pasien Cedera Otak Sedang (COS) Gambar 3 Algoritma tatalaksana pasien cedera otak sedang (COS) (Wahyuhadi, J., 2019). 9 CEDERA OTAK TRAUMATIK Algoritma pasien Cedera Otak Berat (COB) Gambar 4 Algoritma tatalaksana pasien cedera otak berat (COB) (Wahyuhadi, J., 2019). 1.4 IMAGING PADA CEDERA OTAK CT scan kepala adalah modalitas utama yang menjadi pilihan pada kasus cedera otak traumatik. Selain CT scan, permintaan diagnostik penunjang yang dapat dilakukan pada pasien cedera otak adalah thorax AP, cervical lateral maupun CT angiografi (bila ada penetrasi brain Injury maupun fraktur di pembuluh darah sinus). 10 CEDERA OTAK TRAUMATIK Berikut adalah beberapa kondisi pasien yang memerlukan tindakan pemeriksaan penunjang berupa CT-Scan kepala berdasarkan Canadian Head CT Rule dan New-Orleans Criteria (Tabel 1). Tabel 1 Indikasi CT Scan Pada Trauma Kepala (Dewasa) Canadian Head CT Rule New Orleans Criteria • • • • • • • • • • • • • Usia > 65 tahun Mekanisme trauma yang berbahaya Muntah > 1x Amnesia lebih dari 30 menit GCS < 15 pada saat 2 jam Terdapat kecurigaan fraktur basai cranii, fraktur terbuka, atau fraktur depresi Lakukan CT scan pada pasien dengan 1 kriteria atau lebih Usia > 65 tahun Intoksikasi Nyeri kepala Muntah Kejang Amnesia Terdapat trauma yang nyata di atas klavikula Lakukan CT scan pada pasien dengan 1 kriteria atau lebih Pada kasus anak terdapat pula krietria indikasi CT scan pada trauma kepala anak berdasarkan PECARN Rules dengan menggunakan pertimbangan usia pasien (Tabel 2). Tabel 2 Indikasi CT Scan Pada Trauma Kepala (Anak) Berdasarkan PECARN Rules Usia < 2 tahun Usia 2-18 tahun • • • • • GCS ≤ 14 atau perubahan status mental Mekanisme trauma yang berat Hilang kesadaran > 5 detik Hematoma temporal, parietal atau oksipital • • • 11 GCS ≤ 14 atau perubahan status mental Mekanisme trauma yang berat Hilangnya kesadaran Adanya riwayat muntah CEDERA OTAK TRAUMATIK • • • Fraktur kepala yang dapat teraba Nampak berperilaku abnormal menurut orang tua • Adanya tanda fraktur basis cranii Nyeri kepala berat Mass Lesion (hematoma) Beberapa kondisi yang dapat terjadi pada pasien cedera otak pada pemeriksaan CT scan kepala dapat dilihat pada Gambar 5. Hematoma yang terjadi pada pasien memiliki manifestasi klinis yang khas tergantung pada lokasi terjadinya lesi. • EDH Pasien dengan EDH dapat terjadi kehilangan kesadaran setelah trauma, terdapat kondisi lucid interval dan perburukan neurologis. Presentasi klasik ini terjadi pada <20% pasien. Gejala lain adalah nyeri kepala berat, mual, muntah, letargi dan kejang. • SDH SDH dapat terjadi pada cedera otak yang ringan maupun berat. Gejala utama adalah nyeri kepala, mual, muntah, tidak sadar, kejang atau letargis. Pada SDH kronis dapat muncul nyeri kepala, mual muntah, kebingungan, penurunan kesadaran, letargis, defisit motorik dan afasia. • SAH Klinis pada SAH adalah nyeri kepala berat yang sangat menyiksa biasa disebut thunderclap headache. Gejala lain yang dapat muncul adalah mual muntah, pusing, diplopia, kejang, penurunan kesadaran dan kaku kuduk. Dapat muncul defisit neurologis dan gangguan pada nervus kranialis. 12 CEDERA OTAK TRAUMATIK • ICH Defisit neurologis dan penurunan kesadaran secara mendadak menjadi keluhan utama yang penting pada pasien dengan ICH. Gejala lain yang dapat muncul adalah nyeri kepala, mual muntah, kejang, dan peningkatan tekanan darah diastolik lebih dari 110 mmHg. EDH ICH IVH SAH SDH Gambar 5 Tampilan Radiologis (CT scan Kepala) Pasien Dengan Hematoma Cara membaca CT scan kepala Sebelum menentukan apakah pasien memiliki indikasi operasi berdasarkan gambaran CT scan, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca CT scan adalah sebagai berikut (Gambar 6). 1. Identitas pasien + jenis ct scan) (kontras/non kontras) 2. Potongan axial 3. Potongan coronal 4. Potongan sagittal 5. Garis skala (1 skala = 1 cm) Menentukan kisi-kisi volume EDH Mengukur volume perdarahan EDH adalah dengan mencari potongan gambar CT-Scan dengan ukuran perdarahan yang paling besar pada semua potongan (1). Hal tersebut berlaku pada saat menentukan 13 CEDERA OTAK TRAUMATIK midline shift (2). Pada gambar ini midline shift bergeser 0,6 cm (jarak terjauh pergeseran midline) (Gambar 7). 5 1 2 3 4 Gambar 6 Hal yang perlu dipehatikan dalam membaca CT scan kepal 14 CEDERA OTAK TRAUMATIK 2 1 Gambar 7 Menentukan potongan CT scan dengan gambaran EDH paling bermakna Gambar 8 menunjukkan CT scan kepala potongan axial. Lakukan perhitungan dalam penentuan panjang, lebar dan tinggi hematoma. Pada gambar 8A, terdapat beberapa marker yang dapat membantu kita untuk mengetahui midline shift (MLS) pada CT scan. Batas anterior ditunjukkan dengan crista frontalis (1) dan batas posterior dengan protuberantia occipitalis interna/POI (2). Penarikan garis lurus dari kedua titik tersebut akan menunjukkan sumbu midline pada CT scan kepala potongan axial. MLS ditentukan dengan ada tidaknya jarak antara garis midline dengan septum pellucidum (3). Septum pellucidum adalah sekat yang membatasi kedua ventrikel lateral otak. Pada gambar 8B, didapatkan panjang sebesar 10 skala (10 15 CEDERA OTAK TRAUMATIK cm) yang ditunjukkan dengan marker nomor 1 dan lebar sebesar 5 skala (5 cm) yang ditunjukkan dengan marker nomor 2. 1 1 3 2 2 Gambar 8 CT Scan Kepala Potongan Axial Penentuan tinggi hematoma dapat diukur melalui CT scan kepala potongan coronal (Gambar 9A). Pada gambar tersebut didapatkan tinggi (pengukuran dari ujung ke ujung EDH) sebesar 4 skala (4 cm). Ketika instansi tempat kita bekerja tidak memiliki CT scan potongan coronal, perhitungan tinggi hematoma dapat dilakukan dengan melihat banyaknya gambaran EDH pada potongan axial (Gambar 9B). Semisal terdapat 4 potongan dengan gambaran EDH, maka angka tersebut dikalikan dengan skala per potongan yang ada pada informasi mesin CT scan. Jika mesin CT scan menggunakan skala per potongan 1 cm, maka jika ada 4 potongan dengan EDH kita dapat menghitung tinggi EDH tersebut dengan cara 4x1 cm = 4 cm. 16 CEDERA OTAK TRAUMATIK A B 1 2 3 4 Gambar 9 Perhitungan tinggi hematoma pada CT scan kepala, menggunakan potongan coronal (A) dan axial (B) Rumus Broderick Rumus Broderick adalah rumus yang dipakai untuk mengukur jumlah volume perdarahan pada pemeriksaan CT scan (Gambar 6). Sehingga pada contoh gambar di atas, volume perdarahan adalah 10 cm x 5 cm x 4 cm / 2 = 100 cc. VOLUME PERDARAHAN = Panjang X Lebar X Tinggi X 0.52 VOLUME PERDARAHAN = Panjang X Lebar X Tinggi 2 Indikasi operasi berdasarkan CT scan kepala Tabel 3 memuat beberapa indikasi operasi pada pasien cedera otak berdasarkan gambaran CT scan kepala terutama pada pasien dengan EDH, SDH dan ICH. Indikator yang digunakan adalah tebal, midline shift (MLS) dan volume hematoma. Pada ICH, volume 20 cc dapat menjadi indikasi operasi jika disandingkan dengan adanya MLS 0,5 cm. 17 CEDERA OTAK TRAUMATIK Tabel 3 Indikasi Operasi Berdasarkan CT Scan Kepala EDH SDH ICH Tebal 1.5 cm 1 cm (-) MLS 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm Volume (cc) >30cc (-) 20 cc atau 50 cc 1.5 FRAKTUR BASIS CRANII Tanda pasien dengan fraktur basis cranii (FBC) secara klasik meliputi ekimosis periorbital, hemotympanum, CSF rhinnorrhea atau otorrhea dan Battle’s sign. FBC dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan lokasinya, yaitu FBC fossa anterior, media dan posterior (Gambar 10). Gangguan fungsi saraf yang terjadi tergantung dari lokasi fraktur tersebut. • FBC fossa anterior Fossa anterior adalah porsi basis cranii yang berada anterior dari sphenoid ridge. FBC pada fossa ini dapat mengganggu fungsi nervus kranialis I (olfactorius) dan II (opticus). Tampilan klinis pasien berupa bloody rhinorrhea, brill hematoma, gangguan pembauan, gangguan penglihatan dan ophtalmoplegia. • FBC fossa media Fossa media adalah porsi basis cranii yang berada di antara sphenoid hinggda os temporal pars petrosa. FBC pada fossa ini dapat mengganggu fungsi nervus kranialis VII (facialis) dan VIII (vestibulocochlearis). Tampilan klinis pasien berupa bloody otorrhea, battle’s sign, gangguan pendengaran dan keseimbangan (vertigo). 18 CEDERA OTAK TRAUMATIK • FBC fossa posterior Fossa posterior adalah porsi basis cranii yang berada posterior dari os temporal pars petrosa. FBC pada fossa ini dapat mengganggu fungsi cerebellum. Tampilan klinis pasien berupa gangguan pada fungsi cerebellum, seperti gerakan terkoordinasi, keseimbangan, postur tubuh, dll. Gambar 10 Klasifikasi FBC berdasarkan fossa yang terjadi fraktur, fossa anterior (area merah), fossa media (area kuning) dan fossa posterior (area biru). 19 CEDERA OTAK TRAUMATIK 1.6 FRAKTUR CRANII Fraktur cranii (cranial fracture) adalah terjadinya diskontinuitas tulang/fraktur pada cranium walaupun memiliki struktur yang kuat, tangguh dan memberikan proteksi yang baik bagi otak. Fraktur cranii dapat dibagi menjadi fraktur linier, depressed, comminuted dan diastase. • Fraktur linier Secara umum, tulang cranium terdiri dari 3 lapisan, yaitu tabulae interna, diploe dan tabulae externa. Fraktur linier terjadi ketika diskontinuitas tulang dalam garis lurus tanpa adanya displacement dari tulang. • Fraktur depressed Fraktur depressed terjadi ketika diskontinuitas tulang melebihi 1 tebal tulang, yaitu ketika tabulae interna masuk hingga melewati tabulae externa sisi tulang sebelahnya. Fraktur tipe ini beresiko mengekspos konten cranium ke ruang extracranial sehingga mengakibatkan infeksi dan kontaminasi. • Fraktur comminuted Fraktur comminuted adalah fraktur dengan diskontinuitas tulang yang terbagi menjadi beberapa fragmen terpisah (>3 segmen tulang). • Fraktur diastase Fraktur diastase adalah fraktur yang terjadi pada sutura tulang, sehingga diskontinuitas tulang pada area ini menyebabkan pelebaran dari sutura. Fraktur ini lebih sering terjadi pada bayi (karena sutura belum mengalami fusi), sedangkan pada dewasa sering terjadi pada sutura lambdoid. 20 CEDERA OTAK TRAUMATIK Pasien dengan fraktur depressed sebaiknya dilakukan intervensi operatif untuk mencegah terjadinya infeksi. Fraktur ini dapat diberikan tatalaksana non operatif jika tidak ada bukti klinis maupu radiologis yang menunjukkan terjadinya penetrasi dura, ICH bermakna, depresi tulang >1 cm, keterpautan sinus frontalis, deformitas/keluhan kosmetik berat, infeksi luka, pneumocephalus maupun kontaminasi luka. 1.7 KESADARAN Pertama kali didefinisikan oleh William James pada tahun 1890 sebagai suatu keadaan kepekaan terhadap diri dan lingkungan. Plum dan Posner kemudian juga memberikan definisi yang mirip terhadap kesadaran, yaitu the state of awareness of self and the environment. Kesadaran memiliki 2 komponen: arousal (alert) dan awareness (content). • Arousal adalah suatu pola aktivitas atau perilaku yang terjadi saat seseorang bangun dari tidur atau perilaku saat dalam kesadaran penuh. • Awareness, adalah isi dari kesadaran ➔ suatu aktivitas gabungan dari fungsi kognitif dan afektif otak yang akan mempengaruhi pengetahuan seseorang secara individu dan bagaimana memahami kehidupan internal dan eksternal di luar. 21 CEDERA OTAK TRAUMATIK Gambar 11 Ascending Reticular Activating System (ARAS) (Alberstone, C.D. et al., 2009). Ascending reticular activating system (ARAS) telah dianggap sebagai struktur saraf utama untuk kesadaran. ARAS adalah jaringan rumit yang menghubungkan jalur sensorik aferen, formasio retikularis, thalamus, dan korteks serebri (Gambar 11). 22 CEDERA OTAK TRAUMATIK Glasgow Coma Scale (GCS) EYE 4 Spontaneous 3 To speech 2 To pain 1 None VERBAL 5 Oriented 4 Confused conversations 3 Inappropriate words 2 Incomprehensible sounds 1 None MOTORIC 6 Obey commands 5 Localizes pain 4 Flexion withdrawal to pain Alert 3 Abnormal flexion (decorticate) 2 Extension (decerebate) 1 None (flaccid) Gambar 12 Glasgow Coma Scale GCS adalah sistem skor sebagai parameter tingkat kesadaran yang terdiri dari 3 indikator yaitu eye, verbal dan motoric/movement (Gambar 12). Penilaian GCS dilakukan setelah ABC pasien stabil. Total dari skor setiap indikator di atas dapat menjadi penentuan tingkat cedera otak pasien yang selanjutnya dapat mengubah jalannya tatalaksana yang diberikan. Jumlah total GCS tertinggi adalah 15 (E4V5M6) dan terendah 3 (E1V1M1). Pada kondisi khusus seperti edema palpebrae, tracheostomy dan tetraplegi maka penilaian GCS menjadi sukar dilakukan sehingga kondisi tersebut dapat diberikan skor ‘X’. Selain GCS, kita juga mengenal istilah GCS-P yang merupakan singkatan dari Glasgow Coma Scale + Pupils Score. Sistem skor ini mempertimbangkan kondisi pupil pasien yang dinilai dengan Pupil Reactivity Score (PRS). Penilaian PRS: • Jika pada kedua pupil ditemukan tidak bereaksi maka diberi nilai 2. • Jika hanya salah satu pupil yang bereaksi maka diberi nilai 1. • Sementara jika keduanya bereaksi diberi nilai 0. 23 CEDERA OTAK TRAUMATIK Setelah mengetahui PRS, lakukan perhitungan GCS-P dengan rumus: GCS-P = GCS score – (dikurangi) nilai PRS Jika sebelumnya nilai GCS yang diketahui paling rendah 3-15 namun ketika dikombinasi dengan nilai PRS bisa menjadi 1-15. Contoh: Pasien dengan GCS 6 dan hanya pupil kiri yang bereaksi (PRS = 1) GCS-P = GCS (6) – PRS (1) GCS-P = 5 1.8 PATOFISIOLOGI CEDERA OTAK Cedera otak traumatik adalah suatu proses berkelanjutan yang diawali sejak terjadinya cedera dan beresiko mengalami perburukan kondisi oleh beragam faktor cedera sekunder. Otak yang mengalami cedera adalah hasil dari kerusakan progresif yang berkontribusi pada peningkatan kematian sel, atrofi white matter hingga disfungsi jaringan otak dalam periode mulai dari hitungan jam, hari maupun tahun pasca cedera. Kerusakan yang terjadi pada cedera primer disebabkan oleh deformasi mekanik jaringan otak yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian sel neuron dan glial, kerusakan aksonal dan pembuluh darah otak dengan gangguan sawar darah otak (BBB) serta aliran darah otak (CBF). Gambar di bawah adalah skema patofisiologi biomolekuler pada cedera otak traumatik berat (Gambar 13). Saat terjadi cedera kepala berat maka akan terjadi respon release glutamate, sehingga terjadi proses Ca dan Na influx pada sel. Ca pada sel menyebabkan terjadinya enzyme induction dan mitochondrial damage/kerusakan mitokondrial. Kerusakan mitokondrial akan melepaskan ROS (Reactive oxygen Spesies)/RNS (Reactive Nitrogen Spesies) sehingga terjadilah membrane degradasi dan 24 CEDERA OTAK TRAUMATIK neuroinflamation yang menyebabkan berbagai hal yang merugikan seperti infiltrasi leukosit, mikroglia activation, BBB opening. Gambar 13 Biomolekuler cedera otak traumatik berat (Marklund et al, 2020) Na yang masuk kedalam sel mengalami 2 hal, yang pertama Na influx menyebabkan K Efluks sehingga terjadi suatu depolarisasi neuronal, yang kedua natrium selalu berikatan dengan H2O (Air) sehingga menyebabkan terjadinya edema/cell swelling. Depolarisasi neuronal ini akan mengkibatkan terjadinya CBF turun, Produksi ATP Turun, Kebutuhan ATP Naik dan akhirnya terjadi Energy Failure. Semua ini akhirnya akan menyebabkan kematian sel. 25 CEDERA OTAK TRAUMATIK 1.9 KOMPLIKASI NEUROTRAUMA Beberapa komplikasi pada neurotrauma adalah: • Hydrocephalus • Post Traumatic Seizure • Long Term Functional Disability • Infection • Aesthetics • Neurovascular Injuries • Pseudoaneurysm • Post Traumatic Aneurysm • Trephined Syndromes Hidrosefalus Hidrosefalus dapat menjadi suatu indikasi tindakan operatif pada pasien dengan SAH. Pemeriksaan funduskopi akan menunjukkan tampilan papil edema pada kondisi hydrocephalus. Pada CT Scan kepala, hidrosefalus ditandai dengan adanya (Gambar 14): 1. Ukuran temporal horn (TH) ≥ 2 mm dan fisura Sylvii, interhemisferik serta sulkus sereberal tidak tampak, atau 2. TH ≥ 2 mm dan rasio frontal horn (FH) dan internal diameter (ID)> 0,5. Tanda lain yang mengesankan gambaran hydrocephalus pada CT scan kepala adalah: 1. Frontal horns Balloning dari ventrikel lateral atau biasa disebut “Mickey Mouse” Ventricles, dan/atau ventrikel 3 (Ventrikel 3 secara normal tampak hanya seperti celah kecil. 2. Hipodensitas pada daerah periventricular pada CT Scan atau hiperintensitas periventricular pada MRI T2W1 menggambarkan absorbs trans ependymal dari CSF. 26 CEDERA OTAK TRAUMATIK 3. Rasio FH: ID: <40% adalah normal, 40-50% borderline, sedangkan > 50% mengarah hidrosefalus. 4. Evans ratio >0,3. Evans ratio adalah perbandingan antara FH dengan Biparietal Diameter (BPD). 5. MRI potongan sagittal terdapat penipisan corpus callosum. Gambar 14 Tampilan Hydrocephalus Pada CT Scan Kepala Post Traumatic Seizure (PTS) Kejang post trauma adalah kejang yang terjadi setelah keadaan trauma. Terdapat 2 kategori kejang post trauma yaitu early (≤ 7 hari) dan late (> 7 hari) setelah trauma kepala. Antikejang (AED) dapat diberikan sebagai profilaksis untuk PTS pada pasien yang risiko tinggi 27 CEDERA OTAK TRAUMATIK mengalami kejang. AED tidak mengurangi kejadian kejang pada late PTS. Hentikan AED setelah 1 minggu kecuali terdapat kriteria spesifik. Terdapat kategori ketiga untuk PTS yaitu immediate yaitu kejang yang terjadi dalam hitungan menit dan jam setelah terjadi trauma kepala. Long Term Functional Disability Gambar 15 Long term functional disability (Brook, J. C. et al., 2013) Prognosis kelangsungan hidup adalah salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan pasien cedera otak traumatik beserta keluarga, terutama bagaimana kemungkinan pasien akan menjalani kehidupannya dengan kecacatan dan defisit neurologis jangka panjang setelah trauma. Perhitungan derajat disabilitas pasien dapat dinilai menggunakan Disability Rating Scale (DRS) maupun Functional Independent Measure (FIM). Gambar 14A membagi prognosis kelangsungan hidup pasien menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat kemandirian pasien untuk aktivitas sehari-hari dalam skala DRS. Kelompok 1 adalah pasien mandiri dengan bantuan minimal, kelompok 2 adalah pasien yang membutuhkan bantuan mekanik atau asistensi pada beberapa aktivitas, kelompok 3 adalah pasien yang 28 CEDERA OTAK TRAUMATIK membutuhkan asistensi dalam segala aktivitas dan kelompok 4 untuk pasien dependen total setiap saat (24 jam). Gambar 14B menunjukkan grafik kelangsungan hidup pasien laki-laki berusia 40 tahun setelah mengalami cedera 1 tahun yang lalu sebagai gambaran populasi umum. Estimasi grafik kelangsungan hidup pada pasien dengan disabilitas minimal didapatkan lebih buruk daripada gambaran populasi umum. Pasien dengan disabilitas yang lebih berat (seperti kelompok 4) memiliki perkiraan rata-rata kelangsungan hidup berupa tambahan 13,4 tahun yaitu hingga pasien mencapai usia 53,4 tahun. Infeksi Pasien dengan cedera otak traumatik memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kejadian infeksi nosokomial jika dibandingkan dengan pasien bedah saraf lainnya. Angka kejadian mortalitas yang berkaitan dengan infeksi mencapai 28%. Infeksi saluran pernafasan adalah lokasi kejadian infeksi dengan kejadian tertinggi serta Acinetobacter spp. sebagai patogen terbanyak (Gambar 16). Meningitis terjadi dalam 2% dari keseluruhan pasien dimana surgical site infection (SSI) selain meningitis terjadi sebanyak 4,25%. Hubungan langsung antara CSF dengan lingkungan (akibat penggunaan alat) merupakan faktor resiko tinggi terjadinya SSI secara umum hingga meningitis. Adanya kebocoran CSF dan infeksi di luar lapang operasi dapat menjadi perhatian klinisi akan kemungkinan terjadinya SSI pada populasi pasien cedera otak. Perawatan pasien di ICU merupakan faktor resiko independen terhadap kejadian meningitis pada pasien cedera otak, terutama jika pasien berada di ICU lebih dari 7 hari. 29 CEDERA OTAK TRAUMATIK Gambar 16 Lokasi terjadinya infeksi dan bakteri patogen yang sering ditemukan pada pasien cedera otak traumatik (Kourbeti, I.S. et al., 2012) Aesthetics Proses penyembuhan pasien dengan cedera otak adalah sesuatu yang sukar untuk diprediksi dan membutuhkan strategi perawatan yang fleksibel pada setiap tahapnya. Pengetahuan empiris akan memberikan kerangka kerja dalam memberikan perawatan berdasarkan prinsip ilmiah. Pengetahuan estetika seperti intuisi dapat menjadi suatu kesempatan untuk mengetahui dan memahami pasien cedera otak sekaligus respon mereka dalam proses perawatan paska cedera. Menyatukan pengetahuan empiris dan estetika dalam strategi perawatan pasien tentunya akan memberi kesempatan pada perawat untuk membantu pasien dan keluarga dalam mendapatkan outcome perawatan terbaik (Gambar 17). 30 CEDERA OTAK TRAUMATIK Gambar 17 Penggunaan Pengetahuan Estetika Dalam Tatalaksana Pasien Cedera Otak (Alverzo, J., 2004) Syndrome of the Trephined Sindrom Trephined adalah komplikasi yang jarang terjadi dari craniectomy dengan karakteristik disfungsi neurologis yang membaik dengan rekonstruksi cranial sekunder seperti cranioplasty. Sindrom ini memiliki gejala yang bervariasi dalam fungsi motorik, kognitif dan defisit berbahasa (Gambar 18). Berdasarkan temuan mayoritas laporan kasus yang ada, sindrom ini memiliki 3 gejala utama, yaitu defisit neurologis jangka panjang yang terjadi pada beberapa minggubulan setelah craniectomy, kejadian independent terjadi pada lokasi lesi dan terjadinya perbaikan klinis setelah cranioplasty. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi beberapa teori yang dapat menjadi mekanisme patofisiologi terjadinya sindrom ini 31 CEDERA OTAK TRAUMATIK (Gambar 19). Salah satu teori adalah peran tekanan atmosfer dimana skin flap yang terbenam dapat diartikan bahwa defek tulang memberikan tekanan eksternal pada jaringan otak dibawahnya. Tekanan barometrik eksternal pada scalp akan diteruskan ke vaskularisasi otak dan menyebabkan penurunan aliran darah di areak defek. Semakin besar area defek tulang maka semakin rendah aliran di daerah tersebut. Gambar 18 Gejala Pada Pasien Dengan Sindrom Trephined 32 CEDERA OTAK TRAUMATIK Gambar 19 Mekanisme terjadinya sindrom Trephined Cranioplasty adalah tindakan operatif dalam perbaikan defek cranium. Material yang digunakan dapat berupa tulang pasien itu sendiri maupun material lainnya. Penutupan defek tulang dapat memberi manfaat kosmetik dan perlindungan bagi pasien yang mengalami gangguan fisiologis paska craniectomy. Cranioplasty turut memperbaiki abnormalitas dalam elektroencephalografik, CBF dan status neurologis pasien. Beberapa material yang ideal digunakan untuk cranioplasty yaitu bersifat radioluscent, resisten terhadap infeksi, tidak konduktif pada panas dan dingin, resistan terhadap proses biomekanik, mudah dibentuk untuk menutupi defek, terjangkau dan siap digunakan. Gambar 20 menunjukkan perbandingan material yang dapat digunakan sebagai material cranioplasty. Gambar 20 Perbandingan material yang umum digunakan pada cranioplasty (Shah, A. M. et al., 2014) Material cranioplasty cenderung mahal. Walaupun metal telah umum digunakan sebagai material cranioplasty, namun autologous bone graft masih menjadi pilihan untuk cranioplasty karena material ini mampu mengurangi zat asing masuk ke dalam tubuh serta dapat segara diterima oleh tubuh pasien dan diintegrasikan ke dalam skull. 33 CEDERA OTAK TRAUMATIK Selain autologous bone graft, methyl methacrylate (MMA) dapat menjadi alternatif material sintetis dengan bahan yang lebih kokoh. Titanium wire mesh dapat ditambahkan untuk mengurangi kemungkinan patah pada penggunaan MMA. Dari sekian banyak pilihan dan inovasi, belum ada material yang paling ideal untuk cranioplasty. Akan tetapi, material yang kokoh, resistan terhadap infeksi, radioluscent, terjangkau, mudah digunakan dan mampu memperbaiki defek tulang pasien akibat craniotomy akan memberikan manfaat terbaik bagi pasien. Herniasi Peningkatan konten intrakranial pada cedera otak traumatik dapat menyebabkan peningkatan TIK. Pada fase dekompensata, parenkim otak akan mencari dan memberi efek desak ruang pada struktur sekitarnya hingga terjadi herniasi. Gambar di bawah menunjukkan potongan coronal kepala dengan macam herniasi (Gambar 20). Setiap jenis herniasi otak memiliki tampilan klinis yang khas pada pasien, sehingga pemahaman mengenai anatomi dan struktur kompartemen cranium penting untuk dimiliki oleh klinisi (Tabel 4). 34 CEDERA OTAK TRAUMATIK Gambar 21 Jenis herniasi otak dalam potongan coronal. Panah merah menunjukkan arah perpindahan posisi jaringan otak. Herniasi uncal (1), central transtentorial (2), subfalcine/cingulate (3), transcalvarial (4), reverse transtentorial (5) dan tonsillar (6) (Kan PKY, et al., 2016). Tabel 4 Jenis Herniasi Otak Beserta Tampilan Klinis Pasien Jenis Herniasi Subfalcine Transalar Uncal Keterangan Girus cingulatum ipsilateral bergesar di bawah falx anterior, menyebabkan infark pada daerah distal dari arteri serebral anterior Dapat muncul infark pada teritori arteri serebral media akibat kompresi dari sphenoid ridge pada versi posterior dari hernia transalar. Pada veris anterior, kompresi dari segment supraklinoid dapat menyebabkan infark pada arteri serebri anterior dadn media Menyebabkan kompresi dari CN III menyebabkan kontriksi dan dilatasi dari pupil ipsilateral 35 CEDERA OTAK TRAUMATIK Central Terdapat progresivitas dari postur fleksor abnormal menjadi respon ekstensor abnormal karena terdampaknya traktus rubrospinal dan vestibulo spinal Cerebellar tonsil Penekanan pada fosa posterior menyebabkan cerebellar tonsil turun pada foramen magnum. Herniasi akut dapat menekan arteri serebellar inferior posterior, arteri vertebralis, dan cabangcabangnya menyebabkan iskemia pada batang otak, tonsils, dan cerebeluum bagian bawah Edema cerebri Edema cerebri adalah kondisi patologis berupa akumulasi abnormal cairan pada parenkim otak sehingga menyebabkan peningkatan volume dan tekanan intrakranial (TIK). Secara umum, edema cerebri dapat dibagi menjadi edema sitotoksik dan edema vasogenik (Tabel 5). Tabel 5 Patofisiologi Terjadinya Edema Cerebri EDEMA SITOTOKSIK EDEMA VASOGENIK Pada iskemia cerebri terjadi penurunan brain blood flow → gangguan glucose supply untuk sel-sel otak → deplesi ATP Deplesi ATP menginduksi kegagalan sistem transport Na+ intra-ekstraseluler → akumulasi Na+ intraseluler yang berlebihan. Endothelial tight junctions mengalami gangguan oleh reaksi inflamasi dan stres oksidatif setelah kejadian cedera otak Akktivasi sel glial akan mengeluarkan faktor permeabilitas vaskular → akselerasi hiperpermeabilitas blood-brain barrier (BBB) → Ekstravasasi cairan dan albumin yang berujung 36 CEDERA OTAK TRAUMATIK Peningkatan Na+ intraseluler menyebabkan masuknya cairan ekstraseluler ke dalam sel secara abnormal sehingga mengakibatkan pembengkakan sel. pada akumulasi cairan ekstraseluler ke dalam parenkim otak. Cairan ekstravasasi terakumulasi di luar sel dan menimbulkan peningkatan volume dan TIK. Daftar Pustaka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alberstone, C.D. et al. (2009). Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis.New York: Thieme. Alverzo, J. (2004). The Use of Aesthetic Knowledge in the Management of Brain Injury Patients. Rehabilitation Nursing, 29(3), 85–89.doi:10.1002/j.2048-7940.2004.tb00316.x American College of Surgeons (2018) Advanced Trauma Life Support. Chicago: American College of Surgeons. Ashayeri, K., M. Jackson, E., Huang, J., Brem, H., & R. Gordon, C. (2016). Syndrome of the Trephined. Neurosurgery, 79(4), 525– 534.doi:10.1227/neu.0000000000001366 Brennan P.M. et al. (2018). Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: The GCS-Pupils score: an extended index of clinical severity. Journal of Neurosurgery, 128:1612-1620. Brooks, J.C., et al. (2013). Long-Term Disability and Survival in Traumatic Brain Injury: Results From the National Institute on Disability and Rehabilitation Research Model Systems. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94(11), 2203– 2209.doi:10.1016/j.apmr.2013.07.005 Bullock, M.R., et al (2006). Surgical Management of Depressed Cranial Fractures. Neurosurgery, 58(Supplement), S2–56–S2– 60.doi:10.1227/01.neu.0000210367.1 37 CEDERA OTAK TRAUMATIK 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dixon J, Comstock G, Whitfield J, Richards D, Burkholder TW, Leifer N, Mould-Millman NK, Calvello Hynes EJ. Emergency department management of traumatic brain injuries: A resource tiered review. Afr J Emerg Med. 2020 Sep;10(3):159-166. doi: 10.1016/j.afjem.2020.05.006. Epub 2020 Jun 16. PMID: 32923328; PMCID: PMC7474234. Handbook of Neurosurgery Greenberg 8th Edition and Youmans Neurological Surgery Textbook 7th Edition. Intensive care treatment of traumatic brain injury in multiple trauma patients : Decision making for complex pathophysiology]. Unfallchirurg. 2017 Sep;120(9):739-744. German. doi: 10.1007/s00113-017-0344-z. PMID: 28389734. Jang, S.H. and Kwon, Y.H. (2020). The relationship between consciousness and the ascending reticular activating system in patients with traumatic brain injury. BMC Neurology, 20:375. Kan PKY, Chu MHM, Koo EGY, Chan MTV. Brain Herniation. Complicat Neuroanesthesia. Published online 2016:3-13. doi:10.1016/B978-0-12-804075-1.00001-8 Keep, R. F., Andjelkovic, A. V., & Xi, G. (2017). Cytotoxic and Vasogenic Brain Edema. Primer on Cerebrovascular Diseases, 145–149. doi:10.1016/b978-0-12-803058-5.00029-1 Kourbeti, I.S., et al. (2012). Infections in traumatic brain injury patients. Clinical Microbiology and Infection, 18(4), 359– 364.doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03625.x Lindsay, K. W., Bone, I., Fuller, G. and Callander, R. (2011) Neurology and Neurosurgery Illustrated. Fifth. Edinburgh: Churchill Livingstone Inc. Marklund N, Tenovuo O. Pathophysiology of severe traumatic brain injury. In: Sundstrøm T, Grände P-O, Luoto T, Rosenlund C, Undén J, Wester KG, editors. Management of Severe Traumatic Brain Injury [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 38 CEDERA OTAK TRAUMATIK 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2020 [cited 2022 Feb 28]. p. 35–50. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-39383-0_6 Michinaga, S. and Koyama, Y. (2015). Pathogenesis of Brain Edema and Investigation into Anti-Edema Drugs. International Journal of Molecular Sciences, 16:9949-9975. Penelitian Karya Akhir Cedera Kepala di Kotamadya Surabaya 2011. Joni Wahyuhadi, Gde Budi Setiawan, Tedy Apriawan, Budi Susanto & Muhammad Fadli Said. Shah, A. M., Jung, H., & Skirboll, S. (2014). Materials used in cranioplasty: a history and analysis. Neurosurgical Focus, 36(4), E19.doi:10.3171/2014.2.focus13561 Sergio A. Calero-Martinez et al.. Development and assessment of competency-based neurotrauma course curriculum for international neurosurgery residents and neurosurgeons. NeurosurgFocus, 2020. Sivanandapanicker J, Nagar M, Kutty R, Sunilkumar BS, Peethambaran A, Rajmohan BP, et al. Analysis and clinical importance of skull base fractures in adult patients with traumatic brain injury. J Neurosci Rural Pract. 2018 Sep;9(3):370– 5. Tenny S, Thorell W. Intracranial Hemorrhage. [Updated 2022 Aug 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470242/ Tim Neurotrauma RSUD Dr. Soetomo. 2018. Pedoman Tatalaksana Cedera Otak edisi ketiga. RSUD Dr. Soetomo: Surabaya Wahyuhadi, J. (2019). Patofisiologi dan Tatalaksana Cidera Otak Berbasis Bukti Ilmiah. Third Edition. Surabaya: SMF/Departemen Ilmu Bedah Saraf Dr. Soetomo General Academic Hospital – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 39 BAB II BAB II CEDERA SPINAL 2.1 PENDAHULUAN Kejadian cedera spinal berkisar antara 250.000-500.000 di seluruh dunia setiap tahunnya. Keberadaan cedera spinal perlu dipertimbangkan pada pasien multi trauma baik dengan adanya defisit neurologis maupun tidak. Kejadian cedera spinal berkaitan dengan cedera otak. Sekitar 5% pada pasien dengan cedera otak juga mengalami cedera spinal, dimana 25% pasien dengan cedera spinal ternyata juga mengalami cedera otak ringan. Pada pasien yang berpotensi mengalami cedera spinal, manipulasi berlebihan dan immobilisasi pergerakan spinal yang inadekuat dapat menyebabkan kerusakan saraf lebih lanjut dan memperburuk prognosis pasien. Data menyebutkan bahwa setidaknya 5% pasien dengan cedera spinal mengalami defisit neurologis maupun perburukan gejala saat tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Diperlukan penanganan yang baik dan cermat, tidak hanya dalam lingkup tatalaksana kedaruratan, namun hingga masa rehabilitasi pasien agar gejala residual cedera spinal didapatkan seminimal mungkin sehingga pasien memiliki kualitas hidup yang baik dan lebih optimal menjalani sisa hidupnya. 2.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI SPINAL Columna vertebralis manusia tersusun oleh 33 vertebrae, yang terbagi menjadi 7 cervical, 12 thoracal, 5 lumbal, 5 sacral yang fusi menjadi 1 tulang sacrum dan segmen coccygeal. Seluruh vertebrae tersebut tersusun sedemikian rupa dan membentuk canalis spinalis di dalamnya sebagai tempat berjalannya medulla spinalis beserta pembungkusnya. Vertebrae secara umum terdiri dari corpus di anterior dan arcus vertebrae di posterior membentuk ruang berupa foramen vertebralis. 40 CEDERA SPINAL Pedicle adalah struktur berbentuk silindris dan berada di kedua sisi arcus vertebrae beserta struktur pipih bernama laminae yang membentuk arcus pada sisi posterior. Arcus vertebrae memberi 7 processus, antara lain 1 spinosus, 2 transversus dan 4 articularis. Medulla spinalis merupakan bagian dari sistem saraf pusat berbentuk silindris yang merupakan kelanjutan dari medulla oblongata dan berakhir pada batas bawah vertebrae lumbal ke-1 sebagai conus medullaris. Sebagai sistem saraf pusat, medulla spinalis memiliki pembungkus selayaknya pada otak, yaitu dura mater, arachnoid mater dan pia mater. Medulla spinalis akan memberikan cabang berupa radiks yang keluar di kedua sisi pada setiap levelnya. Terdapat 8 radiks cervical, 12 radiks thoracal, 5 radiks lumbal dan 5 radiks sacral pada kedua sisi medulla spinalis. Perlu diperhatikan bahwa radiks spinalis tersebut merupakan bagian dari sistem saraf tepi, sehingga gangguan pada struktur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda daripada gangguan langsung pada medulla spinalis. 2.3 PENEGAKAN DIAGNOSIS CEDERA SPINAL Penegakan diagnosis pada cedera spinal perlu dilakukan dengan teliti dan cermat. Pemeriksaan harus dilakukan secara runtut dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan penunjang. Anamnesis Penggalian informasi mengenai mekanisme trauma penting untuk mengetahui resiko terjadinya cedera spinal, antara lain: • Pasien dengan penurunan kesadaran • Pasien dengan keluhan menggerakkan tangan dan atau kaki pasca trauma • Pasien dengan riwayat trauma pada kecepatan tinggi/jatuh dari ketinggian >3 m 41 CEDERA SPINAL • Pasien dengan intoksikasi alkohol • Pasien dengan riwayat cedera yang belum diketahui Pada pasien yang sadar dapat diminta untuk menggerakan ekstremitas atas dan bawah, jika ada kesulitan curigai adanya cedera spinal. Sekitar 55% cedera spinal terjadi pada level cervical, sehingga kecurigaan pada cedera di level ini perlu diperhatikan oleh pemeriksa dengan seksama. Pasien dengan kecurigaan mengalami cedera cervical, antara lain: • Terdapat jejas di atas clavicula • Terdapat quadriplegia/tetraplegia setelah trauma (akut) • Pasien multi trauma Namun perlu diperhatikan bahwa tidak adanya temuan-temuan di atas pada pasien, bukan menjadi eksklusi bahwa pasien bebas dari kecurigaan cedera cervical. Pasien cedera multipel harus dicurigai terdapat cedera spinal hingga dibuktikan tidak, dengan konsekuensi perlu dilakukan proteksi pada spinal sampai terbukti tidak ada kelainan spinal. Pemeriksaan Fisik Setelah anamnesis terlaksana dengan baik maka penegakan diagnosis dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum pemeriksaan fisik dimulai, pastikan proteksi jalan nafas dan spinal (Cspine control) adekuat serta tekanan darah dalam kondisi stabil. Pada pasien dengan penurunan kesadaran maka dianggap memiliki cedera spinal. Pada pemeriksaan fisik, pemeriksa perlu untuk mengetahui kekuatan motorik keempat ekstremitas, defisit sensorik dan gangguan otonom pada cedera spinal. Temuan yang didapat selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan cedera spinal pada pasien. Pemeriksaan fisik pada pasien cedera spinal dapat dibantu dengan 42 CEDERA SPINAL mengisi worksheet International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) oleh American Spinal Injury Association (ASIA) di bawah ini (Gambar 21). Gambar 22 International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) oleh American Spinal Injury Association (ASIA) 43 CEDERA SPINAL Pada lembar isian ISNCSCI terdapat panduan dalam klasifikasi cedera spinal secara klinis dalam 5 langkah sebagai berikut: 1. Penentuan sensory level sisi kanan dan kiri pasien 2. Sensory level adalah segmen paling caudal dari spinal cord pasien dengan fungsi sensorik normal. Pemeriksaan sensorik yang dapat dilakukan adalah sensasi pin prick dan light touch. 3. Penentuan motor level sisi kanan dan kiri pasien 4. Motor level adalah segmen dengan otot yang memiliki fungsi motorik setidaknya skala 3 dari 6. 5. Penentuan neurological level of injury (NLI) 6. NLI adalah segmen paling caudal dari spinal cord pasien dengan fungsi sensorik dan motorik normal pada kedua sisi. Dapat diartikan juga bahwa NLI adalah segmen paling rostral pada sensory dan motor level pasien. 7. Penentuan tipe cedera (komplit/inkomplit) 8. Cedera dapat dikatakan komplit apabila voluntary anal contraction (-), deep anal pressure (-) dan nilai fungsi sensorik S4-5 (0). 9. Apabila tiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka cedera dapat dikatakan inkomplit. 10. Penentuan AIS Grade 11. AIS terdiri dari A (komplit), B (inkomplit sensorik), C (inkomplit motorik), D (inkomplit motorik) dan E (normal). Klasifikasi ND digunakan ketika hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tidak dapat menentukan tipe cedera spinal pada pasien. 2.4 SINDROMA KLINIK CEDERA SPINAL Pasien dengan cedera spinal dapat memiliki karakteristik yang khas pada tampilan klinis, yaitu seperti pada anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, central cord syndrome dan Brown-Sequard syndrome. Pemeriksa perlu cermat dalam mengenali karakteristik pola sindroma klinik tersebut pada pasien. 44 CEDERA SPINAL Anterior Cord Syndrome Pasien dengan anterior cord syndrome mengalami cedera pada jaras motorik dan sensorik yang berjalan di sisi anterior spinal cord. Tampilan klinis berupa paraplegia dan kehilangan sensasi nyeri dan suhu pada kedua sisi. Jarak yang berjalan di sisi posterior spinal cord (columna dorsalis) tetap intak sehingga fungsi proprioseptif dan getaran dalam batas normal. Sindroma klinis ini memiliki prognosis paling buruk bagi pasien. Posterior Cord Syndrome Pasien dengan posterior cord syndrome mengalami cedera pada jaras sensorik yang berjalan di sisi posterior spinal cord. Columna dorsalis yang berisi fasciculus gracilis dan cuneatus memiliki fungsi proprioseptif, getaran dan sensasi sentuh sehingga cedera pada sisi posterior akan menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi tersebut. Fungsi motorik dalam batas normal. Central Cord Syndrome Pasien dengan anterior cord syndrome mengalami cedera pada jaras yang melalui area tengah/sentral spinal cord. Mekanisme cedera terjadinya sindroma klinik ini adalah gaya hiperekstensi pada pasien yang telah memiliki cervical canal stenosis sebelumnya (terutama pada kelompok usia lansia). Tampilan klinis berupa kelemahan motorik dan fungsi sensorik bilateral terutama lebih buruk pada anggota tubuh bagian atas. Hal ini terjadi karena posisi anatomi serabut saraf di spinal cord untuk area tubuh atas hingga bawah tersusun bersebelahan dari medial hingga lateral, sehingga cedera dari tengah akan memberi dampak lebih dahulu pada segmen serabut bagian tubuh atas (cervical – thoracal – lumbal – sacral). 45 CEDERA SPINAL Brown-Sequard syndrome Pasien dengan Brown-Sequard syndrome mengalami cedera pada jaras yang berjalan di salah satu sisi spinal cord (hemisectio). Mekanisme terjadinya cedera pada sindroma klinik ini adalah luka tusuk (penetrating injury), luka tembak pada punggung maupun fraktur dislokasi columna vertebralis. Tampilan klinis berupa paraplegia dan gangguan proprioseptif, getaran dan sentuh pada sisi ipsilateral disertai kehilangan sensasi nyeri dan suhu pada sisi kontraleral dari cedera. 2.5 NEUROGENIC SHOCK DAN SPINAL SHOCK Gambar 23 Patofisiologi Neurogenic Dan Spinal Shock Pada Pasien Dengan Cedera Spinal Neurogenic shock kerap terjadi pada cedera spinal level tinggi (diatas T6) dan menyebabkan penurunan fungsi sistem saraf simpatis, baik gangguan aliran simpatis ke sistem vaskular sistemik sehingga sistem saraf parasimpatis menjadi dominan pada pasien. Penurunan sistem saraf simpatis menyebabkan dilatasi pasif sistem vaskular sistemik sehingga terjadi penurunan preload, stroke volume, 46 CEDERA SPINAL afterload, heart rate yang mana menjadikan penurunan cardiac output. Hal tersebut menyebabkan tampilan klinis berupa penurunan blood pressure, pulse rate dan body temperature pada pasien. Sementara itu, spinal shock adalah kondisi hilangnya refleks, fungsi bladder dan tonus otot di bawah level cedera yang terjadi secara akut setelah kejadiaan cedera spinal. 2.6 EKSKLUSI CEDERA SPINAL Pada pasien trauma dengan kecurigaan cedera spinal, pemeriksa dapat melakukan eksklusi secara pengamatan klinis menggunakan beberapa pilihan yaitu National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) Criteria dan Canadian C-spine Rule (CCR). Gambar 24 NEXUS Criteria 47 CEDERA SPINAL Gambar 25 Canadian C-spine Rule (CCR) Pasien dengan kecurigaan cedera spinal kerap kali telah terpasang cervical collar sebagai upaya c-spine control dan terbaring di long spine board sejak awal. NEXUS dan CCR dapat menjadi panduan untuk melakukan eksklusi cedera spinal secara klinis dan apabila tereksklusi maka pemeriksaan radiologi belum perlu dilakukan. Menurut kriteria NEXUS (Gambar 24), terdapat 5 kriteria resiko rendah yang perlu diperhatikan pada pasien. Apabila seluruh kriteria tersebut tidak ada pada pasien, maka cedera spinal dapat dieksklusi 48 CEDERA SPINAL dan pasien belum perlu melakukan pemeriksaan radiologi lanjutan. Sementara itu pada CCR (Gambar 25), perlu diperhatikan bahwa skema digunakan pada pasien trauma yang stabil dan sadar penuh (GCS 15) dimana cedera spinal dicurigai. Apabila pasien tidak memiliki faktor resiko tinggi yang memerlukan radiografi, terdapat faktor resiko rendah untuk dilakukannya pemeriksaan ROM dengan aman yang dilanjutkan dengan mampu melakukan rotasi leher ke kanan dan kiri secara aktif maka pasien belum perlu melakukan pemeriksaan radiologi lanjutan. 2.7 PENGGOLONGAN CEDERA SPINAL Penggolongan cedera spinal dapat dilakukan menggunakan sistem klasifkasi yang telah tervalidasi dan dikembangkan oleh AO Spine Knowledge Forum Trauma. Sistem Klasifikasi AO Spine untuk Subaxial dan Thoracolumbar Injury adalah hasil dari penilaian sistematis dan revisi dari klasifikasi Magerl dan telah mencapai konsensus sebagai klasifikasi yang menggabungkan morfologi fraktur dan faktor klinis yang relevan untuk pengambilan keputusan klinis. Gambar 26 Sistem Klasifikasi Cedera Subaxial oleh AO Spine 49 CEDERA SPINAL Fraktur pada subaxial (C3-C7) dapat diklasifikasikan menggunakan Sistem Klasifikasi Thorakolumbal oleh AO Spine (Gambar 4). Cedera dapat dibagi menjadi 4 kelompok: a. Cedera kompresi b. Tension Band Injuries c. Cedera bilateral d. Cedera translasi e. Cedera pada facet Penggolongan cedera dimulai dengan mengikuti alur bagan yang tersedia, pemeriksa dapat mencermati keberadaan dislokasi, tension band injury, fraktur pada corpus dan processus vertebra. Gambar 27 Sistem klasifikasi cedera thoracolumbar oleh AO Spine Sementara itu, fraktur pada thoracolumbar dapat diklasifikasikan menggunakan Sistem Klasifikasi Thorakolumbal oleh AO Spine (Gambar 5). Cedera dapat dibagi menjadi 3 kelompok: a) Cedera kompresi 50 CEDERA SPINAL b) Cedera distraksi c) Cedera translasi Penilaian status neurologis pasien menurut klasifikasi AOSpine sebagai berikut: a) N0 Neurologis intak b) N1 Defisit neurologis sementara, yang sudah tidak ada lagi c) N2 Gejala radicular d) N3 Trauma medspin inkomplit/adanya derajat cedera cauda equina apapun e) N4 Cedera medulla spinalis total f) NX Status neurologis tidak diketahui karena sedasi atau cedera kepala 2.8 TATALAKSANA CEDERA SPINAL Tindakan pencegahan pada kasus curiga fraktur tulang belakang harus diterapkan pada semua pasien trauma, sampai trauma tulang belakang dapat dieksklusi. Membatasi fleksi, ekstensi, rotasi, pada tulang belakang dapat membantu menghindari memperburuk cedera pada sumsum tulang belakang. Tindakan pencegahan dapat dihentikan setelah pemeriksaan radiografi dan pemeriksaan fisik mengindikasikan tidak adanya fraktur atau ketidakstabilan tulang belakang. Mempertahankan perfusi ke sumsum tulang belakang dengan perawatan suportif, termasuk tatalaksana jalan napas, pernapasan, dan manajemen sirkulasi dengan menjaga Mean Arterial Pressure (MAP) di atas 85 mmHg, sangat penting untuk meningkatkan perfusi sumsum tulang belakang. Prinsip penatalaksanaan awal cedera spinal di ruang gawat darurat, mengikuti prinsip Primary Survey pada ATLS: 51 CEDERA SPINAL • Airway dan C-spine control: Pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, pasang oropharyngeal airway (OPA)/nasopharyngeal airway (NPA) bila ada indikasi, pasien GCS < 8 setelah resusitasi adekuat, pertimbangkan untuk intubasi. Lakukan fiksasi pada leher dengan pemasangan cervical collar dan baringkan pasien pada long spine board. • Breathing: Nilai pergerakan dinding dada, frekuensi nafas, dan berikan suplementasi oksigen dengan Simple mask 6 LPM, cegah pasien mengalami hipoventilasi. • Circulation: Nilai tekanan darah, frekuensi nadi dan kekuatan nadi, dan saturasi oksigen, nilai tanda syok seperti akral dingan dan CRT< 2 detik, pasang IV-line berikan normal saline dan ambil sampel darah untuk pemeriksaan penunjang. • Jika pasien mengalami instabilitas dan masalah neurologis, tindakan pembedahan darurat mungkin diperlukan. Pasien dengan cedera multipel, resusitasi dan operasi darurat adalah prioritas pertama, sedangkan penundaan fiksasi fraktur umumnya dilakukan untuk memberi jalan pada tindakan penyelamatan nyawa. • Disability: Nilai fungsi neurologis awal pada pasien • Exposure/Environmental control: Pastikan pasien dalam kondisi hangat dan aman, lakukan pemeriksaan pada sisi posterior tubuh dengan melakukan manuver log roll. Setelah melakukan primary survey dan kondisi pasien stabil, pemeriksa dapat melanjutkan ke secondary survey yang terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan diagnostik lanjutan. Tatalaksana cedera spinal memiliki beberapa kontroversi, yaitu terkait manfaat pemberian steroid (Methylprednisolone) dan tindakan operatif awal untuk pasien. • Menurut kajian sistematis pada tahun 2017, pemberian steroid tidak memberikan dampak yang bermakna pada masa 52 CEDERA SPINAL • • • • pemulihan neurologis jangka panjang walaupun pemberian dosis tinggi dalam 8 jam pertama setelah cedera dikatakan memberi manfaat minimal untuk pemulihan motorik jangka panjang. Panduan pelatihan ATLS edisi ke-10 tahun 2018 oleh komite trauma dan American College of Surgeons menyebutkan bahwa penggunaan steroid untuk cedera spinal belum disokong dengan bukti yang cukup. Pada Greenberg handbook edisi ke-9 tahun 2019 disebutkan bahwa pemberian methylprednisolone tidak disetujui oleh FDA sebagai pengobatan cedera spinal akut. Dekompresi dalam 24 jam pertama setelah trauma dapat dilakukan secara aman dan berhubungan dengan peningkatan prognosis neurologis pasien. Tindakan operatif awal dapat menjadi pilihan bagi pasien cedera spinal pada level manapun. 2.9 RUJUKAN KASUS CEDERA SPINAL Pasien dengan fraktur spinal maupun defisit neurologis perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu memberikan tatalaksana definitif. Hindari penundaan rujuk yang tidak perlu dan segera rujuk pasien di IGD untuk penanganan lanjutan pasien yang diduga cedera spinal dengan menggunakan long spine board dan collar neck untuk menjaga spinal dalam kondisi inline. Pasien dengan cedera cervical diatas C6 beresiko mengalami gangguan fungsi pernafasan parsial maupun total. Pada kasus yang sudah terkonfirmasi cedera spinal, tetap lakukan imobilisasi sampai dilakukan terapi definitif. 53 CEDERA SPINAL Daftar Pustaka 1. American College of Surgeons (2018) Advanced Trauma Life Support. Chicago: American College of Surgeons. 2. Anissipour, A.K. et al. (2017). Traumatic Cervical Unilateral and Bilateral Facet Dislocations Treated With Anterior Cervical Discectomy and Fusion Has a Low Failure Rate. Global Spine Journal, 7(2), 110-115 3. Calvo-Invante, RF. et al. (2018). Cardiovascular complications associated with spinal cord injury. Journal of Acute Disease. 7(4): 139-144 4. Dai, L. (2012) ‘Principles of Management of Thorakolumbal Fractures’, Orthopaedic Surgery, 4(2), pp. 67–70. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1757-7861.2012.00174.x. 5. Fernández-de Thomas, R.J. and de Jesus, O. (2022) Thorakolumbal Spine Fracture. Treasure Island: Statpearls Publishing. 6. Joaquim, A.F. et al. (2018) ‘Clinical application and cases examples of a new treatment algorithm for treating thoracic and lumbar spine trauma’, Spinal Cord Series and Cases, 4(1), p. 56. Available at: https://doi.org/10.1038/s41394-018-0093-4. 7. Lee, P., Hunter, T. B., & Taljanovic, M. (2004). Musculoskeletal Colloquialisms: How Did We Come Up with These Names? RadioGraphics, 24(4), 1009–1027.doi:10.1148/rg.244045015 8. Nagasawa, H. et al. (2017). A case of real spinal cord injury without radiologic abnormality in a pediatric patient with spinal cord concussion. Spinal Cord Series and Cases, 3, 17051. 9. Rumboldt, Z., Cianfoni, A., & Varma, A. (Eds.). (2018). Clinical Imaging of Spinal Trauma: A Case-Based Approach. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139871372. 54 CEDERA SPINAL 10. Tattersall, R., & Turner, B. (2000). Brown-Séquard and his syndrome. The Lancet, 356(9223), 61–63.doi:10.1016/s01406736(00)02441-7 11. Vaccaro, A.R., et al. (2013). AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System. Spine, 38(23), 2028–2037. doi:10.1097/brs.0b013e3182a8a3 12. Vaccaro, A.R., et al. (2016). AOSpine subaxial cervical spine injury classification system. European Spine Journal, 25(7), 2173–2184. doi:10.1007/s00586-015-3831-3 13. Verheyden, A.P. et al. (2018) ‘Treatment of Fractures of the Thorakolumbal Spine: Recommendations of the Spine Section of the German Society for Orthopaedics and Trauma (DGOU)’, Global Spine Journal, 8(2_suppl), pp. 34S-45S. Available at: https://doi.org/10.1177/2192568218771668. 55 BAB III BAB III MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL 3.1 PENDAHULUAN Hipertensi intrakranial atau yang lebih dikenal dengan peninggian tekanan intrakranial (TIK), yang tidak dapat diatasi akan menyebabkan kerusakan dan kematian sel-sel otak karena tekanan perfusi ke otak tidak mencukupi kebutuhan metabolisme otak. Keadaan ini dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, misalnya trauma, perdarahan, tumor, infeksi maupun infark. Semenjak ditemukannya alat monitoring untuk mengukur TIK, banyak informasi telah dikumpulkan mengenai proses pathofisiologi yang terjadi. Serta macam- macam pengobatan untuk menurunkan TIK. 3.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI Tengkorak pada orang dewasa adalah merupakan rongga yang tertutup dan berisi komponen saraf, cairan otak dan darah (arteri dan vena) yang mempunyai volume ± 1400 - 1500 cc. Tiap-tiap komponen ini tidak dapat di tekan. Tengkorak hanya memiliki satu lubang yaitu foramen magnum. Otak dipisahkan secara kaku oleh tentorium menjadi serebelum dan serebrum, melalui incisura tentorium, lewat mesencephalon. Falx cerebri memisahkan serebrum menjadi hemisphere kiri dan kanan. Sirkulasi Cairan Otak (Liquor Cerebro Spinalis Fluid = LCS) LCS ± diproduksi terutama oleh plexus choroidus yang berada di ventrikel lateral kiri dan kanan, ventrikel III dan Ventrikel IV. Sedangkan yang 30% oleh ekstra choroidal (ependym dan parenkim otak). Tiap menit produksi liquor ± 0,35 cc, 24 jam ± 500 cc. Plexus choroideus terbentuk dari invaginase vasular pia yang dilapisi permukaan epithelium dari ependym yang melapisi ventrikel. Luas permukaan 56 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL plexus choroideus dari kedua ventrikel lateral ± 40 cm2. Produksi liquor melalui proses yang kompleks. Beberapa komponen dari plasma secara selektif melalui dinding kapiler serta epithelium choroids, yang lain secara difusi sedang yang lain lagi melalui bantuan aktivitas metabolisme sel-sel epithel choroids. Aktif transport ion-ion tertentu (Na) melalui epithelial sel, diikuti pergerakan pasif dari air untuk mempertahankan keseimbangan osmotis antara CSF dan plasma darah. Produksi liquor dari choroid plexus mengalir di dalam sistim ventrikel lateral kiri dan kanan melalui sepasang foramen Monro ke dalam ventrikel III dan melalui aquaduct Sylvii menuju ke ventrikel IV, selanjutnya mengalir ke rongga subarachnoid melalui sepasang foramen Luscha dan foramen Magendi ke sisterna magna. Sebagian liquor mengalir ke rongga subarachnoid di spinal dan sebagian besar ke sisterna ambien disekitar mesencephalon dan sebagian lagi ke rongga subarachnoid di konveksitas hemisphere. Penyerapan dari liquor ini terjadi melalui villi arachnoid ke sistim vena (sinus sagitalis seperior). Villi ini bekerja berdasarkan perbedaan tekanan dan bergerak ke satu arah. Bila tekanan liquor lebih tinggi dari tekanan vena, katup terbuka, sedangkan bila tekanan liquor menurun dibawah tekanan vena, katup akan menutup untuk mencegah darah masuk dari sinus ke rongga subarachnoid. Saat kondisi normal produksi dan absorbsi liquor seimbang, absorbsi akan bertambah bila tekanan liquor bertambah. Bila terjadi halangan pada aliran liquor akan terjadi peninggian tekanan liquor yang akhirnya dikompensasi dengan peninggian TIK untuk mengalirkan cairan liquor dan absorbsi lebih baik. Absorbsi liquor ditempat lain selain villi arachnoid yaitu di lapisan ependym ventrikel dan di selubung saraf spinal. Sebagian besar liquor mengelilingi seluruh permukaan otak dan medulla spinalis, di rongga subarahnoid sebanyak 75-100 cc, diventrikel sebanyak 25-40 cc. 57 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Fungsi liquor sebagai pembersih zat-zat pathologi yang ada dalam otak (pengukuran jumlah cairan liquor dengan MRI). Jumlah liquor bertambah dengan bertambahnya umur. Liquor terdiri dari air, sedikit protein, O2 dan CO2 yang larut di dalamnya, ion Natrium, ion Kalium, ion Chlorida, glukosa dan beberapa limposit. LCS (cairan otak) merupakan cairan isotonik terhadap plasma. Di dalam ventrikel kadar protein 0,256 ± 0,059 gr/lt di cisterna magna 0,316 ± 0,059 gr/lt. Dalam keadaan normal tekanan intrakranial ditentukan oleh 2 faktor : 1. Hubungan tekanan pembentukan LCS dan resistensi aliran LCS ke vena cerebri. 2. Tekanan sinus venous dura (efek tekanan yang dapat membuka sistim drainage) TIK = CSF pressure = (Banyaknya pembentukan X Resisten Aliran) + Tekanan Sinus Venous Gambar 28 Rumus Tekanan Intrakranial Tekanan pembentukan liquor hampir selalu konstan pada perubahan TIK, mungkin menurun bila TTIK sangat tinggi. Sebaliknya absorbsi cairan liquor tergantung perbedaan tekanan LCS dengan sinus venous, sehingga absorbsi akan bertambah, bila TIK makin tinggi. Cerebral Blood Volume (CBV) Penyebab yang paling sering menimbulkan peninggian TIK dan nyata secara klinis adalah bertambahnya volume darah di otak. Hal ini disebabkan dilatasi pembuluh darah arteri yang berhubungan dengan bertambahnya cerebral blood flow (CBF; aliran darah ke otak) atau oleh adanya penyumbatan aliran darah vena dari rongga otak, yang berhubungan dengan penurunan CBF. Pengukuran CBV, CBF, dan extraxsi O2 dapat dilakukan secara langsung dengan Position Emission Tomography (P.E.T) scaning. Jumlah volume darah di otak ± 58 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL 100 cc; 70% jumlah darah yang diotak berada di pembuluh vena. Dari 3 komponen yang berada di otak, volume darah yang paling cepat berespons terhadap perubahan TTIK. PaCO2, PaO2, CBF, dan CBV Pembuluh darah arteriole di otak merupakan pembuluh darah di dalam tubuh yang paling sensitif terhadap perubahan metabolisme dilingkungannya, yang berarti regional CBF akan berespons terhadap kebutuhan metabolisme didaerah tersebut. Bahan yang paling sering menyebabkan vasodilatasi adalah CO2. Tiap perubahan 1 mmHg CO2, akan menyebabkan perubahan CBF 2-4 %. Jadi CBF akan naik 2x lipat bila PCO2 naik dari 40 mmHg menjadi 80 mmHg dan turun ½ nya bila PCO2 20 mmHg. Bila PaCO2 < 20 mmHg, CBF tidak berefek lagi, malah terjadi vasokontriksi. hebat dan akan mengakibatkan hypoxia. Bila kadar PaO2 menurun, CBF akan naik. Pada PaO2 30 mmHg, CBF akan naik 2x lebih banyak. Tujuan dilatasi pembuluh darah adalah agar penambahan CBF ke otak mencukupi kebutuhan jaringan otak. Selama penambahan CBF dapat mengkompensasi kadar O2 darah; metabolisme otak akan normal. Bila PaO2 turun sampai 20 mmHg rangsang untuk vasodilatasi akan maksimal, akan terjadi anaerob glikolisis dan penurunan oksidasi posforilasi. Peninggian PaO2 mengakibatkan sedikit perubahan CBF. Pemberian oxygen 100% (1 atmosfir) akan menurunkan CBF 10% dengan 2 atmosfir hanya akan menurunkan 20%. Perubahan PaCO2 dan PaO2, mem-pengaruhi ICP melalui perubahan diameter pembuluh darah dan CBF. Mekanisme yang bertanggung jawab terhadap perubahan pembuluh darah ini karena pengaruh konsentrasi H+ di cairan ekstraseluler, calcium, kalium, prostaglandin, dan adenosin. Efek lain dari hypoksia terhadap dinamika intrakranial saat ini dapat diukur dengan alat transduser 59 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL yang dipasang di dalam ventrikel lateral kanan dengan hasil akurat, aman mudah dan tidak mahal. Volume Otak Otak mempunyai volume 1500 cc; merupakan 2% dari berat badan. Volume glia 700- 900 cc dan neuron sebanyak 500-700 cc. Glia dan neuron menempati 70% volume otak sedangkan cairan extraseluler, darah dan liquor masing-masing 10%. Kadar air di substansia alba 70%, sedangkan disubstansia grisea 80%. Sebanyak 80% air berada di intraceluller. Cairan extraceluller mengandung air < 75 cc, dan ini bisa bertambah sampai 10%. Ronggga extraceluller ini berhubungan dengan liquor melalui ependym. Blood Brain Barrier (Sawar Darah Otak) Komponen anatomi Sawar Darah Otak (SDO) adalah kapiler di otak yang merupakan sel endothel yang membatasi darah yang ada didalam kapiler dengan jaringan di sekitarnya. Disekitar permukaan sel endothel dilapisi oleh lamina basal yang sangat erat berhubungan tight junction. Disebelah luarnya dilapisi oleh kaki-kaki astrosit dan mempunyai celah diantara kaki-kakinya. Dinding kapiler ini dapat dilalui oleh bahan- bahan yang larut dalam lemak dan membatasi lewatnya molekul hidropolik yang polar karena adanya tight junction tersebut. Gula dan asam amino melewati dinding kapiler ini dengan proses pembawa molekul yang spesifik. Pada transport natrium dan kalium dan juga air ATP berperanan sangat penting. Gangguan SDO ini dapat terjadi pada beberapa penyakit misalnya trauma sehingga molekul-molekul yang besar dapat melewati SDO ini, dan akibatnya terjadi edem. Gangguan SDO dapat terjadi dengan pemberian cairan hipertonis atau kontras media atau mannitol, bila di berikan melalui arteri. Hal ini akan menyebabkan 60 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL terbukanya SDO secara temporer, sehingga sering dipakai sebagai pengobatan. Harus dibedakan pemberian mannitol secara IV untuk mengobati TTIK. Pada keadaan ini perubahan osmolaritet darah. 3.3 PATOLOGI DARI TEKANAN TIK Bila sutura sudah sempurna terbentuk, volume intrakranial akan selalu konstan. Isi dari cranium yaitu jaringan otak, liquor dan darah, bila mengalami peninggian TIK, salah satu dari komponen tersebut harus dikurangi/dipindahkan. LCS dialirkan dari sistem ventrikel ke rongga subarachnoid melalui sepasang foramen Luscha dan Magendi yang kemudian akan diabsorpsi di sinus spenosus melalui villi choroid ke sinus sagitalis superior (SSS). Rongga subarachnoid di medulla spinalis masih dapat berkembang karena adanya lemak dan vena plexus venous di ruang epidural. Mekanisme pengeluaran liquor ini terbatas. Bila terjadi sumbatan atau gangguan aliran produksi liquor yang terus terjadi diatas sumbatan tersebut akan meninggikan TIK. Darah yang dapat dipindahkan atau dialirkan kedalam sinus venosus dura adalah darah vena yang berada dipermukaan superficial dan vena-vena yang dalam, ke vena-vena ekstrakranial. Seperti halnya pengeluaran liquor dari rongga tengkorak, mekanisme ini juga terbatas karena volume darah yang dapat dikeluarkan dari otak hanya sedikit. Otak sendiri merupakan bagian yang paling sedikit dapat dipindahkan ke bagain yang lain. Pada tumortumor yang tumbuh lambat, misalnya meningioma pergeseran otak dapat banyak tanpa perubahan TIK yang berarti, mungkin hal ini disebabkan karena penurunan cairan di ekstraseluler dan kadar lemak disekitar tumor tersebut. Pada masa yang cepat berkembang otak akan bergeser ke bagian yang lain (Tentorial Herniasi atau Subfalcin Herniasi) atau melalui foramen Magnum (Tonsilar Herniasi). Pertambahan volume di dalam intrakranial mula-mula akan dapat dikompensasi, dengan cara mengeluarkan darah vena dan 61 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL liquor sampai titik tertentu dimana liquor dan darah tidak dapat dikeluarkan lagi dan terjadi keadaan dekompensasi, yaitu setiap CC pertambahan volume akan secara signifikan meninggikan TIK. Tekanan intrakaranial diatas 20 mmHg berhubungan dengan peninggian resistensi aliran liquor. Pada CT scan bila cisterna perimesencephalic mengalamai obiterasi, hal ini menunjukkan peninggian TIK dan merupakan tanda-tanda adanya bahaya. Pada keadaan klinis tertentu (head injury) perubahan volume merupakan suatu proses yang komplek dimana bekuan darah, edem cerebri, gangguan absorbsi liquor yang disebabkan oleh adanya darah dirongga subarachnoid atau di dalam ventrikel. Juga ditambah dengan vasodilatasi karena kerusakan autoregulasi atau adanya hypercapia. Hubungan antara peninggian TIK dengan gambaran klinis tergantung dari cepatnya perubahan volume dan adanya pergeseran dari otak. Peninggian TIK dapat ditolerir bila tidak didapatkan perpindahan jaringan otak sebagai contoh bila komunikasi aliran liquor lancar, dan tidak di dapatkan pergeseran jaringan otak walaupun didapatkan pupil edem yang jelas. Konsekuensi dari peninggian TIK Penambahan masa yang cepat misalnya epidural hematoma, mula-mula TIK bertambah sedikit demi sedikit dimana pasien masih sadar, tetapi bila masa bertambah dan terjadi dekompensasi, pasien mengeluh sakit kepala, terjadi penurunan kesadaran dan bila terjadi penekanan batang otak akan terjadi tekanan darah meninggi sedangkan nadi menurun. Bila perdarahan terus bertambah, TIK terus meninggi terjadi dilatasi pupil pada sisi yang sama akhirnya reflek batang otak menurun. Akhirnya fungsi batang otak hilang, tekanan darah menurun, nadi berkurang, pernafasan perlahan dan tidak teratur lalu berhenti. 62 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Tekanan Intrakranial dan CBF Tekanan intrakranial dapat berpengaruh terhadap CBF melalui beberapa langkah: 1. Penekanan dari arteri cerebri anterior karena adanya herniasi subfalcin atau penyumbatan arteria cerebri posterior karena herniasi tentorium. 2. Karena batang otak terdorong ke bawah perforating arteri tertarik dan menyebab- kan ishemi batang otak serta putusnya arteri tersebut dan vena-vena batang otak. 3. Penurunan Cerebral Perfusi. Meskipun otak hanya 2% dari berat badan otak menerima 15% dari cardiac output dan menggunakan 20% glukosa. Bila terjadi ischemi dalam waktu yang singkat akan mengakibatkan gangguan neuron yang irreversible. CBF selalu dipertahankan normal 50 CC/100 gr jaringan otak/menit. CBF di substansia grisea 80 CC/100 gr jaringan otak/menit, sedangkan di substansia alba 20 CC/100 gr jaringan otak/menit. CBF yang normal ini diatur oleh autoregulasi yang berada di arterioles. Bila tekanan darah naik arterioles menyempit yang akan mengakibatkan peninggian resistensi pembuluh darah dan mencegah peninggian CBF. Sebaliknya bila tekanan darah menurun terjadi dilatasi arterioles. Di pembuluh darah aliran tergantung perbedaan tekanan antara arteri dan vena – tekanan perfusi – dan resistensi pembuluh darah: Aliran Darah = Tekanan Arteri – Tekanan Vena Resistensi Pembuluh Darah Pada tengkorak yang sudah tertutup: CBF = Tekanan Arteri – Tekanan Sinus Sagittalis Resistensi Pembuluh Darah Otak 63 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Pada kenyataannya tekanan sinus sagittalis adalah 1-2 mmHg lebih rendah dari TIK, sehingga ICP dapat dianggap sama dengan tekanan sinus sagittalis superior: CBF = Tekanan Arteri – TIK Resistensi Pembuluh Darah Peninggian TIK akan menurunkan tekanan perfusi. Bila pembuluh darah masih dapat me lakukan autoregulasi, maka terjadi penurunan resistensi pembuluh darah otak sehingga menyebabkan CBF konstan. Bila autoregulasi terganggu, CBF akan menurun, bila auto regulasi hilang resistensi pembuluh darah otak akan berdilatasi secara pasif. Perubahan CBF disesuaikan dengan kebutuhan metabolisme regional, CBF ditentukan oleh: 1. Tekanan darah arteri 2. Tekanan intrakranial 3. Autoregulasi 4. Stimulasi merangsang metabolisme 5. Penekanan atau pergeseran pembuluh darah karena herniasi atau masa Tekanan Intrakranial dan Pergeseran Otak Gejala klinik TIK yang meninggi banyak disebabkan karena adanya pergeseran otak dari pada peninggian TIK-nya. Pergeseran otak dibagian medial temporal (uncus) melalui hiatus tentorium akan menyebabkan batang otak terdorong ke ke arah transversal. Nerves III yang terdorong menyebabkan dilatasi pupil satu sisi. Pendesakan cerebral peduncle menyebabkan hemiparese sisi yang lain. Pendesakan yang berlangsung lebih lanjut akan mendorong peducle cerebri sisi lain sehingga menyebabkan hemiparese sisi yang sama atau tetraparese. Penekanan pada sisi yang lain itu disebut juga Kernohan Notch. Arteri cerebri posterior dapat terjepit pada tepi tentorium akan menyebabkan infark di lobus occipitalis dan menyebabkan hemianophia. 64 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Herniasi central dapat terjadi bila didapatkan tumor di frontal sehingga kedua temporal lobe bagian medial mendorong batang otak, penekanan ini menyebabkan tectum terdorong ke arah bawah sehingga terjadi parese upware dan bilateral ptosis. Herniasi tonsilar terjadi bila masa supratentorial mendorong secara progresif menekan batang otak ke bawah, dapat juga oleh tumor fossa posterior sehingga tonsil masuk ke dalam foramen Magnum yang menyebabkan fungsi batang otak terganggu. Gambaran klinis terjadinya tortikolis, penurunan kesadaran serta gangguan pernafasan secara cepat. Bila terjadi pergeseran garis tengah dari otak terjadi herniasi subfalcine yaitu girus cinguli yang berada di bawah falx akan terdesak ke bagian yang lain sehingga arteri cerebri anterior terjepit dan menyebabkan parese tungkai pada sisi yang lain hal ini jarang terjadi. Pada keadaan normal hubungan cairan pada rongga subarachnoid dengan tekanan sepanjang neuroasis adalah samal. Bila didapatkan masa di dalam tengkorak yang makin bertambah, mula-mula tekanan ini dialirkan melalui cairan liquor ke semua arah tetapi bila aliran melalui tentorium atau foramen Magnum sudah mulai tersumbat tekanan di bawah sumbatan tersebut tidak lagi menggambarkan tekanan di atasnya. Pemeriksaan TIK melalui lumbal fungsi pada keadaan demikian tidak bisa dipercaya dan sangat bahaya. Pada keadaan dimana masa semakin bertambah akan terjadi pergeseran jaringan otak ke arah dimana TIK yang rendah agar terjadinya keseimbangan. Selama masih bisa terjadi pergeseran, tekanan intrakranial dapat menurun kembali karena penambahan masa tersebut secara temporer dapat menyesuaikan. Brain Edema menambah volume otak karena bertambahnya air didalam jaringan otak, sedangkan Brain Sweling bertambahnya volume yang bisa terjadi didalam jaringan otak (Brain edema) atau di dalam intravaskuler. Seperti telah kita ketahui air yang ada didalam substansia grisea otak adalah 80%; didalam 65 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL substansia alba 68%. Pada otak yang mengalami edematus jumlah cairan yang berada di dalam substansia grisea menjadi 82% sedang yang disubstansia alba menjadi 77%. Jadi penambahan air lebih banyak ter- jadi disubstansia alba yang bila dilihat pada CT atau MRI; beberapa jenis brain edema: 1. Vasogenic 2. Cytotoxic 3. Hydrostatic 4. Hypoosmoler 5. Intertitial Yang terpenting pada kasus-kasus bedah saraf adalah vasogenic edema yang ditandai dengan adanya peninggian permeabilitas kapiler di otak. Hal ini terlihat disekeliling contusio cerebri, tumor cerebri, absces dan pinggiran infark. Edem macam ini yang berespon baik terhadap pemberian steroid. Pada edem citotoxic semua elemen sel di dalam otak baik neuron, glia, maupun endothel dapat mengalami pembengkakan yang diikuti dengan hilangnya rongga ekstraseluler. Hypoxia dan hypoosmoler yang terjadi secara akut yang terlihat pada intoksikasi air akan memberikan gambaran seperti ini. Pada akut hydrocephalus obstruktif akan tampak gambaran radiolucent periventrikuler bila dilakukan pemeriksaan dengan CT Scan. Edem ini disebut intertitial edem karena tekanan liquor dalam ventrikel menyebabkan air menyeberangi ependym ke dalam substansia alba di periventrikuler, ha ini juga dibuktikan dengan MRI. Kemampuan isi tengkorak untuk menampung perubahan volume tergantung dari tekanan intrakranial dan kelenturan otak, seperti pada gambar dibawah ini setiap penambahan volume akan meninggikan tekanan intrakranial setelah elastan otak terlampaui. 66 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL 3.4 Gambar 29 Tekanan intrakranial (TIK) dan penambahan volume. CSS: cairan serebrospinal GEJALA KLINIS TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL (TTIK) Gambaran klasik dari TTIK adalah sakit kepala, papil edema dan muntah-muntah. 2/3 penderita dengan masa mempunyai 3 gejala tersebut atau paling sedikit 2 gejala tersebut. Gejala-gejala TTIK tergantung dari cepatnya masa itu bertambah dan dimana letak masa tersebut. Tidak ada hubungan antara tingginya TIK dengan beratnya gangguan tersebut. Sakit Kepala Bagian dari otak yang sensitif terhadap rasa sakit adalah cabangcabang dari arteri meningea media, bagian proximal, pembuluh darah arteri yang besar di basis, sinus venosus dan bridging vein serta dura di dasar tengkorak. TIK yang berhubungan dengan pergeseran otak atau pergeseran pembuluh darah dan sinus venosus menyebabkan sakit kepala yang terlokalisir. Makin terlokalisirnya rasa sakit karena pergeseran daerah di basal dura mater yang dibawa oleh saraf otak sensoris ke V, IX dan X. Sakit kepala dapat juga disebabkan oleh spasme otot-otot di dasar 67 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL tengkorak yang bisa terjadi karena ototnya sendiri atau sebagai refleks bila mekanisme sakit berperanan. Sakit kepala yang ber-hubungan dengan TTIK digambarkan oleh Wollf; sakit kepala bila penderita dalam posisi duduk karena pengeluaran liquor dan hal ini dirasakan didaerah depan dan vertex pada percobaan dengan menyuntikkan NaCl intratekal selama 1-2 menit yang menyebabkan tekanan intrakranial mencapai 60 mmHg, hal ini tidak menyebabkan sakit kepala. Begitu juga bila seseorang meniup balon sehingga terjadi penekanan vena atau pada percobaan falsafah yang menyebabkan TIK mencapai 35-70 mmHg penderita tidak merasakan sakit kepala. Jadi TTIK walau sangat tinggi tidak selalu menimbulkan sakit kepala. Kombinasi dari dilatasi venous, tarikan dari bridging vein dan tarikan arteri di basal kranii yang sering menyebabkan sakit kepala. Pada penderita dengan TIK yang meninggi secara difus, tarikan dari pembuluh darah minimal dan jarang menimbulkan sakit kepala. Bila diikuti dengan tarikan pembuluh darah atau penekanan dura di basal yang sensitif akan lebih sering menyebabkan sakit kepala. Jadi rasa sakit dikepala ini sering terbatas pada Nervus V, IX dan X bersama sama dengan arteri posterior dari tiga saraf teratas cervical. Macam-macam sakit kepala Sakit kepala karena TTIK dirasakan tidak begitu hebat, hanya dirasa sebagai rasa tidak enak, tapi akan terasa hebat bila penderita batuk, bersin, atau menundukkan kepala. Sakit kepala ini tidak terlokalisir secara jelas dan tidak spesifik dapat dirasakan dikedua frontal atau occipital. Sakit kepala didaerah occipital dapat menyebar ke leher seperti adanya masa di fossa posterior atau tumor di CPA yang menyebabkan sakit disekitar telinga. Sakit kepala ini baik dengan analgetik tetapi bertambah jelek dengan alkohol. 68 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Sakit kepala pagi hari sering terjadi bila penderita bangun yang hilang dalam 1-2 jam, sakit kepala pagi hari ini karena TIK terjadi pada malam harinya karena posisi penderita terlentang, adanya peninggian PCO2 saat tidur, karena depresi pernafasan dan mungkin karena absorbsi CSF menurun. Pada waktu tidur pada periode non-rem ventilasi akan berkurang, makin dalam tidur seseorang makin rendah ventilasinya. Peninggian PCO2 ini akan menyebabkan vasodilatasi dan meninggikan jumlah darah di otak, TIK dan brain swelling yang akan memperburuk tarikan atau pergeseran dari pembuluh darah di otak sehingga menyebakan sakit kepala. Pada waktu bangun pasien dengan sakit kepala hebat dapat menyebabkan muntah, merangsang terjadinya hiperventilasi dan penurunan PaCO2. Bila penderita duduk tegak akan terjadi venous return bertambah lalu akan menyebabkan penurunan ICP sehingga penderita merasa lebih enak dan melakukan aktifitas normal, gejala tadi sering diabaikan dan dianggap sebagai gejala psikologis. Papil Edema Saraf otak ke-2 adalah tonjolan dari otak yang dilapisi oleh meningen dan subarachnoid. TIK juga disebabkan disekeliling saraf tersebut, hal ini dapat dilihat secara jelas melalui funduskopi pada nerves optikus. Papil edema akan tampak setelah beberapa waktu walaupun TIK yang meninggi itu terjadi secara akut misal adanya SAH ataupun cedera kepala berat. Walaupun TIK yang meninggi yang sudah terjadi beberapa waktu pada funduskopi tidak tampak adanya papil edem hal ini disebabkan tidak adanya penekanan langsung pada N. II atau adanya obiterasi aliran liquor karena adanya tumor. 69 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL 3.4 GAMBARAN KLINIS Papil edema pada anak-anak tidak jelas tampak karena TIK masih dapat dikompensasi dengan bertambahnya rongga kranium. Pada orang tua dimana otak sudah mengalami atropi, bertambahnya masa yang luas seperti halnya pada kronik subdural hematom tidak menyebabkan TTIK. Visus biasanya terganggu pada tahap akhir, gambaran kampimeter menunjukkan adanya blind spot yang melebar dan lapang pandang yang menyempit. Gangguan pandangan atau hilang sebagian atau seluruhnya selama beberapa detik kemudian kembali normal yang disebut amakurosis fugax mempunyai arti yang penting. Selain gambaran tersebut diatas kadang-kadang mendapatkan serangan pandangan kabur atau gangguan persepsi warna yang berubah, ini mungkin disebabkan karena gangguan suplai darah pada papil edem yang hebat, gejala-gejala tersebut diatas sering disalah interpretasikan sebagai epilepsi atau vertigo. Gambaran histologis yang mula-mula tampak adalah pembengkakan disc adalah dilatasi axon diikuti transport axoplasmic autograf dari neuron di retina. Axoplasmic transport ini merupakan alur yang kompleks diorganel intrasesuler dari nucleus ke sinaps yang disebut orthograde atau sebaliknya yang disebut retrograde. Pelebaran pembuluh darah dan edem menambah bengkaknya tetapi perubahan yang terjadi sebenarnya berada di selaput saraf tersebut. Mula-mula di duga TIK yang meninggi menyebakan cairan liquor disekitar nervus optikus meng- antarkan tekanan tersebut dan menekan vena sentralis di retina. Edem dari ujung saraf ke II yang tampak pada funduskopi dan kelihatan edem karena vena retina tersebut melebar. Mekanisme papil edem tersebut secara tepat sampai saat ini sebenarnya belum diketahui mungkin disebabkan campuran antara hipoxia, mekanik dan faktor vaskuler. 70 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Gejala lain Gejala akhir secara klinis pada TTIK adalah bradicardi dan tekanan arteri sistemik yang meninggi. Bradicardi dan hipertensi disebabkan karena penekanan pada batang otak atau ischemi, ini tidak berhubungan dengan tingginya TIK. Adanya gejala- gejala tersebut merupakan merupakan gejala-gejala yang sudah terlambat dan berbahaya dan biasanya oleh adanya masa yang sudah besar atau yang menekan langsung batang otak. Gejala lain yang sering tampak pada pasien dengan TTIK adalah dilatasi pupil, ptosis bilateral, gangguan melihat keatas, ekstensi estrimitas pada rangsang sakit, pernafasan yang irreguler. Gambaran tersebut diatas karena adanya herniasi tentorium dan herniasi tonsil atau penekanan langsung pada batang otak. Pupil yang oval merupakan gejala penting karena adanya tahapan transisi antara pupil normal dan pupil yang tidak bereaksi, hal ini menunjukkan adanya peninggian tekanan intrakranial yang signifikans yaitu bila tekanan intrakranial berada diantara 20-30 mmHg. 3.5 PENANGANAN Penanganan TIK harus dilakukan sedini mungkin. Penderita kelainan intracerebral secara akut misalnya cedera kepala dan stroke harus dianggap memiliki potensi peninggian TIK sampai terbukti tidak ada peninggian intrakranial. Pada setiap langkah penanganan dimulai pada tempat kejadian dan menghindarkan faktor-faktor yang dapat meninggikan TIK. Monitoring ICP menunjukkan bahwa standard anesthesi dan prosedur pemakaian peralatan sering menyebabkan peninggian TIK, sebagai contoh TTIK dapat meninggi secara cepat ketika melakukan intubasi, karena cadangan volume intrakranial sudah berkurang karena adanya masa. Fisiotherapi pada dada dan suction endotracheal dapat menyebabkan TIK meninggi cepat walaupun pasiennya lumpuh. 71 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Prosedur Penanganan Standar prosedur penangan pasien yang diduga mengalami peninggian TIK atau yang sudah mengalami intrakranial, yaitu: 1. Posisi kepala pasien 30°, meskipun posisi yang lebih tinggi daripada badandapat menurunkan tekanan sistemik arteri hal ini dapat juga menimbulkan CPP. Perlu dilakukan monitoring secara hati-hati. 2. Menjaga agar temperatur badan normothermi 3. Pemberian obat-obatan analgetik yang cukup 4. Pemasangan endotracheal bila jalan nafas terganggu Pada cedera kepala sedang atau berat selalu harus dipikirkan kemungkinan peninggian TIK karena hal-hal tersebut dibawah ini: 1. Adanya lesi masa (bekuan atau contusi) 2. Penambahan volume darah otak 3. Penambahan air di otak 4. Penambahan cairan liquor Lesi masa harus dideteksi dengan pemeriksaan CT Scan dan bila positif harus segera di keluarkan. Penyebab yang paling sering peninggian intrakranial pada 24 jam pertama setelah suatu cedera kepala adalah dilatasi pembuluh darah yang menyebabkan volume darah otak bertambah. Edema otak biasanya terjadi kemudian, kecuali disekitar jaringan otak yang mengalami contusi. Obstruksi dari aliran liquor sering terjadi bila didapatkan darah di dalam ventrikel dan bisa diketahui dengan CT scan. Ventilasi Pembuluh darah otak sangat sensitif terhadap kadar CO2 (N 3540 mmHg). Hubungan CBF dan PCO2 arteri yang pada grafik diatas masih berbentuk linier sampai 20 mmHg dan bila terjadi penurunan akan sedikit berefek pada CBF. TIK akan menurun dalam waktu beberapa menit bila dilakukan hiperventilasi dan efek ini dapat 72 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL berlangsung beberapa jam, setelah itu pembuluh darah otak akan berdilatasi dan akan menyebabkan TTIK. PCO2 tidak boleh diturunkan < 25 mmHg, pada titik ini efek vasokonstriksi karena hypocardia dapat menyebabkan hypoxia dan dilanjutkan ischemi dan kerusakan otak. Cara atau metode untuk melakukan kontrol ventilasi 1) IPPV (Intracranial Positive Pressure Ventilation) Cara ini banyak digunakan dengan tekanan yang positif dan volume yang tetap diikuti ekspirasi yang pasif pada tekanan atmosfir, ini berarti tekanan intrathoracal lebih tinggi daripada pernafasan spontan dan keadaan ini dapat menyebabkan tekanan vena intracerebral meninggi dan mengakibatkan tekanan intrakranial meninggi 2) PEEP (Positive and Expiratory Pressure) Tekanan positif pada expiratory bertujuan untuk menghindarkan kolaps alveolar dan transudasi cairan ke dalam alveoli (edem paru). Tekanan intrathoracal rata-rata lebih tinggi dari IPPV saja. Kecenderungan peninggian tekanan intrakranial dapat dihindarkan dengan posisi kepala lebih tinggi 30°. Efek dari PEEP pada tekanan intrakranial harus diawasi secara ketat. 3) NEEP (Negative and Expiratory Pressure) Menurunkan tekanan pada akhir expiratory dibawah atmosfir menyebabkan tekanan rata-rata intrathoracal menurun dan akan menambah darah ke vena bertambah banyak. Hal ini akan menyebabkan penurunan tekanan intrakranial, tetapi bila digunakan terlalu lama NEEP akan menyebabkan atelectasis. 4) Hyperventilasi secara manual Hyperventilasi secara manual dapat menurunkan tekanan intrakranial secara cepat meskipun hyperventilasi mekanik dapat 73 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL secara maksimum dan efektif. Tindakan ini dapat dipergunakan untuk keperluan yang sangat akut. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah melakukan monitor secara hati-hati setelah suatu ventilasi dengan pemeriksaan analisa gas darah dan foto thoraks. Jalan nafas harus bebas dari lendir. Fisioterapi pada paru-paru dapat meninggikan tekanan intrakranial. Untuk menghindari hal ini terjadi dapat diberikan thiopenton sebelum fisioterapi dimulai. Pemakain kontrol ventilasi pada pasien-pasien dengan cedera kepala berat terutama di Amerika banyak digunakan kontrol ventilasi, hal ini didasarkan karena pada pasien- pasien dengan penurunan kesadaran setelah suatu trauma kapitis pada jam-jam pertama menunjukkan PO2 yang rendah karena respirasi yang inadequat, inhalasi yang terhalang lendir dan liur, bersamaan dengan trauma di daerah dada. Ventilasi kontrol dapat menurunkan ICP yang sudah tinggi maupun mencegah naiknya ICP. Harus diingat bahwa kontrol ventilasi tidak merupakan penanganan yang mudah pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Indikasi pemasangan kontrol ventilasi adalah: 1. Tidak baiknya pertukaran gas karena trauma thorax 2. Melakukan kontrol tekanan intrakranial bila tindakan yang lain gagal Penggunaan kontrol ventilasi tidak berguna bila dilakukan terus menerus, karena PCO2 25 mmHg selama 20 jam terjadi reaktif CO2 yang meninggi, sehingga bila PCO2 kembali ke normal pembuluh darah cerebral akan berdilatasi dan akan meninggikan TIK. Pengeluaran LCS Pengeluaran LCS bisa dikerjakan bila catheter untuk mengukur TIK berada dalam ventrikel; prosedur ini adalah cara yang paling efektif untuk menurunkan tekanan intrakranial. Pada cedera kepala yang berat ventrikel biasanya mengecil dan hanya sedikit liquor yang 74 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL bisa dikeluarkan sehingga penurunan TIK terbatas. Untuk praktisnya ujung catheter dipasang pada ventrikel contra lateral dimana tidak ada contusi atau perdarahan intracerebral. Bila cairan otak dikeluarkan untuk mengontrol ICP pada sisi yang tidak contusi atau hematom walaupun TIK dapat menurun tetapi pergeseran otak akan lebih banyak terjadi sehingga menyebabkan keadaan lebih memburuk. Liquor dapat dikeluarkan secara kontinu atau intermiten. Pengeluaran secara kontinu diatur sampai 20 cmH2O untuk mencegah agar ventrikel jangan menyempit sehingga ujung catheter tidak berada lagi didalam ventrikel. Karena keterbatasan ini pengeluaran liquor secara intermiten dipakai hanya bila terjadi keadaan darurat. Pengeluaran liqour merupakan pengobatan penting bila TIK disebabkan oleh tersumbatnya aliran CSF. Osmotik Diuretik Osmotik diuretik mulai dipakai pada tahun 1919 oleh Weeg dan NcKibben untuk digunakan sebagai kontrol TIK. Mekanisme dari osmotik diuretik ini masih banyak diperdebatkan, tetapi fungsi utamanya adalah karena adanya perbedaan gradient osmosis pada dinding kapiler, sehingga menarik cairan dari rongga ekstraseluler (20% dari volume otak). Dalam keadaan normal osmolaritet didalam serum dan cairan ekstraceluler adalah 295 mmol/kg, sehingga tidak terjadi perbedaan gradient osmoler melalui SDO. Perbedaan gradient 30 mmol/kg dibutuhkan untuk mengurangi cairan di ekstraseluler sehingga dapat menurunkan ICP. Teori ini hanya berlaku pada daerah dimana SDO masih utuh, jadi pemberian cairan osmolaritet dapat menurunkan cairan ekstraseluler pada daerah otak yang normal. Dengan pemeriksaan MRI mannitol dapat menarik cairan dari daerah otak yang edematus dan tidak pada otak yang normal dan juga adanya penarikan air di daerah substansia alba setelah cedera kepala. 75 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Efek kedua dari diuretik osmotik adalah menurunkan fiskositas darah, hal ini akan menyebabkan refleks vasokonstriksi dan mengakibatkan penurunan TIK. Fiskositas autoregulasi ini tergantung dari utuhnya autoregulasi. Osmotik diuretik dapat menurunkan jumlah liquor. Mannitol dapat berperanan sebagai scavenger radikal bebas yang sering diakibatkan karena ischemi akibat bengkaknya otak. Daerah otak yang mengalami cedera dimana SDO rusak terjadi perembesan air pada daerah otak disekitarnya sehingga menambah bengkaknya otak; masalah ini terjadi perlahan-lahan tetapi bila sering diberi-kan berkali-kali dapat menyebabkan otak makin bertambah bengkak. Mannitol Mannitol adalah golongan alkohol yang mempunyai 6 carbon gula manosa dengan berat molekul 180 dan mempunyai bentuk seperti glukosa. Mannitol ini tidak di metabolisme dan tetap berbentuk kompartemen ekstraseluler; merupakan diuretik yang sangat baik dan banyak digunakan. Mannitol 20% diberikan untuk efek dapat diberikan 1 gr (5 cc) per kg berat badan dalam waktu 10-15 menit. TIK akan turun dalam waktu 5- 10 menit setelah pemberian dan mempunyai efek 3-4 jam. Untuk mempertahankan TIK mannitol dapat diberikan dengan dosis yang lebih kecil 0,25-0,5 gr/kg berat badan. Untuk menghindari kerusakan ginjal tekanan osmosis harus <25 mmol. Pada pemakaian mannitol penting mempertahankan sirkulasi volume darah dengan pengukura n central venous pressure dan jumlah urine. Pemakaian hiperventilasi dan pemberian mannitol dapat digunakan bersama-sama pada pasien dengan TIK yang meninggi karena adanya hematom, bila segera dilakukan operasi. Bila operasi ditunda akan terjadi penambahan dari perdarahan dan akan memperburuk keadaan. Masalah dengan penggunaan Mannitol: 76 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL 1. Efek penurunan dengan pemberian dosis berulang. Mannitol tembus SDO yang utuh secara perlahan-lahan dan lebih mudah keluar dari pembuluh darah bila SDO rusak. Osmolaritet intraseluler bertambah sebagai jawaban adanya peninggian tekanan osmolaritet diplasma dan ekstraseluler, sehingga osmolaritet plasma harus bertambah untuk mempertahankan gradient tersebut. 2. Asidosis sistemik dan renal failure dapat disebabkan karena osmolaritet plasma yang meninggi. Osmolaritet plasma harus diperiksa secara berulang dipertahankan agar serum osmolaritet berada < 320 mmol/kg untuk menghindarkan komplikasi diatas. 3. Terjadinya peninggian kembali TIK bila mannitol dihentikan. Fenomen ini banyak di bicarakan tetapi secara klinis tidak berarti. Secara teoritis bila mannitol dihentikan secara mendadak terjadi penurunan osmolaritet plasma sedangkan osmolaritet di intra dan ekstraseluler yang tinggi dapat menyebabkan cairan masuk ke dalam otak sehingga menimbulkan TIK yang meninggi kembali. Renal Diuretik 1) Frusemide (furosemide). Obat ini berkerja pada tubulus sistal dengan menyerap Na kembali lebih banyak, hal ini akan menyebabkan osmolaritas plasma meninggi dengan bertambah urin. Obat ini menurunkan produksi LCS secara langsung; bersama dengan mannitol mempunyai efek sinergis. Pemberian frusemide 20-40 mg bersamaan dengan mannitol akan menurunkan TIK lebih lama. 2) Carbonic anhydrase inhibitors (Diamox) Obat ini selain menyebabkan diuresis juga menurunkan produksi liquor di plexus choroideus dan berperanan pada penurunan tekanan intrakranial yang kronis. 77 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Steroid Steroid berefek untuk mengurangi edem disekitar tumor otak. Pemberian steroid berefek secara klinis setelah pemberian 24 jam, tetapi TIK menurun setelah 40-72 jam. Diduga steroid menstabilkan aliran darah dan volume otak via pengurangan jaringan edematus sehingga pada pengukuran ICP menurunkan fluktuasi TIK. Pemberian steroid tidak berefek (sedikit) pada trauma, bahkan memberikan side efek lebih berat. Barbiturat Pemberian barbiturat dapat menurunkan metabolisme otak sehingga terjadi penurunan CBF; secara tidak langsung menurunkan TIK. Dosis Phentobarbital 10mg/kg BB IV dalam 30 menit, dilanjutkan 5 mg/kg BB per jam dalam 3 dosis, maintanance 1mg/kg/jam. Barbiturat juga mempunyai efek langsung pada otot polos pembuluh darah di otak yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga jumlah darah di otak berkurang dan akhirnya menurunkan TIK. Komplikasi barbiturat adalah terjadinya sistemik hipotensi dan gangguan paruparu sehingga perlu monitoring dengan catheter Swan-Ganz. Harus diperhatikan bahwa pemberian barbiturat untuk menurunkan tekanan intrakranial tidak boleh mengakibatkan penurunan tekanan arteri. Karena pemberian barbiturat tidak menurunkan mortalitas pada penderita dengan peninggian tekanan intrakranial. NaCl Hypertonic Pemberian mannitol berulang dapat menurunkan Na dalam darah, hipovolemi dan akut renal failure. Na hypertonic 5 mmol/mm dapat menurunkan TIK tanpa diuresis; mempertahankan kadar Na dan volume darah di sirkulasi menjadi normal. 78 MANAJEMEN TEKANAN TINGGI INTRAKRANIAL Referensi 1. North B, Reilly P: Raised ICP A Clinical Guide. Heinemann Med Books, Oxford 1990. Chesnut RM, Marshall LF, Piek J, et al. Early and late systemic hypotension as a frequent and fundamental source of cerebral ischemia following sever brain injury in the Traumatic Coma Data Bank. Acta Neurochirurgica 1993a); S59: 121-125. 2. Janny P, Chazal J, Colnet G, et al. Benign intrakranial hypertension and disorders of CSF absorption. Surg Neurol 1981;15:168-174. 3. Cruz J, Minoja G, Okuchi K. Improving clinical outcome from acute SDH with the emergency preoperative administration of high doses of mannitol: A Randomized Trial. Neurosurgery 2001;49(4). 4. Marmarou A, Allen C. The measurement of raised CVP and ICP in TBI, in Hakuba A(ed): Surgery of the intrakranial Venous System. NY, Springer Verlag 1966:145-151. Marshall LF, Smith RW, Shapiro HM. The outcome with aggressive treatment in severe head injuries: Part I- The significant of ICP monitoring. J Neurosurg 1979;50:20-25. 5. Miller JD, Piper IR, Dearden NM. Management of intrakranial hypertension in head injury: matching treatment with cause. Acta Neurochirurgica 1993; S57:152-1159. 6. Rosner MJ, Becker DPP. ICP monitoring: Complication and associated factors. Clin Neurosurg 1976;23:494-519 79 BAB IV BAB IV MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS 4.1 PENDAHULUAN International League Against Epilepsy (ILAE) mendefinisikan status epileptikus (SE) sebagai aktivitas kejang yang berlangsung selama 30 menit terus-menerus, atau dua atau lebih kejang selama suatu periode waktu tertentu tanpa pemulihan pasien seutuhnya. Secara patologis, neuron hipokampus mulai mengalami kerusakan setelah kejang lebih dari 30 menit yang menetap.1 Batasan dari definisi tersebut mengandung makna bahwa terapi tidak boleh ditunda sampai terjadi kerusakan patologis. Namun, definisi operasional terbaru menyatakan bahwa kejang lebih dari 5 menit sepertinya sulit akan berhenti sendiri sehingga harus segera diterapi. Dengan kata lain, terapi SE tidak boleh ditunda.2 4.2 KLASIFIKASI Pada dasarnya, SE dapat diklasifikasikan menjadi compulsive atau non-compulsive SE. Status epileptikus umum atau generalized convulsive status epilepticus (GCSE) adalah bentuk yang paling sering dari SE. Sementara itu, non-convulsive SE (NCSE) dapat mengawali status konvulsi yang umum atau dapat terjadi pada status konvulsi sebagian.3,4 Salah satu bentuk paling umum dari NCSE ialah complex partial status epilepticus (CPSE). Tipe SE ini pada mulanya bersifat fokal, tetapi akan menyebar dengan cepat ke bagian lain dari otak. Pasien dapat menunjukkan gejala bingung atau "twilight state" ditandai dengan perilaku aneh dan otomatisasi. Awalnya CPSE dianggap jinak, namun bukti penelitian yang lebih baru telah menunjukkan bahwa 80 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS pengobatan yang agresif diperlukan untuk menghindari kerusakan seluler dan neuropsikologis jangka panjang.5,6 Identifikasi pasien NCSE seperti ini menjadi penting, terutama setelah adanya laporan bahwa mayoritas pasien trauma kepala mengalami NCSE selama di ruang rawat intensif.5 Claassen5 menemukan adanya perubahan elektrogram kejang pada sepertiga pasien dengan perdarahan intraserebral melalui pemantauan EEG kontinu. Kejadian kejang pada perdarahan kortikal atau luas dapat berdampak pada prognosis yang lebih buruk.5 4.3 EPIDEMIOLOGI Insidens SE di Amerika Serikat telah diperkirakan sekitar 60 kasus per 100.000 penduduk dengan angka kematian dari 9 pasien per 100.000 populasi.4 Angka tersebut relatif tinggi dibandingkan data lokal di RS dr Soetomo, Surabaya, yang hanya menemukan 71 kasus SE pada anak selama tahun 2009.7 Pola insidens SE umumnya bersifat bimodal, sebagian besar terjadi pada pasien umur kurang dari 1 tahun atau lebih dari 60 tahun. Namun, angka mortalitas bervariasi antara 7% pada kelompok anak hingga 28% pada orang tua. Angka mortalitas tersebut dipengaruhi oleh usia, durasi SE, dan penyebab yang mendasari. Prognosis buruk telah didokumentasikan pada kondisi pascaanoksia global, stroke akut, trauma, infeksi, serta gangguan metabolik. Sebaliknya, pasien dengan alkohol atau lepas antikonvulsan, tumor, dan riwayat epilepsi sebelumnya memiliki hasil yang lebih baik.8 4.4 ATOFISIOLOGI Kejadian SE diawali oleh stimulasi eksitasi neuron secara ekstentif, namun pada fase pemeliharaan (maintenance), supresi mediator asam aminobutirat (GABA) lebih dominan. Kegagalan untuk menekan fokus rangsang tersebut mungkin karena perkembangan perubahan isoform GABA, terutama pada kejang yang berkelanjutan. 81 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Secara klinis, fenomena perubahan isoform GABA dapat menjelaskan resistensi terhadap benzodiazepin selama SE. Di samping itu, SE dapat dipertahankan melalui rangsang eksitasi N-metil-D-aspartat (NMDA) yang memediasi stimulasi neuron. Antagonis NMDA telah diusulkan sebagai strategi farmakologis dalam pengobatan SE.9 Pasien dengan SE berkembang melalui tahap fisiologis. Pada fase kompensasi awal, kejang-kejang disertai dengan aktivasi simpatik yang signifikan. Selama tahap ini, hipertensi, peningkatan curah jantung, dan peningkatan aliran darah otak terlihat, dan penanda serum hipermetabolisme seperti asam laktat dan glukosa akan meningkat. Setelah aktivitas kejang yang berkepanjangan (>30 menit), dekompensasi patofisiologis terjadi. Hal ini ditandai dengan disautoregulasi serebral, disfungsi kardiovaskular, dan tanda-tanda krisis metabolisme sistemik: hipoksia, hipoglikemia, dan asidosis. Kegagalan untuk mencegah gangguan fisiologis yang mendalam dapat memperburuk cedera otak sekunder yang terkait dengan refrakter statis epileptikus.9 Prinsip-prinsip umum Fokus utama pengobatan adalah penghentian kejang sesegera munkin. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mengendalikan kejang secara dini dapat meningkatkan luaran (outcome) klinis jangka panjang. Selain itu, kejang dapat resisten terhadap pengobatan apabila SE masih berlanjut.10 Pengobatan harus secepatnya dimulai setelah obat tersedia dengan rute apapun yang memungkinkan. Akses intravena sangat penting, tetapi dalam beberapa keadaan mungkin tidak bisa segera dilakukan terutama pada bayi. Beberapa obat dapat diberikan intramuskular, rektal, atau sublingual. Tabel 6 memperlihatkan dosis obat yang dapat diberikan dengan rute yang umum digunakan ketika akses intravena tidak segera tersedia. Evaluasi secara bersamaan 82 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS identifikasi penyebab yang mendasari terjadinya kejang dan pengobatan komplikasi sekunder juga harus dimulai.10 Tabel 6 Dosis dan Rute Pemberian Obat Status Epileptikus Nama Obat Rute Dosis Lorazepam Intravena 0,1-0,2 mg/kg awal Diazepam Intravena 0,15 mg/kg awal Diazepam Rektal gel 0,2-0,5 mg/kg awal Midazolam Intramuskular 0,07-0,3 mg/kg awal Fenitoin Intravena 20-30 mg/kg awal Fosfenitoin Intravena 20-30 EF/kg awal Fosfenitoin Intramuskular 500-1500 PE awal Fenobarbital Intravena 20-30 mg/kg awal Valproat Intravena 20 mg/kg awal Levetiracetam Intravena 1000-2500 mg awal EF, ekuivalen fenitoin Prinsip manajemen Manajemen SE anak sesuai prinsip bantuan hidup (life support). Manajemen jalan napas pertama-tama dilakukan dengan memposisikan pasien, diikuti ventilasi yang adekuat. Ventilasi dengan bag-mask dengan tambahan oksigen biasanya adekuat untuk menghindari hipoksia. Namun perlu diwaspadai, kejang berkepanjangan dapat menyebabkan obstruksi jalan napas akut dan risiko tinggi aspirasi. Akses intravena memang penting untuk pemberian obat, tetapi relatif sulit pada pasien kejang. Oleh sebab itu, obat sebaiknya diberikan secara intramuskular atau sublingual apabila akses intravena belum terpasang.1 Pada prinsipnya, obat-obat yang diberikan untuk SE dapat mengganggu hemodinamik sehingga obat-obatan SE idealnya diberikan sesegera mungkin. Studi membuktikan, implementasi protokol standar dapat mempersingkat waktu pengendalian aktivitas kejang.2 83 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS EEG darurat diputuskan secara klinis dan sering didasarkan pada sumber daya yang tersedia di rumah sakit. Apabila semua tanda klinis SE dapat dihilangkan segera dengan obat line pertama atau kedua, maka aktivitas kejang berkelanjutan jarang terjadi. Namun, pengobatan berkepanjangan dan adanya tanda kemungkinan aktivitas kejang yang tersamar memerlukan evaluasi EEG yang cepat. Ketika monitoring EEG tidak tersedia dan ada kemungkinan pasien dalam keadaan NCSE, beberapa pakar menganjurkan pemberian anestesi kerja pendek hingga fase pemantauan (monitoring). Keputusan untuk melakukan anestesi tersebut harus mempertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi.1 4.5 PENGOBATAN FARMAKOLOGIS Pengobatan lini pertama Benzodiazepin merupakan pengobatan lini pertama dan yang utama pada SE. Obat tersebut bekerja dengan menstimulasi subunit reseptor GABA sehingga terjadi inhibisi transmisi neural melalui kanal klorida dan membran sel menjadi hiperpolar. Pada dosis tinggi, fungsi benzodiazepin sama dengan fenitoin.11 Terdapat tiga jenis benzodiazepin yang sering digunakan dalam pengobatan SE: diazepam, lorazepam, dan midazolam. Setiap obat memiliki sedikit perbedaan dan rute pemberian. Diazepam mencapai konsentrasi tinggi di otak dengan awitan (onset) 30 detik. Kendati demikian, karena sifatnya yang larut lemak, obat ini juga gampang terdistribusi, kadarnya dalam otak relatif cepat menurun, efektivitas klinis hanya 20 menit, serta angka kekambuhannya juga tinggi. Bila diazepam digunakan sebagai terapi lini pertama, maka akan diperlukan tambahan obat lini kedua.11 Midazolam bukan pilihan pertama untuk SE, tetapi biasa digunakan untuk infus kontinu dalam penanganan SER. Midazolam juga dapat diberikan pada keadaan akut, telah dipakai secara luas, dan 84 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS memiliki banyak rute untuk masuk ke tubuh pasien, seperti intramuskular, rektal, sublingual, bukkal, dan nasal. Midazolam bisa dipakai pada rawat jalan, serta mudah digunakan oleh orang tua. Akan tetapi, waktu paruh midazolam relatif pendek dan angka kekambuhannya cukup tinggi.12 Penelitian Gunawan PI, et al11,12 di RSUD Dr Soetomo Surabaya menunjukkan bahwa midazolam intramuskular dan intranasal efektif untuk digunakan pada kejang akut. Lorazepam merupakan obat benzodiazepin pilihan pertama untuk kejang tunggal ataupun status epileptikus. Waktu awitannya sedikit lebih lambat, kurang lebih dua menit, tetapi lebih tidak larut lemak dibanding diazepam, namun mampu bertahan hingga 12 jam. Penelitian yang dilakukan Veteran Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group menunjukkan, kontrol kejang yang baik dapat dicapai dengan lorazepam, meski tidak ditemukan hasil yang berbeda jauh dibandingkan benzodiazepin lainnya. Efek samping hipotensi pada lorazepam lebih rendah, dan umumnya mampu ditoleransi pasien dibandingkan diazepam. Namun, preparat lorazepam injeksi di Indonesia masih belum tersedia.13 Pengobatan lini kedua Fenitoin atau fosfenitoin, obat dasar ester fosfatnya, dianggap sebagai pengobatan lini kedua yang paling sering digunakan pada SE. Fenitoin merupakan zat yang mirip barbiturat yang dapat mengontrol kejang dengan memperlambat waktu pemulihan kanal natrium yang diaktivasi oleh gelombang listrik. Fenitoin sangat mudah terikat oleh protein, dan hanya bentuk bebas yang aktif. Fenitoin dimetabolisme di hati dan memiliki farmakokinetik khusus. Obat-obatan yang mempengaruhi ikatan protein juga akan berdampak pada tingkat 85 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS aktivitas fenitoin bebas. Oleh karena itu, kadar fenitoin harus dimonitor dengan ketat.13 Dosis awal fenitoin ialah 20 mg/kg, dan harus diberikan pada cairan yang tidak mengandung glukosa. Bila setelah dosis ini masuk kejang masih belum berhenti, dosis dapat ditambahkan 10 mg/kg. Secara farmakologis, pemberian fenitoin ditujukan hingga kadar supraterapeutik (25-30 µg/mL) sebelum mempertimbangkan obat tambahan lainnya. Kekhawatiran overdosis fenitoin sebenarnya terlalu berlebihan karena seluruh efek samping akan hilang setelah kadarnya dalam darah menurun. Pasien yang sudah pernah mendapat fenitoin sebelumnya sebaiknya diberi dosis awal separuh biasanya, apabila kadar fenitoin dalam darah tidak dapat diukur.14 Efek samping fenitoin umumnya berhubungan dengan sistem kardiovaskular, antara lain hipotensi, bradikardia, dan pemanjangan gelombang QT. Penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mmHg merupakan temuan umum pada pasien yang memperoleh fosfenitoin. Hal tersebut seringkali diakibatkan oleh kecepatan infus (kecepatan maksimum 50 mg/menit) dan akan berkurang bila dilakukan penyesuaian kecepatan infus. Oleh sebab itu, penggunaan obat ini harus dilakukan pemantauan EKG berkesinambungan. Efek samping berbahaya lain dari fenitoin ialah nekrosis jaringan, apabila terjadi ekstravasasi obat.14 Fosfenitoin merupakan obat ester fosfat dari fenitoin yang dibuat untuk meringankan efek samping fenitoin. Obat ini larut air sehingga dapat diberikan intramuskular; umumnya diberikan hingga kecepatan 150 mg/menit. Dosis awalnya sama dengan fenitoin dan mungkin memiliki efek samping kardiovaskular yang lebih ringan. Penggunaan fosfenitoin lebih dianjurkan karena dapat diberikan intramuskular, serta dapat diberikan dengan kecepatan lebih tinggi dan dengan efek samping 86 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS yang lebih ringan. Fosfenitoin intramuskular belum diteliti pada status epileptikus.13-15 Beberapa obat lain yang dapat digunakan pada status epileptikus adalah asam valproat dan levetiracetam. Asam valproat merupakan asam lemak rantai pendek yang mengurangi kejang dengan memperlambat pemulihan kanal sodium yang dipengaruhi listrik dan dengan mempengaruhi metabolisme GABA. Asam valproat dapat diberikan secara intravena maupun per rektal. Dosis awal ialah 20 mg/kg intravena dengan kecepatan maksimal 6 mg/kg/menit. Dibandingkan antikejang lain, asam valproat lebih unggul karena tidak menimbulkan gangguan hemodinamik. Akan tetapi, penelitian yang menjabarkan efeknya pada status epileptikus masih sedikit. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa asam valproat sama efektifnya dengan fenitoin pada status epileptikus. Karena asam valproat memiliki efek kardiovaskular penggunaannya pada SE dibatasi sebagai obat lini kedua, sebelum memberikan fenobarbital atau memulai pengobatan SER.14 Tabel 7 Pengobatan Intravena untuk Status Epileptikus Refrakter Pengobatan Midazolam Pentobarbital Tiopental Propofol Dosis Awal 0,2 mg/kg Rumatan 0,05 – 2 mg/kg/jam Awal 5 – 15 mg/kg Rumatan 0,5 – 1 mg/kg/jam Awal 75 - 125 mg Rumatan 1 – 5 mg/kg/jam Awal 3 – 5 mg/kg Rumatan 1 – 15 mg/kg/jam 87 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Pengobatan lini ketiga Fenobarbital dianggap sebagai pegobatan lini ketiga SE. Fenobarbital merupakan barbiturat dengan kerja mirip dengan benzodiazepin, namun juga mampu mengaktifkan berbagai isoform dari reseptor GABAa. Karena waktu paruhnya yang panjang dan efek samping depresan kardiorespiratorik, maka fenobarbital jarang digunakan.13 4.6 STATUS EPILEPTIKUS REFRAKTER (SER) Istilah SER digunakan bila dosis awal standar antikejang tidak mampu menghentikan kejang. SER terjadi pada sepertiga pasien yang diobati sebagai SE. Persentase tinggi tersebut mungkin disebabkan oleh keterlambatan terapi. Beberapa peneliti berpendapat SER dapat dicegah dengan pengobatan yang lebih dini dan lebih agresif.16 Midazolam merupakan benzodizepin kerja pendek yang dianggap sebagai pengobatan lini pertama untuk SER. Obat ini memang cepat menginduksi dan memiliki efek samping kardiorespiratorik lebih jarang daripada propofol maupun barbiturat kerja pendek. Dosis awal 0,2 mg/kg dilanjutkan dengan dosis rumatan 0,05 hingga 0,2 mg/kg/jam. Suatu penelitian yang membandingkan kerja midazolam dengan propofol pada SER menunjukkan bahwa midazolam lebih unggul.17 Propofol merupakan obat anastetik non-barbiturat kerja pendek yang digunakan untuk induksi. Keunggulannya adalah induksi dan eliminasi yang cepat. Propofol mudah ditemukan di semua instalasi gawat darurat maupun ruang rawat intensif. Dosis awalnya 3-5 mg/kg dengan rumatan 1-15 mg/kg/jam. Penggunaan pada anak merupakan kontraindikasi black box karena bisa menyebabkan asidosis metabolik yang berujung pada hipotensi, rabdomiolisis, dan hiperlipidemia. Sindrom tersebut diduga akibat kekurangan enzim mitokondria.17 88 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Pentobarbital merupakan barbiturat kerja pendek yang sering digunakan pada SER. Obat tersebut diberikan dengan dosis awal 5-15 mg/kg selama 1 jam, yang dilanjutkan dengan kecepatan 0,5-15 mg/kg/jam. Pentobarbital sebenarnya memiliki lama kerja pendek, namun pada penggunaan terdahulu, lama kerjanya akan memanjang hingga mendekati fenobarbital. Pentobarbital memiliki efek samping kardiovaskular yang relatif tinggi, dan seringkali membutuhkan pemberian vasopresor. Semua jenis barbiturat memiliki sifat imunosupresif dan dapat meningkatkan infeksi nosokomial.10 4.7 PENGOBATAN STATUS EPILEPTIKUS Tujuan pengobatan ini adalah penghentian kejang sesegera mungkin. Pengobatan juga harus memperhitungkan pencegahan kekambuhan, mencari penyebab dan mengobati semua komplikasi yang terjadi. Sumber daya yang terlibat antara lain tenaga keperawatan, farmasi, tim kegawatdaruratan, dan/atau staf medis yang lain.18 Pendekatan terapi dan diagnosis dilakukan secara runut, seperti yang terlihat pada Gambar 30. Terapi dapat diberikan pada beberapa jalur yang berbeda untuk terminasi kejang yang paling cepat. 89 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Gambar 30 Algoritme Penanganan Status Epileptikus (Sumber: (Sumber: Manno EM, et al. Neurohospitalist. 2011;1(1):23-31) Lorazepam adalah obat dari golongan benzodiazepin yang dipilih sebagai terapi permulaan dalam kasus kejang karena farmakokinetik dan keamanannya. Dosis permulaan 4-10 mg intravena; namun dapat diberikan 0,1-0,2 mg/kg jika kejang tidak berhenti dalam 2-3 menit. Diazepam atau midazolam dapat juga diberikan tetapi jika menggunakan obat ini akan membutuhkan tambahan obat lini kedua. Jika tidak ada akses intravena, benzodiazepin per rektal, sublingual, atau intramuskular dapat diberikan. Kondisi tersebut serupa dengan fosfenitoin yang dapat diberikan intramuskular sambil menunggu akses intravena tersedia.19 Penggunaan benzodiazepin perlu diantisipasi dengan manajemen jalan napas yang baik, jika perlu lakukan intubasi. Jika kejang masih berlanjut, sangat direkomendasikan untuk terapi RSE (lihat jalur 1 pada Gambar 28).19 Alternatif kedua adalah dengan memberikan obat lini kedua untuk terapi RSE (jalur 2, Gambar 28). Pilihan ini banyak dipilih oleh beberapa peneliti untuk menghindari prosedur intubasi pada kondisi 90 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS depresi napas akibat penggunaan benzodiazepin. Pada prinsipnya, para pakar menganjurkan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan kejang hanya karena menunggu ketersediaan obat lini kedua untuk mencegah tindakan intubasi. Kelompok peneliti yang mendukung hal tersebut berpendapat bahwa penggunaan obat lini kedua dan ketiga akan menurunkan efektifitas terapi SE.19 Pilihan ketiga adalah segera memberikan dosis awal fenobarbital jika pemberian obat lini kedua belum juga memberikan tanda perbaikan (lihat jalur 3, Gambar 28). Mayer, et al16 berpendapat bahwa inefektivitas obat lini kedua dan ketiga mungkin mencerminkan keterlambatan terapi yang diberikan untuk mengontrol kejang dan lebih sulit untuk dilakukan.16 Jika pengobatan lini kedua dan ketiga tidak efektif, maka algoritme terapi pindah ke jalur untuk RSE. Hal ini membutuhkan pemantauan EEG dan titrasi obat anestesi. Opini yang menyarankan terapi berkepanjangan dengan propofol, dibandingkan midazolam, sudah mulai ditinggalkan. Kendati demikian, perbandingan penggunaan kedua macam obat tersebut belum pernah diteliti secara luas.16 Hingga saat ini, terapi optimal RSE masih menyisakan sejumlah pertanyaan, misalnya tentang kedalaman induksi obat anestesi. Pada kenyataannya, penggunaan obat biasanya dititrasi untuk menekan gambaran ‘burst’ pada EEG. Semua jenis kejang harus ditekan dan semua terapi dianggap belum adekuat apabila belum tampak gambaran ‘flat line’ pada EEG.20 Time Line Intervensi untuk Instalasi Gawat Darurat, rawat inap, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan tenaga paramedis yang telah terlatih 91 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Apakah kejang berlanjut? Ya 20-40 menit Fase Terapi Kedua Tidak ada bukti ilmiah pilihan terapi kedua yang lebih disukai (Level U): Pilih salah satu opsi dari obat lini kedua berikut ini dan berikan sebagai dosis tunggal: 1. Fosphenytoin intravena (20mg PE/kg, maksimal: 1500mg PE/dosis, dosis tunggal, Level U) ATAU 2. Valproic acid intravena (40mg/kg, maksimal: 3000mg/dosis, dosis tunggal, Level B) ATAU 3. Levetiracetam intravena (60mg/kg, maksimal: 4500mg/dosis, dosis tunggal, Level U) Jika tidak ada dari opsi di atas yang tersedia, pilih opsi di bawah Fase Terapi Ketiga Jika pasien kembali seperti keadaan awal, maka terapi simtomatik Apakah kejang berlanjut? Ya 40-60 menit Tidak Tidak ada bukti ilmiah yang jelas dalam panduan terapi pada fase ini (Level U) Pilihannya meliputi: mengulangi terapi lini kedua atau berikan dosis anestesi yaitu thiopental, midazolam, pentobarbital, atau propofol (semuanya dengan pemantauan EEG secara terus menerus) Tidak Jika pasien kembali seperti keadaan awal, maka terapi simtomatik Gambar 31 Algoritma pengobatan yang dianjurkan untuk status epileptikus20 Sumber: Glauser T et al, Epilepsy Curr 2016;16(1):48-61 92 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Gambar 32 Algoritma Status Epileptikus Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia.21 Sumber: UKK Neurologi IDAI, 2016 Beberapa alternatif tatalaksana Status Epileptikus terdapat pada gambar 2 dan 3. Gambar 3 adalah tatalaksana status yang digunakan dokter anak di Indonesia. Tidak terdapat banyak perbedaan yang mendasar, kecuali obat-obat yang digunakan lebih banyak tersedia dan mudah didapatkan d Indonesia. 4.8 MANAJEMEN KEJANG NEONATAL Dua aspek harus dipertimbangkan dalam pengobatan kejang neonatal: pengobatan kejang itu sendiri dan pengobatan sesuai etiologi yang mendasari. Kejang neonatal membutuhkan terapi darurat, karena kejang dapat mempengaruhi keluaran jangka panjang pada bayi. Selain itu, terapi khusus berdasarkan etiologi penting untuk mencegah cedera otak lebih lanjut. Menstabilkan kondisi umum bayi diperlukan sebelum memulai pengobatan. Jalan napas dan akses ke 93 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS sistem peredaran darah harus memadai pada awal dimulainya pengobatan. Terapi khusus berdasarkan etiologi lebih disukai. Hal ini terutama untuk kejang yang terkait dengan gangguan metabolik akut termasuk hipoglikemia dan hipokalsemia, dan yang terkait dengan sistem saraf pusat atau infeksi sistemik seperti meningitis bakteri, sepsis, dan infeksi herpes simplex. Kelainan metabolik yang jarang namun dapat diobati seperti pyridoxine dependency, folinic acid-responsive seizures, dan gangguan transportasi glukosa juga harus dipertimbangkan sebelum diberikan pengobatan antiepilepsi. Kecuali apabila etiologi yang mendasarinya ditangani dengan tepat, kejang neonatal tidak akan dikontrol oleh pengobatan dengan obat antiepilepsi. Sehingga prosedur diagnostik, termasuk kimia darah, skrining metabolik, kultur bakteri, studi virologi seperti polymerase chain reaction, dan neuroimaging, harus dilakukan untuk menentukan etiologi yang mendasarinya. EEG konvensional kemungkinan juga bisa membantu. Pengobatan dengan obat antiepilepsi dapat dipertimbangkan hanya setelah tersedia bantuan untuk sitem pernapasan dan sirkulasi dan terapi khusus berdasarkan etiologi telah teridentifikasi. Tipe kejang (epilepsi versus nonepilepsi), jika memang benar epilepsi, durasi kejang dan keparahan harus dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah akan memulai pengobatan antiepilepsi. Obat antiepilepsi harus digunakan untuk mengobati kejang neonatal yang disebabkan oleh epilepsi dan bukan yang nonepilepsi, sebab pengobatan ini tidak efektif untuk kejadian paroksismal nonepilepsi. Hal ini menunjukkan bahwa iktal EEG/perekaman aEEG harus dilakukan untuk menentukan apakah kejangnya epilepsi atau nonepilepsi sebelum memulai pengobatan dengan obat antiepilepsi. Tidak perlu untuk mengobati semua kejang neonatal akibat epilepsi, karena beberapa ada yang berlangsung singkat, jarang, dan sembuh dengan sendirinya. Secara teoritis, pengobatan antiepilepsi 94 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS tidak dibenarkan pada bayi dengan kejang yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah ini kejang yang dapat sembuh dengan sendirinya pada masing-masing individu selama beberapa jam pertama setelah onset kejang. Pengobatan yang berlebihan dapat terjadi selama periode akut, terutama ketika kejang terkait dengan tanda-tanda vital yang memburuk seperti bradikardia, hipotensi, dan desaturasi. Namun, bahkan di beberapa kasus ini, pengobatan kronis yang tidak perlu dengan obat antiepilepsi harus dihindari.22 Efikasi pengobatan harus dievaluasi oleh EEG secara terusmenerus /pemantauan aEEG. Subklinis kejang sangat umum setelah kejang dengan manifestasi klinis terkontrol oleh pengobatan antiepilepsi. Ini membuat pengobatan antiepilepsi untuk kejang neonatal menjadi lebih rumit. Tidak ada yang bisa menentukan khasiat pengobatan antiepilepsi tanpa EEG secara terus-menerus /pemantauan aEEG. Untuk alasan ini, bukti efektivitas obat antiepilepsi terbatas. Glass et al, menyelidiki pada kejang neonatal yang didiagnosis secara klinis berhubungan dengan keluaran neurodevelopmental pada bayi dengan hipoksia iskemia setelah mengontrol kejang dan tingkat keparahan cedera otak yang terlihat pada MRI. Bayi dengan kejang neonatal memiliki hasil motorik dan kognitif yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak kejang. Mereka menyimpulkan bahwa kejang neonatal pada bayi yang lahir dengan asfiksia berhubungan dengan keluaran neurodevelopmental yang buruk, tidak tergantung pada keparahan cedera otak akibat hipoksia-iskemik. 23 Kwon et al melaporkan hasil yang berlawanan. Mereka menganalisis hubungan antara kejang neonatal dan keluaran pada usia 18 bulan. Saat penyesuaian dibuat untuk studi pengobatan dan tingkat keparahan ensefalopati, kejang tidak 95 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS berhubungan dengan kematian, cacat sedang atau berat, atau nilai yang lebih rendah pada Bayley Skor Indeks Perkembangan Mental pada 18 bulan kehidupan.24 Kedua studi ini memiliki kekurangan substansial, kejang yang didiagnosis berdasarkan pengamatan klinis, dimana pada beberapa penelitian telah terbukti tidak cukup dan tidak benar. Untuk memperjelas efektivitas obat-obatan antiepilepsi, studi berdasarkan EEG secara terus-menerus/ pemantauan aEEG merupakan hal yang sangat penting. Tidak jelas sebenarnya apakah kejang subklinis harus diobati. Van Rooij et al. mempelajari apakah pengobatan segera pada kejang klinis dan subklinis menghasilkan pengurangan total durasi kejang dan penurunan cedera otak pada MRI. Durasi rata-rata pola kejang adalah 196 menit dalam kelompok di mana subklinis kejang diobati berdasarkan pemantauan aEEG, dibandingkan dengan 503 menit pada kelompok di mana tidak dilakukan pemantauan aEEG. Ada hubungan yang signifikan antara durasi pola kejang dan skor MRI dalam regresi linier yang didapatkan hanya pada kelompok kedua. Mereka menyimpulkan bahwa ada kecenderungan untuk pengurangan durasi kejang dan keparahan cedera otak ketika kejang klinis dan subklinis diobati. 25 Di sisi lain, Freeman menyatakan perhatian yang kuat untuk penerapan pemantauan aEEG untuk mendeteksi kejang subklinis. 26 Saat ini, efektivitas obat untuk pengobatan kejang pada bayi baru lahir belum ditetapkan. Oleh karena itu, konsekuensi dari pengenalan EEG otomatis untuk mendeteksi subklinis kejang neonatal cenderung mirip dengan yang terlihat setelah pengenalan pemantauan jantung janin selama persalinan. Freeman memperingatkan para klinisi untuk berhati-hati terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan. Indikasi untuk pengobatan antiepilepsi harus tergantung pada etiologi kejang neonatal. Kejang subklinis dengan gejala akut seperti cedera otak hipoksik-iskemik cenderung sembuh dengan sendirinya dan mungkin 96 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS tidak memerlukan pemberian obat antiepilepsi tambahan. Di sisi lain, kejang subklinis seperti malformasi otak harus ditangani dengan benar, karena kejang ini dapat diklasifikasikan sebagai ensefalopati epilepsi. Juga tidak jelas apakah gejala motorik paroksismal nonepilepsi harus diobati. Berbagai jenis fenomena ini telah salah didiagnosis sebagai kejang karena epilepsi. Neonatologists mungkin menjadi marah ketika ahli syaraf bersikeras bahwa tidak ada pengobatan yang diperlukan dalam kasus ini. Secara rasional, pengobatan antiepilepsi tidak efektif atau berbahaya dan terapi khusus berdasarkan etiologi harusnya lebih disukai. Pemilihan obat antiepilepsi juga menjadi masalah. Saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan obat antiepilepsi mana yang harus digunakan untuk kejang neonatal. Phenobarbital dan phenytoin sering digunakan sebagai obat awal di seluruh dunia. Namun, tidak ada agen yang tampaknya lebih efektif daripada yang lain, dan tidak seefektif pemikiran sebelumnya. Di Jepang, midazolam juga sering digunakan sebagai obat awal untuk kejang neonatal, tetapi keampuhannya belum dievaluasi secara memadai. 97 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Kejang yang dicurigai pada neonatus beresiko tinggi : Konfirmasi kejang dengan EEG (apabila tersedia) dan mulai EEG berkelanjutan jika memungkinkan Periksa penyebab yang bisa diperbaiki: glukosa, elektrolit Mulai antibiotik jika demam atau berisiko tinggi terjadi infeksi SSP. LP dilakukan segera setelah kejang dan stabil Jika setidaknya satu kejang yang dikonfirmasi EEG dan tidak ada penyebab yang dapat segera diperbaiki: PHENOBARBITAL 20mg/kg iv dan mulai rumatan phenobarbital 5mg/kg/hari terbagi 2 kali sehari atau 4 kali sehari Jika kejang berlanjut: tambahkan PHENOBARBITAL 20mg/kg IV Jika kejang berlanjut: Tiga opsi*: LEVETIRACETAM 50mg/kg IV Kemudian rumatan 40mg/kg/hari (terbagi 2 kali sehari) KAMI LEBIH MENYUKAI PHENYTOIN/FOSPHENYTOIN 20mg/kg IV dan memulai pengobatan rumatan kedua (phenytoin 5mg/kg/hari terbagi tiap 8 jam. Atau pertimbangkan levetiracetam 40mg/kg/hari untuk menghindari pemantauan kadar serum secara terus menerus dan kemungkinan terjadinya toksisitas LIDOCAINE 2mg/kg IV bolus, Kemudian 6mg/kg/jam drip, lalu titrasi diturunkan 2mg/kg/jam tiap 12 jam hingga habis. Juga Jika kejang berlanjut: Pertimbangkan penggunaan pyridoxine, lalu: MIDAZOLAM 0.15mg/kg IV bolus lalu 1 mikrogram/kg/menit drip, titrasi dinaikkan sesuai kebutuhan hingga maksimal 18 mikrogram/kg/menit. Jika kejang berlanjut : Pertimbangkan PENTOBARBITAL drip, atau jika belum pernah mencoba dapat menggunakan LIDOCAINE drip (kecuali phenytoin/fosphenytoin telah digunakan. 98 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Gambar 33 Algoritma pengobatan yang disarankan untuk kejang neonatal berulang.27 Panah menunjukkan langkah berikutnya jika kejang yang dikonfirmasi dengan EEG sedang berlangsung (klinis atau subklinis). Singkatan: CSF = cairan serebrospinal, SSP = sistem saraf pusat, EEG = electroencephalogram, IV = intravena, LP = pungsi lumbal, MRI = magnetic resonance imaging. Sumber: Slaughter LA, Patel AD, Slaughter JL. J Child Neurol 2013;28(3):351-64. 4.9 KESIMPULAN SE adalah kegawatdaruratan neurologis yang sering dihadapi di rumah sakit. Keberhasilan terapi tergantung dari ketersediaan sumber daya dan kecepatan pemberian obat antikonvulsan. Dengan pilihan agen farmakologis saat ini, strategi terapi SE tetap mengutamakan pemberian obat sesegera mungkin dengan rute apapun yang tersedia saat ini. Pada beberapa kondisi tertentu, terapi SE refrakter memerlukan obat-obatan anestesi sebagai obat antikonvulsan. Diagnosis dan penatalaksanaan kejang neonatal merupakan tantangan masalah masa depan. Kejang neonatal harus diPdiagnosis berdasarkan temuan iktal EEG / temuan aEEG dan efikasi pengobatan harus dievaluasi menggunakan EEG/ aEEG. Untuk membuat pengobatan yang efektif, pemantauan menggunakan EEG / aEEG dan tindak lanjut jangka panjang diperlukan. 99 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS Referensi: 1. Epilepsy Foundation of America’s Working Group on Status Epilepticus. Treatment of convulsive status epilepticus: recommendations of the Epilepsy Foundation of America’s Working Group on Status Epilepticus. JAMA. 1993;270:854-9. 2. Fallahian F, Hashemian SMR. Critical management of status epilepticus. J Clin Intensive Care Med 2017;2:1-15. 3. Brophy GM, Bell R, Claasen J, Allredge B, Bleck TP, Glauser T et al. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Neurocrit Care 2012;s12028. 4. Au CC, Branco RG, Tasker RC. Management protocols for status epilepticus in the pediatric emergency room: systematic review article. J Pediatr. 2017;93:84-94. 5. Claassen J, Jette N, Chum F, Green R, Schmidt M, Choi H, et al. Electrographic seizures and periodic discharges after intracerebral hemorrhage. Neurology. 2007;69:1356-65. 6. Rossetti AO, Oddo M, Liaudet L, Kaplan PW. Predictors of awakening from postanoxic status epilepticus after therapeutic hypothermia. Neurology. 2009;72:744-9. 7. Gunawan PI. Etiology and outcome of status epilepticus in Dr Soetomo Hospital. Pediatrica Indonesiana. 2010;50(2):S282. 8. Waterhouse EJ. Epidemiology of status epilepticus. Dalam: Drislane FW, penyunting. Status epilepticus: a clinical perspective. New York: Humana Press; 2005. h.55-75. 9. Poblete R, Sung G. Status epilepticus and beyond: A Clinical review of status epilepticus and an update on current management strategies in super-refractory status epilepticus. Korean J Crit Care Med 2017;32(2):89-105. 10. Manno EM. New management strategies in the treatment of status epilepticus. Mayo Clin Proc. 2003;78:508-18. 100 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS 11. Gunawan PI, Rulian F, Saharso D. Comparison of intranasal midazolam and rectal diazepam as anticonvulsant in Children. J Nepal Ped Soc. 2015;35(2):116-21. 12. Gunawan PI, Kurniawan MR, Saharso D. The efficacy of intramuscular midazolam compared with rectal diazepam for anticonvulsant in children. Pak Ped J. 2015;39(4):217-21. 13. Treiman DM, Meyers PD, Walton N. Veterans affairs status epilepticus cooperative study group a comparison of four treatments for generalized status epilepticus. N Engl J Med. 1998;339:792-79. 14. McNamara JO. Drugs effective in the therapy of the epilepsies. Dalam: Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG, penyunting. Goodman & Gilman's The pharmacologic basis of therapeutics. Edisi ke 10. New York: McGraw-Hill; 2001. h.521-47. 15. Kassala MY, Lobeck IN, Majid A, Xie Y, Farooq MV. Blood pressure changes after intravenous fosphenytoin and levitiracetam in patients after acute cerebral symptoms. Epilepsy Res. 2009;87:268-71. 16. Mayer SA, Claassen J, Lokin J, Mendelsohn F, Dennis LJ, Fitzsimmons BF. Refractory status epilepticus: frequency, risk factors, and impact on outcome. Arch Neurol. 2002;59:205-10. 17. Friedman JA, Manno EM, Fulgham JR. Propofol use in the neuro ICU. J Neurosurg. 2002;96:1161-2 18. Shih T, Bazil CW. Treatment of generalized convulsive status epilepticus. Dalam: Drislane FW, penyunting. Status epilepticus: a clinical perspective. New York: Humana Press; 2005. h.265-88. 19. Manno EM. Status epilepticus current treatment strategies. Neurohospitalist. 2011;1(1):23-31. 20. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Allredge B, Arya R, Bainbridge J, et al. Evidence-based guideline: Treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the guideline 101 MANAJEMEN TERKINI STATUS EPILEPTIKUS PADA ANAK DAN NEONATUS 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. committee of American Epilepsy Society. Epilepsy Curr 2016;16(1):48-61. UKK Neurologi IDAI. Rekomendasi penatalaksaan status epileptikus. Ed Ismail S, Pusponegoro HD, Widodo DP et al. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2016. Okumura A. The diagnosis and treatment of neonatal seizures. Chang Gung Med J 2012;35:365-72. Glass HC, Glidden D, Jeremy RJ, Barkovich AJ, Ferriero DM, Miller SP. Clinical neonatal seizures are independently associated with outcome in infants at risk for hypoxic-ischemic brain injury. J Pediatr 2009;155:318-23. Kwon JM, Guillet R, Shankaran S, Laptook AR, McDonald SA, Eherenkranz RA et al. Clinical seizures in neonatal hypoxic ischeic encephalopathy have no independent impact on neurodevelopmental outcome: secondary analyses of data from the neonatal research network hypothermia trial. J Child Neurol 2011;26:322-8. Van Roooij LG, Toet MC, van Huffelen AC, Groenendaal F, Laan W, Zecic A et al. Effect of treatment of subclinical neonatal seizures detected with aEEG; randomized, controlled trial. Pediatrics 2010;125:e358-66. Freeman JM. Beware: the misuse of technology and the law of unintended consequences. Neurotherapeutics 2007;4:549-54. Slaughter LA, Patel AD, Slaughter JL. Pharmacological treatment of neonatal seizure: a systematic review. J Child Neurol 2013;28(3):351-64. 102 BAB V MANAJEMEN HIDROSEFALUS 5.1 PENDAHULUAN Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga (ventrikel) jauh di dalam otak. Kelebihan cairan meningkatkan ukuran ventrikel dan memberi tekanan pada otak. Cairan serebrospinal biasanya mengalir melalui ventrikel dan menggenangi otak dan tulang belakang. Tetapi tekanan cairan serebrospinal yang terlalu banyak terkait dengan hidrosefalus dapat merusak jaringan otak dan menyebabkan berbagai masalah fungsi otak. Hidrosefalus dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering terjadi pada bayi dan orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Perawatan bedah untuk hidrosefalus dapat memulihkan dan mempertahankan kadar cairan serebrospinal normal di otak. Terapi yang berbeda seringkali diperlukan untuk mengelola gejala atau masalah akibat hidrosefalus. Modul ini bertujuan untuk membantu peserta dalam mengenali hidrosefalus dari neuroanatomi, neurofisiologi, insidensi beserta pathogenesis hingga pemeriksaan dan manajemen yang dapat dilakukan. 5.2 ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM VENTRIKEL DAN ALIRAN CSS Ventrikel adalah kavitas berisi cairan yang terletak di dalam otak. Dinding ventrikel dilapisi dengan sel ependyma dan diisi dengan cairan serebrospinal (CSS). Ventrikel lateral adalah ventrikel terbesar yang mana terdiri dari body, atrium dan memiliki proyeksi ke lobus frontal, temporal dan occipital. Tiga proyeksi ini dikenal dengan anterior, posterior dan lateral horn di kedua sisi. Ventrikel III adalah kavitas 103 MANAJEMEN HIDROSEFALUS tunggal yang berada di medial di antara dua thalamus. Ventrikel IV terletak di antara pon/medulla dan cerebellum. Keseluruhan ventrikel ini akan terhubung melalui saluran-saluran dan akan mengalirkan CSS hingga distal. CSS diproduksi oleh plexus choroideus pada ventrikel. Ventrikel lateral terhubung dengan ventrikel III yang terletak di medial melalui foramen interventricular, sedangkan ventrikel III terhubung dengan ventrikel IV melalui Aqueduct cerebri. Selanjutnya, CSS akan meninggalkan ventrikel IV melalui foramen tunggal di medial (foramen Magendie) dan foramen ganda di lateral (foramen Luschka). Foramen Magendie akan berjalan ke distal hingga menjadi canal centralis, sedangkan foramen Luschka berjalan di lateral menuju cisterna-cisterna cerebri. CSS akan mengalir melalui ruang subarachnoid dan akan diabsorpsi menuju dural venous snius melalui vili arachnoid. Volume CSS pada manusia adalah 80-160 ml, dimana produksi CSS di pleksus choroideus per harinya sebanyak 14-36 ml/jam. Gambar 34 Anatomi dan sirkulasi CSS 104 MANAJEMEN HIDROSEFALUS 5.3 DEFINISI Hidrosefalus adalah penumpukan progresif liquor (CSF) dalam sistem ventrikel otak sehingga dapat diartikan sebagai kondisi ‘cairan berlebih dalam kepala’. Hidrosefalus terjadi dalam 3-25 tiap 10.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti dari 400 bayi lahir hidup, 1 bayi mengidap hidrosefalus. Kondisi ini dapat terjadi akibat gangguan produksi, sirkulasi ataupun reabsorbsi dari CSF. Hidrosefalus Kongenital Bayi mungkin lahir dengan hidrosefalus segera setelah lahir. Dalam kasus ini, hidrosefalus dapat disebabkan oleh: • Kelainan genetik bawaan yang menghalangi aliran CSS • Gangguan perkembangan seperti yang terkait dengan cacat lahir di otak, tulang belakang, atau sumsum tulang belakang • Komplikasi kelahiran prematur seperti perdarahan di dalam ventrikel • Infeksi selama kehamilan seperti rubella yang dapat menyebabkan peradangan pada jaringan otak janin. Hidrosefalus didapat Hidrosefalus didapat faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan risiko berkembangnya hidrosefalus pada usia berapa pun, termasuk: • Tumor otak atau sumsum tulang belakang • Infeksi pada sistem saraf pusat seperti meningitis bakteri • Cedera atau stroke yang menyebabkan pendarahan di otak → perdarahan subarachnoid maupun bekuan darah di dalam sistem ventrikel Hidrosefalus didapat biasanya merupakan hasil dari cedera ataupun penyakit. 105 MANAJEMEN HIDROSEFALUS 5.4 TANDA DAN GEJALA HIDROSEFALUS Tanda dan gejala hidrosefalus bervariasi menurut onset usia: Bayi Tanda dan gejala umum hidrosefalus pada bayi meliputi: • Perubahan tampilan kepala yang luar biasa besar • Peningkatan pesat dalam ukuran kepala • UUB yang menonjol atau tegang (fontanel) di bagian atas kepala • Tanda dan gejala fisik • Mual dan muntah Kantuk atau kelesuan (lesu) • Sifat lekas marah • Susah makan • Kejang • sunset eyes phenomenon • Masalah dengan tonus dan kekuatan otot Balita dan anak-anak yang lebih besar Di antara balita dan anak yang lebih besar, tanda dan gejala yang dapat terjadi, antara lain: • Sakit kepala • Penglihatan kabur atau ganda • Gerakan mata yang tidak normal • Pembesaran kepala balita yang tidak normal • Kantuk atau kelesuan • Mual atau muntah • Keseimbangan tidak stabil • Koordinasi yang buruk • Nafsu makan yang buruk 106 MANAJEMEN HIDROSEFALUS • • • • • • Kehilangan kontrol kandung kemih atau sering buang air kecil Perubahan perilaku dan kognitif Sifat lekas marah Perubahan kepribadian Menurunnya prestasi sekolah Keterlambatan atau masalah dengan keterampilan yang diperoleh sebelumnya, seperti berjalan atau berbicara Orang dewasa (Cognitive impairment, gait disturbance, and urinary incontinence) Tanda dan gejala umum pada kelompok usia ini meliputi: • Sakit kepala, • Kelesuan • Kehilangan koordinasi atau keseimbangan • Kehilangan kontrol kandung kemih atau sering ingin buang air kecil • Masalah penglihatan • Menurunnya daya ingat, konsentrasi dan kemampuan berpikir lainnya yang dapat mempengaruhi performa kerja Sementara itu, pada kelompok usia 60 tahun ke atas dapat mengalami tanda dan gejala hidrosefalus yang lebih umum sebagai berikut: • Kehilangan kontrol kandung kemih atau sering ingin buang air kecil • Hilang ingatan • Hilangnya keterampilan berpikir atau penalaran lainnya secara progresif • Kesulitan berjalan, sering digambarkan sebagai gaya berjalan terseok-seok atau perasaan kaki tertahan • Koordinasi atau keseimbangan yang buruk 107 MANAJEMEN HIDROSEFALUS 5.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS HIDROSEFALUS Gambar 35 Grafik panduan untuk pemantauan lingkar kepala anak dari WHO 108 MANAJEMEN HIDROSEFALUS Parameter yang paling mudah dalam mengenali hidrosefalus pada pediatri adalah melalui pengukuran lingkar kepala. Penambahan lingkar kepala anak dapat dipantau dengan mudah sejak kelahiran menggunakan grafik dari WHO (Gambar 2). Orang tua dan tenaga kesehatan dapat melihat tren dari lingkar kepala anak dan dengan segera mengetahui jika timbul abnormalitas dari tren tersebut. Lingkar kepala mengalami penambahan yang berbeda bergantung usia anak, sebagai berikut: • 0 – 3 bulan: 2 cm / bulan • – 6 bulan: 1 cm / bulan • 6 – 12 bulan: 0,5 cm / bulan • 1 – 3 tahun: 0,25 cm / bulan • – 6 tahun: 1 cm / tahun Selain melihat adanya perubahan lingkar kepala yang abnormal, hidrosefalus akan ditelusuri melalui pemeriksaan fisik dasar sebagai berikut: Status Lokalis pada pediatri Inspeksi: UUB cembung, Sunset Eye phenomenon (+) Venectasi (+) Palpasi: Sutura Melebar, Uub Tegang, Lingkar Kepala Perkusi: Cracked Pot Sign (+) Transilluminasi (+) Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang berupa radiologis dan tes lainnya yang dapat dilakukan pada kecurigaan hidrosefalus antara lain: • Ultrasonografi seringkali merupakan tes pertama yang digunakan dokter untuk mendiagnosis bayi karena relatif sederhana dan berisiko rendah. Ketika digunakan selama pemeriksaan prenatal rutin, USG juga dapat mendeteksi hidrosefalus pada bayi yang belum lahir. 109 MANAJEMEN HIDROSEFALUS • Computed tomography (CT) dapat menunjukkan dokter jika ventrikel membesar atau jika ada halangan. • Karena tulang belakang (pungsi lumbal) memungkinkan dokter memperkirakan tekanan CSS dan menganalisis cairan dengan memasukkan jarum di punggung bawah dan mengeluarkan serta menguji beberapa cairan. • Magnetic resonance imaging (MRI) dapat menentukan apakah ventrikel membesar, menilai aliran CSS, dan memberikan informasi tentang jaringan otak yang mengelilingi ventrikel. MRI biasanya merupakan tes awal yang digunakan untuk mendiagnosis orang dewasa. • Pemantauan tekanan intracranial (TIK) menggunakan monitor tekanan kecil yang dimasukkan ke dalam otak atau ventrikel untuk mengukur tekanan dan mendeteksi jumlah pembengkakan yang mungkin terjadi di otak. Jika tekanan terlalu tinggi, dokter dapat menguras CSS untuk menjaga aliran darah beroksigen ke otak. • Pemeriksaan funduskopi menggunakan alat khusus untuk melihat saraf optik di bagian belakang mata. Ini dapat menunjukkan bukti pembengkakan yang menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial, yang dapat disebabkan oleh hidrosefalus. Diagnosis radiologis Kesesuaian antara PF dan anamnesis dengan hasil pemeriksaan radiologis. Pada CT Scan kepala didapatkan satu diantara tanda berikut: o Evans ratio >30 % o Pembesaran ventrikel lateral, III dan atau IV o Pelebaran temporal horn >2 mm 110 MANAJEMEN HIDROSEFALUS Diagnosis klinis Hidrocephalus Komunikan dan Hidrocephalus Non Komunikan Differential Diagnosis Space occupying lesion (SOL) Intracranial Pseudotumor Cerebri 5.6 EVALUASI PASCA BEDAH Setelah intervensi bedah (pemasangan shunt), evaluasi sangat diperlukan untuk menilai fungsi shunt yang telah terpasang pada pasien. Evaluasi berfungsi untuk mewaspadai terjadinya komplikasi, antara lain infeksi, obstruksi, dislokasi, diskoneksi maupun exposed shunt. Selain itu, evaluasi juga berperan dalam penilaian hasil terapi yang telah diberikan. Disfungsi shunt Disfungsi shunt dapat diketahui dengan cara di bawah ini: Klinis • Lingkar kepala yang sudah mengecil membesar kembali • Fontanel yang sudah cekung, lunak → menjadi cembung dan tegang • Tampilan klinis lainnya Test • Pada percobaan penekanan pompa shunt → terasa keras/tidak kembali • Pungsi steril pada reservoir → tidak terdapat CSS 111 MANAJEMEN HIDROSEFALUS Slit Ventricle Syndrome Slit ventricle syndrome adalah salah satu komplikasi yang kerap terjadi pada pasien hidrosefalus yang telah mendapatkan intervensi shunt, dimana pasien mengalami gejala selayaknya penurunan TIK. Gejala yang bisa didapatkan yaitu nyeri kepala yang memburuk dengan berdiri. Nyeri kepala ini biasanya berkembang seiring berjalannya hari namun membaik dengan berbaring. 5.7 TATALAKSANA Tatalaksana yang dapat dilakukan, antara lain: • Hidrasi, obat-obatan, penyesuaian shunt yang dapat diprogram, atau penambahan komponen antisiphon ke shunt distal • Steroid: Steroid dapat membantu sementara sebelum intervensi bedah. • Hidrasi: cairan IV dapat mengurangi gejala pada anak dengan overdrainage atau ICP rendah. 112 MANAJEMEN HIDROSEFALUS Referensi 1. Snell, Richard S. Clinical Neuroanatomy 7th ed: Lippincot Wiliam & Wilkins; 2010 2. Waman, Stephen G. Clinical Neuroanatomy 26th ed: McGraw Hill; 2010 3. D.Prockop L, Murtagh R. Hydrocephalus. In: Roland LP, Pedley TA, editors. Merritt's Neurology. 12th ed: Lippincot Willam & Wilkins; 2010. p. 350-7. 113 BAB VI BAB VI MANAJEMEN STROKE ISKEMIK 6.1 PENDAHULUAN Stroke Iskemik adalah kondisi medis yang ditandai dengan gangguan pasokan darah ke otak secara tiba-tiba, yang menyebabkan serangkaian gejala yang melemahkan. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi penting ke bagian otak tersumbat atau menyempit, biasanya akibat gumpalan darah atau aterosklerosis, yaitu penumpukan timbunan lemak pada dinding arteri. Gangguan aliran darah ini mengakibatkan timbulnya disfungsi neurologis dengan cepat dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Stroke iskemik menyumbang sekitar 85% dari semua kasus stroke, menjadikannya jenis yang paling umum. Stroke iskemik dapat terjadi pada individu dari segala usia, namun lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, obesitas, dan gaya hidup tidak aktif. Tanda-tanda awal stroke iskemik dapat berupa kelemahan atau mati rasa mendadak pada wajah, lengan, atau tungkai, terutama pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, pusing, sakit kepala parah, dan gangguan penglihatan. Penanganan dan pengobatan stroke iskemik melibatkan pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk memulihkan aliran darah dengan cepat ke area otak yang terkena dan meminimalkan kerusakan otak. Waktu sangat penting, karena pemberian obat penghilang gumpalan secara dini atau teknik penghilangan gumpalan secara mekanis dapat secara signifikan meningkatkan hasil. Rehabilitasi dan perawatan pasca stroke memainkan peran penting dalam membantu pasien yang selamat untuk mendapatkan kembali 114 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK kemampuan yang hilang dan beradaptasi dengan gangguan yang tersisa. 6.2 EPIDEMIOLOGI Stroke iskemik adalah masalah kesehatan masyarakat utama yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia dan menambah beban penyakit dan kecacatan secara signifikan. Informasi penting mengenai prevalensi, insiden, dan distribusi stroke iskemik pada berbagai populasi diperoleh dari studi epidemiologi. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum, terhitung sekitar 70% hingga 80% dari semua stroke, menurut perkiraan dari seluruh dunia. Terdapat perbedaan regional dalam kejadian stroke iskemik, dengan negara-negara industri yang memiliki angka kejadian yang lebih besar daripada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Variasi dalam faktor risiko, sistem perawatan kesehatan, dan variabel gaya hidup menjadi penyebab perbedaan ini. Usia merupakan faktor penting karena meningkatkan kemungkinan terkena stroke iskemik secara dramatis seiring bertambahnya usia. Risiko stroke iskemik yang lebih tinggi telah berulang kali dikaitkan dengan beberapa faktor risiko. Ini termasuk fibrilasi atrium, merokok, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan hipertensi (tekanan darah tinggi). Faktor-faktor risiko ini menjadi lebih umum secara global, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang signifikan. Selain itu, telah ditemukan bahwa ada beberapa perbedaan regional dalam stroke iskemik. Sebagai contoh, angka yang lebih besar telah diamati di beberapa daerah di Asia, seperti Cina dan India, yang mungkin terkait dengan kombinasi karakteristik genetik, kebiasaan makanan, dan keputusan gaya hidup yang unik di daerah-daerah ini. Tingkat stroke iskemik juga dapat dipengaruhi oleh variasi dalam 115 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK sistem perawatan kesehatan dan aksesibilitas terhadap intervensi pencegahan seperti obat antikoagulan untuk fibrilasi atrium. 6.3 ETIOLOGI Jenis stroke yang paling sering terjadi, yaitu stroke iskemik, memiliki interaksi yang rumit dari berbagai penyebab yang berbeda. Faktor utama yang menyebabkan stroke iskemik adalah gangguan aliran darah ke otak, yang sering kali disebabkan oleh penyumbatan arteri darah yang menyuplai daerah tersebut. Dua mode oklusi utama adalah trombotik dan emboli. Perkembangan bekuan darah (trombus) di dalam pembuluh darah yang memasok otak menyebabkan stroke trombotik. Gumpalan ini sering terbentuk di arteri yang telah tersumbat oleh plak akibat aterosklerosis, suatu kondisi di mana timbunan lemak (plak) menumpuk di dinding pembuluh darah. Trombosit berkumpul dan membentuk gumpalan ketika plak pecah atau menjadi tidak stabil, sehingga menghalangi aliran darah. Stroke Emboli terjadi ketika gumpalan darah atau benda asing lainnya, yang biasanya berasal dari lokasi yang jauh seperti jantung atau arteri besar, bergerak melalui aliran darah dan bersarang di arteri darah otak yang lebih sempit daripada pembuluh darah di sekitarnya. Gumpalan darah yang terbentuk di bilik jantung akibat penyakit seperti fibrilasi atrium atau gumpalan yang berasal dari plak aterosklerosis di arteri karotis atau arteri vertebralis adalah dua asal mula emboli yang umum. Stroke iskemik dapat terjadi karena sejumlah faktor risiko. Ini termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, obesitas, kolesterol tinggi, fibrilasi atrium, penyakit genetik yang berhubungan dengan pembekuan darah, dan riwayat stroke dalam keluarga. Kemungkinan mengalami stroke iskemik juga dapat dipengaruhi oleh 116 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK variabel lain, termasuk usia, jenis kelamin (pria agak lebih berisiko), dan ras atau etnis. 6.4 KLASIFIKASI Stroke Trombotik Stroke trombotik adalah jenis stroke iskemik spesifik yang terjadi ketika bekuan darah (trombus) terbentuk di dalam arteri yang memasok darah ke otak, yang mengakibatkan terhalangnya aliran darah. Kondisi ini biasanya timbul akibat kombinasi kondisi yang mendasari, termasuk aterosklerosis, disfungsi endotel, dan aktivasi trombosit. Aterosklerosis, penumpukan timbunan lemak (plak) di dalam arteri, memainkan peran penting dalam perkembangan stroke trombotik. Plak ini dapat pecah, mengekspos jaringan di bawahnya dan memicu pembentukan gumpalan darah. Gumpalan darah ini kemudian menyempitkan atau menyumbat arteri, sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke otak berkurang. Stroke trombotik sering bermanifestasi secara bertahap, dengan gejala yang memburuk dalam hitungan menit hingga jam, sebuah fenomena yang disebut sebagai "stroke dalam evolusi." Tanda-tanda peringatan yang umum termasuk kelemahan atau mati rasa di satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, perubahan penglihatan yang tiba-tiba, sakit kepala yang parah, dan masalah keseimbangan atau koordinasi. Tingkat keparahan gejala dapat bervariasi, tergantung pada lokasi dan luasnya gumpalan. Faktor risiko stroke trombotik meliputi hipertensi (tekanan darah tinggi), kadar kolesterol tinggi, merokok, diabetes, obesitas, gaya hidup tidak aktif, dan riwayat stroke dalam keluarga. Usia juga berperan, karena insiden stroke trombotik meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Individu dengan kondisi medis tertentu, seperti fibrilasi atrium (detak jantung yang tidak teratur) atau penyakit jantung lainnya, memiliki risiko lebih tinggi mengalami pembekuan 117 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK darah, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap stroke trombotik. Intervensi dini sangat penting dalam penanganan stroke trombotik untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan hasil. Pengobatan biasanya melibatkan pemberian obat penghilang gumpalan, seperti aktivator plasminogen jaringan (tPA), yang dapat melarutkan gumpalan dan memulihkan aliran darah. Dalam beberapa kasus, trombektomi mekanis, prosedur yang melibatkan pengangkatan gumpalan dengan menggunakan alat khusus, dapat dilakukan. Strategi pencegahan stroke trombotik berkisar pada penanganan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Modifikasi gaya hidup, seperti menerapkan pola makan yang sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, berhenti merokok, dan mengelola kondisi kronis seperti hipertensi dan diabetes, secara signifikan dapat mengurangi risiko stroke trombotik. Selain itu, penggunaan obat antikoagulan atau obat antiplatelet dapat direkomendasikan untuk individu yang berisiko tinggi, terutama mereka yang memiliki kondisi seperti fibrilasi atrium. Stroke Emboli Stroke emboli adalah jenis stroke iskemik spesifik yang terjadi ketika gumpalan darah atau benda asing lainnya, yang dikenal sebagai embolus, bergerak melalui aliran darah dan tersangkut di pembuluh darah yang lebih sempit di dalam otak, sehingga menghambat aliran darah. Emboli biasanya berasal dari lokasi yang jauh, biasanya dari jantung atau arteri besar. Sumber emboli yang umum termasuk gumpalan darah yang terbentuk di bilik jantung karena kondisi seperti fibrilasi atrium, atau gumpalan yang timbul dari plak aterosklerosis di arteri karotis atau arteri vertebralis. Tidak seperti stroke trombotik yang terjadi di dalam pembuluh darah yang memasok otak, stroke emboli cenderung terjadi secara 118 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK tiba-tiba dan dapat ditandai dengan gejala yang cepat dan parah. Embolus menyumbat arteri, sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke area otak yang terkena stroke terhenti secara tiba-tiba. Gejala stroke emboli dapat bervariasi, tergantung pada lokasi penyumbatan. Gejala-gejala ini sering kali muncul sebagai kelemahan atau mati rasa mendadak pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, perubahan penglihatan, pusing, dan masalah koordinasi. Pengenalan yang cepat terhadap gejala-gejala ini sangat penting, karena intervensi medis dini dapat meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan hasil. Beberapa faktor risiko berkontribusi terhadap perkembangan stroke emboli. Fibrilasi atrium, gangguan irama jantung yang umum terjadi, secara signifikan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah di bilik jantung, yang berpotensi menimbulkan emboli ke otak. Faktor risiko lainnya termasuk riwayat stroke atau serangan iskemik transien (TIA) sebelumnya, kelainan katup jantung, serangan jantung baru-baru ini, beberapa jenis penyakit jantung, dan kondisi yang meningkatkan gangguan pembekuan darah. Penanganan stroke emboli melibatkan penanganan medis segera untuk memulihkan aliran darah ke otak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Perawatan dapat mencakup pemberian obat pelarutan gumpalan seperti aktivator plasminogen jaringan (tPA) atau trombektomi mekanis, suatu prosedur yang melibatkan pengangkatan gumpalan secara fisik. Mengidentifikasi sumber embolus dan mengatasi kondisi yang mendasari seperti fibrilasi atrium melalui terapi antikoagulan atau obat lain sangat penting untuk mencegah kejadian emboli di masa depan. Strategi pencegahan stroke emboli melibatkan pengelolaan faktor risiko dan kondisi yang mendasarinya. Ini dapat mencakup terapi antikoagulan, modifikasi gaya hidup, seperti menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, dan 119 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK mengelola kondisi kronis seperti hipertensi dan diabetes. Individu dengan riwayat stroke emboli mungkin memerlukan pengobatan jangka panjang dengan obat pengencer darah untuk mencegah kejadian berulang. Stroke Iskemik Karena Gangguan Koagulasi Stroke iskemik dapat dipengaruhi oleh gangguan koagulasi, yaitu kelainan dalam proses pembekuan darah. Gangguan ini dapat berkontribusi pada pembentukan bekuan darah di dalam pembuluh darah atau menyebabkan peningkatan risiko perdarahan, yang keduanya dapat berimplikasi pada stroke iskemik. Salah satu gangguan koagulasi yang umum terjadi pada stroke iskemik adalah peningkatan kecenderungan darah menggumpal secara berlebihan, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperkoagulabilitas. Kondisi hiperkoagulabilitas dapat diperoleh atau diwariskan, dan mendorong pembentukan gumpalan darah di dalam arteri yang memasok otak. Kelainan genetik tertentu, seperti mutasi faktor V Leiden atau mutasi gen protrombin, dapat membuat seseorang mengalami pembekuan darah yang tidak normal dan meningkatkan risiko stroke iskemik. Selain itu, kondisi medis tertentu, seperti sindrom antifosfolipid atau keganasan, dapat menyebabkan keadaan hiperkoagulasi dan berkontribusi terhadap perkembangan stroke. Sebaliknya, beberapa orang mungkin mengalami gangguan koagulasi yang mengganggu proses pembekuan normal, sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Obat antikoagulan, seperti warfarin atau heparin, umumnya digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada individu dengan kondisi seperti fibrilasi atrium atau katup jantung mekanis. Namun, jika obat-obatan ini tidak dikelola atau dipantau dengan baik, maka dapat meningkatkan risiko perdarahan, 120 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK termasuk perdarahan di dalam otak, yang dapat meniru gejala stroke iskemik. Mengelola gangguan koagulasi dalam konteks stroke iskemik membutuhkan keseimbangan yang rumit. Untuk individu dengan kondisi hiperkoagulasi, terapi antikoagulan yang tepat dapat diberikan untuk mencegah pembentukan bekuan darah dan mengurangi risiko stroke iskemik. Namun, hal ini harus diimbangi dengan potensi risiko perdarahan. Pemantauan parameter koagulasi secara teratur, seperti rasio normalisasi internasional (INR) untuk individu yang menggunakan obat antikoagulan, sangat penting untuk memastikan dosis yang tepat dan meminimalkan risiko komplikasi. 6.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS STROKE ISKEMIK BEFAST Singkatan BEFAST sering digunakan dalam identifikasi dan diagnosis gejala stroke iskemik. Ini bertindak sebagai panduan referensi cepat untuk mengenali gejala stroke yang dicurigai dan menandakan permintaan akan intervensi medis yang cepat. Singkatan BEFAST adalah singkatan dari gejala atau perilaku tertentu yang harus diwaspadai: B - Keseimbangan: Kehilangan keseimbangan atau koordinasi secara tiba-tiba, kesulitan berjalan, atau perasaan pusing dapat menjadi indikasi stroke iskemik. Perhatikan setiap perubahan mendadak dalam keseimbangan atau kesulitan koordinasi. E - Mata: Masalah penglihatan, seperti penglihatan kabur atau ganda secara tiba-tiba, atau kehilangan penglihatan secara tiba-tiba pada salah satu atau kedua mata, dapat menjadi tanda peringatan stroke iskemik. Setiap perubahan akut pada penglihatan tidak boleh diabaikan dan harus segera dilakukan evaluasi medis. 121 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK F - Wajah: Wajah terkulai atau mati rasa, terutama pada satu sisi wajah, adalah gejala umum stroke iskemik. Mintalah orang tersebut untuk tersenyum dan amati apakah ada ketidakrataan atau asimetri pada wajahnya, karena hal ini dapat mengindikasikan adanya stroke. A - Lengan: Kelemahan atau mati rasa pada salah satu atau kedua lengan, terutama jika terjadi pada satu sisi tubuh, dapat menjadi indikator yang signifikan dari stroke iskemik. Mintalah orang tersebut untuk mengangkat kedua lengannya dan amati apakah salah satu lengannya melayang ke bawah atau terlihat lebih lemah daripada lengan lainnya. S - Bicara: Bicara cadel, kesulitan menemukan kata-kata yang tepat, atau kebingungan tiba-tiba dapat menjadi tanda-tanda stroke iskemik. Mintalah orang tersebut untuk mengulangi kalimat sederhana dan dengarkan apakah ada kelainan atau kesulitan bicara. T - Waktu: Waktu adalah hal yang paling penting dalam menangani stroke iskemik. Jika salah satu gejala di atas terlihat, sangat penting untuk segera menghubungi layanan darurat dan mencari pertolongan medis tanpa penundaan. Mengingat singkatan BEFAST dapat membantu individu dan orang yang melihat dengan cepat mengenali potensi gejala stroke dan mengambil tindakan yang tepat. Pengenalan dini dan intervensi medis yang cepat sangat penting dalam penanganan stroke iskemik untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan hasil. Stroke Siriraj Score (SSS) Sistem penilaian klinis yang disebut Stroke Siriraj Score, juga disebut sebagai Siriraj Stroke Score (SSS), digunakan untuk mengevaluasi tingkat keparahan dan meramalkan prognosis stroke iskemik akut. Skor ini dibuat oleh Pusat Stroke di Rumah Sakit Siriraj di Thailand dan telah terbukti bermanfaat dalam menentukan tingkat keparahan stroke dan memperkirakan hasilnya. 122 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK Skor Stroke Siriraj memberikan skor numerik dengan mempertimbangkan berbagai parameter klinis. Usia pasien, kondisi kesadaran, kelemahan anggota tubuh, dan afasia atau kesulitan bicara adalah beberapa faktor ini. Setiap elemen diberi nilai antara 0 dan 3, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan stroke yang lebih parah. Total Skor Stroke Siriraj kemudian ditentukan dengan menambahkan skor individu. Stroke Siriraj Score sangat membantu di lingkungan dengan sumber daya terbatas di mana metode pencitraan yang lebih baik mungkin tidak mudah diakses. Skor ini membantu para profesional medis untuk segera menentukan tingkat keparahan stroke dan membuat pilihan manajemen dan pengobatan dini. Selain itu, telah ditemukan bahwa Stroke Siriraj Score berkorelasi baik dengan hasil fungsional dan tingkat kematian, menawarkan data prognostik yang penting. Sangat penting untuk diingat bahwa Stroke Siriraj Score hanyalah salah satu dari sekian banyak alat yang tersedia untuk menilai pasien stroke, dan harus digunakan bersama dengan evaluasi klinis dan prosedur diagnostik lainnya. Keadaan setiap pasien berbeda, dan elemen tambahan, seperti komorbiditas dan hasil pencitraan, juga harus dipertimbangkan ketika memilih tindakan terbaik. 123 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK Skor Stroke Siriraj (SSS) (2,5xS) + (2xM) + (2xN) + (0,1xD) – (3xA) – 12 S: Kesadaran (0 = CM, 1 = Somnolen, 2 = sopor/koma) M: Muntah (0 = tidak muntah, 1 = muntah) N: Nyeri Kepala (0 = tidak ada, 1 = ada) D: Tekanan darah diastolik A: Ateroma (0 = tidak ada, 1 = salah satu/lebih: DM, angina, penyakit pembuluh darah) SSS >1 = stroke perdarahan SSS <-1 = stoke ischemic SSS -1s/d 1 = meragukan Gambar 36 Skor Stroke Siriraj (SSS) Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik merupakan komponen penting dalam diagnosis stroke iskemik. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang mungkin perlu dinilai oleh penyedia layanan kesehatan selama pemeriksaan fisik: • Pemeriksaan neurologis: Menilai kekuatan motorik, sensasi, refleks, koordinasi, dan kemampuan bicara dapat membantu mengidentifikasi defisit neurologis yang terkait dengan stroke iskemik. • Pemeriksaan kardiovaskular: Mendengarkan jantung dan paruparu serta menilai denyut nadi perifer dapat membantu mengidentifikasi penyakit atau kondisi kardiovaskular yang mendasari yang dapat meningkatkan risiko stroke iskemik terutama iskemik embolik. 124 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK • Pemeriksaan kepala dan leher: Memeriksa kepala dan leher untuk mencari tanda-tanda trauma, kekakuan, atau kelainan dapat membantu mengidentifikasi penyebab stroke hemoragik. • Tes laboratorium: Tes darah seperti hitung darah lengkap (CBC), elektrolit, glukosa, studi koagulasi, dan tes fungsi ginjal dapat dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kondisi medis yang mendasari atau faktor yang dapat berkontribusi terhadap stroke hemoragik. Pemeriksaan fisik yang komprehensif dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk membuat diagnosis stroke iskemik yang akurat dan mengembangkan rencana perawatan yang tepat untuk pasien. Pemeriksaan Radiologis Pencitraan radiologi memainkan peran penting dalam mendiagnosis stroke iskemik dengan memberikan visualisasi rinci otak dan pembuluh darahnya. Beberapa teknik pencitraan umumnya digunakan untuk mendukung diagnosis dan memandu keputusan pengobatan bagi pasien yang diduga menderita stroke iskemik. Computed tomography (CT) non-kontras sering kali merupakan modalitas pencitraan lini pertama dalam evaluasi stroke akut. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi stroke hemoragik dan menyingkirkan kondisi lain yang mungkin meniru gejala stroke. CT scan dapat dengan cepat mendeteksi tanda-tanda perubahan iskemik, seperti hilangnya diferensiasi materi abu-abu-putih dan tanda-tanda awal infark. Informasi ini membantu menentukan kelayakan untuk intervensi yang sensitif terhadap waktu seperti terapi trombolitik. Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah alat lain yang ampuh untuk mendiagnosis stroke iskemik. Pencitraan berbobot difusi (DWI) sangat sensitif dalam mendeteksi perubahan awal yang terkait dengan iskemia, sehingga memungkinkan visualisasi jaringan otak yang 125 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK terkena dampak dalam beberapa menit setelah timbulnya gejala. DWI dapat mendeteksi perubahan halus dalam difusi molekul air, sehingga memberikan informasi yang berharga mengenai lokasi dan luasnya kerusakan iskemik. Pencitraan berbobot perfusi (Perfusion-weighted imaging/PWI) sering dilakukan bersamaan dengan DWI untuk menilai perfusi darah di dalam otak. PWI dapat mengungkapkan area yang mengalami penurunan aliran darah atau waktu yang tertunda untuk mencapai puncak perfusi, yang mengindikasikan area hipoperfusi atau potensi penumbra. Informasi ini membantu evaluasi jaringan otak yang dapat diselamatkan dan membantu memandu keputusan pengobatan, seperti trombektomi atau strategi revaskularisasi lainnya. Teknik pencitraan canggih lainnya, seperti Magnetic Resonance Angiography (MRA) dan Computed Tomography Angiography (CTA), digunakan untuk memvisualisasikan pembuluh darah dan mengidentifikasi oklusi atau stenosis yang mungkin menyebabkan stroke iskemik. Modalitas pencitraan ini memberikan informasi rinci tentang anatomi pembuluh darah dan dapat membantu mengidentifikasi lokasi oklusi arteri. Pemilihan modalitas pencitraan radiologi bergantung pada beberapa faktor, termasuk rentang waktu sejak timbulnya gejala, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik pasien. Kombinasi berbagai teknik pencitraan, seperti CT non-kontras, DWI, PWI, dan pencitraan vaskular, memungkinkan evaluasi komprehensif stroke iskemik, membantu diagnosis yang akurat, menentukan penyebab yang mendasari, dan memandu keputusan pengobatan yang tepat. The Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECT) Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) adalah sistem penilaian radiologi yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat perubahan iskemik awal yang terlihat pada pemindaian tomografi 126 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK komputasi non-kontras (CT) pada pasien stroke iskemik akut. Sistem ini menyediakan metode standar untuk menilai tingkat keparahan kerusakan iskemik di berbagai wilayah otak. ASPECTS membagi wilayah arteri serebral tengah (MCA) menjadi sepuluh wilayah, dengan memberikan skor 0 pada setiap wilayah berdasarkan ada tidaknya perubahan iskemik. Skor 10 menunjukkan tidak ada perubahan iskemik, sedangkan skor 0 menunjukkan keterlibatan yang luas dari semua wilayah. Daerah yang dinilai oleh ASPECTS meliputi kaudat, nukleus lentiformis, kapsul internal, insula, dan berbagai daerah kortikal. Sistem penilaian ASPECTS membantu dokter mengukur tingkat kerusakan iskemik dan memprediksi hasil akhir pasien. Skor ASPECTS yang lebih rendah menunjukkan inti iskemik yang lebih besar dan berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk, termasuk peningkatan kemungkinan kecacatan dan respons yang kurang baik terhadap terapi reperfusi. ASPECTS dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan terapi trombolitik dan intervensi endovaskular, serta memberikan informasi prognostik. ASPECTS telah menunjukkan keandalan antar-penilai yang baik dan digunakan secara luas dalam praktik klinis dan penelitian. Hal ini memungkinkan komunikasi standar di antara para profesional kesehatan yang terlibat dalam perawatan stroke dan memfasilitasi pelaporan temuan radiologi yang konsisten. Namun, penting untuk dicatat bahwa ASPECTS khusus untuk CT scan non-kontras dan terutama digunakan dalam evaluasi awal stroke iskemik akut. Modalitas pencitraan lainnya, seperti magnetic resonance imaging (MRI), dapat memberikan informasi tambahan mengenai kelangsungan hidup jaringan dan membantu menyempurnakan keputusan pengobatan. Selain itu, ASPECTS hanyalah salah satu komponen dari evaluasi komprehensif yang mencakup penilaian klinis dan temuan pencitraan lainnya. 127 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK Gambar 37 ASPECTS Score Area : C – caudate IC – Internal Capsule L – Lentiform nucleus I – Insular ribbon M1 – Anterior MCA Cortex M2 – MCA cortex lateral to the insular ribbon M3 – Posterior MCA cortex M4 – Anterior cortex immediately rostal to M1 (M4) M5 – Lateral cortex immediately rostal to M3 (M5) M6 – Posterior cortex immediately rostal to M3 (M6) 6.6 TATALAKSANA STROKE ISKEMIK Pengobatan stroke iskemik bertujuan untuk memulihkan aliran darah ke area otak yang terkena, meminimalkan kerusakan otak, dan mencegah stroke di masa depan. Waktu adalah hal yang sangat penting, karena intervensi dini secara signifikan meningkatkan hasil. Pilihan pengobatan spesifik dapat bervariasi, tergantung pada masing128 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK masing pasien, tingkat keparahan stroke, dan waktu sejak timbulnya gejala. Salah satu strategi pengobatan utama untuk stroke iskemik adalah trombolisis, yang melibatkan pemberian obat pelarutan gumpalan. Obat yang paling sering digunakan adalah aktivator plasminogen jaringan (tPA), yang dapat memecah gumpalan darah yang menyebabkan stroke dan memulihkan aliran darah. Trombolisis biasanya dipertimbangkan dalam jangka waktu tertentu sejak timbulnya gejala, biasanya hingga 4,5 jam, meskipun beberapa pasien mungkin memenuhi syarat untuk pengobatan hingga 24 jam setelah timbulnya stroke tertentu. Untuk pasien yang memenuhi syarat dengan oklusi pembuluh darah besar, trombektomi mekanis dapat direkomendasikan. Prosedur ini melibatkan penggunaan alat khusus untuk mengeluarkan bekuan darah dari arteri yang tersumbat secara fisik. Trombektomi mekanis telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam meningkatkan hasil bagi pasien dengan oklusi pembuluh darah besar bila dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 hingga 24 jam sejak timbulnya gejala, tergantung pada masing-masing kasus. Untuk mencegah stroke di masa depan, berbagai tindakan pencegahan diterapkan. Obat-obatan seperti agen antiplatelet, termasuk aspirin atau clopidogrel, umumnya diresepkan untuk mengurangi risiko pembentukan bekuan darah. Terapi antikoagulan dapat digunakan pada kasus tertentu, seperti pada pasien dengan fibrilasi atrium atau kondisi berisiko tinggi lainnya. Mengelola faktor risiko yang mendasari, seperti hipertensi, kadar kolesterol tinggi, dan diabetes, juga sangat penting. Modifikasi gaya hidup, termasuk menerapkan pola makan yang sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, dan membatasi asupan alkohol, merupakan komponen penting dalam pencegahan stroke. 129 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK Selain intervensi medis, rehabilitasi memainkan peran penting dalam pengobatan stroke iskemik. Program rehabilitasi, termasuk terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, dan keperawatan rehabilitasi, membantu pasien mendapatkan kembali fungsi yang hilang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya rehabilitasi berfokus pada mobilitas, kekuatan, koordinasi, kemampuan bicara dan bahasa, serta aktivitas kehidupan sehari-hari. Rencana perawatan setiap pasien disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan dan lokasi stroke, riwayat medis, dan karakteristik individu. Perawatan multidisiplin, yang melibatkan ahli saraf, spesialis stroke, ahli rehabilitasi, dan tenaga kesehatan lainnya, sangat penting dalam memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk pasien stroke iskemik. 130 MANAJEMEN STROKE ISKEMIK Referensi 1. French, B.R., Boddepalli, R.S. and Govindarajan, R. (2016) Acute ischemic stroke: Current status and Future Directions, Missouri medicine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139763/ 2. Hurford, R. et al. (2020) Diagnosis and management of acute ischaemic stroke, Practical Neurology. Available at: https://pn.bmj.com/content/20/4/304 3. Jacquin, G.J. and van Adel, B.A. (2015) ‘Treatment of acute ischemic stroke: From fibrinolysis to neurointervention’, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 13. doi:10.1111/jth.12971. 4. Kristin Walter, M. (2022) Patient information: Acute ischemic stroke, JAMA. Available at: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789540 5. L;, H.C.P. (no date) Ischemic stroke, National Center for Biotechnology Information. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29763173/ 6. Rabinstein, A.A. (2017) ‘Treatment of acute ischemic stroke’, CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology, 23(1), pp. 62–81. doi:10.1212/con.0000000000000420. 7. Skagen, K. et al. (2015) ‘Large-vessel occlusion stroke: Effect of recanalization on outcome depends on the National Institutes of Health Stroke Scale score’, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 24(7), pp. 1532–1539. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.03.020. 8. Zerna, C., Hegedus, J. and Hill, M.D. (2016) ‘Evolving treatments for acute ischemic stroke’, Circulation Research, 118(9), pp. 1425– 1442. doi:10.1161/circresaha.116.307005 131 BAB VII BAB VII MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN 7.1 PENDAHULUAN Stroke hemoragik adalah jenis stroke yang disebabkan oleh pendarahan di otak. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa kejadian stroke hemoragik bervariasi secara signifikan di seluruh dunia. Di beberapa negara, seperti Jepang, kejadian stroke hemoragik lebih tinggi daripada stroke iskemik, sementara di negara lain, seperti Amerika Serikat, yang terjadi adalah sebaliknya. Insiden stroke hemoragik juga bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan etnis, dengan pria dan orang dewasa yang lebih tua lebih mungkin mengalami jenis stroke ini. Faktor risiko stroke hemoragik meliputi tekanan darah tinggi, merokok, dan konsumsi alkohol berat. Strategi pencegahan untuk stroke hemoragik meliputi modifikasi gaya hidup, seperti menjaga pola makan yang sehat dan rutin berolahraga, serta mengendalikan tekanan darah tinggi dan faktor risiko lainnya. Perawatan untuk stroke hemoragik biasanya melibatkan perawatan medis darurat untuk menghentikan pendarahan di otak dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. 7.2 STROKE PERDARAHAN Stroke hemoragik, juga dikenal sebagai pendarahan otak, adalah jenis stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan mengeluarkan darah ke jaringan otak di sekitarnya. Pendarahan ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak dan dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk sakit kepala parah, kelemahan, mati rasa, dan kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. Ada dua jenis utama stroke hemoragik: perdarahan intraserebral, yang terjadi ketika pembuluh darah di dalam otak pecah dan mengeluarkan darah, dan perdarahan subarakhnoid, yang terjadi 132 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN ketika terjadi perdarahan di antara otak dan jaringan tipis yang menutupinya. Stroke hemoragik lebih jarang terjadi dibandingkan stroke iskemik, yang terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat, tetapi sering kali lebih parah dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Penanganan medis yang cepat sangat penting dalam pengobatan stroke hemoragik, karena intervensi dini dapat membantu meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan hasil bagi pasien. 7.3 EPIDEMIOLOGI Stroke hemoragik adalah kondisi kesehatan serius yang bertanggung jawab atas sebagian besar kematian akibat stroke di seluruh dunia. Epidemiologi stroke hemoragik sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan perbedaan tingkat kejadian yang diamati di antara populasi, negara, dan wilayah yang berbeda. Menurut perkiraan global, stroke hemoragik menyumbang sekitar 15% dari semua stroke, dengan tingkat kejadian bervariasi antara 10% dan 30% di berbagai wilayah. Insiden stroke hemoragik cenderung lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan beberapa wilayah, seperti Asia Selatan, menunjukkan angka yang sangat tinggi. Beberapa faktor risiko telah dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke hemoragik, termasuk tekanan darah tinggi, merokok, konsumsi alkohol berat, dan riwayat stroke dalam keluarga. Strategi pencegahan, seperti pengelolaan tekanan darah tinggi dan faktor risiko lainnya, dapat membantu mengurangi kejadian stroke hemoragik, sementara diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk meningkatkan hasil bagi pasien. 133 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN 7.4 KLASIFIKASI Perdarahan Intraserebral (ICH) Pendarahan Intraserebral (ICH) adalah jenis stroke hemoragik yang terjadi ketika pembuluh darah di dalam otak pecah dan mengeluarkan darah ke jaringan otak di sekitarnya. Pendarahan ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak dan dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk sakit kepala, mual, muntah, kelemahan, mati rasa, dan kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. ICH lebih jarang terjadi dibandingkan dengan stroke iskemik, yang terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat, tetapi sering kali lebih parah dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. ICH lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan dikaitkan dengan berbagai faktor risiko, termasuk tekanan darah tinggi, merokok, konsumsi alkohol berat, dan penggunaan obatobatan tertentu, seperti antikoagulan. Perawatan untuk ICH biasanya melibatkan perawatan medis darurat untuk menghentikan pendarahan di otak dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut, seperti pembengkakan otak atau peningkatan tekanan di dalam tengkorak. Rehabilitasi dan perawatan jangka panjang mungkin juga diperlukan untuk membantu pasien pulih dari efek ICH. Pendarahan intraserebral (ICH) adalah kondisi yang kompleks dengan berbagai penyebab yang mendasarinya. Penyebab ICH yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, yang dapat melemahkan pembuluh darah di otak dan meningkatkan risiko pecah. Faktor risiko lain untuk ICH termasuk merokok, konsumsi alkohol berat, penggunaan obat-obatan tertentu seperti antikoagulan atau agen antiplatelet, kelainan darah seperti hemofilia atau penyakit sel sabit, dan kelainan struktural pada pembuluh darah otak. Dalam beberapa kasus, ICH dapat disebabkan oleh malformasi arteriovenosa otak (AVM), suatu kondisi di mana hubungan abnormal antara arteri dan 134 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN vena di otak dapat menyebabkan perdarahan. Jarang, ICH dapat disebabkan oleh tumor otak atau aneurisma, yaitu tonjolan dalam pembuluh darah yang dapat pecah. Memahami penyebab yang mendasari ICH sangat penting untuk memandu pengobatan dan mencegah episode di masa depan. Manajemen faktor risiko, seperti kontrol tekanan darah dan modifikasi gaya hidup, merupakan aspek penting dalam mencegah ICH, sementara perhatian medis yang cepat dan intervensi yang tepat dapat membantu meningkatkan hasil bagi pasien yang telah mengalami ICH. Salah satu arteri yang paling umum yang terkait dengan ICH adalah arteri lentikulostriata, yang memasok darah ke ganglia basalis dan rentan terhadap kerusakan akibat tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan dinding arteri lentikulostriata menebal, sehingga lebih rentan pecah. Arteri lain yang sering terlibat dalam ICH adalah arteri serebri, yang memasok darah ke sebagian besar otak dan rentan pecah pada kasus angiopati amiloid serebri, yaitu suatu kondisi di mana protein menumpuk di pembuluh darah otak. Arteri serebral posterior, yang memasok darah ke bagian belakang otak, kadang-kadang juga terlibat dalam ICH. Memahami arteri mana yang lebih rentan pecah dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi pasien yang mungkin berisiko lebih tinggi terkena ICH dan mengembangkan strategi manajemen dan pencegahan yang tepat. Perdarahan Subarakhnoid (SAH) Pendarahan subaraknoid (SAH) adalah jenis stroke hemoragik yang terjadi ketika pendarahan terjadi di ruang antara otak dan jaringan tipis yang menutupinya. Penyebab paling umum dari SAH adalah pecahnya aneurisma otak, yang merupakan titik lemah dan menonjol dalam pembuluh darah di otak. Arteri yang paling sering dikaitkan dengan aneurisma serebral dan SAH adalah arteri penghubung anterior, arteri penghubung posterior, dan arteri 135 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN serebral tengah. Dalam banyak kasus, aneurisma serebral dan SAH terjadi tanpa gejala apa pun dan hanya dapat didiagnosis melalui pemeriksaan pencitraan, seperti CT scan atau MRI. Namun, ketika aneurisma pecah, dapat menyebabkan sakit kepala yang tiba-tiba, sakit kepala yang parah, mual, muntah, kepekaan terhadap cahaya, kejang, dan kehilangan kesadaran. Penanganan medis darurat diperlukan untuk mendiagnosis dan mengobati SAH, yang mungkin melibatkan pembedahan untuk memperbaiki atau mengangkat aneurisma atau intervensi lain untuk menghentikan perdarahan dan menangani komplikasi. Mengidentifikasi faktor risiko, seperti merokok, tekanan darah tinggi, dan riwayat keluarga dengan aneurisma otak, adalah penting untuk mencegah SAH dan menghindari konsekuensi serius yang dapat ditimbulkan oleh kondisi ini. Perdarahan Intraventrikular (IVH) Perdarahan Intraventrikular (IVH) adalah jenis perdarahan yang terjadi di dalam sistem ventrikel otak, yang merupakan jaringan ruang berisi cairan. Pada orang dewasa, IVH sering kali merupakan komplikasi dari cedera otak traumatik atau sebagai akibat dari kondisi lain, seperti aneurisma atau malformasi arteriovenosa. Pembuluh darah yang terkait dengan IVH pada orang dewasa dapat bervariasi, tergantung pada penyebabnya. Sebagai contoh, IVH yang disebabkan oleh cedera otak traumatis dapat dikaitkan dengan cedera pada pembuluh darah kecil yang memasok darah ke otak. Sebaliknya, IVH yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma atau malformasi arteriovenosa dapat melibatkan pembuluh darah yang lebih besar yang memasok darah ke daerah yang terkena. Insiden IVH pada orang dewasa relatif rendah dibandingkan dengan jenis perdarahan intrakranial lainnya, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pasien. Penanganan IVH meliputi identifikasi dan 136 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN penanganan penyebab yang mendasari, penanganan gejala dan komplikasi, serta memberikan perawatan suportif untuk mempercepat penyembuhan dan pemulihan. 7.5 PENEGAKAN DIAGNOSIS STROKE PERDARAHAN Anamnesis Anamnesis yang akurat dan komprehensif penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mendiagnosis dan mengobati stroke hemoragik. Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin perlu dimasukkan dalam anamnesis: • Kelemahan satu sisi yang mendadak • Keberadaan dan durasi gejala, seperti sakit kepala parah yang tiba-tiba, muntah, pusing, kehilangan kesadaran, atau defisit neurologis lainnya • Riwayat kesehatan, termasuk riwayat hipertensi, diabetes, merokok, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, stroke sebelumnya, atau penyakit kardiovaskular • Riwayat keluarga dengan stroke atau penyakit kardiovaskular • Obat-obatan, termasuk antikoagulan atau agen antiplatelet • Trauma atau cedera kepala baru-baru ini • Faktor gaya hidup, seperti pola makan, olahraga, dan tingkat stres • Usia dan jenis kelamin • Waktu timbulnya gejala dan berapa lama gejala tersebut bertahan • Operasi atau prosedur medis yang baru saja dijalani • Kondisi atau gejala medis lain yang relevan. Mengumpulkan informasi ini selama anamnesis dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk membuat diagnosis 137 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN stroke hemoragik yang akurat dan mengembangkan rencana perawatan yang tepat untuk pasien. Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik merupakan komponen penting dalam diagnosis stroke hemoragik. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang mungkin perlu dinilai oleh penyedia layanan kesehatan selama pemeriksaan fisik: • Tekanan darah: Hipertensi merupakan faktor risiko utama stroke hemoragik, sehingga mengukur tekanan darah merupakan bagian penting dari pemeriksaan. • Pemeriksaan neurologis: Menilai kekuatan motorik, sensasi, refleks, koordinasi, dan kemampuan bicara dapat membantu mengidentifikasi defisit neurologis yang terkait dengan stroke hemoragik. • Pemeriksaan mata: Pemeriksaan pupil, penglihatan, dan gerakan mata dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. • Pemeriksaan kardiovaskular: Mendengarkan jantung dan paruparu serta menilai denyut nadi perifer dapat membantu mengidentifikasi penyakit atau kondisi kardiovaskular yang mendasari yang dapat meningkatkan risiko stroke hemoragik. • Pemeriksaan kepala dan leher: Memeriksa kepala dan leher untuk mencari tanda-tanda trauma, kekakuan, atau kelainan dapat membantu mengidentifikasi penyebab stroke hemoragik. • Tes laboratorium: Tes darah seperti hitung darah lengkap (CBC), elektrolit, glukosa, studi koagulasi, dan tes fungsi ginjal dapat dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kondisi medis yang mendasari atau faktor yang dapat berkontribusi terhadap stroke hemoragik. 138 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Pemeriksaan fisik yang komprehensif dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk membuat diagnosis stroke hemoragik yang akurat dan mengembangkan rencana perawatan yang tepat untuk pasien. Pemeriksaan Radiologis Pemeriksaan radiologi merupakan komponen penting dalam diagnosis dan penatalaksanaan stroke hemoragik, termasuk perdarahan subaraknoid (SAH) dan perdarahan intraventrikular (IVH). Computed tomography (CT) scan adalah modalitas pencitraan yang paling sering digunakan untuk diagnosis stroke hemoragik karena dapat dengan cepat mengidentifikasi keberadaan dan lokasi perdarahan di otak. Pada kasus SAH, CT angiografi atau angiogram otak juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber perdarahan, seperti aneurisma atau malformasi arteriovenosa (AVM). Untuk IVH, pemeriksaan pencitraan seperti CT atau MRI dapat digunakan untuk menentukan tingkat perdarahan dan menilai kerusakan otak yang terkait. Pemeriksaan pencitraan serial juga dapat dilakukan untuk memantau perkembangan perdarahan dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. Secara keseluruhan, pemeriksaan radiologi memainkan peran penting dalam diagnosis dan penanganan stroke hemoragik, dan deteksi dini serta intervensi dapat meningkatkan hasil bagi pasien. 7.6 GRADING/STAGING/SCORING Perdarahan Intraserebral Sistem penilaian atau penskalaan yang paling umum digunakan untuk perdarahan intraserebral (ICH) adalah skor ICH. Skor ICH adalah sistem penilaian klinis yang membantu memprediksi kemungkinan hasil yang buruk pada pasien ICH. Skor ini didasarkan pada lima 139 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN variabel: usia, skor Glasgow Coma Scale (GCS), volume ICH, perdarahan intraventrikular (IVH), dan asal perdarahan. Setiap variabel diberi sejumlah poin, dan skor total dapat berkisar dari 0 hingga 6. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan yang lebih besar untuk hasil yang buruk, seperti kematian atau kecacatan yang parah. Skor ICH dapat digunakan untuk memandu keputusan pengobatan dan membantu penyedia layanan kesehatan untuk memperkirakan prognosis pasien dengan ICH. Gambar 38 ICH Score oleh Hemphill et al. Perdarahan Subarakhnoid Sistem penilaian yang paling banyak digunakan untuk perdarahan subarakhnoid (SAH) adalah sistem penilaian Hunt and Hess. Sistem penilaian Hunt and Hess adalah skala klinis yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keparahan SAH dan memprediksi kemungkinan hasil yang buruk. Sistem ini didasarkan pada tingkat kesadaran pasien, defisit motorik, dan adanya gejala neurologis lainnya. Sistem penilaian Hunt dan Hess dibagi menjadi lima tingkatan: • Tingkat 1: Sakit kepala tanpa gejala atau ringan 140 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN • • • • Tingkat 2: Sakit kepala sedang hingga berat, tidak ada defisit neurologis selain kelumpuhan saraf kranial Tingkat 3: Mengantuk, kebingungan, atau defisit neurologis fokal ringan Tingkat 4: Pingsan, hemiparesis sedang hingga berat, kekakuan awal deserebrasi, atau gangguan vegetatif Tingkat 5: Koma berat, kekakuan deserebrasi, dan penampilan mati suri Sistem penilaian Hunt and Hess membantu memandu keputusan pengobatan dan memprediksi risiko komplikasi seperti perdarahan ulang, vasospasme, dan infark otak. Sistem ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan memperkirakan prognosis pasien SAH. Skala Fisher adalah sistem penilaian lain yang biasa digunakan untuk perdarahan subaraknoid (SAH). Sistem penilaian Fisher didasarkan pada tingkat keparahan perdarahan yang terlihat pada pencitraan computed tomography (CT). Sistem penilaiannya adalah sebagai berikut: • Tingkat 1: Tidak ada SAH yang terlihat pada CT scan • Tingkat 2: SAH tipis dengan ketebalan kurang dari 1 mm • Tingkat 3: SAH dengan gumpalan dan/atau gumpalan lokal dengan atau tanpa perdarahan intraventrikular • Tingkat 4: SAH difus atau tebal dengan atau tanpa perdarahan intraventrikular atau perluasan parenkim Sistem penilaian Fisher membantu memprediksi risiko vasospasme, perdarahan ulang, dan hasil yang buruk. Pasien dengan nilai Fisher yang lebih tinggi memiliki risiko komplikasi yang lebih besar dan mungkin memerlukan penanganan yang lebih agresif. Sistem penilaian Fisher sering digunakan bersama dengan sistem penilaian 141 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Hunt dan Hess untuk memandu keputusan pengobatan dan memperkirakan prognosis pasien dengan SAH. Gambar 39 Grading SAH Hunt and Hess 142 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Gambar 40 Grading SAH Fisher dan Modified Fisher Perdarahan Intraventrikular Terdapat sistem penilaian untuk perdarahan intraventrikular (IVH) yang disebut Skor Graeb. Skor Graeb adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keparahan IVH dan memprediksi kemungkinan hasil yang buruk. 143 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Skor Graeb didasarkan pada tingkat IVH yang terlihat pada pencitraan CT dan dibagi menjadi empat tingkatan: • Tingkat 0: Tidak ada IVH • Tingkat 1: IVH terbatas pada trigone ventrikel • Tingkat 2: IVH meluas ke salah satu atau kedua ventrikel lateral tanpa mengisinya • Tingkat 3: IVH mengisi salah satu atau kedua ventrikel lateral Skor Graeb yang lebih tinggi mengindikasikan IVH yang lebih parah dan kemungkinan hasil yang lebih besar, seperti hidrosefalus, edema serebral, dan kematian. Skor Graeb dapat digunakan untuk memandu keputusan pengobatan dan memperkirakan prognosis pasien dengan IVH. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan Skor Graeb tidak seluas Skor ICH atau sistem penilaian Hunt dan Hess untuk ICH dan SAH. 7.7 TATALAKSANA STROKE PERDARAHAN Perdarahan Intraserebral Menurunkan Tekanan Darah Menurunkan tekanan darah merupakan aspek penting dari pengobatan perdarahan intraserebral (ICH). Tekanan darah yang tinggi merupakan faktor risiko utama untuk ICH dan dapat memperburuk perdarahan serta berkontribusi terhadap perluasan hematoma. Pedoman American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) merekomendasikan untuk menurunkan tekanan darah secara bertahap pada pasien dengan ICH yang memiliki tekanan darah sistolik (SBP) lebih besar dari 150 mmHg. Target SBP 140 mmHg direkomendasikan untuk sebagian besar pasien ICH. Pada pasien dengan hipertensi berat (SBP>220 mmHg atau tekanan darah diastolik (DBP)>120 mmHg), penurunan tekanan darah yang lebih agresif mungkin diperlukan. 144 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Menurunkan tekanan darah dapat membantu mengurangi risiko perluasan hematoma, yang selanjutnya dapat merusak jaringan otak dan menyebabkan hasil yang buruk. Namun demikian, penting untuk memantau tekanan darah secara ketat selama perawatan untuk menghindari hipotensi, yang juga dapat berbahaya. Penurunan tekanan darah yang terlalu agresif dapat menyebabkan penurunan perfusi otak dan memperburuk hasil. Oleh karena itu, strategi manajemen tekanan darah yang optimal untuk pasien dengan ICH harus bersifat individual berdasarkan status klinis pasien dan faktor lainnya. Obat antihipertensi seperti Nikardipine (0.5-6 mcg/kgBB/menit) dan Diltiazem (5-20 mcg/kgBB/menit) sering digunakan untuk mengontrol tekanan darah pada pasien dengan ICH, tetapi pilihan obat dan dosis yang spesifik harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Kontrol Gula Darah dan Temperatur Selain menurunkan tekanan darah, kontrol suhu dan manajemen glukosa darah merupakan aspek penting dalam pengobatan perdarahan intraserebral (ICH). Peningkatan suhu dan kadar glukosa darah dapat memperburuk cedera otak dan meningkatkan risiko hasil yang buruk pada pasien ICH. Pedoman American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) merekomendasikan untuk mempertahankan normotermia (suhu tubuh antara 36,5°C dan 37,5°C) pada pasien ICH. Hal ini dapat dicapai dengan obat antipiretik, selimut pendingin, atau alat pendingin lainnya. Demikian pula, kontrol glikemik yang ketat direkomendasikan pada pasien dengan ICH untuk menghindari hiperglikemia, yang telah dikaitkan dengan peningkatan mortalitas dan hasil yang buruk. Pedoman AHA/ASA menyarankan untuk menargetkan kadar glukosa darah <180 mg/dL pada sebagian besar pasien stroke akut, termasuk ICH. 145 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Kontrol suhu dan manajemen glukosa darah dapat menjadi tantangan bagi pasien dengan ICH, terutama mereka yang membutuhkan perawatan intensif. Pemantauan yang ketat dan penyesuaian obat dan intervensi lain yang sering mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, target optimal untuk kontrol suhu dan glukosa darah dapat bervariasi, tergantung pada status klinis masing-masing pasien dan faktor lainnya. Oleh karena itu, strategi perawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perawatan pasien secara spesifik. Tatalaksana Kejang Kejang adalah komplikasi umum dari pendarahan intraserebral (ICH), yang terjadi pada hingga 15% pasien. Kejang dapat memperburuk cedera otak dan meningkatkan risiko hasil yang buruk pada pasien ICH. Oleh karena itu, penanganan kejang merupakan aspek penting dalam pengobatan ICH. Pedoman American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) merekomendasikan pengobatan obat antiepilepsi profilaksis (AED) untuk pasien dengan ICH yang memiliki risiko kejang yang tinggi, seperti pasien dengan hematoma besar atau perdarahan intraventrikuler. Namun, penggunaan AED profilaksis rutin tidak disarankan untuk semua pasien dengan ICH, karena mungkin tidak memberikan manfaat tambahan dan dapat dikaitkan dengan efek samping. Pada pasien dengan ICH yang mengalami kejang, disarankan untuk segera melakukan penanganan dengan AED. AED seperti fenitoin, levetiracetam, dan asam valproat sering digunakan untuk penanganan kejang pada pasien ICH. Pilihan AED harus didasarkan pada status klinis pasien dan faktor lainnya. Pemantauan ketat terhadap aktivitas kejang sangat penting pada pasien dengan ICH, karena kejang berulang dapat menjadi tanda 146 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN memburuknya cedera otak dan mungkin memerlukan penyesuaian dalam rencana perawatan. Selain itu, manajemen kejang harus diintegrasikan dengan aspek lain dari perawatan ICH, seperti kontrol tekanan darah, manajemen suhu, dan intervensi bedah, jika diindikasikan. Penanganan kejang yang optimal pada pasien dengan ICH harus dilakukan secara individual berdasarkan kebutuhan dan tujuan perawatan pasien secara spesifik. Gambar 41 Algoritma pemberian obat kejang pada stroke perdarahan Kontrol Tekanan Intrakranial Kontrol tekanan intrakranial (ICP) merupakan aspek penting dari pengobatan perdarahan intraserebral (ICH). Peningkatan TIK dapat menyebabkan cedera otak lebih lanjut dan dapat menjadi kontributor 147 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN yang signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas pada pasien ICH. Oleh karena itu, tindakan untuk mengendalikan TIK merupakan komponen kunci dari pengobatan ICH. Langkah pertama dalam pengendalian TIK adalah mengoptimalkan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi pasien. Hipoksemia, hiperkapnia, dan hipotensi semuanya dapat menyebabkan peningkatan TIK dan harus segera ditangani. Selain itu, memposisikan pasien dengan kepala tempat tidur ditinggikan hingga 30 derajat dapat membantu menurunkan TIK dengan meningkatkan drainase vena dari otak. Jika tindakan untuk mengoptimalkan oksigenasi, ventilasi, dan hemodinamika tidak cukup untuk mengontrol TIK, intervensi tambahan mungkin diperlukan. Intervensi ini dapat mencakup terapi osmotik, seperti penggunaan manitol intravena atau garam hipertonik, untuk mengurangi edema otak dan menurunkan TIK. Selain itu, sedasi dan analgesia dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan metabolisme otak dan menurunkan TIK. Jika TIK tetap tinggi meskipun telah dilakukan intervensi ini, tindakan yang lebih agresif mungkin diperlukan, seperti dekompresi bedah. Intervensi bedah, seperti hemikraniektomi atau evakuasi hematoma, dapat mengurangi tekanan pada otak dan meningkatkan hasil pada pasien tertentu dengan ICH. Keputusan untuk melakukan intervensi bedah harus didasarkan pada status klinis masing-masing pasien, temuan pencitraan, dan faktor lainnya. Secara keseluruhan, pengendalian TIK yang efektif sangat penting untuk keberhasilan manajemen pasien dengan perdarahan intraserebral. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan keahlian ahli saraf, ahli bedah saraf, dan dokter perawatan kritis sangat penting untuk mengoptimalkan hasil pada pasien-pasien ini. 148 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Gambar 42 Posisi Low-Fowler’s atau Head Trunk Up 30 Degrees Perdarahan Subarakhnoid Penanganan perdarahan subarakhnoid (SAH) bertujuan untuk mencegah perdarahan ulang, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan hasil. Penanganan awal SAH meliputi menstabilkan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi pasien, serta memastikan tekanan darah dan oksigenasi dioptimalkan. Setelah pasien stabil, pemeriksaan pencitraan segera dilakukan untuk menentukan lokasi dan tingkat keparahan perdarahan. Pengobatan andalan untuk SAH adalah perbaikan aneurisma. Hal ini dapat dicapai melalui pemotongan bedah atau penggulungan endovaskular, tergantung pada lokasi dan morfologi aneurisma. Pilihan modalitas pengobatan didasarkan pada ukuran dan lokasi aneurisma, serta usia, status klinis, dan komorbiditas pasien. Selain perbaikan aneurisma, tindakan pendukung lainnya mungkin diperlukan untuk menangani komplikasi dan mengoptimalkan hasil pada pasien SAH. Tindakan ini dapat mencakup terapi antikonvulsan untuk mencegah kejang, pengendalian nyeri, dan manajemen gangguan elektrolit dan gangguan metabolisme lainnya. Selain itu, pasien dengan SAH yang parah mungkin memerlukan ventilasi mekanis dan pemantauan unit perawatan intensif. 149 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Secara keseluruhan, penanganan perdarahan subaraknoid memerlukan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan keahlian ahli saraf, ahli bedah saraf, dan dokter perawatan kritis. Identifikasi dan penanganan yang cepat terhadap aneurisma yang mendasari, bersama dengan penanganan komplikasi yang terkait, dapat meningkatkan hasil dan mengurangi angka kematian pada pasien dengan kondisi ini. Perdarahan Intraventrikular Penanganan perdarahan intraventrikular (IVH) ditujukan untuk mengendalikan perdarahan, mencegah komplikasi, dan meningkatkan hasil. Penanganan awal IVH melibatkan stabilisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi pasien, serta pemeriksaan pencitraan segera untuk menentukan lokasi dan luasnya perdarahan. Setelah diagnosis dipastikan, pengobatan dapat melibatkan kombinasi intervensi medis dan bedah. Tujuan utama penanganan medis adalah untuk mengontrol tekanan intrakranial (TIK) dan mencegah perdarahan lebih lanjut. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai tindakan, termasuk penggunaan agen osmotik, seperti manitol atau garam hipertonik, untuk mengurangi edema otak dan meningkatkan tekanan perfusi otak. Selain itu, obat antiepilepsi dapat digunakan untuk mencegah kejang, yang dapat memperburuk TIK. Dalam beberapa kasus, intervensi bedah mungkin diperlukan untuk mengendalikan perdarahan dan mengurangi TIK. Hal ini dapat melibatkan penempatan saluran ventrikel eksternal (EVD) untuk mengeringkan cairan serebrospinal dan mengurangi tekanan di otak, atau evakuasi hematoma melalui prosedur kraniotomi atau endoskopi. Secara keseluruhan, penanganan IVH memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan keahlian ahli saraf, ahli bedah saraf, dan 150 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN dokter perawatan kritis. Tujuan pengobatan termasuk mengendalikan perdarahan, menurunkan TIK, mencegah komplikasi, dan mengoptimalkan hasil bagi pasien dengan kondisi ini. IVH Manajemen Bedah IVH spontan + Hidrosefalus Obstruktif PIS spontan <30 mL GCS > 3 IVH membutuhkan EVD PIS spontan < 30 mL IVH membutuhkan EVD EVD EVD + trombolitik Neuroendoskopi + EVD +/- trombolitik Menuru nkan kematia n Memper baiki luaran fungsion al Memp erbaiki luaran fungsi onal Pengu rangan Kemat ian Memp erbaiki luaran fungsi onal Meng urangi kemun gkinan pemas angan shunt Gambar 43 Manajemen bedah pada kasus IVH Indikasi Kraniotomi Pada Perdarahan Intraventrikular Kraniotomi adalah prosedur pembedahan yang sering digunakan untuk menangani perdarahan intraserebral (ICH). Berikut ini adalah indikasi numerik untuk kraniotomi pada kasus ICH: • Volume Hematoma: Jika volume hematoma lebih besar dari 30-50 mL, evakuasi bedah mungkin diperlukan, terutama jika 151 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN menyebabkan efek massa yang signifikan dan gejala neurologis. • Ketebalan Hematoma: Hematoma dengan ketebalan lebih besar dari 1 cm mungkin memerlukan evakuasi bedah karena peningkatan risiko herniasi. • Pergeseran Garis Tengah: Pergeseran garis tengah lebih besar dari 5 mm dapat mengindikasikan perlunya dilakukan kraniotomi untuk meringankan tekanan pada otak dan mencegah kerusakan neurologis lebih lanjut. Penting untuk dicatat bahwa indikasi numerik ini tidak mutlak dan dapat bervariasi, tergantung pada kondisi klinis masing-masing pasien dan faktor lainnya. Keputusan untuk melakukan kraniotomi harus diambil oleh ahli bedah saraf setelah mempertimbangkan semua data klinis dan radiologis yang relevan. Kraniotomi dapat menjadi prosedur penyelamatan nyawa bagi pasien dengan ICH, tetapi juga memiliki beberapa risiko, seperti infeksi dan perdarahan, sehingga manfaat dan risiko prosedur harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum dilakukan. 152 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Referensi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. American College of Surgeons (2018) Advanced Trauma Life Support. Chicago: American College of Surgeons. Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association (2022). American Heart Association/American Stroke Association. Feigin, V.L. et al. (2015) “Update on the global burden of ischemic and hemorrhagic stroke in 1990-2013: The GBD 2013 study,” Neuroepidemiology, 45(3), pp. 161–176. Available at: https://doi.org/10.1159/000441085. Leasure, A.C. et al. (2022) “Abstract 103: Burden of ischemic and hemorrhagic stroke across the US from 1990-2019: A global burden of disease study,” Stroke, 53(Suppl_1). Available at: https://doi.org/10.1161/str.53.suppl_1.103. Metoki, H., Ohkubo, T. and Imai, Y. (2010) “Diurnal blood pressure variation and cardiovascular prognosis in a communitybased study of OHASAMA, Japan,” Hypertension Research, 33(7), pp. 652–656. Available at: https://doi.org/10.1038/hr.2010.70. Zhukov, Y. et al. (2022) “Time trends of epidemiology of hemorrhagic stroke among urban population in Kazakhstan,” Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10(A), pp. 402–408. Available at: https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8688. Qureshi, A.I. et al. (2016) “Intensive blood-pressure lowering in patients with acute cerebral hemorrhage,” New England Journal of Medicine, 375(11), pp. 1033–1043. Available at: https://doi.org/10.1056/nejmoa1603460. Anderson, C.S. et al. (2013) “Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage,” New England 153 MANAJEMEN STROKE PERDARAHAN Journal of Medicine, 368(25), pp. 2355–2365. Available at: https://doi.org/10.1056/nejmoa1214609. 9. Hemphill, J.C. et al. (2015) “Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage,” Stroke, 46(7), pp. 2032–2060. Available at: https://doi.org/10.1161/str.0000000000000069. 10. Brouwers, H.B. et al. (2014) “Predicting hematoma expansion after primary intracerebral hemorrhage,” JAMA Neurology, 71(2), p. 158. Available at: https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2013.5433. 11. Hemphill, J.C. et al. (2001) “The ICH score,” Stroke, 32(4), pp. 891–897. Available at: https://doi.org/10.1161/01.str.32.4.891. 154 BAB VIII MANAJEMEN KOMA 8.1 PENDAHULUAN Keadaan koma adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hilangnya kesadaran dan responsif terhadap rangsangan eksternal. Individu dalam keadaan koma biasanya tidak menunjukkan gerakan sukarela atau kesadaran akan lingkungannya, dan matanya tetap tertutup. Pasien koma sering kali tidak dapat bernapas sendiri, sehingga membutuhkan ventilasi buatan untuk mempertahankan oksigenasi yang memadai. Koma dapat disebabkan oleh berbagai kondisi medis, termasuk cedera otak traumatis, stroke, dan overdosis obat. Tingkat keparahan dan durasi koma dapat sangat bervariasi, tergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan otak. Dalam beberapa kasus, pasien koma dapat pulih kesadarannya dan secara bertahap mendapatkan kembali fungsi kognitifnya, sementara dalam kasus lain, kondisinya tidak dapat dipulihkan. 8.2 KONDISI BANGUN DAN KONDISI AWAS Kondisi terjaga mengacu pada keadaan di mana seseorang sadar dan sadar akan lingkungannya. Saat terjaga, otak seseorang aktif dan mampu memproses informasi dari indera mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kondisi waspada, di sisi lain, mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak hanya terjaga tetapi juga sepenuhnya terlibat dan memperhatikan lingkungannya. Dalam kondisi waspada, otak secara aktif memproses dan menganalisis informasi sensorik yang masuk, sehingga memungkinkan seseorang untuk merespons dengan tepat terhadap perubahan atau rangsangan apa pun. Kondisi terjaga dan waspada sangat penting untuk fungsi sehari-hari dan dipengaruhi oleh 155 MANAJEMEN KOMA berbagai faktor seperti tidur, pengobatan, dan gangguan neurologis. Sebaliknya, kondisi yang mengganggu kondisi terjaga atau waspada, seperti gangguan tidur, cedera otak traumatis, atau obat-obatan tertentu, dapat berdampak signifikan pada fungsi kognitif seseorang dan kemampuannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 8.3 NEUROBIOLOGI KESADARAN Neurobiologi kesadaran adalah bidang penelitian yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memahami mekanisme saraf yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pengalaman sadar. Meskipun dasar saraf yang tepat dari kesadaran masih belum sepenuhnya dipahami, penelitian telah mengidentifikasi beberapa wilayah dan jaringan otak yang diduga terlibat. Thalamus, sebuah struktur yang berada jauh di dalam otak, diyakini bertindak sebagai pintu gerbang bagi informasi sensorik untuk mencapai korteks, di mana informasi tersebut diintegrasikan dan diproses menjadi pengalaman sadar. Korteks prefrontal, sebuah wilayah di bagian depan otak, dianggap memainkan peran penting dalam proses kognitif tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan, memori kerja, dan kesadaran diri. Wilayah otak lainnya seperti jaringan mode default, yang aktif ketika otak dalam keadaan istirahat, juga telah terlibat dalam kesadaran. Selain wilayah otak, neurobiologi kesadaran juga melibatkan pemahaman tentang interaksi antara berbagai jaringan otak dan neurotransmiter yang memodulasi kesadaran. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, neurobiologi kesadaran tetap menjadi bidang penelitian yang aktif dan merupakan tantangan ilmiah yang sulit dipahami. 156 MANAJEMEN KOMA 8.4 ARAS Ascending Reticular Activating System (ARAS) adalah jaringan saraf yang membentang dari batang otak melalui talamus ke korteks, dan memainkan peran penting dalam mengatur kesadaran dan kewaspadaan. ARAS terdiri dari berbagai inti dan jalur, yang secara kolektif mengintegrasikan informasi sensorik dan memodulasi aktivitas korteks serebral. ARAS menerima masukan dari berbagai sistem sensorik dan terlibat dalam menyaring dan memprioritaskan informasi sensorik yang masuk untuk mempertahankan gairah dan perhatian. Selain itu, ARAS bertanggung jawab untuk mengaktifkan korteks selama terjaga dan menghambatnya selama tidur, menjadikannya komponen penting dari siklus tidur-bangun. Gangguan pada ARAS dapat menyebabkan berbagai gangguan, termasuk gangguan tidur, koma, dan gangguan kesadaran. Sebagai contoh, kerusakan pada ARAS akibat cedera otak traumatis atau stroke dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau koma. Sebaliknya, gangguan neurologis tertentu seperti narkolepsi atau insomnia dianggap melibatkan disregulasi ARAS, yang menyebabkan gangguan pada siklus tidur-bangun dan gairah. Dengan demikian, ARAS tetap menjadi area penelitian yang penting dalam memahami mekanisme saraf yang mendasari kesadaran dan gairah. Gambar 44 Bagian otak dan beberapa hormon yang dikeluarkan 157 MANAJEMEN KOMA 8.5 ETIOLOGI Meskipun penyebab koma bisa beragam dan kompleks, satu mnemonik yang dapat membantu mengingat beberapa etiologi adalah "VITAMINS". VITAMINS adalah singkatan dari Vaskular, Infeksi, Trauma, Autoimun, Metabolik, Intoksikasi, Neoplasma, dan Kejang. Penyebab koma akibat pembuluh darah dapat berupa stroke, aneurisma, atau pendarahan di otak yang mengakibatkan penurunan aliran darah atau pengiriman oksigen ke otak. Infeksi seperti meningitis atau ensefalitis juga dapat menyebabkan koma dengan cara mempengaruhi otak secara langsung dan menyebabkan peradangan. Trauma pada kepala atau otak, seperti akibat kecelakaan mobil atau terjatuh, dapat mengakibatkan cedera langsung pada otak dan menyebabkan koma. Gangguan autoimun seperti lupus atau multiple sclerosis dapat menyebabkan koma dengan memengaruhi otak dan menyebabkan peradangan. Penyebab metabolik seperti hipoglikemia atau ketidakseimbangan elektrolit dapat memengaruhi kemampuan otak untuk berfungsi dengan baik dan menyebabkan koma. Intoksikasi obat-obatan atau alkohol juga dapat menyebabkan koma dengan menekan sistem saraf pusat. Neoplasma, seperti tumor otak, dapat menyebabkan kompresi atau kerusakan pada jaringan otak, yang menyebabkan koma. Terakhir, kejang, terutama kejang yang berkepanjangan atau status epileptikus, dapat menyebabkan koma. Memahami potensi penyebab koma sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengobati kondisi yang mendasari serta memberikan perawatan yang tepat bagi pasien. 8.6 PEMERIKSAAN KESADARAN Glasgow Coma Score (GCS) adalah alat penilaian neurologis yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pada pasien dengan cedera otak akut atau kondisi neurologis lainnya. GCS didasarkan pada 158 MANAJEMEN KOMA tiga komponen: pembukaan mata, respons verbal, dan respons motorik. Setiap komponen dinilai dengan skala mulai dari 1 hingga 5, 1 hingga 4, atau 1 hingga 6 tergantung pada respons spesifik, dengan total skor yang mungkin mulai dari 3 hingga 15. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi, sedangkan skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesadaran yang menurun. GCS digunakan secara luas dalam keadaan darurat dan perawatan kritis untuk membantu dokter menilai dan memantau status neurologis pasien dengan cedera otak traumatis atau kondisi neurologis lainnya. GCS juga digunakan untuk melacak perubahan kesadaran dari waktu ke waktu dan untuk membantu memandu keputusan terkait manajemen pasien, seperti kebutuhan untuk intubasi atau pemindahan ke tingkat perawatan yang lebih tinggi. Meskipun digunakan secara luas, GCS memiliki beberapa keterbatasan, termasuk variabilitas dalam keandalan interrater dan potensi untuk meyakinkan palsu pada pasien dengan respons motorik atau verbal yang tidak normal. Oleh karena itu, GCS harus digunakan bersama dengan penilaian klinis lainnya dan tidak boleh diandalkan sebagai satu-satunya indikator status neurologis. 159 MANAJEMEN KOMA Gambar 45 Glasgow Coma Score 160 MANAJEMEN KOMA Gambar 46 Beberapa lokasi rangsang nyeri pada pemeriksaan GCS 8.7 GANGGUAN POLA NAPAS Gambar 47 Beberapa lokasi gangguan otak dan gangguan pernapasan yang terjadi 161 MANAJEMEN KOMA Cheyne-Stokes Pernapasan Cheyne-Stokes adalah pola pernapasan yang ditandai dengan siklus hiperventilasi dan apnea yang bergantian, atau periode tanpa pernapasan. Pola pernapasan ini paling sering dikaitkan dengan gagal jantung, tetapi juga dapat terjadi pada kondisi lain seperti stroke, cedera otak traumatik, dan apnea tidur. Fase hiperventilasi ditandai dengan pernapasan yang cepat dan dalam, diikuti dengan penurunan pernapasan secara bertahap hingga akhirnya berhenti sama sekali selama fase apnea. Siklus ini kemudian berulang, biasanya dalam jangka waktu beberapa detik hingga beberapa menit. Mekanisme yang mendasari pernapasan Cheyne-Stokes diduga terkait dengan fluktuasi kadar karbon dioksida darah dan berkurangnya sensitivitas pusat kontrol pernapasan di batang otak. Pada gagal jantung, penurunan curah jantung menyebabkan penurunan pengiriman oksigen ke otak, yang dapat mengakibatkan penurunan dorongan pernapasan dan hiperventilasi. Ketika kadar karbon dioksida menurun, dorongan pernapasan semakin ditekan, yang menyebabkan apnea. Akhirnya, kadar karbon dioksida meningkat ke titik di mana dorongan pernapasan dirangsang lagi, yang mengarah ke fase hiperventilasi. Pernapasan Cheyne-Stokes dapat menjadi tanda memburuknya gagal jantung atau kondisi lain yang mendasarinya, dan mungkin memerlukan pengobatan dengan obat-obatan atau intervensi seperti tekanan saluran napas positif. Hal ini juga dapat memengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan di siang hari, sehingga penting bagi pasien untuk mendiskusikan setiap perubahan pola pernapasan dengan penyedia layanan kesehatan mereka. 162 MANAJEMEN KOMA Gambar 48 Pola pernapasan Cheyne-Stokes Hiperventilasi Neurogenik Sentral Hiperventilasi neurogenik sentral (CNH) adalah suatu kondisi neurologis langka yang ditandai dengan pernapasan cepat dan dalam yang tidak normal yang digerakkan oleh batang otak, khususnya pusat pernapasan. Kondisi ini sering terlihat pada pasien dengan cedera atau penyakit batang otak, seperti tumor atau stroke. Pernapasan cepat yang terkait dengan CNH dapat menyebabkan penurunan kadar karbon dioksida dalam darah, yang dapat menyebabkan vasokonstriksi dan menurunkan pengiriman oksigen ke otak dan organ lainnya. Mekanisme yang mendasari CNH diduga terkait dengan ketidakseimbangan dalam dorongan pernapasan, yang menyebabkan aktivasi pusat pernapasan yang berlebihan di batang otak. Diagnosis CNH biasanya didasarkan pada gejala klinis dan tes laboratorium, seperti analisis gas darah arteri. Pengobatan dapat melibatkan penanganan cedera atau penyakit batang otak yang mendasari, serta tindakan untuk menormalkan pola pernapasan dan kadar karbon dioksida, seperti ventilasi mekanis atau obat-obatan yang dapat membantu mengatur pernapasan. Prognosis untuk pasien dengan CNH bergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan pada batang otak, dan dapat berkisar dari pemulihan penuh hingga komplikasi pernapasan dan neurologis jangka panjang. 163 MANAJEMEN KOMA Gambar 49 Pola pernapasan CNH Apneustik Pernapasan apnea adalah jenis pola pernapasan abnormal yang ditandai dengan tarikan napas inspirasi yang berkepanjangan, diikuti dengan upaya ekspirasi yang singkat. Pola pernapasan ini biasanya terlihat pada pasien dengan cedera batang otak atau penyakit, seperti stroke atau tumor. Mekanisme yang mendasari pernapasan apneustik diduga terkait dengan disfungsi pada pusat pernapasan di batang otak, yang dapat menyebabkan gangguan pada ritme pernapasan normal. Pernapasan apneustik dapat menyebabkan penurunan pengiriman oksigen ke otak dan organ lainnya, dan dapat mengakibatkan gejala seperti kebingungan, kelelahan, dan gangguan pernapasan. Diagnosis pernapasan apneustik biasanya melibatkan kombinasi gejala klinis dan tes laboratorium, seperti analisis gas darah arteri dan studi pencitraan untuk mengevaluasi cedera atau penyakit batang otak. Perawatan pernapasan apneustik biasanya difokuskan untuk mengatasi cedera atau penyakit batang otak yang mendasarinya, serta tindakan untuk meningkatkan oksigenasi dan mendukung fungsi pernapasan. Hal ini dapat mencakup ventilasi mekanis, terapi oksigen tambahan, dan obat-obatan untuk membantu mengatur pernapasan. Prognosis untuk pasien dengan pernapasan apneustik tergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan pada batang otak, dan dapat berkisar dari pemulihan penuh hingga komplikasi pernapasan dan neurologis jangka panjang. 164 MANAJEMEN KOMA Gambar 50 Pola pernapasan Apneustik Kluster Cluster breathing adalah jenis pola pernapasan abnormal yang ditandai dengan serangkaian napas yang cepat dan dangkal, diikuti dengan periode singkat apnea atau jeda dalam bernapas. Pola pernapasan ini biasanya terlihat pada pasien dengan kondisi neurologis, seperti cedera atau penyakit batang otak, dan dapat dikaitkan dengan gejala lain seperti kelemahan atau mati rasa pada otot wajah, kesulitan menelan, atau perubahan suara. Mekanisme yang mendasari di balik pernapasan klaster diduga terkait dengan gangguan pada ritme pernapasan normal, yang mengakibatkan semburan napas cepat yang terputus-putus, yang diikuti oleh periode apnea. Diagnosis pernapasan klaster biasanya melibatkan kombinasi gejala klinis dan tes laboratorium, seperti analisis gas darah arteri dan studi pencitraan untuk mengevaluasi kondisi neurologis yang mendasarinya. Penanganan pernapasan klaster biasanya difokuskan untuk mengatasi kondisi neurologis yang mendasarinya, serta tindakan untuk mendukung fungsi pernapasan dan oksigenasi. Ini dapat mencakup ventilasi mekanis, terapi oksigen tambahan, dan obatobatan untuk membantu mengatur pernapasan. Prognosis untuk pasien dengan pernapasan klaster tergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan pada batang otak, dan dapat berkisar dari pemulihan penuh hingga komplikasi pernapasan dan neurologis jangka panjang. 165 MANAJEMEN KOMA Gambar 51 Pola pernapasan Kluster Ataksik Pernapasan ataksik, juga dikenal sebagai pernapasan biot atau pernapasan klaster, adalah pola pernapasan abnormal yang ditandai dengan pernapasan yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi dengan kedalaman dan kecepatan yang bervariasi. Jenis pola pernapasan ini biasanya terlihat pada pasien dengan kondisi neurologis, seperti cedera batang otak atau penyakit, dan dapat dikaitkan dengan gejala lain seperti kesadaran yang berubah, kebingungan, atau kejang. Mekanisme yang mendasari pernapasan ataksia diduga terkait dengan kerusakan pada pusat pernapasan di batang otak, yang dapat menyebabkan gangguan pada ritme pernapasan normal. Diagnosis pernapasan ataksia biasanya melibatkan kombinasi gejala klinis dan tes laboratorium, seperti analisis gas darah arteri dan studi pencitraan untuk mengevaluasi kondisi neurologis yang mendasarinya. Penanganan pernapasan ataksia biasanya difokuskan untuk mengatasi kondisi neurologis yang mendasarinya, serta tindakan untuk mendukung fungsi pernapasan dan oksigenasi. Ini dapat mencakup ventilasi mekanis, terapi oksigen tambahan, dan obatobatan untuk membantu mengatur pernapasan. Prognosis untuk pasien dengan pernapasan ataksia bergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan pada batang otak, dan dapat berkisar dari pemulihan penuh hingga komplikasi pernapasan dan neurologis jangka panjang. 166 MANAJEMEN KOMA Gambar 52 Pola pernapasan Ataksik 8.8 KONDISI MIRIP KOMA Kondisi Vegetatif Keadaan vegetatif, juga dikenal sebagai sindrom terjaga yang tidak responsif, adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya kesadaran dan kesadaran akan lingkungan, meskipun ada periode terjaga. Pasien dalam keadaan vegetatif mungkin tampak terjaga, dengan periode membuka mata dan responsif terhadap rangsangan eksternal, tetapi tidak memiliki interaksi atau komunikasi yang berarti dengan lingkungannya. Penyebab yang mendasari keadaan vegetatif dapat bervariasi, tetapi sering kali berkaitan dengan cedera atau kerusakan otak yang parah, seperti akibat cedera otak traumatik atau henti jantung. Diagnosis keadaan vegetatif biasanya melibatkan pemeriksaan neurologis menyeluruh dan studi pencitraan, seperti MRI atau CT scan. Saat ini tidak ada pengobatan khusus untuk keadaan vegetatif, dan penanganannya difokuskan pada perawatan suportif dan penanganan kondisi medis terkait. Beberapa pasien dapat mengalami pemulihan spontan, tetapi prognosis pemulihan jangka panjang umumnya buruk, dengan banyak pasien yang tetap berada dalam kondisi vegetatif selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kondisi Kesadaran Minimal Keadaan sadar minimal (MCS) adalah suatu kondisi kesadaran yang sangat berubah yang berbeda dengan keadaan vegetatif, tetapi 167 MANAJEMEN KOMA masih ditandai dengan gangguan gairah dan kesadaran yang parah. Pasien dalam kondisi sadar minimal mungkin menunjukkan beberapa tingkat kesadaran atau responsif terhadap rangsangan eksternal, tetapi tidak memiliki interaksi atau komunikasi yang konsisten dan terarah dengan lingkungannya. Penyebab utama MCS dapat bervariasi, tetapi sering kali berkaitan dengan cedera atau kerusakan otak yang parah, seperti akibat cedera otak traumatis, stroke, atau anoksia. Diagnosis MCS biasanya melibatkan pemeriksaan neurologis menyeluruh dan studi pencitraan, seperti MRI atau CT scan. Perawatan MCS difokuskan pada perawatan suportif dan pengelolaan kondisi medis terkait, serta terapi yang bertujuan untuk mendorong pemulihan kognitif dan fungsional. Beberapa pasien mungkin mengalami pemulihan spontan, tetapi prognosis pemulihan jangka panjang umumnya buruk, dengan banyak pasien yang tetap berada dalam kondisi sadar minimal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Penanganan MCS dapat menjadi tantangan, karena pasien mungkin memerlukan intervensi medis dan rehabilitasi yang kompleks, serta dukungan dan perawatan yang berkelanjutan dari penyedia layanan kesehatan dan pengasuh. Abulia Abulia, juga dikenal sebagai apatis, adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya motivasi, dorongan, atau inisiatif. Pasien dengan abulia mungkin mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, memulai tindakan, atau menunjukkan minat atau antusiasme terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan atau penting bagi mereka. Kondisi ini sering dikaitkan dengan kondisi neurologis, seperti stroke, cedera otak traumatis, atau gangguan degeneratif yang mempengaruhi lobus frontal otak. 168 MANAJEMEN KOMA Mekanisme yang mendasari abulia belum dipahami dengan baik, tetapi diduga terkait dengan disfungsi sirkuit saraf yang terlibat dalam motivasi, pemrosesan hadiah, dan pengambilan keputusan. Diagnosis abulia biasanya melibatkan pemeriksaan neurologis menyeluruh, serta studi pencitraan, seperti MRI atau CT scan. Pengobatan abulia difokuskan pada manajemen kondisi neurologis yang mendasari, serta intervensi psikoterapi dan farmakologis yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam aktivitas. Beberapa pasien mungkin mendapat manfaat dari terapi kognitif dan perilaku, seperti penetapan tujuan, restrukturisasi kognitif, atau pelatihan keterampilan sosial, sementara pasien lainnya mungkin memerlukan obat untuk mengelola gejala depresi, kecemasan, atau gangguan suasana hati yang mendasarinya. Prognosis untuk pasien dengan abulia bergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan neurologis, serta respons individu terhadap pengobatan dan manajemen yang sedang berlangsung. Dengan intervensi dan dukungan yang tepat, banyak pasien dengan abulia dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam hal motivasi, fungsi, dan kualitas hidup. Keadaan Bingung Akut Keadaan bingung akut, yang juga dikenal sebagai delirium, adalah suatu kondisi yang ditandai dengan timbulnya disfungsi kognitif yang cepat, termasuk kebingungan, disorientasi, kesadaran yang berubah, dan perubahan persepsi, pemikiran, dan perilaku. Keadaan bingung akut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi medis yang mendasari, obat-obatan, infeksi, dan faktor lingkungan. Mekanisme yang mendasari keadaan bingung akut tidak dipahami dengan baik, tetapi diduga terkait dengan gangguan fungsi otak normal, termasuk perubahan aktivitas neurotransmitter, 169 MANAJEMEN KOMA peradangan, dan gangguan metabolisme. Diagnosis keadaan bingung akut biasanya melibatkan riwayat medis dan pemeriksaan menyeluruh, serta tes laboratorium dan studi pencitraan, jika diperlukan. Penanganan keadaan bingung akut difokuskan pada identifikasi dan penanganan penyebab yang mendasari, serta memberikan perawatan suportif dan penanganan gejala. Beberapa pasien mungkin memerlukan obat untuk mengatasi gejala agitasi, kecemasan, atau delusi, sementara pasien lainnya mungkin mendapat manfaat dari intervensi seperti modifikasi lingkungan atau terapi stimulasi kognitif. Prognosis untuk pasien dengan keadaan kebingungan akut tergantung pada penyebab yang mendasari, tingkat keparahan gejala, dan respons terhadap pengobatan. Dengan intervensi dan manajemen yang tepat, banyak pasien dengan kondisi bingung akut dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam fungsi kognitif dan kesehatan secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa kasus, keadaan bingung akut dapat dikaitkan dengan hasil yang buruk, termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas. Mati Otak Mati otak adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hilangnya seluruh fungsi otak, termasuk batang otak, yang tidak dapat dipulihkan lagi, yang mengakibatkan terhentinya fungsi-fungsi vital, seperti pernapasan dan kesadaran. Mati otak biasanya disebabkan oleh cedera otak yang parah dan tidak dapat dipulihkan, seperti akibat trauma, stroke, atau anoksia. Diagnosis mati otak memerlukan pemeriksaan neurologis yang menyeluruh, termasuk tes untuk menilai refleks batang otak, serta studi pencitraan untuk memastikan tidak adanya aliran darah atau aktivitas listrik di otak. Setelah mati otak dikonfirmasi, pasien dianggap mati secara hukum dan klinis, dan tidak lagi dapat mempertahankan hidup tanpa 170 MANAJEMEN KOMA bantuan buatan, seperti ventilasi mekanis atau bantuan peredaran darah. Penanganan mati otak difokuskan pada perawatan suportif dan manajemen kondisi medis terkait, serta memberikan dukungan emosional dan perawatan bagi keluarga pasien. Diagnosis mati otak adalah proses yang kompleks yang memerlukan evaluasi yang cermat oleh tim penyedia layanan kesehatan yang berpengalaman, termasuk ahli saraf, ahli intensif, dan spesialis lainnya. Penentuan mati otak juga tunduk pada pertimbangan hukum dan etika, dan dapat bervariasi menurut yurisdiksi dan konteks budaya. Meskipun diagnosis mati otak sering kali sulit dan menantang secara emosional, diagnosis ini merupakan komponen penting dalam perawatan akhir hayat dan pengambilan keputusan. Sindrom Locked-In Sindrom terkunci adalah kondisi neurologis langka yang ditandai dengan hilangnya fungsi motorik secara total, kecuali kemampuan menggerakkan mata secara vertikal dan berkedip. Sindrom terkunci biasanya disebabkan oleh kerusakan pada batang otak, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan banyak fungsi tubuh yang tidak disengaja, seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah, serta gerakan sukarela. Meskipun memiliki keterbatasan fisik yang parah, banyak pasien dengan sindrom terkunci masih memiliki fungsi kognitif penuh, dan mampu berkomunikasi menggunakan gerakan mata atau bentuk komunikasi berbantuan lainnya. Perawatan sindrom terkunci difokuskan pada perawatan suportif, termasuk pengelolaan kondisi medis yang mendasari, serta menyediakan alat bantu dan dukungan untuk komunikasi dan aktivitas kehidupan sehari-hari. 171 MANAJEMEN KOMA Diagnosis sindrom terkunci dapat menjadi tantangan, karena memerlukan pemeriksaan neurologis yang cermat dan studi pencitraan untuk menyingkirkan kondisi lain yang dapat meniru gejalanya. Prognosis jangka panjang untuk pasien dengan sindrom terkunci bergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat kerusakan neurologis, serta respons individu terhadap pengobatan dan manajemen yang sedang berlangsung. Sindrom terkunci adalah kondisi yang menantang yang membutuhkan perawatan dan dukungan berkelanjutan, serta advokasi untuk pasien dan keluarganya. Terlepas dari keterbatasan fisik, banyak pasien dengan sindrom terkunci dapat mempertahankan kualitas hidup yang tinggi, dengan intervensi dan dukungan yang tepat. 172 MANAJEMEN KOMA Referensi 1. Bates, D. (2001) The prognosis of Medical Coma, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. Available at: https://jnnp.bmj.com/content/71/suppl_1/i20 (Accessed: 19 May 2023). 2. Chandrikasing, R. et al. (2021) ‘Case report: “an unexpected origin of coma in a young adult”’, International Journal of Emergency Medicine, 14(1). doi:10.1186/s12245-021-003905. 3. P;, H.J. (no date) Coma, National Center for Biotechnology Information. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28613473/ (Accessed: 19 May 2023). 4. Zakaria, Z. et al. (2020) ‘The neurological exam of a comatose patient: An essential practical guide’, Malaysian Journal of Medical Sciences, 27(5), pp. 108–123. doi:10.21315/mjms2020.27.5.11. 173 BAB IX SKILL STATION I RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY 9.1 ANATOMI IMAGING Anatomi pencitraan melibatkan studi anatomi manusia melalui penggunaan berbagai modalitas pencitraan. Ketika memeriksa tubuh manusia, tiga bidang dasar yang biasa digunakan: bidang aksial, sagital, dan koronal. Bidang aksial, juga dikenal sebagai bidang transversal, tegak lurus terhadap sumbu panjang tubuh dan membaginya menjadi bagian superior dan inferior. Dalam pencitraan aksial, seperti computed tomography (CT) atau magnetic resonance imaging (MRI), struktur seperti organ, pembuluh darah, dan tulang divisualisasikan dalam penampang melintang, sehingga memberikan pandangan rinci tentang hubungan spasial dan fitur anatomis. Di sisi lain, bidang sagital, sejajar dengan garis tengah tubuh dan membaginya menjadi bagian kiri dan kanan. Pencitraan pada bidang sagital, seperti MRI sagital atau ultrasound, memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap struktur seperti otak, sumsum tulang belakang, dan ekstremitas. Bidang ini memberikan informasi penting tentang organisasi longitudinal struktur anatomi, membantu dalam penilaian asimetri atau patologi di sepanjang garis tengah tubuh. Terakhir, bidang koronal, juga disebut bidang frontal, membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. Teknik pencitraan koronal seperti CT scan koronal atau rontgen gigi panoramik memberikan pandangan yang tegak lurus terhadap bidang aksial dan sagital. Perspektif ini sangat berharga untuk mengevaluasi struktur 174 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY seperti dada, perut, panggul, dan tulang wajah. Dengan memvisualisasikan struktur anatomi pada bidang koronal, para profesional medis dapat secara akurat menilai hubungan antara Gambar 53 Tiga potongan axial, sagital, dan coronal organ, tulang, dan jaringan lunak dari perspektif depan-ke-belakang. Gambar 54 Potongan axial level basal ganglia 175 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 55 Potongan Axial level supra basal ganglia Lingkaran Willis, juga dikenal sebagai circulus arteriosus cerebri, adalah struktur anatomi penting yang terletak di dasar otak. Struktur ini merupakan jaringan arteri melingkar yang menyediakan sirkulasi kolateral ke otak, memastikan suplai darah yang konstan ke organ vital ini. Lingkaran Willis dibentuk oleh perpaduan beberapa arteri utama, termasuk arteri karotis interna dan arteri basilaris. Susunan yang unik ini memungkinkan distribusi darah beroksigen ke belahan otak, batang otak, dan struktur penting lainnya. Lingkaran Willis bertindak sebagai mekanisme perlindungan jika terjadi penyumbatan atau penyumbatan pembuluh darah. Dengan menghubungkan arteri utama, ia menciptakan jalur alternatif untuk aliran darah, sehingga memungkinkan adanya kompensasi ketika salah satu pembuluh darah terganggu. Sirkulasi kolateral ini dapat membantu mengurangi efek stroke atau kondisi vaskular lainnya dengan mempertahankan suplai darah ke daerah otak yang penting. 176 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Anatomi Lingkaran Willis menunjukkan variasi alami dalam strukturnya di antara individu. Meskipun sering digambarkan sebagai lingkaran yang lengkap, variasi dalam ukuran dan konektivitas arteriarteri adalah hal yang umum. Variasi ini dapat memengaruhi Gambar 56 Cirulus Willisi efektivitas sirkulasi kolateral dan mungkin berimplikasi pada kondisi neurologis tertentu. 9.2 FOTO POLOS Rontgen kepala polos, juga dikenal sebagai rontgen tengkorak, adalah teknik pencitraan radiografi yang digunakan untuk mengevaluasi struktur tulang dan anatomi umum tengkorak. Pemeriksaan ini melibatkan pengambilan gambar kepala dengan menggunakan sinar-X, yang merupakan bentuk radiasi elektromagnetik. Modalitas pencitraan ini sering digunakan sebagai alat skrining awal untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi kepala, termasuk patah tulang, tumor, dan kelainan pada tulang tengkorak. 177 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Selama pemeriksaan sinar-X polos kepala, pasien diposisikan di depan mesin sinar-X, dan sinar-X diarahkan ke daerah kepala. Detektor khusus menangkap foton sinar-X yang melewati tengkorak, menghasilkan gambar hitam-putih yang menyoroti struktur tulang tengkorak, termasuk kubah tengkorak, dasar tengkorak, dan tulang wajah. Teknik pencitraan ini memberikan informasi yang berharga mengenai integritas, keselarasan, dan kepadatan tulang tengkorak. Teknik ini dapat membantu mengidentifikasi patah tulang, seperti patah tulang tengkorak atau patah tulang wajah, sehingga membantu dalam diagnosis dan penanganan cedera yang berhubungan dengan trauma. Selain itu, rontgen polos kepala dapat membantu mendeteksi kalsifikasi abnormal, penyakit sinus, benda asing, dan tumor tulang tertentu. Penting untuk diperhatikan bahwa meskipun rontgen polos kepala memberikan informasi yang berharga mengenai struktur tulang, namun memiliki keterbatasan dalam memvisualisasikan jaringan lunak dan struktur internal otak yang mendetail. Untuk evaluasi yang lebih komprehensif, teknik pencitraan tambahan seperti computed tomography (CT) atau magnetic resonance imaging (MRI) mungkin diperlukan. Gambar 57 Foto polos posisi AP dan Lateral 178 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY 9.3 CT-SCAN CT-scan kepala, juga dikenal sebagai pemindaian tomografi terkomputerisasi pada kepala, adalah teknik pencitraan diagnostik yang memberikan gambar penampang melintang yang mendetail pada otak dan struktur di sekitarnya. CT-scan menggunakan sinar-X dan pemrosesan komputer untuk membuat serangkaian gambar yang terperinci, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan profesional untuk menilai anatomi otak, mendeteksi kelainan, dan membantu diagnosis berbagai kondisi neurologis. Selama CT-scan kepala, pasien berbaring di atas meja yang bergerak melalui lubang melingkar pada pemindai CT. Sinar X-ray diarahkan melalui kepala dari berbagai sudut, dan detektor mengukur sinar X-ray yang melewati jaringan. Informasi ini kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar penampang melintang, atau irisan, otak yang terperinci. Gambar-gambar ini memberikan informasi yang berharga tentang struktur otak, pembuluh darah, dan potensi kelainan. CT-scan kepala biasanya digunakan dalam situasi darurat, seperti dugaan trauma kepala atau gejala neurologis akut, karena kecepatan dan kemampuannya untuk memberikan informasi diagnostik yang berharga dengan cepat. Pemeriksaan ini sangat membantu dalam mendiagnosis kondisi seperti perdarahan, stroke, tumor otak, infeksi, dan patah tulang tengkorak. Selain itu, CT-scan dapat memberikan panduan untuk perencanaan pembedahan dan memantau perkembangan atau respons terhadap pengobatan kondisi tertentu. Meskipun CT-scan kepala merupakan alat diagnostik yang berharga, namun penting untuk mempertimbangkan paparan radiasi yang terkait. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dosis radiasi, terutama pada populasi yang sensitif seperti anak-anak dan wanita hamil. Dalam beberapa kasus, modalitas pencitraan alternatif 179 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) dapat digunakan, tergantung pada indikasi klinis dan pertimbangan pasien tertentu. Gambar 58 Beberapa lokasi perdarahan intrakranial Gambar 59 Contoh kasus soft tissue swelling dan fraktur impresi pada CT-Scan 180 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 60 Contoh kasus subgaleal hematoma dan EDH pada CT-Scan disertai fraktur os occipital kiri Gambar 61 Contoh kasus SDH menggunakan CT-Scan 9.4 MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING) MRI Kepala, juga dikenal sebagai pencitraan resonansi magnetik kepala, adalah teknik pencitraan khusus yang digunakan untuk memeriksa struktur di dalam otak dan area sekitarnya. MRI menggunakan medan magnet yang kuat dan gelombang radio untuk membuat gambar anatomi otak yang terperinci, sehingga memberikan informasi diagnostik yang berharga. Selama MRI kepala, pasien berbaring di atas meja yang secara bertahap dipindahkan ke dalam pemindai MRI, yang merupakan mesin silinder besar. Pemindai 181 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY menghasilkan medan magnet yang menyelaraskan atom hidrogen di dalam jaringan tubuh. Gelombang radio kemudian dipancarkan, menyebabkan atom-atom tersebut memancarkan sinyal yang terdeteksi oleh pemindai. Sinyal-sinyal ini diproses oleh komputer untuk membuat gambar penampang otak yang sangat rinci, termasuk belahan otak, batang otak, dan otak kecil. MRI Kepala dapat mengungkapkan berbagai kondisi seperti tumor otak, kelainan pembuluh darah, stroke, sklerosis multipel, dan infeksi. Ini adalah modalitas pencitraan non-invasif yang memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik dan sangat berharga untuk mengevaluasi struktur internal otak tanpa menggunakan radiasi pengion. MRI Kepala memainkan peran penting dalam neuroimaging dan sering kali menjadi alat yang penting dalam mendiagnosis dan memantau gangguan neurologis. Gambar 62 Contoh gambar T1 dan T2 182 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 63 Contoh gambar T2 FLAIR (Fluid Attenuation Inversion Recovery) 9.5 TRAUMA SPINAL Modalitas pencitraan memainkan peran penting dalam evaluasi trauma tulang belakang, yang memberikan informasi berharga tentang integritas tulang belakang dan struktur terkait. Beberapa teknik pencitraan umumnya digunakan untuk menilai cedera tulang belakang, termasuk sinar-X, computed tomography (CT), dan magnetic resonance imaging (MRI). Sinar-X sering kali merupakan modalitas pencitraan awal yang digunakan untuk mengevaluasi trauma tulang belakang. Sinar-X dapat dengan cepat menilai patah tulang, dislokasi, dan kelainan penyelarasan tulang belakang. Sinar-X memberikan informasi yang berharga tentang struktur tulang, seperti badan vertebra, pedikel, dan proses spinosus. Namun, pemeriksaan ini memiliki keterbatasan dalam menilai jaringan lunak dan mungkin tidak selalu dapat mendeteksi cedera yang tidak kentara atau kerusakan sumsum tulang belakang. CT scan sangat berguna dalam memberikan pencitraan yang rinci dari struktur tulang dan dapat memvisualisasikan fraktur yang kompleks, dislokasi tulang belakang, dan kompromi saluran tulang belakang dengan lebih baik. CT dapat memberikan rekonstruksi tiga 183 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY dimensi dan gambar multiplanar yang membantu dalam perencanaan pembedahan dan menilai tingkat keparahan cedera. Hal ini sangat bermanfaat dalam mengevaluasi tulang belakang leher dan torakolumbal untuk trauma. MRI adalah modalitas pencitraan yang penting untuk menilai jaringan lunak, termasuk sumsum tulang belakang, akar saraf, dan diskus intervertebralis. MRI dapat mendeteksi cedera ligamen, kompresi sumsum tulang belakang, dan kelainan jaringan lunak lainnya. MRI memberikan resolusi kontras yang sangat baik dan sangat berharga dalam mengevaluasi cedera sumsum tulang belakang, herniasi diskus, dan edema sumsum tulang belakang. Selain itu, MRI juga dapat membantu mengidentifikasi cedera yang terkait, seperti memar sumsum tulang belakang atau hematoma epidural. Gambar 64 Foto polos tulang cervical posisi lateral pasien post KLL, corpus C5, C7 tidak tampak pada foto ini, harus dicurigai adanya fraktur 184 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 65 Contoh kasus fraktur dan dislokasi pada tulang cervical pada CT Scan Gambar 66 Contoh kasus fraktur cervical pada MRI, didapatkan ruptur lig. Longitudinalis posterior, lig. Flavum, lig. Interspinosum, kompresi medulla spinalis disertai edema 185 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY 9.6 STROKE PERDARAHAN Modalitas pencitraan sangat penting dalam diagnosis dan penanganan stroke hemoragik, jenis stroke yang disebabkan oleh perdarahan di dalam otak. Dua teknik pencitraan utama yang digunakan untuk mengevaluasi stroke hemoragik adalah computed tomography (CT) dan magnetic resonance imaging (MRI). CT scan biasanya merupakan modalitas pencitraan awal pilihan pada kasus dugaan stroke hemoragik karena kecepatan dan ketersediaannya dalam keadaan darurat. CT scan non-kontras dapat dengan cepat mengidentifikasi keberadaan darah di otak dan memberikan informasi berharga mengenai lokasi, ukuran, dan luasnya perdarahan. CT scan sangat efektif dalam mendeteksi perdarahan akut, seperti perdarahan intraserebral (perdarahan di dalam jaringan otak) dan perdarahan subaraknoid (perdarahan di dalam ruang yang mengelilingi otak). Informasi ini sangat penting untuk diagnosis cepat dan menentukan strategi pengobatan yang tepat. MRI juga digunakan dalam evaluasi stroke hemoragik, yang memberikan informasi lebih rinci tentang patologi yang mendasari dan potensi komplikasi. Pemindaian MRI dapat memberikan visualisasi yang lebih baik untuk perdarahan yang lebih kecil, serta jaringan otak dan pembuluh darah di sekitarnya. Urutan pencitraan berbobot difusi (DWI) sangat berguna dalam mendeteksi perubahan iskemik akut di otak, yang dapat terjadi bersamaan dengan atau disalahartikan sebagai stroke hemoragik. Selain itu, MRI dapat membantu mengidentifikasi penyebab yang mendasari perdarahan, seperti malformasi arteriovenosa (AVM) atau aneurisma. Baik CT dan MRI memainkan peran yang saling melengkapi dalam evaluasi stroke hemoragik. CT scan lebih disukai dalam situasi darurat karena akuisisi yang cepat dan kemampuannya untuk mengidentifikasi perdarahan akut secara efektif. Pemindaian MRI menawarkan informasi yang lebih rinci tentang tingkat perdarahan, 186 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY jaringan otak di sekitarnya, dan potensi penyebab yang mendasarinya. Pilihan modalitas pencitraan tergantung pada presentasi klinis, waktu sejak timbulnya gejala, dan kebutuhan spesifik setiap pasien. Gambar 67 Beberapa lokasi perdarahan intrakranial Gambar 68 Contoh kasus ICH dan IVH 187 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 69 Contoh CTA dengan intranidal aneurysma pada bagian AVM Gambar 70 Contoh Kasus SAH 9.7 STROKE ISKEMIK Modalitas pencitraan memainkan peran penting dalam diagnosis dan penatalaksanaan stroke iskemik, suatu kondisi yang ditandai dengan penyumbatan atau berkurangnya aliran darah ke otak. Dua teknik pencitraan utama yang digunakan untuk mengevaluasi stroke iskemik adalah computed tomography (CT) dan magnetic resonance imaging (MRI). CT scan sering menjadi modalitas pencitraan awal yang digunakan pada kasus-kasus yang dicurigai sebagai stroke iskemik 188 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY karena ketersediaannya yang luas dan waktu akuisisi yang cepat. CT scan non-kontras dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda awal iskemia dengan mengungkapkan perubahan kepadatan otak dan mendeteksi adanya perdarahan, yang dapat meniru atau berdampingan dengan stroke iskemik. CT angiografi (CTA) dapat memberikan informasi mengenai pembuluh darah dan potensi penyumbatan, sehingga membantu menentukan penyebab stroke. MRI juga biasa digunakan dalam evaluasi stroke iskemik, terutama pada kasus-kasus di mana CT scan tidak meyakinkan atau untuk menilai luas dan lokasi infark. Pencitraan berbobot difusi (DWI) sangat sensitif dalam mendeteksi perubahan awal pada jaringan otak yang terkena iskemia, sehingga memungkinkan identifikasi infark akut. Selain itu, MRI dapat memberikan pencitraan anatomi otak yang terperinci, serta urutan tambahan seperti Magnetic Resonance Angiography (MRA) untuk memvisualisasikan pembuluh darah dan mengidentifikasi sumber potensial emboli. Baik CT Scan maupun MRI adalah alat yang berharga dalam mendiagnosis dan menangani stroke iskemik, dengan masing-masing modalitas menawarkan keunggulan yang unik. CT scan seringkali lebih cepat dan lebih mudah didapat, sehingga cocok untuk penilaian cepat dalam keadaan darurat. Di sisi lain, MRI memberikan visualisasi jaringan otak yang lebih baik dan dapat memberikan informasi berharga tentang luasnya infark, serta membantu mengidentifikasi penyebab yang mendasari. 189 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 71 Jendela waktu untuk tindakan pada Stroke Iskemik Akut 9.8 ASPECTS SCORE Skor ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) adalah sistem penilaian standar yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan awal pada pemindaian CT non-kontras pada pasien stroke iskemik. Sistem ini secara khusus dirancang untuk menilai tingkat perubahan iskemik awal di wilayah arteri serebral tengah (MCA). Skor ASPECTS dibagi menjadi sepuluh wilayah di dalam wilayah MCA, dengan masing-masing wilayah diberi skor mulai dari 0 hingga 10 berdasarkan ada tidaknya perubahan iskemik. Skor 10 menunjukkan tidak ada perubahan iskemik, sedangkan skor 0 menunjukkan keterlibatan yang luas dan kerusakan iskemik yang signifikan. Tujuan dari skor ASPECTS adalah untuk menyediakan metode yang sederhana dan dapat direproduksi untuk menilai tingkat perubahan iskemik pada pasien stroke iskemik, khususnya di wilayah MCA. Hal ini membantu dalam menentukan kelayakan untuk intervensi pengobatan tertentu, seperti trombolisis intravena dan pengambilan gumpalan endovaskular, dan membantu dalam memprediksi hasil akhir pasien. Skor ASPECTS yang lebih tinggi 190 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY menunjukkan tingkat perubahan iskemik awal yang lebih kecil dan dikaitkan dengan hasil yang lebih baik dan peningkatan kelayakan pengobatan. Skor ASPECTS ditentukan dengan mengevaluasi daerah tertentu di otak pada pemindaian CT non-kontras, termasuk korteks, subkorteks, dan ganglia basal. Adanya kelainan seperti hilangnya diferensiasi materi abu-abu-putih, pembengkakan kortikal, dan efusi sulcal di wilayah ini dinilai untuk memberikan skor yang sesuai. Skor untuk setiap wilayah dijumlahkan untuk mendapatkan skor total ASPECTS. Skor ASPECTS memberikan informasi berharga untuk memandu keputusan pengobatan dan prognosis pada pasien stroke iskemik. Hal ini membantu dokter menilai tingkat keparahan dan luasnya perubahan iskemik, sehingga memungkinkan strategi manajemen yang lebih tepat. Namun, penting untuk dicatat bahwa skor ASPECTS hanyalah salah satu komponen dari evaluasi klinis secara keseluruhan, dan keputusan pengobatan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti waktu sejak timbulnya gejala, presentasi klinis, dan karakteristik pasien secara individual. 191 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Gambar 73 Skor ASPECTS sirkulasi posterior Gambar 72 Skor ASPECTS sirkulasi anterior 192 RAPID ANALYSIS NEUROIMAGING FOR EMERGENCY Referensi 1. GED 2016 Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury Collaborators. Global, rogional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Stury 2015. Lancet Neuro 2019; 18(1): 56-87. 2. Stephanie Ryan, Michelle McNicholas, Stephen Eustace. 2010. Anatomy for Diagnostic Imaging 3rd Edition 3. Yuyun Yueniwati. 2016. Pencitraan pada Stroke. UB Press 193 BAB X SKILL STATION II HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT 10.1 PENDAHULUAN Kasus neurotrauma merupakan salah satu kasus trauma terbanyak yang membutuhkan tindakan rujukan yang terjadi di Indonesia. Sebelum melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi, pertolongan pertama pada kegawatan neurotrauma di fasilitas kesehatan primer sangatlah penting untuk keselamatan pasien. Tindakan pertama dan persiapan untuk melakukan transfer rujukan kasus neurotrauma dari fasilitas kesehatan primer ke fasilitas kesehatan lanjutan merupakan salah satu poin penting yang dipelajari di skill station ini, dan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi perburukan kondisi yang terjadi pada trauma primer. 10.2 PERSIAPAN TIM DALAM TRANSPORTASI PASIEN Pada kasus neurotrauma pada fasilitas kesehatan primer diperlukan beberapa anggota atau personel kesehatan yang harus ada. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: • Personel langsung ke TKP: o Medis o Paramedis o Transporter o Operator kendaraan • Prehospital: o Dokter o Perawat 194 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT o Relawan Terlatih o Sopir ambulance • Antar rumah sakit: o Dokter o Perawat/perawat critical care o Sopir ambulance/air ambulance • Intrahospital: o Dokter o Perawat o Pekarya Pemilihan personil tergantung pada level of care dari pasien dan kondisi di lapangan. 10.3 TINDAKAN YANG DILAKUKAN Tindakan yang bisa dilakukan terhadap pasien akan terbagi dalam dua tahap, yaitu pada saat di TKP dan juga faskes terdekat, setelah melakukan dua tindakan ini maka selanjutnya akan dipersiapkan untuk rujukan ke faskes lanjutan. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan adalah: • TKP o Pelepasan helm o Pemasangan collar neck o Pemasangan scope stretcher o Cara mengangkat pasien o Manajemen basic airway o Manajemen oksigenasi o Penilaian AVPU • Faskes Terdekat o Manajemen advance airway o Manajemen breathing o Penilaian GCS 195 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT o o o o o Penilaian lateralisasi Log roll Penanganan vulnus Sisrute Posisi pasien selama transfer 10.4 PEMERIKSAAN KESADARAN • • • • A : Awake (sadar penuh) V : Respond to Verbal command (ada reaksi terhadap perintah) P : Respond to Pain (ada reaksi terhadap nyeri) U : Unresponsive (tak ada reaksi) 10.5 TINDAKAN SAAT DI FASKES TERDEKAT Ketika pasien sudah tiba di faskes terdekat, lakukan tindakan triage dan tentukan pasien merupakan pasien gawat atau tidak gawat. Pada kondisi pasien tidak gawat maka bisa langsung dilakukan pemeriksaan Anamnesa, Inspeksi, Perkusi, Palpasi, Auskultasi. Tetapi, pada pasien yang gawat dan seringnya kasus neurotrauma adalah pasien gawat, maka bisa dilakukan tindakan call for help dan ABCDE • A: Airway (C-Spine control) • B: Breathing (Tension pneumothorax) • C: Circulation (Bleeding control) • D: Disability (ICP control) • E: Exposure (Temperature control) Apabila kondisi pasien terjadi perburukan dan sampai mengalami kondisi cardiac arrest maka lakukan tindakan call for help, dan lakukan pijat jantung serta berikan nafas buatan. 196 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT 10.6 PEMERIKSAAN FISIK LANJUTAN Pada kondisi pasien yang sudah dilakukan beberapa tindakan diatas dan sudah dikatakan stabil, maka lakukan beberapa pemeriksaan ini untuk membantu menentukan diagnosis atau prognosis dari pasien. Tabel 8. Glasgow Coma Score Nilai Eye Verbal 6 Melakukan perintah 5 4 Buka mata spontan 3 buka mata dengan perintah (pasien terlihat mengatuk) Buka mata dengan rangsang sakit 2 1 Motorik Tidak buka mata Kesadaran penuh (komunikasi baik) Dapat menyusun kalimat tetapi tidak bermakna. Keluar kata. Melokalisir nyeri Menghindari nyeri Dekortikasi (Fleksi abnormal ekstremitas) Dapat bersuara Deserebrasi (Ekstensi abnormal ekstremitas) Tidak ada suara. Tidak ada gerakan 197 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT Pemeriksaan GCS (Glasgow Coma Score) Pemeriksaan Refleks Cahaya Gambar 74 Pemeriksaan refleks cahaya Penanganan Luka Lakukan penanganan luka apabila ada pada pasien, dengan mempertimbangkan bentuk luka, dasar luka, luas luka, dan lain-lain. Gambar 75 Contoh luka pada kepala 198 HOW TO REFER NEUROTRAUMA PATIENT Pemberian Mannitol Pemberian cairan mannitol dapat diberikan pada pasien dengan dosis 0.25 – 1 gr/kgBB dengan cara pemberiannya adalah infus cepat selama 10 menit lalu diulang tiap 6 jam. Referensi 1. American College of Surgeons (2018) Advanced Trauma Life Support. Chicago: American College of Surgeons. 2. Brennan P.M. et al. (2018). Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: The GCS-Pupils score: an extended index of clinical severity. Journal of Neurosurgery, 128:1612-1620. 3. Cottrell, J.E., Patel, P.M. and Warner, D.S. (no date) Cottrell and Patel’s Neuroanesthesia . Edinburgh ; London ; New York ; Oxford ; Philadelphia ; St Louis ; Sydney ; Toronto: Elsevier. 199 BAB XI BAB XI SKILL STATION III CODE STROKE FOR PRIMARY CARE 11.1 PENDAHULUAN Stroke merupakan kasus yang dapat ditemui dalam praktek terutama pada layanan fasilitas kesehatan tingkat 1. Kasus Stroke berpotensi mengancam jiwa jika tidak mendapatkan penanganan dengan baik, tepat, cepat, dan adekuat. Gejala awal dan penanganan awal pada pasien stroke sangat berperan penting. Modul ini mengajarkan bagaimana mengenali gejala awal stroke, tindakan yang menentukan diagnosis, tugas awal sebagai dokter umum, peran dokter spesialis saraf, pemilihan pemeriksaan penunjang, dan tatalaksana awal yang dapat dilakukan, baik sebagai terapi definitif maupun sebagai persiapan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Modul ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan ilustrasi kasus yang akan mempermudah pemahaman peserta. Dengan adanya modul ini, diharapkan peserta dapat mengenali dan memahami code stroke terutama pada fasilitas kesehatan tingkat 1 sebagai garda terdepan. 11.2 CARA MENENTUKAN GEJALA PASIEN STROKE DI LAYANAN PRIMER Stroke adalah keadaan darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terputus atau berkurang, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Istilah "BE-FAST" adalah akronim yang digunakan untuk membantu orang mengenali tanda-tanda stroke dan bertindak cepat untuk mendapatkan perhatian medis. Inilah arti dari setiap huruf: • B: Balance - Kehilangan keseimbangan atau koordinasi secara tiba-tiba 200 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE • • • • • E: Eyes - Kehilangan penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda F: Face - Tiba-tiba terkulai atau mati rasa di satu sisi wajah A: Arms - Kelemahan atau mati rasa secara tiba-tiba pada satu lengan atau tungkai S: Speech - Tiba-tiba kesulitan berbicara atau bicara tidak jelas T: Time - Waktu sangat penting dalam mengobati stroke. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala-gejala ini, segera hubungi layanan darurat. Perbedaan utama antara BE-FAST dan FAST adalah bahwa BEFAST mencakup gejala tambahan berupa hilangnya keseimbangan atau koordinasi secara tiba-tiba (B). FAST adalah akronim lain yang digunakan untuk membantu orang mengenali tanda-tanda stroke dan bertindak cepat untuk mendapatkan perhatian medis Kedua akronim ini dirancang untuk membantu orang mengenali tanda-tanda stroke dan bertindak cepat untuk mendapatkan bantuan medis. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua stroke muncul dengan gejala-gejala ini, dan beberapa stroke mungkin memiliki gejala yang berbeda, tergantung pada bagian otak mana yang terpengaruh. Namun, mengenali tanda-tanda ini dan bertindak cepat dapat membantu meningkatkan kemungkinan hasil yang baik bagi seseorang yang mengalami stroke. Untuk menentukan gejala stroke dengan menggunakan BE-FAST di layanan primer, tenaga kesehatan profesional dapat mengikuti langkah-langkah berikut: • Tanyakan kepada pasien apakah mereka mengalami kehilangan keseimbangan atau koordinasi secara tiba-tiba (B). • Periksa apakah pasien mengalami kehilangan penglihatan mendadak atau penglihatan ganda (E). 201 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE • Perhatikan apakah pasien terkulai atau mati rasa secara tibatiba di satu sisi wajah (F). • Periksa apakah ada kelemahan atau mati rasa mendadak pada satu lengan atau tungkai (A). • Tanyakan kepada pasien apakah mereka mengalami kesulitan berbicara atau bicara cadel secara tiba-tiba (S). • Jika ada gejala-gejala tersebut, segera hubungi layanan gawat darurat (T). Penting untuk dicatat bahwa tidak semua stroke muncul dengan gejala-gejala tersebut, dan beberapa stroke mungkin memiliki gejala yang berbeda, tergantung pada bagian otak mana yang terpengaruh. Namun, mengenali tanda-tanda ini dan bertindak cepat dapat membantu meningkatkan kemungkinan hasil yang baik bagi seseorang yang mengalami stroke. 202 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE Gambar 76 BEFAST Stroke Gejala stroke yang harus dikenali dengan cepat dengan slogan SeGeRa Ke RS 1. Senyum tidak simetris (moncong ke satu sisi), tersedak, sulit menelan air minum secara tiba - tiba 2. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba 3. BicaRA pelo / tiba-tiba tidak dapat bicara / tidak mengeri katakata / bicara tidak nyambung 4. Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh 203 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE 5. Rabun pandangan satu mata/satu sisi lapang pandang mata kabur terjadi tiba-tiba 6. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti teras. Tindakan yang menentukan diagnosis pada pasien Stroke : • Tegakkan diagnosis klinis • Cek GDA, tanda vital • FAST/BEFAST • Paseng IV line • Anamnessa berfokus pada onset stroke • Cek NIHSS • CT SCAN • Harus selesai dalam 20 menit Tugas sebagai dokter umum saat menerima pasien Stroke : • Diagnosis klinis stroke (BE FAST) • Menilai NIHSS (optional) • Cek kriteria inklusi dan eksklusi trombolisis intravena • Siapkan pemeriksaan lab (gula darah, lab lain2 sesuai indikasi) • Siapkan pemeriksaan Radiologi (CT scan / MRI) • Siapkan obat (alteplase, IV hypertensi, insulin) Peran dokter Spesialis Saraf/Neurologi: • Sebagai DPJP utama • Evaluasi ulang dengan cepat, klinis, lab, radiologis • Menentukan pemberian trombolisis • Menentukan tata laksana jika tidak bisa trombolisis IV • Menentukan tata laksana jika timbul komplikasi • Menentukan tata laksana secara umum lainnya 204 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE Kegunaan pemeriksaan CT Scan pada kasus Strok: • CT Scan harus dilakukan pada pasien ini • Tujuan untuk menyigkirkan adanya ICH • Kebanyakan CT Scan hasilnya normal • CT Angiografi dapat untuk melihat tempat penyumbatan pmbuluh darah 205 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE Gambar 77 Contoh Hasil CT Scan A. Loss of insular Ribbon B. Loss of grey-white differentiation C. MCA dense Sign D. Sulcal effacement over right hemisphere 206 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE 11.3 ALGORITMA PENANGANAN STROKE Keterangan: 1. Pasien datang dengan dugaan stroke 2. Pasang 2 infus dengan lubang besar (minimal 20 G). Periksa glukosa dengan fingerstick di samping tempat tidur. Kirim Laboratorium: CBC, Panel Metabolik Dasar, Panel Koagulasi, type and hold, dan Troponin 3. Riwayat: waktu onset, waktu terakhir kali terlihat pada pemeriksaan awal, prosedur pembedahan baru-baru ini, riwayat kesehatan sebelumnya, obat-obatan, alergi. dapatkan riwayat paralel 4. Pemeriksaan: tanda-tanda vital, berat badan, NIHSS 5. CT kepala tidak kontras. CT angiografi dan perfusi. kreatinin serum diperlukan pada pasien dengan diabetes atau penyakit ginjal yang diketahui 207 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE 6. Perdarahan intraserebral o Ya: pengobatan stroke hemoragik o Tidak: Kandidat pengobatan stroke iskemik akut 11.4 KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI PADA STROKE TROMBOLISIS Pasien diabetes millitus dan usia > 80 tahun, time window untuk r-TPA adalah 3 jam Inklusi: • Usia > 18 tahun • Diagnosis klinis stroke dengan deficit neurologis yang jelas • Awitan dapat ditentukan secara jelas (< 3 jam, AHA Guideline 2007 atau < 4,5 jam, ESO 2009) • Tidak ada bukti perdarahan intrakranial dari CT Scan • Pasien atau keluarga mengerti dan menerina keuntungan serta risiko yang mungkin timbul dan harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau keluarga untuk dilakukan terapi r-TPA Eksklusi: • Usia > 80 tahun • Deficit neurologis yang ringan dan cepat membaik atau perburukan deficit neurologis yang berat • Gambaran perdarahan intrakranial pada CT Scan • Riwayat Trauma kepala atau stroke dalam 3 bulan terakhir • Infark multilobar (gambaran hipodens > 1/3 hemisfer serebri) • Kejang pada saat onset stroke • Kejang dengan gejala sisa kelaianan neurologis post ictal • Perdarahan aktif atau trauma akut (fraktur) pada pemeriksaan fisik • Riwayat pembedahan mayor atau trauma berat dalam 2 minggu sebelumnya 208 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE • Riwayat perdarahan p dstinal atau traktur urinarius dalam 3 minggu sebelumnya 11.5 PILIHAN TINDAKAN UNTUK ACUTE ISCHEMIC STROKE Keterangan: 1. Stroke Iskemik Akut onset kurang dari 3 jam 2. Kandidat IV r-TPA a) Kriteria Eksklusi Absolut: i. Operasi besar baru-baru ini ii. Tusukan arteri di tempat yang tidak dapat dimampatkan iii. Perdarahan sistemik baru-baru ini iv. Riwayat ICH sebelumnya v. Koagulopati vi. Pertimbangkan pengobatan IA b) Kriteria Eksklusi Relatif: i. Rapidly improving ii. Minor symptoms iii. Seizure at onset 209 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE iv. Hyper/hypoglycemia v. Pertimbangkan pengobatan IV r-tPA c) Kriteria non Eksklusi: i. Berikan iv r-tpa ii. Oklusi arteri serebral mayor? iii. Pertimbangkan pengobatan IA 11.6 ALGORITMA UNTUK COMPLETE MCAO 11.7 STROKE MIMIC Banyak penyakit yang menyerupai stroke atau disebut dengan Stroke Mimic, yaitu: • Migrain dengan aura • Kejang ictal atau post ictal (Todd’s paralysis) • Simtom psikogenik • Presinkop atau sinkop 210 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE • • • • • • • Delirium akut Neoplasma serebri primer atau sekunder Infeksi otak / abses Ensefalopati metabolic/toksik Vestibulopati perifer Penyakit demielianisasi Amnesia global transien 211 CODE STROKE FOR PRIMARY CARE Referensi 1. Popkirov, S., Stone, J. and Buchan, A.M. (2020) ‘Functional neurological disorder’, Stroke, 51(5), pp. 1629–1635. doi:10.1161/strokeaha.120.029076. 2. Hollist, M. et al. (2021) ‘Acute stroke management: Overview and recent updates’, Aging and disease, 12(4), p. 1000. doi:10.14336/ad.2021.0311. 3. Caso, V. et al. (2007) Determinants of outcome in patients eligible for thrombolysis for ischemic stroke, Vascular health and risk management. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291319/ 212 BAB XII BAB XII SKILL STATION IV ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY 12.1 PENDAHULUAN Luka terbuka di kepala merupakan kasus yang sering ditemui dalam praktek sehari-hari dan berpotensi mengancam jiwa jika tidak mendapatkan penanganan dengan baik dan adekuat. Penanganan luka terbuka di kepala sangat bervariasi, mulai dari kasus laserasi sederhana hingga luka tembus yang mencederai jaringan otak dan struktur pembuluh darah yang ada di bawahnya. Modul ini mengajarkan anatomi SCALP, struktur penting yang harus diwaspadai dan tatalaksana awal yang dapat dilakukan di ruang gawat darurat, baik sebagai terapi definitif maupun sebagai persiapan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Modul ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar, video dan ilustrasi kasus yang akan mempermudah pemahaman peserta. Dengan adanya modul ini, diharapkan peserta dapat mengenali dan memahami tatalaksana luka terbuka di kepala terutama pada setting primary care sebagai garda terdepan. 12.2 ANATOMI SCALP DAN STRUKTUR PENTING DIBAWAHNYA Kulit kepala manusia atau yang biasa disebut dengan SCALP, secara anatomis dapat dibagi menjadi 5 lapisan sebagai berikut: • Skin: Lapisan kulit merupakan lapisan terluar dari kulit kepala sehingga mengandung folikel rambut dan kelenjar minyak selayaknya kulit di bagian tubuh lain. • Connective tissue: Lapisan yang kerap disebut sebagai superficial fascia ini adalah lapisan yang menghubungkan 213 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY kulit dengan aponeurosis dibawahnya serta tempat berjalannya saraf dan pembuluh darah. • Epicranial aponeurosis: Lapisan dengan struktur tendinous tipis sebagai lokasi insertio dari otot occipitofrontalis. Secara anterior lapisan ini menyatu menjadi otot frontalis dan secara lateral menyatu menjadi fascia temporalis. Perlekatan dari lapisan ini akan memanjang dari superior nuchal line hingga superior temporal line. • Loose areolar tissue: Lapisan ini menghubungkan aponeurosis dengan pericranium sekaligus memungkinkan pergerakan dari ketiga lapisan diatasnya untuk bergerak diatas pericranium. Flap kulit kepala akan diangkat pada lapisan ini saat prosdeur pembedahan. Walaupun relatif avaskular namun terdapat vena emisaria yang melewati lapisan ini dan menjadi penghubung antara vena kulit kepala dengan vena diploid dan sistem sinus vena intrakranial. • Pericranium: Lapisan ini merupakan periosteum dari tulangtulang calvaria dan menyatu dengan endosteum di sepanjang garis sutura. Setelah pericranium maka terdapat tulang-tulang calvaria di bawahnya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tabula eksterna, diploe dan tabula interna. Meningens atau selaput pembungkus otak akan dijumpai setelah membuka calvaria. Otak memiliki lapisan pembungkus yang dikenal sebagai meningens dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu duramater, arachnoid mater dan piamater yang melekat mengikuti kontur dari jaringan otak. 214 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY 12.3 JENIS LUKA PADA KEPALA Luka pada kepala dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, antara lain tampilan luka, tingkat kontaminasi maupun kedalaman dan luas luka tersebut. Luka di kepala dapat memberikan tampilan berupa luka insisi, laserasi, abrasi, avulsi dan punctum yang diilustrasikan pada gambar di bawah (Gambar 51). Gambar 78 Macam-macam jenis luka di kepala Berdasarkan tingkat kontaminasi: • Clean wounds (luka bersih) • Clean-contamined wounds • Contamined wounds (luka terkontaminasi) • Dirty or infected wounds (luka kotor atau infeksi) Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka: • Stadium I: Luka superfisial (non-blanching erythema) 215 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY • • • Stadium II: Luka ’Partial Thickness’ Stadium III: Luka ’Full Thickness’ Stadium IV: Luka ’Full Thickness’ Pembagian luka lebih lanjut dapat berdasarkan morfologinya, dimana luka dibagi menjadi skull fracture dan lesi intracranial. Pasien dengan skull fracture dibagi lebih lanjut menjadi fraktur pada skull superior (vault) dan inferior (basis). Sementara itu pasien dengan luka disertai lesi intracranial dibagi kembali menjadi lesi fokal dan diffuse (Gambar 52). Gambar 79 Jenis luka berdasarkan morfologi Pada tubuh manusia dewasa populasi normal, jika cardiac output (CO) sebanyak 5000 cc/menit dan estimasi cerebral blood flow (CBF) adalah 15% dari CO maka aliran darah ke otak dari 2 arteri carotis interna sekiar 750 cc/menit. Jumlah ini sama banyaknya dengan laju aliran darah ke kulit kepala. Sehingga jika terjadi robekan pada kulit kepala 1 sisi dapat diperkirakan laju perdarahan yang terjadi sebanyak 375 cc/menit. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan langsung 216 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY pada pasien adalah dengan bebat tekan dan kompres dingin untuk mencegah perbesaran hematoma. Selain bermacam-macam jenis fraktur cranii, terkadang dapat terjadi cedera kepala penetrasi dan gunshot wound (GSW). Jika menemui pasien dengan luka penetrasi, jangan mencabut/menarik benda yang menancap di kepala karena benda tersebut dapat berperan sebagai tampon pada pasien. Tetap ikuti kaidah primary survey dan persiapan rujuk jika di tempat kerja tidak ada sumber daya dan fasilitas bedah saraf. 12.4 PRINSIP PENANGANAN LUKA Pada saat melakukan penanganan luka, pemeriksa perlu mengawali dengan mencuci tepi luka menggunakan saflon atau air sabun. Hal ini dilakukan untuk membersihkan lemak dan kotoran yang ada pada luka tersebut. Setelah memastikan luka bersih, keringkan luka dan beri anti tetanus pada pasien. Selanjutnya berikan antibiotik profilaksis dan lakukan disinfeksi secara luas menggunakan betadine supaya area luka berada dalam kondisi se-aseptik mungkin. Berikan anestesi lokal dan cuci luka dengan cairan steril seperti NaCl 0.9%. Cairan fisiologis steril sekaligus berperan sebagai langkah debridement untuk mengurangi bacterial load pada bed luka. Tutup luka dengan melakukan penjahitan luka dengan cara yang baik dan benar. 12.5 JENIS DAN TEKNIK PENJAHITAN LUKA Sebelum memulai penjahitan luka, pemeriksa perlu melihat seberapa dalam luka yang ada pada pasien. Luka superfisial (tidak mencapai lapisan aponeurosis) dapat dilakukan penjahitan secara langsung dengan teknik simple maupun mattress suture secara langsung. Namun pada luka yang lebih dalam (telah mencapai hingga melewati lapisan aponeurosis) cenderung lebih menganga sehingga penjahitan perlu dilakukan dalam 2 langkah. Jahitan pertama setinggi lapisan aponeurosis dengan teknik continuous menggunakan benang 217 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY absorbable. Setelah itu lakukan penutupan dengan jahitan interrupted atau continuous interlocking menggunakan benang non-absorbable. Teknik penjahitan luka Pemilihan teknik penjahitan yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi dan keterampilan operator dalam proses penjahitan luka. Berikut beberapa teknik penjahitan dasar yang dapat dilakukan, antara lain: Teknik Simple Running • • Interrupted Pada teknik penjahitan ini, pertemuan kedua tepi luka sebaiknya membentuk eversi. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara memasukkan jarum ke dalam kulit dengan sudut 90 derajat dan ujung jarum harus keluar di sisi lainnya dalam sudut yang sama. Kedalaman jahitan sebaiknya lebih panjang daripada lebarnya. Dengan mengikuti kaidah ini, jahitan akan membentuk eversi sehingga dapat terhindar dari resiko infeksi dan penyembuhan luka lebih optimal. Continuous Teknik penjahitan ini dapat menjadi opsi yang baik untuk luka linear, dengan keuntungan mampu mengurangi edema yang berlangsung dalam masa penyembuhan, namun apabila terjadi kerusakan pada salah satu bagian jahitan maka seluruh jahitan akan rusak dan perlu diperbaiki secara keseluruhan. Teknik continuous dapat menggunakan pola dengan arah jarum 45 atau 90 derajat ke tepi luka sesuai preferensi operator. 218 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY Teknik Mattress • Vertical Teknis matras vertikal dapat digunakan pada area kulit yang kendur dimana tepi luka cenderung terlipat ke dalam luka. Teknik ini menggabungkan penjahitan dalam dan luar sekaligus sehingga dapat menjadi pilihan yang baik untuk penutupan luka dengan kualitas jaringan yang lemah. • Horizontal Teknik matras horizontal dapat dilakukan lebih cepat daripada teknik matras vertikal dan berguna pada area luka dengan tensi tinggi seperti sendi, fascia maupun kulit tebal. Teknik ini dapat menjadi pilihan terutama pada kondisi luka dengan tepi yang rapuh setelah operasi ulangan. Ketelitian dan konsistensi dalam melakukan teknik penjahitan sangat diperlukan untuk mencapai perkiraan jaringan yang ideal. Penjahitan sederhana yang dilakukan dengan benar akan memberi tensi yang ideal pada tiap jahitan untuk menghindari jarak antar jahitan yang tidak sesuai maupun tensi yang berlebihan. Perkiraan yang salah juga dapat menyebabkan inversi hingga tumpang tindih pada kulit. Hal tersebut perlu dihindari karena akan memengaruhi proses penyembuhan luka yang berujung pada infeksi dan komplikasi lainnya. Jenis jahitan Jenis material jahitan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tipe monofilament dan multifilament, maupun absorbable dan nonabsorbable. Keuntungan benang monofilament antara lain memberikan trauma pada jaringan 219 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY lebih minimal sehingga kemungkinan kontak dengan pathogen lebih sedikit dan menurunkan kapilaritas. Akan tetapi benang monofilament cenderung lebih sulit dalam melakukan pengikatan simpul. Sebaliknya, benang multifilament memiliki kekuatan tarikan yang lebih tinggi sehingga pengikatan simpul dapat dilakukan dengan lebih mudah dan kuat, namun kapilaritas yang tinggi menyebabkan resiko infeksi meningkat. Gambar 80 Jenis jahitan Berdasarkan tipe serapan, material jahitan dibedakan menjadi absorbable dan nonabsorbable. Benang absorbable dapat dibagi menjadi tipe biologis dan sintetis. Tipe biologis antara lain chromic gut dan plain gut, sedangkan tipe sintetis seperti Vicryl Rapide (polyglactin), Monocryl (polyglecaprone), coated Vicryl (polyglactin) dan PDS II (polydioxanone). Benang nonabsorbable juga dapat dibagi lebih jauh menjadi tipe biologis dan sintetis. Tipe biologis 220 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY nonabsorbable adalah Perma-hand (silk), sedangkan tipe sintetis seperti Mersilene (polyethylene terephthalate), Ethibond (polyesther), Prolene (polypropylene), Pronova (hexafluoropropylene), Ethilon (polyamide), Nurolon (polyamide) dan stainless steel. Ukuran jahitan Gambar 81 Ukuran jahitan Ukuran jahitan menggunakan pengukuran standar berdasarkan nomenklatur dari USP, berkisar dari 1 hingga 6 yang didasarkan dengan ukuran senar alat musik atau raket tenis. Seiring kemajuan teknologi, ukuran jahitan dapat diproduksi menjadi lebih kecil secara 221 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY signifikan. Angka 0 ditambahkan ke akhir nomenklatur USP untuk menunjukkan ukuran yang lebih kecil (Gambar 2). Jarum jahitan Gambar 82 Bagian jarum jahitan Jarum jahit memiliki beberapa parameter mekanis untuk dipertimbangkan oleh ahli bedah (Gambar 1). Titik jarum, badan, dan swage adalah penanda penting dari jarum. Swage adalah ujung jarum yang terhubung dengan jahitan. Panjang chord didefinisikan sebagai jarak langsung dari titik jarum ke swage. Pengukuran ini jangan dikacaukan dengan panjang, yaitu jarak sepanjang kelengkungan jarum dari ayunan ke titik. Tingkat kelengkungan jarum didefinisikan sebagai fraksi lingkaran yang diukur jarum (misalnya, 1/4 lingkaran atau 5/8 lingkaran). Jari-jari diukur sebagai jari-jari lingkaran yang menentukan tingkat kelengkungan. 222 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY Needle point types Needle shapes Gambar 83 Macam bentuk jarum jahit dan ujung/point Ahli bedah perlu mengetahui berbagai macam dan ukuran jarum jahitan yang tersedia agar pemilihan jarum yang digunakan sesuai untuk penutupan luka sehingga efisiensi kerja dapat meningkat. Bentuk jarum yang tersedia adalah sebagai berikut: • Lurus • 1/4 lingkaran • 3/8 lingkaran • 1/2 lingkaran: Subtipe (dari ukuran besar ke lebih kecil): CT, CT-1, CT-2, CT-3 223 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY • • • • 5/8 lingkaran Kurva compound Ski (setengah lengkung) Kano (setengah lengkung di kedua ujung segmen lurus) Jarum jahit memiliki berbagai jenis ujung agar dapat mencengkeram jaringan sekitar dengan baik yang secara umum dapat dibedakan menjadi tapered, cutting dan blunt. Jarum tapered dibagi menjadi taper point dan taper cutting. Jarum taper point adalah opsi yang baik untuk jaringan lunak karena jarum tipe ini tidak memotong secara langsung, akan tetapi memungkinkan dilatasi jaringan. Sementara itu jarum taper cutting memungkinkan penetrasi jarum melalui jaringan padat dengan perlukaan jaringan lunak sekitar minimal. Jarum cutting dibagi menjadi cutting konvensional dan cutting reverse. Jarum cutting konvensional kerap digunakan untuk penutupan kulit, sedangkan jarum cutting reverse lebih ideal untuk penetrasi jaringan dengan durabilitas tinggi seperti kulit dan tendon. 224 ESSENTIAL SKILL CRANIAL OPEN WOUND AND NEUROSURGICAL EMERGENCY Referensi 1. American College of Surgeons (2018) Advanced Trauma Life Support. Chicago: American College of Surgeons. 2. Bozzeto-Ambrosi, P. et al. (2008). Penetrating Screwdriver Wound to the Head, Arquivos de Neuro-psiquiatria, 66(1):93-95. 3. Cline, D.M. et al. (2012). Tintinalli’s Emergency Medicine: Just the Facts, Third Edition, McGrawHill Medical. 4. Datta, D., & Agarwala, S. (2013). B1 Layers of the Scalp and Suturing. Basic Techniques in Pediatric Surgery, 121– 124.doi:10.1007/978-3-642-20641-2_33 5. Diyora, B. et al. (2018). Perforating head injury with iron rod and its miraculous escape: Case report and review of literature, Trauma Case Reports, 14:11-19. 6. Hendricks, B.K. and Cohen-Gadol, A. (2022, December 22). Suturing and Closure. The Neurosurgical Atlas. https://www.neurosurgicalatlas.com/volumes/principles-ofcranial-surgery/suturing-and-closure 7. Inbar, O.C. (2016) Textbook of Focused NeuroSurgery. Jaypee Brothers, New Delhi. 8. Paulsen, F. et al. (2011) Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol 3, 15th ed, Munich: Elsevier GmbH. 9. Tandean, S. et al. (2017). Pediatric gunshot penetrating head injury: a case report with 2-year follow-up. Medical Journal of Indonesia, 26:302-306. 225 SOFT SKILL BAB XIII SOFT SKILL SERVICE EXCELLENCE Hipokrates (469-377 SM ) Bapak Kedokteran modern, telah menyampaikan bahwa Ilmu Kedokteran adalah “Ilmu yang mulia” dan hanya orang-orang yang sanggup “menjunjung kehormatan diri dan kehormatan profesi”, yang layak menjadi dokter. Semua orang dapat menjadi dokter, tapi tidak semuanya layak menjadi dokter. Dalam menjunjung kehormatan diri dan profesi, yang harus kita lakukan adalah, Satu, Jujur kepada diri sendiri. Kepada pasien serta keluarganya. Jujur dalam menegakkan diagnose dan memberikan terapi yang berbasis ilmu pengetahuan medis dengan tujuan meringankan penderitaan pasien, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Ke dua, Kasih sayang. Kita jaga empati pada pasien dan keluarganya, kita perlakukan pasien dan keluarga seperti kita ingin diperlakukan. Ke tiga, Adil. Tidak membedakan pelayanan kita berdasar ras, suku, agama, golongan, tempat tinggal dan status sosial. Pelayanan kita berpedoman pada kebutuhan medis fisik dan psikis pasien. Dengarkan keinginan dan pendapat pasien dan keluarganya. Ke empat, Mulia. Dokter harus berperilaku dengan mempertimbangkan adad dan etika setempat. Menghargai sesama, menghargai teman kerja, menghormati aturan yang berlaku pada tempat dimana kita bekerja. Bila kita dapat melaksanakan keempat pedoman tersebut maka, kita akan dapat menjaga kehormatan diri dan kehormatan profesi. Melibatkan pasien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan pelayanan, dengarkan voice dan choice mereka. Itulah dokter pemberi layanan yang ekselen. 226 SERVICE EXCELLENCE Dalam tugas sehari-hari kita sebagai dokter, tidak dapat lepas dari sistim organisasi pelayanan kesehatan dimana kita bekerja. Pelayanan Ekselen tidak hanya membutuhkan dokter pemberi pelayanan yang ekselen, namun Institusi pelayanan juga harus menerapkan regulasi yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang terstandard, membudayakan kerja dalam satu tim. Semua komponen penting dan saling menghargai. Pelayanan yang demikian sering disebut sebagai pelayanan yang berfokus pada pasien atau patient centered care (PCC). Tugas dokter dalam PCC ada beberapa tahap yang harus dikerjakan secara berurutan. Yaitu pertama, asesmen pasien. Proses ini membutuhkan pengetahuan, analisis dan pengalaman yang cukup. Menegagkan diagnose berdasar data identitas, keluhan dan tanda penyakit serta hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi memerlukan keahlian. Fase ini mendapat perhatian dan porsi besar dalam program PNNLS. Kedua, Plan of Care atau merencanakan perawatan, juga menuntut keahlian yang meliputi pengetahuan tentang modalitas terapi dengan kebaikan dan kekurangannya. Bukti ilmiah atau evidence base medicine harus dikuasai dengan baik. Ketiga, pemberian tindakan atau terapi juga memerlukan skill dan pemahaman resiko tindakan dengan baik. Tata cara dalam proses tindakan dan terapi yang beresiko tinggi harus mengikuti aturan standard pelayanan yang di tetapkan. Ke empat, monitor proses diagnostik maupun terapi harus dilakukan. Hal ini sering kita lupakan. Perbaikan dan efek negatip akibat tindakan medis harus dipantau dan di catat dengan baik guna perbaikan pelayanan pasien. Kelima, pencatatan dalam medical record yang baik, tepat waktu, seamless (berurutan) dan jelas terbaca, menjadi salah satu sarat penting dalam pelayanan yang ekselen. Semua hal diatas bila dikerjakan dengan baik dan konsisten maka kita akan mencapai apa yang disebut pelayanan ekselen dengan Value of Care yang tertinggi. 227 SERVICE EXCELLENCE Value of Care atau nilai pelayanan yang tertinggi merupakan dambaan setiap penerima layanan kesehatan. Bagi seorang dokter memberikan value of care (VC) yang setinggi tinginya pada setiap pasien yang ditangani adalah suatu keniscayaan. Suatu keharusan. Modal kita agar dapat memberikan VC setingi tingginya adalah pertama, memenuhi kebutuhan medis pasien. Modal yang harus dimiliki dokter adalah kompetensi. Hal ini perlu belajar yang tiada henti. Program PNNLS memberi perhatian besar dalam proses pembelajaran khususnya pada kegawatan sistim syaraf. Kedua adalah memenuhi kebutuhan emosi dari pasien dan keluarganya. Kemampuan yang harus kita miliki adalah empati, suatu rasa untuk memperlakukan pasien seperti kita ingin diperlakukan. Hal ini harus terus dilatih dan diimplementasikan. Yang terkhir adalan membina hubungan baik dengan pasien dan keluarganya. Rasa persahabatan dibina tidak hanya saat merawat tapi terus sampai kapanpun pasien memerlukan kita. Latihan membina persahabatan ini akan mudah bila kita pandai mendengarkan keluhan dan keinginan mereka. PNNLS memberikan perhatian besar pada soft skill yang sangat perlu dimiliki setiap dokter ini. Pelayanan yang mengedepankan VC maka akan memperoleh apresiasi yang tinggi dari pasien dan keluarganya serta kepercayaan akan rasa aman berobat ke kita. Apakah yang diharapkan pasien dan keluarganya dalam pelayanan kita …? Tentunya kesembuhan dan kepuasan. Hasil ini bagus, namun akan lebih baik rasanya bila pasien dan keluarganya dapat menjadi corong pelayanan kita, karena mereka mendapatkan lebih dari yang diharapkan, pelayanan yang membuat mereka terkejut …atau Wow service. Pasien dan keluarganya bisa menjadi media sosialisasi pelayanan kita. Mereka tidak hanya menerima pelayanan yang minimal. Apalagi pelayanan yang mengecewakan, mereka akan mengerutu dan menjadi disosialisasi negatip bagi kita. Bagaimana agar kita bisa memberikan pelayanan yang Wow….? penting bagi semua 228 SERVICE EXCELLENCE pemberi layanan. Ciri pelayanan yang menghasilkan Wow antara lain, mengejutkan. Pasien terkejut heran mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Contoh kecil, kita memberikan perhatian pada penginapan penunggu pasien. Hal kecil ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Kita perhatikan keperluan yang sangat pribadi dan spesifik. Menjaga rahasia pasien dengan ketat. Perhatian pada hal yang privat bagi pasien menjadi penting. Service Wow akan tertularkan secara otomatis karena pasien puas dan terpesona pada sikap dan profesionalitas kita. Metode lain agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan Wow… adalah terus menerus membudayakan Wow Sercive…yang muncul dari dalam jiwa pemberi layanan. Motivasi melayani “Kai san” atau “even If” adalah driver melayani terbaik…kita melayani tanpa pamrih, melayani satu hati, persepsi yang sama dengan pasien dan keluarganya demi kebaikan pasien. Melayani dengan motivasi hanya karena menjalankan tugas profesi “Kai Hao” tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Apalagi bila dasarnya hanya karena reward atau ”Kai mai”….maka kita hanya akan mendapatkan palayanan yang minimal, kaluapun bukan pelayanan yang mengecewakan. Semoga kita semua dapat memberikan layanan yang ekselen, wow service, value of care yang tertinggi. Karena merawat pasien adalah kesempatan besar yang diberikan Allah SWT kepada kita untuk berbuat kebajikan dan membina hubungan kemanusiaan yang mulia. Selamat Bekerja…selamat mengukir prestasi terbaik. 229