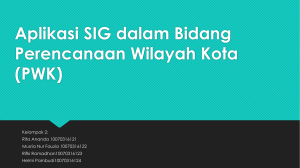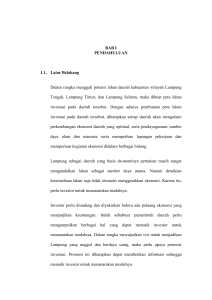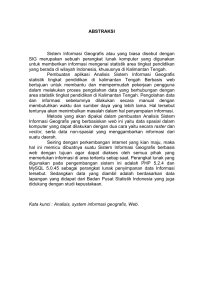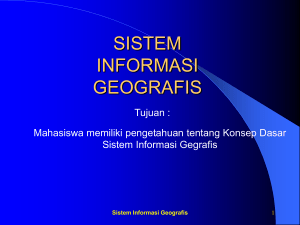MAKALAH DASAR DASAR EKONOMI WILAYAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Wilayah Dosen Pengampu: Alfian Ishak, ST.,M.Si Oleh: Fahril Akbar (223202004) Risdayanti (223202003) Agung Dwi Anugrah (223202009) Erni Yulianti (223202002) PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAKIDENDE 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun tulisan yang berjudul Dasar Dasar Ekonomi Wilayah. Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dasar dasar ekonomi wilayah yang diperuntukan bagi para mahasiswa, peneliti, perencana dan pengambilan keputusan dalam pembangunan wilayah, yang dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya pembangunan dan pengembangan wilayah pada dewasa ini dan masa depan. Ekonomi wilayah adalah salah satu disiplin ilmu ekonomi yang belum terlalu lama dipelajarkan diperguruan tinngi diindonesia. Obyek pembahasanya adalah mempelajari perilaku ekonomi manusia pada tata ruang, dimensi wilayah dan tata ruang sangat penting dan menarik perhatian serta telah dimasukkan sebagai variabel tambahan dalam analisis dan perencanaan pembangunan. UNAAHA, 2025 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 EKONOMI WILAYAH SEBAGAI CABANG ILMU EKONOMI Ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu telah berusia sekitar dua seperempat abad yang lalu. Adam Smith telah menulis bukunya yang berjudul "The Wealth of Nation" pada tahun 1776. Tahun itu dianggap sebagai tahun munculnya ilmu ekonomi yang kebetulan bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat, proklamasi merupakan kemerdekaan politis menjadi erat hubungannya dengan aspirasi harga dan upah dari campur tangan pemerintah. Adam Smith dianggap sebagai bapak Ilmu Ekonomi. Obyek bahasan dalam Ilmu Ekonomi sangat luas, yaitu menge-nai produksi, perkembangan harga, hasil produksi dan penganggur-an, penggunaan sumber daya produksi yang langka atau terbatas, perilaku mansusia dalam mengatur kegiatan, suku bunga, modal dan kekayaan, meskipun lingkup studinya adalah cukup luas dan berkembang semakin cepat, sehingga dibutuhkan pembentukan cabang-cabang Ilmu Ekonomi secara luas, seperti Ekonomi Inter-nasional, Ekonomi Moneter, Ekonomi Industri, Ekonomi Transpor-tasi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Ketenagakerjaan, Ekonomi Sumber Daya Alam, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Ekonomi Lingkungan Hidup, dan lainnya. Setelah depresi dunia pada tahun 1930, standar emas dan per-dagangan bebas yang menjadi unggulan Mashab Klasik (liberal) dilepaskan, maka muncul pandangan-pandangan dan konsep-konsep yang lebih relevan. Pendekatan ekonomi yang menekankan pada segi penawaran (mashab klasik-Hukum Say: "supply creates its own demand" dianggap tidak sesuai lagi dan muncullah analisis permintaan efektif (effective demand) dari John Maynard Keynes (bukunya berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money). Say's Law of Markets (Hukum Say tentang pasar) menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya. J.B. Say tahun 1883 mengemukakan argumentasinya bahwa karena jumlah daya beli adalah sama dengan jumlah pendapatan dan hasil pro-duksi, maka kelebihan penawaran atas permintaan tidak mungkin terjadi. Keynes menyerang hukum Say dan menyatakan bahwa pendapatan tidak selalu harus dibelanjakan seluruhnya, dengan kata lain terdapat kecenderungan mengkonsumsi marjinal (marginal propersity to consume). Pandangan laissez faire (biarkan kami melakukan sendiri) me-nyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mencampuri kegiatan ekonomi. Seperti dikemukakan oleh ahliahli ekonomi klasik yaitu Adam Smith, bahwa peranan pemerintah seharusnya dibatasi pada: (1) pemeliharaan hukum dan ketertiban, (2) pertahanan nasional, dan (3) penyediaan barangbarang kepentingan umum yang tidak dapat diadakan oleh usaha swasta. Pandangan perdagangan bebas ditinggalkan dan muncul pandangan yang menganjurkan campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter) oleh aliran Keynes. Pertanyaan klasik mengenai: what to produce, why to produce dan how to produce dianggap tidak lengkap, masih harus dilengkapi dengan pertanyaan where to produce (dimana pembangunan suatu industri atau pabrik diletakkan pada lokasi yang tepat). Pendekatan sektor telah dilengkapi dengan pendekatan wilayah dan tata ruang, yang berarti "pemanfaatan ruang wilayah adalah pemanfaatan wilayah dengan memperlihatkan aspek ruang". Dimensi wilayah (regional) dan tata ruang (spasial) telah menjadi penting dan diper-hitungkan sebagai variabel tambahan dalam perencanaan pem-bangunan. Studi-studi wilayah telah berkembang setelah tahun 1930-an, seperti Ekonomi Wilayah, Perencanaan Wilayah, dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Wilayah. Ekonomi Wilayah adalah disiplin ilmu yang obyeknya mempelajari perilaku ekonomi manusia pada tata ruang. 1.2 PENTINGNYA DIMENSI REGIONAL DAN SPASIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sebagaimana diketahui bahwa Ekonomi Wilayah merupakan suatu studi atau kajian yang belum lama dikembangkan dan di-pelajarkan pada perguruan-perguruan tinggi di berbagai negara. Dimensi wilayah (regional) dan spasial (tata ruang), telah menarik perhatian dan menjadi lebih penting sebagai variabel tambahan da-lam analisis ekonomi, khususnya bagi para perencana pembangunan. Walaupun studi lokasi telah lama diintroduksikan sejak abad yang lalu di Eropa Tengah, akan tetapi perhatian para ahli mengenai pemilihan lokasi ditinjau dari segi ekonomi dan pentingnya peranan wilayah baru dikembangkan secara lebih luas sejak kira-kira tujuh dasa warsa yang lalu. Dalam hubungan ini dapat dikatakan pula bahwa pemikiran Teori Lokasi dan Ekonomi Wilayah sebenarnya sangat dekat dengan Ilmu Ekonomi yang diibaratkan sebagai saudara dalam keluarga besar Ilmu Ekonomi. Teori ekonomi tradisional mengabaikan aspek tata ruang. Analisis ekonomi klasik bersifat statis dan tanpa tata ruang serta berlaku secara universal. Kemudian timbullah reaksi atau tantangan dari Mashab Historis (Mashab Sejarah) yang dipelopori oleh Friedrich List. Menurut Mashab Historis, hukum ekonomi tidak berlaku sama untuk seluruh waktu dan tidak berlaku mutlak bagi seluruh manusia atau bangsa, melainkan berlaku secara relatif artinya berbeda menurut waktu dan tidak sama untuk seluruh manusia dan bangsa. Mashab Historis juga menentang sifat kosmopolitan dari Mashab Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Mashab Historis menem-patkan kepentingan nasional sebagai yang terpenting dan tertinggi dalam tiap-tiap negara dan untuk itu harus disusun kebijakan eko-nomi nasional. Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam kebijaksanaan ekonomi wilayah yaitu apakah ada usaha untuk mempercepat per-tumbuhan pembangunan wilayah dengan suatu kebijaksanaan pembangunan secara nasional dengan tujuan secara menyeluruh. Proses kemajuan ekonomi dilihat dari pandangan teori pembangun-an akan menempatkan unsurunsur wilayah yang merupakan unsur sub nasional menjadi penting dan menarik dalam perencanaan pem-bangunan, sehingga wilayah-wilayah mempunyai peranan yang semakin jelas dan menentukan. Isu pengembangan wilayah baik di negara-negara yang eko-nominya telah maju maupun yang sedang berkembang pada umum-nya bersumber pada dua hal, yaitu keinginan untuk mencapai se-deretan sasaran-sasaran nasional dan kehendak untuk mengurangi ketimpangan antara pertumbuhan dan kemunduran ekonomi sub-sub nasional secara efektif. Materi utama kepustakaan dalam pembangunan ekonomi belum banyak membahas masalah wilayah secara mendasar yang menitik beratkan pada dimensi spasial atau tata ruang. Faktor per-bedaan spasial sangat menyulitkan dalam analisis yang sifatnya gen-eral. Penggerak utama untuk mengenal lebih jauh tentang masalah wilayah berasal terutama dari para politisi, para administrator, ahli-ahli ekonomi dan perencana-perencana kota yang berkecimpung de-ngan kebutuhan-kebutuhan praktis dalam kebijaksanaan pem-bangunan. Mereka dihadapkan pada pertanyaan "dimana" kegiatan pembangunan akan dilaksanakan. Untuk itu para ilmuwan berusaha mencari dasar secara nasional untuk menentukan pilihan tersebut. Dalam banyak hal pendekatan terhadap masalah-masalah wilayah dilakukan secara antar disiplin. Misalnya arus perpindahan penduduk dari daerah-daerah ke kota-kota besar atau urbanisasi di-pelajari oleh ahli-ahli Ilmu bumi untuk menemukan alasan-alasan untuk penentuan pemilihan lokasi kota; ahli-ahli pengembangan wilayah berusaha membuktikan pengaturan secara sistematis kota-kota dalam suatu negara; para ahli sosiologi meneliti polapola struk-tur sosial perkotaan dan pengaruhnya pada integrasi dan pola-pola kutub pertumbuhan yang berkembang; dan para perencana kota mengkaitkan dengan keperluan investasi dalam prasarana kota dan optimalisasi pola tata guna tanah perkotaan. Pendekatanpendekatan di atas tidak dapat diabaikan terutama apabila kita menyadari se-penuhnya betapa pentingnya peranan kota-kota dalam pengembang-an wilayah. Secara teoretis terdapat dua pertanyaan penting, yaitu (1) mengapa pertumbuhan ekonomi berada secara spasial, dan (2) bagaimana penentuan pola-pola spasial dalam perencanaan pem-bangunan. Pertanyaan pertama menyangkut masalah struktur spasial pembangunan ekonomi baik secara fisik maupun pola kegiatannya. Aspek-aspek struktur spasial pembangunan ekonomi, fasilitas-fasilitas produktif, trayek atau rute transportasi, tata guna tanah dan sebagainya mempunyai arti langsung untuk menghitung investasi. Sedangkan pola kegiatan spasial meliputi arus modal, arus tenaga kerja, arus komoditas, dan komunikasi dalam tata ruang. Aspek-aspek tersebut berpengaruh terhadap usaha-usaha untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Misalnya konsentrasi kegiatan di daerah kota besar seperti daerah metropolis akan ber-kembang terus sepanjang masih memberikan manfaat-manfaat terhadap biaya yang cukup menarik. Kemudian manfaat-manfaat tersebut berkurang karena kegiatan-kegiatan di daerah perkotaan berkembang semakin luas. Selanjutnya pola kegiatan ekonomi cen-derung menyebar dan meluas ke luar daerah metropolis. Jadi jelaslah bahwa struktur spasial dari kegiatan ekonomi terjadi karena interaksi pola fisik dan pola kegiatan. Sebagai contoh dapat dikemukakan yaitu dipelajarinya gejala-gejala seperti kutub-kutub pertumbuhan, poros-poros pembangunan, herarki kota secara fungsional, dan daerah-daerah pusat perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemajuan teknologi dan tingkat produktivitas suatu perekonomian. Bila keadaan-keadaan tersebut berubah maka struktur spasial kegiatan pembangunan akan berubah. Pertanyaan kedua membicarakan alasan-alasan mengapa pola spasial berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama menekankan pada kepentingan historis dan titik beratnya adalah suatu wilayah tertentu. Masalahnya adalah men-jelaskan pembangunan di suatu wilayah pada waktu yang lalu dan membuat proyeksi untuk masa depan. Wilayah-wilayah sisanya dianggap sebagai variabel yang tidak dapat di kontrol atau wilayah eksogin. Pendekatan kedua menitik beratkan pada suatu bangsa atau negara, dimana wilayah teritorialnya dianggap sebagai suatu kesatuan. Masalahnya adalah menjelaskan mengapa pola-pola ekonomi dan organisasi spasial telah mengikuti evolusi ekonomi nasional. Batas-batas wilayah perencanaan berlaku untuk jangka waktu terbatas, artinya terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran temporal dalam hal keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah. 1.3 LINGKUP BAHASAN Dalam buku ini (yang terdiri dari 21 Bab) dibahas berbagai dimensi dalam bidang ekonomi wilayah, yaitu meliputi teori lokasi dan aglomerasi; teori kutub pertumbuhan; wilayah sebagai elemen (unsur) struktur spasial; klasifikasi wilayah; keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah; memilih wilayah untuk pembangun-an; pembangunan wilayah yang komprehensif; implementasi dan perencanaan pembangunan wilayah; penduduk, kegiatan ekonomi, dan transportasi merupakan komponen pengembangan wilayah; migrasi spasial; peranan pusat-pusat pelayanan kecil; teori pem-bangunan polarisasi; pembangunan polarisasi sebagai suatu konsep sosiologis, beberapa isu sosial dalam pengembagan wilayah; pem-bangunan wilayah membutuhkan wiraswasta inovatif; pengentasan kemiskinan, serta model dan strategi pembangunan ekonomi wilayah. Setelah mempelajari dan memahami seluruh materi dalam buku ini diharapkan para pembaca memperoleh wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dasar-dasar ekonomi wilayah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan peralatan untuk menganalisis berbagai masalah kewilayahan dan untuk penyusunan rencana kebijakan pembangunan wilayah baik secara parsial maupun secara komprehensif. BAB 2 PENDEKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH (REGIONAL) 1.1 PERKEMBANGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak di harapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara peme-cahannya telah mengalami perkembangan pula Pembangunan yang terlalu berorientasi pada petumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB pada tingkat nasional) yang tinggi (GDP Oriented) seperti yang telah ditempuh dalam beberapa dasa warsa yang lalu, telah memperlihatkan keberhasilan secara memuas kan di berbagai bidang dan sektor pembangunan, yang diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang memperlihatkan peningkat-an secara terus menerus. Demikian pula pendapatan perkapita, kesempatan kerja, ekspor (baik volume maupun penerimaan devisa), struktur perekonomian menjadi lebih kokoh yang ditunjuk dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor perindustrian dalam PDB). Ternyata pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Kesenjangan atau ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin telah menimbulkan konsep "garis kemiskinan" (poverty line) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Mereka dikatakan berada di garis kemiskinan (absolute poverty) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan tajam. Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi itu dapat diatasi dengan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh wilayah. Pembangunan tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuh-an pokok saja, tetapi manusia mempunyai kebutuhan lainnya yang sangat banyak jumlahnya dan sangat luas jenisnya. Terdapat per-kembangan pemikiran dan pendekatan dari pertumbuhan dengan stabilitas (growth with stability), yang pada hakikatnya menghendaki masyarakat yang lebih berkeadilan, dan selanjutnya menempatkan peranan sumber daya manusia (SDM) pada posisi yang utama dan terutama dalam pembangunan, baik sebagai konsumen maupun sebagai faktor produksi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resource approach) diharapkan dapat memberikan kontri-busi yang besar bagi peningkatan laju pertumbuhan pembangunan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dipandang sebagai faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan yang dapat menjamin ke-majuan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dalam hubungan ini investasi harus diarahkan bukan saja un-tuk meningkatkan physical capital stock, tetapi ditujukan pula untuk human capital stock. Capital stock adalah untuk menunjang pen-ciptaan lapangan kerja, dan human resources untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan perbaikan gisi, diharapkan akan menumbuh-kan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Pembangunan harus merupakan suatu kemauan dan kemampuan internal dalam masyarakat yang bersangkutan, merupakan suatu proses penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, kontribusi dan partisipasi aktif dan kreatif masyarakat lokal dalam pembangunan. Peningkatan pastisipasi masyarakat lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdaya-an masyarakat mencerminkan perkembangan paradigma pem-bangunan yang berorientasi pada manusia (people - oriented), partisipatif (participatory), pemberdayaan (empowerment) dan berkelanjutan (sustainable). Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan pokok (basic needs approach). Secara historis, pendekatan people oriented, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Hal ini sudah sejak lama dilaksanakan dalam masyarakat secara luas dan masih relevan sampai sekarang. Kalau pada waktu yang lalu masih merupakan semboyan, ajakan atau arahan, tetapi pada waktu sekarang pendekatan-pendekatan tersebut telah dijabarkan ke dalam suatu interpretasi akademik yang rasional, sehingga menjadi konsep yang dapat dioperasionalkan dan dapat diimplementasikan (operationable and implementable concept). Daerah-daerah yang terbelakan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar. Mereka melakukan kegiatan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan keterbe-lakangan (backwardness) yang berarti pula untuk mengurangi keter-gantungan (dependency). Namun dalam upaya pembangunan eko-nomi dihadapi hambatan di bidang sosial (sikap, perilaku dan pan-dangan hidup, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi). Daerah-daerah yang terbelakang harus melakukan perubahan yang mendasar atau fundamental (fundamental change) untuk mampu hidup berdiri sendiri (self reliance dan self propelling growth). Untuk tidak tergantung dan mampu melakukan perubahan fundamental diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Teori sumber daya manusia dan paradigma ketidaktergan-tungan dengan daerah lain merupakan pendekatan dasar yang prospektif untuk melakukan perubahan dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang, yaitu pe-nguatan kemandirian lokal. Jadi, dimensi lokal atau lokalitas itu sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam pendekatan pembangunan. 1.2 DARI PEMBANGUNAN SEKOTORAL KE PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SELANJUTNYA KE PEMBANGUNAN LOKAL Pendekatan sektoral menganggap perlu untuk mendekati pembangunan nasional melalui kegiatan usaha demi kegitan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor-sektor dan sub-sub sektor. Adapun dasar berpijaknya adalah "mekanisme pe ngelolaan" satuan maupun kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pemengmbangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan ataupun sasaran pembangun-an yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkapkan secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan kredit yang digunakan. Kesemuanya diungkapkan menurut sektor-sektor, yaitu sektor-sektor pertanian, pertambangan, kontruksi (bangunan), perindus-trian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. Dimensi wilayah (regional), seperti daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota), hanya tampil sebagai indeks, yakni untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam daerah-daerah. Pembangunan nasional yang diuraikan ke dalam pembangun-an daerah-daerah, meskipun hanya menampilkan program sektoral umumnya telah diklasifikasikan ke dalam pendekatan regional. Disini ditekankan pada perencanaan dengan sebanyak mungkin partisipasi dari bawah (daerah). Selangkah lebih maju dari pengertian tersebut ialah pemberian aksentuasi keterpaduan antar sektor. Diharapkan agar masing-masing sektor dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dengan berfungsinya sektor-sektor secara baik, maka daerah yang bersangkutan akan berkembang dengan baik. Namun betapapun baiknya hasil yang dicapai, kesemuanya itu masih ter-golong pada pendekatan sektoral. Pendekatan regional seharusnya bertolak pada kenyataan bahwa setiap usaha selalu terkait pada wilayah, setiap kegiatan usaha selalu memanfaatkan ruang wilayah, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak dalam ruang wilayah tertentu. Kesemuanya terjadi, mungkin karena kesesuaian flora dan faunanya, mungkin karena kesesuaian tanahnya ataupun mineral yang terkandung didalamnya. Aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah mencakup aspek lokasi dan dimensi wilayah. Aspek lokasi dan wilayah adalah saling berkaitan, disatu pihak dengan fungsi lindung, dan di lain pihak dengan masalah pilihan atas lokasi bagi (a) tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha, yakni dalam rangka memperoleh tingkat "kemudahan" yang diinginkan, atau sebaliknya, (b) kegiatan usaha, dalam rangka mempertinggi tingkat "kemudahan" bagi masyarakat di wilayah tertentu, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Pendekat-an regional yang didasarkan pada perhitungan ruang dalam peman-faatan wilayah jelas mengandung maksud untuk mengendalikan terciptanya "kemudahan", baik dalam hal tingkat maupun penye barannya (lokasinya) di daerah-daerah (wilayah-wilayah). Pengerti-an yang melibatkan aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha masyarakat. Sumber dorongan itu berada pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh sentral, yakni yang dapat dirasakan sebagai "kemudahan", kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup meliputi ke tempat kerja, perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, peribadatan dan lainnya (Poernomosidi Hadjisarosa). Pembangunan wilayah dilancarkan melalui pusat-pusat per-tumbuhan masing-masing. Pusat-pusat pertumbuhan umumnya merupakan kota-kota besar. Para investor tertarik untuk menanam-kan investasinya di sektor industri, perbankan dan keuangan, pro-perti, dan lainnya, karena daerah perkotaan besar tersebut telah memiliki infrastruktur dan utilitas perkotaan yang telah tersedia secara cukup, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, pelabuhan, dan lainnya. Investasi tersebut umumnya merupakan kekuatan dari luar (external forces), baik investor asing maupun investor nasional. Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dilakukan dalam skala yang besar dan digerakkan dari pusat/ibukota pemerintahan (Jakarta). Orientasi pembangunan yang sentralistik ini mengabaikan peranan dan potensi pelaku bisnis dan pembangunan yang berada di daerah. Hal ini menimbulkan keke cewaan dan kecemburuan masyarakat, mereka merasa tidak diperhatikan dan diperhitungkan, dengan demikian tidak men-dorong penguatan dan berkembangnya perekonomian masyarakat setempat. Yang lebih mengecewakan lagi adalah bahwa hasil ke-untungan dalam jumlah besar yang diperoleh perusahaan-per-usahaan penanaman modal asing dan dalam negeri dikirim ke luar daerah yaitu ke kantor pusatnya di Jakarta atau ke negara asalnya, sehingga daerah dan masyarakat setempat tidak menikmati manfaat investasi yang berasal dari luar tersebut. Pengalaman yang lalu tidak mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian daerah setempat, merupakan pengalaman dan pelajaran yang harus tidak boleh terulang lagi pada masa yang akan datang, orientasi pembangunan jangan lagi bersifat sentralistik, sebaliknya harus bersifat desentralistik, artinya lebih mengutamakan pada kepentingan dan pengembangan daerah-daerah. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah-daerah tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (external forces), tetapi sudah pada saatnya untuk mengutamakan pada peranan kekuatan dari dalam (internal forces), yang dilakukan melalui upaya-upaya mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelem-bagaan, untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau disebut pula pembangunan ekonomi lokal. Konsep pembangunan ekonomi lokal perlu dirumuskan secara jelas, sehingga mampu menangani perubahan-perubahan fundamental yang lebih bersifat transformatif, memberdayakan sumberdaya lokal untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kegiatan perekonomian lokal. Lingkup regional dapat meliputi provinsi atau kabupaten/kotamadya. Provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten; kabupaten mencakup sejumlah kecamatan. Sedangkan lokal atau lokalisasi dikonotasikan dengan suatu area yang relatif terbatas, dimana pe-manfaatan berbagai sumberdaya alam, manusia, sosial, fisik, tekno-logi, dan kelembagaan dapat ditingkatkan lebih intensif dan interaktif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian lokal dan tingkat kehidupan masyarakat lokal yang lebih sejahtera. Secara empirik, penentuan unit perencanaan pembangunan wilayah yang luas (meliputi beberapa provinsi, satu provinsi, atau beberapa kabupaten) berdasar pengalaman yang lalu ternyata kurang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu muncul suatu keinginan untuk menentukan unit perencanaan yang lebih sempit (kecil) yang dikenal dengan sebutan wilayah pengembangan ekonomi lokal atau lokal-isasi. Secara konseptual, gejala ini memberikan pembenaran bahwa pada tahap pertama, jumlah wilayah perencanaan jumlahnya banyak dan besarannya kecil-kecil. Pada tahap kedua jumlah wilayah peren-canaan berkurang tetapi besaran masing-masing wilayah perencana-an menjadi lebih besar. Dan pada tahap ketiga jumlah wilayah perencanaan menjadi lebih banyak dan besaran masing-masing wilayah perencanaan adalah kecil, mirip seperti pada tahap pertama. 1.3 PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL Terdapat pemahaman dan perhatian yang makin besar di antara para penentu kebijaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, yaitu berusaha untuk melanjutkan strategi ekonomi nasional untuk membangkitkan perekonomian lokal. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas (nasional) ataupun oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil atau terbatas (lokal). Kepentingan ekonomi nasional dan motivasi perusahaan besar seringkali tidak bersesuaian bahkan berbeda secara nyata dengan kebutuhan dan kepentingan masya-rakat lokal, para pekerja lokal yang tidak memiliki keterampilan atau golongan masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang ber-pendapatan rendah, dan perusahaan kecil yang tersebar di seluruh daerah yang modalnya, keterampilannya, kemampuan manajemen-nya dan pemasarannya masih lemah. Dalam sistem ekonomi pasar, pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya perusahaan yang ada sekarang dan perusahaan baru, serta mempertahankan basis ekonominya yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Dalam pembangunan eko-nomi lokal, masyarakat harus memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sumberdaya sosial, sum-berdaya institusional (kelembagaan) dan sumberdaya fisik yang dimiliki untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang mandiri (dalam arti berkecukupan dan berkelanjutan). Seringkali dipertanyakan mengenai perlunya dikembangkan konsep pembangunan ekonomi daerah (lokal). Apakah konsep ini mencerminkan suatu pendekatan baru ataukah merupakan refor-mulasi dari kegagalan kebijaksanaan "trickling down" (tetesan ke bawah) yang diformulasikan oleh Albert Hirscman yaitu dampak penyebaran pembangunan dari pusat pertumbuhan ke daerah-daerah sekitarnya, yang telah dilancarkan dalam beberapa dekade yang lalu. Isu kunci yang dihadapi adalah apakah versi baru ini, yaitu mengenai pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal adalah lebih baik atau lebih efisien dibandingkan dengan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pada masa lalu? Dapatkah pemerintah daerah dan/atau daerah tetangga bersedia bekerja sama, ataukah masing-masing ingin melakukan upaya pembangunan secara sendiri-sendiri (terpisah). Hal ini harus dilihat dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Yang lebih penting dan mungkin lebih fundamental yaitu apakah pendekatan baru itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pekerjaan yang lebih baik dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis teknologi. Jika usaha lokal mampu menciptakan lapangan kerja, apakah usaha-usaha lokal tersebut akan efektif? Atau institusi lokal hanya berusaha pada proses penciptaan lapangan kerja, tanpa memberikan dampak substansial dalam memenuhi kebutuhan nyata, yaitu penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang cukup banyak bagi penduduk atau masyarakat dalam suatu sistem ekonomi tradisional. Dapatkah proses informasi pasar kerja sampai kepada dan diketahui oleh pen-duduk yang benar-benar membutuhkan pekerjaan? Apakah golong-an bawah, golongan minoritas, wanita, penduduk yang tidak me miliki keterampilan dan keahlian akan mendapat manfaat dari setiap bentuk pembangunan ekonomi lokal? Yang terakhir, berapa besar biaya perencanaan regional, relokasi kegiatan-kegiatan ke lokasi yang optimum, dan pertimbangan lingkungan yang harus dilaksanakan untuk mendorong perluasan lapangan kerja lokal? Meskipun pertanyaan-pertanyaan di atas tidak mudah di-jawab, tetapi dapat dijelaskan dengan baik setelah memahami ke-rangka dasar pemikiran konseptual, batasan dan kebijaksanaan yang dilaksanakan untuk mendorong dan memperkuat pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi lokal tidak hanya merupakan retorika baru tetapi mencerminkan suatu pergeseran fundamental peranan pelaku-pelaku pembangunan, demikian pula sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Secara esensial, peranan pemerintah lokal dan/atau kelompok-kelompok ber-basis masyarakat (community based groups) dalam mengelola sumberdaya berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah) ekonomi Ciri atau sifat utama suatu pembangunan yang berorientasi atau berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada kebijaksanaan pembangunan pribumi ("endogenous development" policies) yang memanfaatkan potensi sumberdaya manusia lokal, sumberdaya institusional lokal dan sumberdaya fisik lokal. Orientasi ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal (lokal initiatives) dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara luas. Alasan untuk hal itu adalah sebagai berikut. Teori dan program pembangunan ekonomi sebelumnya sangat menekankan pada anggaran bahwa manfaat pertumbuhan dan perluasan ekonomi pada pusat-pusat pembangunan (perkotaan) akan menetes atau menyebar ke bawah (trickling-down effect) untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan. Tetesan ke bawah tersebut dimaksudkan untuk (1) memper-baiki kelemahan penduduk miskin yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, dukungan masyarakat dan motivasi yang masih lemah pula, dan (2) untuk mengurangi ham-batan dalam struktur dan peluang penduduk miskin menghadapi sisi permintaan pasar tenaga kerja. Pembangunan ekonomi lokal berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan dalam kapasitas perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Secara esensial, pemerintah lokal - dengan partisipasi masya-rakat dan menggunakan sumberdaya kelembagaan yang berbasis masyarakat yang ada sekarang (yang berpotensi ekonomi) - diperlu-kan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki untuk merancang dan melaksanakan pembangunan eko-nomi lokal. Pemerintah lokal dan organisasi kemasyarakatan me-nyadari bahwa semua kegiatan sektor publik mempunyai suatu pengaruh terhadap keputusan-keputusan sektor swasta. Keputusan swasta dan kegiatan ekonomi publik adalah erat terkait satu sama lain dan mempengaruhi peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Dan organisasi-organisasi yang berbasis masyarakat perlu menyusun perspektif baru yang bermanfaat untuk mendorong prakarsa pem-bangunan yang terencana dan terkoordinasi. Dalam masyarakat baik yang besar maupun yang kecil perlu dipahami bahwa pemerintah lokal, lembaga kemasyarakatan, dan sektor swasta adalah merupakan mitra yang esensial dalam proses pembangunan ekonomi. BAB 3 TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 1.1 TEORI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN WILAYAH Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat merupakan kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan semakin majunya studi-studi pem-bangunan ekonomi, banyak teori telah diperkenalkan. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari po-tensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiaya-an pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelem-bagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang mem-bentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah (re-gional) secara komprehensif.Dalam pembangunan ekonomi wilayah (regional) terdapat beberapa teori yang penting, yakni (i) pemikiran-pemikiran menurut beberapa aliran dalam Ilmu Ekonomi (misalnya Klasik, Neo Klasik, Harrod-Domer, Keynes dan Pasca Keynes), teori basis ekspor, teori sektor, struktur industri dan pertumbuhan wilayah, dan teori kausasi kumulatif. Selanjutnya akan dibahas pula teori lokasi dan aglomerasi (dijelaskan dalam Bab 4), teori tempat sentral (diuraikan dalam Bab 5), teori kutub pertumbuhan (dalam Bab 6), dan teori pembangunan polarisasi (Bab 7). 1.2 ALIRAN KLASIK Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 dipelopori oleh Adam Smith yang (dianggap sebagai bapak ekonomi) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat diting-katkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi (pem-bentukan modal) dan persediaan modal (capital stock), yang se-lanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) penduduk. Peningkatan ke makmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Ber-tambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (law of diminishing re-turns), yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal. Doktrin atau semboyan aliran Klasik adalah "laisser faire laisser passer" atau persaingan bebas. Artinya pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian. Pemikiran dan pan-dangan beberapa tokoh atau pengikut aliran Klasik dapat dikemuka-kan yaitu: menurut Adam Smith adalah (dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi) untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produk-tivitas tenaga kerja meningkat. Spesialisasi dalam proses produksi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, untuk selanjutnya akan mendorong diketemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru, dan pada akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi, yang berarti meningkatkan kemakmuran (kesejahteraan) penduduk. Pembangunan dan pertumbuhan itu bersifat kumulatif, artinya akan berlangsung terus dan semakin meningkat. Bila ada pasar yang cukup besar dan ada akumulasi modal akan mendorong pembagian kerja dan meningkatkan pendapatan nasional dan memperbesar jumlah penduduk. Penduduk selain merupakan pasar karena pen-dapatannya meningkat, merupakan pula sumber tabungan yang digunakan untuk akumulasi modal, dan selanjutnya akan men-dorong pertumbuhan semakin meningkat. David Ricardo berpendapat, bila jumlah penduduk dan aku-mulasi modal bertambah terus menerus, maka ketersediaan tanah (lahan) yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka. Maka akibatnya sewa tanah yang subur akan lebih tinggi dari pada tanah yang kurang subur. Perbedaan tingkat sewa tanah adalah karena perbedaan tingkat kesuburan tanah. Pengolahan tanah yang subur akan memperoleh penghasilan dan keuntungan yang tinggi, sehingga mampu untuk membayar sewa tanah yang tinggi. Menurut Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus konsekuensinya adalah permintaan akan bahan pangan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan tingkat pertumbuhan bahan pa-ngan mengikuti deret hitung, artinya akan terjadi gap atau ketim-pangan yang semakin besar antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak terhadap se-makin menurunnya tingkat kemakmuran (kesejahteraan) penduduk. Hukum pasar yang dikemukakan oleh J.B. Say adalah "sup-ply creates its own demand". Artinya setiap barang yang dihasilkan oleh produsen selalu ada pembelinya, sehingga tidak mungkin terjadi kelebihan produksi (over produksi) dan pengangguran. Hukum Say hanya akan berlaku bila kenaikan pendapatan seluruhnya digunakan untuk membeli barang dan jasa, artinya semua tabungan digunakan untuk kegiatan investasi. Jadi tambahan pendapatan adalah sama dengan tambahan konsumsi. Tabungan itu sangat diperlukan untuk pembentukan modal atau investasi. Investasi dilakukan setelah ada kenaikan jumlah permintaan secara agregat (aggregate demand). Jadi tersedia tabungan yang cukup yang digunakan untuk keperluan investasi. Pemikiran J.B. Say dengan hukum pasarnya yang terkenal se-cara luas yaitu "supply creates its own demand" adalah bersifat optimistik, sedangkan Robert Malthus dengan perkiraannya jumlah penduduk bertambah mengikuti deret ukur dan bahan pangan mengikuti deret hitung dikatakan sebagai pandangan yang bersifat pesimistik. 1.3 ALIRAN NEO KLASIK Aliran Neo Klasik menggantikan aliran Klasik. Ahli-ahli Neo Klasik banyak menyumbangkan pemikiran mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertum-buhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang gradual Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, Aliran Neo Klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan (per-kembangan). Meskipun model pertumbuhan Neo Klasik telah digunakan secara luas dalam analisis regional, namun beberapa asumsi mereka adalah tidak tepat, yakni: (i) full employment yang terus menerus tidak dapat diterapkan pada sistem multi-regional dimana persoalan-persoalan regional timbul disebabkan karena perbedaan-perbedaan geografis dalam hal tingkat penggunaan sumberdaya, dan (ii) persaingan sempurna tidak dapat diberlakukan pada perekonomian regional dan spasial. Tingkat pertumbuhan terdiri dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penawaran tenaga kerja dan kemajuan teknik. Model Neo Klasik menarik perhatian ahli-ahli teori ekonomi regional karena mengandung teori tentang mobilitas faktor. Implikasi dari persaingan sempurna adalah modal dan tenaga kerja akan berpindah apabila balas jasa faktorfaktor tersebut berbeda-beda. Modal akan berarus dari daerah yang mempunyai tingkat biaya tinggi ke daerah yang mempunyai tingkat biaya rendah, karena keadaan yang terakhir itu memberikan suatu penghasilan (returns) yang lebih tinggi. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akan pindah ke daerah lain yang mempunyai lapangan kerja baru yang merupakan pendorong untuk pembangunan di daerah tersebut. Model Neo Klasik kurang menjelaskan tentang alasan-alasan riil mengapa beberapa daerah mempunyai daya saing yang kuat dan beberapa daerah lain mengalami kegagalan. Neo Klasik berpendapat bahwa dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, senantiasa akan muncul kekuatan tandingan (counter forces) yang dapat me-nanggulangi ketidakseimbangan dan mengembalikan penyimpangan kepada keadaan keseimbangan yang stabil, sehingga tidak diperlukan intervensi kebijakan pemerintah secara aktif. Seperti penulis-penulis lain, Harrod-Domar menekankan pentingnya peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal mempunyai peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan modal. Secara sederhana teori Harrod-Domar adalah jika keseimbangan pada tingkat full employment hendak dipertahankan maka dibutuhkan investasi dalam jumlah yang cukup besar (ber-tambah), yang berarti pendapatan nasional makin besar untuk me-ngurangi jumlah penduduk yang bertambah. Perbedaan pokok antara cara pendekatan Harrod-Domar dan cara pendekatan Neo Klasik adalah bahwa Neo Klasik mengemukakan teori mobilitas faktor dan analisisnya statika komparatif. 1.4 ALIRAN KEYNES DAN PASCA KEYNES Setelah Perang Dunia I Ilmu Ekonomi mencapai kemajuan be-sar di bidang pembahasan dan analisis perekonomian negara-negara maju dan berkembang. Bersamaan dengan masa depresi yang melanda dunia tahun 1930-an muncullah pemikiran John Maynard Keynes yang mengemukakan perubahan besar. Mula-mula Keynes menekankan pada persoalan permintaan efektif (effective demand). Analisisnya adalah jangka pendek. Kumpulan pemikiran Keynes dibukukan dalam bukunya yang berjudul General Theory of Em-ployment, Interest and Money (1936). Tema sentralnya adalah bahwa karena upah bergerak lamban, maka sistem kapitalisme tidak akan secara otomatis menuju kepada keseimbangan penggunaan tenaga kerja secara penuh (full-employment equilibrium). Menurut Keynes, akibat yang ditimbulkan adalah justru sebaliknya (equilibrium underemployment) yang dapat diperbaiki melalui kebijakan fiskal atau moneter untuk meningkatkan permintaan agregat. Aliran Pasca Keynes memperluas teori Keynes menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang meng-analisis fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya per-kembangan jangka panjang. Beberapa persoalan penting dalam analisis Pasca Keynes adalah: a. Syarat-syarat apakah yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapatan yang mantap (steady growth) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (full employ-ment income) tanpa mengalami deflasi ataupun inflasi. b. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau tingkat inflasi terus menerus. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka pendapatan per kapita akan berkurang, kecuali bila pendapatan riil juga bertambah. Selanjutnya bila angkatan kerja berkembang, maka output harus bertambah juga untuk mempertahankan kesempatan kerj a penuh. Bila terjadi investasi, maka pendapatan riil harus bertambah pula untuk mencegah terjadinya kapasitas yang menganggur (idle capac-ity). 1.5 TEORI BASIS EKSPOR (EXPORT BASE THEORY) Teori basis ekspor adalah bentuk model pendapatan yang pa-ling sederhana. Teori ini sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari ekonomi makro interregional karena teori ini menyeder-hanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Masyarakat itu dapat dinyatakan sebagai suatu sistem sosial ekonomi. Sebagai suatu sistem, keseluruhan masyarakat melakukan perdagangan dengan masyarakat lain di luar batas wilayahnya. Faktor penentu (determinan) pertumbuhan ekonomi dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lain di luar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan material (bahan) untuk komoditas ekspor akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorien-tasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang me-nyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat local. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuh-an wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (mul-tiplier effect) dalam perekonomian regional. Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis (Richardson, 1977, 14). Bertambah banyaknya ke-giatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume ke-giatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. Walaupun teori basis ekspor mengandung kelemahan yang membagi perekonomian rewgional menjadi dua sektor kegiatan yakni basis dan non basis, namun upaya tersebut dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperjelas pengertian mengenai struktur daerah atau wilayah yang bersangkutan dan bukan sebagai alat untuk membuat proyeksi jangka pendek atau jangka panjang. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (location quo-tient, LQ). LQ, digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (leading sectors). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Analisis location quotient merupakan suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah, cepat dan tepat. Karena kesederhanaan-nya, teknik location quotient dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai perubah acuan dan periode waktu. Loca-tion quotient merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu (misalnya industri) atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu (industri) atau total nilai PDRB di suatu daerah (kabupaten) dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama di provinsi dimana kabupaten tersebut berada dalam lingkup-nya. Perhitungan LQ dapat dilakukan pula untuk membandingkan indikator di tingkat provinsi dengan di tingkat nasional. Analisis location quotient dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Asumsi yang mendasari metoda LQ sangat melemahkan daya andalnya karena beranggapan bahwa permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan nasional, bahwa produk-tivitas tiap tenaga kerja di setiap daerah sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap tenaga kerja dalam industri nasional, dan bahwa perekonomian nasional merupakan suatu perekonomian tertutup. Kelemahan dari metoda LQ tersebut hendaknya tidak ter-lalu ditonjolkan karena metoda LQ memiliki pula kelebihan penting, yaitu memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Misalnya, suatu pabrik baja menjual sebagian besar dari outputnya kepada suatu pabrik mobil lokal yang mengekspor kendaraan mobil, output baja memang dijual secara lokal, tetapi secara tidak langsung telah dikaitkan dengan ekspor. 1.6 TEORI SEKTOR (SECTOR THEORY OF GROWTH) Setiap wilayah mengalami perkembangan meliputi siklus jang-ka pendek dan jangka panjang. Faktor-faktor dalam analisis perkem-bangan jangka pendek yang umumnya digunakan adalah penduduk, tenaga kerja, upah, harga, teknologi dan distribusi penduduk, tetapi laju pertumbuhan jangka panjang biasanya diukur menurut keluaran (output) dan pendapatan. Pada umumnya kita sependapat bahwa pertumbuhan dapat terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor penentu endogen maupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam wilayah yang bersangkutan atau faktor-faktor di luar wilayah atau kombinasi dari keduanya. Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori sektor. Teori ini dikembangkan berdasar hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumberdaya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan da-lam sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (sector shift). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah. Alasan dari perubahan atau pergeseran sektor tersebut dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan jasa yang disuplai oleh industri manufaktur dan industri jasa adalah lebih tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer. Maka pendapat an yang meningkat akan diikuti oleh perpindahan (realokasi) susa berdaya dari sektor primer ke sektor manufaktur dan sektor jasa Sisi penawaran, yaitu realokasi sumberdaya tenaga kerja dan modal duktivitas dalam sektor-sektor tersebut. Kelompok sektor-sektor se-dilakukan sebagai italokasi saad tingkat pertumbuhan se kunder dan besar dalam tingkat produktivitas nikmati kemajuandorong peningkatan. BAB 4 TEORI LOKASI DAN AGLOMERASI 1.1 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EΚΟΝΟΜΙ MENGENAI LOKASI Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara nasional maupun secara wilayah harus dipertimbangkan masak-masak dan dipilih dengan tepat agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan efisien. Sebenarnya teori-teori lokasi telah lama diintroduksikan oleh ahli-ahli ekonomi, dimana pada waktu itu implikasi secara teoretis menunjukkan bahwa faktor tata ruang (space) dan faktor jarak (distance) nampak sekunder atau secara implisit dibandingkan dengan unsur waktu (time) dalam analisis ekonomi. Perhatian terhadap teori lokasi telah menjadi semakin besar terutama sekitar tujuh dasa warsa yang lalu bertepatan waktu pada perencanaan tata ruang, dimana dimensi geografis dan lan-sekap ekonomi (economic landscape) dimasukkan sebagai variabel tambahan yang penting dalam kerangka teori pembangunan. Banyak ekonomi telah menyusun berbagai teori lokasi. Akan tetapi analisis mereka ditunjukan pada perusanahaan-perusahaan individual yang memilih lokasinya dalam keadaan yang terisolasi. Artinya pendekatan yang digunakan tidak memperhitungkan ada-nya persaingan dan kemungkinan terjadinya reaksi, yaitu perubahan dalam lokasi, harga, atau output (keluaran) terhadap perusahaan-perusahaan baru yang baru memasuki pasar. Di bawah ini akan diuraikan perkembangan pemikiran mengenai lokasi. Beberapa ahli ekonomi sebelum Adam Smith (1977) masih se-dikit sekali membahas masalah lokasi. Sir William Petty (1662) telah menyadari adanya perbedaan sewa tanah yang disebabkan oleh karena perbedaan lokasi, sedangkan Richard Cantillon (1730) tidak hanya membicarakan masalah lokasi, akan tetapi telah mengemuka-kan pula teori pasar untuk kotakota yang telah berkembang sebagai akibat dari kemajuan ekonomi, yang semula pasarnya tidak teratur kemudian menjadi pasar yang permanen. Dapat dikatakan bahwa ahli-ahli ekonomi klasik tidak menulis secara terarah dan membuat analisis yang panjang lebar mengenai masalah lokasi. Mereka hanya memberikan komentar singkat saja. Adam Smith (1776) telah membahas perbedaan antara kota (town) dan desa (country). Pengaruh lokasi dikemukakan yang per-tama kalinya secara nyata yaitu dalam teori Ricardo (1817) mengenai sewa lahan, yang kemudian dikembangkan oleh Von Thunen. Dalam suatu analisis singkat, J.S Mill (1839) melanjutkan teori klasik di atas, dimana dikemukakan bahwa lahan non pertanian dapat menghasil-kan sewa lahan yang diukur dari perbedaan penghasilan dari suatu lokasi yang sudah dianggap tepat dan di tempat lain yang kurang tepat, misalnya lokasi di desa kecil atau di tempat lain yang kurang tepat. Von Thunen juga menyebut-nyebut biaya transportasi, meski-pun tidak memandangnya sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan Lokasi. Dalam perdagangan internasional, analisis klasik telah me-nyinggung implikasi lokasi yaitu dengan adanya penekanan pada pembagian kerja secara teritorial. Misalnya Robert Torrens (1808) menyatakan bahwa jarak (distance) itu dapat membatasi faktor mobilitas, dimana digunakan asumsi bahwa faktor produksi tidak mobil (immobile faktors) dalam perdagangan internasional sedangkan dalam pedagangan dalam negeri faktor produksi dapat bergerak bebas (mobil). Perbedaan antara perdagangan tanpa mobilitas dan perdagangan dengan mobilitas telah ditekankan secara khsusus oleh J.E Cairness (1874) yang menggunakan istilah commercial competition dan industrial competition. Commercial com-petition menunjukkan pada perdagangan tanpa mobilitas, sedangkan industrial competition pada perdagangan dengan mobilitas. Dilihat dari perkembangan pemikiran teoritis dapat dikatakan bahwa dari masa Adam Smith sampai Pigou tidak ada analisis deduktif yang mengemukakan pemikiran mengenai sebab-sebab yang menentukan lokasi ekonomi. Pemikiran lain dalam abad ke-19 dan sebelumnya yang ber-anggapan bahwa terdapat perkembangan masalah tata ruang yaitu dalam bidang social physics, dimana diaplikasikan analogi-analogi dan teknik-teknik yang berasal dari ilmu-ilmu alam pada perilaku manusia dan sosial. G.W. Von Leibnis pada akhir abad ke-17 serta A. Comte dan A. Quetelet dalam abad ke-19 membahas gejala sosial yang dianalisis dalam pengertian waktu dan tata ruang, khususnya Quetelet memperlihatkan relevansi teori probabilitas terhadap interpretasi perilaku manusia. Generalisasi konsep gravitasi telah ditinggalkan sampai de-ngan permulaan abad ke20. Kemudian pada tahun 1929 W.J. Reilly berusaha mengukur kekuatan daya tarik suatu pusat perdagangan. Hukum gravitasinya tentang perdagangan menyatakan bahwa arus perdagangan antara dua buah kota adalah proporsional terhadap jumlah penduduknya. Dari sekian banyak teori lokasi dan teori perwilayahan yang telah diintrodusir oleh para pencetusnya dapat diketengahkan beberapa di antaranya yang dianggap penting, yaitu Von Thunen (1826), A. Weber (1909), W. Christaller (1933), A. Losch (1944), F. Perroux (1955), W. Isard (1956), dan J. Friedmann (1964). Von Thunen telah mengembangkan hubungan antara perbeda-an lokasi pada tata ruang (spatial location) dan pola penggunaan lahan. Menurut von Thunen, jenis pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh tingkat sewa lahan dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif. Lokasi berbagai jenis produksi pertanian (seperti menghasilkan ta-naman pangan, perkebunan, dan sebagainya) ditentukan oleh kaitan antara harga barang-barang hasil dalam pasar dan jarak antara daerah produksi dengan pasar penjualan. Kegiatan yang mampu menghasilkan panen fisik tertinggi per hektar akan ditempatkan pada kawasan konsentris yang pertama di sekitar kota, karena keuntungan yang tinggi per hektar memungkinkan untuk membayar sewa lahan yang tinggi. Kawasan produksi berikutnya kurang intensif dibandingkan dengan kawasan produksi yang pertama, demikian seterusnya. Analisis penentuan lokasi optimum seperti dikemukakan oleh von Thunen telah mendapat perhatian utama dalam pemikiran Alfred Weber. Ia menekankan pentingnya biaya transportasi sebagai faktor pertimbangan lokasi. Teori Weber sebenarnya menekankan dua kekuatan lokasional primer, yaitu selain orientasi transportasi juga orientasi tenaga kerja. Weber telah mengembangkan pula dasar-dasar analisis wilayah pasar dan merupakan seorang ahli teori Lokasi yang pertama membahas mengenai aglomerasi. Pemikiran Weber telah memberikan sumbangan ilmiah dalam banyak aspek, di antaranya yaitu penentuan lokasi yang optimal dan kontribusinya yang esensial dalam pengembangan wilayah yaitu mengenai munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi (industri). Christaller mengembangkan pemikirannya tentang penyusun-an suatu model wilayah perdagangan yang berbentuk segi enam atau heksagonal. Teorinya adalah teori tempat sentral (central place theory). Heksagonal yang terbesar memiliki pusat paling besar, se-dangkan heksagonal yang terkecil memiliki pusat paling kecil. Secara horisontal, model Christaller menunjukkan kegiatan-kegiatan manusia yang tersusun dalam tata ruang geografis, dan tempat-tem-pat sentral (pusat-pusat) yang lebih tinggi ordenya mempunyai wi-layah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas diban-dingkan pusat-pusat yang kecil; sedangkan secara vertikal, model tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat yang lebih tinggi orde-nya mensuplai barang-barang ke seluruh wilayah dan kebutuhan akan bahanbahan mentah di pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya disuplai oleh pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Prinsip pe-masaran dengan susunan piramidal pada model tempat sentral dapat menjamin minimisasi biaya-biaya transportasi. Menurut Christaller, seluruh wilayah perdagangan dapat dilayani, sedangkan dalam kenyataannya sebagian dari wilayah-wilayah tersebut tidak sepenuh-nya dapat terlayani karena terbatasnya fasilitas transportasi dan hambatan-hambatan geografis. Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur herarkis pusat-pusat kota (wilayah-wilayah nodal) tetapi tidak men-jelaskan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dengan perkataan lain tidak menjelaskan gejalagejala (fenomena) pembangunan. Teori ini bersifat statis; agar teori tempat sentral dapat menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah yang menjelas-kan mengenai proses perubahan-perubahan struktural. Salah satu dari teori pertumbuhan wilayah adalah teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) yang diformulasikan oleh Perroux. Sumbangan positif teori tempat sentral dapat dicatat bahwa teori tersebut relevan bagi perencanaan kota dan wilayah karena sistem herarki pusat merupakan sarana yang efisien untuk peren-canaan wilayah. Distribusi tata ruang dan besarnya pusat-pusat kota merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur wilayah nodal dan melahirkan konsep-konsep dominasi dan polarisasi. Losch mengintroduksikan pengertian-pengertian wilayah pasar sederhana, jaringan wilayah pasar, dan sistem jaringan wilayah pasar. Prasarana transportasi merupakan unsur pengikat wilayah-wilayah pasar. Unit-unit produksi pada umumnya ditetapkan pada pusatpusat pasar yang juga merupakan pusat-pusat urban. Per-usahaan-perusahaan akan memilih lokasinya pada suatu tempat dimana terdapat permintaan maksimum. (Loschian demand cone theory). Berdasar struktur herarkis tempat sentral yang telah ditunjuk-kan oleh Christaller di atas, Isard telah menekankan pentingnya kedudukan pusat-pusat urban tingkat nasional (metropolis) dalam kaitannya dengan aglomerasi industri. Selanjutnya Isard mengembangkan gejala locational economies (penghematan lokasi), dan ur-banization economies (penghematan urbanisasi) sebagai akibat dari pengaruh lokasi. Menurut C.K Zipf, urutan besarnya peranan kota-kota dapat ditentukan dengan cara meranking pusat-pusat yang bersangkutan (rank size rule) menurut jumlah penduduknya. Konsepsi Perroux merupakan langkah utama untuk memberi bentuk konkrit pada aglomerasi. Dinyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala tempat, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu. Ia lebih memberikan tekanan pada aspek konsentrasi proses pembangunan dan menganggap in-dustri pendorong (propulsive industries) sebagai titik awal perubahan unsur yang esensial untuk menunjang pembangunan selanjutnya. Meskipun teori kutub pertumbuhan ini berguna untuk menguji atau membandingkan konsekuensi yang berbeda-beda dari pemilihan alternatif lokasi, akan tetapi teori tersebut tidak dikate-gorisasikan sebagai teori lokasi (spaceless). Dimensi geografis telah dimasukkan ke dalam pengaruh kutub pengembangan. Antara kota dan pedesaan terdapat kaitan yang sangat erat, satu sama lainnya saling melengkapi seperti dikemuka-kan oleh Mosher. Friedmann meninjaunya dari ruang lingkup yang luas dengan menampilkan teori core region (wilayah inti). Wilayah inti dikaitkan dengan fungsinya yang dominan terhadap perkem-bangan wilayah-wilayah di sekitarnya, misalnya sebagai pusat per-dagangan atau pusat industri. Wilayah-wilayah di sekitar wilayah inti disebut wilayah-wilayah pinggiran (periphery regions). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi suatu industri atau unit produksi pada umumnya dikaitkan dengan lokasi sumber bahan mentah dan wilayah pasarnya. Kriteria penen-tuan yang digunakan bermacam-macam, yaitu biaya transportasi yang terendah, sumber tenaga kerja yang relatif murah, ketersediaan sumberdaya air, energi ataupun daya tarik lainnya berupa peng-hematan-penghematan lokasional dan penghematanpenghematan aglomerasi. Dimensi wilayah dan aspek tata ruang telah dimasukkan sebagai variabel tambahan yang penting dalam kerangka teori pembangunan. 1.2 KEKUATAN-KEKUATAN AGLOMERASI DAN DEGLOMERASI Untuk menganalisis pembangunan kota dan wilayah, kita harus memahami sepenuhnya mengenai kekuatan-kekuatan aglo-merasi dan deglomerasi. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat men-jelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi atau dispersi ke-giatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Konsentrasi berbagai kegiatan nampak lebih jelas pada kota-kota besar, misalnya Tokyo, New York, London, Paris, Rio de Janeiro, dan lainlainnya. Manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di atas dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu (1) penghematan skala (scale economies), (2) penghematan lokasi (lokalization economies), dan (3) penghematan urbanisasi (urbanization economies). Penghematan skala. Terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala peoduksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar sebagai akibat investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan, yang memungkinkan dilaksanakan pemanfaatan pabrik dan per-alatan tersebut dalam skala besar dapat membagi-bagi beban biaya-biaya tetap pada berbagai unit yang terdapat dalam sistem produksi. Sebagai konsekuensinya, unit biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Pro-duksi pada skala besar dimaksudkan untuk menghindari unit biaya operasi yang eksesif. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan hanya pada lokasi-lokasi yang melayani penduduk dalam jumlah besar, atau dengan perkataan lain mempunyai suatu pasar yang luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya penghematan skala internal memberikan manfaat pada konsenstrasi penduduk dalam jumlah besar dari pada jumlah penduduk yang sedikit, industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penghematan lokalisasi. Jenis kedua, kekuatan yang terpenting konsentrasi industri diasosiasikan dengan penghematan yang di-nikmati oleh semua perusahaan dalam suatu industri yang sejenis pada suatu lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah keluaran (total output) industri tersebut. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan mengenai pabrik tekstil. Kasus di suatu wilayah yang belum berkembang, dimana terdapat kelayakan untuk men-dirikan pabrik-pebrik modern ukuran kecil yang tidak membutuhkan investrasi modal yang eksesif dan dapat beroperasi tanpa dilayani oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi dan spesialistis. Setiap pabrik tekstil boleh jadi melakukan sendiri reparasi fasilitasnya, misalnya 4 atau 5 kali dalam setiap tahun. Akan tetapi bila pabrik tersebut memerlukan pelayanan reparasi atau perbaikan secara cepat, maka fasilitas reparasi harus berada tidak jauh dari padanya. Unit biaya reparasi akan sangat tinggi bila fasilitas reparasi digunakan hanya oleh sebuah pabrik untuk 4 atau 5 kali dalam satu tahun dan tidak dapat digunakan pada waktu sisanya. Sebaliknya bila terdapat sekelompok 10 buah pabrik, dimana masing-masing pabrik dapat dilayani dengan cepat dan gampang, maka fasilitas reparasi tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih penuh, katakanlah 40 atau 50 kali dalam satu tahum. Biaya-biaya tetapnya dapat disebarkan di antara pemakaian yang lebih banyak, sehingga biaya reparasi menjadi rendah dan disamping itu masih dapat diperoleh sejumlah keuntungan yang cukup. Jadi dengan pengelompokan pabrik-pabrik tekstil tersebut, maka fasilitas dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan diharapkan dapat menurunkan biaya reparasi. Hal ini menciptakan suatu penghematan lokalisasi. Contoh lain yaitu pembangkit tenaga listrik. Pada umumnya perusahaan listrik berskala besar, biaya per kilowat-jam menurun dengan adanya peningkatan keluaran. Sepuluh buah pabrik tekstil akan memperoleh manfaat berupa biaya listrik yang lebih rendah apabila mereka bersama-sama mengusahakan suatu pabrik pem-bangkit tenaga liastrik dari pada masing-masing mendirikan instalasi tenaga listrik yang kecil secara sendiri-sendiri. Berkelompok dan terkonsentrasinya pabrik-pabrik sejenis pada suatu daerah geografis tertentu, misalnya di daerah-daerah perkota-an, akan menciptakan penghematan lokasisasi dan akan meningkattransportasi dan biaya produksi untuk ketiga pabrik tersebut secara bersama-sama, maka lokasi yang terbaik ditetapkan adalah pada titik A, karena dapat mencapai sasaran tersebut. Dalam sistim kapitalis dan bahkan dalam banyak sistem non kapitalis masing-masing pro-dusen secara primer tertarik pada keuntungan sendiri, bukan pada keuntungan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tiap-tiap produsen tertarik pada daerah aglomerasi potensial yaitu di sektor A dan batas yang paling jauh isodapan kritisnya masing-masing. Penghematan urbanisasi. Penghematan urbanisasi adalah jenis penghematan yang ketiga. Penghematan urbanisasi diasosiasikan dengan pertambahan jumlah total (penduduk, hasil industri, pen-dapatan, dan kemakmuran) di suatu lokasi untuk semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Penghematan ini memperkaitkan pada kegiatan industri-industri dan sektor-sektor secara agregatif. Misalnya suatu kegiatan yang sangat tergantung pada manajemen yang kreatif dan tenaga kerja yang terampil. Dalam hal ini terdapat risiko untuk menempatkan kegiatan tersebut di suatu daerah per-kotaan yang relatif kecil. Suatu daerah metropolitan yang besar se-perti kota New York dan Tokyo dapat menyediakan tenaga ahli yang lebih spesialistis yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan da-gang raksasa. Ditunjang dengan perpustakaan teknik yang memiliki koleksi lengkap buku-buku dan jurnaljurnal ilmu teknik yang sa-ngat relevan. Demikian pula dalam hal fasilitas hukum, administrasi perusahaan, berbagai fakultas dalam struktur perguruan tinggi, fasilitas reparasi yang spesialistis, pelayanan jasa dan alat-alat rumah tangga yang tidak terdapat di semua tempat atau kota, dan me-nawarkan berbagai barang berkualitas tinggi. Jika penghematan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap pengembangan dan pertumbuhan kota, maka sebaliknya pemboros-an urbanisasi dan penghematan deglomerasi bersifat membatasi pertumbuhan, misalnya kongesti lalu lintas. Kongesti lalu lintas mengakibatkan waktu perjalanan bertambah lama, demikian pula ketidaknyamanan fisik, ketegangan, dan ketidakpastian umum. Banyak ilmu sosial menyusun hipotesis bahwa masyarakat menjadi kurang manusiawi, tingkat kriminalitas dan kecemasan sosial meningkat bersamaan dengan pertumbuhan kota. Akhir-akhir ini telah dikemukakan mengenai betapa bahayanya ancaman-ancaman di daerah perkotaan, yakni pencemaran udara, pencemaran air, buangan-buangan sampah solid, dan kebisingan suara, yang harus ditanggulangi secara menyeluruh. BAB 5 TEORI TEMPAT SENTRAL (CENTRAL PLACE THEORY) 1.1 SUSUNAN HERARKI PUSAT SECARA SPASIAL Teori tempat sentral (central place theory) diintroduksikan oleh 7 Christaller (ahli ilmu bumi, 1933) yang kemudian diperluas oleh August Losch (ahli ekonomi, 1944). Teoriteori tersebut di atas telah merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatankegiatan produksi dan daerah-daerah perkotaan secara herarkis. Menggunakan asumsi-asumsi yang hampir sama di antaranya wilayah model merupakan dataran yang homogen, penduduk dan enaga belinya tersebar merata di seluruh wilayah. Christaller dan Losch menjelaskan susunan pusat-pusat secara spasial. Obyek pembahasan mereka dapat dikatakan sama yaitu menyoroti persoalan-persoalan lokasi dan distribusi pengelompokan kegiatan-kegiatan ekonomi secara geografis. Meskipun keduanya tidak memperhatikan adanya penghematan eksternal. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan, baik dalam lingkup dan cara pandang yang dikembangkan. Pertama, Christaller mengembangkan modelnya dari atas atau skala besar (nasional). Menurut Christaller, setiap wilayah per-dagangan heksagonal berbentuk segi enam, lihat Gambar 5.1.A memiliki pusat; besar-kecilnya pusat-pusat tersebut adalah seban-ding dengan besar-kecilnya masing-masing wilayah heksagonal. Wilayah heksagonal yang terbesar memiliki pusat yang paling besar, sedangkan wilayah heksagonal yang terkecil memiliki pusat yang paling kecil. Dalam keseimbangan jangka panjang, seluruh wilayah heksagonal yang besarnya berbeda-beda sudah mencakup dan saling bertindih satu sama lain. Susunan herarki ini membentuk model pola pemukiman sistem K=3. Secara horisontal, model Christaller menunjukkan kegiatan-kegiatan manusia yang tersusun dalam tata ruang geografis. Tempat-tempat sentral (pusat-pusat) yang lebih tinggi ordenya mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas. Tempattempat sentral kecil dan wilayah-wilayah komplementernya tercakup dalam wilayah-wilayah perdagangan dari pusat-pusat yang lebih besar. Secara vertikal, model tersebut memperlihatkan keterkaitan dalam pelayanan antara tempat sentral yang lebih tinggi ordenya dan tempat-tempat sentral yang lebih rendah ordenya. Sedangkan Losch mengembangkan modelnya mulai dari bawah yaitu wilayah spasial yang tersempit ruang lingkupnya. Mulamula wilayah per-dagangan berbentuk wilayah pasar sederhana, kemudian ber-kembang menjadi suatu jaringan wilayah pasar, dan akhirnya mem-bentuk sistem wilayah pasar (lihat Gambar 5.2.A sampai dengan gambar 5.2.C). Kedua, barang yang diperdagangkan dalam kedua model tersebut berbeda tipenya. Barang-barang yang digunakan dalam model Losch termasuk dalam golongan barang-barang yang dapat diangkut (transportable commodities). Sedangkan model Christaller menekankan pada jasa-jasa yang tidak mobil (immobile service). Jasa-jasa tersebut untuk melayani distribusi barang-barang (nasional) yang diproduksi hanya pada pusat-pusat sistem. Model susunan spesial yang dikembangkan oleh Losch berdasarkan pada industri-industri sekunder dan terjadinya pola spsialisasi merupakan kasus normal. Bila demikian halnya, maka model Losch dan Christaller dapat dipandang sebagai saling melengkapi satu sama lainnya. Yang pertama menjelaskan susunan spasial pada kegiatan-kegiatan sekunder dan yang kedua berorientasi pada kegiatan-kegiatan jasa. Ketiga, model Christaller menganalisis susunan spasial baik dari segi mikro maupun dari segi makro. Analisis dari segi mikro adalah mengenai distribusi produksi barang-barang secara indi-vidual, dan analisis segi makro menyangkut disribusi aglomerasi, sedangkan model Losch tidak menganalisis susunan spasial secara makro atau agregatif. Karya Losch bukan merupakan susunan spasial yang overall, tetapi lebih merupakan model-model lokasi spesialisasi spasial dan perdagangan barang-barang individual dari pada sebagai model susunan spasial secara kebulatan. Spesialisasi spasial dapat dijelaskan bahwa tidak perlu semua barang diproduksikan pada pusat yang lebih unggul (superior). Menurut model Christaller, pusat-pusat yang lebih tinggi orde-nya melayani pusatpusat yang lebih rendah ordenya, sedangkan menurut Losch pusat-pusat yang lebih kecil melayani pusat yang lebih besar. Meskipun model-model di atas tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, tetapi pembahasan masalah wilayah nodal ter-utama mengenai proses respons nodal yang dikemukakan dalam kerangka dasar tempat sentral memberikan manfaat yaitu menggam-barkan terjadinya hubungan antar pusat dan antar tingkat. Respons nodal menunjukkan ciri bahwa pertumbuhan kegiatan di suatu pusat adalah untuk melayani penduduk di daerah belakang (hinterland). Jika pertumbuhan terjadi di daerah belakang, misalnya dalam bidang pertanian, maka melalui pola suplai hasil-hasil produksinya akan mendorong pertumbuhan di pusat perkotaan. Proses ini berlangsung melalui multiplier intra regional dan mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan struktural di pusat. Gejala ini memperkuat keuntungan-keuntungan aglomerasi. Pendirian industri-industri baru meningkat, demikian pula dalam kegiatan-kegiatan industri substitusi barang impor, produksi perantara, dan lapangan kerja. Dalam keadaan ini dorongan pertumbuhan daerah perkotaan tidak berasal dari daerah belakang. Menurut teori tempat sentral, fungsi-fungsi pokok pusat perkotaan berorientasi pada permintaan penuduk daerah belakang. Tetapı kasus di atas ternyata berorientasi pula pada suplai dari daerah belakang. (H.W. Richardson, 1971, 93). 1.2 GEJALA DINAMIS DAN PERTUMBUHAN WLAYAH Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala (fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori tersebut dapat dikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentral mampu menjelas-kan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salah satu di ataranya adalah teori Perroux (kutub pertumbuhan) yang membahas perubahan-perubahan struk-tural pada tata ruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempat sentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan. Teori tempat sentral sebagian bersifat positif karena berusaha menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa, dan sebagian lagi ber-sifat normatif karena berusaha menentukan pola optimal distribusi tempat-tempat sentral. Teori tempat sentral mempunyai kontribusi pada pemahaman interrelasi spasial dan kota-kota sebagai sistem di dalam sistem perkotaan. Teori tempat sentral tidak memberikan penjelasan secara leng-kap mengenai pertumbuhan kota karena teori tersebut diformulasi-kan berdasarkan pembangunan daerah pertanian yang tersusun secara herarkis dan berpenduduk merata. Dengan tumbuhnya kotakota maka muncullah jasa-jasa yang tidak berkenaan dengan pasar wilayah belakang. Sebagai contoh kehidupan kota metropolitan da-pat menciptakan kebutuhan-kebutuhan sendiri (internal), misalnya peningkatan penyediaan fasilitas penyediaan air minum, listrik, angkutan umum, demikian pula kebutuhan fasilitas parkir. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pertumbuhan kota ter-nyata tidak sesederhana seperti persoalan pemasaran barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh tempat sentral. Analisis tempat sentral menekankan pada peranan sektor perdagangan dan kegiatan-kegiatan jasa daripada kegiatan-kegiatan manufaktur. Kegiatan manufaktur dianggap sebagai kegiatan produktif non tempat sentral. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kota-kota besar dan kota-kota lainnya seringkali mengalami perluasan dalam hal lokasi manufaktur karena kota-kota yang bersangkutan merupakan pasar tenaga kerja yang luas dan pada umumnya memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi, dimana perusahaan-perusahaan manufak-tur lebih banyak melayani pasar nasional dari pada pasarpasar re-gional. Model tempat sentral ternyata tidak berhasil menjelaskan timbulnya kecenderungan yang kuat dalam masyarakat mengenai pengelompokan perusahaanperusahaan karena pertimbangan keuntungan-keuntungan aglomerasi dan ketergantungan. 1.3 TIGA KONSEP FUNDAMENTAL Meskipun model tempat sentral mempunyai keterbatasan-keterbatasan, namun sesungguhnya teori tempat sentral mengan-dung paling sedikit tiga konsep fundamental (H.W. Richardson, 1969. 72), yaitu konsep ambang (threshold), lingkup (range), dan herarki (hierarchy). Proses penyebaran pertumbuhan mengikuti pola ambang (jumlah penduduk) dan pola lingkup (sistem lokasi). Kedua faktor tersebut menentukan herarki tempat sentral. Konsep-konsep ini merupakan unsur-unsur susunan spasial yang penting dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan formal permin-taan dan wilayah-wilayah perdagangan atau wilayah-wilayah pelayanan. 1.4 SUMBANGAN POSITIF TEORI TEMPAT SENTRAL Sumbangan positif teori tempat sentral adalah bahwa teori tersebut relevan bagi perencanaan kota dan wilayah, karena sistem herarki merupakan sarana yang efisien untuk perencanaan wilayah. Tempat sentral besar seringkali merupakan titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke seluruh wilayah. Dengan demikian jelaslah bahwa distribusı tata ruang dan besarnya pusat-pusat kota merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur wilayah-wilayah nodal dan kemudian me-lahirkan konsep-konsep dominasi dan polarisasi. Teori tempat sentral mengemukakan model yang mudah dimengerti untuk menjelaskan pertumbuhan herarki kota dan ketergantungan antara pusat-pusat kota dan wilayah-wilayah di sekitarnya. BAB 6 TEORI KUTUB PERTUMBUHAN 1.1 PEMBANGUNAN TIDAK TERJADI DI SEMUA TEMPAT Sebagaimana diketahui bahwa potensi i dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda-beda satu sama lainnya, demikian pula masalah pokok yang dihadapinya tidak sama. Sehingga usaha-usaha pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronisasikan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Analisis ekonomi pada umumnya hanya cenderung menekan-kan pada masalah "berapa besar" sumberdaya tertentu yang akan dialokasikan untuk mencapai suatu tujuan, tanpa mempertimbangkan masalah yang menyangkut "dimana" usaha tersebut akan ditempatkan. Beberapa ahli ekonomi seperti Friedmann dan Alonso telah mengemukakan pendapatnya mengenai betapa pentingnya masalah penentuan lokasi proyek baru akan ditempatkan. Masalah keadilan sosial (social justice) di samping manfaat pembangunan ekonomi. Hal ini sangat penting akan tetapi sulit diukur. Teori lokasi klasik ternyata tidak berlaku secara sempurna, ka-rena beranggapan bahwa semua kegiatan berlangsung diatas per-mukaan (surface) yang sama, perbedaan geografis dianggap tidak ada, fasilitas transportasi terdapat ke segala jurusan, bahan mentah (baku) industri, pengetahuan teknis dan kesempatan produksi adalah seragam (uniform) di seluruh wilayah. Sebagai akibat dari ketidak-sempurnaan pendekatan klasik tersebut, maka kemudian timbullah pemikiran baru yaitu teori kutub pertumbuhan (growth pole atau pole de croisance). Teori ini pertama kali dilontarkan oleh pencetus-nya yaitu Francois Perroux, seorang ahli ekonomi Perancis. Ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua wilayah, akan tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya. Mengikuti pendapat Perroux tersebut, Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, ter-dapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pu-sat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (growth point atau growth pole). Konsep kutub pembangunan atau pusat pertumbuhan sudah dipakai banyak negara. Di Perancis konsep ini mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan di negara-negara lain. 1.2 KUTUB PEMBANGUNAN DAN INDUSTRI PENDORONG Menurut Perroux terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lain-nya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (geografic space and space dimension). Perusahaan-perusahaan yang menguasai dominasi ekonomi tersebut pada umumnya adalah in-dustri besar yang mempunyai kedudukan oligopolistis dan mem-punyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan para langgan-annya. Pandangan Perroux mengenai proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (economic space theory), dimana industri pendorong (propulsive industries atau industries motrice) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya. Nampaknya Perroux lebih me-nekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan. Meskipun ada beberapa perbedaan penekanan arti industri pendorong, akan tetapi ada tiga ciri dasarnya yang dapat disebutkan, yaitu sebagai berikut. 1. Industri pendorong harus relatif besar kapasitasnya agar mem-punyai pengaruh yang kuat, baik langsung maupun tidak lang-sung terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Industri pendorong harus merupakan sektor yang berkembang dengan cepat. 3. Jumlah dan intensitas hubungannya dengan sektor-sektor lain-nya harus penting sehingga besarnya pengaruh yang ditimbul-kan dapat diterapkan kepada unit-unit ekonomi lainnya. Dilihat secara tata ruang geografis, industri-industri pendorong dan industri-industri yang dominan mendorong terjadinya aglo-merasi-aglomerasi pada kutub-kutub pertumbuhan dimana mereka berada. Jelaslah bahwa industri pendorong mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini pertama kali ditekankan oleh Perroux, kemudian diikuti oleh teman sekolahnya Bauchet, yang menulis bahwa pertumbuhan daerah-daerah yang kurang maju tergantung pada kegiatan dari unit-unit ekonomi yang besar. Industriindusitri besar akan mampu meletakkan dasar per-tumbuhan pendapatan ekonomi bagi daerahnya. Demikian pula Davin mempertahankan pendapatnya bahwa pusat utama pertumbuhan ekonomi terdapat pada tempat-tempat yang memiliki industri berat dan berkapasitas tinggi, dan industri kimia. Setelah menjelaskan beberapa pendapat ahli seperti dikemuka-kan diatas, maka dapat pula dikemukakan bahwa pada umumnya industri pendorong adalah produsen external economies (penghematan eksternal ekonomi), industri pendorong yang memberikan penghematan-penghematan ekonomi bagi perkembangan industri-industri lainnya, Aydalot menyebutkan industri mobil, Regie Renault (nama pemilik pabrik mobil terkenal di Perancis) sebagai pengusaha pendorong. Bila dihubungkan dengan segi masukan-keluaran (inputoutput), maka dapat dikatakan bahwa Renault merupakan suatu kutub yang berpusat di Paris dan daerah pemasarannya tersebar di seluruh dunia. 1.3 BEBERAPA KRITIK Salah satu dasar teori kutub pertumbuhan ekonomi adalah ide yang menjelaskan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai sumber dan mendapat rangsangan yang terus menerus dari kegiatan industri besar. Pada dasarnya pemikiran semacam ini berasal dari teori dominasi. Beberapa kritik terhadap teori kutub pertumbuhan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa besarnya suatu indsutri itu sendiri tidak cukup menjamin pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dapat disebutkan suatu industri besi di Lorraine (Perancis), dimana pembangunan industri tersebut tidak diikuti oleh pembangunan industri-industri lainnya yang membutuhkan besi ersebut sebagai masukannya. Akhirnya Lorraine menjadi sangat tergantung pada daerah lain, suplai mesin-mesin dan peralatan terpaksa didatangkan dari luar. Contoh lain di daerah Lyon yang berbeda dengan pengalaman Lorraine. Lyon secara ekonomis cocok untuk industri tekstil. Pada saat yang sama dibangun pula industri kimia yang ternyata lebih berkembang dan menjadi lebih penting sebagai kutub pertumbuhan. Kedua, dalam konsep pertumbuhan tidak seimbang (unba-lanced growth) Hirschman telah memperkenalkan kegiatan-kegiatan pendorong (propulsive). Investasi dalam industri yang strategis akan menimbulkan kesempatan investasi baru dan memperkuat pem-bangunan ekonomi selanjutnya. Suatu investasi yang besar dalam social overhead capital akan menimbulkan dorongan investasi swasta dalam kegiatan produktif secara langsung (direct productice activi-ties). Aydolt menunjukkan walaupun telah dicoba untuk meng-gabungkan konsep unbalanced growth dengan teori growth pole, akan tetapi hasilnya tidak sukses. Misalnya di negara-negara Afrika, industri-industri pendorong tidak mampu memenuhi peranannya karena negara-negara yang baru saja mebangun itu menghadapi persoalan yang sama dengan negara-negara yang telah maju, selain dari pada itu jumlah wiraswasta (enterpreneur) masih belum cukup tersedia. Ketiga, kedudukan industri pendorong seringkali diartikan terlalu berlebihan (overestimated). Boudeville mengemukakan contoh keadaan di Denmark. Negara tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai suatu wilayah yang independen dimana proses pertumbuhan ekonominya dapat berkembang cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemakmuran negara tersebut tidak dimulai oleh industri-industri pendorong, akan tetapi didukung oleh usaha-usaha kooperatif dari unit-unit usaha pertanian kecil yang tersebar di seluruh negeri. Keempat, teori kutub pertumbuhan tidak memberikan pen-jelasan yang memuaskan mengenai proses aglomerasi, yaitu terkon-senstrasinya industri-industri pada suatu daerah. Vernon memper-lihatkan bahwa industri-industri tertarik berkonsentrasi di suatu tempat oleh karena penghematan eksternal yang diberikan oleh kota-kota besar, bukan karena sifat-sifat oligopolistis industri pendorong. Banyak industri kecil dan menengah berkonsentrasi di suatu tempat disebabkan karena ketergantungan pada jasa bisnis perantara dan adanya keperluan untuk mengadakan kontak yang harus dilakukan dengan langganannya, antara para pembeli dan penjual. Walaupun kutub-kutub pertumbuhan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perkembangan daerah-daerah di sekitarnya, akan tetapi teori kutub pertumbuhan dapat dikategorisasikan sebagai teori tanpa tata ruang (spaceless), karena teori tersebut tidak menjelaskan tentang pemilihan lokasi optimum suatu industri atau per-usahaan. Mengikuti pendapat Perroux, Boudeville mendefinisikan ku-tub pembangunan wilayah sebagai seperangkat industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan men-dorong lebih lanjut perkembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya (localized development pole). Teori Boudeville dapat di-anggap sebagai pelengkap terhadap teori tempat sentral yang di-formulasikan oleh Christaller dan kemudian diperluas oleh Losch. Boudeville mengemukakan aspek "kutub fungsional" dan memberi-kan pula perhatian pada aspek geografis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teori Boudeville telah menjembatani terhadap teori-teori spasial yang terdahulu, yang menekuni persoalan susunan kegiatan-kegiatan pada tata ruang. 1.4 KEGAGALAN DAMPAK PERTUMBUHAN KE WILAYAH PENGARUH Pada dasa warsa pertama pertengahan abad ke-20 (dekade 50-an) muncul teori-teori yang menyatakan pentingnya peranan pusat-pusat pertumbuhan/pembangunan, di antaranya adalah (1) teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) yang diintodusirkan oleh Francois Perroux, (2) teori kutub pembangunan yang terlokalisası (localized development pole theory) yang dilontarkan oleh Boude ville, (3) teori titik pertumbuhan (growth point theory) yang dikemukakan oleh Albert Hirschman. Masih banyak istilah lain mengenai peranan pusat pertumbuhan (pembangunan), mulai dari growth centre, development centre, growing centre, developing cen-tre, growth point development nuclei, sampai pada service centre dan simpul jasa distribusi (Poernomosidi Hadjisaroso). Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke wilayah pengarun di sekitarnya, Albert Hirscman telah memperkenalkan istilah trickling down effect (atau dampak tetesan ke bawah). Pengalaman selama ini, teori kutub pertumbuhan dianggap gagal karena tidak berhasil membuktikan terjadinya dampak tetesan ke bawah secara lugas. Gejala ini disebabkan karena pusat pertum-buhan yang umumnya adalah kota-kota besar ternyata sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial adalah cukup kuat, sehingga terjadi tarikan urbanisasi dari desa-desa dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan (kota besar), atau terjadi dampak polarisasi. Yang dinamakan dampak polarisasi itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan dampak tetesan ke bawah. Dampak polarisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pengaruh yang oleh Gunnar Myrdal disebut backwash effect. Jadi pandangan Hirschman yang optimistik namun dampak tetesan ke bawah ternyata menunjukkan kegagalan, sedangkan dam-pak pengurasan yang dikemukakan oleh Myrdal yang pesimistik itu banyak terjadi di berbagai wilayah. Kegagalan teori kutub pertumbuhan dapat ditunjukkan pula oleh strategi kebijaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah (pusat dan daerah) lebih banyak diarahkan pada wilayah perkotaan. Maka akibatnya kota yang relatif sudah besar itu di-tumpuki dengan investasi prasarana perkotaan, utilitas perkotaan, dan fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial. Pembangunan berbagai infrastruktur, utilitas, dan fasilitas pelayanan perkotaan yang terus meningkat akan menimbulkan kepadatan, kemacetan, dan polusi, maka perlu dibangun berbagai fasilitas untuk mengatasi dan me-nanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan. Wilayah pengaruh atau wilayah belakang menjadi terabaikan dan tetap tertinggal, akibatnya terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang semakin tajam antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya. 1.5 SUNTIKAN DANA DAN INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH PENGARUH Salah satu sasaran utama dari pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan atau ketimpangan regional dan spasial (tata ruang). Kesenjangan terjadi antara perkotaan dan pedesaan, antar desa dalam lingkup suatu wilayah. Kesenjangan antara pusat pertumbuhan dengan wlayah pengaruhnya cenderung bertambah lebar. Hal ini berarti implementasi dari strategi kebijaksanaan kutub pertumbuhan dianggap gagal. Teori kutub pertumbuhan sebagai suatu teori tetap diperlukan karena fungsinya suatu kutub pertumbuhan itu sangat diperlukan sebagai penggerak utama pertumbuhan terhadap wilayah di sekitar-nya. Yang keliru sebenarnya adalah pelaksanaan dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang memberikan porsi terlalu ber-lebihan pada pembangunan perkotaan. Bagaimana upaya memperbaiki atau mengkoreksi terhadap kegagalan tersebut. Rahardjo Adisasmita dalam disertasinya yang berjudul "Pengkajian Teori Simpul Jasa Distribusi melalui Jasa Perdagangan" (1987) dibawah bimbingan mantan Mentri Pekerjaan Umum RI, Bapak Prof. DR. Ing. Poernomosidi Hadjisaroso (sekarang sudah almarhum), penulis mengintrodusksi suatu konsep tandingan terhadap dampak tetesan ke bawah, yaitu dampak "Suntikan Dana Investasi kepada Wilayah Pengaruh" atau Capital Injection to Influence Region. Dasar-dasar pemikirannya adalah sebagai berikut. Keterkaitan ekonomi dan pembangunan antara kota sebagai pusat petumbuhan dan wilayah pengaruh di sekitarnya harus ditingkatkan. Pembangunan wilayah pengaruh yang dilakukan harus berorientasi pada penawaran (supply side), yaitu tersedia-nya sumberdaya yang cukup potensial dan harus pula berorien-tasi pada permintaan (demand side) agar menjadi lebih seimbang antara sisi produksi dan sisi pasar. Di wilayah pengaruh yang memiliki sumberdaya yang potensial dan prospek pasar yang kuat, agar dibangun proyek-proyek (investasi fisik) yang mampu menciptakan (a) comparative adventage, (b) marketability, dan (3) sustainability. Untuk mengetahui jenis program dan proyek pembangunan yang akan dikembangkan secara tepat dan layak, maka pelibatan partisipasi masyarakat lokal harus diberdayakan, karena anggota masyarakat lokal itu dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya (pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat). Suntikan kepada wilayah pengaruh, selain dalam bentuk inves-tasi fisik, misalnya sub sektor tanaman pangan yang didukung oleh prasarana irigasi, jalan desa dan perkebunan, perlu di-dukung oleh pengembangan, penguatan dan tumbuhnya "motivasi masyarakat lokal" sebagai kekuatan pendukungnya. Dengan pengembangan partisipasi dan penguatan motivasi masyarakat lokal tersebut, diharapkan akan dapat menjamin terimplementasikannya program pembangunan dengan baik, mulai dari pemilihan jenis program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasinya, dan pengawasannya akan terjamin keberhasilannya. Dengan memperhatikan pembangunan program tersebut, di-harapkan produksi dan produktivitasnya dapat mencapai ting-kat keunggulan komparatif, pemasaran menjadi lebih terjamin dan cukup besar. Hal ini berarti pendapatan masyarakat lokal meningkat, memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk membeli barang-barang yang dihasilkan daerah perkotaan, sehingga ke-terkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah pengaruh dan pusat-nya berlangsung secara timbal balik dan akan menjadi lebih interaktif, intensif, responsif, dan menjadi relatif berimbang, serta bersifat saling menguntungkan dan berkelanjutan BAB 7 TEORI PEMBANGUNAN POLARISASI 1.1 KERANGKA DASAR TEORI Perencanaan pembangunan wilayah mempunyai berbagai aspek perubahan yang dilaksanakan secara berencana dan terkoor-dinasi dilihat dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional. Fokus dari perencanaan wilayah adalah pencapaian sasaran - sasaran sub sistem kemasyarakatan nasional yang terorganisasi secara teritorial atau spasial. Meskipun dalam praktek perencanaan wilayah telah banyak dimaklumi, akan tetapi dalam hal ini perlu diberikan penjelasan mengenai dasar-dasar teorinya, terutama mengenai keterhubungannya secara sistematis antara pembangunan dan tata ruang, atau dengan perkataan lain mengenai proses pembangunan dalam dimensi spasialnya. Beberapa teori telah menjelaskan kono-tasinya secara umum, akan tetapi teori-teori tersebut kurang me muaskan sebagai suatu kerangka dasar analisis untuk perencanaan pembangunan wilayah. Teori lokasi klasik (classical location theory) menjelaskan tentang lokasi optimum suatu perusahaan atau industri. Dewasa ini telah dikembangkan meliputi analisis industrial complex (kompleks industri), yang kemudian melahirkan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) seperti yang diformulasikan oleh Francois Perroux, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Perancis, dan ahli-ahli ekonomi lainnya. Ditinjau dari perspektif perencanaan wilayah teori lokasi klasik dianggap tidak sempurna oleh karena teori tersebut lebih memfokuskan pada lokasi titik kegiatan-kegiatan ekonomi dari pada sistem wilayah atau tata ruang (spasial). Kaitan antara lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi (teori mikro) dan pembangunan suatu sistem wilayah (teori makro) belum dikemukakan secara jelas. Teori organisasi spasial (spatial organization theory) telah diintroduksikan sebagai dasar untuk perencanaan wilayah. Teori ini menekankan pada karakteristik struktural suatu sistem lokasi titik-titik kegiatan ekonomi. Teori spasial ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) dan bila dibandingkan dengan teori lokasi klasik telah memperlihatkan suatu kemajuan. Walaupun demikian masih kurang memuaskan oleh karena teori ini menggunakan model keseimbangan umum (general equilibrium). Teori ini dapat menjelaskan pola-pola lokasi kegiatan ekonomi pada dua titik periode yang berbeda. Namun demikian teori ini tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap pengertian proses dimana transformasi historis sistem spasial terjadi. Dalam teori pertumbuhan wilayah (regional growth theory), suatu usaha telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan teori lokasi klasik dan menjelaskan dinamika sistem spasial. Dalam ke-lompok ini terdapat dua macam teori yang berbeda fokus analisisnya. Pertama adalah teori yang menekankan pertumbuhan wilayah pada wilayah-wilayah individual. Analisisnya secara tegas mengkonsen-trasikan pada kasus wilayah tunggal. Kedua yaitu teori yang lebih mengelaborasikan dinamika pada suatu sistem wilayah. Teori ini cenderung kembali pada formulasi keseimbangan umum, dimana arus antar wilayah tenaga kerja dan modal dipandang sebagai me-kanisme utama untuk membentuk kembali suatu keseimbangan yang telah mengalami gangguan. Mekanisme teori ini dapat dikata-kan lebih unggul atau superior dibandingkan dengan teori-teori ter-dahulu sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan wilayah, akan tetapi masih mengalami pula keterbatasan, oleh karena kurang menjelaskan pertumbuhan secara nasional. Di antara buku-buku teks (teks books) mengenai pertumbuhan wilayah, John Friedmann berpendapat bahwa Horst Siebert termasuk salah seorang pakar yang mempunyai pandangan komprehensif karena telah memformulasikan model-model yang menyangkut wilayah individual dan sistem wilayah. Meskipun ia seorang ahli ekonomi, Siebert telah mengembangkan topik-topik yang penting seperti pengetahuan teknik, difusi inovasi dan komunikasi seperti yang banyak dibahas sekarang. Masyarakat terorganisir secara spasial dalam arti kata bahwa aktivitas manusia dan interaksi sosial membentuk tata ruang dan bagian-bagian tata ruang. Masyarakat yang melaksanakan pem-bangunan, struktur sosialnya mengalami proses transformasi dan proses pembangunan akan dipengaruhi juga oleh pola-pola hubung-an spasial dan keteganganketegangan dinamis. Dalam hubungan ini tata ruang dilihat dalam arti non fisik, yaitu merupakan arena kekuatan (misalnya tingkat energi, kekuasaan mengambil keputusan, dan komunikasi) yang mengikuti hukum transformasinya tersendiri. Dalam kaitannya dengan teori perubahan sosial dapat di-kemukakan terdapat dua kelompok utama, yaitu teori Everet Hagen dan teori Ralph Dahrendorf. Teori Hagen berlandaskan pada psiko-logi individual dan sukar diintegrasikan dengan teori organisasi spasial. Dahrendorf menggunakan model konflik perubahan sosial, dimana variabel utamanya adalah authority - dependency relation-ship yang memperlihatkan ciri sistem sosial yang terorganisir. Berdasarkan hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pusat utama yang sering disebut core region (wilayah inti) merupakan suatu sub sistem masyarakat yang tersusun secara teritorial yang memiliki kapasitas tinggi untuk perubahan inovatif. Sedangkan wilayah di sekelilingnya (periphery regions) merupakan pula sub sistem dimana perkembangan pembangunannya ditentukan utamanya oleh lembagalembaga di core region. Daerah core dan periphery bersama-sama membentuk suatu sistem spasial yang lengkap. Karena sistem spasial adalah sistem hubungan masyarakat yang tersusun secara teritorial, maka model Dahrendorf dapat dianggap sebagai harapan awal untuk memformulasikan teori umum pembangunan polarisasi. Polarisasi berarti suatu konsentrasi kelompok-kelompok, ke-kuatan-kekuatan, atau kepentingan-kepentingan mengenai beberapa keadaan yang berlainan dan bertentangan. 1.2 PEMBANGUNAN DAN INOVASI Kemajuan historis dapat dipandang sebagai sukses temporal dari sebuah paradigma sosio-kultural dan seterusnya disusul oleh sukses-sukses lainnya. Sesuai dengan interpretasi di atas, pem-bangunan merupakan suatu proses yang diskontinyu dan kumulatif yang terdiri dari serangkaian inovasi-inovasi dasar yang tersusun dalam kelompok-kelompok inovasi dan akhirnya membentuk sistem inovasi skala besar. Inovasi dapat berbentuk secara teknis atau instiusional, dan bila termasuk yang terakhir (institusional) dapat dikategorikan secara sosial, politis dan kultural. Dilihat dari sistem kemasyarakatan, pertumbuhan seyogyanya dibedakan dengan pembangunan. Pertumbuhan menunjukkan suatu pengembangan sistem dalam satu dimensi atau lebih tanpa suatu perubahan dalam strukturnya. Sedangkan pembangunan berhubungan dengan bentangan kemungkinan kreatif yang inherent dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi hanya bila pertumbuhan tersebut diikuti oleh serangkaian transformasi struktural yang sukses dari sistem tersebut. Masyarakat yang gagal melaksanakan transformasi menjadi terhambat dalam pertumbuhannya atau mengalami kemunduran dimana terjadi ketidakstabilan semakin bertambah besar. Pem-bangunan selalu terjadi melalui proses yang tidak sinkron dalam mana kekuatan inovatif tumbuh dari atau diinjeksikan ke dalam suatu sistem masyarakat yang ada. Pengaruh kumulatif dari inovasi yang sukses dapat dilihat dengan munculnya personalitas yang kreatif dan inovatif yang mampu melaksanakan perubahan yang akseleratif dengan beberapa cara, misalnya keberanian menciptakan nilai-nilai baru, sikap dan perilaku yang konsisten dengan inovasi, serta kemampuan menciptakan lingkungan sosial yang favorable terhadap kegiatan inovatif. Inovasi mungkin didasarkan pada ide-ide atau prototipe-prototipe yang telah ditemukan, atau dipinjam, ataupun ditiru. Apa yang telah dilaksanakan di suatu negara dapat dilaksanakan di wilayah lain dengan cara meminjam atau imitasi menjadi suatu inovasi. Setiap inovasi memerlukan suatu organisasi dan adaptasi terhadap keadaan dan persyaratan fungsional dari sarana-sarana yang diintroduksikan. Jadi inovasi dan sarana harus dapat digabungkan secara struktural. Inovasi memerlukan individu-individu atau institusi-institusi yang akan memanfaatkan sumberdaya yang penting dan berani menanggung risiko atau kegagalan dari setiap inovasi, atau dengan perkataan lain yaitu diperlukan pelaksana atau pelaku yang inovatif. Keberhasilan kegiatan inovatif akan tergantung pada beberapa kondisi utama, di antaranya adalah sebagai berikut. 1) Anggapan atau sikap yang sifatnya menentang atau tidak puas terhadap pengunaan sarana-sarana tradisional 2) Kapasitas sistem sosial yang ada untuk menyerap inovasi yang diusulkan tanpa melakukan perubahan strutktural yang utama. 3) Tersedianya personalitas yang inovatif dalam suatu masyarakat tertentu. 4) Kemampuan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya material untuk menunjang inovasi yang efektif. 5) Balas jasa masyarakat yang diberikan untuk mengembangkan kegiatan inovatif. 1.3 PEMBANGUNAN POLARISASI DALAM HERARKI SISTEM SPASIAL Wilayah-wilayah inti atau core regions terletak dalam herarki sistem spasial. Sistem spasial dapat merupakan dunia, wilayah multi-nasional, bangsa, wilayah sub nasional, dan propinsi. Suatu wilayah membentuk suatu sistem spasial. Hal ini tergantung pada pola hubungan internalnya. Suatu core atau pusat mendominasi dalam beberapa keputusan penting dari penduduk di wilayah-wilayah di luar wilayah inti. Dalam suatu sistem spasial tertentu mungkin terdapat lebih dari satu wilayah inti yang berbentuk kota, kota besar, metropolis atau megalopolis. Pada umumnya wilayah inti melak-sanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Ada kemungkinan beberapa wilayah inti memperlihatkan fungsinya yang khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan dan sebagainya. Ada beberapa gejala utama sehubungan dengan peranan wilayah inti dalam pembangunan sistem spasial, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. 1.Wilayah inti mengatur keterkaitan dan ketergantungan wilayah-wilayah di sekitarnya melalui sistem suplai, pasar dan daerah administratif. 2. Wilayah inti meneruskan dengan sistematis dorongan inovası ke wilayahwilayah di sekitarnya yang berada dalam jangkauan-nya. 3. Sampai pada suatu titik waktu tertentu ciri self reinforcing per-tumbuhan wilayah inti akan cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial. Akan tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pengaruh pembangunan wilayah inti kepada wilayah-wilayah di sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga keterkaitan dan ketergantungan wilayah-wilayah di sekitarnya terhadap wilayah inti menjadi berkurang. 4. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh wilayah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran infor-masi. Jelaslah kiranya bahwa wilayah inti, pusat-pusat pelayanan (service poles) atau tata ruang-tata ruang ekonomi (economic space) mempunyai peranan dan fungsi yang dominan dan menentukan terhadap perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Di wilayah inti terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi, pemukiman penduduk, dan tersedianya fasilitas-fasilitas dan kemudahan lainnya yang mempunyai pengaruh pancaran pengembangan terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada dasarnya teori pertumbuhan ekonomi wilayah adalah variant dari teori lokasi klasik. Pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah tunggal biasanya dikaitkan dengan beberapa sumberdaya alamiah yang tidak mobil yang memperoleh banyak permintaan dari wilayahwilayah lain. Investasi tertarik ke wilayah tersebut untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimaksud, yang lama kelamaan wilayah tersebut menjadi wilayah pusat produksi yang menciptakan penghematan eksternal yang berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi wilayah pada tingkat sub nasional dalam jangka panjang tergantung pada partisipasi sektor-sektor yang berkembang dari seluruh total perekonomian. Akhirnya secara umum perlu diperhatikan yaitu bila terjadi ketidakserasian pada beberapa wilayah atau lokasi. Maka hal ini akan diseimbangkan melalui aliran atau arus tenaga kerja dan modal dari wilayah surplus ke wilayah - wilayah defisit. BAB 8 WILAYAH SEBAGAI SUATU ELEMEN STRUKTURAL SPASIAL 1.1 PROBLEMA UTAMA EKONOMI WILAYAH Ekonomi wilayah adalah suatu studi yang mempelajari perilaku ekonomi dari manusia di atas tata ruang. Studi ini manganalisis proses ekonomi dalam lingkungan spasial (mengenai tata ruang) dan menempatkan ke dalam struktur lansekap ekonomi (economic land-scape). Sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi tradisional telah ama tidak mau mengenal aspek spasial dari perilaku ekonomi. Model-model klasik dibuat berdasar pada asumsi bahwa kegiatan ekonomi terjadi pada satu titik waktu (one point) tanpa memperhitungkan dimensi spasial. Pertanyaan utama dari ekonomi klasik adalah berkisar pada what to produce, how to produce danfor whom to produce, yang artinya komoditas apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa komoditas tersebut diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisis tanpa memasukkan unsur jarak dan menganggap tidak ada biaya pengangkutan. Tantangan bagi ekonomi regional yakni dapat dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai gejala-gejala ekonomi akan menjadi lebih penting dan nyata apabila faktor tata ruang diintroduksikan sebagai suatu variabel tambahan dalam kerangka teori ekonomi. Secara eksplisit pertimbangan mengenai pentingnya dimensi tata ruang tersebut meliputi lima persoalan utama ekonomi wilayah. Pertama adalah yang berhubungan dengan penentuan lan-sekap ekonomi, yaitu mengenai penyebaran kegiatan ekonomi atas tata ruang. Dalam hubungan ini beberapa pertanyaan dapat di-kemukakan, misalnya faktor apa yang mempengaruhi lokasi kegiat-an individual? Bagaimana dapat dijelaskan penyebaran kegiatan produksi pertanian di atas suatu permukaan tanah yang luas? Hipotesis apa yang relevan untuk menentukan lokasi usaha tertentu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor tersier? Model apa yang dapat digunakan untuk menentukan perilaku spasial dari lokasi pemukiman? Bagaimana teori lokasi spasial dapat diintegrasikan dalam suatu sistem general? Bagaimana suatu daerah dapat dicirikan sebagai daerah pertanian atau daerah industri dan aglomerasi penduduk? Apakah ada ketergantungan antara pengambilan ke-putusan mengenai lokasi secara individual? Semua pertanyaan di atas berhubungan erat dan termasuk dalam bidang persoalan utama ekonomi wilayah yang pertama, yaitu persoalan penentuan lansekap ekonomi. Yang kedua berhubungan dengan diintroduksikannya konsep wilayah dalam analisis teoretis. Wilayah di sini diartikan sebagai sub sistem spasial dari ekonomi nasional. Konsep baru tersebut telah mendorong pembuatan rencana pembangunan sub sistem spasial dan pengukuran aktivitas ekonominya. Beberapa kriteria telah di-kembangkan untuk menentukan batas suatu wilayah, walaupun diakui bahwa hal ini bukan merupakan hal yang gampang. Persoalan yang ketiga adalah menganalisis interaksi antara daerah-daerah. Dapat dibedakan dua bentuk interaksi antar wilayah, yaitu (1) arus pergerakan faktor produksi dan (2) arus pertukaran komoditas. Penjelasan mengenai mengapa terjadi arus pergerakan faktor produksi dan komoditas, dan bagaimana pengaruhnya ter-hadap kegiatan ekonomi pada suatu wilayah itu merupakan titik sentral dalam studi permasalahan ekonomi. Dalam hubungan ini dapat diajukan beberapa pertanyaan, di antaranya: Mengapa faktor produksi berarus berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar wilayah? Keempat adalah persoalan analisis optimum atau equilibrium antar daerah. Model tipe ini mencoba menentukan beberapa sumber optimum untuk suatu sistem ekonomi dalam suatu lingkungan spasial. Keadaan optimum selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai seperti alokasi sumberdaya yang opti-mal menurut Pareto (Pareto optimum allocation of resources) atau minimisasi faktor masukan (input) tertentu. Beberapa pertanyaan dalam hubungan ini dapat dikemukakan, di antaranya mengenai arus transportasi yang optimal untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda. Spesialisasi produksi wilayah yang optimal dan pertukaran komoditas yang optimal antara wilayah-wilayah. Analisis equilibrium atau keseimbangan tidak membahas persoalan yang riil, akan tetapi memperinci pola optimal mengenai produksi, lokasi dan pertukaran antar wilayah. Akhirnya dapat dikatakan bahwa analisis optimum itu dapat dipandang sebagai pembahasan dan implikasi tujuan-tujuan tertentu. Kelima, yaitu persoalan kebijaksanaan wilayah. Kebijaksanaan ekonomi wilayah dimaksudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang ber-usaha memperhitungkan perilaku ekonomi dalam suatu lingkungan spasial. Kebijakan ekonomi wilayah berusaha mengontrol struktur dan proses ekonomi dalam sub sistem ekonomi nasional. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan, di antaranya yaitu sasaran apakah dari kebijaksanaan wilayah itu? Bagaimana sasaran-sasaran tersebut ditetapkan? Bagaimana sasaran kebijaksanaan wilayah tersebut diinterelasikan pada tujuan kebijaksanaan nasional, dan sebagainya. 1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara. Seringkali dipakai istilah lain yang mempunyai arti yang sama untuk pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi atau pengembangan ekonomi. Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu wilayah. Disini pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan suatu keluaran wilayah. Peningkatan ini meliputi baik kapasitas produksi ataupun volume riil produksi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai pening-katan dalam sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diper-oleh di suatu wilayah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagang-an yaitu dapat diperolehnya komoditas sebagai suplai hasil akhir yang meningkat melalui pertukaran antar wilayah. Kelima bidang persoalan utama ekonomi wilayah seperti telah dijelaskan di atas berkaitan erat dengan studi pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori pertumbuhan wilayah menganalisis bagaimana pertumbuhan terjadi dalam suatu lingkungan spasial yang meng gunakan wilayah sebagai kategori dasar. Perencanaan sub sistem dari ekonomi nasional adalah merupa kan prasyarat untuk teori pembangunan wilayah. Juga persoalan bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah harus dipercahkan. Lebih penting lagi bahwa teori pertum buhan wilayah harus menganalisis suatu wlayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komo-ditas. Dalam hubungan ini beberapa pertanyaan berikut harus dijawab. Dalam cara bagaimana pembangunan ekonomi atau wi-layah mempengaruhi pertumbuhan di wilayah lain? Apakah pem-bangunan dalam suatu wilayah akan meningkatkan permintaan sektor untuk wilayah lain dan selanjutnya mendorong pembangunan di wilayah tersebut, atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah? Bagaimana interrelasi antara pertumbuhan wilayah dengan per-tumbuhan nasional? Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa teori pertum-buhan wilayah harus juga merupakan studi interaksi antar wilayah. Pengembangan wilayah harus juga dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam lansekap ekonomi. Dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi pergeseran dalam permintaan dan terjadi pula per-baikan sistem transportasi, penurunan biaya produksi, dan dinamika masyarakat. Peristiwa ini akan mendorong para wiraswasta dan pengusaha industri untuk mempertimbangkan kembali lokasi industrinya dan mungkin mendorongnya untuk mengadakan relokasi. Jadi dapat dikatakan bahwa lansekap ekonomi merupakan akibat dari per-tumbuhan ekonomi. Di lain pihak tingkat pertumbuhan suatu wilayah tergantung pada alokasi sumberdaya dalam tata ruang pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu hal ini sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dalam hal penentuan lokasi individual. Maka jelaslah bahwa teori pertumbuhan harus memperhatikan analisis lansekap ekonomi. Akhirnya studi pertumbuhan wilayah sebaiknya dikaitkan pula dengan analisis optimum wilayah dan kebijaksanaan wilayah. Kondisi optimum dalam tata ruang dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dalam sistem kebijaksanaan wilayah dan analisis optimum dapat dipakai untuk menetapkan arah secara optimal sepanjang waktu. Aspek-aspek kebijaksanaan pertumbuhan wilayah ber-hubungan dengan persoalan-persoalan seperti alat apa atau kom-binasi dari langkah-langkah kebijaksanaan yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan di suatu wilayah atau beberapa wi-layah? Alternatif strategi apa yang sebaiknya ditempuh dalam me-laksanakan kebijaksanaan pertumbuhan wilayah? Tindakan-tindak-an apakah yang dapat dijalankan untuk mencegah aglomerasi yang berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan di atas harus diusahakan dijawab agar pengembangan wilayah dapat dilaksanakan secara lebih mantap dan terarah. 1.3 PENGEMBANGAN KONSEP TATA RUANG ΕΚΟΝΟΜΙ Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 analisis ekonomi dititik beratkan pada pembahasan masalah lokasi dan tata ruang. Masalah lokasi dari setiap kegiatan produktif terutama dalam pembangunan harus dipertimbangkan dan dipilih secara tepat agar kegiatankegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penentuan dimana kegiatakegiatan pembangunan tersebut akan dilakukan menyangkut masalah tata ruang. Konsep tata ruang ekonomi sangat penting dalam studi pengembangan wilayah. Menurut perkembangan historis, tata ruang ekonomi mengalami perubahan dan pertumbuhan. Beberapa kasus spasial dapat dikemukakan seperti terjadinya pemusatan kegiatan-kegiatan industri dan urbanisasi ke kota-kota besar, terbentuknya pasar-pasar dan pusat-pusat baru yang menimbulkan perubahan dalam wilayah-wilayah pelayanan dan mungkin pula perlu dilaku-kan penyempurnaan dalam pembagian wilayah pembangunan secara menyeluruh. Kasus-kasus di atas merupakan topik-topik yang bersifat kontroversial karena mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap pengembangan tata ruang nasional. Ahli-ahli ilmu bumi, ekonomi, sosiologi, matematika dan para pengusaha mempunyai pendapat atau gagasan yang berbeda-beda mengenai konsep tata ruang. Jadi tata ruang mempunyai bermacam-macam pengertian. Tata ruang mempunyai pula konotasi yang bersifat emotif (perasaan hati). Tata ruang dapat pula diartikan sebagai lingkungan tradisional dari kehidupan manusia, mempunyai ke-tentuan-ketentuan dan kemampuannya sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatan penduduknya, dan bahkan tata ruang dianggap sebagai salah satu sasaran pembangunan. Secara logis dan historis, menurut Boudeville tata ruang dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu tata ruang ekonomi, tata ruang geografis, dan tata ruang matematik. Konsep tata ruang ekonomi mempunyai pengertian yang lebih bersifat operasional dan kurang emotif. Misalnya, investasi modal, jaringan transportasi, industri, dan teknologi pertanian menciptakan perkembangan baru yang meliputi bahan-bahan material baru dan aturan-aturan baru. Konsepsi tata ruang ekonomi dapat dibedakan dengan tata ruang geografis. Ahli-ahli ilmu bumi menempatkan ma-nusia dalam lingkungan alam. Sebaliknya ahli-ahli ekonomi meng-anggap lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan manusia. Tata ruang geografis merupakan tata ruang tiga dimensi, sedangkan tata ruang ekonomi lebih kompleks dan bersifat multi dimensi. Tata ruang ekonomi berbeda pula dengan tata ruang mate-matik. Tata ruang matematik benar-benar bersifat abstrak dan tidak ada hubungannya dengan lokasi geografis, misalnya indifference sur-faces. Jika suatu tata ruang terbentuk semata-semata oleh variabelvariabel ekonomi, maka tata ruang tersebut merupakan tata ruang matematik, artinya secara matematik dapat terjadi dimana-mana. Akan tetapi sebaliknya tata ruang ekonomi merupakan suatu aplikasi varian-varian ekonomi di atas kebutuhan manusia, diatas atau didalam suatu tata ruang geografis, dan melalui suatu transformasi matematik dapat dijelaskan proses ekonomi. Selanjutnya mengenai tata ruang ekonomi, Francois Perroux mendefinisikan berturutturut sebagai a homogeneous aggregate, a field of forces dan a plan. Dilihat dari segi hubungan formal pem-bangunan, tata ruang ekonomi merupakan a field of forces, merupakan tata ruang polarisasi, yaitu sebagai suatu tempat dimana konsentrasi atau pemusatan kegiatankegiatan ekonomi yang relatif besar (pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan) dan nyata berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Di bidang kegiatan industri, dapat ditunjukkan terjadinya gap atau kesenjangan yang semakin besar dalam hal tingkat produktivitas di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, sehingga timbul masalah ketimpangan spasial. Menurut teori Perroux (growth pole theory), pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di seluruh daerah, akan tetapi ter-batas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya. Ia lebih menekankan pada aspek pe-musatan proses pertumbuhan pada titik-titik spasial. Dimensi geo-grafis telah dimasukkan ke dalam pengaruh pusat pengembangan. Friedmann meninjaunya dari ruang lingkup yang luas dengan me-nempatkan teori inti wilayah (core region), yaitu di sekitar wilayah inti terdapat wilayahwilayah pinggiran (periphery region). Wilayah pinggiran seringkali disebut pula wilayah di sekitarnya. Pembangun-an dipandangnya sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi kumulatif yang berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan yang terletak pada titiktitik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan ke luar dari pusat-pusat tersebut menuju ke daerah-daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah. Seperti halnya dengan teori Perroux, Friedmann memberikan pertalian penting pada daerah inti sebagai pusat pelayanan atau pusat pengembangan. Teori Friedmann tidak membahas masalah pemilihan lokasi optimum industri dan tidak pula menentukan jenis investasi apa yang sebaiknya ditempatkan di pusat-pusat urban. Oleh karena itu teori Friedmann diklasifikasikan pula sebagai tanpa tata ruang. Walaupun demikian disadari bahwa pusat-pusat urban mempunyai peranan yang dominan yaitu memberikan pancaran pengembangan ke daerah-daerah di sekitarnnya. Beberapa Pengertian Ruang dan Azas Pemanfaatannya Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara, termasuk di dalamnya lahan/tanah, air, udara dan benda serta sumberdaya lainnya, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidup. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan adanya herarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, peman-faatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencanarencana kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek fungsional tertentu. Interpretasi mengenai ruang atau tata ruang dapat berbeda-beda. Ahli matematik mendeskripsikan tata ruang sebagai tata ruang matematik yang dalam penganalisaannya dilakukan dengan memberikan simbol-simbol. Tata ruang matematik bersifat statis, tata ruang matematik perlu dijabarkan ke dalam tata ruang geografisnya untuk melihat potensi distribusi sumberdaya alam, pemanfaatan ruang dan batas wilayah administrasinya yang kesemuanya diplot-kan pada peta-peta geografis. Peta geografis ini merupakan ins-trumen bagi ahli ilmu bumi dan ahli teknik untuk menganalisis lokasi dan alokasi berbagai kegiatan sektoral pada tata ruang yang tersedia dimana satu sama lainnya mempunyai ciri dan variasinya sendiri-sendiri. Meskipun konsep tata ruang geografis dapat dikatakan lebih maju dibandingkan tata ruang matematik, tetapi masih perlu dikembangkan, dan diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efektif dan efisien. Tata ruang yang diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efektif dan efisien itu disebut sebagai tata ruang ekonomi. Tata ruang geografis menampilkan lokasi dan alokasi peman faatan tata ruang dimana terdapat potensi sumberdaya alam, dimana terjadi berbagai kegiatan interaksi sumberdaya manusia dan umberdaya alam (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan, pariwisata, pemukiman) pada berbagai ruang permukaan (wilayah perkotaan dan pedesaan; kawasan lindung dan kawasan budidaya). Gambaran wajah tata ruang geografis untuk memenuhi ke-butuhan manusia secara efektif dan efisien perlu dilakukan penataan dan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang yang tidak serasi akan menimbulkan dampak negatif (merugikan masyarakat) seperti: pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, penebangan hutan, telah menimbulkan dan mengakibatkan banjir (luapan atau genangan air) pada daerah sekitarnya, yang terjadi setiap tahun, yang mengakibat-kan kerugian harta dan benda yang besar jumlahnya yang harus dipikul oleh masyarakat. Dampak negatif tersebut tidak memenuhi kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya mengsengsarakan masyarakat. Tata ruang geografis yang tidak serasi harus direncana-kan, ditata dan dikendalikan secara serasi sehingga dapat memberi-kan kesejahteraan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan dengan menerapkan azas manfaat, azas keseimbangan dan keserasi-an, azas kelestariaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan azas berkelanjutan. Azas manfaat adalah pemanfaatan ruang secara optimal yang harus dicerminkan di dalam penentuan jenjang dan fungsi pelayanan kegiatan serta sistem jaringan prasarana wilayah. Azaz keseimbang-an dan keserasian dalam (1) struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi pernyebaran penduduk antar daerah/kawasan dan sektor, dan (2) dalam fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten. Azas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. Azas ber-kelanjutan adalah pemantauan ruang yang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumberdaya alam dengan memper-hatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. BAB 9 KLASIFIKASI WILAYAH 1.1 WILAYAH SEBAGAI SUATU KONSEP Menurut logika Aristoteles, segala sesuatu dapat diberi definisi atai batasan pengertian dari tiga sudut pandangan, yaitu dari uraian materiil (material description), menurut hubungan formal (for-mal relation), dan kaitan dengan sasaran atau tujuan akhir (final ob-jective). Sesuai dengan logika tersebut, maka konsep wilayah atau region mempunyai tiga macam pengertian, yaitu wilayah homogen (homogeneous region), wilayah polarisasi (polarization region) atau wilayah nodal (nodal region), dan wilayah perencanaan (planning region) atau wilayah program (programming region). Wilayah homogen diartikan sebagai suatu konsep yang menganggap bahwa wilayahwilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi sebuah wilayah tunggal apabila wilayah-wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang serupa. Ciri-ciri atau karakteristik tersebut dapat bersifat ekonomi, misalnya struktur produksinya hampir sama, atau pola konsumsinya homogen, dapat pula bersifat geografis, misalnya keadaan topografi atau iklimnya serupa, dan bahkan dapat pula bersifat sosial atau politis, misalnya suatu kepribadian masyarakat yang khas, sehingga mudah dibeda-kan dengan karaktersitik wilayah-wilayah lainnya. Secara teori ekonomi, keserupaan dalam tingkat pendapatan per kapita merupakan kriteria yang lazim dipakai untuk menentukan kehomogenan suatu wilayah (interregional macro-economies). Cara pendekatan ini merupakan penerapan model pendapatan nasional dan model pertumbuhan nasional pada tingkat wilayah. Dalam hal ini masing-masing wilayah diperlakukan sebagai suatu perekonomi-an terbuka. dengan demikian model-model analisis di atas menjelas-kan arus perdagangan, arus faktor produksi antar wilayah, dan pen-dapatan wilayah. Persoalan-persoalan pokok seperti perubahan pen-dapatan wilayah, fluktuasifluktuasi wilayah, kebijakan stabilitas dan determinan-determinan pertumbuhan wilayah dapat dibahas berdasarkan kerangka analisis nasional. Pada pertengahan abad ke-20, di Perancis terdapat tiga wilayah homogen yang besar, yaitu (1) wilayah-wilayah yang sangat maju (the most higlhly developed regions) yang terdiri dari kota Paris dan daerah di sekitarnya, wilayah-wilayah bagian Utara dan Timur, (2) kawasan yang baru berkembang (the newly developing zones) seperti wilayah Lyon serta Provence, dan (3) wilayah-wilayah yang kurang berkembang dan lambat pertumbuhannya (less developed and slowly growing regions) yang meliputi wilayah-wilayah Perancis bagian barat, barat daya, dan bagian tengah. Pada tahap awal perencanaan pembangunan (tahun 1950-an), Perancis terdiri dari 87 buah departement (semacam provinsi) yang dapat dikelompokkan menjadi 9 buah wilayah homogen. Wilayah-wilayah nodal (pusat) atau wilayah-wilayah polarisasi (berkutub) terdiri dari satuan-satuan wilayah yang heterogen. Misal-nya distribusi penduduk yang terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu akan mengakibatkan lahirnya kota-kota besar, kotamadyakotamadya dan kota-kota kecil lainnya, sedangkan penduduk di daerah-daerah pedesaan relatif jarang, atau dengan perkataan lain lalu lintas jalan raya nasional memperlihatkan tingkat polarisasi yang lebih rapi dibandingkan dengan kota-kota lain yang tidak terletak pada jaringan lalu lintas jalan raya. Contoh lain adalah proses urbanisasi yang paling pesat yang terjadi di Amerika Latin yaitu Rio Grande do Sul (Brasilia) yang memiliki jaringan lalu lintas yang cukup baik ke berbagai daerah di sekitarnya. Kategori wilayah perencanaan atau wilayah program sangat penting artinya apabila dikaitkan dengan masalah-masalah kebijak-sanaan wilayah. Pada tingkat nasional atau wilayah, tata ruang pe-rencanaan oleh penguasa nasional, wilayah difungsikan sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pembagian wilayah perencanaan disusun berdasarkan pada analisis kegiatan pembangunan sektoral yang terlokasisasi pada satuan lingkungan geografis. Wilayah perencanaan merupakan suatu wilayah pengembangan, dimana program-program pembangunan dilaksanakan. Dalam hal ini yang penting diperhatikan adalah persoalan koordinasi dan desentralisasi pembangunan wilayah dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Misalnya dalam pembangunan wilayah di Perancis, pengambilan keputusan dilakukan di Paris, akan tetapi dapat saja dilaksanakan di Lyon atau di pusat-pusat pem-bangunan wilayah lainnya. Wilayah perei canaan tidak jauh berbeda dengan wilayah polarisasi, karena efisiensi maksimum dalam perencanaan wilayah dipengaruhi oleh saling keterhubungan arus regional secara mak-simum. Perancis dibagi menjadi 21 buah wilayah perencanaan. Terdapat korelasi antara jangka waktu rencana pembangunan dan jumlah wilayah perencanaan. Untuk rencana pembangunan jangka menengah (sekitar 4-5 tahu) jumlah wilayah perencanaan sebanyak 21 buah seperti di Perancis dianggap sudah cukup, akan tetapi untuk rencana pembangunan berjangka waktu lebih panjang (pembangunan prospek if 15-20 tahun yang akan datang) penyeder-hanaan jumlah wilayah perencanaan menjadi 3 buah sampai 8 buah wilayah dianggap lebih bermanfaat. Contoh wilayah perencanaan yang lain dapat dikemukakan yaitu pembagian wilayah pembangunan yang didasarkan pada aliran sungai. Daerah aliran sungai (DAS) atau river basin development region seperti yang seringkali kita dengar adalah the Colorado River Basin di Amerika Serikat. 1.2 BEBERAPA KLASIFIKASI WILAYAH LAINNYA Pusat-pusat yang pada umumnya merupakan kota-kota besar tidak hanya berkembang sangat pesat, akan tetapi mereka bertindak sebagai pompa-pompa pengisap dan memiliki daya penarik yang kuat bagi wilayah-wilayah belakangnya yang relatif statis. Wilayahwilayah pinggiran di sekitar pusat secara berangsur-angsur ber-kembang menjadi masyarakat yang dinamis. Terdapat arus pen-duduk, modal, dan sumberdaya ke luar dari wilayah-wilayah be-lakang yang dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan pusat-pusat, dimana pertumbuhan ekonominya sangat cepat dan bersifat kumulatif. Sebagai akibatnya, perbedaan pendapatan antara pusat dan wilayah pinggiran cenderung bertambah besar. Pembagian wilayah menurut Freidmann dibagi menjadi dua, yaitu wilayah inti (pusat) dan wilayah pinggiran (center periphery). Meskipun merupakan klasifikasi dasar, akan tetapi dapat dianggap sangat kasar sebagai suatu kerangka kebijaksanaan yang bermanfaat untuk pengembangan wilayah. Empat klasifikasi wilayah pem-bangunan telah dikemukakan oleh J. Friedmann dan W. Alonso, yaitu (1) metropolitan regions, (2) development axes, (3) frontier rgions, dan (4) depressed regions. Klasifikasi wilayah di atas dapat dianggap lebih memadai. Metropolitan regions atau wilayah-wilayah metropolitan seringkali disebut pula sebagai core regions (wilayah-wilayah inti) atau growth poles (kutub-kutub pertumbuhan). Pusat-pusat pengembangan ini biasanya merupakan kota-kota besar dengan segala kegiatan dan fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan dan perbankan, serta administrasi pemerintahan, yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya (hinterland) dan kota-kota kecil lainnya (small centres). Development axes atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua wilayah metropolitan atau lebih. Secara kasar dapat dikatakan bahwa prospek pembangunan wilayah-wilayah tersebut kurang lebih akan proprsional dengan tingkat dan luas pembangunan wilayah-wilayah yang dihubungkan yaitu poros pembangunan. Sebagai contoh wilayah poros pembangunan di Jepang terpusat pada tiga wilayah besar yakni Tokyo - Yokohama, Nagoya - Kyoto, dan Osaka - Kobe. Frontier regions atau wilayah-wilayah perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk, demikian pula tujuan-tujuan nasional baru seringkali mendorong pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah (virgin areas) atau wilayah-wilayah yang terletak di wilayah-wilayah perbatasan (frontfier regions). D.C. North telah menyarankan agar penentuan batas suatu wilayah seyogyanya dilakukan berdasar pada kegiatan-kegiatan pembangunan di sekitar suatu basis ekspor (export base). Basis eks-por dimaksudkan sebagai suatu pusat organisasi ekspor yang meng-anggap bahwa pertumbuhan satu pusat adalah sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor. Jadi ekspor merupakan satu-satu-nya penentu yang besifat eksogin. Dasar pembagian wilayah se-macam ini mempunyai manfaat yang penting terutama bila dikaitkan dengan orientasi pengembangan luar negeri. Akan tetapi hal ini bukan berarti sebagai satu-satunya kemungkinan. Terdapat berbagai dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah, misalnya kelancaran administrasi pemerintah, pengembangan industri, produksi pertanian, pengelolaan sumber-daya alam, kepentingan militer dan pertahanan, dan lain sebagainya. Bernard Okun dan Richard W. Richardson membuat klasifikasi berdasar pada tingkat kemakmuran dan kemampuan berkembang masing-masing wilayah. Tingkat kemakmuran dinyatakan dengan pendapatan per kapita, dan kemampuan berkembang dikaitkan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya berdasar pada kriteria tersebut, maka pembagian wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Low per capita income and stagnant regions (LS) atau wilayah-wilayah yang berpendapat per kapita rendah dan kurang ber-kembang. B. High per capita income and stagnant regions (HS) atau wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi tetapi kurang ber-kembang. C. Low per capita income and growing regions (LG) atau wilayah wilayah yang berpendapatan per kapita rendah tetapi ber-kembang. D. High per capita income and growing regions (HC) atau wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi dan berkembang. Klasifikasi wilayah di atas dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketidakserasian antar wilayah dan bagaimana pengaruh mobilitas internal sumberdaya penduduk, modal, dan faktor produksi lainnya. Demikian pula arus perdagangan antar wilayah, apakah akan memberikan manfaat atau sebaliknya akan menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan wilayah, baik dı wilayah asal maupun di wilayah tujuan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, yakni dalam jangka pendek migrasi penduduk keluar dari wilayah yang berpendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang ke wilayah yang berpendapatan rendah tetapi ber-kembang, cenderung akan mengurangi tingkat keserasian antar kedua wilayah tersebut, dan pengaruhnya dalam jangka panjang akan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan baik di wilayah asal maupun wilayah tujuan. Contoh yang lain yaitu arus migrasi masuk ke wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi dan ber-kembang dari wilayah yang berpendapatan perkapita rendah dan kurang berkembang. Pada umumnya terdiri tenaga kerja yang ber-kualitas rendah. Hal ini akan mengurangi tingkat pendapatan per kapita di wilayah tujuan, di lain pihak mengurangi suplai tenaga kerja di wilayah asal, yang selanjutnya cenderung akan meningkat-kan pendapatan per kapita di wilayah asal tersebut. BAB 10 KETERHUBUNGAN DAN KETERGANTUNGAN ANTAR WILAYAH 1.1 REGIONALISASI DAN PENGERTIAN KEUNTUNGAN KOMPARATIF Banyak negara-negara menetapkan balanced growth (pertum-an seimbang) sebagai strategi pembangunannya. Ditinjau dari analisis wilayah, strategi pertumbuhan seimbang diinterpresitasikan bahwa wilayah-wilayah miskin berkembang lebih cepat dari pada wilayah-wilayah kaya, sehingga tingkat pendapatannya cenderung menjadi sama pada masa depan. Dalam konteks pertumbuhan seimbang diupayakan keserasian dalam laju pertumbuhan antar wilayah. Pembangunan wilayah dilancarkan untuk meratakan pembangunan ke seluruh wilayah. Hal ini berarti merangsang parti-sipasi dan keterlibatan masyarakat di seluruh wilayah dalam proses pembangunan. Pembangunan wilayah antar propinsi yang bertetangga akan dapat mengembangkan daya pertumbuhan yang kuat yang terdapat dalam lingkungan sesuatu provinsi dan dapat mendorong pula per-kembangan provinsi-provinsi lainnya yang relatif terbelakang. Dalam hubungan ini perlu digairahkan kerja sama antar wilayah (provinsi) secara saling menguntungkan (mutual regional coopera-tion). Hal ini berarti bahwa produksi dan usahausaha pembangunan dikaitkan dengan keuntungan komparatif dan regionalisasi wilayah pembangunan. Keterkaitan atau keterhubungan (interrelationship) dan keter-gantungan (interdependecy) antar wilayah dapat diperlihatkan dari jaringan arus antar wilayah (termasuk di dalamnya arus perdagang-an). Dalam suatu negara, arus perdagangan antar wilayah tidak dapat berlangsung berdasarkan keuntungan mutlak (absolute advantage), melainkan didasarkan pada keuntungan komparatif (comparative advantage) saja sudah cukup beralasan untuk melangsungkan per-dagangan antar wilayah. Suatu wilayah akan mengekspor barangbarang yang mempunyai keuntungan produksi yang relatif lebih kecil atau mengimpor barang-barang yang mempunyai kerugian produksi yang lebih besar (comparative disadvantage). Masing-masing wilayah akan menspesialisasikan produksi pada satu atau beberapa barang tertentu. Wilayah-wilayah yang tidak memproduksi sendiri barang-barang yang dibutuhkan akan membeli barang-barang yang dimaksud dari wilayah-wilayah lain yang menjadi produsennya. Jelaslah bahwa di antara wilayah-wilayah yang ada mempunyai pengaruh timbal balik dan saling berkepentingan satu sama lainnya. Regionalisme termasuk dalam kerangka kebijaksanaan pem-bangunan ekonomi yang mengelompokkan lingkungan teritorial menjadi wilayah-wilayah sub nasional. Dalam pengelompokan tersebut dipertimbangkan dua aspek utama yaitu pola fisik dan pola kegiatan. Pola fisik meliputi pemanfaatan tata ruang untuk pemukiman penduduk, fasilitas-fasilitas produktif, trayek-trayek transportasi, tata guna tanah, dan lain-lainnya. Pola kegiatan terdiri dari arus modal, tenaga kerja, komoditias dan komunikasi yang menghubungkan elemenelemen fisik dalam tata ruang. Dilihat dari pertimbangan integrasi nasional, salah satu fungsi pengembangan wilayah adalah membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah yang berspesial-isasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional. Jadi regionalisasi wilayah pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan baik sektoral maupun regional secara lebih efektif dan efesien. 1.2 KRITERIA PERWILAYAHAN DAN INTERAKSI ANTAR TITIK-TITIK SPASIAL Kegiatan-kegiatan ekonomi dapat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan produksi dan kegiatan-kegiatan konsumsi. Kegiatan-ke-giatan konsumsi menyangkut penggunaan tata ruang untuk ke-giatan-kegiatan kehidupan rumah tangga. Kegiatan-kegiatan pro duksi meliputi kegiatan-kegiatan sektor pertaruan, sektor industri, dan sektor tersier. Secara lebih luas kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu kegiatan-kegiatan pertanian, industri produksi tersier, dan kegiatan-kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya terdapat permasalahan yakni bagaimana mengintegrasikan teoriteori lokasi parsial ke dalam kerangka dasar umum untuk menjelaskan lansekap ekonomi. Model Von Thunen dapat dipakai untuk menentukan distribusi kegiatan-kegiatan pertanian. Suatu sistem cincin-cincin Von Thunen yang diperluas di sekitar pusat-pusat pemukiman penduduk. Komo-ditas-komoditas pertanian yang mempunyai panen hasil per hektar (ukuran luas tanah) yang lebih rendah dan harga pasar yang lebih rendah akan ditanam diatas tanah yang terletak lebih jauh dari pusat. Pendekatan keuntungan maksimum dapat digunakan untuk menen-tukan lokasi sektor industri. Distribusi spasial ini sektor industri dipengaruhi oleh aspek-aspek penghasilan dan biaya, jadi ditentukan oleh distribusi permintaan faktor produksi atas tata ruang, serta besarnya biaya transportasi untuk menghargai titik spasial. Sektor tersier melayani sektor primer dan sektor sekonder. Konsekuensinya lokasi kegiatan-kegiatan tersier tergantung pada distribusi spasial kegiatan-kegiatan primer dan sekunder. Dan distri-busi kegiatan-kegiatan kehidupan rumah tangga ditentukan oleh faktorfaktor kemudahan pada tempat-tempat sentral. Distribusi kegiatan-kegiatan rumah tangga dapat mempe-ngaruhi lokasi sektor-sektor lainnya melalui segi permintaan. Lokasi industri akan mempunyai umpan balik pada lokasi pertanian. Pada kesempatan berikutnya pengaruh umpan balik tersebut akan men-dorong untuk dilakukan perbaikan (revisi) terhadap lokasi-lokasi parsial yang orisinil. Selanjutnya dalam pembahasan masalah perencanaan wilayah, perlu kiranya dijelaskan pula mengenai konsep dan kriteria per-wilayahan. Wilayah-wilayah harus ditentukan batas-batasnya se-demikian rupa sehingga setiap titik spasial termasuk hanya dalam satu wilayah. Tidak benar kalau satu titik spasial termasuk dalam dua wilayah yang berdekatan. Wilayah I dan wilayah II seperti dilukiskan oleh gambar 10.2 di bawah ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sebagian dari kedua wilayah tersebut saling berhimpitan, atau dengan perkataan lain tidak boleh terjadi overlapping (tumpang tindih) antar titik spasial. Kriteria yang digunakan adalah homogenitas kondisi wilayah. Kriteria homogenitas dapat dinyatakan sebagai karakteristik-karak-teristik geografis, sosial, dan ekonomi. Suatu perencanaan wilayah yang semata-mata hanya didasarkan pada kriteria geografis dapat dikatakan kurang bermanfaat ditinjau dari kepentingan analisis ekonomi. Untuk menentukan homogenitas ekonomi dapat diguna-kan ciri-ciri keserupaan dalam kegiatan-kegiatan produksi, tingkat keterampilan angkatan kerja, dan pendapatan perkapita. Selanjutnya suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan dari sejumlah titik-titik spasial yang mempunyai kegiatan-kegiatan produksi yang serupa atau tingkat pendapatan perkapita yang sama. Dengan demikian dapat dibedakan dengan mudah antara wilayah-wilayah agraria dan wilayah-wilayah industri serta wilayah-wilayah yang berorientasi pada sektor tersier. Dapat dibedakan pula antara wilayah-wilayah dengan tingkat pendapatan rendah (miskin) dan wilayah-wilayah berpendapatan tinggi (kaya). Wilayah dapat pula ditentukan batas-batasnya berdasar pada kriteria interdependensi atau ketergantungan antar wilayah. Dalam interpretasi ini suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang terpadu secara spasial. Suatu sistem diartikan sebagai suatu kumpulan varibel-variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Berdasar kriteria ini tidak boleh mengkonsentrasikan semata-mata pada keterga..tungan yang berat sebelah pada segi suplai (wilayal suplai dari suatu pusat permintaan) atau hanya pada segi permintaan (wilayah permintaan dari suatu pusat suplai). Jadi ketergantungan antar wilayah tersebut harus didasarkan pula pada kedua segi yaitu segi permintaan dan suplai (penawaran). Selanjutan ketergantungan antar wilayah dapat dilihat dari arus pertukaran dan lalu lintas perdangangannya. Disamping kriteria homogenitas dan fungsionalitas, terdapat variabel lain yang dapat digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah yakni uniformitas intensitas, dimana penentuan suatu pe-rangkat titik-titik spatial diperngaruhi oleh rencana pemerintah, penentuan wilayah-wilayah oleh rencana pemerintah, penentuan wilayah-wilayah perencanaan mungkin berubah dalam proses per-tumbuhan karena terjadinya pertumbuhan dalam rencana pem-bangunan nasional. Konsepsi wilayah tersebut meliputi wilayah nodal yang mempunyai ciri yaitu terdapat suatu tempat sentral atau suatu kutub dan daerah komplementer di sekitarnya lengkap dengan jaringan-jaringan pasar. Konsepsi ini berarti pula suatu wilayah polarisasi, dimana pada setiap titik spasial intensitas arus internal komoditas dan jasa lebih besar dari pada intensitas arus eksternal. 1.3 STRUKTUR HERARKI DAN HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTAR PUSAT ATAU KOTA Konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi terletak pada tata-ruang-tataruang yang pada umumnya adalah kota-kota. Proses industrialisasi dan urbanisasi ke kota-kota berlangsung terus dan bahkan menunjukkan gejala yang semakin meningkat. Konsep tata ruang dan wilayah polarisasi muncul sebagai hasil dari observasi struktur kota-kota. Dalam hubungan ini perlu ditunjukkan secara visual sistem dan herarki masyarakat daerah metropolis sampai daerah-daerah pedesaan. Tiap kota besar mempunyai suatu radius kota satelit, dan selanjutnya kota-kota satelit tersebut mempunyai desa-desa satelit. Gejala ini sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia, perkembangan industri dan perdangangan, dimana pertumbuhan kota telah meningkat sangat pesat. Struktur herarki pusat-pusat atau kota-kota dapat ditentukan dengan menggunakan ukuran jumlah penduduk, tingkat kegiatan ekonomi, tersedianya kelengkapan fasilitasfasilitas pelayanan, ting-kat kemakmuran dan kemampuan berkembangnya. Pada umumnya kota-kota besar mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding dengan kota-kota kecil. Fasilitas-fasilitas pelayanan (ter-utama fasilitas distribusi) tersedia relatif lebih lengkap, demikian pula dalam hal jumlah dan jenis lapangan kerja serta tingkat ke makmuran penduduknya yang mempunyai orde yang sama di suatu negara. Justifikasi dari pengertian wilayah polarisasi adalah bersifat empirik. Daerah-daerah di sekitar pusat mempunyai keterhubungan dan ketergan-tungan yang erat dengan pusatnya. Jadi wilayah polarisasi berarti tidak autarkis. Artinya bersifat terintegrasi antara pusat dengan daerah komplementernya. Jaringan transportasi berfungsi menjembatani antara konsep wilayah polarisasi dan pengertian kutub-kutub pertumbuhan. Kon-sep-konsep tersebut merupakan salah satu kunci permasalahan pengembangan wilayah. Suatu kutub pertumbuhan regional me-rupakan suatu perangkat industri-industri yang berkembang dan terletak di daerah perkotaan dan mendorong lebih lanjut kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya ke seluruh wilayah pelayanannya. Jaringan tranportasi dapat disusun secara sederahana yaitu menghubungkan pusat besar dengan pusat-puat sedang, dan selan-jutnya antara pusat sedang dengan pusat-pusat kecil. Pola transpor-tasi semacam ini disebut conventional tree pattern yang mendasarkan pada susunan pohon, yaitu terdiri dari batang, dahan, cabang dan ranting. Dalam susunan trayek atau rute pelayaran dan penerbangan dikenal trunk route dan feeder route. Jaringan jalan raya meliputi jalan arteri (urat nadi), jalan kolektor dan jalan lokal. Untuk melayani kegiatan pembangunan dan mobilitas yang semakin meningkat dan meluas, maka jaringan transportasi nasional harus dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan arus muatan di seluruh wilayah. Jaringan transportasi yang menghubung-kan masing-masing pusat ke seluruh pusat lainnya dikenal sebagai "polygrid pattern" atau pola segala jurusan seperti yang terjadi dalam penerapan di negara-negara yang maju. 1.4 KONFIGURASI (SUSUNAN) PUSAT-PUSAT SPASIAL Berdasarkan kriteria peran kota sebagai pusat pertumbuhan, statusnya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, jumlah fasilitas pelayanan, besarnya jumlah penduduk perkotaan, dan kemudahan-kemudahan lainnya, maka dapat ditentukan herarki masing-masing kota. Antara kota-kota atau pusat-pusat di suatu wilayah terdapat hubungan fungsional. Pusat tingkat (orde) kesatu merupakan pusat yang tidak berada dalam sub ordinasi pusat-pusat lainnya dalam suatu wilayah. Pusat orde kesatu melayani seluruh wilayah pengaruhnya melalui pusat-pusat yang berada dalam sub ordinasinya. Dalam hubungan ke luar, pusat orde kesatu memiliki fasilitas pelayanan distribusi yang ter-lengkap dan kemampuan pelayanan yang tertinggi. Pusat orde kedua ialah pusat yang berada dalam sub ordinasi pusat orde kesatu. Pusat orúe kedua melayani wilayah pengaruhnya melalui pusatpusat yang berada dalam sub ordinasinya. Pusat orde kedua memiliki fasilitas pelayanan yang setingkat di bawah dan kemampuan pelayanan yang setingkat lebih rendah dari pusat orde kesatu. Pusat orde ketiga dan seterusnya pada prinsipnya mempunyai ciri-ciri yang sejalan dengan uraian di atas. Di tinjau dari segi pendekatan pembangunan wilayah, fungsi primer dari suatu pusat yaitu keterkaitan antara pusat Nampak lebih menonjol dari pada fungsi sekondernya adalah pelayanan kepada penduduk perkotaan. Fungsi primer suatu pusat ditunjang oleh jasa distribusi meliputi pelayanan jasa perdagangan dan jasa transportasi yang dilakukan lebih luas lingkupnya yaitu dari pusat tersebut ke wilayah-wilayah belakang dan kota-kota lainnya. Interaksi antara masing-masing pusat ke wilayah-wilayah be-lakang yang merupakan wilayah pengaruhnya merupakan unsur yang penting dalam sistem wilayah yang bersangkutan. Antara pusat (wilayah perkotaan) dan wilayah yang mengintarinya (wilayah pedesaan) terdapat keterhubungan dan ketergantungan yang saling membutuhkan. Di wilayah perkotaan terjadi interaksi penduduk yang lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan wilayah-wilayah pedesa-an. Interaksi tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan jumlah penduduk dan sebaliknya berkorelasi negatif terhadap jarak. Semakin jauh jarak antara dua massa penduduk berarti semakin ren-dah intensitas interaksinya. Berdasarkan pada korelasi di atas dapat dinyatakan pula bahwa semakin besar suatu kota berarti semakin jauh (luas) wilayah pelayanannya atau wilayah pengaruhnya. Dalam kenyataan terdapat di ibukota daerah tingkat II yang memiliki fa-silitas yang cukup ternyata tidak berfungsi sebagai pusat, tetapi sebaliknya ada tempat-tempat yang memiliki fasilitas yang kurang lengkap ternyata berfungsi sebagai pusat. Dalam hal ini terdapat diskrepansi atau ketidakserasian antara sasaran kebijaksanaan spa-sial yang mendasar pada sistem administratif dan proses berkem-bangnya wilayah seperti apa adanya. Terdapat pula ketidakserasian mengenai ruang lingkup wilayah administrasi secara otomatis tercakup dalam wilayah pengembangan. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa bagian wilayah administrasi tidak terjangkau oleh jasa pelayanan perdagangan dan angkutan disebabkan hambatan-hambatan geografis atau karena belum tersedianya prasarana trans-portasi. Wilayah yang terlayani oleh jasa distribusi (jasa perdagangan dan jasa transportasi) yang memperlihatkan adanya interaksi antara sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya pembangunan lain-nya disebut sebagai wilayah pengembangan. Wilayah administrasi tidak selalu identik dengan wilayah pengembangan, dapat lebih besar atau sama atau lebih kecil. Ditinjau dari segi pembangunan wilayah, bentuk wilayah yang kedua (wilayah pengembangan) memberikan manfaat yang lebih besar dari pada wilayah ditentukan berdasarkan jaringan adminis-tratif. Konfigurasi (susunan) kota-kota (pusat-pusat) dalam sistem spasial dapat didentifikasikan dari kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan kebuayaan, yang dalam wujud fisiknya dicerminkan oleh arus distribusi barang. Arus distribusi barang terlaksana secara efisien dalam arti jarak perjalanan yang di tempuh oleh barang-barang dari tempat asal ke tempat-tempat tujuan adalah minimum, konfigurasi pusat-pusat dapat dilihat dari orientasi penduduk di berbagai tempat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan esiensial, misalnya ke tem-pat-tempat pekerjaan, sekolah, rumah sakit, rekreasi, dan peribadah-an. Tingkah laku spasial penduduk berorientasi pula pada jarak per-jalanan terdekat. Gejala ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya manusia dalam mencapai tujuannya berusaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya (prinsip ekonomi). Masalah alokasi-lokasi atas penempatan fasilitas-fasilitas pe-layanan sangat penting karena menyangkut kepentingan sebagian besar penduduk sebagai pengguna jasa pelayanan dan kepentingan pemerintah sebagai penyedia fasilitas. Masalah yang dihadapi para perencana pembangunan adalah menentukan penempatan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut pada lokasi secara paling efisien, dimana investasi pemerintah harus didistribusikan dengan sebaik-baiknya pada pusat-pusat yang tersebar agar diperoleh manfaat yang ter-tinggi bagi seluruh lapisan penduduk.