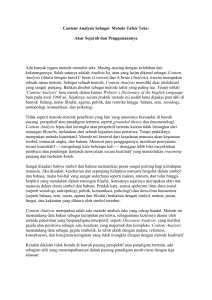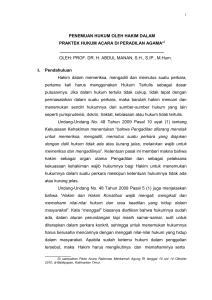Interpretasi QS. Ali Imrān [3]: 64 tentang
Kalimatun Sawa’: Studi Analisis Ma’na-cum-Maghza
Qurrata A’yun1, Lukita Fahriana2
{[email protected], [email protected]}
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 08953321263341,
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 085651468904 2
Abstract. This article aims to examine the interpretation of QS. Ali Imran [3]: 64 regarding the sawa
sentence as a meeting point in the concept of plurality. This study used a descriptive qualitative approach
with the ma'na-cum-maghza hermeneutic theory. The results of this study indicate that the Prophet's
invitation. against Christians and Jews to Islam is carried out through conversation and not with the
element of coercion or threat. The conversation in it is to get to know each other and find common
ground that is a common point between them. Thus, plurality can be accepted as a blessing from Allah
SWT. who are absent from the disputes and hostilities within them.
Keywords: Kalimatun sawa’, ma’na cum maghza, plurality.
Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran QS. Ali Imran [3]: 64 tentang kalimatun sawa’
sebagai titik temu dalam konsep pluralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teori hermeneutika ma’na-cum-maghza. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajakan Nabi
saw. terhadap kaum Nasrani dan Yahudi kepada Islam dilaksanakan melalui perbincangan serta tidak
dengan unsur paksaan maupun ancaman. Perbincangan di dalamnya adalah untuk saling mengenal satu
sama lain dan menemukan titik persamaan yang bersifat sebagai titik temu di antara mereka. Dengan
demikian, pluralitas dapat diamini sebagai rahmat Allah swt. yang absen dari perselihan dan permusuhan
di dalamnya.
Kata kunci: Kalimatun sawa’, ma’na cum maghza, pluralitas.
1
Pendahuluan
Pluralitas merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri. 1 Hakikat pluralitas adalah
potensi yang dapat menjadi rahmat tetapi dapat juga menjadi laknat bagi alam semesta,
tergantung pada cara manusia mengelolanya. Pluralitas yang dikelola dengan baik dapat
menjadi rahmat karena pluralitas menumbuhkan keingintahuan, mobilitas, apresiasi, salingpengertian, ko-eksistensi dan kolaborasi. Namun demikian, pluralitas yang tidak dikelola
dengan baik dapat menjadi laknat karena dapat memunculkan berbagai prasangka. Prasangka
yang tidak didasari oleh apresiasi merupakan kecurigaan. Pluralitas yang dipenuhi dengan
kecurigaan hanya membuahkan iri hati dan kecemburuan. Iri hati dan kecemburuan berlebihan
1
al-Qur’an juga menyebutkan bahwa pada hakikatnya Allah menghendaki keberagaman dari
pada keseragaman (Q.S. Al-Mȃ`idah [5]: 48.), semua itu tercipta agar manusia saling mengenal (Q.S. AlHujurȃt [59]: 13) dan berlomba-lomba dalam kebaikan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)
dapat berkembang menjadi rasa permusuhan dan menghasilkan konflik, perpecahan, dan
kerusakan.
Pengelolaan pluralitas dengan baik dapat direalisasikan dengan berbagai cara. Salah
satunya dalam bentuk wacana untuk saling berdiskusi, berkumpul dan berbagi pandangan,
pemikiran dan aspirasi sehingga dapat mengeliminasi bentuk-bentuk prasangka yang ada.
Sejarah menyatakan peristiwa diskusi ini telah terjadi antar umat beragama, seperti World
Conference on Religion and Peace2 dan A Common Word Between Us and You “Kalimat
Sawa’ bainana wa bainakum (QS. Ali ‘Imran 3: 64)”.3
Dialog antar agama melalui surat terbuka berjudul “A Common Word Between Us and
You “Kalimat Sawa’ bainana wa bainakum (QS. Ali ‘Imran 3: 64)” ini kemudian mendapat
banyak perhatian dari para intelektual di berbagai lembaga keagamaan maupun institusi
universitas dunia. Kajian mengenai dialog tersebut diantaranya telah dilakukan oleh Miroslav
Volf, Ghazi bin Muhammad dan Melissa Yarrington,[3] Waleed El-Ansary dan David K.
Linnan,[4] Joseph Victor Edwin,[5] Joseph Lumbard,[6] Saifurrahman,[7] dan Sulanam.[8]
Selain itu, pemahaman mengenai konsep kalimatun sawa (a common word) juga dibahas
lebih lanjut melalui pandangan para tokoh cendikiawan Muslim, diantaranya dalam kajian
yang dilakukan oleh Mujianto Solichin,[9] Ummi Ati Uwaida,[10] Bahrur Rosi,[11] Abdul
Khalid Aris,[12] Qurrata A’yun dan Hasani Ahmad Said. [13] Kajian-kajian di atas belum
banyak mengkaji penafsiran ayat pokok dari kalimatun sawa’ yakni QS. Ali ‘Imran 3: 64,
terlebih dengan menggunakan pendekatan hermeneutika al-Qur’an. Untuk dapat mengetahui
lebih jauh mengenai hal tersebut, tulisan ini hadir dan mencoba mengungkap interpretasinya
dengan salah satu pendekatan hermeneutika al-Qur’an ma’na cum maghza yang digagas oleh
Sahiron Syamsuddin dengan tiga langkah aplikasi; mengkaji analisis bahasa, konteks sosiohistoris, dan signifikansinya.4
2
Konferensi ini digelar pertama kali di Tokyo tahun 1970 dan dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh
agama. Konferensi tersebut terus berlanjut pada tahun 1974 dan 1979, di dalamnya dirumuskan bahwa
perdamaian merupakan persekutuan dunia (world community) yang dibangun atas dasar cinta kasih,
kebebasan, keadilan dan kebenaran. Lebih lanjut lihat Kata Pengantar oleh Muhadjir Darwin dalam [1]
3
“A Common Word” adalah sebuah dialog antar agama dalam bentuk seminar internasional. “A
Common Word” muncul atas reaksi pernyataan Paus Benediktus XVI dalam “Orasi Agung” pada tanggal
12 September 2006. Orasi tersebut menimbulkan kemarahan umat Muslim karena pernyataannya dinilai
menghina Nabi Muhammad saw. dan Islam. Pada 13 Oktober 2006, 38 pemuka agama dan intelektual
Muslim mengirimkan surat terbuka kepada Paus Benediktus untuk mengklarifikasi soal pernyataannya
tersebut. Hingga akhirnya setahun berikutnya pada tanggal 13 Oktober 2007, surat tersebut
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat terbuka (open letter) yang ditandatangani oleh 138 pemuka
agama dan intelektual Muslim dari berbagai penjuru dunia dan ditujukan kepada 28 pemuka agama
Kristen di seluruh dunia. Surat tersebut menjadi ajakan kepada seluruh umat Kristiani untuk hidup damai
dan harmonis dalam perbedaan antara “Muslim dan Kristiani” dalam rangka membina dan mewujudkan
perdamaian dunia secara bersama-sama. Lebih lanjut lihat Introduction dalam [2]
4
Sahiron Syamsuddin, lahir 5 Juni 1968, merupakan Ahli ilmu al-Qur‟an dan Tafsir
kontemporer dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat ini menjadi sebagai ketua sosiasi Ilmu Alquran
dan Tafsir se-Indonesia (AIAT), Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga, tahun 2015 pernah menjadi
Steering Committee di Netherlands-Indonesian Consortium. Di antara karya-karyanya adalah
Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur‟an (cet.1: 2009, cet. 2: 2017), An examination of Bint
al-Shati''s method of interpreting the Qur'an. (2000), Upaya integrasi hermeneutika dalam kajian alQur'an dan hadis: teori dan aplikasi (2011), Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam
Penafsiran Al-Qur‟an (2002), Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's and alZamakhsharī's Interpretations of Q.3:7 (1999), Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam
2
Hermeneutika Ma’na cum Maghza: Metodologi dan Langkah
Aplikasi
Hermeneutika ma’na-cum-magza adalah teori penafsiran al-Qur’an yang digagas oleh
Sahiron Syamsuddin. Tentunya, gagasan ini tidak terlepas dari asumsi-asumsi dasar yang
bermuara dari sikap ingin “menengahi” pro-kontra penggunaan hermeneutika sebagai metode
menafsirkan al-Qur’an. Sahiron berangkat dari asumsi bahwa Sebagian ide-ide hermeneutika
dapat diterapkan ke dalam Ulūmul Qur’an, bahkan dapat menguatkan metode penafsiran alQur’an. Secara substansial, hermeneutika dan ilmu tafsir tidaklah berbeda: sama-sama
mengajarkan cara untuk memahami dan menafsirkan sebuah teks secara benar dan cermat.
Yang membedakan antara keduanya adalah sejarah kemunculan, ruang lingkup, dan obyek
pembahasannya. Selain itu, ia berpendapat bahwa perlunya menyintesiskan dan
mengintegrasikan kajian Islam dengan disiplin-disiplin ilmu “sekular” atau Barat,
sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Islam sejak abad ke-3 H.[15, hlm. 7–8]
Sahiron mengklasifikasi aliran atau tipologi penafsiran di kalangan Islam saat ini,
kepada tiga aliran, yaitu: (1) Quasi-obyektivis tradisionalis; menurut aliran ini ajaran-ajaran
Al-Qur’an harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan sesuai dengan pemahaman,
penafsiran, dan pengaplikasian pada konteks di mana Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw. dan diajarkan kepada para sahabat.[15, hlm. 54] (2) Quasi-subyektivis; aliran
ini berpandangan bahwa penafsiran sepenuhnya adalah subyektivitas penafsir, karena
kebenaran interpretatif bersifat relatif. Salah satu tokoh aliran ini, Hassan Hanafi menegaskan
bahwa setiap penafsiran Al-Qur’an itu pasti sangat terpengaruh oleh kepentingan dan
ketertarikan penafsirnya, oleh karena itu penafsiran terhadap Al-Qur’an itu pluralistik,[15, hlm.
56] tidak hanya satu. (3) Quasi-obyektivis progesif; aliran ini sama seperti aliran pertama
dalam hal menggali makna asal, namun perbedaannya adalah aliran ini menjadikan makna
asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk menemukan pesan yang terkandung di balik
literal teks. Di antara tokoh aliran ini yaitu Fazlul Rahman dengan konsep double movement,
Muhammad al-Thalibi dengan al-tafsir al-maqaṣidī dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan
konsep al-tafsir al-siyaqī.[15, hlm. 57–58]
Dari ketiga aliran penafsiran di atas, aliran quasi-obyektivis tradisionalis dinilai
memaksakan prinsip-prinsip universal Al-Qur’an dalam konteks apapun ke dalam teks AlQur’an, sehingga pemahaman yang lahir cenderung tekstualis atau literalis. [16, hlm. 55]
Penafsiran seperti itu terkesan agak kaku dan kurang bisa menjawab masalah-masalah
kekinian, bahkan berpotensi melahirkan paham-paham radikalisme dan sebagainya.
Sedangkan aliran kedua, yaitu aliran quasi-subyektivis cenderung semaunya dalam
menafsirkan Al-Qur’an dan sangat kental dengan ideologi-ideologi penafsirnya. Aliran quasiobyektivis progresif lebih dapat diterima sebagai upaya pengembangan metode pembacaan
Al-Qur’an pada masa kini. Dalam menafsirkan Al-Qur’an, aliran ini tidak hanya terpaku
dengan makna asal teks itu diturunkan, tetapi berupaya menangkap pesan utama yang
terkandung di balik makna asal teks. Dengan kata lain, pandangan ini bisa disebut sebagai
“keseimbangan hermeneutika” (balanced hermeneutics),[15, hlm. 140] yaitu memberi perhatian
yang seimbang terhadap makna asal (al-ma’na al-aṣli) dan pesan utama (signifikan; almagza).
Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer
(2006), Hermeneutika al-Qur‟an dan Hadis (2010), Studi Al-Qur‟an Kontemporer: Wacana Baru
Berbagai Metodologi Tafsir (2002), dan lainnya. [14]
Pada hakikatnya, teori ma’na-cum-magza bukanlah sebuah teori baru dalam diskursus
hermeneutika (metode penafsiran). Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa teori ma’nacum-magza diaplikasikan dengan cara memberi perhatian yang sama terhadap makna asal
literal (al-ma’na al-aṣli) dan pesan utama (signifikansi; al-magza) di balik makna literal. Teori
ma’na-cum-magza ini adalah upaya pengembangan metode penafsiran yang diinisiasi dari
salah satu teori hermeneutika Gadamer yaitu teori application (anwendung). Sebagaimana
yang dikutip Sahiron, Gadamer menyatakan bahwa setelah seorang penafsir menemukan
makna yang dimaksud dari sebuah teks pada saat teks tersebut muncul, dia kemudian
melakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi/reinterpretasi dengan tetap
memperhatikan kesinambungan “makna baru” ini dengan makna asal teks. Dengan teori ini
diharapkan bahwa pesan teks tersebut bisa diaplikasikan pada saat penafsiran.[15, hlm. 87]
Ketika teks telah ditemukan makna literalnya, lalu dikolerasikan makna tersebut dengan
kemungkinan adanya makna kedua dan makna ketiga dengan tetap memperhatikan
komponen-komponen yang terkandung di dalam makna literal tersebut. [17, hlm. 102] Konsep
seperti ini diistilahkan oleh Gadamer dengan istilah sinn (arti) dan sinnesgemaβ (makna yang
berarti/mendalam).[15, hlm. 88]
Konsep yang sama dikemukakan oleh Hirch dengan menggunakan istilah meaning
(arti/makna) dan significance (signifikansi). Ia membedakan antara makna dan signifikansi.
Menurutnya, pembedaan itu seharusnya tidak dibatasi pada patokan dasar seputar maksud asli
pengarang. Tetapi, pembedaan itu semestinya memperhitungkan juga semua hal yang terkait
dengan makna anakronistik dan ia menyadari bahwa penyingkapan makna perlu
memperhitungkan konteks secara luas, dan tidak terbatas pada konteks pengarang saja.[18,
hlm. 133–134] Selain itu, dari kalangan sarjana muslim, ada beberapa tokoh yang mempunyai
kesamaan konsep dengan teori ma’na-cum-magza ini, di antaranya al-Ghazali dengan konsep
al-ma’na al- ẓāhir (makna lahiriah) dan al-ma’na al-batīn (makna batin). Fazlul Rahman
dengan teorinya, double movement (gerakan ganda). Dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan
konsep ma’na dan magza-nya. [15, hlm. 88]
Semua teori interpretasi di atas mengidealkan bahwa dalam menafsirkan (teks) perlu
dilakukan dengan memperhatikan konteks tekstual melalui analisa bahasa sebagai pijakan
awalnya, dan konteks sejarah teks itu muncul melalui analisa historis, kemudian digali pesan
utamanya (signifikansi) untuk dikontekstualisasikan sesuai semangat zaman, tempat, dan
waktu teks itu ditafsirkan.
Akan tetapi, menurut Sahiron semua teori hermeneutika di atas tidak membicarakan
secara gamblang mengenai “signifikansi” (magza). Oleh karena itu, dalam teori ma’na-cummagza yang digagasnya ini, ia menambahkan penjelasan tentang “signifikansi”. Menurutnya,
ada dua macam signifikansi: pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama yang
dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa nabi hingga saat
ayat ditafsirkan dalam periode tertentu. Lalu signifikansi fenomenal ini terbagi dua macam
pula yaitu: (a) signifikansi fenomenal historis, yaitu makna sebuah ayat atau kumpulan ayat
yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan; (b) signifikansi fenomenal dinamis,
yaitu pesan Al-Qur’an yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat
tertentu ditafsirkan, dan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Kedua, signifikansi ideal,
yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikansi ayat. Akumulasi
pemahaman ini akan diketahui pada akhir/tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh
Allah Swt.[15, hlm. 140–141]
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan utama seorang penafsir/pembaca
ketika memahami sebuah teks baik ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi adalah menggali pesan
utama (signifikansi) yang terkandung di balik makna literal. Namun, sebelum sampai kepada
tahap penggalian signifikansi, ada beberapa langkah metodis yang perlu ditempuh. Langkah
awal yaitu analisa bahasa; seorang penafsir harus memerhatikan bahwa bahasa yang
digunakan dalam teks ―al-Qur’an misalnya― adalah bahasa Arab abad ke-7 M. Hal ini
sangat penting dilakukan mengingat bahasa itu dinamis. Oleh karena itu, penafsir harus
mampu menguasai dasar-dasar ilmu linguistik seperti sinkronik-diakronik, sintagmatikparadigmatik, dan sebagainya. Di samping itu, untuk mempertajam analisa ini penafsir bisa
melakukan intratekstualitas, yaitu membandingkan penggunaan suatu kata yang sedang
ditafsirkan dengan penggunaannya di hadis yang lain. Apabila dibutuhkan dan
memungkinkan, penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas, yaitu analisa dengan cara
menghubungkan dan membandingkan antara hadis dengan teks-teks lain yang ada di sekitar
Al-Qur’an, seperti hadis-hadis, syair-syair Arab, dan sebagainya.[15, hlm. 141–142] Untuk
membantu dalam menganalisa bahasa, serta kaitannya dengan konteks munculnya teks hadis,
penafsir sebaiknya menghimpun semua hadis yang satu tema bahasan terlebih dahulu, di
samping juga menampilkan penafsiran atau syarh hadis oleh ulama-ulama terdahulu.
Setelah menemukan makna asal (al-ma’na al-aṣli) teks ayat, penafsir selanjutnya
menggali pesan utama (magzā; signifikansi) ayat tersebut. Dimulai dari signifikansi
fenomenal historis, yaitu dengan cara memahami konteks makro dan mikro sosial keagamaan
masyarakat yang hidup pada masa lahirnya sebuah ayat. Konteks makro adalah konteks yang
mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa Nabi itu sendiri. Konteks mikro adalah
kejadian-kejadian kecil (spesifik) yang melatarbelakangi munculnya ayat yang biasa disebut
dengan asbābun nuzul. Dan, signifikansi fenomenal dinamis, yaitu dengan cara memahami
perkembangan pemikiran dan “spirit-masa” pada saat penafsiran al-Qur’an. Selanjutnya,
signifikansi ideal, yaitu dengan memperhatikan secara cermat konteks historis dan ekspresi
kebahasaannya untuk kemudian dapat digali magzā (pesan utama) ayat yang sedang
dipahami/ditafsirkan,[15, hlm. 141–143] sehingga penafsir dapat mengkontekstualisasikan
magzā ayat sesuai konteks kekinian.
3
Analisis Interpretasi Ma’na cum Maghza dalam QS. Ali Imran [3]:
64
Padanan kata kalimatun sawȃ` dalam al-Qur’an terdapat pada satu ayat, yakni pada QS.
Ȃli ‘Imrȃn [3]: 64;
ضنَا
َ ّللاَ َوالَ نُ ْش ِركَ ِب ِه
س َواءٍ بَ ْي َننَا َو َب ْينَ ُك ْم أَالَّ نَ ْعبُدَ ِإالَّ ه
ُ ش ْيئًا َوالَ يَتَّخِ ذَ بَ ْع
ِ قُ ْل يَا أَ ْه َل ْال ِكت َا
َ ب ت َ َعالَ ْواْ ِإلَى َك ِل َم ٍة
. َّللاِ فَإِن ت ََولَّ ْواْ فَقُولُواْ ا ْش َهدُواْ بِأ َ َّنا ُم ْس ِل ُمون
ُون ه
ِ بَ ْعضا ً أ َ ْربَابًا ِهمن د
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan)
yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali
Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian
kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka
berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
3.1
Analisis Bahasa
Kalimat kalimatun sawȃ` merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata kalimah dan
sawȃ`. Kata kalimah merupakan bentuk tunggal dari kata kalim, berasal dari kata kalama yang
berarti al-lafẓah, mȃ yanṭiqu bihi al-insȃn mufradan kȃna au murakkaban (perkataan, apa
yang dibicarakan oleh manusia baik satu kata (tunggal) dan tersusun). [19, hlm. 695] Ibn Fȃris
menyebutkan bahwa kalama mengandung dua makna asal, yang pertama menunjuk kepada
pembicaraan yang dapat dipahami (naṯqin mufhimin) dan kedua kepada luka (jarȃẖin). Bentuk
kata kalimah masuk ke dalam pengertian pertama yang berarti al-lafẕah al-wȃẖidah almufhimah (sebuah perkataan yang dapat dipahami).[20, hlm. 131] Begitu juga dengan al-Fairȗz
Ȃbadȋ dalam Qȃmus al-Muẖȋṯ menjelaskan kata al-kalimah bermakna al-lafẕah dan alqasȋdah (perkataan dan maksud).[21, hlm. 1155]
Kalimah ( ) َك ِل َمةsecara bahasa berarti suatu lafaẕ (kata) yang menunjukkan makna
tunggal, baik terdiri atas satu huruf atau lebih banyak. Juga berarti ‘frasa atau ungkapan yang
sempurna maknanya’. Umpamanya Lȃ ilȃha illȃ Allȃh: kalimatut tauẖȋd. kalimat Allah adalah
hukum atau iradat-Nya.[22, hlm. 424] Kata kalimah juga telah menjadi kata serapan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perkataan atau ucapan. [23] Kata kalimah
(tunggal) di dalam al-Qur’an disebut sebanyak 28 kali, sedangkan dalam bentuk jamak, baik
disandarkan maupun tidak, disebut 14 kali. Selain kata kalimah, turunan lain dari kata kalama
dalam al-Qur’an yakni kata kalim (disebut empat kali), taklȋman (disebut satu kali), kalȃm
(baik disandarkan maupun tidak, disebut empat kali, dalam bentuk fi’l mȃḏȋ disebut enam kali,
dalam bentuk fi’l muḏȃri’ disebut 18 kali).[24, hlm. 722–723] Kata al-kalimah dalam al-Qur’an
memiliki banyak bentuk dan makna. Seperti yang dijelaskan oleh al-Ashfahani dalam
kitabnya, setidaknya lebih dari tiga makna. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 124, yang dimaksud
dengan kata kalimȃtin dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang Allah ujikan kepada Ibrȃhim
berupa perintah untuk menyembelih anaknya dan mengkhitannya serta ujian selain keduanya.
Dan kata kalimah kepada Nabi Zakariya yang termaktub pada QS. Ȃli ‘Imrȃn [3]: 39,
bermaksud kalimat tauhid. Ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah kitab Allah.
Namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata kalimah dalam ayat tersebut adalah
‘Isa. Adapun mengapa ‘Isa disebut dengan kalimah dalam ayat di atas, dan dalam firman-Nya
QS. An-Nisȃ` [4]: 171.[25, hlm. 365] Kata kalimah dalam QS. Al-An’ȃm [6]: 115, memiliki
maksud al-qaḏiyyah yaitu keputusan. Setiap keputusan disebut dengan kalimah baik
keputusan tersebut berupa ucapan maupun sebuah tindakan. Ada juga yang berkata bahwa
yang dimaksud dengan kalimatu rabbuka adalah hukum-hukum-Nya yang telah ditetapkan
dan dijelaskan kepada para hamba-Nya yang telah disampaikan, seperti dalam QS. Al-A’rȃf
[7]: 137, QS. Thȃhȃ [20]: 129, QS. Asy-Syȗrȃ [42]: 14 dan QS. Yȗnus [10]: 82.[25, hlm. 368]
Kata sawȃ` berasal dari kata sawwȃ (س َّوى
َ ), sawwȃ - yusawwȋ - taswiyah, akar katanya
terdiri atas tiga huruf, yaitu sin – wawu – yȃ.[22, hlm. 887] Menurut Ibnu Faris akar kata
tersebut menunjuk pada makna istiqȃmah (kokoh/teguh) dan makna i‘tidȃl baina syai`ain
(keseimbangan atau kesamaan antara dua sesuatu). Dari makna pertama lahir makna
‘menyempurnakan’ karena sesuatu yang sudah sempurna berarti ia telah kokoh dan teguh
demikian pula ‘bagian tengah’ sebuah rumah atau yang lainnya disebut sawȃ` karena yang
pertengahan itu adalah bagian yang paling kokoh di antara bagian-bagian yang lain.
Kemudian, dari makna kedua kata sawȃ` juga dipakai di dalam arti ‘sama’, demikian juga
istilah lȃ siyyamȃ (lebih-lebih) yang secara harfiah menunjukkan arti ‘tidak sama’ karena hal
yang dimaksud itu memiliki keistimewaan dan tidak sama dengan yang lainnya.[26, hlm. 112]
Al-Fairȗz Ȃbadȋ dalam Qȃmus al-Muẖȋṯ menjelaskan kata sawȃ` bermakna al-‘adl wa
al-wasṯ (adil dan tengah-tengah).[21, hlm. 1297] Al-Ashfahani dalam kitabnya membahas kata
sawȃ` dalam bagian dari kata sawȃ. Kata al-musȃwȃh artinya adalah persamaan dalam ukuran
dan timbangan. Dikatakan dalam kalimat arab ب
ِ سا ٍو ِلذَالِكَ الث َّ ْو
َ َهذَا ث َ ْوبٌ ُمartinya adalah kain ini
sama dengan kain itu. Begitu juga dalam kalimat سا ٍو ِلذَالِكَ الده ِْره َِم
َ َهذَا الده ِْر َه ُم ُمartinya dirham ini
senilai dengan dirham itu. Terkadang kata ُ س َاوة
َ ْال ُمjuga digunakan untuk menyamakan kaifiyah
(cara kerja) nya, contoh seperti kalimat سا ٍو ِلذَالِكَ الس ََّوا ِد
َ َهذَا الس ََّوادُ ُمartinya baju duka (yang
berwarna hitam) ini sama proses pembuatannya dengan baju duka yang itu. Meskipun hakikat
persamaan itu kembali pada letak pembuatannya, bukan pada jenis bajunya, namun kalimat
tersebut digunakan untuk menggambarkan adanya kesamaan.[27, hlm. 328]
Derivasi kata sawȃ dalam al-Qur’an menurut al-Ashfahani memiliki makna yang
berbeda. Salah satu diantaranya, kata ا ْست ََوىyang berarti sama, dapat digunakan dalam dua
jenis; salah satunya apabila ada dua fȃ’il (subjek) atau lebih, contohnya seperti kalimat ا ْست ََوى
ع ْم ٌرو فِي َكذَا
َ زَ ْيدٌ َوartinya Zaid dan ‘Amru sama dalam hal ini maksudnya keduanya sama.
Seperti dalam firman Allah QS. At-Taubah [9]: 19. Sedangkan jenis penggunaan kata ا ْست ََوى
adalah untuk menyemakan suatu jenis, contohnya seperti firman Allah pada QS. An-Najm
[53]: 6 dan QS. Al-Mu`minun [23]: 28. Dan ketika kata ا ْست ََوىdisandingkan dengan huruf علَى
َ
maka ia bermakna penguasaan, contohnya seperti firman Allah QS. Thȃhȃ [20]: 5. Ada yang
mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah semua sama di hadapan-Nya antara yang ada
di langit dan di bumi, maksudnya semua tegak dengan kehendak Allah yang menyamakan
semuanya, hal ini seperti firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 29. Ada juga yang mengatakan
bahwa ayat tersebut bermakna segala sesuatu sama di hadapan-Nya, maka tidak ada sesuatu
yang lebih dekat dengan-Nya dibanding yang lainnya, karena Allah swt. tidak seperti jasad
(fisik) yang berada di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Apabila kata ا ْست ََوىdisandingkan
dengan huruf ِإلَى, maka ia bermakna pencapaian akhir, baik dalam artian fisik, ataupun dalam
artian penguasaan atau pengurusan, dan mengenai hal ini terdapat dalam firman Allah dalam
QS. Fushshilat [41]: 11.[27, hlm. 329–330]
Kata س ِوي
َّ الdigunakan bagi orang yang terbebas dari sikap ifrȃṯ (berlebih-lebihan dalam
sesuatu) dan tafrȋṯ (mengurangi hak sesuatu) baik dalam bentuk ukurannya ataupun tata
caranya. Seperti dalam firman-Nya QS. Maryam[19]: 10 dan QS. Thȃhȃ [20]: 135. Kalimat
س ِوي
ُ – س ِوي
َ ٌ َمكَانartinya tempat pertengahan, ia dapat menggunakan kata س َوي
َ – س َوا ٌء
َ artinya
adalah sama, yaitu sama sisi-sisinya. Dan kalimat tersebut dapat digunakan dalam bentuk sifat
dan waktu, asal kata tersebut adalah mashdar. Seperti dalam QS. Ash-Shȃffȃt [37]: 55, QS.
Al-Baqarah [2]: 108, dan QS. Al-Anfȃl [8]: 58. Sedangkan dalam QS. Ȃli ‘Imrȃn [3]: 64 arti
kata س َوا ٌء
َ adalah adil atau benar dalam berhukum. Dan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 6, QS. AlMunȃfiqȗn [63]: 6, QS. Ibrahim [14]: 21, dan QS. Al-Hajj [22]: 25 artinya adalah sama. Kata
س َِوىdan kata س َوا ٌء
َ yaitu selain. Kalimat ِع ْندِي َر ُج ٌل
َ terkadang digunakan untuk mengartikan غي َْر
َ س َِواكartinya aku punya orang selainmu, maksudnya ada orang lain yang mengisi tempatmu
selain dirimu atau yang menggantikanmu.[27, hlm. 334–335]
Penggabungan kata kalimah dan sawȃ` menjadi kalimatun sawȃ` dalam kaidah
kebahasaan menjadi suatu hal yang istimewa, karena kata sawȃ` tidak mengikuti bentuk kata
kalimah (muannats). Hal ini dijelaskan oleh al-Ṯabarȋ yang mengutip para ahli bahasa, bahwa
kata sawȃ` dalam ayat ini merupakan isim dan bukan sifat dari kata kalimah, sehingga
bentuknya mengikuti kata kalimah tersebut.[28, hlm. 445]
Pemaknaan kalimatun sawa’ secara kebahasaan juga telah dibahas oleh al-Ṯabarȋ,[28,
hlm. 441] al-Qurṯubȋ,[29, hlm. 288] dan al-Marȃghȋ[30, hlm. 308–309] dalam tafsirnya sepakat
memaknai kalimatun sawȃ` sebagai kalimat atau perkataan yang sama dan adil yang di antara
kami dan kalian tidak ada perbedaan. Perkataan ini telah disepakati oleh para Rasul dan dalam
Kitab-Kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Yang dimaksud kesepakatan atau
perkataan yang adil adalah hanya beribadah atau tidak tunduk kecuali kepada Allah swt dan
tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dengan demikian antara Islam dan Ahl al-kitȃb
sama-sama meyakini bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang satu yaitu Allah yang
telah mengutus para Nabi dan Rasul.
3.2
Konteks Sosio-Historis QS. Ali ‘Imran [3]:64
Ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah yakni ayat yang turun setelah
migrasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Begitu Nabi mencapai
Madinah pada 622 M, ia menemukan bahwa orang-orang Madinah merupakan masyarakat
plural baik dari segi agama dan etnisnya. Selain Muslim dari golongan Anshar dan Muhajirin,
di sana juga hidup orang Yahudi, Kristen, dan penyembah berhala, bahkan jauh sebelum
migrasi Nabi. Berkenaan dengan suku-suku Arab di kota, setidaknya, ada dua suku utama,
yaitu Aus dan Khazraj, yang saling berselisih satu sama lain. Mempertimbangkan perlunya
persatuan di antara komunitas agama dan suku di sana, Nabi Muhammad kemudian
menginisiasi "Piagam Madinah" (Mithaq al-Madina). Dengan piagam ini, semua komponen
kota dapat hidup bersama secara harmonis dan saling membantu membangun peradaban.[31,
hlm. 133] Secara lengkap isi perjanjian Madinah itu dimuat dalam buku Sirah Muhammad
karya Ibnu Ishaq, yang banyak dinukil oleh tokoh-tokoh sejarah.[32, hlm. 231–233], [33, hlm. 84]
Di antara isi Piagam Madinah adalah bahwa negara mengakui dan melindungi kebebasan
menjalankan ibadah agama masing-masing, semua orang memiliki kedudukan yang sama
sebagai anggota masyarakat.[33, hlm. 93–94] Sehingga pada saat itu, penduduk Madinah dapat
hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
Permulaan Surat Ali ’Imran dari ayat pertama hingga ayat delapan puluh tiga turun pada
utusan dari penduduk Najran yang datang pada 9 H. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam
Dalail an-Nubuwah, Ibnu Ishaq berkata, bercerita kepadaku Muhammad bin Sahal bin Abi
Umamah dengan berkata, ”Ketika penduduk Najran datang kepada Rasulullah saw.
Menanyakan tentang Isa bin Maryam, turun pada mereka ayat awal surat Ali ’Imran hingga
ayat delapan puluhan”.[34, hlm. 91]
Ayat 64 ini dilatarbelakangi oleh peristiwa mubahalah5 yang terjadi pada ayat 59-63.6
Ajakan kepada kalimatun sawa’ (titik temu) menjadi jawaban final dari kisah mubahalah
tersebut. Diceritaakan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, peristiwa mubahalah diawali oleh
kedatangan utusan Nasrani Najran kepada Rasulullah saw. Utusan tersebut terdiri dari 60
orang penunggang. Di antara mereka terdapat 14 orang pemukanya. Ke-60 orang itu
menyerahkan persoalan kepada tiga orang. Ketiga orang itu ialah Aqib, Sayyid, dan Abu
Haritsah bin Alqamah. Ketiganya merupakan pemimpin, orang pintar dalam berunding.
Mereka pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah saw. Dan memasuki masjid ketika
beliau tengah shalat ashar. Ketika waktu shalat mereka tiba, mereka pun mendirikan shalatnya
di dalam masjid. Rasulullah pun bersabda untuk membiarkan mereka beribadah. Ketiga utusan
itu pun berbincang dengan Rasulullah, mereka mengatakan tentang Isa sebagai Allah, putra
Allah, dan tuhan ketiga beserta keterangan mereka akan tiga hal tersebut. Hingga akhirnya
Rasulullah bersabda kepada kedua pendeta, ”Masuk Islamlah kamu!” keduanya menjawab,
”Kami telah masuk Islam.” Nabi bersabda, ”Sesungguhnya kamu belum masuk Islam. Maka
Islamlah!” Keduanya menjawab, ”Bahkan kami telah masuk Islam sebelum kamu.” Nabi
bersabda, ”Kalian berdua berdusta. Kalian menolak Islam. Kalian juga berpandangan bahwa
Allah punya anak. Ibadah kalian kepada salib. Dan kalian juga makan babi.” Kedua pendeta
bertanya, ”Kalau begitu, siapa bapaknya, hai Muhammad?” Maka Rasulullah saw. Diam dan
5
Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa
kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta.
Nabi mengajak utusan Nasrani Najran ber-mubȃhalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti
kebenaran Nabi Muhammad saw. Lihat catatan kaki tentang mubahalah pada [35]
6
Hal ini diungkap dalam banyak penafsiran, di antaranya dalam [29], [36]–[40]
tidak menjawab keduanya. Berkaitan dengan hal itu Allah menurunkan ayat mulai dari
permulaan surat Ali Imran hingga mencapai 80-an ayat.[36, hlm. 525–526]
Setelah Rasulullah saw. Mendapat informasi dan penjelasan dari Allah sebagai landasan
untuk memutuskan perselisihan antara beliau dengan mereka, beliau diperintah untuk
mengajak mereka bermubahalah, jika mereka tetap menolak keputusan itu. Nabi mengajak
mereka saling mengutuk. Namun mereka meminta kesempatan untuk merenungkan persoalan
itu, dan kembali untuk menyampaikan pendapat soal ajakan Nabi ber-mubahalah itu. Hal ini
tidak lain karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah benar-benar
seorang nabi yang diutus, dan tak ada satu pun yang pernah mengutuk seorang nabi. Kalu pun
ada yang berani mengutuknya, maka sungguh ia akan musnah sampai ke akar-akarnya. Aqib
sang pemimpin pun menyarankan untuk kembali memeluk pendapat yang dianut kaum
Nasrani tentang Isa, dan membiarkan Muhammad, serta kembali ke negeri mereka. Seusai
berunding, mereka kembali menemui Nabi saw. seraya berkata, ’Hai Abu Qasim, kami telah
memutuskan untuk tidak akan melaknatmu, membiarkanmu menganut agamamu, dan kami
pun akan kembali menganut agama kami. Namun, utuslah salah seorang sahabatmu yang
kamu ridhai guna menyertai kami dan yang akan memutuskan perselisihan di antara kami
mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekayaan kami. Kami rela dihukum oleh
dia.’ Setelah melaksanakan shalat zhuhur, Nabi pun akhirnya memutuskan untuk mengirim
Abu Ubaidah bin al-Jarah untuk pergi bersama Nasrani Najran dan memutuskan perkara yang
mereka perselisihkan dengan hak.[41, hlm. 381]
Selain dilatarbelakangi perdebatan dengan utusan Najran hingga peristiwa mubahalah,
ayat ini juga menjadi isi dari surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Raja Heraclius di
Romawi. Penjelasan ini telah banyak dikutip oleh para mufassir, 7 salah satu riwayatnya ialah
dalam syarah Bukhari pada riwayatnya yang ia ketengahkan melalui jalur Az-Zuhri, dari
Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Abu Sufyan tentang
kisahnya ketika masuk menemui kaisar, lalu kaisar menanyakan kepadanya tentang nasab
Rasulullah Saw., sifat-sifatnya, dan sepak terjangnya, serta apa yang diserukan olehnya. Lalu
Abu Sufyan menceritakan hal tersebut secara keseluruhan dengan jelas dan apa adanya.
Padahal ketika itu Abu Sufyan masih musyrik dan belum masuk Islam, hal ini terjadi sesudah
adanya Perjanjian Hudaibiyyah dan sebelum penaklukan kota Mekah, seperti yang dijelaskan
oleh hadis yang dimaksud. Juga ketika ditanyakan kepadanya, apakah Nabi Saw. pernah
berbuat khianat? Maka Abu Sufyan menjawab, "Tidak. Dan kami berpisah dengannya selama
suatu masa, dalam masa itu kami tidak mengetahui apa yang dilakukannya." Kemudian Abu
Sufyan mengatakan, "Aku tidak dapat menambahkan suatu berita pun selain dari itu." Tujuan
utama dari pengetengahan kisah ini ialah bahwa surat Rasulullah Saw. disampaikan kepada
kaisar yang isinya adalah seperti berikut:[36, hlm. 529]
، فَأ َ ْس ِل ْم ت َ ْسلَ ْم،ُ أ َ َّما بَ ْعد.ع َلى َم ْن اتَّبَ َع ْال ُهدَى
ُ مِ ْن ُم َح َّم ٍد َر،الرحِ يم
َّ الرح َم ِن
َّ ِ" ِبس ِْم هللا
َ سال ٌم
ِ عظِ ِيم الر
َ سو ِل هللاِ إلَى ه َِر ْق َل
َ ،وم
َّ ََوأ َ ْس ِل ْم يُؤْ تِكَ هللاُ أَجْ َرك َم َّرتَي ِْن فَإِن ت ََولَّيْت
س َواءٍ بَ ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم أَال
ِ َو {يَا أَ ْه َل ْال ِكت َا،علَيْكَ إِثْ َم األريسيهِين
َ فإن
َ ب تَعَالَ ْوا إِلَى َك ِل َم ٍة
َّ ُون
َّ نَ ْعبُدَ إِال
َ ّللاَ َوال نُ ْش ِركَ بِ ِه
َّللاِ فَإ ِ ْن ت ََولَّ ْوا فَقُولُوا ا ْش َهدُوا بِأَنَّا ُم ْس ِل ُمون
ُ ش ْيئًا َوال يَتَّخِ ذَ بَ ْع
ِ ضنَا بَ ْعضًا أ َ ْربَابًا مِ ْن د
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad
Rasulullah, ditujukan kepada Heraklius, pembesar kerajaan Romawi, semoga keselamatan
terlimpah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma Ba'du: Maka masuk Islamlah,
niscaya engkau akan selamat; dan masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberimu pahala
7
Penafsiran yang membahas soal surat dakwah ini dapat ditemukan dalam Tafsir al-Baghawi,
Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Katsir yang ditelusuri dalam [38, hlm. 609], [39, hlm. 279], [42], [43,
hlm. 81]
dua kali. Tetapi jika engkau berpaling, maka sesungguhnya engkau menanggung dosa kaum
arisin (para petani). Dan di dalamnya disebutkan pula firman-Nya: Hai Ahli Kitab, marilah
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak
(pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain dari Allah. Jika
mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami adalah orangorang yang menyerahkan diri (kepada Allah)." (Ali Imran: 64)
Selain diturunkan kepada utusan Nasrani Najran dan Raja-raja Romawi, para mufasir
juga menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi Madinah. Hal ini
dikarenakan khitab yang terdapat dalam ayat ini ialah ahlul kitab. Dalam menerangkan hal ini,
al-Qurthubi dan al-Thabari menjelaskan dua perbedaan, pertama, ayat ini diperuntukkan
kepada ahli Najran dengan mengutip riwayat Muhammad bin Ja’far bin Zubair, dan Ibnu Zaid,
dan al-Suddi, kedua, diperuntukkan kepada Yahudi Madinah dengan mengutip riwayat
Qatadah dan Ibnu Juraij. Sedangkan keduanya (al-Qurthubi dan al-Thabari) sepakat
mengkategorikan kedua golongan yakni Narani Najran dan Yahudi Madinah ke dalam khitab
ahlul kitab dalam ayat ini, karena keduanya sama-sama diberikan kitab yakni Injil dan
Taurat.[28, hlm. 442], [29, hlm. 289]
Dalam tafsir lain, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ahlul kitab dalam ayat ini adalah
yang diturunkan kepadanya kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur’an.[44, hlm. 290–91] M.
Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa ahl al-kitȃb pada ayat ini bukan hanya delegasi
Kristen Najran seperti yang dituju pada ayat sebelumnya, akan tetapi terdiri dari semua orang
Yahudi dan Nasrani. Ia juga mengutip pendapat sementara ulama yang memasukkan
kelompok yang diduga memiliki kitab suci dalam pengertiannya, baik yang bertempat tinggal
di Madinah atau di daerah-daerah lain.8 Ia pun mengatakan bahwa pesan ayat ini ditujukan
kepada mereka semua (dalam artian ahl al-kitȃb tadi) bahkan hingga akhir zaman.[40, hlm.
108]
3.3
Signifikansi Kalimatun Sawa’ dalam QS. Ali Imran [3]: 64
Melalui pembacaan di atas, dapat dipahami signifikansi fenomenalnya ialah dakwah
Nabi Muhammad saw. terhadap kaum Nasrani dan Yahudi kepada Islam melalui
perbincangan di antara mereka dan tidak ada paksaan di dalamnya. Meski pada akhirnya
perdebatan ini tidak membuat kaum Nasrani dan Yahudi berpindah ke Islam, namun pada
dasarnya mereka telah menyadari kebenaran risalah kenabian, sehingga mereka pun menolak
untuk ber-mubahalah dan kembali ke negerinya dengan memberikan jaminan harta mereka
8
Dalam bukunya yang lain, M. Quraish Shihab menjelaskan perihal pengertian ahl al-kitȃb dan
pendapat sementara ulama lain akan hal tersebut. Seperti pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan
bahwa yang disebut ahl al-kitȃb adalah orang Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel, tidak
termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Imam Abu Hanifah dan ulama
Hanafiah menyatakan bahwa yang disebut ahl al-kitȃb adalah siapapun yang mempercayai salah seorang
Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah swt., tidak terbatas pada kelompok penganut agama
Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada orang-orang yang hanya percaya kepada Suẖuf Ibrȃhȋm
atau Kitab Zabur, maka ia termasuk dalam jangkaun pengertian ahl al-kitȃb. Di samping itu sebagian
ulama salaf menyatakan bahwa setiap umat yang diduga memiliki kitab suci dapat dianggap sebagai ahl
al-kitȃb, seperti halnya orang-orang Majusi. Kesimpulan yang diambil oleh Quraish Shihab bahwa yang
dimaksud dengan ahl al-kitȃb adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun dan
dari keturunan siapapun mereka. Lihat [45, hlm. 336–386]
kepada umat Muslim. Kalimatun sawa’ di sini adalah kalimat yang sama dan adil di antara
Ahlul Kitab, bahwa risalah kenabian yakni keimanan dan peribadatan hanyalah kepada Allah
swt., telah tertulis dan diajarkan dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Maka ajakan/dakwah
Nabi saw. kepada titik temu ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada sebelumnya
seperti yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang diutus pada kaum mereka.
Bentuk ajakan Nabi dalam usaha menebarkan ajaran Islam di tengah-tengah perbedaan
kaum ini menjadi salah satu cara yang patut dicontoh dalam hubungan umat beragama
maupun umat manusia secara umumnya. Usaha untuk mencapai sebuah titik temu (kalimatun
sawa’) di tengah keberagaman tentu menjadi sebuah tantangan terlebih dalam kehidupan
masyarakat saat ini, dimana terjadi perkembangan pesat di tiap elemennya. Tapi bukan tidak
mungkin dalam menggapainya, seperti yang juga telah dicontohkan oleh Nabi saw., kita pun
dapat berusaha menggapai titik temu tersebut. Jika sekiranya kita bertemu dalam satu titik,
maka hendaknya bekerja sama dalam hal itu. Namun sekiranya tidak bertemu dalam satu titik
(keyakinan mengenai Tuhan misalnya), maka mari mencoba menggapai titik lain, yakni saling
berlomba pada kebaikan.[46]
Pesan utama (signifikansi) dalam ayat ini adalah untuk berusaha saling mencari titik
temu (kalimatun sawa’) di antara sesama, hal itu didasari oleh kesadaran pemahaman bahwa
Allah telah menentukan penciptaan manusia dengan keragamannya. Pencarian ini didapatkan
salah satunya dengan bentuk dialog agar saling mengenal satu sama lain hingga tidak terjadi
perselisihan, dapat bekerja sama dalam kebaikan dan membangun peradaban yang lebih baik
untuk masa depan.
4
Kesimpulan
Kata kalimatun sawa’ dalam al-Qur’an tercantum dalam Surat Ali ‘Imran ayat 64.
Kalimatun sawa’ secara bahasa berarti kalimat yang sama. Sedangkan setelah dilakukan
analisis interpretasi menggunakan pendekatan ma’na cum maghza, signifikansinya ialah
pertama, ajakan Nabi Muhammad saw. terhadap kaum Nasrani dan Yahudi kepada Islam
melalui perbincangan di antara mereka dan tidak ada paksaan di dalamnya. Ajakan tersebut
diberi istilah kalimatun sawa’ karena ajakan untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah
swt. juga telah termaktub dalam kitab-kitab mereka sebelumnya, sehingga tidak ada perbedaan
di antara mereka dalam hal itu. Kedua, mengajak manusia untuk berusaha saling mencari titik
temu (kalimatun sawa’) di antara sesama, Hal itu didasari oleh kesadaran pemahaman bahwa
Allah telah menentukan penciptaan manusia dengan keragamannya. Pencarian ini didapatkan
salah satunya dengan bentuk dialog agar saling mengenal satu sama lain hingga tidak terjadi
perselisihan, dapat bekerja sama dalam kebaikan dan membangun peradaban yang lebih baik
untuk masa depan.
5
[1]
[2]
[3]
[4]
Referensi
Z. Maliki, Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan
Demokrasi. Yogyakarta: Galang Press, 2000.
Kalimatun Sawa A Common Word Between Us and You. Jordan: The Royal Aal AlBayt Institute for Islamic Thought, 2009.
M. Volf, G. bin M. bin Talal, G. bin M. (Prince of Jordan.), dan M. Yarrington, A
Common Word: Muslims and Christians on Loving God and Neighbor. Wm. B.
Eerdmans Publishing, 2010.
W. El-Ansary dan D. Linnan, Muslim and Christian Understanding: Theory and
Application of “A Common Word.” Springer, 2010.
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
J. V. Edwin, “A Common Word Between Us and You: A New Departure in Muslim
Attitudes Towards Christianity,” University of Birmingham, 2010.
J. E. B. Lumbard, The Uncommonality of a Common Word. Crown Center for Middle
East Studies, Brandeis University, 2009.
S. Saifurrahman, “Muslim and Christian Understanding: Theory and Aplication of ‘a
Common Word,’” TASÂMUH, vol. 13, no. 2, Art. no. 2, Jun 2016, Diakses: Sep 01,
2020.
[Daring].
Tersedia
pada:
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/165.
S. Sulanam, “‘A COMMON WORD’: Sebagai Titik Kesepahaman Muslim – Kristen,”
Toler. Media Ilm. Komun. Umat Beragama, vol. 11, no. 1, Art. no. 1, Nov 2019, doi:
10.24014/trs.v11i1.8287.
M. Solichin, “Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of ‘A
Common Word Between Us and You’ (Studi Pemikiran Mohamed Talbi dalam Buku
‘Iyal Allah Afkar Jadidah fi ‘Alaqat al-Muslim bi Nafsihi wa bi al-Akharin),” J. Religi
J. Studi Islam, vol. 6, no. 1, 2016.
U. A. Uwaida, “Konsep Kalimatun Sawa Menurut Nurcholish Majid,” skripsi, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
B. Rosi, “‘Kalimah Sawa’ Sebagai Konsep Teologi Inklusif Nurcholish Madjid,” Okt
2017,
Diakses:
Mei
27,
2020.
[Daring].
Tersedia
pada:
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36520.
A. K. Aris, “Penafsiran Nurcholish Madjid Atas Al-Qur’an (studi Analisis Surat Ali
Imrān Ayat 64),” Agu 2020, Diakses: Okt 14, 2020. [Daring]. Tersedia pada:
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52150.
Q. A’yun, “Kalimatun Sawȃ` in the Perspective of Indonesian’s Interpretation,”
Afkaruna Indones. Interdiscip. J. Islam. Stud., vol. 15, no. 1, Art. no. 1, Jun 2019, doi:
10.18196/AIIJIS.2019.0095.55-81.
www.uin-suka.ac.id,
“UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta.”
https://uinsuka.ac.id/id/page/detil_dosen/196806051994031003-Sahiron (diakses Mei 29, 2020).
S. Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an. Yogyakarta:
Nawasea Press, 2017.
A. Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKis, 2010.
M. Hanif, “Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap
Penafsiran Al-Qur’an,” MAGHZA J. Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, vol. 2, no. 1, hlm. 93–
108, Mei 2017, doi: 10.24090/maghza.v2i1.1546.
H. Prakosa, “Penyingkapan Makna: Sekedar Kembali ke Maksud Pengarang? (Pokokpokok Pemikiran E.D. Hirsch Jr. Tentang Interpretasi,” dalam Upaya Integrasi
Hermeneutika Dalam Kajian Alquran dan Hadis (Teori dan Aplikasi), Yogyakarta:
Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011.
L. Ma’lȗf, Al-Munjid fȋ al-Lughah. Bairȗt: Dar al-Masyriq, 2002.
A.-ẖusain A. ibn F. Ibn Zakariya, Mu’jam Maqȃyis al-Lughah, vol. 5. Mesir: Maktabah
al-Khabakhȋ, 1981.
M. bin Y. al-Fairȗz Ȃbadȋ, Al-Qȃmȗs al-Muẖȋṯ. Bairȗt: Al-Resalah, 2003.
M. Q. Shihab, Ensiklopedi Al-Qur’an: Kajian Kosakata. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kalimah (diakses
Jun 22, 2020).
M. F. ‘Abd al-Bȃqȋ, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfȃẕ al-Qur’ȃn al-Karȋm. Mesir: Dȃr alHadȋts, 1996.
[25] A.-R. Al-Ashfahani, Al-Mufradȃt fȋ Gharȋb al-Qur’ȃn, vol. 3. Depok: Pustaka
Khazanah Fawa`id, 2017.
[26] A.-ẖusain A. ibn F. Ibn Zakariya, Mu’jam Maqȃyis al-Lughah, vol. 3. Mesir: Maktabah
al-Khabakhȋ, 1981.
[27] A.-R. Al-Ashfahani, Al-Mufradȃt fȋ Gharȋb al-Qur’ȃn, vol. 2. Depok: Pustaka
Khazanah Fawa`id, 2017.
[28] Al-Ṯabarȋ, Jȃmi’ al-Bayȃn ‘an Ta`wȋl Ayi al-Qur’ȃn, vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam,
2008.
[29] Al-Qurthubi, Al-Jȃmi’ li Ahkȃm al-Qur’ȃn, vol. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
[30] M. al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
[31] S. Syamsuddin, “Ma’na-Cum-Maghza Approach to the Qur’an: Interpretation of Q.
5:51,” Nov 2017, hlm. 131–136, doi: 10.2991/icqhs-17.2018.21.
[32] A. Guillaume, The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah.
Karachi: Oxford University Press, 1970.
[33] N. Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
[34] I. As-Suyuthi, Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an. Pustaka AlKautsar, 2014.
[35] K. Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 2010.
[36] M. N. Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Gema Insani,
1999.
[37] S. Quthb, Fi Zhilal al-Qur’an, vol. II. Jakarta: Robbani Press, 2001.
[38] M. H. ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nuur. Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 2000.
[39] H. Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz III. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
[40] M. Q. Shihab, Tafsir Al-Misbȃẖ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta:
Lentera Hati, 2006.
[41] I. Ishaq, Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah saw. Jakarta: Akbar
Media, 2012.
[42] “Al
Quran
KSU
Electronic
Moshaf
project.”
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=en#aya=3_64&m=hafs&qaree=husary&trans=en_s
h (diakses Jun 22, 2020).
[43] I. Taimiyyah, Tafsȋr Syaikh al-Islȃm Ibn Taimiyyah, vol. II. Saudi Arabia: Dar Ibn alJauzi, 1432.
[44] W. Zuhaili, Tafsir al-Munir, vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
[45] M. Q. Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat.
Bandung: Mizan, 1997.
[46] Keragaman Kehendak Tuhan: Inilah Perjanjian Nabi dengan Kaum Nasrani (Part 2) |
Shihab & Shihab. .