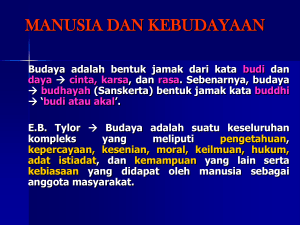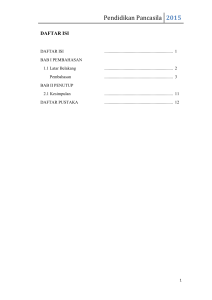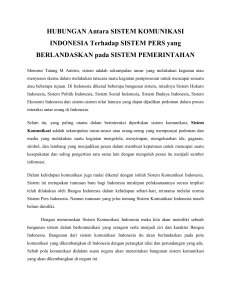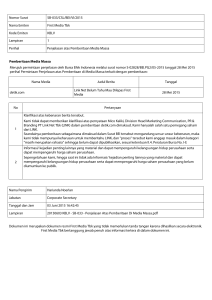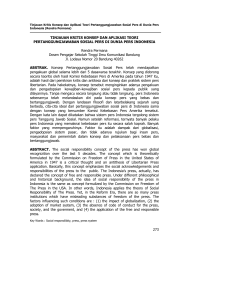1. Salah satu ragam dari beberapa tolok ukur dalam analisis politik di antaranya adalah: a) Analisis negara demokratis tentang kebebasan pers dan sistem multi-partai. b) Peran masyarakat sipil (civil society). Pertanyaannya: Coba anda analisis poin a dan b tersebut untuk menjelaskan perpolitikan di Indonesia saat ini. A..Melihat situasi perpolitikan di Indonesia saat ini jika berbicara dalam konteks kebebasan pers dan sistem multi-partai adalah yang pertama kebebasan pers di Indonesia Kebebasan Pers di Indonesia dinilai memburuk dalam setahun terakhir. Hal ini dipicu oleh rentetan peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. Diketahui, pada 2018, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia hanya menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2018 versi Repoters Without Borders. Bahkan peringkat IKP Indonesia lebih rendah dibanding Timor Leste yang menempati peringkat 93. Kebebasan pers adalah salah satu capaian utama demokrasi Indonesia yang sangat membanggakan hingga kini. Namun, kondisi itu bukannya tidak menimbulkan persoalan. Belakangan, kita mulai merasakan dampak dari ekses kebebasan pers. Di satu sisi, kualitas kerja pers sebagai pengumpul dan penyampai informasi menurun, mungkin lantaran ketatnya persaingan serta merebaknya media daring yang lebih menitikberatkan kecepatan, alih-alih kedalaman dan akurasi berita. Menjadi wajar jika media massa berreputasi besar pun terjebak menyebarluaskan berita yang kebenarannya belum sepenuhnya terkonfirmasi. Di sisi lain, pers juga dianggap belum memaksimalkan perannya sebagai agent of control bagi jalannya kekuasaan. Sebagaimana galibnya demokrasi terbuka, salah satu ukuran keberhasilannya ditentukan oleh peran aktif media massa dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Sayangnya, dalam konteks itu, pers Indonesia justru lebih sering menjadi corong bagi kepentingan politik-ekonomi segelintir elit. Memasuki tahun-tahun politik 2018-2019 pers dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Bagaimana pers memaknai ulang kebebasan di satu sisi dan independensi di sisi yang lain? Akankah pers mampu menjadi elemen demokrasi, di tengah tarikan arus untuk berpihak secara politis dan kebutuhan untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan? Kuasa modal dan kepentingan politik Fred S. Siebert dalam bukunya Four Theories of the Press, membagi pers ke dalam empat corak, yakni otoritarian, libertarian, komunis dan pers bercorak liberal-kritis atau liberal dengan kewajiban tanggung jawab sosial. Jika dipahami secara sederhana, keempat corak itu sebenarnya dapat diringkas ke dalam dua corak saja yakni otoritarian dan libertarian. Corak ketiga dan keempat, dalam banyak hal hanyalah modifikasi dari dua corak arusutama tersebut. Pada corak otoritarian, pers tidak memungkinkan untuk menjalankan fungsi kontrol pada negara, alih-alih mendukung setiap kebijakan pemerintah dengan tanpa syarat. Negara memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terlebih kritik. Hal serupa terjadi pada pers bercorak komunis, dimana pers hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa tunggal, yakni pemerintah. Kondisi sebaliknya terjadi pada pers bercorak libertarian. Pada corak ini, pers dimungkinkan atau bahkan diharuskan untuk menjadi semacam kekuatan check and balances bagi pemerintah. Pada corak inilah adagium pers sebagai pilar keempat demokrasi, setelah lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dapat termanifestasikan. Sekilas, pers libertarian tampak seperti pengejawantahan nilai dan prinsip kebebasan pers yang sesungguhnya. Pers libertarian dianggap nihil dari potensi dominasi negara dan kekuatan lainnya. Padahal sebenarnya tidak. Jika pada corak otoritarian, musuh kebebasan pers adalah negara dengan jejaring kekuasaannya, pada pers libertarian musuh itu bernama "kuasa modal". Pertautan modal dengan pers sebenarnya bukan fenomena baru. Hal itu sudah terjadi sejak awal mula pers lahir di daratan Eropa. Pada mulanya, pers memang diinisiasi oleh kelompok borjuis pemegang kapital yang menganut paham liberalisme. Di Indonesia sendiri, konglomerasi media mulai menggejala pasca reformasi 1998 dan terus bertahan hingga saat ini. Pakar komunikasi Ign. Haryanto dalam bukunya Indonesia Dibreidel, menyebut bahwa pers tidaklah semata-mata memproduksi teks dan informasi, tetapi juga merupakan sebuah kelembagaan, dimana begitu banyak kepentingan ingin merasuki dirinya. Tarik menarik kepentingan inilah yang beberapa tahun belakangan tampak betul dalam dunia pers nasional. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kuasa modal berpengaruh secara signifikan terhadap dunia pers. Jaringan media massa nasional yang berjumlah tidak sedikit itu pun nyatanya hanya dikuasai oleh segelintir elit. Kondisi kian akut ketika para konglomerat pemilik jaringan media massa itu juga memiliki kepentingan politik praktis. Alhasil, media massa di bawah kepemilikannya pun luruh ke dalam kepentingan ekonomi-politik para pemiliknya. Harus diakui bahwa era kebebasan pers yang kita nikmati hari ini nyatanya hanyalah kebebasan yang nyaris semu. Informasi dan berita yang tersaji di hadapan kita hampir pasti sudah terdistorsi oleh ragam kepentingan. Sebuah peristiwa atau fenomena dapat dengan mudah dipelintir, dibingkai dan dimanipulasi demi membentuk persepsi masyarakat. Apa yang mengemuka saat ini boleh jadi adalah perwujudan dari ungkapan sinis Paul Joseph Goebels yang berbunyi "kebohongan yang diulang-ulang akan membentuk persepsi masyarakat bahwa itu adalah sebuah kebenaran". Melawan hegemoni media massa Peradaban manusia hari ini telah sampai pada apa yang diistilahkan Manuel Castels sebagai the age of media society. Era di mana manusia modern nyaris tidak dapat hidup tanpa media. Kondisi yang ideal adalah jika media massa mampu menjadi arena di mana hanya informasi dan gagasan terbaiklah yang pantas ditawarkan (baca: dijual) ke ranah publik. Adalah hal yang mengkhawatirkan ketika peran jurnalistik pers bergeser ke arah peran industrialistis semata. Dua tahun ke depan yang juga adalah tahun politik ini dapat dipastikan menjadi ajang perang informasi. Bukan tidak mungkin media massa, utamanya yang berada di bawah kepemilikan konglomerat cum politisi, akan berlaku layaknya buzzer politik berbayar. Lembaga semacam KPI yang digadang mampu menjadi satu-satunya benteng terakhir dari hegemoni media pun tampaknya tidak mampu berbuat banyak, lantaran kewenangannya justru dikebiri. Harapan terakhir bagi tegaknya pers yang obyektif, bebas dari hegemoni konglomerasi modal dan tarikan kepentingan politik pemiliknya adalah memperkuat jejaring masyarakat sipil. Bagaimana pun juga, hidup-mati pers atau media massa tergantung pada konsumen, yang tiada lain adalah masyarakat luas. Beruntung, pasca reformasi ini Indonesia mengalami ledakan kenaikan jumlah kelas menengah terdidik. Memberdayakan masyarakat sipil, dengan jalan memantik kritisisme serta kesadaran akan konsep analisis wacana adalah cara paling masuk akal yang dapat dilakukan. Jika masyarakat sipil sebagai konsumen utama media massa memiliki tingkat melek wacana yang memadai, media massa partisan dengan kualitas jurnalistik abal-abal pasti akan ditinggalkan. Pada titik tertentu, agaknya kita harus bersepakat bahwa melawan berita bohong, ujaran kebencian, opini menyesatkan yang diproduksi oleh media-media arusutama berkarakter partisan adalah dengan tidak mengkonsumsinya. Perlawanan atas hegemoni modal dalam media massa juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan kemunculan beragam media baru yang hadir dalam bentuk platform digital daring. Kemudahan membangun sebuah platform media massa daring ini hendaknya dimanfaatkan betul oleh kelas menengah terdidik untuk melahirkan semacam etos jurnalistik tandingan. Tujuannya jelas, yakni menjadi proyek bersama (common project) untuk menciptakan atmosfer pers yang obyektif, demokratis dan Dan sampai pada saat ini Indonesia masih menganut sistem multi partai yangmana telah di atur dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terdapat lebih dari dua partai yang berdiri. Sedikit memaparkan Kelemahan Sistem MultiPartai yang mana telah dianut di Indonesia antara lain:Pemerintah tidak memiliki kestabilan karena banyaknya partai yang membuat tidak adanya sebuah partai yang mampu mendukung pemerintahan dan harus melalui koalisi, Pemerintah terkadang ragu dan banyak program yang kurang efektif, Sistem multi partai cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,Logika "lingkaran setan" karena semakin banyaknya partai politik semakin banyak pilihan, Semakin banyak pilihan, akan semakin sulit memilih, Semakin sulit memilih semakin banyak yang tidak memilih dan Semakin banyak Golput, semakin mundur arti sebuah demokrasi. Jadi Semakin Banyak Partai artinya Semakin Jelek Kualitas Demokrasi nyaMenurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara Indonesia karena saking banyaknya partai politik yang ada, Menimbulkan persaingan tidak yang tidak sehat, Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. Menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah.Partai-partai politik dalam arti tidak sehat yang melakukan money politic (lobi-lobi) dan memberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Dari sini lah sifat-sifat para pemerintah yang akan korupsi muncul. Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Adanya konflik SARA.Kekuatan Partai politik satu dengan yang lainnya tidak akan terlalu jauh, sehingga muaranya akan kearah bagi-bagi kekuasaan.Pemerintahan akan semakin Gemuk sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partai yang harus diakomodir dan sulit menempatkan orang yang "benar ditempat yang benar".Biaya Politik yang sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai-partai. contoh ; ringanya dalam pembuatan kartu suara, kalau partainya seperti sekarang ini, kemungkinan kartu suara akan selebar Koran dibandingkan dengan sedikit partai. Dari sisi ini saja sudah memboroskan keuangan Negara. Banyaknya Uang yang di investasikan pada hal-hal yang "kurang produktiv" bagi masyarakat. contoh ringannya saja, lihat, hitung dan analisa sendiri, berapa rupiah yang dihamburkan hanya untuk membuat sticker, baliho, spanduk, bendera dan iklan politik. Dan jika dilihat keadaan politik pada saat ini partai yang tidak memenangkan suara hanya akan menjadi oposisi dalam mengkritisi partai yang menang dengan demikian akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat Demikianlah efek-efeknya yang muncul bilamana menganut sistem kepartaian multipartai. Melihat letak geografisnya wilayah Indonesia, memerlukan suara satu kesatuan untuk membangun negara Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan kekuatan bangsaNya. Bila tidak adanya kesatuan dari negeri ini sendiri, maka pacahanya akan mempengaruhi eksistensinya di mata dunia dan khususnya dengan negara-negara tetangga. pengaruh pecahnya suara didalam negeri ini dapat dilihat dari caruk-maruknya kondisi sosial dan politikNya terlebih karena dipengaruhi Suku, Ras serta Agama Dia menjelaskan Indonesia cuma menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2018 versi Repoters Without Borders. Posisi Indonesia bahkan jauh di bawah Timor Leste yang menempati peringkat 93 dalam indeks tersebut. Hanya dengan masyarakat sipil yang kuat, Indonesia bisa tumbuh menjadi demokrasi terkonsolidasi, dengan pemerintahan bertata kelola yang baik guna lebih memajukan negeri ini. Sayangnya. terjadi stagnasi masyarakat sipil. Mengikuti perbincangan para ahli dan pengamat dari dalam dan luar negeri, kemunduran demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir terkait dengan stagnasi masyarakat sipil (civil society). Jika stagnasi masyarakat sipil ini terus berlanjut, masa depan demokrasi Indonesia dapat pula semakin tidak menentu. Demokrasi Indonesia pernah dipuji berbagai lembaga pemantau dan advokasi demokrasi internasional sebagai full democracy karena adanya masyarakat sipil yang hidup, dinamis, dan bersemangat. Namun, berbagai perkembangan terkait politik beberapa tahun terakhir, lebih khusus demokrasi dan pemerintahan, membuat civil society kian kehilangan elannya. Bahkan, dalam pandangan tertentu, kondisi masyarakat sipil sudah pada tahap mengenaskan. Peter van Tuijl, aktivis demokrasi dan civil society yang lama tinggal di Indonesia, menulis Indonesian Civil Society: Struggling to Survive (2019). Namun, berbagai perkembangan terkait politik beberapa tahun terakhir, lebih khusus demokrasi dan pemerintahan, membuat civil society kian kehilangan elannya. Dalam kaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu April 2019, Van Tuijl, visiting fellow di The Kroc Institute for International Peace Studies, Universitas Notre Dame, Amerika Serikat, mencatat, masyarakat sipil Indonesia kini berada dalam posisi defensif. Dalam posisi itu, masyarakat sipil lebih sibuk mengkritik kelompok intoleran atau uncivil society atau menangkis tuduhan sebagai ”anti-religius” atau bahkan ”antiIndonesia”. Persepsi bahwa masyarakat sipil berjuang untuk sekadar bisa bertahan dikonfirmasi jajak pendapat Kompas (2/3/2020). Sebanyak 52,1 persen dari responden menilai kekuatan masyarakat sipil sekarang mengalami stagnasi dibandingkan dengan masa awal reformasi. Kurang dari setengah (43,5 persen) dari total responden menganggap masyarakat sipil lebih baik. Indonesia sebenarnya sangat beruntung memiliki empat kelompok besar masyarakat sipil. Pertama, kelompok lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi masyarakat di berbagai bidang; kedua, kelompok masyarakat profesional yang bergerak untuk kepentingan profesinya. Selanjutnya, ketiga, kelompok mahasiswa, akademisi, dan intelektual; dan keempat organisasi masyarakat, khususnya berbasis agama, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi berbasis gereja. Kelompok pertama, ketiga, dan keempat, meski bukan organisasi politik, tetapi sebagai masyarakat sipil memainkan peran penting dalam penumbuhan budaya sipil (civic culture), civility yang esensial bagi demokrasi untuk bisa tumbuh. Mereka juga menjadi kekuatan masyarakat dalam penghadapan dengan negara; memainkan peran sebagai kekuatan kritis, dan cek serta keseimbangan terhadap kekuasaan. Masyarakat sipil Indonesia pernah memainkan peran penting dalam menumbuhkan demokrasi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Meski Soeharto sering melakukan represi, masyarakat sipil terus menyemai civic culture sebagai nucleus demokrasi untuk tumbuh. "Masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam berakhirnya era Orde Baru. Berkat masyarakat sipil yang kuat, transisi Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi sejak 1998-1999 dan seterusnya berlangsung relatif lancar dan damai". Namun, demokrasi dan liberalisasi politik masa reformasi juga menjadi awal terjadinya disorientasi kalangan masyarakat sipil. Godaan dan tarikan kekuasaan membuat banyak tokoh dan kelompok masyarakat sipil, terutama intelektual, akademisi, dan aktivis, terjun ke politik. Inilah proses yang penulis sebut sebagai unmaking of civil society. Kalangan masyarakat sipil yang menempuh jalan ini sebagian besar gagal dalam proses politik demokrasi; mereka ”terlalu naif” berpolitik dan ”kekurangan gizi” dalam proses politik yang makin transaksional dan mahal. Masyarakat sipil juga makin tidak berdaya menghadapi jaring kekuasaan yang terus mengunci rapat berbagai bidang kehidupan. Fenomena ini bisa terlihat dalam beberapa kasus mutakhir. Masyarakat sipil tersingkir dalam proses pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK. Masyarakat sipil dan publik sejauh ini juga tidak disertakan dan tidak terlibat dalam pembahasan dan perumusan rancangan undang-undang omnibus law, misalnya. Perkembangan lain juga terlihat kian tidak menguntungkan masyarakat sipil. Belakangan semakin menguat gejala police state dan resentralisasi negara seiring merosotnya kontrol, serta cek dan keseimbangan dari masyarakat sipil. Selain itu, masyarakat sipil juga harus berhadapan dengan ”koalisi politik”—untuk tak menyebut ”konspirasi politik”—yang lebih menempatkan kepentingan politik masing-masing di atas segalanya. Menghadapi gejala ini, masyarakat sipil hampir tak berdaya. Menghadapi fenomena tak kondusif, masyarakat sipil perlu revitalisasi. Tanpa revitalisasi masyarakat sipil, masa depan demokrasi dan lebih-lebih masa depan bangsa Indonesia menjadi pertaruhan sangat mahal. Masyarakat sendiri ada kesediaan cukup kuat untuk memberdayakan kembali masyarakat sipil. Jajak pendapat Kompas menemukan, dua pertiga responden dari kelompok umur 17-30 dan juga 31-40 tahun bersedia terlibat dalam gerakan masyarakat sipil. Sekali lagi, hanya dengan masyarakat sipil yang kuat, Indonesia dapat tumbuh menjadi demokrasi terkonsolidasi, dengan pemerintahan bertata kelola yang baik untuk lebih memajukan negeri ini Namun pasca order baru, pers di Indonesia kembali mendapatkan angin kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Namun, saat ini peran media massa tidak jarang justru menjadi bias, karena apa yang disuguhkan oleh media massa sarat dengan kepentingan. Media massa tidak selamanya “jujur” tapi mengandung pesan tertentu. Kebebasan media massa saat ini telah menjadi kebablasan. Misalnya seperti kasus pertikaian antara Indonesia dan Malaysia yang diekspos secara berlebihan dan tidak berimbang sehingga menimbulkan kebencian di antara masing-masing negara. Menurut saya, kebebasan yang dimililiki oleh pers dalam berekspresi dan berpendapat haruslah kebebasan yang bertanggungjawab. Sebab, kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas, sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban, tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Semestinya kebebasan hak-hak untuk berkomunikasi yang disampaikan oleh media massa tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan sistem politik. Kebebasan pers yang bertanggungjawab memiliki arti penting dalam demokrasi. Banyak sekali peran yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsi pers dalam mewujudkan sistem negara yang demokrasi. Salah satunya adalah media massa juga merupakan sebagai penyaluran informasi (to inform) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini. Namun, agar media massa dikatakan demokrasi dalam menjalankan peranannya terutama dalam menunjang menyampaikan informasi, maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara professional. (McQuail, 2002: 208). Pembatasan Kebebasan Pers Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum. Kebebasan pers tidak pernah berarti kebebasan tanpa kontrol. Negara demokratis lazim memiliki batasan-batasan. Setidaknya, ada enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers, yaitu: 1) menyebarkan kebencian; 2) konten pencabulan dan pornografi; 3) melakukan fitnah dan pencemaran nama baik; 4) iklan yang berbohong (deceptive advertising); 5) promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok); 6) pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara. Oleh karena itu, kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan paling tidak melalui rambu hukum, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. Apabila dalam pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita, dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Upaya mencegah agar pembatasan kebebasan tersebut takberdampak pada melemahnya daya kontrol pers terhadap mereka yang berkuasa dengan menerapkan self regulation yang dibuat sendiri oleh industri media. Self regulation merupakan mekanisme pengaturan yang dikembangkan industri media atau komunitas media untuk meregulasi diri mereka sendiri sehingga tidak merugikan kepentingan publik. Self regulation dikembangkan untuk membuktikan bahwa tanpa campur tangan negara dan pihak lain, media akan memanfaatkan kebebasan yang dimiliki secara bertanggungjawab. Jadi, tidak ada kewajiban hukum formal yang mengikat. Bentuk dari self regulation dapat berupa code of ethics, code of practice, professionalism standard, and voluntary ratyng system.