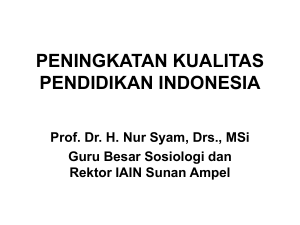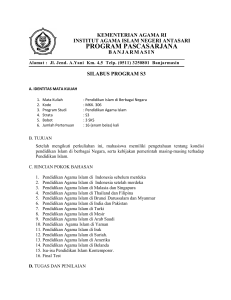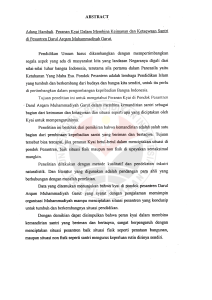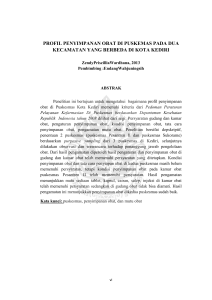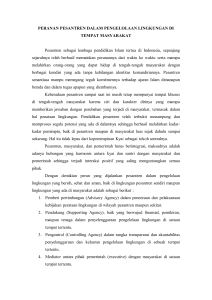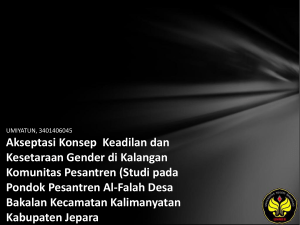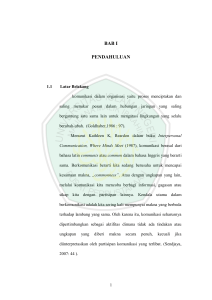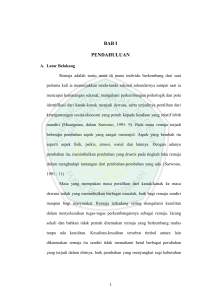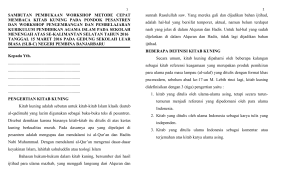MOTIVASI KYAI DALAM MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ma’ruf) TESIS Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen Dosen Pengampu: Dr. Hj. Munifah, M.Pd. Oleh : AHMAD ATHO’UL KARIM NIM: 924.008.19.003 PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI 2020 1 BAB I PENDAHULUAN A. KONTEKS PENELITIAN Secara historis, pesantren juga mengandung makna kemurnian Indonesia, bukan hanya bermakna keagamaan. Karena awal mula suatu lembaga pesantren sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindu-Budha, dan Islam datang sebagai penerus, pelestari, serta perombak sistem pendidikan yang lebih dahulu berkembang di Indonesia, seperti sistem pendidikan Hindu atau Budha. Menurut catatan sejarah Islam di Indonesia, pesantren telah berdiri pada abad ke-13 yang mana saat itu masih sebatas tempat mengaji dan belajar di bangunan kecil seperti gubuk. Setelah beberapa abad, pendidikan Islam semakin berkembang dengan adanya beberapa tempat pengajian. Dari ini, kemudian berdirilah tempat-tempat menginap atau asrama bagi para santri, yang mana disebutlah Pesantren. Sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari keikutsertaan Pesantren dan para tokohnya yang menata dan mewarnai pola kemasyarakatan yang mana berbasis agama dan budaya. Pesantren di Indonesia tidak seperti Pesantren di Turki dan Mesir, seperti ungkapan Ayzumardi Azra dalam pengantarnya di buku Bilik-Bilik Pesantren karya Nur Cholis Majid, dimana sistem pendidikan klasik yang ada di Turki pada era Musthafa kemal Ataturk dan Mesir pada era Gamal Abdul Nashir yang membekukan sistem Madrasah dan Kuttab, kemudian mengganti kebentuk sistem pendidikan umum. Situasi-situasi sosiologis dan politis yang mengitari pesantren di Indonesia, serta perbedaan-perbedaan tersebut pada gilirannya membuat pesantren mampu bertahan sampe saat ini. Ada dua kelompok pesantren yaitu pesantren salaf (tradisional) dan khalaf (modern). Secara garis besar, ciri-ciri dua kelompok tersebut tidak ada perbedaan, namun secara kenyataan terdapat perbedaan-perbedaan terlebih jika dilihat dari apa yang diajarkan. Pesantren salaf (tradisional) merupakan suatu kelompok pesantren 2 yang masih menggunakan sistem pendidikan klasikal, seperti sorogan, wetonan/bandongan, kajian dari permintaan masyarakat atau permintaan santri kepada kyainya untuk diajarkan kitab-kitab tertentu, dan lain sebagainya, serta mempertahankan kitab-kitab klasik Islam (kitab kuning). Namun disisi lain, santri-santri dari pesantren salaf dinilai lambat dalam merespon arus modernisasi. Kebanyakan cenderung tekstual serta terlihat klasik dan kurang mampu dalam aspek literasi, karena terlalu rapat menutup diri dari perkembangan zaman. Sehingga masyarakat muslim Indonesia mempertanyakan reputasi pesantren, karena mayoritas pesantren terkesan elitis, jauh dari realita sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa lulusan pesantren kalah Islami dengan kelompok hijrah. Ditambah lagi, problem sosialisai dan aktualisasi ini dengan problem keilmuan, diantaranya terjadinya kesenjangan, keterasingan dan differensiasi pembedaan antara keilmuan pesantren dengan dunia modern. Belum lagi pesantren yang dihadapkan kepada masalah-masalah globalisasi, yang dapat dipastikan telah menjadi tanggung jawab yang berat bagi pesantren. Dalam konteks dilematis ini, pilihan terbaik bagi santri di pesantren adalah mendialogkannya dengan paradigma dan pandangan dunia yang telah diwariskan oleh generasi pencerahan Islam. Bahwasanya pesantren perlu memosisikan warisan masa lalu sebagai teman dialog bagi modernitas dengan segala produk yang ditawarkannya, maka dari itu pesantren harus membaca khazanah lama dan baru dalam frame yang terpisah. Dengan menghadirkan warisan lama pesantren dan dihadapkan dengan masa kekinian. Bisa jadi warisan lama tersebut terkesan basi, namun tidak menutup kemungkinan masih ada potensi untuk dikembangkan pada masa sekarang atau bahkan masa depan. Sebenarnya sekarang ini telah berlangsung proses dialektika antara tradisi dan modernitas, terutama dilingkungan pesantren yang masih kuat mengusung tradisi. Oleh karena itu, pesantren tersebut pada masa yang akan datang bukan tidak mungkin menjelma menjadi sebuah institusi yang dapat diandalkan baik itu di bidang ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi pesantren sebagai sebuah lembaga 3 Tafaqquh Fiddin untuk melestarikan dan memodifikasi paradigma: “Mempertahankan warisan lama yang masih relevan dan mengambil hal terbaru yang lebih baik” kalau perlu malah mengkreasi hal baru tersebut menjadi lebih baik. Secara geologis, pemilihan tempat di Kediri dikarenakan Kediri merupakan salah satu Kota dan Kabupaten yang memiliki banyak pondok pesantren salafi dan juga di kenal akrab dikalangan masyarakat akan pondok pesantren salafinya. Oleh karena itu menjadi sala satu acuan orang tua untuk menempatkan anaknya di Pondok Pesantren. Dari fenomena-fenomena tersebut baik secara historis maupun geografis, maka dari itu inisiatif penulis untuk memilih judul “Motivasi Kyai dalam Medirikan Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kediri)”. B. FOKUS PENELITIAN Penelitina ini di fokuskan pada motivasi Kyai dalam mendirikan lembaga pendidikan Pesantren yang meliputi: 1. Bagaimana Peran Lembaga Pendidikan Pesantren dalam Pandangan Masyarakat? 2. Bagaimana Motivasi Kyai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan Pesantren di era sekarang? C. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan pesantren dalam pandangan masyarakat. 2. Untuk mendeskripsikan motivasi Kyai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan Pesantren di era sekarang. D. KEGUNAAN PENELITIAN 1. Bagi masyarakat sebagai wawasan dalam mendirikan lembaga pendidikan pesantren. 2. Bagi peneliti dapat dijadikan input referensi dan dikembangkan untuk 4 penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. E. PENELITIAN TERDAHULU 1. Dengan hasil: Tipologi Kyai di Lirboyo antara lain Kyai pasif, Kyai adaptif, dan Kyai progresif. Upaya pengembangan pendidikan agama Islam di Lirboyo sangat bervariasi, Kyai pasif masih mengunakan metode sorogan dan wetonan, Kyai adaptif masih memakai kurikulum DEPAG, dan kyai progresif telah mengadopsi kurikulum DEPAG dan Diknas.1 2. Dengan hasil: pendidikan di Pondok Pesantren sangat mendukung dalam proses pembangunan SDM baik secara individu maupun masyarakat umumnya. Sistem pendidikan pondok pesantren memungkinkan untuk selalu berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.2 (Perbedaan: peneliti lebih ke kepemimpinan Kyai, sedangkan tesis ini lebih ke SDM) BAB II KAJIAN PUSTAKA A. MOTIVASI Pengertian Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “motivation”, yang artinya “daya batin” atau “dorongan”. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan Taufio Lubis, “Peran Kyai dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Lirboyo”, Tesis (2012). 2 Dadan Muttaqien, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat)”, Tesis (1999). 1 5 tertentu.3 Menurut Weiner (dikutip Elliot et. al.) pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno, arti motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan penghormatan.4 Menurut Henry Simamora pengertian motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara definisi motivasi adalah suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Menurut G. R. Terry pengertian motivasi adalah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. 1. Jenis-Jenis Motivasi a. Motivasi Intrinsik Pengertian motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. b. Motivasi Ekstrinsik Definisi motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. 2. Faktor-Faktor Motivasi 1) Faktor Internal (Intern) Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam 3 Parta Ibeng, Pengertian Motivasi, Jenis, Faktor, dan Menurut Para Ahli (2018), https://pendidikan.co.id/pengertian-motivasi-jenis-faktor-dan-menurut-para-ahli/. 4 Saban Echdar, dkk., “Bussiness Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis dan Kewirausahaan”, E-book (2019), h. 247. 6 diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. 2) Faktor Eksternal (Ekstern) Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. B. PONDOK PESANTREN Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya adalah agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Usaha Syaikh menemukan momuntem seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit (1293–1478 M). Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar negara.5 Hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan muballig Islam yang datang dari Jazirah Arab seperti Hadramaut, Persia, dan Irak.6 Lembaga pendidikan pada awal masuknya Islam belum bernama pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Saridjo sebagai berikut: Pada abad ke-7 M. atau abad pertama hijriyah diketahui terdapat komunitas 5 Alwi Shihab, Islam Inklusif (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 23. Fatah Syukur, Dinamika Pesantren dan Madrasah (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 248. 6 7 muslim di Indonesia (Peureulak), namun belum mengenal lembaga pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan yang ada pada masa-masa awal itu adalah masjid atau yang lebih dikenal dengan nama meunasah di Aceh, tempat masyarakat muslim belajar agama. Lembaga pesantren seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Jawa.7 Mengenai sejarah berdirinya pesantren pertama atau tertua di Indonesia terdapat perbedaan pendapat di kalangan peneliti, baik nama pesantren maupun tahun berdirinya. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Depatremen Agama pada 1984-1985 diperoleh informasi bahwa pesantren tertua di Indonesia adalah Pesantren Jan Tanpes II di Pamekasan Madura yang didirikan pada tahun 1762.8 Tetapi data Departemen Agama ini ditolak oleh Mastuhu.9 Sedangkan menurut Martin van Bruinessen seperti dikutip Abdullah Aly bahwa Pesantren Tegalsari, salah satu desa di Ponorogo, Jawa Timur merupakan pesantren tertua di Indonesia yang didirikan tahun 1742 M.10 Perbedaan pendapat tersebut karena minimnya catatan sejarah pesantren yang menjelaskan tentang keberadaan pesantren. Pondok Pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab “fundūk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumunya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.11 Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri.12 Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang 7 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010), h. 17-30. 8 Departemen Agama RI., Nama dan Data Potensi Pondok-Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (Jakarta: Depag RI., 1984/1985), h. 668. 9 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 19. 10 Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 154156. 11 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: P3M, 1986), h. 98-99. 12 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai (Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997), h. 18. 8 dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.13 Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dari segi etimologi pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama. Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.14 Pesantren sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal.15 13 Ibid. Amir Hamzah Wiryosukarto, et al., Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 51. 15 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: KIS, 2001), h. 17. 14 9 BAB III METODE PENELITIAN A. RANCANGAN PENELITIAN Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena memusatkan pada rasa keingintahuan serta tidak menggunakan penghitungan seperti yang ada pada penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu diperoleh dengan cara menangkap fenomena dari objek yang diteliti. Data dan fakta dikumpulkan dari latar yang alami (natural setting) secara mendalam dengan harapan dapat memperoleh gambaran tentang motivasi Kyai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan Pesantren yaitu di pondok pesantren salafi di Kediri. B. DATA, SUMBER DATA, METODE, DAN INSTRUMEN PENELITIAN Data yang akan di cari dalam penelitian ini yaitu data tentang motivasi Kyai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan Pesantren yaitu di pondok pesantren salafi di Kediri. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber baik berupa tindakan, kata-kata, maupun dokumendokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: yang pertama, sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber adalah pengasuh Pondok Pesantren di Kediri beserta keluarganya. Yang kedua, sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber data primer, atau dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maksudnya secara baik jika dilakukan interaksi dengan subjek 10 melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena itu terjadi. Disamping itu, untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang subjek. C. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA Analisis yang dilakukan berupa mengidentifikasi data, menyeleksi data, dan klasifikasi data, serta menyusun data. Adapun tekniknya adalah:mengacu pada konsep Milles dan Huberman yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam rangka memperoleh data yang tepat dan objektif, maka dalam memenuhi data digunakan teknik pengecekan sebagai berikut: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. BAB IV TEMUAN PENELITIAN Pada dasarnya temuan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu: 1. Para remaja yang meneruskan pendidikan di lembaga pedidikan pesantren di sebagian masyarakat bisa diharapkan hasilnya di bidang agama. 2. Lulusan lembaga pendidikan pesantren di pandangan masyarakat sangat baik sebagai penghidup agama tetapi lemah di tuntutan zaman. 3. Bagi Kyai, ilmu pesantren sebagai bekal di kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan akhirat. 4. Pendidikan umum tidak menjamin subtansi dalam beribadah. 11 BAB V PEMBAHASAN 12 BAB VI KESIMPULAN 13 DAFTAR PUSTAKA Aly, Abdullah. 2011. Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Departemen Agama RI. 1984/1985. Nama dan Data Potensi Pondok-Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (Jakarta: Depag RI.). Dhofier, Zamakhsyari. 1997. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai (Cet. VII; Jakarta: LP3ES). Echdar, Saban. dkk. 2019. “Bussiness Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis dan Kewirausahaan”, E-book. Ibeng, Parta. 2018. Pengertian Motivasi, Jenis, Faktor, dan Menurut Para Ahli. https://pendidikan.co.id/pengertian-motivasi-jenis-faktor-dan-menurutpara-ahli/. Lubis,Taufio. 2012. “Peran Kyai dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Lirboyo”. Tesis. Mastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS). Muttaqien, Dadan. 1999. “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat)”. Tesis. Saridjo, Marwan. 2010. Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara). Shihab, Alwi. 2002. Islam Inklusif (Cet. I; Bandung: Mizan). Syukur, Fatah. 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Wahid, Abdurrahman. 2001. Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: KIS). Wiryosukarto, Amir Hamzah. 1996. Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press). Ziemek, Manfred. 1986. Pesantren dalam Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: P3M). 14