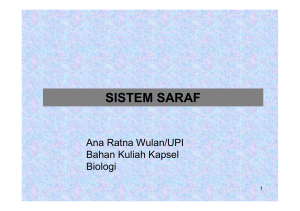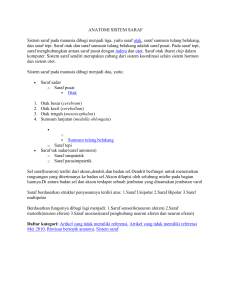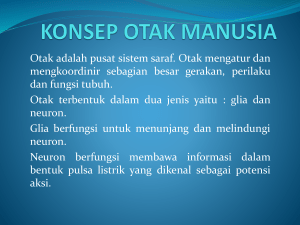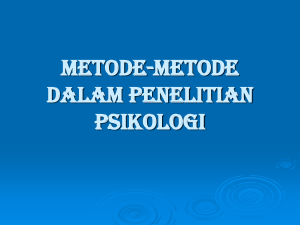Makalah “Prinsip Komunikasi Saraf dan Hormon” Dosen pembimbing : Ns. Chrisyen Damanik, S.Kep, M.Kep Mata Kuliah : Ilmu Dasar Keperawatan Disusun Oleh: Yuliana Dwi Astuti 16.0498.833.01 INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS WIYATA HUSADA SAMARINDA PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah” Prinsip Komunikasi Saraf dan Hormon ”, karena dengan ijinNyalah ringkasan makalah ini dapat terselesaikan. Walaupun makalah ini jauh dari kesempurnaan, namun sedikit dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk terus berjuang mencapai kesempurnaan yang mungkin membutuhkan perjuangan yang tiada hentihentinya. Maka dari itu besar harapan kami untuk masukan saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan ringkasan makalah ini, sehingga dapat menghantarkan para mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional yang dicita-citakan. Dan semoga kegiatan ini dapat mendorong minat belajar dan rasa ingin tahu mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk terus maju. Dan terimakasih pula kami ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Samarinda 20 April 2020 Penulis DAFTAR ISI Cover………………………………………………………………………………i Kata Pengantar…………………………………………………………..………ii Daftar Isi…………………………………………………………………………iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang..................................................................................1 B. Tujuan……………………………………………………………….…….3 C. Manfaat……………………………………………………………………4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Mengenal Komunikasi Saraf…………………………………………..…..5 B. Pontensial Berjenang………………………………………………………9 C. Potensial Aksi………………………………………………………….…11 D. Regenerasi serat saraf…………………………………………………….22 E. Sinaps dan Integrasi Neuron…………………………………………...…24 F. Komunikasi antar sel dan tranduksi sel…………………………………..29 G. Prinsip komunikasi hormone………………………………………….….32 H. Prinsip komunikasi saraf dan hormone……………………………….….36 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………..……..50 B. Saran .............................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem saraf mengontrol apa yang terjadi secara otomatis yang Anda mungkin kurang menyadarinya di tubuh Anda. Seperti jantung terus berdenyut, makanan yang tercerna, udara yang lewat di dan keluar dari paru-paru, dan menyembuhkan luka. Dalam kenyataannya, sistem saraf mengontrol segala sesuatu yang tubuh lakukan, apakah Anda sadar atau tidak. Sistem saraf adalah kumpulan dari miliaran sel khusus dan jaringan ikat dan terdiri dari dua bagian utama. Bagian sentral terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan disebut sistem saraf pusat (SSP). Bagian di luar disebut sistem saraf tepi (perifer) (SST). Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi. Dia mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem endokrin dalam mengatur dan mempertahankan homeostasis (lingkungan internal tubuh kita) dengan mengontrol kelenjar endokrin utama (hipofisis) melalui hipotalamus otak. Melalui reseptornya, sistem saraf membuat kita berhubungan dengan lingkungan kita, baik eksternal dan internal. Seperti sistem lain dalam tubuh, sistem saraf terdiri dari organ, terutama otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan ganglia, yang pada gilirannya, terdiri dari berbagai jaringan, termasuk saraf, darah, dan jaringan ikat yang secara bersama melaksanakan kegiatan yang kompleks dari sistem saraf. Jaringan saraf terdiri dari kelompok sel saraf atau neuron yang mengirimkan informasi disebut impuls saraf dalam bentuk perubahan elektrokimia, dan merupakan sel konduksi. Neuron adalah sel saraf yang sesungguhnya. Jaringan saraf juga terdiri dari sel-sel yang melakukan dukungan dan perlindungan. Sel-sel ini disebut neuroglia atau sel glial. Lebih dari 60% dari semua sel otak adalah sel neuroglia. Neuroglia ini bukan sel konduksi. Mereka adalah jenis khusus dari "jaringan ikat" untuk sistem saraf. Neuron, atau sel-sel saraf, adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Mereka adalah sel halus yang khusus untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuk, tetapi mereka memiliki banyak ciri-ciri yang umum. Neuron bersifat amitotik. Ini berarti bahwa jika neuron mengalami kerusakan, tidak dapat digantikan karena neuron tidak mengalami mitosis. Neuron memiliki dua karakteristik fungsional yang unik: iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas adalah kemampuan untuk menanggapi rangsangan dengan membentuk impuls saraf. Konduktivitas adalah kemampuan untuk mengirimkan impuls saraf sepanjang akson ke neuron lain atau sel efektor. Karakteristik ini memungkinkan berfungsinya sistem saraf. Pensinyalan atau sinyal lewat melalui baik sarana listrik dan kimia. Setiap neuron memiliki tiga bagian yaitu Badan sel, Satu atau lebih dendrit, Satu akson Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Setiap badan sel saraf mengandung inti tunggal. Inti ini merupakan pusat kontrol sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan golgi, lisosom. Dalam sitoplasma badan sel, ada retikulum endoplasma kasar [reticulum endoplasmic rough (RER)]. Dalam neuron, ER kasar memiliki struktur granular disebut sebagai badan Nissl, juga disebut zat chromatophilic, dan merupakan tempat sintesis protein. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang- cabang, seperti cabangcabang pohon. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Ini adalah daerah reseptif neuron. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Akson hilock, adalah prosesus panjang atau serat yang dimulai secara tunggal tetapi dapat bercabang dan pada ujungnya memiliki banyak perpanjangan halus disebut terminal akson yang kontak dengan dendrit dari neuron lainnya. Benang-benang halus yang terdapat di dalam akson disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Membran plasma sel Schwann disebut neurilemma. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang merupakan celah sempit dan tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls Sinapsis merupakan hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Peristiwa ini terjadi dari ujung percabangan akson (terminal akson) dengan ujung dendrit neuron yang lain. Celah antara satu neuron dengan neuron yang lain disebut dengan celah sinapsis. Loncatanloncatan listrik yang bermuatan ion terjadi dalam celah sinapsis, baik ion positif dan ion negatif. Di dalam sitoplasma sinapsis, terdapat vesikel sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neuron (terminal akson), vesikel akan bergerak, lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmiter. Neurotranmiter berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor di membran pascasinapsis. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi jarak jauh yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin tanpa duktus ke dalam darah, yang mengangkut hormon ke sasaran spesifik tempat hormon mengontrol fungsi tertentu dengan mengubah aktivitas protein di dalam sel sasaran B. Tujuan Penulisan 1. Tujuan Umum Tujuan umum dari penulisan makalah ini adalah mahasiswa keperawatan memahami tentang prinsip komunikasi saraf dan hormon. 2. Tujuan Khusus Tujuan Khusus dari penulisan makalah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami Komunikasi Saraf 2. Mahasiswa mampu memahami tentang Pontensial Berjenjang 3. Mahasiswa mampu memahami tentang Potensial Aksi 4. Mahasiswa mampu memahami regenerasi serat saraf 5. Mahasiswa mampu memahami Sinaps dan Integrasi Neuron 6. Mahasiswa mampu memahami komunikasi antar sel dan tranduksi sel. 7. Mahasiswa mampu memahami prinsip komunikasi hormone. 8. Mahasiswa mampu memahami prinsip komunikasi saraf dan hormon C. Manfaat Penulisan 1. Mahasiswa Penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada mahasiwa keperawatan berupa prinsip komunikasi saraf dan hormon. 2. Institusi Pendidikan Penulisan malakah ini diharapkan memberi tambahan refensi dan rujukan terkait prisip komunikasi saraf dan hormon. 3. Insitusi Pelayanan Kesehatan Penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada praktisi berupa mengulang kembali apa yang sudah didapat dalam masa pendidikan dan menambah pengetahuan untuk Prinsip Komunikasi Saraf dan Hormon terbaru. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Mengenal Komunikasi Saraf Semua sel tubuh memperlihatkan potensial membran, yaitu pemisahan muatan positif dan negatif di kedua sisi membran, seperti dibahas di bab sebelumnya. Potensial ini berkaitan dengan distribusi takmerata Na., K., dan anion protein inrrasel besar antara cairan intrasel (CIS) dan cairan el.rstrasel (CES), dan dengan perbedaan permeabilitas membrane plasma terhadap ion-ion ini. Saraf dan otot adalah jaringan peka rangsang. Dua jenis seI, sel saraf dan sel otot, mengalami perkembangan sedemikian sehingga dapat memanfaarkan potensial membran ini. Kedua sel ini dapat mengalami perubahan cepar sesaar pada potensial membrannya. Fluktuasi potensial ini berfungsi sebagai sinyal listrik. Potensial membran konstan yang terdapat ketika sel saraf atau otot tidak memperlihatkan perubahan cepar dalam potensialnya disebut potensial istirahat. Sel saraf dan otot dianggap sebagai jaringan peka rangsang karena jika tereksitasi, keduanya mengubah potensial istirahatnya untuk menghasilkan sinyal listrik. Sel saraf, yang juga dikenal sebagai neuron, frenggunakan sinyal-sinyal listrik ini untuk menerima, memproses, memulai, dan mengirimkan pesan. Di sel otot, sinyal listrik ini memicu kontraksi. Dengan demikian, sinyal listrik sangat penting bagi berfungsinya sistem saraf dan semua otot. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana neuron mengalami perubahan potensial untuk melaksanakan fungsinya. a. Pontensial membrane berkurang sewaktu depolarisasi dan meningkat sewaktu hiperpolarisasi 1. Polarisasi: Muatan-muatan dipisahkan di kedua sisi membran sehingga membran memiliki potensial. Setiap nilai potensial membran bukan 0 mV baik dalam arah positif maupun negatif, maka membran berada dalam keadaan polarisasi. Ingatlah bahwa besar potensial berbanding lurus dengan jumlah muatan positif dan negative yang dipisahkan oleh membran dan bahwa tanda potensial (+ atau -) masing-masing selalu menunjukkan bahwa terjadi kelebihan muatan positif atau kelebihan muatan negatif di bagian dalam membran. Di sel saraf, pada potensial istirahat, membran mengalami polarisasi pada -70 mV 2. Depolarissi Penurunan besar potensid membran negatif; membran menjadi kurang terpolarisasi dibandingkan dengan potensial istirahat. Selama depolarisasi potensia membran bergerak mendekati 0 mV, menjadi kurang negatif(sebagai contoh, perubahan dari -70 mV menjadi -60 m9; muaran yang dipisahkan lebih sedikit dibandingkan dengan potensial istirahat 3. Repolarisasi Membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. 4. Hiperpolarisasi 5. Peningkatan besar potensial membrane negatif; membran menjadi lebih terpolarisasi dibandingkan pada potensial istirahat. Selama hiperrrolarisasi potensial membran semakin menjauhi 0 mV, menjadi Iebih negatif (misalnya perubahan dari -70 mV menjadi 80 mD; lebih banyak muatan yang dipisahkan dibandingkandengan potensial istirahat. Salah satu hal yang membingungkan perlu diklarifikasi. Pada alat yang digunakan untuk merekam perubahan cepat dalam potensial, selama depolarisasi saar bagian dalam menjadi kurang negatif daripada saat istirahat,? enurunan besar potensial ini tercermin sebagai defleksi he atas. Sebaliknya, saat hiperpolarisasi ketika bagian dalam menjadi lebih negative daripada saat istirahat, peninghatan besar potensial ini di wakili oleh deflelai he bawah. b. Sinyal listrik dihasilkan oleh perubahan pada perpindahan ion melintasi membrane plasma Perubahan pada potensial membran terjadi karena perubahan pada perpindahan ion menembus membran. Sebagai contoh, jika aliran masuk netto ion bermuatan positif meningkat dibandingkan dengan keadaan istirahat maka membrane mengalami depolarisasi (bagian dalamnya kurang negatif). Sebaliknya, jika aliran keluar netto ion bermuatan positif meningkat dibandingkan dengan keadaan istirahat maka membrane mengalami hiperpolarisasi (bagian dalam lebih negatif). Perubahan pada perpindahan ion, sebaliknya, ditimbulkan oleh perubahan pada permeabilitas membran sebagai respons terhadap berbagai hejadian pemicu. Bergantung pada jenis sinyal listriknya, kejadian pemicu dapat berupa (1) perubahan medan listrik di sekitar membran peka rangsang; (2) interalai suatu perantara kimiawi dengan reseptor pemukaan teftentu di membrane sel saraf atau otot; (3) rangsangan, misalnya gelombang suara yang merangsang sel-sel sarafkhusus di telinga; atau (4) perubahan spontan potensial akibat ketidak seimbangan inheren siklus bocor-pompa (Anda akan mempelajari mengenai sift berbagai proses pemicu ini seiring dengan berlanjutnya pembahasan kita tentang sinyal listrik). Karena ion-ion larut air yang bertanggung jawab membawa muaran tidak dapat menembus lapis-ganda lemak membran plasma maka muatan ini hanya dapat menembus membran melalui saluran yang spesifik baginya. Saluran membran dapat berupa saluran bocor atau saluran berpintu/bergerbang. Salatan bocor selalu terbuka, sehingga ion-ionnya dapat menembus membran melalui saluran ini tanpa kontrol. Sebaliknya, saluran berpintu memiliki pintu yang kadang terbuka, memungkinkan ion melewati saluran, kadang terturup, mencegah lewatnya ion melalui saluran. Pembukaan dan penutupan pintu terjadi akibat perubahan dalam konformasi tiga dimensi. (bentuk) protein yang membentuk saluran berpintu tersebut. Terdapat €mpat jenis saluran berpintu, bergantung pada faktor yang memicu perubahan konformasi saluran: (1) saluran berpintu voltase, yang membuka atau menutup sebagai respons terhadap perubahan potensial membran; (2) saluran berpintu kimiawi, yang mengubah konformasinya sebagai respons terhadap pengikatan pembawa pesan kimiawi tertentu dengan reseptor membrane yang berkaitan erat dengan saluran; (3) saluran berpintu mekanis, yang berespons terhadap peregangan atau deformasi mekanis lain; dan (4) saluran berpintu termal, yang berespons terhadap perubahan suhu lokal (panas atau dingin). Karena itu, kejadian pemicu mengubah permeabilitas membran dan karenanya mengubah aliran ion menembus membran dengan membuka atau menutup saluran yang melindungi saluran ion tertentu. Perpindahan ion-ion ini menyebabkan redistribusi muatan di kedua sisi membran, menyebabkan potensial membran berfluktuasi. Terdapat dua bentuk dasar sinyal listrik: (l) potensial berjenjang, yang berfungsi sebagai sinyal jarakpendek; dan (2) potensial aksi, yang menjadi sinyal jarak-jauh. Kita sekarang akan membahas jenis-jenis sinyal ini secara lebih detil, dimulai dengan potensial berjenjang dan kemudian kita akan mendalami bagaimana sel saraf menggunakan sinyal-sinyal ini untuk menyampaikan pesan. B. Pontensial Berjenjang Potensial berjenjang (potensial bertingkat) adalah perubahan lokal potensial membran yang terjadi dalam berbagai derajat atau tingkat kekuatan. Sebagai contoh, potensial membran dapat berubah dari -70 menjadi -60 mV (suatu potensial berjenjang 10 mV) atau dari -70 menjadi -50 mV (potensial berjenjang 20 mV). a. Semakin kuat kejadian pemicu,semakin besar potensial berjenjang yang terbentuk. Potensial berjenjang biasanya dihasilkan oleh kejadian pemicu tertentu yang menyebabkan saluran ion berpintu terbuka di bagian tertentu membran sel peka rangsang. Pada sebagian besar kasus, saluran ini adalah saluran berpintu kimia atau berpintu mekanis. Yang biasanya terjadi adalah terbukanya saluran berpintu Na. yang menyebabkan masuknya Na- ke dalam sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi dan listriknya. Depolarisasi yang terjadi potensial berjenjang-terbatas di regio kecil khusus dari keseluruhan membran plasma. Besar potensial berjenjang inisial ini (yaitu, perbedaan antara potensial baru dan potensial istirahat) berkaitan dengan kekuatan kejadian pemicu: Semakin buat hejadian pemicu, semahin banyak saluran berpintu yang terbuka, semakin banyak maatan positif yang masuk ke sel, dan semahin besar potensial berjenjang terdepolarisasi di tempat inisial. Juga semakin lama durasi kejadian pemicu, semabin lama durasi potensial berjenjang b. Pontensial berjenjang menyebar dengan aliran Ketika suatu potensial berjenjang terjadi di membran sebuah sel saraf atau otot maka bagian membran lainnya masih berada dalam potensial istirahat. Daerah yang mengalami depo- arus pasif. larisasi remporal disebut daerah aktif. bahwa di bagian dalam sel, daerah aktif relatif lebih positif daripada daerah inabtif sekitar yang masih berada dalam potensial istirahat. Di luar sel, daerah aktif relatif kurang positif dibandingkan dengan daerah sekitar. Karena perbedaan potensial ini maka muaran listrik, dalam hal ini dibawa oleh ion, mengalir pasif antara daerah aktif dan daerah istirahat sekitar baik di sisi dalam maupun luar membran. Setiap aliran muatan listrik dinamai arus. Berdasarkan perjan.jian, arah aliran arus selalu disebutkan berdasarkan arah aliran muatan positif (Gambar 4-3c). Di bagian da.lam, muatan positif mengalir melalui CIS menjauhi daerah aktif depolarisasi yang relatif lebih positif ke arah daerah istirahat di sekitar yang lebih negatif. Di luar sel, muaran positif mengalir melalui CES dari daerah inaktifdi sekitar yang lebih positifke arah daerah aktifyang relatiflebih negatif Perpindahan ion (yaitu arus listrik) berlangsung di sepanjang membran di antara daerah-daerah yang berdekatan di sisi membran yang sama. Aliran ini berbeda dengan aliran ion menembus membrane melalui saluran ion. Akibat arus lokal antara daerah depoiarisasr aktif dan daerah inaktif di sekitarnya maka terjadi perubahan potensial di daerah yang semula inaktif. Muatan positif mengalir ke daerah sekitar di sisi dalam, sementara secara bersamaan, muaran positif mengalir keluar daerah ini di sisi luar. Karena itu, di daerah sekitar bagian dalam menjadi lebih positif (atau kurang negatif), dan bagian luar kurang positif (atau lebih negatif) daripada sebelumnya.Dengan kata lain, daerah sekitar yang semula inaktif telah mengalami depolarisasi sehingga potensial berjenjang telah menyebar. Potensial daerah ini kini berbeda dari daerah inaktif di sebelahnya di sisi lain, memicu aliran arus lebih lanjut ke daerah baru ini, demikian seterusnya. Dengan cara ini, arus menyebar di kedua arah menjauhi tempat awal perubahan potensial. Besar arus yang mengalir antara dua daerah bergantung pada perbedaan potensial antar daerah dan pada resistensi bahan tempar arus mengalir. Resistensi adalah hambatan rerhadap perpindahan muatan listrik. Semakin besar beda potensial, semakin besar aliran arus; dan semakin rendah resistensi, semakin besar aliran arts. Konduhrar memiliki resistensi rendah sehingga aliran arus tidak banyak mendapat hambatan. Kawat (kabel) Iistrik serta CIS dan CES adalah konduktor yang baik sehingga arus mudah mengalir melalui mereka. Insulator memiliki resistensi tinggi dan sangat menghambat perpindahan muatan. Plastik yang membungkus kawat listrik memiliki resistensi tinggi, demikian juga lemak tubuh. Karena itu, arus tidak mengalir menembus lapis ganda lemak membran plasma. Arus, yang dibawa oleh ion, dapat menembus membran hanya melalui saluran ion. c. Potensial berjenjang mereda hingga lenyap dalam jarak pendek. Aliran arus pasif antara daerah aktif dan daerah sekitar yang inaktif serupa dengan mengalirnya arus listrik di kawat listrik. Kita mengetahui dari pengalaman bahwa arus dapat bocor dari kawat listrik yang menimbulkan bahaya kecuali jika kawat dibungkus oleh bahan insulator misalnya plastik. (Orang tersengat listrik jika mereka menyentuh kawat listrik telanjang). Demikian juga arus melenyap menembus membrane plasma karena ion-ion pembawa muatan bocor melalui bagian-bagian membran yang "tidak berinsulasi", yaitu melalui saluran terbuka. Akibat berkurangnya arus ini maka kekuatan arus lokal secara progresif melemah seiring dengan bertambahnya jarak dari tempat asal. Karena itu, kekuatan potensial berjenjang terus menurun semakin jauh potensial ini merambat dari daerah aktif asal. Cara lain untuk menyatakannya adalah bahwa penyebaran potensial berjenjang bersifat decremental berkurang bertahap (besar perubahan potensial awalnya adalah 15 mV (perubahan dari -70 menjadi -55 mV), yang berkurang sewaktu potensial bergerak di sepanjang membran hingga menjadi 10 mV (dari -70 menjadi -60 mV) dan terus menurun semakin jauh dari tempat aktif awal, sampai tidak lagi terdapat perubahan potensial. Dengan cara ini, arus lokal ini mereda hingga lenyap beberapa millimeter dari tempat awal perubahan potensial dan karenanya dapat berfungsi sebagai sinyal hanya untuk jarak yang sangar pendek. Meskipun potensial berjenjang memiliki jangkauan sinyal yang terbatas namun potensial ini sangat penting bagi fungsi tubuh, seperti dijelaskan di bab-bab berikutnya. Berikut ini adalah potensial berjenjang: potensial pascasinaps, dan potensial gelombang hmbat. Istilah-istilah nini mungkin asing bagi anda sekarang, tetapi anda akan terbiasa dengan mereka seiring dengan pembahasan lanjutan kita tentang fisiologi saraf dan otot. Kami menyertakan daflar ini di sini karena hanya di sinilah potensial berjenjang akan disatukan. Untuk saat ini cukup dikatakan bahwa umumnya sel peka rangsang dapat menghasilkan satu dari berbagai jenis potensial berjenjang sebagai respons terhadap suatu kejadian pemicu. Sebaliknya, potensial berjenjang dapat memicu patensial aksi, yaitu sinyal farak-jauh, di sel peka rangsang. C. Pontensial Aksi Potensial aftsi adalah perubahan potensial membran yang berlangsung singkat, cepat, dan besar (100 m.V) saat potensial sebenarnya berbalik, sehingga bagian dalam sel peka rangsang secara sesaat menjadi lebih positif daripada bagian luar. Seperti potensial berjenjang, satu potensial aksi hanya melibatkan sebagian kecil dari keseluruhan membran sel peka rangsang. Namun, tidak seperti potensial berjenjang, potensial aksi dihantarkan, atau menjalar, ke seluruh membrane secara nondecremental; yaitu, potensial ini tidak berkurang kekuatannya ketika menyebar dari tempat asalnya ke seluruh bagian membran lain. Karena itu, potensiai aksi dapat berfungsi sebagai sinyal jarak jauh yang"taat". Pikirkanlah tentang sel saraf yang menyebabkan kontraksi sel-se l otot di jempol kaki anda ingin menggoyangkan jempol kaki anda maka perintah dikirim dari otak turun ke medula spinalis untuk memulai potensial aksi di pangkal sel sarafini, yang terletak di medula spinaiis. Potensial alai ini berjalan tanpa berkurang menelusuri akson panjang sel saraf yang berjalan di sepanjang tungkai anda untuk berakhir di sel-sel oror jempol kaki anda. Sinyal tidak melemah atau lenyap namun tetap dipertahankan dengan kekuatan penuh dari awal hingga akhir. Marilah kita melihat perubahan pada potensial seiama suatu potensial aksi, serta permeabilitas dan perpindahan ion yang menjadi penyebab terjadinya perubahan potensial ini, sebelum kita mengalihkan perhatian kepada cara,cara yang digunakan oleh potensial aksi menyebar ke seluruh membrane sel tanpa berkurang. a. Sewaktu pontensial aksi,pontensial membran berbalik secara Sewaktu potensial aksi,cepat dan transien. Jika kekuatannya memadai maka perubahan potensial berjenjang dapat memicu potensial aksi sebelum perubahan berjenjang tersebut hilang. (Nanti anda akan menemukan caracara bagaimana inisiasi ini dilakukan untuk berbagai jenis potensial berjenjang). Biasanya bagian membran peka rangsang tempat potensial berjenjang dihasilkan sebagai respons terhadap suatu kejadian pemicu tidak mengalami potensialaksi. Namun, potensial berjenjang, melalui cara listrik atau kimia, menimbulkan depolarisasi bagian-bagian membran sekitar tempat potensial aksi dapat terbentuk. Untuk mempermudah pembahasan, kita akan meloncat dari kejadian pemicu ke depolarisasi bagian membran yang mengalami potensial alai, tanpa membahas keterlibatan potensial berjenjang. Untuk memulai suatu potensial aksi, kejadian pemicu menyebabkan membran mengalami depolarisasi dari potensia istirahat -70 mY (Gambar 4-6). Depolarisasi berjalan lambat pada awalnya, sampai tercapai suatu ambang kritis yang disebut potensial ambang, biasanya antara -50 dan -55 mV. Di potensial ambang ini timbul depolarisasi yang eksplosif. Rekaman potensial pada saat ini memperlihatkan. Defleksi cepat ke atas hingga +30 mV karena potensial dengan cepat membalikkan dirinya sehingga bagian dalam sel menjadi positif dibandingkan dengan bagian luarnya. Membran kemudian mengalami repolarisasi sama ceparnya, kembali kepotensial istirahat. G aya, gaya yane menyebabkan repolarisasi membran sering mendorong potensial terlalu jauh, menyebabkan hiperpolarisasi ikutan singkat saat bagian dalam membran menjadi lebih negatif daripada normal (misalnya -80 m\) sebelum akhirnya potensial istirahat pulih. Keseluruhan perubahan cepat potensial membran dari ambang ke puncak dan kemudian kembali ke istirahat disebar pontensial . T idak seperri durasi potensial berj enj ang yang bervariasi, durasi suatu potensial aksi selalu sama di satu sel peka rangsang. Di sel saraf, potensial aksi berlangsung hanya selama 1 mdet (0,001 detik). Potensial ini berlangsung lebih lama di otot, dengan durasi bergantung pada jenis otot. Bagian potensial aksi ketika potensial berbalik (antara 0 dan +30 m\) disebut oaershoot. Potensial aksi sering disebut sebagai sp ibe, karena gambaran rekamann ya yang seperri duri.Selain itu, juga dikatakan bahwa membran peka rangsang yang terpicu untuk mengalami potensial aksi menghasilkan lepas muatan (fire). Karcna itu, istilah potensial aksi, spike, dan lepas mantan mengacu kepada fenomena pembalikan cepat potensial membran. Jika potensial ambang tidak tercapai oleh depolarisasi awal maka tidak terbentuk potensial aksi. Karena itu ambang adalah titik kritis tuntasatau-gagal (all-or-none). Hanya terdapar dua kemungkinan terhadap proses depoiarisasi yaitu membran akan mengalami depolarisasi sampai ke ambang sehingga terbentuk porensial aksi atau ambang tidak tercapai sehingga tidak terbentuk potensial aksi. b. Perubahan mencolok pada permeabilitas membrane dan perpindahan ion menyebabkan potensial aksi Bagaimana potensial membran, yang biasanya dipertahankan pada tingkat istirahat yang tetap, kehilangan keseimbangannya sedemikian sehingga terbentuk potensial aksi? Ingatlah bahwa K. berperan paling besar dalam pembentukan potensial istirahat karena membran saat istirahat jauh lebih permeabel terhadap K. daripada terhadap Na- (lihat h. 84). Selama potensial aksi, terjadi perubahan mencolok dalam permeabilitas membran terhadap Na. dan K- sehingga ion-ion berpindah cepat mengikuti penurunan gradien konsentrasinya. Perpindahan ion-ion ini membawa arus yang berperan dalam perubahan potensial yang terjadi selama potensial aksi. Potensial aksi terjadi kemudian penurupan dua tipe saluran spesifik saluran berpintu voltase dan saluran K- berpintu voltase. Saluran membran berpintu voltase terdiri dari protein-protein yang memilik sejumlah gugus bermuatan. Medan lisuik (potensial) yang mengelilingi saluran ini dapat menyebabkan distorsi pada struktur saluran karena bagian-bagian dari protein saluran yang bermuatan akan tertarik atau tertolak secara elektris ole muatan yangada di cairan sekitar membran. Tidak seperti mayoritas protein membran, yang tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi potensial membran, protein saluran berpintu voltase sangat peka terhadap perubahan voltase. Distorsi kecil bentuk saluran yang ditimbulkan oleh perubahan potensial dapat menyebabkan saluran mengubah konformasinya. Di sini kembali ditemukan contoh bagaimana perubahan ringan pada struktur dapat berpengaruh besar pada fungsi. Saluran Na- berpintu voltase memiliki dua prnru: pintu pengaktifan dan pintu penginahtifan. Pintu pengaktifan menjaga saluran dengan membuka dan menutup. Seperti pintu berengsel. Pintu penginaktifan terdin dan rang kaian asam-asam amino seperri bola dan rantai. Pintu ini terbuka ketika bola rerganrung bebas di rantainya dan tertutup ketika bola berikatan dengan reseptornya yang terletakdi lubang saluran sehingga saluran rerrurup. Kedua pintu harus terbuka agar Na' dapat melalui saluran, dan penutupan salah satu pintu mencegah lewatnya ion ini. c. Perubahan Permeabilitas dan Perpindahan ion selama pontensial aksi Pada potensial istirahat C70 mV), semua saluran Na' dan K berpintu voltase tertutup, dengan pintu pengaktifan saluran Na. tertutup dan pintu penginaktifannya terbuka; yaitu, saluran Naberpintu voltase berada dalam konformasi "tertutup tetapi dapat membuka". Karena itu, pada potensial istirahat Na- dan K- tidak dapat melewati saluran berpintu voltase ini. Namun, karena adanya banyak saluran bocor K dan sangat sedikit saluran bocor Na. maka membran dalam keadaan istirahat 50 sampai 75 kali lebih permeabel terhadap K. daripada terhadap Na-. Ketika suatu membran mulai mengalami depolarisasi menuju ambang akibat suatu kejadian pemicu, pintu pengaktifan sebagian dari saluran Na' berpintu voltase membuka. Kini kedua pintu saluran ini terbuka. Karena gradien konsentrasi dan gradien listrik untuk Na. mendorong perpindahan ion ini masuk ke sel, maka Na' mulai masuk ke dalam sel.Perpindahan Na' yang bermuatan positif menyebabkan membran semakin mengalami depolarisapi, sehingga lebih banyak saluran Na- berpintu voltase terbuka dan lebih banyak Na- yang masuk, demikian sererusnya, dalam suatu siklus umpan-balik positif. Di potensial ambang, terjadi lonjakan peningkatan permeabilitas Na-, yang disimboikan dengan sewaktu membran dengan cepat menjadi 600 kali lebih permeable terhadap Nat daripada terhadap K-. Masing-masing saluran terbuka atau rerturup dan tidak dapat setengah terbuka. Namun, mekanisme pintu berbagai saluran berpinru voltase ini cepat membuka oleh perbedaan voltase yang ringan. Selama fase awal depolarisasi, semakin banyak saluran Na, yang terbuka seiring dengan semakin menurunnya potensial Di ambang, cukup banyak pintu Na- yang terbuka untuk menghentikan siklus umpan-balik positif yang menyebabkan pintu Na'sisanya dengan cepat membuka. Kini permeabilitas Na. mendominasi membran, berbeda dengan dominasi K pada potensial istirahat. Karena itu, pada ambang Na, menyerbumasuk ke dalam sel, dengan cepat melenyapkan negativitas di bagian dalam dan bahkan membuat bagian dalam sel lebih positif daripada bagian luar dalam upaya untuk mendorong potensial membran ke potensial keseimbangan Na- (yang besarnya +60 mV.. Potensial mencapai +30 mV mendekati potensial keseimbangan Na. Potensial tidak dapat menjadi lebih positif karena, pada puncak potensial aksi, saluran Na, mulaimenutup ke keadaan inaktif, dan P*,' mulai rurun ke nilai rst iraha t nya. Apa yang menyebabkan saluran Na. menutup? Ketika potensial membran mencapai ambang, berlangsung dua proses yang berkaitan erar di pintu masing-masing saluran Na. Pertama, pintu pengaktifan terpicu untuk membuka dengan cepat sebagat respons terhadap depolarisasi, mengubah saluran ke konformasi terbuka (aktif) (Gambar 4-7b). Yang mengejutkan, pembukaan saluran ini memicu proses penutupan saluran. Perubahan konformasi yang membuka saluran juga memungkinkan inaktivasi bola pintu untuk berikatan dengan reseprornya di lubang saluran sehingga mulut saluran tersumbat secara fisik. Namun, penurupan ini memerlukan waktu sehingga pinru penginaktifan menutup secdra lambat dibandingkan dengan kecepatan saluran membuka. Sementara itu, selama 0,5 mdet jeda antara pintu pengaktifan membuka dan sebelum pintu penginaktifan tertutup, keduapintu terbuka dan Na. menyerbu masuk ke sel melalui saluransaluran yang rerbuka ini, membawa potensial aksi ke puncaknya. Kemudian pintu penginaktifan menurup, per, meabilitas membran terhadap Na- merosot ke nilai istirahatnya yang rendah, dan pemasukan lebih lanjut Na- ke dalam sel terhenti. Saluran tetap berada dalam konformasi inaktifnya Bersamaan dengan inaktivasi saluran Na, saluran K' berpintu voltase mulai membuka secara perlahan di puncak potensial aksi. Pembukaan pintu saluran K' adalah suatu respons berpintu voltase yang tertunda dan terpicu oleh depolarisasi awal ke ambang. Karena itu, di ambang terjadi tiga proses yang berkaitan dengan potensial aksi: (1) pembukaan cepat pintu aktivasi Na-, yang memungkinkan Na' masuk, memindahkan potensial dari ambang ke puncaknya yang positif; (2) penutupan lambat pintu inaktivasi Na-, yang menghentikan pemasukan lebih lanjut Na. setelah jeda sangat singkat sehingga potensial tidak dapat terus meningkat; dan (3) pembukaan lambat saluran K-, yang, seperti akan anda lihat, berperan besar menirrunkan potensial dari puncaknya ke tingkat istirahat. Potensial membran akan secara bertahap kembali ke istirahat setelah penutupan saluran Na. karena K. terus bocor keluar tetapi tidak ada lagi Na- yang masuk. Namun, pemulihan ke tingkat istirahat ini dipercepat oleh pembukaan pintu K- saat potensial aksi mencapai puncaknya. Pembukaan saluran K- berpintu voltase sangat meningkatkan permeabilitas K- menjadi sekitar 300 kali daripada p . istirahat. Peningkatan mencolok P". ini menyebabkan K+ menyerbu keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi dan gradien listriknya, membawa muatan positif kembali keluar. Perhatikan bahwa pada puncak potensial aksi, potensial positif di bagian dalam sel cenderung menolak ion K. yang positifsehingga gradien listrik untuk K- adalah ke arah luar,tidak seperti saat potensial istirahat. Perpindahan keluar K' permeabilitas K-. menjadi sekitar 300 kali daripada P*^. istirahat. Perpindahan keluar K' secara cepat memulihkan potensial istirahat yang negatif. Sebagai ringkasan , f6e nai.k pada potensial aksi (dari ambang ke +30 mV disebabhan oleh influx (Na. masuk ke sel) akibat peningkatan mendadak PN"' di ambang. Fase turun (dari +30 mV ke potensial istirahat) terutama disebabban oleh efluks K (K- keluar sel). d. Potensial aksi menjalar dari aksi axon hillockke terminal akson Satu potensial aksi melibatkan hanya sebagian kecil dari permukaan membran total sebuah sel peka rangsang. Tetapi jika akan berfungsi sebagai sinyal jarak jauh maka potensial aksi tidak dapat menjadi sekedar kejadian terisolasi yang terbatas di daerah terrenru di membran sel saraf arau otot. Harus terdapat mekanisme untuk menghantarkan atau menyebarkan potensial aksi ke seluruh membran sel. Selain itu, sinyal harus ditransmisikan dari satu sel ke sel lain (sebagai contoh, di sepanjang jalur saraf spesifik). Untuk menjelaskan bagaimana mekanismemekanisme tersebut terlaksana, kita mulamula akan membahas secara singkat struktur neuron. Kemudian kita akan meneliti bagaimana suaru porensial aksi (impuls saraf) dihantarkan ke seluruh sel saraf, sebelum kita mengalihkan perhatian pada bagaimana sinyal dipindahkan ke sel lain. Sebuah sel saraf, arau neuron, biasanya terdiri dari tiga bagian dasar: badan sel, dendrit, dan ahson,meskipun terdapat variasi dalam struktur, bergantung pada lokasi dan fungsi neuron. Nukleus dan organel terdapat di badan sel, tempat bermunculannya banyak tonjolan yang dikenal sebagai dendrit berbentuk seperti antena untuk meningkatkan luas permukaan yang tersedia unruk menerima sinyal dari sel saraf lain . Sebagian neuron memiliki hingga 400.000 juluran permukaan semacam ini. Di sebagirn besar neuron, membran plasma dendrit dan badan sel mengandung reseptor protein untuk mengikat pembawa pesan kimiawi dari neuron lain. Karena itu, dendrit dan badan sel adalah zona input neuron, karena komponen-komponen ini menerima dan 'mengintegrasikan sinyal masuk. Akson, arau serat saraf, adalah penjuluran memanjang tubular tunggal yang menghantarkan potensial aksi meniauhi badan sel dan akhirnya berakhir di sel lain. Akson sering membentuk cabangcabang samping, atau kolateral, di sepanjang perjalanannya. Bagian perrama akson plus bagian badan sel tempar keluarnya akson dikenal sebagai axon hilloch. Axon hilloch adalah zona pemicu neuron, karena di sinilah potensial aksi terbentuk, atau dimulai, oleh potensial berjenjang jika kekuatannya memadai. Potensial aksi kemudian dihantarkan di sepanjang alson dari axon hilhch ke ujung yang biasanya bercabang-cabang di terminal akson. Terminal ini mengeluarkan pembawa pesan kimiawi yang secara bersamaan mempengaruhi banyak sel lain yang berkontak dengan akson ini. Karena itu, secara fungsional, alson adalah zona penghantar neuron, dan rerminal akson membentuk zona Pengecualian utama terhadap struktur dan organisasi fungsional khas neuron ini adalah neuron yang khusus menyalurkan informasi sensorik. Panjang alcon bervariasi dari kurang dari satu millimeter di neuron yang hanya berkomunikasi dengan sel-sel tetangga hingga lebih dari saru merer di neuron yang berhubungan dengan bagian sistem saraf yang jauh atau dengan organ perifer. Sebagai contoh, alson neuron y^ngmenyarrLfi jempol kaki anda harus menempuh jarak dari badan selnya di dalam medula spinalis di bagian bawah punggung anda menelusuri tungkai hingga ke jempol kaki. Potensial alai hanya dapat timbul di bagianbagian membran yang memiliki banyak saluran Na- berpintulrolias. Yang dapat dipicu membuka oleh kejadian yang menyebabkan depolarisasi. Biasanya bagian-bagian sel peka rangsang tempat berlangsungnya porensial berjenjang tidak mengalaml potensial aksi, karena saluran Na. berpintu volrase jarang ditemukan di sini. Karena itu, tempar-tempar yang mengalami potensial berjenjang tidak mengalami potensial aksi, meskipun dapat mengalami depolarisasi yang bermakna. Namun, potensial berjenjang dapat, sebelum lenyap, memicu potensial aksi di bagian-bagian membran sekitar dengan membawa bagian yang lebih peka tersebut ke ambang melalui aliran arus lokal dari tempat potensial berjenjang. Sebagai contoh, di neuron potensial berjenjang biasanya t.rbentuk di dendrit dan badan sel sebagai respons terhadap sinyal kimiawi yang datang. Jika potensial berjenjang ini memiliki kekuatan cukup besar pada saat menyebar ke axon hilloch maka dapat terbentuk potensial aksi di zona pemicu ini. e. Sekali terbentuk,pontensial aksi dihantarkan sepanjang serat saraf Setelah potensial aksi terbentuk di axon hiltock, tidak lagi diperlukan kejadian pemicu untuk mengaktifkan bagian lain serat saraf. Impuls secara otomatis dihantarkan ke seluruh neuron tanpa stimulasi lebih lanjut dengan satu dari dua cara perambatan: h antaran contiguo us (merambat) atau h antaran sabatorik (meloncat). Hantaran merambat adalah penyebaran potensial aksi di sepanjang membran mengikuti panjang akson (contiguous artinya "menyentuh" atau "di samping pada suatu rangkaian"). Proses ini representasi skematik potongan longitu,dinal, axon hillock dan bagian akson tepat sesudahnya. Membran di axon hilloch berada dalam puncak suatu potensial alai. Di daerah ini, bagian dalam sel positif karena Na telah menyerbu masuk ke dalam sel saraf di titik ini. Bagian akson lainnya, yang masih berada dalam potensial istirahat dan negatif di bagian dalamnya, dianggap inaktif. Agar potensial aksi menyebar dari daerah aktif ke daerah inaktif maka daerah inaktif harus mengalami depolarisasi sampai ambang sebelum dapat mengalami potensial aksi. Depolarisasi ini terlaksana oleh aliran arus lokal antara daerah yang sudah mengalami potensial aksi dan daerah inaktif di sebelahnya, serupa dengan aliran arus yang berperan dalam penyebaran potensial berjenjang. Karena muatan yang berlawanan akan saling tarik, maka daerah inaktif sekitar baik di sisi dalam maupun sisi luar membran. Aliran arus lokal ini menetralkan arau memperkecil sebagian dari muatan yang tak seimbang di daerah inaktif; yaitu, aliran tersebut mengurangi jumlah muaran berlawanan yang dipisahkan oleh membran, menurunkan potensial di daerah ini. Efe depolarisasi ini dengan cepat membawa daerah yang semula inaktif ke ambang, saat saluran Na- berpintu voltase di bagian membran ini semua membuka, menyebabkan potensial aksi di daerah yang sebelumnya inaktif. Sementara itu, daerah yang semula aktif, kembali ke potensial istirahat akibat efluks K-.Selanjutnya, di dekat daerah aktifbaru terdapat daerah inaktif lain, sehingga hal yang sama kembali berulang. Siklus ini mengulangi dirinya dalam suatu reaksi berantai sampai potensial aksi relah menyebar kc ujung aksan. Sekali suatu potensial aksi terbentuk dl salah satu bagian membran sel saraf maha akan terpicu suatu siklus sed.emihian sehinga potensial aksi menjalar he seluruh serat secara otomatis. Dengan cara ini,akson mirip dengan sumbu perasan renteng yang hanya perlu dinyalakan salah satu ujungnya. Sekali menyala maka apiakan menjalar di sepanjang renreng; kita tidak perlu menyalakan setiap petasan secara terpisah. Perhatikan bahwa potensial aksi yang asli tidak perlu berjalan di sepanjang membran. Potensial aksi ini memicu potensial aksi baru identik di daerah sekitar di membran, dan proses ini berulang di seluruh panjang akson. Analoginya adalah "waue" (gerakan penonron seperti geiombang) di stadion. Masing-masing bagian penonton berdiri (fase naik potensial aksi), lalu duduk (fase turun) dalam rangkaian satu rnenyusul yang lain f. Garis tengah serat juga mempengaruhi kecepatan perambatan Selain efek mielinasi, diameter serat mempengaruhi kecepatan suatu akson menghantarkan potensial aksi. Kekuatan aliran arus (yaitu, jumlah muatan yang berpindah) bergantung tidak saja pada perbedaan dalam potensial antar dua regio bermuatan listrik yang berdekatan tetapi juga pada resistensi atau halangan terhadap perpindahan muatan listrik antara dua region tersebut. Jika diameter serat bertambah maka resistensi terhadap arus lokal berkurang. Karena itu, semakin besar garis tengah serat semakin cepat potensial alsi dapat dihantarkan. Serat besar bermielin, misalnya serat yang menyarafi otot rangka, dapat menghantarkan potensial aksi dengan kecepatan hingga 120 m/dtk (268 mllljam), dibandingkan dengan kecepatan hantaran 0,7 mldtk (2 milljam) di serat kecil tak-bermielin misalnya serat yang menyarafi saluran cerna. Perbedaan dalam kecepatan hantaran ini berkaitan dengan urgensi informasi yang disampaikan. Sinyal ke otot rangka untuk menjalankan gerakan tertentu (misalnya, mencegah anda jatuh ketika tersandung sesuatu) harus disalurkan lebih cepat daripada sinyal untuk memodifikasi proses pencernaan yang berjalan perlahan. Thnpa mielinasi, diameter akson di jalur saraf urgen tersebut harus sangat besar dan tidak praktis untuk mencapai kecepatan hantaran yang diperlukan. Memang, hal inilah yang terjadi pada banyak invertebrata. Dalam perjalanan evolusi vertebrata, kebutuhan akan serat sarafyang sangat besar telah diatasi oleh pengembangan selubung mielin, yang memungkinkan pengiriman sinyal jarak jauh yang cepat dan ekonomis. Keberadaan sel bermielin dapat sangat bermanfaat atau sangat merugikan ketika suatu akson terpotong, bergantung pada apakah kerusakan terjadi di saraftepi atau di susunan saraf pusat (SSP). Berikutnya kita akan membahas rentang regenerasi serat saraf yang rusak, suatu pokok yang sangar penting dalam cedera medula spinalis atau trauma lain yang mengenai saraf. D. Regenerasi Serat Saraf a. Sel Schwann memandu regenerasi akson perifer yang putus Pada kasus terpotongnya akson di susunan saraftepi, bagian akson yang terletak lebih iauh dari badan sel mengalami degenerasi, dan sel Schwann sekitar memfagosit debrisnya. Sel Schwann itu sendiri menetap dan membentuk tabung regenerasi untuk menuntun serat saraf melaksanakan regenerasi dalam arah yang benar. Bagian akson sisanya yang terhubung ke badan sel mulai tumbuh dan maju di dalam kolom sel Schwann dengan gerakan amuboid. Ujung akson yang tumbuh maju "mengendus" jalannya dengan arah yang tepat, diruntun oleh bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel Schwann ke dalam tabung regenerasi. Berhasilnya regenerasi serat dirandai oleh pulihnya sensasi dan gerakan beberapa waktu setelah cedera saraf perifer, meskipun regenerasi ini tidak selalu berhasil. b. Oligodendrosit menghambat regenerasi akson sentral yang terputus Serat di SSB yang mendapat mielin dari oligodendrosit dan bukan sel Schwann, tidak memiliki kemampuan regenerasi ini. Akson-akson itu sendiri sebenarnya mampu beregenerasi, tetapi oligodendrosit yang mengelilingi mereka menghambat pertumbuhan akson, sangat berbeda dengan efek sel hewan (yang memielinasi akson perifer) yang mendorong pertumbuhan saraf. Pertumbuhan saraf di otak dan medula spinalis dikontrol oleh keseimbangan rumit antara berbagai protein pendorong pertumbuhan saraf dan protein penghambat pertumbuhan saraf Selama masa perkembangan bayi, pertumbuhan saraf di SSP dapat terjadi karena otak dan medula spinalis sedang terbentuk. Para peneliti berspekulasi bahwa inhibitor pertumbuhan saraf, yang terbentuk pada akhir masa perkembangan janin di selubung mielin yang mengelilingi serat SSB mungkin berfungsi sebagai "pagar jalan" untuk menjaga agar ujung-ujung saraf baru tidak keluar dari jalurnya yang benar. Karena itu, efek oligodendrosit yang menghambat pertumbuhan mungkin berfungsi untuk mensrabilkan struktur SSP yang sangat rumit. Namun, inhibisi pertumbuhan merupakan suatu kendala, ketika akson perlu disambung, misalnya saat medulla spinalis terputus akibat kecelakaan. Serat sentral yang rusak segera memperlihatkan tanda-tanda memperbaiki diri setelah suatu cedera, tetapi dalam beberapa minggu serar rersebur mulai berdegenerasi, dan terbentuk jaringan parut di tempat cedera yang menghambat pemulihan. Karena itu, serar neuron yang rusak di otak dan medula spinalis tidak dapat mengalami regenerasi Serat di SSB yang mendapat mielin dari oligodendrosit dan bukan sel Schwann, tidak memiliki kemampuan regenerasi ini. Aksonakson itu sendiri sebenarnya mampu beregenerasi, tetapi oligodendrosit yang mengelilingi mereka menghambat pertumbuhan akson, sangat berbeda dengan efek sel Schwann (yang memielinasi akson perifer) yang mendorong pertumbuhan saraf. Pertumbuhan saraf di otak dan medula spinalis dikontrol oleh keseimbangan rumit antara berbagai protein pendorong pertumbuhan saraf dan protein penghambat pertumbuhan saraf Selama masa perkembangan bayi, pertumbuhan saraf di SSP dapat terjadi karena otak dan medula spinalis sedang terbentuk. Para peneliti berspekulasi bahwa inhibitor pertumbuhan saraf, yang terbentuk pada akhir masa perkembangan janin di selubung mielin yang mengelilingi serat SSB mungkin berfungsi sebagai "pagar jalan" untuk menjaga agar ujung-ujung sarafbaru tidak keluar dari jalurnya yang benar. Karena itu, efek oligodendrosit yang menghambat pertumbuhan mungkin berfungsi untuk mensrabilkan struktur SSP yang sangat rumit. Namun, inhibisi pertumbuhan merupakan suatu kendala, ketika akson perlu disambung, misalnya saat medulla spinalis terputus akibat kecelakaan. Serat sentral yang rusak segera memperlihatkan tanda-tanda memperbaiki diri setelah suatu cedera, tetapi dalam beberapa minggu serar rersebur mulai berdegenerasi, dan terbentuk jaringan parut di tempat cedera yang menghambat pemulihan. Karena itu, serar neuron yang rusak di otak dan medula spinalis tidak dapat mengalami regenerasi. E. SINAPS DAN INTERGRASI NEURON Ketika mencapai terminal alson, potensial aksi membebaskan pembawa pesan kimiawi yang mengubah aktivitas sel sel tempat neuron ini berakhir. Neuron dapat berakhir di salah satu dari tiga struktur berikut: otot, kelenjar, arau neuron lain. Karena itu, bergantung pada di mana suatu neuron berakhir, neuron dapat menyebabkan sel orot berkontrasi, kelenjar mengeluarkan sel.resinya, neuron lain menyalurkan. Pesan listrik di sepanjang jalur saraf atau fungsi lain. Jika neuron berakhir di otot atau kelenjar, maka neuron dikatakan menyaraff, atau memasok, struktur tersebut. Pertemuan antata saraf dan kelenjar atau otot yang disarafinya akan diterangkan kemudian. Saat ini kita akan berkonsentrasi pada hubungan antara dua neuron-sinaps. (Kadang-kadang kata sinaps digunakan untuk menjelaskan taut antara dua sel peka rangsang, tetapi kita akan membatasi pemakaian kata ini untuk taut antara dua neuron). a. Sinaps adalah taut antara neuron prasinaps dan pascasinaps Biasanya sinaps adalah hubungan antara satu terminal akson suatu neuron, yang dikenal sebagai neuron prasinaps, dandendrit atau badan sel neuron lain, yang dikenalsebagai neuron pascasinaps. (Pra artinya"sebelum', dan pasca artinya "sesudah"; neuron prasinaps terletak sebelum sinaps dan neuron pascasinaps terletak sesudah sinaps). Dendrit dan, dengan tingkat yang lebih rendah, badan sel sebagian besar neuron menerima ribuan masukan sinaptik, yaitu terminal akson dari banyak neuron lain. Sebagian neuron di susunan saraf pusat menerima hingga 100.000 masukan sinaps Anatomi salah satu dari ribuan sinaps ini. Terminal akson suatu neuron prasinaps, yang menghantarkan potensial aksinya menuju ke sinaps, berakhir di suatu pembengkakan ringan, slnalrtic bnob. Synaptic knob mengandung vesikel sinaps, yang menyimpan pembawa pesan kimiawi spesifik, neurotransmiter yang telah disintesis dan dikemas oleh neuron prasinaps. Synaptic knob terletak dekat, tetapi sebenarnya tidak berkontak langsung, dengan neuron pascasinaps, neuron yang potensial aksinya menjalar menjauhi sinaps. Ruang antara neuron prasinaps dan pascasinaps disebut celah sinaps. Arus tidak menyebar langsung dari neuron prasinaps ke neuron pascasinaps karena tidak terdapat saluran di membrane prasinaps untuk lewatnya Nat dan K- yang bermuatan listrik. Karena itu, potensial aksi tidak dapat lewat secara elektris di antara dua neuron. Potensial aksi di neuron prasinaps mengubah potensial neuron pascasinaps melalui metode kimiawi. Sinaps hanya bekerja satu arah; yaitu, neuron prasinaps menyebabkan perubahan potensial membran neuron pascasinaps. Tetapi neuron pascasinaps tidak secara langsung mempengaruhi potensial neuron prasinaps. Penyebab hal ini akan jelas jika anda mempelajari kejadiankejadian yang berlangsung di sinaps. b. Neurotransmiter membawa sinyal menyerbangi suatu sinaps Karena terminal prasinaps mengeluarkan neurotransmitter dan membran subsinaps neuron pascasinaps memiliki reseptor untuk neurotransmiter tersebut maka sinaps hanya dapat beroperasi dalam arah dari neuron prasinaps ke neuron pascasinaps. c. Sebagian sinaps merangsang sementara yang lain menghambat neuron pascasinaps Setiap neuron prasinap biasanya hanya mengeluarkan satu neurotransmiter; neurotransmiter namun, neuron yang berbeda mengeluarkan yang berbeda pula. Setelah berikatan dengan reseptornya di membran subsinaps, berbagai neurotransmitter ini menyebabkan beragam perubahan permeabilitas ion. Terdapat duajenis sinaps, bergantung pada perubahan permeabilitas yang ditimbulkannya di neuron pascasinaps oleh ikatan neurotransmiter spesifik dengan reseprornya: sinaps ehsitatorik dan sinaps inhibitorih. d. Sinaps eksitatorik Di sinaps eksitatorik, respons terhadap pengikatan suaru neurotransmitter ke reseptornya adalah terbukanya saluran kation spesifik di membran subsinaps yang memungkinkan lewatnya Na- dan K. melalui saluran tersebut (lni adalah tipe saluran yang berbeda dari yang pernah anda jumpai sebelumnya). Karena itu, permeabilitas terhadap kedua ion ini meningkat pada saat yang sama. Seberapa banyak ion yang berdifusi melalui saluran kation yang terbuka bergantung pada gradien elektrokimiawinya. Pada potensial istirahat, gradien konsentrasi dan listrik untuk Na- mendorong perpindahan ion ini masuk ke neuron pascasinaps, sementara hanya gradien konsentrasi untuk K. yang mendorong perpindahan ion ini keluar. Karena itu, perubahan permeabilitas yang terpicu di sinaps eksitatorik menyebabkan perpindahan sedikit ion Kt keluar neuron pascasinaps, sementara ion Nadalam jumlah relatif besar secara bersamaan masuk ke neuron ini. Hasilnya adalah perpindahan netto ion positif ke dalam sel. Hal ini menyebabkan bagian dalam membran sedikit kurang negatif daripada saat potensial istirahat sehingga menimbulk depolarisasi kec neueuron pascasinaps. Pengaktifan satu sinaps eksitatorik dapat menyebabkan depolarisasi neuron pascasinaps yang mencapai ambang. Terlaiu sedikit saluran yang terlibat di satu membran subsinaps untuk memungkinkan perpindahan ion yang adekuat untuk mengurangi potensial menuju ambang. Namun, depolarisasi ringan ini membawa neuron pascasinaps lebih dekat ke ambang. Meningkatkan kemungkinan bahwa ambang akan tercapai (sebagai respons terhadap input eksitatorik selanjutnya) dan akan timbul potensial aksi. Yaitu, membran kini lebih peka rangsang (lebih mudah mencapai ambang) daripada saat istirahat. Karena itu, perubahan potensial pascasinaps yang terjadi di sinaps eksitatorik ini disebut potensial pascasinaps eksitatorik (PPE). e. Sinaps inhibitorik Di sinaps inhibitorik, pengikatan neurotransmiter yang berbeda dengan reseptornya meningkatkan permeabilitas membran subsinaps terhadap K. atau Cl. Pada keadaan tersebut kasus, perpindahan ion yang terjadi biasanya menyebabkan hiperpolarisasi hecil nevon pascasinapsyaitu, negativitas bagian dalam yang lebih besar. Pada peningkatan, lebih banyak muatan positif keluar dari sel melalui efluks K., meninggalkan muatan lebih negatif di bagian dalam sel. Untuk menimbulkan hiperpolarisasi membran pada peningkatan P.,-, lebih banyak muatan negatif masuk ke sel dalam bentuk ion Cl', karena konsentrasi Cl- di luar sel jauh lebih tinggi, daripada yang terdorong keluar oleh gradien listrik yang terbentuk oleh potensial membran istirahat (lihat h. 87). Pada keduanya, hiperpolarisasi kecil ini membawa potensial membran semakin jauh dari ambang, memperkecil kemungkinan bahrna neuron pascasinaps akan mencapai ambang dan mengalami potensial atr<si. Yaitu, membran kini kurang peka rangsang (lebih sulit dibawa ke ambang oleh masukan eksitatorik) dibandingkan ketika keadaan istirahat. Membran dikatakan terhambat oleh keadaan ini, dan hiperpolarisasi kecil sel pascasinaps disebut potensial pascasinaps inhibitorik (PPI). Di sel yang potensial keseimbangannya untuk Clsama persis dengan potensial istirahat, peningkatan P.,- tidak menyebabkan hiperpolarisasi karena tidak terdapat gaya pendorong untuk memindahkan C1-. Pembukaan saluran Cl'di sel-sel ini cenderung menahan membran pada potensial istirahatnya, mengurangi kemungkinan tercapainya ambang. Perhatikan bahwa PPE dan PPI dihasilkan oleh pembukaan saluran-saluran berpintu kimiawi, tidak seperti potensial aksi, yang dihasilkan oleh pembukaan saluran-saluran f. Neuron neuron konvergensi dan dihubungkan oleh jalur divergensi yang kompleks. Terdapat dua hubungan penting antara neuron-neuron: konvergensi dan divergensi. Satu neuron dapat memiliki banyak neuron lain bersinaps padanya. Hubungan semacam ini dikenal sebagai konvergensi. Melalui masukan konvergensi ini, sebuah sel dipengaruhi oleh ribuan sel lain Satu. Sel ini, selanjutnya, mempengaruhi tingkat aktivitas banyak sel lain melalui divergensi keluaran. Kata divergensi merujuk kepada percabangan terminal akson sehingga satu sel bersinaps dengan dan mempengaruhi banyak sel lain. Perhatikan bahwa suatu neuron adalah neuron pascasinaps bagi neuron yang berkonvergensi padanya tetapi prasinaps bagi sel lain tempat neuron tersebut berakhir. Karena itu, kata pras inaps dan p as c as inaps hanya merujuk kepada satu sinaps. Sebagian besar neuron adalah prasinaps bagi satu kelompok neuron dan pascasinaps bagi kelompok lain. Diperkirakan di otak saja terdapat 100 milyar neuron dan I 0 la ( I 00 kuadriliun) sinapsl Jika anda memperhitungkan besarnya dan rumitnya interkoneksi yang mungkin terbentuk di antara neuron-neuron tersebut melalui jalur konvergensi dan divergensi, anda dapat membayangkan betapa rumitnya mekanisme interkoneksi sistem saraf kita. Bahkan computer paling canggih sekalipun jauh lebih sederhana daripada otak manusia. "Bahasa" sistem saraf-yaitu, semua komunikasi di antara neuron-neuron*adalah dalam bentuk potensial berjenjang, potensial aksi, sinyal neurotransmiter menyeberangi sinaps, dan bentukbentuk' percakapan' kimiawi non sinaps lainnya. Semua aktivitas yang dikendalikan oleh sistem sarafsetiap sensasi yang anda rasakan, setiap perintah untuk menggerakkan otot, setiap pikiran, setiap emosi, setiap ingatan, setiap percikan kreativitas-bergantung pada pola pembentukan sinyal listrik dan kimiawi di antara neuron-neuron yang membentuk anyaman saraf maha kompleks ini. Sebuah neuron berkomunikasi dengan sel yang dipengaruhi. Semua aktivitas yang dikendalikan oleh sistem saraf setiap sensasi yang anda rasakan, setiap perintah untuk menggerakkan otot, setiap pikiran, setiap emosi, setiap ingatan, setiap percikan kreativitas-bergantung pada pola pembentukan sinyal listrik dan kimiawi di antara neuron-neuron yang membentuk anyaman saraf maha kompleks ini. Sebuah neuron berkomunikasi dengan sel yang dipengaruhinya dengan mengeluarkan neurotransmiter, tetapi ini hanya salah satu dari cara-cata komunikasi antarsel. Sekarang kita akan membahas semua cara yang digunakan oleh sel untuk "saling bercakap-cakap". F. komunikasi antar sel dan tranduksi sel Komunikasi antarsel berlangsung melalui cara-cara berikut: 1. Cara paling intim dalam komunikasi antarsel adalah melalui taut celah, yaitu saluran-saluran halus yang menjembatani sitoplasma selsel yang berdekatan di jenis jaringan tertentu. Melalui susunan anatomic khusus ini, ion dan molekul kecil secara langsung dipertukarkan antara sel-sel yang berinteraksi tersebut tanpa pernah masuk ke cairan ekstrasel. 2. Adanya penanda-penanda identifikasi di membran permukaan sebagian sel memungkinkan mereka langsung berhubungan secara transien dan berinteraksi dengan sel lain dengan carakhusus. Ini adalah cara yang digunakan oleh fagosit pada sistem pertahanan tubuh untuk mengenal dan secara selektif menghancurkan hanya sel yang tidak diinginkan, misalnya sel kanker, sedangkan sel tubuh sendiri yang sehat ridak terpengaruh. 3. Cara tersering yang dilakukan sel untuk berkomunikasi satu sama lain adalah secara ridak langsung dengan menggunakan pembawa pesan (perantara) kimiawi ekstrasel, yang terdiri dari empat jenis: parakrin, neurotransmiter, /tormon, dan neurohormon. Pada masingmasingnya, sel tertentu membentuk perantara kimiawi spesifik untuk tujuan tertentu. Setelah dibebaskan ke dalam CES atas stimulasi yang sesuai, bahan-bahan pembawa sinyal ini bekerja pada sel tertentu, yaitu sel sasaran pembawa pesan, dengan cara yang telah ditetapkan. Untuk menimbulkan efek, pembawa pesan kimiawi ekstrasel ini harus berikatan dengan reseptor sel sasaran yang spesifik untuknya. Keempat jenis pembawa pesan kimiawi berbeda dalam sumber serta jarak dan cara yang digunakan untuk sampai ke tempat kerjanya sebagai berikut: 1. Parakrin adalah pembawa pesan kimiawi lokal yang efeknya hanya terjadi di sel-sel sekitar dalam lingkungan dekat tempat sekresinya. Karena parakrin tersebar melalui proses difusi sederhana, maka kerja bahan ini terbatas pada jarak pendek. Bahan ini tidak masuk ke dalam darah dalam jumlah bermakna karena cepat diinaktifkan oieh enzimenzim lokal. Salah satu contoh parakrin adalah histamin, yang dibebaskan dari sejenis sei jaringan ikat sewaktu terjadi respons peradangan di jaringan yang rusak. Histamin antara lain menyebabkan dilatasi (pelebaran) pembuluh darah sekitar untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan. Efek ini menyebabkan kedatangan iebih banyak selsei pertahanan yang berasal dari darah ke bagian yang cedera arau terinfeksi. Parakrin harus dibedakan dari bahan kimia yang mempengaruhi sel sekitar setelah dibebaskan secara non spesifik selama aktivitas sel. Sebagai contoh, peningkatan konsentrasi CO, lokal di otot yang sedang bekerja adalah salah satu faktor yang mendorong dilatasi lokal pembuluh darah yang mendarahi otot. Peningkatan aliran darah yang terjadi ikut membantu memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik jaringan. Namun, CO, dihasilkan oleh semua sel dan tidak secara spesifik dibebaskan untuk melaksanakan respons khusus ini, sehingga CO, dan bahan-bahan kimia lain yang dikeluarkan secara non-spesifik tidak dianggap parakrin. 2. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi jarak jauh yang secara spesifik dikeluarkan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin sebagai respons terhadap sinyal yang sesuai. Darah membawa pembawa pesan tersebut ke bagian-bagian tubuh lain, untuk mempengaruhi sei sasaran yang berjarak dari tempat sekresinya. Hanya sel sasaran dari hormon tertentu yang memiliki reseptor membran untuk berikatan dengan hormon ini. Sel non sasaran tidak dipengaruhi oleh hormon dalam darah yang mencapai sel tersebut. 3. Neurohormon adalah hormon yang dibebaskan ke dalam darah oleh neuron neurosekretorik. Seperti neuron biasa, neuron neurosekretorik dapat berespons terhadap dan menghantarkan sinyal listrik. Namun, neuron neurosekretorik tidak secara langsung menyarafi sel sasaran tetapi membebaskan pembawa pesan kimiawinya, neurohormon, ke dalam darah setelah mendapat rangsangan yang sesuai. Neurohormon ini kemudian terdistribusi melalui darah ke sel sasaran yang jauh. Karena itu, seperti sel endokrin, neuron neurosekretorik mengeluarkan pembawa pesan kimiawi ke dalam darah, sementara neuron biasa mengeluarkan neurotransmiter jarak pendek ke dalam ruang tertutup. Di masa mendatang, kata umum hormon akan secara perlahan mencakup hormon darah dan pembawa pesan neurohormon. Demikianlah, pembawa pesan kimiawi eksrasel dibebaskan dari satu jenis sel dan berinteraksi dengan sel sasaran lain untuk menghasilkan efek yang diinginkan di sel sasaran. Kini kita mengalihkan perhatian pada bagaimana pembawa pesan kimiawi ini menimbulkan respons sel yang diinginkan. G. Prinsip komunikasi hormone Endokrinologi adalah ilmu tentang penyesuaian kimiawi homeostatik dan aktivitas lain yang dilaksanakan oleh hormon, yang disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin adalah dua sistem regulatorik utama tubuh. Bagian perrama dari bab ini menjelaskan mekanisme molekular dan selular mendasar yang berfungsi sebagai basis bagi bekerjanya keseluruhan sisrem saraf-pembentukan sinyal listrik di dalam neuron dan transmisi kimiawi sinyal antara neuron-n€uron. Kini kita akan berfokus pada ciri molekular dan selular kerja hormon dan akan membandingkan kemiripan dan perbedaan dalam bagaimana sel saraf dan sel endokrin berkomunikasi dengan sel lain dalam melaksanakan tugas regulasi mereka. Yang terakhir, berdasarkan perbedaan cara kerja di tingkat mole kular dan selular, bagian terakhir dari bab ini akan membandingkan secara umum bagaimana sistem saraf dan endokrin berbeda sebagai sistem regulatorik. Hormon diklasifikasikan secara kimiawi sebagai hidrofilik atau lipofilik. Hormon-hormon secara kimiawi tidak sama dan digolongkan ke dalam dua kelompok berbeda berdasarkan sifat kelarutannya: hormon hidrofilik atau lipofilik. Hormon dalam kelompok masing-masing dibagi lagi berdasarkan struktur biokimia dan/atau sumbernya sebagai berikut: 1. Hormon hidrofilik ("menyrrkai air") sangat larut air dan memiliki kelarutan lemak yang rendah. Sebagian besar hormon hidrofilik adaiah peptida atau hormon protein yang terdiri dari asam-asam amino spesifik tersusun dalam rantai dengan panjang bervariasi. Rantai yang lebih pendek adalah peptida, dan yang lebih panjang adalah protein. Untuk memudahkan, selanjutnya kita akan menyebut keseluruhan kategori ini sebagai peptida. Salah satu contoh adalah insulin dari pankreas. Kelompok lain hormon hidrofilik adalah kateholamin, yang berasal dari asam amino tirosin dan secara spesifik dikeluarkan oleh medula adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari medula adrenal di sebelah dalam dikelilingi oleh korteks adrenal di sebelah luar. (Anda akan mempelajari lebih lanjut renrang lokasi dan struktur kelenjar endokrin di bab-bab selanjutnya). Epinefrin adalah katekolamin yang utama. 2. Hormon lipofilik ("menyukai lemak") memiliki kelarutan lemak yang tinggi dan kurang larut dalam air. Hormon lipofilik mencakup ltormon tiroid dan hormon steroid. Hormon tiroid, seperti diisyaratkan oleh namanya, disekresikan secara eksklusif oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroid adalah turunan tirosin beriodium. Meskipun katekolamin dan hormon tiroid berperilaku sangar berbeda namun keduanya kadang disatukan ke dalam golongan h ormon amin karenasama-sama turunan tirosin. Steroid adalah lemak netral yang berasal dari kolesterol. Hormon yang disekresikan oleh korteks adrenal, misalnya kortisol, dan hormon seks (testosteron pada pria dan estrogen pada wanita) yang disekresikan oleh organ reproduksi adalah steroid. H. Perbandingan Sistem Saraf dan Sistem Endokrin 1. SISTEM ENDOKRIN Sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ (kadang disebut sebagai kelenjar sekresi internal), yang fungsi utamanya adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein / senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Hormon bekerja sama dengan system syaraf untuk mengatur pertumbuhan, dan tingkah keseimbangan internal, reproduksi dan tingkah laku. Kedua system tersebut mengaktifkan sel untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan menggunakan messenger kimia. 1.1 Kelenjar Endokrin Kelenjar endokrin menggunakan messenger kimia yaitu hormon yang diedarkan oleh system trasnportasi (darah), dan mempengaruhi sel target yang ada diseluruh tubuh. Kerja system endokrin lebih lambat dibandingkan dengan system syaraf, sebab untuk mecapai sel target hormon harus mengikuti aliran system transportasi. Sel target memiliki receptor sebagai alat khusus untuk mengenali impuls / rangsang. Ikatan antara receptor dengan hormon di dalam atau di luar sel target, menyebabkan terjadinya respons pada sel target. Tabel nama dan letak kelenjar endokrin dalam tubuh: No. Kelenjar Nama Lain Letak 1. Kelenjar pituitary Dibagian dasar cerebrum, Hipofisis dibawah hipotalamus 2. Tiroid Kelenjar gondok Didaerah leher dekat jakun 3. Paratiroid Kelenjar anak gondok Dibagian belakang (dorsal) dari kelenjar tiroid 4. 5. 6. Kelenjar Kelenjar pulau-pulau Dekat lambung pankreas Langerhans Kelenjar gonad Kelenjar kelamin Kelenjar · Laki-laki : testis · Perempuan: ovarium Kelenjar supra renalis Di atas ginjal Kelenjar kacangan Di daerah dada adrenalin 7. Kelenjar timus a. Hypothalamus Hipotalamus adalah bagian dari otak besar yang mengatur homeostasis tubuh dengan pengaturan bagian dalam tubuh seperti detak jantung, suhu tubuh, keseimbangan air dan sekresi dari kelenjar pituitary. b. Kelenjar Pituitari (kelenjar hipofisis) Nama Lain: Master of glands sebab menghasilkan berbagai hormone yang berfungsi mengatur kerja kelenjar endokrin lainnya. Bentuk dan ukuran: Lonjong sebesar biji kacang kapri. Letak: Dibawah hypothalamus. Kelenjar pituitary terdiri atas dua lobus. Hormon yang dihasilkan lobus posterior di sintesis oleh neuron yang ada di hipotalamus. Sedangkan lobus anterior memproduksi hormone dan mengeluarkannya. Perhatikan diagram dibawah ini yang menggambarkan hubungan antara hipotalamus, kelenjar pituitary dan masing-masing kelenjar yang mereka control. c. Kelenjar pituitary lobus posterior Lobus posterior dari kelenjar pituitary berisi ujung akson dari neuron yang memanjang dari hipotalamus. Hormon disimpan di dalam dan dikeluarkan dari ujung akson yang berada di lobus posterior dari kelenjar pituitary. d. Oksitosin Oksitosin merangsang kontraksi rahim untuk mendorong janin saat persalinan. Oksitosin juga merangsang pengeluaran ASI dari kelenjar susu yang disebabkan kontraksi sel-sel disekitarnya. Setelah kelahiran, isapan bayi pada putting susu merangsang pengeluaran hormone oksitosin dari kelenjar pituitary bagian posterior. e. Antidiuretika Hormon (ADH) Hormon antidiuretika meningkatkan permeabilitas dari tubulus kontortus distal dan tubulus kolektifus dari nefron ginjal, sehingga volume urin menurun. Sekresi dari hormone ADH mengontrol mekanisme efek timbal balik sebagai berikut: Konsentrasi darah (kadar air sedikit) menyebabkan darah menjadi lebih encer. Jika darah terlalu encer, system sirkulasi akan merangsang jantung untuk menghasilkan hormone atrial natriuretic (ANF). Hormon ini menghambat pengeluaran hormon ADH dari kelenjar pituitary bagian posterior sehingga volume urin meningkat. Alkohol merupakan zat yang memiliki kemampuan menghambat pengeluaran ADH, sehingga ginjal meproduksi urin yang lebih encer (volume rin meningkat) f. Kelenjar pituitary lobus anterior Hipotalamus menghasilkan hormone yang dibawa dalam pembuluh darah menuju bagian anterior dari kelenjar pituitary. Hormon ini digunakan untuk merangsang pituitary untuk menghasilkan hormonehormon lain. Kelenjar pituitari menghasilkan lebih dari delapan hormon. Masing-masing hormon dihasilkan sebagai respons terhadap hormon pelepas dari hipotalamus (hormon releasing dari hiotalamus). Pembuluh darah membawa hormon pelepas dari hipotalamus menuju kelenjar pituitari melalui perantara yang disebut vena porta, sebab vena porta menghubungkan dua ujung kapiler. Satu ujung kapiler terletak di dalam hipotamus, dan ujung lainya terdapat bagian anterior kelenjar pituitari. Hormon pelepas yang bersifat menghambat (hormone releasing inhibits) dihasilkan oleh hipotalamus, yang berfungsi menghambat pengeluaran hormone pelepas yang memacu (hormone releasing) seperti tersebut di atas. Dari delapan jenis hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary lobus anterior, 3 diantaranya memiliki efek langsung pada tubuh, sedangkan 3 lainnya mengatur kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Hormon lobus anterior dari kelenjar pituitary yang memberikan efek langsung ke tubuh. 1. Hormon Pertumbuhan (Somatotropik hormone / STH) atau growth hormone Hormon pertumbuhan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh. Jika hormone ini diproduksi dalam jumlah sedikit, akan menyebabkan kerdil (dwarfisme), demikian sebaliknya jika produksi hormone ini berlebih akan menyebabkan pertumbuhan raksasa (gigantisme). 2. Prolaktin Prolaktin diproduksi dalam jumlah besar setelah proses kelahiran. Fungsi hormone prolaktin adalah merangsang perkembangan kelenjar susu dan produksi ASI. Selain itu hormone ini juga mempengaruhi proses metabolism lemak dan karbohidrat. 3. Melanosite-Stimulasing Hormon (MSH) Hormon ini menyebabkan warna kulit ikan, amfibi dan reptile berubah-ubah. Pada manusia melanosit stimulasing hormone berfungsi untuk merangsang sintesis pigmen melanin. Ada Tiga jenis hormone yang dihasilkan kelenjar pituitary adalah: a. Tiroid Stimulating hormone (TSH) Fungsi mengendalikan sekresi hormon tiroksin oleh kelenjar gondok. Pengeluaran hormone ini dipacu oleh hormone pelepas (thyrotropic releasing factor). Jika kadar TSH tinggi menandakan tubuh kekurangan hormon tiroksin. Sekresi hormone tiroksi berkurang biasanya disebabkan rendahnya kadar unsur yodium dalam darah. Hal ini akan menyebabkan penyakit gondok (goiter) b. Adenocorticotropic hormone (ACTH) Fungsi merangsang bagian korteks kelenjar adrenal untuk mensekresikan hormone glukokortikoid. Pengeluaran hormone ini dipacu oleh hormon pelepas (corticotrophin releasing factor) yang dihasilkan oleh hipofisis. c. Gonadotropic hormone ( FSH dan LH) 1. FSH (Folikel Stimulating Hormon) Fungsi: Pada perempuan : Merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel dalam ovarium sehingga menjadi folikel de graaf Pada laki-laki : Mengatur perkembangan testis dan merangsang spermatogenesis 2. Luteining Hormon Fungsi: a) Pada perempuan: 1. Mempengaruhi terjadinya ovulasi 2. Membentuk korpus luteum dari sisa folikel 3. Merangsang korpus luteum untuk mensekresikan hormon progesterone b) Pada laki-laki Merangsang sel-sel interstitial (sel-sel leydig) dalam testis untuk mensekresikan hormone testosterone. Hormon LH pada laki-laki biasanya disebut juga ICSH (interstitial stimulating hormone) 1.2 Penghambat Umpan Balik negative Sekresi hormone oleh kelenjar dikontrol oleh hipotalamus. Pengaturan pengeluaran hormon melalui mekanisme negative umpan balik. Ketika jumlah hormone meningkat, maka hormone tersebut akan menghambat hipotalamus dan pituitary lobus anterior akibatnya produksi hormone menjadi menurun. 1) Kelenjar tiroid Kelenjar tiroid menghasilkan hormone tiroksin (disebut T4 karena didalam hormone ini berikatan 4 molekul yodium), dan triiodothyronin (disebut juga T3 karena di dalam hormone berisi 3 molekul iodine). Antara T4 dan T3 memiliki kesamaan efek pada sel target. Dalam sebagian besat jaringan target, T4 dapat dikonversi menjadi T3. T4 dan T3 mempengaruhi kecepatan metabolism, pertumbuhan, dan perkembangan. Produksi hormone tiroksin diatur melalui mekanisme negative umpan balik dimana hormone tersebut menghambat hipotalamus untuk merangsang kelenjar tiroid. Hipotyroidisme terjadi bila kelenjar tiroid menghasilkan hormone tiroksin dalam jumlah sedikit. Pada orang dewasa dampak yang ditimbulkan adalah letargi mental, dan penambahan berat badan. Pada anak-anak menyebabkan kretinisme dengan karakteristik kerdil (dwarfisme) retardasi mental, dan kurang matang seksual. Hipertyroidisme terjadi bila konsentrasi hormone T3 dan T4 meningkat. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan penurunan berat badan. 2) Kalsitonin Kelenjar tiroid juga menghasilkan hormone kalsitonin yang merangsang penyimpanan kalsium dalam tulang. Kerja hormone ini berlawanan dengan hormone yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, perhatikan diagram dibawah ini Produksi hormone kalsitonin tidak diatur oleh kelenjar pituitary lobus anterior. Sekresi hormone ini dirangsang oleh tingginya kadar kalsium dalam darah. 3) Kelenjar paratiroid Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak dipermukaan posterior dari kelenjar tiroid. Kelenjar ini mensekresikan hormone paratiroid (PTH) yang meningkatkan kadar ion Ca dalam darah. Jaringan tulang merupakan tempat timbunan ion kalsium. Hormon paratiroid merangsang pengeluaran ion calcium dari tulang untuk meningkatkan kadar calcium darah. Hormon paratiroid juga meningkatkan reabsorbsi ion kalsium di ginjal sehingga kadar ion kalsium dalam urine menurun. Hormon paratiroid ini juga mengaktifkan vitamin D yang meningkatkan reabsorbsi ion kalsium dari bahan makanan dalam saluran pencernaan. 4) Adrenal Cortex Lapisan terluar dari kelenjar adrenalin disebut korteks adrenal. Bagian ini menghasilkan tiga jenis hormone steroid yaitu Glukokortikoid, mineralokortikoid, dan sejumlah kecil hormone kelamin. 5) Cortisol (A Glucocorticoid) Hormon glukokortikoid dihasilkan berupa tanggapan dalam keadaan stress. Hormon kortisol dalam Glucocorticoids are produced in response to stress. Hormon kortisol menimbulkan peningkatan kadar gula dalam darah dengan cara merangsang hati untuk menghasilkan gula dari sumber non karbohidrat seperti protein dan lemak dan melepas glukosa ke dalam darah. 6) Pankreas Pankreas merupakan kelenjar pencernaan yang mensekresikan enzim pencernaan ke dalam duodenum melalui saluran pancreas. Kelenjar pulau-pulau langerhans adalah kelompok cel di dalam pancreas yang mensekresikan hormone insulin dan hormone glucagon. Kelenjar pulau-pulau langerhans merupakan kelenjar endokrin sebab tidak memiliki saluran, dan hormone dibawa melalui system peredaran darah menuju sel target. 7) Insulin Insulin mendorong pengeluaran glukosa dalam darah untuk disimpan sebagai glikogen (otot, hati), lemak (sel lemak) dan protein. Hormon insulin mendorong pembentuk protein dan lemak dan menghambat pemakaiannya sebagai sumber energy.. 8) Glukagon Hormon glucagon dihasilkan oleh kelenjar pulau-pulau langerhans pada bagian yang berbeda dengan tempat pembentukkan hormone insulin. Pengaruh hormone glucagon berlawanan dengan homon insulin, yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Secara normal sekresi kedua hormone tersebut berfungsi untuk mengatur kadar gluosa dalam darah. 1.3 Pengendalian Endokrin Jika kelenjar endokrin mengalami kelainan fungsi, maka kadar hormon di dalam darah bisa menjadi tinggi atau rendah, sehingga mengganggu fungsi tubuh. Untuk mengendalikan fungsi endokrin, maka pelepasan setiap hormon harus diatur dalam batas-batas yang tepat. Tubuh perlu merasakan dari waktu ke waktu apakah diperlukan lebih banyak atau lebih sedikit hormon. Hipotalamus dan kelenjar hipofisa melepaskan hormonnya jika mereka merasakan bahwa kadar hormon lainnya yang mereka kontrol terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hormon hipofisa lalu masuk ke dalam aliran darah untuk merangsang aktivitas di kelenjar target. Jika kadar hormon kelenjar target dalam darah mencukupi, maka hipotalamus dan kelenjar hipofisa mengetahui bahwa tidak diperlukan perangsangan lagi dan mereka berhenti melepaskan hormon. Sistem umpan balik ini mengatur semua kelenjar yang berada dibawah kendali hipofisa. Hormon tertentu yang berada dibawah kendali hipofisa memiliki fungsi yang memiliki jadwal tertentu. Misalnya, suatu siklus menstruasi wanita melibatkan peningkatan sekresi LH dan FSH oleh kelenjar hipofisa setiap bulannya. Hormon estrogen dan progesteron pada indung telur juga kadarnya mengalami turun-naik setiap bulannya. 2. SISTEM SYARAF Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan (impuls) yang berupa rangsang atau tanggapan. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson (neurit). Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Membran plasma sel Schwann disebut neurilemma. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier, yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. 1. Sel Saraf (Neuron) Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf (neuron). Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson (neurit). Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus (inti sel) dan tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleolus (anak inti sel), dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut badan Nissl. Pada badan sel terdapat bagian yang berupa serabut de ngan penjuluran pendek. Bagian ini disebut dendrit. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang (seperti pohon) dengan berbagai bentuk dan ukuran. Fungsi dendrit adalah menerima impuls (rangsang) yang datang dari reseptor. Kemudian impuls tersebut dibawa menuju ke badan sel saraf. Selain itu, pada badan sel juga terdapat penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Namanya adalah akson atau neurit. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti otot dan kelenjar. Walaupun diameter akson hanya beberapa mikrometer, namun panjangnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Supaya informasi atau impuls yang dibawa tidak bocor (sebagai isolator), akson dilindungi oleh selubung lemak yang kemilau. Kita bisa menyebutnya selubung mielin. Selubung mielin dikelilingi oleh sel-sel Schwan. Selubung mielin tersebut dihasilkan oleh selsel pendukung yang disebut oligodendrosit. Sementara itu, pada akson terdapat bagian yang tidak terlindungi oleh selubung mielin. Bagian ini disebut nodus Ranvier, yang berfungsi memperbanyak impuls saraf atau mempercepat jalannya impuls. Berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Neuron sensorik merupakan neuron yang memiliki badan sel bergerombol membentuk simpul saraf atau ganglion (jamak = ganglia). Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain, sedangkan neuritnya berkaitan dengan dendrit neuron lain. Fungsi neuron sensorik yakni meneruskan impuls (rangsangan) dari reseptor menuju sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Oleh karena itu, neuron sensorik disebut pula neuron indra Sementara itu, neuron motorik merupakan neuron yang berperan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Karena perannya ini, neuron motorik disebut pula neuron penggerak. Dendrit neuron motorik berhubungan dengan neurit neuron lain, adapun neuritnya berkaitan dengan efektor (otot dan kelenjar). Antara neuron sensorik dan neuron motorik dihubungkan oleh interneuron atau neuron adjustor dengan letak yang berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron merupakan neuron yang membawa impuls dari sensorik atau interneuron lain. Karena itu, interneuron disebut pula neuron konektor. 2. Impuls Sel-sel saraf bekerja secara kimiawi. Sel saraf yang sedang tidak aktif mempunyai potensial listrik yang disebut potensial istirahat. Jika ada rangsang, misalnya sentuhan, potensial istirahat berubah menjadi potensial aksi. Potensial aksi merambat dalam bentuk arus listrik yang disebut impuls yang merambat dari sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai ke pusat saraf atau sebaliknya. Jadi, impuls adalah arus listrik yang timbul akibat adanya rangsang. 3. Sinapsis Dalam pelaksanaannya, sel-sel saraf bekerja bersama-sama. Pada saat datang rangsang, impuls mengalir dari satu sel saraf ke sel saraf penghubung, sampai ke pusat saraf atau sebaliknya dari pusat saraf ke sel saraf terus ke efektor. Hubungan antara dua sel saraf disebut sinapsis. Ujung neurit bercabang-cabang, dan ujung cabang yang berhubungan dengan sel saraf lain membesar disebut bongkol sinaps (knob). Pada hubungan dua sel saraf yang disebut sinaps tersebut, dilaksanakan dengan melekatnya neurit dengan dendrit atau dinding sel. Jika impuls sampai ke bongkol sinaps pada bongkol sinaps akan disintesis zat penghubung atau neurotransmiter, misalnya zat asetilkolin. Dengan zat transmiter inilah akan terjadi potensial aksi pada dendrite yang berubah menjadi impuls pada sel saraf yang dihubunginya. Setelah itu, asetilkolin akan segera tidak aktif karena diuraikan oleh enzim kolin esterase menjadi asetat dan kolin. 4. Susunan Sistem Saraf 1) Sistem Saraf Pusat Tanpa sistem saraf pusat, kemungkinan kita menjadi makhluk yang tak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun. Sebab, di dalam sistem saraf pusat tubuh kita terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Dua bagian tubuh inilah yang menjadi sentral pusat koordinasi tubuh kita. Pada manusia, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh suatu tulang. Tulang yang melindungi otak adalah tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Kedua organ penting ini juga dilindungi oleh suatu lapisan pembungkus yang tersusun dari jaringan pengikat. Lapisan ini disebut meninges. Meninges terbagi menjadi tiga lapisan, meliputi lapisan dalam disebut piameter; lapisan tengah disebut arachnoid; dan lapisan dalam disebut durameter. a. Otak Otak merupakan benda lengket yang lunak, bermi nyak, dan kenyal. Jutaan saraf menghubungkannya dengan seluruh tubuh, syaraf tersebut membawa pesan baik menuju otak atau dari otak. Beratnya sekitar 1,6 kg pada laki-laki dan 1,45 kg pada perempuan. Perbedaan ini terjadi semata-mata karena bentuk otak laki-laki yang lebih besar dan berat. Sementara, berat ini tidak terkait dengan kecerdasan seseorang. Namun, banyaknya jumlah hubungan sel dalam otaklah yang menunjukkan kecerdasan. Otak manusia terdiri atas dua belahan (hemisfer) yang besar, yakni belahan kiri dan belahan kanan. Oleh karena terjadi pindah silang pada tali spinal, belahan otak kiri mengendalikan sistem bagian kanan tubuh, sebaliknya belahan kanan mengendalikan sistem bagian kiri tubuh. Tali spinal (sumsum tulang belakang) merupakan tali putih kemilau yang berasal dari dasar otak hingga tulang belakang. Antara bagian tengah sumsum tulang belakang dan otak terdapat saluran yang saling berhubungan, yang disebut ventrikel. Ventrikel membagi otak menjadi empat ruangan. Di dalam ventrikel, terdapat cairan serebrospinal yang dapat bertukar bahan dengan darah dari pembuluh kapiler pada otak. a) Otak depan (Prosensefalon) Pada bagian depan otak manusia terdapat bagian yang paling menonjol disebut otak besar atau serebrum (cerebrum). Serebrum ini terbagi menjadi belahan (hemisfer) serebrum kanan dan kiri. Permukaan luar serebrum (korteks serebrum) berwarna abu-abu karena mengandung banyak badan sel saraf. Selain itu, pada bagian dalam (medula) otak depan terdapat lapisan yang berwarna putih, karena mengandung dendrit dan akson. Korteks serebrum berkaitan dengan sinyal saraf ke dan dari berbagai bagian tubuh. Karenanya, pada korteks serebrum terdapat area sensorik yang menerima impuls dari reseptor pada indra. Di samping itu, bagian tersebut terdapat juga area motorik yang mengirimkan perintah pada efektor. Selain itu, terdapat terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motorik dan sensorik serta berperan dalam berbagai aktivitas misalnya berpikir, menyimpan ingatan, dan membuat keputusan. Otak depan manusia terbagi atas empat lobus (bagian), meliputi lobus frontalis (bagian depan), lobus temporalis (bagian samping), lobus oksipitalis (bagian belakang), dan lobus parietalis (bagian antara depan-belakang). Pada bagian kepala manusia, lobus frontalis berada pada bagian dahi; lobus temporalis berada pada bagian pelipis; lobus oksipitalis berada pada bagian belakang kepala; dan lobus parietalis berada pada bagian ubun-ubun. Hipotalamus merupakan bagian yang berfungsi mengatur suhu tubuh, selera makan, dan tingkah laku. Selain itu, hipotalamus juga mengontrol kelenjar pituitari, yakni kelenjar hormon yang berperan dalam mengontrol kelenjar-kelenjar homon lainya, seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenalin, dan pankreas. b) Otak Tengah (Mesenfalon) Otak tengah manusia berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan kolikulus inferior yang mengatur pendengaran. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. c) Otak Belakang (Rombesenfalon) Otak belakang manusia tersusun atas dua bagian utama yakni otak kecil (serebelum) dan medula oblongata. Serebelum adalah bagian yang berkerut di bagian belakang otak, dan terdiri atas dua. belahan yang berliku-liku sangat dalam. Fungsinya adalah sebagai pusat keseimbangan dalam tubuh, koordinasi motorik/gerakan otot, dan memantau kedudukan posisi tubuh. Adanya serebelum memungkinkan kita belajar gerakan yang terlatih dan saksama, seperti menulis atau bermain musik tanpa berpikir. Di antara kedua belahan serebelum terdapat suatu bagian yang berisi serabut saraf. Bagian tersebut dinamakan jembatan varol (pons varolii). Fungsinya ialah menghantarkan impuls dari bagian kiri dan kanan otak kecil. Selain itu, jembatan varol juga menghubungkan korteks otak besar dengan otak kecil, dan antara otak depan dengan sumsum tulang belakang. Batang otak merupakan bagian otak sebelah bawah yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Batang otak berfungsi mengontrol berbagai proses penting bagi kehidupan, seperti bernapas, denyut jantung, mencerna makanan, dan membuang kotoran. b. Sumsum Tulang Belakang Sumsum tulang belakang atau tali spinal merupakan tali putih kemilau berbentuk tabung dari dasar otak menuju ke tulang belakang. Pada irisan melintangnya, tampak ada dua bagian, yakni bagian luar yang berpenampakan putih dan bagian dalam yang berpenampakan abu-abu dengan berbentuk kupu-kupu. Bagian luar sumsum tulang belakang berwarna putih, karena tersusun oleh akson dan dendrit yang berselubung mielin. Sedangkan bagian dalamnya berwarna abu-abu, tersusun oleh badan sel yang tak berselubung mielin dari interneuron dan neuron motorik. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik; memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Mekanisme penghantaran impuls yang terjadi pada tulang belakang yakni sebagai berikut; rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar dorsal untuk diolah dan ditanggapi. Selanjutnya, impuls dibawa neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspons. 2) Sistem Saraf Tepi Sistem saraf tepi dinamakan pula sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan (impuls) menuju dan dari system saraf pusat. Karena itu, di dalamnya terdapat serabut saraf sensorik (saraf aferen) dan serabut saraf motorik (saraf eferen). Serabut saraf sensorik adalah sekumpulan neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf motorik berperan dalam menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor (otot dan kelenjar) untuk ditanggapi. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan, serta ganglia (tunggal: ganglion). Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Masing-masing saraf ini mempunyai karakteristik fungsi dan jumlah saraf yang berbeda. Sementara itu, ganglia merupakan kumpul an badan sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf dan di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tak sadar merupakan sekumpulan saraf yang mengatur aktivitas yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Misalnya saja, pergerakan paru-paru dan jantung. Kita tidak pernah berkehendak supaya aktivitas gerakan paru-paru dan jantung terjadi dengan koordinasi oleh sistem saraf pusat. Oleh karena itu, sistem saraf sadar disebut juga sistem saraf otonom. Organ yang beraktivitas dan dikontrol oleh sistem saraf sadar, meliputi kelenjar keringat, otot perut, pembuluh darah, dan alat-alat reproduksi. Menurut karakteristik kerjanya, sistem saraf sadar terbagi atas dua saraf, meliputi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Masing-masing saraf ini dapat bekerja pada organ yang sama, namun kerja yang dilakukan saling berlawanan (antagonis). Sebagai contoh, saat saraf simpatik memengaruhi sebuah organ untuk mening katkan aktivitas organ tertentu, justru saraf parasimpatik malah menurunkannya. Perbedaan ini terjadi karena neurotransmiter yang dihasilkan kedua saraf tersebut berbeda. Noradrenalian merupakan neurotransmiter saraf simpatik, sedangkan asetilkolin ialah neurotransmiter saraf parasimpatik. Pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor, yang dinamakan ganglion. Ganglion saraf simpatik berada dekat sumsum tulang belakang. Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglionnya berukuran panjang. Sebaliknya, saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang pendek. Perbedaan Sistem saraf dan Sistem endokrin Sistem saraf Dibentuk dari kumpulan sel neuron Sistem endokrin Dibentuk dari sekumpulan kelenjar rata-rata transmisi sinyal adalah Impuls Bahan kimia yang disebut hormon adalah elektrokimia sarana transmisi sinyal Transmisi sinyal cepat tetapi fungsi tidak Sinyal transmisi lambat, tetapi fungsi yang berkepanjangan tahan lama Sel-sel yang saling berhubungan dan Organ seluruh sistem tidak terhubung seluruh sistem secara kontinyu secara fisik namun mereka adalah diskrit Menggunakan neuron untuk mengirimkan Menggunakan sinyal sistem peredaran untuk mengirimkan sinyal darah BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi. Dia mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem endokrin dalam mengatur dan mempertahankan homeostasis (lingkungan internal tubuh kita) dengan mengontrol kelenjar endokrin utama (hipofisis) melalui hipotalamus otak. Melalui reseptornya, sistem saraf membuat kita berhubungan dengan lingkungan kita, baik eksternal dan internal. Seperti sistem lain dalam tubuh, sistem saraf terdiri dari organ, terutama otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan ganglia, yang pada gilirannya, terdiri dari berbagai jaringan, termasuk saraf, darah, dan jaringan ikat yang secara bersama melaksanakan kegiatan yang kompleks dari sistem saraf. DAFTAR PUSTAKA Subowo.1992 . Histologi Umum. Jakarta : Bumi Aksara Kimball, John W,1994. Biologi Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta. Syamsuri, I. 2004. Biologi. Penerbit Erlangga: Jakarta Raimundus Chalik, S.Si., M.Sc., A. (2016). Anatomi Fisiologi Manusia. Sherwood, Lauralee (2012).Fisiologi Manusia