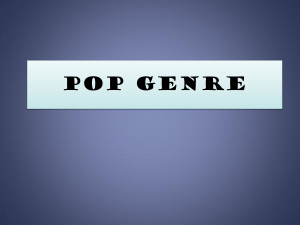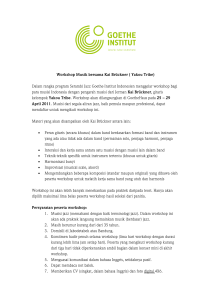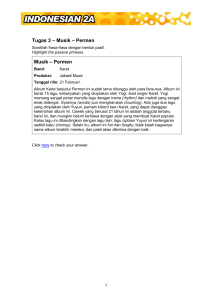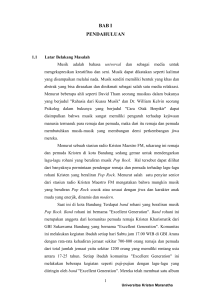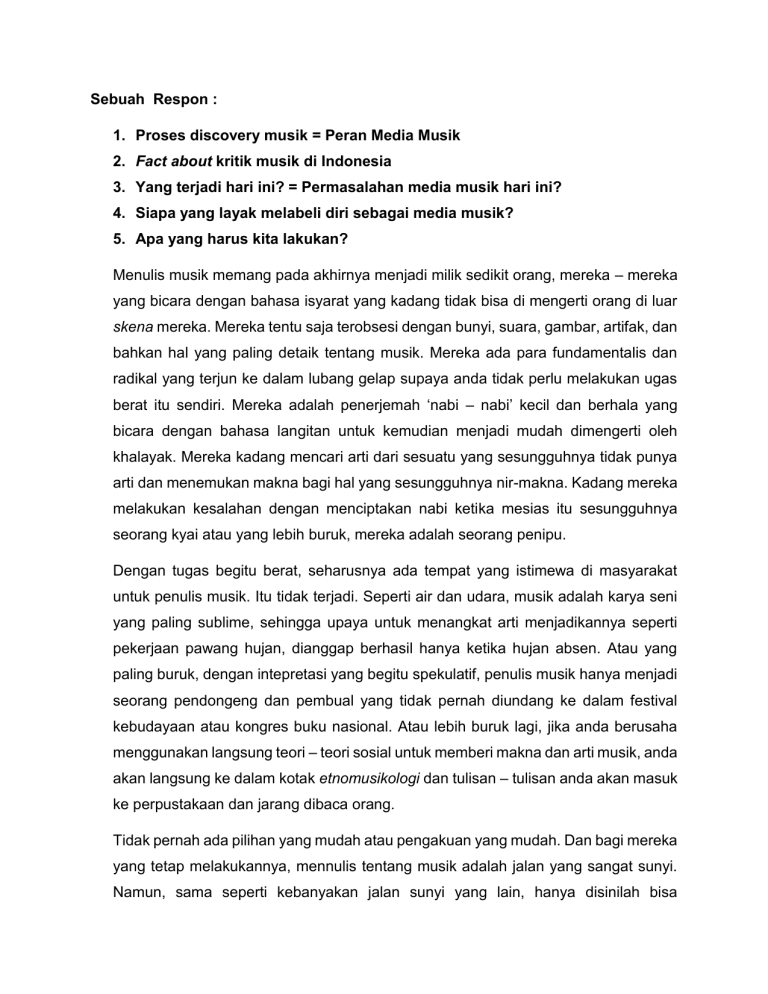
Sebuah Respon : 1. Proses discovery musik = Peran Media Musik 2. Fact about kritik musik di Indonesia 3. Yang terjadi hari ini? = Permasalahan media musik hari ini? 4. Siapa yang layak melabeli diri sebagai media musik? 5. Apa yang harus kita lakukan? Menulis musik memang pada akhirnya menjadi milik sedikit orang, mereka – mereka yang bicara dengan bahasa isyarat yang kadang tidak bisa di mengerti orang di luar skena mereka. Mereka tentu saja terobsesi dengan bunyi, suara, gambar, artifak, dan bahkan hal yang paling detaik tentang musik. Mereka ada para fundamentalis dan radikal yang terjun ke dalam lubang gelap supaya anda tidak perlu melakukan ugas berat itu sendiri. Mereka adalah penerjemah ‘nabi – nabi’ kecil dan berhala yang bicara dengan bahasa langitan untuk kemudian menjadi mudah dimengerti oleh khalayak. Mereka kadang mencari arti dari sesuatu yang sesungguhnya tidak punya arti dan menemukan makna bagi hal yang sesungguhnya nir-makna. Kadang mereka melakukan kesalahan dengan menciptakan nabi ketika mesias itu sesungguhnya seorang kyai atau yang lebih buruk, mereka adalah seorang penipu. Dengan tugas begitu berat, seharusnya ada tempat yang istimewa di masyarakat untuk penulis musik. Itu tidak terjadi. Seperti air dan udara, musik adalah karya seni yang paling sublime, sehingga upaya untuk menangkat arti menjadikannya seperti pekerjaan pawang hujan, dianggap berhasil hanya ketika hujan absen. Atau yang paling buruk, dengan intepretasi yang begitu spekulatif, penulis musik hanya menjadi seorang pendongeng dan pembual yang tidak pernah diundang ke dalam festival kebudayaan atau kongres buku nasional. Atau lebih buruk lagi, jika anda berusaha menggunakan langsung teori – teori sosial untuk memberi makna dan arti musik, anda akan langsung ke dalam kotak etnomusikologi dan tulisan – tulisan anda akan masuk ke perpustakaan dan jarang dibaca orang. Tidak pernah ada pilihan yang mudah atau pengakuan yang mudah. Dan bagi mereka yang tetap melakukannya, mennulis tentang musik adalah jalan yang sangat sunyi. Namun, sama seperti kebanyakan jalan sunyi yang lain, hanya disinilah bisa ditemukan makna. Dan seperti yang para pecinta musik ketahui, musik akan terasa kosong tanpa upaya pencarian makna yang lebih dalam di balik semua ‘sound and fury tha could signify nothing…or something’. Mereka inilah yang membuat musik dan kehidupan memiliki arti, sebab tidak ada yang lebih berbahaya dibandingkan kehidupan tanpa makna. Rolling Stone Indonesia Salah satu majalah waralaba fenomenal lainnya adalah rolling stone indonesia. para pecinta musik mana yang tidak mengenal yang satu ni? Di negeri asalanya, rolling stone boleh dikatakan meruapakantonggak jurnalisme musik. Majalah ini menjadi media yang banyak menyoroti perubahan industri musik sejak pertengahan 1970-an. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang menghadirkan Rolling Stone. Roling Stone Indonesia yang pertama kali terbit pada Mei 2005 dengan gambar sampul Bob Marley diharapkan membawa pengaruh dan refrensi penting bagi industri musik Indonesia. Selain di Indonesia, Rolling Stone di Asia hanya terbit di Jepang (2007), India (2008), dan Cina (2006) –yang berhenti terbit dalam waktu setahun. Ulasan – ulasan yang dimuat Rolling Stone panjang dan memikat. Rolling Stone seperti menjadi panduan dalam mengarungi industri musik. Tulisannya memang tak jauh dari ulasan abum, ulasan konser, wawancara, hingga feature profil band/musisi, terutama musisi yang menjadi cover story, tetapi muatannya bolej diakatan seimbang antara saduran berita musik dari luar negeri dan tulisan – tulisan perihal kondisi industri musik dalam negeri. Rubruk Rolling Stone yang menarik adalah ‘music biz’ asuhan Wendi Putranto, yang banyak menyajikan tulisan –tulisan pentingmengenai kondisi industri musik. Rubric ini dibuat karena banyak musisi yang tak mengerti tentang pola kerja industri musik. Rubrik ‘music biz’ mengulas mulai dari fungsi – fungsi label rekaman, manajemenband, hingga persoalan paling penting yaitu hak cipta. Pada tahun 2009, rubric ini dibukukan dengan judul sama, music biz, dan menjadi satu buku uth yang menjadi panduan penting untuk mengarungi industri musik. Selain ‘music biz’, salah satu rubirk menarik lainnya adalah ‘soundwaves’ yang menyajikan opini segar dari para pelaku industri musik. Jika selama ini para musisi ini hanya menjadi objek tulisan jurnalis musik, maka dalam kolomo ini para musisi bisa mencurahkan opini dan kerisauannya tentang industri musik di Indonesia. Gagasan – gagasan para musisi ini sangat menarik diperhatikan karena mereka pelaku yang terjun langsung di industri. Salah satu tulisan yang menarik ditulis oleh musisi dan aktivis Kartika Jahja tentang buruknya jurnalisme musik di Indonesia. Pada Desember 2007, Rolling Stone Indonesia menerbitkan edisi paling penting yaitu ulasan tentang ‘150 Album Indonesia Terbaik’. Pada edisi khusus tersebut, Rolling Stone Indonesia memberikan ruang apresiasi pada album – album legendaris sepanjang sejarah industri musik indonesia –dan menempatkan album lagu pengisi film badai pasti berlalu di urutan pertama. Album itu memang merupakan bagian penting dalam lanskap musik pop Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya desember 2009, Rolling Stone Indoensia juga membuat edisi khusus ‘150 Lagu Indonesia Terbaik’ Lagu ‘Bongkar’ milik supergroup ‘Swami’ didapuk menempati urutan pertama karena kritis dan berani di tengah represif Orde Baru. Hai, Trax, dan Rolling Stone Indonesia memberikan pengaruh sangat penting bagi perkembangan jurnalisme musik di Indoensia setelah reformasi. Boleh dikatakan ketiga media inilah yang memotret perkembangan industri musik di Indonesia, meskipun tulisan – tulisan di dalamnya masih membahas musik mainstream atau musik – musik industri. Lekatnya media musik dan industri musik makin menjadi pada era ini karena industri musik membutuhkan media promosi yang besar untuk ‘jualan’. Selain kemunculan media – media waralaba, periode pasca reformasi juga ditandai dengan maraknya penerbitan media – media alternatif. Pada pertengahan 1990-an, cikal bakal media alternative memang sudah muncul melalui maraknya penerbitan zine. Media jenis ini berkembang hanya pada lingkup komunitas dan tidak terlalu bergantung kepada industri pers. Pencabutan permnpen No. 1 Tahun 1984 tentang SIUPP di era pasca reformasi memberikan angina segar kepada siapapun yang ingin terjun ke industri media. Hal ini juga memudahkan komunitas untuk membuat media – media musik alternatif, yang coraknya tentu berbeda dan lebih berani untuk melawan industri musik mainstream. Poros informasi pun tak hanya berada di pusat (baca : Jakarta). Di beberapa kota besar muncul majalah – majalah musik alternatif. Sebut saja Riple Magazine dan Trolley Magazine yang berbasis di Bandung. Ada pula Dab magazine dan Out Magazine di Yogyakarta. Sementara di Semarang ada Mosh Magazine, dan ada Common Ground yang lahir di Malang. Selain majalah cetak, banyak pula bermunculan blog dan webzine yang tak terhitung lagi maraknya. Kehadiran media – media alternative seperti ini merupakan ekspresi ideologis karena konten – kontennya lebih banyak mengangkat musik independent dan menolak musik pasar. Kehadiran media – media alternatif ini seiring dengan perkembangan komunitas independen dengan budaya fanzine yang banyak mengangkat isu – isu identitas dan komunitas (docmbe, 1997) Sayangnya, keberadaan media – media alternatif ini juga tidak bertahan lama. beberapa media terpaksa gulung tikar dengan berbagai alasan, terutama alasan yang klise dan sangat mendasar : manajemen dan finansisal. Trolley t erpaksa bubar di edisi ke-11. Salah satu yang paling lama berahan mungkin hanya ripple magazine yang bertahan selama sepuluh tahun. Nasib sama juga menimpa media besar semacam Trax, Hai, dan Rolling Stone Indonesia. Trax memilih bubar pada 2016, kemudian Hai yang lebih memilih fokus di ranah digital dan menutup versi cetaknya. Yang paling mengejutkan, pada penghujung tahun 2017, Roling Stone Indonesia menyatakan diri untuk bubar. Bagaimana masa depan media musik? Kehadiran internet dan perkembangan media sosial memiliki pengaruh cukup besar dalam praktik jurnalisme musik di Indonesia. kini media – media tak hanya ditemukan dalam bentuk majalah. Media musik kini juga banyak ditemui melalui format blog, web magazine (webzine), radio streaming, dan video. Selain mendorong perkembangan format karya jurnalistik musik, kehadiran internet juga memberikan akses kepada semua orang untuk menjadi jurnalis musik. Kini orang tidak perlu bergabung dengan suatuu institusi persuntuk menulis dan meliput acara musik. Arus perkembangan jurnalisme musikpun kini lebih bervariasi. Beberapa media mainstream masih mengedepankan musik – musik pasar. Ada juga beberapa media daring alternative yang masih konsisten menawarkan musik – musk di luar pasar industri musik. Kehadiran berbagai media daring alternatif dan bloger – bloger musik memicu gairah baru bagi jurnalisme musik. Para penulis musik di webzine biasanya ‘non-jurnalis’ ini seolah mengembalikan keautentikan penulisan musik oleh orang – orang yang memang antusias dan memiliki renjana (passion) terhadap musik Kehadiran – kehadiran webzine menjadi oase di tengah kekeringan informasi mengenai musik, terutama musik – musik di luar arus utama. Media – media seperti deathrockstar, Jakarta Beat, Wasted Rock, dan Gigsplay adalah diantaranya. Sayangnya, media – media seperti ini, utamanya di Indonesia, sering kali masih di gerakan oleh manajemen yang belum professional dan belum stabil secara finansial. Tantangan terberat bagi media – media musik daring alternatif ini adalah persaingan ntuk memperoleh pendapatan dari iklan. Jangankan untuk memperoleh laba, bisa bertahan saja masih syukur, padahal pencapaian webzine semisal steregum atau pitchfork di Amerika merupakan contoh sukses webzine yang digermari dan dibaca oleh pecinta musik dan berhasil bertahan lama. Namun, perlu ditekankan bahwa keberadaan media – media musik daring alternatif ini adalah sebagai manifestasi demokrasi media. Media – media musik tumbuh dengan jenis yang makin beragam. Perkembangannya juga tak hanya di pusar – pusat industri seperti Bandung atau Jakarta saja, tapi hingga ke luar dua kota tersebut. Seperti yang sudah diuraikan di atas, jikalau dikatakan jurnalisme musik di Indonesia itu mati, sebenarnya tidak juga. Jurnalisme musik dalam pengertian menulis dan memberikan informasi mengenai musik dan peristiwa di sekitarnya masih hadir menemani keseharian kita. Prinsip konvergensi rasanya dapat membuat media musik mampu mengawinkkan antara jurnalisme musik dengan teknologi media. Informasi – informasi musik tak hanya ditemui dalam format cetak, tetapi dalam jejaring media sosial. Setelah banyak media – media musik mainstream yang berguguran dan kian demokratisnya teknologi internet, seperti apa masa depan jurnalisme musik di Indonesia? Anomali Media Musik Kita bisa memulai ulasan ini dengan fakta, bahwa ‘Menari Dengan Bayangan’ merupakan sebuah album yang ‘kompleks’ nyaris sempurna namun penuh tanda tanya. Kawan saya Fadil lebih senang mendengarkan omong kosong dosen pembimbing-nya, daripada harus mendengarkan album itu. Bagi sebagian orang, kecuali Fadil, album ini menjadi album paling sentimentil, penuh digdaya, menjadi selfreminder, bahkan menjadi bahan untuk menulis caption. Luar biasa hebat bukan? Tak ada gading yang tak retak, Tirto.id menulis ulasan penuh album Hindia, tepat satu hari setelah showcase Hindia di mBloc Space Jakarta, Album baru Hindia : Kemasan bagus, musiknya payah. Kita semua merasa ‘tertampar’ Raka Ibrahim meracau, FelixDass yang juga menghadiri ‘intimate concert’ pun demikian, sebagian lagi tetap berada di poros tengah, karena memang tidak ada alasan yang kuat untuk menjadi bagian itu. Baskara masih tetap santai, walaupun pada akhirnya ‘ndak apa – apa lah, bebas, namanya juga musik, dan jangan jadi pendengar yang kebakaran jenggot’, dan kenyataannya, Hindia / Baskara tetap jadi juara, toh, sebagian orang mengamini ‘Menari Dengan Bayangan’ menjadi sebagai album yang paling estoterik. Lagipula, bagaimana bisa mencari cela di album yang nyaris sempurna? Mungkin ada di kata ‘nyaris’. Terus, bagaimana ulasan ini mempengaruhi selera pasar? Perdebatan panjang ini bisa jadi tidak akan selesai, penting dan tidak penting, peduli dan tidak peduli, bermakna atau tidak selalu jadi pilihan. Terjadi banyak peralihan dalam peran media musik, meskipun pada akhirnya kita selalu terjebak dalam pertanyaan yang sama, ‘bagaimana media musik memberikan impact dalam industri musik?’ Media Musik Kita atau siapapun anda yang memahami ini mungkin merasa kehilangan ketika Jakartabeat atau Rolling Stones Indonesia harus berdiri dari lingkaran, secara bersamaan kita sangat merindukan kedua media tersebut. Mereka bagaikan mercusuar yang terus mencari apa yang seharusnya dicari, dan menenggelamkan apa yang seharusnya di tenggelamkan. Tidak ada pamer diksi, sedikit trivia, dan yang pastinya mereka adalah racun. Selanjutnya, kita menemukan Pop Hari Ini, DCDC, Jurnal Ruang –belakangan juga hilang dan mungkin beberapa media lain yang melihat musik tidak hanya nada dan suara, dan yang lebih hebat, gairah akan zine kolektif dalam ekosistem mulai menemui arwah-nya, ruang skena daerah, Semarang, Jogja, Malang, dan kota – kota lainnya sadar akan publikasi yang epic atas ekosistem. Setidaknya, ada arus alternatif didalam arus alternatif, Hebat! Walaupun pada era ini sudah terjadi bias antara kuping kanan dan kuping kiri, Selayaknya, media musik masih menjadi pelumas yang paling organik dalam proses discovery dan dokumentasi musik. Review album, event report, esai personal, profil musisi, skena musik, hingga kritik budaya menjadi point of view dalam menulis musik. Tidak terelakan, bahwa media musik dulu dan sekarang seharusnya mempunyai tanggung jawab dalam membentuk selera pasar yang begitu ‘liar’, atau mungkin kata ‘membentuk’ diganti dengan ‘menjembatani’(?). Pada kenyataannya, proses discovery dari musisi ke audience, sudah sepenuhnya di pegang oleh audience. Kenyataan ini mungkin bisa diliat dari bagaimana pelaku band dalam hal ini musican dalam meng-utilace sebuah konten di social media masing masing, dan ini juga yang membawa kita kedalam argumen ‘oh iya yang bikin acara juga kan audience’ ‘yang melakukan eksposure ini juga audience’ dan ‘yang mempunyai capital juga audience kok’. Sebagian setuju dengan hal tersebut, dan sebagian lagi menganggap ini nol besar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika case nya adalah musisi medioker yang mempunyai kualitas oke (Baca : meskipun subjektif), namun terhambat dalam proses discovery? Jawabannya adalah media musik dan semua hal yang menjadi lanskap media musik tersebut, seperti zine (majalah), webzine, instazine, event publisher, dan apapun yang masih berkelindan dengan media dan musik, kenapa? Iya media musik dan hal di dalamnya, bisa menjadi pengantar yang elegant sebagai steping stone perjalanan sebuah band/musisi, mutlak tidak bisa diperdebatkan. Selanjutnya adalah konser, karena proses discovery yang paling agung terjadi disini. Tapi seberapa besar hal ini memberikan impact kepada band/musisi, jelas ini masih bergantung seberapa kuat media musik tersebut dalam menggaet pasar. Setelah kehilangan beberapa media musik yang cukup berpengaruh di Indonesia, dan juga perkembangan dunia digital yang semakin luas dan tidak terbatas, banyak terjadi pergesaran antara peran media musik, musisi/band, dan juga publikasi musik. Hari ini mungkin beberapa musisi/band sadar betul bahwa ia tidak bisa berharap kepada media – media konvesial dan mempunyai banyak pengikut lagi perihal publikasi. Proses kurasi yang cukup ketat, dan selera pasar bisa menjadi alasan utama mengapa musisi/band sebisa mungkin memanfaatkan konten sosial media sendiri sebagai kolam yang pas untuk menarik audience. Kesadaran musisi/band terkait publikasi musik akan membawa kita kedalam argumentasi ‘oh yaudah saya sebagai musisi/band bagaimana caranya untuk mem-present konten saya sendiri, dan bagaimana cara meng-utilace sosial media menjadi bagian penting dalam proses discovery ini’. Argumentasi ini memang tidak sepenuhnya benar, tapi saya percaya bahwa, saat ini sosial media menjadi gerbang yang paling kongkrit audience dan musisi/band untuk bertemu. Seberapa penting media musik dalam proses dicovery musik terhadap audience, dan juga pertumbuhan ekosistem di dalamnya mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa diukur secara matematis. Posisi sekarang, dalam upaya pencarian musik baru, audience atau saya -as a listener- romannya engga perlu bersusah payah membaca ulasan album Naif yang di review panjang lebar oleh Harlan boer di Pop Hari Ini. Tahapan pertama adalah saya mendengarkan albumnya dahulu via streaming dan tahapannya selanjutnya adalah Like or Dislike, selesai. Toh jika memang ‘gak pas di kuping’ kemudian saya membaca ulasan album-nya di media manapun engga akan merubah keputusan saya. Dan sebaliknya, saya tidak akan pernah peduli omong kosong jurnalis musik yang membawa ‘senapan’ dalam mengulas suatu album. Persetan dengan itu, saya tetap suka Baskara/Hindia/Wordfangs (tidak dengan .Feast). Tapi ketika saya –as a worshiper- dengan segala bentuk snobisme yang aduhay. Meskipun saya sudah mempunyai platform streaming premium kecenderungan membeli fisik, pasti ada. Mengulik lebih dalam tentang seluk beluk sebuah karya, pasti selalu ada. Mencari refrensi alur genre yang sesuai, pasti akan terus berjalan. Merindukan media musik yang kredibel, ya pasti. Mengulas dan mencari ‘cela’ dalam album yang nyaris sempurna, ya mesti! Edan pooo! Karena pada hakikat-nya, mereka yang mengulas album yang penuh kritik, penuh tumpahan darah dan pastinya sarat dengan subjektifitas adalah mereka yang paling sering mendengarkan album itu, atau setidaknya ada ekspetasi yang tidak tercapai terhadap album itu. benar begitu baginda? Secara umum, media musik hari ini terlihat sangat klise, ia seperti hantu terkadang ada tapi tidak terasa, namun ketika ia muncul, malah menjadi momok yang paling menakutkan, menyeramkan sekaligus bikin penasaran. Karena pada kenyataanya, hari ini dan seterusnya, proses discovery sepenuhnya di tentukan oleh audience, interaksi antara audience dan musisi/band tidak lagi memerlukan tangan ketiga. Sedapp! Jadi, siapakah yang seharusnya disambut pertama kali dalam sebuah pertunjukan, media atau audience? Kita membahas Tapi gapapa, Baskara tidak pernah berfikir kehilangan 1 pendengar dari jutaan peneToh, Baskara tahu betul bagaimana proses packaging yang epic, tahapan yang kadang kali menuai pujian atau makian, ya begitu lah Bas.