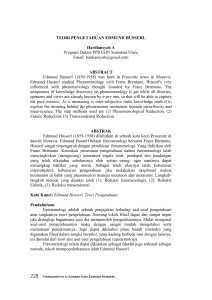Uploaded by
common.user42159
Epistemologi Fenomenologi Edmund Husserl: Konsep Kunci & Reduksi
advertisement

MAKALAH FILSAFAT Diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Dosen Pengampu : Gandung Joko Srimoko, M.Sn Disusun Oleh : Clara Riva 2815161999 Dwi Annisa Navila 2815161450 Shofia R.P 2815163233 Zulvia Alamanda 2815161598 JURUSAN PENDIDIKAN SENI MUSIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020 C. Epistemologi Fenomenologi Edmund Husserl Ketika kita hendak mengeksplorasi epistemologi fenomenologi Edmund husserl, kiranya sangat krusial bila kita memahami istilah-istilah kunci yang digunakan Husserl. Istilah-istilah kunci tersebut mencakup fenomena, kesadaran, intensionalitas, konstitusi, redaksi dan epoche. Istilah-istilah ini menjadi konsepkonsep inti yang saling terkait satu sama lain untuk tiba pada pemahaman epistemologi fenomenologi secara tepat. 1. Konsep-konsep Kunci Fenomenologi Husserl memulai analisis fenomenologinya dengan menggunakan konsep kesadaran atau intuisi langsung. Bagi Husserl, “prinsip segala prinsip” ialah bahwa hanya intuisi langsung dengan tidak menggunakan pengantara apapun juga dipakai sebagai kriterium terakhir di bidang filsafat. Hanya apa yang secara langsung diberikan kepada kita dalam pengalaman dapat dianggap benar dan dapat dianggap salah sejauh diberikan. Dari situ Husserl menyimpulkan bahwa kesadaran harus menjadi dasar filsafat. Alasannya ialah bahwa kesadaran secara langsung diberikan kepada saya selaku subjek. Sebagaimana sudah tersirat dalam namanya, fenomenologi mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri atau fenomena. Tetapi istilah fenomena yang digunakan Husserl memiliki makna yang sama sekali baru dan berbeda dengan fenomena yang digunakan Immanuel Kant sebelumnya. Menurut Kant, ktia sebagai manusia hanya mampu mengenal fenomena-fenomena, bukan hakikat realitas itu sendiri. Bagi Kant, yang tampak bagi kita ialah semacam tirai yang menyelubungi realitas di belakangnya. Kita hanya mengenal pengalaman batin kita sendiri yang diakibatkan oleh realitas di luar yang tetap tinggal suatu x yang tidak kita kenal. Melihat warna merah, misalnya, tak lain tak bukan adalah pencerapan yang diakibatkan oleh sesuatu di luar. Bagi Kant, fenomena adalah sesuatu yang menunjuk kepada realitas, yang tidak dikenal pada dirinya. Dalam perspektif ini, kesadaran dianggap tertutup dan terisolir dari realitas. Sedangkan dalam paradigma Husserl, fenomena adalah sesuatu yang sama sekali lain; fenomena adalah realitas itu sendiri yang tampak. Bagi Husserl, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan kita dari realitas; realitas itu sendiri tampak bagi kita. Dengan demikian, dapat kita mengerti semboyan yang dipilih Husserl bagi filsafatnya, yaitu kembalilah pada benda-benda sendiri. Dengan pandangan tentang fenomena ini Husserl mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Dalam filsafat Barat sejak Descartes, kesadaran selalu dimengerti sebagai kesadaran tertutup atau cogito tertutup; artinya, kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu mengenal realitas. Misalnya, saya mengenal pencerapan-pencerapan saya dan melalui jalan itu saya mengenal realitas. Husserl berpendapat bahwa kesadaran selalu berarti kesadaran akan… sesuatu. Atau menurut istilah yang dipakai Husserl, kesadaran menurut kodratnya berfilsafat intensional; intensionalitas adalah struktur hakiki kesadaran. Dan justru karena kesadaran ditandai oleh intensionalitas, fenomena harus dimengerti sebagai apa yang menampakkan diri. Mengatakan “kesadaran bersifat intensional” sebetulnya sama artinya dengan mengatakan “realitas menampakkan diri”. Dua ucapan ini seakan merupakan dua sisi dair uang logam yang sama. Intensionalitas dan fenomena adalah korelatif. Korelasi ini berlaku bagi kesadaran dan realitas pada umumnya, tetapi juga bagi berbagai aktus kesadaran dan berbagai bentuk realitas, misalnya, pengalaman estetis-objek estetis (karya kesenian). Kemudian istilah lain yang sering dipakai oleh Hasserl adalah konstitusi. Dengan konstitusi dimaksudkan proses tampaknya fenomenafenomena kepada kesadaran. Fenomena-fenomena mengonstitusi diri dalam kesadaran, kata Husserl. Dan karena adanya korelasi antara kesadaran dan realitas yang disebut tadi, dapat dikatakan juga bahwa konstitusi adalah aktivitas kesadaran yang memungkinkan tampaknya realitas. Husserl mengatakan bahwa dunia real dikonstitusi oleh kesadaran. Hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kesadaran mengadakan atau menyebabkan dunia beserta perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya, melainkan hanya bahwa kesadaran harus hadir pada dunia agar penampakkan dunia dapat berlangsung. Tidak ada kebenaran-pada-dirinya, lepas dari kesadaran. Kesadaran hanya mungkin dalam korelasi dengan kesadaran. Dan karena yang disebut “realitas” itu tidak lain dari dunia sejauh dianggap benar, maka realitas harus dikonstitusi oleh kesadaran. Konstitusi ini berlangsung dalam proses penampakkan yang dialami oleh dunia ketika menjadi fenomena bagi kesadaran intensional. Untuk sekadar menjelaskan maksud Husserl engan konstitusi (terutama konstitusi aktif atau konstitusi sebagai aktus kesadaran), kita dapat memandang sebentar proses persepsi. Saya melihat suatu gunung, umpamanya. Tetapi sebetulnya yang saya lihat selalu perspektif dair gunung: saya melihat gunung itu dari sebelah timur atau utara atau dari atas, dan seterusnya. Tetapi bagi persepsi, gunung adalah sebuah sintesis semua perspektif itu. Dalam persepsi, objek telah dikonstitusi. Tetapi hal yang sejenis berlaku untuk setiap aktus kesadaran, juga untuk aktus-aktus intelektual. Misalnya, saya memikirkan “dalil Phythagoras”. Hal itu dapat saya ulangi terus-menerus dan setiap kali saya memandang “dalil Phythagoras” yang sama. Hal itu hanya mungkin karena suatu konstitusi oleh kesadaran. Terakhir, konsep kunci yang sangat signifikan dalam konsep fenomenologi Husserl adalah reduksi fenomenologis, atau reduksi transcendental yang juga menggunakan aplikasi praktis epoche, sebuah metode penundaan atau penyaringan. Lalu apakah yang dimaksud dengan reduksi? Secara sederhana, untuk memahami reduksi Husserl, ktia berangkat dari pengamatan yang sering kali kita lakukan. Dalam pengamatan kita seharihari, kita merasa berhubungan langsung dengan realitas yang tampak di hadapan kita secara secara dangkal atau di level permukaan saja. Ketika kita melihat, mendengar, menyentuh, dan menangkap realitas kehidupan seharihari, kita segera mengakui bahwa semua kenyataan tersebut bersifat objektif: apapun yang kita candra melalui pancaindra kita, begitu pulakeadaan realitas itu sebenarnya. Sudut pandang inilah yang disebut Husserl sebagai sudut pandang awam atau pendirian biasa. Bagi Husserl, natural standpoint yang biasa kita gunakan dalam pengamatan hidup sehari-hari itu belum cukup. Penglihatan itu masih diselimuti kabut yang menutupi hakikat realitas. Kabut-kabut yang menghalangi kita dalam menangkap hakikat dunia eksternal itu adalah konsepsi-konsepsi kita, endapan-endapan kultur dimana kita hidup, cara-cara kita berpikir, dan semua suasana hidup yang sudah menjadi prasangka dalam diri kita. Kabut-kabut perspektif inilah yang menjadikan pengamatan kita terhadap realitas menjadi subjektif sifatnya, tidak lagi objektif. Dengan apa kita dapat menangkap realitas objektif secara esensial? Husserl menjawab dengan jalan reduksi yakni penangguhan sejenak terhadap segala pengetahuan yang telah kita peroleh sebelum kita melakukan pengamatan intuitif. Pencandraan awal kita bersama dengan asumsi-asumsi yang kita bawa, hanya menjadi first look, tilikan pertama yang belum mampu menyingkap selubung yang membaluti hakikat realitas yang sebenarnya. Karena itulah, diperlukan second look, tilikan kedua dengan melakukan pengamatan intuitif agar hakikat dunia eksternal menampilkan wujudnya secara murni sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Ketika kita mnggunakan metode reduksi tersebut, maka Husserl mengklaim bahwa kita telah mengaplikasikan sebuah sudut pandang fenomenologis, the phenomenological stance. Sebagaimana telah dikehendaki Husserl sejak awal, dengan metode reduksi ini ia mendambakan fenomenologi menjadi suatu ilmu yang rigorus. Ucapan-ucapan yang dikemukakan dalam suatu ilmu rigorus harus bersifat apodiktis (tidak mengizinkan keraguan) dan absolut. Kriteria rigorus itu tidak pernah dapat dipenuhi dalam ucapan-ucapan kita tentang dunia real. Setiap benda material selalu diebrikan melalui profil-profil (Abschattungen). Misalnya saja, dari meja yang beridri di depan saya, saya hanya melihat permukaan dan sebelah depan saja; saya tidak melihat sebelah belakang. Tentu saja, saya bisa memilih sudut lain, sehingga kita melihat sebelah belakang itu. Tetai, kalua begitu, saya tidak melihat lagi sebelah depan dan profil-profil lain. Inilah cara benda material tampak bagi saya: berkeluasan dalam ruang. Suatu benda material tidak pernah diberikan kepada saya menurut segala profilnya, secara total dan absolut. Cara realitas material tampaknya bagia saya bersifat demikian rupa, sehingga tidak dapat dikemukakan pernyataan-pernyataan apodiktis dan absolut tentangnya. Karena alas an-alasan itu fenomenologi sebagai ilmu rigorus harus mulai dengan mempraktikkan reduksi transcendental. Jika kita menempatkan realitas material antara tanda kurung dengan mempraktikkan reduksi transcendental tersebut, apakah yang tinggal untuk mendasari fenomenologi sebagai ilmu rigorus? Ataukah kita harus meninggalkan saja seluruh usaha kita? Husserl berpendapat bahwa yang tinggal adalah kesadaran atau subjektivitas. Kesadaran tidak berkeluasan dalam ruang. Kesadaran tampak bagi saya secara total dan langsung. Karena itu menjadi mungkin mengemukakan pernyataan-pernyataan apodiktis dan absolut tentangnya. Adanya kesadaran juga struktur kesadaran dapat dinyatakan secara absolut. Jadi, kesadaran harus dipilih sebagai dasar bagi fenomenologi sebagai ilmu rigorus. Tetapi, kalua begitu, apa yang terjadi dengan dunia real? Apakah itu berarti bahwa fenomenologi sama sekali tidak dapat berbicara tentang dunia? Tidak. Janganlah ktia lupa apa yang sudah dikatakan tentang intensionalitas kesadaran yang begitu dipentingkan Husserl. Kita tidak berbicara lagi tentang dunia dengan cara naif, seakan-akan dunia sama sekali tidak berkaitan dengan kesadaran, seperti dibuat dalam sikap natural. Tetapi dalam sikap fenomenologis kita menemui dunia sebagai korelat bagi kesadaran, dunia sebagai fenomena. Demikianlah fenomenologi dapat mempelajari dunia dan merumuskan ucapan-ucapan apodiktis dan absolut tentangnya. Dunia dapat diberi tempat dalam fenomenologi sebagai ilmu rigorus. Dalam fenomenologi kita tidak bertolak belakang dengan dunia; sebaliknya, realitas material ditemui dalam suatu perspektif baru, yaitu sebagai korelat bagi kesadaran. 2. Tiga Tahapan Reduksi Pertama, reduksi fenomenologis. Reduksi feomenologis ditempuh dengan menyisihkan atau menyaring pengalaman pengamatan pertama yang terarah kepada eksistensi fenomena. Pengalaman indrawi itu tidak ditolak, tetapi perlu disisihkan dan disaring lebih dahulu sehingga tersingkirlah segala prasangka, praanggapan, dan prateori, baik yang berdasarkan keyakinan tradisional, maupun yang berdasarkan keyakinan agamis, bahwa seluruh keyakinan dan pandangan yang telah dimiliki sebelumnya. Segala sesuatu yang diketahui dan dipahami, lewat pengamatan biasa terhadap fenomena itu, harus diuji sedemikian rupa dan tidak boleh diterima begitu fenomena itu, harus diuji sedemikian rup dan tidak boleh diterima begitu saja. Fenomena itu diamati dalam hubungannya dengan kesadaran tanpa melakukan refleksi terhadap fakta-akta yang diemukan lewat pengamatan itu karena yang utama dalam hidup ini ialah menemukan dan menyingkirkan subjektivitas- subjektivitas yang merupakan penghambat bagi fenomena itu dalam mengungkapkan hakikat dirinya. Kalau kita analogikan dengan figure manusia, pada tahap pertama, dengan reduksi fenomenologis, kita mulai membersihkan perspektif diri kita dari segala subjektivitas yang telah menggelayuti benak kita terhadap sosok manusia. Semua bentuk subjektivitas perspektif kita yang berasal dari pandangan filsafat, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, sains, bahkan agama mesti kita tunda terlebih dulu dalam menilai sosok manusia. Kalau kita melihat mausia dari perspektif ilmu mantiq atau logika, kita membingkai seorang manusia dengan istilah animale rationale sebagai makhluk yang berpikir (dalam istilah ilmu kalam disebut hayawanan nathiq). Bila kita memandang manusia dari kaca mata filsafat, kita memotret manusia sebagai homo sapiens; sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang mempunyai budi pekerti. Sedangkan bila kita menilik manusia dari sudut pandang ilmu semiotika atau ilmu tanda, para filsuf bahasa menamakan manusia sebagai animal symbolicum: makhluk yang hanya dengan menggunakan lambing-lambanglah ia dapat mencapai potensi dan tujuan tertinggi kehidupannya, atau homo semioticus: sebagai makhluk yang hidup dengan tanda-tanda yang memerlukan penafsiran. Bahkan, dalam wacana filsafat juga, manusia disebut sebagai homo iudens yakni makhluk yang bermain, sebab manusia juga sangat menyukai permainan dan itulah alasannya mengapa tercipta beragam bentuk permainan yang hingga saat ini masih terus berkembang. Namun sosok manusia menghasilkan konsep yang berbeda pula kalau dipotret melalui kajian filsafat agama atau spiritualitas: manusia menjelma homo religious: makhluk yang beragama; makhluk yang senantiasa dahaga akan makna (as meaning-seeking creatures). ;atau spiritual animal being: makhluk spiritual yang selalu memiliki kerinduan ontologies untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, Dzat Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa sekaligus Maha Paripurna. Meskipun demikian, manusia juga bisa menjadi homo economicus: manusia yang mengetahui prinsip-prinsip ekonomi jika dilihat dari ilmu ekonomi; menjadi homo faber: makhluk yang pandai membuat perkakas jika dilihat dari ilmu budaya; menjadi homo socius: manusia yang hidup berkelompok dalam masyarakat jika dilihat dari perspektif ilmu sosiologi. Dan menjadi zoon politikon makhluk yang hidup dalam polis, atau makhluk sosial, makhluk yang pandai bekerja sama dalam kehidupan politik bila ditilik dari perspektif wacana politik. Demikian seterusnya, di mana setiap sudut pandang tentang manusia akan menghasilkan label-label spesifik yang menggambarkan masing-masing aktivitas manusia secara unik. Namun, pertanyaan yang mengganggu benak kita ialah apakah semua konstruksi yang dibangun oleh semua pemikiran diatas sudah melukiskan hakikat kodrat manusia secara holistic? Pandangan manakah dari semua perspektid diatas yang paling benar dalam melukiskan kodrat manusia? Tentu saja masing-masing pandangan di atas memiliki kebenarannya masing-masing secara perspektivistik. Artinya, ketika figure manusia disoroti eksistensinya dari sebuah sudut pandang yang spesifik, maka akan menghasilkan gambaran tentang manusia yang sesuai dengan sudut pandang tersebut secara spesifik pula. Ada kebenaran dalam pandangan spesifik itu tentang manusia. Setiap sudut pandang di atas menyuguhkan kebenarannya masing-masing sesuai dengan paradigm yang digunakannya. Tapi dalam konteks ini pula, kita akan menyadari bahwa kebenaran yang telah dibentangkan oleh beragam pemikiran tersebut bersifat fragmentaris, terpecah-pecah dan belum utuh dalam membingkai makna tentang manusia. Hakikat kodrat manusia dengan segala kompleksitas dan keunikannya belum tergambarkan secara komprehensif. Dalam perspektif Husserl, tatkala kita melihat sosok manusia melalui kaca mata dari berbagai konstruksi filosofis di atas, pandangan kita terhadap manusia sudah bersifat subjektif: kita menggunakan asumsi, konsep, teori, atau perspektif-perpektif dari orang lain, siapa pun mereka. Kita belum memotret eksistensi manusia apa adanya, sebagaimana ia hadir menyapa kehidupan kita secara transparan, sederhana, dan murni. Di sinilah reduksi fenomenologis harus memainkan perannya. Husserl menyarankan kita menggunakan metode yang disebutnya dengan epoche menempatkan sesuatu di antara dua tanda kurung atau bracketing, pengurungan/(), yang berarti penundaan atau penghentian. Metode epoche itu digunakan dengan cara yang secara literal. Terapi ang dimaksud dengan epoche adalah melupakan pengetahuan-pengetahuan tentang objek untuk sementara dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan pengetahuanpengetahuan yang ada sebelumnya. Semua paradigma para ilmuwan dan filsuf di atas mengenai manusia kita letakkan dulu dalam dua tanda kurung/(). Sbab sewaktu kita menggunakan konsep-konsep mereka terhadap manusia, maka kita sudah melihat eksistensi manusia dari sudut pandang ilmu logika dan filsafat, dari perspektif semiotika atau filsafat bahasa, dari sudut pandang ilmu ekonomi dan politik, dari perspektif ilmu budaya dan politik, dari perpektif searah agama atau filsafat agama. Kita tidak menggunakan intuisi kita secara langsung terhadap manusia, tapi kita justru memakai pandangan-pandangan orang lain tentang manusia: sehingga penglihatan kita mengenai hakikat keberadaan manusia tidak objektif apa adanya, tapi sudah bias dengan mengenakan salah satu atau beberapa sudut pandang tentang manusia. Karena itu, reduksi fenomenologis tahap pertama ini berfungsi membersihkan diri kita dari segala subjektivitas yang dapat mendistorsi pandangan kita tentang hakikat realitas, tentang esensi objek, tentang hakikat manusia. Dengan reduksi fenomenologis inilah, diharapkan kita sudah bisa memahami lebih awal untuk melihat hakikat eksistensi manusia. Tahap kedua, reduksi eidetic. Istilah eidetic berasal dari kata eidos yang berarti intisari atau esensi sesuatu. Reduksi eidetic berupaya melakukan penyaringan dan penundaan penilaian dengan menempatkan dalam kurung (proses epoche) terhadap segala hal yang bukan eidos, bukan intisari, bukan esensi dari sebuah objek. Dalam tilikan Husserl reduksi eidetic tidak lain dari upaya untuk menemukan eidos atau hakikat fenomena yang tersembunyi. Pada tahap ini, segala sesuatu yang dianggap sebagai hakikat fenomena yang diamati harus disaring untuk menemukan hakikat yang sesungguhnya dari fenomena itu. Itu berarti segala sesuatu yang dilihat harus dianalisis secara cecrmat dan lengkap agar tidak ada yang terlupakan. Dalam upaya menganalisis fenomena yang diamati dengan cermat dan lengkap itu, perhatian pengamat harus senantiasa terarah kepada isi yang paling fundamental dan segala sesuatu yang bersifat paling hakiki. Dengan reduksi eidetis, semua segi, aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan. Karena aspek dan profil tidak pernah menggambarkan objek secara utuh. Setiap objek adalah kompleks mengandung aspek dan profil yang tiada terhingga. Hakikat (realitas) yang dicari dalam hal ini adalah struktur dasar meliputi isi fundamental dan semua sifat hakiki. Untuk menentukan apakah sifat-sifat tertentu adalah hakikat atau bukan, Husserl memakai prosedur mengubah contoh-contoh. Ia menggambarkan contoh-contoh tertentu yang representative melukiskan fenomena. Kemudian dikurangi atau ditambah salah satu sifat. Pengurangan atau penambahan yang tidak mengurangi atau menambah makna fenomena dianggap sebagai sifat-sifat yang hakiki. Reduksi eidetic ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi kriteria koherensi berlaku.. artinya, pengamatan-pengamatan yang beruntun terhadap objek harus dapat disatukan dalam suatu horizon yang konsisten. Setiap pengamatan memberi harapan akan tindakan-tindaan yang sesuai dengan yang pertama atau yang selanjutnya. Bila kita kembali melihat kepada ilustrasi manusia, reduksi eidetic hendak mengetahui esensi manusia. Pada sosok setiap manusia, bila kita melihat berbagai atribut yang bisa kita kurangi atau kita tambahkan untuk melihat sejauhmana esensi manusia masih tersisa-ada. Atribut-atribut yang melekat dalam kehidupan manusia sebagai makhluk social misalnya status-status yang mereka kenakan: status seorang menteri, gubernur, dan bupati; status sebagai seorang ilmuwan, filsuf, ekonom, politikus, budayawan, sejarawan, agamawan, dan anggota legislatifl status sebagai seorang guru, dosen, dokter, petani, pedagang, dan nelayan; Ataupun juga berbagai titel-titel yang melekat pada manusia, seperti titel professor, doktor, master, sarjana, insinyur, dan lain-lain. Ataupun kondisi-kondisi yang melekat dalam kehidupan mereka, seperti sebagai orang kaya dan miskin, orang terkenal dan orang biasa, para konglomerat dan orang-orang melarat, para ningrat keturunan bangsawan dan kaum papa keturunan rakyat jelata. Dengan reduksi eidetic, kita bisa meletakkan semua status-status social, titel-titel keahlian, dan kondisi-kondisi yang menyertai hidup mereka dalam epoche, dalam pengurungan untuk mencari inti sari seorang manusia yang sesungguhnya. Apakah dengan menghilangkan semua atribut-atribut social dan titel-titel keahlian mereka, akan menyebabkan manusia kehilangan emosinya? Apakah ketika atribut-atribut menteri dan gubernur, ilmuwan dan filsuf, ekonom dan anggota legislative kita hilangkan, maka mereka yang menyandangnya menjadi berubah bukan lagi manusia? Apakah ketika titeltitel mentereng bergengsi sebagai gubernur dan doktor, maser dan sarjana atau insinyur dienyahkan dari seorang manusia, maka mereka menjelma bukan lagi sosok manusia? Ketika kekayaan dan kemiskinan, ketenaran dan kesahajaan, bangsawan dan kejelataan tidak lagi menghiasi kehidupan seorang anak manusia, apakah dengan tiba-tiba mereka tidak pantas lagi disebut dengan manusia? Fakta kehidupan menampilkan dirinya secara langsung di hadapan kita bahwa sosok manusia yang hakiki bukan ditentukan oleh beragam emblememblem social tersebut. Seorang manusia tidak disebut manusia hanya karena status sosialnya, pngkat jabatannya, gelar-gelar yang disandangnya, ataupun kondisi-kondisi kekayaan dan kemiskinan mereka semata. Kita semua sadar bahwa segala bentuk atribut, status, dan kondisi social seseorang sering kali bersifat dangkal dan tidak mencerminkan karakter pribadi sejati orang-orang yang menyandangnya. Sayangnya, banyak di antara kita memberikan penilaian kepada manusia berdasarkan status dan jabatan-jabatan social tersebut. Banyak di antara kita yang meletakkan standar kriteria pada kebangsawanan, kekayaan, dan kemasyhurang seseorang. Kita terpukau dengan segala bentuk emblem-emblem social yang tidak autentik. Kita katakana tidak autentuk, sebab hokum kehidupan sudah mengisahkan kepada kita bahwa semua bentuk atribut-atribut social itu dapat digantikan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Seorang presiden yang begitu ditakuti ketika berkuasa, namun justru mengundang hujatan tanpa henti saat turun dari singgasana kekuasaannya. Seorang menteri dan gubernur, bupati dan anggota legislative, bisa diganti oleh orang lain kapan pun saja. Ilmuwan, dokter, ekonom, dan agamawan pun satu waktu akan pudar dikikis putaran zaman dan diganti tunas-tunas baru yang lebih berarti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya. Apalagi factor kekayaan yang sebenarnya amat fluktuatif: banyak orang-orang kaya yang tiba-tiba langsung jatuh miskin dan tidak sedikit orang-orang miskin dengan cepat menjadi orang kaya baru. Dengan alasan-alasan inilah, reduksi eidetic hendak mengatakan kepada setiap kita bahwa semua bentuk atribut-atribut social yang mengiringi kehidupan manusia, entah itu pangkat jabatan, titel yang mentereng, ebangsawanan, ataupun kekayaan dunia, bukanlah inti sari yang menggambarkan sosok manusia sebenarnya. Esensi sejati seorang manusia tidak ditentukan oleh segala macam atribut, titel, pangkat social dan kemewahan dunia yang disandangnya. Jika semua atribut-atribut yang memayungi manusia itu sudah kita hilangkan dengan reduksi eidetic, kita mulai melihat titik-titik terang esensi seorang manusia yaitu rohani dan jasmani yang menyatu dalam dirinya: hati, perasaan, emosi, dan akal yang bersemayam dalam diri mereka; yang dengan semua fakultas-fakultas itulah mengalir dalam bentuk tutur kata, sikap, dan perilaku yang menjadi cermin jernih yang mampu memantulkan otentitas seorang manusia yang sejati. Tahap ketiga, reduksi fenomenologi-transendental. Dalam reduksi tahap ketiga ini, yang harus kita tunda penilaiannya dengan menggunakan epoche, kita tempatkan dalam tanda kurung adalah eksistensi dan segala sesuatu yang tidak ada hubungan timbal balik dengan kesadaran murni, agar dari objek itu akhirnya orang sampai kepada apa yang ada pada subjek itu sendiri. Reduksi ini dengan sendirinya bukan lagi mengenai ojek, atau fenomena bukan mengenai hal-hal yang metampakkan diri kepada kesadaran. Reduksi ini merupakan pengarahan ke subjek dan mengenai hal-hal yang metampakkan diri dalam kesadaran. Dengan demikian, yang tinggal sebagai hasil reduksi ini adalah aktus kesadaran sendiri. Kesadaran di sini bukan pula kesadaran empiris lagi, bukan kesadaran dalam arti menyandarkan diri berdasarkan penemuan dengan fenomena tertentu, kesadaran yang ditemukan adalah kesadaran yang bersifat murni atau transcendental, yaitu yang ada bagi diriku di dalam aktus-aktus. Dengan singkat dapat disebut sebagai subjektivitas atau “aku” transendenta. Dengan kata lain, reduksi transcendental ini diterapkan kepada subjeknya sendiri dan kepada perbuatannya, kepada kesadaran yang murni. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dunia yang tampak kepada kita tidak dapat memberi kepastian, bahwa pengertian kita tentang realitas adalah benar. Dunia tidak dapat memberikan kebenaran kepadakita. Agar supaya ada kepastian akan kebenaran pengertiak kita, menurut Husserl, kita harus mencarinya dalam erlebnisse, yaitu pengalaman yang dengan sadar. Di dalam pengalaman yang dengan sadar ini kita mengalami diri kita sendiri atau “aku” kita senantiasa berhubungan dengan dunia benda di luar kita. Aku kita senantiasa berada di dalam situasi jasmaniah tertentu, umpamanya” aku sedang duduk, sedang membaca, sedang bercakap-cakap dan lain sebagainya. Pengalaman ini tidak termasuk “aku” kita yang sejati. “aku” di dalam pengalaman ini adalah “aku yang empiris”, yang dijangkau oleh dunia benda. Oleh karena itu, untuk sementara waktu “aku yang empiris” ini harus kita tempatkan di antara tanda kurung, harus kita saring dahulu. Setelah “aku yang empiris” kita beri tanda kurung akan tinggal “kesadaran yang murni”, yang tidak empiris lagi atau “aku yang murni”, yang tidak empiris lagi, yang mengatasi segala pengalaman, yang transcendental. Inilah dasar yang pasti dan tidak dapat dibantah lagi bagi segala pengertian. Dengan kembali kepada kesadaran murni, kembali kepada ego transcendental, atau kembali kepada intuisi murni, membawa Husserl merumuskan konsepnya yang termasyhur: evidenz. Evidenz adalah sesuatu yang hadir langsung, niscaya, dan absolut, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Intuisi selalu menghasilkan pengetahuan yang membuktikan dirinya sendiri, sebuah evidenz. Konsep evidenz berakar dari pemikiran Descartes. Cogito adalah sebuah evidenz bagi Descartes. Namun, Husserl mengambil jalan berbeda. Bagi Husserl, metode meragukan segala sesuatu memang menyisakan satu yang tidak bisa diragukan lagi. Namun, yang tidak bisa diragukan lagi bukan hanya aku berpikir, melainkan juga semua aktivitas mental lainnya. Segala aktivitas mental hadir secara langsung dan niscaya, berbeda dengan benda-benda, jadi, saya tidak perlu tahu apakah pengetahuan ini benar atau tidak, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Metode keraguan Descartes masih dipusingkan dengan pertanyaan dunia ada atau tidak. Sedang Husserl mengambil sikap idiferen (acuh) apakah dunia ada atau tidak. Bagi Husserl, yang paling dapat dipastikan adalah berbagai tindak mental saya, karena mereka hadir secara apodiktis (tanpa setetes pun keraguan). Husserl menginginkan fenomenologi dikuras dari segala sesuatu yang sifatnya factual. Ia bahkan membual bahwa fenomenologi dapat terus berjalan meski dunia lenyap. Ini disebabkan fenomenologi tidak berbicara tentang eksistensi factual, melainkan struktur konstitusi-makna yang memungkinkan kesadaran. Husserl menginginkan fenomenologi bertindak sebagai ilmu “murni” yang bebas lepas dari muatan empiris. Fenomena tidak dipahami sebagai sesuatu yang factual. Artinya, perbincangan tentang fenomena tidak lagi berurusan dengan eksistensi dan noneksistensi. Fenomena adalah korelat kesadaran sebagai sesuatu yang imanen dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga turut mencakup yang transenden. Pengalaman saya tentang satu objek selalu berarti adanya objek di luar pengalaman yang memiliki kualitas berbeda dengan pengalaman saya tentangnya. Menangkap esensi adalah menangkap sesuatu yang memiliki transendensi dalam imanensi. Akan tetapi, di sini perlu ditegaskan bahwa melalui tahapan-tahapan reduksi tersebut dan dengan menggunakan cara penundaan epoche, bukanlah berarti kita harus bersikap skeptis. Dalam perpektif Donny Gahral Adian, kita akan melakukan kesalahmengertian yang cukup fatal bila mempersamakan antara metode penundaan dalam epoche dengan sikap skeptis. Menempatkan sesuatu dalam kurung (epoche) tidak berarti meragukan eksistensinya, melainkan hanya menunda semua asumsi tentangnya. Seperti sudah dijelaskan, Husserl lebih memilih sikap indiferen (acuh) daripada ragu. Adatidaknya objek-objek tidak ditanggapi secara serius. Apa yang menjadi focus semata struktur tindak psikis dan korelatnya, bukan objek-objek yang terhampar factual. Epoche mengandalkan adanya kebebasan. Kebebasan kita dalam memilih sudut pandang. Kita tidak perlu hanyut dalam sudut pandang naturalism maupun psikologisme. Kita sepenuhnya bebas mengubah sudut pandang kita seiring arus pengalaman. Epoche mengatasi karakter factual dari kesadaran manusia. Artinya, sifat kesadaran yang melulu percaya akan sesuatu yang hadir terlepas darinya harus dilepas. Lepasnya sifat factual dari kesadaran akan membawa kita pada fenomena murni. Saat kita mendayagunakan penundaan fenomenologis, semua karakter factual lenyap dan menyisakan kita kesadaran murni, kesadaran sebagai eksistensi absolut di mana objek-objeknya selalu korelat baginya. Dunia tampil dalam terang baru, yaitu sebagai korelat bagi kesadaran, sebagai sesuatu yang memiliki modus berada tertentu. Kesadaran oleh Husserl tidak cukup cogito. Husserl membaginya menjadi dua bagian: cogitationes dan cogitate. Cogitationes adalah tindak ego, sedang cogitate adalah objek tindak kesadaran tersebut, apakah itu fisikal ataupun mental. Kesadaran kita memiliki keterarahan. Kesadaran selalu terarah pada objek. Ini disebut sebagai intensionalitas kesadaran. Tindakan intensionalitas menyeruak ke luar menuju objek transenden. Jika saya memikirkan sebuah kardus, maka objek pikiran saya adalah kardus; sedang jika saya mengimajinasikan sebuah pulau fantasi, maka pulau fantasi adalah objek imajinasi saya. Intensionalitas artinya kita tidak pernah memikirkan atau membayangkan kekosongan. Ini adalah kritik keras terhadap konsep cogito (aku berpikir) Descartes. Cogito Descartes adalah cogito tertutup, bersibuk dengan isi pikiran sendiri, dan memisahkan diri dari dunia luar serta cogito lainnya. Cogito selalu cogito yang berintensionalitas. Artinya, pikiran selalu pikiran tentang sesuatu. Pikiran mengimplikasikan objek. Berdasarkan itu, Husserl menambahkan konsep cogitations adalah tindak pikiran, sedang cogitate adalah objek sebagai korelat cogitations. Sampai di sini, kiranya cukup jelas bahwa melalui tahapan-tahapan ketiga macam reduksi tersebut, akhirnya Husserl hendak menunjukkan kesadaran murni, kesadaran transcendental, atau ego transcendental-lah yang menjadi pijakan fundamental bagi semua ilmu pengetahuan dan wacana filsafat yang bersifat absolut, tak tergoyahkan. Akan tetapi, konsep ego transcendental tetap sangan berisiko terjebak pada solipsism. Solipsism adalah penyangkalan ego lain dengan embekukan kebenaran egoku orang lain? Persoalan “ego lain” selalu menggayuti konsep ego transcendental. Husserl mengatasi kesulitan ini dengan memperkenalkan konsepnya tentang intersubjektivitas.pengalaman manusia, menurut Husserl, adalah pengalaman intersubjektif. Persepsi saya tentang pohon di luar sana senantiasa menunjukkan saya bahwa pohon itu hadir juga bagi orang lain. Manusia senantiasa berkubang dalam dunia intersubjektif. Dia terisolasi ke dalam dunia yang dihayati bersama. Tidak ada satu pun yang murni subjektif. Dunia yang kita amati, pikirkan, rasakan, bayangkan adalah dunia bersama (shared world). Dunia senantiasa ada di sana bagi kita (us) melalui saya (me). Intersubjektivitas adalah karakteristik utama ego. Sesuatu yang menyelamatkan fenomenologi Husserl dari jebakan solipsism.


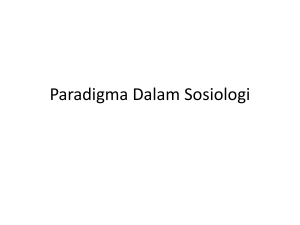

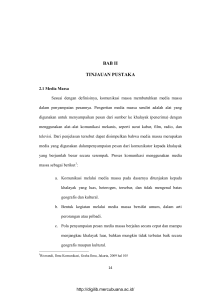
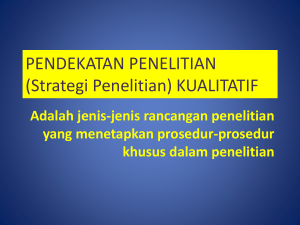
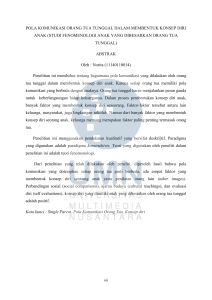
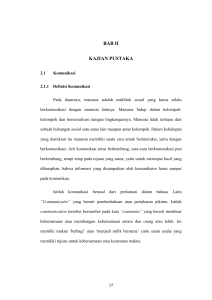
![Modul Teori Komunikasi [TM14]](http://s1.studylibid.com/store/data/000298276_1-9950dfa4151b78a2dcd5a0fbaf677190-300x300.png)