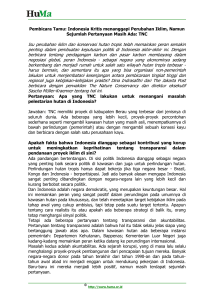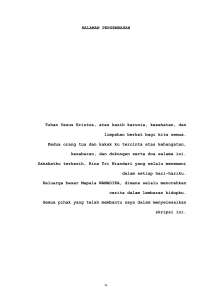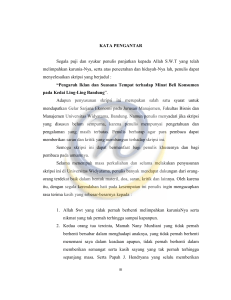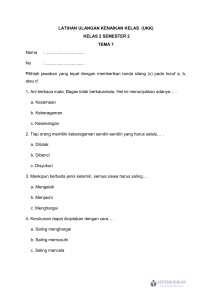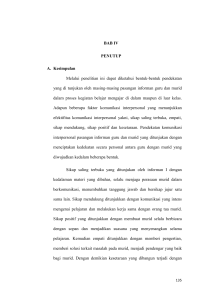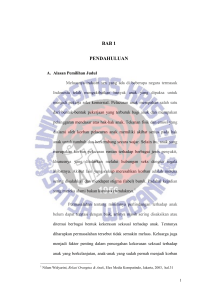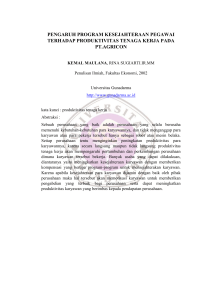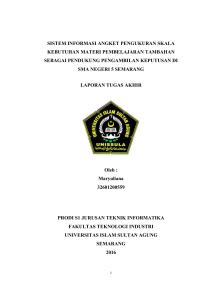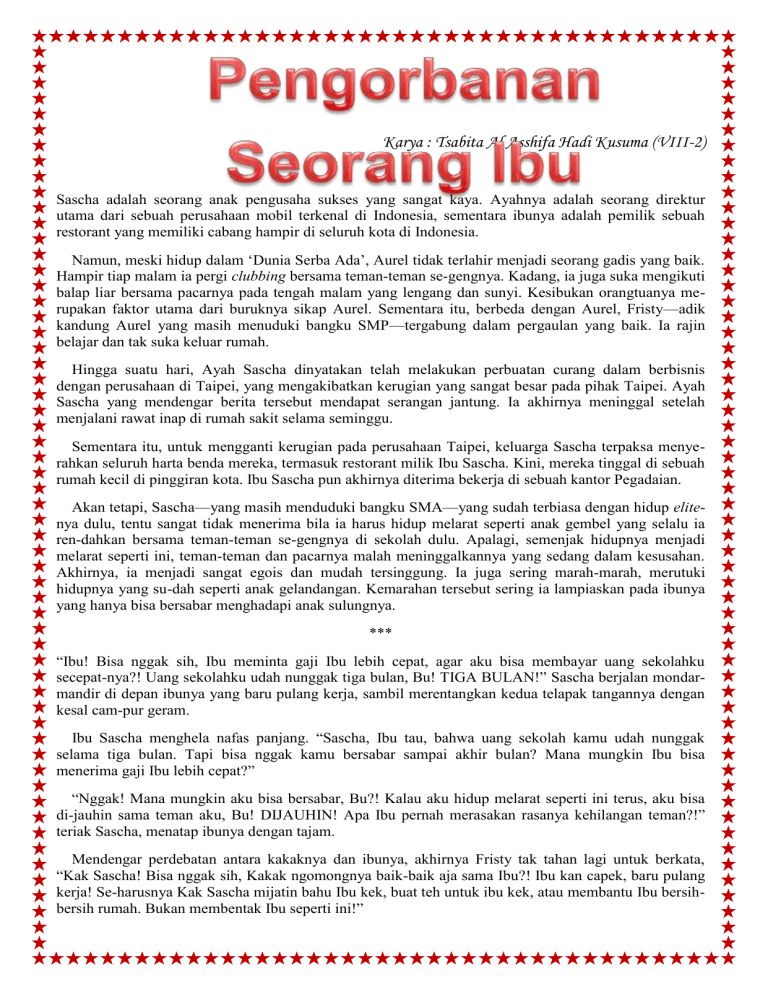
Karya : Tsabita Al Asshifa Hadi Kusuma (VIII-2) Sascha adalah seorang anak pengusaha sukses yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang direktur utama dari sebuah perusahaan mobil terkenal di Indonesia, sementara ibunya adalah pemilik sebuah restorant yang memiliki cabang hampir di seluruh kota di Indonesia. Namun, meski hidup dalam ‘Dunia Serba Ada’, Aurel tidak terlahir menjadi seorang gadis yang baik. Hampir tiap malam ia pergi clubbing bersama teman-teman se-gengnya. Kadang, ia juga suka mengikuti balap liar bersama pacarnya pada tengah malam yang lengang dan sunyi. Kesibukan orangtuanya merupakan faktor utama dari buruknya sikap Aurel. Sementara itu, berbeda dengan Aurel, Fristy—adik kandung Aurel yang masih menuduki bangku SMP—tergabung dalam pergaulan yang baik. Ia rajin belajar dan tak suka keluar rumah. Hingga suatu hari, Ayah Sascha dinyatakan telah melakukan perbuatan curang dalam berbisnis dengan perusahaan di Taipei, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak Taipei. Ayah Sascha yang mendengar berita tersebut mendapat serangan jantung. Ia akhirnya meninggal setelah menjalani rawat inap di rumah sakit selama seminggu. Sementara itu, untuk mengganti kerugian pada perusahaan Taipei, keluarga Sascha terpaksa menyerahkan seluruh harta benda mereka, termasuk restorant milik Ibu Sascha. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ibu Sascha pun akhirnya diterima bekerja di sebuah kantor Pegadaian. Akan tetapi, Sascha—yang masih menduduki bangku SMA—yang sudah terbiasa dengan hidup elitenya dulu, tentu sangat tidak menerima bila ia harus hidup melarat seperti anak gembel yang selalu ia ren-dahkan bersama teman-teman se-gengnya di sekolah dulu. Apalagi, semenjak hidupnya menjadi melarat seperti ini, teman-teman dan pacarnya malah meninggalkannya yang sedang dalam kesusahan. Akhirnya, ia menjadi sangat egois dan mudah tersinggung. Ia juga sering marah-marah, merutuki hidupnya yang su-dah seperti anak gelandangan. Kemarahan tersebut sering ia lampiaskan pada ibunya yang hanya bisa bersabar menghadapi anak sulungnya. *** “Ibu! Bisa nggak sih, Ibu meminta gaji Ibu lebih cepat, agar aku bisa membayar uang sekolahku secepat-nya?! Uang sekolahku udah nunggak tiga bulan, Bu! TIGA BULAN!” Sascha berjalan mondarmandir di depan ibunya yang baru pulang kerja, sambil merentangkan kedua telapak tangannya dengan kesal cam-pur geram. Ibu Sascha menghela nafas panjang. “Sascha, Ibu tau, bahwa uang sekolah kamu udah nunggak selama tiga bulan. Tapi bisa nggak kamu bersabar sampai akhir bulan? Mana mungkin Ibu bisa menerima gaji Ibu lebih cepat?” “Nggak! Mana mungkin aku bisa bersabar, Bu?! Kalau aku hidup melarat seperti ini terus, aku bisa di-jauhin sama teman aku, Bu! DIJAUHIN! Apa Ibu pernah merasakan rasanya kehilangan teman?!” teriak Sascha, menatap ibunya dengan tajam. Mendengar perdebatan antara kakaknya dan ibunya, akhirnya Fristy tak tahan lagi untuk berkata, “Kak Sascha! Bisa nggak sih, Kakak ngomongnya baik-baik aja sama Ibu?! Ibu kan capek, baru pulang kerja! Se-harusnya Kak Sascha mijatin bahu Ibu kek, buat teh untuk ibu kek, atau membantu Ibu bersihbersih rumah. Bukan membentak Ibu seperti ini!” Tatapan Sascha beralih pada Fristy. “Heh, kamu nggak usah sok ikut campur, deh! Ini urusan Kakak sa-ma Ibu! Nggak ada sangkut pautnya sama kamu! So, mendingan kamu mundur!” Tatapan tajam dari Sascha membuat Fristy takut kalau-kalau kakaknya itu melemparnya dengan vas bu-nga. Akhirnya, ia hanya bisa terdiam menatap kakaknya. Sascha kembali menatap ibunya. “Bu, kalau dua hari lagi Ibu masih belum membayar uang sekolahku, aku pastikan aku akan BERHENTI SEKOLAH!” ancam Sascha, sebelum akhirnya ia masuk ke dalam kamar-nya setelah membanting pintu kamar dengan sangat keras. Ibu Sascha yang melihat kelakuan Sascha, mengelus dadanya, berusaha untuk bersabar. Fristy memeluk ibunya sekilas. “Bu, Ibu sabar aja, ya. Kak Sascha kan emang kayak gitu. Sekarang, Ibu istirahat aja dulu, ya.” Ibunya hanya mengangguk kaku. *** “Kamu yakin, mau menggadaikan cincin pernikahanmu itu? Cincin itu kan kenang-kenanganmu dengan suamimu. Dan kamu rela menggadaikannya karena seorang anak bodoh yang selalu memarahimu setiap hari? Ada apa denganmu?” Bu Vera—teman sekerja Bu Rina (Ibu Sascha)—menatap Bu Rina yang tengah mengelus cincin pernikahannya yang terpasang manis di jari manisnya. Bu Rina mengangguk. “Ya. Aku akan menggadaikannya. Aku tidak ingin anakku berhenti sekolah. Aku ingin melihatnya sukses meraih cita-citanya ....” Spontan mata Bu Vera menyipit tak suka pada Bu Rina. “Meraih cita-citanya? Bukannya ia pemalas be-lajar? Bukannya kerjanya hanya bisa merutuki nasibnya yang menjadi anak melarat? Bukannya ia selalu melampiaskan kemarahannya padamu?” “Veraaa ... dia anakku! Aku yakin, dia akan berubah menjadi seorang gadis yang baik suatu saat nanti ...” kilah Bu Rina, melepaskan cincin pernikahannya dengan perlahan. Bu Vera terdiam dan menatap Bu Rina dengan iba. “Aku menggadaikan cincin ini.” Bu Rina meletakkan cincin pernikahannya di meja Bu Vera. “Kamu yakin?” Bu Vera terlihat enggan menyentuh cincin tersebut. Bu Rina mengangguk mantap. *** BRAK! Pintu toilet terbuka dengan kasar. Bu Rina menerjang masuk dengan langkah sempoyongan. Kepalanya sakit, tubuhnya pun lemas. ‘Aku akan mati? Tidak. Tidak! Aku tidak akan mati! Aku tidak akan pernah meninggalkan anakanakku. Aku ingin melihat mereka sukses dan bahagia ....’ jeritnya, dalam hati. Air matanya pun bergulir membasa-hi pipinya. Bu Rina menatap pantulan dirinya pada cermin setengah badan di hadapannya. Pikirannya langsung menerawang pada perkataan dokter beberapa bulan yang lalu—beberapa hari setelah kematian suaminya. Dokter tersebut berkata bahwa Bu Rina mengidap penyakit kanker otak stadium 4. Dokter juga berkata, bahwa ia mungkin masih bisa bertahan hidup hingga beberapa bulan ini. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Bu Rina sedih dan putus asa. Ia sangat takut menelantarkan anaknya. Apalagi putri sulungnya yang setelah suaminya meninggal, hanya tergantung padanya. Air mata kembali menetes di pipi Bu Rina, tapi kali ini ia segera menghapusnya dan berkata, “Aku pasti kuat!” *** “Ibu! Kenapa sih, Ibu tidak mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar saja? Kan kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Seperti dulu!” beberapa hari kemudian, Sascha kembali marah-marah pada ibunya ketika ibunya baru pulang kerja. “Sascha, apalagi maumu? Bukannya Ibu sudah membayar uang sekolahmu, sekaligus sama bulan ini?” tanya Ibu Sascha. “Iya, aku tau. Tapi aku hanya ingin Ibu merubah nasib kita, Bu! Aku nggak mau nasib kita seperti ini terus. Aku ingin kehidupan kita seperti dulu!” jawab Sascha, dengan nada tinggi. “Sascha, nasib kita itu ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada yang tau, bagaimana nasib kita nantinya!” tukas Ibu Sascha, berusaha sabar. “Tuhan, Tuhan, Tuhan. Semuanya selalu Tuhan! Bu, kita pasti juga bisa mengubah hidup kita sendiri, Bu! Nggak mungkin semuanya tergantung pada ...” “Astaghfirullah ... Sascha, istighfar, Nak. Kamu nggak boleh bicara seperti itu!” sela Ibu Sascha. “Tuh kan, Ibu selalu bicara seperti itu! Udahlah, Bu. Aku pusing, nih. Tapi satu hal yang pasti, AKU NYE-SEL JADI ANAK IBU!” bentak Sascha, sebelum akhrinya ia berbalik meninggalkan ibunya. “Kakak! Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu, dong!” sorak Fristy, berusaha menahan niatnya untuk melempar kakaknya dengan sebuah gelas berisi air yang ia pegang. Tapi, Sascha tak menyahut. Ia tetap berjalan menuju pintu rumah, membukanya, dan keluar dari rumah setelah membanting pintu dengan keras. Melihat kelakuan anaknya, gejolak emosi langsung memenuhi otak Ibu Sascha. Perlahan, pandangannya mulai kabur, hingga akhirnya ... BRUK! “IBU!” *** CKLEK! CKLEK! Sascha kebingungan ketika menyadari pintu rumahnya terkunci, setelah ia pulang dari sebuah warung untuk membeli makanan ringan. Ia mengetuk pintu rumah. “Ibuu! Friissty!” panggil Sascha. Namun, tak ada yang menyahut. Tak ada pilihan lain. Sascha langsung mengambil kunci rumah cadangannya dari dalam saku jaketnya dan membuka pintu. ‘Aneh sekali. Ibu dan Fristy ke mana, sih?’ Pergi kok nggak ngajak-ngajak?! ’ omel Sascha, dalam hati. Ia hendak membuka pintu kamarnya, ketika ia mendengar seseorang membuka pagar rumahnya. Ia kembali berjalan menuju pintu rumah. Tapi, sebelum sempat menyentuh gagang pintu, pintu tersebut telah terbuka dan tampaklah Fristy berdiri di hadapannya dengan wajah pucat. Namun, wajah pucat tersebut berubah menjadi wajah penuh amarah ketika melihat Sascha. “Kak Sascha!” pekik Fristy. Sascha terperangah kaget. Ia mengernyit menatap Fristy. “Kakak jahat! Kakak jahat! Anak macam apa Kakak ini?! Tega sekali membuat Ibu menderita dengan se-luruh omelan dan permintaan Kakak! Dan sekarang, lihatlah. Ibu masuk rumah sakit karena menderita kanker otak stadium empaat!!! Dan penyakitnya itu sudah tumbuh dari beberapa bulan yang lalu. Ibu ter-paksa menyembunyikan penyakitnya itu dari kita karena tidak mau membuat kita bersedih!!! Dia juga ti-dak mau membuat Kak Sascha bersedih, sementara Kakak sendiri sudah membuat Ibu sedih setiap hari!” jerit Fristy, menerjang memukul-mukul lengan Sascha. Sascha berusaha menghindari dari serangan tangan Fristy. “Fristy! Tolong diam dulu, dan jelaskan semuanya pada Kakak! Ada apa sebenarnya dengan Ibu?” Tapi Fristy tak memedulikan panggilan Sascha. Ia masih fokus pada rencananya untuk meluncurkan be-berapa pukulan pada lengan Sascha. “FRISTY!” bentak Sascha, membuat Fristy berhenti dan menatap Sascha dengan tatapan membunuh. “Ceritakan pada Kakak, apa yang terjadi pada Ibu?!” Sascha mengulang pertanyaannya. “Ibu ... masuk rumah sakit. Ia mengidap penyakit kanker otak stadium empat!” Fristy terisak. Matanya mulai berkaca-kaca. Sascha terdiam mendengarnya. Lidahnya kelu beberapa saat. Pikirannya sibuk menganalisis betapa pa-rahnyakah penyakit yang diderita ibunya saat ini? Detik selanjutnya, Sascha sudah menarik Fristy untuk pergi menuju rumah sakit tempat Ibu dirawat. *** “Kamar nomor berapa?” tanya Sascha, menatap Fristy yang berjalan canggung di sampingnya. Mereka sudah tiba di rumah sakit tempat ibu mereka dirawat, dan tengah berjalan menuju kamar rawat ibu mereka. Fristy menoleh kaku dan menjawab, “Nomor 207.” Langkah mereka mulai mendekati kamar nomor 207. Hati Sascha berdebar-debar. Ia mempercepat langkahnya, hingga akhirnya tiba di ambang pintu kamar yang terbuka. Ia tercengang. Fristy pun ikut ter-cengang. Kamar itu kosong. Dan kamar itu rapi, seperti baru selesai dirapikan. “Ibu ke mana, ya?” tanya Fristy, bingung. Sehelai kertas berwarna hijau muda terletak di atas selimut putih ranjang rumah sakit. Sascha berjalan menuju ranjang rumah sakit, dan mengambil kertas tersebut. Seorang dokter tiba-tiba masuk ke ruangan. Baik Sascha mau pun Fristy, langsung mengalihkan perha-tian mereka pada dokter tersebut. “Apa kalian keluarga Bu Rina?” tanya dokter tersebut. Sascha dan Fristy mengangguk bersamaan. “Hmm ... maaf jika saya kurang sopan mengatakannya, tapi Bu Rina ... telah berlalu. Kanker otak yang ia derita sudah sangat parah, hingga kami harus melakukan operasi. Tapi, operasi tu gagal ....” ujar dokter itu, lagi. Sascha dan Fristy terbelalak. “Dokter bercanda kan?” Sascha makin merasa tak menginjak bumi, ketika melihat dokter itu—dengan tatapan seriusnya— menggeleng pelan. *** Untuk anak sulungku, Sascha Laura Ningrum ... Sascha, maafin ibu ya, Nak. Ibu sepertinya akan pergi tanpa pamit padamu. Ibu berpesan, agar kamu menjaga Fristy. Jangan bersikap kasar padanya, jika ia tak ada salah. Aturlah pola makanmu dan jaga kesehatanmu. Jangan menangisi Ibu jika Ibu sudah tak ada lagi di sampingmu. Anak cengeng bukan anak Ibu, lho ... Tapi, ada satu permintaan Ibu untukmu, dan Ibu harap kamu bisa mengabulkannya. “Berubahlah.” Ibu. *** Sascha menangis pilu membaca surat yang ditinggalkan Ibu padanya. Surat berwarna hijau muda itu terletak di atas selimut yang terlipat rapi di atas ranjang. Mungkin, Ibu sengaja berpesan pada salah satu pe-rawat di rumah sakit tersebut agar suratnya tetap diletakkan di atas ranjang, berharap kedua anaknya melihat surat tersebut “Ibu ...” isak Sascha di tengah tangisnya. “Maafin aku, Bu ...” Mendengar hal itu, Fristy melangkah maju, memeluk kakaknya. “Kak, aku rasa Ibu sudah memaafkan Kakak dari dulu, deh ... hiks.” Sascha tak membalas pelukan Fristy. Ia masih sedih memikirkan kata ‘maaf’ untuk ibunya yang sudah terlambat untuk diucapkan. *** Sascha menangis tersedu-sedu menatap pusara di hadapannya. Jenazah ibunya baru saja dikebumikan beberapa menit yang lalu. ‘Ibu ... kenapa Ibu harus pergi? Bu ... aku minta maaf, Bu .... Aku minta maaf atas semua kesalahanku pada Ibu .... Maafkan aku, Bu ... maafkan aku. Aku janji, aku akan berubah menjadi seorang gadis baik yang Ibu harapkan, Bu. Aku janji. Tapi kenapa Ibu malah pergi, Bu??’ raung Sascha, dalam hati. “Kak Sascha, kita harus pulang, Kak. Hiks ...” kata Fristy, terisak. “Nggak! Kakak nggak mau pulang, sampai Ibu memaafkan Kakak!” tolak Sascha. Ia memeluk batu nisan pusara ibunya dengan erat. “Kak! Ibu udah memaafkan Kakak! Sekarang, tinggal Kakak aja yang harus membuktikan kata ‘maaf’ Kakak itu!” tangis Fristy, tertahan. Sasha menoleh. “Apa maksudmu?” “Buktikan kata ‘maaf’ Kakak pada Ibu, dengan cara mengubah pola hidup Kakak! Kakak harus bisa menerima hidup kita yang sekarang! Dan sekarang, ayo pulang!” *** Setelah kematian ibunya, kehidupan Fristy dan Sascha semakin membaik. Atas rasa kepedulian perusahaan Pegadaian terhadap salah satu karyawan mereka, Sascha dan Fristy dibiayai sekolah oleh pihak Pegadaian. Kehidupan mereka sehari-hari juga menjadi tanggungan perusahaan Pegadaian. Sascha dan Fristy sangat bahagia dengan kehidupan mereka saat ini, meski mereka lalui tanpa kehadiran seorang ibu. Sascha juga menepati janjinya pada ibunya untuk berubah menjadi gadis yang baik. Ia lulus SMA dengan nilai yang sangat tinggi, dan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia. Ia masuk ke jurusan ekonomi. Sementara itu, Fristy lulus SMP dengan nilai yang sangat bagus, dan melanjutkan pendidikannya ke SMA favoritnya. *** Suatu hari, Sascha tengah berjalan bersama teman satu kuliahnya untuk pergi ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu denga Fristy yang kebetulan baru pulang sekolah. “Fristy kok cepat banget pulangnya?” tanya Sascha, heran. “Kan hari ini hari Sabtu!” sahut Fristy, menyamai langkahnya dengan langkah Sascha. “Ooh ... tapi ...” ucapan Sascha terhenti begitu salah satu temannya menepuk bahunya, menunjuk sebuah gedung yang kini berada di hadapan mereka. Sascha dan Fristy menoleh bersamaan ke arah gedung tersebut, dan tersenyum lebar menatap gedung Pegadaian di hadapan mereka. Tanpa diduga-duga, Sascha dan Fristy berteriak serentak, “Mengatasi masalah, tanpa masalah!” Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi tertawa dan melanjutkan perjalanan untuk pulang sembari menikmati cuaca yang tidak terlalu cerah pada siang itu.