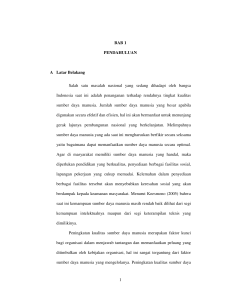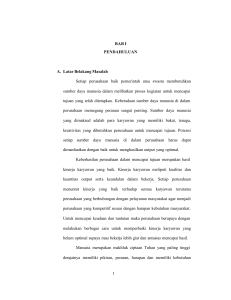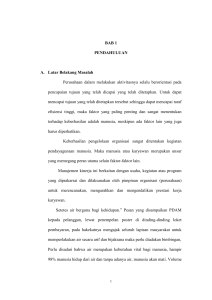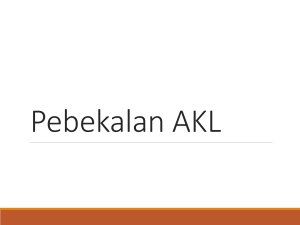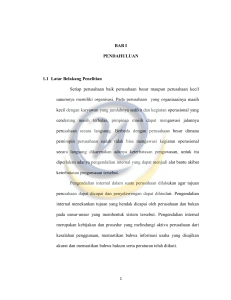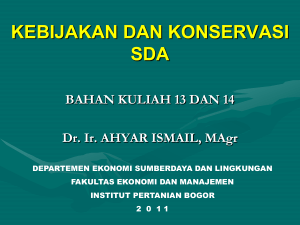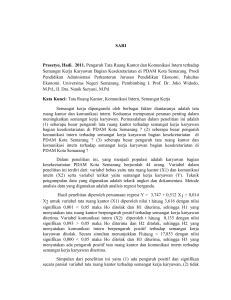DAFTAR ISI Kata Pengantar Sekapur Sirih Daftar Isi Bab 1 Surat Protes Buat PDAM 1 Bab 2 Rp 4,3 Triliun Utang PDAM Bab 3 Menata Piramid PDAM Bab 4 Trilogi Air Bab 5 Perbaiki Pilar PDAM Bab 6 Pegawai Yang Cakap Bab 7 Desain yang Inovatif Bab 8 Area Servis Perluas Terus Bab 9 Manajemen Akur Bermoral Bab 10 Tarif vs Mau-Bayar Bab 11 PDAM atau PAM Swasta? Bab 12 Amik versus Amiku Bab 13 Membasmi Wabah Pemula Bab 14 “Wabah” Petamula Bab 15 “Beternak” Bakteri Daftar Pustaka 15 31 44 64 72 87 104 122 144 171 193 213 233 247 259 Sekilas Penulis Amazon Pond Institute 261 262 MEMAKNAI KONSEP ALAM CERDAS DAN KEARIFAN NILAI BUDAYA LOKAL (CEKUNGAN BANDUNG, TATAR SUNDA, NUSANTARA, DAN DUNIA) ASAS-ASAS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP PIDATO ILMIAH DALAM RANGKA DIES NATALIS KE XXV DAN WISUDA SARJANA KE VIII TAHUN 2010 UNIVERSITAS KEBANGSAAN DI AULA UNIVERSITAS KEBANGSAAN, BANDUNG 16 OKTOBER 2010 oleh Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Dosen Fakultas Tekologi Industri ITB Teknologi Kimia Dosen Sekolah Pascasarjana UPI Kajian Fenomenologi Nilai Dosen Sekolah Pascasarjana UNAIR Ekonomi Islam Dosen Fakultas Psikologi UNPAD Konsep Teknologi Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132 E-mail : [email protected] Abstrak Hipotesa keilmuan yang melandaskan diri pada keterbatasan sumberdaya alam karena pertambahan penduduk ternyata tidak benar dan mengingkari keyakinan kehadiran Kasih sayang dan Kemahadilan Allah Yang Mahakuasa. Keberlanjutan kehidupan manusia justru memerlukan pertambahan kehidupan lain, yaitu tanaman dan binatang, sehingga hipotesa keilmuan yang seharusnya diterapkan adalah memelihara dan menjamin terjadinya keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan pertambahan tanaman dan binatang. Pertambahan kehidupan memerlukan ruang hidup untuk tumbuh, bergerak, menyimpan pasokan air dan udara sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian dapat diidentifikasi adanya dua siklus utama yang berinteraksi kuat dalam suatu ekosistem yaitu siklus ruang dan siklus kehidupan, yang seharusnya menjadi sasaran semua upaya keilmuan. Rujukan hipotesa baru ini akan mencetuskan berbagai kegiatan ramah lingkungan dan ramah kehidupan, seperti pertanian, perindustrian, perekonomian, dan pengembangan wilayah yang ramah lingkungan. Dikemukakan pula tiga prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin keberlanjutan, yaitu paradigma keterkaitan alami (ekosistem), keterkaitan hayati (keanekaragam), dan keterkaitan insani (kesejahteraan). Ketiga prinsip dasar ini memerlukan pemahaman yang benar, utuh dan tulus pada semua tingkatan, namun penguasaan keterampilan dan penerapannya akan berbeda sesuai dengan kemampuan dan skala interaksi yang mampu dilakukannya. Ketiga prinsip dasar tadi sebenarnya sudah merupakan kearifan budaya lokal di Tatar Sunda, yang akan memelihara keberlanjutan peradabannya dengan mengacu prinsip siliasih, siliasah, dan siliasuh, untuk meraih predikat Siliwangi. Pengelolaan ketiga prinsip keterkaitan di atas merujuk polapikir kesinambungan yang memperhatikan struktur ekosistem untuk pengembangan infrastruktur alam dan buatannya, evolusi nilai pembudayaannya, dan pengembangan kelembagaan upaya penerapannya. Penerapan hipotesa baru keilmuan pada olah lahan membuka inovasi penggunaan kompos sebagai generator siklus ruang dan mikroorganisme lokal (MOL) sebagai pemicu terjadinya siklus kehidupan, dan bangunan keterkaitan alami, hayati dan insani secara utuh mampu membuka paradigma baru penyuburan bumi untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya, khususnya bagi para petani. Kata Kunci : Hipotesa Baru Keilmuan, Siklus Ruang, Siklus Kehidupan, Keterkaitan Ekosistem, Keterkaitan Keanekaragaman, Keterkaitan Kesejahteraan, Model Budaya, Siliasih, Siliasah, Siliasuh, Siliwangi, Infrastruktur Alam, Infrastruktur Buatan, Siklus Udara, Siklus Air, Siklus Biomassa, Ekosistem Bioreaktor-Tanaman, Kompos, Mikroorganisme lokal (MOL), Intensifikasi Proses (PI), Production on demand (POD), Pendidikan Lingkungan Hidup 1. Hipotesa Baru Keilmuan Hipotesa keilmuan yang melandaskan diri pada keterbatasan sumberdaya alam akibat pertambahan penduduk perlu dipertanyakan. Karena kalau hipotesa ini benar berarti Gusti Allah tidak adil, hanya memberikan yang lebih baik kepada generasi terdahulu, padahal keyakinan agama mengajarkan Kemahaadilan Allah yang melebihi batas waktu seperti itu. Lebih lanjut untuk mengatasi masalah terbatasnya sumberdaya alam ternyata banyak pilihan yang ditawarkan sebagai solusi ilmiah hanya menjadi sumber pembenaran ketidakadilan. Hal ini terjadi karena pengembangan ilmu yang menganggap dirinya harus bebas nilai, akhirnya tunanilai, dan sekuler. Hipotesa keilmuan yang lebih benar yang mengacu adanya fenomena nilai harus dicari, dengan kembali mempertanyakan apalagi yang bisa bertambah di muka bumi ini selain manusia, karena memang jumlah tanah, air dan udara adalah tetap tidak bertambah. Ternyata yang bisa bertambah hanyalah tanaman dan binatang, sementara keberlanjutan kehidupan manusia justru memerlukan pertambahan kehidupan lain yaitu tanaman dan binatang. Sehingga hipotesa keilmuan yang seharusnya diterapkan adalah memelihara dan menjamin terjadinya keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan pertambahan tanaman dan binatang. Upaya untuk menambah tanaman dan binatang ilmu lama memberikan solusi dengan menambah luasan lahan sehingga terjebak pada hipotesa keterbatasan sumberdaya alam. Padahal yang diperlukan untuk pertambahan kehidupan adalah pertambahan ruang hidup untuk tumbuh, bergerak, menyimpan pasokan air dan udara sebagai sumber kehidupan, bukan pertambahan luas lahan. Fenomena rekayasa pertambahan ruang ini secara alami diajarkan oleh tanaman, yang tumbuh berdahan, bercabang dan beranting, menambah ruang hidup yang memberikan kesempatan hidup bagi banyak makhluk lain. Kemudian pada saat tanaman mati, dikompos lalu dikubur dalam tanah, memberikan banyak ruang kecil bagi kehidupan mikro di dalam tanah. Kehidupan kecil ini tidak akan ada kalau ruang hidupnya tidak disediakan, dan kalau kehidupan berskala kecil ini tidak ada maka kehidupan berskala besar pun tidak akan ada. Dengan demikian dapat diidentifikasi adanya dua siklus utama yang berinteraksi kuat di alam ini yaitu siklus ruang dan siklus kehidupan, yang seharusnya kedua siklus utama ini menjadi sasaran semua upaya keilmuan. Rujukan hipotesa baru ini akan mencetuskan berbagai kegiatan ramah lingkungan dan ramah kehidupan, seperti pertanian, perindustrian, perekonomian, dan pengembangan wilayah yang ramah lingkungan. 2. Paradigma Keterkaitan Alami (Ekosistem) Keterkaitan alami atau keterkaitan ekosistem mendefinisikan batas alam interaksi keberadaan seluruh unsur alam, makhluk hidup dan manusia lainnya dalam satu ruang alam yang sama. Bentuk keterkaitan ekosistem yang sering diungkapkan adalah fenomena globalisasi, suatu peristiwa alamiah yang menggeser pendekatan sistem terbuka menjadi sistem semitertutup atau sistem tertutup. Mengubah pandangan konsep nilai tambah ke nilai manfaat, yang meminimumkan masukan sumberdaya alam dan keluaran limbah, yang memelihara hak-hak alam sehingga kesinambungan dijamin oleh kompleksnya siklus rangkai manfaat, bukan oleh penguasaan hulu hilir sepenuhnya secara sepihak. Suatu siklus rangkai tertutup dari berbagai usaha yang saling terkait dirancang untuk memaksimumkan nilai manfaat dan meminimumkan penggunaan sumberdaya alam serta buangan limbahnya, yang sekaligus menjamin berlangsungnya semua aktivitas secara berkesinambungan. Dalam bahasa sehari-hari pendekatan sistem terbuka dinyatakan dalam ungkapan “saya hanya peduli pada diri saya sendiri, karena yang lain bukan bagian dari sistem saya atau di luar sistem saya, yang penting bagi saya, harus membuat untung sistem saya saja, saya tidak peduli orang lain rugi”. Ungkapan kata akan berubah tatkala menggunakan pendekatan sistem semitertutup menjadi : “saya dan yang lain berada dalam satu sistem yang sama, sehingga saya dan yang lain harus sama-sama untung, saling menarik manfaat ”. Pernyataan terakhir ini identik dengan pesan kearifan budaya lokal Sunda: Siliasih, yaitu saling mengasihi karena berada bersama dalam satu sistem yang sama: sadulur, sasumur, salembur, dan seterusnya sesuai dengan skala interaksi keberadaannya. 3. Paradigma Keterkaitan Hayati (Keanekaragaman) Secara alamiah penganekaragaman terjadi karena adanya interaksi multikomponen dan multiskala yang memiliki ciri khasnya masing-masing pada suatu ekosistem yang terdefinisi. Kehadiran banyak skala dan banyak pihak ini justru untuk saling menguatkan dan menstabilkan dinamika ekosistem pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang paling baik untuk suatu ketersediaan sumberdaya tertentu, sehingga lebih menjamin berlangsungnya kesinambungan peradaban. Contoh alam paradigma ini diberikan oleh aliran air di sungai yang terlihat memiliki banyak pusaran besar atau kecil yang masingmasing berputar pada porosnya selain mengikuti aliran utama sungai itu sendiri. Keterkaitan keanekaragaman juga dapat ditunjukkan dengan cara putaran perekonomian mikro, makro dan global yang tidak bisa dibiarkan semata-mata hanya berputar pada satu poros perputaran ekonomi global saja, karena hal tersebut hanya akan menambah beban, memberatkan dan menyebabkan keruntuhan putaran ekonomi secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi pada fenomena perubahan iklim global akibat keseimbangan ekosistem pada skala mikro dan regionalnya tidak tercapai sehingga semua penyimpangan terakumulasi pada skala yang paling besar yang mengakibatkan terjadinya bencana yang semakin sering dan besar daya rusaknya. Inilah yang melahirkan kesadaran think globaly but act locally, berfikir harus dengan wawasan global tapi dalam bertindak harus dalam keterkaitan utuh setempat atau secara lokal. Memulai dari yang kecil, dari diri sendiri, pada saat ini juga. Secara sosial-budaya paradigma ini merupakan upaya yang akan mencegah terjadinya sentralisasi dan penyeragaman yang selalu akan membuat kerdil dan tidak bertahan lama. Tuntutan kebebasan, otonomi dan perlindungan hak asasi manusia adalah bentuk pengungkapan paradigma ini dalam bahasa sosial-budaya, seperti juga ungkapan pesan kearifan budaya Sunda Siliasah, saling mendukung dan memberi peluang kebebasan untuk berkembang secara mandiri. 4. Paradigma Keterkaitan Insani (Kesejahteraan) Keterkaitan kesejahteraan ditunjukkan dengan tumbuh-kembangnya ekonomi jasa secara eksponensial. Pentingnya usaha jasa ini dapat diukur dengan melihat kenyataan keberhasilan ekonomi di suatu tempat sangat ditentukan oleh usaha jasanya yang efisien dan efektif, hampir 70% kegiatan ekonomi adalah usaha jasa, peluang kerja yang dapat diciptakan sangat luas baik jenis maupun jumlahnya, raihan kesejahteraan yang diberikan dapat meningkatkan secara berarti dan merata di berbagai lapisan masyarakat, jauh lebih baik daripada sekedar pemerataan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, berkembangnya usaha jasa dalam masyarakat akan berdampak baik pada peningkatan layanan publik oleh masyarakat, yang berarti menciptakan privatisasi layanan publik secara spontan dan benar, serta menciptakan birokrasi pemerintahan yang lebih ramping sehingga efisien dan efektif. Harapan kesejahteraan pada kesempatan kerja jasa menyangkut kemampuan atau keterampilan yang khas pada setiap individu atau kelompok, sehingga sebenarnya pengangguran itu tidak perlu terjadi bila keterkaitan usaha jasa bisa dibangun secara spontan, yang pada akhirnya juga akan membangun keterkaitan kesejahteraan manusia seluas mungkin. Kesempatan tersebut tentunya terbuka selama kualitas dan kemampuan diri manusianya tersedia dan memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Terbukanya peluang kesempatan kerja tidak karena ketiadaan melainkan karena kesiapan manusianya yang setiap saat dapat diantisipasi oleh pendidikan dan perencanaan kerja. Ekonomi jasa tidak dapat dipaksakan dengan kemampuan yang tidak teruji, melainkan timbul secara spontan karena kesiapan manusianya baik secara kemampuan maupun kemauan. Demikianlah keterkaitan kesejahteraan timbul bukan karena membagi-bagikan uang atau kekayaan melainkan dengan keterbagian kesempatan kerja yang sesuai di antara manusia yang ada. Paradigma ini sangat mendasar bagi kemanusiaan, yang dalam pesan nilai kearifan budaya Sunda disebut Siliasuh, saling membuka peluang atau memfasilitasi agar semua orang dapat bekerja atau berkiprah sesuai dengan kemampuannya untuk kesejahteraan bersama, rempug jukung babarengan nyambut gawe sauyunan. 5. Kerangka Pikir Kesinambungan Struktur Ekosistem Terdapat tiga aspek penataan yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan, yaitu: Struktur Ekosistem, Perkembangan Nilai, dan Perkembangan Kelembagaan. Pemahaman ekologi sangat penting untuk dapat merancang struktur keterkaitan ekosistem. Keterkaitan ini akan menjadi operasional kalau ditunjang oleh infrastruktur yang diperlukan. Investasi infrastruktur sangat mahal, namun merupakan suatu kemestian, sehingga perlu dipahami dengan baik adanya infrastruktur alam dan infrastruktur buatan. Perbedaan mendasar dari infrastruktur alam dan infrastruktur buatan adalah pada keandalan proses alam yang harus ditegakkannya. Infrastruktur alam seperti hutan, sungai, danau dan sebagainya memberikan jaminan agar siklus alam yang dihasilkannya benar-benar ditunjang oleh proses alam yang tidak terpotong-potong sehingga biaya operasi dan investasinya dapat ditekan seminimal mungkin. Peran infrastruktur alam umumnya tidak tergantikan, sehingga infrastruktur buatan hanya dibuat untuk menguatkan peran infrastruktur alam, dan tidak akan pernah mampu menggantikannya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dimulai dengan penyelamatan atau pemulihan fungsi infrastruktur alamnya terlebih dahulu. Dalam hal tertentu peran infrastruktur alam ini sangat menentukan sehingga bukan saja tidak tergantikan bahkan pengabaiannya akan menjadi sumber bencana, menutup peluang penambahan kapasitas dan peningkatan nilai manfaat, inilah yang biasa disebut dengan pusaka alam atau warisan alam, seperti puncak-puncak gunung, puncak-puncak bukit, lembah alam, hutan pantai, lorong angin, urat air dan lainnya yang secara kearifan budaya lokal yang sering dianggap keramat. Pengeramatan ini lebih bersifat metoda edukatif, karena seringkali makam yang dirujuk sebagai keramat hanyalah kuburan kosong belaka, semata-mata untuk mencegah agar para pengembang tidak merambah hingga ke puncakpuncak gunung atau bukit, dengan ditunjukkan seakan-akan wilayah itu sudah ada yang menguasai yang maha adil dan maha mengetahui, aya anu ngageugeuh. Kearifan budaya Sunda membagi ketinggian topografis gunung atau bukit menjadi tiga bagian, yaitu : 1/3 pada bagian puncak merupakan wilayah hak alam tempat awan sumber air terikat, bagian ini sama sekali tidak boleh diganggu oleh aktivitas manusia, disebut leuweung tutupan; 1/3 pada bagian tengah merupakan hak kehidupan agar tanaman dan binatang dapat berkembang biak, disebut leuweung titipan; dan hak untuk manusia untuk memanfaatkannya secara komersial berada pada 1/3 bagian paling bawah, disebut leuweung baladaheun. Budaya Sunda mengartikan leuweung dengan penuh makna sehingga mampu menjamin kesinambungan dan keberlanjutan, tidak sebatas dengan apa yang disebut hutan yang bermakna terbatas. Oleh karena itu, tidak perlu kaget bila kearifan budaya Sunda menginginkan sebuah kota di leuweung bukan sekedar hutan kota. Tatar Sunda memang berbasis budaya leuweung, baik itu lahan pertanian, permukiman, desa, kota maupun infrastruktur buatan lainnya tidak boleh mengurangi atau meniadakan makna yang kaya dari leuweung, yaitu adanya keterkaitan alami, hayati dan insani yang paripurna. Memang peran infrastruktur alam hutan sebagai generator oksigen, air dan biomasa tidak terbantahkan, sehingga konsep hutan sebagai kawasan lindung harus dikonsepsikan lebih utuh lagi sebagai leuweung: leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak (no forest, no water, no future). Sementara itu dalam penanganan infrastruktur pada umumnya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, menyangkut semua sektor aktivitas, tidak ada dominasi sektor tertentu, semua sesuai dengan manfaat dalam keterkaitannya; yang kedua adalah menyangkut cara menetapkan pilihan alat dan prosedur yang menjamin tercapainya interaksi keterkaitan; dan yang ketiga adalah inisiatif yang merupakan inti dari upaya pengembangan yang berkesinambungan. Jelas sekali bahwa tugas research and developement (R&D) pada dasarnya adalah mengelola inisiatif, terutama dari dalam yaitu dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya manusia menjadi sangat vital. Ketiga unsur keberlanjutan akan bermuara pada mutu kemampuan manusianya, bukan saja dalam inisiatif operasional namun juga dalam inisiatif pengembangan nilai atau pembudayaan, maupun pengembangan kelembagaannnya. Kemampuan orang seorang diri akan selalu terkalahkan oleh kemampuan terorganisir dalam kerjasama, misalnya dalam ketahanan dan kecermatan. Demikian juga nilai yang berkembang secara bersama dalam pembudayaan masyarakat akan lebih tahan dan lebih dapat diandalkan daripada peningkatan nilai individual semata. 6. Kerangka Pikir Kesinambungan Evolusi Nilai dan Kelembagaan Jaminan agar proses keterkaitan berlangsung ke arah yang lebih utuh dan berkesinambungan adalah tumbuh-kembangnya kelembagaan yang terkait, yaitu lembaga pemberdayaan maupun lembaga pembudayaannya. Upaya pemberdayaan sekurangkurangnya memerlukan tiga lembaga pemberdayaan, yaitu lembaga keuangan, lembaga pasar, serta lembaga penyimpanan dan penyampaian. Ketiga lembaga ini akan berbeda untuk setiap skala ruang dan waktu yang berbeda. Penggabungan kelembagaan secara vertikal untuk semua skala akan menghasilkan mekanisme sentralisasi dan penyeragaman yang bertentangan dengan paradigma multiskala atau keanekaragaman. Lembaga keuangan terdiri atas lembaga keuangan mikro di perekonomian rakyat, lembaga keuangan makro di perekonomian nasional, dan lembaga keuangan dunia (mega) dalam perekonomian global. Keterkaitan vertikal yang sentralisasi di antara lembaga ketiga skala tersebut membuat praktik ekonomi sangat bergantung pada putaran global yang mengakibatkan kerentanan untuk mengalami krisis kemandekan. Lembaga pasar juga seharusnya memperhatikan paradigma multiskala, sehingga antara pasar dunia, pasar regional, pasar nasional, dan pasar tradisional harus jelas perbedaan mekanismenya. Secara fisik pasar saat ini masih merupakan tempat tercampur baurnya berbagai kegiatan mulai dari tempat menjajakan, menyimpan hingga tempat tinggal pedagangnya sekaligus. Padahal dalam perkembangannya ke masa depan pasar bukan lagi untuk menjadi gudang atau pusat pengepakan barang melainkan akan lebih merupakan pusat pertukaran informasi, sementara barangnya sendiri bisa langsung dikirim dari gudang atau produsen ke konsumen. Pasar modern akan menjadi pusat informasi bagi putaran skala ekonominya, sementara pasar tradisional akan tetap bertahan sebagai sarana pertukaran barang sekaligus sehingga secara fisik perlu dirancang kembali agar fasilitas dan fungsi layanannya lebih cepat, efisien dan efektif. Lembaga penyimpanan dan penyampaian, khususnya untuk barang, praktis belum dipahami secara luas terutama berkaitan dengan paradigma multiskala. Hilangnya pengertian lumbung rumah atau lumbung desa untuk putaran perekonomian desa juga adalah akibat hilangnya kesadaran akan keberadaan paradigma multiskala. Upaya pembudayaan atau evolusi nilai merupakan upaya untuk proses kesinambungan yang akan berfungsi membangun kepekaan aspiratif untuk meningkatkan potensi manfaat. Upaya ini juga sekurang-kurangnya memerlukan tiga lembaga, yaitu lembaga keyakinan, lembaga silaturahmi dan lembaga pembelajaran atau pendidikan. Lembaga keyakinan berfungsi seperti bank aspirasi yang akan memelihara arah evolusi nilai mulai dari keyakinan ilahiyah (ketakwaan, moralitas dan akhlak) menjadi aspirasi keikhlasan dan kearifan yang lebih operasional dalam aktivitas pembudayaan sehari-hari. Lembaga silaturahmi atau kenduri berfungsi seperti pasar aspirasi untuk membangun nilai kebersamaan dan sinergi secara berkesinambungan dalam aktivitas pembudayaan sehari-hari. Lembaga pembelajaran berfungsi sebagai gudang dan wahana perpindahan aspirasi, tempat tumbuh kembangnya aspirasi secara berkesinambungan dalam aktivitas pembudayaan sehari-hari. 7. Model Budaya Pengelolaan dan Pendidikan Lingkungan Hidup Model budaya akan menjadi sumber inspirasi dan aspirasi bagi tumbuh kembangnya kreativitas dan evolusi nilai dalam pendidikan sehari-hari. Tanpa sumber inspirasi dan aspirasi, pendidikan menjadi hanya sebatas mesin produksi atau infrastruktur ekonomi semata, bukan merupakan bagian dari ruh kesinambungan membangun peradaban kemanusiaan. Produknya hanya akan berupa keangkuhan ilmu dan miskin manfaat, baik secara individual maupun profesional. Membangun model budaya merujuk langkah berikut: 1. Mengidentifikasi ciri kunci budaya; 2. Mendefinisikan lingkup wilayah; 3. Menciptakan budaya kerja sendiri; 4. Mengevaluasi dengan memperbandingkan terhadap standar global; 5. Menyempurnakan dan percepatan dengan koreksi pada langkah 1, 2 dan 3. Ciri kunci budaya bagaikan unsur genetika dalam kehidupan, artinya merupakan ciri hidup, daya hidup, bahkan mencakup penangkalan terhadap potensi penyimpangan karena semua kecenderungan telah terpetakan dalam ciri kunci budaya ini. Ciri kunci budaya Sunda yang sangat berharga untuk upaya ini adalah rujukan siliasih, siliasah, dan siliasuh yang sebenarnya merupakan kesadaran keterkaitan ekosistem (globalisasi), keterkaitan multiskala (keanekaragaman), dan keterkaitan kesejahteraan (ekonomi jasa), yang sangat sesuai dengan rujukan pendidikan pascamodern membangun keterkaitan alami, hayati dan insani, yang diharapkan mampu memberi dasar kemampuan bersinergi saling mewangikan, siliwangi. 8. Konsep Alam Cerdas Indonesia Fenomena pergeseran lempeng bumi di Indonesia dan kerentanan pergerakan tanah di Jawa Barat memberikan kesadaran akan konsep alam cerdas pertama yang harus dipahami, karena akan melandasi rancangan peradaban kemanusiaan yang akan dibangun di Nusantara. Kearifan budaya Sunda sudah merespon dengan baik kenyataan alam ini dengan membangun rumah-rumahnya menggunakan material bambu yang ringan dan lentur, dan tidak meletakkan pemukimannya di lereng bukit yang labil sehingga mampu meredam bencana ketika gempa bumi terjadi. Kealfaan akan hal ini mengundang bencana alam yang besar dan memaksa penduduknya untuk mengkaji ulang ketahanan papan dalam perjalanan peradabannya. Konsep alam kedua adalah pergerakan aliran udara dan air di Indonesia yang dalam kenyataan alamnya berpulau-pulau besar-kecil dan banyak, yang terbentang di antara dua benua dan dua lautan serta dilintasi garis khatulistiwa. Hal ini menempatkan Nusantara sebagai pusat sirkulasi udara dan aliran air di muka bumi yang terjadi secara bersamaan yang akan berperan penting dan memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi dalam perubahan iklim dan cuaca di dunia, baik global, regional maupun lokal. Sangat layak Indonesia ditempatkan di bagian tengah peta dunia sebagai pusar dunia sehingga mampu menyadarkan masyarakat global maupun lokal akan peran penting alami Nusantara dalam membuka peluang kehidupan di muka bumi ini. Konsep alam ketiga berkaitan dengan kenyataan percepatan pertumbuhan berbagai jenis kehidupan yang tinggi di alam Indonesia. Sesungguhnya hipotesa keterbatasan sumber daya karena pertambahan penduduk, tidak sepenuhnya benar. Kehidupan manusia justru memerlukan kehidupan lain yaitu tanaman dan binatang, sehingga hipotesa yang harus diambil adalah menjamin terjadinya keseimbangan pertambahan penduduk dengan pertambahan kehidupan lainnya. Pertambahan kehidupan tidak semata-mata memerlukan luas bidang lahan sebagai pijakan, namun memerlukan ruang hidup untuk menjamin tersedianya aliran air dan udara sebagai sumber kehidupan. Indonesia dapat diidentifikasi sebagai tempat terjadinya interaksi kuat dua siklus utama ekosistem yaitu siklus kehidupan dan siklus ruang. Contoh alam adanya keterkaitan siklus ruang dan siklus kehidupan ini adalah penggunaan kompos sebagai generator siklus ruang pada olah lahan pertanian. Penggunaan kompos pada tanah merupakan input ruang, terutama ruang berskala mikro dalam jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang beraneka, dan bisa berubah dari waktu ke waktu secara berkelanjutan, yang disebut sebagai siklus ruang. Struktur ruang intensif ini memungkinkan sekaligus fasilitasi air, udara, perkembangan perakaran dan kehidupan biota tanah yang akan berada dalam ruang hidup tersebut secara bersamaan dan berketerkaitan, menyelenggarakan intensifikasi proses dan mekanisme production on demand. Rekayasa ruang dalam tanah ini hanya bisa dilakukan oleh kompos yang mengandung unsur keanekaragaman dan merupakan bahan organik, tidak oleh butiran tanah yang homogen. Ruang antarpori, antarakar, dan antaragregat dalam tanah lebih diperkaya oleh rekayasa ruang yang dilakukan, sebagai pabrik mikro dengan segala fungsi ruang dan prosesnya. Jumlah dan keanekaragaman hayati yang hidup dalam ruang ini berfungsi sebagai para pekerja pabrik nutrisi bagi tanaman atau mahluk lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan biota tanah ini dipicu oleh semaian mikroorganisme lokal yang diaplikasikan pada ruang hidup dalam tanah yang telah tersedia. Sistem kehidupan dalam ruang dalam tanah tersebut kemudian berkembang menjadi suatu siklus kehidupan yang pada gilirannya merupakan suatu siklus nutrisi yang sangat handal di mana tanaman itu sendiri berada di dalamnya. 9. Peran Hutan dan Semak Belukar sebagai Infrastruktur Alam Sejalan dengan peran kompos sebagai generator siklus ruang mikro dalam tanah maka peran tanaman besar adalah sebagai pemicu siklus ruang pada skala makro untuk menegakkan fungsi konservasi baik di hutan maupun di kebun. Keberadaan tanaman besar yang bisa mencapai ketinggian dan diameter naungan tanaman hingga 10 meter, bercabang banyak dan berdaun lebat dengan ukuran perlembar daun hingga 11-12 cm, maka tanaman besar akan mampu berfungsi sebagai tajuk puncak atau kanopi utama tutupan hutan, yang memungkinkan fasilitasi siklus kehidupan yang lebih banyak dan beraneka ragam. Dalam kerangka pikir kesinambungan yang seutuhnya, aplikasi tanaman seperti ini akan membangun ekosistem skala makro sebagai infrastruktur alam untuk menjamin keberlajutan pada skala ekosistem berikutnya yang lebih kecil. Terdapat dua jenis infrastruktur yaitu infrastruktur buatan seperti jalan, jembatan, bangunan, bendungan, dan infrastruktur alam seperti hutan dan semak belukar, danau, sungai, lembah, puncak-puncak bukit, dst. Hal pertama dan utama yang harus direalisir adalah infrastruktur alam, karena infrastruktur buatan tidak akan pernah bisa menggantikannya melainkan hanya untuk memperkuat dan menambah manfaat dari peran infrastruktur alam itu. Dalam kegiatan pertanian untuk pencapaian semua sasarannya peran infrastruktur alam sangat menentukan. Semua masukan primer sistem semitertutup pertanian baik pada skala tanaman, skala kebun, maupun skala global sumbernya hanya dari infrastruktur alam hutan dan semak belukar. Terdapat tiga peran hutan dan semak belukar yang tidak tergantikan, pertama sebagai generator siklus oksigen, kedua sebagai generator siklus air, dan ketiga sebagai generator siklus karbon atau biomassa yang akan menjadi sumber bahan kompos dalam jumlah yang senantiasa tersedia dan dalam ketersebaran yang diperlukan, sebagai pembangkit siklus ruang dan siklus kehidupan untuk kegiatan pertanian. Hutan dan semak belukar, terutama di puncak-puncak bukit dan gunung merupakan generator siklus air yang sangat andal. Tiga perempat dari hujan yang jatuh di hutan dan semak belukar akan kembali diuapkan sebagai awan yang menggantung di atasnya, sementara seperempatnya secara berkesinambungan akan diatur sebagai pasokan air yang ke luar sepanjang tahun dari mata air. Jadi gudang air yang sebenarnya adalah di awan di puncak bukit dan gunung itu, yang hanya bisa dikendalikan dengan menurunkan temperatur muka bumi dan memanfaatkan pengaruh topografi bumi terhadap aliran awan rendah tersebut. Satu-satunya upaya untuk dapat melakukan itu adalah dengan menjaga hutan dan semak belukar dalam ruang yang memadai di puncak bukit dan gunung, lembah dan daerah-daerah antarmuka di mana awan dapat ditimbulkan. 10. Keterkaitan Ekosistem Multiskala Sebaiknya digunakan istilah ekosistem bukan lingkungan. Dengan istilah lingkungan seolah-olah ada sistem dan ada bagian di luar sistem yang disebut lingkungan, padahal yang dimaksud adalah baik sistem maupun lingkungannya dianggap sebagai satu sistem bersama. Jadi lebih tepat menganalisis keterkaitan ekosistem, bukan analisis dampak lingkungan. Analisis dilakukan sebelum intervensi terhadap ekosistem dikerjakan. Sasarannya adalah menjamin kesinambungan ekosistem, memelihara ketersediaan, dan menambah manfaat. Contoh alam suatu ekosistem adalah ekosistem tanaman dengan bioreaktornya. Pengendalian sistem semi-tertutup antara tanaman dengan bioreaktornya dalam tanah dengan siklus ruangnya dilakukan oleh tanaman itu sendiri dengan menggunakan mekanisme eksudasi. Eksudat yang secara fisik berupa bahan kimia padat atau cairan adalah komunikator antara tanaman dengan sistem biota dalam bioreaktornya (siklus kehidupan), sehingga terjadi kesesuaian antara bahan yang diperlukan oleh tanaman dan bahan yang diproduksi oleh biota tanah. Siklus kehidupan dalam tanah cenderung menghasilkan jenis nutrisi tertentu sesuai dengan interpretasinya atas informasi yang dibawa oleh komunikator yang berasal dari tanaman secara berkesesuaian dan berkesepadanan. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia (buatan) terhadap tanaman baik sebagai pupuk maupun pestisida harus dihindarkan, terutama untuk menjaga agar tidak terjadi persenyawaan kimia yang akan mengikat dan menghilangkan fungsi bahan komunikator sehingga informasi dari tanaman tidak dapat sampai kepada kehidupan di dalam tanah, yang akhirnya baik tanaman maupun kehidupan dalam tanah hidup sendirisendiri tanpa sinergi dan memutus siklus kehidupan yang seharusnya berfungsi sebagai siklus nutrisi yang dapat diandalkan. Dalam sistem semitertutup kriteria yang diukur bukan lagi nilai tambah, melainkan nilai manfaat yang didasarkan pada pertukaran aliran di dalam sistem, yang secara termodinamika merujuk neraca exergetik. Terlihat pada ekosistem skala yang pertama (N1) mencakup interaksi antara tanaman dengan bioreaktornya, maksimasi keluarannya berupa produk panen buah didasarkan pada maksimasi masukan berupa make-up kompos yang ditambahkan. Hal ini sesuai dengan pemahaman di lapangan, karena kegiatan pertanian tidak pernah menghasilkan panen NPK tetapi memanen CxHyOz berupa pati atau gula atau selulosa dan sebangsanya. Berarti kalaupun ada input yang diperlukan maka seharusnya adalah penambahan CxHyOz juga. Berupa penambahan C sebagai kompos yang selain berfungsi sebagai generator siklus ruang juga berfungsi sebagai sumber C yang memberikan pasokan energi dan gas CO2 secara setempat pada jumlah dan kecepatan yang bersesuaian dengan kebutuhan tanaman. Penambahan H diberikan berupa ketersediaan air yang tersimpan dalam ruang mikro dalam kompos, dan penambahan O berasal dari udara yang bisa masuk ke dalam ruang mikro di dalam kompos juga. Sementara kebutuhan NPK dan nutrisi mikro dipenuhi sepenuhnya oleh siklus kehidupan yang beranekaragam yang tumbuh dan berkembang dalam siklus ruang yang diciptakan oleh penggunaan kompos, yang merupakan siklus semitertutup antara tanaman dengan bioreaktornya. Pada ekosistem skala yang kedua (N2) mencakup bumi dan cahaya matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi yang juga merupakan sebuah sistem semitertutup. Dengan masukan cahaya matahari inilah biomassa berupa hutan dan semak-belukar dapat tumbuh dan berkembang sebagai sumber bahan kompos untuk menciptakan siklus ruang di dalam tanah, yang pada gilirannya memfasilitasi tumbuh dan kembangnya siklus kehidupan yang dapat mengimbangi kebutuhan nutrisi atau energi yang diperlukan manusia dan pertambahannya. Terbukanya peluang penyeimbangan kebutuhan karena pertambahan penduduk adalah akibat dimungkinkannya pertambahan siklus kehidupan yang dipicu oleh kemampuan pertambahan siklus ruang dalam tanah dengan menggunakan kompos yang bersumber dari pertambahan produksi biomassa di muka bumi ini, yang juga dibangun oleh generator siklus ruang pada skala makro berupa tanaman, pepohonan dan semak belukar yang beragam ukuran, bentuk dan ketinggian dalam biosfer di atas permukaan bumi. 11. Rancangan Penerapan Rancangan penanaman sumber biomassa dan percepatannya, serta pengelolaannya menjadi generator siklus ruang merupakan langkah awal paling penting untuk meningkatkan kegiatan pertanian dan produktivitasnya, untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan dan energi bagi umat manusia. Teknik pengomposan, saung kompos dan pembudayaan pembuatan dan penggunaan kompos secara mandiri (pada lokasi yang terdistribusi) adalah langkah strategis yang harus digarap dengan baik. Demikian juga upaya memperkaya jenis dan ukuran tanaman di hutan dan kebun yang juga merupakan generator siklus ruang pada skala makro harus dijadikan rujukan utama pengelolaannya. Dengan ketiga fungsinya sebagai generator siklus oksigen, siklus air dan siklus biomassa, ruang hutan dan semak belukar benar-benar merupakan infrastruktur alam yang sangat menentukan dan harus menjadi prioritas penataan sistem pertanian dan pembudayaannya. Demikianlah dalam kerangka pikir kesinambungan, teknologi intensifikasi proses yang digagas penulis di atas hanyalah memberikan masukan untuk mendapatkan rujukan prosedur kerja, menyangkut masalah teknis dan tampilan fisik semata. Akan tetapi aplikasi secara lebih menyeluruh akan memerlukan rujukan tentang keutuhan aktivitas semua sektor yang ada, yang tentunya harus sejalan dengan upaya pengembangan kelembagaan upaya tani yang seharusnya. Juga memerlukan rujukan upaya inisiatif pengembangan yang harus sejalan dengan rencana pengembangan pembudayaan upaya tani yang seharusnya juga. Hal ini merupakan arah pengembangan pasca-industri yang menggali kembali nilai dasar pertanian untuk penguatan dan penyempurnaan aktivitas perindustrian. Tentunya hal ini akan menjadi peluang besar bagi peran Indonesia dengan konsep alam cerdas dan kearifan budayanya yang sejalan dengan itu. 12. Menerapkan Tani Ramah Lingkungan di Rumah, Kota dan Desa Lebih lanjut dengan adanya kenyataan ujicoba pertanian di pot yang selalu lebih baik, karena memang rancangan paling sempurna antara tanaman dengan bioreaktornya akan diperoleh dalam pot sementara di lapangan akan melibatkan lebih banyak lagi faktor lain yang akan berpengaruh. Pada kenyataan penggunaan teknologi intensifikasi proses ini di pot mampu memberikan peningkatan produktivitas yang sangat berarti hingga 10 kalinya adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk mengembangkan gagasan pertanian produktif baru, yang lebih dapat diandalkan, lebih mandiri dengan sumber pasokan, dan lebih menjamin kesinambungan. Maksud tersebut memerlukan perancangan gagasan yang lebih menyeluruh dengan pola pikir yang telah diubah. Memanfaatkan sampah kota untuk kompos, dan menggunakan komposnya untuk pertanian di pot dan dilaksanakan juga oleh masyarakat kota, dan bukan saja untuk maksud estetika atau bahan racikan obat atau bahan bumbu makanan tetapi untuk menjaga ketersediaan dan keanekaragaman pangan sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan kesehatan di kota, maka sesungguhnya penulis sedang mulai membangun kembali suatu budaya pertanian kota yang baru, baru dari sisi argumentasi ilmiah namun lebih sesuai dengan kearifan budaya dan kecerdasan lokal yang ada. Pengembangan pertanian produktif di pot bukan saja membuka peluang pembudayaan pertanian di kota, tetapi juga membawa kegiatan produktif secara terdistribusi ke wilayah konsumen, sehingga prinsip production on demand dapat juga dikembangkan secara multiskala, ke skala yang lebih luas. Demikian juga kearifan lokal budaya Sunda yang menunjuk leuweung sebagai infrastruktur alam menjadi lebih realistis, karena akan lebih banyak lahan pertanian tersedia yang alih fungsinya justru untuk penguatan infrastruktur alam menjadi hutan dan semak belukar atau leuweung, yang bisa diterapkan secara lebih terdistribusi baik di dataran tinggi, rendah maupun perkotaan. Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak, atau no forest, no water, no future. 13. Kesimpulan Penegakan asas-asas pembangunan lingkungan hidup merupakan langkah awal dari upaya pembangunan secara menyeluruh dan berkesinambungan di semua sektor pembangunan, bukan sekedar pembangunan sektoral. Asas-asas pembangunan lingkungan hidup bersumber dari hipotesa keilmuan yang menjunjung tinggi keyakinan nilai Kasihsayang dan Kemahaadilan Allah yang Mahakuasa : bertambahnya manusia harus diimbangi dengan bertambahnya tanaman dan binatang atas dasar pengembangan siklus ruang dan siklus kehidupan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterkaitan alami, hayati, dan insani. Membangun Struktur Fisik Ekosistem, Kelembagaan Pemberdayaan dan Pembudayaan dalam kerangka pikir kesinambungan memerlukan komitmen dan kerja nyata semua pihak dalam upaya penegakan kegiatan olah lahan yang ramah lingkungan: o Memulihkan infrastruktur alam untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan dan kemanfaatan daur alami air, udara dan biomassa agar siklus ruang dan siklus kehidupan berlangsung menunjang keandalan kinerja pertanian menyediakan pangan, papan dan energi. o Menggunakan secara maksimal bahan lokal yang strategis seperti kompos dan mikroorganisme lokal serta penguasaan ilmunya untuk membangun kembali jati diri dan kemandirian pertanian. o Menggunakan potensi keanekaragaman hayati untuk keandalan ketersediaan, manfaat dan kesinambungan. o Revitalisasi organisasi dan pengembangan kelembagaan pada semua tahap kegiatan pertanian untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kecermatan layanan kerja, mencakup semua aktivitas sektor secara menyeluruh sehingga mampu mengantisipasi kompleksitas permasalahan dengan upaya penyempurnaan yang berkelanjutan. o Mengelola secara seksama potensi pasar domestik dan upaya cerdas untuk menembus pasar dunia. o Membangun keterbagian yang cerdas dan berkearifan antara kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan maupun bahan energi terbarukan. o Membangun metodologi pertanian adaptif yang sesuai dengan kegiatan pertanian di luar Pulau Jawa yang kurang penduduk dengan di pulau Jawa yang rapat penduduk, antara tani rakyat dalam skala keluarga dengan usaha tani dalam skala perusahaan. o Melakukan upaya pembudayaan kembali kegiatan pertanian pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia di desa maupun di kota sebagai arah peradaban pasca-industri Perlunya Pendidikan Lingkungan Hidup menunjukkan harapan kuat dari semua pihak agar mampu membangun kenyataan perilaku sehari-hari generasi barunya menjadi lebih pro-lingkungan, pro-kehidupan, dan pro-kemanusian sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu keberadaannya sehingga lebih mampu menjamin kesinambungan peradaban kemanusiaan. Identifikasi konsep-konsep alamnya yang cerdas dan kearifan budaya lokalnya yang sejalan akan memahamkan generasi baru Indonesia pada wawasan lingkungan alam, kehidupan dan kemanusiaannya secara praktis dan kreatif pada skala individu, keluarga, kota, negara, bahkan global sehingga lebih mampu menciptakan pemecahan masalah lingkungan yang dihadapinya, serta membangun kembali kualitas kehidupan dan kesejahteraannya secara nyata dan berkelanjutan, sebagai wawasan kebangsaan baru Indonesia. Sumber Pustaka 1. Mubiar Purwasasmita, “Konsep Teknologi”, ITB, 1990. 2. Mubiar Purwasasmita, ”Kajian Fenomenologi Nilai”, Pascasajana UPI, 2000. 3. Mubiar Purwasasmita, ”Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal”, Seminar Teknik Kimia Suhadi Reksowardoyo, Bandung, Desember 2007. 4. Mubiar Purwasasmita, ”Wawasan Lingkungan Hidup Kota Bandung”, Semiloka Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup untuk sekolah dasar dan menengah sekota Bandung, UNPAS, 2008. 5. Mubiar Purwasasmita,” Menerapkan Intensifikasi Proses (PI) dan Produksi yang Berkesepadanan (POD) dalam bidang Pertanian”, Teknik Kimia ITB, 2009. 6. Mubiar Purwasasmita, “System of Rice of Rice Intensification (SRI) : Olah lahan sebagai Bioreaktor- Menerapkan Process Intensification dan Production on Demand dalam Bidang pertanian”, Bahan Seminar yang disampaikan di BALITPA Bogor, Kamis,24 Mei 2007. 7. Mubiar Purwasasmita, ”Wanatani - Upaya Konservasi DAS Hulu Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani”, Lokakarya PLA - Departemen Pertanian, SOLO 15 April 2008. 8. Mubiar Purwasasmita, Hutan dan Semak belukar Infrastruktur Alam, CiomasCiamis 2009. 9. Settle,W., “Living Soil, Training exercise for integrated soils management”, 2000. 10. Christian V. Stevens and Roland Verhe, “Renewable Bioresources, Scope and Modification for non-food application”, Wiley, 2004. 11. P Morrisey, JM Dow, GL Mark, FO Gary, “Are microbe at the root of a solution to world food production : Rational exploitation of interactions between microbes and plants can help to transform agriculture”, European Molecular Biology Organization Reports vol.5, No. 10, 2004. 12. N. Kockmann, “Transport Phenomena in Micro Process Engineering”, SpringerVerlag, Berlin Haidelberg, 2008. 13. Stankievics, Moulijn, “Re-engineering the Chemical Processing Plant: Process Intensification” , Marcel Dekker Inc, New York, 2004. Ucapan terima kasih: Disampaikan kepada teman-teman, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak yang secara konsisten memelopori dan memberikan pemahaman baru tentang keterkaitan alami, hayati, dan insani di berbagai pelosok Indonesia melalui penyebarluasan kegiatan tani ramah lingkungan. * PENGANTAR Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita No forest - no water - no future; hilang hutan hilang air - hilang masa depan; leuweung ruksak - cai beak - manusa balangsak. Itulah aspirasi adat atau keseharian-nya masyarakat Jawa Barat, suatu logika utuh ekosistem yang menjadi basis kerja DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda). Betapa sulitnya kita. Kita dihadapkan pada ancaman hilangnya air di tatar Sunda karena hutannya dijarah dan tidak dikelola dengan baik, sementara banyak pihak yang masih belum tergerak untuk menuju ke arah keutuhan hutan sebagai sumber utama air bagi kehidupan. Demikian pula hal yang dikemukakan Sdr. Gede H. Cahyana dalam buku ini. Keberadaan air di tengahtengah kita, dirundung banyak permasalahan yang mendasar dalam pengelolaannya. Air yang semakin hari semakin langka ketersediaannya itu baru menggugah usaha bagi para pemodal untuk meraup keuntungan yang lebih besar, sementara masyarakat kebanyakan masih terlena, kurang peduli, dan pasrah pada pengelolaan apa adanya. Juga tidak ada program, baik formal maupun inisiatif masyarakat guna memelihara keberfungsian sumur atau tampian di pedesaan. Bahkan di daerah perkotaan pun usaha publik pengelolaan air PDAM dibiarkan kehilangan kemampuannya bahkan jati dirinya. Lalu, bagaimana air yang tersedia ini harus dikelola? Bagaimana organisasi pengelola seperti PDAM itu harus berbuat? Perubahan paradigma apa yang harus terjadi di tataran masyarakat, pemerintahan maupun pengelola air? Maka, ketika Rancangan Undang-undang i Sumber Daya Air (RUSDA) disahkan menjadi Undangundang, kami pun terhenyak karena menyisakan banyak pertanyaan. Ganjalan bagi DPKLTS adalah prinsipprinsip pengaturan kegiatan dan usaha pemanfaatan air, terlebih lagi untuk PDAM atau PAM swasta bila ada kelak. Dalam kaitan dengan itu, buku PDAM BANGKRUT? Awas Perang Air ini minimal mampu membuka mata kita pada masalah air khususnya air minum. Sebab, bukan tak mungkin terjadi “perang” dalam memperebutkan sumber air di masa nanti. Dalam kasus-kasus terbatas, perkelahian fisik dan jebolmenjebol saluran air sering terjadi. Baik di daerah yang sudah punya organisasi air seperti Mitracai di Jawa Barat, Darmatirta di Jawa Tengah, Subak di Bali, maupun yang dikelola secara tradisional. Penulis juga mengangkat perang air antara air minum kemasan (amik) dengan depot air minum kemasan ulang (amiku). Juga potensi perang antara PDAM dan lembaga lain dan bahkan antar-PDAM itu sendiri. Terasa semrawut urusan air ini. Pemerintah, apalagi pemerintah daerah, tentu tidak boleh diam menunggu kasusnya meletus. Di lain sisi, PDAM bisa bangkrut kalau tidak mulai menata dirinya. Secara menarik, penulis menganalogikan upaya perbaikan atau reformasi PDAM dengan piramid. Setiap sudut piramid merepresentasikan pilar P, D, A, dan M. Pilar P untuk pegawai, D untuk Desain, A adalah Area servis, dan M, manajemen. Inilah, menurut penulis, yang harus ditata kembali agar PDAM tidak bangkrut. Kalau itu tidak diindahkan oleh PDAM, juga oleh pemerintah kabupaten/kota, maka bencana massal dapat terjadi. Misalnya, wabah penyakit menular lewat air seperti tifus, muntaber, disentri. Juga penyakit akibat zat ii pencemar dalam air minum. Ini melanda seluruh penduduk kota. Semua orang sakit. Maka, alangkah baiknya PDAM introspeksi dan mau menelusuri pola reparasi piramid yang ditawarkan buku ini. Yaitu, memperbarui kualitas SDM-nya, meluaskan area servisnya, memodernkan desainnya, dan menata lagi manajemennya agar efisien dan efektif. Demikianlah langkah demi langkah yang dilakukan Sdr. Gede untuk membuka wacana publik dalam membahas pengelolaan air bagi kesejahteraan masyarakat kita khususnya di perkotaan dengan PDAM-nya. Dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola air sebagai sarana publik ini, yang masih menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat calon/pelanggan di perkotaan. Mudah-mudahan saja bahasan seperti ini akan terus berkembang, membuka wacana terbuka bagi seluruh stake holders-nya. Jangan sampai kebijakan yang diambil untuk PDAM justru menjadi bumerang bagi kesinambungan pengelolaan air di perkotaan. Kenalilah PDAM dengan segala permasalahannya; tak kenal maka tak sayang. Itu-lah semangat nyata dan manfaat kehadiran buku ini. Maka, DPKLTS sangat mendukung penerbitan buku ini. Buku ini layak menjadi bacaan wajib pejabat pusat dan daerah, anggota dewan, rekan-rekan pegiat di LSM, guru, dosen, mahasiswa, juga pengusaha, apalagi pemilik pabrik yang potensial mencemari lingkungan. Pelanggan PDAM pun hendaklah membaca buku ini. Terlebih lagi orang PDAM, pengusaha amik dan amiku. Semoga buku ini mampu membangun sinergi antara pemerintah sebagai regulator, PDAM sebagai pengelola, dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengontrol. Jangan sampai aset dan masa depan kita digantungkan pada pihak asing. iii Demikian dan selamat membaca. Bandung, Mei 2004 DPKLTS Ketua Dewan Pakar Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita iv Sekapur Sirih Tak putus dirundung malang. Tiada hari tanpa keluhan. Tidak kemarau, tidak musim hujan, pelanggan selalu mengeluh. Ada-ada saja sebabnya. Benarbenar tak habis pikir dibuatnya. Aneh tapi nyata. Semuanya terkait dengan layanan PDAM yang tak jua membaik. Sekali waktu lantaran airnya keruh dan kali lain karena airnya tak mengalir. Sering juga akibat debitnya kecil. Atau, ada pipa bocor di jalan yang tak kunjung diperbaiki. Tarifnya sudah berkalikali naik, tetapi servisnya tetap buruk. Tak terhitung lagi jumlah surat protes yang diterima redaksi koran, majalah, dan radio perihal perusahaan ini. Bayangkan saja, di sela-sela tumpukan utangnya yang mencapai Rp 4,3 triliun (tahun 2003), kita terus saja dihantui (malah disetani & diiblisi) oleh wabah penyakit menular lewat air seperti tifus, disentri, dan diare. Bahkan kolera pun boleh jadi meletus lagi dan merajalela di mana-mana terutama di daerah rawan air bersih. Tapi ironisnya, kasus tersebut justru kerap mengepidemi di daerah yang ada sumber airnya dan/ atau ada PDAM. Kalau begitu apa masalahnya? Begini. Sekarang ini tak seorangpun mengingkari bahwa perusahaan daerah tadi menyimpan seabrek masalah, mulai dari kualitas dan kuantitas air, mutu SDM hingga manajemennya. Pun setumpuk problem lainnya, seperti bentrok alias “perang” dengan warga dan departemen atau lembaga lain. Atau, “perang” ii dengan PAM swasta, pabrik air minum kemasan dan air isi ulang. Perang persaingan ini kian tajam saja. Satu contoh problemnya ialah soal servis. Bisa diduga, semua pelanggannya pernah kecewa walaupun hanya sebagian yang melayangkan surat protes ke media massa selain dikirim langsung ke PDAM. Aneka ragam alasannya. Misal, karena tak pernah kebagian air sehingga meter air dan kran-krannya cuma menjadi penghias rumah sementara tagihannya jalan terus. Atau, airnya sering keruh; jangankan untuk makan-minum, buat mandi saja banyak yang enggan memakainya. Waswas takut sakit; cemas keracunan. Ini menggayut di hati pelanggannya. Bukan itu saja. Mutu administrasinya pun jadi masalah krusial. Gawat dan kacau. Soal tagihan air sekian tahun silam, misalnya. Pelanggan yang terus telaten menyimpan rekening tagihan airnya tentu takkan bermasalah. Lain halnya dengan yang tidak dapat memperlihatkan bukti pembayarannya karena hilang atau sebab-sebab lain. Tak pelak lagi mereka diharuskan bayar ulang. Bayangkan, bayar lagi! Di sini boleh jadi ada oknum yang ingin dapat untung dalam kebuntungan orang lain. Tetapi tak menutup kemungkinan karena ketakbecusan administratif! Problem tersebut kerapkali menimpa pengontrak rumah. Para “kontraktor”. Khususnya rumah yang dikontrakkan dari tahun ke tahun dan berbeda-beda pengontraknya. Sebab, tidak ada estafet rekening air antar pengontrak. Tentu saja bisa terjadi sebaliknya. Pengontrak sebelumnya memang benar menunggak. Hanya saja PDAM belum memutus atau menyegel iii meter airnya sehingga pengontrak berikutnya yang kena getahnya. Sudah pasti rumah yang dihuni oleh si empunya juga bisa mengalami kasus serupa. Yang juga kerap diprotes ialah soal tarif. Tidak jarang terjadi, baru sebatas niat yang dipublikasikan di koran-koran saja kontan diprotes oleh pelanggan. Pelanggan dan LSM bak kebakaran jenggot. Panik. Terjadi tarik-ulur. Ada yang setuju, ada pula yang menentang. Yang emosi pun ada dan menuntut agar PDAM dibubarkan. Adapun kelompok yang setuju biasanya merasa butuh PDAM dan tetap berharap agar ada reformasi di PDAM. Baru setelah itu, kalau kinerjanya belum optimal juga, mereka setuju pada kehadiran PAM swasta dan melikuidasi PDAM. Ini saya kutipkan contoh protes itu. “... naik tarif, saya tidak setuju. Tingkatkan dulu servisnya,” gugat konsumen. “Bau kaporitnya jangan terlalu keras, takut ada dampak buruknya!” katanya lagi. Ada juga yang begini. “…belum pernah sekali pun menunggak bayar rekening. Tiba-tiba ada surat panggilan bahwa saya belum bayar selama dua bulan setahun lewat. Uang tagihannya, bagi ukuran saya, sangat mahal. Ketika ke PDAM mereka meminta saya menunjukkan bukti tagihan itu. Karena teledor, bukti itu tak bisa saya temukan. Tapi PDAM ngotot agar saya melunasi tagihan itu dulu…” Dan..., masih sebendel lagi hal serupa itu ada di koran-koran. Belum lagi di radio dan televisi. Demikianlah faktanya. Sejatinya PDAM memang tidak bernasib mujur seperti perusahaan air minum kemasan (amik) atau depot air minum kemasan iv ulang (amiku). Ia lebih rawan digugat konsumennya. Selain masalah sumber air dan kinerja instalasinya, juga karena jaringan pipanya banyak yang bocor dan jebol lantaran tua atau salah rawat. Namun, kalau diurai lagi dan kita jujur menanggapinya seharusnya masyarakat dan industri pun ikut bertanggung jawab. Sebab, buruknya kinerja PDAM bukan semata-mata kesalahannya melainkan juga kesalahan masyarakat dan industri yang telah memporak-porandakan dan mencemari sumber-sumber airnya. Tak peduli pada konservasi air sekaligus sebagai perusak lingkungan. Di lain sisi, banyak juga yang menginginkan ada privatisasi atau penswastaan di PDAM asalkan tarifnya tak terlalu tinggi. Masih terjangkau oleh warga kebanyakan. Walaupun demikian, ada juga kalangan yang setuju pada tarif tinggi namun disertai syarat: airnya bermutu tinggi dan tak perlu diolah lagi. Tak berbahaya dan siap diminum. Tinggal buka kran dan langsung bisa di-glek. Hal seperti ini, dari kacamata peluang dan tantangan bisnis, tentu baik-baik saja buat kemajuan PDAM. Dan memang itu tujuannya. Penikmat air yang saya hormati, pernak-pernik di atas lalu ditambah dengan paparan tentang piramid PDAM yang terdiri atas pilar P (pegawai), pilar D (desain), pilar A (area servis), dan pilar M (manajemen) sebagai pola reparasinya dan soal perseteruan amik dan depot amiku, dikupas di buku ini tanpa sedikit pun maksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Bagi saya, sebagaimana PDAM, mereka pun rekan dalam perairminuman. Apalagi ceruk pasarnya khas. Tersegmentasi. Hanya saja perlu dibuat aturan v main agar sama-sama untung: produsen untung, konsumen untung, negara atau pemerintah pun untung! Sebagai tambahan dan masih terkait dengan air minum, di Bab 13 saya kupas ringkas tentang upaya membasmi wabah pemula (penyakit menular lewat air, waterborne diseases) seperti tifus, kolera, dan disentri. Dalam kupasan itu saya tulis beberapa cara disinfeksi untuk membasmi kuman/mikroba dalam air. Maka, andaikata air olahan PDAM sudah baik kualitasnya, cukup debitnya dan tersedia 24 jam tentu makin mudah kita menumpas pemula itu. Saya juga mengajak pembaca “terbang” ke abad XIX dengan memakai mesin waktu atau dengan loncatan kuantum, ke sebuah sumur tua di kawasan Broad Street, London, Inggris yang menjadi saksi bisu manakala wabah pemula berjangkit amat sangat di situ. Tak kurang dari 10.000 orang tewas atau 20.000-an orang menemui ajalnya jika wabah akibat polusi di Sungai Thames disertakan. Pada masa itu angka tersebut fantastis benar! Itulah sebabnya kasus tadi dijadikan pilar klasik sejarah perwabahan kolera di dunia. Atau, sebut saja: menjadi pilar pemula. Lalu di Bab 14 saya tambahi dengan persoalan penyakit tak menular lewat air (petamula) yang erat hubungannya dengan zat kimia, baik tidak sengaja karena kasus pencemaran maupun yang berasal dari reagen (zat untuk reaksi kimia) dalam proses pengolahan air. Penyakit jenis ini memang tidak mewabah seperti diare, tapi bisa membunuh secara diam-diam sekian tahun berselang setelah bertumpuk-tumpuk di dalam organ tubuh kita. Timbul pascaakumulasi. vi Adapun di bab pamungkas, yaitu Bab 15, saya hendak “membela” bakteri yang di bab sebelumnya begitu banyak dituduh dan didakwa sebagai biang kerok pemula. Saya percaya betul pada keganasan jasad renik ini. Saya dan keluarga pernah berurusan dengannya. Namun, lepas dari sisi buruknya itu, di bab ini saya uraikan manfaat bakteri bagi kita, bumi dan makhluk lainnya. Akan tampak betapa jasad renik itu begitu besar faedahnya bagi kita dan telah kita akrabi tanpa kita sadari. Lantas, atas segala kekurangan dan kesalahan isi buku ini (apapun ujudnya) sehingga mengakibatkan ketaknyamanan hati pelbagai pihak, maka saya, lewat Sekapur Sirih ini, meminta maaf. Maaf yang setulus-tulusnya. Sebab, dalam buku ini saya hanya hendak menyingkap sejumput persoalan air minum lalu mengabarkannya kepada penikmatnya. Semoga kita belum terlambat melawan potensi bahaya yang ada dalam air minum sembari terus mengupayakan pencegahannya. Itu semua demi kesehatan kita! Lebih jauh lagi saya berharap agar air minum tak akan pernah menjadi “emas” pada masa mendatang. Jangan pernah terjadi. Kalau air saja bisa semahal itu, saya khawatir udara pun khususnya oksigen akan harus dibeli juga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sekali lagi, dalam hal air, kita kaya air. Dan sainstek pun sudah maju. Pasti ada solusinya. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Pandir nian kalau ini terjadi. Kaya air tapi krisis air. Keterlaluan. Sangat-sangat tidak lucu; kecuali kita badut semua. vii Juga, harapan saya, janganlah kita tunduk atas interes anasir lokal-interlokal, nasional-internasional yang haus rakus akan air kita. Jangan jual negeri ini; jangan jual tanah ini; jangan jual pula air ini kepada imperialis berbaju investasi. Investor, kita memang butuh. Tapi jangan yang ingin laba semata di tengah mayoritas rakyat sekarat yang kerongkongannya pun tercekat. Minat kita ialah investasi (investment) yang bukan infestasi (infestation: serbuan, gangguan) atas kedaulatan kita di negeri ini. Masa kita mau dijajah dan menjadi jongos kaum imperialis-materialis itu?! Mari kita acu lagi pasal sosioekologis, yaitu pasal 33 UUD 1945. Kita tafsirkan atas nurani bersih demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelasjelas di sana tertulis bahwa kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi ini adalah milik rakyat. Dan negara wajib sewajib-wajibnya memberikan kekayaan alam itu kepada pemiliknya: rakyat. Negara, lewat tangan pemerintah, wajib mempermudah kehidupan rakyat. Bukannya malah membantai dan menggusur rakyat tanpa mencarikan solusinya. Ini bukan jargon. Tak hendak saya begitu. Sekelebat pun tiada niat jual kecap. Sebab, setuju-menolak, peduli-semau gue, itu terserah Anda, pejabat di legislatif dan eksekutif. Pembaca, sebelum saya pungkasi tulisan ini, saya mengajak Anda untuk menghela napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan pelan-pelan lewat sela-sela gigi (dua rahang dikatupkan) sambil merenungkan satu nukilan berikut, satu refleksi. Lakukan sambil santai saat duduk, berdiri, berbaring. Siangmalam, pagi-petang. viii “Krisis lingkungan terjadi bukan karena pengembangan sains dan teknologi, tetapi hasil dari sikap mental dan life-style (gaya hidup) dunia modern,” tandas E.F. Schumacher. Namun, saya tak hendak membahasnya. Selanjutnya, terserah Anda. Silakan tafsirkan siratan maknanya sebanyak-banyaknya. Kemudian, saya berterima kasih kepada pakar lingkungan Universitas Padjadjaran, Bapak Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, atas masukan dan koreksi yang diberikan. Hal senada saya tujukan kepada sesepuh masyarakat Jawa Barat yang juga menjadi Ketua Dewan Penasihat DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda), Bapak Letjen TNI (purn) Solihin GP, seorang mantan Gubernur Jawa Barat dan Sesdalobang yang peduli pada mutu lingkungan tatar Sunda. Juga kepada Ketua Dewan Pakar DPKLTS, Bapak Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita, yang memberikan seuntai pengantar untuk buku ini. Terakhir, tentu saja terima kasih kepada rekan-rekan aktivis atau pegiat lingkungan di DPKLTS. Akhir kata, semoga buku ini dapat meluaskan kawasan dan wawasan khalayak pembaca, terutama yang tidak berlatar studi Teknik Lingkungan, tentang potensi perang air, perairminuman di Indonesia, baik itu PDAM, amik, amiku maupun PAM swasta bila hadir kelak di kemudian hari. Bandung, Mei 2004 Gede H. Cahyana ix Bingkisan untuk: Bapak & Ibu di Bali, Nuning dan zuriatku: Yasmin, Faris, dan Rehani. x 1 SURAT PROTES BUAT PDAM Di Bandung. Parijs van Java, pada suatu ketika. Waktu itu pagi-pagi benar, nyaris semua orang di perumahan yang lokasinya di selatan kota itu heboh. Ada yang menggerutu, menggumam, kesal, sebal. Juga ada cetusan sumpah serapah. Berkecamuk. Dari siswa sekolah, kaum ibu hingga para bapak yang hendak berangkat kerja. Tak sedikit yang bertanyatanya, gerangan apa yang terjadi. Sebelumnya tak pernah separah ini. Baru kali inilah fatal kasusnya. Terjadi panik masal. Apa pasal? Ini peristiwanya. Semalaman, dari petang hingga pagi, air PDAM di kompleks itu tak keluar setetes pun. Bayangkan, disedot dengan pompa cuma angin yang mendesis. Sessss.... kontan saja penghuninya kalang kabut terutama yang akan pergi karena tidak bisa mandi dan tidak pula mencuci. Untuk minum, air minum kemasan (singkat, amik) dan air minum isi ulang (air minum kemasan ulang, amiku) menjadi pilihan. Mahal, tentu saja. Dengan berat hati dibeli juga. Namun, dalam kemuraman itu ternyata masih 16 ada yang lega lantaran sehari sebelumnya sempat mengisi bak-bak airnya. Tapi, selang sehari, habislah air tampungannya itu karena pasokan PDAM tak jua kunjung tiba. Pukul enam dua puluh menit. Pagi-pagi sekali. Pagi itu juga kasus tadi sudah mengudara lewat radio. Paling tidak, seingat saya, ada tiga atau empat stasiun radio yang membahasnya. Pokoknya ramai. Riuh dan hiruk-pikuk. Sampai-sampai ada penyiar yang kesal. Sebab, berkali-kali Humas PDAM ditelefon tapi tiada tanggapan. Katanya, kalau nadanya tidak sibuk terus, pasti tak ada yang ngangkat. Maka bertubi-tubilah keluhan, umpatan, cacian, makian, hujatan, dan kritikan menyembur dari penelefon lalu lepas ke angkasa lewat pemancar radio, menyusup ke rumah, warung, toko, pasar, dan kantor PDAM (jika tune in di gelombang radio itu, tentu saja). Hingga petang krisis air itu jadi topik bincangbincang hangat kalau tak bisa disebut panas. Benarbenar seru! Hari kedua air belum juga muncul. Cucian setumpuk. Lantai berdaki. Badan bau. Untung ada titik terang. Kata pejabat PDAM, lewat radio juga, ada perbaikan di ruas pipa dan ini berdampak pada aliran air ke sejumlah perumahan. Bagaimanapun, paparnya, ini bagian dari perawatan jaringan distribusi demi peningkatan mutu layanan ke depan. Perbaikan seperti ini, lanjutnya, akan terus ada baik di sistem distribusi, transmisi maupun di instalasi pengolahnya. Waktu itu juga, PDAM yang layanannya baru 53% dari total warga Bandung ini, 17 minta maaf bila setelah perbaikan nanti airnya agak keruh. Tapi tidak lama; berangsur-angsur akan jernih kembali, tuturnya lagi. Empat hari berlalu. Pagi itu, matahari sudah sepenggalahan naik. Sambil buka-buka koran, mata saya terpaku di lembar tengah. Saya terhenyak. Ada surat pembaca di koran lokal Jawa Barat itu yang amat pedas katakatanya. Memerahkan telinga semua petugas sektor keairan ini. Heboh pagi itu isinya. Dan ada belasan pucuk surat senada, tulis koran bertiras terbesar di Jawa Barat itu, masuk ke redaksi. Ini fakta. Surat itu adalah bukti, alangkah luas kegalauan pelanggan akan air bersih. Satu-satu tanpa disuruh, tanpa dikomando, mereka mengirim surat protes lewat koran. Dimuat atau tidak, ditanggapi atau tidak, itu bukan soal; itu soal ke sekian. Yang penting bagi mereka, unek-uneknya bisa lepas lewat tulisan, jadi pelipur lara pereda stres/stress. Syukursyukur dijawab oleh PDAM via surat pembaca juga. Lalu apa kenyataannya? Jauh lebih banyak yang tak dijawab. Cuma dimuat, dibaca dan dilupakan. Bak angin semilir yang lalu begitu saja. Pada kali lain saya sempat membaca surat-surat protes pelanggan PDAM di Jakarta, Tangerang, dan Palembang yang dimuat di koran terbitan Jakarta. Surat-surat serupa itu, saya yakin, banyak bertebaran di kota-kota lain dan di koran-koran lain yang tidak saya baca. Isinya pasti rupa-rupa. Namun intinya tak akan jauh dari kekecewaan atas buruknya layanan PDAM. Kritik yang tak tanggung-tanggung itu tentu tamparan telak bagi segenap pelaku perairbersihan 18 di Indonesia, tanpa kecuali. Mirip cermin retak atau pazel (puzzle), mainan anak balita. Sudah tak utuh lagi potret wajahnya. Centang perenang. Pada satu-dua alinea berikut ini saya kutipkan sepenggal-dua penggal surat-surat pelanggan yang berserakan itu. Isinya saya ringkas sedemikian rupa sehingga fokus ke soal PDAM semata. Adapun surat aslinya tentu saja luas lagi panjang. Ini saripatinya. Mari kita simak lalu diresaprenungkan. Adakah hal serupa itu menimpa kita? Lantas apa dan bagaimana jalan keluarnya? Saya optimis, pasti ada solusinya. Tinggal dicari. Bisa lewat diskusi, textbook, dana, dan kemauan keras! Isinya seperti ini. “…setahun ini, air PDAM yang mengalir ke rumah kami cuma sekali seminggu. Itu pun hanya sepuluh menit dan tidak besar sehingga dalam satu minggu kami hanya kebagian sepanci air. Sepanci! Meskipun jarang mengucur, rekening tagihannya tetap harus dibayar. Ini memberatkan dan tidak adil. Kalau lancar pasti kami mau membayarnya. Berapa yang kami pakai, segitu juga yang kami bayar. Ada hak, ada kewajiban …” Yang lain, seorang pensiunan, menulis begini. “…kami tak setuju kenaikan tarif. Tingkatkan dulu layanannya, baru tarifnya. Apalagi airnya kerap keruh dan tidak pernah mengalir sehari penuh atau semalaman. Paling sering dapat air pada malam hari terutama dini hari, sekitar jam tiga. Jadi kami harus begadang. Capek, bukan? Kalau tidak, terpaksa beli ke tukang air yang sejerikennya, isi 20 liter, seharga 19 seribu rupiah. Kalau sepuluh jeriken atau 200 liter berarti sepuluh ribu rupiah…” Pernah seorang ibu menulis surat yang nadanya begini. “…belum pernah sekali pun saya menunggak bayar air. Tiba-tiba ada surat panggilan bahwa saya belum bayar selama dua bulan, setahun lewat. Uang tagihannya, bagi ukuran saya, sangat mahal. Ketika datang ke PDAM, mereka terus meminta saya untuk menunjukkan bukti tagihan itu. Karena teledor, bukti itu tidak bisa saya temukan. Tapi PDAM ngotot agar saya melunasi tagihan itu dulu…” Demikianlah surat-surat itu. Protes, itu intinya. Kata yang populer pada saat reformasi 1998 ini sarat akan rasa tidak puas. Rasa tidak senang atas sesuatu. Haus perubahan, lapar perbaikan. Temannya tak lain daripada demonstrasi. Hulunya selalu saja masalah rakyat kecil, para wong cilik. Atau, cuma mencatutcatut dan mengeksploitasi nama mereka di semua lini tanpa kecuali seperti politik, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, kebijakan yang tak bijak, tidak populis, dan tidak merakyat. Kita sama-sama tahu. Tahu dari mata kepala ini. Apalagi mata hati, nurani. Bahwa itu terjadi sampai detik ini. Omong kosong kalau ada yang berkata bahwa keadaan sekarang, yaitu pancawarsa kedua pasacareformasi, jauh lebih baik. Apanya yang lebih baik? Apa pembandingnya? Dari paparan di atas bisa kita lihat betapa besar peran media massa dalam soal per-PDAM-an. Kita percaya media massa mampu mencetak opini. Opini apa saja. Yang positif, bisa; negatif juga bisa; yang benar dan yang rumor alias gosip pun bisa. Perannya 20 pun tak sekadar penyebar ketakpuasan warga atas layanan peladen rakyat, aparat pamong praja dan pelaku manajemen di perusahaan daerah, tapi lebih dari itu juga efektif dalam mengubah kebijakan yang tidak populer, tak populis dan berseberangan dengan kemauan kebanyakan warga. Contohnya, PDAM Kota Bandung. Selama lima tahun (hingga Oktober 2001) PDAM ini selalu gagal menaikkan tarifnya karena diprotes banyak kalangan di banyak media massa. Itu terjadi setelah ribut-ribut di koran yang akhirnya berpengaruh pada keputusan DPRD, yakni menolak rencana tarif baru. Semuanya bermula dari protes dan informasi warga yang terus diudarakan di radio dan ditulis di koran-koran. Selain melalui koran, tabloid, dan majalah ada juga protes yang dilayangkan lewat radio dan TV. Sekadar contoh adalah lewat radio swasta Maraghita yang lebih dikenal dengan sebutan Mara. Di acara Info Mara-nya, penghuni 106,7 FM ini siap menerima keluh-kesah orang Bandung. Acara yang mengudara dari Senin sampai Sabtu, tiga kali sehari ini: pagi (06.00-09.00), siang (12.00-13.00), dan malam (18.00-20.00) berupaya menampung semua problem pendengarnya yang disampaikan lewat telefon, surat, faksimili atau SMS (servis madah singkat) seperti fenomena sosial, layanan PLN, Telkom, angkot, kereta api, tol, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan tingkah-polah aparat negara. Dari amatan saya kirakira 40% berkaitan dengan PDAM. Apa yang dilakoni Mara dan media massa lainnya penting bagi masyarakat. Penting buat kita. Kita butuh informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat. 21 Misalnya begini: ketika pipa transmisi air baku dari Sungai Cisangkuy pecah pada Agustus 2001, Mara lalu menyiarkannya kepada pelanggan PDAM Kota Bandung. Waktu itu suplai air tersendat-sendat terutama di Bandung Tengah-Selatan dan sebagian di Timur-Barat. Pelanggan kecewa. Mereka heran dan tak habis pikir mengapa pipa sepenting itu, yang fungsinya bak urat nadi kita, bisa bocor begitu saja. Entah apa dan bagaimana asal-muasalnya, entah siapa yang iseng, tiba-tiba ada seloroh. Ada sabotase. Teror. Pipa itu dibom, begitu isu atau tepatnya gosip yang muncul. Namanya juga gosip, tentu tak dijamin kebenarannya. (Maklumlah, pada Agustus 2001 itu sudah belasan kali terjadi ledakan bom di banyak daerah di Indonesia menyambut duet anyar buah Sidang Istimewa MPR: Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz, pasca-pelengseran Gus Dur atau Abdurahman Wahid). Dengan upayanya, pada saat itu Mara berhasil mengontak manajemen PDAM yang berada di lokasi kebocoran di Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dan menyiarkan perbaikan pipa transmisi berusia 40 tahun itu. Adapun pihak PDAM selain minta maaf di media massa juga menyarankan pelanggannya untuk menampung air yang dialirkan dari reservoir PDAM buat keperluan dua-tiga hari ke depan. Mau tak mau, pelanggan pun akhirnya maklum. Sebab, kalaupun tak rela, mereka tetap tak bisa mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Bisa kita lihat betapa efektif peran media massa dalam mengubah opini masyarakat termasuk untuk meraih haknya. Dalam banyak kasus, media massa 22 bahkan jadi pencetus gerakan rakyat lewat berita dan opininya kemudian menerjang kemapanan dan membuka revolusi. Gerakan mahasiswa 1998 contohnya. (Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya tak kalah banyak seperti memopulerkan hedonisme/budak nafsu, gaulseks bebas, propaganda minor, dusta-publik, dan berkepribadian ganda/split personality, berperilaku menyimpang, hidup ber-MKKN, dll.) Karena itu, khususnya di Bandung, peran media massa (cetak & elektronik) begitu besar. Makanya banyak pelanggan yang lebih suka melapor ke Mara daripada ke PDAM. Alasannya, katanya, lebih cepat ditanggapi. Kalau lewat surat, selain waktunya lama juga tidak langsung diterima oleh direksinya. Kalau lewat hot-line-nya, nadanya sering sibuk atau tidak diangkat-angkat. Namun, jika lewat radio mungkin salah satu direkturnya, atau kepala bagiannya atau petugas lainnya sedang memonitor sehingga segera bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti. Begitulah alasan pelanggan. (Tapi bisa juga terjadi pelanggan malah diomeli oleh sang petugas lapangan karena melapor ke radio, bukannya ke PDAM. Barangkali petugas ini didamprat oleh atasannya karena tidak cepatcepat memperbaiki kerusakan). Dari gambaran di atas bisa kita katakan bahwa gundukan protes tadi tak lain daripada lukisan kelam PDAM sekaligus rekaman kondisi hubungan antara pelanggan dan PDAM yang masih buram, kusam, belum harmonis. Posisi jual belinya belum setara. Dacinnya timpang. Ini mesti dibenahi agar sejajar. Sepadan! Jangan dibiarkan berlarut-larut. Bisa bum di kemudian hari. Meledak. Apalagi protes demi 23 protes itu bukanlah barang baru dewasa ini. Ia sudah lama bergulir di metropolis Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Bisa menular kapan saja ke lain PDAM. Lihat saja nanti. Tunggu waktunya. Disulut sudah sumbunya; sudah hitung mundur, countdown: 4, 3, 2, 1, bum! Satu contoh yang kerapkali diprotes adalah tarif, yaitu kebijakan tarif yang tidak bijak. Semua orang tahu, di sektor apapun: listrik, telefon, angkot, kereta api, dan bis, kenaikan tarif pasti sensitif. Lebih-lebih lagi di sektor yang terpeka, yaitu air bersih komunal yang nyaris tak seorang pun yang tidak membutuhkannya. Protes pun menggelora. Di mana-mana! Saat ini apalagi. Pascarezim Orde Baru ambruk, terutama pancawarsa pertama, setiap ada tarif baru selalu saja meletupkan protes. Gegap-gempita dan anarkhistis. Begitu pun di PDAM. Tak pelak lagi, ini nyaris terjadi di lebih dari 300-an PDAM di tanah air kita, dari yang kaya seperti PAM Jaya di Jakarta sampai PDAM miskin yang untuk sekadar hidup saja masih terseok-seok di pelosok. PDAM miskin inilah yang justru banyak jumlahnya. Berhasilkah protes-protes itu? Dari amatan saya, ternyata belum. Belum signifikan. Tak terasa bagi mayoritas pelanggan. Andaipun ada, saya yakin tak banyak hasilnya. Cuma secuil. Maknanya, kesulitan pelanggan belum juga sirna. Kemalangannya belum beranjak. Bergeming saja. Mirip buah simalakama, kian terjepit. Begini alasannya: jika berlangganan, tutur pelanggan, layanannya tidak memuaskan; tapi jika tidak langganan bisa-bisa malah tambah susah 24 air karena tidak ada lagi sumber air yang lain. Cuma PDAM sumber airnya. Cuma itu. Bayangkan. Siapa yang tak butuh air? Yang benar-benar bersih? Yang 100% laik diminum? Jangankan kita, hewan dan tumbuhan saja perlu air. Apalagi 65% berat badan kita dan kira-kira 75% berat badan anak-anak adalah air. Air! Sekali lagi, air. Mau tak mau, suka tak suka, rela tak rela, harus terus jadi pelanggan setia walaupun kecewa berat. Begitulah keluhan pelanggan terutama yang tinggal di zone rawan air bersih sepanjang tahun. Janganjangan kita termasuk di dalamnya. Itu kenyataannya. Aksi protes sekeras apapun terbukti belum mampu mengubah kinerja PDAM menjadi lebih baik. Demo masif pun tak mempan. Seolah-olah kebal diprotes, tahan digugat. Makanya tumbuh isu minor bahwa sulit dan berbelit-belit bila berurusan dengan PDAM. Capek. Banyak dukanya ketimbang sukanya, sergah pelanggan. Ini buktinya: dari dulu sampai sekarang kondisi pelanggan begitu-begitu saja, tak pernah membaik. Sayangnya lagi, pelanggan pun masih belum mampu berbuat banyak kendati ada landasan yuridisnya: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8/1999 yang telah berlaku efektif per 20 April 2000. Memang, sejumlah kasus gugat perwalian atau class action pernah mencuat di satu-dua kota besar tapi akhirnya pupus ditelan masa. Tiada beritanya lagi; nyaris luput dari pemberitaan nasional. Ini tentu lantaran posisi tawar pelanggan berada di bawah 25 PDAM. Maju kena, mundur kena. Kiri-kanan, atasbawah tak bisa apa-apa. Diam, tak beringsut jua. Kalau demikian keadaannya akankah pelanggan diam saja, pasrah pada nasib? Tak berdaya apa-apa? Pada saat yang sama, apa yang mesti diperbuat oleh PDAM yang katanya menjadi pelayan publik agar misi servisnya tercapai sekaligus menampik tuduhan sebagai perusahaan berkuping tebal, masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Benarkah pemegang otoritas air publik ini yang salah total tanpa senoktah celah kebenaran? Bagaimana caranya agar noda, cacat, stigmanya itu lenyap dari tubuh PDAM? Lalu, tidakkah pelanggan kebablasan dalam memojokkan citra PDAM dan tak senang jika tarifnya naik? Yang pasti, kedua pihak hendaklah mau bekerja sama, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Adil! Adil antara hak dan wajib. Ini posisi idealnya: pelanggan mudah mendapatkan air yang menyehatkan, setidak-tidaknya tidak menimbulkan penyakit; di lain sisi PDAM jangan sampai rugi. Jangankan rugi, impas saja tidak boleh. Harus untung. Namun ada syaratnya. Semua labanya itu wajib digunakan untuk mengembangkan usahanya agar area servisnya kian luas seraya terus serius menata profesionalisme. Kecuali itu, tentu saja buat kesejahteraan pegawai dan sanak keluarganya. Dan ujung-ujungnya tak lain daripada kepuasan dambaan pelanggannya. Karena itu, ketidakberdayaan PDAM selama ini sehingga terus-menerus menuai protes hendaknya dicari sebab-musababnya apakah karena perlakuan pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten yang tidak tepat ataukah lantaran kemampuan dan kecakapan 26 sumber daya insaninya yang rendah. Boleh jadi juga lantaran kuantitas dan kualitas sumber-sumber air bakunya yang betul-betul kritis (debitnya kecil tetapi besar polusinya) sehingga membebani biaya operasirawat instalasinya. Ongkosnya terlalu mahal karena rendah efisiensinya. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak penggerogot kekayaan PDAM. Yang juga harus dicek ialah tarif airnya. Janganjangan terlampau murah dan tak sebanding dengan ongkos produksinya. Makanya perlu ada bincangbincang antara PDAM dan pelanggannya atau antara kepala daerah, DPRD, pakar terkait, dan lembaga perwakilan pelanggan yang betul-betul jadi tameng pelanggan. Jadi pelindungnya. Tetapi sayang sejuta sayang, lembaga atau badan semacam ini belum ada. Kalaupun ada, pelanggan merasa tak terwakili dan aspirasinya tak diindahkan. Sebab, tak ada komunikasi intensif. Malah cenderung mengusung misi dan kepentingannya sendiri. Mencari duit buat dirinya sendiri dengan pura-pura dan seolah-olah membela pelanggan. Padahal itu tak lebih daripada tindakan eksploitasi. Kata orangtua, pengisap darah: lintah! Masalah lainnya adalah keadilan tarif antarjenis pelanggan. Intinya, subsidi silang atas asas keadilan. Pelanggan domestik atau rumah tangga harus lebih murah dibandingkan dengan tarif industri (termasuk home industry), hotel, toko, kantor, dan segmen komersial lainnya. Pelanggan domestik pun masih harus dipilah-pilah lagi sesuai dengan kemampuan ekonominya, termasuk pemberlakuan tarif progresif. Polanya ialah si kaya membantu si miskin. Tinggal dirumuskan alat atau instrumennya yang pas guna 27 pemilahannya itu. Tata-tarif itu pun harus senantiasa mengacu pada kondisi ekonomi mayoritas pelanggan dan fakta debit dan mutu sumber air baku PDAM. Yang terakhir tapi tak kalah penting atau malah jauh lebih penting adalah soal kepastian bahwa tidak ada manipulasi dana dalam wujud apapun. Misalnya, pencurian air dengan segenap modusnya termasuk proyek-proyek fiktif-kolutif yang membuat PDAM sengsara seperti saat ini. Ini memang sulit tapi tidak berarti tak bisa diminimalkan. Malah kalau bisa, dibasmi habis saja. Musnahkan! Kepastian yang lain, coba akhiri kreasi dulangmendulang uang PDAM buat kepentingan pribadi pejabat pemegang kemudi, baik itu kepala daerah dengan jajarannya, anggota dewan, maupun pejabat teras di perusahaan air itu dan juga aktivis LSM. Harapan kita, jika tak bisa 100% bersih mudahmudahan bisa berkurang lantas terkikis pelan-pelan dalam rotasi waktu. Semoga kita bisa berbangga hati atas kejujuran aparat dan kecanggihan PDAM pada saatnya nanti.* Pengada air bersih layak dianugerahi, tidak cuma Nobel, tapi juga bintang. 28 Yang pasti, pelanggan dan PDAM harus bekerja sama. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Pelanggan harus untung dan PDAM pun tak boleh rugi; malah harus berkembang dan makin profesional, makin cakap. 29 6 PEGAWAI YANG CAKAP Pintar. Profesional. Daya saingnya tinggi. Posisi tawarnya bagus. Itulah sifat yang dapat melekat pada manusia. Maka, langkah pertama untuk menata ulang PDAM adalah mereformasi pilar atau sudut P piramid, yaitu pegawai. Biasa disebut SDM: sumber daya manusia atau SDI: sumber daya insani. Inilah otak PDAM. Ini yang membentuk corak wataknya. Merekalah ujung tombak perusahaan jasa pengolah air milik pemerintah daerah (kabupaten atau kota) ini sehingga maju-mundurnya bergantung pada potensi insan-insan tadi. Semestinyalah mereka bahu-membahu, bersama-sama menegakkan pilar PDAM. Sama persis dengan filosofi lidi yang jadi adikuasa saat bergabung menjadi sekepal sapu. Menata sudut P tak lain dari membengkelkan SDI lalu mereparasinya secara total dan sungguhsungguh. Turun mesin, cuci otak lantas memberinya energi, daya, ilmu, dan motivasi supaya bersemangat dan bekerja optimal. 88 Hakikatnya, inilah reformasi kekaryaan, yaitu memperbarui mutu SDI agar mumpuni. Profesional. Tidak hanya cakap otak atau intelegensia tapi juga cakap emosi. Lebih baik lagi kalau mencapai taraf cakap tertinggi, yaitu cakap spiritual. Menjadi orang yang kaya komitmen, senantiasa memberdayakan dirinya sekaligus orang lain. Mengerahkan kekuatan kolektif guna meraih cita-cita diri dan perusahaan, yaitu kesuksesan. Intelegensia terakhir inilah yang diharapkan mampu mengontrol etika, moral, etos kerja, dan spirit pegawai. Ujung-ujungnya tak lain dari peningkatan layanan dan laba perusahaan. Ada kisah yang ilustrasinya seperti ini. Seorang calon pelanggan marah-marah bukan kepalang. Hatinya suntuk. Unek-uneknya lantas dia lepas ke radio lewat acara bincang-bincang (talk show). Dia ditipu. Tertipu sambungan baru yang fiktif belaka. Melapor ke PDAM sudah dilakukannya. Berkali-kali, malah. Adu argumentasi, silat lidah dengan pegawai PDAM pun dilakoninya. Tapi itulah, mentah-mentah ia diperdayai. Habis-habisan lagi! Habis tenaga, habis waktu, habis uang, dan habislah harga dirinya sebab tidak dimanusiakan. Celakanya lagi, sudah hilang ratusan ribu uang panjarnyadiserahkan ke orang berseragam PDAM yang mendatangi rumahnyalenyap pulalah idamannya memperoleh sambungan air minum. Pupuslah harapannya menjadi pelanggan. Raiblah mimpinya memperoleh air kran. Hanya mengurut dada yang bisa ia lakukan. Cuma itulah pelampiasannya. Ini menjadi bukti, meskipun baik niatnya tapi karena 89 kurang informasi dan tidak waspada malah buruk hasilnya. Semoga kasus ini ada hikmahnya bagi kita. Saya yakin kasus seperti itu tidak cuma sekali duakali terjadi. Pasti kerapkali terjadi. Dan tinggi kekerapannya. Bagaikan puncak gunung es, cuma puncaknya yang menyembul di muka laut. Yang tak kelihatan lebih banyak lagi. Di sini saya tidak bicara soal persentase. Sekecil apapun persentasenya tetap tak dapat ditolerir. Apalagi fakta di lapangan berkata lain. Ya itu tadi, banyak kasus serupa namun tidak tersingkap ke permukaan karena, mungkin saja, sang korban malu atau enggan melapor ke polisi, koran, majalah atau radio. Atau, bisa juga lantaran sebabsebab lain yang bersifat pribadi dan rahasia. Namun yang betul-betul aneh, kasus seperti ini senantiasa terjadi di mana-mana padahal direksi dan humas PDAM telah mengumumkan lewat media massa bahwa tidak ada sambungan baru pada tahun itu. Selain di kantor pusat PDAM, di banyak tempat pembayaran rekening pun pengumuman itu sudah ditempelkan dengan jelas, terang, mudah dilihat dan gampang dibaca. Meskipun sudah dipampangkan di lokasi strategis tetapi yang tertipu tetap saja ada. Malah tak berbilang jumlahnya. Seabrek. Kalau begitu, siapa yang salah? Setahu saya dan ini biasa terjadi, yang salah atau disalahkan adalah si kambing hitam. Pada kasus itu dan juga kasus-kasus lainnya, si kambing hitam biasanya laris. Dan yang dikambinghitamkan lagi-lagi orang bernama oknum. Oknum. Sepatah kata ini acapkali dimunculkan buat mematahkan opini yang beredar di masyarakat. Kata 90 ini biasanya muncul jika ada hal yang menyangkut tindak kriminal seperti penipuan sambungan baru, pemutusan aliran air (penyegelan meter air) dan penyambungannya kembali lewat “belakang” atau kasus-kasus pembayaran tunggakan di jalur tol alias tidak resmi. Orang yang terkait itu pun saling lempar tanggung jawab, mengklaim dirinya tidak bersalah sambil menunjuk batang hidung orang lain yang ia anggap bersalah atau dipersalahkan. Barangkali pas kalau kita sebut dengan oknum terorganisir. Adakah dampak buruknya bagi SDM? Saya rasa Anda menjawab, ada! Jawaban saya pun demikian. Dengan selalu mengorbankan oknum dalam setiap kasus berarti, bisa disinyalir, PDAM sebagai institusi seakan-akan tak rela disalahkan. Padahal institusi, di mana saja, tak bisa lepas dari orang-orangnya. Orang bisa mencetak institusi; sebaliknya institusi pun bisa membentuk bahkan mengubah total karakter, watak atau perilaku orang yang bekerja di dalamnya. Insan arif yang bekerja di institusi bobrok bisa drastis berubah menjadi bobrok karena ikut-ikutan rekan sekerjanya, diimbas lalu dibelit oleh jaringan kriminal korporasi masif yang sulit diurai. Coba saja bayangkan, andaikan dari jajaran direksi sampai klinsi (cleaning service) terjerat tindak amoral maka semua pilarnya akan lemah. Remuk lalu ambruk. Dan daya rusak terbesarnya tentulah ada di otak para pejabatnya. Ada pada perilaku pejabatnya. Kini, berbusuk moral seperti itu sudah bukan rahasia lagi. Sudah rahasia umum dan tak terhitung jumlahnya. Macam-macam modusnya. Ini sekadar 91 contoh. Ada oknum: satu atau dua orang, mungkin juga lebih, berseragam PDAM menyambangi rumah pelanggan sambil membawa gulungan kertas berisi angka atau data (entah angka atau data apa) yang ditujukan pada ibu-ibu rumah tangga. Kebanyakan mengaku dari LSM, konsultan PDAM, atau sebagai petugas survei lapangan. Setelah melihat-lihat meter air, bertanya ini-itu dan berlagak sok tahu, ujung-ujungnya selalu biaya. Muaranya di ongkos. Uang. Pungutan liar. Tipuan klasik berdalih memudahkan urusan ini tak lain dari eksploitasi keawaman pelanggan. Apalagi ibu-ibu rumah tangga (terlebih lagi pembantu rumah tangga) enggan bertanya tentang maksud dan tujuan oknum tadi. Dan fakta berkata, mayoritas pelanggan masih awam akan PDAM sehingga perlu terus dicerahkan baik lewat pamflet, seminar, penyuluhan, maupun lewat buku. Ini adalah tugas kita, para insan sanitasi, dan terutama sekali tugas pemerintah. Begitu pun soal pencurian air oleh oknum insan PDAM atau orang yang mengaku dari PDAM. Ada yang terang-terangan dengan cara memotong pipa servis distribusi lalu memasanginya dengan pipa lain dan menyalurkan airnya ke rumah, toko, hotel, atau perusahaan yang membayarnya. Tebaran sambungan ilegal ini disinyalir ada di setiap PDAM. Jumlahnya saja yang berbeda. Ada yang tinggi persentasenya, ada juga yang rendah. Jadi, nyaris tiada PDAM yang bebas dari pencurian air. Ini berarti di setiap kota selalu saja ada pencuri. Ada penjahat. 92 Yang merepotkan, kebanyakan sambungan liar itu sulit dideteksi karena ada di dalam tanah. Lebihlebih lagi kalau sistem perpipaannya tidak teratur, tumpang-tindih, dan semrawut. Jarang atau bahkan mungkin tidak ada gambar utuh yang bisa dijadikan acuan jalur pipa yang tepat, khususnya di kota-kota besar. Hal inilah yang bisa merepotkan semua orang. Ketika ada perbaikan, yang pusing tak hanya buruh gali dan mandornya tapi juga kontraktor dan PDAM. Termasuk warga pengguna jalan. Masih ada dampak lainnya, yaitu sulit mengontrol secara akurat volume airnya yang terjual. (Apalagi kalau tanpa koordinasi antara satu galian dengan galian lainnya. Minggu ini digali oleh PDAM, minggu berikutnya digali lagi oleh PLN, lalu digali lagi oleh Telkom. Begitulah siklusnya. Dan lebih parah lagi kalau kontraktornya bekerja asal-asalan. Bisa berantakan itu jalan). Kita kembali ke soal pencurian air. Ini bisa juga dilakukan di atas kertas, secara administratif. Caranya dengan memanipulasi angka tagihan rekening pelanggan sehingga sekian persen uang pelanggan masuk ke saku oknum. Biasanya ada kerjasama dan melibatkan orang dalam, antara oknum pegawai dan pelanggan atau orang yang diamanati membayarkan tagihan sekelompok rumah dalam lingkup RT/RW. Biasanya terjadi di perumahan yang jauh dari kantor pembayaran rekening sehingga ada yang mengoordinasikannya. Pada kasus ini yang rugi bisa PDAM, bisa juga pelanggan, dan bisa juga keduanya. Dari dua modus pencurian tersebut sungguh luar biasa hasilnya: air produksi yang hilang mencapai 93 40-50%. Setengah dari total air olahannya. Nyaris sama dengan penghasilan PDAM per bulan. Angka ini begitu besar jikalau dibandingkan dengan jumlah air olahannya. Nilainya bisa miliaran rupiah dalam sehari. Satu hari! Boros dan mubazir. Atau, apakah ini disengaja oleh kalangan terkait, oleh penguasa daerah setempat demi alasan tertentu? Katakanlah, alasan politis, keamanan atau imej (image) dari donor dan investor? Selain pelakunya, pasti Tuhan sematalah yang tahu. Ada lagi masalah parah lainnya. Misalnya, soal proyek-proyek penyediaan air bersih untuk kaum miskin di berbagai daerah berdana miliaran rupiah. Ini kerap melibatkan, selain pejabat di eksekutif dan legislatif, juga konsultan-konsultanan yang tak jelas juntrungannya. Kinerjanya tidak memuaskan dan kemampuannya dipertanyakan. Mereka lebih mirip konsultan gurem atau LSM benalu yang perlahanlahan mengisap PDAM sembari berteriak-teriak atas nama konsumen, berkoar-koar layaknya pendekar pembela rakyat sambil memenuhi kocek-koceknya dengan duit proyek-proyekan. Makanya tak usah heran kalau banyak pipa, hidran umum, dan tempattempat MCK yang buruk mutunya. Bobrok. Cuma seumur jagung. Sekali jadi lalu mati dan memfosil. Sekadar tugu atau monumen kesaksian MKKN anak negeri ini. Pelanggan sejati, begitulah penyakit kronis yang bersangkut-paut dengan profesionalisme insan-insan PDAM. Profesionalismenya itu pun bisa kita kaitkan dengan semangat kerjanya. Entahlah, apakah mereka 94 bekerja sepenuh hati pada jam-jam kerjanya ataukah sama-sebangun dengan pegawai-pegawai negeri di kantor pemerintah lainnya yang, kata orang-orang, pola karibnya ialah datang, duduk, baca koran, tulistulis, rehat lalu pulang. Kemudian, awal bulan dapat gaji tapi merasa tidak cukup lantas minta naik lagi sementara negara tak berdaya untuk memenuhinya. Padahal beragam pajak & retribusi telah dibuat (atau dibuat-buat) dan diterapkan sampai-sampai menjerat leher rakyat miskin nan kurus kering. Sedihnya lagi, separo dari pajak itu, kata anggota dewan, dikorupsi pejabat di kantor perpajakan. Pagar makan tanaman. Tak berlebihan apabila ada beberapa pakar ilmu pemerintahan yang mempredikati PNS itu dengan julukan brigade 804: datang jam delapan, kinerja nol besar, pulang jam empat sore. Malah banyak yang mangkir, tak bekerja tanpa alasan jelas. Terlebih lagi pada liburan massal seperti hari raya dan tahun baru. Banyak yang bilang lembek disiplinnya, tapi keras malasnya. Sekadar contoh, saya kebetulan membaca Metro, 30/9/03. Judul beritanya, PNS Cianjur Sering Mangkir. Dan di Metro, 28/2/04: Puluhan PNS Ditangkap Saat Keluyuran di Ciamis. Juga ada yang main gaple saat ngantor. Maka dengan serta-merta warta teranyar itu mengisi buku ini agar dijadikan pelajaran. Hikmahnya diambil. Tentu saja temuan GOWA (Government Watch) itu hanyalah sebuah sampel. Artinya, di lain tempat pasti terjadi hal serupa. Sudah rahasia umum. Tiada yang mampu membantahnya. Adakah yang bisa mengelak? Tengok saja di supermarket, mal ataupun 95 pusat belanja dan bermain lainnya pasti ada orang berseragam pegawai yang asyik “bekerja” pada jamjam kantor (bagaimana dengan PNS yang tidak di bawah pemda?) Untuk yang satu ini masyarakat nonPNS wajar bertanya, apakah siklus kerjanya identik seperti itu atau lebih parah lagi? Kalbulah yang jujur menjawabnya; nurani tidak bisa berbohong. Letupan suara hati tak mungkin dusta, bukan? Namun demikian, kendati berita seperti itu telah menjadi cap buruk atas kinerja PNS yang kian santer disingkap media massa dari dulu sampai sekarang, saya masih yakin bahwa tidak semua insan PNS itu, khususnya insan-insan PDAM, berperilaku begitu. Saya pun sangat-sangat tidak ingin menuduh bahwa semua pegawainya begitu. Saya masih optimis. Saya yakin, betul-betul yakin, masih ada PNS yang tinggi dedikasinya, mengemban amanahnya, mau bekerja keras. Minimal buat rakyat yang perlu layanannya lewat curahan ilmu, waktu, daya pikir, tenaga, dan kemampuannya. Memang, orang-orang seperti itu pada zaman edanisme ini adalah orang-orang langka tapi nyata. Insan profesional. Hanya saja personil seperti ini di sejumlah PDAMjadi tidak di semua PDAMbelum berpeluang tampil menjadi pejabat yang mereparasi PDAM. Kebanyakan masih berkutat di manajemen menengah-bawah dan tidak (belum) meraih peluang promosi. Karena itu, sayang sekali kalau insan-insan profesional seperti itu tak diberi kesempatan untuk memajukan PDAM, sementara potensinya sudah tak diragukan lagi dan etos kerjanya telah teruji. Yang 96 rugi pastilah perusahaan, baik rugi duit maupun rugi spirit dalam bekerja. Malah yang kerap terjadi, akibat adanya politik suka-tak suka atau like-dislike, mereka kebanyakan dikebiri. Dibonsai oleh atasannya. Karirnya memang tidak dibunuh tapi tidak diberi peluang berkembang menjadi besar. Mereka diarahkan menjadi orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang luar biasa prestasinya lantaran takut prestasi insan-insan cakap ini dapat menggeser posisinya kelak. Pejabat seperti ini, yang hanya ingin enak sendiri, adalah manusia paling egois di jagat ini. Makanya, kalau tidak bisa dinasihati, ya basmi saja. Jangan pernah diamanahi jabatan atau posisi penting apapun kalau tidak mau perusahaan menjadi hancur. Sebab, pada akhirnya, yang rugi masyarakat juga. Tentu saja kasus di atas tidak berdiri sendiri tapi erat kaitannya dengan para pejabat di eksekutif dan legislatif. Nuansa politisnya kental sekali. Jabatan penting di perusahaan daerah seperti itu, kita tahu, sangat bergantung pada kepala daerah, yaitu bupati walikota dan juga lembaga kontrolnya, yaitu DPRD. Merekalah yang benar-benar bisa mewarnai PDAM. Mau hitam, bisa; mau putih, bisa; mau pelangi bisa; mau tanpa warna pun bisa. (Saya jadi teringat pada tutur kata seseorang. Kita, demikian ujaran orang itu, sebagai orang yang peduli akan gerak maju semua perusahaan daerah, BUMN, dan mekanisme birokrasi daerah dan pusat, hendaklah senantiasa memilih orang yang amanah, jujur dan adil. Jangan yang cacat moral dan tak jelas juntrungannya). 97 Atau, jangan-jangan pegawai profesional itu telah langgeng terkungkung dan dibelit oleh tentakel “gurita” di dalam labirin korporasi yang pekat dan jenuh akan orang-orang berbusuk moral. Andaikata sinyalemen ini benar, seperti halnya Anda, saya pun berdoa semoga tak lama lagi terjadi perubahan di PDAM dan di instansi pemerintah lainnya agar pembaruan segera terwujud. Lalu siapa yang memulai? Tentu saja kita semua. Dan tak usah muluk-muluk. Mulailah dari diri sendiri sambil berupaya mengubah lingkungan dan sistemnya. Sampai di sini bisa kita pahami, betapa penting peran pegawai terutama karakternya. Sikap jujur, cakap, dan etos kerjanya yang tinggi, bila ini benarbenar mendarah daging memang bukan main. Sebab, kemajuan bergantung pada kinerja dan moral SDM atau SDI. Merekalah pengoperasi dan pengatur benda-benda mati seperti mesin-mesin, dosing zat kimia, pintu air, katup, dan tata-kerja unit instalasi agar berfungsi optimal dan menghasilkan air layak minum. Mereka pula yang mengelola dana miliaran rupiah dalam sebulan hasil berjualan air. Termasuk membagi-baginya menurut alokasi dalam rencana pengembangan perusahaan. Bisa diduga apa yang akan terjadi kalau dana itu dikelola oleh orang yang khianat dan culas!? Kemudian, yang juga sering disoroti adalah etos kerja untuk senantiasa bekerja sama dalam tim yang akur. Saling dukung antarkaryawan. Mau menerima gagasan dari rekan kerja meskipun sang penggagas lebih muda dalam hal usia dan ilmu. Sebab, mutiara 98 ilmu bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Jangan sekali-kali ada nafsu untuk sikut sana-sikut sini tapi berkompetisilah secara sehat untuk menjadi pegawai yang betul-betul berkompeten di bidangnya dan mampu mengukir prestasi. Misalnya, jabatan yang erat kaitannya dengan Teknik Lingkungandunia akademis paham bahwa PDAM ditulangpunggungi oleh sainstek ke-TL-an sebaiknya dilimpahkan kepada orang yang berlatar TL. Lebih bagus lagi orang TL yang tinggi daya atau kemampuan manajerialnya dan memiliki intuisi dan insting kepemimpinan, leadership! Apalagi kalau diikuti oleh moral yang baik. Tentu inilah insan yang mendekati ideal, yang tak cuma cerdas otaknya tapi juga cerdas spiritual (termasuk di dalamnya cerdas secara emosi). Bagaimana kalau tak ada sarjana TL di PDAM? Sudah pasti boleh-boleh saja orang lain asal paham soal ke-TL-an, berpengalaman di bidang ke-TL-an, dan berkemampuan manajerial dan kepemimpinan. (Lewat buku ini saya menggugah dan menghimbau alumni baru TL agar mau bekerja di PDAM untuk mengelola air minum bagi masyarakat. Daya pikir Anda diperlukan sekarang. Ayolah! Siapa lagi yang bakal memajukan PDAM kalau bukan Anda, wahai alumni TL. Percayalah, Anda pasti bisa!) Oleh karena itu, sebagai perusahaan, sekalipun perusahaan daerah yang kerap dicap tidak bonafid, tidak bermutu, underdog, bahkan perusahaan kelas teri, semestinya PDAM memiliki visi profesional, unggul kualitas personalnya, dan ahli dalam ilmunya 99 seperti yang dikembangkan oleh perusahaan swasta mapan dengan prinsip “orang tepat di tempat yang tepat, the right man on the right place”. Peduli amat dengan sindiran seperti itu. Jangan terlalu diambil pusing. Anggap saja gesekan untuk maju. Bukankah kita perlu gesekan atau friksi, kata Newton, untuk bergerak? Seperti ditulis di alinea di atas, insan yang hampir ideal ini berpeluang memajukan perusahaan, bukan menjadikannya ambruk terpuruk. Maka, mau maju atau mundur atau mau hancur sekalipun itu semua kembali pada orang-orang yang mengelola perusahaan, yaitu pegawai. Pegawai itu mirip orang yang menggenggam pistol. The man behind the gun. Kalau baik orangnya, tentu baik pula hasilnya. Kalau buruk orangnya, buruk pula perusahaan itu. Maka terbukti, pembinaan pegawai yang terkait dengan jabatannya menduduki kursi penting dalam pilar PDAM. Selanjutnya, jabatan tersebut hendaklah dipadupadankan dengan tingkat kebutuhannya dan besarkecilnya perusahaan. Di PDAM besar berpelanggan ratusan ribu unit tentu ketersediaan jabatannya lebih besar dibandingkan dengan PDAM yang pelanggannya cuma belasan ribu unit. Tetapi yang pasti, dan ini terbukti, kebutuhan tenaga ahli perairminuman ini akan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Apalagi kalau PAMS buat kalangan terbatas benarbenar hadir pada masa mendatang dengan tetap mengindahkan pasal 33 UUD 1945, tentu kebutuhan sarjana teknik ini makin banyak lagi. 100 Namun begitu, harus diupayakan agar jabatan struktural jangan sampai gemuk agar terhindar dari beban berlebih yang percuma. Struktur organisasi sebaiknya ramping-ramping saja. Hindarilah ‘arisan’ jabatan tanpa mengindahkan kompetensi atau kapabilitas. Apalagi kalau cuma diada-adakan sekadar bagi-bagi jabatan antarteman. Semua kawan diberi posisi syahdan yang di luar ilmu dan kecakapannya. Membabi buta. Beraji mumpung. Atau, penyakit kronis lainnya, yaitu nepotisme: memilih orang-orang dekat atau yang kira-kira bisa disetir dan penurut. Ini tidak sehat. Makanya pakar manajemen bilang, mereka adalah orang-orang tak tahu diri; ambisius nista! Itu ditempuh hanya untuk menancapkan kuku-kukunya agar langgeng berkuasa tanpa peduli pada prestasi, kerja keras, nasib orang lain dan perusahaan. Pola pikir di atas amat riskan. Mesti dihilangkan karena dapat membunuh organisasi baik perusahaan swasta (CV, NV, firma, PT), BUMN, BUMD, LSM, koperasi, yayasan, lembaga kursus, dan pendidikan. Paling tidak, bisa membunuh karakter dan spirit kerja pegawai. Jika ini melanda PDAM, semuanya bakal rugi: insan PDAM, pelanggan, rekanan konsultan, kontraktor, vendor, dan pemda. Bahkan menimpa kaum akademisi, dosen dan mahasiswa, jika PDAM bangkrut. Sebab, tak ada lagi peluang magang, praktek dan riset di PDAM. Kalau demikian, percayalah. Kita rugi, langsung tak langsung. Orang Betawi bilang, sudah kagak ketulungan lagi. Ente-ane bakal apes. * 101 Ibaratnya, pegawai adalah orang yang menggenggam pistol. The man behind the gun. Kalau baik orangnya, baik pula hasilnya. Kalau buruk orangnya, tentu buruk pula perusahaan itu. Agar segar, airlah penawarnya. 102 7 DESAIN YANG INOVATIF Kekaryaan, kepegawaian, SDM, atau SDI. Itulah reformasi pertama. Dan selanjutnya,......? PDAM, kini, mengemban reformasi rekayasa. Pembaruan desain, baik desain instalasi pengolahnya maupun perpipaannya, yaitu transmisi dan distribusi, termasuk volume dan lokasi tandon-(tandon) atau reservoir-(reservoirnya). Ini tentu pekerjaan besar, rumit dan sarat modal. Dibutuhkan konsultan yang kepakarannya tak diragukan lagi dan penyandang dana (investor) dari dalam dan luar negeri. Tentang hal ini, yaitu rambu privatisasi dan kemitraan antara PDAM dan swasta saya uraikan di Bab 11. Tetapi, kalau kita mau dan serius bisa saja dana itu berasal dari APBN dan/atau APBD. Bukankah ini tugas negara atau pemerintah yang berkuasa baik di pusat maupun daerah untuk menyediakan air bersih? Apalagi tak seorang rakyat pun yang tidak perlu air. Yang kaya dan yang miskin, sama saja, semuanya butuh air. Jadi, harus ada teknologi yang mampu menyediakan air bersih 24 jam per hari, tujuh hari per minggu. Maka, apabila kita banding-bandingkan, 103 nilai penting desain ini setara dengan SDM, pilar pertama piramid. Kalau diandaikan dengan organ tubuh kita maka instalasi pengolah air dan perpipaan PDAM serupa dengan jantung, aorta, dan arteri atau urat nadi. Dari “jantung” inilah air dialirkan (dipompa atau secara gravitasi) ke pelanggan. Jika jantungnya sehat, sehat pula pelanggannya. Begitu sebaliknya. Jantunglah kunci mutu dan tolokukur atau barometer air olahan PDAM. Dan ini tak lepas dari “urat nadinya”. Lewat urat nadi atau pipa-pipa inilah air PDAM masuk ke rumah-rumah pelanggan. Jikalau pipa-pipanya bocor, sambungannya tak kedap air, alirannya tak kontinu atau sistemnya tak laik guna maka tercemar lagilah air olahannya itu. Mutunya memburuk, nyaris sama dengan air yang belum diolah seperti air sungai, danau, atau waduk yang penuh bakteri, kaya pencemar. Jangan-jangan malah jauh lebih parah. Lantaran itulah, pilar kedua ini, yaitu reformasi desain menjadi signifikan bukan hanya karena debit air bakunya yang kian susut melainkan juga karena mutunya yang kian buruk akibat polusi yang terus menderanya sehingga airnya kaya akan pelbagai zat berbahaya dan beracun. PDAM mau tak mau harus legowo mengakui bahwa jantungnya atau teknologi pengolah airnya sudah tidak mampu lagi menangani zat seperti logam berat, pestisida, sabun, deterjen, nitrat, nitrit, dan lain-lain yang justru makin tinggi konsentrasinya dalam air baku. 104 Artinya, sekali lagi, pada masa sekarang ini ada PDAM sudah dalam taraf mengolah air baku yang sekualitas dengan air comberan. Maka logikanya, PDAM harus membuat unit pengolah yang mampu mengolah air “comberan” itu. Masalah yang sedikit berbeda dialami oleh PDAM Banjarmasin. PDAM ini pernah tidak berproduksi karena kadar garam air Sungai Barito dan Martapura melebihi 250 mg/l. Kualitas air sungai itu memang dipengaruhi pasang surut air laut karena landai kemiringannya. Dan ini berlangsung setiap tahun terutama saat kemarau. Buruknya kualitas air baku dan terjadinya kasus pencemaran lagi (rekontaminasi) air olahan PDAM di sistem distribusi itulah yang menyikalbakali ide reformasi desain instalasi dan distribusi. Mesti ada pembaruan! Jangan berkutat dan berputar-putar dari sistem itu ke itu saja. Secara logika saja tidak dapat diterima; masa sistem pengolah air lima puluh tahun lalu ketika nyaris tak ada pencemaran disamakan dengan air baku sekarang yang kaya pencemar? Pun begitu dengan pipa distribusi. Selain bahannya bebas zat racun, pemasangannya harus kedap air atau tidak bocor. Dan ada cara untuk menahan air kotor agar tidak masuk ke pipa, terutama ketika ada perbaikan. Bagaimanapun dan apapun alasan PDAM, hal ini mendesak. Hendaklah segera diantisipasi, jangan sampai terlambat. Bisa dirintis mulai sekarang. Dan pasti bisa. Inovasi desain habis-habisan ini selekaslekasnya dikibarkan menyusul maraknya kasus poludi mana-mana, dari kota sampai desa, dari darat hingga laut. Terlebih lagi banyak ada data dan bukti 105 soal keluhan pelanggan PDAM yang dirilis di media massa setiap hari. Di bawah ini saya kutipkan satudua kasusnya, sebagai contoh. “Air PAM (masih) kotor dan berbau!” Inilah judul berita yang disajikan Republika, 26/2/00 untuk menanggapi hasil jajak pendapat (polling) tentang kualitas air dan keluhan pelanggan PAM Jaya di lima wilayah DKI Jakarta, menyusul kegiatan serupa tahun 1997. Dari 474 responden, tulis koran itu, keluhan terbanyak (62,4%) adalah air ledeng sangat kotor dan keruh. Angka ini naik 12,4% dari tingkat keluhan tahun 1997 sebesar 50% (228 responden). Disusul keluhan bau kaporit (41,1%), debitnya kecil (34,2%), tidak mengalir (30,4%) dan rasanya asin (3,4%). Selain itu, ada 0,2% responden yang bilang airnya beracun dan 14,8% yang tidak punya keluhan berarti. Maka disimpulkan, kualitas air PAM Jaya yang sampai ke pelanggannya makin buruk. Lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kecuali jajak pendapat di atas, saya kutipkan juga beberapa kualitas air PDAM yang sempat dimuat di media massa. “40% Air PDAM Indonesia Tercemar Bakteri E. coli,“ tandas Pikiran Rakyat, 21/3/01. Bahkan ada yang marah-marah lantaran air ledengnya bercacing-cacing kecil. Yang lain berkata bahwa airnya cepat berubah dari bening menjadi kuning. Saat yang lain airnya terlalu keruh sehingga gentong air mesti sering dibilas-kuras. Republika, 14/8/01, pernah menjuduli beritanya, “Air PDAM Surabaya Masih Mengandung Racun”. Jika ini kenyataannya lalu apa komentar PDAM? 106 Klaim-klaim itu tidak diperpanjang lagi di sini. Terlalu banyak. Yang ingin saya katakanterlepas dari komentar dan pembelaan PDAMadalah bahwa pelanggan PDAM banyak yang hanya tahu air yang mereka terima buruk kualitasnya. Mereka tidak tahu dan mungkin saja tak peduli apa biang keladinya. Apakah lantaran sistem pengolahnya yang buruk ataukah sistem distribusinya yang kacau-balau? Kata anak baru gede, EGP (emang gue pikirin). Ini yang menggayut di benak mayoritas pelanggan. Tapi tidak bisa begitu saja mereka disalahkan; apalagi banyak yang sudah melunasi rekeningnya setiap bulan. Sebaliknya saya yakin 100%, PDAM pun akan membela diri dan mengklaim bahwa air olahannya sudah bagus (jernih) sembari jari telunjuk kanannya mengarah ke tangki atau reservoir airnya. “Saudarasaudara bisa lihat. Itu airnya. Jernih, kan?” mungkin itu kata pejabatnya. Pada saat yang sama pelanggan ikut-ikutan menunjuk ke air tampungannya di dalam gentong yang tak sesuai dengan harapannya. Inti masalahnya tak lain dari beda mutu antara air olahan di reservoir PDAM dan air yang sampai di rumah pelanggannya. Di PDAM sangat jernih tetapi di bak dan gentong pelanggannya malah keruh dan bau. Sampai-sampai ada yang protes lantaran airnya bercacing! Ini bukan soal sepele. Beda mutu ini tak bisa dipandang enteng. Dan PDAM, ini logikanya, wajib bertanggung jawab atas bahaya yang mungkin timbul dari air pasokannya itu. Lebih-lebih lagi tarif airnya terus naik dan terasa mahal di kantong rakyat. 107 Pelanggan yang saya hormati, di atas tadi sudah disitir bahwa sumber air baku PDAM kita khususnya sungai telah banyak yang tercemar akibat tingkah polah manusia, baik dari limbah domestik maupun industri, baik padat maupun cair. Tercemar berat. Sungai Cikapundung di Bandung contohnya. Sungai berhulu di daerah wisata Maribaya ini sudah kotor. Padahal 800 l/d (600 l/d diolah di IPAM Dago dan 200 l/d di IPAM Badaksinga, dalam areal kantor pusat PDAM Kota Bandung) airnya disadap untuk air PDAM Kota Bandung. Dan kini sungai sepanjang 28 km itu debitnya sudah jauh berkurang. Kasus serupa terjadi di Citarum, sebuah sungai yang merupakan “muara” dari Sungai Cikapundung. Parahnya, tak hanya limbah domestik, industri, dan pertanian yang mencemari Citarum tapi juga dari vulkanik seperti Gunung Tangkubanparahu di utara dan Kawah Putih di selatan Bandung. Lengkaplah sudah sumber-sumber pencemarnya. Pantas pulalah warganya yang mengaku Masyarakat Cinta Citarum (MCC) begitu gusar kemudian berupaya mencarikan solusinya. Wujud forum semacam ini, kendati telat, tentu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seingat saya, dulu pernah digelar diskusi dalam rangka Hari Air Sedunia ke-10 pada 22 Maret 2002. Hasilnya apa? Yang pasti, polusi di Citarum itu tak jua mau peduli. Makin berat dan pekat saja. Kental. Itulah faktanya. Pencemaran seolah-olah tradisi yang menyita perhatian kita dari dulu sampai kini. Padahal ada Program Kali Bersih. Dan banyak lagi program lainnya. Tapi kenapa pencemaran terus saja 108 terjadi, tak kunjung usai? Jangan-jangan tidak akan pernah selesai. Ini bahaya. Dari tilikan ekologis, ia tak hanya merusak citra estetika perairan tapi juga membasmi biotanya dan mengancam kesehatan kita baik langsung maupun tak langsung, bersifat kronis maupun akut. Makanya, tak sedikit kalangan yang meragukan kinerja Gerakan Cikapundung Bersih (GCB) lantas menganggapnya sebatas slogan. Gerakan yang dicanangkan pada 7 Februari 2004 itu diduga akan idem ditto, sama saja hasilnya dengan MCC. Nasibnya ditengarai setali tiga uang dengan Gerakan Citarum Bergeutar [bersih, geulis (Sunda: cantik), lestari] yang muncul tanggal 14 Agustus 2001, yaitu tanpa hasil optimal sementara projek miliaran rupiah telah digulirkan. Banyaklah yang menyambutnya dengan dingin-dingin saja. Malah ada yang “gatal” seraya menantang. Ayo “bertaruh”, katanya, akankah tahun 2010 nanti sungai pembelah kota Bandung itu jadi berhiber (bersih, hijau, berbunga)? Ataukah makin berhiber (bersampah, hitam, berbau)? (NB. Limbah padat, yaitu sampah di Sungai Cikapundung, bukanlah hal tersulit yang harus ditangani. Justru limbah cairlah, yaitu air limbah yang paling sulit dipantau. Sebab, sepanjang sungai tersebut banyak sekali sumber air limbah domestik dan industri. Makanya, tidak cukup hanya dengan pembersihan sampah setiap bulan berdana jutaan rupiah. Tapi harus “menyusup” juga ke pemukiman dan industri yang memang terpotensial meracuni Cikapundung. Ada ungkapan bijak: kalau ingin 109 “membersihkan” bagian bawah, harus “dibersihkan” dulu bagian atasnya. Dalam hal ini, Cikapundung adalah bawah dan pemukiman-industri adalah atas. Mulailah dari atas lantas turun ke kali). Pembaca, sebentar lagi di bawah alinea ini saya beberkan lagi secara ringkas tentang sungai Citarum tersebut plus tiga waduknya, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang tercemar berat. Kronis dan krodit, keluh warga di sekitarnya. Yang kerap kita dengar ialah bencana Saguling atau gegar Saguling. Ribuan ton ikan di waduk teratas dari tritunggal dam mega di Citarum itu dijemput kematian. Karena terjadi berulang-ulang maka disebut siklus Saguling: daur kematian ikan Saguling. Dan itu telah menuai kritik tajam dari pakar dan mukimin di sepanjang Citarum dan ketiga waduknya itu. Namun, sebelum ke Citarum, kita bertandang dulu ke daerah yang kena kasus serupa dengan gegar Saguling, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara. Di danau berpulau Samosir ini pernah ada demo besarbesaran dan menasional, melibatkan pabrik pulp dan kertas PT. Inti Indorayon Utama di Sosor Ladang, Porsea, Sumatera Utara. Waktu itu pemicunya, selain politis-ekonomis, adalah mutu efluen IPALnya yang mencemari Danau Toba selama 11 tahun operasinya. Populasi ikan di danau berkurang dan daur air terganggu lantaran pepohonannya ditebang untuk bahan kertas. Kasus itu masih menyisakan bara dalam sekam. Banyak ketakpuasan menggayut di hati warganya, baik yang pro maupun kontra. 110 Kasus senada terjadi pula di Irian Jaya. Malah lebih parah! Berat benar derita suku Amungme dan Komoro akibat limbah cair (tailing) dan batuan sisa (overburden) dari PT Freeport Indonesia yang sudah berlangsung sejak 1972, tapi baru terungkap setelah seperempat abad firma asing itu malang-melintang di tanah Cendrawasih. Telah berkali-kali longsor di sana. Yang sempat dirilis di koran adalah kasus ke Danau Wanaghon, 4 Mei 2000 (Kompas, 29/8/01). Namun jauh hari sebelumnya, Sungai Agawaghon, Otomona, dan Ajkwa pun telah disesaki pasir-batuan serupa yang membuatnya dangkal, di samping meracuni airnya (Forum Keadilan, No.5, 22/6/95). Dan..., banyak lagi hal sedemikian itu di tanah air kita. Tetapi saya tak hendak memperpanjangnya. Kita jeda dulu di sini dan sekarang kembali ke soal protes yang terkait dengan air PDAM. Ternyata tak cuma PAM Jaya yang didera protes berkaitan dengan mutu air olahannya. PDAM Kota Bandung pun kena. Apa solusinya? Ya, perbaruilah desainnya agar mampu menanggulangi pencemar yang jahat pada kesehatan kita. Kecuali soal polusi tersebut, debit air bakunya pun kian tipis. Mengawali dasawarsa pertama abad ke-21 ini krisis air di kota pegunungan ini sudah di gerbang stadium tiga. Larut senja. Betapa tidak, dari 20 sumur artesis (bor) milik PDAM tahun 1980-an tinggal delapan unit saja yang berair tahun 2003. Ini kata PDAM. Lain lagi temuan Wahana Lingkungan Hidup, Walhi. Katanya, cuma empat yang layak secara ekonomis. LSM lain pun datanya berbeda. Tapi yang pasti, airnya susut. 111 Celakanya lagi, 39 utas sungainya tanpa kecuali tercemari air limbah domestik berupa urin dan tinja. Gara-garanya, masih banyak rumah yang tak punya tangki septik; limbahnya langsung dibuang ke sungai atau parit terdekat. Tengok saja rumah-rumah di tepi sungai atau selokan, yang mewah maupun kumuh, tak sedikit air limbahnya dilepas begitu saja ke kali. Hebatnya lagi, masih banyak tua-muda, besar-kecil yang buang hajat tanpa malu-malu di sungai atau selokan, di WC umum maupun di ruang terbuka di tepinya. Malah kotoran kambing, domba, sapi, dan unggas ikut diglontor ke sungai. Dan yang terakhir, buruknya kinerja unit pengolah di instalasi pengolah air limbah (IPAL) Bojongsoang kian membludakkan jumlah bakteri coli tinja di Citarum. Citarum, dulu dan kini, sungguh jauh berbeda. Sebagai kolektor semua air sungai, parit, kali, dan selokan se-Bandung Raya dan wadah semua limbah domestik dan industri di tatar Parahyangan, pantaslah mutu airnya buruk. Polusi seolah-olah pantang mundur; malah jalan terus tak terputus. Entah sudah berapa ribu ton polutan organik dan anorganik lewat di sungai itu. Entah sudah berapa ton ikan peternak di sana mati mengenaskan. Ratusan juta rupiah pun lenyap dalam sekejap dari saku peternak. Padahal mereka tidak bersalah. Yang salah adalah pembuang limbah dan pemerintah yang tak jua tegas menindak pengusaha (atau lantaran limbah pakan ikannya?). Takut investornya hengkang? Pilih mana, investor tak jujur itu kabur lantas diganti oleh investor yang peduli lingkungan ataukah 112 nyawa rakyatnya yang “kabur” dari badannya akibat pencemaran? Sebab, andai Citarum terus dicemari, sejatinya sudah tak layak lagi airnya diperuntukkan sebagai air baku PDAM kecuali ada terobosan unit pengolah agar tidak konvensional seperti yang lazim dan jamak diterapkan sekarang ini. Pengolah kuno seperti itu hanya mampu menjernihkan air keruh dan mengurangi jumlah bakteri patogennya saja. Tidak lebih dari itu, titik! Malah ada kemungkinan bakteri tertentu tidak bisa dibasmi dengan cara itu. Juga tak kuasa mengurangi apalagi menghilangkan zat racun seperti merkuri, pestisida, dan zat toksik lainnya yang berlipat-lipat jumlahnya. Lantas yang sakit dan rugi jelas-jelas dan lagi-lagi pelanggan PDAM. Ya kita-kita ini. Selain itu ada titik lemah yang mengakibatkan interpretasi kerapkali keliru pada monitoring sumber air baku. Ini bisa terjadi di mana pun dan kapan saja. Biasanya, analisis itu cuma mengacu pada parameter konvensional tanpa mempertimbangkan parameter lain seperti logam berat, pestisida, dan deterjen. Inilah yang berbahaya andaikata PDAM tak mau dan tak jua mampu mengolahnya. Termasuk sering diperoleh angka atau nilai lump parameter seperti BOD (Biochemical Oxygen Demand=Kebutuhan Oksigen Biokimia) dan COD (Chemical Oxygen Demand= Kebutuhan Oksigen Kimia) yang kecil, tapi karena ada zat yang tak terdeteksi dengan parameter COD ituapalagi BODnamun amat berbahaya. Inilah zat xenobiotik, “musuh” organ tubuh kita. 113 Kelemahan kedua, jarang atau mungkin tidak pernah di-sampling sedimen atau endapan sungainya yang boleh jadi konsentrasi polutannya ratusan kali lebih besar daripada di air sungai. Polutan yang terlekat atau teradsorpsi pada pasir dan lempung di sedimen itu pada saat hujan dan banjir akan lepas lagi (flushing) sehingga konsentrasinya tambah besar di air sungai. Air itu lalu masuk ke instalasi PDAM lantas menjelma menjadi “monster” pembunuh yang kalem (the silent killer) bagi pelanggannya karena mengandung zat berbahaya-beracun berkadar tinggi. Sekali lagi, alat-alat dan unit pengolah airnya yang biasanya “sakti mandraguna” kini menjadi lemas tak berdaya. Adem ayem saja. Akan tetapi, andai Anda belum yakin juga pada paparan tadi cobalah jalan-jalan di bantaran sungai atau lintasilah jembatan yang melintang di atasnya. Luangkan secuil waktu buat pergi ke sana. Saksikan dan tataplah! Akan tampak airnya coklat kalau tidak hitam pekat khususnya saat kemarau. Cobalah amati juga bengkel mobil dan motor yang gemuk, bensin, oli, solar, dan minyak bekasnya dibuang ke parit dan akhirnya melimpas ke sungai juga. Begitu pun restoran, rumah makan dan warung. Sama saja: daun, kertas, plastik, sisa nasi, sayur, dan tulang-belulang hewan ikut luber di sungai. Dengan tambahan air cucian kaya minyak, deterjen, sabun, dan karbol dari berbagai merek lengkaplah sudah polutan di sungai itu sepanjang masa. Akhirnya tiaptiap polutan itu masuk ke perut lalu ke ginjal, hati, 114 dan beredar ke seluruh tubuh. Bertumpuk-tumpuk atau terakumulasi di sana selama bertahun-tahun. Lantas, kalau sempat atau disempat-sempatkan saja, cobalah kunjungi instalasi pengolah air minum (IPAM) milik PDAM untuk melihat-lihat bagaimana rentetan pengolahannya. Iseng-iseng tapi serius atau serius tapi santai, tanyakanlah jenis-jenis pencemar yang mampu disisihkan di IPAM itu. Kalau bisa, jangan cuma datang ke satu PDAM tetapi cobalah ke beberapa PDAM lalu bandingkan unit pengolahnya, samakah atau beda. Semoga survai itu memperkaya wawasan Anda tentang per-PDAM-an dan akhirnya ada saran buat PDAM. Tapi sayang, seperti tercermin pada hasil jajak pendapat Republika di atas, kebanyakan pelanggan masih awam akan kualitas air dan ogah datang ke PDAM. Jangankan untuk menambah ilmu, untuk menyelesaikan urusannya pun banyak yang enggan. Seabrek sebab-sebabnya. Selain, katanya, tak ada waktu senggang juga karena pengetahuan tentang kesehatan masih kurang; begitu pun soal publikasi bahaya pencemaran. Makanya konsumen banyak yang acuh tak acuh saja. Bisa juga karena tiada sumber air alternatif yang terjangkau secara ekonomi. Fenomena ini tak hanya menggejala di masyarakat menengah bawah tetapi juga melanda kalangan atas, yakni para elite sosial, ekonomi, politik, dan akademisi. Tentu ini berkaitan dengan latar belakang pendidikannya sehingga pola pikirnya satu tipe. Yaitu, air yang baik ialah air yang 115 jernih. Tidak lebih dan tak kurang. Hal ini tentu bisa kita maklumi; itulah tampak visualnya. Di lain pihak, konsultan pun selalu berupaya mendapatkan air tanah atau mata air walaupun jauh jaraknya dari calon daerah layanan asalkan airnya memenuhi syarat sehingga sesedikit mungkin perlu pengolahan. Tapi bagaimana dengan air sungai yang kotor dan tak ada lagi sumber air yang lain? Mau tak mau sistem itu harus dilengkapi lagi dengan unit pengolah tahap lanjut. Misalnya, memakai pelbagai jenis teknologi membran. Mahal? Sudah pasti. Tapi yang penting, air yang masuk ke perut pelanggan sudah baik kualitasnya. Terjamin keamanannya. Yang juga penting, hal tersebut harus didukung oleh sistem distribusi yang benar-benar baik. Hal ini berkaitan dengan kualitas pipa dan perlengkapannya, dan bergantung pada sistem pengalirannya, seperti kesetimbangan atau perataan tekanan di semua alur pipa. Kalau tidak demikian, air olahan yang sudah bagus akhirnya tercemar lagi. Ini mubazir. Buangbuang uang saja. Apalagi kalau ada pelanggan (atau semua pelanggannya) yang membabi buta menyedot habis-habisan air PDAM memakai pompa berdaya tinggi. Rekontaminasi bisa makin parah. Oleh sebab itu, coba terapkan sistem zoning yang khusus melayani pelanggan dalam lingkup kecil agar gampang dipantau dan relatif tak bermasalah ketika reparasi. Pembaca, saya hinggakan di sini saja bahasan mengenai pilar desain ini. Adapun detail desainnya saya yakin seyakin-yakinnya banyak sarjana TL yang memiliki bekal ilmu dan teknologi dalam bidang ini. 116 Apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa bekerja di konsultan yang “baik dan benar” sembari ajek giat mendalami dunia teoretis. Atau, mereka yang tak kenal lelah dan terus-menerus belajar lewat kursus, sekolah, dan secara otodidak. Pengalaman demikian itu, teoretis maupun praktis, akan bermanfaat pada saatnya nanti ketika menginovasi desain pengolah. Akhirnya, mari kita contoh negara-negara Arab yang mampu mengolah air laut menjadi air layak minum. Kapasitasnya pun sangat besar. Jangan lagi ada alasan bahwa itu terjadi lantaran mereka negara petrodollar. Apa nusantara ini bukan negara petrodollar? Ke mana saja devisa minyak dari perut bumi pertiwi ini? Yang bisa menjawab ini bukanlah wong cilik tapi wong gedhe, para pejabat di pemerintahan khususnya mereka yang membawahkan sumber daya alam tersebut. Atau, kalau negara-negara Arab itu terlampau jauh dari sini, kita lihat saja Singapura. Negara mini seluas kuku di peta Asia Tenggara itu sudah mampu mengolah air limbah domestik dan industri menjadi air minum. Instalasinya dinamai Newater. Apabila diterjemahkan, artinya air anyar. Maksudnya kirakira begini: air limbah dari sumbernya dianggap “air lama” yang kaya pencemar lalu diubah menjadi “air anyar” atau “baru” berupa air bersih. “Baru” di sini tentu saja mengacu pada mutunya yang jauh berbeda dari mutu awalnya. Hal itu ditempuh, kata pemerintahnya, sebagai upaya waspada kalau-kalau suatu saat kelak, akibat diimbas oleh sikon ekonomi, politik, dan keamanan 117 bilateral ataupun regional, air dari Pulau Batam dan Johor, Malaysia di-stop. Kalau tidak disiapkan dari sekarang bisa-bisa nanti mati kehausan jauh sebelum perang yang sebenarnya berkobar. Artinya, mereka telah siap mengantisipasi “perang” air dan boleh jadi perang militer. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? * Instalasi pengolah air dan perpipaan PDAM mirip dengan jantung, aorta, dan arteri (urat nadi) tubuh kita. Dari “jantung” inilah air dialirkan ke setiap pelanggan. Kalau “jantung”-nya sehat tentu sehat pula pelanggannya. Begitu sebaliknya. 118 Tak mungkin hidup tanpa air. AIRKU Air baku ada di sungai di danau-waduk di tanah di laut dan air hujan Biasanya air bersih itu jernih tiada senoktah racun tiada sezarah kuman Air limbah datang dari rumah dari rumah sakit dari pabrik dari yang lain lagi kaya polutan kaya racun! 119 8 AREA SERVIS PERLUAS TERUS * Sedih. Sekarat di lumbung padi. Pilu. Bayangkan, 80% rakyat Indonesia pada awal abad ke-21 ini belum diakses air bersih. Angka ini saya kutip dari Badan (dahulu, Biro) Pusat Statistik. Pernyataan ini tentu bisa kita terjemahkan menjadi, “kondisi sanitasi kita sama-sebangun dengan negaranegara di Afrika yang ganas alamnya, dan miskin ekonominya, dan senantiasa didera krisis air bersih sepanjang masa”. Ini aneh. Tak masuk akal. Padahal negara kita, secara garis besar, tidaklah semiskin negara-negara di Afrika dalam hal sumber air asalkan kita mampu mengelolanya ketika musim hujan dan kemarau. Itu teorinya. Tapi karena luasan hutan kita susut terus maka yang terjadi justru kelebihan air (banjir dan longsor) waktu hujan dan kurang air waktu kemarau. Pada detik ini saja hektaran hutan dibabat. Makanya Daerah Aliran Sungai makin kritis sehingga sawah mengering, pasokan listrik menurun, dan air baku PDAM menyusut. Pantas saja krisis air. 120 Kita dilanda badai. Badai multikrisis. Dan dari sekian banyak krisis itu, krisis air bersih adalah satu di antaranya. Air bersih semakin langka dan mahal. Tak semua orang bisa mudah mendapatkannya. Di Kota Bandung saja area servis (layanan) PDAM-nya baru 53%. Setengah lebih sedikit. Ini angka resminya. Namun, angka resmi yang dipublikasikan di media massa ini sering dipertanyakan. Benarkah itu angka yang sesungguhnya? Angka eksaknya? Kalau kita mengacu pada angka tersebut berarti nyaris separo dari warga Bandung belum disuplai air PDAM. Area servisnya masih sempit sehingga perlu diperluas. Padahal Bandung adalah kota besar atau kota jasa berpenduduk 2,5 juta orang (tahun 2003) dan di seputarnya ada sumber air baku berupa sungai yang debitnya layak dieksploitasi, secara gravitasi lagi. Dan teoretisnya, relatif tidak semahal sistem pemompaan. Tinggal pasang pipa dan perlengkapannya, mengalirlah air baku itu ke unit pengolahnya di wilayah Bandung. Lalu menyebar ke pelanggan. Sambil santai selonjor kaki bersandar punggung mari kita hitung berapa kebutuhan air PDAM Kota Bandung. Saya pilih kota ini hanya untuk contoh tanpa maksud apa-apa selain sekadar contoh. Juga bukan lantaran saya berdomisili di Bandung ketika buku ini saya susun. Semata-mata karena ingin saja. Begini maksud saya. Kalau mau, kita pun bisa saja melakukan hal yang sama atas PDAM di kota lain. Sederhana caranya. Tak perlu pakai kalkulator rumit apalagi program komputer. Simpel. 121 Taruhlah kebutuhan air bersih per orang per hari sekitar 100 liter (dalam sehari rata-rata kita minum 2-3 liter; sedikit sekali; yang terbanyak justru buat MCK). Kita pun dapat menghitung bahwa satu liter per detik (1 l/d) setara dengan 86.400 liter per hari. Artinya, debit air 1 l/d itu bisa menyuplai 864 orang. Apabila mukimin di Bandung 2,5 juta orang berarti kebutuhannya 2.894 l/d. Kita pun bisa menghitung, jika benar debit olahan PDAM Kota Bandung 2.500 l/d berarti 86,4% sudah terpenuhi. Namun faktanya, baru 53% yang disuplai; kemana air sisanya? (Saya tidak membahas kehilangan air di instalasi, baik di filter maupun di unit lainnya, dan kehilangan air di sistem distribusi). Begitu pun PAM Jaya, Jakarta. Data yang saya dapatkan waktu bab ini disusun, baru 49% dari 8,5 juta penduduknya yang terlayani air bersih. Jadi, lebih dari setengahnya warga di sana mendapatkan air dari sumur gali (air tanah dangkal), sumur bor, atau dari sumber-sumber lain. Termasuk warga yang terpaksa memanfaatkan air payau buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan air tanah yang payau ini, akibat intrusi air laut dari Utara Jakarta, sudah sampai di Monas dan terus merambat ke Selatan. Dan katanya, ini yang saya dengar, agar mampu meladeni 100% warganya, PAM Jaya perlu waktu 20 tahun lagi; baru tercapai tahun 2023/2024. Tentu dengan syarat, sumber air bakunya yang berasal dari waduk Jatiluhur tidak susut pada masa itu dan sumber-sumber air dari sungai lainnya masih bisa diandalkan. Tapi masalah lain menghadang. Pada 122 masa itu pasti polusi sungai sudah parah dibandingkan dengan masa sekarang. Artinya, PAM Jaya harus mereformasi IPAMnya dan tidak mengandalkan pengolah konvensional lagi. Atau, kalau air baku dari Citarum susut terus dan kian parah polusinya, olah saja air laut di Utara Jakarta. Rumit? Mahal? Ini sudah pasti. Akan tetapi, semua orang mesti minum dan harus air yang layak diminum. PAM Jaya pun tak ingin bangkrut. Maka, mau tak mau harus punya air yang layak dijual agar mau dibeli oleh pelanggannya dan bebas dari protes. Apalagi nanti masyarakat dan LSM kian pintar dalam soal kualitas air. Laboratorium pun bertambah banyak sehingga gampang mengetahui mutu airnya. Dua data di atas hanyalah sampel bahwa area servis PDAM harus terus ditingkatkan. Secepatnya mencapai angka yang setinggi-tingginya dan seluasluasnya. Angka-angka tadi masih jauh dari syarat hidup sehat, higienis, dan saniter bagi suatu kota. Di sinilah peran pemerintah atau penguasa untuk terus berusaha agar masyarakat mudah memperoleh air bersih. Gunakanlah pajak dari rakyat itu untuk terus memperluas layanan air bersih dan tak lagi rakus membungkus dana itu ke kantong masing-masing. Lalu bagaimana di luar Bandung dan Jakarta atau di kota-kota di luar Jawa? Kemungkinan besar lebih parah lagi. Perkecualian tentu saja ada, yaitu yang daerahnya kaya air tanah sehingga warganya bisa membuat sumur gali atau sumur bor sendiri. Di sini, barangkali, PDAM tidak laku-laku juga kecuali mampu memberikan nilai tambah. Misalnya, airnya 123 siap diminum tanpa perlu dididihkan lagi plus bebas zat berbahaya dan beracun. Kalau ini tercapai pasti membludak pelanggannya, laris manis airnya. Di atas telah saya sebutkan bahwa salah satu barometer dalam servis air minum kota ialah jumlah penduduk yang terlayani. Makin besar jumlahnya tentu makin bagus. Tapi yang terjadi, merujuk ke dua PDAM tadi kita justru krisis air. Ketika area servisnya belum luas malah debit airnya susut secara signifikan. Inilah krisis servis. Contohnya sbb. Debit pemompaan air tanah dalam di Bandung, merujuk hasil riset Ditjen. Geologi-Tata Lingkungan, sudah kritis, antara 620-1.700 l/d. Akibatnya, muka atau paras air tanahnya turun antara 0,5-12 m per tahun. Drastis! Dampak terburuknya, menurut riset itu, bisa dideteksi di Soreang, Batujajar, Buahbatu, Cimindi, Majalaya, dan Pameungpeuk. Namun krisis itu tidak hanya di Bandung. Krisis air bersih terus meluas di banyak kota di Indonesia terutama di Jawa, dari kota besar hingga kota kecil. Di luar Jawa juga idem ditto: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Bali, dan Nusa Tenggara nyaris tak pernah sepi dari krisis air bersih. Justru makin parah saja. Berjenis-jenis media massa yakni koran, radio, televisi, dan internet disarati berita kekeringan dan krisis air bersih yang biasa terjadi dari Juli hingga Oktober, setiap tahun. Seperti sudah tradisi, sudah klasik. Tapi kenapa kita tak berdaya, tak jua mampu “melawan” kondisi alam ini? Kenapa kita “kalah” dan terus “kalah”? Haruskah rumput bergoyang yang menjawabnya? 124 Ada lagi cerita pilu dari Cilacap, Jawa Tengah. Area servis PDAM belum sampai di daerah krisis air ini. Ada sekitar 20.000-an KK kesulitan air bersih, tinggal di 28 desa, di 6 kecamatan. Di situ tak satu pun air sumurnya tawar; semuanya payau akibat intrusi air laut. Upaya dicoba untuk menawarkannya, tulis Pikiran Rakyat, 23/9/95, seperti dengan filter pasir, kerikil, dan daun kelapa tetapi tidak berubah. Rasa asinnya masih terasa. Untuk mendapatkan tigaempat jeriken air tawar, terpaksalah mereka pergi ke Nusakambangan. Kejadian ini berulang tahun setiap tahun. Ulang tahun ratapan. Berikutnya masih hal serupa itu yang terjadi di daerah pegunungan di Brebes, Jawa Tengah. Di sini saya sempat antri air untuk sekadar membasahi atau lebih tepat mengelapi tubuh. Waktu itu saya survai sumber air, tugas dari Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) untuk desa-desa di Kab. Brebes. Adalah Cipetung, salah satu dari sekian banyak desa itu, letaknya di lereng bukit yang tandus berpinus, jalannya sempit berliku dan cuma diperkeras batu pecah. Tak satu sumur gali pun saya jumpai di desa berwarga 1.500 orang itu; tidak juga sawah; ladang jagung-singkong saja sejauh mata memandang di ketinggian 1.100 m dari muka laut. Padahal di atas desa itu, sekitar 12 km jaraknya, ada Telaga Ranjeng. Tetapi sayang, tidak ada airnya yang menjadi mata air di desa itu. Satu-satunya sumber air berupa rembesan yang kecil debitnya, di bawah kebutuhan standar pedesaan, 2,5-5 l/d. Untuk mandi dan cuci, warga mesti ke sungai di kaki bukit 125 dengan naik motor atau sepeda. Rata-rata cuma dua kali mereka mandi per minggu. Mungkinkah mereka bisa hidup higienis-saniter? Niscaya tak mungkin. Kemudian, selama musim kemarau 2002-2003, pantai utara (pantura) Brebes pun kena krisis air plus paceklik lantaran sawahnya sulit air. Di Pemalang, Pekalongan, dan Batang (ketiganya di Jawa Tengah), juga sama. Senada dengan itu, mewabah di pantura Jawa Barat, dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, sampai Kuningan. Malah di Cirebon air lautnya sudah masuk ke sungai sejauh 2-3 km kemudian menggarami sawahsawahnya hingga memutih. Begitu pun intrusi di pantura, tulis Republika, 28/2/03, jauhnya sudah 15 km. Tak cuma itu, lahannya tercemari oli dan solar dari pelabuhan Cirebon, papar Media Indonesia, 4/7/02. Kedua hal itu, paceklik dan krisis air, bisa diduga tambah menjadi-jadi pada tahun-tahun berikutnya kalau manajemen DAS belum membaik. Kisah ini terus berlanjut. Masih di Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri dan Jimbaran (Gunung Kidul). Sungguh merisaukan hati lantaran bukan cuma air sumur yang susut melainkan juga air waduk Gajah Mungkur, dam-dam kecil, dan kali. Gajah Mungkur, dam yang diresmikan Presiden Soeharto tanggal 16 November 1981, di usianya yang ke-21 ternyata sudah lumpuh. Tebal nian lumpurnya, ulas Pikiran Rakyat, 18/11/02. Tepinya dilebati rerumputan yang tumbuh subur di lumpur, yang karena susut airnya, tampak jelas akar-akarnya. 126 Di area sungainya seraya itu muncullah petakpetak sawah dan kolam-kolam wadah air. Dengan jeriken, air tampungan di kolam itu dipikul warga ke rumahnya masing-masing di lereng bebukitan yang pepohonannya meranggas. Bisa setahun penuh siklus pikul air itu berlangsung di selatan Jawa TengahYogyakarta. Sekarang pun begitu, tak berubah sama sekali. Adakah solusinya? Bagaimana caranya? Kini kita ke seberang timur. Ke Bali. Ke Pulau Dewata. Pulau Kahyangan. Secara garis besar pulau seluas 5.600-an km2 ini bisa dibelah dua: belahan barat bercurah hujan tinggi dan bagian timur yang rendah curah hujannya. Selain Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan, krisis air kerap melanda sisi timur Pulau Dewata ini, terutama Kab. Klungkung, Karangasem, dan bagian timur Buleleng. Daerah wisata pura Besakih di kaki Gunung Agung (tertinggi di Bali) dan sekitarnya: ke utara, ke timur, ke selatan adalah zone rawan air. Sungai-sungainya kering; bongkahan batu letusan Gunung Agung terserak-serak di sela ilalang. Sawah pun jarang, cuma ladang yang berkembang. Di Bali tengah (contoh: Tabanan), walau tinggi curah hujannya tetap saja tak luput dari krisis air. Ada daerahnya yang sulit meraih air bersih baik dari mata air maupun sumur dangkal. Pada dekade 1980an, ada saja antrian warga penampung air ledeng di tepi Jl. Sindumerta (kini, Diponegoro), Desa Dajan Peken. Bukan hidran umum yang mereka kerumuni melainkan kran yang dipasang di pipa distribusi lalu diberi selang. Lantaran rendah tekanan sisanya, tak 127 lebih dari semeter, airnya benar-benar tak bisa naik ke bahu jalan sehingga mesti turun dulu ke selokan untuk mewadahinya. Waktu itu, yang saya alami, betul-betul sulit air bersih. Yang juga rawan air bersih adalah tanah tinggi tengah-barat, yakni sepanjang jalan Pupuan di Kab. Tabanan dan Negara di Kab. Jembrana. Di sana tanah-tanahnya merekah dan dalam sumur-sumurnya sehingga banyak terlihat pipa dan selang yang saling silang menyusup di sisi jalan, mengalirkan air dari mata air nun jauh di sana ke hidran-hidran umum di pemukiman. Yang juga susah air adalah Bali barat termasuk Taman Nasional Bali Barat yang terkenal dengan burung endemiknya: si putih Jalak Bali. Inginkah Anda bersaksi? Bisa! Cobalah susuri ruas-ruas jalan Gilimanuk-Singaraja dengan sepeda motor. Pakai mobil juga boleh tapi jangan ber-AC. Rugi kalau ber-AC. Di sana, biarkan mentari meruapkan tubuh Anda dan nikmatilah nuansa kental kegersangannya. Datanglah ke sana pada bulan Juli hingga Oktober. Selamat datang di Bali, para wisatawan domestik. Maaf. Saya ngelantur ke soal wisata. Tapi saya ingin melanjutkan wisata krisis air ini yang relevan dengan area servis PDAM. Sekarang lebih ke timur lagi. Saksikanlah, betapa krisis air tengah mendera kota-kota di Prov. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang bertanah tandus, berpadang rumput (sabana). Bentangan krisis air itu mulai dari Pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Solor, Alor, Rote, Sawu hingga Timor bagian barat. Rasa128 rasanya sulit mencari solusi air bersih di kawasan ini. Entahlah nanti ketika ada dana untuk menawarkan air laut menjadi air layak minum. Di Sumatera dan Kalimantan juga senada. Di dua pulau ini masalah utamanya justru warna air gambut yang sulit dihilangkan. Membandel. Gambut ialah air yang banyak mengandung senyawa organik aromatik (aroma: bau) atau asam humus; warna coklatnya disebabkan ion besi sehingga intensitas atau taraf warnanya bergantung pada konsentrasi ion besi ini. Warna bandel ini baru bisa hilang kalau diolah dengan proses adsorpsi (penyerapan) dengan karbon aktif. Tapi proses ini mahal. Oleh karena itu, umumnya digunakan proses koagulasi dan flokulasi dengan pembubuhan tawas, kapur, polimer, dan sedikit tanah gambut. Lalu sedimentasi dan filtrasi. Namun ini tetap menguras tenaga, waktu, dan uang PDAM dalam hal biaya operasi-rawat instalasinya. Demikianlah. Hingga di sini sudah banyak kita simak kisah krisis air di negara kaya air ini. Yang pasti, pasokan air bersih cuma jalan di tempat atau malah berkurang sementara kebutuhan air bersih bak pelari cepat (sprinter) yang melesat laksana kilat dan tumbuh eksponensial. Inilah yang membuat krisis air kian parah dari tahun ke tahun. Semoga bangsa kita terhindar dari petaka: ayam mati di lumbung padi. Alangkah, maaf..., tololnya kita kalau hal itu sampai terjadi. Jika kita disebut tolol bin bodoh nan pandir maka presiden dari kepandiran itu tak lain dan tak bukan adalah pejabat yang tak jua becus mengurus negeri ini. Benar demikian, bukan? 129 Itu sebabnya, segala daya upaya harus dilakukan untuk melawan krisis itu. Caranya, tak lain daripada memperluas area layanan PDAM. Apapun caranya, berapapun biayanya harus ada eksplorasi sumber air baru. Pemerintah daerah harus berupaya agar suatu saat kelak krisis air yang sudah mentradisi itu bisa tercerabut sampai ke akar-akarnya. Mungkinkah? Andaikata kendalanya dana maka melibatkan swasta bukanlah hal tabu. Yang penting, sekali lagi, tidak berdampak buruk atas tarifnya, yaitu jangan terlampau tinggi bagi kebanyakan pelanggan. Maka dari itu, program-program semacam subsidi energi untuk air bersih sebaiknya tidak berjangka pendek saja melainkan juga merintis solusi jangka panjang. Apalagi kalau itu cuma program akal-akalan dan sekadar bagi-bagi duit antarkawan, antarpejabat agar semuanya diam seribu basa. Sungguh tak sederhana persoalan air bersih ini. Banyak daerah yang betul-betul tak punya air baku. Kalaupun ada, debitnya kecil sehingga tidak layak dieksploitasi. Di lain pihak, ada yang besar debitnya tapi polusinya pun tak kalah besar. Namun, karena ada acuan hirarki bahwa air adalah kebutuhan dasar maka apapun caranya rakyat harus bisa mendapatkan air bersih dengan mudah-murah. Inilah tugas besar PDAM untuk terus meluaskan area servisnya. Harus menjadi basis spiritnya. Kini kita beralih ke masalah lain di area servis, yaitu distribusi air. Boleh jadi ada suatu daerah yang kaya air tapi ada pelanggannya yang tak dapat suplai air dengan lancar. Ini bisa terjadi jika area servisnya 130 amat luas atau berbukit-bukit. Karena keterbatasan dana, PDAM biasanya cuma membuat satu reservoir distribusi, tidak beberapa reservoir, sehingga ada daerahnya yang tak teratur disuplai. Masalah di atas relatif lebih mudah dipecahkan dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki air baku sama sekali. PDAM bisa menerapkan zona servis (zoning) di sini. Oleh sebab itu, sebaran dan jumlah reservoir distribusi (tandon air) itu menjadi penting. Tapi nyatanya, selain jumlah dan sebaran reservoirnya yang kurang, lokasinya pun sering tidak tepat sehingga air tidak merata ke setiap pelanggan. Reservoir distribusi, menurut fungsinya, selain sebagai distributor air ke pelanggan juga penampung kelebihan air saat pemakaiannya rendah (biasanya malam hari) dan pengatur tekanan di daerah distribusi. Bagaimanapun pola suplainya, gravitasi atau pemompaan, reservoir tetap dibutuhkan buat merawat sistem distribusi dan menjaga keajekan pasokan air sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari area servis. Area servis ini bisa meliputi 70% dari sistem keseluruhan dalam hal luasan, kerumitan, dan biaya konstruksinya. Apalagi kalau menyangkut perizinan dan pembebasan tanah, luar biasa berbelit-belit, makan waktu, tenaga, uang, dan harga diri. Secara teoretis, dalam perluasan area servis ini, PDAM hendaknya setia mengacu pada kepentingan pelanggan. Semua pelanggan tanpa kecuali, di mana pun ia tinggal, harus disuplai secara kontinu dengan tekanan mencukupi. Itu sebabnya, desain area servis 131 harus tepat dengan pertimbangan matang atas topografi dan luas daerah servis. Umumnya, dalam rekayasa air minum, water supply engineering, ada dua pola sistem distribusi. Pertama, sistem cabang; dan kedua, sistem cincin. Pun bisa ditambahkan sistem ketiga, yaitu gabungan antara dua sistem itu. Analoginya, sistem cabang ini mirip pohon dengan cabang-cabangnya. Dan sistem cincin mirip cincin atau jala yang saling berkaitan sehingga tiada ujungnya. Adapun sistem campuran adalah sistem yang pipa induknya ada yang berujung (dead end) dan ada pula yang berhubungan. Setiap pola sistem ada keuntungan dan kerugiannya. Dan senantiasa dipengaruhi oleh topografi daerah suplai. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam area servis ini adalah meter air. Letaknya harus di tempat terang agar mudah dibaca, mudah didatangi petugas, dan aman. Pada kenyataannya, banyak rumah yang sulit didatangi petugas PDAM karena selalu terkunci dan pagarnya tinggi kokoh. Sudah itu ada gambar anjing galak. Ada herdernya. Ini yang bikin keder petugas dan urung bertugas. Maka yang terjadi justru pemilik rumahlah yang menuliskan angka meteran itu lalu dipajang di tembok rumahnya. Sang petugas lantas menyalinnya lalu balik kanan, grak. Ini catatan buat pelanggan. Seharusnya petugas meteran diberi izin dan bebas masuk serta melihat langsung meterannya agar dia tahu kondisi terkini meteran itu. Agar tidak kecele dan saling tunggu sebaiknya disepakati hari apa dan tanggal berapa petugas pencatat itu datang sehingga pelanggan bisa 132 siap-siap menerimanya. Suguhan ala kadarnya, kalau mau, bisa saja disiapkan. Ini pun dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian atau tuduhan macam-macam lainnya. Di pihak lain, para pencatat meteran harus rutin datang pada waktu yang telah disepakati. Minimal ada pemberitahuan lewat telefon kalau berhalangan. Memang ada satu-dua kasus, petugas enggan datang ke rumah pelanggan karena bosan ditanyai terus atau digugat soal airnya yang keruh, kecil, ataupun tidak mengalir. Mereka malas meladeni omelan. Jadilah main tebak-tebakan. Petugas menebak angka meter air itu. Jika jumlah anggota keluarganya diketahui mudahlah memperkirakan kebutuhan airnya dalam sebulan. Apalagi kalau sudah ada angka pemakaian airnya pada bulan-bulan sebelumnya. Cara ini akan makin gampang. Sambil ongkang-ongkang kaki di kursi goyang, angka taksirannya bisa ia peroleh. Itu tadi soal pencatat meter air. Yang juga perlu diperhatikan adalah faktor keamanan. Sebab, banyak meter air yang raib. Di PDAM Cianjur, ini dilansir Metro, 21/4/03, pada kwartal pertama 2003 sudah 65 unit meteran airnya hilang. Selain PDAM, yang rugi pasti pelanggan. Malah pelanggan yang lebih banyak menanggung kerugian. Jangan-jangan PDAM tidak rugi sepeser pun karena meter air itu tidak cumacuma. Tidak gratis alias harus dibayar. Adapun para pelanggan, selain keluar uang buat membeli meteran baru, juga mesti membayar biaya pasang ulang, upah pekerja, dan sewa meteran per bulan. Belum lagi bea administrasi di PDAM, biaya 133 transportasi, waktu, tenaga, dan banyak lagi yang lain, yang bisa “diuangkan”. Itulah tetek-bengeknya jika meteran air sampai hilang. Belum lagi sanksinya kalau tidak cepat-cepat dilaporkan ke PDAM. Berikutnya adalah masalah kalibrasi atau tera. Secara rutin meteran air harus ditera ulang. Apabila rusak, segeralah diganti. Kabarnya ini gratis. Sebab, apabila tidak akurat, yang rugi bisa PDAM, bisa juga pelanggan. Andaikan pelanggan yang rugi, misalnya dalam sehari menggunakan satu meter kubik air tapi tercatat 1,5 meter kubik maka jelaslah pelanggan rugi 0,5 meter kubik per hari. Dalam sebulan 15 meter kubik. Setahun? Besar sekali. Kalau ini terjadi berarti PDAM menzalimi pelanggannya dan bisa dituntut secara hukum! Jika sebaliknya yang terjadi, berarti PDAM-lah yang salah karena tidak bekerja optimal. Pelanggan sama sekali tidak salah. PDAM menzalimi PDAM. Sebab, PDAM-lah yang membeli, lalu mengalibrasi, memasang, dan memantau meteran air itu di rumah pelanggannya. Namun, apabila pelanggan mengutakatik meter airnya maka PDAM bisa bertindak tegas. Tuntut dan ganjar saja sesuai dengan aturan PDAM dan hukum yang berlaku. Tapi awas, oknum jangan “bermain” di sini. Kalau tetap nekat “bermain”, juga ganjar saja dengan hukuman setimpal. Yang terakhir, tetapi penting, adalah sisa klor di area servis. Selama ini, klor (bisa kaporit, bisa juga gas klor) digunakan untuk membasmi kuman atau bakteri dalam air minum. Senyawa itu umumnya dibubuhkan atau diinjeksikan di reservoir. Namun 134 masalahnya, sisa klor yang sampai ke pelanggan ada yang rendah atau bahkan nol. Di lain tempat sisa klornya justru tinggi sekali sehingga pelanggan waswas memakai airnya. Sisa klor yang disyaratkan di daerah distribusi adalah 0,2 mg/l. Ini untuk berjagajaga apabila terjadi rekontaminasi di pipa distribusi akibat perbaikan atau karena kebocoran. Juga akibat penggiliran air. Karena itu, bisa saja ada titik-titik injeksi di pipa distribusi kalau dipandang perlu. PDAM, di mana pun berada dan apapun caranya (tolong dipikirkan oleh insan PDAM) harus terus berupaya meluaskan area servisnya agar 80% rakyat Indonesia bisa menikmati air bersih dan bisa hidup saniter. Bebas dari penyakit menular lewat air. Jika berhasil maka Indonesia sehat bukanlah utopia. Tak cuma mimpi; bukan sekadar khayalan. Semoga. Dan ini tidak mengada-ada. Pada saatnya kelak BPS mencatat bahwa sudah 80% penduduk negara ini terlayani air bersih. Air yang tak sekadar jernih. Mudah-mudahan.* Air, the elixir of life. 135 Layanan PDAM Kota Bandung baru 53% dari 2,5 juta penduduknya. Dan PAM Jaya, Jakarta, baru 49% dari 8,5 juta penduduknya. Untuk meladeni 100% warganya, PAM Jaya perlu waktu 20 tahun lagi; tercapai tahun 2023/2024. 136 9 MANAJEMEN BERMORAL Sekarang tibalah kita pada pilar terakhir PDAM, yaitu M: manajemen. Kata yang sudah tak asing di kuping ini merupakan pengindonesiaan kata bahasa Inggris, management. Salah satu artinya menurut kamus, selain direksi, pemimpin, ialah pengelolaan. Dari sini kita dapatkan akar katanya: kelola. Jadi, pilar keempat ini bisa kita katakan sebagai pilar pengelolaan, pengaturan atau penatalaksanaan yang bertujuan mengatur sesuatu agar teratur dengan terus mengacu pada aturan yang sudah dibakukan. Aturan itulah rambu-rambunya agar semua strata pemimpin (manajemen, direksi) tidak tersesat dalam mengelola perusahaan dan sumber daya insaninya. Erat kaitannya dengan itu kita bisa belajar dari semesta alam yang kekal hingga kini karena teratur sistemnya. Dengan keteraturan pulalah manajemen PDAM tidak hanya akan bertahan lama atau “kekal” tapi juga maju, profesional dan yang terpenting ialah terhormat di mata pelanggannya. Dipercaya sebagai satu-satunya sumber air bersih dan keberadaannya dibela oleh setiap keluarga. 137 Bisa kita lihat, pilar M ini hakikatnya berkaitan dengan pilar pertama tadi, yaitu pegawai. Pegawai dan manajemen tak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Manajemen adalah kata benda mati yang hanya dapat “dihidupkan” oleh makhluk bernama manusia. Peran manusia (pegawai), khususnya yang memegang kendali, adalah bagian terkuat dalam mereparasi tata-kerja manajemen. Manajemen perlu didukung oleh stafnya. Hanya dengan cara itulah, disertai kemauan teguh dan kegigihan pemimpin dan stafnya, PDAM akan menjelma menjadi perusahaan mapan. Tapi apa daya, fakta bicara lain. Sampai sejauh ini mayoritas PDAM yang terpuruk justru disebabkan oleh SDI-nya yang tidak bagus; sekadar menjadi tukang tanpa kemauan menimba ilmu lebih jauh lagi, juga tidak kreatif, tidak inovatif. Terspesialisasi secara sempit. Spesialis, tentu bagus-bagus saja, dan malah perlu. Asal jangan terkungkung. Namun yang lebih bagus ialah kemauan untuk menambah ilmu supaya mampu berkiprah di bidang lain, syahdan di PDAM. Sifat mau-belajar ini mutlak wajib dimiliki oleh orang yang duduk di kursi manajemen. Selain berdaya membina stafnya menjadi profesional juga mampu mengelola pikirannya demi pengembangan perusahaan. Senantiasa melaksanakan pengayaan dan perluasan kerja bagi pegawainya dengan aturan yang jelas dan adil sehingga tidak ada kecemburuan dan grup-grupan. Apabila tidak jelas, apalagi berbau MKKN, hasilnya pasti akan kontraproduktif. Alih-alih maju malah mundur. 138 Kecuali dapat memola pikirannya, manajemen pun hendaknya mampu memotivasi pegawainya agar bekerja keras lagi cerdas. Mampu memberikan suri teladan bagaimana unjuk kerja yang bermutu itu dan secara jantan bertanggung jawab atas hasil kerjanya sambil toleran pada sejawatnya. Mau terus-menerus meluaskan kawasan & wawasan ilmunya, siap-sedia bekerja di semua seksi karena punya stok ilmu yang memadai. Beremosi relatif stabil agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh masalah yang mencuat di perusahaan. Terlebih lagi ketika merilis keputusan penting sepatutnya pintar-pintar mengatur emosinya. Maka, cerdas-emosi, kendali-diri, pimpin-diri adalah syarat mutlak yang patut melekat di sanubari direksi. Dengan ungkapan lain, insan manajemen tidak hanya harus cerdas intelektualcuma otaknya yang cerdastapi juga cerdas emosi, mampu mengelola emosinya dan emosi orang lain. Faktanya, banyak pejabat yang terlampau dikuasai emosinya, merajakan, memperturutkan dan diperbudak kehendak emosinya. Jangankan memimpin orang lain, memimpin dirinya saja tidak sanggup. Orang seperti ini tahu dirilah; jangan memaksakan diri jadi pemimpin. Pimpin saja diri sendiri dulu. Berbekal dua jenis kecerdasan di atas, tentu saja kalau dikelola dengan benar, PDAM akan berhasil menata manajemennya menjadi lebih baik. Tambah bernas lagi apabila dibarengi kecerdasan yang satu lagi, yaitu spiritual. Inilah kecerdasan yang terwujud dalam kemampuan mengamalkan makna iman dan menerapkan ilmu yang dimilikinya. Jika ini berhasil 139 maka setiap unit kerja di PDAM, dari unit teratas sampai terbawah, akan merasa saling memerlukan sehingga standar perilakunya sama, visi-misinya pun sama dan menjurus ke satu arah yang benar sesuai dengan kesepakatan. Apabila rasa itu sudah terbentuk, kegagalan di satu bagian akan terasa juga di bagian lain. Malah mengganggu kinerja bagian lain. Ini mirip dengan tubuh kita. Kalau kaki yang sakit maka nyut-nyutnya terasa hingga kepala. Contoh, bila bagian pencatat meteran pelanggan bekerja serampangan dan tidak becus, maka bagian keuangan ikut kacau-balau. Bisa PDAM yang rugi, bisa juga pelanggannya. Andaikata PDAM yang rugi otomatis labanya berkurang sehingga mengganggu biaya operasi-rawat instalasinya. Kenaikan gaji pegawai pun bisa saja tertunda. Namun biasanya, pelangganlah yang rugi. Saya pernah membaca surat pelanggan PDAM di satu koran. Dalam sebulan, katanya, tagihannya tak lebih dari Rp 50.000. Tiba-tiba saja dia harus membayar ratusan ribu. Ini pasti kesalahan petugas PDAM dalam memasukkan angka meter airnya. Seandainya kejadian tersebut berulang-ulang maka pada saatnya kelak PDAM menuai protes. Yang teledor satu-dua pegawai tapi yang kena getahnya PDAM. Namun, kalau kesalahan tulis itu tidak ketahuan atau nilainya kecil sehingga pelanggan tidak merasa ada kejanggalan pada rekeningnya, berarti PDAM telah menzalimi pelanggannya. Padahal syarat jualbeli adalah tidak menzalimi. Maka, sudah waktunya PDAM berupaya keras untuk menerapkan spiritual 140 bisnis: bisnis yang orientasinya tidak semata-mata pada laba tapi juga pada kemaslahatan pelanggan. Tanpa pelanggan, PDAM bukan apa-apa; PDAM tidak akan pernah ada. Manajemen pun selayaknya terus mengobarkan semangat pegawainya lewat contoh yang diberikan, yaitu dengan cara lebih dulu bekerja keras. Mampu memanfaatkan potensi daya atau kekuatannya dalam mengerahkan daya stafnya untuk menaikkan mutu PDAM. Mampu menggalang kekuatan dana (modal) investor dan pemda, bahkan daya dana pelanggan. Termasuk daya eksplorasi dan eksploitasi sumber air bagi kepentingan rakyat dalam kaitannya dengan lembaga legislatif (khususnya undang-undang soal air yang tidak membelit mayoritas rakyat) agar air tidak mutlak dikuasai oleh korporasi asing atau lokal yang disetir asing. Ini jangan sampai terjadi. Jangan pernah terjadi! Curiga atau waspada kepada orang, lembaga, atau negara yang sudah sering berbohong dan berkhianat tentu sah-sah saja dan tidak salah. Ingat, jangan keliru menerapkan prasangka baik. Namun hal itu hanya bisa dilakukan bila direksi punya kekuatan politis, punya posisi tawar, dan juga kekuatan melobi anggota DPRD. Artinya, selayaknyalah dewan direksi memiliki kecerdasan daya atau pengaruh, baik di kalangan dewan maupun pemda. Dia atau mereka mungkin saja figur publik yang jujur, adil, pakar, dan kaya harta. Cerdas-daya ini akan membantu menaikkan posisi politisnya di mata pelanggan. Bagaimana tidak, dia atau mereka adalah orang-orang mapan secara lahir dan batin. 141 Kecuali itu, direksi jangan condong dan terlalu berpatokan pada daftar hadir, absensi atau presensi. Boleh jadi pada jenis pekerjaan tertentu kehadiran di kantor bukanlah yang utama melainkan kinerjanya. Ada kasus, pejabat ngantor dari pagi sampai sore bahkan malam hari tapi kinerjanya nol besar. Hadir tanpa mutu dan menghambur-hamburkan barang dan uang perusahaan berupa air, telefon, listrik, dan alatalat tulis kantor. Tunjangan jabatannya pun mubazir. Malah ada gejala pejabat yang begitu itu lagi bermasalah: entah di rumahnya, entah di tempat tinggalnya (lingkungan). Mustahil bagi akal orang seperti itu dapat memajukan perusahaan. Itu sebabnya saya yakin bahwa kehadiran pada job tertentu tidak bisa langsung dijadikan tolokukur untuk menguji mutu pegawai. Yang patut dan layak diuji ialah unjuk kerjanya atau prestasinya apakah sedikit ataukah banyak manfaatnya bagi perusahaan. Tidak hadir karena alasan tertentu yang justru dapat memajukan perusahaan, tentu tidak apa-apa. Ini lebih baik daripada pegawai yang hadir setiap hari di kantor tapi tidak bisa unjuk prestasi. Cuma mengisi absensi lalu luntang-lantung tak tentu arah dan pergi setelah teng jam pulang. Tidak berhenti sampai di situ. Manajemen pun dituntut untuk mampu menghargai kinerja prestatif stafnya. Responnya harus selalu positif atas aktivitas pegawainya yang bermutu tinggi. Misalnya, dengan menghadiahkan uang atau barang, kenaikan pangkat atau jabatan kepada yang berprestasi; pada saat yang sama senantiasa bertindak tegas dengan memberikan 142 hukuman setimpal kepada yang salah. Siapa pun dia! Setimpal artinya tidak lebih dan tidak kurang. Hal itu, kendati berat, seharusnya dibiasakan. Minimal dirintis dari sekarang. Sebab, kemauan dan kemampuan untuk menghukum bawahan belum mentradisi di PDAM seperti halnya di instansi dan lembaga pemerintah lainnya. Apalagi kalau sampai muncul klik dan intrik, suasana kerja bisa luluhlantak berantakan. Tiada sisi kondusif yang memacu pegawai untuk maju dan menjadi bernas. Malah bisa meruntuhkan reputasi perusahaan. Maka, manajemen laksana pisau cukur. Hatihati menggunakannya; jangan salah guna. Misalnya, ini hanya contoh, Direktur Teknik PDAM wajib orang yang paham soal teknik air bersih. Jabatan ini sebaiknya (tidak harus) diemban oleh orang yang berlatar Teknik Lingkungan. Di situ “kesaktiannya”. Tapi saya pun setuju pada prinsip “serahkan pekerjaan kepada ahlinya, bukan jurusannya”. Sejujurnya, jika dibandingkan dengan jurusan lain, alumni TL tentu lebih banyak mencicipi asam-garam ke-TL-an daripada orang dari jurusan lain. Ini logis. Kompetensi legal formalnya di situ. Ia mahir di situ. Jika sisi pandangnya nonformal tentulah semua orang bisa menjadi pejabat tidak peduli pada latar belakangnya. Asal mampu, boleh-boleh saja duduk di jabatan itu. Berpatokan pada pola pikir ini maka job Direktur Keuangan pun hendaklah diamanahkan kepada orang yang berlatar studi ekonomi, akuntansi ataupun yang dekat dengan itu. Begitu pun job yang lainnya, setali tiga uang. Pokoknya di segmen ilmu 143 masing-masing yang jelas juntrungannya. Selain itu tentu saja harus berinsting kepemimpinan, berkemampuan manajerial, dan berjejak-moral (track record) yang bersih. Selanjutnya, manajemen diamanahi kewajiban agar mampu meninggikan posisi tawar PDAM atas pemerintah dan jangan mau disetir alias menjadi boneka binaan pejabat daerah meskipun hirarkinya berada di bawah pemda. Tapi jangan diterjemahkan bahwa manajemen harus menyempal dari pemda. Tidak demikian. Bagaimanapun, PDAM itu milik pemda. Dan “rajanya” adalah bupati atau walikota. Maksud saya begini, manajemen hendaklah mampu mandiri dalam berpendapat dan bertindak dan juga profesional berasaskan sainstek yang ada. Andaikata iklim ini sudah terbentuk maka kasus MKKN atau upaya eksploitasi PDAM oleh “tikustikus kantor dan gudang” dapat direduksi sehingga kinerjanya meningkat ke titik optimum. Terlebih lagi ada UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang ikut memacu pemda untuk giat meningkatkan PADnya lewat instrumen pajak dan retribusi. Maka, jangan sampai PDAM diperah habis-habisan agar misi pasal 33 UUD 1945 tidak tersendat-sendat atau bahkan kandas atas nama PAD. Itulah sebabnya, mulai saat ini dan seterusnya, reparasi manajemen dan pegawai mutlak mendesak dilakukan karena menyangkut sumber daya insani berkualitas tinggi. Kita tahu, sosok pemimpin yang mengedepankan profesionalisme, bukan nepotisme apalagi sekadar senioritas pasti menjadi dambaan 144 pegawai. Bahkan kalau bermutu tinggi, pegawai tak lagi peduli dari mana asal “induknya”, apakah sosok pemda karir, sosok perusahaan ataukah “orang luar” sekalipun. “Orang luar” ini boleh jadi eksekutif yang berpengalaman dan sukses memimpin perusahaan. Lebih disukai adalah orang yang sukses memimpin perusahaan sejenis atau pernah berkecimpung dalam perusahaan air minum. Bisa kita rasakan betapa hal utama bagi pegawai adalah bahwa tataran manajemen diisi oleh insaninsan berkompeten, bermoral mulia, dan motivator ulung. Oleh karena itulah, hendaknya elite di pemda (bupati-walikota) maupun di perusahaan bisa lapang dada dan egaliter dalam penetapan direksi PDAM yang dilandaskan pada tingkat pemahaman terhadap perairbersihan. Jangan asal tunjuk apalagi bernuansa otoriter egosentris. Sebab, dan ini patut dimaklumi, PDAM itu perusahaan air minum, bukan perusahaan listrik, telefon, ataupun kereta api. Pun sudah disebut bahwa PDAM merupakan perusahaan daerah yang dikelola pemda. Jadi, semua bupati-walikota memiliki hak “prerogatif” dalam menyusun direksi dan jajarannya. Pun sudah rahasia umum bahwa dewan direksinya sekian lama ini adalah sosok pemda karir yang dekat dengan Sang Boss sehingga ada tirani keangkuhan di sini. Ini yang transparan. Apabila tidak semuanya, sebagian besar direksinya berasal dari pemda atau teman dekat bupati-walikota atau yang satu aliran dengan bupatiwalikota, ataupun orang yang dekat dengan partai politik tertentu. Bagi saya, ini tak lain daripada 145 nepotisme birokratis yang mengikis habis semangat bersaing secara sehat dan prestatif. Makanya saya salut dan hormat kepada PDAM Kota Surabaya. Pemkotnya saya acungi dua jempol karena berupaya merekrut direksi PDAM itu lewat iklan di media massa, seperti di Kompas, 6/10/03. Semoga terobosan yang anggun ini dibarengi oleh prosesnya yang jujur dan adil lewat uji patut-layak, fit and proper test. Mudah-mudahan saja fenomena penjaringan dan penyaringan model ini bergetuktular, menular ke semua daerah agar semua nakoda PDAM betul-betul insan profesional terbaik yang bermoral mulia, best of the best, sehingga mampu menyulap PDAM menjadi perusahaan yang segar bugar bergairah. Namun saya pernah prihatin. Justru di kota tempat kelahiran pionir pakar Teknik Lingkungan di Indonesia, yaitu Bandung, ada kasus mengenaskan. Pada April 2004 terjadi ketegangan antara Walikota Bandung dengan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Bandung. Pasalnya, Walikota mengganti Dirut PDAM setahun sebelum masa jabatannya usai. Dan ini dianggap cacat hukum oleh Dirut lama. Adapun Dirut baru sudah langsung bertugas dan bersikukuh bahwa dirinyalah Dirut yang sah. Masing-masing menganggap dirinya sebagai Dirut. Jadilah dualisme: satu tubuh dengan dua kepala. Krisis pun terjadilah. Pegawai khawatir gajinya tak lancar dan pelanggan waswas servisnya tersendat-sendat. Apa sebenarnya yang salah? Bagi saya, ini cuma soal komunikasi. Soal silaturahmi. Saya menduga ini 146 terjadi karena tak ada komunikasi antarpihak terkait. Terlampau condong pada hak dan juga kewenangan masing-masing. Padahal institusi ini adalah bagian dari sistem pemerintahan baik daerah maupun pusat. Jadi harus terkoordinasi. Sistem saraf dan otot tubuh saja terkoordinasi dengan baik. Kalau tidak, tubuh ini bisa kacau. Bisa pincang, cacat, tremor, atau gila. Begitu juga di sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Simpel saja masalahnya. Walikota harus mengevaluasi kinerja bawahannya secara transparan. Meskipun punya hak untuk mengganti bawahannya, hendaklah dilakukan dengan bijak terbuka. Ada parameter ujinya. Parameter uji inilah komunikasi. Ada hak tanya dan hak jawab. Misalnya, nilailah kinerjanya seperti berapa labanya, kondisi servisnya apakah meluas dan pelanggannya puas, serta bebas MKKN. Objektif, jujur dan adil. Jadi, jangan alasan politis yang dikedepankan. Bisa terjadi like-dislike dan sektarian atau grup-grupan. Ini yang saya sebut dengan egosentris di atas. Lantaran itulah perlu ada terobosan baru. Perlu ada reformasi formula dewan direksi di pelbagai PDAM. Salah satunya adalah dengan cara rekrutmen terbuka dan transparan. Saya optimis ini dapat kita laksakan di masa datang. Tentu harus didukung oleh DPRD. Bagaimanapun, DPRD ikut mewarnai dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang akur, aman, dan efektif. Seandainya ini terlaksana maka masyarakat khususnya pelanggan akan semakin yakin bahwa PDAM adalah institusi profesional berorientasi kerakyatan yang dikendali147 kan oleh figur-figur yang familiar dan mengakrabi teknologi air, selalu mengedepankan etika bersaing profesional tanpa main uang (money politics). Dengan kata lain, selain tahu soal pemasaran atau marketing juga memahami rekayasa di bidang pengolahan air, integritasnya teruji, bebas MKKN, dan bebas busuk moral, moral hazard. Andaikata tidak demikian maka potensi friksi atau gesekannya akan membesar. Terutama antara pegawai perusahaan dan pegawai yang dikaryakan dari pemda atau bahkan dari pihak luar. Ketegangan ini lantas terus memperburuk kinerja perusahaan. Kemudian, dalam pandangan kasat mata saya, dan maaf kalau keliru, pada saat ini kendati jumlah karyawan perusahaan lebih besar daripada limpahan pegawai pemda tetapi banyak yang hanya berada di manajemen menengah-bawah. Tidak di tataran top management. Fakta bicara bahwa yang “di atas” itu mayoritas kalangan PNS dari pemkot atau pemkab yang sangat boleh jadi “asam-garam” yang mereka makan sejauh ini bukanlah “asam-garam” perihal perairminuman melainkan dari dinas, biro ataupun badan lain yang tak ada sangkut-pautnya dengan air. Padahal pegawai perusahaan itu, ini cuma opini saya tanpa titipan dari siapapun dan sedikit pun tiada maksud negatif, banyak yang profesional dan layak menjadi pembuat keputusan utama karena, minimal, didukung oleh ilmu, wawasan, dan pengalamannya yang tidak hanya berkutat jadi birokrat administratif di instansi pemda selama belasan tahun tetapi juga menyelami seluk-beluk “sumsum tulang” PDAM. 148 Dengan demikian, coba dipertegas lagi syaratsyarat dan aturan promosi pegawai agar mereka tahu akan ke mana langkah-langkah masa depannya di PDAM. Akan ke mana tapak jejak hidupnya nanti di PDAM. Karirnya harus jelas dan terang-benderang seterang mentari siang. Ada sistem promosi yang mapan-objektif agar budaya perusahaan yang baik dan benar bisa terwujud. Selain profesionalisme, kepemimpinan, manajemen, dan transparansi jenjang karir, yang juga kerap jadi masalah ialah perihal gaji dan honor. Sebagai masalah sensitif, gaji dan honor memang seharusnya ditangani dengan hati-hati. Pada galibnya bisa kita katakan bahwa kebanyakan pegawai yang bekerja di mana saja selalu dilatarbelakangi oleh pendapatan, gaji atau honor. Berkaitan dengan ini perlu benar ditransparankan apakah sumber gaji antara pekerja perusahaan dan pegawai pemkot/pemkab itu sama ataukah beda. Adakah yang dapat dobel? Benarkah orang berpangkat atau berjabatan sama bisa berbeda penghasilannya walau gajinya sama? Yang juga mendesak adalah kerja sama dengan instansi atau PDAM lain terutama soal pengelolaan air baku yang makin runyam saja saat ini lantaran terjadi klaim-mengklaim antar-PDAM, antarpemda, atau antarwarga. Vital sekali pengelolaan sumber daya air ini bagi PDAM. Tanpa air baku, PDAM mau menjual apa? Tanpa air berarti tanpa PDAM. Lebih-lebih lagi pada masa otonomi daerah sekarang ini, kebutuhan saling tolong jelas-jelas makin besar. 149 Yang penting, hal ini hendaklah dikembangkan dalam tatanan bisnis yang tetap setia mengacu ke pasal sosioekologi, pasal 33 UUD 1945: bahwa air adalah 100% milik rakyat dan digunakan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada dimensi spiritualnya: air adalah titipan Yang Mahaesa untuk manusia lalu dikelola oleh negara buat rakyatnya. Makanya tak menutup kemungkinan air di satu daerah bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia di lain daerah dengan syarat-syarat dan kalkulasi bisnis yang tidak memberatkan. Ini erat kaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang turut memengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku PDAM. Kerja sama ini begitu mendesak di daerah yang sumber airnya di luar daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Aturan mainnya pun mesti disepakati dulu, yakni berorientasi pada kepemilikan bersama. Kalaupun perlu ditarif maka tetap harus semurah-murahnya lantaran air mewakili eksistensi bangsa; tanpa air lenyaplah bangsa. Maka, buatlah aturan main yang sama-sama untung tanpa ada satu orang atau lembaga atau perusahaan yang buntung! Akhirnya, manajemen yang akur bermoral dapat terwujud apabila antarpegawai saling berempati, dan antarpegawai dan pejabat tidak saling menyalahkan. Yang salah apalagi tahu bahwa itu adalah benarbenar kesalahannya hendaklah jantan pula mengakui kesalahannya itu dan siap sedia menerima risikonya. Mau bertanggung jawab. Tentu saja tanggung jawab pejabat lebih besar daripada stafnya. Apalagi kalau kesalahan stafnya itu cuma lantaran melaksanakan 150 tugas atas perintah atasannya. Jenderallah yang salah dan bukan prajurit, begitu tutur ahli hikmah. Dengan demikian janganlah pegawai cuma cuek bebek, menjadi yesman, si pemanut-turut. Pegawai harus punya kreativitas yang inovatif agar produktif sehingga mandiri. Kalau ada pegawai yang begini maka manajemen harus mendukungnya bukannya malah mengebirinya. Apalagi cuma dijadikan flora bonsai, dipelihara, dirawat dengan baik tetapi tak diizinkan menjadi besar dan tangguh. Seharusnya sebaliknya, manajemen menugasi pegawai untuk menimba ilmu agar keterkaitan antara dunia teori dan praktik semakin kuat. Ada keterkaitan dan kesepadanan, ada Link & Match. Pegawai senantiasa disuguhi sainstek baru di bidang masing-masing. Kemudian, dalam tempo-tempo tertentu manajemen bisa mengadakan kegiatan adu-ide, curah-ide, buka gagasan, brainstorming, baik di kantor maupun di luar (outbound, outbond). Segala ide di benak pegawai dikeluarkan demi kemajuan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Dalam diskusi itu akan terjadi debat untuk mencari yang benar dan bukan yang terbanyak suaranya. Suara terbanyak belum tentu benar. Bisa-bisa malah terjadi salah massal. Salah kaprah. Makanya cobalah diupayakan agar jangan terjadi pemungutan suara. Dan setiap pegawai wajib mengusung semangat demi kemajuan PDAM, demi peningkatan kualitas layanannya. Jadi, manajemen akur bermoral ini harus dianut oleh insan PDAM, tidak hanya manajemennya tapi juga stafnya. Idealnya, ketika ada pemilihan direksi 151 dan jajarannya maka sebaiknya bupati atau walikota sudah bertanya secara diam-diam dulu atau dengan mekanisme lainnya seperti memasang iklan di media massa untuk memilah dan memilih insan yang pas mengisi jabatan itu. Dan yang jauh lebih penting lagi ialah bupati dan walikota haruslah orang yang jujur, adil, dan berilmu. Bukan orang berbusuk moral. Di sinilah arti penting dari seorang bupati atau walikota yang tinggi taraf kecerdasan otaknya, stabil emosinya, dan mantap kecerdasan daya-spiritualnya. Hal ini akan mampu meniadakan kepentingan politis sesaatnya seperti demi jabatan dan partainya semata. Sebab, kalau ini benar terjadi maka PDAM cuma akan dijadikan ladang uang oleh pejabatnya, kepala daerah dan jajarannya serta oleh anggota DPRD. Relakah kita, pelanggan PDAM dan rakyat Indonesia pada umumnya, menyaksikan orang-orang tadi mengamburadulkan PDAM dan memikulkan beban itu kepada kita? 152 Manajemen 5S Sebagai penuntas bab ini, berikut saya tuliskan hal yang berkaitan dengan pegawai atau staf dan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bisa berkembang dan sukses. Mudah-mudahan prinsip ini dapat membangun manajemen yang akur bermoral seperti yang saya paparkan di atas. Semoga prinsip ini dapat berlaku umum, tidak hanya buat PDAM tetapi juga untuk perusahaan yang lain. Saya yakin prinsip dasarnya sama. Bisa berlaku universal. Prinsip tersebut saya sebut manajemen 5S dan disingkat M5S. Lima prinsip ini pun bisa divisualkan dengan piramid. Empat S pertama tak lain daripada pilar-pilar piramid dan S terakhir mengisi puncak piramid. Di bawah ini adalah uraiannya. Pertama, suka. Siapapun, baik itu staf maupun pejabat atau manajemen dan direksi hendaklah suka pada tempat kerjanya. Kalau sudah suka maka akan tumbuh rasa cinta dan sayang sehingga senantiasa ingin merawatnya supaya sehat dan tumbuh optimal. Rasa suka ini tentu terpulang lagi kepada motivasi orang per orang dalam bekerja atau niat awalnya. Bisa dibayangkan orang yang tidak suka bekerja di suatu perusahaan tentu tak punya motivasi untuk memajukan perusahaan. Tiada terbersit di hatinya rasa memiliki. Alih-alih memajukan perusahaan tapi merusaklah yang dilakukannya. Setidak-tidaknya dia menjadi pengacau, trouble maker. Pegawai jenis ini, kalau tidak bisa dinasihati dalam kurun tertentu, sebaiknya dilepas saja. Dipecat! Ini demi kebaikan 153 yang bersangkutan agar bisa menemukan tempat kerjanya yang cocok. Juga demi sterilisasi perusahaan dari orang yang tak laik kerja. Ibaratnya, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kedua, sikap. Pilar kedua ini terbentuk setelah rasa suka dan cinta merasuk ke kalbu para pegawai. Sikap mulia ini membentuk karakternya dan dapat memunculkan etos kerja brilian. Sikap ialah wujud kecerdasan emosi yang dikelola dengan baik. Dalam pada itu, sikap pun ikut mengimbas ke orang lain sehingga pada akhirnya menghasilkan sinergi yang menguntungkan perusahaan. Sikap yang berani karena benar, takut karena salah harus dijadikan pedoman, baik oleh pegawai maupun tataran manajemen. Tidak ada yang arogan, sombong bak kokok ayam jago usai bertarung. Sikap mau bekerja keras dan ikhlas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dapat memupuk kekompakan dalam bekerja dan meraih hasil optimal. Dengan sikapnya itu orang lain bisa menilai dan meniru agar memiliki spirit memajukan perusahaan. Akhirnya, insan ini makin yakin akan pilihannya untuk bekerja di suatu perusahaan, misalnya PDAM. Sikap tersebut turut membentuk komitmen jiwanya dalam membangun moral mulia staf dan manajemen perusahaan. Pilar sikap ini laksana radiasi cahaya yang menerangi malam temaram dan menuntun kita menuju tujuan. Ketiga, sambung. Pilar ketiga piramid M5S ini mengajak setiap insan perusahaan untuk senantiasa 154 meluaskan jejaring (networking) lewat silaturahmi, komunikasi intensif antarpegawai-pejabat dan antarkorporasi. Memperbanyak kerja sama dan saling bantu, baik di unitnya, antarbagian maupun antarunit pelaksana terkecil. Membangun kebersamaan sambil bersama-sama mengelola perusahaan lewat kompetensi masing-masing. Juga rela menularkan ilmunya demi kemajuan bersama lewat serikat pekerja-pejabat. Dan idealnya, kedua kubu ini bisa akur dan saling dukung. Ada sambung rasa, teposeliro, dan toleransi. Artinya, staf menghormati pejabat dengan menunaikan setiap tugasnya dengan sebaik-baiknya dan pejabat sayang pada stafnya dengan selalu berupaya agar gaji dan jumlah honorariumnya layak, dibayar tepat waktu atau sebelum keringatnya kering. Dengan prinsip sambung ini insan perusahaan diharapkan mampu memintal jejaring koneksitas dengan perusahaan lain yang sejenis atau kompetitor dan juga perusahaan lain yang tak sejenis. Dan untuk memaksimalkan prinsip ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan ilmu dan teknologi canggih sehingga hubungan menjadi luas dan perusahaan kian dikenal. Artinya, sikap mau belajar dan mengajarkan sainstek menjadi misi penting pada prinsip ini sehingga setiap hal dapat mudah dikomunikasikan. Orang bilang, tidak telmi, tidak telat mikir. Keempat, sumbang. Pengorbanan para staf dan manajemen tidak hanya dituntut secara fisik belaka tetapi juga secara psikis. Mereka harus mau dan mampu menyumbangkan daya dan karya terbaiknya 155 buat perusahaan. Menjadi motor motivator bagi para pegawai dan pejabat lainnya. Tentu masing-masing menyumbang sesuai dengan kemampuannya dalam hal ilmu, uang, kecakapan atau profesionalismenya. Di pihak lain, pilar sumbang ini pun menjaga harga diri setiap pegawai agar jangan menjadi orang yang meminta terus. Minta ini minta itu sembari tugas atau kewajibannya belum dituntaskan secara baik dan benar. Dalam prinsip tersebut, lebih dulu menyumbangkan atau memberikan suatu kebaikan adalah lebih mulia daripada minta disumbangi terus. Tangan di atas lebih mulia ketimbang di bawah. Ada ungkapan, jangan kautanya apa yang dapat diberikan perusahaan untukmu tapi tanyailah dirimu apa yang kauberikan buat perusahaan. Maka, kalau pegawai sudah ikhlas menyumbangkan ilmu, tenaga, waktu, pikiran, dan potensi lainnya, perusahaan pun wajib menyumbangkan sesuatu yang kaya manfaat bagi pegawainya, apapun ujudnya. Setimbang. Tidak boleh berat sebelah. Ada take and give yang adil. Jangan sampai pegawai dan pejabatnya menzalimi perusahaan dan perusahaan jangan memperdayai pegawai. Pegawai wajib bekerja yang prestatif sebaliknya perusahaan wajib memberikan gaji dan honor yang setimpal. Jangan ditunda-tunda apalagi dikurangi/disunat. Saat terjadi pemutusan hubungan kerja pun pesangonnya wajib sesuai dengan aturan Depnaker. Kalau tidak, itu artinya perusahaan telah “merampok” pegawainya. Jadi, harus seia sekata. Singkron. Inilah spiritual bisnis. 156 Akhirnya, setelah keempat pilar tersebut tertata dengan baik dan mencetak budaya perusahaan maka saya yakin titik puncak piramid itu, yaitu S yang kelima: sukses segera tercapai. Tidak seorang pun memungkiri bahwa sukseslah cita-cita pamungkas setiap orang, setiap perusahaan. Tentu saja sukses yang berkaitan dengan kontribusi pegawai dan perusahaan ini berdimensi jasad dan jiwa. Lahir dan batin, sebuah sampel sukses yang paripurna. Bagi perusahaan, sukses ialah kemampuannya untuk senantiasa eksis, tumbuh, dan memuaskan pegawainya dalam kadar yang layak. Sukses ialah kemampuan manajemen untuk memompa semangat pegawainya agar terus berprestasi. Begitu pun sukses ialah daya, kekuatan atau kemampuan pegawai untuk berkinerja tertinggi yang mungkin dicapainya. Maka, sukses adalah wujud optimalisasi kecerdasan otak, emosi, spiritual, dan kekuatan (daya). Interaksi positif atau sinergis inilah yang membawa seseorang menuju jenjang kesuksesan hakiki. Pembaca, mudah-mudahan prinsip M5S di atas bisa memotivasi pegawai, manajemen, dan pemilik perusahaan/pemerintah agar rajin memperbarui niat, memperbaiki sikap, meningkatkan kerja sama dan mutu kerjanya, dan memperbesar kekuatannya. Terakhir, saya kutipkan mutiara hikmah ini. Bekerjalah, jangan kaupikirkan berapa uang yang kaudapat. Bayarlah upahnya, sebelum kering keringat pegawaimu dan jangan bertindak zalim!! * 157 Air dan Manusia Kendati asalnya dari air Manusia diatur air? Jangan pernah terjadi. Tapi nyatanya? Air mubazir saat banjir dan pontang-panting saat kering Air, hendaklah ditata Manajemen sumber daya air Dan paling penting hendaklah ditata nafsu serakah kita akan air. Air milik siapa? Air milik si papa Air milik si kaya Ditata oleh negara buat kita semua 158 12 AMIK Versus AMIKU “Perang” karena air... “Tirthayudha”... Water wars... (Entahlah, apakah fenomena Kevin Kostner dan teman-temannya yang hidup terapung-apung di laut, bisa benar-benar terjadi nanti. Saya tak tahu. Yang saya tahu, ketika kehilangan rumah, tanah, dan air, mereka hidup di kapal. Mirip kisah Nabi Nuh. Waktu itu, Bumi telah tenggelam lantaran es di kutub mencair akibat pemanasan global. Cuma air laut yang ada sehingga si “Dances With Wolves” ini sampai-sampai mendaur ulang air kencingnya untuk diminum. Jijik? Tak ada itu. Kan sudah diproses. Bersama rekan-rekannya, aktor Hollywood ini kerap bertarung dengan kelompok lain untuk mendapatkan sejengkal tanah dan air tawar. Sebagai sebuah skenario, film produksi 1995 dan sempat mencatat box office ini, tentu sah-sah saja. Terjadi atau tidak, itu bukanlah soal. Yang penting kreatif. Fiktif yang saintifik!) 209 Di Indonesia, sekarang ini, bagaimana? Serupa tapi tak sama. Kita benar-benar telah mengalaminya. Meletus sudah perang itu. Tak hanya antara masyarakat dan PDAM dalam memperebutkan sumber-sumber air, atau antara satu daerah dan daerah lainnya akibat otonomi daerah (otda), atau antarpetani, tapi juga antara produsen air siap-minum. Ini mirip dengan perang global yang tak hanya melibatkan negara tapi juga lembaga setingkat kabupaten. Luas benar “perang” itu. Sekalipun demikian, yudha lainnya tak dibahas di sini. Yang saya kupas ialah yudha air siap-minum. Air siap-minum ini saya pilah menjadi dua kelompok. Yang pertama, air minum kemasan (diakronimkan menjadi amik; dulu orang menyebutnya air mineral, lalu berubah jadi air minum dalam kemasan) yang sudah lama hadir. Kedua, sang pemain baru yang vini, vidi, vici dan dinamai air minum kemasan ulang (amiku; lebih populer disebut air minum isi ulang ) Khusus air siap-minum, tetabuhan genderang perangnya kuat sekali tahun 2003. Pasalnya, pada tahun itulah pemain anyar ini begitu ekspansif di mana-mana. Dalam hitungan setahun saja jumlahnya mencapai ribuan depot. Ada yang bilang delapan ribuan dalam skala nasional. Dalam skala regional, terbanyak beroperasi di Jadebotabek, yaitu Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Berapa angka pastinya, sampai sekarang sulit didata sebab banyak yang tak terdaftar. Yang saya lihat, baik depot yang terdaftar maupun yang tidak (belum) terdaftar biasa210 nya ada namanya walaupun produknya sendiri tak bermerek. Nirmerek. Sedangkan amik mulai pesat berkembang kirakira pada dekade 1980-an. Waktu itu nilai gengsinya tinggi. Saya duga tidak ada yang membeli amik saat itu kecuali terbersit di benaknya jaga gengsi. Coba lihat minumanku; air mahal dan aku orang modern. Inilah bersitan hati penikmat amik pada masa itu. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Setahu saya, sekarang pun masih banyak yang tak habis pikir kenapa air “putih” saja dijual mahal. Padahal air di rumahnya, katanya, berlimpah-ruah dan terbuang percuma. Apalagi yang dari mata air, selama 24 jam terus-menerus deras mengalir ke sungai di dekat rumah, ujarnya lagi. Pendapat seperti ini mungkin saja masih membekas di hati masyarakat sampai kini. Tetapi, ya begitulah. Pendapat tinggal pendapat sementara bisnis terus bergulir. Sekarang saja, pada dasawarsa pertama abad ke-21 ini, peredaran amik semakin luas karena pabriknya kian banyak. Malah disinyalir sudah mencapai ratusan merek di tanah air ini. Satu perusahaan amik bahkan ada yang memiliki instalasi pembotolan di mana-mana. Umumnya di daerah yang kaya mata air dan dekat pegunungan. Gunung. Satu kata inilah kekhasannya. Amik-amik itu senantiasa mengklaim sumber airnya dari mata air pegunungan kemudian diolah dengan teknologi canggih dan higienis. Semuanya unjuk produk. Jadi, sesama amik pun ketat bersaing merebut konsumen. Minimal merebut citra atau imejnya (image). 211 Untuk sekadar tahu perseteruannya itu kita bisa saksikan di media massa seperti televisi dan koran. Kita dapat meniliknya dari pelbagai berita dan dari iklannya. Misalnya, iklan yang ditayangkan di TV. Dalam iklan dimaksud terlihat Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) begitu gencar mematri imej pemirsa lewat iklannya. Iklan yang berkisah tentang anak yang sakit perut itu memunculkan kalimat yang secara tegas mengajak konsumen untuk minum amik dan bukan sembarang diisi ulang agar tidak sakit perut. Lantas, di bagian akhir tayangannya dan dilengkapi dengan narasi atau cerita muncullah label Aspadin. Bisa kita simpulkan bahwa iklan itu dibuat dan ditayangkan atas biaya perusahaan amik yang tergabung dalam Aspadin. Selain itu juga ada perusahaan amik yang rutin menayangkan produknya dengan visualisasi kesegaran air pegunungan, multitahap prosesnya atau caracara lain yang mengusung kelebihan produknya. Ujud iklannya bermacam-macam dan kreatif. Secara tersirat kerapkali menyentil kompetitornya, amiku. Tentu anggarannya tak sedikit. Dari simakan saya, belanja iklannya mencapai milyaran rupiah setahun. Bukan main. Pasti mereka sudah mereka-reka, kirakira berapa rupiah keuntungannya. Sebab, potensi pasarnya sungguh tak tanggung-tanggung. Triliunan rupiah. Peluang pun terbuka lebar. Ada yang mau bisnis di sektor amik ini? Namun, sebelum Anda terjun di kancah itu ada yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya tulis tadi memang fakta. Tak hanya iklannya yang jor-joran 212 menyedot uang, tapi investasinya pun, seperti pembangunan instalasinya, betul-betul tak kepalang tanggung. Milyaran rupiah: meliputi biaya pekerjaan sipil, mekanikal-elektrikal, instrumentasi, alat dan glassware laboratorium plus zat kimianya termasuk izinnya yang berbelit bak kucing mengejar ekornya. Anda pasti akan kucing-kucingan mengurusinya. Tetapi jangan kecil hati dulu. Kalau Anda dan rekan-rekan benar-benar ingin tarung (fight) dalam sektor ini, ya coba saja. Hanya harus diingat bahwa sekarang ini semua perusahaan amik yang bermodal raksasa itu, mau tak mau, harus siap-tarung dengan depot amiku yang hadir di setiap pemukiman dan dekat perkantoran. Dari data yang saya peroleh dan analisis sepak terjang pebisnis dan manajemennya, tampak pabrik amik agak “gerah”, seperti kebakaran jenggot. Diakui atau tidak, amiku adalah pesaing barunya yang gigih menyusup di sela-sela konsumen setianya. Dan jumlah pelanggannya yang beralih ke amiku bisa dikatakan cukup signifikan. Nah, dalam pada itu, Asosiasi Pengusaha Depot Air (Aspada), tentu tak tinggal diam menyaksikan tingkah polah pelaku bisnis amik. Kendati labelnya adalah usaha berskala kecil dan cuma ratusan liter air yang terjual per hari per depotnya, tapi karena jumlah depotnya jauh melebihi jumlah pabrik amik maka tirthayudha antara dua jawara air siap minum ini berlangsung seru. Malah asosiasinya, Aspada, gencar menjawab tuduhan, klaim, dan tulisan di koran dan majalah dari orang-orang yang dianggap menyerang eksistensinya. Departemen Perindustrian 213 dan Perdagangan pun dituding menghambat lantaran menunda-nunda penerbitan regulasi bisnis amiku. Termasuk adanya tuduhan bahwa riset para periset adalah pesanan Aspadin. Bisa diduga, Aspadin tentu membantahnya. Maka, gugat-menggugat dan ancammengancam pun kerap kita baca dan dengar. Kira-kira, adakah jalan keluarnya agar kedua produsen air siap-minum ini bisa saling melengkapi dan bersama-sama melayani konsumen tanpa harus merugikan secara ekonomi dan kesehatan? Bisakah mereka harmonis berbisnis di sektor ini? Yang pasti, dalam pandangan saya, keduanya adalah “dewa” penolong masyarakat yang tidak mendapatkan suplai air PDAM dan air sumurnya tak layak diminum. Paling tidak, untuk kebutuhan minum bisa diatasi, tinggal memikirkan air buat yang lain, seperti MCK. Amik-amiku, keduanya saya sebut sebagai dewa penolong. Di pihak lain, konsumen pun adalah dewi penyelamat pabrik dan depot itu. Tanpa konsumen mana mungkin keduanya mampu hidup-berkembang seperti sekarang. Realitasnya, dua “makhluk” tadi, yaitu “dewa”-“dewi” itu semestinyalah berpasangan. Tetapi, seperti pertanyaan di atas, ada saja timbul tanda tanya mengapa bisnis amik-amiku bisa laris. Dua kubu ini memang bersaing tapi tetap saja ada konsumennya. Lalu, siapa penggagas orisinalnya? Adakah mantra ajaibnya? Baiklah. Kita analisis dulu pionirnya, yaitu perusahaan amik. Tapi tidak saya katakan apa mereknya. Nanti jadi iklan dan ada yang protes. 214 Menurut sahibul hikayat, bisnis ini bermula dari fenomena “air plastik” yang akrab pada anak-anak SD ketika kehausan dan berebut membeli air minum dalam plastik yang diikat karet. Air ini tentu bukan air olahan dari teknologi canggih seperti sekarang. Ia hanyalah air sumur yang dididihkan agar kumannya mati, didinginkan dan dibungkus plastik. Sekali lagi, cuma air sumur yang direbus sampai mendidih lalu didinginkan, dikemas dalam plastik dan diikat karet. Hanya itu. Sampai sekarang pun penjual air ini bisa kita saksikan di kota-kota kecil terutama di sekitar lapangan bola dan halaman SD. Tentu ada kisah lain. Kata yang empunya cerita, bisnis ini berawal dari musafir, yaitu pelancong dan petualang yang kehabisan air atau tidak membawa minuman karena malas, berat, tidak praktis ataupun karena gengsi. Ini terjadi di stasiun, terminal, dan pusat-pusat keramaian. Mereka sulit mendapatkan minuman yang tak bersoda, tak beralkohol, dan tak berasa. Pokoknya, mereka ingin minum air “putih” yang tak berasa, tak berbau, dan tak berwarna alias air jernih atau bening yang matang dan segar. Maka, dibidiklah musafir ini dengan air minum kemasan plastik, seperti di atas. Ada yang dilengkapi dengan pipet penyedot agar praktis ketika diminum. Tak hanya anak-anak pembelinya tapi sopir angkot, pegawai, buruh, pengamen, penganggur, dan banyak lagi yang lainnya adalah pelanggan setianya. Untuk ukuran kantong rakyat kecil, uang berdagang air ini cukup besar. Laris tiap hari. Kemudian, orang-orang berinsting tajam mengendus uang di sana. Mulailah 215 mereka memproduksi air minum dalam skala besar dengan kemasan yang bagus dan bergengsi. Jadilah mereka menangguk untung sampai sekarang. Dan sampai hari-hari mendatang! Sudah barang tentu apa yang saya tulis di atas, namanya juga kisah, adalah ilustrasi belaka. Anggap saja cerita logis yang realistis. Dan masih ada 1001 macam cerita serupa itu. Tentang fakta yang benarbenar melatarinya haruslah ditanyakan kepada orang yang mendirikan pabrik itu. Yaitu, pemiliknya. Yang pasti, amik praktis bagi konsumen karena siap-saji, ringan, bergengsi sehingga memudahkan seseorang yang bepergian antarkota. Mudah dibeli di terminal, stasiun atau warung pinggir jalan. Habis diminum, wadahnya langsung dibuang tanpa perlu membebani tas. Tapi, ada masalahnya. Kemasannya yang dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate), zat turunan petroleum yang tak kuasa diurai oleh bakteri, berserakan di mana-mana, mengambang dan menyumbat parit, selokan, gorong-gorong, dan anak sungai. Mampet. Apalagi sekarang, bidikan pebisnis tidak hanya musafir tapi juga orang-orang di rumah, kantor, para undangan upacara atau resepsi pernikahan, khitanan, ulang tahun, rapat, rumah sakit dan bahkan aktivitas demontrasi massa. Dalam acara tersebut berdus-dus amik diminum setiap hari. Kemasannya pun macammacam. Ada yang ukuran 220 ml, 300 ml, 375 ml, 500 ml, 600 ml, 620 ml, dan ada pula 1.500 ml. Juga ada yang ukuran besar (family size), yaitu 5 gallon (1 gallon = 3,785 l; jadi 5 gallon sekitar 19 l). Setiap 216 kemasan, dan ini uniknya, memiliki segmen pasar fanatik. Ada yang memilih berdasarkan kenyamanan dan ada pula karena hitung-hitungan hemat-boros. Selain bervariasi volumenya, mereknya juga begitu. Ada satu merek malah diproduksi oleh lebih dari satu perusahaan. Satu perusahaan ini memiliki anak-anak perusahaan. Apalagi namanya, macammacam. Ada yang “aneh” dan “lucu-lucu”. Ada yang mirip-mirip atau meniru merek terdahulu yang sudah dikenal dengan sedikit modifikasi. Ada juga yang rada-rada sains. Terlepas dari semua itu, yang pasti setiap merek dan produsen ingin produknya mudah dikenal, diingat, dan tentu saja dibeli. Tujuannya adalah laku. Laris. Dan ini terbukti. Di Indonesia, menurut Indonesian Bottled Drinking Water Association, IBDWA produksi amik mencapai 8,4 miliar liter tahun 2002. Taruhlah harganya seribu rupiah seliter maka total harganya adalah 8,4 triliun per tahun. Dan angka ini diprediksi terus meningkat meskipun amiku bertubi-tubi menyerbunya di setiap kota khususnya di segmen rumah tangga dan kantor. Saat ini amiku memang hanya mampu bertarung di segmen rumah tangga dan kantor. Keunggulan amik yang tidak (belum) bisa dilawan amiku ialah kemasan produk dalam volume kecil. Sampai saat ini amiku belum diizinkan terjun di segmen kemasan kecil. Padahal, ceruk inilah yang besar pasarnya. Ditambah lagi ada pernyataan seorang Kepala Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa amiku hanya tahan 24 jam (Metro, 20/8/03). Jadi, harus habis dalam satu hari satu malam, begitu katanya. Tentu 217 saja parameter yang dimaksud adalah bakteriologi, bukan kimiawi. Zat kimia, terutama mineralnya, tak akan berubah walaupun dibiarkan lama. Pembaca dan penikmat air di mana saja berada. Ada yang perlu diwaspadai. Demi melihat kelarisannya, tak ayal lagi amik ramai dipalsukan. Penjahat memproduksi amik aspal, asli tapi palsu. Caranya, botol bekasnya diisi ulang dengan air yang diolah secara sederhana dan tampak jernih lalu diberi label dan segel palsu. Pembotolan ulang seperti itu dengan tetap mencantumkan merek aslinya ini (logo palsu) jelas-jelas, menurut undang-undang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah pemalsuan. Ini tindak pidana berat. Amat berat. Kecuali produsen, yang sangat dirugikan adalah konsumen. Malah nyawa konsumen atau minimal kesehatannya menjadi taruhan. Ini tak sekadar kasus kriminal murni tapi tergolong kejahatan kemanusiaan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang meminum amik palsu. Semuanya lalu sakit! Kantor, pasar, dan jalan menjadi sepi. Rumah sakit, poliklinik, puskesmas lantas ramai. Dokter panen? Belum tentu. Bisa jadi dokter pun ikut-ikutan sakit. Bencana nasional, bukan? Contoh kasus pemalsuan amik berskala besar dari berbagai merek pernah terjadi di Bekasi pada akhir Oktober 2000. Atas kasus ini kita terhenyak lagi karena merupakan pengulangan kasus serupa. Itu pun cuma puncak gunung es. Yang tak terungkap masih banyak lagi. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang pun beredar amik “aspal” ini dari berbagai 218 merek. Tapi sayang seribu sayang, dari dulu hingga kini konsumen tetap bergeming. Diam saja. Tak mau menggugat produsen dan juga pemalsunya padahal undang-undang nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah berlaku efektif sejak 20 April 2000. Inikah bukti kegagalan sosialisasi UUPK sampai sekarang? Hingar bingar gebyarnya nyaris tak terdengar. Pesss.....sepi. Menurut hemat saya, dalam kasus pemalsuan itu produsen seharusnya bertanggung jawab. Kita tahu, produsen pasti rugi finansial dan sial secara imej. Tapi, ini pertanyaan kita, kenapa produknya mudah dipalsukan? Mengapa tidak menerakan label atau informasi yang sulit ditiru pada kemasannya? Labellogo ini pun hendaklah dipublikasikan secara terusmenerus agar konsumen tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Upayakanlah label dan angkanya komunikatif agar tak usah berpikir panjang untuk memahaminya. Apalagi kalau cetakannya tidak jelas dan samar-samar, bisa pusing kita dibuatnya. Lalu di pihak konsumen, bagaimana caranya agar terhindar dari amik palsu itu? Apalagi untuk air siap-minum ini kita hanya mampu mengidentifikasi kualitas fisikanya saja. Itu pun cuma secara visual. Dan paling-paling hanya warna dan kekeruhan. Lain dari itu, tidak bisa. Kalau air PDAM yang keruh atau berwarna, itu lumrah. Ini sering terjadi dan agak bisa “dimaafkan”. Tidak demikian dengan amik. Ia harus bening. Kemasannya tak boleh berwarna agar jelas terlihat kekeruhannya akibat padatan tersuspensi, 219 koloid atau ada penguraian zat organik oleh bakteri. Urungkanlah membelinya jika berwarna atau keruh. Berikut ini ada tips sederhana dalam memilih amik. Ini mudah dilakukan oleh siapa saja. Cobalah perhatikan kondisinya apakah dingin yang berembun atau tidak. Penjual sering mendinginkan amik dalam benaman es bersama minuman “soft drink. Pilihlah amik yang tidak dibenamkan dalam es alias tidak didinginkan. Sebab, botol dingin berembun menyulitkan kita untuk melihat langsung airnya, apakah keruh atau jenih. Apalagi kita sudah tahu bahwa air jernih belum tentu bersih. Jernih bukanlah jaminan mutu air minum. Ia cuma salah satu parameternya. Begitu juga warna botolnya. Sudah disebut tadi, jangan yang warna-warni. Yang bagus adalah bening atau tak berwarna agar tidak menipu mata. Air yang keruh, berlendir, atau kehijauan bisa tampak jernih apabila botolnya berwarna. Jadi, pilihlah yang tidak berwarna. Ini lebih aman. Mudah-mudahan. Sudah itu, bagaimana mencek kualitas kimianya? Yang satu ini memang sulit. Juga mahal kalau dilakukan secara pribadi atau perseorangan. Apalagi yang kemasannya kecil dan tidak rutin membelinya (bukan hotel, kantor atau restoran). Namun, LSM atau sekelompok konsumen dapat mengujinya ke sejumlah laboratorium air terakreditasi. Minimal ke tiga laboratorium berbeda untuk perbandingan dan dilaksanakan reguler untuk tiap merek dan kemasan. Perlu biaya, tentu saja. Namun, dengan tindakan ini diharapkan kualitas amik makin terkendali dan yang lebih penting lagi, menciutkan nyali pemalsunya. 220 Selain itu, lokasi dan jenis sumber airnya pun bisa kita lihat. Mesti dicantumkan apakah air permukaan, air tanah dalam atau mata air. Demikian halnya dengan jenis dan konsentrasi mineralnya. Harus jelas dan benar satuannya. Jangan samar-samar sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini penting karena mineral berpengaruh pada kondisi pembuluh darah, ginjal, hati, dan tulang. Data tadi pun bermanfaat jika ada gugatan karena dapat dicek dari formasi geologi sumber airnya dan kemungkinan adanya zat berbahaya dan beracun. Yang tak kalah penting ialah tanggal kadaluwarsanya. Pencantumannya sebaiknya dicetak agar tak mudah luntur bila digosok. Permanen, agar tak gampang diutak-atik. Jangan sampai terjadi produk kadaluwarsa yang kebetulan masih bagus diundur lagi tanggalnya. Hati-hati. Di sinilah peran penting Ditjen POM (Pengawasan Obat dan Makanan) agar tegas, anti-MKKN dengan produsen. Usahakanlah hasil evaluasi produk yang diawasinya itu dipublikasikan di media massa agar konsumen terbantu dan minimal membelajarkannya. Mendidiknya menjadi orang yang peduli pada kesehatan dirinya. Terakhir adalah kualitas biologi atau lebih tepat bakteriologi. Setiap produsen amik dituntut menerakan metode disinfeksinya apakah ozonasi, ultraviolet, klorinasi atau yang lainnya. Amik harus suci hama, bebas bakteri (steril) sebab langsung diminum tanpa direbus dulu sehingga syarat kualitas bakteriologinya di atas air olahan PDAM. 221 Namun tentu saja perlu pengawasan ketat. Ini penting dalam kegiatan ekonomi agar kita nyaman dan tenang saat beraktivitas. Tidak ada gejolak yang membuat masyarakat resah gelisah apalagi marah. Pengawasan harus dilaksanakan di setiap lini proses produksi, terlebih di instalasi pengolahnya. Malah wajib disertifikasi. Berikutnya adalah pengawasan di segmen transportasi, pergudangan, dan penjualan. Dalam hal sertifikasi, di sejumlah kemasan amik bisa kita lihat pencantuman frasa certified bottler. Hak-cantum ini diperoleh setelah diaudit oleh badan internasional. Begitu katanya. Tentu saja badan ini, agar adil (fair), wajib diuji juga kompetensinya. Kini kita sampai pada produsen air siap-minum yang lain, yakni amiku. Air siap-minum jenis ini mulai berkembang tahun 2000. Nyaris di setiap jalan di kota-kota sedang dan besar ada saja depot air ini. Makanya disebut bak jamur di musim hujan; tibatiba muncul serentak di sisi dan sudut pemukiman. Banyak sekali. Silakan, iseng-iseng, dicek sendiri di sekitar tempat tinggal. Seperti biasanya, kehadiran amiku ini otomatis mereduksi volume amik yang lebih dulu bermain di pasar. Ceruk pasarnya mulai terkoreksi sedikit demi sedikit, khususnya yang kemasan besar atau gallon. Amiku hingga kini hanya melayani kemasan besar. Setahu saya belum ada yang menjualnya secara legal dan terbuka dalam wadah kecil, kecuali amik aspal yang dibahas tadi. Entahlah pada masa mendatang apakah amiku juga siap menjual produknya dalam kemasan kecil. Jika ini terlaksana berarti kualitasnya 222 harus tahan dalam jangka panjang, dalam hitungan bulan. Kalau bisa malah dalam hitungan tahun. Dulu, saya tulis lagi, pernah ada polemik ketika seorang pejabat di Dinas Kesehatan berkata bahwa air amiku cuma tahan selama 24 jam. Sudut pandang secara bakteriologi ini merupakan hantaman telak bagi depot amiku waktu itu. Parameter ini mensyaratkan air siap-minum harus nihil dari bakteri. Dan ada riset di sepuluh kota bahwa 16% depot amiku tercemar bakteri E. coli (Swa, Mei 03). Ini dikuatkan lagi oleh temuan BPPOM yang mengatakan bahwa ada amiku yang tercemari E. coli dan logam berat (Metro, 28/5/03). Itu baru dari sudut pandang bakteriologi. Belum lagi kualitas kimianya. Seperti halnya amik, kualitas kimianya pun boleh jadi tak sesuai dengan baku mutu seperti yang dilaporkan BPPOM di atas, yaitu ada yang mengandung logam berat. Hulu kasus ini tak lain daripada unit operasi dan prosesnya. Pada instalasi pengolahnya. Sudah diungkap, mutu amik-amiku bergantung pada unit operasi-prosesnya. Bergantung juga pada aspek sanitasinya ketika dibotolkan dan pencucian wadahnya. Pembotolannya harus higienis. Botolnya harus benar-benar dicuci bersih, tak sekadar diucekucek lalu dibilas. Kalau cuma demikian, ada bahaya mengintai karena mikrobanya berkembang biak. Apalagi kalau ada zat organik dalam air. Ini alamat petaka. Kuman kemudian berbiak dari satu bakteri menjadi ribuan bakteri dalam tempo singkat. 223 Dengan demikian, depot amiku mau tak mau harus bersih. Mesti diakui bahwa ada depot amiku yang tidak bersih lingkungannya dan kurang saniter dalam pembotolan. Ini kait-mengait dengan pegawai dan ilmunya. Pegawai selayaknya disiplin, bersih, tahu cara mengolah air, tahu operasi-rawat instalasi, tahu fungsi setiap unit instalasi, tahu umur unitnya dan kapan harus dibersihkan atau diganti. Tentu saja harus jujur, apalagi dalam melayani konsumen. Jujur akan menguntungkan pemilik depot. Terkait dengan pembotolan tersebut ada yang perlu diketengahkan. Begini. Botol kemasan gallon pabrik amik, tandas pejabatnya, adalah aset usaha sehingga tidak boleh diisi ulang oleh depot amiku kecuali ditukar lagi dengan merek yang sama alias konsumen membeli amik lagi. Kasus ini membuat megap-megap pabrik amik lantaran botol-botolnya berkurang. Karena botolnya tidak boleh digunakan untuk amiku, maka muncullah botol serupa yang berwarna-warni dan dijual bebas di pasaran. Sekarang kita beralih ke sumber air. Pendapat saya, sumber air yang dapat digunakan untuk amikamiku tidak harus air tanah atau mata air. Tapi hal ini terpatri kuat di benak kita selama ini. Air sungai, danau, waduk, estuasi, laut pun bisa dijadikan air baku. Kasarnya, air limbah pun, seperti saya ungkap di bab terdahulu, bisa untuk air baku asalkan unit operasi-prosesnya mampu mengolah pencemar yang terkandung di dalamnya. Pembedanya tentu saja biaya investasi dan operasi-rawatnya. Makin buruk mutu air bakunya, makin mahallah investasinya dan 224 besar pula ongkos operasi-rawatnya. Harganya pun jadi ikut-ikutan mahal. Dengan demikian, air PDAM pun bisa dijadikan air baku buat amik-amiku walaupun sekitar 65% air PDAM tidak memenuhi syarat kesehatan (Metro, 20/8/03). Dalam hal ini instalasi PDAM dianggap sebagai pengolahan awal (pretreatment) yang dapat menyisihkan partikel kasar, zat tersuspensi, koloid, oksida logam, kimflok (chemiflocc), bioflok, algae, bakteri, jamur, dll. Setelah itu barulah zat terlarutnya ditangani oleh instalasi di pabrik/depot amik-amiku. Unit pengolahnya bisa berupa penukar ion (kation dan anion), sistem membran, adsorbsi (misal, karbon aktif), aerasi ataupun presipitasi kimia. Perlu dicatat, tahap pengolahan awalnya harus berfungsi optimal agar umur unit di amik-amiku menjadi panjang. Lantas mengapa selama ini dipilih mata air atau menurut klaim perusahaan amik-amiku, mata air pegunungan sebagai sumber airnya? Ongkos adalah jawabannya. Relatif murah! Air dari mata air tidak membutuhkan pompa; airnya keluar secara alami. Hemat bahan bakar dan listrik. Sangat jernih karena difilter oleh butiran tanah. Juga relatif bebas bakteri. Jadi, tinggal memperbaiki kualitas kimianya berupa zat padat terlarut (mineral). Inilah yang menjadikan biaya produksinya murah sehingga harga jualnya pun murah tapi tetap dapat laba yang signifikan. Juga lantaran ada imej bahwa air pegunungan selalu segar tanpa pencemar. Frasa tanpa pencemar ini perlu digarisbawahi. Sebab, belum tentu tanpa pencemar. Mungkin saja air pegunungan itu kaya 225 akan mineral yang justru tidak boleh berlebih dalam air minum. Ini bergantung pada bebatuan yang dilewati air tanah. Apalagi kalau unit pengolahnya tidak lengkap atau tidak mampu mengolahnya. Oleh sebab itu, kualitas amik-amiku harus dicek secara reguler oleh badan bersertifikat yang orang-orangnya kompeten di bidang ini. Sertifikasi. Inilah kata kuncinya. Terkait dengan kualitas airnya yang kerap disorot, Aspada pun ingin produknya memperoleh sertifikat kelayakan sebagai air siap-minum. Niatnya ini ditanggapi positif oleh Dinas Kesehatan dan BPPOM. Sebagai konsumen, kita pun ikut senang. Maka, sampai Desember 2003 sudah 45 depot yang bersertifikat dari 62 depot yang terdaftar di Aspada. Namun Dinas Kesehatan Kota Bandung punya catatan lain. Ada 180 depot yang terdaftar di dinas itu tapi baru 45 yang bersertifikat. Jumlah sesungguhnya diduga antara 250-300 depot (Metro, 13/12/03). Dalam keterbatasan kita, mudahmudahan jumlah tersertifikasi itu bertambah terus. Persoalannya, sertifikasi itu harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai baku mutu yang berlaku. Masalah lainnya, lembaga mana yang layak dan berkompeten merilis sertifikat itu? Ini harus dibahas secara transparan agar nihil dari nuansa MKKN. Apalagi kita paham betul akan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang begitu mudah terlibat tindak MKKN. (Semua bisa diatur asalkan tahu sama tahu; ini yang kita dengar). Inilah fakta tak terbantahkan pada masa reformasi kebablasan ini. 226 Yang terakhir tapi sangat penting adalah semua orang yang terlibat dalam bisnis air siap-minum ini hendaklah tidak demi kepentingan pribadi semata. Boleh saja ada muatan pribadi tetapi tidak sematamata. Sebab, sejauh yang namanya manusia maka tidak mungkin kita menihilkan muatan pribadi itu. Di sela-sela muatan tersebut hendaklah hadir muatan sosial. Membantu yang tak mampu mengakses air bersih lantaran kendala ekonomi, alam, dan politik. Siapa saja yang terlibat dalam bisnis ini? Benar, mereka adalah pengusaha, penguasa (misal, Dinas Kesehatan, Ditjen/BPPOM, Dept. Perindustrian dan Perdagangan, pemkab/pemkot, PDAM), DPR(D), peneliti, akademisi, supplier, pekerja pabrik/depot, LSM, dan konsumen. Adakah yang kurang, belum saya sebut? Silakan ditambah lagi. Semua lembaga dan orang tersebut di atas wajib berpijak pada kebenaran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan melacurkan ilmu dan teknologi untuk sekadar dapat uang, puluhan juta maupun milyaran rupiah. Sebab, setiap pelacur ilmu dan teknologi (iltek) sangat mungkin mengadu domba masyarakat dari anasir dan grup yang berseberangan dan beda kepentingan. Apalagi menjual harta kekayaan bangsa/negara milik bersama itu (milik si fulan yang gelandangan, juga menjadi milik si fulanah yang istri ponggawa negara), hanya untuk menggembungkan pundi-pundi pribadinya. Benar-benar bejat nian moral pelakunya bila demikian, bukan?! * 227 Siklus air Air baku bergolak di PDAM mengetuk pintu rumah pelanggan Desiran, tetesan, limpasan, bilasan, dan ricikan air limbah mendobrak selokan, saluran, dan sungai menjadi air baku lagi tapi sayang, ia ditemani oleh berbagai-bagai pencemar Sang Pembunuh-sunyi 228 13 BASMI WABAH PEMULA Air, kita butuh. Ada air, pasti sehat!? Belum tentu...! Tifus, disentri, muntaber terus mengintai. Anak-anak kena, orang dewasa pun kena. Namun..., tak ada air pasti sekarat. Kita mafhum akan hal ini. Tak semua air aman bagi tubuh kita. Ada yang jernih tetapi kaya bakteri dan tercemar. Yang kita butuhkan adalah air bersih. Jernih belum tentu bersih! Bersih artinya bebas dari mikroba patogen, tanpa zat berbahaya-beracun serta berisi mineral. Tubuh ini butuh mineral dalam kadar tertentu. Sebaliknya, air kotor adalah air yang tak layak diminum, mengandung mikroba patogen. Mikroba patogen itulah yang bisa menimbulkan wabah. Tak cuma anak-anak yang kena tetapi orang dewasa pun dalam ancamannya. Mereka menyerang kita, selain lewat makanan juga lewat minuman atau air yang tidak higienis. Kalangan petugas kesehatan 229 dan sanitasi biasa menyebutnya penyakit menular lewat air (disingkat: pemula). Dalam buku-buku teks berbahasa Inggris disebut waterborne diseases. Nah, ini dia. Pemula inilah salah satu indikator kualitas sanitasi. Ia bisa menyebar melalui feses atau tinja. Artinya, wabah klasik ini terjadi bila sanitasi masih buruk. Misalnya, krisis air bersih dan krisis hidup sehat akibat membuang hajat (tinja) ke sungai, selokan, kolam. Apalagi kalau di kebun, tegal, atau halaman belakang rumah. Di desa-desa kita, saya tak ingin menyebutkan namanya, sudah biasa dilakukan. Selain itu, juga lantaran buruknya sanitasi makananminuman kita, di desa maupun kota, tanpa kecuali! Berhubungan dengan wabah tersebut, ada kisah begini. Penduduk kota San Paulo (300.000 orang, bukan Sao Paulo) heboh. Air ledeng yang sumber air bakunya dari Danau Chavez telah tercemar. Ribuan orang jatuh sakit dan ratusan meninggal. Gejalanya, setiap penderita merasa haus yang teramat sangat setelah minum air olahan “PDAM” tersebut. Besarkecil, tua-muda, laki-perempuan semuanya kena dan sama gejalanya. Mereka akhirnya tidak berani lagi minum air itu. Jangankan diminum, untuk kumurkumur dan menyikat gigi saja tidak berani. Kebetulan tak ada lagi “PDAM” lain di kota itu. Instalasinya pun cuma satu. Dan sumber airnya dari danau itu saja. Maka bisa diduga, krisis air minum meledaklah di kota kabupaten itu. Bala bantuan pun dikerahkan dari berbagai daerah. Ribuan liter air bersih per hari dikirim dari kota-kota terdekat. Tapi, seperti biasa kita lihat dalam antrian sembako di 230 negara kita, orang-orang lantas berebut. Buas. Tak mau berbagi lagi. Terlalu mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Tentara dan polisi terpaksa turun tangan untuk mengamankan penjatahan air itu. Pilu hati menyaksikannya. Betul-betul ngeri, menyayat hati. Adapun amik yang relatif aman, melambung setinggi langit harganya. Ada yang 100 dollar per 12 ons (mahal sekali saat itu). Cuma kalangan kaya dan pejabat yang mampu membelinya. Dan ini segelintir saja jumlahnya. Tak hanya dokter dan aparat keamanan yang sibuk. Praktisi dan pakar sanitasi pun bekerja keras. Berbagai upaya dicoba. Mereka mereka-reka dan menduga zat kimia adalah penyebabnya. Awalnya yang dicurigai ialah PAC (polyaluminum chloride). PAC ini digunakan untuk mencegah karat, sebagai pengganti alum sulfat (tawas) yang telah digunakan selama 50 tahun di sana. Lalu diganti lagi dengan tawas tapi hasilnya sama. Maka disimpulkan bahwa wabah itu bukan karena PAC tapi sesuatu yang lain. Apa sesuatu itu? Setelah banyak jatuh korban, akhirnya diketahui juga biang keroknya. Bukan zat kimia, dan bukan pula akibat sabotase. Dia adalah Cryptosporidium-C. Mikroba dari grup protozoa ini mampu membentuk spora di usus halus manusia lalu menghalangi penyerapan air oleh usus. Makanya si penderita haus terus. Dan hebatnya, mikroba ini tak mempan diklorinasi (dibasmi dengan senyawa kimia berupa gas klor atau klorin); malah tahan dalam air mendidih lebih dari sepuluh menit. Kuat sekali. 231 Singkat cerita, setelah berkali-kali dicoba dan dianalisis di laboratorium barulah diketahui bahwa ozon mampu membasmi parasit itu. Sang pahlawan, yakni seorang sarjana Teknik Lingkungan yang juga operator di instalasi tersebut, lantas menggunakan ozon untuk membasminya. Tapi proses pemakaian ozon ini ternyata tidak mudah. Menegangkan. Salahsalah tangkinya bisa meledak. Tegangannya tinggi. Namun akhirnya, mereka berhasil melakukan proses ozonasi pada air baku. Si mikroba terbasmi. Aman lagilah air danau itu dan siap dimanfaatkan. Penduduk pun lega. Hidup seperti sedia kala. Dan..., demikianlah sepenggal kisah dalam film “THIRST” (haus, dahaga) produksi tahun 1998. Film ini pernah ditayangkan pada 24 Maret 2002 di Trans TV untuk menyambut Hari Air Sedunia (22 Maret). Film ini memberi kita gambaran betapa luas dampak wabah pemula dan riskan bagi eksistensi penduduk kota. Memang di film tersebut-namanya juga filmsetting-nya bahagia, happy ending. Tapi bukan tidak mungkin hal serupa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari suatu saat kelak. Yang saya tulis di atas adalah penggalan kisah Cryptosporidium dalam film. Tapi berikut ini saya bercerita tentang kisah nyata. Begini. Diare rupanya menjadi momok bagi pemerintah Amerika Serikat (AS). Makanya, Badan Pangan dan Obat (FDA) AS berupaya keras mendapatkan obat untuk melawan Cryptosporidium parvum dan Giardia lamblia, dua protozoa yang membuat pusing pemerintah Paman Sam. Keduanya sering terdapat dalam air minum dan 232 menyebabkan diare berkepanjangan pada anak-anak dan orang dewasa selama berminggu-minggu. Dalam setahun di negara itu terjadi 375 juta kasus diare; 73 juta di antaranya pergi ke dokter dan 1,8 juta dirawat inap; yang meninggal 3.100 orang. Dan biaya totalnya tak kurang dari 20 milyar dollar AS (Media Indonesia, 5/12/02). Wabah seperti itu, meskipun tidak seseram film tadi, pernah terjadi di mana-mana. Lebih-lebih lagi di negara berkembang seperti negara-negara di Asia Tenggara (termasuk Indonesia), di Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan (Sri Langka, Bangladesh, dan India). Di negara maju pun saat ini terjadi kasus serupa walau persentasenya lebih kecil ketimbang di negara berkembang. Tetapi dulu, pada waktu negara itu masih berkembang, mereka juga direpotkan oleh wabah pemula. Ini saya tulis pada paragraf berikut. Riwayat wabah Kalau dirunut jauh ke belakang, sudah ribuan tahun umur konsep sanitasi yang kini kita kenal. Ia bukanlah barang baru. Malah dalam arti yang paling sederhana bisa kita katakan bahwa konsep ini setua kehadiran manusia di Bumi. Sebab, manusia yang selalu makan dan minum pastilah perlu buang hajat (besar dan kecil) setiap hari. Maka, ia perlu fasilitas dalam bentuk yang paling simpel sekalipun. Kecuali tempat, ia tentu butuh air, kayu, daun, dan lain-lain dalam peturasannya itu. 233 Hal tadi diperkuat oleh fakta di situs arkeologi. Banyak temuan di sejumlah situs di Asia, Mesir, dan Timur Tengah yang menjadi saksi bisu tingkat ilmu penyehatan (sanitary) manusia kala itu. Perpipaan air bersih, riul, sewerage atau koleksi air limbah dan cubluk dalam ujud awalnya (prototipe) sudah ada. Tinggalan dan bekas-bekas sejarahnya membentang dari Sungai Nil di Mesir, Tigris dan Eufrat di Irak hingga Sungai Kuning di Cina. Luas nian sebaran budaya saniter itu. Contohnya adalah kebudayaan Minoan di Kreta, 4.000 tahun lalu. Masyarakatnya telah menggunakan pipa lempung (tanah liat) untuk air bersih dan air limbah. Toilet sederhana milik pribadi pun ada. Di Roma juga sama. Kekaisaran ini punya sistem suplai air bersih dan drainase di pusat kotanya. Saluran air (aquiduct) sepanjang 50 km, Nimes Aquiduct namanya, dibangun untuk fasilitas kota. Ada pula saluran untuk campuran air hujan dan air cubluk (latrines) mirip saluran air limbah tercampur zaman sekarang yang mengalir ke luar kota. Yang mengagumkan, mereka sudah punya IPAL domestik. Mereka telah menerapkan prinsip konservasi lingkungan. Tapi sayang, biarpun seabrek tinggalan sejarahnya ternyata sulit kita temukan literatur ataupun manuskrip yang mencantumkan wabah apa saja yang terjadi pada masa itu dan berapa jumlah korbannya. Nyaris tiada datanya. Yang bisa kita lakukan cuma menafsirkannya bahwa saat itu kerap terjadi wabah pemula sehingga dibuatlah sarana sanitasi tersebut. 234 Kini, mari kita lompati waktu menuju abad ke19, ke suatu tempat, tepatnya di sebuah sumur tua di bilangan Broad Street, Gold Square, London, Inggris atau United Kingdom. Kita perlu menengok sumur ini karena dialah “penebar” wabah pemula di sana pada waktu itu. Korbannya tak kurang dari 10.000 orang atau menjadi sekitar 20.000 orang bila wabah akibat polusi di Thames, sungai sepanjang 338 km dari Costwolds sampai North Sea, turut disertakan. Sebuah angka fantastis dari 1,25 juta orang warga London pada masa itu. Mason menulis, polusi di sungai itu telah terjadi sejak abad ke-13 dan makin parah pada abad ke-18 setelah dipasangi riul tahun 1843. Riul inilah yang melikuidasi 200 ribuan jamban warganya. Hanya sayangnya, kata Mason, air limbah riul itu langsung dialirkan ke Thames tanpa pengolahan terlebih dulu. Padahal sebelumnya isi jamban-jamban itu dikuras secara periodik lalu dibuang ke ladang untuk pupuk. Maka, meledaklah wabah “hitam” pada 1849-1854 dan, untuk mengenangnya, dijadikan pilar klasik sejarah wabah pemula. Adalah John Snow, dokter kerajaan Inggris saat itu, yang membuktikan bahwa ada korelasi positif antara wabah dengan air sumur yang tercemari rembesan air limbah domestik (sewage). Pasalnya, yang sakit bukan cuma warga di dekat sumur melainkan juga yang tinggal di luar kota dan pernah minum air sumur itu ketika lewat di sana. Dengan hipotesisnya itu Snow lalu mencabut tangkai pompa sumur agar airnya tak bisa diminum lagi. Dan terbukti. Sejarah 235 kemudian mencatat, wabah itu reda. Perlu dicatat, fakta itu terjadi sebelum konsep penyakit menular lewat air berbasis mikrobiologi dari Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis, ditemukan pada akhir abad ke-19. Dalam putaran waktu terbukti bahwa wabah itu tidak hanya terjadi di Inggris tapi juga di negaranegara lain, bahkan di benua lain selama kurun satu abad berselang. Sekitar tiga puluh tahun pascawabah di London itu, di Tokyo Jepang juga terjadi kolera. Penderitanya 162.637 orang (105.786 orang tewas). Ini terjadi tahun 1879. Kemudian, tahun 1886 wabah ini menyerang 155.923 orang (108.405 orang tewas). Padahal pada era Meiji itu, kota Tokyo (Edo) mulai peduli pada sanitasi. Malah di Amerika Latin pada tahun 1991 wabah kolera kembali beraksi. Awalnya adalah penemuan Vibrio cholerae, bakteri kolera di pantai Peru pada Januari 1991 yang akhirnya meluas ke segala arah di Amerika Latin. Korbannya dari 1991 sampai 1995 mencapai 1,34 juta orang; 11.300 orang di antaranya meninggal (sekitar 1% dari kasusnya). Di Afrika dan negara miskin lainnya seperti Bangladesh dan India sama saja. Untunglah wabah di atas sudah tidak ada lagi (mudah-mudahan demikian) di Indonesia, meski wabah lainnya, secara sporadis kerap juga muncul. Contohnya, muntaber yang menyerbu pemulung di kawasan kumuh di Pulo Gadung, Jakarta Timur (Kompas, 1/8/01). Muntaber ini termasuk salah satu penyakit perut, intestinal, atau gastroenteritis yang ditransmisikan lewat feses. Mikroba patogen dalam 236 feses antara lain virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Rute penularannya disebut rute amul (anus-mulut), yakni dari feses penderita kemudian masuk ke mulut lalu ke perut orang lain yang sehat. Rute ini bisa langsung dari orang sakit ke orang sehat melalui jari tangan atau tak langsung lewat makanan atau air. Adapun kolera dan tifus punya siklus panjang, long cycle. Seorang penderita dapat menyebarkan kuman patogen melalui tinja atau muntahannya yang dibuang ke sungai, selokan, kolam, riul, atau muka tanah. Air hujanlah yang menyebarkan kuman itu ke segala penjuru. Semakin banyak penderitanya kian banyaklah sumber siklusnya sehingga penderitanya cepat bertambah. Eksplosif! Feses penderitanya pun bahkan masih mengandung kuman kolera sekitar 1-2 minggu pascasembuh. Maka, dia pun kini menjadi pembawa (carrier) penyakit. Sebenarnya kasus pemula tak mengenal musim kemarau dan musim hujan. Walau demikian, kasus muntaber sering terjadi pada musim kemarau karena sumber-sumber airnya mengalami reduksi debit dan buruk kualitasnya. Termasuk di sini adalah air tanah dangkal seperti sumur gali. Bahkan di Jakarta nyaris 90% air tanahnya sudah tercemari bakteri dan zat kimia di samping masalah intrusi air laut yang telah menyusup ke Monas. Di kota lain tak jauh berbeda. Maka..., riwayat wabah tersebut akan ajek ada; tak terduga-duga. Ia bertandang ke rumah ketika kita tak peduli pada sanitasi. Dengan tiba-tiba saja dia “merobek-robek” perut kita, perut anak-anak kita, perut saudara kita, kemudian mengisap cairan tubuh 237 kita, lalu lunglailah kita, dan... sekarat dalam tempo singkat. Sakaratul maut menjemput. Tapi saya yakin, kita tak mau mati konyol hanya lantaran si jasad renik yang bercokol di perut ini. Masa sih, kita mau kalah terus dari serbuan si superkecil ini. Menyerah? Jangan sekali-kali! Oleh sebab itu, upayakan pembasmiannya. Salah satu caranya..... Disinfeksi. 238 Cara disinfeksi Inilah tahap akhir... ujung dari pengolahan air. Terjadi di reservoir... Disinfeksi, ini nama prosesnya, ditujukan untuk membasmi (destruksi) mikroba patogen yang ada di dalam air. Caranya ada empat: (1) fisika, dengan mendidihkan air 100oC selama 10-15 menit (nyatanya, air tidak selalu mendidih pada 100oC. Apabila tekanan udaranya tidak satu atmosfer, maka titik didihnya di bawah 100oC), pembekuan (freezing), dan ultrasound; (2) mekanis, terjadi di unit pengolah air minum, misalnya di filter pasir lambat dan cepat (slow & rapid sand filter), ultrafiltrasi, dan osmosis balik; (3) radiasi, menggunakan sinar UV, X, dan gamma (); (4) kimia, memakai fenol, ozon, klor (gas atau padat, misal kaporit: kalsium hipoklorit), klor dioksida (ClO2), kalium permanganat, atau hidrogen peroksida. Lalu, ada persyaratan zat untuk disinfeksi atau disinfektan atau biosida. Persyaratannya: (1) toksik bagi mikroba pada konsentrasi yang tidak berbahaya bagi manusia-hewan; (2) cepat bereaksi membunuh bakteri dengan waktu kontak yang singkat; (3) tahan lama agar mampu menanggulangi rekontaminasi di zone distribusi; (4) ekonomis (murah) dan mudah diperoleh; (5) mudah dianalisis di laboratorium; dan (6) mudah menentukan dosisnya. Selain syarat tersebut juga ada sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas disinfeksi: (1) waktu 239 kontak; makin lama waktu kontaknya makin banyak bakteri yang terbunuh; (2) temperatur air; makin tinggi temperaturnya makin cepat reaksi disinfektan dengan enzim dalam bakteri sehingga mempercepat kematiannya; (3) jenis dan konsentrasi atau dosis disinfektan; kemampuan setiap disinfektan berbedabeda dalam membunuh bakteri dan keefektivannya meningkat pada dosis tinggi; (4) jumlah mikroba; makin banyak jumlah mikrobanya makin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk membasminya; (5) jenis organisme; ada yang mudah dibasmi, ada yang sulit karena berspora; (6) keadaan air; pembasmian di air jernih lebih mudah daripada di air keruh. Secara garis besar beberapa cara itu saya kupas berikut ini. Adapun cara pemanasan yang biasa kita lakukan di rumah, tidak saya bahas di sini. Ini sudah lumrah kita laksanakan setiap hari. Sedangkan cara pendinginan, misalnya dimasukkan ke kulkas atau ditimbuni es, pun biasa kita lakukan pada makanan untuk mencegah perkembangbiakan bakteri. Disinfeksi: klor Sejarahnya, paling tidak menurut catatan yang saya peroleh, senyawa klor pertama kali digunakan sebagai disinfektan, biasa disebut proses klorinasi, dalam penyediaan air minum di Jersey City, New Jersey, Amerika Serikat tahun 1908 oleh George Johnson dan John Leal. Makanya sejarah disinfeksi identik dengan sejarah klorinasi. Di Indonesia, kalau orang menyebut disinfeksi air PDAM berarti 99,9% 240 adalah klorinasi, baik ujudnya gas klor maupun yang padat, kaporit. Senyawa ini, menurut sebuah bukuajar, ditemukan oleh ahli kimia yang juga apoteker asal Swedia bernama Scheele (1742-1786). Dalam sistem periodik (tabel semua unsur atau zat kimia berikut sifat-sifatnya), unsur klor termasuk golongan halogen (VIIA) yang memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Tujuh elektron ini sangat stabil sehingga cenderung mengoksidasi pada setiap reaksi kimia (sebagai oksidator kuat) untuk melengkapi jumlah elektronnya menjadi delapan di kulit terluar (outer shell). Pada suhu kamar klor berujud gas; klor yang larut cenderung menguap atau tervolatilisasi ke udara. Dibandingkan dengan yang terhidrolisa maka jumlah yang menguap sangat kecil karena prosesnya begitu cepat, sedetik pada temperatur 20oC dan lebih lambat lagi (beberapa detik) pada 0oC. Disinfeksi kimiawi dengan klor dan/atau kaporit banyak digunakan PDAM untuk membasmi bakteri, algae dan bau. Setelah diinjeksikan atau dibubuhkan dalam reservoir, kisaran waktu kontaknya antara 1530 menit. Upayakan tak ada aliran singkat (shortcircuiting) agar disinfeksinya efektif. Misal, dengan memasang sekat-sekat (baffle) baik secara vertikal maupun horisontal di sepanjang reservoir. Hendaklah ada sensor untuk mengetahui konsentrasi klor dalam air. Pada umumnya dosis total klor bervariasi antara 0,2-40 mg/l (White, dari Droste, 1997). Keuntungan menggunakan zat ini ialah ada sisa klor. Sisa yang diharapkan 0,2–0,5 mg/l. Sisa klor ini dibutuhkan apabila di ruas pipa distribusi terjadi 241 rekontaminasi (air kotor berbakteri masuk ke pipa) akibat kebocoran. Sisa klor inilah yang diharapkan membasmi bakteri di air kotor itu. Hanya saja pada saat yang sama klor pun bereaksi dengan zat organik dalam air lalu membentuk THM (trihalomethanes) yang karsinogenik, pencetus kanker. Serentetan data awal dari percobaan pada binatang menyatakan bahwa ada korelasi antara klorinasi dan penyakit jantung (kardiovaskuler). Tentu perlu dievaluasi lagi apakah benar atau tidak. Kira-kira apa solusinya? Yang pasti, senyawa THM tersebut takkan terjadi jika digunakan ozon. Disinfeksi: ozon. Ozon (O3) adalah disinfektan yang kuat. Lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Efektif. Sudah digunakan di IPAM kota Nice, Prancis tahun 1906 (Droste, 1997). Selain sebagai disinfektan, ozon juga sebagai pengendali rasa (taste) dan bau. Dan dapat menghancurkan prekursor limbah halogenasi seperti THM, haloasetat, dan haloasetonitril yang terbentuk pada proses klorinasi. Juga lebih destruktif, papar Manahan, terhadap virus ketimbang klor. Serta kuat mengoksidasi zat anorganik. Pendeknya, ozon jauh lebih efektif mengoksidasi ketimbang klor dan permanganat. Terkait dengan ini, menurut Tate, sudah ada 2.000-an unit IPAM di Prancis, 50-an di Kanada, 40-an di Amerika Serikat yang menggunakan ozon (Droste, 1997). Adapun di 242 Indonesia, ozon kebanyakan diterapkan di instalasi amik. Biasanya digabung dengan sinar UV. Dalam mengoperasikan IPAM dengan ozon ini memang diperlukan operator yang skilnya tinggi. Zat yang dihasilkan pada tegangan 20.000 volt (ozone generator) tersebut mahal investasinya. Mahal juga operasi-rawatnya. Sudah itu sistem distribusinya tak boleh bocor karena ozon tak punya sisa ozon seperti halnya klor yang memiliki sisa klor. Ini lantaran dekomposisi ozon menjadi oksigen dalam air begitu cepat. Kelarutannya di air relatif rendah sehingga membatasi daya disinfektifnya. Waktu kontaknya di dalam reservoir biasanya 10-15 menit (Manahan, 1994). Dan waktu paruh tipikalnya (half-life), menurut Droste, sekitar 20 menit. Seandainya disatukan dengan radiasi UV, baik dari matahari (surya) maupun lampu, maka kemampuan ozon dalam menguraikan asam humat dan zat organik lainnya semakin kuat. Disinfeksi: surya Kemampuan sinar surya (matahari) membunuh bakteri (germicidal) telah dikenal luas. Radiasi surya adalah semua jenis radiasi matahari yang mencapai bumi setelah melewati atmosfer. Ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu radiasi ion seperti sinar X dan gamma dan radiasi nonion yang terdiri atas sinar tak tampak (ultraviolet dan infrared) dan rentang sinar tampak (warna pelangi, mejikuhibiniu). 243 Radiasi surya dapat digunakan untuk membasmi mikroba (bakteri) berbahaya yang ada di dalam air. Proses fotokimia ini memanfaatkan energi foton yang diabsorbsi bakteri. Rentang panjang gelombang maksimum yang diabsorb bakteri adalah 260-265 nm (nanometer. 1m = 109 nm). Semua energi foton yang diabsorbsi (emisi langsung, pantulan ataupun hamburan) sangat potensial sebagai disinfektan. Radiasi surya khususnya ultraviolet (UV) dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dengan rentang 400-100 nm. Ada juga yang mengatakan antara 4004 nm. Rinciannya: UV-A: panjang gelombangnya 320-400 nm; UV-B: 280-320 nm; UV-C: 200-280 nm; dan UV ekstrim atau UV vakum: 100-200 nm (Acra, 1990). Namun ingin saya sampaikan bahwa ada sejumlah angka berbeda menyangkut rentang panjang gelombang itu. Dari beberapa buku dan makalah yang saya baca, demikianlah adanya. Sedangkan rentang panjang gelombang yang punya kemampuan untuk membasmi bakteri ialah 280-200 nm (di atas disebut 260-265 nm). Menurut Sterrit, radiasi dengan panjang gelombang 250-300 nm-lah yang potensial/mampu membasmi bakteri. Germisida atau biosidanya tinggi. Walau demikian, tentu ada kendalanya. Efisiensinya akan turun kalau airnya keruh atau ada zat yang mengabsorbsinya. Tetapi sayang, serupa dengan ozon, kita tidak bisa mendapatkan sisa UV. Konsekuensinya, apabila ada rekontaminasi di sistem distribusi PDAM berarti air tersebut mesti didisinfeksi lagi agar tidak berbahaya. Minimal dididihkan (100oC) selama 10 menit. 244 Lalu bagaimana mekanisme “pembantaian” itu? Seperti halnya gelombang yang lain, radiasi surya yang mencapai unit disinfeksi ini pun mengalami absorbsi, refleksi dan transmisi; ini bergantung pada panjang gelombang radiasi yang datang, sudut jatuh radiasinya, indeks biasnya, koefisien absorbsi dan ketebalan bahan alat/reaktornya. Itulah yang besar pengaruhnya pada derajat-bantai atas bakteri, selain variabel lainnya. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses disinfeksi dengan UV adalah intensitas radiasi surya. Dan hal ini dipengaruhi oleh letak geografis daerah, meteorologi, musim dan posisi matahari. Adapun media transmisi radiasi dipengaruhi oleh bahan dan dimensinya serta mutu airnya seperti kekeruhan, temperatur, kadar garam serta jenis dan konsentrasi mikroba yang akan dibasmi. Di antara parameter tersebut yang paling tinggi pengaruhnya adalah intensitas radiasi. Radiasi ini mampu merusak membran sel bakteri, asam nukleat (DNA) dari sistem enzimnya dengan panjang gelombang 254 atau 253,7 nm. Hanya saja, masih mungkin terjadi mekanisme pulih kembali atau fotoreaktivitas oleh radiasi berpanjang gelombang lebih besar dari 300 nm. Fenomena basmi-pulih ini ternyata begitu kompleks reaksinya sehingga perlu perhatian serius pada disinfeksi surya karena dapat menimbulkan bahaya jika proses pengolahannya tidak sempurna. Adapun keunggulan primanya adalah dari sisi kemudahannya dalam memperoleh pancaran energi surya yang gratis sepanjang tahun khususnya daerah 245 atau negara-negara tropis. Hanya saja, seperti di negara kita ini, langit sering ditutupi awan terutama pada musim hujan. Keuntungan lainnya, tidak ada konsumsi zat kimia sehingga tak perlu bak tampung, tidak ada transportasi, dan aman; waktu kontaknya singkat; tiada limbah (by-product) berbahaya, dan persyaratan energinya rendah. Pengembangannya yang masih diperlukan ialah cara menampung radiasinya itu agar dapat berfungsi pada malam hari atau ketika tidak ada radiasi surya saat mendung atau hujan. Untuk tindakan preventif pada saat tidak ada sinar surya maka dapat disiapkan radiasi UV artifisial dari lampu neon/merkuri. Inilah yang diterapkan di pabrik amik dan amiku. Variabel yang memengaruhi disinfeksi dengan sinar surya ialah (1) intensitas, yaitu: lokasi geografi, musim, kondisi meteorologi (kelembaban, curah hujan, kondisi awan), sudut jatuh sinar; (2) lama pemaparan; (3) media transmisi, terdiri atas: unit reaktor (bahan dan ketebalan), dimensi saluran dan air: kekeruhan, temperatur, salinitas, oksigen terlarut dan nutrien, predator dan disinfektan; (4) jenis atau macam mikroba: tipe dan strains, konsentrasinya. Disinfeksi: klor dioksida, ClO2 Biosida yang saya bahas sekarang ini masih ada sangkut-pautnya dengan rumpun senyawa klor. Tapi ada bedanya. Di dalam bukunya, Droste menulis bahwa daya oksidasi senyawa ini 2,5 kali klor. Ini berarti, lebih efektif dibandingkan dengan gas klor 246 (Cl2) apalagi kaporit [Ca(OCl)2]. Sejarahnya, biasa digunakan untuk menghilangkan rasa dan bau akibat fenol. Dan salah satu keunggulannya dibandingkan dengan klor ialah tidak memproduksi THM yang mutagenik dan karsinogenik itu; malah mengurangi timbulan (produksi) zat yang memicu pembentukan atau prekursor THM. Efisiensinya pun tidak bervariasi terhadap pH air sebagaimana gas klor dan kaporit yang jelas-jelas dipengaruhi oleh pH. Pun mampu mengoksidasi besi dan mangan dengan baik daripada klor. Juga tidak bereaksi dengan amoniak/amonium sehingga tidak ada kebutuhannya berkaitan dengan zat tersebut. Hanya saja perlu hati-hati karena gas klor dioksida sangat reaktif-eksplosif jika kena cahaya. Makanya, gas ini dibuat di tempat injeksinya (di instalasinya atau onsite) dengan proses reaksi antara gas klor dan natrium hipoklorit (NaOCl). Demikianlah... Kupasan ringkas disinfeksi usai di sini. Proses yang menjadi bagian penting di dalam pengolahan air minum ini ternyata banyak opsinya. Dari alternatif yang beragam itu bisa dipilih satu yang paling sesuai dengan kondisi air, tujuan serta biayanya. Tetapi ingat, apapun cara yang kita pilih selalu saja ada si kembar, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Namun kita bisa memilih yang paling aman dan relatif murah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, gabungan beberapa cara kerap ditempuh. Tapi tidak berarti bisa mereduksi keku247 rangannya secara maksimal. Belum lagi kompleksitas masalahnya yang muncul akibat gabungan itu. Termasuk dari sisi finansial, pasti mahal biayanya. Ini otomatis. * Ternyata, jasad renik mampu meng-KO manusia. Membungkam keangkuhannya. 248 Air itu: tirtha nirmala, tirtha kamandalu, amrta njiwani (Sansekerta), maaul hayat (Arab), nectar-ambrosia (Yunani), the elixir of life, the liquid of life (Inggris). 249 14 “WABAH” PETAMULA Awas! Racun dalam air. Tak terlihat, tapi membuat kita sekarat. Entah sudah berapa kali disinggung di buku ini bahwa banyak zat kimia yang dapat larut dalam air termasuk zat berbahaya dan beracun. Tapi untunglah konsentrasi zat berbahaya itu secara umum dan ratarata tak begitu besar. Namun masalahnya, pada saat ini ada ribuan atau malah ratusan ribu pencemar berdatangan dari pertanian, perkebunan, domestik, komersial, dan industri lalu masuk ke air tanah dan air permukaan seperti sungai, danau, dan laut. Jadi, air tidak hanya menyebarkan wabah diare dan disentri tetapi juga menimbulkan penyakit yang tak menular namun berbahaya. Penyakit tak menular lewat air yang disingkat petamula ini asalnya dari zat kimia yang larut dalam air minum akibat polusi tadi. Atau, justru berasal dari zat kimia dalam proses pengolahan air dan dari peralatan instalasi seperti jenis pipa dan bahan tangki yang digunakan. 250 Di negara yang sanitasinya sudah baik sehingga wabah pemula nyaris tidak ada lagi, justru penyakit inilah (petamula) yang potensial; adapun di negara berkembang termasuk Indonesia, insidensi keduanya relatif besar sekalipun pemula lebih sering diberitakan secara nasional dan internasional. Barangkali penyakit akibat minum air yang tak higienis ini tertutupi penyakit lain yang disebabkan oleh mikroba dalam makanan dan minuman kemasan (kalengan). Terkait dengan efek kesehatan zat kimia dalam air, sifatnya bisa dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama, efek akut: segera terlihat dampaknya akibat minum air yang tercemari zat berbahaya-beracun. Yang kedua, efek kronis: dampaknya tampak atau terasa pascakontaminasi jangka panjang. Biasanya sudah terlambat sehingga sulit dipulihkan. Dikaitkan dengan PDAM, pelanggan bisa kena dampaknya kalau terjadi kecelakaan yang disengaja seperti sabotase atau murni lantaran teledor (human error). Kasus ini bisa terjadi mulai dari sumber air, pipa transmisi air baku hingga di instalasi dan sistem distribusinya. Bayangkan jika ada orang “gila” yang frustrasi akan hidupnya dan siap menjadi maniak pembunuh jutaan orang dan siap menghuni neraka jahanam dengan cara meracuni sumber air PDAM. Ini betul-betul petaka buruk. Buruk bagi eksistensi manusia sebab mampu melenyapkan orang sekota. Tapi mudah-mudahan saja orang begini ini, sebelum sempat niatnya terlaksana, sudah sekarat duluan. Sudah kualat dan tamat riwayatnya. 251 Jadi, semua segmen di PDAM riskan dan rentan dari “serangan” para penjahat, bandit, dan manusia durjana bermental inferior. Penjahat kemanusiaan. Besar potensinya menjadi sumber petaka. Makanya perlu pengamanan khusus (dan ini belum dilakukan) tidak saja oleh PDAM, pemerintah daerah-pusat, dan aparat penegak hukum tapi juga oleh masyarakat. Ayolah bahu-membahu mengamankan sumbersumber air kita, baik dari tindak kriminal maupun dari penjarah bersafari, berjas, berdasi yang bangga menamai dirinya investor. Investor serigala berbulu domba. Kalau tidak demikian, yang rugi tentu rakyat Indonesia, si empunya tanah air ini. Selain pelanggan PDAM, perlu juga diwaspadai oleh warga yang bukan pelanggan. Mereka pun bisa kena dampaknya terutama yang memakai air sumur. Kasus peracunan sumur yang pernah merebak pada akhir dekade 1980-an dan akhirnya diketahui cuma terjadi satu-dua kasus adalah contohnya. Pengguna air sungai pun, dan ini masih banyak di pedesaan, mesti hati-hati. Misalnya, menggunakan batu padas seperti jembeng di Bali, juga potensial keracunan terutama dari limbah pertanian (pestisida). Belum lagi dari peracunan yang disengaja. Namun biasanya, pada kasus pencemaran dan aksidensi atau kecelakaan yang serius, air tidak akan enak rasanya atau baunya tidak sedap sehingga tidak lantas diminum. Kalau telanjur masuk ke mulut dan rasanya pahit atau “aneh”, biasanya secara refleks kita pun menyepahnya. Inilah salah satu mekanisme pencegahan secara alami. 252 Atau, kalau tertelan juga segeralah telan karbon aktif, misalnya tablet norit, agar racunnya diserap (diadsorbsi). Namun masalahnya adalah kalau zat itu tidak menimbulkan bau dan warna yang mengubah warna air; atau bisa juga karena konsentrasinya amat rendah sehingga tanpa curiga kita langsung meminumnya. Timbullah petaka itu. Keracunan! Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama dalam air minum adalah zat berbahaya dan beracun dalam konsentrasi rendah namun menerus. Sedikitdemi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sebab, kita baru merasakan dampaknya setelah terpapar lama. Sesudah teracuni selama bertahun-tahun. Contohnya ialah zat karsinogenik pencetus kanker dari grup PAH (polyaromatic hydrocarbon), dari grup THM (trihalomethanes), dan organochlorine plus organophosphorous. Semuanya harus serendah-rendahnya dalam air minum. Kalau bisa, hingga nol koma nol mikrogram per liter. Kendati demikian, masih ada batas konsentrasi yang diizinkan, yaitu konsentrasi yang masih mampu dideteksi oleh detektor yang paling sensitif. Namun masalahnya, adakah detektor supersensitif itu? Jika ada, punyakah PDAM alat itu? Kalau punya, sudah rutinkah dicek? Berapa kali? Berapa dan dari mana biayanya? Andai sudah dilaksanakan secara berkala, apakah PDAM mengumumkan hasil ujinya itu ke pelanggannya? Dan seterusnya dan selanjutnya. Ini penting. Apalagi masyarakat cuma terpaku pada soal kejernihan atau kebeningan dan tak peduli atau tak tahu soal mutu kimianya yang justru lebih bahaya. 253 Pascabahasan tentang potensi pencemaran zatzat kimia, baik yang disengaja maupun tidak sengaja akibat kegiatan ekonomi masyarakat seperti industri, pertanian, dan domestik, sekarang ini kita memasuki bahasan tentang potensi pencemar dalam air minum yang berasal dari zat kimia dan lumrah digunakan dalam pengolahan air. Kita tahu, semua pun tahu. Air sungai begitu keruh. Kaya bakteri. Juga sampah. Dan limbah lainnya. Begitu air keruh itu keluar dari instalasi PDAM menuju tangki atau reservoir airnya, air sungai itu sudah jernih, bebas bakteri atau jumlahnya masih dalam batas toleransi. Kondisi demikian terwujud karena ada zat kimia yang dibubuhkan dalam proses pengolahannya. Zat yang ditambahkan ke dalam satu atau lebih unit pengolah, baik untuk penjernihan, disinfeksi maupun untuk stabilisasi atau pengatur pH (tingkat keasaman) air ini biasa disebut reagen. Dan faktanya, setiap reagen selalu mengandung kotoran (pengotor). Yang terbaik tentu saja yang bebas pengotor. Semurni mungkin dan tidak berbahaya-tidak pula beracun. Beberapa zat yang terlibat dalam pengolahan air dibahas ringkas di bawah ini. Masih banyak lagi zat kimia lain yang bisa dan biasa digunakan. Apalagi mereknya, pasti bermacam-macam. Lain pabrik, lain namanya; tapi kandungan zatnya, bisa saja sama. 254 a. Tawas atau alum sulfat Aluminum sesungguhnya terkandung dalam air tanah dan air sungai secara alamiah. Dalam proses pengolahan air atau lebih tepat adalah penjernihan air diperlukan koagulan untuk memisahkan zat padat penyebab kekeruhan seperti koloid dan padatan tersuspensi (suspended solid). Yang biasa digunakan adalah tawas karena harganya murah dan mudah diperoleh. Selain itu juga bisa digunakan ferisulfat. Fungsi senyawa tersebut ialah untuk menghilangkan kestabilan koloid atau destabilisasi agar koloid bisa bergabung menjadi besar dan berat, membentuk flok sehingga mudah mengendap. Pada proses ini biasanya dilarutkan juga polimer untuk membantu penggumpalan. Polimer ini mirip tangan-tangan yang menjalar-jalar kian kemari lalu merengkuh banyak koloid dan menggabungkannya dengan yang lain. Dengan proses kimia ini, setelah melewati unit pengendap atau sedimentasi, air baku yang keruh sudah lumayan jernih. Tinggal disaring lagi di filter. Namun demikian, dan ini persoalannya, air yang dihasilkannya kaya akan aluminum. Apalagi tawas bisa mengandung krom dan merkuri yang berasal dari bahan bakunya, bauksit. Keduanya termasuk zat berbahaya-beracun. Sumber lainnya adalah alat pemanas air seperti panci dan teko. Nyaris setiap keluarga memiliki alat ini. Aluminum dalam air minum bisa tinggi konsentrasinya karena kita menggunakan panci aluminum. Apalagi kalau airnya asam atau merebus masakan berasam (pH-nya rendah). Aluminum yang tinggi 255 konsentrasinya dalam air minum dapat menimbulkan problem kesehatan. Telah diketahui ada indikasi meningkatkan penyakit alzhemir, alzheimer (pikun, ketuaan). Karena itulah banyak yang lantas menggantinya dengan besi sulfat atau garam besi sebagai koagulan. Secara ekonomis, senyawa ini lebih mahal daripada tawas. Namun bukan berarti masalahnya kemudian lenyap seketika. Sebab, besi pun berefek samping. Walaupun kita perlu zat besi tetapi kalau kelebihan tentu tidak baik bagi kesehatan. Begini salah, begitu salah? Terus, bagaimana jalan keluarnya? Nah, yang perlu dicari adalah cara agar dosisnya tepat dan airnya jernih agar tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ternak. Inilah kewajiban PDAM untuk mencarikan dosis optimumnya agar pelanggan setianya tidak sampai sakit ginjal akibat aluminum dan harus rutin cuci darah (hemodialisis). Dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dana dan tenaga kerja. Produktivitas lantas meningkat. Minimal membantu pencapaian cita-cita Indonesia Sehat 2010. b. Kalsium (dan magnesium) Air tanah umumnya kaya kalsium dan magnesium. Apalagi yang ada di formasi batu kapur atau gamping. Keduanya dapat menyebabkan kesadahan (hardness), yang didefinisikan sebagai keberadaan kation-kation logam multivalen (valensi 2 atau 3) di dalam air yang konsentrasinya cukup tinggi. 256 Kesadahan air ada dua macam, yaitu kesadahan temporer dan kesadahan tetap. Air sadah tidak baik bagi kesehatan. Apabila konsentrasinya terlalu tinggi bisa membahayakan ginjal dan hati. Air sadah juga memboroskan sabun (sodium soap) sebab sabun itu bereaksi dengan kation multivalen lalu membentuk endapan (presipitat) sehingga surfaktannya hilang. Sabun takkan berbusa sampai semua ion penyadahnya habis diendapkan. Kerugian lainnya, endapan kesadahan ini dapat melekat di alat-alat plambing seperti wastafel, bidet, kloset, bathtub, urinal dll sehingga menjadi kusam, tak sedap dilihat. Warna kain dan porselen pun bisa memudar. Ini memboroskan uang. Malah pori-pori kulit kita pun bisa tersumbat sehingga kasar dan tak nyaman rasanya. Makanya kesadahan air perlu dikurangi. Yang biasa dilakukan adalah dengan cara pelunakan atau softening, selain dengan cara pemanasan untuk jenis kesadahan temporer. Salah satu prosesnya dikenal dengan nama kapur-soda, menggunakan kapur dan soda abu. Bisa juga dengan soda api. Ini tentu saja untuk mengolah debit yang besar seperti di PDAM dan tidak ekonomis untuk perorangan. Pelunakan ini otomatis akan meningkatkan ion natrium dalam air minum yang juga riskan bagi hati, ginjal, jantung. Natrium berasal dari material tanah yang hancur, bersifat reaktif sehingga banyak kita jumpai dalam air. Garam natrium mudah larut dalam air. Apabila kadarnya sangat tinggi dapat menyebabkan rasa asin–pahit. Natrium pun bersifat korosif 257 pada permukaan logam dan toksik pada tanaman bila kadarnya tinggi. Belum lagi zat pengotor yang ada dalam kapur seperti stronsium dan barium atau organoklorin yang berasal dari proses pembuatannya. Bahkan kapur ini boleh jadi terkontaminasi krom dan seng. Bertambah lagilah potensi bahayanya. c. Timbal (timah hitam, plumbum) Logam berat ini bisa berasal dari pipa, bisa juga dari tangki air. Pipa-pipa lama PDAM banyak yang berbahan atau berlapis timbal. Juga bisa berasal dari PVC, alat makan keramik berglasur, bensin, cat, aki, baterei, dan kabel. Tentu saja sumber asupan utamanya ialah makanan, antara 100-300 g/liter. Adapun kadarnya di tanah 5-25 mg/kg tanah; di udara kurang dari 1 g/m3; di air 1-60 g/liter (Lu, F. C, 1995). Historisnya, penggunaan pipa berlapis timbal ini kemudian memunculkan kata atau istilah plumbing dan plumber. Plumbing (plambing) ialah instalasi pipa dalam bangunan/gedung. Tapi sekarang maknanya meluas ke setiap instalasi pipa di suatu tempat, apakah itu di kapal, di pabrik, dll. Yang dialirkannya pun tidak hanya air tetapi juga minyak, oli, lumpur (sludge), dan bisa juga gas. Adapun plumber dalam arti leksikal atau kamus ialah orang yang profesinya sebagai tukang ledeng. Namun di Jurusan Teknik Lingkungan istilah itu dikhususkan buat mata kuliah instalasi pipa di dalam gedung, baik untuk air bersih, air limbah dan pipa ventilasinya, pemadam kebakaran (sprinkler), dan 258 air hujan (talang dan atapnya). Termasuk alat-alat semacam pompa, katup, reservoir, alat ukur, lubang pembersih/clean out, dll. Kalau air yang dialirkannya lunak, maka timbal dapat larut sehingga konsentrasinya menjadi tinggi di pelanggan PDAM. Kita bisa keracunan setelah terpapar kontinu selama bertahun-tahun atau jangka waktu lama. Apalagi kalau ada asupan dari sumber lain tentu makin parah akibatnya. Bisa menginhibisi atau menahan pembentukan sel darah merah, terjadi kerusakan ginjal dan sistem saraf. Terkait dengan itu, Masyarakat Eropa mematok kadar timbal 50 g/liter. Tapi taraf ini sulit dicapai karena kebanyakan airnya bersifat pelarut timbal (plumbosolvent) atau justru pipa-pipanya berbahan timbal. Cara menghindarinya tak lain dari mengganti pipanya dengan pipa nontimbal. Atau, pH-nya diatur agar airnya tidak asam dengan penambahan kapur dan/atau soda kaustik. Tentu ini menambah ongkos produksi air olahan PDAM. Namun, kalau demi kesehatan kenapa harus irit? Sebab, kalau nanti sakit pasti akan keluar duit juga, kan? Selain timbal masih ada logam toksik lainnya yang larut dalam air. Dalam kadar rendah logam ini berbahaya bagi manusia dan organisme lain. Logam toksik yang larut dalam air itu ialah arsen, barium, kadmium, krom, merkuri, dan perak. Logam ini bisa terkumpul di tubuh organisme yang tertinggi dalam suatu rantai makanan. Dan, tentu saja, yang menjadi sumbernya tidak hanya air tapi juga beras, jagung, gandum, dan sayur-sayuran. Apalagi kalau tanaman 259 tersebut dibudidayakan di tanah yang baru saja kena letusan gunung api. d. Nitrat dan nitrit. Senyawa nitrogen ini muncul alamiah di tanah sehingga air tanah dan air permukaan menjadi kaya akan kandungannya. Pertanian yang intensif seperti pemakaian pupuk nitrogen dapat pula meningkatkan nitrat dalam air baku PDAM. Begitu juga air limbah domestik, pasti kaya nitrat. Senyawa nitrat agak tidak berbahaya bagi orang dewasa namun sangat berbahaya bagi bayi di bawah usia 6 bulan. Di bawah usia itu bayi belum punya flora (bakteri) normal dalam ususnya sehingga tidak mampu menangani produk nitrit akibat reduksi nitrat di dalam perutnya. Jika bayi mengonsumsi banyak nitrat ada kemungkinan darahnya menyerap nitrit sehingga transportasi oksigennya terganggu. Lantas muncullah sakit methemoglobinemia atau blue-baby diseases: tubuh bayi membiru. Methemoglobin atau MetHb ialah salah satu bentuk hemoglobin yang besinya dioksidasi menjadi bentuk trivalen dan tidak bisa mengangkut oksigen. Efeknya fatal! Kemudian, kalau ada pestisida dalam air maka nitrit dapat bereaksi membentuk nitrosamines, zat yang diketahui bersifat karsinogenik dan mutagenik (menyebabkan mutasi pada makhluk) (Zakrzewski, 1991). Selain itu dampak lainnya adalah hipertensi. Dalam kasus keracunan kronis bisa mengakibatkan depresi umum, sakit kepala, dan gangguan mental. 260 e. Fluorida Zat yang satu ini hadir secara alami di air baku. Dalam banyak literatur dan iklan pasta gigi, fluorida diklaim dapat mencegah kerusakan gigi karena ada efek inhibitornya, khususnya pada anak-anak. Oleh karena itu, fluorida direkomendasikan hingga 1 mg/l dalam air minum. Kalau kurang dari 1 mg/l bisa terjadi karies gigi (dental caries); tapi kalau lebih dari 1,5 mg/l gigi dan tulang bisa rusak; ini disebut dental fluorosis. Jadi, zat ini berguna jika kadarnya pas dan berbahaya kalau kurang atau lebih. Dengan kata lain, penanganannya harus hati-hati. Kendati begitu, berikut saya tuliskan hasil riset yang berhubungan erat dengan fluor. Dalam buku Kesehatan Lingkungan (Soemirat, 1996) disebutkan bahwa terjadi kasus penyakit Mongoloid pada bayi yang ibunya minum air berkadar fluor tinggi. Terjadi 23,6 kasus per 100.000 orang pada ibu-ibu yang minum air berkadar fluor antara 0,0-0,1 ppm; 71,6 kasus per 100.000 orang pada ibu yang air minumnya mengandung 1,0-2,6 ppm. (Catatan: ppm=part per million= bagian per sejuta=mg/l). Kemudian, pada kasus keracunan yang berat bisa terjadi cacat tulang, lumpuh atau kematian. Ada juga hasil riset yang mengejutkan, bahwa ada kaitan antara fluorida dengan kanker tulang (diriset pada tikus). Lantaran itulah perlu ada tinjauan ulang atas baku mutu air untuk keperluan minum, khususnya fluoridasi. Air yang defisiensi (kekurangan) fluorida biasanya difluoridasi setelah unit filter atau karbon aktif. Yang umum digunakan ialah natrium fluorida 261 (NaF), natrium silikofluorida (Na2SiF6), dan asam fluorosilikat (H2SiF6). Namun pada umumnya konsentrasi fluorida di air tanah dan air permukaan melebihi syarat di atas. Konsentrasinya dalam air tanah biasanya lebih tinggi daripada air permukaan. Di beberapa tempat bahkan sangat tinggi. Karena saya belum memperoleh data di negara kita, maka saya hanya menyantumkan data di mancanegara. Ada data menyebutkan bahwa di India sampai 19 mg/l. Di Afrika lebih dari 50 mg/l; dan di Kanada 4,5 mg/l (Droste, 1997). Kadar ini membahayakan kesehatan manusia jika tidak ada pengolahan. Makanya harus ada unit defluoridasi. Misalnya ion exchanger, presipitasi kimia, alumina aktif (butir zeolit alami), adsorpsi/absorpsi, dll. Sebenarnya masih banyak zat berbahaya yang potensial ada dalam air baku dan air olahan PDAM. Yang dibahas di sini ialah yang langsung berkaitan dengan pengolahannya, yaitu yang dibubuhkan atau dilarutkan. Itu pun sekelumit. Masih panjang tabelnya. * 262 Air tak hanya menyebarkan diare dan disentri tapi juga menimbulkan penyakit tak menular namun berbahaya. Asalnya dari zat kimia yang larut dalam air minum akibat polusi. Atau, justru berasal dari zat kimia dalam pengolahan air dan dari peralatan instalasinya. Penyakit itu dari makanan dan minuman. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan dan minumlah yang halal dan toyib (thayyib: bersih, yakni tidak berbahaya-beracun, higienis, bergizi) 263