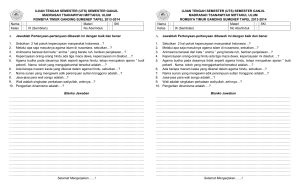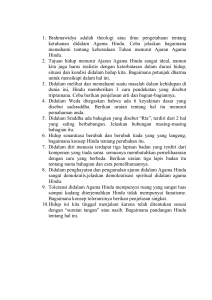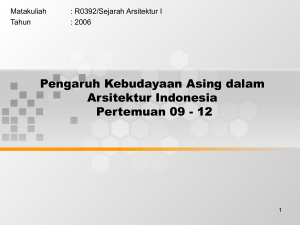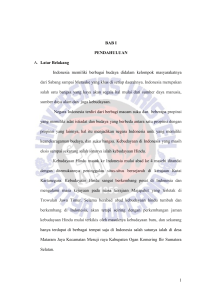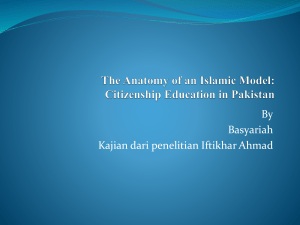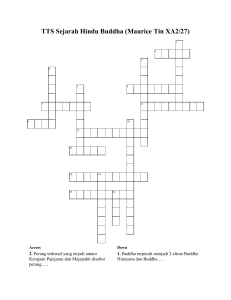GITANJALI MUSIM gugur tahun 1947, tidak ada tempat bagi umat
advertisement

GITANJALI MUSIM gugur tahun 1947, tidak ada tempat bagi umat Hindu di Pakistan. Mereka harus memilih India atau kematian. Dan, tidak ada tempat pula di India bagi umat Islam. Kaum Muslim harus memilih Pakistan atau kuburan. Sesaat lagi, bis terakhir yang akan ditumpangi umat Hindu yang berada di Pakistan, segera melaju ke India. “Kuharap kau tidak membenci Islam, Ammaji,” ujar putri Suniya, Radha, di antara lautan umat Hindu di Pakistan yang mengungsi menuju India. “Meskipun Muslim, Rahima dan suaminya menyelamatkan aku dari pembantaian dan pemerkosaan. Bahkan, tak hanya diriku yang mereka selamatkan. Puluhan umat Hindu juga berlindung di ladang-ladang dan gudang mereka.” Saat mendengar penjelasan Radha, Suniya merasa dirinya diceburkan hidup-hidup ke dalam kobaran api yang disulut dengan perasaan bersalah. “Lihatlah, kami sangat mirip, Ammaji,” tutur Radha dengan senyum lebar. Segaris suka-cita membiaskan pelangi di wajahnya yang diselimuti mendung kesedihan. “Bila aku dan Rahima memakai saree atau shalwar kameez dengan gaya yang sama, orang-orang pasti sulit membedakan kami. Setiap aku berkaca, aku akan selalu melihat wajah Rahima dipantulkan permukaan cermin. Bukankah ini mukjizat?” Suniya tiba-tiba merasa sangat lelah. Di hadapan matanya, berdiri seorang perempuan bernama Rahima yang sangat mirip dengan Radha. Mereka memiliki paras bagai pinang dibelah dua. Tidak hanya sama-sama cantik, tapi juga cara menggerakkan leher dan tersenyum. Masihkah Suniya mengingkari perempuan bernama Rahima adalah putri sulungnya? “Radha,” pinta Rahima, “Naiklah ke dalam bis lebih dulu. Aku dan ibumu ingin berbicara sebentar.” 1 “Jadi, kalian telah saling mengenal?” tanya Radha agak bingung. “Rahima benar, Radha,” sahut Suniya tanpa menghiraukan pertanyaan Anjali. “Izinkan kami berbicara berdua. Nanti, Ibu akan menyusulmu.” Radha menatap canggung ke arah Rahima. Rahima mengangguk tenang. Perlahan-lahan, Radha memeluk Rahima. “Aku takkan pernah melupakanmu, Behanji!” seru Radha sebelum melangkah menuju bis. Setelah Radha menghilang ke dalam bis, jarak di antara Suniya dan Rahima semakin menyusut. “Aku tidak pernah mengatakan pada Radha bahwa diriku adalah kakak kandungnya. Bukankah itu yang Ibu inginkan?” ujar Rahima. “Maafkan aku, Nak,” ujar Suniya terbata-bata. “Tidak apa-apa,” sahut Rahima. “Aku tidak bisa menyalahkan Ibu. Bagaimana pun, Ibu berusaha menyelamatkan masa depan adik kandungku.” “Kau dan seluruh dewa-dewi pun tahu,” tutur Suniya sambil menggenggam kedua tangan Rahima sehingga membuat jarak di antara mereka lenyap, “aku bukanlah ibu yang baik. Tapi, bila kau bersedia kembali menjadi Gitanjali-ku, aku bersumpah mengabdi padamu di seluruh sisa usiaku.” “Kami minta semua orang Hindu yang menuju India segera masuk ke dalam bis!” teriak seorang polisi India di kejauhan. Suniya dan menatap Rahima menatap polisi berperut gembul itu. Cukup dengan mengaku Hindu, Rahima akan menjelma putri sulung Suniya yang bernama Gitanjali. Mereka bisa naik ke bis bersama, berangkat ke India, dan kembali berkumpul sebagai keluarga di Calcutta. *** Setelah menghilang di Sungai Gangga, lima belas tahun yang lalu, Suniya menganggap Gitanjali telah mati. Waktu menghilang, Gitanjali berusia delapan tahun. Suniya memakamkannya di dasar jiwanya. Pemakaman itu berlangsung tanpa pelayat, tanpa bunga, tanpa lantunan Veda, dan tanpa upacara. Suniya berharap, bayangan gadis cilik itu memudar dalam ingatan. Ia tak menduga, menjelang terpisahnya Pakistan dan India, putri sulungnya bangkit dari kematian. 2 “Apakah engkau memiliki putri lain?” tanya seorang pedagang kain sutra yang mengaku bernama Rahima. Ia singgah di rumah Suniya di awal musim semi. “Apa maksudmu?” “Apakah Ibu memiliki seorang putri lagi, selain Radha?” Pertanyaan itu bagai jarum yang menusuk dada Suniya. Kepiluan masa lalu tiba-tiba menyergap dirinya. Perlu beberapa menit baginya untuk lepas dari cengkraman masa lalu. “Ya, Nak,” tutur Suniya gemetar. “Aku memiliki seorang putri sebelum kelahiran Radha. Namanya kuambil dari karya Rabindranath Tagore. Gitanjali. Sayangnya, ia telah mati tenggelam di Sungai Gangga.” “Oh, Ibu,” ujar Rahima. “Putrimu yang hilang di Varanasi, Gitanjali, masih hidup. Ia tidak tenggelam di Sungai Gangga.” “Bagaimana kautahu begitu banyak?” desis Suniya nyaris tak percaya. “Sewaktu kau sembahyang di Sungai Gangga,” tutur Rahima, “kau meninggalkannya di Ghat Tulsi, bukan?” “Benar, Nak,” ujar Suniya dengan nada harap-harap cemas. Kerinduan setinggi Himalaya mencuat di dada Suniya. “Nah, tiga orang sadhu telah menculik dan menjualnya sebagai pelacur.” Saat mendengar kata pelacur, sebuah genta berukuran raksasa seolah menghantam kepala Suniya. Kerinduan setinggi Himalaya itu hancur seketika. Perutnya tibatiba mual. Ia nyaris muntahkan di tumpukan kain-kain sutra dagangan itu. “Tiga tahun lalu, seorang pemuda Muslim menebus harga Gitanjali pada mucikarinya,” sambung Rahima tanpa memperhatikan perubahan raut wajah Suniya. “Lalu membawanya ke Pakistan dan menikahinya. Kini, mereka dikaruniai sepasang anak kembar. Setelah Gitanjali menceritakan tentang nenek mereka di Calcutta, sepasang anak kembarnya memaksa untuk dipertemukan dengan Anda. Ia dan suaminya mengerahkan segala cara untuk mencari dirimu.” 3 Rahima terus bercerita mengenai Gitanjali. Tapi, Suniya tidak lagi berminat mendengarkan penjelasan Rahima. Kata ‘pelacur’ dan ‘menikah dengan Muslim’ telah membuat semua yang dituturkan Rahima menjelma kabar buruk. “Aku mengenal Gitanjali sebagaimana aku mengenali diriku sendiri,” jelas Rahima menutup kisah Gitanjali. Dengan gerakan perlahan, ia melepas gelung rambutnya dan membiarkannya tergerai membingkai wajahnya. Suniya tergeragap. Matanya terbelalak. Sebuah wajah jelita meretakkan pagi musim semi. Bila suami Suniya, Raam, menatap Rahima—lelaki tua itu tentu tidak bisa membedakan Rahima dengan Radha. Saat itu pula, Suniya sadar bahwa Rahima adalah Gitanjali! Suniya ingin memeluk dan menenggelamkan Gitanjali ke dalam pelukannya. Saat tangannya mulai membentang dan menggapai-gapai, ia melihat rajah bertulisan Arab di tangan Gitanjali. Itu membuat langkah Suniya surut ke belakang. Suniya merasa, sebuah jarak yang mencapai ribuan tahun cahaya, membentang di antara dirinya dan putrinya yang hilang. Gadis yang lahir dari rahimnya, telah dicemari sekelompok sadhu, menjadi pelacur, dan kini menjadi istri seorang pria Muslim. Di tangan gadis itupun telah dirajah nama seorang muslimah ‘Rahima’. Tidak hanya kehormatannya saja yang telah menguap ke langit, tapi juga agamanya pun tergadai. Bila gadis itu kembali ke dalam pelukannya, tak ada orang Hindu yang akan akan minum satu gelas pun di bawah atap rumahnya. Pertunangan putrinya yang bernama Radha dengan putra saudagar terkaya di Calcutta, terancam dibatalkan. Siapakah yang ingin menjadi bagian dari keluarga bekas pelacur yang murtad? “Gitanjali selalu merindukan dirimu,” tutur Rahima dengan mata yang memijarkan bara kerinduan. Suaranya yang sebening denting-denting kristal membangunkan Suniya dari lamunan. “Tidak, Nak!” bantah Suniya dengan bibir bergetar. “Gitanjali yang kau kenal bukanlah putriku! Sebab, Gitanjali yang lahir dari rahimku, benar-benar telah tenggelam di Sungai Gangga dan tewas lima belas tahun yang lalu.” “Apakah mayatnya ditemukan?” tanya Rahima dengan nada kecewa. 4 Suniya menggigit bibir dan membisu seribu bahasa. Setelah menggelung kembali rambutnya, Rahima membungkus kembali kain-kain sutra dagangannya ke dalam buntelan. Airmata luruh di kedua belah pipinya. “Baiklah, Ibu,” ujarnya sambil menghapus lelehan air mata dengan punggung tangannya. Ia telah kembali menjadi Rahima. “Aku akan memberi tahu Gitanjali bahwa engkau bukanlah ibunya.” Perlahan-lahan, Rahima bangkit dengan buntelan berisi dagangannya. Pinggangnya yang terbuka secelah di antara lipatan kain saree, menampilkan kulitnya yang berwarna kuning bercahaya. Dengan kelembutan angin musim semi yang membelai ranting-ranting pohon neem, ia meninggalkan Suniya yang diremukkan perasaan berdosa. Seiring mendekatnya hari pernikahan Radha, kesibukan Suniya semakin banyak, sehingga ia melupakan kedatangan Rahima atau Gitanjali. Ia menyiapkan satlara mutiara dan seperangkat perhiasan emas untuk Radha. Selain itu, ia menyiapkan lima belas saree dan seprai serta sarung bantal dari sutra. Raam telah menyediakan tandu yang dihiasi emas untuk mengantar Radha ke rumah pengantin lelakinya. Mereka mengundang seluruh bangsawan dan berusaha tidak memedulikan perselisihan Hindu dan Islam yang semakin meruncing tajam. Namun, sehari sebelum pesta pernikahan itu, India dan Pakistan terbelah kedua umat beragama tersebut. Muslim diusir ke Pakistan. Hindu diusir ke India. Seorang pemuda Muslim yang telah lama jatuh cinta pada Radha, nekad membawa kabur calon pengantin itu ke Pakistan. Sementara Raam tenggelam dalam dasar rasa malu yang luar biasa, Suniya menumpang bis pengungsi Muslim yang bergerak menuju Pakistan. “Aku tak ingin putriku mati untuk kedua kalinya!” bisik Suniya sepanjang perjalanan menuju Pakistan. Setiba di Pakistan, dengan bantuan kepolisian India, Suniya memeriksa setiap penganut Hindu di Pakistan. Di tengah malam, ia mengaturkan sesaji di reruntuhan kuil. Sambil berdoa, ia membenturkan kepalanya di kepingan patung Shiwa dan Parvati. Berharap dewa-dewi kasihan dan mengembalikan Radha. Bagaimana pun Suniya memohon, patung-patung itu hanya diam membisu. 5 Sungguh, Suniya tak menduga. Pada hari terakhir yang menjadi batas waktu keberangkatan Hindu di Pakistan menuju India, dua perempuan yang memiliki wajah yang sama, menyongsongnya: Rahima (Gitanjali) dan Radha! *** Kini, Suniya kembali berdiri di hadapan putri sulungnya yang pernah menyamar menjadi pedagang kain sutra. Berbeda dengan India dan Pakistan yang telah terpisah, mereka yang terpisah malah menenyatu erat. Mereka pun masih bergenggaman tangan dan tak rela melepaskan. Sebelumnya, Suniya menyangka putri sulungnya itu akan menimbulkan malapetaka. Tapi, sosok yang dianggap pembawa malapetaka itulah yang menyelamatkan Radha serta sebagian umat Hindu yang beruntung mendapat perlindungan keluarga kecilnya. Deru mesin bis terakhir membangunkan Suniya dan putri sulungnya dari masa lalu. Mereka berhadapan dengan satu pilihan yang terus merenggangkan jarak antara India dan Pakistan. “Sungguh, aku selalu mendambakan berkumpul dengan seluruh keluarga kita. Tapi suamiku, Irsyad, telah menjadikan diriku ratu di hatinya. Kini, rumahku di Pakistan,” tutur putri sulung Suniya dengan nada yang tak terpatahkan. Angin musim gugur mempermainkan dupatta yang menutupi kepalanya. “Kau membenciku?” Suniya menahan tangis. “Sebelum bersujud di masjid, aku telah berdoa di seluruh kuil yang kutemui,” tutur Rahima sambil melepaskan genggaman tangan Suniya. “Jika Tuhan berada di kedua rumah ibadah itu, mereka pasti menyaksikan bahwa aku tidak pernah membencimu Ibu. Aku selalu mendoakan kebahagiaanmu” Rahima melanjutkan, “Meskipun tubuhku telah dicemari ratusan lelaki, cintaku padamu lebih suci daripada embun pagi. Entah diriku bernama Gitanjali atau Rahima, rasa hormatku padamu, tidak pernah tergerus waktu. Entah diriku Islam atau Hindu, dirimu tetaplah ibuku. Entah Tuhan manapun yang aku sembah, engkau abadi dalam jiwaku. India dan Pakistan boleh saja berpisah, tapi dalam cinta, kita takkan pernah berjarak.” 6 Perlahan-lahan, putri sulung Suniya merangkul lengan suaminya, Irsyad. Di pelukan Irsyad, sepasang anak kembar menatap riang pada Suniya. “Selamat jalan, Nenek!” teriak mereka sambil lambaikan tangan dalam kepungan awan debu. “Siapakah yang mengajarkan mereka memanggilku Nenek?” bisik Suniya dalam hati sambil terus menyeret tubuh ringkihnya menuju pintu bis. Ketika berada di dalam bis, Suniya untuk menatap ke luar jendela. Pada detik-detik yang seharga nyawa manusia itu, ia menoleh ke arah keluarga putri sulungnya dan membalas lambaian tangan sepasang anak kembar tersebut. “Selamat jalan, Nenek!” teriak dua bocah itu sekali lagi. Itulah terakhir kali dalam hidup Suniya bisa menatap Gitanjali dan keluarga kecilnya. Saat itu pula, makam dalam jiwa Suniya porak-poranda. Di dalam liang makam itu, Suniya tidak menemukan apa-apa selain hati-nya sendiri. Tangis Suniya memecah siang dan mematahkan hatinya menjadi dua kepingan yang sama besar. Perlahan-lahan ia menyadari, bukan Gitanjali yang mati dan dimakamkan lima belas tahun lalu, melainkan hatinya sendiri. Bila hatinya tidak mati, ia tentu memilih anak kandungnya daripada segala bentuk kejayaan dan kehormatan. Namun, cinta putri sulungnya yang ia duga telah mati, meniupkan nyawa bagi hatinya. Perlahan-lahan, jarak ribuan tahun cahaya antara ia dan putri sulungnya, remuk menjadi kepingan-kepingan ganjil yang tak berbentuk dan tak bermakna. “Hanya orang-orang kuat yang memiliki cinta. Hanya orang-orang memiliki cinta yang bisa memaafkan dan mendamaikan. Semoga India dan Pakistan dipimpin orang-orang yang penuh cinta,” bisik Suniya sambil mengingat ketulusan putri sulungnya. Dalam bayangan Suniya, putri sulungnya bagaikan Sungai Gangga—tetap suci walau dicemari ribuan kali. “Sebagaimana kisahku dan Gitanjali, setiap bangsa tidak bisa memilih awal yang indah,” bisik Suniya sebelum terlelap karena kelelahan, “tapi selalu ada pilihan untuk menemukan akhir yang indah.” Bis terakhir yang membawa umat Hindu terus melaju ke India, membawa separuh hati Suniya menuju India dan meninggalkan separuh lagi di Pakistan. [...] 7