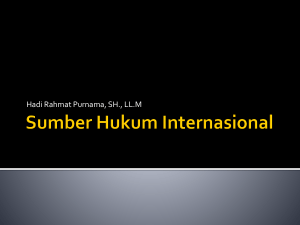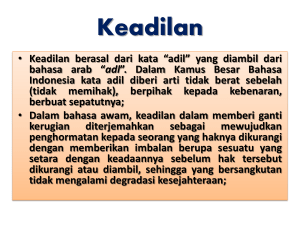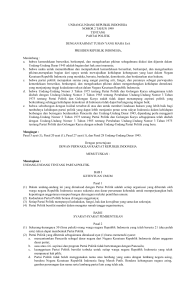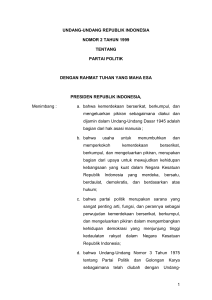menggapai keadilan konstitusi - Konsorsium Reformasi Hukum
advertisement

MENGGAPAI KEADILAN KONSTITUSI SUATU REKOMENDASI UNTUK REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI KRHN USAID @2008 DRSP BAB I PENDAHULUAN A. Mengapa UU MK Harus Diubah? Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam system ketatanegaraan Indonesia, telah memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan negara hukum yang demokratis. Kehadiran MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dapat dianggap sebagai kemenangan terhadap supremasi hukum dan konstitusi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari kekuasaan peradilan, MK adalah institusi peradilan yang bisa menjaga dan menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak konstitusi (basic rights) warga negara. MK merupakan perwujudan mekanisme cheks and balances, yang berfungsi membatasi kekuasaan mayoritas, sekaligus bertindak sebagai hakim yang dapat menundukkan masalah politik sesuai dengan rel konstitusi. Jadi, betapa penting dan strategisnya peranan MK dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peranan itu berangkat dari perubahan evolusioner terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme, yang menghendaki produk legislasi harus merujuk dan bersumber pada perintah imperative konstitusi. Hal itu terjadi seiring dengan menyusutnya gagasan kedaulatan parlemen dalam praktek demokrasi, sekaligus menguatnya gagasan centralized system sebagai akibat dari lunturnya kepercayaan terhadap decentralized system1 dalam kekuasaan peradilan. Gagasan-gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam perubahan konstitusi baru, yang digunakan pula sebagai koreksi terhadap system pemerintahan otoriter oleh rezim pemerintahan demokratis. MK merupakan salah satu pertandanya, dan kemudian tumbuh berkembang di negara-negara demokrasi baru di kawasan Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin dan Asia.2 Tak terkecuali Indonesia, yang telah memutuskan membentuk MK melalui amandemen konstitusi (UUD 1945) pada tahun 2001. 1 System decentralized mengandung pengertian bahwa kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas produk legislasi dilakukan oleh semua organ pengadilan (hakim). Sedangkan centralized system adalah kebalikannya, yang hanya memberikan kewenangan tersebut kepada satu institusi peradilan. Mengenai hal ini lihat dalam, Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford Universyty Press, 1989, hal. 132-133. 2 Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University Press, 2003, hal. 8-10. Sejak terbentuk Agustus 2003, hingga kini MK telah menjalankan 3 (tiga) dari 5 (lima) kewenangan yang telah ditentukan konstitusi. Kewenangan tersebut adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (constitutional review), memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Sejak awal pembentukan hingga saat ini, kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, merupakan kewenangan yang paling sering dilakukan. Kurang lebih dua puluh (20) perkara pengujian undang-undang yang diperiksa dan diputus MK dalam setiap tahun. Untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), MK telah memeriksa dan memutus 10 perkara. Pada perkara sengketa hasil pemilu tahun 2004, MK telah memutus 45 perkara dari kasus yang diajukan 23 partai politik, 21 perkara yang diajukan anggota DPD, dan 1 perkara diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.3 Sedangkan kewenangan lainnya, berkaitan dengan pembubaran partai politik dan pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden, hingga kini belum dilakukan. Bersamaan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, MK membangun dan mengembangkan organisasi kelembagaannya (capacity building). Selain telah memiliki gedung yang sangat representative, MK berhasil membangun system administrasi peradilan (judicial administration system) yang dapat memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang baik kepada publik. Publik, terutama para pemohon dapat memperoleh informasi setiap perkembangan perkara yang ditangani MK. Putusan-putusan MK, tidak hanya dapat diketahui dengan cepat melalui publikasi media massa dan website MK, tetapi dapat diperoleh secara gratis. Dengan kata lain, prinsip-prinsip peradilan yang cepat, mudah, murah dan transparan telah diterapkan oleh MK. Suatu hal yang nampaknya masih sulit dipraktekkan pada institusi peradilan umum ataupun institusi negara lainnya. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan dalam praktek penyelenggaraan MK. Permasalahan yang seringkali menjadi sorotan adalah berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK, terutama dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang. Tidak jarang putusan MK sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra. Dalam hal ini, beberapa putusan diantaranya dianggap merupakan putusan yang ‘progressif’ dan bersejarah (landmark decisions). Sebaliknya, ada juga putusan-putusan yang 3 Lihat dalam, Empat Tahun Mengemban Amanat Konstitusi 2003-2007, Mahkamah Konstitusi, 2007, hal. 19. kemudian dinilai janggal, membingungkan sekaligus mengecewakan.4 Kontroversi lainnya adalah, ketika sejumlah putusan MK dinilai ‘melanggar’ prinsip yang melarang hakim mengabulkan melebihi tuntutan atau permohonan (ultra petita).5 Terkadang dalam mengadili dan memutus perkara, MK bertindak ‘melampui kewenangan’ dengan memasuki ranah legislasi. Bahkan kemungkinan besar terjadi conflict of interest ketika MK harus menilai dan mengadili dirinya sendiri. Disisi lain, putusan MK seringkali tidak segera ditindaklanjuti dengan merevisi undangundang yang telah dibatalkan. Pemerintah dan DPR sangat lamban dan cenderung tidak merespon secara positif putusan-putusan MK. Ini bisa berakibat terjadinya kekosongan hukum. Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding), terkadang bak macan diatas kertas. Bergigi tapi tidak begitu efektif. Putusan final merupakan putusan pertama dan terakhir, yang dapat dimaknai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Putusan final yang semestinya dipatuhi, faktanya malah diabaikan bahkan ditolak oleh aktor-aktor negara judicial maupun non judicial.6 Akan tetapi, bagaimana jika dalam putusan final terdapat kekeliruan? Hal ini pernah terjadi misalnya dalam perkara sengketa hasil pemilu, dimana MK dinilai ‘salah hitung’ yang berakibat hilang atau bergesernya hak kursi seseorang.7 Bagaimana dengan putusan MK dalam perkara lainnya? Meski sebagian belum terlaksana, tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi persoalan yang sama. Bisa jadi kontroversi dalam putusan MK, karena ada sudut pandang, pemahaman dan juga ‘kepentingan’ yang berbeda dalam memaknainya. Sebagaimana hakim MK yang kerap kali berbeda tafsir atau pendapat (dissenting atau concurring opinion) dalam putusan. Kemungkinan pula 4 karena pengaruh dari keluasan dimensi issue atau persoalan (politik, Beragam penilaian dari sejumlah kalangan antara lain, Asian Human Rights Comission (AHRC), “MK Gagal Mencatat Sebuah Sejarah Dalam Gerakan HAM di Indonesia”, Publikasi, 2 Nopember 2007; Adnan Buyung Nasution, “Quo Vadis Hukum dan Peradilan Indonesia”, Kompas, 22 Desember 2006; Todung Mulya Lubis, “Tiga Putusan MK”, Kompas, 31 Januari 2005; Refly Harun,” Kontroversi Putusan MK”, Koran Tempo, 22 Pebruari 2005; Marwan Mas, “Pro Kontra Putusan Judicial Review MK”, Sinar harapan, 4 Agustus 2004. 5 Misalnya, putusan MK terhadap UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 40/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional; UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial; UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi. 6 Lihat, “Theo Divonis 6 Tahun, Putusan MK Tak Dipakai”, Kompas, 26 Agustus 2006. Juga “UU Migas: MK Ingatkan Presiden untuk Patuhi Putusan MK”, Majalah Mingguan Gatra, 10 Oktober 2005; “PGRI Tolak Putusan MK”, Radar Cirebon, 18 April 2008. 7 Lihat, “Sifat Final dan Mengikat Putusan MK Digugat Lewat Permohonan Fatwa”, http://hukumonline.com/detail.asp?id=10539&cl=Berita, diakses 16 April 2008; Juga, Suara Pembaruan, “MK Diminta Koreksi Putusan Perkara Dahlan Rais”, 18 Juni 2004. ekonomi, hak asasi manusia, pidana, dan perdata) yang mesti diputus MK dalam perkara pengujian undang-undang. Sehingga memaksa putusan MK bersikap ‘moderat’, tetapi disisi lain menjadi ‘tidak tegas’. Demikian halnya ketika putusan MK tidak implementatif, besar kemungkinan karena selalu dihadang oleh kompleksitas masalah yang mengemuka ditahap aplikasi putusan final. Namun jika dibiarkan terus berlangsung, dapat dipastikan akan melahirkan ketidakadilan, menciptakan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan terhadap MK. Ini tentunya menjadi persoalan serius yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Disadari bahwa putusan-putusan MK memiliki dampak yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beragam persoalan dan respon yang muncul mengiringinya, mendorong keinginan kuat untuk melihat dan mempertanyakan kembali peraturan perundangundangan tentang MK. Sejauh mana peraturan perundang-undangan, khususnya UUMK (UU No.24/2003), telah mengatur secara lengkap dan memadai. Sebab, putusan sebagai hasil dari pelaksanaan kewenangan, memerlukan tatacara (hukum acara) yang dapat menuntun dan menjadi pedoman terlaksananya kewenangan dengan baik. Adakah yang keliru dalam pengaturannya, ataukah belum secara lengkap UUMK mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara? Apabila UUMK sudah mengatur secara lengkap, sejumlah persoalan yang muncul dapat diantisipasi. Tentunya selain dapat mendukung pelaksanaan kewenangan yang akan berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil. Sebagaimana diketahui UUMK memang belum memberikan pengaturan secara lengkap bagi kebutuhan terselenggaranya peranan MK. Masih terdapat sejumlah pertanyaan atau permasalahan dalam UUMK yang memerlukan rincian, penjelasan dan penegasan lebih lanjut.8 Kelemahan dan kekurangan itu dirasakan ketika UUMK diterapkan, terutama dalam hal ketika MK menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Berbagai kelemahan dan permasalahan dalam UUMK tentu saja memerlukan perbaikan dan perubahan. Perubahan yang setidaknya dapat dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menyangkut aspek hukum acara, akan tetapi menyangkut juga persoalan lain yang diperlukan bagi pengembangan dan penguatan peranan MK kedepan. 8 Catatan-catatan terhadap sejumlah permasalahan yang ada dalam UU MK, setidaknya dapat dilihat dalam, KRHN, Hukum Dan Kuasa Konstitusi, KRHN, 2004. Bandingkan pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Fajrul Falakh dalam, “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna” Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Nomor 3, 2006, hal. 112-114. Sekalipun MK telah membuat beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), terutama berkaitan dengan hukum acara, kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim konstitusi, serta tata cara untuk pemilihan Ketua MK. Namun demikian, PMK tersebut belum cukup memadai untuk menutupi kelemahan UUMK dan menunjang pelaksanaan kewenangan MK kedepan. Selain karena legitimasinya kurang kuat, meskipun dibenarkan atas perintah UUMK, PMK tidak bisa digunakan untuk menjawab dan mengatasi seluruh kekurangan dan problem yang muncul dari UUMK. Misalnya, bagaimana seleksi hakim konstitusi dapat dilakukan secara transparan dan partisipatif, bagaimana membuat ‘pengawasan’ bagi MK, bagaimana sebaiknya mekanisme dan hukum acara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jelas beberapa issue atau persoalan tersebut tidak cukup diatur dan diatasi hanya melalui PMK. Jadi harus melalui revisi UUMK. Kebutuhan revisi UUMK ini kemudian mendapatkan dorongan dari putusan MK. Dalam perkara uji materi UU Komisi Yudisial (UUKY) dan UU Kekuasaan Kehakiman (UUKK), dinyatakan dalam putusannya;9 “…Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU KY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu…” Melalui putusan tersebut, MK meminta kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perbaikan terhadap UU MK bersama UU lainnya dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi. Meski pada dasarnya materi pokok permohonan dan putusan menyangkut soal ‘pengawasan’ hakim oleh KY. Perintah putusan MK kepada DPR dan Presiden itu, merupakan sebuah dorongan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam UUMK. Ini fenomena menarik, karena revisi atau perubahan UUMK didorong dan dikehendaki sendiri oleh MK. Dalam putusan lainnya, setidaknya dapat dikatakan bahwa MK telah ‘mengubah’ sendiri salah satu ketentuan dalam UUMK. Ketentuan tersebut adalah Pasal 50 yang mengatur tentang larangan bagi MK untuk menguji undang-undang yang lahir sebelum amandemen UUD 1945. 10 9 Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 201. 10 Pasal 50 UU MK mengatur bahwa, “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam penjelasannya Pasal 50 ini sebelumnya dikesampingkan, ketika MK memutus permohonan perkara pengujian UU MA No. 14/1985 yang diajukan oleh Machri Hendra, seorang hakim dari Padang (perkara Nomor: 004/PUU-I/2003). Setahun kemudian, lewat putusan pengujian UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang & Industri yang diajukan bersama UUMK oleh DR. Elias Tobing, ketentuan Pasal 50 tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekwensi dari putusan tersebut, MK kemudian menerima dan memutus sejumlah permohonan pengujian undang-undang yang lahir sebelum amandemen UUD 1945.11 Saat ini revisi UUMK sudah diagendakan dalam Prolegnas tahun 2008. Artinya, dari segi politik legislasi telah ada kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan merevisi UUMK. Bersamaan dengan hal itu, berkembang keinginan kuat dari kalangan parlemen untuk membatasi kewenangan MK.12 Sekalipun tidak sepenuhnya tepat, bisa dipahami ‘kegelisahan’ dan ‘kemarahan’ kalangan DPR, karena terkadang ‘begitu mudahnya’ MK membatalkan produk undang-undang yang dihasilkan. Mereka menganggap kewenangan MK terlalu luas, dan berkehendak mambatasi kewenangan MK. Hal ini cukup mengkhawatirkan, dan malah akan menimbulkan persoalan baru. Jika sudah berkembang menjadi wacana politik dan melembaga, maka yang terjadi adalah resistensi yang berpotensi mengancam eksistensi dan peranan MK. Hingga pada gilirannya dapat memperlemah upaya penegakan hak-hak konstitusi dan proses demokratisasi yang sudah berjalan. Tentunya, bukan hal seperti itu yang kita inginkan bukan?. Berangkat dari uraian diatas, alasan mengapa UUMK harus diubah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Situasi dan kondisi yang berkembang dalam praktek penyelenggaraan MK disertai akibatnya, memerlukan pengaturan lebih lanjut didalam UUMK. 2. Terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UUMK. dikatakan, “Yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999”. 11 Contohnya, MK telah memutus perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh Eggy Sudjana (No. 013-022/PUU-IV/2006) dan Dr. R. Panji Utomo (No. 06/PUU-V/2007), serta UU No. 22/1997 tentang Narkotika (No. 2-3/PUU-V/2007). 12 Lihat, ”Ketika Putusan MK Gelisahkan Dewan”, Sinar Harapan, 22 Desember 2006; Juga “Kewenangan MK Akan Dibatasi”, Kompas, 20 September 2006. 3. Sebagai akibat dari putusan-putusan MK, yang telah membatalkan ketentuan dalam UUMK dan merekomendasikan perubahan atau perbaikan terhadap UUMK. 4. Adanya kebutuhan kedepan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan MK, terutama dalam hal kebutuhan bagi pengembangan organisasi/kelembagaan. B. Proyeksi Dan Tujuan Perubahan Perubahan UUMK haruslah senantiasa diarahkan untuk memperjelas gambaran MK sebagai lembaga penjaga konstitusi (the Guardian of Constitution). Hal itu diperlukan agar keadilan berdasarkan konstitusi (constitutional justice) semakin tercapai, serta diletakkan dalam konteks memperkuat kebutuhan cheks and balances serta perlindungan hak asasi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dalam pengertian bahwa, kekuasaan negara tidak hanya berdasarkan konstitusi, tapi negara tunduk pula terhadap pengawasan hukum. Akan tetapi pengawasan oleh lembaga hukum, memerlukan pula suatu pertanggungjawaban yang dapat dikreasikan dan diatur dalam perundang-undangan. Sebab, jika pengawasan hukum atas kekuasaan negara tidak memadai, maka negara akan terperosok kedalam negara kekuasaan (machstaat). Dan bila pengawasan kekuasaan peradilan tanpa pertanggungjawaban, maka peradilan akan kehilangan kepercayaan (distrust of justice) karena penuh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Perubahan UUMK ini, setidaknya dapat pula diharapkan menjadi sarana untuk meneguhkan ‘kewibawaan’ MK sebagai institusi peradilan, mempermudah upaya pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Yang kita inginkan pula dalam revisi UUMK adalah, perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada dalam UUMK. Perbaikan yang diperlukan untuk menunjang keberadaan serta terlaksananya tugas dan kewenangan konstitusional MK dengan baik. Dimaksudkan pula untuk mengatasi kebutuhan dan problem-problem yang muncul pada saat praktik penyelenggaraan MK selama ini. Dalam hal lain, perbaikan UUMK tidak hanya bagi keperluan sinkronisasi dan harmoniasi dengan perundang-undangan lainnya, tetapi dapat pula menjawab keperluan ‘pengawasan’ yang mencerminkan pelaksanaan cheks and balances terhadap MK. Sejatinya, kesemuanya itu menjadi sarana bagi pemenuhan keadilan, perlindungan hak-hak konstitusi serta penguatan demokratisasi yang masih terus tumbuh berkembang melalui peranan MK. Tidak ketinggalan tentunya, perubahan UUMK memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat (civil society). Dukungan dan partisipasi yang secara konsisten dan kontinyu mengawal perubahan UUMK agar hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan Dalam konteks kebutuhan itu, kegunaan praktis perubahan UUMK ditujukan untuk; 1. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UUMK. 2. Mengatasi dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam praktek penyelenggaraan MK. 3. Memberikan jaminan bagi keperluan pengembangan organisasi kelembagaan MK kedepan. 4. Mengoptimalkan peranan MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan konstitusi. C. Ruang Lingkup Perubahan Pada dasarnya perubahan atau revisi suatu perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berkembang. Perubahan itu dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:13 1. Menambahkan atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya. 2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, setelah melalui pembahasan dalam waktu yang relatif singkat. UUMK yang terdiri dari delapan (8) Bab dan 88 Pasal, pada intinya mengatur soal kedudukan dan susunan (organisasi kelembagaan), kekuasaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta hukum acara MK (lihat tabel 1). Materi itu merupakan perintah langsung dari UUD 1945 hasil amandemen. Pasal 24C ayat (6) telah menyatakan bahwa, “Pengangkatan dan Pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang.” Sedangkan menyangkut soal kewenangan, hakim konstitusi (jumlah, syarat, dan pengajuan) serta soal pemilihan dan pengangkatan Ketua MK, telah ditentukan dalam UUD 1945. 13 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (2); Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta-Kanisius, 2007, hal. 179. Usul perubahan dan rekomendasi dalam position paper ini berangkat dari materi yang sudah ada dalam UU MK, yang kemudian dipandang perlu untuk diubah atau ditambahkan. Materi tersebut adalah menyangkut perihal, hukum acara, susunan dan kedudukan (organisasi dan kelembagaan), pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Menyangkut soal kekuasaan, hanya akan disinggung beberapa bagian issue yang perlu diperhatikan. Sedangkan masalah yang menyangkut soal kewenangan, tidak akan disinggung secara mendalam karena hal itu sudah berkaitan dengan materi UUD. Perihal lainnya yang perlu ditambahkan dan dilengkapi adalah menyangkut persoalan ‘pengawasan’, persyaratan serta system seleksi/rekuitmennya. Jadi, position paper ini akan lebih banyak menyinggung issue dan masalah yang ada dalam UU MK. Tabel 1: Anatomi UU Mahkamah Konstitusi No. 1. 2. 3. 4. 5. Keterangan Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Kedudukan dan Susunan Bab III : Kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Bab IV : Pengangkatan & Pemberhentian Hakim Bab V : Hukum Acara b. a b. b - 6. 7. 8. Umum Khusus Pengujian Undang-Undang Sengketa Kewenangan Pembubaran Partai Politik Perselisihan Pemilu Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden Bab VI : Ketentuan Lain-lain Bab VII : Ketentuan Peralihan Bab VIII : Ketentuan Penutup Pasal Jumlah 1 2 s/d 9 10 s/d 14 15 s/d 27 28 s/d 85 1 Pasal 8 Pasal 5 Pasal 23 Pasal 57 Pasal 28 s/d 49 21 Pasal 50 s/d 60 61 s/d 67 68 s/d 73 74 s/d 79 80 s/d 88 11 Pasal 7 Pasal 6 Pasal 6 Pasal 9 Pasal 86 87 88 1 Pasal 1 Pasal 1 Pasal Adapun menyangkut soal kewenangan MK, memang telah disadari bahwa masih ada kekurangan dan barnagkali belum sepenuhnya dianggap tepat ketentuan yang telah dirumuskan dalam UUD 1945. Tentunya hal itu akan sangat berpengaruh terhadap rumusan-rumusan yang ada dalam UUMK, termasuk dalam praktik pelaksanaan MK selama ini. Saat ini memang telah dirasakan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan (amandemen) kembali UUD 1945, juga hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan MK. Oleh karena itu, sejumlah issue/persoalan ditingkat UUD akan disinggung dan dikupas juga, sebagai bagian yang tak terhindarkan dari position paper ini. BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR MAHKAMAH KONSTITUSI Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diputuskan MPR dalam Sidang Tahunan MPR 9 Nopember 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diletakkan dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 (2) UUD 1945 mengatur bahwa; “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan MK. MK ditentukan berdiri sendiri, terpisah dan berada diluar MA. Keduanya sama-sama merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Dari rumusan tersebut dipahami bahwa, saat ini Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu MK dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen. Ada beberapa alasan mengapa MK ditempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstitusionalitas keberadaan MK: a. Pada prinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menjamin, melindungi dan menegakkan nilai-nilai HAM itu harus pula diletakkan dalam konstitusi. b. Konstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme cheks and balances antara cabang kekuasaan. Adanya MK beserta kewenangannya menunjukkan bahwa, perubahan konstitusi sudah memuat adanya pembatasan dan mekanisme cheks and balances tersebut. c. Keberadaan MK berikut dengan kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang telah dimuat dalam perubahan konstitusi. Karena ciri-ciri dari negara hukum dapat ditunjukkan dari adanya wewenang untuk menguji konstitusionalitas (constitutional review) undang-undang oleh kekuasaan kehakiman (MK). d. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten oleh siapapun. Oleh karena itu, konstitusi harus pula menyediakan lembaga yang berwenang untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, yang mesti ditempatkan didalam konstitusi. Sebagai lembaga yang telah ditentukan konstitusi, maka terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur dan menjadi prinsip atau asas dasar bagi keberadaan dan peranan MK. Prinsipprinsip dasar yang merupakan ratio logis atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum, sekaligus merupakan pengarah umum untuk menganjurkan yang seharusnya menurut hukum. Sebagai sebuah institusi peradilan, maka MK harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik yang berlaku secara universal bagi pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power). Dilihat dari karakteristik perkara yang ditangani MK yang berkaitan dengan urusan kepentingan publik, maka dapat berlaku pula asas-asas yang digunakan dalam hukum publik (administrasi). Demikian halnya prinsip atau asas sebagai sebuah institusi peradilan dalam konteks pemerintahan yang bersih (good governance), dapat pula diterapkan di dalam penyelenggaraan MK. Prinsip-prinsip tersebut haruslah menjadi jiwa dan dasar dalam pengaturan UUMK, yang perlu ditegaskan, dijelaskan, dirinci didalam ketentuan-ketentuan UUMK. Demikian halnya dalam konteks kebutuhan perubahan UUMK, sedapat mungkin prinsip-prinsip dasar ini dapat dirumuskan jika sebelumnya tidak ada atau tercermin di dalam UUMK. Adapun prinsip atau asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut; 1. Supremasi Hukum (Supremacy of Constitution). Prinsip supremasi hukum pada dasarnya menghendaki hukum-lah yang harus memegang komando tertinggi dalam penyelenggaran negara. Hukum tertinggi yang mengikat semua pihak dan menjadi pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan adalah konstitusi. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa segala cara, tindakan dan kewenangan para penyelenggara negara, harus berpedoman pada konstitusi. Tidak dibenarkan jika pemerintahan dijalankan dengan mengabaikan konstitusi. Apabila terjadi penyimpangan (abuse of power), perselisihan atau sengketa dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan koreksi berdasarkan prinsip-prinsip atau ketentuan dalam konstitusi. Untuk itulah maka kemudian diperlukan adanya MK, yang diharapkan dapat memperkuat berjalannya prinsip-prinsip dalam negara hukum. Prinsip ini mendudukkan MK sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengawal agar konstitusi dapat ditegakkan dan dijalankan secara konsisten (the guardian of constitution). Konstitusi telah menempatkan MK sebagai lembaga peradilan yang dibutuhkan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Dalam mengadili dan memutus perkara haruslah selalu mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, dan MK berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi (the interpreter of constitution). Jadi, tidak hanya keberadaan dan kekuasaan yang ditentukan konstitusi, tetapi ukuran-ukuran yang digunakan MK harus sesuai dengan konstitusi. Prinsip ini juga bertujuan untuk membatasi MK menggunakan ketentuan lain selain konstitusi, sekaligus ’melarang’ siapapun aktor/lembaga negara (formal atau informal) bersikap dan melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan prinsip, nilai dan norma-norma konstitusi. 2. Bebas dan Tidak Memihak (Independent and Impartial) Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam negara hukum untuk menjamin proses peradilan yang fair. Prinsip ini sudah diterima dan diatur dalam berbagai ketentuan internasional. Pada dasarnya, prinsip peradilan yang bebas atau merdeka (independent) tidak menghendaki adanya campur tangan, terutama ke dalam proses pengambilan putusan, dari kekuasaan eksekutif dan legeslatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Termasuk campur tangan dari unsur-unsur kekuasaan kehakiman itu sendiri, serta bujukan atau pengaruh dari kekuasaan ekonomi dan politik di luar sistem kekuasaan negara. Prinsip independensi ini telah dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi Pasal 24 (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Prinsip independensi yang mesti dijamin tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi menyangkut juga independensi personal setiap hakim. Sebab kelengkapan pertama dan utama untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang independent ada pada hakim. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari rasa takut, tekanan, bujukan dan ancaman yang dapat mempengaruhi putusan. Persoalannya sekarang bagaimana merumuskan parameter yang diperlukan untuk mengukur bahwa kekuasaan kehakiman (MK) itu independent atau tidak. Untuk menjamin prinsip independensi itu setidaknya perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan yang mengatur; (1) tata cara penunjukkan hakim; (2) masa jabatan hakim; (3) pemberhentian hakim; (4) hak atas anggaran Sedangkan prinsip tidak memihak, pada dasarnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Hakim dalam mengadili harus tidak membeda-bedakan dan menghargai secara adil hak-hak para pihak di dalam proses pemeriksaan yang bersifat terbuka. Sehingga hakim dalam mengadili perkara terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan proses pengadilan dapat berjalan secara fair dan obyektif. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik. 3. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting yang diperlukan untuk mendorong lahirnya sebuah institusi yang dapat dipercaya. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas yang juga menjamin kepastian. Kedua prinsip ini menjadi keniscayaan konstitusional untuk dikreasikan sedemikian rupa dalam revisi UUMK. Keduanya diperlukan untuk mempermudah access to justice guna pemenuhan hak-hak konstitusional, selain pemenuhan doktrin universal peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (contante justice) bagi para pencari keadilan (justitiabelen). Prinsip transparansi/keterbukaan pada dasarnya menghendaki agar pengadilan dalam menjalankan fungsinya dapat dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini prinsip persidangan yang terbuka untuk umum, mulai dari pemeriksaan sampai putusan, sudah sewajarnya dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Apalagi mengingat saat ini hak atas informasi sudah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, terbuka ruang selebar-lebarnya guna mengetahui informasi mengenai proses pemeriksaan setiap perkara dan mendapatkan putusan-putusan yang diperlukan. Dan MK sebagai peradilan yang mengadili system hukum (court of law), yang perkaranya berkenaan dengan kepentingan umum dan mempunyai implikasi yang luas, sudah sewajarnya jika publik dapat dengan mudah mengetahui setiap persidangan dan mendapatkan putusan-putusan yang dikeluarkan MK. Sedangkan prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban dapat dimaknai merupakan salah satu cara untuk menciptakan cheks and balances, sekaligus mekanisme untuk menilai seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang mandat kekuasaan, baik secara individual hakim maupun secara institusional lembaga pengadilan.14 Dalam penjelasan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas ini diperlukan untuk meminimalisir tindakan diluar batas kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Setidaknya, memudahkan pihak-pihak eksternal yang berkompeten untuk melihat/menilai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan atau berperilaku menyimpang. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, masyarakat dapat ikut memantau kemampuan dan kinerja pemegang kekuasaan. Bagi pemegang kekuasaan, keberadaan suatu mekanisme pertanggungjawaban akan mendorong profesionalisme dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Dalam konteks pengadilan, akuntabilitas dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan prinsip independensi. Keduanya tidaklah bertentangan, tetapi justru saling memperkuat. Akuntabilitas diperlukan karena, independensi hakim dan pengadilan tanpa akuntabilitas berpotensi terjerumus ke dalam perilaku yang korup, despotis dan oligarkhis. Akuntabilitas dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya perilaku tersebut yang dapat merusak system pengadilan secara keseluruhan. Sejatinya prinsip pertanggungjawaban ini mencakup pertanggungjawaban secara organisasi, legal, politik, moral dan profesional. Konsep pertanggungjawaban tersebut masih harus dimodifikasi dan diadaptasi atau perlu disesuaikan dengan konsep lembaga MK. Setidaknya sebagai sebuah institusi peradilan, pertanggungjawaban yang mesti dilakukan MK berkaitan dengan putusan, perkara dan manegemen perkara, personalia, serta pengelolaan keuangan/anggaran. 14 Dalam konteks ini menurut pandangan Mauro Cappelletti, setidaknya ada empat type akuntabilitas individu hakim maupun institusi peradilan yaitu; 1) Political Accountability, yang pada prinsipnya merupakan akuntabilitas dengan lembaga politik dan konstitusi; 2) Societal or Public Accountability, akuntabilitas terhadap publik atau masyarakat; 3) Legal Accountability, akuntabilitas karena jabatannya sebagai hakim dan 4) Legal accountability yang merupakan akuntabilitas secara personal dari tindakan kriminal, perdata dan pelanggaran disiplin. Lihat Mauro Cappelletti, The Judicial Process..., opcit, hal. 72 4. Partisipasi dan Sosial Kontrol. Partisipasi dan kontrol sosial merupakan hal yang esensial dalam kehidupan negara demokrasi. Prinsip ini merupakan perwujudan hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan keikutsertaan dalam pemerintahan yang telah dijamin konstitusi. Keduanya diperlukan untuk menutupi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam mekanisme formal kenegaraan. Sehingga, proses maupun keputusan yang dibuat menjadi lebih legitimate dan dapat berfungsi secara maksimal. Lebih jauh lagi, partisipasi secara aktif dan langsung dari masyarakat dapat menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat yang pluralis dan heterogen. Dalam konteks proses pembuatan dan penegakan hukum, adanya partisipasi masyarakat dapat membuat hukum berfungsi maksimal, karena mendapatkan legitimasi yang kuat. Tanpa legitimasi yang kuat dari masyarakat, hukum akan mudah diselewengkan demi kepentingankepentingan partial dan sesaat. Sedangkan kontrol sosial yang dapat muncul dari, pers, kampus dan organisasi masyarakat, dapat mencegah dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Sekaligus dapat mendorong ke arah perbaikan yang diharapkan bersama untuk pencapaian keadilan dan kebenaran. Bagi MK, prinsip ini setidaknya perlu dikreasikan dalam proses seleksi hakim konstitusi yang bersifat terbuka. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan menilai seseorang yang dianggap tepat, berintegritas dan kredibel untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian pula dalam hal pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat yang mendapat perhatian luas, dapat diatur suatu mekanisme yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Prinsip ini juga dapat dikreasikan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perkara sesuai interest/kepentingannya, terlibat dalam konteks pengawasan MK, dalam hal bahwa hakim dan institusional MK harus akuntable, maka perlu tersedia system/mekanisme (internal dan eksternal) yang dapat menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau keberatannya. 5. Cepat, Sederhana dan Murah Prinsip peradilan yang cepat dan sederhana, adalah salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses peradilan. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa tindakan yang prosedural harus pula menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses di MK harus dibuat sedemikian rupa secara sederhana, baik dari segi biaya, lokasi, dan prosedur, termasuk dalam hal mendapatkan putusan. Sehingga tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh keadilan (access to justice). Proses di pengadilan yang harus ditempuh para pencari keadilan, juga diharapkan tidak memakan waktu yang lama. Dengan kata lain, proses pengadilan haruslah cepat, jelas, dan tepat waktu. Proses yang lama dan tidak jelas limitasi waktunya, bukan hanya membuat pesimisme para pencari keadilan, tetapi mengundang ‘kecurigaan’ atau dugaan yang bersifat negatif. Oleh karena itu, proses persidangan di MK harus dapat ditentukan dalam batas waktu yang tidak terlalu lama, jelas dan berkepastian. Untuk itu harus didukung dengan system administrasi dan managemen perkara yang modern dan bersifat on line. Sehingga tidak hanya untuk para pihak, tapi publik pun dapat mengetahuinya dan memperolehnya dengan mudah. Sedangkan mengenai prinsip murah, diartikan bahwa proses di pengadilan harus tidak dengan biaya yang mahal. Bahkan jika perlu dibebaskan dari biaya perkara, agar orang miskin yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Adanya biaya perkara ini sudah menjadi kelaziman dalam berperkara di lingkungan pengadilan umum, baik dalam system common law maupun civil law. Hanya saja seberapa besar biaya perkara itu ditentukan, jangan sampai memberatkan para pihak yang berperkara. Biaya yang terlalu besar bisa jadi akan memberatkan, bisa membuat para pencari keadilan tidak bisa berperkara. Dan itu berarti menjauhkan hak atas keadilan (access to justice) bagi para pencari keadilan. Selain itu, dalam system peradilan yang belum bisa berjalan secara transparan dan akuntabel, adanya biaya perkara ini dapat menjadi sumber ‘pungli’ (korupsi). Meskipun biaya perkara sudah menjadi kelaziman di pengadilan, namun ketika berperkara di MK sebaiknya dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ongkos perkara. Alasannya, proses peradilan di MK pada intinya bukanlah untuk mengadili kepentingan pribadi orang per orang, melainkan menyangkut kepentingan umum atau kepentingan lembaga negara yang bersifat publik. Karena itu berurusan dengan MK tidak perlu dibebani dengan biaya sama sekali. Selain itu, tiadanya keharusan biaya perkara alias gratis berperkara di MK, untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan MK dari kemungkinan persoalan yang akan timbul yang berhubungan dengan uang dari pihak lain. Sebaiknya, seluruh kebutuhan MK dibebankan saja kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut diatas, sebagian sudah terakomodir dan dijamin dalam UUMK. Misalnya, prinsip akuntabilitas dalam hal laporan MK yang wajib disampaikan setiap tahun (Pasal 12 – 13). Jaminan bagi transparansi dalam seleksi hakim MK (Pasal 19), penjadwalan sidang (Pasal 34), sidang dan pembacaan putusan (Pasal 28 ayat 5). Sedangkan sebagian lainnya, ditegaskan dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diantaranya, prinsip larangan menolak perkara (Pasal 16), jaminan bagi prinsip pelaksanaan prinsip independensi dan imparsialitas yang mengharus kan hakim mengundurkan diri apabila terdapat kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara (Pasal 29). Untuk mengatur secara lebih komprehensif, sebaiknya prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No.4/2004 dimasukkan pula kedalam revisi perubahan UUMK. BAB III PENGEMBANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI Perkembangan atau perubahan dalam sebuah lembaga adalah suatu keniscayaan. Perkembangan sebuah lembaga, terkadang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dimana lembaga tersebut berada. Perkembangan dalam sebuah lembaga, memperlihatkan adanya respon terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapinya, termasuk sebagai jawaban terhadap tuntutan yang muncul dari publik/lingkungan. Perkembangan lembaga merupakan bagian dari sebuah proses penyesuaian ke arah yang lebih baik. Sejauh mana kemudian melihat sebuah lembaga dapat mengembangkan diri, bergantung dari kebutuhan serta kemampuan lembaga tersebut tanpa menghilangkan prinsip atau kesepakatan dasar yang telah dibuat. Dan perkembangan tersebut, sedapat mungkin kemudian diakomodir atau diatur sehingga memperoleh legitimasi dan dapat dijalankan dengan baik. Lazimnya lembaga pengadilan, terdapat sejumlah perangkat penting kelembagaan yang dibentuk agar pengadilan dapat berjalan dengan baik dalam mengadili dan memutus perkara. Bagi Mahkamah Konstitusi (MK), perangkat penting dari organisasi/kelembagaannya, seperti soal kedudukan lembaga, kekuasaan/kewenangan, dan jumlah hakim, telah ditentukan dalam UUD. UUMK kemudian mengaturnya lebih lanjut, dan menambahkan komponen penting lainnya terutama menyangkut soal sekretariat dan panitera, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, UUMK belum mengatur secara rinci dan lengkap perangkat organisasi lainnya, misalnya soal sekretaris dan asisten hakim. Oleh karena itu, pengembangan organisasi MK dalam revisi UUMK ini dimaksudkan untuk mendorong agar komponen organisasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan MK, dapat diakomodir. Selain itu, dipandang perlu untuk menegaskan, mengubah, melakukan sinkronisasi dan merinci ketentuan-ketentuan yang sudah ada berkaitan dengan kelembagaan MK. A. Kedudukan dan Susunan A.1. Kedudukan Mengkaji kedudukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat di suatu negara. Sebab, kehadiran MK bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ditegaskan dalam UUD, melainkan juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara ke arah yang positif. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, setidaknya mesti melihat secara keseluruhan sistem negara yang bersangkutan. Misalnya, dalam struktur negara Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal merupakan lembaga konstitusi tertinggi (supreme constitutional body) sama seperti halnya Pemerintah Federal. Mahkamah Konstitusi di Jerman merupakan badan peradilan murni (true court) dan bukan lembaga politis. Hal ini diperkuat berdasarkan beberapa alasan, pertama, MK Federal tidak bertindak ex officio namun hanya diadakan atas permintaan lembaga yang berwenang. Kedua, dasar utama dari pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman adalah konstitusi atau Basic Law negara Jerman. Meski Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diantaranmya memiliki kewenangan untuk mengontrol kekuasaan kehakiman namun itu tidak beratio Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan dalam tingkat banding atau kasasi dari kasus-kasus hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana biasa. Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum konstitusi.15 Desain konstitusi Indonesia (UUD 1945) menempatkan eksistensi MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Jadi MK merupakan salah satu lembaga peradilan yang merdeka yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung. Meski ditempatkan sama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, tetapi MK diberi tugas dan kewenangan yang berbeda dengan MA. MK diposisikan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.16 Melihat kewenangan dan kewajiban tersebut, tugas pokok dari MK adalah untuk menegakkan konstitusi dalam kerangka negara hukum. MK adalah pengawal sekaligus penafsir konstitusi (the guardian and interpreter of constitution). Ini merupakan ide dasar dari pembentukan MK, yang setidaknya dapat terlihat dari kewenangan untuk menguji 15 Ms. Justice Ulrike Mullerm (Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman), “The Federal Constitutional Court of Germany- Competencies and Impact of the Courts Jurisdiction”, Makalah disampaikan di LIPI, 20-22 Maret 2002. 16 Lihat Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945. konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga. Umumnya MK dibanyak negara, diberikan pula kewenangan seperti, constitutional complaint, constitutional question, interpreter of constitution. Menurut Harjono, dapat dikatakan kewenangan uji konstitusionalitas tersebut merupakan kewenangan yang utama, sedangkan kewenangan lainnya bersifat asesoris atau pelengkap.17 Oleh karena itu, MK disebut juga sebagai Peradilan Konstitusi (constitutional judiciary) yaitu organ yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan persengketaan hukum (legal dispute) berdasarkan konstitusi.18 Peradilan ini dapat memfasilitasi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk mempertanyakan kelayakan suatu kebijakan negara (eksekutif dan legeslatif), yang biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara konseptual peradilan konstitusi ini mengandung dua fungsi strategis yaitu; (i) untuk melindungi hak-hak fundamental masyarakat, dan (ii) untuk mengawasi aktifitas legeslatif pemerintahan. Apabila hal itu dilaksanakan secara berkesinambungan maka akan mencapai titik kulminasi yang disebut sebagai keadilan konstitusional (constitutional justice).19 Dengan demikian, MK merupakan satu-satunya lembaga yang paling berwenang untuk menjaga dan menegakkan konstitusi. MK adalah mekanisme formal kenegaraan yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konstitusi. MK dibentuk dan diadakan lewat konstitusi, dan dasar bertindak atau mengambil keputusan adalah konstitusi. Namun demikian bukan berarti MK lebih tinggi dari lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk lebih tinggi dari MA. Pendekatan dan pandangan yang bersifat struktural-hierarkhis seperti itu, selayaknya ditinggalkan dalam membaca sistem ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945. Jadi, posisi atau kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu dilihat berdasarkan fungsi dan kewenangannya memperkuat cheks and balances di dalam kerangka negara hukum. Masalahnya, Bab II Pasal 2 UUMK tentang Susunan dan Kedudukan, hanya menegaskan bahwa, ”MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. 17 Harjono, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), Hukum dan Kuasa Konstitusi, Jakarta:KRHN, 2004, hlm. 25-27. 18 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi; Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta-Pradnya Paramita, 2006, hal. 75. 19 Ibid., hal. 82-85. Ketentuan ini sedikit berbeda dengan pengaturan yang ada dalam UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 1 UU KK menentukan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 2 UU KK bahwa, MK sebagai peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, nampak ada ketidaksinkronan antara ketentuan dalam UU MK dengan UU KK. Lebih dari itu, tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila’, dan bagaimana hal itu harus dilaksanakan oleh MK? Rekomendasi : Kedudukan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan konstitusi, perlu ditegaskan dalam UUMK. Hal ini penting untuk mengukuhkan peranan MK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain itu, dapat mencegah institusi lain melakukan tafsir dan bertindak sendiri dengan mengatasnamakan atau mengabaikan konstitusi. Konsekwensi dari penegasan itu, akan mendorong secara maksimal peranan MK yang memungkinkan adanya ’kreasi lain’ dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. A.2. Susunan Pasal 4 ayat (2) UU MK mengatur, ”Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”. Dari ketentuan ini dikehendaki, unsur utama pelaksanaan organisasi MK adalah Ketua, Wakil Ketua dan anggota hakim konstitusi. Susunan seperti ini nampaknya menggambarkan bangunan struktur organisasi MK yang disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan MK. Ramping dan sederhana, namun belum lengkap menyebutkan unsur-unsur lain yang dipandang penting bagi kelembagaan MK. Susunan seperti itu juga belum menggambarkan adanya pemisahan antara susunan yang organisasi MK secara keseluruhan dengan susunan dalam hal untuk mengadili dan memutus perkara.20 Artinya, baik untuk urusan atau tugas yang bersifat kelembagaan secara umum dengan tugas judicial akan 20 Bandingkan dengan pengaturan susunan bagi Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur, “Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris”. Selanjutnya Pasal 5 ayat 1 menentukan, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. bertumpu dan menjadi tanggungjawab Ketua MK/hakim konstitusi. Susunan seperti itu juga belum memberikan penegasan tentang tugas dan kewenangan yang disertai mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas. Hal ini terlihat misalnya dari pengaturan mengenai Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Dalam hal Ketua MK, UUMK mengatur posisi Ketua MK sebagai Ketua yang merepresentasikan Lembaga/Organisasi MK, sekaligus sebagai pimpinan majelis dalam persidangan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” Namun UUMK ini tidak menegaskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing dari Ketua dan Wakil Ketua MK. Dengan kata lain, tidak diatur pembagian tugas yang jelas antara Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Hal ini juga tidak dibuat atau ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan MK (PMK). Pasal 28 ayat (2) UUMK hanya menentukan tugas Wakil Ketua sebagai pengganti dalam sidang pleno MK jika Ketua berhalangan. Jadi tidak lebih jabatan Wakil Ketua seperti ‘ban serep’, yang hanya siap mengganti Ketua jika berhalangan hadir dalam sidang pleno MK. Bagaimana seadainya Ketua MK wafat atau mengundurkan diri, apakah secara otomatis posisinya bisa langsung digantikan oleh Wakil Ketua? Rekomendasi: Perlu diatur susunan organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan perangkat dan urusan kelembagaan secara umum, dengan perangkat pelaksana judicial secara khusus. Pemisahan ini penting untuk memberikan kejelasan apa tugas dan kewenangan masing-masing, serta alur pertanggungjawaban. Termasuk dalam hal ini menyangkut soal pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua. Rincian tugas dan kewenangan ini perlu dijabarkan sebagai konsekwensi dari jabatan yang telah disebutkan dalam undang-undang. A.3. Perihal Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Konstitusi Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 telah menegaskan, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Dan Pasal 4 ayat (3) UUMK menambahkan ketentuan bahwa, “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun”. Tidak begitu jelas apa maksud atau tujuan dari pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK ini. Apakah untuk mencegah kemungkinan munculnya intervensi atau dominasi dari lembaga lain, mengingat hakim konstitusi berasal dari DPR, Presiden dan MA. Jika yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua adalah hakim konstitusi yang berasal dari Presiden, maka bisa jadi MK tidak independent, karena cenderung berpihak kepada Presiden. Masa jabatan 3 tahun itu juga tidak mendapat ketegasan, sampai berapa kali seorang hakim konstitusi boleh menjadi Ketua/Wakil Ketua MK. Akan tetapi, pengaturan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 3 tahun itu, tidak begitu efektif. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan soal masa jabatan bagi hakim MK. Pasal 22 UUMK menentukan masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan Wakil Ketua adalah juga hakim konstitusi, yang tentunya terikat dengan masa jabatan 5 tahun itu. Ini bisa menjadi problem, dan mengganggu kinerja MK. Karena bisa jadi hakim konstitusi yang sedang menjadi Ketua/Wakil Ketua MK, tidak akan terpilih/diajukan kembali pada saat masa jabatan 5 tahun sudah harus selesai. Atau kalaupun terpilih kembali, apakah jabatan Ketua/Wakil Ketua otomatis terhenti dan harus dilakukan pemilihan kembali? Rekomendasi: Aturan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua tidak perlu ada. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua mengikuti atau sama dengan masa jabatan hakim konstitusi. Misalnya, masa jabatan hakim konstitusi 9 tahun, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua ditentukan 9 tahun juga (lihat pembahasan masa jabatan hakim) B. Memperjelas Kewenangan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam ayat dua (2) ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7B ayat (1) merupakan pelanggaran hukum berupa, penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara umum dapat dikatakan bahwa, kewenangan MK adalah mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan soal konstitusi. UUMK semestinya bisa memperjelas, mengelaborasi dan mengatur lebih lanjut wewenang MK yang telah diberikan konstitusi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan persoalan yang justru malah menjadi penghambat. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 10 UUMK memberi pengaturan yang bunyinya kurang lebih sama dengan ketentuan konstitusi, dan hanya menambahkan ketentuan (satu ayat) berkenaan dengan maksud dari dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebaliknya, UUMK malah memberikan pembatasan, seperti ketentuan Pasal 50 UUMK yang melarang MK untuk menguji undang-undang yang lahir sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wewenang MK terutama terhadap tiga (3) yang telah dilakukan yaitu, kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum, telah mengalami perkembangan atau perubahan yang menuntut pengaturan lebih lanjut. Pengaturan ini diperlukan agar dapat memperjelas dan memberi penegasan terhadap kewenangan yang telah dilakukan. Harapannya kedepan, peranan MK dalam melaksanakan kewenangan tersebut menjadi lebih optimal. Untuk itu pembahasan mengenai kewenangan tersebut akan coba diurai satu persatu. 1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD (constitusional review) Pada dasarnya wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi (UUD) sebagai bagian dari penerapan prinsip pemerintahan yang terbatas. Pembatasan ini terutama ditujukan terhadap organ kekuasaan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden). Berdasarkan penelitian sejarah dan analisa hukum, watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya, kelompok dominan (penguasa) dapat membentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku.21 Pelaksanaan dari kewenangan ini dilakukan agar konsistensi tindakan bernegara seperti yang telah disepakati dalam konstitusi dapat dipertahankan. Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian (diskrepansi) antara preferensi atau kepentingan rakyat dengan yang mewakilinya dapat diatasi. Selain sebagai penerapan pemerintahan yang terbatas, kewenangan menguji ini disebabkan oleh adanya kecenderungan yang mengharuskan persoalan diatur melalui serangkaian 21 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta-LP3ES & UII Press, 1998, hlml. 359. peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakselarasan baik secara vertikal maupun horizontal antarsesama norma hukum yang lebih rendah, atau antara norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Dalam sebuah doktrin hukum yang bersifat hierarkhi struktural, yang juga digunakan dalam sistem hukum di Indonesia (UU No. 10/2004), bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Untuk hal itu, baik UUD 1945 maupun UUMK memberikan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga cenderung membatasi upaya pencapaian perlindungan dan keadilan konstitusional secara utuh. UUD 1945 menentukan dengan cara membagi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD oleh MK. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).22 Selanjutnya bagaimana pelaksanaan terhadap wewenang menguji undang-undang ini, Pasal 50 UUMK memberikan pengaturan yang membatasi bahwa, Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, undang-undang yang lahir dan dibuat sebelum amandemen UUD 1945 tidak dapat dilakukan pengujian oleh MK. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3), pengujian dapat dimohonkan terhadap; (i) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 (uji formil), dan/atau (ii) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (uji materiil). Terhadap ketentuan UUD 1945 yang telah membagi kewenangan menguji peraturan perundang-undangan antara MK dan MA, memang berpotensi menimbulkan masalah. Bagaimana jika peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, siapa yang akan menguji? Hal itu sangat mungkin terjadi, dan jika tidak ada lembaga yang berwenang mengujinya maka pelaksanaan penegakan konstitusi menjadi terbatas dan partial. Namun demikian hal ini merupakan masalah system kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, dan bukan merupakan bagian materi atau masalah dari UUMK. Adapun mengenai ketentuan Pasal 50 UUMK, hal ini jelas membatasi hak atas keadilan 22 Pengujian produk hukum oleh Peradilan Konstitusi (MK) biasanya diselenggarakan dengan 3 cara, yaitu (i) pengujian abstrak, sebelum produk hukum disahkan, (ii) pengujian konkret, dilakukan setelah produk hukum disahkan, (iii) pengaduan konstitusional. Masing-masing memiliki prosedur acara persidangan sendiri, manfaat dan implikasi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk hal ini lihat, Ahmad Syahrizal, dalam Peradilan Konstitusi., opcit., hal. 88. konstitusional bagi masyarakat. Pasal ini secara gradual sudah diamputasi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi oleh putusan MK, setelah sebelumnya hanya dikesampingkan. Pada saat pembatalan Pasal 50 tersebut, MK beralasan diantaranya bahwa, kewenangan MK yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945 tidak dapat dikurangi oleh undang-undang. Sebab, MK adalah organ undang-undang dasar, bukan organ dari undang-undang. Disamping itu, keberadaan Pasal 50 UUMK dipandang tidak hanya mereduksi kewenangan MK, tetapi dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda.23 Pembatalan Pasal 50 melalui putusan MK sangatlah tepat, dan tidak dapat dikatakan bahwa MK telah melampaui kewenangannya, karena ada kepentingan yang lebih luas yang harus dikedepankan oleh MK. Dalam melaksanakan kewenangan menguji ini, tidak jarang MK melakukan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Uji konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dari segi formil maupaun materil. Artinya, MK memberi tafsir atas undang-undang apakah sudah sesuai dengan UUD atau justru bertentangan dengan UUD. MK menentukan apakan perintah UUD sudah termaktub dalam undang-undang, sekaligus menentukan apakah proses pembentukannya telah sesuai dengan perintah UUD atau belum. MK menjadi pengaman (the guardian) konstitusi agar tidak dilanggar oleh undang-undang. Permasalahan yang kemudian muncul ke permukaan, adalah bahwa MK ternyata tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang. Meskipun MK dianggap melakukan penafsiran dengan metode teristematis, dengan tetap menggunakan UUD sebagai pijakan utama tafsir, akan tetapi jika dilihat dari pertimbangan hukum yang dipilih, terang pada perkara tertentu MK membenturkan undang-undang satu dengan undang-undang lain. Kasus ini terjadi pada judicial review UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No, 5 Tahun 2000 yang dianggap bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2001, dengan argumen asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generalis. Kasus semacam ini berulang kembali pada perkara judicial review UU No. 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal. Meski pijakan utama penafsiran adalah Pasal 33 UUD 45, namun pada dasarnya MK menganggap UU No. 25 Tahun 2008 bertentangan dengan UU Pokok Agraria No. 23 Alasan tersebut merupakan pendapat dari mayoritas hakim. 3 hakim lainnya yaitu, Laica Marzuki, Achmad Roestandi dan HAS Natabaya mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Lihat putusan perkara Nomor: 066/PUU-II/2004., hal. 53-55. 5 Tahun 1960. Di sini tidak berlaku asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generalis. Walaupun kedua putusan tersebut mendapat apresiasi positif dari masyarakat, sebagai pijakan hukum, hal-hal yang demikian ke depan harus dihindari, karena bisa memunculkan persepsi bahwa MK telah keluar dari kewenangannya. Wewenang menafsirkan itu memang melekat, dan dapat dikatakan secara langsung sudah menjadi bagian atau hak yang harus dilakukan oleh para hakim ketika mengadili perkara. Namun sekiranya hal ini perlu ditegaskan dalam ketentuan UUMK. Disamping itu, dengan adanya kompleksitas persoalan hukum dan konstitusi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang MK kemudian dimintai pertimbangannya dari berbagai pihak. Akan lebih baik pula, jika mengenai hal ini dapat ditegaskan dalam UUMK. Seperti halnya bagi MA yang dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Rekomendasi; 1. Pasal 50 UUMK dicabut atau dihapus dari ketentuan UUMK 2. Memperjelas/menegaskan hak dan kewenangan yang secara langsung dan implicit sudah dilakukan dan seharusnya dilakukan oleh MK, yaitu; - Hak/wewenang menafsirkan UUD - Memberikan pertimbangan, keterangan dan nasihat masalah konstitusi kepada siapapun jika diminta (constitutional question) 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Kewenangan MK dalam hal memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, merupakan kewenangan utama. Wewenang ini dimaksudkan agar persoalan yang bisa menimbulkan sengketa antarlembaga negara dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, yaitu jalur peradilan MK. Setidaknya hal ini belajar dari masa lalu ketika timbul persoalan atau sengketa antarlembaga negara tidak begitu jelas proses penyelesaiannya. Kalaupun ada, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui jalur atau proses politik. Kewenangan ini dapat pula dipandang sebagai langkah antisipasi kedepan, yang diperkirakan akan banyak timbul masalah sengketa antarlembaga negara seiring dengan makin rumit dan kompleksnya urusan atau persoalan kenegaraan. Masalahnya adalah apa yang dimaksudkan dengan sengketa kewenangan lembaga negara? Dan yang selalu menjadi pertanyaan adalah siapa yang bisa disebut atau dikualifikasi sebagai lembaga negara. Istilah atau terminologi lembaga negara ini merupakan istilah yang belum begitu jelas dan multitafsir, terutama pascaperubahan UUD 1945. Namun istilah itu sudah ditempatkan menjadi sebuah norma dalam konstitusi (Pasal 24C ayat 1 dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945) maupun UUMK, yang terkait soal pengaturan subyek pemohon dalam pengujian undang-undang (Pasal 51 ayat 1 huruf d UU No.24/2003). Hal ini berbeda jika merujuk pada pengaturan sebelumnya dalam UUDS 1950 dan Ketetapan MPR No. III tahun 1978 yang menyebutkan dengan jelas siapa saja yang disebut sebagai organ/lembaga negara. Hal ini bisa menjadi persoalan ketika akan menentukan legal standing, siapa yang bisa mengajukan permohonan jika ada sengketa ke MK. Perihal keduanya tidak mendapat penjelasan lebih lanjut dalam UUMK. Pengertian sengketa kewenangan antar lembaga negara itu sendiri, menurut Jimly Asshiddiqie ialah, “perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.”24 Sedangkan yang menjadi objek sengketa ialah kewenangan konstitusional dari masing-masing lembaga negara, bilamana terjadi sengketa penafsiran dalam pelaksanaan kewenangan konstitusonal tersebut, antara lembaga negara satu dengan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih.25 Dalam konteks ini, menurut Fajrul Falakh, yang penting berkaitan dengan kewenangan MK ini adalah kualifikasi sengketa macam apa dari sengketa lembaga negara yang menjadi kompetensi MK. Didalam UUD disebutkan wewenang konstitusional, jadi kuncinya disitu.26 Sedangkan mengenai apa dan siapa lembaga negara itu, berdasarkan hasil penelitian KRHN bersama Sekretariat Jendral MKRI, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara yang diatur dengan jelas dalam UUD 1945 ada 18 yaitu; MPR, DPR, DPD, Presiden, Kementrian Negara, MA, BPK, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, komisi pemilihan umum, Komisi Yudisial, MK, bank sentral, TNI, Kepolisian, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Namun dari 18 lembaga negara tersebut yang berpotensi terjadinya sengketa dan dapat menjadi pihak di MK ada 16 lembaga negara yaitu; MPR, DPR, DPD, Presiden, Kementrian Negara, MA, BPK, Pemerintah Daerah Propinsi, 24 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, 2006, hal. 4. 25 Ibid., hal. 13. 26 Lihat dalam transkip “Expert Meeting Revisi UU Mahkamah Konstitusi”, diselenggarakan oleh KRHN-DRSP di Hotel Millenium, Jakarta, 27-28 Agustus 2007. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, komisi pemilihan umum, Komisi Yudisial, MK, TNI, Kepolisian, dan Dewan Pertimbangan Presiden.27 Menyangkut persoalan lembaga negara, beberapa hakim konstitusi memiliki posisi dan pendapat yang berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada 28 lembaga negara yang terdapat di dalam UUD, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit, yaitu: 1) Presiden; 2) Wakil Presiden; 3) Dewan pertimbangan presiden; 4) Kementrian Negara; 5) Duta; 6) Konsul; 7) Pemerintah Daerah Propinsi; 8) Gubernur; 9) DPRD Propinsi; 10) Pemerintah Daerah Kabupaten; 11) Bupati; 12) DPRD Kabupaten; 13) Pemerintah daerah Kota; 14) Walikota; 15) DPRD Kota; 16) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 17) Dewan Perwakilan Rakyat; 18) Dewan Perwakilan daerah; 19) Komisi pemilihan umum; 20) Bank sentra; 21) Badan Pemeriksa Keuangan; 22) Mahkamah Agung: 23) Mahkamah Konstitusi; 24) Komisi Yudisial; 25) Tentara Nasional Indonesia; 26) Kepolisian Negara RI; 27) Satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus/istimewa; 28) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Di samping itu terdapat badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Dari 28 organ atau subyek tersebut, yang keberadaan dan kewenangannya ditentukan dengan tegas dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek jabatan. Empat organ lainnya yaitu, bank sentral, duta, konsul dan badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam UUD 1945.28 Lain halnya dengan Jimly, HAS Natabaya menyimpulkan bahwa lembaga/organ negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah; MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial (KY), komisi pemilihan umum, Pemerintahan Daerah dan bank sentral. Kecuali bank sentral, juga MA dan MK, apabila terjadi sengkata kewenangan antarlembaga negara tersebut, maka dapat disampaikan gugatannya kepada MK.29 Sedangkan menurut Harjono melalui pendekatan objectum litis, memasukkan Partai Politik sebagai lembaga negara. Karena ketentuan UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945), serta hak partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). 27 28 29 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara & Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara, KRHN-MKRI, 2005, hal.. Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan..., Op.cit., hal. 53-54. HAS Natabaya, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008, hal. 215. Menurutnya, karena yang menjadi objectum litis adalah kewenangan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka dalam kasus demikian partai politik dengan sendirinya dikualifikasi sebagai lembaga negara menurut UUD 1945. Dengan contoh tersebut, jelas yang dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 adalah ”sengketa kewenangan” dan bukan ”sengketa lembaga negara”.30 Dari berbagai pendapat diatas, dapat menunjukkan penafsiran yang beragam tentang apa yang dimaksud dengan lembaga negara ataupun sengketa kewenangan lembaga negara. Berbagai pendapat atau penafsiran tersebut tentunya membutuhkan penjelasan dan penegasan dalam UUMK. Dalam perkembangannya, MK nampaknya telah menentukan pendirian mengenai persoalan ini. Dalam putusan perkara SKLN yang diajukan oleh Drs. HM. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari, dengan termohon Presiden, Mendagri dan DPRD Kabupaten Bekasi, telah ditegaskan bahwa; “….rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar”, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah;”31 Berdasarkan putusan tersebut, MK telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Dari putusan ini nampaknya kemudian mendasari lahirnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.32 Dalam PMK tersebut dijelaskan sebagai berikut; a. Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (pasal 1 angka 5). b. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 (pasal 1 angka 6). 30 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 461- 462. 31 Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, hal. 88 32 Putusan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2008, sedangkan PMK tentang SKLN baru ditetapkan pada 18 Juli 2008. c. Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara (pasal 1 angka 7). Namun demikian, penegasan dan penjelasan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk istilah lembaga negara itu sendiri, sudah merupakan materi dari undangundang. Tidak tepat jika hal tersebut hanya diatur dalam bentuk PMK, apalagi mengingat bahwa UUMK tidak menjelaskan pengertian dari SKLN. Oleh karena itu pengertian yang telah ditegaskan dalam putusan maupun PMK, sebaiknya ditempatkan menjadi materi undangundang MK. Rekomendasi : Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara, serta penjelasan mengenai lembaga negara dan kewenangan konstitusional sebagaiman diatur dalam PMK No. 08/PMK/2006, sebaiknya ditempatkan menjadi materi UUMK. 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sengketa atau perselisihan hasil pemilu dapat dikatakan banyak macamnya. Namun, tidak semua sengketa itu diselesaikan melalui MK. Selain MK, ada KPU, Lembaga Pengawas Pemilu, Pengadilan umum yang juga menjadi bagian dari lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Adapun sengketa yang penyelesaiannya berada di tangan MK adalah sengketa hasil akhir pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum secara Nasional. Pengertian perselisihan pemilu seperti itu, tidak mendapatkan penjelasan di dalam UUMK. Sebelumnya, perselisihan hasil pemilu hanya dimaknai atau dikhususkan bagi peserta pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tergambar dalam Pasal 74 dan 75 UUMK yang menjelaskan kurang lebih bahwa yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu adalah sengketa tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik. Ketentuan ini juga diikuti oleh Peraturan MK Nomor : 04/Pmk/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/Pmk/2004 Tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Sedangkan pemilu bagi kepala daerah (Pilkada) Gubernur maupun Bupati/Walikota, tidak termasuk obyek sengketa hasil yang ditangani MK. Penyelesaian sengketa hasil pemilu pilkada ditangani oleh MA sebagaimana ditentukan lewat UU Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004). Hal itu dipengaruhi oleh pandangan bahwa pilkada dianggap termasuk dalam rezim pengaturan Pemerintahan Daerah, bukan termasuk rezim pengaturan pemilu dalam konstitusi. Pandangan tersebut kemudian seperti mendapat penegasan oleh MK dalam putusan pengujian UU Pemda, bahwa; “….Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung…” 33 Dalam perkembangannya pandangan tersebut telah dikoreksi. Dalam hal ini, politik legislasi telah menempatkan pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Setidaknya perspektif demikian tercermin dalam pengaturan UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 yang telah menyatuatapkan Pilkada menjadi bagian dari Pemilu sesusai UUD 1945. Pergeseran pandangan dan perubahan arah politik legislasi seperti itu, kemudian berpengaruh pula terhadap prosedur penanganan perselisihan hasil pemilu pilkada. Dalam revisi terhadap UU Pemerintahan Daerah ditentukan, perselisihan hasil pilkada yang semula ditangani MA, kini telah berpindah ke MK.34 Perpindahan prosedur penyelesaian sengketa hasil ini, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh putusan MA dan/atau Pengadilan Tinggi yang mengundang kontroversi, seperti putusan dalam penyelesaian sengketa pilkada Depok, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Perkembangan lainnya, sebagai akibat dari putusan MK (putusan Nomor 5/PUU-V/2007), dalam pemilu pilkada juga telah mengakomodasi dimungkinkannya pasangan calon kepala daerah dari perseorangan (independen), selain pasangan calon kepala daerah yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.35 33 Lihat putusan MK Nomor 072-073/PMK/PUU-II/2004, hal. 115 34 Lihat UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C telah dirumuskan bahwa, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkmah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 35 Lihat Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemerintahan Daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut, tentunya memerlukan pemaknaan ulang terhadap pengertian atau definisi terhadap perselisihan hasil pemilihan umum selama ini. Hal ini perlu diperjelas dan ditegaskan karena akan mempengaruhi penentuan siapa saja subyek pemohon perselisihan hasil pemilu di MK. Sayangnya, pengertian atau definisi tersebut tidak ditemukan dalam UUMK. Pengertian perselisihan hasil pemilu malah terdapat dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Disebutkan dalam Pasal 258 ayat (1) UU No. 10/2008 bahwa, “Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”. Sedangkan pada ayat (2) nya ditentukan, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”. Meskipun terdapat sedikit gambaran dari pengertian atau definisi perselisihan hasil pemilu, namun pengertian yang terkandung dalam UU No. 10/2008 itu masih bersifat sempit. Artinya, konteks pengertian tersebut hanya dikhususkan bagi peserta pemilu yang disebutkan dalam UU No. 10/2008 yaitu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pengertian tersebut dapat dikatakan belum mencakup pengertian dari keseluruhan peserta pemilu sebagaimana tergambar dari perubahanperubahan tersebut diatas. Hal ini harus dijelaskan dalam UUMK agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi para peserta pemilu. Penjelasan yang dapat merangkum atau memberikan gambaran secara komprehensif keseluruhan dari perubahan-perubahan diatas. Rekomendasi; Perlu ada penjelasan sendiri dalam UUMK tentang pengertian perselisihan hasil pemilihan umum. Pengertian yang dimaksud pada intinya dapat mencakup pengertian yang akan menentukan subyek pemohon dalam perselisihan hasil pemilu yang akan diajukan ke MK. Dalam hal ini perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum untuk anggota legeslatif (DPR, DPRD dan DPD), eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan juga untuk Kepala Daerah. 4. Pembubaran Partai Politik Dalam sejarah politik Indonesia, pembubaran suatu partai politik seperti menjadi sesuatu yang lumrah dan sering terjadi, khususnya ketika rezim pemerintah otoritarian berkuasa. Pada masa Soekarno setidaknya tercatat dua parpol yang dibubarkan, yaitu MASYUMI dan PSI. Kemudian pada masa Soeharto, selain pembubaran PKI, juga terdapat penggabungan partai- parti politik (fusi) yang dilakukan oleh pemerintah. Persoalannya, pembubaran partai politik pada masa yang lampau, lebih didasari oleh sikap suka atau tidak suka (like or dislike) pemerintah terhadap suatu partai politik, dan menjadi upaya pengekangan kebebasan berserikat. Bukan didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang terang dan jelas. Hal demikian itu lebih mencerminkan watak otoritarian dari pemeritah berkuasa, yang tentunya sangat bertentangan dengan asas dan sistem demokrasi yang hendak dibangun dan dikembangkan. Belajar dari pengalaman di masa lalu, sebagai upaya mencegah timbulnya watak otoritarian dari pemerintah, pembubaran partai politik tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi melalui jalur pengadilan yaitu MK. Pasal 24C UUD 1945, salah satunya memberi wenang kepada MK untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UUMK, sedangkan mengenai proses beracaranya diatur dalam Pasal 68-73 UUMK. Dari serangkaian aturan tersebut menjadi terang, bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembubaran partai politik adalah MK. Pemerintah masih diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pembubaran partai.36 Kendati demikian bubarnya partai politik tidak hanya sebagai akibat keluarnya putusan MK. Dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008, diatur bahwa bubarnya partai politik bisa dikarenakan membubarkan diri atas keputusan sendiri; menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi menurut Fajrul Falakh, peranan MK dalam pembubaran parpol adalah resultan. Ibarat main bilyard, itu adalah hasil sodokan dari sebuah kompromi politik. Pemerintah yang sebelumnya berkuasa terhadap partai-partai, termasuk dalam membubarkan partai, masih punya peranan tapi hanya sebagai pemohon. Bubar tidaknya partai politik ditentukan oleh pengadilan (MK), pemerintah boleh mengajukan alasan-alasannya.37 Lebih dari itu, wewenang mengenai pembubaran partai politik ini mengesankan adanya kontradiksi nilai dalam konstitusi. Disatu sisi, konstitusi memberikan ruang bagi kebebasan berorganisasi melalui partai politik sebagai wujud dari pelaksanaan hak asasi dan demokrasi. Tetapi disisi lain, konstitusi juga memberi pengaturan untuk dimungkinkannya partai politik dibubarkan, meski melalu jalur pengadilan. 36 Lihat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 37 Transkip Expert Meeting….KRHN-DRSP, Op.cit Oleh karena itu, UUMK mesti dapat memberikan batasan yang jelas berkenaan dengan alasan-alasan pembubaran sebuah partai. Batasan melalui pengaturan yang terperinci dan terukur sangat diperlukan, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dengan alasan yang dibuat-buat ketika mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK. Jika tidak, maka pelaksanaan wewenang ini tidak hanya mengancam mati hidupnya sebuah partai, tetapi berpotensi membunuh demokrasi. Untuk pembahasan masalah ini lebih lanjut, lihat pada bagian hukum acara khusus pembubaran partai politik. 5. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Impeachment lebih merupakan suatu proses tuntutan atau dakwaan terhadap seorang pejabat publik, karena dianggap melakukan pelanggaran hukum yang telah ditentukan undangundang dasar. Hasil akhir dari proses impeachment itu bisa membuat si pejabat publik yang dituntut tersebut diberhentikan dari jabatannya. Setiap negara yang mengadopsi impeachment ini, memiliki praktek yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi, baik menyangkut objeknya, alasan-alasan maupun mekanisme yang digunakan. Tetapi pada umumnya mekanisme impeachment melibatkan lembaga yudikatif, MA atau MK. Dan bagi negara yang memiliki keduanya, besar kemungkinannya MK lah yang dipilih terlibat dalam proses impeachment. Keterlibatan MK dalam proses impeachmet di setiap negara juga berbedabeda. Sejumlah negara ada yang menempatkan peranan MK sebagai bagian akhir setelah tahapan proses di lembaga negara lain, seperti di Austria, Jerman dan Korea Selatan. Sedangkan beberapa negara lainnya, seperti di Lithuania dan Indonesia, menempatkan peranan MK sebagai jembatan yang memberikan landasan pertimbangan hukum kepada proses selanjutnya di lembaga politik (parlemen).38 Bagaimana mekanisme atau prosedur impeachment yang telah diatur dalam konstitusi UUD 1945? Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tahapan impeachment adalah sebagai berikut; Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR atas dugaan melakukan melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 38 Lihat Jimly Asshiddiqie dalam Pengantar Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005 Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat. Permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya 90 hari setelah permintaan itu diterima. Apabila MK memutuskan terbukti pendapat DPR tersebut, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari setelah usul diterima. Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Keputusan MPR harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dari tahapan proses impeachment yang diatur dalam konstitusi tersebut, pada intinya dapat disimpulkan bahwa pertama, impeachment atau proses pemberhentian dalam masa jabatannya hanya dikhususkan bagi Presiden dan Wakil Presiden.39 Kedua, alasan pemberhentian tersebut apabila terbukti; [a] melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; [b] tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga, proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ini melibatkan 3 lembaga yaitu, DPR, MK dan MPR. Keempat, kata akhir untuk memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 39 Hal ini berbeda dengan ketentuan yang banyak diadopsi negara-negara lain, dimana mekanisme impeachment bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara merupakan objek yang dapat dikenakan tuntutan impeachment sehingga dapat diberhentikan. Demikian halnya dengan negaranegara yang memiliki MK, seperti Austria, Jerman, dan Korea Selatan, mekanisme impeachment bisa dilakukan terhadap pejabatpejabat tinggi negara lainnya, tidak hanya untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden. berada pada kewenangan MPR. Sedangkan peranan MK adalah melayani permintaan atau usulan dari DPR untuk memberikan landasan hukum bagi proses pemberhentian tersebut.40 Ketentuan-ketentuan impeachment tersebut diatas, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana caranya dan atas dasar apa DPR sampai pada kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat? Apabila usul pemberhentian ditolak, atau batal dibicarakan karena quorum tidak tercapai, bolehkah diulang kembali pada sidang yang sama? Apakah pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B, merupakan pendapat hukum yang harus terukur bobot pembuktiannya ketimbang pertimbangan politik? Bagaimana pula proses pembuktiannya dalam sidang MK? Mungkinkah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diberhentikan sementara (non aktif) dari jabatan? Jika harus ditentukan, lembaga mana yang harus diberi kewenangan untuk melakukannya? Jika kemudian ternyata Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah, apakah ada proses untuk rehabilitasi dan menjadi kewenangan siapa? Untuk menjamin terlaksananya prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law), apakah diperlukan kehadiran Presiden dan /atau Wakil Presiden di depan persidangan MK? Jika putusan MK dianggap tidak bersifat final, apakah terbuka kemungkinan bagi MPR untuk membuat putusan lain. Dengan pengertian bahwa MPR tidak memberhentikan Presiden, meskipun menerima putusan MK? Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya, apakah masalah pelanggaran hukumannya akan diproses tersendiri, mengingat konstitusi tidak menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan terbatas hanya berupa pemberhentian dari masa jabatannya.41 Beragam pertanyaan yang muncul diatas, berangkat dari kelemahan, kekurangan dan inkonsistensi pengaturan yang ada dalam konstitusi. Untuk menjawabnya, tidak cukup sepenuhnya ditempatkan dalam pengaturan UUMK. Apalagi jika kemungkinan diatur dalam pengaturan internal masing-masing lembaga. Tetapi harus diatur pula dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR. Bahkan jika perlu, harus melalui proses amandemen kembali UUD 1945 untuk mempertegas sifat dan proses 40 Peranan MK dalam proses impeachment ini, setidaknya terkait pula dengan ketentuan Pasal 24C ayat (2) yang memisahkan posisi MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam kewenangan lainnya. 41 Lihat dan bandingkan dengan pertanyaan dalam Laporan Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment ….Op.cit., hal. 11-12. Juga Marsilam Simanjuntak, “Impeachmen Presiden; Catatan untuk RUU Mahkamah Konstitusi” dalam Firmansyah Arifin (peny), “Hukum & Kuasa…, Op.cit., hal. 81-90. impeachmen ini. Sedangkan dalam UUMK, telah diatur lebih lanjut mengenai soal alasan pemberhentian dan hukum acara persidangan MK. Menyangkut soal alasan pemberhentian, Pasal 10 ayat (3) UUMK menentukan bahwa; (a) pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;42 (b) korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;43 (c) tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (d) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden; (e) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.44 Sedangkan menyangkut soal hukum acaranya diatur mengenai DPR sebagai satusatunya pihak pemohon, masalah pembuktian dan beban pembuktian, gugurnya permohonan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri, serta masalah putusan. Rekomendasi 1. Amandemen kembali UUD 1945 untuk memperjelas dan mempertegas proses impeachmen. 2. Mengatur lebih lanjut tata cara impeachmen didalam undang-undang terkait (UU Susduk DPR/MPR dan UU tentang Kepresidenan). C. Memahami Sifat Putusan Final Putusan dalam suatu peradilan adalah merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik 42 43 Pasal 104-129 KUHP dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 44 Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah; (1) Syarat seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (2) tidak pernah mengkhianati negara; (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang.45 Putusan hakim seringkali diibaratkan dengan putusan Tuhan (judicium dei). Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fairtrial) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan (moral justice), dan bukan sematamata berdasarkan keadilan undang-undang (legal justice). Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, konstitusi (Pasal 24C ayat 1 UUD 1945) menempatkan MK sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan ini kemudian diikuti pengaturannya di Pasal 10 ayat (1) UUMK. Putusan final berarti bahwa putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa pihak-pihak, semua orang, badan publik atau lembaga negara akan mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Dengan kata lain, sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan, berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperoleh kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habetur). Mengapa konstitusi menempatkan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final? Pertanyaan ini menjadi relevan jika dihubungkan dengan kritik yang disampaikan sejumlah pihak yang mempertanyakan, sekaligus menghendaki adanya upaya hukum atau banding ketika putusan MK dianggap bermasalah. Barangkali secara filosofis dapat dimaknai bahwa, perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK merupakan perkara konstitusi. Artinya, konstitusi yang akan menjadi tolak ukur atau alat untuk menguji dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke MK. Oleh karena konstitusi yang menjadi rujukan, dan konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum tertinggi dalam kontreks negara hukum Indonesia, maka tidak tepat jika MK diposisikan bukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Disamping itu, karena perkara yang menjadi kewenangan MK memiliki dimensi yang luas (sifat, kepentingan dan akibatnya) dari segi social-politik, ekonomi maupun lingkup ketatanegaraan. Dengan melihat keluasan dimensi perkara tersebut, apabila disediakan upaya hukum terhadap putusan MK, maka akan mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bukan hanya pada para pihak pemohon tetapi Lihat dalam Maruara Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 193. 45 juga banyak pihak. Ketidakpastian dan ketidakadilan itu tentu saja dapat berujung pada “kekacauan” dan “instabilitas” di dalam masyarakat maupun pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan pula adalah, mengapa para pembentuk UUD dalam menempatkan putusan final untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan MK, membuat ketentuan yang terpisah antara dengan ayat (2). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan putusan final itu diperuntukkan bagi perkara pengujian undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Sedangkan pasal 24C ayat (2) nya menentukan, bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya pengaturan yang terpisah ini, terutama terhadap ketentuan pasal 24C ayat (2), tentu saja mengundang penafsiran, apakah putusan MK dalam perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden itu tidak bersifat final dan mengikat (final dan binding), sehingga terbuka kemungkinan bagi MPR untuk sependapat atau membuat putusan yang berbeda dengan putusan MK. Dengan kata lain, MPR dapat menafsirkan ulang dan tidak mengikuti atau menindaklanjuti putusan MK? Nampaknya filosofi itu yang digunakan oleh pembentuk UUD, yang menempatkan MK bukan sebagai pemutus akhir dalam perkara pemberhentian (impeachmen) Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK hanya menjadi lembaga yang memberikan landasan hukum dalam proses impeachmen Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme di MPR lah yang akan menjadi akhir dari proses impeachmen (lihat pembahasan mengenai impeachmen). Tidak begitu jelas alasan pembentuk UUD, mengapa masih menempatkan MPR sebagai lembaga yang akan memutuskan pemberhentian, meskipun sudah dibentuk MK. Barangkali karena masih terpengaruh pandangan dan pikiran UUD 1945 sebelum amandemen, yang menempatkan/mendudukkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, kemungkinan putusan final MK itu memang diperuntukkan bagi perkara selain perkara impeachmen. Masalah lainnya dalam pengaturan ketentuan undang-undang adalah, apakah putusan final itu harus juga diikuti dengan kata ‘mengikat’ (binding). Yang berarti undang-undang harus menentukan secara eksplisit putusan final diikuti dengan kata mengikat (final and binding). UUD 1945 maupun UUMK memang tidak mengatur atau menegaskan secara demikian. UUMK hanya menyatakan bahwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”46. Dengan tidak adanya pengaturan yang menyatakan secara eksplisit bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, apakah hal ini berarti putusan final MK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Untuk hal ini, meskipun sifat mengikat (binding) tersebut tidak disebutkan, akan tetap memiliki makna yang sama dengan yang disebutkan secara eksplisit. Karena final akan selalu diikuti dengan mengikat.47 D. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Ketentuan soal Sekretariat Jendral (Sekjend) dan Kepaniteraan dalam UUMK dirumuskan secara singkat, hanya diatur dengan 2 (dua) pasal. Terkait dengan hal ini ada beberapa issue masalah yang perlu dicermati. Issue masalah tersebut menyangkut soal keberadaan, susunan organisasi, tugas dan kewenangan serta syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekjend dan Panitera. 1. Keberadaan Sekjend dan Kepaniteraan Pasal 7 UU MK menyebutkan bahwa, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Kata ‘dibantu’ dalam rumusan pasal tersebut, seperti menunjukkan adanya keharusan dari unsur atau lembaga lain yang dapat berperan membantu/menunjang kelembagaan MK. Terbukti, jika melihat ketentuan pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 51/2004 tentang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, yang menyatakan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan adalah aparatur Pemerintah.48 Tidak jelas alasan pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan seperti itu. Apakah karena hakim konstitusi yang berasal dari 3 lembaga? Atau karena MK merupakan lemabaga baru sehingga memandang perlu mendapat bantuan? Dan apakah bantuan tersebut bersifat fakultatif yang bisa ada atau tidak ada sama sekali? 46 Pasal 47 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 47 Lihat dalam laporan penelitian Denny Indrayana, dkk, “Analisis Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Pada Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) Dan Peradilan Tata Usaha Negara”, FH-UGM, Yogyakarta, Juni 2007, hal. 142143. 48 Pasal 1 Keputusan Presiden No. 51/2004, “Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah aparatur Pemerintah y.ang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan seperti ini seakan kemudian merefleksikan pejabat di lingkungan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan yang merupakan aparatur pemerintah (eksekutif) hanyalah bersifat sementara, yang sewaktu-waktu bisa kembali ke lembaga asal jika sudah selesai melaksanakan tugasnya di MK. Yang jelas rumusan pada Pasal 7 UUMK itu tidak tepat, dan tidak benar pula Kepres yang menyebutkan Sekjend dan Kepaniteraan adalah aparatur Pemerintah.49 Rumusan seperti itu jelas akan mereduksi independensi MK yang bisa membuka ruang intervensi dari lembaga lain. Rekomendasi : Pasal 7 UUMK perlu dirumuskan secara lebih tegas, yang menyatakan bahwa “pada Mahkamah Konstitusi dibentuk atau ditetapkan adanya Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan”. Dan ditentukan pula bahwa Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan merupakan aparatur MK, bukan pegawai atau aparat dari lembaga lain. Sehubungan dengan fungsi dan tugasnya, dalam Pasal 7 UUMK menjelaskan bahwa, ”Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.” Rincian tugas dan fungsi Sekjend dan Kepaniteraan tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Keppres No. 51/2004. Tabel 2: Rincian Tugas dan Fungsi Sekjen & Kepaniteraan MKRI Sekretariat Jendral Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administrative Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah- tanggaan; Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga; Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan Kepaniteraan Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; Pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. 49 Bandingkan hal ini dengan Panitera di MA. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan di Mahkamah Agung, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Panitera adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MA. Penempatan fungsi/tugas dari Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan dalam penjelasan UUMK sangat tidak tepat. Penjelasan tersebut sudah mengatur soal norma yang semestinya diletakkan di dalam batang tubuh undang-undang. Sedangkan rincian pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana ditentukan lewat Keppres, nampaknya masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran yang dapat menunjukkan adanya kewenangan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing. Disamping itu, perlu ada pengkajian kembali terhadap fungsi dan tugas tersebut apakah sudah cukup memadai atau tidak. Rekomendasi : Penjelasan Pasal 7 UUMK perlu dipindahkan ke dalam batang tubuh undang-undang. Perlu dirumuskan kewenangan pokok lain yang diperlukan bagi Sekjend dan kepaniteraan, yang setidaknya hal ini diatur dan ditentukan melalui Peraturan Presiden. Perlu penjabaran lebih lanjut pelaksanaan fungsi dan tugas Sekjend dan Kepaniteraan sebagaimana diatur dalam Kepres. Dan seiring dengan perkembangan, perlu mengkaji kembali apakah fungsi dan tugas tersebut sudah cukup memadai atau tidak. 2. Susunan Organisasi Sekjend dan Kepaniteraan Pasal 8 UUMK merekomendasikan agar, “Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Keppres No.51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK mengatur, Kesekretariatan memiliki tugas dan fungsi administratif umum sedangkan kepaniteraan mempunyai fungsi administratif justisial. Perangkat kesekretariatan membidani semua kegiatan teknis administratif kerumahtanggaan. Kesekretariatan adalah eksekutif dalam jalannya pemerintahan di tubuh MK. Sedangkan kepaniteraan melayani teknis administratif justisial dalam artian semua hal teknis yang berkaitan dengan jalannya tahapan proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan, struktur kelembagaan di MK saat ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan. Adanya Sekjend dan Kepaniteraan pada MK dapat dikatakan sudah tepat, karena keduanya dibutuhkan untuk menjalankan tugas/fungsi yang berbeda. Meskipun ada juga pemikiran bahwa dua fungsi/tugas dapat disatukan dengan alasan kelembagaan MK yang tidak perlu terlalu besar. Sekretariat Jendral dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral, dan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera. Keduanya berkedudukan sejajar, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua MK. Meskipun bertanggungjawab kepada Ketua MK, pengangkatan dan pemberhentian Sekjend dan Panitera dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua MK.50 Struktur Organisasi MKRI Struktur seperti itu menyebabkan adanya dua lembaga yang sejajar dibawah Ketua MK, namun terpisah. Hakekat dari pemisahan ini, dimaksudkan agar terjadi pemisahan perlakuan terhadap persoalan administrasi umum dan penanganan perkara. Meskipun yang memiliki porsi kewenangan administratif secara umum berada ditangan Sekretariat Jenderal MK, bahkan pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan kepaniteraan pun dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK. Susunan organisasi sekretariat jendral ditentukan terdiri atas 5 biro, dan dimungkinkan dalam lingkungan sekretariat jendral dibentuk Pusat untuk penelitian dan pengkajian.51 Sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera. Adapun status pegawai dilingkungan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan adalah pegawai negeri sipil PNS.52 Susunan organisasi sebagaimana di atas, memperlihatkan belum adanya perimbangan antara Sekjend dan Kepaniteraan. Kepres memberikan porsi pengaturan yang lebih jelas 50 Ibid., Pasal 11 ayat (1) 51 Ibid., Pasal 5 & 8. 52 Sampai akhir Juli 2007, pegawai Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK terdiri dari, yang berstatus PNS sebanyak 130 orang, CPNS 5 orang, tenaga honorer 5 orang, tenaga ahli 10 orang, administrator 3 orang, tenaga perbantuan non instansi 11 orang, dokter non instansi 2 orang, pengemudi 17 orang, dan tenaga perbantuan Polri sebanyak 19 orang. Lihat, “Empat Tahun Mengemban Amanat Konstitusi”, MKRI, 2007, hal. 60. dan definitif susunan organisasi untuk Sekretariat Jendral. Sehingga terlihat susunan organisasi Sekjend lebih ’gemuk’, bahkan peranannya juga dominan. Seperti, ada satuan tugas yang kinerjanya berkaitan dengan Kepaniteraan, tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada Setjend. Pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh Sekjend. Namun tidak demikian halnya dengan Kepaniteraan. Padahal, Kepaniteraan merupakan unsur yang dapat dikatakan lebih vital peranannya bagi sebuah lembaga peradilan. UUMK maupun Keppres No. 51/2004, belum memberikan pengaturan yang memadai bagi kedudukan dan peranan Kepaniteraan/Penitera. Rekomendasi : Susunan organisasi Kepaniteraan mesti diatur lebih rinci dan jelas, terutama dengan menyebutkan secara tegas satuan tugas lain yang diperlukan. Dalam susunan Kepaniteraan perlu diakomodir dan disebutkan unsur lain seperti Panitera Muda atau Panitera Pengganti. Hal ini akan lebih memberikan kesan kuat performance MK sebagai institusi peradilan. Setidaknya memperlihatkan pula adanya keseimbangan dalam struktur kelembagaan MK antara Sekjend dan Kepaniteraan. Agar memperoleh legitimasi yang kuat, sebaiknya susunan organisasi untuk Sekjend dan Kepaniteraan diatur dalam undang-undang. 3. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan memiliki peranan yang penting bagi kelembagaan MK. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan itu, tentunya memerlukan personil yang memiliki kualitas memadai, profesional dan berintegritas. Persyaratan ini diperlukan agar fungsi dan tugas Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga menunjang kinerja MK secara keseluruhan. Sayangnya, UUMK tidak mengatur mengenai syarat-syarat yang diperlukan seseorang untuk dianggap layak dan tepat sebagai Sekjend dan Panitera. Hal itu juga tidak diatur dalam Keppres No. 51/2004. Semestinya soal persyaratan ini diatur dalam UUMK, mengingat organ kelembagaan dan kewenangannya disebutkan dalam UU, maka mengenai pejabat pelaksanannya juga harus diatur didalam UUMK. Demikian halnya dengan alasan pemberhentian bagi Sekjend dan Panitera, tidak ada pengaturannya dalam UUMK maupun Keppres.53 Pentingnya kualifikasi persyaratan itu diatur adalah, supaya jelas ukuran yang digunakan untuk menilai dan menentukan layak tidaknya seseorang memegang jabatan 53 Bandingkan hal ini dengan UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam UU MA diatur secara komprehensif syarat-syarat seseorang untuk menjadi Panitera, Panitera Muda dan Pengganti serta Sekretaris MA. Termasuk didalamnya juga diatur alasanalasan pemberhentian Panitera dan Sekretaris MA. Sekjend dan Panitera. Prosesnya pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan masuknya seseorang yang tidak cakap, atau karena ada unsur KKN. Selain itu, agar lebih terjamin pelaksanaan fungsi dan tugas Sekjend dan Kepaniteraan secara profesional dan bertanggungjawab. Setidaknya syaratsyarat penting bagi calon Sekjend dan Panitera yang perlu diatur dalam UUMK adalah, (i) syarat pendidikan minimal sarjana; (ii) pengalaman; (iii) tidak tercela, termasuk dalam hal ini tidak pernah melakukan tindak pidana dan terkena hukuman disiplin; (iv) melaporkan harta kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pentingnya alasan-alasan pemberhentian dari jabatan itu diatur dalam UUMK adalah, untuk memudahkan mekanisme yang harus diterapkan ketika Sekjend atau Panitera tidak dapat lagi melakukan tugasnya, atau karena melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang. Selain itu, dimaksudkan pula untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin timbul terhadap Sekjend atau Panitera. Sehingga lebih menjamin proses pemberhentiannya dilakukan secara fair dan obyektif. Pengaturan ini merupakan cermin dan penjabaran dari prinsip akuntabilitas yang senantiasa harus dikedepankan oleh MK. Adapun alasan-alasan pemberhentian yang harus dirumuskan dan diatur dalam UUMK, sebagaimana lazimnya diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan lainnya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu; alasan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Rekomendasi: Perlu diatur mengenai syarat pengangkatan dan alasan pemberhentian bagi Sekjend dan Panitera. Termasuk dalam hal ini adalah mekanisme/proses yang digunakan secara transparan, obyektif dan akuntable. E. Perihal Asisten Hakim (Tenaga Ahli) Unsur lain yang tidak kalah pentingnya bagi MK adalah Asisten Hakim (legal assistant). Di negara-negara lain, Asisten Hakim memiliki peranan penting dan strategis bagi kinerja MK. Misalnya di MK Federal Jerman dan Republik Korea Selatan. Asisten hakim di MK Jerman sering pula disebut Senat Ketiga, atau diibaratkan black box yang akan merekam seluruh proses kegiatan sistem pengambilan putusan di MK. Keberadaannya diatur berdasarkan Article 13 Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court. Melalui ketentuan tersebut, dikatakan tugas asisten adalah untuk mendukung kinerja hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas keseharian. Artinya, asisten hakim memainkan peranan penting, dimulai dari tahap pemeriksaan awal suatu perkara hingga tercapainya putusan berkekuatan hukum final dan mengikat. Peranan penting asisten hakim itu tergambar dari tugas-tugasnya seperti; menangani perkara yang baru diregistrasi, mengumpulkan data, melalukan observasi atau evaluasi, membuat analisa atau terhadap suatu perkara, atas nama hakim, membuat dan mengirimkan laporan kepada para pihak yang berperkara untuk mendapatkan tanggapan, mempersiapkan suatu penetapan yang terkait dengan diterima atau tidaknya perkara, dan merancang sebuah keputusan. Para asiten hakim itu mayoritas berasal atau berprofesi sebagai hakim, JPU, pegawai administrasi yang pernah bekerja di pengadilan umum, serta dari akademisi. Rata-rata berusia 30 -40 tahun. Pengetahuan khusus soal tata negara terkadang tidak diharapkan. Setiap hakim memiliki 3 asisten hakim, dan masing-masing hakim diberi keleluasaan untuk memilih dan mengangkat para asistennya. Namun dibolehkan mengalokasikan asisten semata-mata hanya atas dasar keinginan hakim itu sendiri. Besarnya peranan asisten hakim ini bisa dilihat juga dari pendanaan yang dialokasikan untuk asisten ini berasal dari Anggaran Belanja Rep. Federal Jerman, 5 juta DM atau setara dengan 2.4 juta dollar setahun.54 Sedangkan asisten hakim di MK Korea Selatan, disebut juga constitution research yang keberadaannya diatur dalam article 19 Constitutional Court law. Constitution resesearch dan asisten constitution research, merupakan anggota/pegawai tetap MK yang diangkat dan diberhentikan oleh President MK. Tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan dan keputusan suatu perkara. Mereka berasal dari kalangan praktisi hukum; pegawai hukum (legal officers) di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah, National Assembly atau pengadilan dengan pengalaman minimal 3-5 tahun; serta berasal dari kalangan akademisi. Bagaimana dengan MK Indonesia? Meskipun tidak diatur dalam UUMK, demikian pula dalam Keputusan Presiden maupun PMK, asisten hakim pernah hadir dan dipraktekkan di MK Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Blue Print MK, ada 11 orang yang direkuit menjadi asisten hakim (legal assistant) yang seluruhnya berasal dari kalangan perguruan tinggi. Tugas 54 Ahmad Syahrizal, op cit., hal. 222-227. pokoknya adalah;55 a. Menyusun pendapat hukum (legal opinion) atas perkara yang masuk. b. Mengumpulkan dan menganalisis konsep, teori dan dalil atau dogma hukum dan bidang terkait lainnya untuk diterapkan terhadap perkara. c. Mendampingi kerja Ketua MK, Wakil Ketua, atau hakim di dalam maupun ke luar d. Mendampingi Ketua MK, Wakil Ketua MK atau hakim MK dalam rapat yang tidak bersifat rahasia di dalam dan ke luar MK e. Mewakili Ketua MK, Wakil Ketua MK atau hakim dalam memenuhi undangan dan kerjasama dengan pihak luar. f. Memberikan pertimbangan strategi nasional terhadap MK. Pada intinya tugas utama para asisten hakim ini adalah, untuk membantu hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Peranan asisten hakim ini diharapkan dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Apalagi jika mengingat hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang, bisa jadi akan terbatas untuk menangani perkara-perkara dalam jumlah yang banyak dan dengan issue/masalah yang beragam. Yang perlu dipikirkan lagi adalah bagaimana menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap keseluruhan substansi dalam suatu perkara. Karena besar kemungkinan terjadi, putusan bisa berbeda meskipun dasar hukum yang menjadi alat ukurnya sama. Atau suatu perkara yang sudah sekian lama diputus, suatu ketika akan muncul kembali, sedangkan hakim yang memutus sudah berganti. Artinya, secara kelembagaan MK harus bisa menjaga dan menjamin konsistensi putusan-putusan yang telah dikeluarkannya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah ’kebingungan’ yang bisa berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dikemudian hari. Peranan ini setidaknya bisa diberikan kepada asisten hakim. Jadi, betapa penting dan strategisnya peranan dari asisten hakim bagi MK. Meskipun disadari akan pentingnya peranan dari asisten hakim, namun keberadaannya belum dijamin secara jelas. Dalam prakteknya, asisten hakim/tenaga ahli MK direkuit dan diangkat oleh Ketua MK berdasarkan sistem kontrak. Sistem kontrak ini tentu saja belum memberikan jaminan yang jelas dan pasti atas keberadaan asisten hakim. Karena besar kemungkinan keberadaan asisten hakim, amat bergantung dari keperluan dan penilaian subyektif para hakim 55 Lihat Cetak Biru MKRI, Membangun MK Sebagai Institusi Peradilan Yang Modern Dan Terpercaya, MKRI, hal. 72- 73 Rekomendasi: Keberadaan Asisten hakim ini perlu diakomodir dalam UUMK. Selain akan memberikan kejelasan dan kepastian, pengaturan asisten hakim dalam UUMK ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pelembagaan asisten hakim di dalam kelembagaan MK. Adapun hal-hal yang perlu diatur mengenai asisten hakim ini adalah; (i) posisi dan statusnya; (ii) pengangkatan dan pemberhentian; (iii) syarat-syarat, misalnya syarat umur, pengalaman dan jenjang pendidikan yang menunjukkan kualifikasi profesional; (iv) serta masa jabatannya. F. Independensi Anggaran/Keuangan Independensi peradilan merupakan sebuah prinsip penting yang harus diakui dan dijamin dalam sebuah konstitusi negara demokrasi. Namun demikian jaminan independensi, baik secara personal hakim maupun institusional pengadilan, tidak hanya sebatas pengakuan formal dalam konstitusi. Tetapi bagaimana prinsip independensi itu dapat dilihat dalam hal penunjukkan dan pemberhentian hakim, jaminan masa jabatan, hak atas pengelolaan anggaran (financial). Seberapa jauh karakteristik independensi peradilan itu telah diatur dan ditentukan dalam konstitusi atau undang-undang, akan menjadi penanda seberapa besar perhatian negara tersebut dalam menjamin dan menerapkan prinsip independensi peradilan. Sebagaimana disebutkan, salah satu upaya untuk menjamin independensi peradilan adalah dengan cara menjamin independensi anggaran bagi pengadilan. Pengadilan akan sulit melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara independen, apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi atau besar kecilnya anggaran terlalu tergantung pada pihak lain (eksekutif atau legeslatif). Bahkan bisa jadi, pihak eksekutif atau legeslatif akan menggunakan issue anggaran ini untuk ‘menekan’ dan ‘mengintervensi’ lembaga peradilan jika tidak ada jaminan independensi anggaran. Oleh karena itu, beberapa konvensi international menegaskan bahwa adalah kewajiban negara untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi terselenggaranya pengadilan yang baik.56 Di sejumlah negara, issue atau masalah independensi anggaran bagi pengadilan ini menjadi penting, sehingga merasa perlu untuk diatur dalam konstitusi. Seperti di Thailand dan Philipina.57 Bahkan dalam konstitusi Philipina disebutkan bahwa, pengadilan mempunyai 56 Misalnya dalam Article 13 International BAR Association Code of Minimum Standarts of Judicial Independence, “Court Service should be adequately financed by the relevant government”. 57 Dalam Konstitusi Thailand section 275 disebutkan, “The Office of the Courts of Justice shall have autonomy in personnel administration, budget and other activities as provided by law”. Sedangkan konstitusi Philipina Article VIII Section 3 otonomi keuangan dan ditegaskan bahwa legeslatif tidak boleh menyetujui anggaran bagi pengadilan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Hal yang sama diatur pula dalam UU Constitutional Court Russia, yang menyebutkan adanya jaminan independensi anggaran untuk menunjang pelaksanaan aktifitas Cons. Court secara efektif dalam kerangka independensi pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara penuh. Dan larangan untuk budget yang akan dikeluarkan/digunakan tidak boleh berkurang jika dibandingkan budget tahun sebelumnya.58 Konstitusi, Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 telah memberikan jaminan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Selanjutnya untuk menjaminan independensi tersebut, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memerintahkan bahwa untuk urusan organisasi, administrasi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan MA/MK, dan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang masing-masing lembaga.59 Hal demikian ditegaskan kembali dalam UUMK bahwa, MK bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (Pasal 12). Selain itu, sehubungan dengan masalah anggaran (financial) ditentukan bahwa kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara (pasal 6 ayat 1); dan kewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya (pasal 13 ayat 1); serta soal sumber anggaran MK yaitu APBN (Pasal 9). Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat memunculkan pertanyaanmenyebutkan, “ The Judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the Judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year and, after approval, shall be automatically and regularly released.” 58 Section 7 Federal Constitutional Law of the Russian Constitutional Court, “The Constitutional Court Russian Federation is independent in organizational, financial and material-technical respects from any other bodies. Financing of the Constitutional Court of the Russian Federation shall be effected at the expense of the federal budges and shall ensure the possibility of independent implementation of constitutional proceedings to the full extent. The budget of expenses of the Constitutional Court of the Russian Federation may not be reduced as compared to the previous financial year.” 59 Pasal 13 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur; (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilari yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) untuk masing-masing Iingkungan, peradilan diatur dalam undangundang sesuai dengan kekhususan Iingkungan peradilan masing-masing pertanyaan yang perlu dijelaskan dan ditegaskan lebih lanjut. Apakah ketentuan bahwa MK bertanggung jawab untuk urusan keuangan dapat ditafsirkan memiliki makna, MK berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengelola keuangannya sendiri? Sebab, UUMK tidak memberikan ketentuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa MK berhak secara mandiri menentukan dan mengelola keuangannya. Demikian halnya dengan soal protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua dan para hakim konstitusi, mengapa harus diatribusikan kembali lewat peraturan perundang-undangan (biasanya lewat Kepres atau Perpres), dan tidak ditegaskan saja dalam UUMK? Tidakkah hal ini akan mereduksi independensi para hakim, ketika hak-haknya ditentukan oleh eksekutif yang bisa jadi amat bergantung pada kepentingan subyektif Presiden? Dapat dikatakan pengaturan masalah keuangan/financial dalam UUMK, belum sepenuhnya mencerminkan independensi MK. Oleh karena itu dirasakan perlunya penegasan kembali soal pengelolaan financial ini, dan hak-hak para hakim yang harus diberi dan dijamin undang-undang. Penegasan ini tidak perlu terpengaruh pada persoalan apakah dalam pelaksanaan urusan keuangan telah dianggap cukup baik atau terpenuhi semua kebutuhan anggaran MK. Atau harus bergantung pada adanya performa kinerja yang baik terlebih dahulu, sebelum hak dan pengelelolaan anggaran ini diberikan. Prinsipnya, hal ini memang harus ditegaskan dalam undang-undang untuk lebih menjamin prinsip dan pelaksanaan independensi MK, terutama dalam hal financial. Sehingga siapapun (eksekutif dan legeslatif) nantinya tidak akan mudah untuk mempengaruhi independensi MK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan melalui pengaturan anggaran. Disamping itu, jika dalam UUMK ada ketentuan yang mewajiban MK melaporkan tentang pengelolaan keuangan, supaya ada prinsip perimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan pemberian hak, mengapa tidak masalah independensi keuangan dan hak-hak para hakim ditegaskan dalam UUMK. Rekomendasi : 1. Perlu penegasan yang menjamin independensi MK dalam urusan keuangan/financial. 2. Hak-hak keuangan, protokoler ataupun tunjangan lainnya bagi para hakim konstitusi, perlu diatur dalam undang-undang. G. Transparansi dan Akuntabilitas Perihal mengenai transparansi dan akuntabilitas diatur dalam Pasal 12-14 UUMK. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut masih bersifat umum, dan hanya menyangkut transparansi dan akuntabilitas secara kelembagaan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, menyangkut soal kewajiban MK melaporkan secara terbuka tentang perkara yang telah terdaftar, diperiksa dan diputus, serta penggunaan anggaran dan tugas administrasi lainnya. Disamping itu, ditegaskan pula hak dari masyarakat untuk mengakses/mendapatkan putusan MK. Pengaturan mengenai hal ini dapat dikatakan sudah cukup memadai. Prakteknya, prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat diselenggarakan dengan baik oleh MK. Laporan yang berisikan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam menerima dan memutus perkara, serta penggunaan anggaran dan tugas administrasi, rutin diterbitkan dalam laporan tahunan. Demikian halnya dalam hal managemen dan administrasi perkara, systemnya telah didukung dan dilakukan secara on line. Sehingga bagi masyarakat, tidak hanya bisa mendapatkan putusan MK secara mudah, cepat dan gratis, masyarakat dapat pula mengetahui setiap perkembangan perkara yang masuk ke MK. Hal ini memang sudah selayaknya dapat dilakukan/diterapkan MK. Mengingat bahwa perkara-perkara yang ditangani oleh MK tidak hanya menyangkut kepentingan orang per orang, akan tetapi mengenai sistem yang menyangkut kepentingan semua orang/warga negara. Penerapan sistem managemen dan administrasi perkara yang modern seperti itu, sangat sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan mudah. Rekomendasi: Agar lebih menjamin keberlangsungan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana telah dipraktekkan selama ini, maka sistem manajemen dan administrasi perkara secara on line tersebut sebaiknya dapat diakomodir dan ditegaskan dalam UUMK. Demikian pula hak dari masyarakat untuk bisa mengetahui perkembangan perkara, tidak hanya berkenaan dengan soal putusan, dapat dirumuskan dan diatur dalam UUMK. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI Sebagaimana layaknya lembaga peradilan, personil utama dari Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah hakim yang disebut hakim konstitusi. Hakim konstitusi inilah yang nantinya menjalankan tugas dan kewenangan MK, dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang diajukan para pihak. Untuk menentukan hakim konstitusi ini, prosesnya tidak dilakukan oleh satu lembaga, tetapi dilakukan oleh beberapa lembaga yang dapat mengusulkan atau mengajukan orang yang dianggap tepat menjadi hakim MK. Masing-masing lembaga yang ditunjuk, memiliki hak preogratif dalam memilih atau menyeleksi calon hakim konstitusi, yang kemudian diangkat dan disahkan. Proses pengajuan hakim MK yang dilakukan oleh beberapa lembaga, lazim dipraktekkan di hampir semua negara yang memiliki MK (lihat tabel 2). Mengapa hakim MK harus diusulkan atau berasal dari beberapa lembaga? Setidaknya hal ini dapat dipahami pertama, pembagian kewenangan (sharing power) dalam pengajuan hakim MK dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masing-masing lembaga, sekaligus sebagai penyeimbang (balancing power) kekuasaan/kepentingan lembaga lain. Kedua, model pengajuan hakim oleh beberapa lembaga, dapat dilihat sebagai bagian dari keperluan untuk membangun system cheks and balaces bagi MK. Ketiga, melalui pengajuan hakim oleh beberapa lembaga itu, legitimasi personal hakim diharapkan dapat berkorelasi secara positif terhadap eksistensi dan peranan MK secara kelembagaan. Artinya, keberadaan hakim konstitusi yang telah memperoleh dukungan maksimal itu, dapat menjadi jaminan bagi MK agar dapat memberikan keadilan sesuai tugas dan kewenangan konstitusional yang telah diberikan. Meskipun keberadaan hakim konstitusi melalui proses seleksi beberapa lembaga, akan tetapi tetap harus dijamin bahwa hakim konstitusi independent dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para hakim diharapkan bisa bertindak netral dan ’menjaga jarak’ dengan lembaga yang mengusulkan. Tindakan itu diperlukan agar hakim dalam memeriksa perkara dan memberikan putusan, berlaku dan bersikap adil tanpa mudah dipengaruhi oleh kepentingan lembaga-lembaga lain. Demikian pula sebaliknya, lembagalembaga yang memiliki kewenangan konstitusional mengajukan hakim konstitusi, sedapat mungkin menahan diri untuk tidak mempengaruhi hakim dalam proses penanganan perkara. Oleh konstitusi Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, hakim konstitusi pada MKRI ditentukan berjumlah sembilan (9) orang hakim yang berasal masing-masing 3 orang dari MA, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden. Jadi, selain menentukan soal jumlah hakim konstitusi 9 orang, konstitusi telah memberikan kewenangan dan menunjuk 3 lembaga yang berhak untuk mengajukan hakim konstitusi. Disamping itu, konstitusi juga telah menentukan syarat keharusan hakim konstitusi. Bagaimana kemudian UUMK mengaturnya lebih lanjut? Apakah masalah rekuitmen dan persyaratan hakim konstitusi telah diatur secara jelas, rinci dan komprehensif di dalam UUMK? Ini penting diperhatikan agar dapat menjamin terlaksananya prinsip independensi dan akuntabilitas para hakim konstitusi. A. Mengukur Syarat Materiil Mengenai masalah persyaratan ini, Pasal 24 ayat (5) UUD 1945 telah menentukan bahwa, Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sedangkan dalam UUMK, perihal persyaratan ini kemudian dibedakan menjadi syarat untuk hakim konstitusi dan syarat calon hakim konstitusi. Masalahnya adalah; pertama, UUMK tidak menjelaskan lebih lanjut perihal syarat hakim konstitusi yang telah ditentukan UUD. Misalnya, apa yang dimaksud bahwa hakim konstitusi harus negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan? Bagaimana mengukur seorang hakim konstitusi telah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ada kesan pengaturan yang memisahkan syarat atau keharusan hakim konstitusi, dengan syarat seseorang yang dianggap tepat untuk menjadi calon hakim konstitusi dalam UUMK, tidak berkorelasi satu sama lain. Seolah-olah, syarat pencalonan hakim konstitusi adalah sesuatu yang berbeda dengan keharusan ketika seseorang sudah menjabat sebagai hakim konstitusi. kedua, Pasal 16 UUMK menentukan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syaratsyarat; (a) warga negara Indonesia; (b) berpendidikan sarjana hukum; (c) berusia sekurangkurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; (c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (d) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan (e) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Syarat-syarat tersebut belum cukup tepat dan representative untuk menjelaskan persyaratan keharusan menjadi hakim konstitusi. Dengan kata lain, persyaratan calon hakim konstitusi itu kurang mendekati kualifikasi persyaratan ideal hakim konstitusi sebagaimana diinginkan oleh UUD 1945. ketiga, persyaratan hakim konstitusi yang diatur lebih lanjut pada Pasal 15 UUMK, rumusannya kurang sesuai dan tidak konsisten dengan rumusan ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Pasal 15 UUMK hanya menyebutkan bahwa Hakim konstitusi harus memenuhi syarat: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sedangkan syarat tidak merangkap sebagai pejabat negara, ditentukan terpisah dalam Pasal 17 UUMK. Rekomendasi: Syarat-syarat hakim konstitusi sebagaimana telah ditentukan UUD, perlu dijelaskan atau diatur lebih rinci. Hal itu diperlukan untuk mengukur sejauh mana seseorang dapat dianggap layak, dan bisa menjalankan tugasnya ketika sudah menjadi hakim konstitusi. Dengan kata lain, syarat-syarat yang ditentukan bagi calon hakim konsitusi harus mengarah kepada kualifikasi persyaratan hakim konstitusi yang telah ditentukan UUD. Sebaiknya sistematika perumusan ketentuan pasal-pasal mengenai syarat hakim konstitusi, dapat dirumuskan secara konsisten dan disesuaikan dengan bunyi rumusan UUD. Selanjutnya adalah bagaimana menjelaskan sekaligus mengkualifikasi syarat keharusan hakim konstitusi ke dalam UUMK. Karena syarat yang diharuskan konstitusi yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, syarat negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, serta syarat tidak merangkap jabatan, merupakan syarat ideal yang masih bersifat umum dan abstrak. Jadi, perlu dirumuskan kriteria-kriteria yang terukur yang bisa menunjukkan seseorang mendekati atau berperilaku sesuai persyaratan tersebut. 1. Memiliki Integritas Dan Kepribadian Yang Tidak Tercela. Integritas berasal dari kata "integrity", yang berarti "soundness of moral principle and character honesty". Dengan kata lain, mereka yang memiliki integritas, lazimnya memiliki hati nurani yang bersih, mempunyai prinsip moral yang tangguh, adil serta jujur, dan tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Jadi dapat didefinisikan, integritas itu adalah jujur dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab. Integritas (integrity) merupakan hal yang esensial yang layak dilaksanakan oleh pejabat lembaga peradilan. Merujuk pada pedoman perilaku hakim, integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai- nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untukmencapai tujuan terbaik.60 Sedangkan “Kepribadian” (personality) secara umum diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang menentukan pola perilakunya. Secara spesifik kepribadian terdiri dari sifat-sifat yang mengakibatkan perbedaan individu dalam perilaku. Sifat-sifat seseorang itu mungkin sama-sama dimiliki dalam satu kelompok (keluarga, masyarakat), tetapi polanya antara individu berbeda. Jadi, kepribadian sebagai “sesuatu” yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Dan kepribadian itu bukan merupakan sesuatu yang bersifat statis, kepribadian itu dinamis dan senantiasa dapat berubah. Dari penjelasan atas pengertian tersebut diatas, yang dimaksud integritas dan kepribadian yang tidak tercela itu adalah seseorang harus bersikap jujur dan adil, serta senantiasa memelihara karakter dan sifat-sifat pribadi yang baik dan positif yang setia berpegang teguh pada nilai kebenaran dan norma-norma yang berlaku. Sikap dan karakter yang positif itu setidaknya telah tercermin sebelum seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi. Jadi, apabila seseorang yang hendak mencalonkan/dicalonkan menjadi calon hakim konstitusi harus dapat menunjukkan integritas dan kepribadian yang terpuji dan jauh dari perbuatan/perilaku buruk. Demikian halnya ketika sudah menjadi hakim konstitusi, integritas dan kepribadiannya itu dapat terus terlaksana dan terjaga secara konsisten, terutama pada saat menjalankan tugas secara bertanggungjawab sebagai hakim konstitusi. Rekomendasi: Untuk dapat mengukur bahwa seorang calon atau hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, setidaknya dapat dilihat dan dinilai dari ada/tidaknya; (1) catatan/laporan harta kekayaannya; 60 Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. (2) melakukan tindak kejahatan/kriminal dan pidana penjara; (3) melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (4) pelanggaran terhadap etika profesi dan etika akademis; (5) pelanggaran norma kesusilaan; (6) melakukan tindakan indisipliner. Agar integritas dan kepribadian yang tidak tercela itu terjaga, merujuk pada ‘The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002’, maka bagi hakim konstitusi setidaknya diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat larangan seperti; (1) mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan karena ada hubungan pribadi, keluarga dan pertemanan; (2) mengadili berdasarkan prasangka; (3) menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Hal-hal tersebut sebaiknya juga diatur dalam kode etik dan perilaku yang berlaku khusus bagi hakim konstitusi. 2. Adil Untuk memahami makna adil dan mengetahui bahwa seseorang itu memiliki sifat adil, bukanlah suatu hal yang mudah. Barangkali hal itu dapat mudah terlihat ketika hakim konstitusi sudah memutus perkara. Namun demikian, Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.61 Rekomendasi : Sikap atau perilaku Adil yang dapat diterapkan oleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya; (1) tidak boleh memberikan kesan mengistimewakan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi putusan; (2) tidak boleh menunjukkan rasa suka atau tidak suka, membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, status ekonomi, aliran politik; (3) dilarang mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan yang dapat mengesankan adanya keberpihakan; (4) memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan; (5) dilarang berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan. 61 Lihat., Pedoman Perilaku Hakim 3. Negarawan Yang Memahami Konstitusi dan Ketatanegaraan. Syarat negarawan nampaknya merupakan syarat yang khusus bagi hakim konstitusi, yang tidak ditemukan pada persyaratan hakim di lingkungan peradilan umum maupun pejabat di lembaga-lembaga negara lainnya. Mengapa demikian? Barangkali karena tugas dan kewenangan hakim konstitusi yang harus menangani perkara berkaitan dengan masalah-masalah konstitusi dan kenegaraan. Atau karena para hakim yang berasal/diusulkan dari 3 lembaga, maka dituntut sikap dan tindakan negarawan yang selalu mengedepankan pada kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, hakim konstitusi harus bisa berada diatas kepentingan semua lembaga, dan tidak berpihak pada kepentingan lembaga yang mengusulkan. Masalahnya apa pengertian dari negarawan itu, dan bagaimana mengukur seseorang itu negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan? Menurut pengertian umum selama ini, yang disebut sebagai negarawan itu adalah seseorang yang menunjukkan kebijaksanaan, ketrampilan, dan visi-pandangan jauh kedepan dalam mengurus soal-soal kenegaraan dan dalam menangani masalah-masalah yang timbul yang menyangkut masalah umum dan masyarakat. Merujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Depdiknas dan diterbitkan Balai Pustaka (2005) mengartikan negarawan sebagai ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola negara dengan kebijaksanaan dan kewajiban. Tafsir yang hampir sama ditemukan pada Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (1995). Negarawan adalah pakar yang menjalankan pemerintahan atau negara; pakar di bidang kenegaraan. Bisa pula berarti seorang pemimpin politik yang menciptakan kebijakan negara secara taat asas dengan suatu pandangan ke depan. Dari pengertian dan definisi tersebut, setidaknya dapat dikualifikasikan bahwa seseorang bisa disebut negarawan pertama, pengalaman (ahli) dalam menangani dan menyelesaikan masalah kenegaraan dan masalah-masalah umum kemasyarakatan. Kedua, pengalaman tersebut dilakukan baik pada lembaga-lembaga formal negara maupun lembaga/institusi masyarakat. Artinya, seorang negarawan itu tidak harus berasal dari lembaga di lingkungan legeslatif, eksekutif dan peradilan, tetapi bisa juga berasal dari lingkungan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, dalam menangani masalah kenegaraan dan kemasyarakatan tersebut, senantiasa didasarkan atas kebijaksanaan dan pandangan serta kepentingan yang jauh kedepan. Jadi dalam bersikap dan bertindak, tidak didasarkan atas kepentingan yang sempit, tetapi selalu melampaui diatas kepentingan dan bias politik, ras, gender, dan golongan. Namun tidak hanya sebatas negarawan, konstitusi menghendaki dan menekankan negarawan tersebut harus memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Penekanan ini dapat dipahami karena masalah-masalah yang akan ditangani MK berkaitan dengan masalah konstitusi dan ketatanegaraan. Kriteria atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur syarat ini, setidaknya dapat dilihat dan ditentukan dari pengalaman seseorang dalam menangani masalah kenegaraan, syarat umur, dan dari pengetahuan yang didasarkan latarbelakang pendidikan/akademisnya. Pasal 16 ayat (1) UUMK mengatur, syarat seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi berumur sekurang-kurangnya 40 tahun, pendidikan sarjana hukum dan pengalaman 10 tahun di bidang hukum.62 Syarat yang ditentukan UUMK ini, belum cukup memadai dan kurang mencerminkan kualifikasi seseorang adalah negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, syarat minimalis ini akan sangat berpengaruh terhadap ‘kredibilitas dan kewibawaan’ MK ketika mengadili perkara atau berhadapan dengan institusi negara lainnya. Khusus mengenai syarat umur minimal 40 tahun, batas usia minimal ini bagi seseorang dipandang masih terlalu muda dan minim pengalaman dalam menghadapi soal-soal kenegaraan. Disamping itu, terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi 5 tahun yang dibatasi untuk 2 kali periode jabatan, diperkirakan usia maksimal setelah menjadi hakim konstitusi adalah 50 tahun. Pada usia ini, bagi seseorang yang telah pensiun dari jabatan hakim konstitusi, dipandang masih produktif dan besar kemungkinan masih memiliki hasrat yang tinggi untuk menduduki posisi jabatan di lembaga lain. Bahayanya adalah, jika hasrat atau keinginan tersebut muncul ketika masih menjadi hakim konstitusi, sangat potensial berpengaruh terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Akibatnya, putusan bisa menjadi tidak obyektif dan independent. Syarat negarawan yang merupakan syarat mulia dan terhormat yang harus dimiliki oleh hakim konstitusi, pada akhirnya akan 62 Bandingkan hal ini dengan syarat menjadi hakim agung. Untuk menjadi hakim agung ditentukan persyaratan sekurang- kurangnya berusia 50 tahun, pengalaman 20 tahun untuk hakim karier dan 25 tahun untuk kalangan non karier, serta berijazah magister ilmu hukum bagi calon dari non karier (Pasal 7 ayat 1 & 2 UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung) mudah tereduksi oleh kepentingan-kepentingan yang sempit dan bersifat personal. Selain batas usia minimal tersebut diatas, perlu juga diatur batas usia minimal ketika diajukan menjadi hakim konstitusi. Jangan sampai ketika dicalonkan/diajukan, usianya sudah mendekati usia pensiun. Sehingga dipastikan dirinya, tidak akan produktif karena tidak lama menjadi hakim konstitusi.63 Rekomendasi: Untuk lebih mendekatkan pada kualifikasi syarat negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, sejumlah syarat yang telah ditentukan dalam UUMK harus direvisi. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah; (1) umur sekurang-kurangnya adalah 50 atau 55 tahun, dan berusia maksimal 60 tahun ketika diajukan/dicalonkan. Syarat usia minimal itu, berkorelasi dengan pengalaman seseorang yang dapat diasumsikan telah mencapai tingkat ‘kenegarawanannya’; (2) syarat pendidikan ditingkatkan minimal magister ilmu hukum (S2), yang juga memiliki pengetahuan mengenai konstitusi dan ketatanegaraan; (3) berpengalaman selama 15-20 tahun di bidang hukum. (4) memiliki pengalaman dalam menghadapi/mengatasi persoalan-persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan secara umum. 4. Tidak Rangkap Jabatan Syarat tidak merangkap jabatan merupakan syarat yang bersifat kondisional, yang berarti sesuatu baru akan terjadi atau dilakukan apabila kondisinya telah memenuhi syarat dan memungkinkan. Jadi, larangan rangkap jabatan ini baru akan dilaksanakan ketika seseorang telah menjadi hakim konstitusi. Syarat ini tidak memperkenankan hakim konstitusi dalam waktu yang bersamaan merangkap jabatan atau profesi lainnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya conflict of interest, agar hakim konstitusi tetap terjaga obyektifitas dan independensinya dalam memutus perkara. Disamping itu, agar terhindar dari conflict of the time yang dapat mengganggu kelancaran didalam menyelesaikan perkara-perkara yang telah diterima MK. Disebutkan dalam Pasal 17 UUMK, jabatan/profesi yang tidak diperkenankan untuk dirangkap oleh hakim konstitusi yaitu; (a) pejabat negara lainnya; (b) anggota partai politik; (c) pengusaha; (d) advokat; atau (e) pegawai negeri. Pejabat negara lainnya, misalnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selama menjadi hakim konstitusi, status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara, dan bagi advokat, tidak boleh menjalankan 63 Sangat disayangkan bahwa dalam seleksi hakim konstitusi jilid II, hakim konstitusi terutama pilihan MA dan Presiden sudah mendekati usai pensiun. Diantaranya. Prof. Dr. Muktie Fadjar (66 Tahun), Arsyad Sanusi & Muhammad ALim (64 Tahun). profesinya. Sedangkan untuk pengusaha dijelaskan maksudnya adalah, direksi atau komisaris perusahaan. Masalahnya adalah, meski larangan rangkap jabatan baru dilaksanakan ketika seseorang sudah dipastikan terpilih sebagai hakim konstitusi, ketentuan ini memberikan toleransi yang mendorong ketidaksungguhan seorang untuk menjadi hakim konstitusi. Jabatan hakim konstitusi hanya akan jadi mainan, karena bisa jadi seseorang hanya akan coba-coba atau menjadi jobseekers seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Praktik ini berpotensi pula mereduksi independensi dan imparsialitas hakim, karena besar kemungkinan seorang calon hakim konstitusi masih sangat kuat dan kental keterikatannya dengan latarbelakang jabatan/profesi sebelumnya, terutama calon yang berasal dari partai politik. Disamping itu, larangan rangkap jabatan ini tidak pernah dinyatakan secara terbuka dan transparan ketika seseorang sudah diangkat menjadi hakim konstitusi. Bisa jadi seorang hakim konstitusi masih menjabat dan menjalankan tugas pada jabatan yang dilarang undang-undang. Konsekwensinya lebih lanjut, akan terjadi inefisiensi anggaran karena hak/fasilitas dari jabatan sebelumnya masih diterima, meskipun yang bersangkutan sudah menjadi hakim konstitusi. Rekomendasi: Sebaiknya larangan rangkap jabatan dilakukan pada saat seseorang belum terpilih menjadi hakim konstitusi. Diatur mengenai jeda waktu antara yang dapat diberlakukan sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi hingga terpilih dan diangkat menjadi hakim konstitusi. Atau setidak-tidaknya pernyataan mundur/lepas dari jabatan sebelumnya, sudah disampaikan pada saat seseorang mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Pernyataan tidak rangkap jabatan dan mundur atau berhenti dari jabatan sebelumnya, harus dinyatakan secara terbuka, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat melunturkan integritas hakim konstitusi. B. Seleksi Hakim Konstitusi Seperti yang telah ditentukan UUD, untuk mengajukan hakim konstitusi prosesnya dilakukan oleh 3 lembaga (DPR, Presiden dan MA). Pasal 18 ayat (1) UUMK menegaskan kembali hal tersebut, yang kemudian harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Bagaimana proses seleksi hakim konstitusi itu dilakukan di masing-masing lembaga? UUMK menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi (Pasal 20 ayat 1). Sekalipun demikian, UUMK juga meminta agar proses pancalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19). Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Dan dalam proses pemilihannya, dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat 2). Pertanyaannya adalah bagaimana cara DPR, Presiden dan MA melakukan seleksi hakim konstitusi? Adakah tata cara tersebut diatur lebih lanjut kemudian, dan bagaimana prinsipprinsip seleksi yang ditentukan UUMK itu diterapkan? Pada kenyataannya, masing-masing lembaga itu menerapkan tata cara seleksi yang tidak sama baik pada seleksi jilid I tahun 2003 maupun yang kedua pada tahun 2008.64 Pada seleksi hakim konstitusi jilid I, DPR menggunakan cara fit and proper test terhadap calon-calon hakim konstitusi yang diusulkan fraksi-fraksi di DPR. Cara yang sama kemudian dilakukan pada seleksi hakim konstitusi jilid II tahun 2008, namun dengan proses yang lebih terbuka yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar diri atau dicalonkan. Calon yang terdaftar pun kemudian diumumkan di media massa, agar masyarakat dapat memberikan masukan ataupun catatan tentang track record calon meski dalam waktu yang sangat terbatas. Lain halnya seleksi yang dilakukan oleh Presiden. Pada seleksi jilid I, Presiden melalui Departemen Hukum & HAM melakukan penjaringan calon hakim konstitusi, yang kemudian diteliti dan diputuskan bersama oleh Mentri Hukum & HAM, Jaksa Agung dan Menkopolkam sebelum diajukan ke Presiden. Untuk yang kedua, Presiden memberikan mandat kewenangannya itu kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).65 Sedangkan seleksi oleh MA, baik yang pertama maupun kedua, dapat dikatakan sangat tertutup jika dibandingkan dengan cara yang dilakukan DPR dan Presiden. Tidak jelas dengan cara bagaimana MA melakukan seleksi tersebut. MA hanya menentukan nama calon hakim konstitusi yang berasal dari kalangan hakim (Hakim Agung dan Hakim PT/PTUN), yang kemudian diajukan ke Presiden untuk diangkat/disahkan. 64 Untuk seleksi jilid I merupakan seleksi hakim konstitusi yang pertama kali dilakukan, sehubungan dengan baru terbentuknya lembaga MK. Seleksi pada saat itu, dilakukan dalam waktu yang terbatas kurang lebih 10 hari. Sedangkan seleksi hakim konstitusi jilid II dilakukan sehubungan dengan adanya hakim konstitusi yang pensiun dan selesai masa jabatan 5 tahun pertamanya. 65 Dewan Pertimbangan Presiden membentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, Advokat dan Akademisi). Panitia Seleksi Watimpres ini dalam batas-batas tertentu telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Hasilnya, Watimpres mengajukan 9 nama dari sejumlah calon hakim konstitusi untuk dipilih dan diputuskan Presiden sebanyak 3 orang. Tata cara seleksi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga itu, jelas mereduksi prinsipprinsip yang telah ditentukan, bahkan pada prakteknya bertentangan dengan UUMK. Sayangnya, UUMK tidak mengatur soal konsewensi atau pemberian sanksi, jika hal itu dilanggar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme seleksi dengan cara menyerahkan kepada masing-masing lembaga perlu ditinjau ulang. Karena cara seleksi seperti ini mengkondisikan masing-masing lembaga untuk menafsirkan dan menerapkan proses seleksi secara berbeda-beda. Dengan cara seperti itu membuat proses seleksi kurang transparan, diskriminatif dan berpotensi menyimpang dari ketentuan UUMK sebagaimana yang telah terjadi dalam praktek. Untuk itu, semestinya dibuat sebuah mekanisme seleksi yang bisa digunakan bersama. Pada saat pembahasan RUU MK, KRHN pernah mengusulkan agar mekanisme seleksi bersama itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan proses penjaringan dan penelitian (track record, fit and proper test/wawancara) calon hakim konstitusi. Sedangkan untuk pemilihan dan penentuannya diserahkan kepada masing-masing lembaga sebelum diajukan ke Presiden.66 Namun melalui peranan Komisi Yudisial ini, terkendala ketentuan dalam Konstitusi yang hanya memberikan kewenangan Komisi Yudisial melakukan rekuitmen/seleksi hakim agung. Untuk menjamin proses seleksi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, maka kedepan sebaiknya KY ditempatkan pula peranannya dalam seleksi hakim konstitusi. Rekomendasi : 1. Tata cara seleksi berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan masing-masing lembaga, tidak diserahkan kepada masing-masing lembaga, tetapi diperjelas dan dipertegas dalam UUMK. 2. Sehubungan dengan hal yang pertama, penjelasan pada pasal 19 UUMK bahwa “calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”, sebaiknya ditempatkan dalam batang tubuh UU. 3. Sebagai penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka dalam setiap tahapan itu harus ditentukan pula alokasi waktu yang diperlukan. 4. Perlu ada aturan mengenai sanksi apabila tahapan-tahapan seleksi diatas tidak dilakukan. 5. Amandemen kembali UUD 1945 yang menempatkan peranan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim konstitusi. C. Masa Jabatan Hakim Konstitusi 66 Firmansyah Arifin dkk (penyusun), Pokok-Pokok Pikiran RUU Mahkamah Konstitusi, KRHN-Kemitraan, 2003, hal. 26- 28. Masa jabatan merupakan suatu masa atau kurun waktu dimana seseorang telah ditentukan lamanya menjalankan tugas jabatannya sebagai hakim konstitusi. Ketentuan mengenai masa jabatan ini berkaitan dengan status hakim konstitusi sebagai pejabat negara (Pasal 5 UUMK). Dalam hal ini, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, status pejabat negara berbeda dengan PNS. Pejabat negara merupakan pimpinan dan anggota Lembaga/Komisi negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, dan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun ciri-ciri yang biasanya dimiliki oleh setiap pejabat negara adalah; (a) pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme tertentu; (b) kedudukannya dalam lembaga negara bersifat setara; (c) memiliki independensi dan akuntabilitas; (d) memiliki aturan protokoler dan kesejahteraan sendiri; (d) dapat mengatur sendiri ketentuan kepegawaiannya. Adanya pengaturan mengenai masa jabatan bagi hakim konstitusi merupakan salah satu faktor utama untuk menjamin independensi selama masa kerjanya. Biasanya masa kerja pejabat negara ditentukan secara periodik, seperti masa jabatan atau berdasarkan masa usia pensiun dalam jabatan hakim agung. Pejabat negara tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatan. Karena itu umumnya pejabat negara hanya dapat dicopot dari posisinya melalui mekanisme tertentu, yang biasanya bersifat politis untuk kondisi tertentu yang dianggap fatal, seperti melakukan tindak pidana, atau karena sakit terus menerus. Sehubungan dengan jaminan masa kerja tersebut, maka pertanggungjawaban pejabat negara umumnya dikaitkan dengan prosedur pemilihan kembali pejabat yang bersangkutan. Apabila pejabat tersebut memiliki kinerja yang baik, maka sebagai bentuk akuntabilitasnya, ia berpeluang untuk dipilih kembali pada periode selanjutnya. Pasal 22 UUMK menentukan masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pada prinsipnya UUMK menentukan masa jabatan hakim konstitusi itu adalah 5 (lima) tahun. Apabila dikehendaki kembali, dan belum memasuki usia pensiun, maka dimungkinkan untuk dipilih dan meneruskan jabatan hakim konstitusi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pengaturan periodisasi masa jabatan seperti itu bagi hakim konstitusi itu memiliki beberapa kelemahan; Kesatu, periodesasi masa jabatan 5 tahun itu berpotensi mempengaruhi independensi MK sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. Karena hal itu, menurut Saldi Isra akan membuka ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi, untuk melakukan intervensi melalui pengisian atau penempatan kembali hakim konstitusi yang cenderung sepihak dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Atau sebaliknya, dengan tidak memilih kembali hakim konstitusi yang dinilai berseberangan dan dapat menghambat kepentingan rezim penguasa. 67 Dalam pemahaman yang sama, menurut Tom Ginsburg, karena metode pengangkatan hakim konstitusi yang ditentukan oleh Presiden dan DPR, dimana keduanya adalah lembaga politik, maka model pengangkatan seperti itu akan menempatkan posisi MK kedalam politic institutional environment. Persoalan itu setidaknya dapat diatasi dengan melalui cara membatasi masa jabatan hakim konstitusi hanya untuk satu kali masa jabatan. Karena masa jabatan hakim yang dapat dipilih kembali dapat mengurangi tingkat independensi peradilan.68 Kedua, pengaturan periodesasi masa jabatan itu mendorong terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, menurut Prof. Amzulian Rifa’i para hakim konstitusi akan berusaha untuk terpilih kembali pada masa jabatan berikutnya, yang kemudian berpotensi melakukan hal-hal yang menyimpang.69 Ketiga, tidak jelas tolak ukur yang digunakan dalam hal menentukan hakim konstitusi yang dianggap layak untuk dipilih kembali dan diteruskan masa jabatannya. Atau ketika hakim konstitusi yang telah selesai masa jabatannya, tidak dipilih kembali dan ditentukan untuk tidak diteruskan masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.70 Keempat, adanya periodesasi masa jabatan lima tahunan dapat mengganggu kinerja MK dalam menangani dan memutus perkara. Hal itu dapat terjadi jika pada saat yang bersamaan pula, sejumlah hakim konstitusi telah memasuki usia pensiun. Sehingga mayoritas hakim atau bahkan seluruhnya harus menjalani atau mengikuti proses seleksi yang diadakan. Rekomendasi : Periodesasi masa jabatan 5 (lima) tahun perlu ditiadakan. Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya 67 Lihat dalam transkip “Expert Meeting Revisi UU Mahkamah Konstitusi”, diselenggarakan oleh KRHN-DRSP di Hotel Millenium, Jakarta, 27-28 Agustus 2007. 68 Tom Ginsburg, Judicial Review…., opcit, hal. 47. 69 Ibid., 70 Pada seleksi hakim konstitusi jilid II, Maret 2008, Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Harjono mengikuti proses seleksi hakim konstitusi di DPR untuk periode masa jabatan kedua (2008-2013). Oleh Komisi III DPR, keduanya hanya diminta menyatakan kesediaannya secara tertulis yang kemudian disampaikan secara terbuka didepan Sidang Komisi III DPR. Hasilnya, DPR memilih Jimly Asshiddiqie untuk dapat meneruskan masa jabatan periode berikutnya. Sedangkan Harjono, digantikan oleh Aqil Mochtar (F-Golkar), yang terpilih bersama Mahfud MD (F-PKB) menggantikan hakim Achmad Roestandi yang berhenti karena pensiun. Tidak begitu jelas alasan dan tolak ukur apa yang digunakan DPR, mengapa lebih memilih kembali Jimly Asshiddiqie sedangkan Harjono tidak. ditentukan hanya untuk sekali menjabat dengan masa jabatan 9 atau 10 (sepuluh) tahun. Dengan begitu, prinsip independensi dapat lebih terjaga, peluang terjadinya intervensi dan penyimpangan dapat diminimalisir, prakteknya lebih mudah diselenggarakan dan tidak menyulitkan, serta tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja MK dalam mengadili perkara. Apalagi jika melihat perbandingan di banyak negara, pilihan satu kali masa jabatan hakim konstitusi ini merupakan pilihan yang paling banyak digunakan/dipraktekkan (Lihat Table 3). Tabel 3: Komparasi Hakim Mahkamah Konstitusi Beberapa Negara Negara Jumlah Pengajuan usul dan Pengangkatan Albania 9 orang Dipilih oleh Presiden atas persetujuan Majelis. Armenia 9 orang 5 orang oleh National Assembly dan 4 orang oleh Presiden. Bulgaria 12 orang BosniaHerzegovi na Republik Czech Republik Federal Jerman Italia 9 orang 1/3 oleh Presiden, 1/3 oleh National Assembly dan 1/3 oleh joint meeting para hakim Supreme Court tingkat kasasi dan Supreme Administration Court 6 orang oleh Parlemen, 3 orang oleh Presiden European Court of Human Right berkonsul-tasi dengan lembaga kepresidenan Oleh Presiden atas persetujuan Senate 15 orang 16 orang 15 orang Lithuania 9 orang Federasi Rusia 19 orang Republik Slovenia 9 orang Spanyol 12 orang Afrika Selatan Korea Selatan 11 orang Thailand 15 orang 9 orang Terdiri dari 2 panel, masing-masing panel beranggotakan 8 hakim. ½ dari tiap panel dipilih Bundestag sisanya oleh Bundesrat. 5 orang oleh Parlemen, 5 orang oleh Presiden, dan 5 orang oleh Supreme Ordinary and Administrative Court Usul dari Presiden, Ketua Seimas dan Ketua Suprema Court yang menentukan adalah Seimas Usul oleh Presiden Federation Council, Deputies of State Duma, Supreme Court, Biro hukum negara federal, legal societies, legal scientific dan institusi pendidikan Usul oleh Presiden pengangkatan oleh National Assembly Usul 4 orang dari Congress 4 orang dari Senate, 2 orang oleh pemerintah dan 2 orang oleh General Council kekuasaan Yudicial. Penunjukkan oleh Raja Spanyol (tidak ada keterangan) 3 orang dipilih Presiden, 3 orang dipilih National Assembly dan 3 orang ditunjuk oleh Ketua Supreme Court Usul Senat, pengangkatan oleh Raja D. Pemberhentian Hakim Konstitusi Masa Jabatan 9 tahun tidak dapat dipilih kembali, 1/3 anggotanya diperbaharui setiap 3 tahun. Berakhir jika masuk usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dijatuhi hukuman pidana/penjara. 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali 5 tahun 10 tahun, tidak ada larangan pemilihan kembali 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali 9 tahun 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali Berakhir jika mencapai usia 70 tahun, meninggal dunia, mengundurkan diri, melanggar ketentuan jabatan hakim, dijatuhi hukuman pidana/ penjara. 9 tahun dan tidak dapat diperpanjang, setiap 3 tahun komposisinya diperbaharui. 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali 6 tahun dan dapat dipilih kembali Berakhir jika pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri. Melanggar ketentuan jabatan hakim, dijatuhi hukuman pidana/ penjara Ada 2 pokok bahasan masalah yang berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi ini yaitu, mengenai alasan pemberhentian dan mekanisme/prosedur pemberhentiannya. 1. Alasan Pemberhentian Untuk alasan pemberhentian hakim konstitusi, Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUMK membedakan alasan diberhentikan dengan hormat dan alasan diberhentikan dengan tidak hormat. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila; (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; (c) telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun; (d) telah berakhir masa jabatannya; atau (e) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sedangkan diberhentikan dengan tidak hormat apabila; (a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; (d) melanggar sumpah atau janji jabatan; (e) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (f) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 soal larangan rangkap jabatan; atau (g) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Masalah yang hendak dibahas berkenaan dengan alasan pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan perbuatan tercela dan dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu yang telah ditentukan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945. Pasal ini mengatur kewenangan MK sehubungan dengan proses pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. a. Kualifikasi Perbuatan Tercela Ketentuan larangan melakukan perbuatan tercela sepertinya sudah menjadi suatu hal yang lazim diatur dalam undang-undang, terutama ketika mengatur prasyarat untuk pencalonan dan pemberhentian anggota/pejabat di lingkungan lembaga/komisi negara. Demikian halnya untuk hakim konstitusi. Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan tercela. Penjelasan UUMK Pasal 23 ayat (2) huruf b menjelaskan “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi”. Namun penjelasan seperti ini belum menjelaskan apa yang dimaksud “perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi”. Atau perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dikualifikasikan merendahkan martabat hakim konstitusi? Jika melihat pada undang-undang lainnya, seperti UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "'perbuatan tercela" adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.71 Sedangkan dalam penjelasan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikatakan, yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.72 Apakah cukup demikian jika yang dimaksud perbuatan tercela tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan adat? Jika pengertian atau kualifikasi perbuatan tercela adalah seperti itu, kesannya hanya bersifat personal dan tidak terkait dengan posisi jabatannya. Semestinya pengertian ataupun perbuatan yang dapat dikualifikasi menjadi perbuatan tercela, harus mencakup perbuatan yang bersifat personal maupun berhubungan pula dengan posisinya sebagai pejabat negara. Rekomendasi: Perlu pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif bahwa yang dimaksud perbuatan tercela atau perbuatan yang dianggap merendahkan martabat hakim dalam UUMK ini adalah perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan moral yang bersifat personal/pribadi dan juga sehubungan dengan posisinya sebagai pejabat negara. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah; 73 a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat seperti berjudi, mabuk, pecandu narkoba dan berzina; b. melakukan kebohongan publik; c. tidak melakukan kewajiban sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, diantaranya, tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya, melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat, KKN, melaksanakan 71 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 5 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 72 Penjelasan Pasal 58 huruf l UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Pasal 6 huruf j UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 73 Lihat dalam siaran pers KRHN tentang Usulan dan Saran Terhadap Substansi RUU Mahkamah Konstitusi- Hasil Pertemuan KRHN & Tim Pakar, Jakarta 1 Agustus 2003. tugas dengan membeda-bedakan suku, agama ras dan golongan. b. Wajib Memberi Putusan Dalam Waktu Yang Ditentukan. Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945. Pasal 7B ayat (4) ini mengatur soal kewajiban MK untuk memutus perkara yang diajukan DPR dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlunya penegasan waktu 90 hari bagi MK untuk memutus, dapat dipahami maksudnya adalah untuk memberikan kepastian agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan. Mengingat pula perkara yang berkaitan dengan proses pemakzulan (impeachment) ini, memiliki dimensi politik yang tinggi. Sehingga kemungkinan terjadinya ‘gejolak politik’ di masyarakat dan kepentingan publik yang terabaikan karena Presiden dan/atau Wakil Presiden sedang mengikuti proses hukum, dapat minimalisir dan dihindari. Namun pertanyaannya, mengapa hanya dalam perkara itu saja hakim konstitusi wajib memutus dalam batas waktu yang telah ditentukan? Jika ada unsur kesengajaan menghambat, maka hakim konstitusi diancam untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Bukankah setiap perkara yang menjadi kewenangan MK pada hakikatnya sama karena diatur dalam UUD? Dan juga dapat dipandang memiliki ‘resiko politik’ dan implikasi yang luas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Apalagi kemudian, UUMK juga memberi pengaturan kewajiban bagi MK dalam batas waktu tertentu untuk memberi putusan dalam perkara pembubaran partai politik dan perselisihan pemilu.74 Rekomendasi : Ketentuan wajib memutus dalam waktu yang telah ditentukan dan menjadi alasan untuk memberhentikan hakim konstitusi, sebaiknya tidak hanya untuk perkara yang berkenaan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi juga perlu diberikan untuk perkara pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Alasannya, agar legitimasi putusan MK memiliki derajat yang sama dan tidak 74 Pasal 71 UUMK menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”. Sedangkan Pasal 78 UUMK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu….” terjadi perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Bahkan jika perlu, diberikan/diberlakukan sama untuk semua perkara. 2. Mengatasi Kekosongan Hakim Konstitusi. Pada saat hakim konstitusi harus berhenti, karena masa jabatannya habis atau sudah memasuki usia pensiun, kursi jabatan hakim konstitusi akan menjadi kosong. Kosongnya posisi hakim konstitusi itu jelas harus segera diisi, dan proses ini mesti dipersiapkan oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan. Apabila tidak segera diisi, maka kursi hakim konstitusi yang kosong bisa berpengaruh terhadap jalannya penanganan perkara. Bahkan bisa jadi membuat MK tidak bisa bersidang, atau bisa dianggap tidak sah kelembagaannya karena jumlah hakim konstitusi sebagaimana dipersyaratkan konstitusi adalah 9 orang, dan minimal 7 orang hakim dalam keadaan luar biasa, menjadi berkurang atau tidak terpenuhi. Sementara disisi lain, proses seleksi hakim konstitusi untuk menggantikan yang sudah berhenti, juga membutuhkan waktu. Kekhawatiran semacam itu sempat terjadi ketika Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengingatkan Presiden, DPR dan MA untuk melakukan seleksi hakim konstitusi yang baru, sehubungan dengan beberapa hakim konstitusi yang pensiun dan akan habis masa jabatannya di tahun 2008. Peringatan yang disampaikan jauh hari melalui surat itu, mengkhawatirkan jangan sampai terjadi kekosongan hakim konstitusi yang membuat MK tidak bisa bersidang. Sebagai sebuah langkah antisipasi, Pasal 26 ayat (1) UUMK sebenarnya sudah mencoba mengatur bahwa, “Apabila terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan”. Sedangkan pada ayat (2) nya ditentukan, “Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden”. Namun demikian ketentuan tersebut dapat dikatakan belum cukup memadai, karena yang diatur berkenaan dengan limit waktu yang disediakan undang-undang kepada lembaga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi pengganti. Ketentuan tersebut belum menjawab persoalan ketika masa jabatan atau usia pensiun hakim konstitusi sudah tiba, tetapi calon hakim konstitusi yang akan menggantikan belum terpilih atau diangkat/disahkan. Oleh karena itu, dipandang perlu membuat sebuah ketentuan yang dapat mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut. Dalam hal ini, ketentuan tersebut dimaksudkan agar kosongnya kursi hakim konstitusi yang berakibat MK tidak bisa bersidang atau MK tidak sah/tidak ada, tidak terjadi. Rekomendasi: Perlu dibuat ketentuan sebagai antisipasi jangan sampai terjadi kekosongan hakim konstitusi. Ketentuan ini mengatur bahwa sebelum ada hakim konstitusi yang baru yang akan menggantikan, maka hakim konstitusi yang lama masih bisa bertugas dalam menangani perkara. 3. Mekanisme Pemberhentian Lewat Majelis Kehormatan Atau Pengawasan Eksternal? Masalah pemberhentian hakim konstitusi, terutama dalam hal pemberhentian dengan tidak hormat, telah ditentukan bahwa pemberhentian itu akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK.75 Satu hal yang patut diapresiasi dalam proses pemberhentian dengan tidak hormat ini, UUMK telah mengatur soal pemberhentian sementara dan larangan untuk menangani perkara. Apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan, maka yang bersangkutan direhabilitasi.76 Ketentuan seperti ini sangat penting agar terjadi proses yang benar-benar fair dan obyektif dalam proses pemberhentian hakim konstitusi. Jika hakim konstitusi yang diancam dengan pemberhentian sementara masih menjabat dan menangani perkara, dikhawatirkan akan bisa menggunakan ‘kekuasaannya’ untuk mengganggu ataupun menghambat proses hukum yang sedang dijalankan untuk dirinya. Lebih dari itu, dapat dipastikan integritas hakim konstitusi yang sedang dipersoalkan dan diragukan itu, akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebelum hakim konstitusi itu diberhentikan dengan tidak hormat, Pasal 23 ayat (3) UUMK memberi kesempatan yang bersangkutan dapat membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selanjutnya, apa dan bagaimana MKMK itu, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut mengatur sebagai berikut; a. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. 75 76 Pasal 23 ayat (4) dan (5) UUMK Lihat Pasal 24 dan 25 UUMK. b. Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. c. Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut di atas dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi. d. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir b dicalonkan oleh Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon Anggota Tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. e. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Hakim Konstitusi. Ditentukan pula dalam Pasal 4 ayat (2) nya bahwa tugas dari MKMK adalah; a. Majelis Kehormatan bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. b. Mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. c. Memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Mahkamah Konstitusi Membaca ketentuan dalam PMK tersebut diatas, MKMK yang dimaksudkan dalam PMK tidak hanya semata-mata untuk proses pemberhentian hakim konstitusi, tetapi ditugaskan pula untuk menegakkan kode etik dan tingkah laku hakim konstitusi. Pengaturan MKMK dalam PMK seperti itu bisa membuat proses di forum MKMK bermasalah, karena hal-hal sebagai berikut; Kesatu, forum MKMK yang ditujukan bagi penegakkan kode etik dibuat berbeda dengan MKMK yang ditujukan untuk pelanggaran yang diancam sanksi pemberhentian. MKMK yang ditujukan untuk penegakkan kode etik, unsurnya hanya berasal dari hakim konstitusi. Sedangkan MKMK untuk proses pemberhentian dimungkinkan ada unsur diluar hakim konstitusi yang bisa dilibatkan. Padahal ketentuan dalam kode etik yang harus ditegakkan, terdapat hal yang sama dengan norma yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam UUMK. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) ketentuan kode etik, hakim konstitusi harus mematuhi sumpah jabatan dan menjauhkan perbuatan tercela, yang mana keduanya juga ditentukan menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam UUMK. Apabila terjadi pelanggaran terhadap sumpah jabatan atau dianggap melakukan perbuatan tercela, mekanisme MKMK mana yang akan digunakan? Jelas hal ini bisa menimbulkan kebingungan dalam praktek. Kedua, apabila hal itu terjadi, sebagaimana penjelasan pada point pertama, maka akan terjadi diskriminasi karena untuk persoalan yang sama, kemungkinan prosesnya dilakukan dengan cara yang berbeda. Ketiga, ada kesan kuat bahwa MKMK yang diatur dalam PMK itu cenderung memunculkan esprit de’corps (melindungi kepentingan hakim konstitusi) yang terkena ancaman pemberhentian. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari, pemilihan/penetapan anggota MKMK dari unsur diluar hakim konstitusi (mantan hakim agung, praktisi hukum senior dan guru besar ilmu hukum) yang berasal dari usul/saran masyarakat, yang harus dipilih/ditetapkan dalam rapat pleno MK. Demikian juga Ketua MKMK yang ditentukan harus berasal dari unsur hakim konstitusi. Seperti pada umumnya mekanisme penindakan atau pengawasan yang dibuat sendiri oleh lembaga yang bersangkutan (mekanisme internal), berjalan sangat partial dan kurang obyektif, sehingga pada gilirannya mekanisme itu diragukan berjalan secara efektif. Jelas dan dapat dipastikan, kemungkinan seperti itu bakal terjadi pada MKMK. Adakah mekanisme lain yang bisa dibuat atau digunakan? Sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kode etik maupun mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, dipandang perlu membuat sebuah mekanisme yang berfungsi mengawasi personal hakim konstitusi maupun kelembagaan MK. Pengawasan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan pelaksanaan prinsip independensi dan akuntabilitas. Karena Kekuasaan Kehakiman yang independen tanpa diimbangi dengan akuntabilitas berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ataupun juga menjadi tyrani judicial. Dengan kata lain, harus ada mekanisme kontrol (cheks and balance) terhadap MK yang dapat meminta sekaligus menuntut akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang telah diberi dan dimilikinya. Sebelumnya politik hukum untuk kebutuhan itu, menempatkan peranan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dalam hal ini, UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial memberikan wewenang pengawasan kepada KY dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pengertian hakim dimaksudkan dalam UUKY, tidak hanya sebatas hakim agung atau hakim pada lingkungan pengadilan umum, tetapi juga dimaksudkan untuk hakim konstitusi. Untuk kepentingan itu, KY dapat melakukan penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan pemanggilan, memeriksa, dan mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan penyimpangan, serta dapat memberikan penghargaan terhadap prestasi/jasa kepada hakim.77 Namun pasal-pasal yang berkenaan dengan pengawasan hakim konstitusi itu telah dimandulkan oleh putusan MK. MK menganggap bahwa hakim konstitusi bukan merupakan bagian dari obyek pengawasan KY dengan alasan; (i) sesuai dengan original inten permusan UUD, KY tidak dimaksudkan berkaitan dengan MK; (ii) hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap dan diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun saja; (iii) dalam proses pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi, tidak ada peran KY; (iv) khawatir kewenangan MK, terutama dalam perkara sengketa kewenangan, akan terganggu. Karena kemungkinan ketika timbul sengketa antara KY dengan MA, sengketa itu harus diadili oleh MK.78 Meskipun putusan itu telah bersifat mengikat, namun demikian tidak seluruhnya pendapat atau pertimbangan dalam putusan MK itu benar. Hasil eksaminasi terhadap putusan MK ini diantaranya berpandangan dan menilai bahwa; pertama karena kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim. Kedua, hakim konstitusi tidak diawasi KY karena masa jabatannya yang hanya lima tahun dan setelah itu kembali ke profesi semula, tidak pula tepat. Argumentasi demikian adalah pendapat yang anti akuntabilitas. Padahal semua lembaga negara dan pejabat negara harus diminta akuntabilitasnya.79 77 Sebelum dibatalkan oleh putusan MK, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 21 – 24 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 78 Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman., hal. 173- 176. Perkara ini diajukan oleh 31 orang hakim agung yang memohon dan meminta MK membatalkan pasal-pasal yang berkenaan dengan pengawasan hakim agung dalam UU KY dan UUKK. 79 Hasil Eksaminasi Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU KY dan UU KK. Majelis Eksaminasi terdiri atas Prof. Dr. Yohannes Usfunan, SH, Saldi Isra, Denny Indrayana, Fajrul Falakh, Iwan Satriawan, Sahlan Said, Lukman Hakim Lebih jauh menurut Denny Indrayana, putusan UUKY kental terkontaminasi conflict of interest. Perilaku hakim konstitusi diputuskan bukan obyek pengawasan KY, dengan alasan bahwa sistematika pembahasan di dalam konstitusi adalah MA, KY baru MK, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. The second founding parents yang merumuskan perubahan UUD mengungkapkan bahwa susunan demikian bukan berarti hakim konstitusi tidak diawasi oleh KY. Susunan itu terjadi by accident karena proses pembahasan perubahan UUD 1945 memang tidak sistematis. Sehingga yang lebih banyak didiskusikan adalah pengawasan terhadap MA dan jajaran peradilan lainnya. Namun, itu sama sekali bukan berarti hakim konstitusi tidak dapat diawasi oleh KY.80 Akhirnya, pilihan membatalkan semua pasal pengawasan dalam UUKY adalah pilihan yang masih debatable secara ilmu hukum konstitusi. Justru yang sudah pasti, pilihan itu menumbuhsuburkan praktik mafia peradilan. Suatu pilihan yang bertentangan dengan moralitas-konstitusionalitas (constitutional morality), yang bermakna setiap konstitusi harus diartikan sesuai dengan landasan moralitas. Sewajibnya setiap pilihan interpretasi hukum tidak boleh menabrak fondasi moralitas antimafia peradilan.81 Idealnya KY memang tetap diberi peran dalam proses pengawasan, terutama terkait dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Sebagaimana halnya Judicial Service Commission di Afrika Selatan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan saran (advice) kepada Presiden sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua MK, MA dan Semua Lembaga Peradilan.82 Namun untuk kearah itu tidak cukup dilakukan melalui revisi UUMK, tetapi harus melalui amandemen UUD. Dengan tetap memberi wewenang pengawasan pada KY, semestinya MKMK tidak perlu lagi ada. Kalaupun tetap diadakan, proses pembentukan forum MKMK tersebut sebaiknya diinisiasi/difasilitasi oleh KY bukan melalui mekanisme internal MK. Rekomendasi; Syaifuddin, Firmansyah Arifin. Diselenggarakan oleh Pukat UGM dan Indonesia Court Monitoring (ICM), Yogyakarta, 26-27 September 2006. 80 Denny Indrayana, “Negara Antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan”, Kompas, 2008, hal. 25. 81 Ibid., hal. 31 82 A. Ahsin Tohari, “ Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan”, Elsam, 2004, hal. 135. System pengawasan bagi MK perlu diperjelas, yang didalamnya tersedia mekanisme pemberhentian/pemecatan bagi hakim konstitusi. Untuk hal itu maka; 1. Revisi UUMK perlu mengatur tugas, kewenangan serta unsur dari MKMK, dimana salah satu unsurnya adalah Komisi Yudisial. Sebaiknya dalam MKMK ini, KY diberi peranan untuk menginisiasi/memfasilitasi forum MKMK yang hasilnya dapat langsung disampaikan kepada Presiden. 2. Amandemen kembali UUD yang dapat memperjelas/mempertegas posisi dan peranan KY dalam hal mengawasi hakim, tidak hanya untuk mengawasi hakim agung dan hakim di pengadilan umum, tetapi juga termasuk hakim konstitusi. BAB V MELENGKAPI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Hukum acara sangat mutlak diperlukan bagi sebuah institusi pengadilan. Kebutuhan hukum acara tidak hanya dilihat secara teknis prosedural guna mendukung penyelesaian perkara sesuai kewenangan pengadilan. Tetapi harus dilihat dan dimaknai bahwa, kebutuhan hukum acara untuk menjamin terlaksananya proses yang jujur (fair trial). Tujuannya adalah agar hak setiap orang dapat diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, benar dan adilnya penyelesaian perkara di hadapan pengadilan, tidak hanya dilihat dari putusan yang telah dijatuhkan, tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan telah memberi pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak (due process of law atau undue process). Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (due process law), berarti pengadilan telah menegakkan ideologi fair trial yang dicitacitakan negara hukum dan masyarakat demokratis. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi pengadilan (court of system), jelas memiliki hukum acara. Ketentuan mengenai hukum acara bagi Mahkamah Konstitusi cukup banyak diatur dalam UUMK. Terdapat kurang lebih 57 pasal yang mengatur soal hukum acara, dan nampaknya merupakan ketentuan/pengaturan yang paling mendominasi isi dari UUMK. Secara sistematika, pasal-pasal yang mengatur hukum acara ini terdiri dari dua (2) bagian. Pertama hukum acara yang bersifat umum, dan yang kedua bersifat khusus untuk mengatur pelaksanaan masing-masing kewenangan. Meskipun UUMK sudah mengandung banyak pasal hukum acara (pasal 28 – 85), tetapi bukan berarti tanpa kelemahan dan kekurangan. Seperti diakui pula oleh salah seorang hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, pengaturan hukum acara yang dimuat dalam UUMK sangat sumir sehingga terdapat begitu banyak kekosongan.83 Untuk menutupi kekurangan dan kekosongan tersebut, MK telah membuat beberapa Peraturan tambahan yang berkaitan dengan hukum acara. Hal ini memang dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UUMK yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”. Selain untuk melengkapi kekurangan UUMK, 83 Maruarar Siahaan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Konstitusi Press, 2005, hal. 4. Lihat pula wawancara Maruarar Siahaan dalam, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Masih Mengandung Kekurangan”, Hukumonline, 9 Desember 2003. peraturan MK mengenai hukum acara lahir karena adanya kebutuhan dalam praktek pelaksanaan kewenangan. Peraturan MK tersebut diantaranya adalah; (1) PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; (2) PMK Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004; (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; (4) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Namun demikian, meskipun telah ada sejumlah peraturan hukum acara yang dibuat, peraturan tersebut belum sepenuhnya melengkapi kekurangan yang ada dalam UUMK. Dengan kata lain, terdapat persoalan yang muncul dan berkembang di dalam praktek serta adanya kebutuhan baru dalam pelaksanaan tugas/wewenang MK, yang belum terjawab dan diatur baik didalam UUMK maupun peraturan MK. Disamping itu beberapa hal yang telah diatur dalam PMK, merupakan materi undang-undang sehingga lebih tepat jika diatur dan ditempatkan menjadi kedalam UUMK. Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi hukum acara MK ini dimaksudkan untuk mengubah ketentuan, melengkapi atau menambahkan kekurangan, serta mengambil dan memindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada ke dalam UUMK. A. UMUM Kedudukan dan kewenangan MK yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman selain MA dan badan peradilan lainnya, dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara konstitusi berlaku juga asas yang biasa digunakan pengadilan lainnya. Dalam hal ini proses yang dilakukan MK, tunduk dan mengikuti asas dan ketentuan umum yang berlaku dalam praktek kekuasaan kehakiman sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, maupun secara universal. Asas ini tidak akan menjadikan sesuatu mendorong proses yang tidak akan mendukung dalam satu dua hari belakangan ini. Asas-asas yang terkandung dalam UUMK seperti adanya, persidangan terbuka untuk umum, diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (1); independen dan imparsial peradilan (pasal 2). Selain menyangkut soal asas-asas, UUMK juga sudah mengatur beberapa ketentuan yang dipandang positif untuk menunjang peradilan MK dan menjamin pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntable. Selain itu beberapa ketentuan yang diatur dalam hukum acara ini dapat dipandang merupakan suatu hal yang baru yang berbeda dan belum diatur dalam hukum acara peradilan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut soal; a. Limitasi Waktu Yang Jelas, misalnya dalam hal untuk melengkapi berkas permohonan (Pasal 32 ayat 1), penetapan hari sidang pertama setelah registrasi (Pasal 34 ayat 1), pemanggilan saksi sebelum hari sidang (Pasal 38 ayat 2), penyampaian putusan kepada para pihak (Pasal 49) b. Kewajiban Mengumumkan Hari Sidang (Pasal 34 ayat 2 dan 3). c. Alat Bukti dalam Bentuk Elektronik atau Alat Optic (pasal 36 ayat 1). d. Perolehan Alat bukti yang harus dipertanggungjawabkan secara Hukum (Illegally Obtained Evidence/pasal 36 ayat 2). e. Pemeriksaan Pendahuluan (pasal 39). f. Countempt of Court atau kewajiban menaati tata tertib sidang (pasal 40). g. Dissenting Opinion dalam putusan (pasal 45 ayat 10). Meskipun demikian, berbagai ketentuan hukum acara yang sudah diatur dalam UUMK dan dilengkapi dengan beberapa PMK, sekiranya masih terdapat kekurangan dalam pengaturan hukum acara tersebut. Kekurangan yang sudah seharusnya dapat dilengkapi dengan mengadopsi, menambah ataupun mengelaborasi sejumlah ketentuan yang sudah ada. Dalam hal ini, mengingat pula bahwa perkara-perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam persidangan MK merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka beberapa asas penting dan relevan dapat menjiwai dan ditentukan pengaturannya kedalam UUMK. 1. Melengkapi Asas-Asas Hukum Acara a. Larangan menolak perkara (ius curia novit) Prinsip ini mendasarkan pada anggapan bahwa Pengadilan mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas. Dengan kata lain, MK harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Prinsip ini memberikan kewajiban kepada hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, untuk menentukan penyelesaian perkara melalui penafsiran, penelitian, mengkonstruksikan maupun melalui penemuan hukum (rechtsvinding). b. Hak Untuk Mendengar Secara Berimbang (Audi At Alteram Partem) Dalam proses peradilan, setiap pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk didengarkan keterangannya secara berimbang. Termasuk dalam hal mengajukan buktibukti yang dipandang perlu untuk memperkuat dalil-dalil permohonan yang diajukan. Asas ini untuk menjamin prinsip independensi dan impartialitas yang harus ditegakkan. Dalam hal ini pula, pengadilan atau Mahkamah dapat memanggil dan meminta keterangan dari pihak–pihak yang dianggap relevan. Bahkan bilamana perlu, pengadilan juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan diri memberikan keterangan. c. Hakim Bersifat Aktif (Dominus Litis). Pada dasarnya perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara yang berkaitan denga kepentingan umum atau publik. Seperti pada umumnya yang berlaku di dalam hukum publik, maka hakim dalam persidangan di MK harus berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapi segi hukumnya. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas suatu peristiwa yang merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik harus diberi wewenang yang besar. Dengan sikap aktif ini, hakim apabila perlu dapat menentukan sendiri hal-hal yang diperlukan (misalnya dengan, memanggil dan menentukan para pihak yang perlu didengarkan keterangannya, melakukan pemeriksaan pendahuluan, memanggil dan mendengarkan saksi-saksi yang diperlukan, menentukan dan menilai alat bukti), dengan maksud memperoleh kebenaran materiil, tanpa harus tergantung pada inisiatif dan keaktifan para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, hakim aktif ini tertuju kepada upaya untuk memperbaiki fakta yang tidak didalilkan oleh para pihak. Sikap aktif hakim ini dimaksudkan pula untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak setara, antara pemohon yang merupakan orang atau warga negara dengan penguasa (pemerintah/legeslatif) sebagai termohon. Dalam hal ini, Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo menyatakan bahwa, pada umumnya penguasa mempunyai kedudukan lebih kuat, juga dalam beracara. Hal ini dapat dikompensasi dengan meminimalkan aturan-aturan beracara dan memaksimalkan kebebasan hakim.84 84 Suparto Wijoyo, “Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi”, Surabaya-Airlangga University Press, 1997, hal. 69. Rekomendasi; UUMK harus melengkapi asas-asas hukum acara yang dapat menjadi pengarah bagi MK dalam melaksanakan fungsinya mengadili perkara. Asas-asas tersebut adalah; 1. Larangan menolak perkara 2. Hak untuk mendengar secara berimbang 3. Hakim bersifat aktif 2. Menambahkan Ketentuan Penting. Sebagaimana telah disebutkan bahwa, beberapa hal yang belum diatur dalam UUMK telah ditentukan lebih lanjut dalam PMK. Ketentuan tambahan dalam PMK tersebut selain timbul karena adanya kebutuhan, juga sebagai akibat dari adanya peristiwa atau persoalan yang berkembang didalam praktek. Tentu saja ketentuan tambahan yang telah dimuat dalam PMK, merupakan sesuatu yang positif yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penanganan perkara, sekaligus sebagai langkah antisipatif jika suatu saat nanti ditemukan peristiwa atau kasus yang sama. Beberapa ketentuan penting yang sudah diatur dalam PMK seperti; pengajuan permohonan dapat melalui media elektronik (fax atau email), pembebasan dari biaya perkara, pemeriksaan persidangan jarak jauh melalui teleconference, keterangan ahli yang tidak memiliki kepentingan (conflict of interest) dengan pokok perkara. Bahkan secara khusus dalam hukum acara untuk pengujian undang-undang, PMK Nomor 06/PMK/2005 telah mengatur soal akses bagi pihak terkait/ad informandum dan penghentian pemeriksaan jika terdapat dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang (Prejudiciil Geschill).85 Namun demikian, beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam PMK tersebut dapat dipandang merupakan materi muatan undang-undang, yang ketentuan maupun akibatnya akan mengikat banyak pihak. Para pihak yang tidak hanya sedang berperkara di MK, tetapi mengikat pihak-pihak lain, baik pemerintah, DPR, masyarakat secara luas. Apabila hanya diatur dan ditentukan melalui PMK, dikhawatirkan kurang mendapat Pasal 16 ayat 1 PMK Nomor 06/PMK2005 menentukan bahwa “ Mahkamah dapat menghentikan sementara proses pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang dapat hal terdapat dugaan terjadinya perbuatan pidana dalam proses pembentukan undang-undang, yang telah diproses secara hukum”. 85 pengakuan, dukungan atau legitimasi dari pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain, bisa saja pada suatu saat ketentuan yang sudah diatur dalam PMK tidak diakui, bahkan ditentang atau ditolak ketika akan diterapkan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya materi yang sudah ditentukan dalam PMK tersebut sebaiknya perlu dimasukkan menjadi materi atau ketentuan dalam UUMK. Sehingga dapat memperoleh jaminan dan legitimasi yang kuat, serta memudahkan segi penyampaian atau sosialisasinya kepada publik secara lebih luas. Rekomendasi: Beberapa materi dalam PMK mengenai hukum acara, sebaiknya diakomodir dan ditempatkan menjadi materi UUMK. Materi tersebut adalah; (a) pengajuan permohonan dapat melalui media elektronik (fax atau email), (b) pembebasan dari biaya perkara, (c) pemeriksaan persidangan jarak jauh melalui teleconference, (d) keterangan ahli yang tidak memiliki kepentingan (conflict of interest) dengan pokok perkara; (e) akses bagi pihak terkait/ad informandum dan (g) penghentian pemeriksaan jika terdapat dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang. 3. Masalah Pembuktian Pembuktian dalam sebuah persidangan bukanlah merupakan persoalan yang mudah untuk diterapkan. Hal ini amat bergantung dari system pembuktian yang dianut dan alat bukti yang dipergunakan atau diperkenankan undang-undang. Oleh karena perkara yang diadili MK merupakan perkara yang memiliki karakteristik perkara publik, maka system atau asas pembuktian yang digunakan MK adalah mengacu kedalam hukum publik, yaitu asas pembuktian bebas (vrij bewijs). Konsekwensi dari asas pembuktian bebas ini maka berlaku; 1) dalam melakukan pembuktian hakim tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan para pihak; 2) hakim yang membagi beban pembuktian di antara para pihak; 3) hakim tidak terikat pada ketentuan yang ada untuk memilih alat bukti; 4) penilaian terhadap hasil pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang bersangkutan.86 Prinsip umum dalam hukum acara juga menggunakan dalil bahwa “siapa mendalilkan harus membuktikan”. Kecuali peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum (notoire feit), dan hal-hal yang telah diketahui sendiri oleh hakim baik karena 86 Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara…, Opcit., hal. 67-69 pengalaman maupun karena dilihat sendiri didepan persidangan. Untuk masalah pembuktian ini, UUMK tidak mengatur beberapa hal penting dalam proses pembuktian, misalnya apa yang harus dibuktikan? Apa yang tidak perlu dibuktikan? Kapan dan kepada siapa pembuktian harus dibebankan?87 Namun karena asas hukum asas hukum acara yang digunakan dalam hukum publik dipandang dapat berlaku juga di MK, maka berdasarkan asas pembuktian bebas hakim bebas untuk menentukan beban pembuktian dan menilai alat-alat bukti. Adapun menyangkut soal alat bukti, Pasal 36 ayat (1) UUMK menentukan alat bukti ialah; a) surat atau tulisan; b) keterangan saksi; c) keterangan ahli; d) keterangan para pihak; e) petunjuk; dan f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dalam hal alat bukti surat atau tulisan yang dimaksud, berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.88 UUMK juga menentukan harus dapat dipertanggunjawabkan perolehannya secara hukum (Illegally Obtained Evidence). Jika tidak, surat atau tulisan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (Pasal 36 ayat 2 dan 3). Menyangkut alat bukti ini, terutama soal keterangan ahli, UUMK tidak memberikan definisi ataupun menentukan kriteria seorang ahli. Pernah dalam suatu perkara pengujian undang-undang MK ‘kecolongan’, karena seseorang yang memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang sedang diproses justeru dimintai keterangan sebagai ahli.89 Oleh karena itu perlu diberikan kriteria dan batasan mengenai ahli ini. Dalam PMK keterangan ahli adalah diberi penjelasan, “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.”90 Dari penjelasan tersebut 87 Lihat Maruara Siahaan, Hukum Acara…., opcit., hal. 126-127 88 Pasal 19 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2006 89 Lihat dalam “Kriteria Ahli dalam Persidangan MK Perlu Dipertegas”, http://hukumonline/detail.asp?id=11917&cl=Berita, diakses 14 April 2008. 90 Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diketahui bahwa, yang dimaksud ahli tidak hanya karena pendidikan atau memiliki gelar akademis, tetapi karena pengalamannya sehingga memiliki keahlian atau pengetahun mendalam tentang suatu hal tertentu yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan. Selain itu untuk lebih menjamin obyektifitas, seorang ahli tidak boleh memiliki kepentingan tersendiri dengan perkara yang diajukan.91 Ketentuan mengenai alat bukti dalam bentuk elektronik atau alat optik ini merupakan sesuatu yang baru yang diatur dalam hukum acara sebuah pengadilan. Dalam ketentuan hukum acara pidana, perdata maupun tata usaha negara ketentuan mengenai alat bukti seperti ini belum ada. Boleh jadi hal ini merupakan sebuah perkembangan hukum, yang dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga suatu fakta atau peristiwa yang dibuktikan dengan informasi yang tersimpan secara elektronik ini dapat dikatagorikan menjadi alat bukti. Namun pengaturan mengenai bentuk elektronik atau alat optic dalam UUMK ini lebih ringkas jika dibandingkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 26A UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26A ditentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, dapat diperoleh dari; (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Rekomendasi: 1. Perlu ditentukan kriteria dan batasan mengenai ahli dalam UUMK. 2. Alat bukti berupa alat elektronik dan alat optic perlu dielaborasi lagi lebih lengkap. 91 Pasal 22 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 menentukan, Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict of interest) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa. B. KHUSUS B.1. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang a. Melihat Kembali Subyek Pemohon Dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK dikatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang” . Siapa saja pihak yang dimaksud? Dalam pasal itu juga ditentukan pihak-pihak yang menjadi subyek pemohon atau memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; c) badan hukum publik atau privat; dan d) lembaga negara. Apabila pihak-pihak tersebut menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, maka wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan tentang; a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 (Uji Formiil); (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (uji materiil).92 Masalahnya, ketentuan yang terdapat dalam pasal itu sesungguhnya mengandung ketidakjelasan yang bisa berakibat menyulitkan para pemohon untuk mendalilkan, termasuk para hakim konstitusi untuk membuktikan dan mengaitkan pelanggaran yang didalilkan pemohon terhadap ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun kemudian ditentukan dengan bersandar pada pada yurisprudensi Amerika, sebagian hakim MK kemudian memberi tafsir, bahwa untuk memiliki standing to sue, harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut: (1) adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat (i) spesifik atau khusus, dan (ii) actual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial; (2) adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang; (3) kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.93 92 Pasal 51 ayat 2 dan 3 UUMK 93 Maruarar Siahaan, Op.Cit., hal. 80. Sebagaimana mengutip Lujan v. Defenders of Wildlife, 112 S.Ct.2310,2316 (1992). Senada dengan hal ini, lihat Jimly Asshiddiqie, dalam Op.Cit., hal. 67-72. Tradisi Amerika yang menganut paradigma konkret review, sebenarnya dipengaruhi oleh jenis perkara yang diajukan. Perkara yang dimintakan judicial review ke MA (Supreme of Court) Amerika Serikat, oleh hakim Negara Bagian, umumnya adalah perkara-perkara konkret yang sedang disidangkan di pengadilan negara bagian. Dari pendapat tersebut bisa ditarik simpulan, bahwa MK di Indonesia menganut paradigma konkret/aktual review, bukan abstrak/potensial review, sehingga pemohon harus secara terang bisa membuktikan kerugian konstitusional yang dialaminya, bukan sekedar prediksi akan mengalami kerugian konstitusional. Namun demikian, bagaimana permohonan yang diajukan oleh perorangan atau kelompok warga negara yang mempermasalahkan atau hendak menguji keberlakukan sebuah undang-undang dianggap tidak berdasarkan UUD 1945 (uji formiil)? Bagaimana kemudian pemohon harus mendalilkan dan membuktikan adanya causal verband bahwa proses pembentukan suatu undang-undang telah merugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya? Hal ini tentunya tidak mudah dan sulit ditemukan. Karena tindakan menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945 dalam proses pembentukan undangundang, tergolong tindakan legeslatif dengan kekuasaannya yang bersifat negative yang lebih besar potensi kerugiannya dialami oleh anggota atau kelompok minoritas di parlemen. Oleh sebab itu, sebaiknya pengujian secara formil tidak dapat diajukan oleh perseorangan, tetapi bisa diberikan kepada kelompok minoritas diparlemen.94 Fenomena lain, ada kecenderungan mereka yang sedang menjalani proses hukum atau didakwa karena kasus pidana, mengajukan permohonan uji materiil ke MK. Kasus semacam ini terutama ramai pada perkara-perkara korupsi, di mana para terdakwanya berbondong-bondong mengajukan permohonan judicial review UU PTPK. Seolah-olah upaya yang dilakukan oleh mereka, dapat dibenarkan dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak yang harus dipenuhi. Dan MK membuka akses seluas-luasnya, yang tidak tertutup kemungkinan mengabulkan permohonan yang diajukan para terdakwa. Namun tak bisa dipungkiri, kalau kenyataan tersebut memberikan kesan kuat bahwa apa yang dilakukan para terdakwa kasus pidana, seperti memperoleh sebuah upaya hukum yang bisa memberikan ‘amunisi’ baru untuk lolos dari jeratan hukum (impunitas). 94 Ahmad Sjahrizal, Peradilan Konstitusi.., Opcit., hal. 312-313. Yang dapat dibenarkan adalah bukan para terdakwa kasus pidana, tetapi para hakim di pengadilan umum. Alasannya, para hakim-lah yang bisa melihat dan akan menentukan apakah pasal-pasal yang akan digunakan untuk menghukum bertentangan atau melanggar konstitusi atau tidak. Jika hakim merasa ragu, maka dirinya bisa mengajukan permohonan untuk meminta pertimbangan konstitusionalitas kepada MK. Sedangkan para terdakwa, dapat mengajukan permohonan uji materiil jika kasus yang menimpa dirinya sudah diputus oleh pengadilan. Praktek seperti ini yang lazim berlaku di banyak negara yang memiliki MK. Rekomendasi; Meninjau kembali ketentuan mengenai subyek hukum pengujian undang-undang, dengan membatasi hak perorangan dapat mengajukan permohonan pengujian formiil dan membatasi mereka yang sedang menjalani proses hukum kasus pidana mengajukan uji materiil. Sekaligus menegaskan kelompok minoritas di parlemen dan hakim di pengadilan umum dapat menjadi subyek pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. b. Legitimasi dan Akibat Putusan Dalam ketentuan Pasal 58 UUMK dinyatakan bahwa, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945”. Ketentuan ini berarti memposisikan putusan MK berlaku kedepan (prospektif), tidak berlaku surut (retroaktif). Konsekwensi dari putusan prospektif adalah segala peristiwa, perbuatan atau keputusan yang telah terjadi sebelum ketentuan pasal/ayat/undang-undang dibatalkan, selalu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan putusan yang telah dijatuhkan (rechtmatig). Keputusannya hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Suatu hal yang dirasakan dan oleh banyak pihak sulit dipahami adalah putusan prospektif itu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (Rechtvacuum). Landasan hukumnya sudah tidak ada, tetapi secara de facto fakta atau peristiwa hukumnya masih berlangsung. Dalam hal ini, masalahnya organ pembentuk UU tidak cepat tanggap terhadap sifat mengikat dari putusan MK. Bahkan mereka terkesan mengacuhkan kehendak putusan MK. Akibatnya putusan MK memiliki problem di tingkat implementasi. Banyak UU yang sudah dibatalkan kekuatan mengikatnya, kemudian tidak jelas kelanjutannya, sehingga berimplikasi pada tidak adanya aturan hukum yang bisa menjadi pegangan. Pada sisi lain, jamak juga UU yang kekuatan mengikatnya telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku (ex: UU Minyak dan Gas). Melihat perkembangan yang demikian, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum), khususnya bagi perkara-perkara yang krusial, strategi yang ditempuh MK selanjutnya adalah dengan cara mengundurkan periode pembatalan suatu UU. Guna memberikan tenggat waktu bagi organ undang-undang, untuk menyiapkan pengganti UU yang dibatalkan, sehingga tidak terjadi periode kekosongan hukum. Contoh nyata tindakan ini adalah pada perkara uji konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam putusannya secara dejure Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan inkonstitusional, namun MK memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi organ pembentuk UU, untuk menyiapkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara defacto dinyatakan inkonstitusional. Meskipun demikian, organ pembentuk UU pun masih lambat menanggapinya. Pemberlakuan putusan bagi UU selain yang diuji (erga omnes) adalah sebuah bentuk bahwa putusan tersebut dipatuhi oleh berbagai pihak. walaupun tidak dapat diartikan mengikat terhadap ketentuan serupa dalam UU yang berbeda (UU yang tidak diuji) namun dalam hal ketentuan serupa menjadi dasar sengketa di pengadilan mestinya hakim memperhatikan putusan MK. Dalam hal di luar pengadilan mestinya pembentuk UU termasuk Perda segera merubah produk hukum yang bersangkutan untuk disesuaikan dengan putusan MK. Misalnya tentang syarat untuk calon legislatif Pasal 60 huruf g. Dengan demikian perlu diatur agar sifat final dan mengikat putusan MK dirinci tentang tindakan yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara yang lain untuk tidak memberlakukan ketentuan yang sudah dinyatakan tidak mengikat atau segera mereviu produk hukum yang memiliki ketentuan senada. Selama ini putusan MK bisa dikatakan tidak berwatak implementatif, di mana ketika mencapai tahap aplikasi, seringkali putusan MK dihadang oleh sekian banyak rintangan yang menggangu eksekusi putusan tersebut. Oleh karenanya, kiranya perlu suatu strategi kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan MK pada kondisi yang dikehendaki konstitusi. Akan sangat absurd pengimplementasian putusan MK tanpa adanya respon positif dari organ pembentuk undang-undang dan pemerintah berkuasa. Selama ini kerap kali terjadi kesenjangan dan disparitas antara tahap pembacaan dengan implementasi putusan final di lapangan. Jika persoalan ini terus dibiarkan, niscaya putusan MK hanya akan memiliki kekuatan simbolik yang menghiasi lembaran berita negara. Ke depan, organ MK sebaiknya tidak sekedar memiliki kewenangan yang besar dalam hal pengujian konstitusionalitas, melainkan juga harus dibekali kewenangan untuk mengawasi putusannya, artinya putusan final harus disertai dengan judicial order yang diarahkan kepada perorangan atau pun institusi negara. Selanjutnya harus pula diadakan ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final dan mengikat, selain diperkuat dengan adanya kesepakatan kolektif dari lembaga dan aktor negara untuk melakukan tindakan koordinatif dan kolaboratif yang mendukung pelaksanaan/implementasi dari putusan MK. Persoalan besarnya pada dasarnya terdapat pada daya ikat atau keberlakukan putusan MK. Bilamana organ pembentuk undang-undang memiliki kesadaran untuk segara menindaklanjuti atau melakukan eksekusi atas keluarnya suatu putusan MK, yang membatalkan UU tertentu, sebenarnya permasalahan kekosongan hukum tidak akan pernah terjadi. Artinya, yang perlu didorong adalah bagaimana membuat putusan MK memiliki daya eksekutorial yang kuat. Disamping masalah kekosongan hukum, putusan pengujian undang-undang juga dirasakan tidak memberi rasa keadilan secara langsung kepada para pemohon, maupun masyarakat lain yang potensial merasakan keadilan sebagai akibat dari putusan yang dijatuhkan. Hak atas keadilan dari pemohon atau masyarakat yang mendapatkan akibat dari putusan MK, tidak serta merta didapatkan, melainkan harus menunggu atau menempuh suatu proses lain di lembaga lain. Bahkan besar kemungkinan malah diabaikan atau ditolak. Jika hal ini terus berlanjut, bisa jadi MK akan ditinggalkan para pencari keadilan. Kondisi demikian terjadi karena faktor-faktor yang saling berkaitan, antara putusan MK yang berlaku prospektif dengan respon negatif dari aktor dan lembaga negara terhadap putusan MK. Ada baiknya kemudian memberikan kemungkinan untuk pemberlakukan putusan yang dapat berlaku surut (retroaktif), seperti MK di Italia dan Korea, terutama dalam kasus-kasus pidana atau yang mendapatkan perhatian dan berdampak luas kepada masyarakat.95 Namun sebaliknya, dalam beberapa putusan MK telah ‘berijtihad’ dengan membuat kondisi dimana ada Conditionally Constitutional (konstitusional bersyarat). Artinya, ada suatu muatan atau norma yang konstitusional bila dimaknai sesuai dengan yang ditentukan MK berdasarkan penafsiran terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, kondisi tersebut harus ditafsirkan sesuai pertimbangan hukum MK. Apabila sebaliknya, undangundang tersebut tidak tertutup kemungkinan diuji kembali. Setidaknya konstitusional bersyarat terdapat dalam putusan pengujian UU Air, UU PPTKI, UU Pemilu No. 10 tahun 2008 dan UU Perfilman. Putusan yang memberi pertimbangan konstitusional bersyarat ini, jelas ‘menabrak’ ketentuan yang melarang pengujian kembali terhadap terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji (Pasal 60 UUMK). Tetapi disatu sisi, dapat ditafsirkan bahwa konstitusional bersyarat ini membuka ruang keadilan, terutama bagi pemohon, apabila dikemudian hari ditemukan bahwa suatu keadaan yang dianggap merugikan hak konstitusional yang telah diajukan sebelumnya, dapat dimohonkan kembali. Putusan semacam ini, dapat dianggap merupakan bagian dari asas kebebasan hakim untuk menentukan pilihan demi mencapai kebenaran materiil berdasarkan konstitusi. c. Memberikan Putusan ‘Provisi’ Selama ini MK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara yang dapat meminta kepada para pihak untuk tidak mengeluarkan keputusan hingga keluarnya putusan MK. Putusan sela (provisi) memang hanya ditentukan pada perkara SKLN, tidak dikenal pada perkara lain.96 Dalam perkara pengujian UU, MK sekedar memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pemberitahuan kepada MA, bahwa MK sedang sedang melakukan pengujian suatu UU. Hal ini sebagai antisipasi jikalau UU 95 Lihat dalam Allan R Brewer, Judicial Review in Comparative Law, Newyork-Cambridge University Press, 1989, hal. 224. Juga Ahmad Sjahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hal. 243244. 96 Pasal 63 UUMK menentukan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi” yang sedang diuji oleh MK, tengah menjadi sandaran hukum dalam penanganan suatu perkara oleh MA atau peradilan di bawahnya. Persoalan lain kemudian muncul, seperti pada kasus pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam kasus tersebut ketentuan dalam UU a quo yang menjadi sandaran KPU untuk mengeluarkan keputusan tentang siapa yang berhak menjadi peserta pemilu 2009, justru dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh MK. Meskipun putusan MK berlaku propektus, toh kemudian muncul gugatan dari parpolparpol yang tidak lolos verifikasi, yang kemudian berimbas pada bertambahnya jumlah parpol peserta pemilu. Peristiwa ini tentunya menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, dalam hal dengan tidak selarasnya agenda atau jadwal pemerintahan yang harus berjalan. Disisi lain, besar kemungkinan pemerintah atau siapapun pihak terkait yang akan terkena dampak dari perkara yang diuji MK, akan menyiasati kondisi maupun ketentuan yang ada untuk kepantingannya. Hal semacam ini tentunya dapat dianggap tidak etis, mengingat perkara yang sedang berjalan di MK berpotensi mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan dibuat dan dikeluarkannya. Kemungkinan seperti ini pernah disorot oleh Frans Limahelu, dalam memberikan kesaksian di MK pada perkara pengujian UU Pemda. Dikatakan bahwa, ketika suatu undang-undang sedang dibahas di sidang pengadilan maka berarti semua kegiatan tentang pembuatan undang-undang harus berhenti.97 Rekomendasi : Memberikan kewenangan bagi MK untuk bisa mengeluarkan penetapan bagi pihak terkait untuk tidak membuat atau mengeluarkan keputusan/kebijakan atau peraturan yang bersifat penting dan strategis terkait dengan perkara yang sedang diuji. d. Boleh Tidaknya Ultra Petita Dalam beberapa putusan pengujian undang-undang, MK telah bertindak ultra petita atau memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon. Misalnya, putusan tentang 97 Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004, hal. 90. judicial review UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 30 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan judicial review UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta putusan judicial review UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Pada putusan pengujian UU PTPK, MK mengambil langkah ultra petita, dengan membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang mempersempit ruang lingkup ajaran sifat melawan hukum. Sedangkan pemohon pada waktu itu hanya sekedar memohonkan pembatalan beberapa frasa dari UU PTPK, tidak keseluruhan kalimat. Pada putusan pengujian UU KY, MK membatalkan kewenangan KY untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, padahal pemohon hanya memintakan pembatalan kewenangan KY untuk mengawasi hakim agung. Fungsi substansial KY menjadi terhapuskan, KY sekedar memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi hakim agung, dan pengawasan hakim pada lingkungan peradilan umum, di bawah MA. Sedangkan pada putusan pengujian UU KKR, MK memotong jantung UU KKR, sehingga tamatlah riwayat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Terhadap ketiga putusan tersebut MK beralasan, bahwa materi yang dilakukan pengujian adalah materi inti (organ vital) undang-undang, yang berakibat pada batalnya materi-materi lain, sebagai implikasi batalnya organ vital tersebut. Sebagian pakar kemudian berpendapat, bahwa secara tidak langsung, MK sebagai negative legislature telah mengambil peran DPR sebagai positif legislature, karena MK membuat putusan yang sifatnya mengatur (regeling), melalui putusan yang sifatnya ultra petita. Padahal fungsi MK adalah untuk menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD, bukan membatalkan UU yang pengaturannya dinyatakan terbuka oleh UUD, dan menjadi kewenangan DPR untuk menafsirkannya.98 Pada dasarnya ultra petita hanya dilarang dalam ranah peradilan perdata, sebab mereka yang bersengketa adalah individu melawan individu, sehingga jika diperbolehkan ultra petita dikhawatirkan akan menguntungkan sekaligus merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Lagipula dalam mekanisme sengketa perdata, diperkenankan adanya tahapan banding yang dapat melawan kembali putusan yang telah dijatuhkan pengadilan dibahwanya. Berbeda dengan MK yang perkaranya menyangkut kepentingan umum, tidak hanya terkait kepentingan para pemohon secara an sich. Para hakim 98 Moh. Mahfud MD, Mendudukkan Soal Ultra Petita, KOMPAS, Senin, 5 Februari 2007. Lihat juga Moh. Mahfud MD, Kontroversi Vonis Ultra Petita, Seputar Indonesia, Selasa, 30 Januari 2007. konstitusi dapat secara ’leluasa’ memberikan penafsiran yang dibutuhkan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, dengan karakteristik sikap aktifnya hakim konstitusi memang dapat melakukan memutus diluar permohonan (ultra petita). Meski demikian, hakim tidak boleh memutus tentang hal-hal yang berada di luar batas permasalahan dan isi dari kebijakan (undang-undang) yang dimohonkan. Hakim hanya dapat memeriksa dan memutus tentang hal-hal yang langsung terkait dengan permasalahan pokok yang digugat, meskipun hal tersebut tidak dimohonkan oleh pemohon untuk diputus. Dari ultra petita itu, dapat pula menjurus kepada adanya ”reformatio in peius”, dimana putusan yang nantinya dikeluarkan bisa jadi merugikan atau mengurangi kepentingan hukum penggugat/pemohon. Artinya, putusan yang dikeluarkan akan membawa situasi yang lebih merugikan baginya daripada keadaan sebelum perkara diajukan.99 Oleh karenanya, ultra petita seharusnya tidak dilarang dalam ranah peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi). Jika ultra petita dilarang, MK akan menjadi sangat positivis dan legalistik, yang akan merugikan kepentingan banyak pihak, sebab hanya mengabulkan permohonan yang diajukan para pemohon saja. Tugas MK adalah menguji norma-norma yang sifatnya umum, bukan sengketa antara individu yang satu dengan lainnya, dan bukan perkara yang sifatnya legalistik saja, melainkan norma konstitusi. Karenanya ultra petita dibutuhkan untuk menjaga tetap berdirinya norma-norma umum/konstitusi, dan tidak dilanggaranya kepentingan umum. Dan yang paling mendasar adalah, larangan terhadap ultra petita akan menabrak prinsip independensi hakim yang sudah ditegaskan dalam konstitusi. Putusan merupakan ranah independensi hakim yang patut dijaga dan dijunjung tinggi, dan tidak boleh diintervensi. Dengan kata lain, larangan ultra petita akan bertentangan dengan konstitusi yang berpotensi diajukan pengujiannya ke MK. B.2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara a. Memastikan Lembaga Negara. Dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUMK dikatakan, “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung 99 Lihat Suparto Wijoyo, Opcit., hal. 73 terhadap kewenangan yang dipersengketakan”. Dari ketentuan ini ada dua hal pokok yang harus dipastikan lebih lanjut, yaitu pemohon adalah lembaga negara dan adanya kepentingan langsung yang dipersengketakan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, terdapat beragam penafsiran untuk menentukan siapa yang bisa dikualifikasikan sebagai negara, termasuk dikalangan hakim konstitusi (lihat pembahasan mengenai kewenangan dalam sengketa lembaga negara). Namun demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) telah menentukan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah;100 a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) f. Pemerintah Daerah g. Lembaga Negara Lain Yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Masalahnya, PMK malah membuka ruang penafsiran lain yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam point g, apa yang dimaksud dengan, lembaga negara lain yang kewenangannhya diberikan oleh UUD 1945? Jika ada lembaga negara lain dalam UUD 1945, mengapa lembaga negara tersebut tidak disebutkan pula dalam ketentuan PMK?. Disamping itu, apa yang ditentukan dalam pasal 2 PMK No. 08/PMK/2006 sudah merupakan materi undang-undang yang tidak tepat jika hanya diatur/ditentukan dalam PMK. 100 Pasal 2 No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Rekomendasi : 1. Ketentuan dalam PMK yang menyebutkan secara rinci tentang lembaga negara yang dapat menjadi pihak pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara, sebaiknya ditempatkan kedalam materi undang-undang. 2. Perlu diperjelas dan dipertegas lebih lanjut, siapa lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD. b. Kedudukan MA Sebagai Pihak Pasal 65 UUMK melarang bahwa Mahkamah Agung (MA) menjadi pihak dalam perkara SKLN. Tidak begitu jelas alasan pembentuk undang-undang, mengapa terdapat ketentuan yang melarang MA menjadi pihak dalam perkara SKLN. Padahal dari segi teoritik, MA merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan atau diatur dalam UUD 1945. Dan pada kenyataannya, konflik atau sengketa antara MA dengan lembaga negara lain pernah terjadi. Misalnya, sengketa MA dengan Komisi Yudisial (KY) mengenai obyek dan cara pemeriksaan hakim agung yang diduga melakukan penyimpangan. Juga sengketa yang belum lama terjadi antara MA dengan BPK mengenai biaya perkara. Terhadap ketentuan larangan tersebut, MK memberikan penafsiran bahwa MA tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan yang bersifat teknis peradilan (yudisial).101 Jika menyangkut perkara non teknis yudisial, maka dimungkinkan MA menjadi pihak dalam perkara SKLN. Alasan tersebut sebenarnya tidaklah logis, sebab yang menjadi objek sengketa bukanlah putusan MA, melainkan kewenangan konstitusonal yang dimiliki MA. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika MA dapat menjadi pihak dalam perkara SKLN, karena sangat dimungkinkan MA akan berselisih kewenangan dengan lembaga negara lainnya. Rekomendasi : Sebaiknya pasal ini dihapus atau ditiadakan. 101 Pasal 2 ayat (3) PMK No. 08/PMK/2006 B.3. Perselisihan Hasil Pemilu a. Melengkapi Para Pihak Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan proses politik selama 4 tahun terakhir telah mengubah saluran demokrasi yang berpengaruh terhadap adanya perubahan hukum mengenai pemilu. Perubahan tersebut juga sebagai akibat dari putusan MK, yang telah memberikan kesempatan masuknya calon dari luar partai politik (independen) untuk ikut dalam bursa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Untuk yang terakhir ini, perubahan tersebut telah diakomodasi dalam revisi UU Pemerintah Daerah yang telah disahkan beberapa waktu lalu (lihat pembahasan masalah kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu). Disamping itu, dinamika perpolitikan menjelang pemilu 2009 juga diperkirakan akan mempengaruhi kompleksitas dan kerumitan masalah dalam sengketa pemilu. Selain partai politik yang bertarung pada pemilu 2009 lebih banyak (48 partai), juga karena sistem yang diberlakukan adalah parlementary treshold dimana partai politik yang tidak memperoleh prosentase yang telah ditentukan, akan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya. Jadi, ini berarti hidup dan matinya partai politik. Adanya partai politik yang menerapkan suara terbanyak dalam pemilu legeslatif, juga berpotensi memunculkan masalah konflik internal. Dalam hal ini, tidak hanya antara partai dengan KPU, tetapi juga partai dengan caleg-calegnya. Melihat perkembangan dan perubahan tersebut, tentu saja ketentuan Pasal 74 UUMK dipandang sudah tidak relevan lagi. Dalam pasal tersebut ditentukan, subyek pemohon terdiri atas; a) perorangan calon anggota DPD; b) pasangan calon presiden dan wakil presiden; c) partai politik. Sementara sejalan dengan realitas perkembangan yang ada sekarang, subyek pemohon tidak lagi terdiri atas 3 pihak tetapi telah bertambah. Sebagai tambahan dari 3 unsur yang sudah ditentukan undang-undang, lainnya adalah; calon perseorangan dalam pemilu pilkada, calon legeslatif /anggota partai peserta pemilu legeslatif. 30 b. Putusan Final vs Penetapan KPU Perselisihan hasil pemilu yang dapat diajukan ke MK sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 74 ayat (2) UUMK, merupakan permohonan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU secara nasional. Penetapan hasil tersebut berpengaruh terhadap terpilihnya calong anggota DPD, penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran kedua serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden, dan perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan. 1) Berdasarkan data dan catatan hasil pemilu 2004, sebagai hasil dari proses di MK, yang di dalamnya ada 4 gugatan partai yang dimenangkan berkenaan dengan perolehan kursi DPR, ada 4 kursi yang beralih dari satu partai ke partai lainnya. 1) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, satu kursi yang menurut penetapan KPU sebelumnya dimenangkan oleh Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), melalui putusan MK dialihkan menjadi milik Partasi Bintang Reformasi (PBR) 2) di daerah pemilihan Irian Jaya Barat, Partai Damai Sejahtera (PDS) mendapatkan satu kursi yang semula ditetapkan oleh KPU untuk Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (Partai PDK). 3) MK memberikan kemenangan kepada Partai Pelopor yang mendapatkan satu kursi di daerah pemilihan Papua yang sebelumnya ditetapkan KPU untuk Partai Golkar. 4) di Sulawesi Tengah, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan kursi DPR dari Partai Demokrat setelah memenangkan gugatan di MK. Perubahan kursi DPD dari hasil Keputusan MK tidak sebanyak yang terjadi untuk kursi DPR. Hanya satu kursi yang bergeser di sini, yaitu untuk Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya ditetapkan bahwa calon yang menempati peringkat ke-4 dalam perolehan suara adalah Dahlan Rais, dengan keputusan MK dialihkan kepada KH Ahmad Helwani (yang sebelumnya menempati peringkat 5 dalam perolehan suara). Di Provinsi Sumatera Selatan juga ada kasus, namun akhirnya MK mengukuhkan perolehan kursi calon anggota DPD terpilih Ruslan Nurjaya. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh calon dengan perolehan suara ke-5 terbesar dikalahkan. Dengan 31 kata lain tidak ada perubahan terhadap penetapan yang dibuat oleh KPU untk provinsi tersebut102. Sebelumnya, KPU meminta fatwa MK yang berharap agar keputusan MK mengenai sengketa kursi DPR dari Irian Jaya Barat dan Sulawesi Tengah bisa tidak dieksekusi. Alasannya, data-data yang digunakan MK itu terbukti hasil manipulasi saat penghitungan suara. Di Provinsi Irian Jaya Barat, kursi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan beralih menjadi milik Partai Damai Sejahtera melalui keputusan sidang MK. Begitu pula Partai Amanat Nasional memperoleh tambahan satu kursi dari yang seharusnya milik Partai Demokrat. Tapi kemudian, Pengadilan Neger di Sorong dan Donggala memenangkan gugatan Partai PDK dan Partai Demokrat. Keputusan dua pengadilan negeri yang berbeda dengan keputusan MK ini menyebabkan kesulitan KPU untuk menetapkan dua kursi itu. Selanjutnya seusai hasil konsultasi dengan Ketua MK pada tanggal 12 Januari 2006 lalu, dapat ditarik kesimpulan, yakni, pertama, putusan MK atas sengketa Irjabar Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) dan antara Partai Pelopor dengan Partai Golkar, sudah bersifat final," paparnya. Ia mengatakan, keputusan Pengadilan Negeri (PN) Sorong dan PN Wamena atas pemalsuan hasil rekapitulasi Pemilu adalah murni kasus pidana dan bukan kasus perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan UU tentang MK, maka putusan perkara pidana itu tidak bisa dijadikan untuk mengenyampingkan putusan MK. B.4. Pembubaran Partai Politik a. Syarat/Alasan Pembubaran Dalam UUMK, Pasal 68 mengisyaratkan bahwa syarat pembubaran partai politik berkait dengan ideology partai, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai. Tetapi tidak jelaskan ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan seperti apa yang dapat menjadi alasan bagi pembubaran partai politik. Pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di bagian Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik, pun tidak 102 KPU Online, 30 Juli 2004 32 terdapat pengaturan mengenai syarat atau alasan pembubaran partai politik. Perihal syarat pembubaran justru diatur dibagian larangan, dan tentang posisi MK dimunculkan pada bagian sanksi. Dalam UU Partai Politik ditegaskan bahwa Parpol dilarang:103 (2) Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Partai Politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Dari sekian larangan yang berakhir dengan sanksi pembekuan/pembubaran, hanya larangan pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) saja yang merupakan wenang dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembubaran.104 b. Tata Cara dan Siapa yang Harus Membubarkan Pasal 24C UUD 1945, salah satunya memberi wenang kepada MK untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UUMK, sedangkan mengenai proses beracaranya diatur dalam Pasal 6873 UUMK. Dari serangkaian aturan tersebut menjadi terang, bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembubaran partai politik adalah MK. Kendati demikian bubarnya partai politik tidak hanya sebagai akibat keluarnya putusan MK. Dalam UU 103 Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 104 Pasal 48 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 33 Partai Politik No. 2 Tahun 2008, diatur bahwa bubarnya partai politik bisa dikarenakan membubarkan diri atas keputusan sendiri; menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemberian wewenang pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai upaya menjamin dan menegakkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sebab jika kewenangan pembubaran partai politik ada di tangan pemerintah berkuasa, maka yang akan terjadi ialah perilku persaingan dan saling jegal antara partai berkuasa (pemerintah) dengan partai oposisi. Akan sangat bias tentunya jikalau kewenangan pembubaran parpol berada di tangan pemerintah. Meskipun demikian, yang berhak menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, hanyalah pemerintah berkuasa.105 Tidak ada pihak lain di luar pemerintah yang memiliki legal standing untuk menjadi pihak/pemohon dalam perkara tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar tidak ada upaya saling jegal antara partai satu dengan partai lain, dalam berkontestasi. Secara umum pengaturan mengenai pembubaran partai politik, termasuk hukum acaranya, masih sangat minim diatur dalam UUMK. Hingga saat ini pun belum terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai pedoman beracara pada perkara pembubaran partai politik. Selain prosedur beracara, UU juga belum mengatur mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi dasar/alasan MK untuk menjatuhkan putusan pembubaran parpol,106 hal ini penting untuk memudahkan MK dalam penyusunan pedoman beracara perkara pembubaran partai poltik. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara partai berkuasa (pemerintah) dengan partai opisisi. Sebab jika perkara pembubaran partai politik memiliki nuansa politis yang kental sekali, sehingga UU perlu mengaturnya secara tegas dan terperinci. B.5. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam system politik presidensil, pemakzulan terhadap presiden adalah sebuah upaya yang luar biasa sulit. Mengingat kuatnya posisi presiden, yang dipilih secara langsung 105 Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi. 106 Meskipun hal ini telah diatur secara tersebar dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008, namun sebaikanya hal ini diatur pula dalam UUMK, mengingat sering terjadinya pergantian UU Partai Politik di negeri ini, setiap kali menghadapi penyelenggaraan pemilu. 34 oleh rakyat, bukan melalui mekanisme parlemen. Apalagi jika partai pemerintah adalah partai mayoritas di parlemen (DPR). Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan, bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat dihentikan pada masa jabatanyya, jika terbukti telah melakaukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres. Ketentuan UUD tersebut selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 10 ayat (3) UUMK. Terkait dengan hukum acaranya, pun sebenarnya sudah cukup jelas mengatur, tinggal diimplementasikan ke dalam PMK yang mengatur pedoman beracara pada perkara impeachment presiden. Pada dasarnya yang perlu ditegaskan lagi ialah menyangkut objek sengketa dan para pihak yang bersengkata. Perkara impeachment adalah perkara yang penuh dengan nuansa politiknya. Selain pertimbangan yang dikemukanan oleh Pasal 7A UUD, bisa saja kemudian pertimbangan DPR hanya atas dasar rasa suka atau tidak suka (like or dislike) kepada presiden. Artinya, fakta dan pertimbangan yang diberikan adalah tolok ukur yang sifatnya politis, sehingga keberadaan MK menjadi penting. Objek perkara yang menjadi kewenangan MK adalah fakta yuridis atas temuan-temuan yang diungkap oleh DPR, untuk mengukur apakah benar presiden dan/atau wapres telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, atau tidak layak lagi menjabat sebagai presiden dan/atau wapres. MK tidak memiliki wenang untuk memutus apakah presiden dan/atau wapres bersalah, melainkan hanya memutus apakah temuan-temuan yang diajukan DPR benar atau keliru menurut hukum. Penghakiman politis selanjutnya menjadi wewenang dari MPR, untuk menyatakan presiden bersalah dan tidak bersalah, harus berhenti atau melanjutkan jabatannya. Dalam perkara impeachment, yang dapat menjadi pemohon hanyalah DPR, sedangkan kedudukan termohon secara eksplisit tidak ada, sebab meskipun dalam persidangan dihadirkan Presiden dan/atau Wapres, kapasitasnya bukanlah sebagai pihak, melainkan sebagi saksi, untuk memberi keterangan atas temuan-temuan yang dikemukakan DPR. Berkait isu apakah putusan MK berakibat pada terjadinya nebis in idem, bilamana dari temuan yang diungkap DPR, terbukti telah terjadi pelanggaran pidana? Tidak tentunya, sebab objek perkara di MK berbeda dengan objek perkara jikalau kasusnya kemudian dibawa ke paradilan umum. MK memeriksa dan memutus temuan DPR atas dugaan 35 presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran pidana, sedangkan umum objek perkaranya berakit dengan kasus pelanggaran pidananya. Pengaturan mengenai Impeachment dapat dilakukan dengan PMK sepanjang mengenai prosedur pemeriksaan. Namun demikian memang perlu dipikirkan secara cermat karena pemohon adalah DPR. Sementara pihak yang didakwa melanggar hukum adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jabatan termohon mesti ditempatkan sesuai dengan kehormatan yang disandangnya. Apakah termohon dapat diperlakukan sebagai pesakitan, seperti di pengadilan biasa, tentu saja tidak. Apakah mungkin pemeriksaan permohonan dibatasi hanya memeriksa berkas yang diajukan DPR atau pemeriksaan keabsahan dakwaan berikut bukti-buktinya. Apakah putusan MK mengikat dan berlaku asas nebis in idem (tidak boleh lagi diperiksa oleh pengadilan lain meskipun terbukti melakukan tidak pidana?). 36 DAFTAR PUSTAKA Buku Ahsin, A. Tohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Elsam, 2004. Cappelletti, Mauro., The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford Universyty Press, 1989. Arifin, Firmansyah, dkk (penyusun), KRHN, Hukum Dan Kuasa Konstitusi, KRHN, 2004. ------------------------, Pokok-Pokok Pikiran RUU Mahkamah Konstitusi, KRHN-Kemitraan, 2003. -----------------------, Lembaga Negara & Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara, KRHN-MKRI, 2005. Asshiddiqie, Jimly , Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, 2006 Asshiddiqie, Jimly & Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006. Farida, Maria Indarati S, Ilmu Perundang-Undangan (2); Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta-Kanisius, 2007. Ginsburg, Tom., Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University Press, 2003. Harjono., Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 461-462. Vol. 3 Nomor 3, 2006 Indrayana, Denny., Negara Antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, 2008. Indrayana, Denny., dkk, Laporan Penelitian “Analisis Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Pada Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) Dan Peradilan Tata Usaha Negara”, FH-UGM, Yogyakarta, Juni 2007, hal. 142-143. --------------. Empat Tahun Mengemban Amanat Konstitusi 2003-2007, Mahkamah Konstitusi, 2007. --------------, Cetak Biru MKRI, Membangun MK Sebagai Institusi Peradilan Yang Modern Dan Terpercaya, MKRI, 2005 --------------, Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005. --------------, Lihat dalam transkip “Expert Meeting Revisi UU Mahkamah Konstitusi”, diselenggarakan oleh KRHN-DRSP di Hotel Millenium, Jakarta, 27-28 Agustus 2007. Mahfud, Moch MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta-LP3ES & UII Press, 1998. Natabaya, HAS Natabaya, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008, hal. 215. R. Brewer, Allan Carias, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University, 1989. Maruarar Siahaan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Konstitusi Press, 2005. Syahrizal, Ahmad., Peradilan Konstitusi; Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta-Pradnya Paramita, 2006. Wijoyo, Suparto “Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi”, Surabaya-Airlangga University Press, 1997. 37 Makalah Atmadja, I Dewa Gde, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, DImensi Konstitusionalisme, Makalah Expert Meeting, KRHN – DRSP, 2007. Harun, Refly., Pokok-Pokok Pikiran Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Makalah Expert Meeting, KRHN – DRSP, 2007. Marwan, Mas., Memaknai Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Makalah Expert Meeting, KRHN – DRSP, 2007. Rifai, Amzulian, Struktur Kelembagaan Mahkamah Konstitusi, Makalah Expert Meeting, KRHN – DRSP, 2007. Ulrike, Ms. Justice Mullerm (Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman), “The Federal Constitutional Court of Germany- Competencies and Impact of the Courts Jurisdiction, 2002. Zanibar, Zein., Mengapa UU MK Perlu Diubah?, Makalah Expert Meeting, KRHN – DRSP, 2007. Peraturan/Putusan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Pengujian UndangUndang. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan di Mahkamah Agung The Constitution of Thailand The Constitution of Republic Philipina Federal Constitutional Law of the Russian Constitutional Court International BAR Association Code of Minimum Standarts of Judicial Independence 38 39