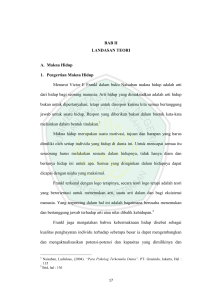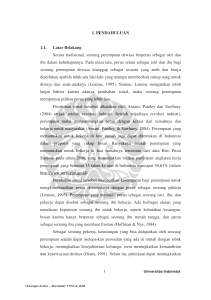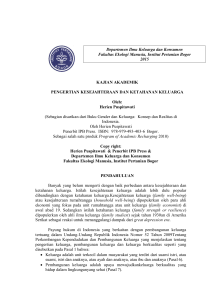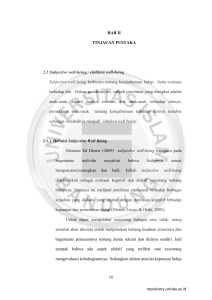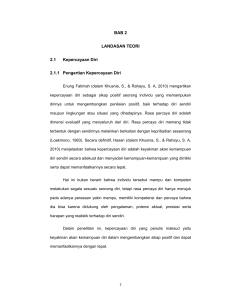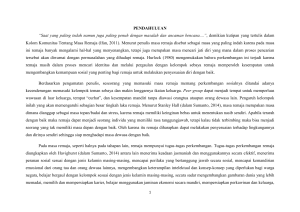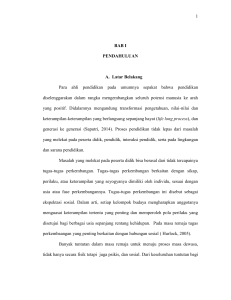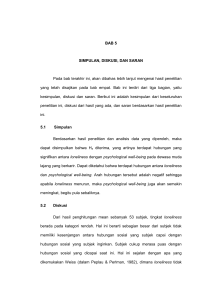School Connectedness dan Dukungan Sosial Teman Sebaya
advertisement

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Subjective well-being (SWB) merupakan konsep yang luas akan kehidupan seseorang secara keseluruhan. Ada aspek-aspek serta faktor-faktor yang menjadi prediktor bagi subjective well-being seseorang, khususnya di kalangan siswa. Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai SWB dan teori-teori yang mendasari perkembangan SWB itu sendiri, serta bagaimana hubungan SWB dengan faktor school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya yang menjadi prediktornya. 2.1. SUBJECTIVE WELL-BEING 2.1.1. Definisi Subjective Well-Being Sepanjang sejarah, filsuf yang berbeda-beda telah memberikan perhatian yang bervariasi pada definisi subjektif mengenai hidup yang baik. Beberapa berpendapat bahwa hidup yang paling diinginkan (desirable) bisa didefinisikan melalui karakteristik-karakteristik seperti virtue (kebaikan/kebajikan), dan hal-hal lainnya yang menunjukkan perasaan menyenangkan sebagai esensi dari hidup yang baik (Diener, 2009). Walaupun banyak peneliti kadang-kadang mendiskusikan kebahagiaan dan well-being seolah-olah direfleksikan sebagai satu konstruk, namun sebenarnya tidak ada satupun penilaian atau pendapat (single judgement) yang bisa mencakup keseluruhan subjective well-being (Diener & Ryan, 2008). Menurut Veenhoven (1991) SWB secara keseluruhan bisa dipahami dalam ungkapan kepuasan hidup, kesenangan/kepuasan hati dan level kesenangan, sementara aspek yang berbeda-beda dari SWB meliputi penilaian diri seperti kepuasan atas pekerjaan, harga diri, dan kontrol kepercayaan. Kepuasan hidup merupakan level di mana individu menilai kualitas hidupnya secara menyeluruh sebagai kesatuan yang menyenangkan. SWB didefinisikan sebagai evaluasi individu terhadap kehidupan, yang dijelaskan dalam terminologi mengenai bagaimana dan mengapa individu mengalami kehidupan dalam cara yang positif, sehingga pengalaman pribadi mereka berkaitan dengan kualitas hidup yang dirasakan (Diener & Diener; Diener, Biswas-Diener & Tamir, dalam Yang dkk., 2008). Keyes dan Waterman (2003) mereview literatur dengan judul, “A brief history of the study of well-being in children and adults” (Sejarah singkat studi well-being pada anak dan orang dewasa) dan menyimpulkan bahwa individu mengevaluasi dirinya dalam ungkapan apakah mereka merasa baik atau senang dengan dirinya dan apakah dirinya berfungsi dengan baik secara pribadi dan secara sosial. Para ahli juga telah menganalisis bahwa evaluasi mengenai kehidupan individu ini berlangsung dalam periode saat ini dan periode lampau (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Evaluasi ini meliputi reaksi emosi individu atas suatu peristiwa, suasana hati mereka, dan bentuk penilaian mereka mengenai kepuasan dalam hidup, pemenuhan kebutuhan, dan kepuasan dalam domain tertentu, seperti dalam pernikahan dan pekerjaan. SWB merupakan istilah besar yang digunakan untuk menggambarkan level well-being yang dialami individu menurut evaluasi subyektif mereka atas hidup mereka sendiri. Seperti telah disebutkan di atas, evaluasi ini bisa berupa positif atau negatif, termasuk penilaian dan perasaan mengenai kepuasan hidup, minat dan keterikatan, reaksi-reaksi afektif seperti gembira dan sedih atas peristiwa hidup, kepuasan dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, hiburan, makna dan tujuan, dan bidang-bidang penting lainnya (Diener & Ryan, 2008). SWB juga didefinisikan sebagai kecenderungan global untuk mengalami hidup dalam cara yang menyenangkan (Quevedo & Abella, 2011). Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa SWB merupakan evaluasi subjektif individu yang meliputi tingginya kepuasan hidup, pengalaman akan emosi yang menyenangkan (positive affect) dan level rendah dari emosi yang negatif (negative affect). 2.1.2. Teori-teori Subjective Well-Being Ada banyak pandangan teoritis mengenai bagaimana well-being diuji, yang berasal dari perspektif biologi yang menaruh perhatian pada predisposisi genetik dari kebahagiaan, sampai pada teori standar relatif, yang menguji bagaimana membandingkan pengaruh seseorang terhadap orang lain dalam merasakan SWB. Berikut adalah gambaran singkat mengenai beberapa teori SWB seperti yang dijelaskan oleh Diener & Ryan (2008). 1) Teori Telic Teori Telic mengenai SWB menyatakan bahwa individu mencapai kebahagiaan ketika titik akhir, seperti tujuan (goal) atau kebutuhan (need) dicapai. Inti dari teori ini adalah apa saja titik akhirnya. sebagai contoh, filsuf dulu sering mempertanyakan, apakah “pemenuhan akan kebutuhan” atau “keinginan” membawa pada well-being atau apakah keinginan-keinginan tersebut malah merusak atau mengganggu wellbeing. Selain itu, apakah lebih baik memenuhi keinginan jangka pendek dan mengorbankan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang? Dan juga bagaimana jika terjadi konflik antara keinginan individu yang satu dengan keinginan yang lain? Pertanyaan lain yang juga muncul adalah, apakah melangkah melebihi “yang diinginkan” lebih memberikan pemenuhan daripada mencapai objek keinginan itu sendiri atau tidak? Teori kebutuhan (need theory) seperti konsep psikologi well-being dari Ryff dan Singer (dalam Diener & Ryan, 2008) dan teori determinasi diri (self-determination) dari Ryan dan Deci (dalam Diener dan Ryan, 2008) menemukan bahwa ada kebutuhan tertentu yang ada sejak lahir, yang dicari individu untuk dipenuhi dalam rangka mencapai well-being. Sehubungan dengan ini, teori tujuan menunjukkan bahwa individu yang secara sadar mencari tujuan tertentu, akan menghasilkan well-being yang tinggi ketika tujuan itu terpenuhi. Akan tetapi, dalam teori tujuan, tujuantujuan bisa muncul dari sumber-sumber tambahan selain kebutuhan yang didapatkan sejak lahir. 2) Teori Top-Down Versus Bottom-Up Debat mengenai teori well-being “top-down” dan “bottom-up” merupakan hal yang penting dalam bidang ini. Teori “bottom-up” menyatakan bahwa saat-saat atau peristiwa-peristiwa dalam hidup seseorang ditambahkan dalam rangka menghasilkan perasaan subjective well-being individu. Dalam pandangan ini, saat atau peristiwa bahagia atau positif akan membuat individu mengalami well-being, dan semakin positif saat yang dialami individu, maka semakin meningkat level wellbeing. Sebaliknya teori “top-down” menyatakan bahwa kecenderungan yang melekat pada individu dalam merasakan dan mengalami peristiwa dunia dalam cara tertentu akan memengaruhi interaksi individu dengan dunia. Oleh karena itu, menurut teori “top-down”, individu dengan keadaan pikiran yang positif mengalami atau menginterpretasi peristiwaperistiwa tertentu sebagai “lebih bahagia” daripada individu dengan perspektif negatif, hal ini membuat faktor positif sebagai salah satu faktor penentu sujective well-being. Dalam pendekatan top-down, fitur-fitur global dari kepribadian diperkirakan memberi pengaruh pada cara seseorang beraksi terhadap suatu kejadian. Contohnya, orang dengan temperamen sanguinis mungkin mengniterpretasikan sejumlah peristiwa sebagai hal yang positif. Dalam pendekatan bottom-up, seseorang harus mengembangkan disposisi yang jelas dan penampilan sanguinis sebagai pengalaman positif yang diakumulasikan dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, para penganut hedonis mengemukakan bahwa seseorang bisa disebut berbahagia jika peristiwa-peristiwa yang menyenangkan benarbenar dipilih dan terus diakumulasikan. Sehingga akumulasi dari setiap peristiwa tertentu yang menyenangkan itu akan terus membuat orang merasa bahagia. Ada dua perdebatan umum mengenai subjective well-being yang berkaitan dengan dua teori yang memiliki pandangan berbeda ini, yang pertama memerhatikan apakah well-being didefinisikan sebagai sifat (trait) dan yang melihat well-being sebagai keadaan atau peristiwa. Teori yang memerhatikan well-being sebagai sifat menunjukkan bahwa level well-being yang tinggi merupakan kecenderungan untuk bereaksi secara positif daripada sekadar perasaan bahagia, yang lainnya berpendapat bahwa well-being merupakan keadaan yang disebabkan oleh sejumlah saat-saat bahagia (happy moments). Perdebatan yang kedua memberikan perhatian pada peran “peristiwa-peristiwa menyenangkan” dalam menciptakan well-being. Contohnya, apakah kurangnya peristiwa-peristiwa menyenangkan dalam hidup membawa pada depresi, ataukah depresi yang membawa pada kegagalan untuk merasa senang ketika terlibat secara normal dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan? Argumen dasar bagi pendekatan bottom-up adalah bahwa pemenuhan kebutuhan tertentu akan meningkatkan kepuasan pada domain tertentu dan memberikan dampak pada kepuasan hidup secara keseluruhan. Teori bottom-up mengungkapkan bahwa kepuasan hidup merupakan jumlah keseluruhan dari kepuasan dan perasaan positif dalam domain-domain tertentu (Schimmack, dkk. 2002; Campbell dkk.; Diener; Andrews dan Whitney dalam Voicu dan Pop, 2011). Merasa puas dan bahagia dengan hubungan sosial, hubungan rumah tangga, kesehatan, atau keluarga, bisa menjadi penentu kepuasan hidup secara keseluruhan (Voicu dan Pop, 2011). Selain itu, ditambahkan pula bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan standar kriteria individu yang bersangkutan. Dilain pihak, pendekatan top-down memandang bahwa kepuasan hidup semata-mata disebabkan oleh kestabilan faktor kepribadian. Namun demikian menurut Diener (2008), keduastruktur teori ini yang membentuk SWB sebagai satu variabel yang utuh. 3) Teori Kognitif Sama seperti pendekatan “top down”, teori kognitif dari well-being fokus pada kekuatan proses kognitif dalam menentukan well-being individu. Model AIM dari well-being – Attention, Interpretation, Memory (atensi, interpretasi dan memori) menunjukkan bahwa individu dengan subjective well-being yang tinggi cenderung memfokuskan perhatian mereka pada stimulus positif, menginterpretasi peristiwa secara positif, dan mengingat kembali peristiwa-peristiwa lampau dengan bias kenangan positif. Dalam terminologi atensi, partisipan yang mampu untuk lebih fokus pada stimulus positif dibandingkan yang negatif cenderung untuk bertaruh dengan lebih baik dalam semua level wellbeing. Lebih penting lagi, abilitas untuk mengarahkan atensi keluar dari diri sendiri merupakan prediktor yang signifikan bagi well-being. Studi menunjukkan bahwa walaupun kebanyakan orang yang sering merenung cenderung untuk lebih khawatir dan mengalami subjective well-being yang lebih rendah pada umumnya, namun mengarahkan atensi pada diri sendiri bisa menyebabkan orang yang secara normal mengalami wellbeing yang tinggi mengalami well-being yang lebih rendah secara signifikan. Lebih jauh lagi, orang dengan subjective well-being yang tinggi secara natural menginterpretasi peristiwa-peristiwa netral dan ambigu dalam cara yang positif. Dengan demikian, interpretasi positif bertindak sebagai penahan pelindung atau tenaga pelindung (protective buffer). Akhirnya, ketika orang yang bahagia secara disposisi telah menunjukkan tidak ada perbedaan dalam jumlah peristiwa-peristiwa positif dan negatif yang mereka alami, mereka cenderung untuk mengingat peristiwa dengan lebih baik daripada yang sebenarnya, menggunakan interpretasi positif yang bias. 4) Teori Evolusioner Teori evolusioner muncul belakangan ini dan berpendapat bahwa perasaan senang dan well-being dihasilkan oleh hal yang membantu manusia untuk bertahan. Evolusioner menilai bahwa emosi-emosi negatif (misalnya, takut, marah, dan cemas) yang menolong leluhur kita bereaksi dalam lingkungan yang mengancam. Akan tetapi, manfaat adaptif yang diberikan oleh well-being, dan secara spesifik peran positif emosi sebagai motivator yang mendorong perilaku adaptif mulai dipahami sekarang. Teori “broaden and build” dari Frederickson (dalam Diener dan Ryan, 2008) merupakan model teori evolusioner yang relatif baru yang menyatakan bahwa perasaan positif mengijinkan individu untuk memperluas daftar pemikiran – aksi dan terus-menerus membangun sumber-sumber intelektual, psikologi, sosial dan fisik. Oleh karena itu, Frederickson berpendapat bahwa subjective well-being yang tinggi dan pengaruh positif menghasilkan keadaan dimana individu dengan percaya diri dapat mengeksplor lingkungannya, melakukan pendekatan terhadap tujuan baru, dan dengan demikian mendapatkan sumber daya pribadi yang penting. Dibandingkan emosi yang negatif, emosi positif memiliki manfaat adaptifnya sendiri yang berkontribusi pada kesuksesan evolusioner spesies dan berlanjut untuk menolong manusia dalam mempertahankan hidup. 5) Relative Standards Teori relative standards berpendapat bahwa well-being berasal dari perbandingan antara beberapa standar, seperti masa lalu seseorang, masa lalu orang lain, tujuan-tujuan, atau cita-cita, dan kondisi aktual. Menurut teori perbandingan sosial, seseorang menggunakan orang lain sebagai standar, yang berarti bahwa individu akan mengalami well-being yang lebih tinggi jika mereka lebih baik dari orang lain (Carp & Carp; Michalos dalam Diener, 2009). Misalnya, Easterlin (dalam Diener, 2009) berpendapat bahwa, jumlah pendapatan yang akan memuaskan orang tergantung pada pendapatan orang lain dalam masyarakatnya. Sebagai tambahan, Emmons, Larson, Levine, dan Diener (dalam Diener, 2008) menemukan bahwa perbedaan sosial merupakan prediktor kepuasan yang paling kuat dalam banyak sektor. Dalam teori yang lain, seperti teori adaptasi Brickman, Coates, dan Janoff-Bulman (dalam Diener, 2009), masa lalu individu merupakan standar untuk perbandingan. Misalnya, jika kehidupan seseorang saat ini melebihi standar masa lalunya, maka dia akan merasa puas. Akan tetapi, teori adaptasi juga menyatakan bahwa kekuatan dari peristiwa-peristiwa untuk menimbulkan emosi, berkurang seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika seseorang mengalami peristiwa positif seperti promosi, teori adaptasi berpendapat bahwa orang ini akan mengalami well-being yang tinggi karena promosi menjadi diatas standar mereka sebelumnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teori adaptasi mendalilkan bahwa promosi menjadi standar baru, dengan demikian kehilangan kekuatannya untuk menimbulkan perasaan well-being bagi individu. Dalam hal seperti ini, individu didesak oleh apa yang disebut “hedonic treadmill”, yang menggambarkan proses di mana perubahan baru yang terjadi dalam kehidupan meningkatkan subjective well-being individu secara sementara sebelum individu akhirnya menyesuaikan diri pada standar kondisi yang baru. Jadi, menurut teori adaptasi, peristiwa dan keadaan hanya menjadi penting dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan temperamen menjadi pengaruh jangka panjang utama pada well-being. Dari penjelasan beberapa teori di atas, peneliti memilih teori topdown versus bottom-up sebagai landasan untuk penelitian ini, karena menurut penulis asumsi dasar dari pendekatan top-down versus bottomup sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu bahwa pemenuhan kebutuhan dan perasaan positif yang didapatkan dari pemenuhan keebutuhan atau kepuasan pada domain tertentu bisa memberikan pengaruh pada kepuasan hidup seseorang secara keseluruhan dan juga memberikan rasa nyaman dan bahagia yang mana secara langsung berdampak pada SWB-nya. Teori ini secara bersamaan mendukung SWB dari dua komponen yang membentuk SWB itu sendiri, top-down mendukung komponen emosi, sedangkan bottom-up mendukung komponen kognitifnya. 2.1.3. Aspek-aspek Subjective Well-Being SWB memiliki dua komponen umum : komponen kognitif dan komponen emosional (Diener, & Larsen, 1993; Diener, & Suh, 1997; Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 1991; Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto, & Ahadi, 2002; Ayyash-Abdo & Alamuddin, 2007). 1) Komponen kognitif berkaitan dengan indikator kepuasan hidup individu, yang digambarkan sebagai penilaian kognitif individu mengenai hidupnya secara keseluruhan maupun kepuasan dalam bidang-bidang tertentu, yang meliputi pekerjaan, sekolah, kesehatan, kehidupan keluarga, tujuan hidup, prestasi, keamanan, dan hubungan sosial. Dalam hal ini, kepuasaan bisa meliputi penilaian kepuasan akan keseluruhan hidup individu, namun juga bisa meliputi kepuasan pada domain-domain tertentu dari hidup individu. Huebner (2001) secara rinci membagi domain kepuasan hidup individu dalam lima domain, antara lain kepuasan pada keluarga, kepuasan pada teman, kepuasan pada sekolah, kepuasan pada lingkungan tempat tinggal, dan kepuasan pada diri sendiri. 2) Komponen emosi terdiri dari dua indikator utama : perasaan positif dan perasaan negatif. Perasaan positif merefleksikan keadaan suasana hati yang positif dari seseorang yang meliputi antusias atau bersemangat, aktif, dan alert moods. Perasaan negatif merefleksikan tingkat keadaan suasana hati seseorang yang tidak bersahabat yang meliputi marah, jijik, benci, takut dan gugup. Watson, Clark dan Tellegen (dalam Ayyash-Abdo & Alammudin, 2007) melalui positive and negative affect schedule merincikan perasaan positif antara lain, tertarik, waspada, penuh perhatian, bergairah, antusias, terinspirasi, bangga, teguh pendirian, kuat, dan aktif, sedangkan perasaan negatif terdiri dari, tertekan, sedih, perasaan bersalah, malu, bermusuhan, lekas marah, gugup, gelisah, takut, dan khawatir. Dalam penelitian ini akan digunakan komponen kognitif dari Huebner (2001) dan komponen emosi dari Watson, Clark & Tellegan (dalam Ayyash-Abdo & Alammudin, 2007) 2.1.4. Faktor-faktor yang memengaruhi subjective well-being Sebagai salah satu studi yang menjadi populer saat ini, penelitian mengenai subjective well-being kemudian diteliti dari berbagai sudut pandang dengan bermacam-macam variabel yang mewakili bermacam isu. Diener (2009) mengungkapkan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menjadi penentu subjective well-being. Beberapa kondisi kelihatannya dibutuhkan bagi subjective well-being (mis, kesehatan mental, hubungan sosial yang positif), namun hal-hal tersebut tidak cukup dalam menyebabkan kebahagiaan. Para filsuf dan peneliti telah menemukan sejumlah hal yang menyebabkan kebahagiaan. Menurut Diener, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kondisi demografis yang sangat berperan pada subjective well-being seseorang, antara lain : A. Faktor Demografis 1) Agama, religiusitas dan praktek-praktek spiritualitas Hubungan antara agama, praktek-praktek spiritualitas dan wellbeing merupakan hal yang paradoks. Pada umumnya, orang yang cenderung mengalami level well-being yang lebih tinggi, lebih spesifik untuk hal-hal partisipasi dalam layanan keagamaan, kekuatan afiliasi agama, hubungan dengan Tuhan, dan doa (Ferriss; Poloma & Pendleton; Witter, Stock, Okun, & Harin dalam Diener & Ryan, 2008). Hubungan yang positif antara agama dan well-being yang tinggi berasal dari makna dan tujuan serta jaringan sosial dan sistem dukungan yang diciptakan oleh agama dan institusi lain yang diatur oleh agama. Akan tetapi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap agama merupakan faktor yang penting dalam hubungan positif (Ardelt; Ardelt & Koenig dalam Diener & Ryan, 2008), dan kekuatan hubungan ini kelihatannya lebih kuat untuk kelompok masyarakat tertentu, khususnya perempuan African-americans dan orang-orang tua Eropa (Argyle dalam Diener & Ryan, 2008). Beberapa studi empirik yang berkembang belakangan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor substantif yang berhubungan dengan tujuan hidup, makna, keterlibatan dalam hal keagamaan, religious coping, dukungan komunitas jemaat (congregational support), dan praktekpraktek spiritual ditemukan sebagai prediktor utama well-being (Koenig, McCullough, & Larson, 2001; Ellison; Harker; Maton; Seybold & Hill dalam Morris dkk., 2010). 2) Pendapatan (income) Ada begitu banyak penelitian yang menemukan bahwa pendapatan dan SWB memiliki hubungan yang positif. Selain itu keadaan sosioekonomi seseorang juga berpengaruh. Namun demikian, penelitian mengenai hal ini masih belum konklusif (Diener, 2009; Frey & Stutzer, 2002). 3) Pernikahan, perceraian, dan hubungan sosial Jumlah dan kualitas hubungan sosial individu telah dikonfirmasi memiliki hubungan dan menjadi anteseden dari SWB (Diener & Biswas Diener, 2008). Pada umumnya orang lebih bahagia ketika mereka bersama-sama dengan orang lain, ada interaksi sosial yang terjadi (Kahneman & Krueger, 2006). Orang cenderung lebih mengekspresikan pengaruh positif ketika mereka berada dengan orang lain (Diener & Biswas-Diener, 2008). SWB meningkat melalui ikatan sosial seperti pernikahan, dan kemudian pemenuhan hubungan sosial lainnya (Helliwell, Barrington-Leigh, Harris, & Huang, 2009). Orang yang menikah biasanya mengalami level SWB yang lebih tinggi daripada orang yang tidak menikah menurut studi longitudinal (Lucas, Clark, Georgellis, & Diener, 2003) dan sampel representatif yang besar (Glenn; Lee, Seccombe, & Shehan dalam Diener & Ryan, 2008) ; akan tetapi, data juga menunjukkan bahwa orang cenderung beradaptasi dengan cepat pada pernikahan dan kembali pada level dasar well-being mereka (Lucas, Clark, Georgellis, & Diener, 2003). Berbeda dengan orang yang menikah, orang yang bercerai menunjukkan level well-being yang lebih rendah secara rata-rata (Lucas, 2005). Lebih lanjut menurutnya, perceraian pada umumnya menyebabkan kemunduran dalam SWB disebabkan perceraian, dan mereka yang bercerai tidak mudah kembali pada level dasar wellbeing sepanjang waktu (Lucas, 2005). Dengan demikian, peristiwa perceraian kelihatannya lebih memengaruhi level SWB dibandingkan peristiwa pernikahan. 4) Jender Hubungan level well-being yang relatif antar gender telah sering diuji, namun data yang dikumpulkan selama ini mengindikasikan bahwa perempuan dan laki-laki secara substansi tidak berbeda secara rata-rata dalam SWB. Eryılmaz (2010) menguji SWB remaja Turki dalam hubungannya dengan usia, jender, dan status sosio-ekonomi orang tua, menemukan bahwa tidak ada perbedaan jender pada SWB remaja. Namun demikian, dalam banyak penelitian, perempuan kelihatannya mengalami emosi positif dan negatif lebih sering dan lebih intens dibandingkan laki-laki (Diener & Ryan, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Nielsen, Paritski dan Smyth (dalam Diener, 2009) pada supir taksi di Beijing menemukan bahwa tidak ada perbedaan jender yang signifikan dalam skor personal well-being index pada para supir taksi tersebut. Satu-satunya perbedaan statistik secara signifikan berhubungan dengan kepuasan dan hubungan pribadi, di mana skor laki-laki lebih tinggi. B. Faktor-faktor lain yang memengaruhi SWB Selain kondisi demografis, studi genetik yang dilakukan di Universitas Minnesota dan direview oleh Lykken (dalam Diener & Ryan, 2008) menemukan bahwa kembar monozygotic yang dibesarkan secara terpisah memiliki kemiripan dalam level kebahagiaan daripada kembar dizygotic yang tinggal terpisah. Studi kembar menunjukkan bahwa beberapa bagian variabel dalam kebahagiaan mungkin disebabkan kontribusi genetik. Namun demikian, ada juga penelitian yang menemukan bahwa level subjective well-being seseorang tidak ditentukan oleh faktor genetiknya. Diener dan kolega (Diener dkk., 2002; Lucas dkk., 2004 dalam Diener, 2009) melakukan studi longitudinal di Jerman dan menemukan bahwa faktor genetik tidak memberi pengaruh pada SWB seseorang. Mereka secara berulang-ulang menemukan bahwa orang yang menjadi pengangguran (unemployed) merasa kurang bahagia, dan berlanjut demikian untuk waktu yang cukup lama, dibandingkan dengan mereka yang memiliki pekerjaan mapan. Hal ini menentukan bahwa genetik yang ada dalam diri individu tidak memengaruhi dirinya melainkan keadaan demografis dirinya yang membutuhkan pekerjaan. Sejumlah studi juga telah mengkonfirmasi pentingnya temperamen dan kepribadian dalam menemukan kapasitas individu untuk merasa wellbeing. Diantara sifat-sifat kepribadian yang berbeda, ekstraversi dan neurotisime merupakan dua tipe kepribadian yang paling konsisten dan kuat berelasi dengan well-being (Diener, Oishi & Lucas,. 2003; Rusting & Larsen dalam Diener, 2009). Ekstraversi bisa memprediksi pengaruh positif (Lucas & Fujita, 2000), sementara pengaruh negatif dengan kuat diprediksi oleh neurotisisme (Fujita, 1991). Lebih lanjut, studi lintas negara menunjukkan bahwa orang yang ekstrovert cenderung untuk mengalami sejumlah besar perasaan positif dan terjadi secara intens jika dibandingkan dengan yang introvert (Diener & Biswas-Diener, 2008). Oleh karena itu, sementara lingkungan memainkan peranan dalam ekspresi genetik, jelas bahwa sifat-sifat warisan genetik memiliki pengaruh subtansi pada level well-being individu. Selain itu, penentuan tujuan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi well-being. Hasil penelitian Eryilmaz (2011) menunjukkan bahwa penentuan tujuan hidup remaja berkorelasi dengan SWB mereka. Jika individu percaya bahwa tujuan mereka penting dan mereka bisa mencapai tujuan ini maka mereka memiliki level SWB yang lebih tinggi. Dari sudut pandang remaja, penemuan ini menemukan bahwa penentuan tujuan karir memberikan SWB yang lebih baik pada remaja.Tujuan meningkatkan level SWB individu dengan memfokuskan mereka pada masa depan dan menambahkan arti dalam hidup mereka. Optimisme juga menjadi faktor yang memengaruhi SWB individu (Utsey, Hook, Fischer & Belvet, 2008). Gottlieb dan Rooney (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa optimisme secara positif berkorelasi dengan kesehatan seseorang. Optimisme juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan hidup (Bailey, Eng, Frisch, & Snyder, 2007). Optimisme memberikan pengaruh yang positif pada kepuasan hidup orang dewasa awal (Isaacowitz dalam Isaacowitz, Vaillant & Seligman, 2003) dan remaja akhir (Heo & Lee, 2010; Isaacowitz dalam Isaacowitz, dkk., 2003), remaja perdesaan (Alder, 2008), mahasiswa (Harju & Bolen, 1998), dan siswa SMA (Wong, 2009). Persepsi dukungan sosial merupakan hal yang krusial dalam menilai seberapa baik remaja berjuang dalam kondisi lingkungannya (Barnes, Katz, Korbin, & O’Brien; Brennan dkk.; Brennan, Barnett, & Lesmeister; Bowes & Hayes; McGrath dalam McGrath, Brennan, Dolan & Barnett, 2009). Orang tua dan teman sebaya merupakan pendukung yang penting dalam aktivitas fisik siswa SMA. Orang tua dilihat sebagai teladan dan penyedia dukungan emosional, yang meliputi mendorong anak untuk menjadi aktif atau memerhatikan anak-anaknya (Duncan dkk; McGuire, Hannan, Neumark-Sztainer, Crossrow, & Story dalam Robbins, Stommel & Hamel, 2008). Walaupun demikian, teman sebaya merupakan prediktor yang kuat dalam konteks remaja (Prochaska dkk. dalam McGrath dkk., 2009). Namun demikian, dalam konteks sekolah, hasil penelitian Richman, Rosenfeld & Bowen (1998) menemukan bahwa guru bersama dengan orang tua bisa dilihat oleh siswa “bermasalah” sebagai sumber dukungan sosial utama, dalam hubungan dengan hubungan emosional, bantuan praktis, dan untuk apresiasi yang diterima atas usaha yang dilakukan. Selain orang tua, guru juga merupakan pendukung yang memberikan kontribusi pada prestasi akademik, keterikatan/komitmen dengan sekolah, dan well-being dalam kelas (Brewster & Bowen; Chen; Vedder, Boekaerts, & Seegers dalam Flaspohler dkk., 2009). Beberapa penelitian pada remaja menemukan beberapa faktor yang memengaruhi SWB remaja, antara lain, usia dan status ekonomi orang tua menjadi faktor penting bagi SWB remaja Turki (Eryilmaz, 2010), optimisme dan hubungan sosial (Morris, Martin, Hopson, dan Welch- Murphy, 2010), rasa puas pada sekolah, tubuh (pada siswa perempuan), dan kesehatan diri, dan strategi interaktif siswa-guru (Katja, Paivi, MarjaTerttu, dan Pekka, 2002), peristiwa dalam hidup (McCullough, Huebner, dan Laughlin, 2000), dan konsep diri sosial (Chang, McBride-Chang, Stewart, dan Au, 2003), dan dukungan teman sebaya (Robbins dkk., 2008). Selain itu, konteks yang mendukung di mana remaja itu tinggal dan melakukan aktivitasnya juga memengaruhi SWB remaja. Studi yang dilakukan oleh McGrath dkk. (2009) pada remaja Florida dan Irlandia menemukan bahwa dukungan sosial informal dan kepuasan di sekolah (school satisfaction) merupakan prediktor terkuat dari remaja di kedua lokasi tersebut. Dari sumber-sumber informal, dukungan emosional dari teman dan dukungan nasehat/konkrit/penghargaan dari orang tua hadir sebagai dimensi prediktif yang penting. Kesukaan terhadap sekolah, persepsi akan keberhasilan di sekolah merupakan prediktor utama kepuasan akan sekolah oleh siswa Irlandia, sementara di Florida, persahabatan siswa dan pengalaman mengalami bullying muncul sebagai faktor yang signifikan. Selain itu, prediktor global SWB remaja juga antara lain nilai-nilai tertentu seperti keseimbangan pribadi, hubungan keluarga yang nyaman dan aman, tipe keluarga itu sendiri (keluarga kandung, orang tua tunggal, dan step family) khususnya dalam beberapa aspek tertentu, seperti persepsi remaja akan tingginya level kebersamaan dan stabilitas dalam keluarga dan rendahnya masalah-masalah serius dalam keluarga tersebut (Rask, Asted-Kurki, dan Laippala, 2003). Studi lintas-budaya di remaja Perancis, China, dan Australia telah mengkonfirmasi pengaruh yang lebih besar dari hubungan orang tua-anak dalam hubungan dengan persepsi kualitas hidup remaja (Leung & Leung; Petito & Cummins; Sastre & Ferriere; Shek dalam Huebner, Suldo, Smith dan McKnight, 2004). Dalam konteks sekolah, ada beberapa faktor penting yang menjadi penentu SWB remaja, antara lain school connectedness. Siswa yang merasa memiliki ikatan atau hubungan yang baik dengan sekolahnya melaporkan level emosional well-being yang tinggi (Eccles, Early, Frasier, Belansky & McCarthy, 1997; Steinberg dalam McNeely dkk, 2002; Libbey, 2004), dukungan sosial teman sebaya dan guru (Flaspohler dkk., 2009), orang tua (del Valle dkk., 2010), school connectedness (Eccles dkk., 1997; Steinberg dalam McNeely dkk, 2002; Libbey, 2004), self-efficacy (Yang dkk., 2008). Dari faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa SWB dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam diri individu (internal) maupun faktor eksternal (kondisi, lingkungan) individu. Faktor internal meliputi, kepribadian, usia, jender, genetik, dan optimisme, sedangkan faktor eksternal meliputi, dukungan sosial dari teman sebaya, orang tua, guru, strategi interaktif siswa-guru, agama, pendapatan, status sosioekonomi orang tua, konsep diri sosial, peristiwa dalam hidup, penentuan tujuan, konteks tempat tinggal remaja, school connectedness, hubungan sosial sosial, SES, dan kesehatan diri. Dari semua faktor-faktor di atas, dua variabel yang akan digunakan sebagai variabel prediktor SWB remaja yaitu school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya. 2.2. PERKEMBANGAN REMAJA Penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada siswa SMA yang dari segi usia masih tergolong kelompok remaja. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara singkat mengenai remaja dan tugas perkembangannya. 2.2.1. Defenisi Remaja Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.” Istilah adolescence, seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2003). Santrock (2010) menyebut remaja (adolescence) sebagai periode pertumbuhan antara anak-anak ke dewasa atau masa transisi dari anakanak menuju ke masa dewasa. Dengan kata lain, mereka tidak termasuk golongan anak, tetapi mereka tidak juga masuk golongan dewasa (Mönks, Knoers & Haditono, 2002). Masa remaja seringnya dikenal sebagai masa “badai dan tekanan” (storm and stress) seperti yang diungkapkan oleh G. Stanley Hall (dalam Santrock, 2010). Akan tetapi, ketika Daniel Offer dan koleganya (dalam Santrock, 2010) melakukan studi untuk melihat gambar-diri remaja (self-image) di Amerika, Australia, Bangladesh, Hungaria, Israel, Italia, Jepang, Taiwan, Turki, dan Jerman Barat, ditemukan bahwa 73% remaja menunjukkan gambar diri yang sehat. Walaupun ada beberapa perbedaan diantara sampel tersebut, namun hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebanyakan remaja merasa bahagia, menikmati hidup mereka, merasa dirinya mampu mengontrol diri, menghargai sekolah dan pekerjaan mereka, percaya diri, dan merasa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi stres. Hal ini menunjukkan bahwa masa remaja tidak selalu diidentikan dengan masa tekanan dan badai. Masa transisi remaja dimulai kira-kira pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir di usia antara 18 sampai 22 tahun (Santrock, 2003). Mönks dkk., (2002) membagi perkembangan dalam masa remaja ke dalam tiga bagian besar yang secara global berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun; masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun) dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Remaja awal umumnya adalah mereka yang memasuki pendidikan di bangku sekolah menengah tingkat pertama, remaja tengah memasuki pendidikan sekolah menengah atas dan remaja akhir adalah mereka yang lulus SMA atau masuk perguruan tinggi dan mungkin mereka yang sudah bekerja (Dariyo, 2004). Menurut Hurlock (2003) secara umum masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal masa remaja dan akhir masa remaja. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13-16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun-18 tahun, yaitu masa usia matang secara hukum. Sebagai patokan dalam penelitian ini, penulis menggunakan batasan usia remaja seperti yang ditetapkan Mönks, dkk., (2002) yaitu usia 12 sampai 21 tahun. 2.2.2. Tugas Perkembangan Remaja Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal, menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugastugas berikutnya (Havighurst dalam Hurlock, 2003). Havighurst mengemukakan delapan tugas perkembangan remaja yang meliputi: a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita b. Mencapai peran sosial pria dan wanita c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab e. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya f. Mempersiapkan karier ekonomi g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis Disadari atau tidak, setiap remaja pasti menghadapi tugas-tugas perkembangan tersebut. Untuk menjalankan semua tugas tersebut setiap remaja memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri. Kesulitan itu semakin bertambah bila remaja itu sendiri tidak menyadari akan tugastugas perkembangannya atau juga lingkungan hidup yang tidak mendukungnya secara optimal. 2.3. SCHOOL CONNECTEDNESS 2.3.1. Definisi School Connectedness School connectedness telah dipelajari dengan variasi nama dan definisi (Blum & Libbey, 2004). Beberapa istilah yang sering digunakan meliputi, “school belonging” (Osterman, 2000; Willms dalam Frydenberg, Care, Freeman & Chan, 2009), “student engagement” (Taylor & Nelms, 2006), “school bonding” (Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming & Hawkins, 2004), dan “teacher support” (Klem & Connell, 2004; Reddy, Rhodes, & Mulhall, 2003). Konstruk mengenai school connectedness sendiri didefinisikan oleh Goodenow (1993) sebagai tingkat di mana siswa secara personal merasa diterima, dihormati, merasa menjadi bagian, dan didukung oleh orang lain dalam lingkungan sosial sekolah. School connectedness telah muncul sebagai prediktor potensial yang utama dari masalah psikososial remaja dan kesehatan mental mereka, khususnya depresi (Shochet, Dadds, Ham & Montague, 2006). School connectedness didefinisikan meliputi indikatorindikator umum seperti: kesukaan terhadap sekolah, perasaan memiliki, hubungan positif dengan guru dan teman, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah (Thompson, McGrath dkk., 2009). Rasa terhubung dengan sekolah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai tingkat di mana siswa merasa sebagai bagian dari sekolah. Lebih kompleks lagi, meliputi persepsi bahwa sekolah memberikan dukungan terhadap cita-cita akademik siswa, memiliki iklim disiplin, dan budaya yang mendukung. Selain itu, school connectedness juga merupakan konsep yang muncul dari interaksi individu dengan lingkungan sekolahnya (Hawkins dkk.; McBride dkk. dalam Resnick dkk., 1997). Libbey mereview studi yang didesain untuk mengukur hubungan siswa dengan sekolahnya dan mengemukakan definisi school connectedness sebagai keyakinan bahwa orang dewasa di sekolah peduli terhadap siswa secara individu dan proses belajar yang mereka lakukan (Libbey dalam Waters, Cross & Runions, 2009). Indikator dasar yang digunakan dalam konstruk definisi tersebut meliputi sikap dan motivasi siswa terhadap sekolah dan belajar, level di mana siswa merasa mereka disukai oleh orang lain di sekolah dan komitmen siswa, keterlibatan, dan keyakinan dalam aturanaturan sekolah (Libey, 2004). Selain itu, school connectedness juga didefinisikan sebagai perasaan dipedulikan, diterima, dihargai, dan didukung oleh orang lain baik oleh keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat luas (Lee & Robbins, 1995; Resnick dkk., 1993; Rutter dalam McGraw, Moore, Fuller & Bates, 2008). Dari definisi-definisi di atas, maka untuk tujuan penelitian ini, definisi school connectedness yang akan digunakan yaitu persepsi siswa mengenai penerimaan dirinya di sekolah oleh guru dan pengidentifikasian serta keterlibatan aktif dirinya sebagai bagian dari sekolah. 2.3.2. Aspek-aspek School Connectedness Menurut Langille, dkk. (2010) School connectedness memiliki dua aspek, yaitu : 1) Social connectedness, perasaan berintegrasi atau menyatu secara sosial dan bahagia di sekolah. 2) School stewardship, sekolah dirasakan memberikan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Connell dan Wellborn (dalam Stracuzzi dan Mills, 2010) menyatakan bahwa school connectedness terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu: 1) Social support, khususnya dukungan guru, didasarkan pada sejauh mana siswa merasa dekat dan bernilai oleh guru dan staf lainnya di sekolah. Biasanya diukur melalui laporan siswa mengenai apakah gurunya menyukai dirinya atau tidak, kepedulian mereka terhadap guru, kenyamanan ketika berbicara dengan guru, seberapa sering guru memuji mereka (Resnick dkk., 1997) 2) Belonging, didefinisikan sebagai rasa yang dimiliki oleh siswa mengenai dirinya sebagai bagian dari sekolah. Mengukur belongingness ini sering meliputi tingkat di mana siswa merasa dihormati di sekolahnya, menjadi bagian dari sekolahnya, merasa orang-orang yang ada di sekolah peduli dengannya, dan memiliki teman di sekolah (Voelkl, 1996). 3) Engagement, merefleksikan resiprokasi siswa atas rasa memiliki (belonging) dan dukungan yang didapat melalui kepedulian yang aktif dan keterlibatan dalam bagiannya (Karcher 2003). Dalam penelitian ini akan digunakan tiga dimensi school connectedness dari Connell dan Wellborn (1991), antara lain social support (teacher support), belonging dan engagement. Ketiga dimensi ini digunakan dengan alasan bahwa pada dasarnya keterikatan atau hubungan yang terjalin di antara siswa dengan sekolahnya, tidak hanya melibatkan satu pihak saja, dalam hal ini para guru, namun juga melibatkan keterlibatan aktif siswa. Jadi ada hubungan timbal balik yang tercipta. Oleh karena itu, penggunaan tiga dimensi ini dalam mengukur school connectedness siswa dianggap sesuai. 2.3.3. Efek School Connectedness pada Subjective Well-being Sebagai institusi signifikan dalam komunitas, sekolah memiliki hubungan yang penting dengan rasa well-being remaja. Sekolah bisa bertindak sebagai sumber psikososial yang penting dalam mendukung anak muda, khususnya remaja yang terisolasi dari jaringan-jaringan sosial (Rostosky, Owens, Zimmerman, & Riggle, 2003). Literatur penelitian-penelitian yang dilakukan di sekolah menemukan bahwa kalangan anak muda yang merasa terhubung dengan sekolah melaporkan kesehatan yang lebih baik dan emosional wellbeing yang lebih baik begitupun juga dengan berkurangnya penyalahgunaan minuman keras, keinginan bunuh diri, gejala-gejala depresi, dan resiko kekerasan atau perilaku kriminal, dan kehamilan di luar pernikahan (Blum, McNeely, & Rinehart, 2002; Bonny, Britto, Klosterman, Hornunq, & Slap, 2000; Eccles dkk., 1997; Jacobson & Rowe, 1999; Resnick, Bearman, & Blum dalam McGrath dkk., 2009). Walaupun konstruk school connectedness secara empiris dikembangkan sebagai indikator umum akan perasaan ikatan siswa dan kualitas hubungan dengan teman sebaya dan guru, Whitlock (2006) kemudian mengusulkan model teoritikal untuk menjelaskan bagaimana hal ini beroperasi sebagai kekuatan pelindung bagi anak muda. Dia menemukan dukungan untuk konseptual model yang didasarkan pada hubungan connectedness dengan peningkatan siswa dalam (a) keterlibatan dalam peran-peran yang berarti di sekolah, (b) keamanan di sekolah, (c) kesempatan untuk keterlibatan yang kreatif, dan (d) kesempatan keterlibatan akademik. Para peneliti telah melaporkan bahwa school connectedness berasosiasi dengan berkurangnya resiko hasil perkembangan yang negatif. Lebih jauh, school connectedness secara positif berasosiasi dengan berkurangnya penggunaan alkohol/minuman keras (Wang, Matthew, Bellamy, & James, 2005), kerentanan terhadap kekerasan bersenjata (Henrich, Brookmeyer, & Shahar, 2005), keinginan awal untuk merokok (Dornbusch, Erickson, Laird, & Wong, 2001), dan pencegahan dropping out dari sekolah (Miltich, Hunt, & Meyers, 2004). Ketika remaja merasa diperhatikan oleh orang lain di sekolah dan menjadi bagian dari sekolah mereka, maka mereka memiliki level well-being yang lebih tinggi (Resnick dkk., 1997; Eccles dkk., 1997; Steinberg dalam McNeely dkk., 2002). Dengan demikian, ketika remaja memiliki hubungan yang baik dengan sekolah secara keseluruhan, pada umumnya remaja terhindar dari perilakuperilaku bermasalah dan lebih terikat dengan perkembangan yang sehat. Dalam hal ini school connectedness menjadi faktor protektif bagi remaja dan meningkatkan level SWB-nya. 2.4. DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 2.4.1. Definisi Dukungan Sosial Dukungan sosial penting dalam mengatur berfungsinya diri secara optimal setiap hari dan juga sebagai pelindung untuk mengurangi kecenderungan hasil negatif ketika individu mengalami tekanan hidup (Cobb, 1976; Cohen & Wills, 1985 dalam Flaspohler dkk., 2009). Kaplan dkk. (dalam Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005) mendefinisikan dukungan sosial dalam ungkapan derajat atau level di mana kebutuhan sosial seseorang dipuaskan melalui interaksi dengan orang lain. Gottlieb (dalam Armstrong dkk., 2005) mendefinisikan dukungan sosial sebagai “informasi atau nasihat verbal dan non-verbal, bantuan nyata atau aksi yang diajukan oleh “teman sosial” atau disimpulkan melalui kehadiran mereka dan memiliki manfaat emosional atau efek perilaku pada penerima. Malecki, Demaray, dan Elliott (2002) menggambarkan dukungan sosial sebagai “dukungan umum atau perilaku dukungan spesifik individu dari orang-orang tertentu dalam jaringan sosial, yang meningkatkan fungsi mereka dan/atau menahan mereka dari hasil penderitaan/kemalangan”. Dalam konteks sekolah, guru dan teman sebaya cenderung merupakan bagian yang penting dari jaringan sosial anak yang menyediakan bentuk dukungan yang bermacam-macam, termasuk dukungan emosi, motivasi, instrumental, dan informasi (Tardy dalam Flaspohler dkk., 2009). Cutrona (dalam McGrath dkk., 2009) mengusulkan definisi ringkas dari dukungan sosial sebagai “semua aksi atau tindakan yang menunjukkan responsivitas bagi kebutuhan orang lain.” Teori dukungan sosial mengusulkan dua model utama, yaitu the main effect dan the buffering effect untuk menjelaskan asosiasi atau hubungan antara dukungan sosial dan well-being. The main effect mengusulkan bahwa dukungan sosial didefinisikan sebagai integrasi sosial atau kelekatan sosial yang memiliki efek menguntungkan pada well-being bilamana seseorang berada atau tidak dibawah stres. The buffering model berhipotesa bahwa dukungan sosial melindungi/menjaga individu dari potensi efek berbahaya dari peristiwa yang penuh tekanan (Armstrong dkk., 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memberikan efek yang positif bagi well-being individu dalam melakukan fungsinya sebagai makhluk individu dan sosial dengan baik. 2.4.2. Dukungan Sosial Teman Sebaya Dukungan sosial yang diberikan teman sebaya merupakan salah satu dukungan penting yang dibutuhkan oleh remaja dalam masa-masa perkembangannya (Duncan dkk. dalam Robbins dkk., 2008). Teman menyediakan sumber jaringan sebagai anggota atau bagian dalam suatu tim, khususnya ketika remaja (Cotterell, 1996; Feldman & Elliot, 1993). Persahabatan remaja secara tipikal menyediakan bantuan yang sifatnya konkrit dan nasehat-nasehat selain dari orang tua (Dolan dalam Robbins, 2008). Studi menunjukkan bahwa teman sebaya menjadi landasan penting atau kelompok penting bagi topik-topik yang mungkin terbatas dengan keluarga selain itu menjalin persahabatan yang kuat bisa menjadi penghalang perilaku bullying (Cowie; Naylor & Cowie dalam McGrath, Brennan, Dolan, dan Barnett, 2009). Mead, Hilton dan Curtis (dalam Solomon, 2004) telah jauh meneliti dukungan teman sebaya dan menyatakan bahwa dukungan teman sebaya merupakan sistem memberi dan menerima bantuan yang dibangun berdasar prinsip-prinsip kunci yang meliputi rasa hormat, berbagi tanggung jawab, dan persetujuan yang sama mengenai apa itu menolong. Sejumlah kelompok teman sebaya menyediakan fungsi-fungsi penting selama masa remaja, misalnya melalui pengidentifikasian diri dengan teman sebaya, remaja mulai membangun penilaian dan pandangan moral mereka (Bishop & Inderbitzen dalam Gentry & Campbell, 2002) dan pada saat yang sama juga menyediakan sumber-sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga dan juga mengenai diri mereka sendiri (Santrock dalam Gentry & Campbell, 2002), serta sebagai penguatan yang positif, memberikan status, penghargaan dan penerimaan diri. Dengan demikian, dukungan sosial teman sebaya merupakan persepsi remaja terhadap tingkat dukungan yang diterima dari teman sebayanya, yang meliputi dukungan emosional, instrumental, penilaian, dan informasi. 2.4.3. Dimensi-dimensi Dukungan Sosial Tardy (dalam del Valle dkk., 2010) menekankan kompleksitas konsep dukungan sosial dari sudut pandang pengukuran (measurement), mengidentifikasi lima dimensi dukungan sosial, antara lain : 1) Arahan, dukungan yang diberikan atau diterima 2) Disposisi, ketersediaan (ada) atau dibuat-buat 3) Deskripsi atau penilaian, dukungan sosial yang secara sederhana digambarkan atau dinilai dalam cara tertentu 4) Isi, meliputi dukungan emosional, instrumental, informasional, atau penilaian 5) Jaringan, orang tua, guru, teman sebaya, dsb. House (dalam Glanz dkk., 2008) mendefinisikan dukungan sosial sebagai konten fungsional dari suatu hubungan yang melibatkan perhatian, bantuan dan informasi mengenai seseorang (diri sendiri) dan lingkungan. Dimensi dukungan sosial mencakup: 1) Dukungan emosi, keberadaan seseorang atau lebih yang bisa mendengarkan dengan simpati ketika seorang individu mengalami masalah dan bisa menyediakan indikasi kepedulian dan penerimaan. 2) Dukungan penilaian, meliputi ketersediaan informasi yang berguna dalam rangka evaluasi diri – dengan kata lain, memberikan umpan balik dan penguatan atau penegasan. 3) Dukungan informasi, meliputi ketersediaan pengetahuan yang berguna dalam menyelesaikan masalah, seperti menyediakan informasi mengenai sumber-sumber dan layanan komunitas atau menyediakan nasehat dan tuntunan mengenai suatu aksi atau hal-hal tertentu untuk menyelesaikan masalah. 4) Dukungan instrumental, melibatkan bantuan nyata atau praktis yang secara langsung dapat membantu seseorang yang membutuhkan. Cohen dan Wills (1985) membedakan antara empat tipe dukungan, esteem support (didefinisikan sebagai penyediaan informasi dan sikap yang mengindikasikan keberhargaan dari seseorang), informational support (didefinisikan sebagai menyediakan bantuan dalam mengartikan dan mengatasi masalah dari suatu peristiwa), social companionship (yang melibatkan availabilitas seseorang yang mana seseorang bisa berpartisipasi dalam aktivitas luang dan aktivitas sosial, seperti perjalanan bersama atau pesta, aktivitas-aktivitas kebudayaan, misalnya pergi nonton atau ke museum, aktivitas rekreasi, seperti berolahraga atau hiking), dan instrumental support (merupakan dukungan yang berfokus pada masalah, dalam hal ini bukan hanya informasi yang diberikan, namun juga tindakan nyata dalam menyelesaikan suatu masalah atau peristiwa). Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, maka dimensi-dimensi dukungan sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah aspekaspek dukungan sosial dari House (dalam Glanz dkk., 2008) yang terdiri dari dukungan emosional, dukungan penilaian, dukungan informasi, dan dukungan instrumental. Dimensi-dimensi dukungan sosial dari House digunakan dengan alasan bahwa dimensi-dimensi tersebut bisa mencakup keseluruhan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa. 2.4.4. Efek Dukungan Sosial Teman Sebaya pada SWB Signifikansi dukungan sosial bagi remaja biasanya dipahami dalam konteks psikologi well-being mereka dan perannya sebagai penahan (buffer) dalam melawan stres (Barbee; Cobb; Cohen & Wills; Gottlieb; Tardy; Teelan, Herzog, & Kilbane;Weiss dalam McGrath dkk., 2009). Keberadaan dukungan sosial dapat membantu well-being remaja melalui pengembangan self-esteem dan self-efficacy (Axelsson & Ejlertsson dalam McGrath, 2009). Dolan (dalam Mcgrath, 2009) menyatakan bahwa, teman, dalam dunia remaja bisa menjadi sumber informasi tertentu mengenai keanggotaan suatu jaringan sosial. Pertemanan remaja biasanya menyediakan juga bantuan konkrit dan nasehat selain nasehat dan bantuan yang diterima dari orang tua. Banyak studi menunjukkan bahwa teman sebaya memberikan nasehat atau pemikiran penting bagi topik-topik yang mungkin terbatas untuk dibicarakan bersama keluarga. Selain itu memiliki ikatan persahabatan yang kuat juga bisa menjaga dari perilaku bullying (Cowie; Naylor & Cowie dalam McGrath, 2009). Dengan demikian, teman sebaya memiliki peran yang penting dan juga sentral dalam menyediakan bentuk-bentuk dukungan biasa/umum yang langsung dan bisa diakses dan menunjukkan konsistensi signifikansi dalam mempromosikan well-being remaja. Hasil penelitian yang dilakukan McGrath dkk. (2009) pada remaja di Amerika dan Irlandia menemukan bahwa penerimaan dan penguatan dari teman dekat merupakan hal yang krusial bagi stabilitas dan keamanan well-being remaja. Hasil penelitian juga mengkonfirmasikan bahwa teman merupakan sumber penting yang menyediakan dukungan emosional. Dukungan emosional merupakan bentuk dukungan yang lebih sensitif dan berhubungan dengan perasaan dan biasanya melibatkan hubungan yang dekat (hubungan karib). Biasanya hal ini menyangkut hal-hal seperti, selalu ada untuk orang yang dekat, mendengarkan mereka ketika mereka sedang sedih, dan memberikan dukungan yang tanpa syarat. 2.5. HASIL PENELITIAN TERDAHULU Penelitian mengenai subjective well-being tergolong penelitian yang masih baru di Indonesia. Belum banyak penelitian yang dipublikasi mengenai SWB ini. Namun demikian, publikasi mengenai penelitian ini telah banyak dilakukan oleh negara-negara asing, seperti Amerika dan Eropa, bahkan di beberapa negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea, Singapura dan Malaysia. Berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai SWB yang khususnya berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh penulis. 2.5.1. School Connectedness dan Subjective Well-being Fydenberg dkk., dengan analisis path dalam penelitiannya menemukan bahwa school connectedness memiliki hubungan yang positif dengan well-being, secara khusus emotional well-being, namun hubungannya lemah (.29). Semua bobot regresi yang ditemukan dalam penelitian ini secara statistik signifikan ( < .05). Dilakukan juga Multivariate analysis of varian (MANOVA) untuk menguji perbedaan gender dari school connectedness dan well-being, produktif coping dan non-produktif coping. Hasilnya, ditemukan bahwa ada perbedaan jender (1.531) = 5.90, < .001, μ = .04. Dari hasil univariate test dibuktikan bahwa perbedaan ini terutama pada school connectedness. Dalam pengukuran 20.60, 3.26), (1.534) = 19.96, Oberle, penelitian connectedness, perempuan = = 2.92) memiliki skor lebih tinggi daripada laki-laki = 19.41, .40. school Schonert-Reichl mengenai dan perkembangan < .001, μ = Zumbo (2010) melakukan positif remaja, khususnya komponen kognitif SWB yang dipengaruhi oleh optimisme dan konteks sosial (school connectedness, dukungan sosial yang dirasakan dari lingkungan, dukungan keluarga, dan hubungan dengan teman sebaya), menemukan bahwa optimisme dan semua konteks sosial (ecological asset) secara signifikan dan positif merupakan prediktor kepuasan hidup remaja awal. Penelitian ini dilakukan dengan analisis multi level dan conditional model, dengan hasil prediktor signifikan pada model yang dibuat mengindikasikan hubungan dukungan orang tua/keluarga, 10 = .19, dari teman sebaya 1,339.23 = 4.80, < .001, hubungan positif 20 = .12, (1,339.55) = 4.00, < .001, dan optimisme 30 =. 61, (1,339.66) = 20.85, < .001 pada kepuasan hidup remaja awal. Lebih daripada signifikansi dan efek positif dari school connectedness 40 dukungan dari lingkungan = .18, (1,339.33) = 6.11, 50 < .001, dan = .05, (1,339.25) = 2.33, < .001 pada level siswa, ditemukan juga pengaruh yang signifikan dari ratarata school connectedness = .43, (18.59) = 2.76, dengan kepuasan hidup, = .01. 01 Penelitian untuk menguji hubungan siswa dengan sekolahnya juga dilakukan oleh Lau & Li (2011). School connectedness yang dalam penelitian ini dikelompokkan dalam variabe school capital merupakan salah satu variabel yang memberikan pengaruh terhadap SWB anak ( = .337, tua ( = .245, < .001) disamping hubungan dengan orang < .001) dan teman ( = .342, < .001). Studi ini merupakan cross-sectional survey design dengan pengambilan sampel stratifikasi random sampling. Total sampel dari penelitian ini 1306 siswa kelas 6 SD dan juga orang tua mereka yang berasal dari 16 sekolah di Shenzen, Cina. 2.5.2. Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Subjective Well-being Penelitian Gülaçt yang dilakukan pada mahasiswa calon guru di Turki ditemukan bahwa dukungan teman tidak menjadi prediktor bagi SWB, sebaliknya dukungan keluarga menjadi penting. Hasil analisis regresi berganda menemukan bahwa 18% (R2 = 0.18) dukungan sosial yang diterima dari keluarga berpengaruh pada SWB siswa. Sebaliknya dukungan sosial teman dan orang terdekat (kekasih, pacar) tidak berpengaruh terhadap SWB (t=1857, > 0.05; = 0.341, > 0.05). Gülaçt mengindikasikan bahwa hubungan positif yang terjalin dengan keluarga menyebabkan perkembangan dalam aspek emosi, sosial dan kognitif anak dan hal ini secara positif berdampak pada kehidupan yang dijalani oleh anak; anak mengalami kepuasan dan lebih bahagia. Chou (1999) dalam penelitiannya mengenai dukungan sosial dan SWB yang dilakukan pada dewasa awal (young adult) dengan jumlah sampel 475 orang menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara emosi positif (positive affect) dan semua dimensi dukungan sosial, kecuali jaringan komposisi teman dan keluarga dekat dan frekeunsi pertemuan secara teratur. Kuatnya nilai asosiasi antara afektif (skor positif afek dan negatif afek) dan dukungan sosial atau jaringan sosial antara . 23 ≥ | | ≥ .10. Dengan model regresi berganda ditemukan bahwa kepuasan dengan anggota keluarga dan teman secara konsisten berasosiasi dengan semua ukuran SWB, dan jumlah teman dekat yang dimiliki secara positif berhubungan dengan emosi positif (positive affect). Secara spesifik, semakin tinggi level kepuasan dalam hubungan dengan keluarga dan teman maka semakin rendah level gejala depresi. Model analisis regresi untuk dukungan sosial atau jaringan sosial terhitung 10% dari setiap varian, 3.41, < .0001, (15,459) = = .10. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 12 sekolah yang secara random diikutsertakan untuk berpartisipasi. Kef dan Dekovic (2004) dalam penelitian yang dilakukan mengenai dukungan sosial teman sebaya dan dukungan orang tua pada well-being remaja; dalam penelitiaannya digunakan dua kelompok, kelompok pertama adalah remaja dengan masalah penglihatan/tidak bisa melihat dan kelompok kedua remaja yang tidak mengalami masalah penglihatan, menemukan bahwa dukungan teman sebaya dan dukungan orang tua terbukti penting bagi kedua kelompok tersebut; untuk remaja dengan masalah penglihatan ( = 0.47, remaja tanpa masalah penglihatan ( = 0.24, < 0.05); < 0.05), tapi besarannya lebih rendah. Di mana pada kelompok dengan masalah penglihatan terdapat hubungan positif yang linear antara dukungan sosial teman sebaya dan well-being, sedangkan pada kelompok yang tidak mengalami masalah penglihatan, well-being kelihatannya tidak dipengaruhi oleh dukungan sosial teman sebaya. Dukungan orang tua yang lebih memberikan pengaruh pada kelompok ini. Dalam penelitian ini juga digunakan multivariate analysis of variance (MANOVA) untuk menguji efek kelompok, jenis kelamin dan usia pada dukungan sosial. Hasilnya, ditemukan perbedaan antara dua kelompok dalam semua variabel dukungan sosial (dukungan emosional, 23.94, < 0.001; dukungan praktis, (1.513) = 21.93, dan social companionship, (1.513) = 53.46, (1.513) = < 0.001; < 0.001). Dari ketiga variabel dukungan sosial, yang menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan yaitu social companionship, (1.513) = 9.37, < 0.05. Dari pengujian ini juga ditemukan bahwa untuk skor dukungan sosial teman sebaya, perempuan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (social companionship 0.05; emosi 12.29, (1,513) = 19.21, (1,513) = 4.95, < 0.001; praktis < (1,513) = < 0.001). Sedangkan untuk dukungan sosial dari orang tua tidak ditemukan perbedaan. Pengujia ANOVA untuk well-being tidak menemukan adanya perbedaan dalam kelompok (1,513) = 2.42, > 0.05, namun laki-laki merasa lebih bahagia dibandingkan perempuan (1,513) = 6.30, < 0.05. Ratelle, Simard & Guay (2012) melakukan studi untuk menginvestigasi hubungan antara dukungan autonomi dari tiga sumber dukungan yang signifikan (orang tua, teman, dan kekasih) dan SWB mahasiswa dengan menggunakan dua pendekatan: pendekatan berpusat pada variabel dan pendekatan yang berpusat pada orang. Partisipan adalah 256 mahasiswa (191 perempuan, 65 laki-laki) yang memiliki pasangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dukungan yang diterima dari ketiga sumber ini dapat memprediksikan level yang lebih tinggi pada SWB. Korelasi yang paling kuat terutama dari teman ( = .42) dan orang tua ( = .43), diikuti oleh pacar/kekasih ( = .17). Dengan pengujian model yang menggunakan hybrid SEM, yang mana meliputi alat ukur dan struktur komponen, ditemukan bahwa semua variabel eksogen berkorelasi satu dengan yang lainnya. Nilai untuk model ini adalah 268.25 ( signifikan ( < .01). Rasio memuaskan (NNFI=.95; / = 165) dan secara statistik dibawah 3 (1.63), dan indeks fit CFI=.96; RMSEA=.05). SWB dapat diprediksikan melalui dukungan yang diperoleh dari keluarga ( = .27, < .05), teman ( = .35, < .05). < .05) dan kekasih/pacar ( = −.22, Dari beberapa penelitian di atas, ada penelitian yang menemukan hubungan yang signifikan, namun ada pula yang hubungannya rendah atau sama sekali tidak ada hubungan yang signifikan. 2.6. Landasan Teori 2.6.1. School Connectedness dan Dukungan Sosial Teman Sebaya sebagai prediktor Subjective Well-Being Remaja dalam perkembangannya membutuhkan lingkungan yang juga mendukung dirinya untuk berkembang secara optimal ke arah yang positif. Selain lingkungan keluarga, teman dan lingkungan sekolah menjadi lingkungan pendukung utama bagi dunia remaja. Sekolah sebagai tempat di mana remaja bersosialisasi, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam upaya pengembangan dirinya. Keterhubungan yang dimiliki dengan sekolah, bisa memberikan pengalaman belajar dan pendidikan yang menyenangkan bagi masa remaja anak. Sampai saat ini, school connectedness menjadi salah satu faktor penting yang berpartisipasi secara potensial dalam mengurangi tingkat perilaku bermasalah yang terjadi di kalangan remaja (Goodenow, 1993). Penelitian yang dilakukan sesudahnya juga menemukan bahwa school connectedness memainkan peran yang krusial dan luas dalam perkembangan kesehatan remaja (Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming & Hawkins, 2004). Keterhubungan atau keterikatan dengan sekolah membantu remaja mengembangkan tujuan dan memberi arah, serta melindungi dari perasaanperasaan tertekan secara psikologi (Roeser, Eccles & Sameroff, 1998), increases self-esteem (Hagborg, 1994; Osterman, 2000) dan mengurangi kemungkinan remaja memulai pola perilaku yang bermasalah (Dornbusch, Erikson, Laird & Wong, 2001). School connectedness juga ditemukan berasosiasi dengan kesehatan mental pada orang muda. Jacobson dan Rowe (1999) menemukan bahwa suasana hati yang depresi secara signifikan berkorelasi dengan family connectedness dan school connectedness. Dalam studi lintas budaya dengan menggunakan model hierarki linear, Anderman (2002) menemukan bahwa level school connectedness individu yang tinggi berkaitan dengan tingginya optimisme dan rendahnya level depresi dan perilaku bermasalah begitu juga dengan peningkatan performa akademik. Dalam studi baru-baru ini pada lebih dari 2000 sampel, Shochet, Dadds, Ham, dan Montague (2006) menemukan school connectedness memprediksikan gejala-gejala kesehatan mental dari depresi, kecemasan, dan fungsi-fungsi umum lainnya, setelah terlebih dahulu melakukan kontrol untuk gejala-gejalanya setahun sebelumnya. Keterikatan atau keterhubungan secara umum berkaitan dengan individu maupun lingkungan (Whitlock dalam Waters dkk., 2009) dan juga interaksi antara setiap orang dalam lingkungan partikular dan lingkungan secara umum, yang mana school connectedness kelihatannya dipromosikan oleh ekologi sekolah yang positif (Connel & Wellborn dalam Waters dkk., 2009). Adanya ikatan antara siswa dengan sekolah, berkaitan dengan rentang kesehatan yang luas, sosial, dan hasil akademik dari anak dan remaja. Selain itu, memiliki koneksi yang kuat dengan sekolah juga berasosiasi dengan pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi (Anderman, 2002; Klem & Connell, 2004; Goodenow, 1993), peningkatan motivasi akademik, dan rasa memiliki atau menjadi bagian sekolah yang lebih besar (Resnick dkk., 1993; Wingspread Converence, 2004; Bond dkk., 2007; Klem & Connell, 2004), serta partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler (Whitlock dalam Waters dkk., 2009; Thompson, Iachan, Overpeck, Ross & Gross, 2006; Fullarton, 2003). Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa school connectedness kelihatannya menjadi prediktor bagi masalah kesehatan mental, yang mana membawa pada perkembangan yang lebih sehat dan meningkatkan well-being remaja (Waters dkk., 2009). Selain school connctedness, dukungan dari teman sebaya juga bisa memberikan pengaruh yang besar bagi siswa. Quedero dan Abella (2011) dalam penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh optimisme dan dukungan sosial pada komponen SWB menemukan bahwa dukungan sosial yang dirasakan berasosiasi dengan aspek yang berbeda-beda dari well-being, walaupun tingkat korelasinya lebih rendah. Partisipan dengan persepsi dukungan sosial yang lebih menunjukkan penyesuaian yang lebih baik, lebih puas dalam hidup, dan kepuasan akan partner atau teman, memiliki emosi positif yang lebih baik dan kurang dalam emosi negatif. Ketika keduanya (dukungan sosial yang dirasakan dan optimisme) dianalisis bersama-sama, ditemukan bahwa optimistis dan dukungan sosial yang tinggi menunjukkan emosi positif yang lebih, emosi negatif yang kurang, dan lebih mengalami kepuasan dalam hidup. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronen dan Seeman (2007) menemukan bahwa dukungan sosial menjadi variabel yang kuat dalam memprediksi SWB remaja, khususnya dukungan teman sebaya. Teman sebaya memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu sumber dukungan sosial bagi remaja dalam konteks sekolahnya. Dukungan sosial teman sebaya berhubungan secara positif dengan prestasi akademik dan harga diri (self-esteem), dan secara negatif dengan depresi dan komplain-komplain somatik, seperti sakit kepala dan pusing (Colarossi & Eccles, 2003; Domagala-Zysk, 2006; Torsheim &Wold, 2001). Hasil penelitian Rigby (2000) menemukan bahwa untuk siswa perempuan, dukungan sosial dari teman dekat dan teman sekelas berasosiasi dengan laporan mengenai mental well-being mereka, sementara untuk siswa laki-laki tidak ditemukan hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan wellbeing. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu secara terpisah telah menemukan school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya sebagai prediktor SWB siswa. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan lingkungan dan situasi dengan sampel penelitian yang akan dilakukan saat ini, ditambah penelitian ini juga akan melihat school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya secara simultan menjadi prediktor terhadap SWB siswa karena sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya secara simultan sebagai prediktor SWB. 2.7. MODEL PENELITIAN School Connectedness (X1) Dukungan sosial teman sebaya (X2) Subjective well-being siswa (Y) 2.8. HIPOTESIS Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori, hipotesis penelitian ini adalah, school connectedness dan dukungan sosial teman sebaya menjadi prediktor SWB siswa.