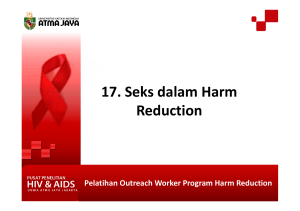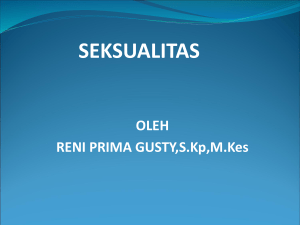Keberagaman kompleks gender dan seksualitas di
advertisement

Keberagaman kompleks gender dan seksualitas di Indonesia (Dédé Oetomo) Matatimoer Institute 2017 Keberagaman kompleks gender dan seksualitas di Indonesia1 Dédé Oetomo Yayasan GAYa NUSANTARA [email protected] Sepanjang sejarah berbagai masyarakat di Kepulauan Nusantara, konstruksi sosial gender senantiasa beraneka ragam, tidak melulu lelaki dan perempuan saja. Individu yang terlahir sebagai jantan (lelaki biologis) tidak semuanya tunduk pada konstruksi gender lelaki secara sosial-budaya. Mereka memilih atau mengkonstruksi sendiri perilaku dan identitas gendernya, dan masyarakat pun dengan berbagai derajat toleransi atau penerimaan mengenali mereka sebagai banci atau kedi (Melayu), bandhu (Madura), calabai (Bugis), kawe-kawe (Sulawesi umumnya), sara siwe (Bima), wandu (Jawa) dan istilah-istilah lainnya yang belum semuanya dikenali bahkan oleh para peneliti gender dan seksualitas pun, namun memang ada dan dikenali oleh masyarakat setempat. Belum lagi adanya orang-orang yang interseks, yang dalam derajat tertentu memiliki (sebagian) ciri-ciri kelamin biologis lelaki dan/atau perempuan dalam berbagai kombinasi, yang acapkali disebut juga dengan istilah-istilah tadi. Pada beberapa masyarakat adat, tidak saja penerimaan yang terjadi pada orang-orang yang menyeberang gender atau memadukan dua atau lebih gender dalam dirinya: ada pranata-pranata (institusi) yang secara signifikan melibatkan orang-orang macam itu, seperti bissu di masyarakat Bugis, yang dahulu menjaga dan memelihara arajang (pusaka kerajaan) di lingkungan istana, dan hingga kini pun masih menjadi perantara manusia dengan para dewata, yang membantu Allah, Tuhan yang Esa; atau basir di masyarakat Dayak Ngaju, yang juga menjadi perantara antara dunia ini dengan dunia para arwah nenek-moyang; atau tadu mburake pada masyarakat Toraja Pamona, yang memimpin ritus-ritus spiritual; atau para seniman pertunjukan tradisional yang memerankan gender yang lain, seperti pada ludruk di Jawa Timur. Secara lebih terbatas, umumnya karena androsentrisme (virisentrisme) dunia ilmu pengetahuan kita, kita kenal juga dengan konstruksi gender orang-orang yang secara biologis perempuan (betina), tetapi mengkonstruksi perilaku dan identitas gender yang sesuai atau lebih mirip konstruksi gender lelaki. Masyarakat Bugis Naskah acuan untuk Sekolah Kritik Budaya, Matatimoer Institute, Jember, 18 Mei 2017. Untuk uraian yang lebih lengkap, periksa Dédé Oetomo, “Homoseksualitas di Indonesia,” dlm Memberi Suara pada yang Bisu (Yogyakarta, Galang, 2001), hal. 30–36. Informasi tambahan dan kerangka pikir seks dan gender mengenai bissu dan gender-gender lain pada masyarakat Bugis diperoleh dari Sharyn Graham, “Sulawesi’s Fifth Gender,” Inside Indonesia (www.insideindonesia.org) 66 (April–June 2001), hal. 16–17. 1 1 Keberagaman kompleks gender dan seksualitas di Indonesia (Dédé Oetomo) Matatimoer Institute 2017 mempunyai nama calalai untuk orang-orang macam ini, dan pada masyarakat Bima dikenal juga istilah sara siwe, tetapi pada masyarakat-masyarakat lainnya, walaupun orang penyeberang gender macam ini dikenal, tidak ada istilah yang dipakai untuk menyebut mereka. Kadang istilah seperti banci dipakai untuk menyebut orang-orang ini juga. Dalam budaya nasional kita pun dikenal identitas gender waria (wadam), dan sampai batas tertentu, tomboi. Belakangan mulai muncul identitas gender priawan dan lelaki transgender (trans man). Sebagian masyarakat merancukan identitas gender ini dengan identitas seksual macam homoseks/gay atau lesbian, dan memang acapkali terjadi tumpang-tindih antara identitas gender dan orientasi/identitas seksual seperti ini bahkan di kalangan waria maupun gay/lesbian sendiri. Belakangan ini ditengarai juga mulai timbulnya orangorang beridentitas biseks, namun wacana sosial di seputar ini masih terbatas di masyarakat kita. Menengok berbagai masyarakat adat, dalam rekaman sejarah, kita temukan juga hubungan seksual dan/atau emosional antarlelaki, baik di antara mereka yang sebaya maupun yang beda usia (transgenerasi). Apakah di Atjeh di kalangan ulëëbalang (umumnya dengan budak belian dari Nias) maupun di lingkungan perdagangan di pantai timur dan barat di masa lampau, di Minangkabau (induak jawi—anak jawi) dalam konteks kehidupan di surau, di Ponorogo (warok, warokan, gemblakan) dalam konteks ilmu kanuragan dan kesenian reyog, di pesantrenpesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur (mairilan, amrot-amrotan) serta Madura (laq-dalaqan) dalam konteks kehidupan nyantri/nyantre, maupun di beberapa budaya Melanesia dalam konteks ritus inisiasi anak laki-laki, hubungan antarlelaki, dengan berbagai pemaknaan sosial-budaya, memang ada, termasuk hubunganhubungan “biasa” (artinya, tidak dalam konteks ritual tertentu) seperti di Jawa dan Bali, umpamanya. Yang signifikan adalah bahwa hubungan itu hampir senantiasa terjadi bersamaan dengan maupun disusul oleh pernikahan atau hubungan dengan perempuan atau kadang-kadang juga individu semacam waria. Dalam budaya nasional kita, di mana dikenal pranata waria, juga cukup banyak lelaki yang menjalin hubungan seksual dan/atau emosional, baik kasual maupun lebih permanen, dengan waria. Dalam berbagai kasus anekdotal pun kita temukan perempuan (baik yang beridentitas lesbi maupun tidak) yang menjalin hubungan dengan waria, baik dalam pernikahan sah (karena warianya dipandang lelaki oleh agama dan hukum) maupun di luarnya. Kembali kiranya karena androsentrisme ilmu pengetahuan, belum banyak yang kita ketahui tentang hubungan antarperempuan dalam berbagai masyarakat adat kita. Pernah dicatat adanya warok perempuan dan gemblakannya di Ponorogo, namun tampaknya tidak banyak. Di dunia pesantren budaya Jawa dan Madura ditengarai juga ada hubungan antarsantri perempuan, yang disebut dengan istilah 2 Keberagaman kompleks gender dan seksualitas di Indonesia (Dédé Oetomo) Matatimoer Institute 2017 sihaq atau musahaqah. Sebagaimana pada hubungan antarlelaki tadi, perlu dicamkan bahwa hubungan antarperempuan ini berjalan bersamaan dengan atau disusul oleh hubungan dengan gender lain, apakah itu dalam pernikahan atau tidak, dan unsur kesukarelaan acapkali tidak relevan, terutama untuk perempuan ini, mengingat sifat pernikahan yang cenderung masih didasarkan pada anggapan bahwa perempuan tidak sepatutnya berkehendak bebas dan seksualitas. Di masyarakat modern tentunya kita kenal hubungan seksual dan/atau emosional antarperempuan, baik oleh mereka yang mengenal konsep lesbian atau tidak. Ditengarai di kalangan perempuan yang bekerja di industri seks, di kalangan buruh pabrik dan buruh migran, terutama di Hong Kong, juga cukup banyak terjadi hubungan macam ini, yang baru sedikit dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Pendek kata, dapatlah dikatakan bahwa konstruksi gender dan seksualitas di masyarakat-masyarakat Nusantara maupun masyarakat Indonesia masa kini adalah teramat kompleks dan beragam. Kaum ilmuwan, aktivis sosial, maupun anggota masyarakat sendiri, seringkali masih tidak tahu atau sengaja membisukan (karena berbagai alasan: moralitas, rasa risih, kemalasan berpikir) kenyataan yang rumit dan kaya ini. Mereka yang berpretensi menekuni bidang kajian gender pun cenderung hanya mewacanakan isu-isu perempuan (dengan hampir secara kategoris melupakan kaum lesbian maupun kemungkinan perilaku biseksual, maupun acapkali enggan membahas perempuan dalam industri seks dengan berbagai kompleksitasnya), sehingga akhirnya kajian gender di Indonesia hanyalah merupakan istilah lain untuk “kajian perempuan,” serta tidak memproblematikkan maskulinitas. Konstruksi teoretis gender mereka pun umumnya tidak menangkap kemungkinan kompleks kecairan, kehibridan dan liminalitas gender. Orang-orang yang sama juga cenderung tidak memperhatikan seksualitas, selain dalam wujud perilaku reproduksi atau perkosaan dan tindak kekerasan lainnya. Juga yang kurang diperhatikan adalah kompleksitas berbagai dimensi hubungan seksual dan/atau emosional: perbedaan anatomi (termasuk difabilitas), kebangsaan dan etnisitas, kelas sosial, keterlibatan uang dan materi lainnya, serta dimensi-dimensi relasi kuasa lainnya.2 Untuk kajian komprehensif mengenai hal ini, periksa Tom Boellstorff, The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia (Princeton, Princeton Univ. Press, 2005), diterjemahkan [oleh Esti Sumarah] sebagai The Gay Archipelago: Seksualitas dan Bangsa di Indonesia ([Jakarta: Qmunity, 2009]). 2 3